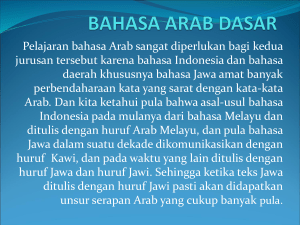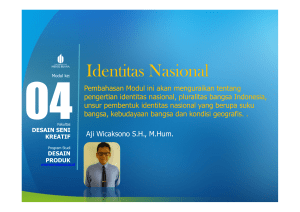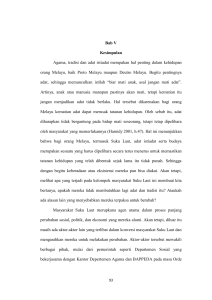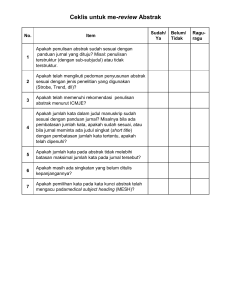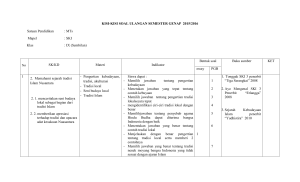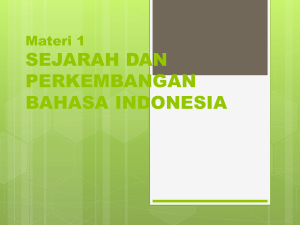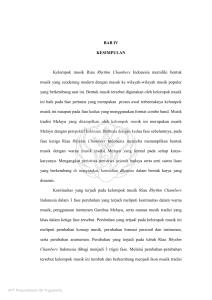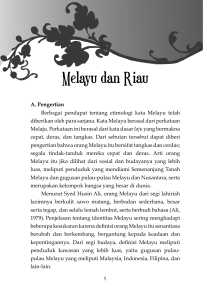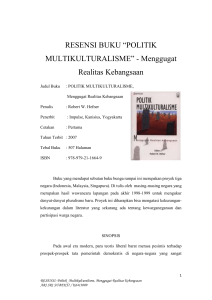Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan
advertisement

Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan 2013 JARINGAN ULAMA-ULAMA MELAYU DALAM MANUSKRIP Oleh: Dr. Ajidar Matsyah, Lc., MA Abstrak Manuskrip menjadi sumber utama untuk mengungkapkan jaringan hubungan ulama dan intelektual, hubungan guru-murid, sahabat, keluarga ataupun kerabat. Kitab Umdat alMuhtajin karya Abdurrauf al-Fansuri menjelaskan jalur silsilah dan jaringan antara guru dan murid dalam tarekat Syattariyah. Kitab-kitab salinan karyanya yang lain juga menjadi acuan sebagai referensi, kitab Tarjuman al-Mustafid dan Mir’atul Thullab tetap dipelajari di berbagai wilayah dalam beberapa abad setelahnya, seperti di Mindanao (Fhilipina), Pathani (Thailand), Malaysia, Brunai Darussalam dan beberapa daerah di Nusantara. Selain informasi jaringan intelektual, manuskrip juga menjadi mediator transfer ilmu pengetahuan (knowledge), terutama dari jazirah Arab. Mayoritas kitab ibadah, tata bahasa, hingga muamalah adalah terjemahan dan penjabaran (syarah) dari kitab-kitab utama dari ulama-ulama semenanjung Arab. Sehingga informasi tersebut menjelaskan ragam pemikiran ulama Melayu yang berkembang terekam dalam manuskrip. Kitab-kitab Nuruddin al-Raniry, seperti Shirat al-Mustaqim, Hidayat al-Habib, dan Bustan al-Salatin menunjukkan kesatuan pemikiran dan intelektual ulama-ulama Arab, India dan Melayu-Nusantara dalam manuskrip. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama Melayu-Nusantara lainnya hingga periode kolonial Belanda di Nusantara. Pendahuluan Keterbukaan wilayah negeri “di bawah angin” Melayu-Nusantara terhadap pengaruh luar merupakan karakteristik wilayah ini yang sangat menonjol dan memberikan perubahan besar dalam berbagai aspek, baik bidang budaya, adat, politik, ekonomi maupun keyakinan (akidah) yang melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual searah dan berkesinambungan dengan negara-negara luar. Negeri di bawah angin sudah dikenal dalam dunia perdagangan dan pelayaran untuk membedakannya dengan wilayah luar seperti India, Arab, dan Eropa, yang dikenal negeri “di atas angin”, memanfaatkan angin muson Samudera Hindia.1 Pertemuan dan perpaduan budaya dan ideologi antara orang di “negeri bawah angin” dan “negeri di atas angin” telah melahirkan intensifikasi dan dinamika intelektual yang dinamis dan beragam. Perpaduan tersebut telah terjadi masa Kesultanan Perlak, Kesultanan Pasai, Kesultanan Malaka, hingga kesultanan Aceh. Kebangkitan beberapa kerajaan Muslim di Nusantara sejak abad ke-13 telah menciptakan momentum baru bagi hubungan politik, bisnis, dan agama antara Timur Tengah (Jazirah Arab) dengan Melayu-Nusantara. Kebangkitan beberapa kerajaan Muslim di Melayu-Nusantara, khususnya di Sumatera, sejak abad ke13, menciptakan momentum baru bagi hubungan-hubungan politik sosial dan kultural. Momentum ini ditandai dengan kehadiran sejumlah ulama dari Timur tengah dan Eropa. Ibn Batutah melaporkan, bahwa ia, ketika berkunjung ke Samudera Padai pada tahun 1345 M bertemu dengan para pembesar istana kerajaan tersebut, ahli fiqih dari kelompok orang-orang Timur Tengah, di antaranya al-Qadhi al-Syarif Amir Sayyid alSyirazi dari Syiraz dan Taj al-Din al-Isfahani dari Isfahan (Persia).2 Hubungan tersebut bukan hanya saja terjalin dengan Jazirah Arab, akan tetapi juga dengan beberapa kerajaan besar Islam seperti Turki (Rum). Nuruddin ar-Raniry dalam Bustan as-Salatin meriwayatkan, Sultan ‘Alauddin Ri’ayat Syah al-Qahhar mengirim suatu misi diplomatik ke Istambul untuk menghadap Sultan Rum (Dinasti Ustmani).3 Hubungan politik dan diplomatik antara Aceh dan Dinasti Ustmani terjalin sesuai dengan kondisi perkembangan politik kedua Negara tersebut, khususnya Aceh. Meskipun demikian beberapa Sultan terpilih di Aceh tetap menjalin hubungan dengan Turki, termasuk periode Sultan Iskandar Muda yang dianggap mencapai kebangkitan dan kegemilangan. Oleh karenanya, ulama-ulama penting di Aceh yang 17 Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan 2013 berasal dari Turki cukup memiliki posisi strategis dan mendapat kehormatan di Aceh, seperti Syekh Baba Daud Ismail ar-Rumi, Tgk Di Bitai, Syekh Fairus al-Baghdady, dan lainnya. Hubungan Aceh dengan Jazirah Arab, khususnya Haramain (Mekkah dan Madinah), -sebagai pusat keagamaan Islam-, memiliki keistimewaan tersendiri dari beberapa wilayah di Melayu-Nusantara. Meski hubungan ini lebih bersifat keagamaan daripada politik, penting dicatat bahwa Kesultanan Aceh juga pernah mendapat kehormatan besar dengan menerima “stempel mas Bayt al-Haram, Mekkah” periode Sultan ‘Alauddin Syah.4 Selain itu, secara politis terjadi pasca Sultanah, bahwa keluarga Syarif Mekkah menjadi sultan di Aceh, dari tahun 1699 sampai 1727 M. Bukan hanya Aceh, akan tetapi juga Banten dan Mataram menjalin hubungan erat dengan Haramain, dan sekaligus mendapat gelar sultan dari penguasa Tanah Suci tersebut. Demikian juga Sultan Palembang menerima beberapa pucuk surat dari Mekkah, yang dikirimkan dengan kapal-kapal Aceh. Jaringan yang terbangun antara kesultanan di bawah angin dengan di atas angin menjadikan Aceh sebagai pusat penghubung keduanya, baik sebagai para pedagang, jamaah haji, atau menuntut ilmu, akan memainkan peran sebagai duta-duta kerajaan mereka di Haramain. Hubungan-hubungan antara Timur Tengah dengan Nusantara sejak kebangkitan Islam sampai paruh kedua abad ke-17 menempuh beberapa fase dan juga mengambil beberapa bentuk. Dalam fase pertama sejak akhir abad ke-8 samapai abad ke-12, hubungan-hubungan yang ada umumnya berkenanan dengan perdagangan. Inisiatif dalam hubungan-hubungan semacam ini kebnayakan diprakarsai Muslim Timur Tengah, khususnya Arab dan Persia. Dalam fae berikutnya, sampai akhir abad ke-15, hubungan-hubungan antara kedua kawasan mulai mengambil aspek –aspek lebih luas, sebagai pedagang atau pengembara sufi mulai mengintensifikasikan penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara. Pada tahap ini hubunganhubungan keagamaan dan kultural terjalin lebih erat. Tahap ketiga adalah sejak abad ke-16 sampai paruh kedua abad ke-17. Dalam masa ini hubungan-hubungan yang terjalin lebih bersifat politik di samping keagamaan sebagaimana di atas. Dalam periode ini, Muslim Nusantara semakni banyak ke Tanah Suci, yang pada gilirannya mendorong terciptanya jalinan keilmuan antara Timur Tengah dengan Nusantara melalui ulama Timur Tengah dan murid-murid Jawi.5 Kuatnya pengaruh kerajaan Aceh menjadikan posisinya di wilayah perairan selat Malaka sebagai bandar Internasional dan transit jalur perdagangan dari dan ke berbagai negara, baik dilakukan oleh pedagang, pelayar ataupun ulama. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya bahwa hubungan antar negara sudah terjalin beberapa abad, dan telah tumbuh peradaban, pemikiran serta kerjasama perdagangan (bisnis), realitanya terekam oleh sejarah baik lisan, surat-surat perjanjian kerajaan antar negara maupun naskahnaskah kuno karya para ulama yang masih tersimpan di museum negara ataupun koleksi pribadi. Dapat dipastikan, pada abad ke-16 dan ke-17 M, Aceh mencapai puncak keselarasan tersebut. Pada saat itu Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat transaksi, jalan perdagangan Internasional dan puncak kemajuan sastra, khususnya sastra Aceh. Bukti ini dapat terlihat pada naskah-naskah kuno yang ditulis oleh para ulama dengan berbagai disiplin ilmunya yang hinga saat ini masih ditemui tersimpan di berbagai museum perpustakaan yayasaan dan pesantren, baik yang terdapat di luar negeri maupun di dalam negeri, lain lagi dengan koleksi-koleksi pribadi yang belum terdata. Jaringan Intelektual Arab dan al-Jawiyah Jaringan Arab dengan wilayah Melayu-Nusantara telah terjalin sejak lama dalam berbagai situasi dan aspek, baik politik, agama, budaya dan kultural. Tokoh utama Ahmad al-Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani (1670-1733) menjadi jaringan penting antara Haramain dengan Melayu-Nusantara. Ibrahim al-Kurani sendiri menulis kitab Ithaf al-Dhaki bi Syarh al-Tuhfat al-Mursalah ila Ruh al-Nabi. Kitab ini ditulis sebagai respon atas pertanyaan sahabat al-Jawiyyah (ashhab al-Jawi) merupakan penjelasan terhadap kitab al-Tuhfat al-Mursalah ila Ruh al- 18 Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan 2013 Nabi, karangan Muhammad ibn Fadhlullah al-Burhanpuri, yang menjadi pembahasan “hangat” periode tersebut, tidak hanya di Hijaz, Syiria, India, tetapi juga di Nusantara. Keterlibatan ulama asal India dalam jaringan jelas membantu perluasan jaringan ulama. Tidak kurang pentingnya, mereka memperluas ranah pengaruh taarekat, khususnya Syatariyah dan Naqsyabandiyah, yang sebelumnya terutama diasosiasikan sebagai tasawuf Anak Benua India. Kedua tarekat tersebut membesar setelah eksis di Haramain, dan memberikan warna penting bagi al-Jawiyah atau al-Hindi sendiri yang berada disana. Tokoh seperti Nuruddin al-Raniry dan pamannya Muhammad Jailani ibn Hasan ibn Muhammad Hamid al-Raniry merupakan bagian yang mengikuti proses tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Bustan al-Salatin, bahwa pamannya kembali ke Haramain setelah sekian lama berada di Kesultanan Aceh. Nuruddin al-Raniry menjadi mufti dan syaikhul Islam di Aceh periode Sultan Iskandar Tsani (16371641 M) dan Sultanah Safiyatuddin Syah Tajul ‘Alam (1644 M), sebagai pengarang kitab-kitab tasawuf, juga ia mengarang kitab fiqih al-Shirat al-Mustaqim.6 Kitab tersebut merupakan kitab fiqih dalam edisi lengkap perdana di Melayu-Nusantara yang ditulis sekitar tahun 1634 M. Sebelumnya ketentuan fiqih memang sudah dikenal baik secara lisan maupun tulisan yang terpenggal-penggal. Karena faktor kelengkapan dan kemudahan analisisnya, kitab ini kemudian dijadikan sumber bacaan dan rujukan berabad-abad, sehingga kitab al-Shirat al-Mustaqim juga dicetak dipinggir matan kitab Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquhi fi Amr ad-Din karangan Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah al-Banjari (1710-1812 M), seorang ulama paling terkenal dari Banjar, Kalimantan Selatan.7 Hal tersebut menunjukkan kitab-kitab ulama Melayu memiliki keterkaitan di wilayah Melayu-Nusantara, sehingga kitab tersebut dicetak ulang secara kontinu di Mesir dan Surabaya hingga abad 21 M. Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri (w. 1693 M) merupakan salah seorang ulama di Aceh dan Melayu yang memiliki jaringan internasional,8 karya-karyanya pun mengembara hingga ke Fathani, Buton Sulawesi dan Mindanao Selatan. Salah satunya kitab Tarjuman al-Mustafid, kitab tafsir ini disebut sebagai karya emas ‘Abdurrauf dalam bidang tafsir al-Qur’an. Dia alim pertama yang di bagian dunia Islam yang bersedia memikul tugas besar mempersiapkan tafsir lengkap al-Qur’an dalam bahasa Melayu. Kitab tafsir ini diselesaikan di Aceh semasa ia menjabat sebagai Qadhi dan Syaikhul Islam di Kesultanan Aceh. (1661-1693 M). Sebagai tafsir paling awal, tidak mengherankan kalau karya ini beredar luas di wilayah MelayuNusantara. Bahkan, edisi tercetaknya dapat ditemukan di kalangan komunitas Melayu di tempat sejauh Afrika Selatan. Mengenai manuskrip-manuskrip yang tersedia dalam banyak koleksi, Riddell menegaskan bahwa salinan paling awal yang kini masih ada dari Tarjuman al-Mustafid berasal dari akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18.9 Yang lebih penting lagi, edisi-edisi tercetaknya diterbitkan tidak hanya di Singapura, Penang, Jakarta, dan Bombay (India), tetapi juga di Timur Tengah. Di Istambul, ia diterbitkan oleh Mathba’ah al‘Ustmaniyyah pada tahun 1302 H/1884 M (dan juga pada tahun 1324/1904); dan kemudian di Kairo oleh penerbit Sulayman al-Maraghi, dan di Makkah oleh Al-Amiriyyah. Kenyataan bahwa Tarjuman al-Mustafid diterbitkan di Timur Tengah pada masa yang berbeda-beda, mencerminkan nilai tinggi karya ini serta ketinggian intelektual Abdurrauf al-Jawi al-Fansury. Edisi terakhirnya diterbitkan di Jakarta pada tahun 1401 H/1981 M. Ini menunjukkan, bahwa karya ini masih digunakan di kalangan kaum Muslim Melayu-Indonesia (termasuk Thailand Selatan dan Kepulauan Philifina) pada masa kini. Sebagai catatan penting yang harus dibenahi adalah, tafsir ini telah lama dianggap semata-mata sebagai terjemahan bahasa Melayu karya al-Baidhawi, Anwar al-Tanzīl. Snouck Hurgronje, tanpa meneliti lebih dulu karya itu secara seksama, menyimpulkan dalam caranya yang khas sinis, bahwa karya tersebut hanyalah sebuah terjemahan yang buruk dari tafsir al-Baidhawi.10 Dengan kesimpulan ini, Snouck bertanggung jawab atas tersesatnya dua sarjana Belanda lainnya, Rinkes dan Voorhoeve. Rinkes, murid 19 Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan 2013 Snouck, menciptakan kesalahan-kesalahan tambahan dengan menyatakan bahwa Tarjuman al-Mustafid, selain mencakup terjemahan al-Baidhawi, juga merupakan terjemahan dari sebagian Tafsir al-Jalalain 11 kitab ini merupakan karya Jalaluddin al-Mahalli (w. 1459) dan Jalaluddin al-Suyuthi. Sedangkan Voorhoeve, setelah mengikuti Snouck dan Rinkes, akhirnya mengubah kesimpulannya dengan menyatakan bahwa sumber-sumber Tarjuman al-Mustafid adalah berbagai karya tafsir berbahasa Arab.12 Di kemudian hari, Riddell dan Harun, dalam telaah mereka, membuktikan secara meyakinkan bahwa karya itu merupakan terjemahan dari Tafsir Jalalain. Hanya pada bagian-bagian tertentu saja, ‘Abdurrauf alFansuri memanfaatkan tafsir al-Baidhawi dan al-Kanzin berjudul Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil yang dikenal Tafsir al-Khazin. Demikian, selama hampir tiga abad, Tarjuman al-Mustafid dan karya-karyanya yang fenomenal lainnya seperti Mir’at al-Thullab menyertai kitab terkenalnya. Kitab tafsir Melayu menjadi satu-satunya terjemahan lengkap al-Qur’an di Tanah Melayu-Nusantara; baru dalam tiga puluh tahun terakhir ini muncul tafsir-tafsir baru di wilayah Melayu-Indonesia. Namun, perkembangan terakhir ini tidak lantas berarti bahwa Tarjuman al-Mustafid kehilangan daya tariknya. Karya ini memainkan peranan penting dalam memajukan pemahaman lebih baik atas ajaran-ajaran Islam. Selain kitab bidang fiqih dan tafsir di Melayu Nusantara, kitab-kitab karya ulama Aceh berbahasa Jawi dalam bidang syariah, baik hukum pidana maupun perdata, bidang tersebut menjadi acuan utama di wilayah Melayu-Nusantara. Salah satunya, kitab hukum perdata tertua di Aceh adalah Mir’at al-Thullab fi Tashil ma’rifat Ahkam al-Syar’iyyah li al-Malik al-Wahhab, karya Syekh ‘Abdurrauf al-Jawi al-Fansury yang ditulis ats permintaan Sultanah Safiyatuddin Syah Tajul ‘Alam (1641-1675 M). Kitab Mir’at al-Thullab berisi aturan-aturan tentang muamalah (mencakup hukum dagang dan perdata), munakahat, (hukum keluarga), dan jinayat (pidana). ‘Abdurrauf menulis kitab ini menunjukkan kepada Muslim di Melayu-Nusantara bahwa doktrin-doktrin hukum Islam tidak terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari mereka. Hooker mengemukakan, kitab ini masih digunakan kaum Muslim di Maquidanao, Filipina, sejak pertengahan abad ke-19, sebagai acuan utama.13 Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlish al-Khashsham karya Jalaluddin bin Kamaluddin bin Baginda Khatib dari Tarusan, ditulis atas permintaan Sultan ‘Alaiddin Johan Syah (1735-1760 M). Sejauh ini, dalam berbagai katalog di Aceh, kitab ini hanya tersimpan di tiga tempat koleksi; satu naskah di Museum Aceh, satu naskah di Yayasan Ali Hasjmy dan satu naskah koleksi Zawiyah Tanoh Abee. Kitab Safinat al-Hukkam, akhirnya, melengkapi kitab hukum perdata lainnya di wilayah Melayu-Nusantara. Penutup Hubungan antara ulama-ulama di Tanah Melayu-Nusantara telah tejalin sejak masa-masa awal Islam di Melayu-Nusantara. Ikatan tersebut terbina dengan baik dalam tradisi keilmuan dan intelektual keagamaan yang berkembang, khususnya di Aceh, dalam setiap periode pada penegasan harmonisasi syariah dengan tasawuf. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya sejumlah karya-karya tulis di bidang syariah, hukum, kenegaraan, sastra, sosial budaya yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf (sufi). Manuskrip tersebut menjadi acuan satu wilayah dengan wilayah lainnya di belahan Asia Tenggara, sehingga transmisi keilmuan dan intelektual terus terjalin dalam berbagai situasi dan kondisi. Catatan Akhir 1 Anthony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan (Charting the Shap of Early Modern Southest Asia). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, h. 5-6 2 Ibn Bathutah, Rihlat Ibn Bathutah, Tuhfat an-Nadhhar fi ‘Ara’ib al-Amshar wa ‘Aja’ib al-Asfar. Mesir: Mathba’at Musthafa Muhammad 1358 H/1938. 152 20 Seminar Serantau Kajian Manuskrip Melayu dan Kearifan Tempatan 2013 3 Nuruddin ar-Raniry, Bustan al-Salatin, peny. Teuku Iskandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966: 31-2. 4 Djajdiningrat, Kesultanan Aceh, terj. T. Hamid. Banda Aceh: Depertemen P&K, 1984: 46-8 5 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII. Jakarta: Prenada Media, 2005: 49-50. 6 Kitab al-Shirat al-Mustaqim; kitab berisi ajaran tentang ibadah amaliyah yakni thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan tentang hukum kurban, beruru, hukum halal dan haram dalam hal makanan. Kitab ini ditulis pada periode 1634-1644 M, atau sejak ia berada di Pahang dan di Aceh. 7 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, 13. 8 Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII. Jakarta: Prenada Media, 2005: 228-259. Azra telah mengkaji lebih dalam jaringan Abdurrauf antara guru murid dan sahabat seperjuangannya di belahan dunia dan Melayu Nusantara. 9 P. Riddell, Transferring a Tradition: ‘Abd al-Rauf al-Singkili’s Rendering into Malay of the Jalalayn Commentary. Berkeley: Monograph No. 31, Centers for South and Southeast Asia Studies, University of California at Berkeley, 1990. 10 Snouck Hurgronje, The Achehnese, II, 17, catatan 6. 11 Lihat D.O Rinkes, Abdoerraoef van Singkel: Bijdroge tot de kennis van de mystiek op Sumatra en Java, Heerenven: Hepkema, 1909 12 P. Voorhoeve, Bayan Tajalli: Gegevens voor een nadere studies over Abdurrauf van Sinkel. TBG, 85, 1982 13 M.B Hooker, Islamic Law in South-East Asia. Singapore: Oxford University Press: 9184, 20, 32, 41 21