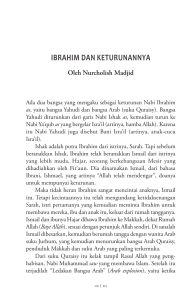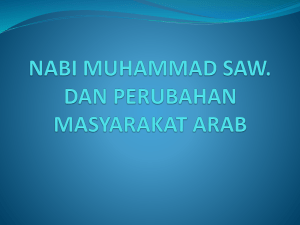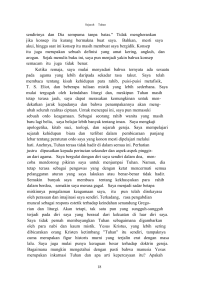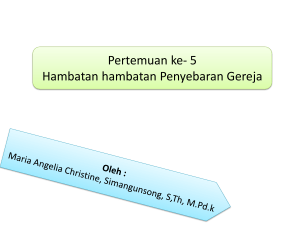Rahmatan Lil-`Alamin dan Toleransi
advertisement

JURNAL PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIKA 25 KAMIS, 15 DESEMBER 2011 WORDPRESS Rahmatan Lil-‘Alamin dan Toleransi U Muhammad Idrus Ramli Pengurus Lajnah Ta’lif wan Nasyr PWNU Jawa Timur mat Islam tentu meyakini misi rahmatan lil-‘alamin sebab istilah itu telah dinyatakan oleh Alquran. Istilah rahmatan lil-‘alamin dipetik dari salah satu ayat Alquran, “Ma maa arsalnaaka illaa rahmatan lil-‘aalamiin (Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam).” (QS al-Anbiya’ [21]: 107). Dalam ayat itu, “rahmatan lil-‘alamin” secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Artinya, Allah SWT tidaklah menjadikan Nabi SAW sebagai rasul, kecuali karena kerasulan beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena rahmat yang diberikan Allah SWT kepada semesta alam ini dikaitkan dengan kerasulan Nabi SAW, maka umat manusia dalam menerima bagian dari rahmat tersebut berbeda-beda. Ada yang menerima rahmat tersebut dengan sempurna dan ada pula yang menerima rahmat tersebut tidak sempurna. Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, sahabat Nabi SAW, pakar dalam Ilmu Tafsir menyatakan, “Orang yang beriman kepada Nabi SAW, maka akan memperoleh rahmat Allah SWT dengan sempurna di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW, maka akan diselamatkan dari azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu ketika masih di dunia seperti diubah menjadi hewan atau dilemparkan batu dari langit.” Demikian penafsiran yang dinilai paling kuat oleh alHafizh Jalaluddin al-Suyuthi dalam tafsirnya, al-Durr al-Mantsur. Penafsiran di atas diperkuat dengan hadis shahih yang menegaskan bahwa rahmatan lil-‘alamin telah menjadi karakteristik Nabi SAW dalam dakwahnya. Ketika sebagian sahabat mengusulkan kepada beliau agar mendoakan keburukan bagi orang-orang Musyrik, Nabi SAW menjawab, “Aku diutus bukanlah sebagai pembawa kutukan, tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat.” (HR. Muslim). Penafsiran di atas memberikan gambaran, bahwa karakter rahmatan lil-‘alamin memiliki keterkaitan sangat erat dengan kerasulan Nabi SAW. Dalam kitab-kitab tafsir, tidak ditemukan keterkaitan makna rahmatan lil-‘alamin dengan sikap toleransi yang berlebih-lebihan dengan komunitas non-Muslim. Ini berangkat dari kenyataan bahwa rahmatan lil-‘alamin sangat erat kaitannya dengan kerasulan Nabi SAW, yakni penyampaian ajaran Islam kepada umatnya. Maka seorang Muslim, dalam menghayati dan menerapkan pesan Islam rahmatan lil‘alamin tidak boleh menghilangkan misi dakwah yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Misalnya, memberikan khotbah dalam acara kebaktian agama lain, menjaga keamanan tempat ibadah agama lain dan acara ritual agama lain, atau doa bersama lintas agama dengan alasan itu adalah “Islam rahmatan J Asep Sobari Peneliti INSISTS lil-‘alamin”. Kegiatankegiatan semacam itu justru mengaburkan makna rahmatan lil-‘alamin yang berkaitan erat dengan misi dakwah Islam. Sebagaimana dimaklumi, selain sebagai rahmatan lil-‘alamin, Nabi SAW diutus juga bertugas sebagai basyiiran wa nadziiran lil‘aalamiin (pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh alam). “Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (Alquran) kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.” (QS al-Furqan [25]: 1). “Dan, Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan (basyiiran wa nadziiran), tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” (QS Saba’ [34] : 28). Sebagai pengejawantahan dari ayat-ayat ini, seorang Muslim dalam interaksinya dengan orang lain, selain harus menerapkan watak rahmatan lil-‘alamin, juga bertanggung jawab menyebarkan misi basyiran wa nadziran lil-‘alamin. Islam tidak melarang umatnya berinteraksi dengan komunitas agama lain. Rahmat Allah yang diberikan melalui Islam, tidak mungkin dapat disampaikan kepada umat lain, jika komunikasi dengan mereka tidak berjalan baik. Karena itu, para ulama fuqaha dari berbagai mazhab membolehkan seorang Muslim memberikan sedekah sunnah kepada non-Muslim yang bukan kafir harbi. Demikian pula sebaliknya, seorang Muslim diperbolehkan menerima bantuan dan hadiah yang diberikan oleh non-Muslim. Para ulama fuqaha juga mewajibkan seorang Muslim memberi nafkah kepada istri, orang tua, dan anakanak yang non-Muslim. Di sisi lain, karena seorang Muslim bertanggung jawab menerapkan basyiran wa nadziran lil-‘alamin, Islam melarang umatnya berinteraksi dengan non-Muslim dalam hal-hal yang dapat menghapus misi dakwah Islam terhadap mereka. Mayoritas ulama fuqaha tidak memperbolehkan seorang Muslim menjadi pekerja tempat ibadah agama lain, seperti menjadi tukang kayu, pekerja bangunan, dan lain sebagainya karena hal itu termasuk menolong orang lain dalam hal kemaksiatan, ciri khas dan syiar agama mereka yang salah dalam pandangan Islam. “Dan, tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS al-Ma’idah [5]: 2). Doa lintas agama Doa bersama lintas agama dewasa ini juga agak marak dilakukan. Sebagian beralasan Islam rahmatan lil-‘alamin. Padahal, karakter rahmatan lil-‘alamin sebenarnya tidak ada kaitannya dengan doa bersama lintas agama. Sebagaimana dimaklumi, doa merupakan inti dari pada ibadah (mukhkhul ‘ibadah) yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Tidak jarang, seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan harapan memperoleh pertolongan agar segera keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Tentu saja, ketika seseorang berharap agar Allah segera mengabulkan doanya, ia harus lebih berhati-hati, memperbanyak ibadah, bersedekah, bertaubat, dan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Dalam hal ini, semakin baik jika ia memohon doa kepada orang-orang saleh yang dekat kepada Allah. Hal ini sebagaimana telah dikupas secara mendalam oleh para ulama fuqaha dalam bab shalat istisqa’ (mohon diturunkannya hujan) dalam kitab-kitab fiqih. Ada dua pendapat di kalangan ulama fuqaha tentang hukum menghadirkan kaum non-Muslim untuk doa bersama dalam shalat istisqa’. Pertama, menurut mayoritas ulama (mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), tidak dianjurkan dan makruh menghadirkan non-Muslim dalam doa bersama dalam shalat istisqa’. Hanya saja, seandainya mereka menghadiri acara tersebut dengan inisiatif sendiri dan tempat mereka tidak berkumpul dengan umat Islam, maka itu tidak berhak dilarang. Kedua, menurut mazhab Hanafi dan sebagian pengikut Maliki, bahwa nonMuslim tidak boleh dihadirkan atau hadir sendiri dalam acara doa bersama shalat istisqa’, karena mereka tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Doa istisqa’ ditujukan untuk memohon turunnya rahmat dari Allah, sedangkan rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Demikian kesimpulan pendapat ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqih. Maka, jika doa diharapkan mendatangkan rahmat dari Allah, sebaiknya didatangkan orang-orang saleh yang dekat kepada Allah, bukan mendatangkan orangorang yang yang jauh dari kebenaran. Forum Bahtsul Masail al-Diniyah alWaqi’iyyah Muktamar NU di PP Lirboyo Kediri, 21-27 November 1999, menyatakan bahwa “Doa Bersama Antar Umat Beragama” hukumnya haram. Diantara dalil yang mendasarinya, yaitu Kitab Mughnil Muhtaj, Juz I hal 232: “Wa laa yajuuzu an-yuammina ‘alaa du’aa-ihim kamaa qaalahu ar-Rauyani li-anna du’aal kaafiri ghairul maqbuuli.” (Lebih jauh, lihat: Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (19262004), penerbit: Lajtah Ta’lif wan-Nasyr, NU Jatim, cet ke-3, 2007, hal 532-534). (Wallahu a’lam). ■ Toleransi Nabi SAW kepada Yahudi auh sebelum berbagai bangsa mengenal toleransi, pada awal abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh toleransi beragama di Madinah. Termasuk terhadap kaum Yahudi. Di tengah kondisi Madinah yang cukup akomodatif, Nabi SAW menetapkan perangkat-perangkat dasar untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni bagi seluruh unsur masyarakat Madinah. Maka lahirlah Shahifah al-Madinah atau Piagam Madinah yang menurut Dr M Hamidullah merupakan konstitusi negara tertulis yang pertama di dunia (the first written constitution in the world). Piagam Madinah menjelaskan bentuk negara, mengatur hubungan antarkelompok masyarakat, hak dan kewajibannya kepada negara, kehidupan beragama, asas peradilan dan sumber hukum, dan lain sebagainya. Selain mengejawantahkan konsep kenegaraan baru berupa al-ummah al-muslimah (umat muslim), isu kemajemukan juga menjadi sorotan utama Piagam Madinah. Terkait kaum Yahudi, berdasarkan susunan Dr Hamidullah, dari 47 pasal Piagam Madinah, terdapat sekitar 24 pasal yang menyebut kaum Yuhudi. Pasal-pasal tersebut mencakup beragam isu, di antaranya, status kewarganegaraan, kebebasan beragama, tanggung jawab bersama dalam bidang sosial, ekonomi dan keamanan, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Berdasarkan teks Piagam Madinah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam as-Sirah an-Nabawiyyah, jilid dua hal 94-96, Nabi SAW menyatakan, “Wa inna yahuda bani `auf ummatun ma`al mu’minin (sesungguhnya Yahudi Bani `Auf adalah satu umat bersama kaum Mukmin).” Dengan pengakuan ini, otomatis kaum Yahudi memperoleh hak-hak selayaknya warga negara. Salah satu yang terpenting adalah hak kebebasan beragama, “Lil yahudi dinuhum wa lil muslimin dinuhum, mawalihim wa anfusuhum (kaum Yahudi menjalankan agamanya sendiri, sebagaimana kaum Muslim juga menjalankan agamanya sendiri. Ini berlaku bagi orang-orang yang terikat hubungan dengan Yahudi dan diri Yahudi sendiri).” Dengan adanya jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama ini, kaum Yahudi di Madinah dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang di lingkungannya. Begitu juga dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah agama Yahudi yang disebut Bayt al-Midras beraktivitas sebagaimana biasa, bahkan semakin giat dari sebelumnya karena terpacu dengan kehadiran Islam di Madinah. Ibnu Ishaq menyebutkan, Rasulullah SAW pernah berkunjung dan masuk ke sekolah Yahudi untuk berdialog dengan para Ahbar (pemuka Yahudi). Begitu juga Abu Bakar RA, dikabarkan pernah masuk ke dalam Midras dan “mendapati banyak sekali orang di sana.” (Jilid dua hal 129 dan 134). Terkait dengan keamanan kota Madinah, kaum Muslim dan Yahudi harus bahu-membahu mewujudkannya. Kaum Muslim tidak akan membiarkan Yahudi diserang musuh dari luar dan begitu juga sebaliknya. Dalam teks Piagam Madinah, Nabi SAW menyatakan, “Wa inna baynahum an-nashr `ala man dahama Yatsrib (kaum Muslim dan kaum Yahudi saling menolong dalam mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar).” Karena itu, baik Muslim maupun Yahudi sama-sama berkewajiban menanggung beban biaya perang untuk mempertahankan Madinah dari serangan musuh, “wa innal yahuda yunfiqun ma`al mu’minin ma damu muharabin (sesunguhnya kaum Yahudi dan kaum Mukmin sama-sama menanggung biaya perang bila diserang musuh).” Dari penjelasan sebagian pasal Piagam Madinah yang menyangkut kaum Yahudi, tampak sejak awal Rasulullah SAW menghendaki terbangunnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis di Madinah. Pendekatan persuasif ini tampak semakin jelas, ketika Nabi SAW menyebut kaum Yahudi (bersama Nasrani) sebagai Ahl al-Kitab. Dengan sebutan ini, maka dampaknya, antara lain, lelaki Muslim masih dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan daging hewan sembelihan Yahudi halal dimakan oleh Muslim. Dalam muamalat, jual beli dan pelbagai bentuk transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kaum Muslim juga dibolehkan melakukannya dengan Yahudi. Faktanya, setelah kedatangan Nabi SAW ke Madinah, kaum Muslim tetap melakukan transaksi di pasar Yahudi. Abdurraman bin `Auf, seorang sahabat terkemuka, memulai peruntungannya di hari-hari pertama keberadaannya di Madinah dengan berdagang di pasar Bani Qainuqa`, milik Yahudi (Shahih al-Bukhari, no 3780). Ali bin Abu Thalib, menantu Nabi SAW, sebagian persiapan walimahnya ditangani oleh seorang dari Bani Qainuqa` (Shahih Muslim, no 5242). Bahkan, Nabi SAW menggadaikan baju perangnya dengan 30 Sha` gandum kepada seorang Yahudi Bani Zhafar bernama Abu Syahm (Ibnu Hajar, Fathul Bari, Jilid tujuh hal 461). Batas toleransi Nabi Jaminan konstitusi dan pendekatan-pendekatan persuasif yang dilakukan Nabi SAW menunjukkan toleransi yang tinggi kepada kaum Yahudi. Tapi, seiring perjalanan waktu, kaum Yahudi melihat masyarakat Muslim sebagai ancaman bahkan musuh. Sejumlah individu Yahudi membuat kericuhan dan menyebarkan permusuhan. Fanhash, seorang Ahbar (Rabbi) Yahudi, menghina Allah dan Alquran di hadapan Abu Bakar (Ibnu Ishaq, Jilid dua hal 134); Ka`ab bin al-Asyraf, pemuka Bani Nadhir, merusak kioskios di pasar baru milik kaum Muslim (as-Samhudi, Wafa al-Wafa, Jilid satu hal 539); Sallam bin Misykam, pemuka Bani Nadhir, sempat menjamu Abu Sufyan di rumahnya dalam perang Sawiq dan memberi informasi penting tentang kaum Muslim (Ibnu Ishaq, Jilid tiga hal 4). Sikap permusuhan yang digalang para pemuka agama dan tokoh masyarakat Yahudi ini semakin dipertajam oleh para penyair. `Ashma binti Marwan, Abu `Afak, dan Ka`ab bin al- Asyraf adalah penyair-penyair terkemuka Yahudi yang hampir tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan lisannya untuk melontarkan baitbait yang menghina Islam dan sosok Nabi SAW. Nabi SAW menghadapi para penyair ini dengan sikap tegas karena mereka orang-orang berpengaruh di masyarakat. Nabi SAW memerintahkan mereka dihukum mati. Terlebih Ka`ab bin al-Asyraf yang menyampaikan simpatinya secara langsung dan terbuka kepada Quraisy setelah kekalahan mereka di Badar. Bahkan, ia terus mengobarkan dendam agar segera bangkit dan menyiapkan perang besar melawan Madinah. (Prof Dr Muhammad bin Faris, anNaby wa Yahud al-Madinah, hal 101-120)’ Permusuhan Yahudi semakin meluas dan dilakukan berkelompok. Kasus pelecehan terhadap seorang Muslimah di pasar Bani Qainuqa` berujung pada terbunuhnya pemuda Muslim yang membelanya, Bani Qainuqa` menggalang solidaritas dan menantang secara terbuka, “Hai Muhammad, jangan lekas bangga hanya karena berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka itu hanyalah orang-orang liar yang tidak pandai berperang. Demi Allah, jika kami yang engkau perangi, maka engkau akan merasakan kehebatan kami. Engkau tidak akan pernah merasakan lawan sekuat kami!” (Ibnu Ishaq, Jilid dua hal 129). Dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW pun bersikap tegas. Tantangan Bani Qainuqa’ dijawab dengan tegas. Mereka diperangi. Yahudi Bani Quraizhah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Klan terakhir Yahudi ini berkhianat dengan mendukung pasukan musuh (Ahzab) dalam perang Khandaq. Menghadapi permusuhan kolektif ini, Nabi SAW tidak punya pilihan selain menghukum mereka secara kolektif. Bani Qainuqa` dan Bani Nadhir diusir dari Madinah. Sedang Bani Quraizhah, semua lelakinya yang sanggup berperang dieksekusi. Itulah toleransi Nabi Muhammad SAW terhadap Yahudi. Wallahu a’lam bil-sahawab. ■