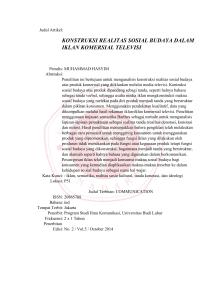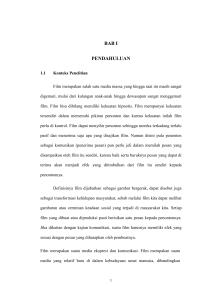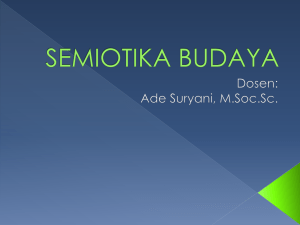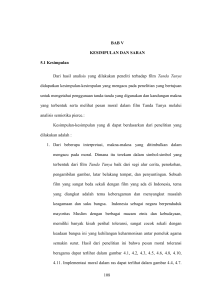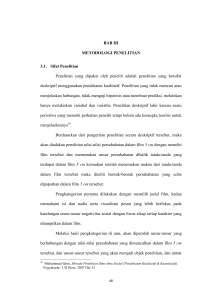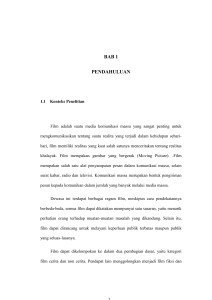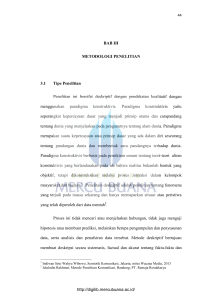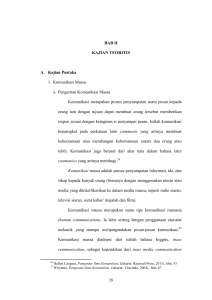BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Perspektif/Paradigma Kajian Guba
advertisement

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Perspektif/Paradigma Kajian Guba dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai serangkaian keyakinankeyakinan dasar (basic beliefs) atau metafisika yang berhubungan dengan prinsipprinsip pokok. Paradigma ini menggambarkan suatu pandangan dunia (world view) yang menentukan bagi pengamat sifat dari “dunia” sebagai tempat individu dan kemungkinan hubungan dengan dunia tersebut beserta bagian-bagiannya (Sunarto dan Hermawan, 2011: 4). Keyakinan-keyakinan ini bersifat dasar dalam pengertian harus diterima secara sederhana semata-mata berdasarkan kepercayaan saja disebabkan tidak ada suatu cara untuk menentukan suatu kebenaran akhir. Paradigma adalah basis kepercayaan atau metafisika utama dari sistem bepikir: basis dari ontologi, epistemologi, dan metodelogi. Paradigama dalam pandangan filosofis, memuat pandangan awal yang membedakan, memperjelas, dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Dengan demikian paradigma membawa konsekuensi praktis berperilaku, cara berpikir, interpretasi dan kebijakan dalam pemilihan terhadap masalah (Salim, 2006: 96). Macam paradigma itu sendiri tertnyata bervariasi. Guba dan Lincoln (1994) menyebutkan empat macam paradigma, yaitu positivisme, post positivisme, konstruktivisme dan kritis. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme kritis (critical constructivism). Paradigma ini adalah penggabungan dari pandangan konstruktivis dengan pandangan kritis yang dikembangkan oleh Frankfurt School. Menurut Ardianto dan Q-Anees (2007) paradigma konstruktivis memandang bahwa semesta secara epistemologi sebagai hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi bermakna terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian dunia muncul dalam pengalaman manusia secara terorganisasi dan bermakna. Keberagaman pola konseptual/kognitif merupakan hasil dari lingkungan historis, kultural, dan personal yang digali secara terus-menerus. Bagi Universitas Sumatera Utara kaum konstruktivisis, semesta adalah suatu konstruksi, artinya bahwa semesta bukan dimengerti sebagai semesta yang otonom, akan tetapi dikonstruksi secara sosial, dan karenanya plural. Konsekuensinya, kaum kontruktivis menganggap bahwa tidak ada makna yang mandiri, tidak ada deskripsi yang murni objektif. Kita tidak dapat secara transparan melihat “apa yang ada di sana” atau “yang ada di sini” tanpa termediasi oleh teori, kerangka konseptual atau bahasa yang disepakati secara sosial. Semesta yang ada di hadapan kita bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan selalu termediasi oleh paradigma, kerangka konseptual, dan bahasa yang dipakai. Masalah kebenaran dalam konteks konstruktivis bukan lagi permasalahan fondasi atau representasi, melainkan masalah kesepakatan pada komunitas tertentu. Sedangkan paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya (Eriyanto, 2001: 6). Teori kritis dapat dianggap sama dengan paradigma konstruktivisme dengan alasan sebagai berikut: (1) teori kritis meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu dikonstruksi atas dasar kepentingan manusiawi; (2) dalam praksis penelitian (dari pemilihan masalah untuk penelitian, instrumen dan metode analisis yang digunakan, interpretasi, kesimpulan dan rekomenasi) dibuat sangat bergantung pada nilai-nilai peneliti; (3) standar penilaian ilmuwan bukan ditentukan oleh prinsip verifikasi atau falsifikasi melainkan didasarkan konteks sosial historis serta kerangka pemikiran yang digunakan ilmuwan. Konstruktivis kritis mengkombinasikan pemikiran yang berkaitan dengan cara manusia berpikir sambil berinteraksi dengan lingkungan sosial (konstruktivis) atau bagaimana makna diperoleh secara sosial dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan di masyarakat, juga konsekuensi etis dari pilihan manusia (kritis). Istilah konstrutivis kritis pertama kali digunakan tahun 1960-an di bidang pendidikan dan kemudian di bidang psikologi (LittleJohn & Foss, 2009: 216). Universitas Sumatera Utara Istilah konstruktivisme kritis—yang juga bisa disebut kontruksionisme kritis— pertama kali dipublikasikan dalam studi komunikasi tahun 1999 di buku Questioning Technology karangan filsuf teknologi Amerika Andrew Feenberg. Kemudian, Maria Bakardijieva memunculkan istilah tersebut secara independen di disertasi doktoral komunikasinya tahun 2002 (dia juga meraih gelar PhD di Sosiologi), yang lalu menjadi awal diterbitkannya buku terkenal The Internet in Everyday Life, yang terbit tahun 2005. Kini, Feenberg dan Bakardjieva adalah tokoh-tokoh terpenting dalam tradisi ini (LittleJohn & Foss, 2009: 216). Keduanya sepaham dengan pendekatan kontruktivis kritis pendidikan yang dikembangkan oleh sekolah berpikir kritis dalam pandangan terhadap perubahan dan berfokus pada gagasan konstruksi untuk menjelaskan proses pemahaman. Namun, para sarjana ini berangkat dari landasan bersama ini dalam pendekatan mereka terhadap kritik. Dari perspektif mereka, konstruktivisme kritis mengacu pada integrasi pembangunan sosial teori realitas, yang diajukan dalam tradisi sosiologi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teori kritis, yaitu, kontribusi filsuf Jerman, Herbert Marcuse dan Jurgen Habermas (LittleJohn & Foss, 2009: 216). Menurut Feenberg, pendekatan kontruktivis kritis mengkritisi pandangan deterministik, yang berpendapat bahwa teknologi membentuk masyarakat dengan sendirinya, independen dari perkembangan utama politik dan kebudayaan. Feenberg membuat tiga dalil: (1) teknologi dibentuk oleh proses sosial di mana pilihan terhadap teknologi dipengaruhi berbagai kriteria kontekstual; (2) proses sosial ini memuaskan berbagai kebutuhan kultural yang berhubungan dengan teknologi; dan (3) definisi kompetitif teknologi mencerminkan pandangan masyarakat yang bertentangan. Karena itulah, pilihan terhadap teknologi dipengaruhi oleh pengaturan kekuatan di dalam masyarakat (LittleJohn & Foss, 2009:216). 2.2 Kajian Pustaka 2.2.1 Semiotika Secara etimologis, kata “semiotika” berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti “tanda” (Sudjiman dan van Zoest, 1996: vii) atau seme, yang berarti Universitas Sumatera Utara “penafsir tanda” (Cobley dan Jansz, 1999:4). Semiotika berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni, logika, retorika, dan poetika (Kurniawan, 2001: 49). Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Barthes menyebutkan bahwa semiotika merupakan suatu ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 2004: 15). Umberto Eco (1979: 4-5) mengatakan bahwa semiotika adalah “ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai, mengelabui, atau mengecoh.” Lebih lanjut lagi, menurutnya “semiotika menaruh perhatian apa pun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut tidak perlu harus ada, atau tanda itu secara nyata ada di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Dengan begitu, semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari apa pun yang bisa digunakan untuk mengatakan sesuatu kebohongan, sebaliknya, tidak bisa digunakan untuk mengatakan kebenaran...” (Berger, 200a: 11-12). Fiske (dalam Bungin, 2005: 67) mengatakan, bahwa semiotika mempunyai tiga bidang studi utama yaitu: a) Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara-cara tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya. b) Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikannya. c) Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri. Universitas Sumatera Utara Di lain pihak, menurut Littlejohn (2009: 55-56) semiotika dapat dibagi ke dalam tiga dimensi kajian, yaitu semantik, sintaktik, dan pragmatik. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: 1. Semantik, berkenaan dengan makna dan konsep. Dalam hal ini membahas bagaimana tanda memiliki hubungan dengan referennya, atau apa yang diwakili suatu tanda. Prinsip dasar dalam semiotika adalah bahwa representasi selalu diperantara atau dimediasi oleh kesadaran interpretasi seorang individu dan setiap interpretasi atau makna dari suatu tanda akan berubah dari suatu situasi ke situasi lainnya (Morrisan, 2009: 29). 2. Sintaktik, berkenaan dengan keterpaduan dan keseragaman, studi ini mempelajari mengenai hubungan antara tanda. Tanda di lihat sebagai bagaian dari sistem tanda yang lebih besar atau kelompok yang diorganisir melalui cara tertentu. Sistem tanda seperti ini biasa disebut dengan kode. Menurut pandangan semiotika, tanda selalu dipahami dalam hubungan dengan tanda lainnya (Morrisan, 2009: 30). 3. Pragmatik, berkenaan dengan teknis dan praktis. Aspek ini mempelajari bagaimana tanda menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia dengan kata lain adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda serta efek yang dihasilkan tanda. Berkaitan pula dengan mempelajari bagaimana pemahaman atau kesalahpahaman terjadi dalam berkomunikasi (Morrisan, 2009: 30). Ada dua pendekatan penting terhadap tanda-tanda yang biasa menjadi rujukan para ahli (Berger, 2000b: 11-22). Pertama, adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand de Sausurre (1857-1913) yang mengatakan bahwa tanda-tanda disusun dari dua elemen, yaitu aspek citra tentang bunyi (semacam kata atau representasi visual) dan sebuah konsep di mana citra bunyi disandarkan (Sobur, 2004: 31). Bagi Sausurre, hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrer (bebas), baik secara kebetulan maupun ditetapkan. Menurut Sausurre, ini tidak berarti “bahwa pemilihan penanda sama sekali meninggalkan pembicara” namun lebih dari itu adalah “tak bermotif” yaitu arbitrer dalam pengertian penanda tidak mempunyai hubungan alamiah dengan petanda (Sausurre, 1996, dalam Berger 2000b:11). Pendekatan kedua adalah pendekatan tanda yang didasarkan pada pandangan seorang filsuf dan pemikir Amerika yang cerdas, Charles Sanders Perce (18391914). Pierce (dalam Berger, 2000b: 14) menandaskan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional Universitas Sumatera Utara dengan tanda-tanda tersebut. Ia menggunakan istilah ikon untuk kesamaannya, indeks untuk hubungan sebab-akibat, dan simbol untuk asosiasi konvensional. Menurut Pierce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Ketiga, kurang lebih, perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebagai simbol (Sobur, 2004: 35). Semiotika memecah-mecah kandungan teks menjadi bagian-bagian, dan menghubungkan mereka dengan wacana-wacana yang lebih luas. Sebuah analisis semiotik menyediakan cara menghubungkan teks tertentu dengan sistem pesan di mana ia beroperasi. Hal ini memberikan konteks intelektual pada isi: ia mengulas cara-cara beragam unsur bekerja sama dan berinteraksi dengan pengetahuan kultural kita untuk menghasilkan makna. Semiotika memiliki keuntungan dalam menghasilkan apa yang disebut Clifford Geertz (1973) sebagai “deskripsi tebal” (thick descriptions) yang berstruktur serta analisis-analisis yang kompleks. Karena sangat subjektif, semiotika tidak reliable dalam konteks pemahaman ilmu pengetahuan sosial tradisional—peneliti lain yang mempelajari teks yang sama dapat saja mengeluarkan sebuah makna yang berbeda (Stokes, 2006: 78). Analisis semiotik biasanya diterapkan pada citra atau teks visual (Berger, 1987; 1998a). Metode ini melibatkan pernyataan dalam kata-kata tentang bagaimana citra bekerja, dengan mengaitkan mereka pada struktur ideologis yang mengorganisasi makna (Stokes, 2006: 78). 2.2.1.1 Semiotika Komunikasi Visual Semiotika sebagai sebuah cabang keilmuan memperlihatkan pengaruh pada bidang-bidang seni rupa, seni tari, seni film, desain produk, arsitektur, termasuk desain komunikasi visual. Menurut Tinarbuko (dalam Piliang, 2012: 339-340) semiotika komunikasi visual yaitu semiotika sebagai metode pembacaan karya komunikasi visual. Dilihat dari sudut pandang semiotika, desain komunikasi visual adalah sistem Universitas Sumatera Utara semiotika khusus, dengan perbendaharaan kata (vocabulary) dan sintaks (sintagm) yang khas, yang berbeda dengan sistem semiotika seni. Fungsi signifikasi adalah fungsi di mana penanda yang bersifat konkrit dimuati dengan konsep-konsep abstrak, atau makna, yang secara umum disebut petanda. Dapat dikatakan di sini, bahwa meskipun semua muatan komunikasi dari bentuk-bentuk komunikasi visual ditiadakan, ia sebenarnya masih mempunyai muatan signifikasi, yaitu muatan makna. Efektivitas pesan menjadi tujuan utama dari desain komunikasi visual. Berbagai bentuk desain komunikasi visual: iklan, fotografi jurnalistik, poster, kalender, brosur, film animasi, karikatur, acara televisi, video klip, web design, cd interaktif adalah di antara bentuk-bentuk komunikasi visual, yang melaluinya pesan-pesan tertentu disampaikan dari pihak pengirim (desainer, produser, copywriter) kepada penerima (pengamat, penonton, pemirsa). Semiotika komunikasi mengkaji tanda konteks komunikasi yang lebih luas, yang melibatkan berbagai elemen komunikasi, seperti saluran, sinyal, media, pesan, kode (bahkan juga noise). Semiotika komunikasi menekankan aspek produksi tanda di dalam berbagai rantai komunikasi, saluran dan media, ketimbang sistem tanda. Di dalam semiotika komunikasi, tanda ditempatkan di dalam rantai komunikasi, sehingga mempunyai peran yang penting dalam penyampaian pesan. 2.2.1.2 Semiotika Roland Barthes Roland Barthes dikenal sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dan semiologi Sausurrean. Dalam studinya, Barthes menekankan pentingnya peran pembaca tanda (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi (Sobur, 2004: 63). Karakteristik semiotika Barthes adalah adanya dua tataran sistem pemaknaan. Dalam Mythologies, sistem pemaknaan tataran pertama disebut denotatif, sedangkan sistem pemaknaan tataran kedua disebut konotatif. Barthes menjelaskan dua tingkat dalam pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. ‘Denotasi’ adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara Universitas Sumatera Utara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Sementara, ‘konotasi’ adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti (artinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsiran). Selain itu, Barthes juga melihat makna yang lebih dalam tingkatnya, akan tetapi lebih bersifat konvensional, yaitu makna yang berkaitan dengan mitos. Mitos, dalam pemahaman semiotika Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial (yang sebetulnya arbitrer atau konotatif) sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Gambar 2.1 Peta Tanda Roland Barthes 1. signifier (Penanda) 2. signified (Petanda) 3. denotative sign (tanda denotatif) 4. CONNOTATIVE SIGNIFIER (PENANDA KONOTATIF) 5.CONNOTATIVE SIGNIFIED (PETANDA KONOTATIF) 6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) Sumber : Cobley, Paul & Jansz, Litza. (1999). Introducing Semiotics. New York: Totem Books, hlm. 51 Dari peta tanda Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari penanda (1) dan petanda (2), namun bersamaan pula dengan tanda denotatif menjadi penanda konotatif (4). Tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan tapi mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai ‘mitos’, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu Universitas Sumatera Utara (Budiman, 2001: 28). Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau, dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Barthes memampatkan ideologi dengan mitos karena, baik di dalam mitos maupun ideologi, hubungan antara penanda konotatif dan petanda konotatif terjadi secara termotivasi (Budiman, 2001: 28). Seperti Marx, Barthes juga memahami ideologi sebagai kesadaran palsu yang membuat orang hidup di dalam dunia yang imajiner dan ideal, meski realitas hidupnya yang sesungguhnya tidaklah demikian. Menurut Roland Barthes tuturan mitologis bukan hanya berupa tuturan oral, namun tuturan itu bisa saja berbentuk tulisan, fotografi, film, laporan ilmiah, olah raga, pertunjukan, iklan, lukisan. Mitos pada dasarnya adalah segala yang mempunyai modus representasi. Artinya, paparan contoh di atas memiliki arti yang belum tentu bisa ditangkap secara langsung (Iswidayanti, 2006). Bagi Roland Barthes, di dalam teks beroperasi lima kode pokok (five major code) yang di dalamnya terdapat penanda teks (leksia). Lima kode yang ditinjau Barthes yaitu (Sobur, 2004: 65-66) : 1. Kode hermeneutik atau kode teka-teki berkisar pada harapan pembaca untuk mendapatkan “kebenaran” bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Kode teka-teki merupakan unsur struktur yang utama dalam narasi tradisional. Di dalam narasi ada suatu kesinambungan antara pemunculan suatu peristiwa teka-teki dan penyelesaiannya di dalam cerita. 2. Kode proaretik, atau kode tindakan/lakuan dianggap sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca orang, yang artinya antara lain semua teks bersifat naratif. Secara teoritis Barthes melihat semua lakuan dapat dikodifikasi. Pada praktiknya ia menerapkan beberapa prinsip seleksi. Kita mengenal kode lakuan atau peristiwa karena kita dapat memahaminya. 3. Kode simbolik, merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural, atau tepatnya menurut konsep Barthes, pascastruktural. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa makna berasal dari beberapa oposisi biner atau pembedaan—baik dalam taraf bunyi menjadi fonem dalam proses produksi wicara, maupun pada taraf oposisi psikoseksual yang melalui proses. Pemisahan dunia secara kultural dan primitif menjadi kekuatan dan nilai-nilai yang berlawanan yang secara mitologis dapat dikodekan. 4. Kode kultural atau gnomik merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Menurut Barthes, realisme tradisional didefenisi oleh acuan budaya apa yang telah diketahui. Rumusan suatu budaya atau subbudaya adalah hal-hal kecil yang telah dikodifikasi yang di atasnya penulis bertumpu. Universitas Sumatera Utara 5. Kode semik atau kode konotatif banyak menawarkan banyak sisi. Dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema suatu teks. Ia melihat bahwa konotasi kata atau frase tertentu dalam teks dapat dikelompokkan dengan konotasi kata atau frase yang mirip. Jika kita melihat suatu kumpulan konotasi, kita menemukan suatu tema di dalam cerita. Jika sejumlah konotasi melekat pada suatu nama tertentu, kita dapat mengenali suatu tokoh dengan atribut tertentu. Di samping penanda teks (leksia) dan lima kode pembacaan yang telah dijabarkan di atas, beberapa konsep penting dalam analisis semiotika Roland Barthes adalah: 1. Penanda dan Petanda Menurut Sausurre, bahasa merupakan sebuah sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu penanda (signifier) dan petanda (signified). Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah “bunyi yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”. Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa: apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca . Petanda adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi petanda adalah aspek mental dari bahasa (Bertens, 2001: 180). Menurut Sausurre, penanda dan petanda merupakan kesatuan seperti dua sisi dari sehelai kertas. Sausurre menggambarkan tanda yang terdiri atas signifier dan signified itu sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara Gambar 2.2 Elemen-Elemen Makna Sausurre Sign Composed of signification Signifier plus signified external reality of meaning Sumber: Sobur, Alex. (2004). Analisis Teks Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Pada dasarnya apa yang disebut signifier dan signified tersebut adalah produk kultural. Setiap tanda kebahasaan, menurut Sausurre, pada pada dasarnya menyatukan sebuah konsep (concept) dan suatu citra suara (sound image), bukan menyatakan sesuatu dengan sebuah nama. Suara yang muncul dari sebuah kata yang diucapkan merupakan penanda (signifier) sedangkan konsepnya adalah petanda (signified). Dua unsur ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Pemisahan hanya akan menghancurkan ‘kata’ tersebut. 2. Denotasi dan Konotasi Denotasi biasanya dimengerti sebagai makna harfiah, makna yang “sesungguhnya”, bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. Proses signifikasi yang secara tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti sesuai dengan apa yang terucap (Sobur, 2004: 70). Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting di dalam ujaran. Universitas Sumatera Utara Denotasi bersifat langsung, dapat dikatakan sebagai makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, sehingga sering disebut sebagai gambaran sebuah petanda. Sedangkan menurut Kridalaksana, denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu. Makna denotatif suatu kata ialah makna yang biasa kita temukan dalam kamus. Makna konotatif ialah makna denotatif ditambah dengan segala gambaran, ingatan, dan perasaan yang ditimbulkan oleh kata itu. Kata konotasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin connotare, "menjadi tanda" dan mengarah kepada makna-makna kultural yang terpisah/berbeda dengan kata (dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi). Denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam tingkat pertama dalam sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting di dalam ujaran. (Lyons, dalam Pateda, 2001: 98). Makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda (Berger, 2000b: 55). Harimurti Kridalaksana (2001: 40) mendefinisikan denotasi (denotation) sebagai "makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu; sifatnya objektif." Sedangkan konotasi (connotation, evertone, evocatory) diartikan sebagai "aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca)". Dengan kata lain, "makna konotatif merupakan makna leksikal + X" (Sobur, 2004: 263). Makna denotatif (denotative meaning) disebut juga dengan beberapa istilah lain seperti makna denotasional, makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial, atau makna proporsional (Keraf, 1994: 28). Disebut makna denotasional, referensial, konseptual, atau ideasional, karena makna itu menunjuk (denote) kepada suatu referen, konsep, atau ide tertentu dari suatu referen. Disebut makna kognitif karena makna itu bertalian dengan kesadaran atau pengetahuan; stimulus (dari pihak pembicara) dan respons (dari pihak pendengar) menyangkut hal-hal yang dapat diserap pancaindra (kesadaran) dan rasio manusia. Dan makna ini disebut juga makna proposisional karena ia bertalian Universitas Sumatera Utara dengan informasi-informasi atau pernyataan-pernyataan yang bersifat faktual. Makna ini, yang diacu dengan bermacam-macam nama, adalah makna yang paling dasar pada suatu kata (Sobur, 2004: 265). Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif (Keraf, 1994: 29). Makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan sebagainya pada pihak pendengar; di pihak lain, kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa pembicaranya juga memendam perasaan yang sama (Sobur, 2004: 266). Makna konotatif sebuah kata dipengaruhi dan ditentukan oleh dua lingkungan, yaitu lingkungan tekstual dan lingkungan budaya (Sumardjo & Saini, 1994: 126). Yang dimaksud dengan lingkungan tekstual ialah semua kata di dalam paragraf dan karangan yang menentukan makna konotatif itu. Pengaruh lingkungan budaya menjadi jelas kalau kita meletakkan kata tertentu di dalam lingkungan budaya yang berbeda (Sobur, 2004: 266). Di dalam semiologi Roland Barthes dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna dan, dengan demikian, sensor atau represi politis. Sebagai reaksi yang paling ekstrem melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif, Barthes mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi semata-mata. Penolakan ini mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap berguna sebagai sebuah koreksi atas kepercayaan bahwa makna “harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (Budiman, 1999: 22 dalam Sobur, 2004: 71). 3. Paradigmatik dan Sintagmatik Di dalam konteks strukturalisme bahasa, tanda tidak dapat dilihat hanya secara individu, akan tetapi dalam relasi dan kombinasinya dengan tanda-tanda lainnya di dalam sebuah sistem. Analisis tanda berdasarkan sistem atau kombinasi yang lebih besar ini (kalimat, buku, kitab) melibatkan apa yang disebut aturan Universitas Sumatera Utara pengkombinasian yang terdiri dari dua aksis, yaitu aksis paradigmatik, yaitu cara pemilihan dan pengkombinasian tanda-tanda, berdasarkan aturan atau kode tertentu, sehingga dapat menghasilkan sebuah ekspresi bermakna. Bahasa adalah struktur yang dikendalikan oleh aturan main tertentu, semacam mesin untuk memproduksi makna. Dalam bahasa, kita harus mematuhi aturan main bahasa (grammar, sintaks) jika kita ingin menghasilkan ekspresi yang bermakna. Aturan main pertama dalam bahasa, menurut Sausurre adalah: bahwa di dalam bahasa hanya ada prinsip perbedaan. Misalnya, tidak ada hubungan keharusan antara kata topi dan sebuah benda yang kita pakai sebagai penutup kepala kita: apa yang memungkinkan terjadinya hubungan adalah perbedaan antara topi, tapi, tepi, kopi, dan seterusnya. Kata-kata mempunyai makna disebabkan mereka berada di dalam relasi perbedaan. Jadi, yang pertama-tama dilihat di dalam strukturalisme bahasa adalah relasi, bukan hakikat tanda itu sendiri. Perbedaan dalam bahasa, menurut Sausurre, hanya dimungkinkan lewat beroperasinya dua aksis bahasa yang disebutnya aksis paradigma dan aksis sintagma. Paradigma adalah satu perangkat tanda yang melaluinya pilihan-pilihan dibuat, dan hanya satu unit dari pilihan tersebut dapat dipilih. Sintagma adalah kombinasi tanda dengan tanda lainnya dari perangkat yang ada berdasarkan aturan tertentu, sehingga menghasilkan ungkapan bermakna (Piliang, 2012: 302-303). Gambar 2.3 Poros Paradigma dan Sintagma Sintagma Paradigma Sumber: Piliang, Yasraf Amir. Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna (2012), hlm. 303 Universitas Sumatera Utara Menurut semiotika Sausurrean, apa pun bentuk pertukaran tanda, ia harus mengikuti model kaitan struktural antara penanda dan petanda yang bersifat stabil dan pasti (Sobur, 2004: 278). 4. Mitos Pada umumnya mitos adalah suatu sikap lari dari kenyataan dan mencari "perlindungan dalam dunia khayal". Sebaliknya dalam dunia politik, mitos kerap dijadikan alat untuk menyembunyikan maksud-maksud yang sebenarnya, yaitu membuka jalan, mengadakan taktik untuk mendapat kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan "melegalisasikan" sikap dan jalan anti-sosial. Tujuan dari suatu mitos politi adalah selalu kekuasaan dalam negara, karena dianggap bahwa tanpa kekuasaan keadaan tidak dapat diubahnya (Susanto, 1985: 220). Demikianlah mitos mudah menjadi "alat kekuasaan" yang sukar dibuktikan kebenarannya selama tujuan mitos belum menjadi kenyataan, maka apa yang dijanjikan oleh mitos masih saja dapat diproyeksikan ke masa "lebih ke depan" lagi (Sobur, 2004: 223-224). Mitos dalam pandangan Lappe & Collins (Rahardjo, 1996: 192) dimengerti sebagai sesuatu yang oleh umum dianggap benar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan fakta," sekalipun perlu dicatat bahwa penafsiran fakta oleh Lappe & Collins itu belum tentu benar atau disetujui oleh masyarakat ilmiah pada umumnya. Apa yang disebut Lappe & Collins sebagai mitos itu adalah jenis "mitos modern". Dalam bukunya Mythology (1991, dikutip Rahardjo, 1996: 192), Fernand Comte memang membagi mitos menjadi dua macam: mitos tradisional dan mitos modern. Mitos modern itu dibentuk oleh dan mengenai gejala-gejala politik, olah raga, sinema, televisi dan pers. Mitos (mythes) adalah suatu jenis tuturan (a type of speech), sesuatu yang hampir mirip dengan sesuatu yang hampir mirip dengan "representasi kolektif" di dalam sosiologi Durkheim (Budiman, 1999: 76). Barthes mengartikan mitos sebagai "cara berpikir kebudayaan tentang sesuatu, sebuah cara mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu hal. Barthes menyebut mitos sebagai rangkaian konsep yang saling berkaitan" (Sudibyo, 2001: 245). Mitos adalah sistem komunikasi, sebab ia membawakan pesan. Maka, mitos bukanlah Universitas Sumatera Utara objek. Mitos bukan pula konsep atau suatu gagasan, melainkan suatu cara signifikasi, suatu bentuk. Lebih jauhnya lagi, mitos tidak ditentukan oleh objek ataupun suatu gagasan, melainkan cara mitos disampaikan. Mitos tidak hanya berupa pesan yang disampaikan dalam bentuk verbal (kata-kata lisan ataupun tulisan), namun juga dalam berbagai bentuk lain atau campuran antara bentuk verbal dan nonverbal. Misalnya dalam bentuk film, lukisan fotografi, iklan, dan komik (Sobur, 2004:224). 2.2.2 Video Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidi-visum yang artinya melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat melihat (K. Prent dkk., 1969: 926). Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 1119) mengartikan video dengan: 1) bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; 2) rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Senada dengan itu, Peter Salim dalam The Contemporary English-Indonesian Dictionary (1996: 2230) memaknainya dengan sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan dan pemancaran gambar. Tidak jauh berbeda dengan dua definisi tersebut, Smaldino (2008: 374) mengartikannya dengan “the storage of visuals and their display on television-type screen” (penyimpanan/perekaman gambar dan penayangannya pada layar televisi) (Amien & Lamere, 2010). Video, dilihat sebagai media penyampai pesan, termasuk media audio-visual atau media pandang-dengar (Setyosari & Sihkabuden, 2005: 117). Media audiovisual dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, dinamakan media audio-visual murni; dan kedua, media audio-visual tidak murni. Film bergerak (movie), televisi, dan video termasuk jenis yang pertama, sedangkan slide, opaque, OHP dan peralatan visual lainnya yang diberi suara termasuk jenis yang kedua (Munadi, 2008: 113). Perkembangan video sebagai media komunikasi tak lepas dari eksistensi fotografi. 'Foto bergerak' pertama berhasil dibuat pada tahun 1877 oleh Eadward Muybridge, fotografer Inggris yang bekerja di California. Mubridge mengambil serangkaian gambar foto kuda berlari, mengatur sederetan kamera dengan benang tersambung pada kamera shutter. Prosedur Mubridge mempengaruhi para penemu Universitas Sumatera Utara di pelbagai negara dalam mengembangkan perekam citra bergerak. Salah satu dari mereka adalah Thomas Edison (1847-1931) yang untuk pertama kalinya mengembangkan kamera citra bergerak pada 1888 ketika ia membuat film sepanjang 15 detik yang merekam salah seorang asistennua ketika sedang bersin. Segera sesudah itu, di tahun 1895, Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere (18641948) memberikan pertunjukan film sinematik kepada umum di sebuah kafe di Paris. Dengan demikian lahirlah teknologi dan seni gambar bergerak (motion picture) yang mungkin merupakan sebentuk seni paling berpengaruh dalam abad yang lalu. Jika saat ini kita hidup dalam dunia yang 'termediasi-secara-visual'— sebuah dunia tempat citra visual membentuk gaya hidup dan mengajarkan pelbagai nilai perilaku, kebiasaan dan gaya hidup—kita berhutang pertama-tama dan yang terutama pada film. Media berbasis penglihatan dan yang diperkuat oleh penglihatan menjadi begitu umum dan kita hampir tidak menyadari betapa mereka menjadi demikian intrinsik di dalam tatanan signifikasi modern (Danesi, 2010: 133). Film juga sebetulnya tidak jauh beda dengan televisi. Namun, film dan televisi memiliki bahasa yang berbeda (Sardar & Loon, 2001: 156). Tata bahasa itu terdiri atas semacam unsur yang akrab, seperti pemotongan (cut), pemotretan jarak dekat (close-up), pemotretan dua (two shot), pemotretan jarak jauh (long shot), pembesaran gambar (zoom-in), pengecilan gambar (zoom-out), memudar (fade), pelarutan (dissolve), gerakan lambat (slow motion), gerakan yang dipercepat (speeded-up), efek khusus (special effect). Namun, bahasa tersebut juga mencakup kode-kode representasi yang lebih halus, yang tercakup dalam kompleksitas dari penggambaran visual yang harfiah hingga simbol-simbol yang paling abstrak dan arbitrer serta metafora. Metafora visual sering menyinggung objek-objek dan simbol-simbol dunia nyata serta mengonotasikan makna-makna sosial dan budaya. Berbeda dari permasalahan “tanda” bahasa di mana hubungan bersifat arbitrer (semena) antara tanda (demikian pun antara significant dan signifie) dan benda (choses), penanda (significant) sinematografis memiliki hubungan “motivasi” atau “beralasan” (motivation) dengan penanda yang tampak jelas melalui hubungan Universitas Sumatera Utara penanda dengan alam yang dirujuk. Petanda sinematografis selalu kurang lebih, kata Christian Metz, “beralasan” dan tidak pernah semena. Hubungan motovasi itu berada baik pada tingkat denotatif maupun konotatif. Hubungan denotatif yang beralasan itu lazim disebut analogi, karena memiliki persamaan perseptif/auditif antara penanda/petanda dan referen. Perlu diketahui bahwa analogi ini hanyalah salah satu bentuk dari motivasi karena konotasi sinematografis juga termasuk di dalamnya. Meskipun analogi perseptif/auditif bukanlah prasyarat keberadaannya, Metz menggarisbawahi tesis tentang polisemi motivasi dari Eric Buyyens dengan mengatakan bahwa konotasi sinematografis bersifat simbolis: petanda memotivasi penanda, tetapi melampauinya (Masak, 2000: 283 dalam Sobur, 2004: 13). 2.2.2.1 Teknik dalam Pengambilan Gambar Tabel 2.1 Teknik Pengambilan Gambar Pengambilan Gambar Extreme Long Shot Kesan luas dan keluarbiasaan Full Shot Hubungan Sosial Big Close Up Emosi, dramatik, momen penting Close Up Intim atau dekat Medium Shot Hubungan personal dengan subjek Long Shot Konteks perbedaan dengan publik Sudut Pandang (Angle) Pengambilan Gambar High Dominasi, kekuasaan dan otoritas Eye-Level Kesejajaran, kesamaan dan sederajat Universitas Sumatera Utara Tabel 2.1 (sambungan) Low Didominasi, dikuasai, dan kurang otoritas Fokus Selective Focus Meminta perhatian (tertuju pada satu objek) Soft focus Romantis serta nostalgia Deep Focus Semua unsur adalah penting Pencahayaan High Key Riang, cerah Low Key Suram, muram High Contrast Dramatikal, teatrikal Low Contrast Realistik dan terkesan dokumenter Sumber: Selby, Keith & Coedery, Ron. (1995). How to Study Television. London: Mc Millisan Universitas Sumatera Utara 2.3 Model Teoritik Gambar 2.4 Bagan Model Teoritik Konstruksi Makna dalam Video Takotak Miskumis Karya Cameo Project Objek Penelitian Scene dan lirik lagu pada Video Takotak Miskumis karya Cameo Project Semiotika Roland Barthes -Analisis Leksia dan 5 Kode Pembacaan -Denotasi dan Konotasi -Mitos Level Analisis -Teks (gambar/scene, lirik lagu) -Konteks (sosial, budaya, sejarah, politik) -Pemaknaan dalam video -Mitos Universitas Sumatera Utara