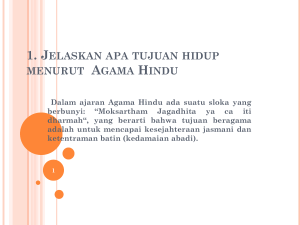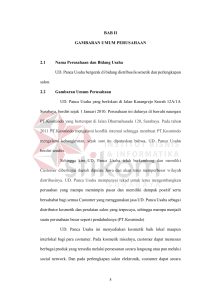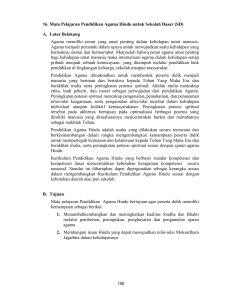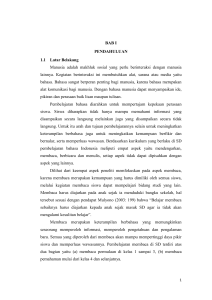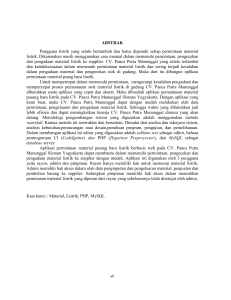caru panca sata simbol keharmonisan manusia
advertisement

1 CARU PANCA SATA SIMBOL KEHARMONISAN MANUSIA DENGAN KOSMOS Oleh I Made Arista Dosen Fakultas Pendidikan Agama dan Seni UNHI Denpasar E-mail: [email protected] ABSTRAK Caru dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut sarana, pemanfaatan dan fungsi, diantaranya: caru eka sata, panca sata, panca sanak, panca kelud, rsi gana, dan lain sebagainya. Hal ini diamanatkan oleh “Bhagawad Gita” sebagai perputaran Cakra Yadnya ‘berkurban secara timbal balik antara Tuhan dengan manusia’. Salah satu tindakan yang mengikuti konsep cakra yadnya ialah Caru Panca Sata. Sarana dan praktek caru ini, tertanam berbagai simbol keharmonisan manusia dengan kosmos/alam secara sekala maupun niskala. Bagi umat Hindu, hal ini tidak bisa diabaikan, karena naskah-naskah Hindu sejak lama telah menyadari dan meramalkan kerusakan alam yang akan terjadi. Kata Kunci: Caru Panca Sata, harmonis, manusia, kosmos I. PENDAHALUAN Manusia dan alam merupakan satu kesatuan, seperti yang dinyatakan oleh Anton Bakker (1995) bahwa, alam semesta tidak dapat dipahami tanpa ada manusia dan manusia tidak dapat dipahami tanpa ada alam. Keduanya saling membutuhkan, saling mengisi dan selalu berinteraksi. Kesejahteraan manusia tidak terlepas dari eksistensi alam. Alam lestari karena tindakan arif manusia. Senada dengan itu, Frintjof Capra (2001: 13) menyatakan hubungan kosmos atau alam dengan manusia, dipandang sebagai suatu realitas yang tak terpisah; selamannya berada dalam gerak, hidup, organik; bersifat spiritual dan material pada waktu yang bersamaan. 2 Khusus dalam pandangan Hindu, seperti dinyatakan oleh Prof. Dr. I Gusti Ngurah Nala (1995: 4, dalam Suda (ed), 2010: 6) bahwa: di alam semesta ini harus ada keseimbangan antara unsur yang tidak hidup, disebut dengan Panca Mahabhuta, meliputi: teja ‘sinar matahari’, apah ‘air’, bayu ‘udara’, pertiwi ‘tanah’, dan akasa ‘ether’, dengan unsur hidup yang disebut sarwa prani”. Unsur-unsur tersebut merupakan inti dari siklus kosmos dan atau kelimanya saling bersinergi dalam bhuana alit ‘tubuh manusia’ dan bhuana agung ‘alam semesta’. Dalam konteks ini, Bhuta Yadnya merupakan simbol penetralisir kekuatan-kekuatan destruktif atau tenaga penghancur Panca Maha Bhuta. Dengan harapan, alam semesta dan isinya menjadi bhuta hita ‘makhluk harmoni’ seperti yang diamanatkan dalam Sarascamuscaya 135 (Kajeng, 1997). Dan sebaliknya tidak menjadi bhuta krodha ‘makhluk penghancur’. Jika manusia arogan terhadap alam, tentu alam juga membalas dengan kemurkaan. Tindakan illegal loging ‘penebangan hutan sembarangan’ berdampak tanah longsor, erosi, banjir dan lain sebagainya. Lalu siapa yang disalahkan? Dengan melihat masalah tersebut, ternyata spirit keharmonisan antara manusia dengan alam telah diingkari oleh sebagian besar manusia modern. Masuknya “kapitalisme” dan isme-isme sejenis dapat memudarkan berbagai kearifan lokal tentang pelestarian lingkungan. Jika dihayati, lingkungan sangat berperan dan atau berarti luar biasa bagi kehidupan manusia. Karena sejalan eksistensi kehidupan manusia, lingkungan menyediakan berbagai limpahan kebutuhan pokok; sandang, pangan, papan hingga kebutuhan rohani. Melihat jasa alam begitu luar biasa bagi manusia, semestinya manusia tidak angkuh terhadap alam. Jika alam terusik, sesekali ia menampakkan kemurkaan. Lihat saja banjir bandang di Wasior (Papua) yang terjadi baru-baru ini, telah mengingatkan kita pada keganasan alam yang terusik. 3 Oleh masyarakat Hindu di Bali, keharmonisan manusia dengan alam disebut palemahan. Hubungan seperti ini tidak hanya dilakukan dengan lingkungan, juga dengan Sang Pencipta/Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Parhyangan) dan sesama manusia (Pawongan). Kesatuan segitiga harmonisasi universal ini disebut Tri Hita Karana. Konsep ini menjadi landasan dasar kehidupan masyarakat Hindu di Bali, dalam tatanan agama, adat, budaya, ekonomi, individu dan sebagainya. Konsep ini telah diakui oleh dunia internasional sebagai maskot world peace ‘perdamaian dunia, keharmonisan dunia’. Pengamalan konsep tersebut pada hakekatnya menghantarkan manusia menuju Moksartham jagadhita ya ca iti dharma ‘kebahagiaan di dunia dan akhirat’. Khusus dengan palemahan, juga tersirat dalam upacara, seperti; bhuta yadnya merupakan kegiatan hidup untuk ber-yadnya kepada alam, karena alam sudah sedemikian besar ber-yadnya kepada manusia (Wiana, 2007: 166). Yadnya berupa simbol-simbol ini dipraktekan lewat masegeh, tawur, pakelem dan mecaru. Caru dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut sarana, pemanfaatan dan fungsi, diantaranya: caru eka sata, panca sata, panca sanak, panca kelud, rsi gana, dan lain sebagainya. Hal ini diamanatkan oleh “Bhagawad Gita” sebagai perputaran Cakra Yadnya ‘berkurban secara timbal balik antara Tuhan dengan manusia’: Evam pravartitam cakram nānuvartayatītha yah, aghāyur indiyārāmo mogham pārtha sa jīvati (B. G. III. 16) ‘Dia yang didunia ini tidak ikut memutar roda (cakra yadnya) yang sudah ditetapkan untuk selalu bergerak, adalah jahat di dalam sifatnya, hanya pemuasan indria saja yang menjadi tujuan hidupnya dan orang seperti itu wahai Partha (Arjuna) akan hidup sia-sia’ (Pudja, 2004: 88). Salah satu tindakan yang mengikuti konsep cakra yadnya ialah Caru Panca Sata. Sarana dan praktek caru ini, tertanam berbagai simbol keharmonisan manusia dengan kosmos/alam secara sekala ‘nyata’ maupun 4 niskala ‘tak nyata’. Bagi umat Hindu, hal ini tidak bisa diabaikan, karena naskah-naskah Hindu sejak lama telah menyadari dan meramalkan kerusakan alam yang akan terjadi. Sehingga ajaran Hindu banyak mengandung nilai pelestarian alam. Meminjam teori ekosentrisme bahwa etika terpusat pada seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun tidak, sehingga kewajiban moral untuk menjaga tidak hanya pada mahkluk hidup namun juga pada unsur alam yang tidak hidup (Keraf, 2010: 92-93). Sebaliknya manusia saat ini sebagai penganut paham antroposentrisme: manusia sebagai pusat kosmos atau alam semesta. Maka dari pada itu, muncul egoisme manusia terhadap alam. Lahirnya ekosentrisme sebenarnya untuk mengikis antroposentrime, dan dalam usaha memperjuangkan hak asasi lingkungan yang “diperkosa”. Fenomena pemerkosaan alam dilukiskan oleh Anton Bakker, (1995: 6) bahwa: “Bumi kita adalah dalam bahaya: manusia sedang membongkar kekayaan makhluk-makhluk yang menjadi ‘rekannya’ di bumi ini, dan sedang mengosongkan dan malahan meracun lingkungannya”. Memang benar, segala yang ada di alam ini telah mengandung racun, dari yang tampak – tak tampak, besar – kecil, seperti: tanah, air, udara, manusia, tumbuhan, hewan, eter (ozon). Maka dari pada itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Caru Panca Sata dan caru/tawur yang lain parlu digali dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat modern dan global. II.PEMBAHASAN 2.1. Pengertian, Bentuk dan Pelaksanaan Caru Panca Sata 2.1.1. Pengertian Caru Panca Sata Ritus Hindu memiliki keragaman bentuk, jenis, fungsi, dan makna. keberagaman ini disebabkan oleh tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Secara umum keberagaman ini dirangkum dalam Panca Yadnya ‘lima jenis korban suci atau tindakan yang dilakukan secara tulus iklas’: (1) Dewa 5 Yadnya ‘yadnya kepada para Dewa’; (2) Pitra Yadnya ‘yadnya kepada leluhur dan orang tua’; (3) Rsi Yadnya ‘yadnya kepada rohaniawan dan guru’; (4) Manusa Yadnya ‘yadnya kepada sesama manusia’ dan (5) Bhuta Yadnya ‘yadnya kepada makhluk halus dan lingkungan’. Pengelompokan ke dalam lima jenis yadnya tersebut, didasari oleh konsep Tri Rna ‘tiga hutang yang harus dibayar oleh manusia’. Begitu gencar yadnya di Bali dilaksanakan, atau dapat dikatakan tiada yadnya setiap hari yang terlewatkan. Dari yadnya terkecil hingga terbesar selalu ada dalam bingkai keagamaan dan kebudayaannya. Walaupun demikian, sebagian besar masyarakat Bali dihadapkan dengan masalahmasalah mendalam, seperti; mereka melakukan yadnya secara rutin, namun bila ditanya tentang, makna, nilai, arti yadnya yang dilakukan, terkadang “bingung” dan “tidak tahu” dalam benak mereka. Hal ini tidak bisa disalahkan begitu saja, mungkin karena umat Hindu di Bali sejak lama telah menjalankan agama dengan praktek langsung dan jarang para pendahulu untuk menceritakan apa sebearnya terkandung dalam sebuah yadnya. Minat baca rendah menyebabkan teks-teks keagamaan jarang dibaca atau Hindu sejak lama bukan “agama kitab”, yang terpusat pada satu kitab suci baku atau dogma. Pada lain sisi, teks-teks keagamaan hanya diketahui dan dipegang oleh Geria atau rohaniawan. Penekanan konsep aywa/aja wera ‘tidak boleh diremehkan’ pula menjadi penyebab utama. Namun agama-agama Smit terpusat mengamalkan “perintah” kitab suci. Seperti pelaksanaan Caru Panca Sata, jarang diketahui maknanya, padahal ritual ini sering dipraktekakan. Oleh kerena itu, untuk mengetahui secara menyeluruh, terlebih dahulu berangkat dari pengertian Caru Panca Sata. Secara etimologi Caru Panca Sata terdiri kata Caru, Panca, dan Sata. Caru dalam kitab “Swara Samhita” artinya harmonis atau cantik (Wiana, 2007: 174). Panca ‘lima’ (Zoetmulder, 2004: 751) dan Sata ‘ayam’ (Panitia Penyusun, 1978: 503; Zoetmulder, 2004: 1054). Jadi Caru Panca Sata adalah 6 suatu bentuk persembahan yang terbuat dari lima jenis ayam, disembelih dan diolah menjadi simbol-simbol berupa jenis-jenis makanan khas Bali untuk menjamu Bhuta Kala supaya harmonis. Dapat dikatakan Caru Panca Sata merupakan makanan atau sebagai perjamuan terhadap para bhuta dan kala berjumlah lima, berada pada posisi Timur, Selatan, Barat, Utara dan Tengah. Ajaran agama Hindu yang mendasari tata pelaksanaan macaru adalah konsep krodha ‘marah’ dan (menjadi) somya ‘ruatan’. Meruat dari sifat yang destruktif menjadi yang konstruktif, dari yang merusak menjadi harmonis, dari sekala ke niskala, dari kemarahan menjadi kedamaian. 2.1.2. Bentuk Caru Panca Sata Secara umum Caru Panca Sata terbuat dari bahan utama berupa lima jenis/warna ayam yang disembelih (putih, biying, putih syungan, hitam dan brumbun), bayang-bayang/layang-layang ‘kulit, bulu, kepala, kaki dan sayap tetap utuh melekat pada kulit’. Darah dipisahkan berdasarkan jenis ayam, dipakai untuk melengkapi tetandingan (mentah dalam takir daun pisang) dan sebagai campuran urab barak. Masing-masing daging ayam diolah menjadi sate lembat ‘tumbukan daging dicampur dengan bumbu Bali dan kelapa parut’, ususnya diolah menjadi sate asem dan serapah ‘usus atau daging yang direbus ditusuk dengan bambu kecil yang diraut (katikan), 3 irisan tiap katik’. Begitu pula disertakan urab barak, urab putih, sayur, garam, balung ‘tulang’. Jumlah sate dan bayuhan dari masing-masing ayam ditentukan dengan urip/neptu ‘hitungan angka-angka mistis dihubungkan dengan arah mata angin’, seperti: (1) Ayam putih dengan urip 5, arah Timur; (2) ayam biying ‘merah’ urip 9, arah Selatan; (3) ayam putih siyungan urip 7, arah Barat; (4) ayam hitam urip 4, arah Utara dan (5) ayam brumbun urip 8, arah Tengah (lihat pula dalam tabel di bawah). 7 Bayang-bayang ditata dan dibentangkan di atas sengkui, di lengkapi dengan sorohan banten caru, tumpeng dan nasi menurut warna, urip masingmasing ayam atau arah mata angin. Masing-masing dilengkapi dengan sanggah cucuk, diatasnya diletakkan banten dananan. Tetabuhan (arak, berem dan air) dimasukkan dalam cambeng. Masing-masing jenis ayam dilengkapi dengan sanggah cucuk. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No Ayam Arah Urip Warna Bhuta Dewa Aksara 1 Putih Timur 5 Putih Jangitan Iswara Sa (Sang) 2 Biying Selatan 9 Merah Langkir Brahma Ba (Bang) 3 Putih Barat 7 Kuning Lembukanya Mahadewa Ta (Tang) Siungan 4 Hitam Utara 4 Hitam Taruna Wisnu A (Ang) 5 Brumbun Tengah 8 Panca Tiga Sakti Siwa I (Ing) Warna Disamping itu, dilengkapi pula dengan soroan: peras, penyeneng, pengambeyan dan lain sebagainya, untuk banten pesaksi ‘bentuk persembahan untuk memohon saksi’ ke Surya. Banten pemiak kala, prayascita, durmangala sebagai pebersihan. 2.1.3. Pelaksanaan Caru Panca Sata Setelah upakara Caru Panca Sata tertata pada tempat ritual, Pemangku lalu ngantebang ‘menghantarkan, mempersembahkan, memantrai’ caru. Terlebih dahulu dilakuakan dengan mantra penyucian diri, dan memohon tirtha penglukatan. Selanjutnya Mebiakala/byakaonan, matur piuning ‘memohon saksi kepada Ida Hyang Widhi Wasa dalam prabawa sebagai Sang Hyang Surya Raditya’ di hadapan sanggar surya. Dilanjutkan dengan makalahias/pebersihan/nyapsap ‘pembersihan secara niskala’. Puncaknya: 8 ngaturang caru (ngundang bhuta, penyuguhan kepada bhuta, ngewaliang ‘mengembalikan’ bhuta agar menjadi Dewa), nuludang sanggah cukcuk ke arah tengah, dan ngerarung caru. Adapun mantra Caru Panca Sata yang lazim dipakai oleh pemangku dalam ngantebang upakara ini adalah: Ong Sang bhūta Janggitan, aneng pūrwa, pĕţak warņa nira, pañca uripnya, Sang Bhūta Langkir aneng daksina, abang warna nira, sanga uripnya. Sang Bhuta Lĕmbukanya, aneng pascima, pita warna nira, sapta uripnya. Sang Bhuta Taruna aneng uttara, krsna warna nira, catur uripnya. Sang Bhuta Tiga Sakti, aneng Madhya, manca warna warna nira, asta uripnya. Mapupul ta sira kabeh, den amangan caru, wus sira amangan anginum caru iki, pamantuka sira ring desa soangsoang, anadi watĕking dewata kabeh, angradana urip waras, tĕguh timbul, akulit tĕmaga, aotot kawat, awalung wĕsi, mangkana de nira nugraha ring sang adruwe caru. Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, Ang Ung Mang. Ong Ang Khang Kasol kaya Isana swasti swasti swasti, sarwa Bhuta sukha pradhana namo namah swaha. Ong Siddhir astu swaha. ‘Oh, Sang Bhuta Jangitan di Timur, putih warnamu, lima jumlah angkamu. Sang Bhuta Langkir di Selatan, merah warnamu, sembilan jumlah angkamu. Sang Bhuta Lembukanya di Barat, kuning warnamu, tujuh angkamu. Sang Bhuta Taruna di Utara, hitam warnamu, empat angkamu. Sang Bhuta Tiga Sakti di tengah, lima warna (campuran putih, merah, kuning dan putih) warnamu, delapan angkamu. Berkumpullah engkau semua dan memakan suguhan caru ini, setelah engkau makan dan meminum pulanglah engkau, dan ciptakanlah hidup sehat, tegar, berkulit tembaga, berotot kawat, bertulang besi, begitulah kau berikan kepada orang yang mempersembahkan caru ini. Ong Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang, Ang Ung Mang 9 Caru ini biasa dipakai mengawali piodalan madia, meruat pekarangan rumah, meruat cuntaka, pengrupukan (satu hari sebelum hari raya Nyepi) dan dasar-dasar dari caru dan tawur yang lebih besar seperti: Caru Panca Sanak, Caru Rsi Gana, Caru Panca Klud, Panca Sanak Medurga, Tawur Balik Sumpah, Tawur Panca Wali Krama, Eka Dasa Ludra dan lain sebagainya (Wikarman, 1998). Bila tidak demikian, caru atau tawur yang lebih besar dianggap tidak memiliki arti, karena Caru Panca Sata merupakan inti dari caru/tawur yang lebih besar. Begitu arif leluhur Bali mengkonsepsi yadnya seperti ini, bahkan dalam konsepnya menekankan struktur (dari tingkat nistaning nista (inti, sederhana) menuju uttamaning uttama (paling utama). Senada dengan itu, meminjam pendapat Kontjaraningrat bahwa “komponen sistem kepercayaan, komponen sistem upacara dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia” (Koentjaraningrat, 2008: 149). Selain itu Ny. I. G. A. Mas Putra (1993) mengelompokkan menjadi dua bagian pemakaian Bhuta Yadnya: (1) Yang berdiri sendiri: Tawur Kesanga, dasar dari sebuah pembangunan rumah atau tempat suci dan lain sebaginya; (2) yang menyertai upacara-upacara yang lainya, seperti piodalan, dan lain sebagianya. 2. 2. Fungsi dan Makna Caru Panca Sata Tindakan manusia terarah pasti memiliki tujuan dan fungsi, secara simbol maupun realita. Seperti Caru Panca Sata, secara spesifik dilihat dari sarana, rangkaian, puja mantra, maka memiliki fungsi-fungsi di antaranya: 2.2.1. Fungsi Caru Panca Sata 1. Fungsi Niskala “Kosmos dipandang suatu realitas yang tak terpisah; selamanya berada dalam gerak, hidup, organik; bersfat spiritual dan material pada waktu yang bersamaan” (Capra, 2001: 13). Maka dari pada itu umat Hindu melaksanakan 10 upacara caru Panca Sata yang sarat akan nuansa spiritual. Adapun fungsi niskala atau spirit dari Caru Panca Sata adalah: a. Sebagai Jamuan kepada Bhuta dan Kala, seperti bhuta petak/putih = Bhuta Jangitan dari arah Timur, bhuta abang/merah = Bhuta Langkir dari arah Selatan, bhuta kuning = Bhuta Lembukanya dari arah Barat, bhuta ireng/hitam = Bhuta Taruna dari arah Utara, dan Bhuta Tiga Sakti di Tengah. b. Sebagai Pengendalian atau Nyomya/Nyupat, yang berhubungan erat dengan fungsi jamuan di atas. Fungsi ini dapat diketahui dari sebagian puja mantra Caru Panca Sata di atas, seperti: “Wus sira amangan anginum caru iki, pamantuka sira ring desa soang-soang, anadi wateking dewata kabeh….. ‘Setelah engkau memakan, meminum caru ini, pulanglah engkau kepada asalmu masing-masing, jadilah engkau Dewata’. Sehingga kekuatan Tuhan (Bhuta kala) yang memiliki aspek destruktif, garang, krodha ‘marah’, supaya kembali ke aspek santhi/santha ‘damai’, dalam wujud Panca Dewata (aksara suci Sang (Sayojata) = Dewa Iswara di Timur, Bang (Bamadewa) = Brahma di Selatan, Tang (Tatpurusa) = Mahadewa di Barat, Ang (Agora) = Wisnu di Utara, dan Ing (Isana) = Siwa di Tengah. Begitu pula dalam Manawa Dharmasastra menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan dari unsur mahābhūta yang bersumber dari Tuhan itu sendiri: Tatah svayambhūr bhagavān avyakto vyañjayannidam, mahābhutādi vŗttaujāh prādurāsītta monudah (M. D. I. 6.). ‘kemudian dengan kekuatan tapanya, Yang Maha Ada dengan sendirinya walaupun tanpa wujud, menciptakan alam semesta ini secara bertahap, dari mahābhūta (unsur alam semesta) dan lainnya, yang melenyapkan kegelapan (Pudja dan Sudharta, 2004: 2). c. Sebagai harapan permohonan keharmonisan oleh orang yang melaksanakan caru, seperti tertuang dalam puja mantra Caru Panca Sata 11 di atas: angradana urip waras ‘membuat tubuh sehat’, teguh timbul ‘anti, kuat, tahan terhadap mara bahaya’, akulit temaga ‘kulit kuat seperti tembaga’, aotot kawat ‘berotot kawat’, awalung wesi ‘bertulang seperti besi’, mangkana de nira nugraha ring sang adruwe caru ‘demikian engkau (Bhuta yang sudah di-somya menjadi dewa) menganugrahkan orang yang melaksanakan caru’. 2. Fungsi Sekala Selain secara Niskala, dalam realita (sekala) yang dimaksud dengan Bhuta Kala adalah personifikasi unsur-unsur alam yang tampak, dari kesatuan unsur tersebut, alam ini mengambil wujud (kesatuan Panca Maha Bhuta: Prthiwi = padat/bumi, Apah = cair, Teja = cahaya/panas, Bayu = udara dan Akasa = langit/eter). Begitu pula Frincof Capra (2001: 14) mengemukakan hubungan ini seperti “…….melihat dunia sebagai sebuah sistem dari komponen-komponen tak terpisah, saling berintegrasi, dan selalu bergerak, bersama manusia sebagai satu bagian yang integral dari perputaran kosmos”. Secara nyata Caru Panca Sata dilakuakan kepada lima unsur alam tersebut (Panca Maha Bhuta), dengan menjadikan diri harmonis dengan alam, diwujudkan dengan prilaku moral melestarikan dan menjaga kelangsungan ekologi alam sehingga harmonis. Misalnya wujud dalam tindakan nyata seperti: a. Prthiwi = Bumi, tanah, benda padat. Kepada bumi semestinya manusia memelihara kesuburan tanah, melestarikan hutan. b. Apah = zat cair, air. Tidak mengotori air dengan limbah, sampah dan zat beracun lainnya. c. Teja = api, panas, cahaya, dijaga agar tidak sampai membakar hutan yang merupakan paru-paru dunia, panas di bumi dijaga stabilitasnya dengan cara melestarikan hutan agar tidak terjadi global warming ‘pemanasan global’ dan memanfaatkan energi bumi dan matahari dengan tepat guna. 12 d. Bayu = angin, udara, dilakukan dengan cara tidak mencemari dengan asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok, asap kebakaran hutan dan lain sebagainya. e. Akasa = Eter/langit, ruang, dilakukan dengan cara menjaga tata ruang yang ada pada lingkungan, sehingga lingkungan tertata dengan rapi dan tidak mengalami gerah, sumpek dan kepadatan. Kelima unsur alam tersebut harus seimbang dan saling melengkapi, dengan cara melakukan tindakan pelestarian lingkungan, satwa, dan tumbuhan. Sehingga tercipta siklus ekologi alam yang dinamis. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi sekala dari pelaksanaan Caru Panca Sata adalah mengharmoniskan bhuana alit ‘manusia’ dengan bhuana agung ‘alam semesta’. Secara lebih khusus pelestarian ini dilakuakan dalam tindakan Sad Kertih: Atma Kertih ‘melestarikan keharmonisan jiwa’, Wana Kertih ‘melestarikan keharmonisan hutan sebagai penampung air dan produksi oksigen’, Danu Kertih ‘pelestarian sumber-sumber air di danau, mata air dan sungai’, Samudra Kertih ‘pelestarian keharmonisan laut’, Jagat Kertih ‘pelestarian sosial yang dinamis’. Tindakan ini secara umum dilakukan dengan ritual-ritual yang sarat akan simbol, dalam maksud mengarahkan tindakan manusia untuk melestarikan lingkungan dengan kearifan lokal yang sangat dibutuhkan pada era globalisasi dan modernisasi, misalnya pemakaian kain poleng ‘kain bermotif kotak-kotak hitam dan putih’ diikatkan pada pohon besar’. Diikatkan kain ini, secara tidak langsung telah ikut andil dalam pelestarian lingkungan, walaupun dalam tradisi di Bali, bahwa kayu yang diikatkan tersebut, diyakini sangat angker dan pantang untuk ditebang (Suda (ed) 2010). Kemungkinan keyakinan ini berasal dari kepercayaan animisme yang masih berlanjut seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tidak bisa ditampik bahwa kepercayaan animisme memiliki andil dalam pelestarian alam di seluruh dunia. Hampir kebudayaan suku-suku tradisional memiliki cara- 13 cara tersendiri dalam mempraktekkannya. Terkadang oleh masyarakat modern, tradisi adiluhung ini dianggap remeh. 2.1.2. Makna Caru Panca Sata Dari fungsi Caru Panca Sata yang telah disebutkan di atas, maka semakin jelas makna dari caru. Adapun makna yang sangat mendasar dari caru ini adalah Asih, yadnya dan bhakti. 1. Mengasihi (Asih) segala makhluk yang bersifat gaib (Bhuta dan Kala). Kasih ini diwujudkan dengan pelaksanaan yadnya caru, dengan menjamu mereka dengan makanan (caru) dan minuman berupa tetabuhan (arak, berem dan air). Bhakti kepada kekuatan Tuhan dalam simbol Bhuta Kala yang telah dalam keadaan somya. 2. Asih diwujudkan dengan pelestarian unsur terpenting pada alam seperti: tanah, air, energi alam, udara, dan tata ruang. Mengarah kepada tujuan keseimbangan kosmos merupakan sebuah yadnya yang tak ternilai. Tindakan ini pula didasari penuh rasa bhakti. 3. Penggunaan lima jenis ayam secara simbolik-diktatik mengarah kepada manusia yang hendaknya mengurbankan sifat buruk. Dalam hal ini disamakan dengan sifat-sifat dari ayam. Mereka terkadang berkelahi untuk berebut makanan, kekuasaan dan sex. III. SIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka tulisan singkat tentang Caru Panca Sata ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Caru Panca Sata merupakan suatu bentuk persembahan yadnya umat Hindu di Bali, terbuat dari lima jenis ayam dan diolah sedemikian rupa 14 sehingga terbentuk beberapa jenis makanan untuk menjamu Bhuta Kala. Secara umum memiliki fungsi Niskala dan Sekala. Pada intinya untuk mengharmoniskan dunia (bhuana agung dan bhuana alit) beserta unsur-unsurnya. Caru Panca Sata dan jenis Bhuta Yadnya lain pada intinya mengandung makna asih, yadnya dan bhakti. Dari kasih kita akan rela berkorban dengan ketulusan hati (yadnya). Dari korban yang tulus ini kita dapat berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi dalam berbagai perbawa-Nya, termasuk kepada kekuatan Ida Sang Hyang Widhi sebagai Sang Hyang Panca Maha Bhuta yang telah di-somya. DAFTAR PUSTAKA Bakker, Anton. 1995. Kosmologi dan Ekologi Filsafat Tentang Kosmos Sebagai Rumahtangga Manusia. Yogyakarta: Kanisius. Capra, Frintjof. 2001. Tao of Physics: Menyingkap Paralelisme Fisika Modern dan Mistisme Timur. Terjemahan Pipit Maizier. Yogyakarta: Jalasutra. Kajeng, I Nyoman, dkk. 1997. Sārasamuccaya: Dengan Teks Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuna. Surabaya: Paramita. Keraf, Sonny. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Kompas. Keramas, Dewa Made Tantera. 2008. Metode Penelitian Kwalitatif dalam Ilmu Agama dan Kebudayaan. Surabaya: Paramita. Koentjaraningrat. 2008. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Cet ke23. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Panitia Penyusun. 1978. Kamus Bali-Indonesia. Dinas Pengajaran Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Pudja, Gede. 2004. Bhagavad Gita (Pancama Veda). Surabaya: Paramita. 15 ________dan Tjokorda Rai Sudharta. 2004. Manawa Dharmaśāstra (Manu Dharmaśāstra) atau Veda Smŗti Compendium Hukum Hindu. Surabaya: Paramita. Putra, I. G. A. Mas. 1993. Panca Yadnya. Jakarta: Yayasan Dharma Sarathi. Suda, I Ketut (ed). 2010. “Idiologi Di Balik Pemakaian Saput Poleng Pada Pohon Besar Di Bali”. Dalam Pelestarian Lingkungan Menurut Agama Hindu (Dalam Teks dan Konteks). Surabaya: Paramita. (Hal. 1-22). Tim Penyusun. 1996/1997. Panca Yadnya: Dewa Yadnya, Bhuta Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, dan Manusa Yadnya. Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama Tersebar di 9 Daerah Tingkat II. Wiana, I Ketut. 2007. Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu. Surabaya: Paramita. Wikarman, I Nyoman Singgih. 1998. Caru Palemahan dan Sasih. Surabaya: Paramita. Zoetmulder, P. J dan S. O. Robson. 2004. Kamus Jawa Kuna Indonesia. Cet. Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 16