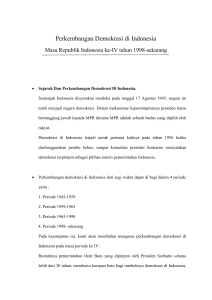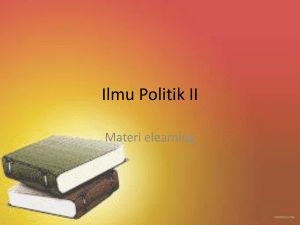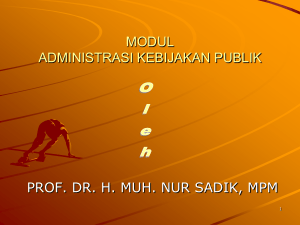BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Orang Katobengke
advertisement
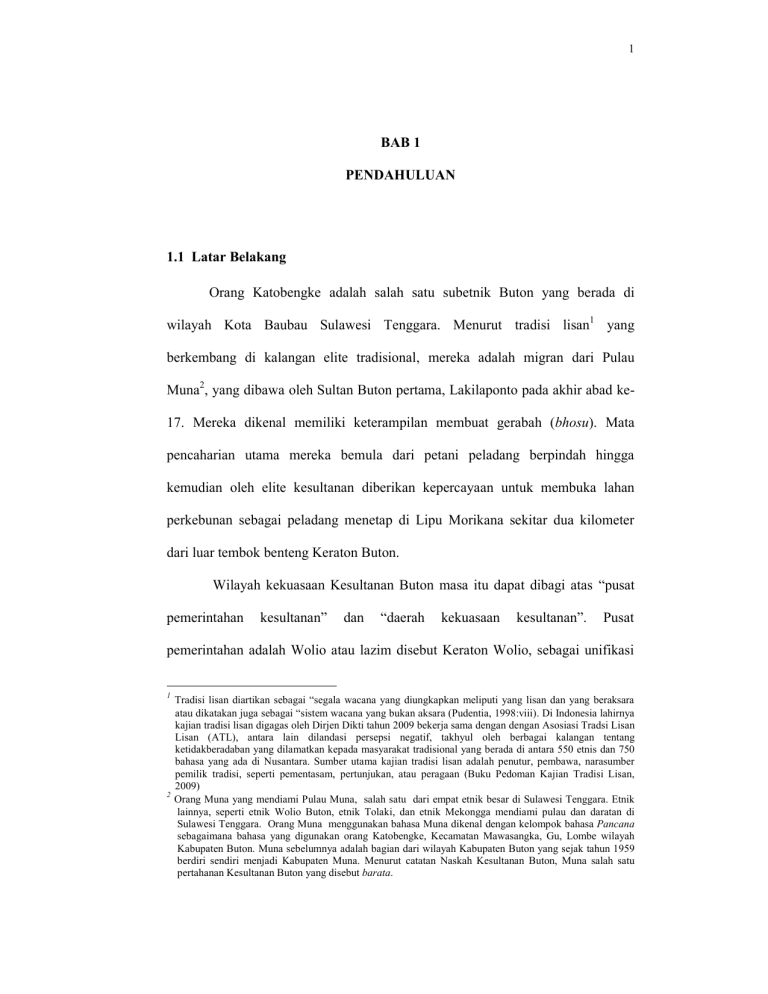
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Orang Katobengke adalah salah satu subetnik Buton yang berada di wilayah Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Menurut tradisi lisan1 yang berkembang di kalangan elite tradisional, mereka adalah migran dari Pulau Muna2, yang dibawa oleh Sultan Buton pertama, Lakilaponto pada akhir abad ke17. Mereka dikenal memiliki keterampilan membuat gerabah (bhosu). Mata pencaharian utama mereka bemula dari petani peladang berpindah hingga kemudian oleh elite kesultanan diberikan kepercayaan untuk membuka lahan perkebunan sebagai peladang menetap di Lipu Morikana sekitar dua kilometer dari luar tembok benteng Keraton Buton. Wilayah kekuasaan Kesultanan Buton masa itu dapat dibagi atas “pusat pemerintahan kesultanan” dan “daerah kekuasaan kesultanan”. Pusat pemerintahan adalah Wolio atau lazim disebut Keraton Wolio, sebagai unifikasi 1 2 Tradisi lisan diartikan sebagai “segala wacana yang diungkapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara atau dikatakan juga sebagai “sistem wacana yang bukan aksara (Pudentia, 1998:viii). Di Indonesia lahirnya kajian tradisi lisan digagas oleh Dirjen Dikti tahun 2009 bekerja sama dengan dengan Asosiasi Tradsi Lisan Lisan (ATL), antara lain dilandasi persepsi negatif, takhyul oleh berbagai kalangan tentang ketidakberadaban yang dilamatkan kepada masyarakat tradisional yang berada di antara 550 etnis dan 750 bahasa yang ada di Nusantara. Sumber utama kajian tradisi lisan adalah penutur, pembawa, narasumber pemilik tradisi, seperti pementasam, pertunjukan, atau peragaan (Buku Pedoman Kajian Tradisi Lisan, 2009) Orang Muna yang mendiami Pulau Muna, salah satu dari empat etnik besar di Sulawesi Tenggara. Etnik lainnya, seperti etnik Wolio Buton, etnik Tolaki, dan etnik Mekongga mendiami pulau dan daratan di Sulawesi Tenggara. Orang Muna menggunakan bahasa Muna dikenal dengan kelompok bahasa Pancana sebagaimana bahasa yang digunakan orang Katobengke, Kecamatan Mawasangka, Gu, Lombe wilayah Kabupaten Buton. Muna sebelumnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Buton yang sejak tahun 1959 berdiri sendiri menjadi Kabupaten Muna. Menurut catatan Naskah Kesultanan Buton, Muna salah satu pertahanan Kesultanan Buton yang disebut barata. 2 sembilan perkampungan yang didirikan pada masa awal terbentuknya kerajaan. Wilayah ini merupakan tempat tinggal golongan penguasa atau bangsawan, raja, dan pejabat pemerintahan kesultanan, sedangkan daerah kekuasaan, ada yang secara langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat dan ada yang tidak. Yang pertama disebut kadie (wilayah kampung) dengan 72 kadie dan kedua disebut barata (pertahanan) yang berstatus daerah otonom atau semacam negara bagian yang mengatur pemerintahannya sendiri yang terdiri atas empat barata, yaitu Barata Muna, Barata Tiworo, Barata Kulisusu, dan Barata Kaledupa (Maulana dkk, 2011: 69-70). Rudyansyah (1997: 44--53) dalam bukunya berjudul Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan menyakatan bahwa klasifikasi kelas penguasa dan kelas yang dikuasai dalam Kesultanan Buton menjadikan struktur masyarakat Buton dalam tiga lapisan3 masyarakat, yakni (1) kaomu (bangsawan), dan (2) walaka (menengah), dan (3) papara (rakyat desa) yang menempati 70 wilayah desa (kadie) dan dua kadie berada dalam benteng Keraton Buton yang ditempati golongan penguasa atau elite tradisional, yaitu golongan kaomu dan walaka. Kaomu dan walaka adalah golongan penguasa dan sebagai pendiri kerajaan, sedangkan kelompok papara sebagai golongan yang dikuasai adalah penduduk desa (kadie). Beberapa papara adalah pribumi daerah itu dan sebagian orang didatangkan sebagai budak untuk menambah jumlah penduduk desa. Ligtvoet (1878) dalam bukunya berjudul Beschrijving en Geshiedenis van Boeton yang 3 Susanto Zuhdi (2010:76) mengklasifikasikan bahwa kaomu dan walaka adalah peletak dasar kerajaan Buton sedangkan lapisan papara adalah orang jauh yang tidak diketahui asal usulnya. Selanjutnya ia memerinci lapisan keempat adalah batua atau budak yang berasal dari papara karena tidak membayar pajak. Kantinale adalah budak yang dimerdekakan dan paraka adalah budak yang dirampas dari tangan musuh. 3 dikutip oleh Schoorl (2003: 3) menyatakan bahwa perdagangan budak4 sangat penting bagi Buton pada abad ke-17 dan ke-18. Sistem “perbudakan”5 pada zaman kesultanan pada abad tersebut, merupakan implikasi dari kewajiban Buton atas tekanan Belanda untuk membayar upeti kepada Ternate. Di samping itu, juga sebagai konsekuensi kontrak perjanjian antara Sultan Buton Muhammad Asyikin dan Brugman tahun 1906. Kemudian pascakontrak politik 1906 itulah kekuasaan di Buton mengalami perubahan, yaitu Belanda melanggar perjanjian atas kesultanan Buton. Jika selama ini hubungan sebagai sahabat sederajat, kemudian berubah menjadi tuan dan hamba. Sultan Buton dan semua menterinya dipaksa berjanji harus patuh pada Raja Belanda. Tatanan pemerintahan tradisional kesultanan dan beberapa jabatan dihapuskan oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, rakyatlah menjadi tumbal, dan tekanan kewajiban membayar pajak. Peristiwa pada 20 November 1912, merupakan awal mulainya perlawanan rakyat atas kebijakan Belanda tersebut. Para kepala distrik sebagai pemungut pajak sebagai akibat tekanan Belanda menjadi sasaran protes rakyat atas kebijakan tersebut. Perlawanan La Ode Boha atas kebijakan perpajakan Belanda, menimbulkan korban antara lain terbunuhnya Kepala Distrik Tiworo La Raa Eta oleh rakyatnya yang dianggap terlalu tinggi menetapkan pajak. Selain itu, La Ode Sambira seorang Kepala Distrik (sekarang camat) Pasar Wajo yang dianggap sangat otoriter dalam menerapkan sistem membayar pajak juga menjadi korban. 4 5 Sistem budak Brazil sangat paternalistik, budak–budak pertama dipasok ke Brazil dari Afrika sekitar pertengahan abad ke-16. Pekerjaan mereka di samping di perkebunan juga sebagai budak rumah tangga (Sanderson, 2011: 362) Blandier (1986: 67) menyatakan bahwa dalam masyarakat segmenter yang memiliki sistem perbudakan domestik itu, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian pengucilannya, dari sebuah garis keturunan dan setiap ambil bagian dalam kontrol atas kehidupan masyarakat secara terang memperlihatkan berfungsinya metode keturunan itu. 4 Rakyat Laporo melakukan perlawanan, yang dipimpin oleh Maatalagi seorang tokoh Laporo yang kemudian diketahui secara geneologis keturunan bangsawan Keraton Buton. Maatalagi dan kelompoknya melakukan penyergapan terhadap kepala Distrik dan berhasil menangkap kepala distrik tersebut, kemudian dieksekusi tragis, yaitu dipenggal kepalanya (Zahari 1977: 99; Fahimudin, 2011: 34). Penghujung pemerintahan Kesultanan Buton memasuki era kemerdekaaan, era orde lama dan pemerintahan orde baru menandai mulainya pergulatan antara golongan elite tradisional, bangsawan (kaomu), dan golongan walaka (menengah) memperebutkan kekuasaan pemerintahan di Kota Baubau hingga diskriminasi elite-elite terhadap rakyat (papara). Orang Katobengke dalam struktur Kesultanan Buton tergolong kelas papara (rakyat). Sebagian kalangan elite tradisional mengidentifikasikan mereka sebagai budak dengan ciri khas pakaian yang ditampal-tampal (kabhaleko) dan kotor. Dalam tradisi lisan berkembang pula di kalangan elite bahwa stigma yang dialamatkan atas diri mereka berkaitan dengan perlawanan yang dilakukan terhadap kebijakan sultan, yang konon ditunggangi orang Muna. Sebagai konsekuensinya, mereka dijatuhi hukuman sebagai budak oleh aparat kesultanan. Stigma tersebut terus terwariskan ke alam pikiran elite tradisional dari generasi ke generasi. Di tengah perlakuan tidak adil atas kelompok papara selama tiga abad terhegemoni pemerintahan kesultanan, terlebih lagi orang Katobengke sebagai sasaran utamanya karena wilayah permukiman mereka berlokasi sekitar dua kilometer di luar pagar benteng keraton. Tugas wanita Katobengke, di samping keistimewaan mereka sebagai pembuat gerabah (bhosu) juga bertugas sebagai 5 pengasuh bayi bangsawan dan bagi laki-lakinya memiliki kekuatan fisik sebagai tenaga buruh tani. Sesemua itu untuk kebutuhan elite kesultanan, tetapi kemudian keisitimewaan itu, justru menjadi sasaran kekerasan pemerintah kolonial Belanda. Mereka memperlakukan orang Katobengke sebagai buruh tani yang sadis. Selain itu, para wanita sering dijadikan sebagai the second sex yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Tampaknya pada era orde baru birokrasi pemerintahan di Kota Baubau masih mewarisi birokrasi kolonial Belanda. Artinya, memperlakukan rakyat secara semena-mena, khususnya stigmatisasi terhadap orang Katobengke. Senada dengan tulisan Setiono (2002: 115) dalam buku yang berjudul Jaring Birokrasi bahwa budaya birokrasi Indonesia masih tetap seperti birokrat 300 tahun lalu, yaitu mulai zaman Kerajaan Majapahit, Mataram, VOC, dan Hindia Belanda yang menganggap bahwa bawahan dan rakyat adalah inlander dan kawulo yang harus dieksploitasi. Rakyat tetap saja pada posisi tertindas sebagaimana ditindas (dieksploitasi) oleh para punggawa kerajaan kuno. Ketertindasan tersebut sebagaimna tulisan Yekti Maunati (2006) dalam bukunya Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Di dalam buku itu dibahas konstruksi pemerintahan orde baru terhadap identitas6 orang Dayak tentang pencitraan mereka yang dilabelkannya sebagai etnik primitif. Demikian 6 Gidden (1991:219--220), identitas diri tercipta dari kemampuan untuk mempertahankan narasi perihal diri dan dogma membangun perasaan yang konsisten perihal kesinambungan biografis. Identitas sebagai proyek yang merupakan ciptaan kita, sesuatu yang selalu berproses berdasarkan situasi masa lalu, dan masa kini dan suatu gerak menuju masa depan yang kita inginkan. Barker mengutip Gidden (1984) menyebutkan bahwa identitas menjadi penting tidak hanya penggambaran diri, tetapi juga ciri-ciri sosial. Identitas sosial .terkait dengan hakhak, kewajiban-kewajiban, dan sanksi-sanksi normatif yang dalam masyarakat tertentu menjadi penentuan peran. 6 pula orang Katobengke, yaitu mulai era orde baru, sudah mendapat stigma dan kekerasan fisik yang menjadi korban dari keganasan rezim ABRI. Mereka dituduh terlibat G30 S PKI. Akibatnya hampir seluruh tokoh dan pemuda Katobengke ditangkap dan dimasukkan ke penjara, tetapi sebagian di antara mereka terpaksa melarikan diri keluar daerah Buton. Hingga sekarang orang Katobengke telah banyak beranak cucu di Kalimantan, Ambon, dan Jayapura. Dengan demikian, stigma atas diri mereka sudah diperlakukan tidak adil sejak era kesultanan dan kolonialisme Belanda. Kekerasan rezim Zainal Arifin yang sejak menduduki takhta Bupati Buton pada tahun 1969 mulai menerapkan kebijakan melarang orang Katobengke mengenakan pakaian adat, yang biasanya dipakai, baik dalam ritual maupun dalam aktivitas sehari-hari. Bentuk kekerasan simbolik yang paling menonjol dialamatkan kepada orang Katobengke sebagai warisan kesultanan adalah penerapan tabu adat elite, seperti ” orang Katobengke tidak boleh kawin dengan kaomu dan walaka dan tidak boleh melaksanakan ibadah haji”. Hal itu, sesuai dengan bentuk kekerasan simbolis menurut Bourdieu (dalam Jenkins, 2010: 157), yaitu pemaksaan sistem simbolisme dan makna (misalnya kebudayaan) terhadap kelompok atau kelas sehingga hal itu sebagai sesuatu yang sah. Legitimasinya meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Sebagaimana bagi orang Katobengke, hingga tahun 1980-an pendidikan mereka rata-rata hanya sampai tingkat SLTP. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan elite yang terkesan membatasi ruang mereka untuk tidak bebas memilih sekolah lanjutan. Strategi pembatasan itu dilakukan oleh para guru sekolah biasanya dengan cara 7 memberikan anjuran, agar anak-anak Katobengke mendirikan sekolah di lingkungan mereka sendiri. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak Katobengke tidak bergabung dengan anak-anak non-Katobengke. Beberapa anak Katobengke yang memiliki keinginan tinggi untuk bersekolah terpaksa harus menyembunyikan identitas sebagai orang Katobengke agar dapat bebas bersekolah di mana saja di Kota Baubau. Strategi tersebut tampaknya efektif karena beberapa di antara mereka berhasil menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Inilah sumber motivasi anak-anak Katobengke generasi sekarang. Motivasi ini pulalah tampaknya memperoleh dukungan dari pemuda Katobengke lainnya yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan di daerah perantauan. Pilihan pendidikan yang paling disukai adalah bidang pendidikan ketentaraan. Sejak era reformasi ini beberapa di antara mereka mulai mampu beradaptasi dengan orang-orang non-Katobengke. Namun, secara umum masih tampak jarak komunikasi sosial budaya dengan elite tradisional yang masih merasa sebagai kelas penguasa, sedangkan orang Katobengke tetap diposisikan sebagai kelas dikuasai. Salah satu indikatornya adalah masih bertahannya sistem taboo (incest) adat “larangan perkawinan antara stratifikasi sosial tradisional”. Pada era kesultanan pernah terjadi revisi adat untuk memperbolehkan adat perkawinan antara kaomu dan walaka dengan prasyarat harus mematuhi tata cara perhitungan besarnya mas kawin (popolo). Suatu kekecualian bagi orang Katobengke yang masih tetap berlakunya taboo antara perkawinan kaomu dan mereka. Bilamana terjadi perkawinan laki-laki bangsawan dengan mereka, 8 apalagi sebaliknya perempuan bangsawan dengan laki-laki yang disebut budak adat, maka yang bersangkutan akan “dihukum buang”. Di samping itu, budak adat tersebut dilarang bercerita tentang hubungan kekerabatan dengan bangsawan Buton. Dalam konteks inilah perlunya penggalian orang Katobengke yang dalam tradisi lisan berkembang adanya stigma atas diri mereka oleh elite kaomu dan walaka. Kebijakan elite tradisional dari era kesultanan hingga orde baru, berkaitan dengan soal perkawinan. Hal itu, terus bertahan di kalangan kaum elite sampai pada akhirnya mereka melakukan berbagai cara penolakan, baik secara pasif maupun aktif. Diskriminasi dalam bentuk stereotipe negatif itu, sebagaimana ditulis Tasrifin (2010: 1). Bahkan, dicontohkan dalam ungkapan tradisional, yaitu suatu kekesalan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat ejekan atau konotasi negatif, seperti pernyataan pakemu yitu pasea miana Katobengke (perilakumu seperti orang Katobengke); kawarena aemu yitu pasea miana Katobengke (lebarnya kakimu persis orang Katobengke). Di pihak lain, sejak era kesultanan elite tradisional sangat membutuhkan jasa orang Katobengke berkaitan dengan kemampuan mereka merawat dan mengobati anak bayi bangsawan secara ritul. Sehubungan dengan itu, jadilah semacam kelaziman bagi golongan elite bahwa memanggil orang Katobengke dengan panggilan Naa Laode (ibu bangsawan La Ode) bagi ibu-ibu Katobengke dan Maa Laode (bapak bangsawan La Ode) bagi orang tua laki-laki Katobengke, sedangkan para gadis terpilih bertugas sebagai belobamba (dayang-dayang) sultan (Ruslan, 2005: 71). Istilah panggilan Maa Laode tidak pernah dicantumkan di 9 depan nama mereka. Namun, kini mulai tampak seorang elite Katobengke mencatumkan gelar tersebut pada layar baliho “Maa Laode Zaami” dalam rangka pemilihan legislatif dan calon Walikota Bau-Bau 2014. Hal itu merupakan suatu keberanian yang tidak pernah dilakukan selama ini. Elite tradisional menilai bahwa orang Katobengke dikenal sebagai penurut hingga awal tahun 80-an. Akan tetapi, kemudian berbalik melakukan perlawanan, baik laten maupun manifes atau kekerasan fisik. Perlawanan pasif hingga fisik mulai tampak menonjol dalam satu dasawarsa ini. Mereka mulai memberikan penilaian terhadap sikap dan perangai elite tradisional, khususnya yang bermukim dalam lingkaran keraton dan sekitarnya dengan menyatakan “La Ode yang tidak sopan di depan kami dan bisa kami jatuhkan sumpah, niscaya mereka tidak akan selamat”. Lebih lanjut adanya indikasi kelompok generasi muda atau elite Katobengke modern melakukan perlawanan, baik atas identitas mereka sendiri seperti elite agama7 maupun golongan terpelajar menyembunyikan identitasnya, khususnya ketika mereka berada di luar daerah Buton yang lebih senang menyebut diri “orang Lipu” dan atau “orang Betoambari”. Mereka tidak pernah mengaku sebagai orang Katobengke. Indikator perlawanan fisik orang Katobengke secara terorganisasi mulai tampak ke permukaan ketika terjadi peristiwa berdarah pada tahun 2000 antara orang Katobengke dan eksodus Ambon. Peristiwa itu merenggut korban 7 Penelitian Japri Basri (dalam Abdullah, 1988: 140) di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara menganalisis elite agama antara dua aliran Islam yang berlawanan paham, yaitu “paham golongan tua” yang cenderung mempertahankan tradisi lama dan “paham baru” yang melaksanakan ajaran Islam murni, yang pada umumnya meninggalkan tradisi dan kepercayaan yang tidak bersumber pada ajaran Islam. 10 kedua belah pihak, antara lain terbunuhnya dua orang polisi yang bermaksud mengamankan peristiwa tersebut dan kemudian pelakunya diketahui orang Katobengke sendiri. Orang–orang non-Katobengke di sekitar Kota Baubau keheranan menyaksikan perilaku orang Katobengke yang dulunya dikenal sebagai penurut, bodoh, dan penakut, kemudian berbalik menjadi pemberani, menakutkan, dan para tokohnya menunjukkan kesaktian di depan lawan-lawannya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa orang Katobengke memiliki kesadaran diri dan merasakan sudah terlampau lama diperlakukan tidak adil, yaitu sejak era kesultanan hingga orde baru. Fokus kajian, penelitian ini adalah “mengapa orang Katobengke mendapat stigma dari elite tradisional, sementara pada sisi lain elite tradisional mengagungkan peran mereka sebagai pengasuh anak-anak bangsawan (maa laaode dan Naa Laode)”. Kemudian sejak reformasi berjalan, orang Katobengke menunjukkan indikasi melakukan perlawanan terhadap sistem pengetahuan elite tradisional maupun perlawanan secara terbuka di Kota Baubau. Dengan demikian, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk perlawanan apa sajakah yang dilakukan oleh orang Katobengke terhadap hegemoni elite tradisional di Kota Baubau? 2. Mengapa orang Katobengke melakukan perlawanan terhadap elite tradisional di Kota Baubau? 11 3. Bagaimana implikasi perlawanan orang Katobengke, baik bagi kelompok sendiri maupun terhadap kelompok elite? 1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum Secara umum penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan praktek hegemoni elite tradisional dan perlawanan orang Katobengke terhadap hegemoni elite tradisional berdasarkan pengalaman sejarah serta implikasinya baik dari kelompok sendiri maupun terhadap elite tradisional Buton di Kota Baubau. 1.3.2 Tujuan Khusus Secara spesifik tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk-bentuk perlawanan orang Katobengke dan praktik sistem stratifikasi sosial tradisional di Kota Baubau 2. Mengkaji dan memahami lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi perlawanan orang Katobengke di Kota Baubau 3. Memahami implikasi perlawanan orang Katobengke, baik bagi kelompok sendiri maupun terhadap kelompok elite tradisional. 1.4 Manfaat Penelitian 1. 4.1 Manfaat Teoretis Secara teoretis manfaat penelitian ini dapat digunakan, baik sebagai bahan referensi maupun penemuan model, konsep, dan metode baru sebagai berikut. 12 1. Sebagai bahan referensi studi lebih lanjut bagi peneliti yang tertarik untuk lebih mendalami masalah perlawanan dan kekuasaan, khususnya bidang kajian perlawanan rakyat terhadap hegemoni elite 2. Agar dapat ditemukan model, konsep, dan metode baru dalam rangka pengembangan studi kajian budaya dan tradisi lisan. 1.4.2 Manfaat Praktis Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai masukan terhadap pemerintah agar dijadikan referensi dalam memberdayakan masyarakat termarginalkan yang diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan, terutama pemerintah dalam upaya memediasi kepentingan kelompok dan subetnik. 2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menciptakan keteraturan sosial dan pelestarian identitas budaya orang Katobengke dengan memanfaatkan potensi kearifan lokalnya. `