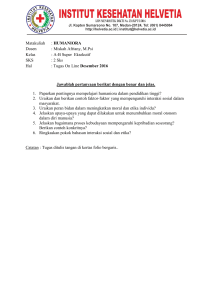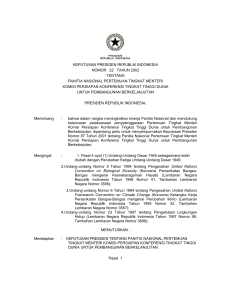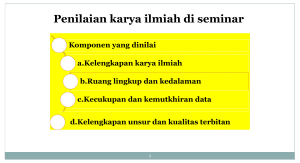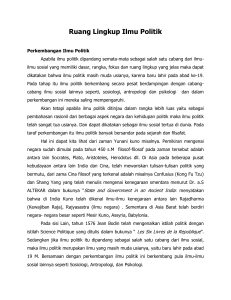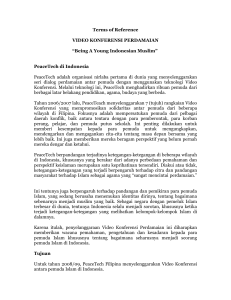1. Sebagai Ketua Steering Committee konferensi - ic
advertisement

1. Sebagai Ketua Steering Committee konferensi ICTHuSI, bisakah Anda jelaskan target dan sasaran yang hendak dicapai? Tujuan penyelenggaraan konferensi IC-THuSi ini pada dasarnya adalah untuk merintis usaha ilmiah mengkonstruksi apa yang kita sebut sebagai sains sosial dan budaya Islam, yaitu disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan dalam pengertian luas yang dikembangkan berdasarkan pandangan dunia dan prinsip-prinsip islam secara ontologis, antropologis, epistemologis, dan metodologis. Sedangkan sasaran utama konferensi ini adalah para sarjana Muslim umumnya dan Indonesia khususnya. Kami mengundang para akademisi dan peneliti ilmu-ilmu sosial dan humaniora Indonesia untuk mengirimkan artikel ilmiah mereka. 2. Mengenai istilah “human sciences” itu sendiri, apakah itu sama dengan ilmu humaniora atau ilmu pengetahuan budaya? Kata “human sciences” dalam konferensi ini mencakup ilmu-ilmu sosial dan sekaligus ilmu humaniora atau ilmu-ilmu budaya. Kami sengaja menggunakan nama “human sciences” (ilmu-ilmu kemanusiaan) yang meliputi kedua bidang ilmu tersebut karena selama ini dalam nomenklatur filsafat ilmu kontemporer kedua bidang tersebut dipisahkan secara epistemologis dan metodologis. Itulah yang hendak kami koreksi. Menurut hemat kami, yang sejalan pandangan dunia Islam, ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora sangat terpaut erat. Memang kedua rumpun ini bisa dibedakan, yaitu pada ilmu-ilmu sosial, kita lebih melihat perilaku manusia sebagai anggota masyarakat (fakta sosial) sementara pada ilmu humaniora tindakan manusia dipahami dan ditafsirkan sebagai individu. Nah, merujuk pada pemikiran Islam, kedua ranah ini, yaitu dimensi individu dan sosial manusia, tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi, kurikulum modern selama ini telah memisahkan keduanya sehingga lahirlah ilmu-ilmu sosial yang miskin wawasan tentang manusia di satu sisi dan ilmu-ilmu budaya yang abai dengan realitas sosial di lain sisi. Secara metodologis pun, keduanya juga sangat berjarak. Ilmu-ilmu sosial menggunakan pendekatan observasi empiris dan analitis yang cenderung positivistik, sedang ilmu-ilmu budaya - dengan merujuk pada hermeneutika Wilhelm Dilthey dan tradisi neo-Kantian- cenderung menggunakan pendekatan interpretasi-subyektif, yang kini malah berujung kepada paham relativisme dan anti-realisme. Jadi, kita seakan memiliki dua kutub dunia yang saling bertolak belakang, yaitu obyektivisme vs subyektivisme atau positivisme vs relativisme. Padahal, subyek kajian adalah sama-sama manusia. Inilah salah satu titik lemah ilmu-ilmu sosial dan budaya kontemporer. 3. Lalu, bagaimana dengan pandangan Islam sendiri mengenai kedua rumpun ilmu tersebut? Islam menganut pandangan interaksional antara kedua bidang ilmu tersebut. Maksudnya, keduanya memang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Konsekuensinya adalah keduanya saling berpengaruh timbal balik. Dalam sebuah momen tertentu, fakta sosial bisa mempengaruhi fakta manusiawi (sementara sebut saja seperti itu; bisa juga kita sebut dengan ‘nilai manusiawi’). Sebaliknya, dalam momen yang lain, fakta manusiawi dapat mengkonstruksi fakta sosial. Sebagai contoh, Ayatollah Murtadha Mutahhari dalam karyanya “Masyarakat dan Sejarah” (Bandung, 1987) menguraikan bagaimana peristiwaperistiwa sosial dibentuk oleh fakta-fakta manusiawi seperti ada tidaknya moralitas, hadir tidaknya religiusitas, ada tidaknya solidaritas sosial yang terbentuk oleh komunitas. Di sini Mutahhari mematahkan tafsiran materialistik terhadap peristiwa sosial dan sejarah. Sebaliknya, Mutahhari juga mengakui bahwa fakta-fakta sosial bisa mengkonstruksi cara pandang manusia, baik disadari secara individu atau tidak (disebut juga collective unconsciousness). Akan tetapi, Mutahhari menolak keras paham determinisme sosial yang linier dengan menyebut bahwa selalu terbuka kemungkinan bagi manusia untuk melepaskan diri dari struktur sosial yang menderanya karena manusia adalah makhluk potensial; manusia adalah pengada yang serba mungkin. Itulah contoh bagaimana filsafat manusia Mutahhari diterapkan dalam memahami peristiwa dan dinamika sosial. Bandingkan dengan, misalnya, karya Francis Fukuyama “The End of History and The Last Man” (New York, 1992), yang secara linier dan simplistis mengultimatum bahwa kapitalisme dan demokrasi liberal adalah terminal akhir sejarah manusia yang tak terelakkan; sebuah tesis yang dipatahkan oleh pelbagai peristiwa tiga dasawarsa terakhir. Yang saya herankan juga adalah para sarjana dan aktivis Teori Kritis (Critical Theory) ternyata berdiam diri saja terhadap tesis Fukuyama tersebut dan tampaknya mereka telah kehilangan harapan dengan proyek emansipasi dan pembebasan manusia yang mereka sendiri canangkan sejak 1960-an. Kenapa bisa demikian? Mungkin hal ini terkait dengan modus pemahaman tokoh-tokoh Teori Kritis tersebut (sebut misalnya Herbert Marcuse, Horkheimer, Adorno, Habermas) terhadap kodrat dan jati diri manusia itu sendiri, yang telah kehilangan dimensi spiritual sehingga perjuangan emansipasi mereka mudah pupus di tengah jalan oleh kuasa kapital dan aliran pesimisme yang mulai merasuki filsafat kontemporer. Nah, inilah salah satu sumbangan yang kita harapkan dari perspektif Islam dalam memahami dan menafsirkan peristiwa-peristiwa sosial yang tidak kehilangan visi holistik terhadap manusia, dan karenanya berpotensi “menghidupkan kembali manusia dalam arena sosial dan dinamika sejarah”. 4. Terkait dengan program konstruksi ilmu-ilmu kemanusiaan Islam tadi, menurut Anda langkah apa yang perlu dilakukan? Pada November 2013 lalu saya diundang mengikuti “International Congress on Islamic Humanities” (ICIH) di Teheran. Dalam kesempatan itu, saya mengajukan dua program utama dalam “ A Road Map for the Islamic Humanties” ini. Pertama, secara kontekstual, kita mesti memahami betul ilmu-ilmu sosial dan budaya kontemporer dengan mengidentifikasi segenap problemanya di level ontologi, kosmologi, antropologi, epistemologi, dan metodologi. Kita tidak muncul dari kevakuman. Sarjana-sarjana Muslim di seluruh dunia yang menekuni bidang-bidang psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, kesejahteraan sosial, dan studi-studi kebudayaan selama ini umumnya hanya mengenal tokoh-tokoh pemikir Barat modern. Kita tidak menolak mentah-mentah pemikiran Barat modern dalam ilmu-ilmu kemanusiaan ini. Justru yang diperlukan adalah mempelajari semuanya dengan terbuka dan kritis. Sikap menolak atau menerima mentah-mentah tanpa bertanya dan kritis adalah sikap yang tidak ilmiah. Sesuai dengan spirit Al-Qur‘an: Wa lā taqfu mā laysa laka bihī ‘ilmun. Inna al-sam‘a wal-bashara wal-fuada kullu ulā-ika kāna ‘anhu mas-ūlā (Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabnnya) - Surat Al-Isra ayat 36, kita mestinya mempertanyakan, mengelaborasi, dan mengungkap asumsi-asumsi filosofis yang melahirkan sarjana-sarjana seperti Freud, Pavlov, Durkheim, Marx, Locke, Adam Smith, Geertz, Weber, Giddens, dan seterusnya. Langkah kedua adalah mengkonstruksi ilmu-ilmu kemanusiaan yang digalikembangkan dari prinsip-prinsip dan filsafat Islam (ontologi, kosmologi, epistemologi, metodologi) secara kreatif dan aktual. Dalam konteks ini, saya kurang sepakat dengan istilah “Islamisasi ilmu-ilmu kemanusiaan” karena tiga alasan. Pertama, istilah itu mengesankan bahwa Islam hanya berperan sebagai pemoles atau stempel. Kedua, istilah itu juga mengindikasikan sikap yang tidak kreatif karena seakan-akan cuma sibuk mencari padanan dan kecocokan antara Islam dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Ketiga, istilah itu juga problematis secara metodologis. Ternyata, mayoritas peserta konferensi ICIH juga berpandangan yang sama, yaitu kurang menyukai istilah “Islamisasi ilmu-ilmu kemanusiaan” tersebut. Kita sebut saja langsung sebagai upaya rasional mengkonstruksi ilmu-ilmu kemanusiaan Islam secara ilmiah dan filosofis, bukan stempelisasi apalagi ‘ayatisasi’. Yang mesti digarisbawahi di sini adalah - sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam Proposal konferensi IC-THuSI - bahwa alasan mengapa kita mengusung perlunya ilmu-ilmu kemanusiaan Islam adalah karena krisis ilmiah-filosofis yang terjadi pada ilmuilmu kemanusiaan kontemporer. Ernst Cassirer sendiri berkata, “Teori-teori modern tentang manusia telah kehilangan pusat intelektualnya. Kita memang maju dalam instrumen teknis untuk observasi dan eksperimentasi tetapi kita tidak memiliki wawasan umum siapa sesungguhnya manusia itu” (An Essay on Man, New Haven: 1979) Pemenang Nobel Alexis Carrel juga menulis, “Manusia modern adalah seseorang yang asing di dunia yang dia ciptakan. Dia tidak mampu mengelola dunia ini karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang kodratnya sendiri” (Man The Unknown, New York:1979). 5. Tadi disebutkan bahwa para pemikir Barat dalam ilmu-ilmu kemanusiaan pasti memiliki asumsi-asumsi filosofis tertentu. Bagaimana dengan dunia Islam sendiri? Bukankah Islam memiliki tradisi filsafat Islam juga, tetapi mengapa mereka tidak kreatif dan produktif melahirkan ilmu-ilmu kemanusiaan Islam? Itulah persoalan besar kita. Ada dua problem atau tantangan utama yang kita hadapi secara bersamaan. Pertama, banyak sarjana Muslim kontemporer telah kehilangan visi tradisi intelektual Islam sehingga banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa Islam hanyalah sebuah agama yang mengajarkan ritus-ritus individual. Mereka tidak tahu bahwa Islam adalah juga sebuah peradaban dengan warisan intelektual dan capaian ilmiah yang gemilang. Kedua, sebaliknya ada juga sarjana Muslim yang membatasi diri untuk berkutat dengan peninggalan karya-karya agung para filsuf yang lalu seperti Ibn Sina, Suhrawardi, Mulla Shadra dan sebagainya tanpa melatih kemampuan berpikir merespons tantangan dan masalah pemikiran aktual yang kita hadapi. Saya teringat dengan sambutan Prof. Reza Davari Ardakani, seorang filsuf-budayawan senior Iran, pada Konperensi “Islamic Philosophy and the Challenges of the Present-Day World” tahun 2009 lalu di Teheran dan Hamadan. Beliau menyebutkan bahwa filsafat adalah aktivitas berpikir yang membantu kita untuk: (1) membuka sebuah horizon baru; (2) menciptakan sebuah horizon baru; (3) berpikir ke depan (thinking ahead); dan (4) mengingatkan kita akan batasan-batasan dan sekaligus kapasitas mengatasi batasan-batasan itu (beyond limit). Filsafat, menurut Ardakani, juga harus selalu berinteraksi dengan dunia kontemporer; jika ia hanya berurusan dengan sejarah, ia mati (if it deals with only the past, it dies). Pada momen yang sama, Ayatollah Muhammad Khamenei direktur SIPRIn (Sadra Islamic Philosophy for Research Institute), mengingatkan bahwa filsafat selalu muncul dari tantangan-tantangan. Filsafat harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Nah, penyelenggaran IC-THuSI oleh Sadra International Institute ini bisa dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban filsafat Islam terhadap masalah kemanusiaan hari ini.