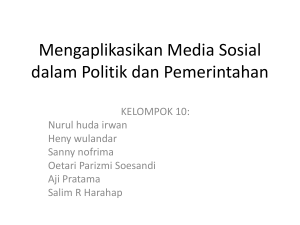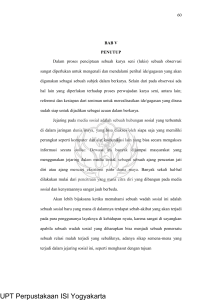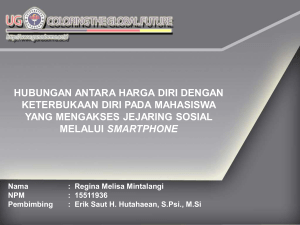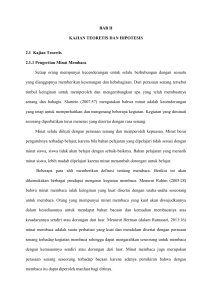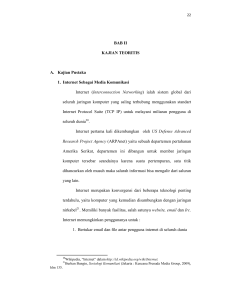Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012
advertisement

PENGELOLA ISSN: 2088-4133 • Pemimpin Umum: Rudy Gunawan, • Pemimpin Redaksi: Khairunnisa, • Penyunting Ahli: Muhammad Zamzam Fauzanafi, Sita Hidayah, • Redaktur Usaha: Adela Nisita Nari Arundita, • Redaktur Fotografi: Dian Ayu Aryani, Muhammad Arief Al Fikri, • Anggota Redaksi: Elvina Handayani, Muhammad Ichsan Rahmanto, Nur Rosyid, • Penyunting: Des Christy, • Keuangan: Ellin Khairani, • Humas: Yulina Dwita Putri, • Pemasaran dan Sirkulasi: Agnes Gita Cahyandari, Brigitta Engla Aprianti, Fata Hanifa, Fatiha Akbari Rochimawati, Tabita Termiati Makitan, • Artistik dan Tata Letak: Antonius Nurhadi Kusno, Gregorius Septian Christianto, • Foto Sampul: Muhammad Ichsan Rahmanto Alamat Redaksi Sekretariat Keluarga Mahasiswa Antropologi (KEMANT) Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Jurusan Antropologi Jl. Sosio-Humaniora No. 1, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Surat elektronik: [email protected] Situs internet: www.kemant.or.id Jurnal RANAH adalah jurnal mahasiswa Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikelola oleh Keluarga Mahasiswa Antropologi (KEMANT) FIB UGM. Jurnal ilmiah ini terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Harga eceran Rp. 25.000,-/eksemplar. Redaksi menerima naskah artikel baik yang bersifat teoritis, metodologis, hasil penelitian (laboratorium, lapangan, kepustakaan) maupun etnografis, atau tinjauan buku atau wacana yang masuk wilayah kajian antropologi. Artikel harus sesuai dengan tema yang ditawarkan tiap nomor terbitan. Naskah yang masuk diseleksi dan disunting oleh redaksi bekerjasama dengan penyunting ahli. ISSN: 2088-4133 Hak cipta © 2012 KEMANT dan para kontributor. Dilarang menggandakan, menyalin, atau menerbitkan ulang artikel atau bagianbagian artikel dalam jurnal ini tanpa seizin penerbit/redaksi. RANAH ISSN: 2088-4133 JURNAL MAHASISWA ANTROPOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA Budaya Digital dan Netnografi Th. II, No. 1, April 2012 DAFTAR ISI Kata Pengantar____________________________________________________ii ARTIKEL Antropologi Digital dan Hiperteks: Sebuah Eksplorasi Awal ________________2 Sita Hidayah Konsep Diri dan Penyebaran Wacana dalam Cyberspace: Tantangan Bagi Penelitian Antropologi__________________________________________12 Nindyo Budi Kumoro Budaya Manusia Digital____________________________________________22 Rio Heykhal Belvage Jejaring Sosial: Memupus Sekaligus Mengalienasi_______________________30 Gaffari Rahmadian Jejaring Sosial: Ruang Besi pada Konstruksi Inovasi dan Identitas Budaya Massa_____________________________________________________38 Yuda Rasyadian Jejaring Sosial: Lahan Reproduksi Kekerasan Terhadap Perempuan__________46 Gregorius Septian Christianto Jangan Melihat Buku dari Wajahnya: Studi tentang Interaksi dan Komunikasi dalam Facebook_______________________________________________54 Odit Budiawan BERITA Tantangan Antropologi Menghadapi Ruang Maya: Sebuah Intisari Diskusi____63 Dian Ajeng Pangestu, Muhammad Ichsan Rahmanto, Nur Rosyid Berita Buku_____________________________________________________67 i KATA PENGANTAR Salam hangat. Mulai tahun ini RANAH terbit dengan format baru. Jika sebelumnya berupa majalah semi-jurnal, maka saat ini RANAH hadir di hadapan pembaca dalam format jurnal ilmiah (seutuhnya) yang menyajikan tulisan-tulisan dari dosen, mahasiswa, alumni, dan segenap keluarga Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM). Dengan format baru RANAH diharapkan menjadi ruang untuk mengkritisi permasalahan yang sedang terjadi saat ini lewat tulisan ilmiah. Budaya Digital dan Netnografi adalah tema yang diangkat redaksi dalam edisi RANAH kali ini. Internet merupakan salah satu media yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang terkait dengan internet, seperti berkirim surat elektronik, pencarian data, unggah-unduh, hingga jejaring sosial. Kehadiran dunia maya (cyberspace) dan revolusi informasi ditengarai telah membawa banyak sekali perubahan yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial-budaya masyarakat itu sendiri. Kompleksitas terus berkembang tidak lain karena ekspansi teknologi informasi yang tidak terbatas. Di satu sisi, ekspansi ini patut dihargai karena kemajuan inovasi-inovasi baru telah membuat banyak aktivitas manusia menjadi semakin terbantukan. Di sisi lain, ketidaksiapan atas kehadiran suatu teknologi informasi bisa menimbulkan tekanan sosio-kultural yang menyebabkan manusia menjadi kaget (shock). Bahkan hal ini bisa jadi melahirkan dua kemungkinan dampak terhadap kultur suatu masyarakat, yakni kontinuitas dan diskontinuitas budaya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya berimplikasi pada terbenturnya budaya lama saja. Kehadiran teknologi informasi telah melahirkan “ruangruang sosial baru”, yakni jejaring sosial. Di dalamnya orang dapat berinteraksi dan membangun relasi tanpa harus menghadirkan tubuhnya. Realitas kehidupan sosial baru ini ternyata terekonstruksi dalam sebuah laman jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Bahkan laman sederhana itu bisa menciptakan interdependensi yang begitu kuat. Dalam jejaring sosial orang menjadi “dikejar” oleh informasi-informasi yang menuntut untuk selalu up-to-date. Ini hanyalah sekelumit fenomena baru yang bisa ditangkap dari munculnya revolusi informasi. Sayangnya meski internet secara mangkus dan sangkil telah mempengaruhi kehidupan (termasuk kebudayaan) manusia, dalam ranah antropologi Indonesia “dunia maya” ini masih menjadi terra incognito, tanah tak dikenal. Kajian-kajian antropologis/etnografis mengenai bidang ini masih terhitung sedikit di Indonesia. Melalui tema edisi ini RANAH mencoba merangsang para antropolog (maupun calon antropolog) untuk turut mewarnai kajian baru ini dengan tulisan-tulisan ilmiah—baik berupa gagasan konseptual maupun hasil penelitian. ii Warga Antropologi Bulaksumur cukup antusias menyambut tema ini, terlihat dari banyaknya naskah tulisan yang masuk ke meja redaksi. Dari belasan naskah tulisan yang masuk, redaksi harus memilih tujuh artikel terbaik untuk dimuat pada RANAH nomor ini—sesuai dengan tema, memenuhi syarat artikel ilmiah, dan beberapa kali direvisi oleh penulisnya sesuai saran penyunting ahli. Pada nomor ini terdapat delapan tulisan yang terangkum dalam tujuh artikel dan satu berita. Artikel pertama oleh Sita Hidayah, staf pengajar Jurusan Antropologi Budaya UGM. Ia membahas kajian teoritis antropologi/etnografi di dunia internet, yang sangat cocok sebagai pengantar sebelum melangkah lebih jauh. Selanjutnya diisi oleh Nindyo Budi Kumoro, mahasiswa Antropologi Budaya UGM, yang menulis tentang fenomena penyebaran wacana di internet. Lalu tulisan Rio Heykhal Belvage membahas bagaimana budaya cyber ditilik dari kacamata eksistensialisme. Lantas ada Gregorius Septian Christianto yang menganalisis kekerasan terhadap perempuan yang direproduksi ke dalam lahan baru berupa jejaring sosial. Terdapat juga tulisan dari mahasiswa pascasarjana Antropologi Budaya UGM, Gaffari Rahmadian dan Odit Budiawan. Masingmasing menulis tentang kaitan antara jejaring sosial dan teori alienasi, juga studi interaksi dan komunikasi dalam Facebook. Artikel tentang jejaring sosial dan teori alienasi ini (ternyata) mendapat sanggahan dari Yuda Rasyadian dengan tulisannya terkait jejaring sosial dan teori iron cage (kurungan besi). Selain tujuh artikel tadi, ada pula tulisan kolaborasi yang dibuat oleh Tim Divisi Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa (PSDM) Keluarga Mahasiswa Antropologi (KEMANT) UGM. Tim ini membuat intisari diskusi mengenai kajian antropologi di ranah internet. Terdapat pula rubrik Berita Buku yang menyajikan informasi seputar buku-buku terbaru terkait dengan tema nomor terbitan ini. Akhirnya melalui pengantar singkat ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta berpartisipasi dalam pembuatan RANAH. Semoga dengan adanya jurnal ini wacana-wacana ilmu antropologi makin berkembang di Indonesia. Selain memperkaya wawasan dan pengetahuan, diharapkan jurnal ini bisa membuat para pembaca lebih lebih dalam mengkritisi suatu fenomena sosial-budaya. Jurnal yang hadir di hadapan pembaca ini jelas tidak lepas dari kekurangan, maka redaksi mengharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang nantinya sangat berguna bagi untuk peningkatan kualitas jurnal ke depannya. Tabik. Redaksi iii Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Dian Ayu Aryani ANTROPOLOGI DIGITAL Era digital kian berwarna dan mewabah, antropologi pun bergerak cepat untuk mencoba masuk ke dalamnya. Dengan berbagai perspektif berbeda dari ilmu-ilmu lainnya, sesuatu yang berbeda akan dikaji. Artikel berikut akan menelaah tentang antropologi digital dan hiperteks, sebagai sebuah eksplorasi awal. 1 Sita Hidayah - Antropologi Digital dan Hiperteks TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 2-10 ANTROPOLOGI DIGITAL DAN HIPERTEKS: SEBUAH PEMBAHASAN AWAL Sita Hidayah1 ABSTRAK Tulisan ini adalah sebuah pengantar mengenai antropologi digital pada umumnya. Tulisan ini dibuat berdasarkan pengamatan bahwa meski akses internet di Indonesia tumbuh dengan kecepatan eksponesial, dan hampir tidak ada lagi aspek kehidupan yang tak termediasi teknologi digital, jagad digital masih menjadi tanah tak dikenal—terra incognito antropologi Indonesia. Selain ingin mengangkat antropologi digital dalam perbincangan ilmiah, tulisan ini ingin mengajak para pembaca untuk mencermati komunitas-komunitas online yang terus bermunculan dan juga melihat potensi netnografi dan etnografi hiperteks dalam memperkaya kajian mengenai manusia dan kemanusiaan Indonesia. Kata Kunci: antropologi digital, netnografi, hiperteks, komunitas online Kilasan Awal mengenai Digital Ethnography dan Hypertext dalam Antropologi Sebelum kita memulai perbincangan mengenai digital etnografi dan hiperteks dalam antropologi, saya membuat pembedaan mengenai (1) digital etnografi, yaitu etnografi yang dihasilkan melalui perangkat digital. Pada etnografi ini, meski field penelitian bukan komunitas online, istilah digital etnografi bisa dipakai sepanjang proses penelitian memakai perangkat digital. Lalu (2) digital etnografi sebagai metode yang dipakai untuk mempelajari dan memahami dunia digital dan online communities yang umumnya dikenal sebagai netnography. Pada pengertian yang pertama, kita akan melihat suatu etnografi yang termediasi komputer (computer-mediated ethnography), di mana keseluruhan kerja etnografi bisa dan telah dilakukan dengan teknologi digital. Sementara pengertian yang kedua lebih menekankan pada etnografi tentang budaya dan jaringan sosial yang termediasi melalui internet (internet-mediated culture). 1 Staf Pengajar Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Pada bagian pengantar ini kita akan membahas mengenai hubungan antropolog dengan teknologi digital yang semakin erat. Bahkan bagi para penentang digital etnografi yang paling kukuh sekali pun akan sulit mengabaikan realita bahwa teknologi digital telah mewarnai kehidupan dan merasuki kemanusiaan kita yang paling mendasar: cinta, identitas, tubuh, kekerabatan, politik, agama bahkan realita. Teknologi digital tidak hanya mempengaruhi kehidupan orang kebanyakan, teknologi digital juga mempengaruhi bagaimana cara para antropolog merekam, menyimpan, menganalisis, menghasilkan, dan menyebarkan kerja ilmiah mereka. Jika kita melihat situasi saat ini, kita bisa menemukan banyak sekali yang bisa dilakukan para antropolog dengan teknologi digital yang mereka punya. Pandangan bahwa digital etnografi melulu tentang etnografi visual (film dan foto) tidaklah benar. Para antropolog dengan mangkus telah memanfaatkan komputer, kamera dan perekam digital, bahkan telepon seluler dalam kerja etnografi mereka. Perekam digital, baik perekam suara maupun gambar semakin meluas penggunaannya dalam etnografi. Para antropolog kontemporer menyimpan data etnografi dalam bentuk digital karena keuntungan dari format ini: mudah disimpan, disebarluaskan, dan mudah dipakai. Pada tataran analisis, makin banyak antropolog memanfaatkan komputer untuk membuat hubungan berbagai variabel penelitian dan menafsirkan data awal mereka. Kita bicara mengenai beragam software untuk menganalisis data kualitatif mau pun data kualitatif: mulai dari Windows Excel, SPSS, Athena, MACQDA sampai CAQDAS. Dengan mediasi komputer, para antropolog menghasilkan tidak hanya teks etnografi tunggal, tapi juga dokumen etnografi yang hypertext. Etnografi dalam format hypertext biasanya berwujud teks dengan rujukan teks atau informasi lain yang tertaut link. Hiperteks adalah struktur yang membangun internet (World Wide Web) sehingga tidak heran etnografi hiperteks memiliki domain di internet2. Dengan platform web.2.0 yang ada saat ini, masa depan etnografi tidak lagi harus berupa dokumen hypertext, tapi juga hypermedia. Pada akhirnya kita akan melihat suatu etnografi dalam bentuk dokumen teks yang terhubung tidak hanya dengan teks/informasi lain, tapi juga dengan gambar/grafis yang tak terbatas kecuali kapasitas komputer dan jaringan internet. Setelah fokus pada kerja antropolog dan hubungannya dengan teknologi digital dan hiperteks, kita akan beralih pada fokus mengenai etnografi mengenai dunia yang termediasi teknologi digital dan dalam wadah hiperteks. Etnografi tentang Budaya Internet Saya tidak terlalu menguasai komputer jaringan, kurang paham mengenai 2 Apple “hypercard program” menggunakan format hypertext untuk fungsi pencarian. 3 Sita Hidayah - Antropologi Digital dan Hiperteks wacana netnografi dan juga tidak terlalu terlibat dalam komunitas online. Dengan keterbatasan-keterbatasan saya, pembahasan ini hanya akan membicarakan mengenai online ethnography dan lapangannya (field). Sarjana paling otoritatif dalam studi mengenai budaya dan komunitas online adalah Robert V. Kozinets yang sudah menulis banyak sekali buku mengenai netnografi. Salah satu karya Kozinets yang paling bernas berjudul Netnography: Doing Ethnographic Research Online yang terbit tahun 2009. Dalam bukunya terdapat pernyataan bahwa komunitas-komunitas online membentuk dan mengejawantahkan nilai-nilai, adat kebiasaan dan kepercayaan yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku komunitas tersebut (Kozinets, 2010:12). Singkatnya, meski interaksi sosial anggota komunitas online ini termediasi komputer, komunitas online membentuk dan dibentuk suatu kebudayaan. Segala bentuk kebudayaan manusia adalah subjek pembicaraan antropologi. Anggaplah kita menerima asumsi bahwa sebuah komunitas online adalah subjek penelitian yang sama derajatnya dengan satu komunitas di lereng Merapi, komunitas online tetap akan mengusik pandangan tradisional kita mengenai lapangan (field) penelitian etnografi. Diawali dengan munculnya webnography sebagai sub disiplin antropologi, lapangan etnografi baru tergelar: suatu lapangan sosial yang mewujud melalui teknologi digital dan jaringan internet. Lantas sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dalam antropologi—etnografi tanpa ethnos, tidak hanya mungkin tapi menjadi keniscayaan (Wittel, 2010). Merangkum dua paparan singkat mengenai budaya internet dan lapangan penelitian antropologi baru ini, kita tidak perlu membatasi cakrawala pandang kita pada anggapan bahwa internet semata produk material kebudayaan (Paterson, 2002). George Marcus (1998:79 dalam Wittel 2010) telah mengingatkan kita mengenai perlunya para antropolog untuk mencermati “sirkulasi makna-makna, objek-objek dan identitas kultural dalam ruang dan waktu yang difusif” ini. Marcus secara tidak langsung mengarahkan kita pada definisi lapangan online ini. Lapangan yang difusif, yang tidak lagi terikat pada batasan-batasan teritorial geografis dan tidak terikat waktu linear, dengan tautan (link) informasi dan media yang menggurita, secara langsung menguji metode etnografi yang biasa dipakai dalam antropologi. Lapangan etnografi ini sulit karena pengertian baru ini menentang asumsi dasar etnografi yang menekankan pentingnya mempelajari sebuah kebudayaan dalam lingkungan alaminya. Ditambah lagi dengan anggapan bahwa lapangan online ini tidak hanya tidak alami, tapi juga bersifat imajiner— tidak dalam pengertian Anderson dalam bukunya Imagined Communities, tapi pada sesuatu yang tidak sungguh-sungguh ada dan sepele—membuat lapangan etnografi baru ini tidak menarik bagi beberapa kalangan. Tulisan ini tidak akan membahas persoalan mengenai pembedaan realitas nyata dan tidak nyata dalam 4 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 dunia digital ini. Tulisan ini dibuat dengan asumsi bawa meski tanpa kontak fisik dan tatap muka langsung, para anggota komunitas online (netizen: internet citizen) mengaggap pengalaman sosial online mereka tidak hanya nyata dan otentik tapi juga bermakna. Seperti yang ditulis Kozniaks (2009) ratusan juta penduduk dunia berinteraksi dalam dunia cyber setiap hari. Ini berarti bahwa lebih dari 22 persen penduduk dunia terhubung melalui internet. Dalam laporan Digital Future yang dikeluarkan oleh University of Southern California tahun 2008, kenaikan jumlah netizen di Amerika melonjak lebih dari 100 persen selama tiga tahun terakhir dan penggunaan internet di Asia meningkat lebih dari 400 persen pada kurun waktu 2000-2008 (Kozniaks, 2009). Perlu ditekankan di sini, para netizens ini tidak hanya mengunjungi web: mereka secara berkala berinteraksi serta menemukan kepuasan dan makna dalam berbagai aktivitas blogging, micro blogging, videocasting, social networking, online gaming, instant messaging, emailing, dan seterusnya dalam world wide web ini. Ada beragam nama disematkan pada sub disiplin antropologi yang mempelajari budaya dan komunitas online, mulai dari webnography, virtual ethnography, digital ethnography, cyber anthropology dan juga netnography dengan berbagai nuansa dan spektrum paradigma (Kozinets, 2009:5). Menurut saya, akan lebih produktif apabila kita meneruskan perbincangan kita mengenai netnografi daripada membahas mengenai beragam penamaan sub disiplin antropologi ini. Persoalan kita selanjutnya adalah, apa itu komunitas online yang menjadi “lokasi” penelitian etnografi kita? Mengikuti definisi Howard Reingold dalam buku Virtual Community: Homesteading on The Electronic Frontier, komunitas online adalah: “Social aggregations that emerge from the net when enough people carry on…public discussions long enough, with sufficient human feelings, to form webs of personal relationships in cyberspace” (Kozinets, 2009:8). Melalui pengertian di atas, kita bisa menarik beberapa batasan mengenai komunitas online: komunitas bersifat kolektif dengan interaksi individu-individu yang termediasi komputer, memiliki simbol-simbol yang dipertukarkan oleh minimal 20 orang (batas minimal yang dibuat Kozinets) dan pertukaran ini bisa diakses oleh peneliti, di mana interaksi-interaksi online ini berlaku seperti hubungan yang berkelanjutan dan melibatkan perasaan-perasaan manusiawi sehingga menghasilkan sebuah jaringan sosial dengan identitas bersama (Ibid. 2009:8-9). Batasan-batasan yang dibuat Kozinets ini cukup berguna bagi kita untuk mengidentifikasi komunitas online yang hendak dipelajari. Apabila kita sudah 5 Sita Hidayah - Antropologi Digital dan Hiperteks menemukan komunitas pilihan, maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana kita akan melakukan penelitian etnografi melalui internet. Netnography: Sebuah Metode Tahapan penelitian etnografi online ini hampir serupa dengan tahapan etnografi tradisional. Tahap awal dimulai dengan membuat batasan penelitian dan membuat pertanyaan, menyeleksi komunitas online, melakukan partisipasi observasi, dilanjutkan dengan menganalisis data dan menyajikan laporan etnografi kita. Dari segi substansi, etnografi tradisional dan netnografi tidak banyak berbeda. Sebelum membahas mengenai perbedaan kedua hal ini, apa itu netnografi? Dalam buku Netnography, netnografi didefinisikan sebagai “sebuah bentuk etnografi yang diadaptasi untuk dunia sosial yang dimediasi perangkat komputer” (Kozniaks, 2009:1). Singkatnya, netnografi adalah sebuah metode untuk mempelajari cybernetics space (cyberspace). Belakangan ini netnografi telah diusung sebagai sebuah satu-satunya metode yang secara khusus dirancang untuk mempelajari kebudayan dan komunitas online (Bowler Jr, 2010). Kozniaks lebih lanjut menerangkan keunggulan-keunggulan netnografi dalam mempelajari interaksi sosial online: “…online interactions are valued as a cultural reflection that yields deep human understanding. Like in-person ethnography, netnography is naturalistic, immersive, descriptive, multi-method, adaptable, and focused on context. Used to inform consumer insight, netnography is less intrusive than ethnography or focus groups, and more naturalistic than surveys, quantitative models, and focus groups. Netnography fits well in the frontend stages of innovation, and in the discovery phases of marketing and brand management.” Kelebihan-kelebihan netnography ini membuat metode pengamatan (sering dianggap metode “menguntit”/lurking), content analysis dan text mining yang dulu biasa dipakai untuk meneliti aktifitas-aktifitas online menjadi kurang mendalam dan kurang menghasilkan dalam memahami para netizen. Karena pada prinsipnya sama, etnografi dan netnografi memiliki banyak persamaan. Persamaan yang paling fundamental dari kedua metode ini adalah: sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan peneliti dan pentingnya konteks dalam penggambaran kebudayaan online ini. Perbedaan antara kedua metode ini terletak pada bagaimana penelitian dilakukan dan bagaimana antropolog melakukan penelitian. Bagaimana mencari, mencatat dan merekam, menyimpan, menganalisis dan menampilkan representasi kebudayaan online? Mencari data di dunia maya tentu tidak sama dengan penelitian lapangan pada sebuah komunitas di pesisir Jawa, misalnya. Kalau dalam penelitian etnografi data terutama diperoleh 6 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 melalui wawancara mendalam, dalam netnografi data terutama diperoleh dari interaksi hiperteks para netizen. Kelebihan format hiperteks, segala bentuk pertukaran simbol yang berupa tulisan, suara atau gambar bisa disimpan dalam format asli, sehingga makna mencatat data juga bergeser. Dalam netnografi, jotting dan transkrip tidak lagi perlu. Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian pertama tulisan, para antropolog sekarang bisa menganalisis data dan menampilkan laporan etnografi dalam bentuk hypertext (hypermedia). Sedikit pembahasan mengenai analisis data dan penulisan hypertext: karena sifatnya yang multilinear, proses penelitian tidak lagi kronologis. Dokumen data dan dokumen analisis bisa saling bertautan sehingga batasan antara data dan analisis menjadi kabur. Kita bisa membaca tautan sebagai sebuah dokumen analisis, dan sebaliknya satu dokumen analisis bisa menjadi dokumen data pada tautan dokumen yang lain. Tentu saja kita bisa memutuskan sebuah dokumen sebagai sebuah teks akhir, akan tetapi dengan kemudahan tautan (link) hiperteks, sangat mudah bagi kita tergoda untuk mengikuti tautan tersebut. Bandingkan perbedaan tanggapan kita ketika membaca sebuah dokumen dengan rujukan berupa catatan kaki dan dokumen dengan rujukan berupa tautan hiperteks. Dalam tahap analisis, penggunaan kerangka berfikir dan teori dalam netnografi akan sangat bergantung pada keputusan sang antropolog, seperti halnya dalam etnografi biasa. Akan tetapi karena sifat hiperteks, tentu saja pelukisan hiperteks mengubah pemaknaan dan hubungan antara pengarang (dalam hal ini antropolog) dan pembaca. Etnografi online mutakhir sangat partisipatoris dan demokratis, sehingga pembacaan akan teks bisa menjadi sangat cair. Bahkan saking partisipatoris dan demokratis, pembaca bisa menggeser peneliti dalam membangun wacana mengenai sebuah representasi kebudayaan. Menutup pembahasan mengenai metode netnografi ini, perbedaan yang paling menyolok antara etnografi dan netnografi terutama terlihat dalam aspek etika penelitian. Interaksi sosial ini termediasi teknologi menyebabkankehadiran peneliti tidak serta merta bisa tampak, sehingga sangat penting bagi para peneliti online untuk mendapatkan persetujuan dari para netizen yang menjadi subjek penelitian mereka. Aspek privasi juga harus menjadi prioritas karena dalam interaksi online, batasan publik dan privat sangat tipis. Batasan publik dan privat bisa jadi sangat subjektif, meski pun ada undang-undang yang mengatur interaksi dan transaksi internet, misalnya. Persoalan etika ini cukup penting sehingga persoalan kehadiran peneliti dalam komunitas masih akan dibahas pada bagian di bawah. Beranjak dari perdebatan mengenai lapangan, mengutip Wittel (2010), ada beberapa hal yang perlu kita bahas lebih lanjut: “(1) Ethnographic practice is attendance, is a co-presence of ethnographer and the observed social situation. 7 Sita Hidayah - Antropologi Digital dan Hiperteks Whether this co-presence requires one single shared space, is a problem worth discussing, particularly in the context of online-ethnographies… (2) Ethnography is about revealing context and thus complexity. The potential of this method lies not in a reduction of complexity, not in the construction of models, but in what Geertz calls “thick description”.” Prinsip kehadiran dalam etnografi penting untuk ditekankan dalam penelitian etnografi online ini. Meski dalam etnografi online ruang dan waktu tidak lagi bersifat tunggal dan linear, namun partisipasi observasi tetap menjadi patokan untuk menggali pengetahuan komunitas online ini. Partisipasi observasi ini yang membedakan metode etnografi online atau netnografi dengan metode yang dipakai untuk memetakan jaringan, analisis user-generated content atau metode pencarian dan penggunaan web lainnya. Kedua, etnografi bertujuan untuk menemukan hubungan-hubungan yang kompleks dan holistik dan juga harus mampu mengungkapkan konteks yang mendalam mengenai sebuah kebudayaan. Pertanyaan besar untuk kita adalah bagaimana membuat pelukisan yang mendalam mengenai komunitas online ini sementara ada lubang besar yang belum juga bisa ditutup dalam netnografi ini: anonimitas pengguna internet. Menyoal Internet di Indonesia: Awal Kesimpulan? Sebelum mengakhiri tulisan ini saya ingin memaparkan beberapa data menarik mengenai pemanfaatan internet di Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan pengguna Facebook terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan juga merupakan negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia setelah Jepang dan India (Kompas, 28 November 2011). Untuk sebuah negara dengan akses internet yang tidak masuk dalam peta internet superpower dunia, Indonesia sungguh istimewa. Dengan pengguna internet lebih dari 55 juta orang dan dengan angka penetrasi lebih dari 30 persen di wilayah perkotaan Indonesia (Mark Plus Insight 2011 dalam Kompas, 28 Oktober 2011), sudah sepantasnya para antropolog memberikan perhatian lebih pada fenomena ini. Di tengah ketakjuban saya akan kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia, saya juga merasa prihatin. Dari dua data di atas kita bisa langsung membuat hubungan sederhana: dari 55 juta orang pengguna internet di Indonesia, 40,8 juta adalah pengguna Facebook. Kesimpulan ini diperkuat oleh data yang dikumpulkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika bahwa penggunaan internet di Indonesia sebagian besar dipakai untuk jejaring sosial (58 persen) dan online gaming (35 persen) (Bisnis, 21 Desember 2010). Mengapa bangsa Indonesia sangat gandrung dengan 8 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 jejaring sosial dan online gaming ini? Mungkin saya tidak tahu jawaban dari pertanyaan saya sendiri, sebuah persoalan muncul di sini. Dari paragraf-paragraf di atas, kita para antropolog bisa melakukan penelitian dan membuat representasi kebudayaan dengan perangkat digital hiperteks atau melakukan penelitian kebudayaan melalui perangkat digital hiperteks. Saya ingin memanfaatkan ruang yang sempit ini untuk mengingat sebuah cara pandang yang paling umum dalam penelitian budaya internet. Saya memakai contoh untuk menggambarkan pandangan yang paling umum dalam penelitian mengenai internet sekarang ini: adanya hubungan langsung dan berarti antara dunia maya dan dunia nyata. Misalnya, bagaimana kehidupan offline kita berjalan dalam logika jejaring sosial online. Dalam logika semisal Facebook dan Twitter, pengguna selalu ditantang untuk menampilkan diri, sehingga tidak heran para pengguna menjadi sangat sadar akan pentingnya dokumentasi. Peristiwa tidak lagi bisa berlalu begitu saja tanpa catatan atau foto di profil akun Facebook seseorang. Kedua, emoticon dalam microblogging dan instant messenger. Emoticon adalah gambar-gambar wajah yang melukiskan beragam perasaan dan emosi manusia. Penggunaan emoticon memang bertujuan untuk memampatkan berjuta kesan dalam ikon yang sangat sederhana. Apabila dicermati lebih dalam, emoticon tidak hanya menyederhanakan komunikasi, tapi juga menumpulkannya. Benarkah demikian? Bibliografi Buku Anderson, Benedict. 2001. Komunitas Terbayang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dicks, Bella, Bruce Mason et. al. 2005. Qualitative Research and Hypermedia Ethnography for the Digital Age. London: Sage. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Culture. New York: Basic Books. Kozinets, Robert V. 2009. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: Sage. Marcus, George. 1998. Ethnography through Thick and Thin. Princeton: Princeton University Press. Jurnal Coleman, E. Gabriella. 2010. ”Ethnographic Approach to Digital Media” dalam Annual Reviews of Anthropology Vol. 39 (2010). Mason, Bruce, dan Bella Dicks. 2001. “Going Beyond the Code: The Production of Hypermedia Ethnography” dalam Social Science Computer Review Vol. 19 (2001). 9 Sita Hidayah - Antropologi Digital dan Hiperteks Wilson, Samuel M. dan Leighton C. Peterson. 2002. “The Anthropology of Online Communities” dalam Annual Reviews of Anthropology. Vol. 31 (2002). Wittel, Andreas. 2000. “ Ethnography on the Move: From Field to Net to Internet” dalam Forum: Qualitative Social Research, Vol. 1 No. 1 Art. 21. Januari 2000. Koran Wahyudi, Reza dan Tri Wahono. “Naik 13 Juta, Pengguna Internet Indonesia 55 Juta Orang” dalam www.teknokompas.com edisi 28 Oktober 2011 dan diakses pada tanggal 17 Desember 2011. Zuhri, Sepudin. “Penggunaan Internet belum Produktif” dalam www.bisnis.com edisi 21 Desember 2010 diakses pada tanggal 17 Desember 2011. Mark Plus Insight via “Pengguna Facebook Indonesia 40,8 Juta” dalam www. femalekompas.com. edisi 28 November 2011 dan diakses pada tanggal 17 Desember 2011. Internet Kozinets, Robert V. 2010. “Netnography: the Marketers’s Secret Weapon: How Social Media Understand Drives Innovation” [http://info.netbase.com/rs/netbase/ images/Netnography_WP.pdf] diunduh tanggal 13 Desember 2011. 10 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Dian Ayu Aryani TENTANG SEMBILAN KATA Peduli atau tidak, disadari ataupun tidak, jejaring sosial telah mengalihkan kita untuk berekspresi lebih bebas. Mereka mampu membuat kita untuk berkembang dan tumbuh sebebas mungkin di dunia maya. Menjadi apa yang kita mau apa yang kita sukai. Sedikitnya seperti itu tentang sembilan kata di atas. 11 Nindyo Budi Kumoro - Konsep Diri dan Penyebaran Wacana dalam Cyberspace TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 12-20 KONSEP DIRI DAN PENYEBARAN WACANA DALAM CYBERSPACE: TANTANGAN BAGI PENELITIAN ANTROPOLOGI Nindyo Budi Kumoro1 ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi melahirkan dunia baru bagi manusia, yaitu yang sekarang disebut dengan “ruang maya” atau cyberspace. Struktur cyberspace dalam internet memberi ruang yang bebas bagi setiap individu untuk melakukan tindakan apapun. Orang juga tak lagi pasif menerima informasi-informasi dari media massa, namun dapat secara aktif memproduksi dan menyebarkan informasinya sendiri. Saat ini kekuasaan wacana tidak lagi dipegang oleh pusat-pusat penyebar informasi seperti negara atau media massa melainkan pada setiap individu yang dapat mengakses teknologi informasi. Di sisi lain fenomena ini juga memicu booming informasi di mana orang tak lagi dapat membedakan yang bermanfaat atau tidak, yang pantas atau tidak. Tentunya penggunaan interaksi dalam dunia maya ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat nyata dan membentuk pola-pola baru dalam hubungan sosial manusia. Kata Kunci: cyberspace, realitas, identitas, wacana Pendahuluan Masih ingat peristiwa antre BlackBerry yang berujung rusuh? Memang sebuah fenomena yang menarik, karena sebelumnya orang antre panjang berdesakdesakan biasanya berebut sembako kalau bukan tiket sepakbola. Kejadian ini, berebut sebuah gadget canggih seharga jutaan rupiah yang katanya sudah kena potongan harga. Padahal masih banyak orang Indonesia dengan uang segitu bisa untuk hidup berbulan-bulan. Lalu apa yang menyebabkan semua itu? Mungkin saja taraf hidup orang Indonesia sudah meningkat, tapi mungkin juga karena suatu permasalahan lain: munculnya cyberspace2 sebagai dunia baru 1 Mahasiswa Angkatan 2007 Program Studi S1 Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2 Di sini saya menggunakan istilah cyberspace, ruang maya, dan dunia maya secara bergantian. 12 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 saat ini. Semua orang kini digiring untuk menggunakan internet sebagai dunianya yang “lain”, yang tak kalah penting dari dunia nyata. BlackBerry diperebutkan karena ia adalah alat yang paling populer digunakan orang untuk menjelajah dunia cyberspace. Bukan BlackBerry yang akan saya bahas, namun apa yang membuat alat-alat itu menjadi kebutuhan primer manusia saat ini, yakni realitas dunia maya. Di Indonesia sendiri, orang yang sudah menggunakan internet mencapai kurang lebih 50 juta3, tapi saya yakin jumlah sebenarnya jauh melebihi angka itu. Ini dikarenakan pengguna internet tak hanya dari komputer atau kepemilikan akun web saja, tetapi saat ini hampir semua handphone dapat untuk mengakses internet. Dari waktu ke waktu harga gadget semakin murah hingga menjangkau semua kalangan, juga hampir semua ruang publik telah terkoneksi internet (hotspot, wifi, warnet). Sama saja membicarakan keadaannya di desa dan kota. Walaupun tidak secara aktif menggunakan, tapi semua orang kini “dipaksa” untuk mengenal internet. Lihat saja kebijakan e-KTP, e-pajak, sistem Real Time On-line (RTO) pendaftaan sekolah, sampai ojek online pun di manamana. Artinya kini semua orang disuruh “melek” teknologi. Ia bukan lagi sebuah dunia asing/canggih seperti saat orang tua mendongeng masa depan, namun ia ada di tempat kita duduk saat ini, ada di setiap sudut perkotaan, ia ada di sebuah kampung yang sedang kekeringan, ada di ruang operasi rumah sakit, dan di sudut paling terpencil di dunia sekalipun. Disadari atau tidak, diinginkan atau tidak. Sederhananya, cyberspace telah menjadi fenomena umum dalam masyarakat saat ini. Walaupun menggunakan istilah “maya” (virtual/cyber), namun kita tidak bisa serta merta menilai bahwa ruang tersebut fiktif atau imajiner belaka. Contohnya saja kita bertransaksi secara maya, tapi uangnya bisa kita cairkan untuk membeli sesuatu; atau misalnya kita mempunyai pacar di dunia maya, namun setelah janjian bertemu nyatanya orang itu bisa kita sentuh. Semua itu dikarenakan komunikasi yang berlangsung di dalamnya bersifat aktual, meski segala sesuatu yang hadir di hadapan kita bersifat maya (Supelli dalam Hardiman, 2010:329). Tulisan di bawah ini akan akan membahas bagaimana fenomena ruang maya secara lebih jauh hadir dan bersanding dengan realitas nyata. Selain itu bagaimana kebebasan beridentitas dan berwacana muncul dalam cyberspace mutakhir. Di bagian akhir tulisan secara singkat akan disampaikan uneg-uneg dan pertanyaan saya tentang bagaimana seharusnya peran ilmu antropologi dalam membaca realitas cyberspace ini. 3 Berdasarkan berita detikinet.com <http://www.detikinet.com/read/2010/06/09/121652/1374756 /398/pengguna-internet-indonesia-capai-45-juta> diunduh pada tanggal 1 Desember 2011. 13 Nindyo Budi Kumoro - Konsep Diri dan Penyebaran Wacana dalam Cyberspace Sekilas Tentang Cyberspace Mungkin keadaan di dunia saat ini mirip dengan apa yang digambarkan William Gibson dalam novelnya Neuromancer (1984) bahwa “ruang” tak lagi berbentuk fisik. Ruang itulah yang disebut Gibson sebagai cyberspace, sebuah ruang yang berisi bit-bit data terprogram dalam komputer yang memungkinkan orang saling berkomunikasi. Cyberspace juga disebut sebagai fenomena “pascaruang” yang di dalamnya berlangsung bukan lagi tindakan sosial seperti yang dibicarakan oleh sosiolog klasik, tetapi sebuah teleaksi sosial, yaitu tindakan sosial yang termediasi oleh komputer (Piliang, 2011:62). Di dalamnya kehadiran bukan dalam bentuk ruang-waktu nyata tapi maya, sebuah pelipatan dunia yang menyebabkan perpindahan fisik tak diperlukan lagi. Dalam komunikasi ini representasi diri, peran dan penampilan fisik tersirat dari citra visual dan teks tertulis dalam layar. Singkatnya cyberspace adalah “dunia” dalam dunia. Itulah posisi internet saat ini. Sebagai pemikir awal tentang cyberspace, Jean Baudrillard telah menyebut fenomena ini sejak kemunculan televisi dan media massa yang lain pasca perang dunia di masyarakat Barat. Munculnya media elektronik televisi dalam sekejab membuat kesadaran manusia tentang dunia menjadi mengecil. Dimensi-dimensi ruang dunia dilipat dalam sebuah kotak layar kaca. Hanya dengan menekan remote control kita dapat berkeliling dunia tanpa memindahkan tubuh sedikitpun. Tak hanya itu, realitas yang ada di bagian bumi lain sampai ke kita bukan dalam bentuk fakta atau real tapi direkayasa oleh media agar tampak lebih menghibur, yang oleh Baudrillard disebut simulasi. Dunia cyberspace saat ini merupakan efek lanjut dari gejala simulasi tersebut. Bersamaan dengan perkembangan globalisasi, teknologi membuat dunia ini menjadi apa yang disebut Marshall McLuhan sebagai global village. Realitas simulasi tak terjadi di masyarakat Barat saja namun sudah menjalar ke seluruh dunia. Dunia ibarat menjadi kampung global karena terpasok aras informasi yang sama melalui media massa, televisi, dan media online. Dalam realitas simulasi ini manusia dianggap tak lebih dari “massa diam” yang menerima segala informasi yang datang melalui media populer dan komunikasi hanya berjalan satu arah. Jika Baudrillard dan pemikir awal cyberspace lainnya menganggap era televisi membentuk massa diam dalam kendali informasi terpusat, maka perkembangan cyberspace mutakhir saat ini menunjukkan gejala yang berbeda. Hal ini terutama dengan hadirnya jejaring sosial (social network) seperti Facebook, Twitter, MySpace, Youtube, Yahoo!Messanger, Skype, Kaskus dan lainnya. Ciri pasif massa “diam” sebelumnya yang bersifat fisik (sedentarity) maupun tak dapat merespon mengalami perubahan saat ini. Pertama, individu tidak hanya lebih banyak “diam” secara fisik, namun lebih-lebih pergerakan fisik 14 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 pun terancam punah karena segala aktivitas sosial dan kebutuhan hidup dapat terpenuhi lewat layar komputer. Kedua, manusia tak hanya menjadi obyek pasif yang menerima segala informasi, tapi dapat merespon aktif informasi tersebut bahkan memproduksi informasi itu sendiri. Dengan adanya internet, kita dapat membuat wacana dan berita sendiri dengan efek penyebarannya sekelas dengan media-media massa besar. Setiap individu dapat menyebarkan berita, lagu, filmnya sendiri ke seluruh dunia. Hal ini juga yang membuat jejaring sosial marak di mana-mana dan menjadi fenomena masyarakat saat ini. Ia bagaikan negara yang setiap orang bisa menjadi penduduknya dan bebas berbuat apapun di dalamnya. Jejaring Sosial: Kebebasan Beridentitas dan Berwacana Sebagian besar orang saat ini, lebih-lebih masyarakat perkotaan mempunyai “kehidupan” lain yaitu di dalam akun Facebook, BlackBerry Messenger (BBM) atau Twitter-nya. Ada semacam mitos bahwa hidup kita akan sulit jika tidak meng-update atau tak punya akun jejaring sosial tersebut. Kadangkala ini saya rasakan sendiri, semisal ketinggalan suatu acara atau info-info penting dari teman hanya karena tak meng-update Facebook maupun Twitter, atau kalau tidak, kabarkabar tersebut di-broadcast lewat BBM yang saya sendiri tidak punya. Semakin lama ini membuat orang yang tak punya akun jejaring sosial merasa terasingkan oleh lingkungannya karena orang-orang sekelilingnya telah berkomunikasi lewat internet. Artinya bahwa keterlibatan seseorang ke dalam cyberspace tak hanya keinginan pribadi atau alasan mengikuti trend semata, namun secara sosial kita digiring untuk masuk ke dalamnya. Orang menjadi betah setelah menghuni dan menemukan berbagai kemudahan. Lama-lama orang menjadi sulit lepas, kecanduan dunia maya karena ia membuat orang “takut” ketinggalan informasi. Setelah menghuni dalam dunia cyberspace (baca: jejaring sosial), interaksi individu dengan lain “diwakili” oleh avatar atau perwujudan diri dalam bentuk citra yang ditampilkan dalam layar komputer. Menariknya di dalam jejaring sosial representasi diri dan identitas dapat dikonsep sebebas mungkin. Struktur cyberspace memberi ruang lebar bagi setiap orang untuk menciptakan identitasnya secara artifisial. Dalam Facebook maupun Twitter kita dapat membuat avatar diri sesuai dengan yang diinginkan. Apakah itu tidak mencerminkan diri kita yang sesungguhnya tak jadi soal. Misalnya saja jika kita hendak mengunggah foto untuk profil Facebook pasti akan memilih yang terlihat paling tampan atau cantik. Sudut yang membuat kita terlihat kurang menarik dihilangkan dan kalau perlu di-edit terlebih dahulu. Tak masalah jika foto itu jauh dari wajah kita sesungguhnya. Fotofoto yang lain akan dimasukkan dengan syarat dapat mencerminkan kita sebagai pribadi yang menarik dan ideal. Status, wall, atau twit yang tampil harus menarik, lucu atau sebijak mungkin, bahkan jika ada foto atau komentar dari orang lain 15 Nindyo Budi Kumoro - Konsep Diri dan Penyebaran Wacana dalam Cyberspace yang akan merusak citra kita dengan mudah akan kita hapus. Dengan demikian jejaring sosial bersifat free society (Awang, 2009:105) memberi kesempatan setiap orang menampilkan citra diri ideal yang sulit ditampilkan dalam realitas nyata dikarenakan sekat-sekat sosial tertentu. Ini membuat identitas orang dalam cyberspace tampak manipulatif dan tidak menampilkan citra diri secara utuh. Sejalan dengan hal ini, fenomena lain yang muncul adalah kecenderungan mengunggah foto di manapun kita berada ke dalam jejaring sosial. Seperti halnya jauh-jauh ke tempat wisata, yang paling penting bukan untuk menikmati pemandangan, tetapi mengambil foto kita dan nantinya ditampilkan di Facebook agar semua orang tahu kita pernah ke sana. Tujuan dari semua itu hanyalah untuk mendapatkan penghargaan sosial dan menunjukkan eksistensi semata. Inilah era yang disebut Guy Debord sebagai “masyarakat tontonan” yang segalanya hanya untuk menampilkan citra, penampilan, permukaan artifisial tanpa kedalaman makna (Piliang, 2011:348). Selain konsep diri, aspek cyberspace lain yang penting untuk dicermati adalah kebebasan dalam mengeluarkan wacana. Kebebasan berwacana ini salah satu aspek yang membuat jejaring sosial berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. Tidak seperti jejaring sosial sebelumnya, Facebook muncul dengan fitur update status yang paling menarik minat masyarakat. Bahkan Twitter yang menggeser kepopuleran Facebook hanya memberi fitur twit yang fungsinya mirip dengan update status. Keduanya memungkinkan orang menyuarakan pendapat sebebas mungkin untuk didengar khalayak jejaring sosial. Kita dapat curhat, memprotes sesuatu, menanggapi pendapat, menyiarkan berita, beriklan, menunjukkan posisi, berkuis, dan banyak lagi. Seringkali fitur ini menjadi ajang keluh kesah yang tidak secara eksplisit ditujukan kepada seseorang. Ini seperti seseorang yang berbicara kepada “entah” atau sedang ber-soliloquy4. Misalnya “Kenapa kamu berbeda?”; “bab 3 selesai, lanjut ke bab 4”, maupun menggambarkan kegalauan hatinya: “lalu kapan aku akan diwisuda...” atau “Ya Allah, kapan skripsiku akan selesai?”. Mungkin dikiranya Tuhan memiliki akun Facebook atau Twitter, meskipun jelas yang dituju sesungguhnya bukan Tuhan ataupun sedang soliloquy belaka, tapi bermaksud agar semua orang tahu apa yang sedang dirasakan. Belum tentu dalam dunia nyata orang berani mengungkapkan apa yang ditulisnya dalam status/twit. Tujuannya pun bukan agar doanya terkabul tetapi agar mendapat respon dan mencari perhatian orang lain. Dengan demikian isi hati seseorang kini bukan lagi dimensi pribadi, namun sudah menjadi urusan publik. Publik dipaksa untuk mengetahui, memikirkan, dan menanggapi perasaan seseorang. 4 Yaitu “omongan dengan diri sendiri dalam batin” mengambil istilah Laksono, Soliloquy, dalam Esei-Esei Antropologi, Ahimsa-Putra (ed.) (Yogyakarta: Kepel Press, 2006), 229. 16 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Fenomena status dan twit di atas seperti apa yang dikatakan Abraham Maslow bahwa kebutuhan (needs) manusia telah sampai pada taraf membutuhkan penghargaan dari orang lain (esteem needs) dan pengaktualisasian diri (selfactualization) (Awang, 2009:115) yang merupakan ciri masyarakat urban saat ini. Melalui psikoanalisa Sigmund Freud kita menjadi tahu bahwa situasi diri yang terbahasakan melalui jejaring sosial merupakan id (motif tak sadar), ego (akal rasional), dan super ego (kesadaran sosial), sehingga apa yang dikatakan bukanlah hasil dari diri yang utuh (Ibid. 116). Apa yang disampaikan yaitu antara ketidaksadaran dan juga motif kepentingan tertentu. Dengan adanya fitur penyampaiaan pendapat dalam jejaring sosial tersebut, kekuasaan memproduksi dan menyebarkan wacana berlaku bebas dan menjadi milik semua orang. Apalagi setiap orang dituntut selalu update status atau menulis twit agar mendapatkan eksistensinya. Selain dapat membentuk identitas dan bereksistensi, melalui jejaring sosial wacana dapat diproduksi dan disebarkan terus-menerus dengan bebas. Suatu topik pembicaraan dapat didiskusikan oleh berapapun orang dan di manapun mereka berada. Fitur Trending Topic dalam Twitter dapat menjadi contoh. Fitur ini menampilkan wacana yang paling banyak didiskusikan oleh “rakyat” Twitter di seluruh dunia. Ini membuat orang dengan mudah mengerti dan mengobrolkan apa yang sedang tren di dunia setiap harinya. Lewat Twitter dunia benarbenar merealisasi gagasan global village McLuhan. Penduduk sedunia dapat memperbincangkan satu topik seperti halnya orang-orang yang sedang mengobrol di pos ronda kampung. Jangan berharap sebuah diskusi yang berbobot, mendalam dan bermanfaat, karena orang dengan mudah dapat offline atau berpindah topik. Orang juga mudah lupa akan sebuah wacana yang didiskusikan karena banyaknya wacana lain setiap harinya. Di dunia internet informasi penting bercampur baur dengan informasi remeh-temeh sehingga tak ada beda antara “yang penting” dan “yang tidak penting” (Supelli dalam Hardiman, 2010:343). Efek lanjut dari booming informasi ini dapat berakibat menggeser nilai dan norma yang ada di masyarakat menjadi semakin permisif. Konsep cyberspace sebagai free society dan open society (Awang, 2009) membuat orang dengan mudah dapat masuk dan berbuat di dalamnya. Bentuk komunikasinya yang tidak tatap muka seringkali membuat nilai dan norma yang ada di masyarakat diabaikan. Kemudahan untuk mengakses cyberspace membuat lenyapnya batas antara anak dan dewasa, ketika anak-anak dapat melihat tontonan-tontonan dewasa (video porno atau kekerasan). Orang lama-lama juga akan kehilangan kepedulian dan sensivitas secara sosial ketika semua kebutuhan hidup tercukupi tanpa tatap muka (online). Sebagaimana pasar yang dulunya tempat terjalinnya relasi sosial, saat ini hilang tergantikan dengan logika kepraktisan, individual, 17 Nindyo Budi Kumoro - Konsep Diri dan Penyebaran Wacana dalam Cyberspace dan ekonomis semata. Lenturnya komitmen dan ikatan tanggung jawab dalam cyberspace kerap digunakan sebagai wadah untuk cybercrime, seperti ancaman, penipuan, pelecehan seksual. Dunia maya yang menawarkan sejuta pesona baru dapat membuat kita terlena dan melupakan realitas sosial sesungguhnya di sekitar. Walaupun demikian, kebebasan yang luas dalam berwacana dapat menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, kreativitas dan mengimbangi kekuasaan informasi dari media-media besar. Lewat Twitter berita yang datang bisa kita tanggapi dan sanggah; lewat Youtube film yang kita tonton bisa kita parodikan; lewat Facebook masyarakat dapat melakukan gerakan sosial melawan ketidakadilan5; lewat blog kita dapat menyebarkan gagasan; fenomena citizen journalism bahkan membuat individu dapat memproduksi berita yang aksesnya sama dengan media-media besar6. Fenomena ini mempertegas pendapat Michel Foucault bahwa kekuasaan sudah tidak terpusat tetapi menyebar. Kuasa wacana (informasi) sekarang ada di tangan individu yang mempunyai akses teknologi informasi. Jika Foucault sebelumnya berpendapat kekuasaan bersumber pada kuasa pengetahuan (power/knowledge), maka sekarang juga ditentukan oleh kuasa kecepatan (power/speed), yaitu mereka yang mempunyai kecepatan mengakses informasi, kecepatan menyebarkan wacana, kecepatan mengetahui hal baru, dan kecepatan mengikuti perkembangan teknologi baru (Piliang, 2011:82). Penutup: Sikap Antropologi dalam Cyberspace Perkembangan jagad Teknologi Informasi yang sangat pesat melahirkan adanya cyberspace “generasi kedua”, yaitu orang tidak hanya pasif mendapatkan informasi dari seluruh dunia, namun setiap orang di seluruh dunia sudah dapat memproduksi dan menyebarkan informasinya sendiri. Tidak hanya itu, kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan internet membuat realitas-realitas sosial di dunia nyata dapat “dipindahkan” ke dunia maya. Setiap orang dapat berinteraksi, membentuk komunitas, bermasyarakat dan berkebudayaan melalui avatar-avatar yang diciptakan dalam jejaring sosial. Pada kenyataannya relasi yang terbangun melalui cyberspace telah mengurangi hubungan face to face secara substansial; diri hanya ditampilkan oleh citra yang dapat direkayasa; struktur cyberspace yang bebas membuat lemahnya komitmen dan tanggung jawab pada relasi sosial yang dibangun; nilai dan norma di masyarakat terancam hilang karena relasi sosial yang terbangun hanya bersandar pada logika kepraktisan, penampilan dan ekonomis semata. Realitas cyberspace ini bukan semata-mata realitas semu yang terpisah 5 Seperti halnya gerakan 1 juta Facebookers dukung Bibit-Chandra atau Prita. 6 Baru-baru ini Metro TV meluncurkan program baru yang bertemakan citizen journalism, yang menayangkan liputan berita yang dibuat oleh masyarakat. 18 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 dari dunia nyata, tapi mempunyai implikasi riil di masyarakat. Bahkan bisa jadi dengan semakin terjangkaunya teknologi semua orang lebih memilih berkomunikasi melalui cyberspace. Lantas tidak ada lagi batas-batas geografis maupun kultural, karena orang dapat berinteraksi dan membangun komunitas dengan orang lain di seluruh dunia. Ini menyebabkan akan sangat usang jika kita membicarakan esensi kebudayaan dari sebuah masyarakat “nyata”. Dalam konteks perubahan ini, tentunya antropologi sebagai ilmu yang membaca realitas sosial budaya di masyarakat mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan adanya realitas cyberspace. Bukankah cyberspace juga sebuah “dunia” atau “ruang” yang di dalamnya terdapat “masyarakat” dengan “kebudayaannya” sendiri? Jika benar, maka bagaimana dengan persoalan metodologis antropologi paling tidak dalam rangka “to grasp the native’s point of view”? Selain itu jika semua orang telah saling berinteraksi di dalam cyberspace, apakah antropolog masih harus blusukan seperti halnya observasi partisipasi di Petungkriyono? Munculnya istilah etnografi internet atau netnografi mungkin sebuah upaya agar antropologi dapat masuk dan melihat realitas cyberspace secara lebih dalam. Kelihatannya akan muncul persoalan jika kita masih menggunakan sudut pandang etnografi konvensional walaupun praktiknya dalam dunia internet. Pertama, Seperti yang kita tahu sebelumnya, dengan adanya globalisasi informasi seperti saat ini kita akan sulit menemukan simbol-simbol yang esensial dari sebuah kebudayaan karena individu sudah mengalami pengayaan budaya dari mana saja melalui internet. Kedua, tak adanya komunikasi yang face to face di internet membuat kita tidak bisa secara langsung mengidentifikasi realitas sosial yang melatarbelakangi informan yang sebelumnya merupakan bagian dari sensibilitas etnografi. Serangkaian teknis dan analisis wawancara mengalami hambatan karena kita tidak memahami konteks sosial di mana ia berada (Abdullah, 2006:23). Ketiga, individu-invividu yang hanya terwakili oleh avatar ini membuat kita sulit untuk menetapkan informan atau subyek yang akan diteliti. Kita tidak akan tahu mana orang-orang yang paling representatif untuk dijadikan informan. Keempat, kebebasan membuat identitas diri dan berwacana membuat tak bisa mengambil data “lapangan” dari apa yang tertampilkan dalam cyberspace karena segalanya mengandung unsur rekayasa dan manipulasi. Kelima, interaksi sosial dalam cyberspace bisa saja merupakan “pindahan” dari interaksi sosial yang terjadi di dunia nyata sebelumnya, sehingga makna-makna dari relasi sosial yang terjalin mudah ditangkap. Lebih banyak dunia maya saat ini membangun realitasnya sendiri yang hanya bersandar pada logika pencitraan, ekonomis, individualistis sehingga makna-makna yang terlihat 19 Nindyo Budi Kumoro - Konsep Diri dan Penyebaran Wacana dalam Cyberspace terkesan dangkal. Dengan demikian pembacaan etnografis dari suatu realitas cyberspace dengan mudah dapat ditebak. Persoalan-persoalan di atas memang tidak mudah dipecahkan. Diinginkan atau tidak, teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Diperlukan penelitian lebih lanjut secara antropologis untuk mendapatkan metodologi yang mampu membaca realitas cyberspace, agar ilmu antropologi tetap relevan dalam mengikuti perkembangan zaman. Bibliografi Buku Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ahimsa-Putra, Heddy Shri (ed.). 2006. Esei-Esei Antropologi: Teori, Metodologi, dan Etnografi. Yogyakarta: Kepel Press. Hardiman, F. Budi (ed.). 2010. Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius. Laksono, Paschalis Maria. 2011. Memahami Kebudayaan (Indonesia) Dari Perspektif Antropologi. Bahan untuk Pembahasan RUU Kebudayaan dari Pendamping Ahli Komisi X DPR untuk Pembahasan RUU Kebudayaan. Piliang, Yasraf Amir. 2011. Sebuah Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui BatasBatas Kebudayaan. Bandung: Matahari. _______________. 2004. Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra. Spradley, James P. 2007. Metode Etnografi, edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana. Jurnal Awang, E.N.R. 2009. “Dunia Maya Sebagai Media Komunikasi Alternatif: Studi Facebook Sebagai Menia Komunikasi Virtual” dalam Majalah Dimensi vol.7No.1 hal. 105, 2009. Internet Djibran, Fahd. 2011. Cyberculture, Transformasi Kebudayaan Pascaruang, dan Bayangbayang Kematian Sosial, 2007 <http://komahi.umy.ac.id/2010/12>, diunduh 25 November 2011. Hidayat, Medhy Aginta. 2011. Kebudayaan Posmodern Menurut Jean Baudrillard, <http://elasgary.wordpress.com/2011/09/11/>, diunduh 25 November 2011. 20 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Muhammad Arief Al Fikri DUNIA TANPA BATAS Internet adalah media serbaguna. Di dalamnya, manusia bisa dengan bebas melakukan apa saja. Jaringan-jaringan yang terjalin di situ tidak akan pernah melarang manusia untuk mengekspresikan apa saja. Justru manusialah yang membuat larangan atau peraturan tersebut, karena pada hakikatnya manusia jugalah yang menciptakan internet. Pada jaringan internet yang sungguh kompleks itu, manusia bisa memindahkan kegiatan yang biasanya dilakukan di “kehidupan nyata” ke suatu dunia yang seakan tanpa sekat ruang dan waktu. Kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya berdagang, memamerkan foto, merekam video, mengobrol dengan teman atau bahkan orang yang tidak dikenal, dan masih banyak lagi. Ajaibnya, manusia dari belahan dunia manapun dapat mengakses atau menyaksikan itu semua secara bersamaan, meskipun misalnya di sini siang dan di sana malam, di sini ujung utara dan di sana ujung selatan. 21 Rio Heykhal Belvage - Budaya Manusia Digital TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 22-28 BUDAYA MANUSIA DIGITAL Rio Heykhal Belvage1 ABSTRAK Fenomena cyberspace sudah bukan lagi hal yang wah di masyarakat kita—terutama di perkotaan. Komunikasi manusia di cyberspace dengan sesamanya terjalin melalui teks, gambar, video dan suara. Manusia mengenali dirinya melalui hal itu— yang entah disadari ataupun tidak merepresentasikan identitas manusia cyber. Melalui pendekatan eksistensialisme saya akan mencoba menerapkan bagaimana aliran filsafat ini berbicara ketika ia digunakan untuk meneropong dunia cyberspace— dengan disertai beberapa penerapan dari konsep yang dicetuskan oleh para pemikir kebudayaan. Kata Kunci: cyberspace, manusia cyber, kebudayaan, digital “Mereka tak lekang oleh ruang maupun waktu. Mereka terus tumbuh, terjaga dalam centang-perenang dunia. Sebuah dunia karya manusia yang lebih dikenal dengan nama cyberspace. Di dalamnya manusia adalah teks, manusia adalah gambar, ia adalah suara, video—dan oksigen yang merupa uang.” Pendahuluan Eksistensi dalam KBBI (2008:378) diartikan sebagai “keberadaan”. Dalam dunia filsafat, istilah ini identik dengan jenis aliran pemikiran yang digagas oleh Soren Abey Kierkegaard. Dia adalah seorang filsuf Denmark, murid Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang tidak sepakat dengan proyek besar gurunya saat hendak merangkum filsafat menjadi satu kesatuan dan kebenaran tunggal yang mencakup semua hal. Demi membatasi ruang penulisan agar tak jauh melenceng dari tema yang akan dibahas, saya tidak akan menerangkan lebih jauh perihal apa itu eksistensialisme. Di sini saya akan mencoba menerapkan bagaimana aliran filsafat ini ketika digunakan untuk meneropong dunia cyberspace—dengan disertai 1 Alumni Program Studi S1 Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 22 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 beberapa penerapan dari konsep yang dicetuskan oleh para pemikir kebudayaan. Pada pendahuluan ini perlu saya sampaikan bahwasanya meski mungkin pembaca akan menganggap tulisan ini sebagai imajinasi belaka, akan tetapi bukan di situ poinnya, melainkan saya ingin mengajak pembaca yang setia pada pandangan teoritis untuk sekali-kali keluar dari “kotak” dengan kemampuan imajinasi yang dimiliki. Saya beranggapan bahwa tanpa campur tangan imajinasi, ilmu pengetahuan ibarat padang gersang yang sama sekali tidak menarik untuk dilalui. Di sini saya akan membuktikan bagaimana imajinasi juga mampu menyajikan hasil analisis yang menarik. Terkait dengan tema tulisan ini, bukankah cyberspace juga bermula dari konstruksi imajiner yang akhirnya menciptakan sebuah dunia? Sebuah dunia yang sebelumnya hanya berada dalam angan seperti dalam novel Neuromancer (1984) karya William Gibson. Dunia dalam Cyberspace Pengertian cyberspace seperti yang kita tahu adalah dunia maya. Alangkah lebih baik jika di sini dikemukakan terlebih dahulu definisi cyberspace sebagai syarat tulisan ilmiah. Telah banyak pemikir kebudayaan mendefinisikan apa itu cyberspace, namun saya lebih tertarik untuk mengikuti definisi si pembuat istilah cyberspace sendiri. Menurut Gibson, cyberspace dipahami sebagai sebuah “dunia” di mana masyarakat berkomunikasi secara virtual melalui jaringan komputer2. Fenomena cyberspace sudah bukan lagi hal yang wah di masyarakat kita—terutama di perkotaan. Akhir-akhir ini kita bisa dengan mudah menjumpai fenomena cyberspace. Dari cyberspace dalam monitor berukuran 14 inch sampai monitor selebar cermin bedak. Di mana ada sinyal, di situ ada cyberspace. Kadang kita jadi penonton, namun tak jarang juga kita jadi pelaku di dalamnya. Tidak perlu dipertanyakan lagi, cyberspace memang sebuah fenomena menarik. Bukan cuma menarik untuk dinikmati, tapi juga menarik untuk dikaji, dijadikan hidangan di meja akademis. Cyberspace adalah sebuah produk yang menandai tingginya ilmu pengetahuan saat ini. Tanpa kejeniusan manusia menyatukan ilmu pengetahuan dan imajinasi (dalam hal ini para ilmuwan di bidangnya), tak akan ada cyberspace. Kita tidak akan mengenalnya. Industri teknologi tak akan menciptakan sebuah budaya konsumsi yang semeledak sekarang dan tak ada kajian mengenai cyberspace—yang berarti mustahil tulisan ini ada di depan pembaca. Telaah mengenai cyberspace bukan hal baru. Jejaknya sudah tampak sejak beragam konsep lahir dari para pemikir postmodernisme, seperti Althusser, Baudrillard, Barthes, Deleuze-Guattari, sampai yang lokal: Piliang. 2 Definisi diambil dari <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/05> diakses 6 Desember 2011. 23 Rio Heykhal Belvage - Budaya Manusia Digital Menggunakan istilah Piliang (2006), saya membayangkan cyberspace sebagai sebuah tempat di mana ruang, waktu, benda, dan juga manusia mampat ke dalam satu dunia. Sebuah dunia lain yang disusun sedemikian rupa dengan sistem yang kompleks, mulai logam, optik, sampai jaringan kabel yang dialiri listrik. Sebuah dunia “lain”, berarti lain pula ruang dan waktu yang berlaku di dalamnya. Kalau boleh saya mengutip sebuah buku yang berjudul Dunia yang Dilipat perihal dunia cyber, penulis buku tersebut memberi gambaran cukup menarik untuk disampaikan di sini: “Pada abad 21 ini pengertian waktu di dalam batasan ruang yang ada telah lenyap. Kita hidup di dalam awal miniaturisasi aksi dan waktu yang bersifat paradoks. Pengerutan waktu, lenyapnya ruang teritorial membawa pada situasi di mana pengertian masa lalu dan masa kini lenyap di dalam kecepatan citraan waktu di dalam media simulasi. Dengan dikuasainya medan dan teritorial oleh waktu, maka yang menjadi persoalan sosial abad ke-21 tak lain dari permainan waktu semata” (Piliang, 2006:237). Bisa dibayangkan, ruang dan waktu di dunia sungguhan yang semula tak lepas dari rezimentasi dan kapitalisasi kini memperoleh kemerdekaannya di dunia cyber. Kesadaran manusia berubah, ruang dan waktu yang semula mengontrol perilaku namun di dalam dunia cyber, manusia bisa dengan mudah melenturkannya. Di dunia cyber setiap ruang adalah liminal, begitu juga dengan waktu. Dalam hitungan detik manusia bisa beralih dari satu ruang ke ruang lain, dalam hitungan detik manusia bisa beralih dari satu waktu ke waktu yang lain. Ia bisa bertemu masa lalu melalui video-video rekaman di Youtube misalnya, atau ia juga bisa berpindah dari ruang religius (website yang berisi pengetahuan tentang religi) ke ruang tabu (bokep, pornografi). Begitulah gambaran umum tentang sebuah dunia. Dunia cyber, sebuah dunia yang sama sekali lain dari dunia yang dikenal manusia pada abad-abad sebelumnya. Manusia dalam Cyberspace Seperti yang telah diungkapkan di bagian awal tulisan ini, tubuh manusia cyber tersusun dari rangkaian organ non-biologis yang mampu berdiri sendirisendiri. Singkatnya, eksistensi manusia cyber bukan diwakili oleh tubuh secara nyata, melainkan diwakili oleh teks, oleh gambar, video, dan suara. Semakin banyak ia diwakili oleh organ-organ tersebut, semakin eksis ia dalam dunia cyber. Jika dibandingkan dengan dunia nyata, pakem etika-moral dalam dunia cyber lebih renggang. Seperti yang telah saya sampaikan, dunia cyber pada akhirnya 24 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 menjadi semacam area pembebasan terhadap segala macam rezimentasi—karena bagaimana mungkin merepresi ide dan imajinasi dalam dunia yang bebas? Hal ini bukan kemudian bebas diartikan sebagai lepas dari tanggung jawab dan komitmen. Tetap ada polisi di sana (cyber-law). Hanya tak seketat seperti di dunia nyata. Komunikasi manusia cyber dengan sesamanya terjalin melalui teks, gambar, video dan suara. Ia mengenali dirinya melalui hal itu—yang entah disadari ataupun tidak hal tersebut merepresentasikan identitas manusia cyber. Ketika dalam dunia nyata manusia tidak bisa memperoleh eksistensi seperti yang dikehendakinya, eksistensi masih bisa didapat di dunia cyber. Di dalamnya, manusia bisa hidup gagah dengan idenya, dengan alter-ego, dengan hasratnya, dan dengan imajinasinya. Seperti di dunia sungguhan, ada beragam karakter manusia yang bisa dengan mudah ditemui dalam dunia cyber. Tinggal mengakses www.google.com dan kita tuliskan kata kunci, kita bisa bertemu manusia-manusia cyber bertebaran di sana, dari karakter yang seolah memberi kesan serius, religius, sampai karakter yang humoris, nakal, dan lain sebagainya. Jangan dikira di dunia cyber tak ada siklus kehidupan seperti halnya di dunia sungguhan. Dalam dunia cyber juga ada yang namanya kelahiran, rejeki, jodoh, dan kematian. Hanya saja kuasa tersebut bukan berada pada tampuk kekuasaan Tuhan, melainkan di tangan manusia cyber itu sendiri. Kelahiran adalah saat manusia meninggalkan jejak dan bergabung dalam jejaring sosial di dunia cyber, entah itu berupa teks, gambar, suara maupun video—entah itu Facebook, Twitter, web, ataupun blog, dan lain-lain. Siklus rejeki misalnya saat manusia mencoba peruntungan dagang di dunia cyber, siklus jodoh saat manusia mendapat kenalan baru dan kencan dalam dunia cyber. Manusia juga bisa mati di dalamnya, setelah ia menon-aktifkan segala akun jejaring sosial yang sebelumnya ia miliki karena tidak mendapatkan ekstasi seperti yang diharapkan. Di dunia cyber bukan berarti kemudian manusia terbebas dari berbagai tindakan orang yang punya niatan jahat. Kejahatan tetap berlangsung, seperti pencurian dan pembunuhan. Barangkali masing-masing dari kita juga pernah merasakannya, merasakan siklus kehidupan dan bentuk kejahatan dalam dunia cyber. Kebudayaan dalam Cyberspace Ada dunia, ada manusia, tentu juga ada kebudayaan. “Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia” (Koentjaraningrat, 1990:180). Jika di dunia nyata Koentjaraningrat mendefinisikan mengenai tujuh unsur yang membentuk suatu kebudayaan dalam masyarakat, pada bagian ini saya akan mencoba meneropong kebudayaan masyarakat cyber melalui tujuh unsur seperti yang didefinisikan oleh antropolog kawakan tersebut. 25 Rio Heykhal Belvage - Budaya Manusia Digital Bahasa. Dalam kehidupannya di dunia cyber, manusia memiliki beragam bahasa; dari bahasa tanda yang berupa gambar, sampai bahasa lisan dan tulisan. Misalnya bahasa tanda, kita bisa membayangkan dalam sebuah jejaring sosial komunitas fotografi, percakapan yang berlangsung di sana adalah percakapan yang disampaikan melalui objek gambar dan warna. Meski kebudayaan manusia cyber hanya berada dalam dunia cyber, namun tetap tidak menutup kemungkinan adanya bentuk rezimentasi—sebab bukankah bahasa merupakan wajah lain dari kolonialisme? Saat kita mulai bermigrasi dari dunia nyata ke dunia cyber, yang paling sering kita temui adalah jenis bahasa Inggris. Kenapa demikian? Silahkan dijawab sendiri. Kepercayaan dan Organisasi Sosial. Ada banyak ragam kepercayaan dalam dunia cyber dan setiap manusia cyber bebas memilih kepercayaan mana yang menjadi keyakinannya. Kepercayaan berasal dari kata dasar “percaya”. Saat manusia cyber sudah menyerahkan kepercayaannya pada salah satu jejaring sosial misalnya, maka pada saat yang bersamaan manusia cyber sudah menjatuhkan pilihannya. Perlu ditegaskan bahwa kepercayaan yang saya maksud berbeda dengan agama. Kepercayaan lebih bersifat personal, tidak butuh institusi seperti halnya agama. Contoh kepercayaan yang sedang populer misalnya Facebook dan Twitter. Saat sebelum tidur dan bangun pagi, tak lupa kita “beribadah”, membuka Facebook atau Twitter untuk sekedar mengecek ada pesan masuk atau tidak. Selain kepercayaan, jejaring sosial juga bisa menciptakan organisasi sosial baru. Ketika dalam suatu jejaring sosial terbentuk beberapa komunitas, misalkan komunitas sepeda, komunitas penggemar kopi, komunitas film, komunitas sastra, dan lain sebagainya, di situlah organisasi sosial manusia cyber terjalin. Kesenian dan Teknologi. Ada banyak ragam kesenian dalam dunia cyber—bahkan bukan lagi bisa dibilang banyak, melainkan semua kesenian yang pernah kita dengar dan kita tahu di dunia nyata semua ada di sana. Dari mulai taritarian, teater, seni rupa, seni lukis, dan banyak lagi lainnya. Kesenian-kesenian dalam dunia cyber diangkut dari dunia nyata ke dunia cyber melalui teknologi tinggi yang bisa menghentikan ruang dan waktu (kamera dan video). Berkat munculnya teknologi-teknologi tinggi ini jugalah dunia cyber ada dan bisa kita nikmati sekarang. Sudah sepatutnya kita berterima kasih pada para pembuat teknologi tinggi tersebut, yang membuat kita lupa bahwa estetika seni dikenal melalui keotentikannya. Mata Pencaharian. Dalam dunia cyber ada banyak sekali mata pencaharian yang bisa ditemukan. Mulai dari bisnis pemasaran sampai pasar cyber yang di dalamnya berkumpul pedagang dari semua kalangan. Dunia cyber membuka peluang kerja yang instan dan lebih praktis bagi manusia cyber yang 26 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 kreatif. Sebab dalam dunia cyber kreatifitas lebih unggul daripada gelar akademis dan bukan sebaliknya seperti yang terjadi di dunia nyata. Ilmu Pengetahuan. Dunia cyber memang lebih praktis dan instan, termasuk dalam konteks ilmu pengetahuan (maupun pengetahuan). Dapat dibayangkan betapa ajaibnya saat hampir sebagian besar ilmu pengetahuan manusia sejak kemunculan manusia pertama di bumi sampai sekarang mampat jadi satu dalam sebuah dunia yang lain, dunia cyber. Industri ilmu pengetahuan dalam dunia nyata yang semula berada dalam etalase-etalase mewah, kini bisa diakses oleh siapa saja. Ilmu pengetahuan pada akhirnya menjadi lebih manusiawi— meski tak dapat dikesampingkan adanya distorsi-distorsi dalam penyampaiannya kepada manusia. Refleksi Berbicara tentang dunia cyber, manusia cyber dan alam kebudayaan manusia cyber, adalah proses belajar untuk mengenali diri dengan liyan. Saya sendiri adalah bagian dari mereka, orang-orang cyber. Saya hidup di dalamnya dan saya juga berkebudayaan seperti mereka. Mungkin begitu juga Anda, atau semua orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Inilah fenomena sosio-kultural di mana perubahan demi perubahan terus berlangsung. Begitu juga dengan antropologi. Seorang pengamat ibarat seekor semut yang mencoba menggambarkan bentuk seekor gajah, dan bukan sebaliknya. Penjelasan di atas tentu masih sebatas permukaan saja. Setiap bagian dalam tulisan ini sangat bisa untuk dikritik maupun ditelisik lebih jauh. Inilah usaha manusia yang berposisi sebagai semut ketika mencoba menjelaskan bentuk induk seekor gajah bernama netnografi. Bibliografi Buku Piliang, Yasraf Amir. 2006. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra. Geertz, Clifford. 1992. Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Hardiman, Budi. F. 2010. Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius. Laksono, Paschalis Maria. 2011. Memahami Kebudayaan (Indonesia) Dari Perspektif Antropologi. Bahan untuk pembahasan RUU Kebudayaan dari Pendamping Ahli Komisi X DPR untuk pembahasan RUU Kebudayaan. 27 Rio Heykhal Belvage - Budaya Manusia Digital Lyotard, Jean-Francois. 2009. Kondisi Postmodern: Suatu Laporan mengenai Pengetahuan. Surabaya: Selasar Surabaya Publishing. O’Donnell, Kevin. 2009. Sejarah Ide-ide. Yogyakarta: Kanisius. Tim Redaksi Sugono, Dendy dkk. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional. 28 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Dian Ayu Aryani DUA DIMENSI, DUA GENERASI Apakah waktu pernah memaksa kita untuk diasingkan atau mengasingkan dunia? Ketika era modern telah muncul dengan berbagai teknologi canggih, riil adanya untuk duduk seolah berdiam diri dalam sepi. Pada nyatanya eksistensi dalam relasi telah dijalin lebih hebat di dunia baru yang bernama dunia maya. Berbagai kafe, restoran, dan kafe baca saat ini didesain sedemikian rupa sehingga menjadi tempat nongkrong favorit masyarakat urban. Laki-perempuan, tua-muda banyak ditemui di tempat-tempat seperti ini, sendiri atau bersama kerabat dekat. Apalagi jika tersedia fasilitas wireless fidelity (wi-fi). Sekarang ini para pelanggan tidak hanya pesan makan-minum di kafe atau membaca di perpustakaan, tapi juga berselancar di dunia maya. Bahkan keinginan berinternetlah yang acap kali menjadi niat utama mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Seperti yang sering dijumpai, mereka paling banyak memilih tenggelam atau ditenggelamkan oleh dunia jejaring sosial, sadar atau tidak sadar. Interaksi dengan teman, keluarga, atau pelanggan lain kerap terdistorsi oleh interaksi jejaring sosial di dunia maya. Ambiguitas antara yang nyata dan maya pun tercipta; yang manakah sebenarnya dunia nyata dan dunia maya? Di manakah mereka sebenarnya hadir? 29 Gaffari Rahmadian - Jejaring Sosial: Memupus Sekaligus Mengalienasi TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 30-36 JEJARING SOSIAL: MEMUPUS SEKALIGUS MENGALIENASI Gaffari Rahmadian1 ABSTRAK Jejaring sosial sebagai sebuah fenomena sosial yang berkembang di Indonesia ditandai dengan kemunculan Friendster pada tahun 2000-an. Maraknya jejaring sosial sebagai sebuah fenomena sosial ini tidak terlepas dari pengaruh ekonomi kapitalis yang berkembang di Indonesia sendiri yang selanjutnya membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat konsumsi. Dalam analisisnya Marx mengatakan bahwa keterputusan pekerja dari barang yang diproduksi akhirnya mengalienasi pekerja di dalam masyarakat yang kapitalis. Lalu ketika masyarakat kapitalis tersebut bertransformasi menjadi masyarakat konsumtif bentuk alienasinya pun berubah. Hal inilah yang saya lihat dalam fenomena jejaring sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini. Kata Kunci: jejaring sosial, alienasi, interaksi, kapitalisme Pendahuluan Jika kita berbicara jejaring sosial pikiran kita pasti akan tertuju pada dunia maya yang di dalamnya terdapat Facebook dan Twitter. Hal ini tidak salah mengingat betapa masifnya media massa mengiklankan Facebook dan Twitter baik sebagai alat jual sebuah produk, smartphones misalnya atau sebagai sebuah fenomena sosial. Masifnya pemberitaan tersebut tidak terlepas dari popularitas jejaring sosial di masyarakat. Popularitas jejaring sosial di dalam masyarakat ini menyisakan pertanyaan, mengapa jejaring sosial begitu populer di masyarakat Indonesia? Apa yang ditawarkan oleh jejaring sosial tersebut? Apa yang ingin diungkapkan orang melalui jejaring sosial? Lalu apa yang bisa kita tangkap dari fenomena maraknya pengguna jejaring sosial? Untuk menjawab pertanyaan di atas saya mencoba melihatnya melalui teks-teks yang beredar di jejaring sosial, terutama Facebook dan Twitter. Dari 1 Mahasiswa Angkatan 2011 Program Studi S2 (Pascasarjana) Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 30 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 penangkapan saya mengenai teks-teks tersebut saya mencoba melihat lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi sehingga jejaring sosial begitu populer. Alienasi menurut Karl Marx terjadi karena “di bawah kapitalisme semua agen-agen pasar, dalam hal ini pekerja, produsen kecil, dan pemilik modal besar harus menjual baik tenaga kerja mereka atau barang sebagai komoditas abstrak di dalam pasar untuk dipertukarkan dengan uang yang kemudian digunakan oleh mereka sebagai konsumer untuk membeli komoditas-komoditas abstrak lainnya. Hasilnya adalah orang, ketimbang terhubung satu sama lain melalui produksi dan distribusi barang, terhubung melalui pasar sebagai agen-agen kecil yang untuk memperoleh informasi mengenai seberapa bagus sebuah barang diproduksi menggunakan kebutuhan individual mereka untuk menentukan pilihan pasar” (Marx dalam Fridell, 2007:4). Artinya, alienasi terjadi karena relasi sosial tidak terjadi antar personal, namun terjadi melalui perantara pasar dalam kegiatan konsumsi. Alienasi juga terjadi, menurut Lasch, karena “masyarakat kapitalis menempatkan mereka dalam posisi yang bertentangan satu sama lain di dalam lingkungan kompetitif tingkat tinggi dalam mencari pekerjaan dan keabsahan. Sementara itu pada saat yang bersamaan, orang dibebaskan dari ikatan-ikatan institusi (agama) dan kekeluargaan, yang pada akhirnya meninggalkan perasaanperasan kesepian serta terisolasi. Hal ini pada akhirnya memunculkan impulsimpuls narsistik. Untuk melawan perasaan terisolasi itu, lanjut Lasch, kapitalisme menawarkan konsumsi sebagai penyembuh” (Lasch via Fridell, 2007:8). Senada dengan Lasch, Baudrillard mengatakan bahwa dalam masyarakat saat ini, yang dia sebut sebagai masyarakat konsumsi, alienasi tidak hanya terjadi ketika kita kehilangan—atau menjual citra, imaji dan bayangan diri, namun ketika sebuah hasil kerja selesai diproduksi dan mulai diobjektifikasi (Baudrillard dalam Putranto, Hendar dan Mudji Sutrisno ed., 2005:264). Artinya alienasi saat ini terjadi ketika barang hasil produksi menjadi objek. Oleh karena itu media massa, lanjut Baudrillard, menjadi mukjizat dalam liturgi objek (Ibid.) Mengenai masyarakat konsumsi sendiri, Roberta Sassateli mengatakan jika masyarakat konsumsi adalah masyarakat yang kebutuhan sehari-harinya dipuaskan oleh cara-cara kapitalis melalui akusisi komoditas, maka hal itu juga terjadi ketika setiap konsumen harus terhubung secara terus-menerus dalam reevaluasi objek-objek tersebut melampaui harganya, untuk menstabilkan makna dan relasi sosial. Jejaring Sosial 31 Jejaring sosial merupakan situs pertemanan dalam bentuk halaman Gaffari Rahmadian - Jejaring Sosial: Memupus Sekaligus Mengalienasi elektronik. Bentuk dari jejaring sosial ini sangatlah beragam. Ada Friendster, yang menawarkan fasilitas menyimpan foto dan berkomentar antara satu dan pengguna yang lain. Jejaring sosial Friendster tersebut mulai booming pada tahun 2003 akan tetapi popularitasnya menurun dan digantikan oleh popularitas Facebook. Facebook sendiri menawarkan fasilitas untuk mengunggah foto, membuat status, membuat hubungan kekerabatan. Sementara itu Twitter, menawarkan penggunanya kemampuan berekspresi dalam 140 karakter, mengikuti/diikuti pengguna lain, dan mengutip kata-kata yang dituliskan oleh pengguna lain. Meskipun kemampuan setiap jejaring sosial berbeda, media ini menawarkan hal yang sama, yaitu berekspresi dan menjalin relasi dengan orang lain. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Tempo pada tanggal 5 Agustus 2008, Facebook untuk sementara mengungguli situs-situs jejaring sosial lainnya. Pertumbuhannya terbilang pesat, 135 persen per tahun. Berdasarkan data comScore, sebuah lembaga metrik online, Facebook memiliki 132,1 juta pengguna unik sampai Juni 2011 lalu. Lebih lanjut, Hermawan, dalam Kompas pada tanggal 7 September 2009, mengatakan bahwa, “penduduk di Facebook memiliki rata-rata 120 kawan. 30 juta orang terus mengabarkan statusnya setiap hari paling tidak sekali. Salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan jumlah pengguna Facebook adalah mobile connector. Di dunia, ada sekitar 65 juta user aktif yang mengakses jejaring sosial ini lewat handphone. Menurut data yang dikeluarkan oleh Facebook, user yang menggunakan aplikasi Facebook di handphone praktis menjadi 50 persen lebih aktif ketimbang mereka yang non Facebook-mobile. Sejak Juni 2009 lalu, menurut kabar, Facebook telah menjadi web nomor satu yang paling sering diakses oleh orang di Indonesia yang kini jumlah pengguna internet diperkirakan sekitar 31 juta orang”. Menurut Suci Lestari Yuana melalui tulisannya di forum Kompas tertanggal 21 Desember 2010, jejaring sosial ini telah berhasil menyentuh hampir seluruh kalangan masyarakat, tua-muda, pelajar-karyawan, lebih-lebih dengan adanya persaingan ketat provider seluler untuk memberikan layanan internet tanpa batas dengan biaya yang cukup murah, sosial media pun bisa dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Dari data yang diambil melalui media elektronik di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan jejaring sosial di Indonesia sendiri sangat pesat, dari tahun ke tahun jumlah penggunanya terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari campur tangan pasar dalam hal penyediaan layanan internet melalui telepon seluler, provider dalam hal ini, sehingga menambah pengguna aktif jejaring sosial dengan menggunakan mobile connector. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang dengan aktif berjejaring sosial? Apa 32 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 yang bisa ditangkap dari teks-teks yang hadir di jejaring sosial? Galau, Sebuah Ekspresi Keterasingan dalam Jejaring Sosial Kata demi kata, kalimat demi kalimat, tulisan demi tulisan berganti setiap detik dan menit. Sebagai sebuah arena berekspresi jejaring sosial berisi berbagai macam “celotehan” yang dibuat oleh para anggotanya. Satu hal yang menarik perhatian saya dari berbagai bentuk ekspresi di jejaring sosial adalah “galau”. Kata “galau” dalam jejaring sosial merupakan kata yang bisa ditemui setiap hari. Arti dari kata galau yang dimaksud oleh para pemakai jejaring sosial sendiri tidak pernah jelas. Jika merunut kepada definisi “galau” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, maka: “ga·lau a, ber·ga·lau a sibuk beramai-ramai; ramai sekali; kacau tidak keruan (pikiran); ke·ga·lau·an n sifat (keadaan hal) galau” Pada bagian ini saya akan berusaha menangkap apa yang dimaksud dengan “galau” di jejaring sosial. Lebih jauh, apa yang ingin diungkapakan oleh para pemakai jejaring sosial? Berikut saya contohkan pemakaian kata “galau” dalam jejaring sosial Twitter. “@Kuntil: udah, buat apa pacaran kalau sering disakitin, mending putusin aja #penggalauanmassal” Pada kutipan twit ini, pemilik akun @kuntil menyatakan bahwa hubungan kalau hanya menyakiti lebih baik diakhiri, kemudian ia menambahkan dengan tanda pagar kalau celotehannya ini untuk membuat galau banyak orang. Di sini “galau” oleh akun @kuntil diartikan keresahan yang berkaitan dengan hubungan berpasangan. Akun @kuntil berasumsi banyak yang akan galau karena ocehannya yang ia tandai dengan tanda pagar. “@manika: huks... no words could explain my feeling...#galau” Di sini pemilik akun @manika mengekspresikan rasa sedihnya yang ditampilkan dengan kata “huks”. Lebih lanjut akun @manika menjelaskan karena tidak ada kata yang bisa mengekspresikan perasaanya, akhirnya ia menandai ekpresinya ini dengan tanda pagar #galau. “Galau” di sini berarti kebingungan karena tidak ada kata yang bisa mengekpresikan perasaannya. Selanjutnya adalah yang diekpresikan oleh nama akun @Deborah. “@Deborah nyampe kampus bersiap buat presentasi, tp gak tau bahan presentasinya kaya gimana #GALAU. 33 Gaffari Rahmadian - Jejaring Sosial: Memupus Sekaligus Mengalienasi Pemilik akun @Deborah di sini menjadi galau karena dia akan melakukan presentasi, sedangkan dia tidak tahu bahan yang akan dipresentasikannya. Pemakaian kata “galau” di atas berbeda-beda, akan tetapi bila dicermati terdapat satu persamaan, yaitu kata “galau” dikaitkan dengan perasaan yang mengambang, tidak menentu, tidak pasti, yang disebabkan oleh suatu hal. Pada akun @kuntil, galau disebabkan hubungan yang tak menentu, pada akun @manika disebabkan oleh ketidakbisaanya mengungkapkan perasaan, sementara pada akun @Deborah karena ketidaktahuannya mengenai bahan yang akan dipresentasikan. Pemaknaan kembali kata “galau” dalam jejaring sosial ini oleh para penggunanya bagi saya menandakan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sebuah kata yang bisa mewakili perasaan mereka, yaitu perasaan mengambang, liminal, tidak pasti sebagai akibat dari alienasi pada masyarakat konsumtif. Membuat Relasi Sekaligus Mengalienasi Semua halaman elektronik yang disebutkan di atas menawarkan hal yang sama, yaitu membangun jaringan baik dengan orang yang kita sudah kenal di dunia nyata maupun dengan orang yang kita kenal di dunia maya. Hal ini bisa dilihat dari tampilan di halaman muka, yang menunjukan berapa teman yang dimiliki, dan darimana teman tersebut terhubung. Selain itu, jejaring sosial juga memungkinkan kita berkomunikasi dengan teman yang jaraknya sangat jauh, baik itu melalui sapaan di kotak tertimonial pada Friendster, wall di Facebook, atau fungsi mention di Twitter. Dalam arti lain, jejaring sosial memungkinkan sesorang untuk membangun berkomunikasi dan membangun relasi sosial laiknya relasi sosial di dunia nyata. Dimas (21 tahun) misalnya, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta ini mengatakan kalau hampir 75 persen waktunya dalam sehari digunakan untuk melihat Twitter baik melalui laptop ataupun smartphone miliknya. Aktivitas itu terjadi bahkan ketika dia sedang berkumpul bersama teman satu rumah kontrakan ataupun pacarnya. Alasan yang ia kemukakan sederhana saja, “ya pengen tau aja perkembangan temen-temen di Twitter”. Jawaban Dimas menyiratkan kalau ia tidak tahu kabar teman-temannya, oleh karena itu ia melihat Twitter. Jika dilihat lebih jauh lagi jawaban Dimas menandakan kalau ia ingin berelasi dan dengan “membuka” Twitter ia menjadi terhubung dengan teman-temannya.. Serupa dengan Dimas, Diana (23 tahun) seorang perempuan asal Sumatra, juga senang ber-Twitter ria, menurut dia hal pertama yang dilakukannya ketika terbangun dari tidur adalah melihat Twitter. Saat ditanya lebih jauh apa yang ingin dilihatnya, dia menjawab, “ya update temen-temen deket, soal cinta-cintaan, kan biasanya temen-temen suka galau tuh di Twitter”. Teman-teman dekat yang 34 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 dimaksud oleh Diana di sini adalah temannya beraktivitas sehari-hari. Di sini Diana dengan lebih gamblang menyatakan kalau dia melihat perkembangan teman-temannya yang notabene ia jumpai setiap hari terutama yang berkaitan dengan cinta. Artinya, walaupun setiap hari Diana bertemu dengan temantemannya tidak menjadikan Diana mengetahui perkembangan mereka. Diana melihat perkembangannya di Twitter. Lebih jauh, hal ini juga menunjukan kalau Diana mencoba berelasi dengan teman-temannya karena relasi yang terjalin di kehidupan sehari-hari tidaklah cukup bagi Diana untuk mengetahui perkembangan teman-temannya. Apa yang diungkapkan oleh Dimas dan Diana, memberikan penjelasan peran jejaring sosial dalam masyarakat konsumsi seperti saat ini, yaitu menawarkan ruang untuk membangun relasi sosial yang tidak didapatkan lagi di dunia nyata. Semakin menghilangnya relasi sosial tersebut dalam analisis Baudrillard (Baudrillard dalam Putranto, Hendar dan Mudji Sutrisno eds., 2005) karena setiap individu diasingkan antara yang satu dan lainnya, melalui konsumsi komoditas. Lebih lanjut, orang dalam masyarakat konsumsi seperti itu dijauhkan dari institusi keagamaan dan keluarga yang pada akhirnya meninggalkan perasaan kesepian serta keterasingan (Lasch dalam Fridell, 2007). Akan tetapi di sisi lain, “convinced that they are too powerless to affect life in a meaningful way, people turn toward self improvement and building superficial identity based on “material furnished by advertising and mass culture” (Lasch dalam Fridell, 2007:8). Jejaring sosial sebagai sebuah komoditas budaya massa justru mengalienasi penggunanya dengan menempatkan mereka sebagai objek di dalam jejering sosial itu sendiri melalui objektifikasi terhadap teknologi yang digunakan mengakses jejaring sosial. Artinya, relasi sosial yang dibentuk dalam sebuah jejaring sosial pada akhirnya hanyalah menjadi relasi sosial yang semu. Kesimpulan Makin merajalelanya kapitalisme dalam masyarakat Indonesia mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang kapitalistik. Perkembangan tersebut selain membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang konsumtif juga membuat setiap personal menjadi terasing dalam masyarakatnya sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui kata galau dan penggunaan mobile connector untuk mengakses jejaring sosial. Keterasingan itu yang akhirnya mendorong individu-individu untuk membuat menjalin kembali relasi sosial yang semu di dalam ruang baru bernama jejaring sosial. Di sisi lain jejaring sosial sebagai sebuah komoditas justru semakin mengasingkan para penggunanya. 35 Gaffari Rahmadian - Jejaring Sosial: Memupus Sekaligus Mengalienasi Bibliografi Buku Putranto, Hendar dan Mudji Sutrisno (eds.). 2005. Teori-teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Piliang, Yasraf Amir. 1999. Hiper-realitas Kebudayaan. Yogyakarta: LKIS Sassateli, Roberta. 2007. Consumer Culture: History, Theory, and Politics. London: Sage. Jurnal Fridell, Gavin. 2007. “Fair Trade Coffee and Commodity Fetishism: The Limits of Market-Driven Social Justice” dalam Journal of Historical Materialism Vol. 15, No. 2. Media cetak dan internet Kertajaya, Hermawan. “From Belief to Humanity”. Senin, 7 September 2009 | 15:35 WIB, diunduh 6 Desember 2011. Yuana, Suci Lestari. “Merayakan Perdamaian dengan Jejaring Sosial”. Forum Kompas. Selasa, 21 September 2010 | 11:43 WIB, diunduh Senin 6 Desember 2001. Tempointeraktif. “Facebook Dominasi Jejaring Sosial”. Jum’at, 15 Agustus 2008 | 10:35 WIB Tempointeraktif.com. Diunduh Senin 6 Desember 2011. 36 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Muhammad Arief Al Fikri KEBUTUHAN MASYARAKAT GLOBAL Jejaring sosial adalah candu bagi sebagian besar orang. Sekali merasakannya, timbul semacam efek ketergantungan yang makin lama tidak disadari. Di mana pun dan kapan pun, banyak orang yang selalu berpikir untuk mengakses akun jejaring sosialnya. Tidak peduli koneksinya lambat, akan ditunggu sampai ia bisa melihat status yang berseliweran, foto dan video yang diunggah, atau mungkin informasi terbaru apa saja yang sedang hangat diperbincangkankan di situ. Tidak hanya pada level individu, media jejaring sosial juga dimanfaatkan sebagai lahan pasar oleh para instansi atau korporasi. Mereka mempromosikan barang dan jasanya dengan beriklan di sana. Berbagai strategi dilakukan demi merangkul target pasar. Demikian, pada akhirnya kita akan sampai pada wacana globalisasi. Pengaruhnya yang sungguh luar biasa ini terkait jejaring sosial telah mengungkung masyarakat dan membuat mereka tidak sadar terperangkap di dalam kungkungannya. Alih-alih menemukan jalan keluar agar bisa bebas, media jejaring sosial terus berinovasi memperkokoh dinding-dinding ruang kungkungannya. 37 Yuda Rasyadian - Jejaring Sosial: Ruang Besi pada Konstruksi Inovasi dan Identitas Budaya Massa TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 38-44 JEJARING SOSIAL: RUANG BESI PADA KONSTRUKSI INOVASI DAN IDENTITAS BUDAYA MASSA Yuda Rasyadian1 ABSTRAK Saya memperkuat konteks komoditas dan inovasi sebagai latar belakang dalam melihat jejaring sosial adalah hasil dari daya kreativitas manusia untuk menciptakan cara-cara baru dalam komunikasi yang memiliki interdependensi dengan tetakan komoditas sosial serta ekonomi yang baru untuk membentuk identitas. Singkatnya, saya mencoba menganalisis bagaimana jejaring sosial dapat membuat—meminjam istilah Weber— “ruang besi” dalam kehidupan manusia. Kata Kunci: jejaring sosial, simbol, ruang besi, kapitalisme Latar Belakang Masyarakat dunia mutakhir tampaknya tumbuh beriringan dengan globalisasi dan transformasi kapitalisme media. Fenomena ini ditandai dengan menjamurnya ruang-ruang relasi baru dengan media baru seperti internet atau cyberspace. Terdapat perubahan besar pada pandangan diri manusia dalam menemukan cara pemasaran ekonomi, cara mengekspresikan relasi yang lebih luas, proses interaksi dalam menumbuhkan identitas dan memperkuat identitas, juga memanipulasi diri dalam konteks sosial yang ada setelah adanya internet. Hal ini, tidak luput saya lihat, mendapat pengaruh kuat dari media-media sosial yang dibentuk lewat jaringan internet—yang kita sebut “jejaring sosial”, atau dalam istilah lain adalah social media network, seperti Friendster, MySpace, Twitter dan lainnya—sebagai paham baru dalam komunikasi dan relasi sosial. Jejaring sosial ini adalah sebuah invention dan inovasi yang dibangun untuk membentuk kekuatan baru dalam budaya massa, serta model interaksionisme simbolik yang baru. Interaksionisme simbolik biasanya memfokuskan pada interaksi tatap muka (face-to-face) dalam konteks kehidupan sehari-hari (George H. Mead). 1 Mahasiswa Angkatan 2006 Program Studi S1 Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 38 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Munculnya jejaring sosial saat ini merubah proses simbolik tersebut—mungkin bisa saya sebut sebagai tahapan yang baru. Mead memandang interaksi sosial dalam masyarakat terjadi dalam dua bentuk, yakni percakapan isyarat (interaksi non-simbolis) dan penggunaan simbol-simbol penting (interaksi simbolis). Dalam berbagai realitas, manusia banyak sekali terlibat dalam interaksi non-simbolis, ketika mereka merespon dengan cepat dan tanpa sadar satu sama lain. Seperti gerakan badan, ekspresi, dan nada suara. Sedangkan interaksi simbolis adalah pada konteks simbol, sebab mereka mencoba mengerti makna atau maksud dari suatu aksi yang dilakukan satu dengan yang lain. Pada konteks jejaring sosial saat ini, interaksi tersebut diimplementasikan pada bentuk yang lain, tidak pada ranah tubuh yang nyata, atau aktif. Seperti gerak badan, ekspresi dan sebagainya ditunjukkan melalui “emoticon”, yaitu simbolsimbol yang ada pada jejaring sosial sebagai pengganti bentuk ekspresi yang nyata. Begitu pula dengan interaksi simbolis, bagaimana menyusun gambar-gambar yang diunggah ke jejaring sosial, sebagai informasi yang mengkomunikasikan sebuah kegiatan (yang aktif pada tubuh nyata) tanpa “melihat” dengan empiris sejauh apa kegiatan tersebut dilakukan, apakah manipulasi ataupun “hanya mewakili”. Pada akhirnya, jejaring sosial menjadi: (1) komoditas utama dari kendaraan sosial untuk menemukan/memperluas ruang relasi, (2) sebagai kendaraan ekonomi (dimana jejaring sosial mencakup lingkaran strategi kapitalisme yang baru) dengan teks-teks simbolnya, (3) menjadi konsep baru komoditas ikonografi, serta (4) tempat bernaung identitas/entitas individu maupun komunitas. Permasalahan Proses komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang mengandung arti dari individu satu ke individu lain, atau dari kelompok satu ke kelompok lain. Harold Lasswell (1969:71) mengatakan “the social process is the totally of value processes for all the valuer important in the society”, maka dapat dikatakan lebih lanjut bahwa proses komunikasi adalah masalah proses pembentukan nilainilai baru. Di sinilah kita dapat melihat bahwa nilai-nilai baru dibentuk dari munculnya jejaring sosial tersebut sebagai langkah dari transformasi komunikasi. Nilai keintiman berubah, yaitu konsep interrelasi sesama antar-individu mulai berkurang untuk hal aktualisasi diri. Konsep komunitas juga berubah, yaitu proses komunikasi yang bersifat diskusi berubah (di mana interaksi langsung dalam public sphere menjadi berkurang) menjadi diskusi di dunia maya. Lalu nilai baru muncul dengan pandangan bahwa kepemilikan identitas yang tercirikan dalam jejaring sosial adalah hal yang eksklusif. 39 Dalam tulisan ini saya memperkuat konteks komoditas dan inovasi Yuda Rasyadian - Jejaring Sosial: Ruang Besi pada Konstruksi Inovasi dan Identitas Budaya Massa sebagai latar belakang. Saya melihat jejaring sosial adalah hasil dari daya kreativitas manusia untuk menciptakan cara-cara baru dalam komunikasi yang memiliki interdependensi dengan tetakan komoditas sosial serta ekonomi yang baru untuk membentuk identitas. Freud (2006:379) berkata bahwa ada hubungan yang erat antara kreativitas dengan values, bahwa fragment yang ada pada jejaring sosial ini sarat akan nilai. Inovasi, dibentuk dengan dasar untuk melakukan suatu perubahan yang lebih efisien terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia, kebutuhan akan relasi, identitas dan kapital. Sistem ini mengkonstruksi respon massa akan ruang interrelasi gaya baru, serta menembus konsep promosi/iklan (salah satu komponen dalam konsep ekonomi-produksi) sebagai strategi baru dalam budaya massa. Secara tidak langsung saya juga menyadari ada yang berubah dari nilai lama, ada yang berubah dari keadaan yang nyata, konsepsi hubungan yang nyata. Terlihat juga ada perasaan terikat yang kuat dari masyarakat sosial akan ruang kehidupannya seakan-akan dipindah ke lingkaran dunia maya ini, yang disebabkan oleh terserapnya secara cepat sistem kasat mata yang dibangun oleh adanya jejaring sosial. Apa yang terjadi selanjutnya pada inovasi kapitalisme media ini? Bagaimana pengaruh relasi sosial yang ada pada “tubuh nyata” di kondisi tersebut? Analisis apa yang bisa dibangun dalam wacana kontrol masa depan dari inovasi sistem relasi ini? Hal inilah yang mendasari tulisan saya tentang budaya digital ini. Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi mercusuar serta menjadi bagian dari sejuta ilmu hasil pikiran dan pengalaman yang bisa menjadi warisan, tidak hanya sebagai selembar kertas yang jadi usang. Pembahasan Masalah Manusia selalu mencari cara untuk dapat memperluas wawasan serta memperluas jaringan. Sekarang hal tersebut didukung dengan teknologi yang mapan yaitu internet, sehingga munculnya jejaring sosial dengan fondasi jaringan internet pun mendapat respon yang sangat luar biasa. Hal ini memang dipengaruhi oleh keinginan manusia untuk mencari inovasi akan modal-modal simbolik, yang dalam pengejawantahannya menjadi gaya hidup massa. Pandangan saya bahwa gaya hidup adalah cara hidup terpola yang dapat dicirikan oleh tema-tema tertentu dalam situs dan strategi. Jejaring sosial sekarang ini juga menampilkan kondisi di mana ikonografi baru berperan dalam strategi massa, baik dalam menggambarkan maupun melihat bentuk-bentuk baru asosiasi sosial, adalah sarana yang paling mendasar dalam menampilkan gaya hidup (Chaney, 1996:168). Lifestyle atau gaya hidup dalam konteks ini bukan pula 40 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 melulu monopoli diri atau pasar dalam penggunaan media jejaring sosial, tetapi lebih kepada bagaimana pelaku terlibat aktif dalam jejaring sosial sebagai budaya massa. Dalam budaya massa si pelaku cenderung “latah” menyulap atau meniru segala sesuatu yang sedang naik daun atau laris dilakukan oleh orang lain. Pada umumnya budaya massa dipengaruhi oleh budaya populer. Pemikiran tentang budaya populer menurut Ben Agger (1992:24) dapat dikelompokkan menjadi: (1) budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengentaskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari, (2) kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional, (3) kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis, (4) kebudayaan populer merupakan budaya yang menetes dari atas. Pemikiran Ben Agger tersebut sangat fondasional untuk mengungkapkan bagaimana inovasi dari kapitalisme media yang mereproduksi jejaring sosial ini muncul. Satu poin yang menarik dari pendapat Ben Agger di atas, kebudayaan “populer” menghancurkan nilai budaya “tradisional”. Pendapat tersebut saya padankan dengan pola pergeseran yang terjadi pada konsep relasi manusia yang umum dan nyata (interaksi yang sejak lama dimiliki), yaitu keintiman interaksi pada dunia nyata. Inilah yang mendasari posisi interrelasi nyata pada manusia mengalami dekadensi dalam batasan tertentu. Jejaring sosial yang diterima secara cepat sebagai mass culture, perlahan-lahan membuat manusia menjadi teralienasi dengan manusia lainnya. Individu yang satu mulai tidak tertarik untuk berbagi permasalahan dengan individu lain, lebih tertarik untuk mengangkatnya ke dalam jejaring sosial, yang mungkin dianggap mempunyai kebanggaan, atau memang sudah terpancing kedalam kebanggaan terlibat dalam budaya massa. Nilai lama (tradisional) dalam cara berelasi memudar. Pengakomodiran akan sebuah gerakan ataupun ide reaktif juga mengalami perubahan ruang dan langkah ke arah jejaring sosial tersebut sebagai medianya. Dengan ini, ide reaktif akan dapat disebarkan lebih luas sekaligus membuka relasi akan informasi yang dimiliki satu kelompok ke kelompok lain ataupun satu individu ke individu lain. Begitu pula dalam relasi ekonomi, di mana orang masa kini banyak menjalankan roda ekonominya melalui jejaring sosial (konsep promosi/iklan yang saya bicarakan di atas), juga promosi akan ruang kata, ruang budaya, serta simbol-simbol transnasional, semua melalui hasil dari transformasi kapitalisme media yang baru ini. Jejaring sosial menjadi ruang tontonan bagi inovasi baru dalam komoditas ikonografi dan ekonomi. Sementara itu, tubuh sebenarnya dari relasi humanis menjadi sebatas ikon yang tertinggal, ruang kedekatan nyata malah menjadi ajang terjadinya alienasi antar individu maupun kelompok, serta terdapat rasa kenyamanan dan kebanggaan ketika menonton interaksi simbolik individu atau 41 Yuda Rasyadian - Jejaring Sosial: Ruang Besi pada Konstruksi Inovasi dan Identitas Budaya Massa kelompok di ruang jejaring sosial sebagai komoditi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kreativitas modern milik manusia telah menjadi suatu budaya tontonan (a culture of spectacle). Perlu diperhatikan bahwa ruang relasi ini bisa menutup kemungkinan kita untuk mengetahui bagaimana identitas asli seseorang atau jaringan ekonomi yang menggunakan jejaring sosial. Semua orang, kaya, miskin, baik, atau bahkan orang buruk/jahat sekalipun bisa terlibat aktif dalam memainkan peran di jejaring sosial. Dalam jejaring sosial seseorang dapat bersandiwara, meniru-niru, ataupun berpura-pura. Seperti halnya orang yang kaya bisa berlagak miskin, bukan karena penganut ideologi asketisme, dan bukan pula pengaruh kampanye akan Pola Hidup Sederhana di jejaring sosial, tetapi lebih karena itu pilihan orang tersebut untuk membentuk identitas yang ingin di tampilkan di jejaring sosial. Jejaring sosial kini mungkin malah bergeser konsepnya dari ruang untuk kebutuhan relasi sosial, dengan memunculkan identitas yang dicirikan untuk mendapatkan aktualisasi diri di dunia yang lebih luas (tidak sebatas komunitas sekitar pada lingkaran sosial yang nyata, yang mungkin terbatas), menjadi kebutuhan untuk membentuk kepribadian/entitas individu yang berbeda dari kenyataan. Ruang jejaring sosial yang ada menjadi tempat pengaburan identitas demi interaksi-interaksi luas dengan tendensi yang bermacam-macam. Ini memungkinkan manusia menjadi lebih memilih untuk terlibat dalam jejaring sosial ini, karena “kita tidak terlihat seperti kita”, semua bisa dimanipulasi, yang sudah terlihat bagus secara virtual dan visual, bisa dibuat lebih bagus, yang tidak bagus pun bisa dibuat menjadi bagus. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa krisis identitas pun terjadi karena proses penyerapan yang tidak sempurna akan kapitalisme media yang sarat kepentingan ini. Fenomena ini harus diwaspadai, karena aplikasinya sebagai ritus dan strategi baru dalam komoditas sosial-ekonomi, dapat membuat manusia menjadi terjebak semakin jauh dalam lingkup entitas diri dan budaya baru dimana fondasinya semakin melemahkan perikemanusiaan. Ruang baru jejaring sosial memberikan hawa baru dalam gaya hidup dan budaya massa tadi, tetapi kontinuitas konstruksinya akan membawa “kerangkeng” bagi interaksi aktif pada keadaan riil antar manusia menuju ke batas irasional. Irasionalitas bentukan yang terkait dengan jejaring sosial memberikan pertanyaan serius mengenai masa depan cara komunikasi dan inter-relasi pada masyarakat. Konstruksi interaksi dan identitas yang terjadi ketika manusia menjadi teralienasi dengan adanya reproduksi jejaring sosial ini, dapat mencengkram ikatan manusia itu sendiri ke dalam “kurungan besi” (Weber, 2000). “Kurungan besi” yang saya maksud adalah jejaring sosial memiliki kemungkinan akan mendominasi lebih banyak sektor kemasyarakatan, yang akan lebih tidak mungkin lagi bagi masyarakat untuk “melepaskan diri” darinya. 42 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Frasa “kurungan besi” mengimplikasikan pandangan negatif akan sesuatu yang memenjarakan orang-orang. Weber mengatakan, ada kerangkeng besi dalam konsep rasionalitas yang sangat tidak manusiawi bahkan mengakibatkan dehumanisasi. Lalu, sistem rasional akan menimbulkan berbagai dampak irasional. Irasionalitas utama dari jejaring sosial ialah kemungkinan orang-orang akan kehilangan kontrol atas sistem relasi dan komunikasi tersebut, yang suatu saat bisa mengontrol mereka. Seperti yang telah terjadi, sistem-sistem yang dianggap rasional ini mau tak mau telah mengontrol banyak aspek kehidupan orang-orang. Gaya hidup, roda ekonomi, komunikasi, serta pembentukan identitas-identitas yang kadang menyimpang dari praktik sebenarnya. Konteks komunal semakin hancur lebur karena dilindas individu-individu yang menyerang rasionalitas interaksi lahiriah manusia itu sendiri (konsep interrelasi yang nyata sebagai keabsahan komunikasi antar manusia yang sebenarnya). Gambaran kerangkeng besi mengilustrasikan rasa kebekuan, kesulitan, dan ketidaksenangan. Saat ini hampir sebagian besar manusia sadar jejaring sosial telah mengkungkungnya, namun mereka mendapati diri mereka menikmati kenyamanannya. Mereka menyukai, bahkan menggandrungi, dunia yang dibungkus dalam jejaring sosial serta menyambut perkembangannya dan penyebarannya. Mereka menyukai sebuah dunia yang tertata rapi secara simbolik dan bisa membolak-balikan identitas diri mereka. Mereka menyukai keberadaan individu yang masing-masing berkutat di depan layar komputer atau pun smartphone, dengan bertegur ide lewat dunia maya tanpa melihat kondisi "alien" yang ada di sekitarnya. Mereka bersandar pada dunia impersonal sebagai tempat berinteraksi dengan manusia, bahkan benda-benda otomatis non-manusia. Bagi sementara orang yang mewakili sejumlah besar populasi pengguna, jejaring sosial bukanlah suatu ancaman melainkan surga. Bagi yang lainnya, jejaring sosial itu tidak ubahnya kerangkeng karet dengan jeruji yang bisa diulur. Dalam hal ini, ketersediaan untuk bergulat dalam jejaring sosial dengan segala bentuk relasi dan interaksi simboliknya, akan membuat mereka bisa melakukan aktivitas non-rasional lain. Bahkan, jika semakin terbuai tanpa disikapi, jejaring sosial online benar-benar dapat menjadi kerangkeng besi yang seakan berbagi kelam dengan pandangan pesimistis Weber terhadap sistem seperti ini. Selanjutnya, meski orang-orang masih nampak mengontrol keadaan ini (ruang jejaring sosial), sistem-sistem rasional ini bisa berputar di luar kontrol mereka yang menduduki posisi tertinggi dalam sistem tersebut, dan yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang akan kehilangan identitasnya di dalam tubuh yang nyata, men are avatars. 43 Yuda Rasyadian - Jejaring Sosial: Ruang Besi pada Konstruksi Inovasi dan Identitas Budaya Massa Kesimpulan Di tengah krisis nasional yang melunturkan jati diri bangsa Indonesia, ada baiknya ketika kita mau mengkaji lagi konsep atau tujuan seperti apa yang seharusnya diterapkan dalam mengimplementasikan entitas diri dan ide di jejaring sosial, agar tidak terjebak juga tidak sampai teralienasi atau mengalienasi individu lain serta komunitas sekitar. Hal itu akan terjadi, jika memang masing-masing dari kita mau memompa dengan penuh perpindahan identitas dari kehidupan nyata ke dalam dunia maya tersebut. Paling tidak, tak ada yang salah dalam konsep inovasi dan kreativitas, karena mungkin yang paling penting bahwa apresiasi terhadap mudahnya cara komunikasi dan membangun relasi sekaranglah yang patut disikapi dengan penghargaan, walaupun transformasi ini datang menggunakan kendaraan kapitalisme media untuk menyokong komoditas sosial yang baru. Dalam usahausaha semacam itu, orang-orang bisa mengekspresikan alasan paling manusiawi dalam dunia yang dalam beberapa hal telah mempersiapkan sistem-sistem terasionalisasi guna mengingkari ekspresi orang-orang. Motivasi utama saya di kesempatan kali ini ialah untuk memperingatkan para pembaca akan fragmen lain dari jejaring sosial yang mempunyai potensi jerat dehumanisasi, potensi berbahaya bagi rasa penghargaan kepada cara komunikasi tradisional, serta mengajak untuk menyikapi dengan bijak gelombang jejaring sosial agar tidak terjadi krisis identitas. Ketahanan konseptual dan pemahaman amat diperlukan antar-individu ataupun antar-komunitas, dengan harapan tidak dicengkeram oleh “ruang besi” yang memenjarakan humanisme, serta dapat menciptakan dunia yang lebih manusiawi dan masuk akal. Bibliografi Buku Chaney, David. 1996. Lifestyle. London: Routledge. Scott, James C. 1998. Seeing Like A State. New York: Yale University Press. Storey, John. 2003. Teori Budaya Dan Budaya Pop. Yogyakarta: Qalam Press. Tabrani, Primadi. 2006. Kreativitas dan Humanitas. Yogyakarta: Jalasutra. Tester, Keith. 1994. Media, Culture and Morality. London: Routledge. Wardhana, Veven S.P. Kapitalisme Televisi dan Strategi Budaya Massa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Weber, Max. 2000. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Surabaya: Pustaka Promethea. 44 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Dian Ayu Aryani ARAH MANA YANG ANDA PILIH? Hebatnya, dalam dunia teknologi serba canggih Anda juga dituntut untuk memilih arah tujuan diri dalam dunia maya. Keberadaan jejaring sosial yang telah membebaskan kita untuk berekspresi diri telah dijadikan berbagai kalangan untuk melakukan motif-motif tertentu, salah satunya telah marak kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk kebaikan dan kejahatan pula. Jadi, mana arah yang akan Anda pilih untuk diri di dunia maya? 45 Gregorius Septian Christianto - Jejaring Sosial: Lahan Reproduksi Kekerasan terhadap Perempuan TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 46-52 JEJARING SOSIAL: LAHAN REPRODUKSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Gregorius Septian Christianto1 ABSTRAK Kita mungkin sering mendengar pernyataan: kenyataan di dunia nyata telah dipindahkan ke dunia maya. Terkait dengan itu, tulisan ini mencoba melihat bagaimana fenomena kekerasan muncul di internet dengan mengambil contoh kasus pada jejaring sosial. Kekerasan terhadap perempuan tak hanya terjadi secara langsung di “dunia nyata”, namun juga melalui media internet. Jejaring sosial, sebagai ruang publik baru menjadi lahan baru tempat kekerasan terhadap perempuan. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana fenomena kekerasan terhadap perempuan direproduksi ke dalam ruang baru, yakni jejaring sosial di internet. Kata Kunci: jejaring sosial, gender, perempuan, kekerasan Pendahuluan Suatu waktu saya bersama seorang teman dekat berkendara menuju ke Kota Ngawi, untuk mengunjungi kakek dan nenek saya. Di perjalanan, di sekitar Kota Sragen, saya melihat sepasang laki-laki yang mengemudikan sepeda motor dan berkendara dekat dengan sepasang perempuan yang juga bersepeda motor. Dari belakang mereka, kami menyaksikan sepasang laki-laki itu menggoda sepasang perempuan dengan menyiuli lalu menggoda dengan kata-kata. Tangan si laki-laki yang duduk di jok bagian belakang kemudian mencubit kaki pengendara perempuan. Dua perempuan itu tersebut lantas mengendarai kencang sepeda motornya meninggalkan sepasang laki-laki yang menggoda mereka. Sepasang laki-laki mengakhiri tindakan mereka dengan tertawa keras-keras. Perilaku semacam ini tentu tidak terjadi sekali saja sewaktu saya melihatnya dalam perjalanan ke Ngawi. Lain waktu lagi, saya menyaksikan pula kejadian yang serupa di jalanan di Yogyakarta pada malam hari. Laki-laki di atas sepeda motor menggoda perempuan di jalan dengan siulan dan senyum, tak jarang 1 Mahasiswa Angkatan 2008 Program Studi S1 Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 46 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 pula dibumbui dengan cubitan dan jawilan ke anggota tubuh perempuan. Kejadiankejadian serupa selanjutnya saya rekam dalam ingatan saya terhitung sejak saya mengendarai sendiri sepeda motor di awal tahun 2000-an. Bentuk-bentuk perilaku tidak menyenangkan baik verbal maupun nonverbal terhadap perempuan kerap sekali terjadi. Tindakan yang paling kerap saya lihat adalah siulan dan kata-kata yang menggoda, meskipun tak jarang kontak fisik juga terjadi. Bentuk-bentuk perilaku ini adalah bentuk konkrit kekerasan di ruang publik, di ruang yang terbuka bagi semua orang dan bukan menjadi tempat dominasi laki-laki (Wattie, 2002). Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik ini semakin sering saya sadari sejak saya mengenal kata gondes (gentho ndeso), sebuah label bagi lakilaki yang berperilaku norak dan cenderung menyebalkan bagi perempuan. Merujuk pada data Hubungan Sosial Pelaku-Korban KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) Seksual dan KTP Nonseksual di Empat Provinsi (2002:11), bentuk-bentuk kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal terhadap perempuan di Yogyakarta didominasi oleh orang tidak dikenal, yakni 53,6 persen di desa dan 63,3 persen di kota (lihat gambar 1). Gambar 1: Pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan di Yogyakarta Sumber: Hubungan Sosial Pelaku-Korban KTP Seksual dan KTP Nonseksual di Empat Provinsi, 2011 Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dilakukan secara acak dan spontan. Ruang publik juga menjadi tempat yang paling banyak tercatat sebagai lokasi terjadinya tindak kekerasan, baik verbal maupun non-verbal terhadap perempuan di Yogyakarta, yakni 82,0 persen di desa dan 74,1 persen di kota untuk tindakan kekerasan seksual; 46,5 persen di desa dan 45,2 persen di kota untuk tindakan kekerasan non-seksual (lihat gambar 2). 47 Gregorius Septian Christianto - Jejaring Sosial: Lahan Reproduksi Kekerasan terhadap Perempuan Gambar 2: Bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik di Yogyakarta Sumber: Hubungan Sosial Pelaku-Korban KTP Seksual dan KTP Nonseksual di Empat Provinsi, 2011 Kekerasan terhadap perempuan di ruang-ruang publik menjamur seiring banyaknya gondes yang berkeliaran dengan sepeda motornya. Dengan keangkuhannya di jalanan, gondes menjadi teror bagi perempuan di ruang publik dengan menebarkan rasa tidak aman lewat godaan-godaannya yang mengganggu, bahkan sering dengan menggunakan tangan. Apakah kekerasan terhadap perempuan semacam ini masih akan terjadi di jejaring sosial, yang dewasa ini menjadi ruang publik baru? Hubungan Teman-dari-Temannya-Teman-Temanku Pada tahun-tahun berikutnya, di era awal 2000-an mulailah mewabah jejaring sosial, sebuah wadah pertemanan di dunia maya yang memberikan bentuk identitas baru melalui akun pribadi. Ramai-ramai anak muda membuat akun jejaring sosial dan memperluas pertemanan mereka dengan saling menambahkan nama dalam daftar teman mereka di dunia maya. Para gondes yang juga bagian dari anak muda tak luput melakukan hal yang sama. Dimulai dengan jejaring sosial bernama Friendster, anak-anak muda mulai membangun relasi di dunia maya dengan akun pribadinya. Menawarkan pertemanan dan relasi lewat foto sebagai identitas profil, anak-anak muda mulai saling menyapa. Dengan adanya foto dalam tampilan profil, memilih siapa saja yang akan menjadi teman di dunia maya semakin seru. Tak lama setelah itu, jejaring sosial diramaikan dengan kehadiran Facebook. Kehadiran Facebook 48 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 membuat kehidupan dunia maya semakin kompleks dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Pemilik akun Facebook dapat saling berbagi foto dan video; juga fitur chat antar pemilik akun yang sudah berteman. Persamaan antara Friendster dan Facebook adalah pada pemilihan siapa saja yang layak dianggap sebagai teman. Pada hal ini bentuknya dua arah, kedua belah pihak harus sama-sama setuju untuk berteman di dunia maya. Keinginan untuk membangun relasi dan menambah pertemanan membuat semakin maraknya jejaring sosial ini merebak. Ditambah lagi dengan adanya jaringanjaringan pertemanan (dalam Facebook dikenal kolom “people you may know”) yang semakin memperluas bertemunya dua pribadi yang sebelumnya tidak pernah bertemu. Proses penambahan teman ini kemudian semakin menemui titik “temandari-temannya-teman-temanku” atau dengan kata lain sampai pada jaringan yang sangat jauh sehingga kemungkinan untuk benar-benar bertemu di dunia nyata sangat minim. Pada titik ini, dengan embel-embel menambah teman, pihak yang dimintai konfirmasi untuk mau diajak berteman biasanya masih menerima permintaan penambahan teman walaupun entah siapa itu yang meminta. Ketidaktahuan pada siapa-siapa saja yang sudah ada dalam daftar pertemanan ini tidaklah dirasa begitu penting, yang terpenting adalah seberapa banyak teman baru yang bisa didapat dari jejaring sosial. Dunia (Seperti) Baru Merebaknya jejaring sosial secara masif ini menandai lahirnya dunia baru. Dunia maya dengan ketidaknyataannya menggeser dunia yang nyata. Obrolan-obrolan saat anak manusia berkumpul dipenuhi topik-topik mengenai jejaring sosial. Manusia dan manusia bukan lagi bertemu di ruang publik yang dahulu menjadi tempat bagi semua orang, melainkan di dunia maya, lewat akunakun yang sudah tertera info dan fotonya. Wadah pertemuan bukan lagi di jalanan, taman, alun-alun, dan tempat-tempat bebas lainnya namun menjadi lebih sempit lagi: layar monitor. Obrolan-obrolan yang dulu dilakukan secara lisan juga berubah menjadi barisan kata-kata dengan tulisan (Mulyana dan Rakhmat eds., 2003). Remaja berkumpul lebih banyak diam memandangi layar telepon selulernya ketimbang melakukan obrolan ringan, alasannya sama: mengakses dunia maya. Selanjutnya, proses menambah teman di dunia maya tentu saja tidak terjadi begitu saja. Ada unsur memilih siapa yang akan menjadi teman atau tidak. Dapat dilihat tanpa riset yang mendalam di jejaring sosial, perempuan dengan paras yang dianggap ayu (cantik) oleh orang banyak akan lebih banyak memiliki teman di dunia maya daripada perempuan yang dianggap buruk wajahnya. Foto yang dipajang sebagai gambar profil merupakan syarat yang menentukan 49 Gregorius Septian Christianto - Jejaring Sosial: Lahan Reproduksi Kekerasan terhadap Perempuan bagaimana seseorang akan menjadi “terkenal” di dunia maya. Sejalan dengan semakin bertambahnya teman di dunia maya semakin banyak pula orang-orang tak dikenal yang “merasa” mengenali satu sama lain. Taruh saja contoh akun Facebook milik Denis2, lebih dari separuh temannya di dunia maya adalah orang-orang yang belum pernah bertemu. Sebagian besar isi dari daftar pertemanannya di jejaring sosial adalah orang-orang dari lingkup sepakbola, yang tidak benar-benar berinteraksi di dunia nyata dengannya. Denis sendiri memang seorang penonton sepakbola yang kerap muncul di stadion, namun ia mengaku bahwa sebagian orang yang menulis di beranda akun profilnya di jejaring sosial tidak ia ketahui bagaimana bentuk aslinya di dunia nyata. Bentuk-bentuk sapaan yang ditulis di jejaring sosial dirasa Denis kerap mengganggu karena banyaknya notifikasi yang masuk ke email-nya, sedangkan bentuk sapaannya sangatlah tidak penting dan cenderung mengganggu karena berisi gombalan-gombalan. Kasus lain terjadi pada Dita. Ia dulunya menerima permintaan pertemanan dari siapapun. Pada awal menggunakan Friendster dan Facebook, ia belum merasa terganggu sampai akhir-akhir ini sudah terlalu banyak orang tidak dikenal yang ada di daftar pertemanannya. Seringkali ketika online, banyak chat (yang menjadi fitur andalan Facebook) masuk dari orang-orang tidak dikenal yang mengajak berkenalan. Tidak hanya sekali, chat yang masuk bahkan bisa berulang kali dari orang yang sama setiap hari. Bahkan pernah terjadi ada akun yang tidak diketahui siapa pemilik aslinya yang menyindirnya lewat chat. Kasus chat yang mengganggu tidak hanya dialami Dita, ada lagi contoh kasus yang dialami oleh Stefi. Stefi juga seringkali diajak mengobrol lewat chat di jejaring sosial sampai harus menonaktifkan fitur chat di akun Facebook miliknya karena merasa terganggu dengan ajakan yang datang tiap kali ia online. Bukan hanya itu saja, Stefi kerap pula dikirimi direct message dengan isi yang juga mirip dengan ajakan chat dari orang tak dikenal, bahkan sampai pada ajakan untuk melakukan hubungan seksual dari akun yang di luar daftar pertemanan sekalipun. Ajakan-ajakan ini dirasa sangat mengganggu karena baik Dita maupun Stefi akhirnya harus menonaktifkan fitur chat mereka, padahal mereka juga ingin berhubungan dengan orang-orang yang benar-benar mereka kenal, yang terpisah jarak sehingga tidak memungkinkan bertemu secara langsung. Belum lagi dengan keharusan untuk memutus pertemanan di dunia maya satu persatu dengan orang yang dianggap mengganggu ketika mereka sedang online. Selain menyita waktu, terlalu banyak yang harus dihilangkan dari daftar mereka. 2 Nama samaran, bukan nama sebenarnya. Selanjutnya semua contoh memakai nama samaran. 50 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Reproduksi Kekerasan Bentuk-bentuk ajakan untuk chat yang menggoda dan juga mengganggu bukan hal yang luar biasa terjadi. Sudah banyak kasus terjadi seperti yang saya paparkan di bagian sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan bentuk godaan berupa siulan dan kata-kata serta cubitan dan jawilan oleh para gondes di jalanan. Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan terjadi pula di jejaring sosial sebagai ruang publik dunia maya. Bentuk-bentuk kekerasan yang kerap terjadi ini merupakan sebuah kebiasaan yang dahulu kerap dilakukan di jalanan. Praktik-praktik kekerasan verbal di dunia maya terhadap perempuan, baik seksual maupun non-seksual, bagi saya merupakan bentuk kebiasaan yang direproduksi. Kekerasan verbal terhadap perempuan masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang dahulu diucapkan, sekarang berubah menjadi tulisan. Esensinya dari keduanya masih sama, ucapan dan tulisan adalah membentuk kata-kata (Ibid.). Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di jejaring sosial, lewat cara apapun (chat, direct message, tulisan di beranda profil), masih sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para gondes di jalanan. Para pelaku kekerasan ini memiliki moral budayanya sendiri yang mereka anggap benar dan dilakukan terus-menerus di ruang publik (Harker et. al., 1990). Kebiasaan-kebiasaan ini tidak terbatasi dengan dikotomi maya dan nyata. Perbedaannya hanya pada pertemuan yang tidak tatap muka. Jika di jalanan gondes-gondes harus mendekati dulu perempuan sebelum menggodanya, di jejaring sosial para penggoda harus mengajak si perempuan untuk sama-sama masuk dalam daftar pertemanan. Godaan-godaan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di dunia nyata berupa aksi nyata dan dapat dilihat secara langsung. Sedangkan di dunia maya, kekerasan verbal terhadap perempuan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Pada kasus kekerasan saat chat di Facebook dengan akun milik Dita, kekerasan berlangsung secara live, berbeda dengan kasus tulisan di beranda akun profil milik Denis dan ajakan melakukan hubungan seksual di direct message pada akun milik Stefi yang dapat dilakukan kapan saja dan akan secepatnya diterima oleh korban (si penerima godaan dan rayuan, serta tindakan tidak menyenangkan yang mengganggu lainnya) ketika mereka membuka akun jejaring sosial mereka. Kekerasan-kekerasan ini menjadi praktik yang berulang-ulang karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari ruang publik jalanan ke ruang publik jejaring sosial (Ibid.). Tidak ada batasan yang berarti antara nyata dan maya saat kekerasaan verbal terhadap perempuan yang dilakukan di jalanan terjadi pula di jejaring sosial. Dunia maya sebagai ruang publik baru menjadi lahan reproduksi kekerasan yang masih saja merugikan perempuan, sama merugikannya dengan 51 Gregorius Septian Christianto - Jejaring Sosial: Lahan Reproduksi Kekerasan terhadap Perempuan praktik-praktik godaan dan rayuan di jalanan. Kesimpulan Perempuan kerap mendapat kekerasan seksual dan nonseksual baik verbal maupun nonverbal. Contoh nyata kekerasan terhadap perempuan adalah kebiasaan gondes untuk mbajul, menggoda dengan kata-kata dan siulan, bahkan cubitan dan jawilan terhadap perempuan di jalanan. Bentuk-bentuk kebiasaan gondes yang merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan di jalanan dilakukan secara acak, bukan terhadap orang yang dikenalnya. Jalanan sebagai ruang publik menjadi lahan praktik kebiasaan-kebiasaan yang merugikan perempuan. Kebiasaan yang dilakukan secara acak juga terlihat di jejaring sosial sebagai ruang publik baru yang hadir di masyarakat. Permintaan pertemanan di berbagai jejaring sosial dilakukan secara acak dengan melihat foto profil akun jejaring sosial. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang tidak mengenal secara pasti akun laki-laki yang menjadi temannya dalam jejaring sosial. Dari daftar teman yang tidak diketahui betul siapa pemilik akunnya tersebut lalu muncul tindakan-tindakan tidak menyenangkan berupa godaan dan rayuan, bahkan sampai pada ajakan melakukan hubungan seksual. Kata-kata yang dulu diucapkan gondes di jalanan untuk menggoda perempuan direproduksi lewat tulisan. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, tidak ada batasan yang nyata antara dunia nyata dan maya. Jalanan dan jejaring sosial sebagai ruang publik sama-sama menjadi lahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan lewat kata-kata yang tertulis terjadi lewat fitur-fitur yang ditawarkan sebagai ajang mencari teman. Kebiasaan-kebiasaan menggoda perempuan yang dilakukan gondes di jalanan direproduksi lagi di jejaring sosial sebagai ruang publik yang baru, yang masih saja merugikan perempuan. Bibliografi Buku Harker, Richard, Mahar, C., dan Wilkes, C. 1990. (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. (diterjemahkan oleh: Pipit Maizier). Yogyakarta: Jalasutra. Mulyana, D. dan J. Rakhmat. 2003. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Wattie, Anna Marie. 2002. Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik : Fakta, Penanganan, dan Rekomendasi. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 52 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Foto: Muhammad Arief Al Fikri DUNIA DAN FACEBOOK Facebook merupakan salah satu media jejaring sosial yang sangat populer di seluruh dunia. Jika Facebook adalah negara, maka ia merupakan negara yang mungkin jumlah penduduknya paling banyak. Masyarakat Facebook mempunyai gaya berinteraksi dan berkomunikasi yang beragam, seperti layaknya yang terjadi di “dunia nyata”. Di sana, manusia bisa membagi ungkapan isi hatinya atau memberitahukan sedang melakukan aktifitas apa dan di mana melalui fasilitas update status, bisa mengobrol dengan “teman” mereka lewat fasilitas chatting, saling menyapa, mengucapkan selamat ulang tahun, mengundang orang ke suatu acara, berbagi foto dan video, dan sebagainya. Bahkan ada yang memanfaatkan Facebook sebagai sarana diskusi, meskipun para anggota yang terlibat di dalamnya belum pernah bertemu secara tatap muka langsung. 53 Odit Budiawan - Jangan Melihat Buku dari Wajahnya TH. II NO. 1 APRIL 2012 RANAH HALAMAN 54-62 JANGAN MELIHAT BUKU DARI WAJAHNYA1: STUDI TENTANG INTERAKSI DAN KOMUNIKASI DALAM FACEBOOK Odit Budiawan2 ABSTRAK Tulisan ini mencoba memaparkan secara detail bagaimana proses interaksi dan komunikasi di dalam jejaring sosial Facebook. Bagaimana Facebook mampu menyebar dan “menjangkiti” hampir seluruh penduduk dunia, menjadikan dunia tanpa batas. Kajian ini terkait dengan Facebook sebagai ruang publik baru. Kata Kunci: jejaring sosial, Facebook, interaksi, komunikasi Pengantar “Facebook helps you connect and share with the people in your life.” Beranjak dari kalimat itu, dua kolom tersedia untuk memasukkan alamat surel berserta kata kuncinya di sudut kanan atas, sign in lalu bersiaplah untuk “terjebak” dalam duduk manis yang menghabiskan detik ke menit hingga putaran jam terlalui untuk online. Aktifitas sosial hari ini terjadi dalam “jejaring maya”. Setelah log in itu, halaman Home (beranda) akan langsung menghadirkan berbagai berita, rentetan status (ataupun gambar) milik teman. Informasi tentang siapa yang berulang-tahun hari ini, bahkan “siapa mengkomentari siapa” juga dihadirkan di sana. Kemudian di dalam halaman Profile, di sudut sebelah kiri atas ada foto untuk mewakili dirinya (sesuai subjek dimakud) yang asli, kemudian terdapat pula Wall yang berisi keluhan-pernyataan aktivitas si pemilik di Facebook. Di Wall ini, orang lain yang telah menjadi teman bisa menuliskan testimoni maupun mengomentari status (selama pemilik menyediakannya). Menghapus testimoni maupun komentar status update di Wall, adalah hak sepenuhnya pemilik account, pada halaman itu pula terdapat sarana info tentang pemilik account, Photos, Boxes, Video, dan aplikasi lain yang bisa ditambahkan 1 Plesetan pameo “jangan melihat buku dari sampulnya” (don’t judge a book by its cover). Artikel ini dibuat tahun 2009 lalu, namun atas kepentingan penulisan RANAH maka disunting dan dirombak kembali pada bulan Desember 2011 2 Mahasiswa Angkatan 2008 Program Studi S2 (Pascasarjana) Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 54 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 sendiri. Pada setiap halaman, di sudut kanan bawah adalah notification yang memberi setiap info terbaru, sedangkan di sebelah kirinya terdapat fasilitas untuk chatting (fasilitas untuk mengobrol langsung sesama pengguna Facebook yang sedang online). Sebagian besar pemilik akun Facebook (yang menjadi “teman” saya) biasanya punya nama, foto, status serta keterangan personal seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bahkan siapa pacar, kakak, adik, paman, suami, istri juga bisa dicantumkan dalam profil Facebook. Persoalan apakah nama palsu atau akun buatan milik orang lain hingga bisa jadi seorang “teman” yang berinteraksi tidak terlalu diperdulikan (selama tidak ada konfirmasi), karena “figur imajiner”lah yang sedang dipakai guna berinteraksi dalam Facebook. Itulah Facebook, dan jika saya merefleksi diri saya sendiri aktivitas yang saya lakukan ketika membuka Facebook adalah: saya menulis apa yang sedang saya lakukan pada suatu hari, dan orang lain silahkan berkomentar. Saya memasang foto-foto di sana, bukan saja untuk kenang-kenangan, namun juga untuk dipuja, pamer. Sesekali saya juga menanyakan kabar seorang kawan dengan klik namanya akan terbuka profilnya. Jika orang itu gemar update status, saya merasa cukup tahu kabarnya sekarang tanpa bertanya. Fasilitas chating disediakan untuk mengobrol dengan “teman” yang juga online. Pun jika ada orang yang mengundang saya menjadi temannya, saya bebas untuk menerima atau menolaknya. Itulah kiranya asumsi saya ketika membuka halaman Facebook yang sudah saya miliki sejak 2008 lalu. Tentu saja orang lain punya pendapat lain soal “jejaring dunia maya” itu, “dunia” di mana orang-orang “seolah-olah” menjadi dirinya sendiri. Dunia berbagai hasrat dan kepentingan ada tercurah, mungkin demi pergaulan, sarana komunikasi, mencari pekerjaan, hingga berkampanye3. Inilah buah karya Mark Elliot Zuckerberg4. Di usia 25 tahun, dia memperkenalkan “The Facebook” (namanya saat itu), pada Februari 2004 dari kamarnya di asrama Harvard University. Dengan dibantu tiga temannya; Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, mereka membuat jejaring mahasiswa melalui internet agar dapat saling kenal. Dalam dua puluh empat jam, 3 Seperti Presiden Amerika, Barack Hussein Obama yang memanfaatkan situs ini sebagai salah satu cara untuk meraih dukungan dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat, 2008 lalu. 4 Nama Zuckerberg sudah melejit ke seluruh dunia bak meteor. Banyak pengguna Facebook merupakan orang-orang elit dunia. Facebook juga menjadi sarana komunikasi para karyawan Toyota, Ernst & Young, dan perusahaan kaliber dunia lainnya. Di Facebook, Zuckerberg bertanggung jawab untuk urusan garis kebijakan umum dan penyusunan strategi perusahaan yang kini menjadi rebutan para pemasang iklan dan para investor. Oleh Forum Ekonomi Davos 2009, Zuckerberg termasuk dalam daftar pemimpin muda karena prestasi dan komitmennya terhadap masyarakat serta berpotensi menyumbangkan ide untuk membentuk tatanan dunia baru. Sedang oleh majalah TIME, Zuckerberg diberi julukan sebagai “salah satu orang yang paling berpengaruh pada tahun 2008” dan juga mendapat penghargaan sebagai “TIME Person of the Year 2010”. 55 Odit Budiawan - Jangan Melihat Buku dari Wajahnya 1.200 mahasiswa Harvard bergabung dan dengan segera jejaring ini menyebar ke kampus lain. Kini, Facebook telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Arab5 (Kompas, 23 Juni 2009). Sebuah artikel Kompas yang bertajuk “Dunia tersihir Facebook”, menceritakan tentang Facebook yang sudah menjadi konsumsi dunia, beberapa orang seperti keranjingan berbagi informasi, rasa, canda, tawa, hasrat, ekspresi, dan impian lewat jaring sosial di dunia maya ini. Perihal beberapa orang yang merasa kurang lengkap hidupnya jika dalam sehari tidak membuka Facebook, sampai pada Facebook mampu memenuhi hasrat narsistik pada orang yang menggunakannya, dijabarkan dengan baik. Apa pun itu yang dibicarakan orang di Facebook, situs itu terbukti sukses menjadi media komunikasi baru yang sanggup merajut relasi sosial. Proses terbentuknya jaring sosial dan persahabatan di Facebook berlangsung cepat. Di Facebook, orang tak hanya mencari, tetapi juga dicari. Facebook disebut sebagai cara paling modern generasi sekarang memelihara relasi sosial, kekerabatan, dan bahkan dianggap sebagai media komunikasi baru yang menembus batas negara juga budaya. Bahasa, mulut bicara, gerak, ekspresi, bertemu, berjabat tanggan dianggap bagian dari interaksi dunia nyata. Bagaimana bisa, internet seperti halnya Facebook yang notabene adalah dunia maya (yang artifisial) bisa menjadi kenyataan dan fakta sosial? Mengapa tatanan sosial dalam berinteraksi dan berkomunikasi bisa terbentuk dengan adanya “jejaring media sosial” seperti Facebook? Tulisan ini akan mencoba menelusuri persoalan ini. Sepakat Media Sosial Sedikit menilik pada peranan media massa yang pernah ada dalam masyarakat kita saja sudah cukup beragam. Saya menengarai bahwa media massa acap kali mencerminkan harapan dan keinginan “politis” yang berubah setiap zaman terhadap alat komunikasi massa ini. Misal dahulu radio dipakai sebagai alat perjuangan, alat revolusi, media pembangunan, hingga menjadi pers Pancasila. Kini, fungsi media massa (tidak terkecuali internet) pada intinya sudah banyak berubah dari yang dahulu. Fungsi pokoknya bisa saja meliputi pengamatan atau pengawasan lingkungan (surveillance of the environment), membangun korelasi dari berbagai bagian masyarakat guna menciptakan konsensus (mufakat), sosialisasi atau pewarisan budaya dan fungsi hiburan. Fungsi-fungsi ini tidak selalu dapat dijalankan sekaligus. Salah satu diantaranya mungkin mendapat prioritas utama oleh suatu media (pada suatu ketika), sehingga mengabaikan fungsi lainnya. Bila fungsi hiburan yang diutamakan misalnya, maka komunikasi 5 Sejak artikel ini selesai dibuat Facebook kini tersedia dalam 64 bahasa. 56 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 yang memenuhi fungsi pengamatan tidak akan mungkin dijalankan dengan efektif. Efektivitas media dalam mengkomunikasikan suatu substansi ikut ditentukan oleh fungsi yang diutamakan media yang bersangkutan. Fungsi internet-Facebook yang sering diutamakan adalah fungsi yang pertama. Bagi kebanyakan pemilik akun Facebook biasanya menggunakannya sebagai sumber informasi serta sarana komunikasi untuk mengamati perubahan “lingkungan” yang langsung dapat mempengaruhi kehidupan. Media ini dapat online kapan saja (saat ini pengguna ponsel yang terdapat fasilitas internet bisa) di mana saja, sehingga dapat memberitahukan perubahan keadaan terakhir secara cepat. Makin tidak menentu keadaan, makin tinggi rasa ketidakpastian, makin ramai isu, makin cepat perkembangan. Fungsi kedua, pengembangan konsensus melalui media massa, biasanya mengemuka pada waktu timbulnya perkembangan ke arah perubahan. Setelah mendapat informasi tentang perkembangan baru yang dianggap penting, masyarakat membicarakannya dari berbagai segi serta menelaah implikasinya bagi mereka. Secara formal khalayak bertukar pikiran melalui Facebook—atau tanpa media namun dirangsang oleh media—dan mencoba mencari kesepakatan: apa perlu reaksi bersama, (dan jika demikian) apa yang harus dilakukan. Kesepakatan ini tidak hanya soal yang serius seperti masalah politik, tetapi dapat juga sepele. Banyak hal, termasuk nilai sosial budaya tentang apa yang baik dan buruk, gaya hidup baru, penyakit, cuaca, bisa jadi disepakati melalui wacana yang beredar lewat media internet. Terkait erat dengan konsensus adalah sosialisasi. Secara ringkas, sosialisasi adalah fungsi pendidikan dalam arti kata yang luas. Media massa meneruskan apa yang telah disepakati, baik yang baru maupun yang lama. Kesepakatan (perihal konsensus) lama yang telah menjadi warisan budaya termasuk pengalaman bangsa, nilai-nilai tradisional, adat istiadat bisa dimuat media untuk melengkapi pengetahuan generasi muda dan mengingatkan generasi tua. Barulah disosialisasikan untuk mengukuhkan dan mengajarkan konsensus yang baru diputuskan. Paparan di bawah ini mungkin akan lebih memudahkan penjelasan di atas. Mengentas Interaksi dan Komunikasi dalam Facebook Pengguna Facebook itu manusia (yang bisa membaca), dan manusia selalu berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, dari kebutuhan ekonomis hingga kebutuhan sosial dalam berkelompok (Malinowski 1938 dalam Apadurai, 1996). Pemenuhan kebutuhan sosial manusia baik untuk berkelompok maupun bergaul mencirikan manusia sebagai makluk homo socious yang mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi dalam wujud berkelompok dan berkomunikasi, dengan demikian manusia juga tidak akan lepas dari sebutan 57 Odit Budiawan - Jangan Melihat Buku dari Wajahnya homo symbolicum yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbolsimbol dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain (Turner, 1990:63). Interaksi juga merupakan kebutuhan psikologis bagi kelompok ataupun bagi individu yang antara lain untuk memenuhi keinginan mendapatkan rasa aman. Schultz (dalam Verhaar, 1989:41) menjelaskan bahwa setiap orang memerlukan kebutuhan kendali (control), afeksi (affection), dan inklusi (inclusion). Kebutuhan kendali dimaksudkan bahwa setiap orang ingin mencari kedudukan tertentu, menyangkut hal mengontrol dan dikontrol orang lain. Kebutuhan afeksi (rasa kasih) mempunyai makna bahwa setiap orang memiliki hubungan antar pribadi, menemukan seseorang yang dapat dicintai dan mencintai, sehingga terjadi hubungan yang intens, intim. Sedangkan kebutuhan inklusi (atau ketermasukan) dimaksudkan bahwa setiap orang ingin agar menjadi bagian atau termasuk ke dalam golongan tertentu, sehingga mereka merasa dirinya dikatakan sebagai orang yang mempunyai jati diri atau identitas6. Kesemuanya disediakan di Facebook yang merupakan public sphere, istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Juergen Habermas. Terminasi public sphere biasanya digunakan dalam kerangka komunikasi politik yang positif. Public sphere digambarkan oleh Habermas sebagai sebuah ruang inklusif di mana masyarakat secara kolektif membuat sebuah opini publik dalam sebuah lingkungan terkait dengan kondisi sosial politik maupun ekonomi. Kebutuhan interaksi bagi manusia merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap manusia. Kini, dalam dunia yang multikultur, dunia kita tengah menuju proses untuk menjadi sebuah pemukiman global (a global village)7. Karenanya Facebook merupakan public sphere namun inklusif, semua orang asal “melek” komputer bisa menggunakannya. Pun tujuan orang menggunakan Facebook juga kian berkembang. Orang mulai meliriknya sebagai tempat untuk melemparkan sebuah wacana. Ketika wacana yang dilemparkan ditanggapi oleh pihak lain, mereka merasa eksis di sana hingga seterusnya berkembang tanpa sadar menjadi sebuah opini publik. Bisa jadi dalam situasi seperti ini yang paling diuntungkan adalah dunia marketing, dari marketing barang elektronik, tas, baju, sepatu sampai “marketing politik”. Ada sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dalam public sphere ini baik dalam mengarahkan opini maupun memobilisasi dukungan8. Facebook sebagai sebuah jejaring sosial diakui 6 Konsep identitas yang saya pakai merujuk pada sesuatu yang dianggap mewakili diri sendiri, dianggap sama, dan merupakan hasil interaksi dengan orang lain. 7 Lihat Appadurai: Teori global village dimunculkan oleh Marshal McLuhan, kata ini sering digunakan untuk menilai sebuah media baru pada satu komunitas. 8 Pionirnya yang (mungkin) melegenda adalah Barack Obama. Grupnya yang bertajuk “One Million Strong for Barack” mampu mengumpulkan 300.000 lebih pendukung dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu saja. Hal itu wajar karena 90 persen masyarakat Amerika telah memiliki akses internet dan sebagian besar memiliki account Facebook. Di Indonesia lebih 58 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 memang cukup ampuh untuk mengikat modal sosial. Facebook banyak membantu orang untuk berhubungan dengan kolega lamanya, berinteraksi secara langsung dengan orang yang terpisah jarak dan hubungan-hubungan tersebut sering kali menghasilkan sebuah keuntungan bersama. Pranata Jejaring Dunia (Maya) dalam Facebook Facebook, sejak kelahirannya di tahun 2004 lalu telah berhasil membuat penggunanya jenak di depan monitor ataupun layar ponsel. Ia membuat orang menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengonsumsi kehidupan orang lain atau “menghias” profilnya sendiri dengan serangkaian argumen di wall yang biasanya remeh-temeh. Facebook sedang membuat perubahan kultural dalam berinteraksi. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan dalam Facebook, seperti pertanyaan bagaimana cara orang menghadapi komunikasi verbal misalnya, wawancara perkerjaan, pidato, berekspresi, bersopan santun, memperhatikan cara bicara, tentu saja tidak terjawab. Karena itu, bagi saya Facebook justru membentuk sifat komunikasi yang loyo dan merusak keterampilan dalam berkomuikasi. Tidak berhenti sampai di situ saja, Facebook juga mempunyai potensi terhadap bergesernya “tatanan sosial”. Hal ini terjadi pada perubahan arti kata “teman” misalnya. Sikap ini di kemudian hari bisa menimbulkan beberapa resiko, karena “teman” di sini bersifat verbal, artinya hanya teman dalam sebutan. Setelah itu “mereka adalah orang asing”. Sebuah tulisan dalam harian Kompas Minggu (2009) pernah menyebutnya sebagai “the illusion of intimacy”. Relasi sosial di dalam Facebook hanyalah sebuah ilusi belaka, palsu. Orang merasa dekat dan intim di dunia maya, namun tidak saling menyapa di dunia nyata. Inilah "ilusi akan keintiman" yang berusaha dijembatani, dan Facebook menjadi penting dalam masyarakat yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas hubungan sosial, karena tidak memungkinkan untuk mewacanakan esensi pertemanan sesungguhnya seperti kepercayaan dan kasih. Adapun fenomena ini malah mengakibatkan orang untuk menghindari komunikasi secara tatap muka. Alasan klasik yang biasa dikemukakan adalah karena lebih mudah. Sedikit cerita, beberapa waktu lalu saya mendengar dua orang (sebut saja X dan Y) bergosip–penasaran tentang kawannya yang “putus” dengan pacarnya. “Eh si A putus ya sama B?” tanya Y. “Lho kamu tahu dari mana?” sambut X balas bertanya. “Kok, statusnya B sering galau-galau terus ya? fenomenal lagi, sebuah page bernama Say No To Megawati mampu meraup hampir 100.000 pendukung hanya dalam tiga hari. Padahal di negeri ini hanya ada lima belas juta orang yang memiliki akses internet dengan jumlah account Facebook dua juta saja. Entah berpengaruh secara langsung atau tidak, yang jelas keesokan harinya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) turun hingga lima persen dalam pemilu legislatif. 59 Odit Budiawan - Jangan Melihat Buku dari Wajahnya Bentar, coba aku lihat di Facebook dulu”, kata Y sembari membuka Facebook. Dilihatnya kolom info yang menyediakan pilihan single, in relationship with, married, cerai, bahkan cerai mati. Pertanyaan langsung bertatap muka menjadi sungkan untuk ditanyakan, karena (jawabnya ketika saya tanya) selain tidak mau turut campur urusan orang lain (meski tetap bergosip) juga takut jika nanti malah menginggatkan luka hatinya. Terjadinya gap antara dunia nyata dengan dunia maya yang dikhawatirkan akan mengancam kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara verbal tidak sepenuhnya tepat. Bergosip yang dianggap sebagai kontrol sosial dalam masyarakat masih saja dilakukan di dunia nyata. Bahan pembicaraan yang terjadi di jejaring dunia maya bisa jadi fakta dari kenyataan di dunia nyata. Begitu juga sebaliknya, segala yang ada di Facebook bisa juga menjadi bahan pembicaraan ketika bertatap muka. Sedangkan yang terakhir adalah memudarnya “nuansa privasi seseorang” dalam masyarakat. Sudah barang tentu apa yang “dibagikan” dalam situs ini mudah sekali dibaca oleh orang lain (kecuali memang benar-benar sudah diatur dengan cermat). Kurangnya rasa tanggung jawab sosial pengguna Facebook terkait privasi masih nyata. Mereka mungkin sangat ketat menjaga privasi masingmasing namun tanpa disadari mereka sangat mungkin melanggar privasi orang lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya posting yang berbau bullying dan hal-hal yang bertujuan untuk membuat malu orang lain. Sebuah Penutup Facebook sebagai sebuah jejaring sosial diakui memang cukup ampuh untuk mengikat modal sosial. Ia banyak membantu orang untuk berhubungan dengan kolega lamanya, berinteraksi secara “langsung” dengan orang yang terpisah jarak dan hubungan-hubungan tersebut sering kali menghasilkan sebuah keuntungan bersama. Di balik kekuatannya ini Facebook juga menyimpan potensi bagi terbentuknya “tatanan sosial” baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sebanyak apapun orang berkata jika “Facebook adalah suatu temuan besar yang mengubah dunia dalam berkomunikasi”. Nyatanya Facebook tetaplah salah satu cara dalam berinteraksi hingga kini. Linda M. Gallant (dalam Kompas, 2009) berargumen bahwa Facebook melejit adalah karena, "situs internet umumnya menyajikan informasi dan para penjelajahnya hanya menerima apa adanya. Sekarang ini para penjelajah ingin berpartisipasi sebagai pengisi situs. Facebook memenuhi hasrat itu". Dunia digital mengubah interaksi manusia yang secara evolutif membutuhkan pertemuan fisik dan psikis menjadi pertemuan virtual yang dingin. 60 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 Jika jejaring sosial seperti Facebook tidak digunakan dengan bijak, hubungan kekerabatan antar manusia bakal kehilangan keintimannya. Evolusi tubuh kita dirancang untuk bertemu secara fisik dan psikis. Dari kedua hal itu, manusia diarahkan untuk masuk situasi konflik, ada perasaan senang, gembira, bengong, marah, benci. Ragam cara itu manusia bisa bertahan hidup, dengan kontak fisik manusia bisa mengasah kewaspadaannya, mampu mengenali orang lain, bahkan bisa membaca emosi seseorang. Manusia yang (kecanduan) membangun pertemanan lewat internet tanpa disertai pertemuan fisik dengan orang tersebut akan kehilangan pijakan dengan dunia nyata. Ia masuk dalam dunia simulasi yang seolah-olah punya banyak teman, padahal tidak. Tanpa monitor dan internet dia akan kaku, sulit bicara dan menyampaikan bahasa. Jadi waspadalah. Bibliografi Buku Askew, Kelly dan Richard R.Wilk. 2000. The Anthropology of Media. Minneapolis: University of Minneapolis Press. Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2006. Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta: Kepel Press. Ajidarma, Seno Gumira. 2002. Kisah Mata. Yogyakarta: Galang Press. Apadurai, Arjun.1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. London: Routledge Bakhtin, M.M. 1981. The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press. Barker, Chris. 2005. Cultural Studies, Teori dan Praktik. Yogyakarta: Bentang. Barnard, Alan. 2000. History and Theory in Anthropology. Cambridge University Press. Barth, Fredrik. 2005. One Discipline. Four Ways: British, German, French, and American Anthropology ED. University of Chicago Press. Bellah, R.N. 1976. Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. New York: Harper and Row. Boudrillard, Jean. 2004. Masyarakat Konsumsi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Featherstone, Mike. 1995. Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage. Douglas, Mary dan Baron Isherwood. 1996. The World of Goods, towards an Anthropology of Consumtion. London and New York: Routledge. Daiches, David. 1981. Critical Approaches to Literature. New York: Longman. De Certeau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press. Dominick, Josep R. 1990. The Dynamics of Mass Communication, Third Edition. 61 Odit Budiawan - Jangan Melihat Buku dari Wajahnya McGraw-Hill Harvey, David. 1989. The Condition Of Postmodernisme. Oxford: Basil Blackwell. Hojsgaard, Morten T. dan Margaret Wartbung (eds.). 2005. Religion and Cyberspace. New York: Routledge. _________. 2007. Cyber Religion on the Cutting Edge Between the Virtual and the Real. New York: Routledge. Kleden, Ignas. 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES Laksono, Paschalis Maria. 2004. “Memotret Wajah Kita Sendiri (kata pengantar)” dalam Roem Topatimasang (ed.), Orang-orang Kalah. Yogyakarta: Insist Press. _________. 2007. Visualitas Gempa Yogya 27 Mei 2006. Yogyakarta: Rumah Sinema. Miller, Daniel. 2000. The Internet: An Ethnographic Approach. New York: Berg. Mrazek, Rudolf. 2006. Engineers Of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Rogers, Everett M. 1994. A History of Communication Study: A Biographical Approach. Free Press. Strinati, Dominic. 2003. Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Popular. Yogyakarta: Bentang. Turner, Victor. 1990. Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life (Body, Commodity, Text). Duke University Press. Verhaar. J.W.M. 1989. Pengantar Linguistik. Yogyakarta: UGM Press. Walker, John A. dan Sarah Chaplin. 1997. Visual Culture. Manchester & New York: Manchester University Press. Wirodono, Suwardian. 2005. Matikan TVmu: Teror Media Televisi di Indonesia. Yogyakata: Resist Book. Winangun, Wartaya. 1990. Masyarakat Bebas Struktur, Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner. Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius. Jurnal Kleden, Ignas. 1987. “Kebudayaan Pop: Kritik dan Pengakuan” dalam Prisma No. 5 Tahun XVI Mei 1987. Hal: 3-7. Surat kabar Kompas. 2009. Dunia tersihir Facebook, 15 Maret. Kompas. 2009. Kekerabatan Baru itu Facebook, 15 Maret. Koran Tempo. 2009. Waspada dengan Jejaring dunia Maya, no. 7, 19 April. 62 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 BERITA TANTANGAN ANTROPOLOG(I) MENGHADAPI RUANG MAYA: SEBUAH INTISARI DISKUSI1 Dian Ajeng Pangestu, Muhammad Ichsan Rahmanto, Nur Rosyid2 Kehadiran jejaring sosial dalam dunia maya ditengarai membawa berbagai dampak signifikan dalam relasi antar manusia atau komunitas belakangan ini. Orang sekarang tidak perlu menghadirkan tubuhnya secara langsung untuk bertatap muka dan berkomunikasi. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter telah menyediakan fasilitas untuk tidak hadirnya tubuh dalam berelasi itu. Di sana orang bisa berteriak, curhat, bercanda, nggombal, dan mengumpat sesukanya. Tidak hanya itu saja, ada berbagai persoalan baru yang muncul dari perubahan cara orang berkomunikasi. Tulisan hasil diskusi ini hendak memberikan beberapa gambaran baru mengenai social network (jejaring sosial) dalam kacamata antropologi. Sehingga ke depannya para (calon) antropolog bisa mengembangkan penelitian dan etnografi ke sana. Jejaring Sosial sebagai Ruang Sosial Baru Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai bagaimana kultur yang terkonstruksi dari tumbuhnya jejaring sosial yang baru itu, Muhammad Zamzam Fauzanafi menjelaskan, dunia internet termasuk rumit untuk dipahami daripada organisasi sosial yang nyata, seperti masyarakat, komunitas, atau kelas tertentu. Dunia internet harus dipahami ke dalam tiga hal yang membangunnya, yakni manusia, media, dan teks. Pertama, manusia yang menggunakan internet harus dibedakan dengan “penonton” (audience). Penonton di sini mempunyai dua arti: penonton yang pasif sebagai pemirsa dan penonton interaktif sebagaimana yang ada ketika pertunjukan sedang berlangsung. Kemudian ada konsep lain yang disebut sebagai “pengguna’”(user). Pengguna ini sifatnya lebih interaktif dari 1 Diskusi bertemakan “Budaya Digital dan Netnografi” diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2011 pukul 15.00 WIB di Perpustakaan Jurusan Antropologi dengan menghadirkan pemantik Muhammad Zamzam Fauzanafi, S.Ant., M.A., Staf Pengajar Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2 Tim Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Keluarga Mahasiswa Antropologi (KEMANT) Periode 2011/2012, Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tim ini mencatat/merekam hasil diskusi dan menuliskan kembali dalam bentuk artikel utuh. PSDM rutin menyelenggarakan diskusi terbuka setiap bulan.. 63 Tantangan Antropolog(i) Menghadapi Ruang Maya penonton jenis kedua. Mereka mempunyai posisi yang sentral dalam membangun jejaring sosial tersebut. Kedua adalah “teks”. Teks ini ditulis oleh user, dibaca dan dikomentari oleh user itu sendiri. Singkatnya, user itulah yang membangun wacana. Akan tetapi, wacana yang dibangun di jejaring sosial satu dengan yang lain, antara di Facebook dengan Twitter misalnya, itu berbeda. Salah satunya terlihat dari bentuk curhatan di Facebook yang berbeda dengan Twitter. Hal ini salah satunya dikarenakan karakter yang disediakan berbeda. Sehingga “bangunan” media jejaring sosial ikut menentukan kecenderungan wacana yang dibangun. Antara user, wacana (teks, audio dan/atau visual), dan media merupakan tiga elemen dari jejaring sosial. Jejaring Sosial dan Isu Perubahan Sosial Ada beberapa informasi dari hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan hadirnya jejaring sosial, seperti contohnya: internet menyebabkan identitas ganda (multiple identity) pada user, revolusi di negara-negara Arab, gerakan Facebookers “Koin Untuk Prita”, relawan twit untuk korban Merapi, dan sebagainya. Inti dari penelitian-penelitian itu mengindikasikan, jejaring sosial mendorong terjadinya perubahan sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Asumsi ini berawal dari gagasan bahwa sebelum lahirnya jejaring sosial, belum pernah ada gerakan-gerakan sosial yang masif dan berpengaruh. Fauzanafi pertama-tama menjelaskan kasus multiple identity. Beberapa peneliti berasumsi, “semenjak ada internet dan orang mempunyai akun Facebook, mereka lebih banyak meninggalkan dunia nyatanya. Mereka lebih suka curhat di dunia maya. Mereka lebih suka menggunakan akun yang lain dari namanya dan kadang tidak jelas”. Fenomena ini memang menarik untuk diteliti. Apa memang benar orang meninggalkan dunia nyata? Apa dunia maya berbeda dengan dunia nyata? Apa konektornya? Dosen alumni University of Manchester ini menjelaskan, pernah ada seorang temannya meneliti fenomena “relawan Twitter” ketika erupsi Merapi berlangsung. Peneliti menemukan bahwa kejadian meningkatnya aktivitas erupsi berbarengan dengan meningkatnya pemberitaan erupsi di Twitter atau “aktivitas nge-twit”. Selain itu, orang-orang juga semakin ramai menjadi relawan. Cara menelitinya sangat sederhana dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti tersebut menghitung frekuensi aktivitas erupsi Merapi bersamaan dengan aktivitas orang mengabarkan berita erupsi itu melalui Twitter. Ternyata kedua hal ini menunjukkan grafik frekuensi yang ekuivalen. Merapi meletus ini merupakan kejadian alam dan Twitter adalah kejadian media. Seorang teoritikus 64 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 dari Israel pernah menyatakan bahwa hal ini disebut sebagai gejala media event. Seperti halnya kasus “Koin Untuk Prita”, kasus ini sama-sama dikompori oleh gerakan kolektif. Dalam bencana Merapi, ketika Merapi meletus, frekuensi pemberitaan kejadian melalui Twitter meningkat, ada orang beramai-ramai menjadi relawan. Jika dihubungkan, ada tiga ruang yang terbentuk: Merapi meletus adalah kejadian alam, Twitter adalah media kultural, dan relawan adalah kejadian di dunia nyata (sehari-hari). Bagaimana hubungan ketiga hal tersebut? Relasi antara tiga ruang ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan pendekatan antropologis. Sebelum solidaritas “Koin Untuk Prita” tersebut terbentuk sebenarnya sudah ada penggalangan solidaritas yang sejenis untuk korban Lapindo melalui jejaring sosial. Ada asumsi dari sebuah penelitian yang mengatakan, “jejaring sosial atau internet bisa memancing solidaritas”. Menurut Fauzanafi, “jika memang demikian, mengapa hasil kasus Prita dengan kasus Lapindo berbeda?”. Penggalangan dana untuk Prita yang sukses ini harus diakui bukan karena jejaring sosial, tetapi ada syarat-syarat dasarnya: konteks. Kasus Prita jelas berbeda dengan Lapindo. Prita adalah seorang pribadi yang teraniaya, ia berasal dari kelas menengah yang kebetulan mengakses sebuah rumah sakit elit. Ini berarti ketika kita bersimpati kepada Prita lalu meng-klik tombol dukungan, maka tidak akan beresiko apa-apa. Sedangkan Lapindo adalah kasus yang berspektrum luas, ada unsur kekerasan, ekonomi, dan bahkan politik. Sudah jelas ini cukup beresiko. Sehingga dalam memahami suatu gejala sosial-budaya, harus dikembalikan kepada konteksnya. Di sinilah antropologi mempunyai peran yang potensial. Kesimpulan lain yang bisa kita petik dari hal di atas adalah hadirnya jejaring sosial bukan merupakan penyebab tumbuhnya solidaritas. jejaring sosial berperan hanya sebatas memfasilitasi berbagai solidaritas itu. Jejaring Sosial sebagai Lapangan Baru bagi Kerja Antropolog(i) Salah satu kunci dari penelitian antropologi untuk memahami kelompokkelompok manusia tertentu adalah merasakan langsung dan hadir di dunia mereka. Kerja lapangan ini perlu dilakukan agar kontekstualitas suatu fenomena tidak hilang dalam memahaminya. Apa yang pertama-tama dilakukan antropolog dalam menghadapi dunia maya, adalah mengenali “bangunan” jejaring sosial dan bahasa-bahasa yang dipakai di sana. Tanpa pengetahuan akan dua elemen itu, kita belum bisa memaksimalkan pemahaman kita mengenai konstruksi kultur baru dalam ruang maya. Selanjutnya yang membedakan penelitian antropologi dengan disiplin ilmu lain ialah terletak pada penggunaan kata tanya “bagaimana” dalam menyusun 65 Tantangan Antropolog(i) Menghadapi Ruang Maya permasalahannya, bukan “mengapa”, “kapan”, atau yang lainnya. Seorang antropolog bisa mengembangkan penelitiannya pada tiga elemen atau hanya salah satunya saja, kemudian diwacanakan ke aspek lain, apakah ekologi, politik, ekonomi, gender, aktivitas user di luar dunia maya, teks atau perbincangan yang di-share-kan, dan lain sebagainya. Seorang peneliti harus memahami sejauh mana gejala di ruang maya itu berhubungan dengan penggunanya. Sebagai contoh, kalau seseorang hendak memahami user lewat lingkungannya, akan tidak jauh berbeda dengan seseorang yang meneliti petani dengan sawahnya. Selain itu relasi manusia dengan media internet dan jejaring sosialnya bukan hanya apa yang diterima user dari media itu, tetapi bagaimana benda atau media itu digunakan. Di era digital ini, kalau antropologi ingin tetap diakui dalam memberikan sumbangsih pada pengetahuan maka kerja lapangan harus tetap dijalankan. Bisa dikatakan lapangan yang dipakai sudah berubah, tidak selalu di desa atau kota yang batas-batasnya sudah tidak tampak lagi. Dunia maya sangat potensial untuk digarap karena alasan-alasan di atas. Pada akhirnya, jika ingin meneliti sesuatu, maka fokuslah pada apa yang ingin diketahui. Jangan berpatok pada tema yang ditentukan, apakah itu netnografi atau tema lainnya. Sekarang yang mesti dipikirkan adalah apa yang ingin peneliti ketahui, sementara masalah istilah itu belakangan. Fokus dan pegangan awal yang jelas yakni: “aku ingin meneliti yang berhubungan dengan internet”. Begitu[.] 66 Jurnal RANAH Th. II, No. 1, April 2012 BERITA BUKU Digital Anthropology Daniel Miller dan Heather Horst Oxford: Berg Publishers, 2012, 256 halaman Antropologi memiliki dua tugas utama: untuk memahami apa artinya menjadi manusia, dan untuk mengkaji bagaimana kemanusiaan diwujudkan secara berbeda dalam keragaman budaya. Tugas-tugas ini telah mendapatkan sokongan baru dari perkembangan jagad digital yang sangat drastis. Buku ini menyajikan beberapa kajian antropologi pada budaya digital, antara lain untuk menunjukkan betapa produktifnya pendekatan antropologis pada bidang ini. Buku ini mengungkapkan bagaimana etnografi dapat menyajikan asumsi tentang dampak budaya digital dan mengungkapkan konsekuensi yang mendalam bagi kehidupan sehari-hari. Miller dan Horst menggabungkan ketegasan penjelasan ala buku teks dengan gaya penyampaian yang menarik, sehingga buku ini menjadi bacaan penting bagi mahasiswa maupun praktisi antropologi, sosiologi, ilmu komunikasi, atau disiplin ilmu sosial-budaya lainnya. ____________________________________ Virtual Lives: A Reference Handbook James D. Ivory Santa Barbara: ABC-CLIO, 2012, 300 halaman Buku pengantar ini memaparkan sejarah, perkembangan, dan peran dunia maya dengan latar belakang mendalam tentang dunia maya dan dampak sosialnya. Beberapa kunci dari kajian dunia digital dipaparkan, seperti deskripsi fungsi dunia maya dan diskusi masalah sosial-virtual. Dunia maya dalam bentuknya saat ini, yakni lingkungan sosial online adalah fenomena yang relatif baru. Isi buku ini meliputi beberapa perkembangan teknologi virtual, yang dapat ditarik sejak pertengahan abad ke-XX. Fokus utama adalah pada perkembangan internet dan masyarakat online sejak pertengahan 1990-an dan dampak sosial dunia maya di seluruh dunia. 67