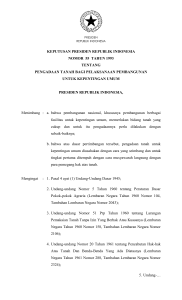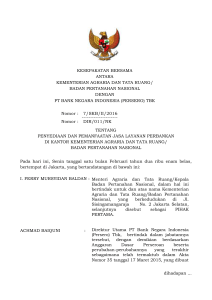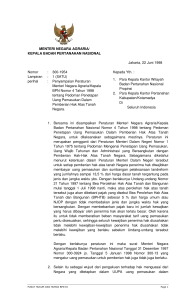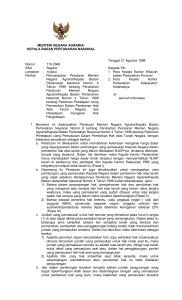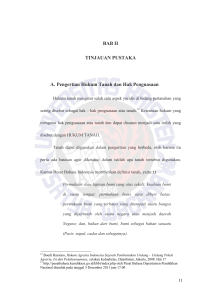BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian
advertisement

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian ini untuk menganalisis kecenderungan resistensi petani yang hidup dalam suatu desa pada penguasaan sawah dari warga luar desanya. Penelitian mengkhususkan pada sektor agraria berupa konflik memperebutkan, mempertahankan kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian di internal masyarakat maupun antara internal dengan eksternal. Eksternal di sini dapat warga luar desa, pemerintah dan korporat. Tanah merupakan hasil dan sumber makanan bagi petani. Memiliki dan menguasai tanah berarti mendapatkan makanan dan tiang hidup. Maka itu petani sangat sensitif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Mereka akan membuat gerakan atau menempuh semua cara dan rela mengorbankan segala yang ada, bahkan menumpahkan darah, demi mempertahankan tanah dan kelanjutan hidup. Tanah bagi petani bukan hanya sekedar modal atau harta benda semata tetapi lebih dari itu tanah merupakan faktor krusial bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat pedesaan, termasuk juga terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik secara luas bagi negaranegara agraris (Soetrisno, 1995). Tanah menjadi perebutan karena dipandang sebagai sumberdaya yang sangat penting (Tjondronegoro, 1999). Apalagi tanah di Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk berorientasi pada 1 2 pertanian. Di sini, tanah pertanian merupakan faktor utama dalam kedaulatan pangan, atau bisa menjadi keterjaminan akan pangan dan penghidupan. Polanyi (2001) menjelaskan bahwa tanah dan relasi sosial merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tanah tidak bisa dijadikan barang dagangan semata dengan cara memisahkan dengan relasi-relasi sosial yang sudah melekat, akan tetapi jika dipaksa harus menjadi komoditas yang lepas dari hubungan sosial yang ada maka niscaya akan melahirkan gerakan-gerakan untuk memulihkan kembali situasi relasi sosial yang rusak (Rahman, 2013). Bagi masyarakat lokal, tanah bukanlah sekedar suatu sumberdaya produksi, suatu habitat, atau batas politik. Tanah memiliki makna lebih dari itu. Tanah merupakan basis bagi organisasi sosial, sistem ekonomi, dan identifikasi kultural masyarakat (La Via Campesina, 2008). Maka itu dikuasainya tanah oleh masyarakat luar desa, menjadi sebuah ancaman pada sebuah eksistensi kehidupan, terlebih usaha untuk peningkatan kesejahteraan. Disinilah yang kemudian menimbulkan konflik. Masyarakat luar desa, dapat sesama masyarakat yang sederajat atau kekuatan politik dan ekonominya relatif sama, maupun yang lebih kuat seperti kaum pemodal, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Terlebih, di tengah situasi berkutat masyarakat petani yang masih saja dengan persoalan minimnya lahan untuk bertanam, ancaman gagal panen, dan sulitnya menjual produk pertaniannya, pada saat bersamaan petani harus berhadapan dengan masifnya ekspansi modal yang semakin gencar ke pelosok-pelosok desa. Sementara perhatian pemerintah sangat kurang terhadap 3 petani, maka dalam situasi tersebut tentu mereka semakin terjepit. Dalam kondisi seperti itulah masyarakat desa akan mengalami apa yang Geertz sebut dengan involusi. Oleh karena itu sangat mudah ditebak apa yang menjadi konsekuensi dari keadaan tersebut yaitu semakin meningkatnya konflik-konflik agraria seiring dengan semakin meluasnya kasus-kasus pencaplokan/okupasi dan konservasi lahan, baik di sektor pertambangan maupun di sektor perkebunan dan kehutanan. Dalam perkembanganya persoalan konflik agraria seringkali semakin rumit akibat banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya yang meliputi institusi/penerima konsesi dengan masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain baik secara individual maupun kelembagaan (Billa, 2010). Perebutan penguasaan lahan, akan semakin meningkat jika ternyata lahan yang diperebutkan memiliki keunggulan, seperti letaknya strategis, kualitas tanah yang mampu menghasilkan komoditas terbaik dan mengandung sumber daya untuk ditambang. Bagi Gunawan Wiradi (2009), secara umum akar krisis agraria terletak pada sumber-sumber fakta terjadinya agraria baik ketimpangan dalam dan bentuk kesenjangan terhadap penguasaan maupun pengalokasiannya, serta tumpang tindihnya berbagai macam produk kebijakan hukum yang mengatur atas sumber-sumber didasarkan dari persoalan agraria tersebut. diatas itu pulalah ‘persaingan’ Sehingga memperebutkan sumber-sumber agraria kerapkali meruncing menjadi ‘konflik agraria’. 4 Mochtar Mas’oed dalam Noer Fauzi (1997) menyebut empat isu pokok persoalan tanah. Pertama, reduksionisme persoalan tanah. Dalam masyarakat berkembang semakin kapitalistik, nilai tanah dilepaskan dari berbagai dimensi, sosial, kultural dan politik yang melekatnya. Tanah hanya dilihat dari utilitas ekonominya. Kedua, tanah sebagai alat spekulasi akumulasi kapital. Perkembangan kapitalisme juga mendorong perubahan fungsi tanah yaitu fungsi sebagai salah satu faktor produksi utama menjadi investasi. Akibatnya tanah dibeli tidak untuk digarap atau dikembangkan. Ketiga, konsentrasi pemilikan atau penguasaan secara besar-besaran. Keempat, adanya ‘keharusan struktural’ bagi pemerintah nasional untuk mengakomodasi tuntutan investor asing dalam hal lahan untuk keperluan pembangunan pabrik. Savitri dalam Luthfi (2012) menyebut kondisi krisis agraria diantaranya ditandai, pertama terjadinya konflik klaim penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Kedua, hilangnya penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Ketiga, keterbatasan akses pada sumbersumber ekonomi dan penghidupan, dan keempat, keterbatasan tata kuasa dan tata kelola mandiri rakyat atas proses kerusakan ekologis. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam kajian arah kebijakan pengelolaan pertanahan nasional 2015- 2019 menyampaikan data yang diterima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2012 tercatat 7.196 kasus pertanahan yang terdiri atas sengketa, konflik dan perkara. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan (Bappenas, 2013) 5 Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) (2013) mencatat sepanjang tahun 2012, terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, yang melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK). Dari sisi korban 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka akibat penganiayaan, 25 diantaranya luka akibat tertembak dan 3 jiwa melayang dalam konflik-konflik agraria yang terjadi. Sementara sepanjang tahun 2013, terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Jika konflik yang terjadi dilihat berdasarkan setiap sektor konflik agraria, maka persebarannya berdasarkan sektor sepanjang tahun adalah sebagai berikut; sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%). Konflik agraria sebagaimana yang dilaporkan oleh KPA adalah konflik agraria struktural, yaitu konflik agraria yang mengakibatkan dampak serta korban yang meluas dalam dimensi sosial ekonomi dan politik akibat kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, sengketa pertanahan dan perkara pertanahan yang kerap muncul tidak termasuk kedalam kategori konflik di dalam laporan ini. (KPA,2013) Sedang sepanjang kekuasaan SBY sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2014, KPA (2014) mencatat terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar, dimana ada lebih dari 926.700 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik 6 berkepanjangan. Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengaki-batkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru aparat, serta tewasnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut. Konflik-konflik yang menonjol tersebut diantaranya kasus pertanahan di Kabupaten Mesuji Lampung dan Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan, Kasus Pertanahan di Desa Harjokuncaran Malang Jawa Timur, Kasus Pertanahan di Alastlogo Pasuruan Jawa Timur, Permasalahan Tanah Pangkalan Udara Atang Sanjaya Sukamulya Bogor Jawa Barat. Sejak 2006 sampai pendataan akhir tahun 2012 HuMa mendokumentasikan 232 konflik sumberdaya alam dan agraria. Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Yang memprihatinkan, luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektare atau lebih dari 20 ribu km2. Dari 22 provinsi konflik yang didokumentasikan, tujuh provinsi di antaranya memiliki konflik paling banyak, Kalimantan Tengah sebanyak 67 kasus dengan luasan 254.671 hektare. Jawa Tengah (36 kasus, 9.043 ha), Sumatera Utara (16 kasus, 114,385 ha), Banten (14 kasus, 8,207 ha), Jawa Barat (12 kasus, 4,422 ha), Kalimantan Barat (11 kasus, 551,073 ha) dan Aceh (10 kasus, 28.522 ha) (Widiyanto, 2012). Konflik-konflik diatas menunjukkan perebutan tanah yang terjadi akibat adanya kelangkaan tanah. Sifat tanah relatif tidak bertambah, sementara 7 kebutuhan tanah untuk keperluan tempat tinggal dan pangan semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut akan menimbulkan kompetisi di masyarakat untuk menguasainya. Penguasaan atas tanah mempengaruhi hubungan manusia dengan ketersediaan pangan karena tanah merupakan sumberdaya yang berhubungan dengan produksi. Ketimpangan dalam penguasaan tanah akan mempengaruhi kemampuan produksi. Peningkatan produksi pertanian terutama pangan, sangat diharapkan untuk mencapai kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup (Saleh, 2011). Perebutan penguasaan lahan ini terjadi antara warga dalam satu wilayah tempat tinggal atau desa maupun dengan warga di luar desa. Masing-masing pihak menempuh berbagai cara, seperti membeli, menyewa, bahkan termasuk menikah. Merebut kembali tanah yang sudah dibeli dan disewakan pun ditempuh baik dengan jalan halus atau kekerasan. Langkah halus, ini dapat dilakukan dengan memperkuat solidaritas untuk soliditas antar warga. Solidaritas ini dengan memperkuat lembaga sosial masyarakat, yang pada derajat tertentu mampu memproteksi tanah di desa dari penguasaan warga luar desa. Sehingga saingan menjadi berkurang. Sebab persaingan hanya diantara warga dalam satu desa. Penelitian ini penting, karena juga terjadi konflik perebutan lahan di Desa Trasan yang berada di kaki Gunung Sumbing. Konflik ini terkait erat dengan kemampuan tanah di desa yang berada di ketinggian 300 meter diatas permukaan 8 laut tersebut dalam menghasilkan komoditas pangan berupa beras, selain daerahnya yang dinilai strategis untuk tempat usaha dan pemukiman. Menarik diteliti gerakan atau langkah-langkah yang dilakukan warga Desa Trasan dalam memproteksi lahan, seperti bagaimana penanaman pentingnya kepemilikan lahan, perkuatan ideologi dan memperkuat lembaga sosial hingga adanya kesepakatan masyarakat, meski tidak secara tertulis, untuk tidak menjual tanah pada warga luar desa terutama etnis tertentu. Di sini terdapat pertarungan antara moral ekonomi warga yang berusaha untuk mempertahankan aset tanah dengan membangun relasi-relasi sosial diantara warga, serta membuat gerakan perlawanan (resistensi) pada mereka yang berusaha untuk menguasai tanah di desa, atau dalam kata lain ada perlawanan petani terhadap penetrasi modal. 1.2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan inti permasalahan mengapa masyarakat desa bersikap resisten pada penjualan dan penyewaan tanah di desa terhadap masyarakat dalam satu desa dan terhadap masyarakat luar desa: Dari pertanyaan inti tersebut diajukan tiga pertanyaan turunan berupa 1. Bagaimana transaksi jual beli dan sewa menyewa tanah di Desa Trasan? 2. Bagaimana praktek transaksi jual beli dan sewa menyewa antara masyarakat desa dengan masyarakat di luar desa ? 9 3. Bagaimana sikap resistensi warga desa terhadap penjualan dan sewa menyewa tanah warga desa terhadap warga luar desa? 4. Mengapa sikap resistensi tersebut muncul ? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasar rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan konflik pertanahan dalam komunitas untuk proteksi tanah. 2. Mendalami permasalahan jual beli dan sewa menyewa lahan yang dapat menimbulkan konflik, terutama permasalahan pertanahan di Jawa. 3. Mendalami kohesi sosial masyarakat desa untuk memperkuat kontrol orang desa terhadap penjualan tanah. 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan secara akademis dapat menjelaskan penyebab terjadinya resistensi petani pada penjualan dan penyewaan tanah di desa, memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sosial, ekonomi dan pertanian secara umum, serta manajemen konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para akademisi dalam mengkaji dan mengembangkan model teoretis untuk memahami pola-pola konflik agraria di masyarakat petani. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis yang akan diambil mengenai agraria, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. 10 1.5. Tinjauan Pustaka Telah banyak studi yang membahas tentang kehidupan sosial ekonomi petani dan resistensi petani. Di Indonesia penelitian ‘diawali’ oleh Sartono Kartodirdjo pada 1966 yang meneliti peran gerakan sosial pedesaan di Banten. Tulisan tersebut yakni ‘ Pemberontakan petani Banten 1888: Sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia’, yang kini menjadi bacaan wajib bagi peminat studi gerakan dan kehidupan petani. James C. Scott (1992) meneliti kehidupan dan perlawanan petani di Asia Tenggara. Dia menemukan adanya “etika subsistensi” atau etika untuk bertahan hidup dalam kondisi minimal, yang melandasi segala perilaku kaum tani dalam hubungan sosial di pedesaan, termasuk pembangkangan terhadap inovasi yang datang dari penguasa. Ia membuktikan bahwa ‘kepasrahan kaum tani’ bukanlah benar-benar kepasrahan, melainkan aksi-aksi perlawanan anonim dalam diam yang berlangsung setiap harinya, yang bahkan telah menjadi suatu subkultur Widiyanto, dkk (2010) yang meneliti dinamika nafkah rumah tangga petani pedesaan dengan pendekatan Sustainable livehod Approach pada petani tembakau di lereng gunung Merapi-Merbabu, Propinsi Jawa Tengah menyimpulkan petani menghadapi situasi kerentanan antara lain fluktuasi harga, perubahan cuaca dan musim, kecenderungan luas kepemilikan dan penguasaan lahan sempit dan degradasi lingkungan. Situasi kerentanan itu akan berpengaruh pada mekanisme rumah tangga petani dalam “memainkan” berbagai asset yang dimiliki (modal alami, modal sumberdaya manusia, modal fisik, modal finansial, dan modal sosial). Pada petani lahan luas lebih menggunakan 11 strategi akumulasi sedangkan pada petani lahan sedang dan sempit menerapkan strategi konsolidasi (pada situasi normal) dan bertahan hidup (pada situasi krisis). Bambang Winarso (2012) pada penelitian dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah Pedesaan di Indonesia menemukan perkembangan kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan, khususnya di wilayah agroekosistem lahan pertanian bergerak dinamis serta ada kecenderungan ke arah kepemilikan yang semakin sempit, terutama di desa-desa yang dominan padi sawah. Hal yang demikian tentu berimplikasi terhadap pola kepemilikan maupun penguasaan lahan itu sendiri yang cenderung semakin beragam. Implikasi lainnya ialah pendapatan petani yang cenderung mengikuti pola kepemilikan maupun penguasaan lahan itu sendiri. Semakin meningkatnya petani tuna kisma (petani non lahan) dan petani gurem (petani berlahan sempit) akan membawa dampak sosial maupun ekonomi bagi keluarga petani tersebut. Sistem waris tidak bisa dibendung, dan transaksi jualbeli lahan tidak bisa di cegah. Hal utama yang perlu mendapat perhatian ialah kesejahteraan masyarakat desa khususnya masyarakat lapisan bawah. Hal tersebut karena justru lapisan inilah yang sangat rentan terhadap gejolak sosial maupun ekonomi. Ghesilla Resha Rosita (2014) yang meneliti Kemiskinan Masyarakat Petani (Studi Tentang Perubahan Kelembagaan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan serta Hubungan Kerja Pada Masyarakat Dataran Tinggi Dusun Arjosari Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan). Hasilnya menunjukkan bahwa pada perkembangannya terjadi perubahan kepemilikan 12 lahan melalui waris, penjualan lahan, serta penyewaan. Perubahan tersebut turut berdampak pada posisi tawar petani setempat yang beralih menjadi buruh tani, bahkan tidak sedikit yang bekerja pada lahan pertanian bekas milik mereka. Dari kondisi yang demikian itu, kemiskinan tidak dapat dihindari lagi oleh sebagian besar masyarakat petani apel. Achmad Habib (2004) meneliti pergolakan petani Jawa dengan etnik Cina. Dia memotret adanya kesamaan maksud dan tujuan dari etnis Cina dan Jawa dalam penguasaan tanah, yakni peningkatan pendapatan. Sehingga mereka samasama melakukan berbagai usaha untuk menguasai dan mempertahankannya. Langkah itu dengan cara kasar berupa protes atau secara halus dengan memperkuat solidaritas internal. Disinilah kedua etnis sama-sama menunjukkan ketidakadilan. Dia menuliskan bahwa masalah masyarakat pedesaan juga punya kompleksitas tersendiri yang sangat memungkinkan memunculkan gerakan perlawanan yang semakin luas. Gunawan Wiradi (2009) dalam Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi (2010) meneliti tentang land reform lokal a la Desa Ngandagan. Tulisan ini menunjukkan perlindungan atas tanah bisa dilakukan atas inisiatif lokal, dengan syarat adanya kepemimpinan yang demokratis tapi tegas dan berwibawa, dan didukung rakyat. Hiroyoshi Kano dalam Sediono dan Wiradi (1984) mengemukakan pada 1868 Pemerintah Hindia Timur melakukan survey tentang tanah. Resume akhir atau Eindresume diterbitkan pada 1876 dan disusul dua jilid berikutnya 1880 dan 13 1896. Di resume itu disampaikan pemindahtanganan tanah telah diatur oleh desa, aturan itu diantaranya jika terpaksa menjual tanah maka dilarang ke orang dari daerah lain, demikian halnya menggadai atau sewa tanah tahunan. Maksud orang dari daerah lain ini mengacu pada orang yang tinggal di luar desa terutama orang Eropa dan Cina. Dari resume itu disimpulkan hubungan penguasaan tanah didesa dipengaruhi peraturan-peraturan komunal desa yang ketat. Tanah pertanian pada umumnya tidak dipandang sebagai komoditi penuh, hal ini mencegah konsentrasi penguasaan tanah yang luas melalui penjualan pembelian dan penggadaian. Hubungan ‘sakap – menyakap’ diantara petani telah dapat diamati secara langsung tetapi ditandai lebih kuat oleh gotongroyong antarpetani daripada hubungan kelas. Sedangkan penelitian mengenai kelembagaan sosial belum banyak dikaitkan dengan proteksi atau perlindungan atas tanah yang mereka kuasai atau miliki. Selama ini penelitian kelembagaan sosial, yang dalam hal ini pada resiprositas (pertukaran sosial) lebih pada penggambaran dinamika interaksi komunitas warga desa dalam penguatan hubungan sosial. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan (Hefner 1983, Djawahir, dkk. 1999, Abdullah 2001, Kutanegara 2002, Widyastuti 2003, Prasetyo 200, Lestari 2010) menunjukkan meskipun masyarakat desa hidup dalam situasi kemiskinan yang menekan ‘tradisi nyumbang’ tetap memiliki kekuatan sosialnya. Dalam tradisi masyaralat pedesaan di Jawa, ‘tradisi nyumbang’ merupakan kegiatan tolong menolong dan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial yang sangat 14 penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Nyumbang merupakan pranata sosial yang menunjukkan kepada kebersamaan perasaan moral dan komunitas (Abdullah, 2001). Pada penulisan ini, penulis berusaha untuk menjelaskan ada tidaknya kaitkan penguatan internal petani dan hubungan-hubungan sosial yang terbina dengan keberhasilan dalam memproteksi tanah. Tulisan mengambil studi di masyarakat petani di Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupate Magelang. 1.6. Landasan Teori Eric R. Wolf (1983) menggambarkan petani (peasant) sebagai orang desa yang bercocok tanam. Jadi siapapun kelompok masyarakat yang melakukan usaha pertanian dapat dikategorikan sebagai petani. Usaha pertanian ini berupa bercocok tanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan menunaikan surplus sosial dan ritualnya. Wolf tidak menggunakan istilah farmer sebab farmer mengarah pada warga yang melakukan kegiatan pertanian sebagai sebuah usaha bisnis (kapitalis) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya (Mosher, 1966). Wolf (1993) melukiskan kehidupan petani dari waktu ke waktu adalah menyeimbangkan tuntutan-tuntutan dari luar dan kebutuhan petani untuk menghidupi keluarganya. Terdapat dua langkah yang ditempuh yakni memperbesar produksi dan mengurangi konsumsi. Langkah pertama, ditempuh dengan meningkatkan hasil kerja di atas tanahnya untuk menaikkan produksi dan memperbesar jumlah hasil bumi yang akan dijual di pasar. Maka itu, petani harus 15 mengerahkan faktor-faktor produksi yang diperlukan seperti tanah, tenaga kerja, modal, bibit, pupuk, dan pemahaman tentang pasar. Langkah kedua, berupa mengurangi konsumsi. Maka petani harus mengurangi masukan kalorinya dan jenis-jenis barang makanan yang paling pokok saja, sehingga mampu menekan belanja di pasar sampai pada beberapa jenis barang esensial saja. Sebagai gantinya, petani mengerahkan anggota-anggota keluarganya sendiri untuk menghasilkan bahan makanan yang diperlukan di lingkungan rumah dan sawah ladangnya. Pada saat yang sama petani mendukung usaha mempertahankan hubungan sosial tradisional dan pengeluaran dana seremonial yang diperlukan untuk menopang hubungan-hubungan tersebut. Dalam pemenuhan surplus-surplus sosial, Wolf berpendapat, petani mempunyai dua perangkat imperatif sosial, yakni dana seremonial dan dana sewa tanah. Dana seremonial, seperti di masyarakat pada umumnya, selain pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan primer. Mereka juga harus menyelenggarakan hubungan-hubungan sosial di antar sesamanya. Misalnya, dalam hal mencarikan jodoh untuk kerabat, menjaga ketertiban, dan saling membantu memenuhi kebutuhan dasar (primer) sesamanya. Dalam sebuah hubungan sosial tidak pernah semata-mata karena bermanfaat dan dianggap sebagai alat belaka. Tetapi setiap hubungan sosial selalu dikelilingi konstruksi-konstruksi simbolik yang menjelaskan, membenarkan dan mengaturnya. Semua hubungan sosial tidak terlepas dari adanya upacara atau seremoni yang harus dibayar dengan kerja, barang maupun uang. Sebuah dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran 16 upacara sosial disebut dana seremonial (Ceremonial Fund). Besar kecilnya dana seremonial suatu masyarakat itu sangat relative. Dana sewa tanah, di masyarakat yang kompleks terdapat hubunganhubungan sosial yang tidak simetris, dalam bentuk penyelengaraan kekuasaan. Dimana seseorang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dan efektif (domain) atas petani. Sehingga petani mengalami beban permanen atas produksinya. Dana sewa tanah adalah dana yang harus dikeluarkan petani – baik dengan bekerja, hasil tanaman, atau uang - untuk membiayai beban permanen produksinya, sebagai akibat adanya hak yang lebih tinggi atas pekerjaanya. Kerugian petani merupakan keuntungan bagi pemegang kekuasaan, oleh karena dana sewa tanah yang disediakan petani adalah bagian dari dana kekuasaan yang dapat digunakan pemegang kekuasaan. Dengan demikian eksistensi kaum tani tidak sekedar hubungan antar petani dan bukan petani, melainkan suatu tipe penyesuaian (adaptasi) terhadap komunikasi sikap-sikap dan semua kegiatan yang bertujuan untuk menopang petani bertahan diri bersama sesamanya di dalam satu tatanan sosial dari ancaman keberlangsungan hidup mereka. Dalam berhubungan sosial kemasyarakatan petani membutuhkan suatu kerukunan untuk mencapai apa yang diinginkan. Hildred Geertz (1961) menyatakan ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah-kaidah yang dimaksud, pertama adalah kaidah yang mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri 17 hendaknya adalah menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukan mereka. Franz Magnis-Suseno (1984) menamakan kedua kaidah tersebut dengan sebutan prinsip kerukunan untuk kaidah pertama dan sebutan prinsip hormat untuk kaidah yang kedua. Prinsip rukun disampaikan Mulder dalam Frans Magnis-Suseno (1984) bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan semacam itu disebut rukun. Rukun berarti ‘berada dalam keadaan selaras’, ‘ tenang dan tentram’, ‘tanpa perselisihan dan pertentangan’, ‘bersatu dalam maksud untuk saling membantu’.. Menurut Frans Magnis-Suseno (1984) terdapat dua segi dalam tuntutan kerukunan. Pertama, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu. Kedua, prinsip kerukunan pertama-tama tidak menyangkut suatu sikap batin atau keadaan jiwa, melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara. Yang perlu dicegah ialah konflik-konflik yang terbuka. Manifestasi dari prinsip rukun adalah diterapkannya konsep-konsep musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong, serta berusaha memperlakukan orang lain sebagai anggota keluarga sendiri. 18 Dalam kehidupan sehari-hari penerapan prinsip rukun tidak jarang menimbulkan perilaku berkata “inggih” meski tidak setuju dengan pernyataan,tawaran ataupun permintaan orang lain. Selain itu juga prinsip rukun sering menimbulkan sikap berpura-pura atau “ethok-ethok” untuk menghindari kekecewaan pihak lain atau untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya yang tidak perlu diperlihatkan kepada pihak lain di luar lingkungan keluarga inti sedemikian rupa jika tidak disembunyikan dikhawatirkan bisa menimbulkan ketidak-rukunan dengan pihak lain tersebut (Franz Magnis-Suseno, 1984). Jadi prinsip kerukunan tidak berarti bahwa orang Jawa tidak mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi, melainkan merupakan suatu mekanisme sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan itu demi kesejahteraan kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Clifford Geertz dalam Franz Magnis-Suseno (1984) mengatakan rukun, sebagai suatu nilai, tidak mengikat orang-orang komunis primitif yang diasosiasikan secara berlebihlebihan, tetapi mengikat petani-petani materialis yang agak merasa diri cukup dengan pengetahuan yang jelas mengenai dimana adanya kepentingan mereka (Franz Magnis-Suseno, 1984). Salah satu kegiatan yang mencerminkan usaha pencapaian kerukunan di masyarakat petani adalah digelarnya slametan yang juga sekaligus sebagai salah satu pengeluaran dana seremonial (Ceremonial Fund). Slametan menjadi pusat dari kehidupan masyarakat Islam Jawa. Di samping itu, slametan merupakan ritual yang unik serta di dalamnya terdapat unsur-unsur mistik. Geertz yang membagi struktur agama Jawa menjadi tiga varian (trikotomi), yakni abangan, santri, 19 dan priyayi, pada tulisan The Religion Of Jawa, menyampaikan selamatan banyak dilakukan oleh varian abangan. Bagi Geertz, “selamatan” merupakan upacara yang utama dalam kehidupan petani Jawa yang terdiri atas suatu upacara makan makanan suci bersama, dapat diadakan dengan cara sederhana ataupun dengan sangat luas (Koentjaraningrat, 1984). Selamatan-selamatan yang memiliki bentuk dan isi dengan hanya sedikit variasi pada segala kesempatan yang memiliki makna religius — pada titik peralihan daur hidup, pada hari-hari suci menurut penanggalan, pada tahap-tahap tertentu daur panen, dimaksudkan baik pada untuk waktu memberi pindah rumah, persembahan dan bagi seterusnya — roh-roh maupun mekanisme-mekanisme bersama bagi keutuhan hidup bersama. (Geertz, 2002). Menurut Clifford Geertz, selamatan terbagi dalam empat jenis, pertama, berkisar sekitar krisi kehidupan seperti: kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Kedua, berhubungan dengan hari-hari besar Islam seperti: Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Ketiga, berhubungan dengan integrasi sosial desa, misalnya: bersih dusun (pembersihan desa dari roh jahat). Keempat, selamatan yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak tetap, tergantung kejadian luar biasa yang dialami seseorang, seperti: keberangkatan untuk perjalanan jauh, pindah tempat, ganti nama, sakit, terkena tenung dan sebagainya (Geertz, 1989), Selamatan berimplikasi pada tingkah laku sosial dan memunculkan keseimbangan emosional individu karena telah dislameti. (Geertz, 1989). 20 Hubungan sosial kemasyarakatan petani tidaklah selalu mulus, akan timbul pertentangan-pertentangan apalagi jika ada ketidaksesuaian tujuan antara dirinya dengan pihak lain. Pertentangan ini akan diekspresikan dengan perlawanan (resistensi). James C.Scott (1993) menjelaskan resistensi bagi petani adalah setiap tindakan petani yang dimaksudkan untuk melunakkan atau menolak tuntutan seperti membayar pajak, sewa dan penghormatan, yang dilakukan oleh atasan-atasannya seperti tuan tanah, negara, pemberi pinjaman, atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri seperti pekerjaan dan penghargaan bagi petani. Peran negara yang semakin meluas dalam proses transformasi perdesaan menurut Scott mengakibatkan: (1) perubahan hubungan antara petani lapisan kaya dan lapisan miskin, (2) munculnya realitas kaum miskin untuk membentuk kesadaran melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang merupakan pembelotan kultural, dan (3) terbangunnya senjata gerakan perlawanan menghadapi kaum kaya maupun negara. Scott (1981) menjelaskan mengenai alasan petani marah disebabkan pembebanan atau tuntutan baru yang secara tiba-tiba merugikan banyak orang sekaligus dan melanggar aturan serta adat istiadat yang diterima. Hal ini dapat membangkitkan solidaritas pemberontakan atau revolusi di setiap jenis masyarakat petani karena tidak ada satu pun tipe masyarakat petani yang kebal terhadap pemberontakan atau revolusi. Meskipun demikian, ada variasi dalam potensi eksplosif yang dapat dihubungkan dengan tipe-tipe masyarakat petani (Geidy dan Rilus, 2011). 21 Popkin (1979) menyatakan gerakan perlawanan petani lebih karena faktor determinan individu, bukan kelompok. Setiap manusia ingin menjadi kaya. Biang keladi atas terjadinya perlawanan para petani tradisional datang dari penetrasi kapitalisme ke kawasan perdesaan yang dalam banyak kasus melahirkan eksploitasi terhadap para petani oleh para tuan tanah, oleh Negara dan kaum kapitalis. Gurr (1970) dalam Mustain (2007) juga memandang faktor frustasi dan pengurangan hak relatif yang terjadi dalam masyarakat petani dengan pihak lain menjadi pendorong bagi petani melakukan perlawanan. Kornhouser (1959) dalam Mustain (2007) memandang faktor keterasingan dan anomi yang dialami warga petani oleh karena mereka justru semakin miskin dan terpinggirkan. Popkin tidaklah (1979) dimaksudkan menyebutkan untuk bahwa menentang semua perlawanan petani program negara tapi lebih dimaksudkan untuk menentang kekuasaan elite desa (petani kaya) yang selama ini mengklaim komunitas tradisional, padahal lebih untuk mempertahankan tatanan demi keuntungan mereka. Model gerakan perlawanan petani di Asia disampaikan James C. Scott (1981) merupakan gerakan petani miskin yang lemah dengan organisasi yang anonim, bersifat nonformal melalui koordinasi asal sama tahu saja, dengan bentuk perlawanan kecil dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, mencuri, memperlambat kerja, berpura-pura sakit dan bodoh, mengumpat dan sejenisnya. Hal ini sangat sesuai 22 dengan karakteristik petani yang lemah karena tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan. Scott (1993) menjelaskan perbedaan antara perlawanan “sungguhsungguh” dengan perlawanan yang bersifat “insidental”. Perlawanan “insidental” ditandai oleh: (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan dan pamrih, (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) dalam maksud dan logika mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominan yang ada. Sebaliknya perlawanan “sungguh-sunguh” ditandai dengan: (a) lebih teroganisasi, sistematis, dan kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi. Scott juga mengatakan bahwa apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dapat dilihat sebagai perlawanan seperti aksi mencuri hasil panen jika hal tersebut sesuai dengan tujuan definisi perlawanan. Perlawanan petani juga tidak harus dalam bentuk aksi bersama. Dalam kata lain gerakan resistesi ini ditempuh dua cara, pertama resistensi aktif atau public transcript berupa perlawanan secara terbuka yang dilakukan secara terorganisir dan tersistematis. Kedua resistensi pasif atau hidden transcript yang seringkali terwujud dalam bentuk perlawanan dengan berpura-pura setuju terhadap tuan tanah atau penguasa, fitnah, sikap acuh, menolak membayar sewa dan kerja paksa atau pun tidak menghormati penguasa. Menurut Scott prinsip mendahulukan keselamatan menjadi sumber kekuatan moral yang 23 memungkinkan para petani untuk menolak perubahan dan siap melakukan perlawanan bila dihadapkan pada kenyataan yang tidak berpihak pada mereka. 1.7. Kerangka Pemikiran Penelitian Kerangka pemikiran dalam penelitian resistensi petani terhadap penjualan dan persewaan lahan kepada warga luar desa yang mengambil studi kasus di Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang bahwa tanah selain sebagai sumberdaya produksi, suatu habitat, atau batas politik juga memiliki makna sebagai merupakan basis bagi organisasi sosial, sistem ekonomi, dan identifikasi kultural masyarakat, sehingga harus dipertahankan. Penguasaan lahan pada orang luar desa dianggap akan merusak harmonisasi tradisi kultural yang telah ada dan berlaku. Langkah yang dilakukan petani adalah dengan memperkuat basis ekonomi keluarga dengan memperbesar produksi dan mengurangi konsumsi. Dalam penguatan sosial, mereka melakukan hubungan-hubungan sosial tradisional dengan mengeluarkan dana sosial dan dana sewa tanah. Pengeluaran dana sosial, diantaranya dengan gelaran aneka ritual selametan. Ritual juga sebagai pengikat berbagi diantara petani, sehingga semua warga sekitar turut merasakan apa yang dirasakan yang punya hajat. Keinginan petani adalah terciptanya kerukunan pada masyarakat yang dengan kerukunan itu akan dapat melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun tersembunyi pada masyarakat luar desa yang berusaha untuk menguasai tanah. Selain pula 24 penguasaan tanah oleh warga luar desa dikhawatirkan mengganggu kerukunan yang ada. Ada dua dampak yang kemungkinan terjadi dari strategi yang diterapkan petani yakni berhasil atau gagal. Berhasil disini adalah warga dapat memproteksi lahan dari penguasaan warga luar desa, baik berupa terjualnya tanah, penyewaan, gadai, hibah dan pewarisan. Sedangkan kegagalan adalah warga luar desa dapat menguasai lahan melalui pembelian, penyewaan, gadai hibah dan pewarisan. 25 Gambar 3 , kerangka berpikir penelitian Penjualan dan penyewaan tanah pada warga luar desa Ganggu Ekonomi, Kultural Masyarakat dan Kerukunan Langkah Petani Perkuat basis Ekonomi - Memperbesar produksi - Mengurangi konsumsi Penguatan Petani Penguatan Sosial Tradisional - Mengeluarkan dana sosial - Mengeluarkan dana sewa tanah Sifat Perlawanan: Public transcript (Sungguhsungguh) dan Hidden transcript (insidentil) Kerukunan Strategi perjuangan Bentuk : Aksi massa, sendiri, adat istiadat, jalur hukum, Petani berhasil proteksi lahan di desa dari penguasan warga luar desa. ( Hak milik, Sewa, Gadai, Hibah, Pewarisan ) Keterangan : Pengaruh Komponen Rangkaian Aktivitas Petani gagal proteksi lahan di desa dari penguasaan warga luar desa. ( Hak milik, Sewa, Gadai, Hibah, Pewarisan ) 26 1.8.Metode Penelitian 1.8.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Desa tersebut terdiri dari sebelas dusun. Lokasi ini menarik diteliti sebab sabagai salah satu daerah penghasil beras bermutu dan lokasinya dekat dengan Kota Magelang yang merupakan daerah kota yang tengah berkembang. Di desa tersebut terdapat warga yang memiliki lahan luas dan pendapatan besar, tetapi disatu sisi ada warga yang hidup sebagai buruh tani karena tidak punya lahan atau lahan sawah yang dimilikinya sempit. Warga harus dihadapkan realitas bahwa bertani dengan lahan sempit tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup yang semakin membengkak. Maka itu petani berusaha untuk memperluas penguasaan lahannya agar hasilnya memenuhi kebutuhan hidup, langkahnya dengan membeli, menyewa, mendapatkan waris lahan dan hibah lahan. Petani juga berusaha mengeksploitasi diri dengan bekerja di luar pertanian. Namun, letak desa yang tidak jauh dari perkotaan, menjadikan warga luar desa khususnya warga kota berjuang untuk mendapatkan lahan, yang akan dijadikannya sebagai perumahan dan tempat usaha. Di sisi lain ada upaya dari warga desa yang ingin mengalihfungsikan lahan yang dimiliki menjadi rumah atau dari pertanian ke non pertanian. 27 Dalam penelitian ini penulis mengambil rentang waktu dalam 30 tahun terakhir. Rentang tersebut terdapat jual beli, persewaan, pewarisan dari orang tua pada anaknya. Serta hibah dari seorang pada orang lain. 1.8.2. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai sesuatu dengan cara yang jelas serta mencermati berbagai peristiwa melalui fakta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis berusaha menggambarkan secara terperinci realita kehidupan masyarakat di daerah penelitian, sehingga dapat tergambar sikap dan perilaku dalam keseharian. Peneliti mula-mula akan mencari data tentang gambaran kepemilikan lahan, transaksi terkait dengan tanah dan pengalihan kepemilikan tanah. Dari data itu akan dicari pendalaman informasi dengan wawancara dengan mereka yang terlibat, atau yang menentang dalam transaksi. Dari hal diatas akan diketahui pola transaksi jual beli dan sewa menyewa tanah dan bagaimana masyarakat desa bersikap resisten pada penjualan dan penyewaan tanah di desa baik yang masih dalam satu desa mapun dengan warga luar desa. Selain itu juga tergambar konflik-konflik penanganannya. yang terjadi ada bagaimana upaya dalam 28 1.8.3. Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, banyak peristiwa unik yang dapat diamati maupun digali. Untuk itu data maupun informasi digali melalui wawancara mendalam (indepth interview) secara interatif yang dilakukan sealamiah mungkin serta pengamatan secara terlibat (participant observation) untuk mendapatkan informasi permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendalam. Wawancara secara mendalam antara lain dilakukan pada mantan kepala desa, kepala desa berikut perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan beberapa warga masyarakat pemilik lahan, serta makelar tanah untuk menggali informasi terkait dengan kepemilikan lahan, pengamatan dan pengalaman dalam menjual, membeli, menyewa, mewariskan dan menghibahkan tanah. Data dalam penelitian ini juga didapat dari data sekunder yakni dari dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Dokumen yang dimaksud seperti buku tanah atau ‘Letter C’ desa, laporan hasil pembangunan desa, data BPS, dan hasil penelitian atau catatan-catatan terkait yang relevan.