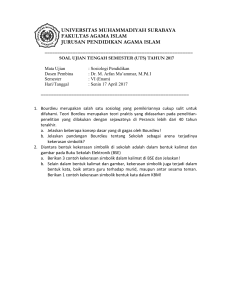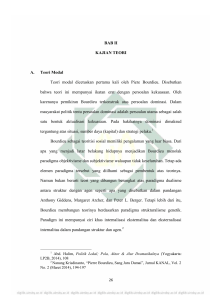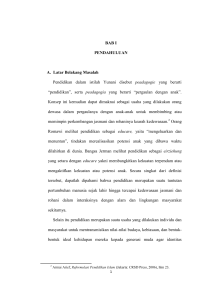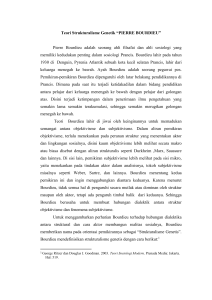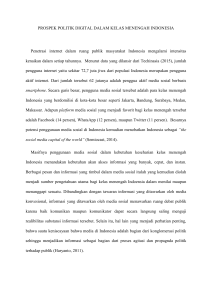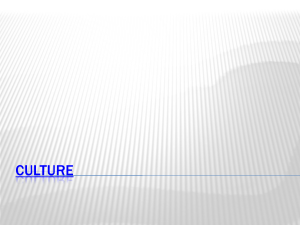Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Studi ini dipicu
advertisement

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Studi ini dipicu oleh menggejalanya politik klan yang terlihat dari tampilnya kekuatan Klan Qahhar Mudzakkar dalam pentas politik di Sulawesi Selatan. Nama Qahhar Mudzakkar yang dalam wacana politik nasional diidentikkan dengan pemberontak (DI/TII), terbukti memiliki kekuatan politik yang signifikan bagi keturunannya untuk berkompetisi menduduki jabatan politik di Sulawesi Selatan. Kajian ini mencoba untuk melihat bagaimana pola relasi kuasa dalam politik klan terkait dengan sumber daya yang mereka gunakan dan implikasinya terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Dengan menguraikan hadirnya politik klan khususnya di tingkat lokal, studi ini memberikan update bagi pemahaman fenomena politik lokal dalam demokrasi yang berkembang pasca reformasi di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi telah membuka peluang bagi perubahan dinamika politik lokal di berbagai daerah. Kajian politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa transisi konstitusional tersebut telah melahirkan dominasi kekuasaan. Hampir di semua daerah mengindikasikan hal tersebut, sehingga dengan mudah akan kita temukan adanya orang kuat lokal maupun kembalinya entitas politik masa lalu yang mendominasi kekuasaan (Dwipayana, 2004; Hadiz, 2005; Nordholt, 2007; Palmer, 2010; dan Luthfillah, 2012). Dalam dinamika ini, para aktor politik di tingkat lokal menjalankan mobilisasi politik berdasarkan identitas (misalnya: klan, suku, agama dan bahasa) dan jaringan (misalnya birokrat dan pengusaha), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kandidat dengan jejaring personal (personal network) terkuat yang akan memenangkan pemilihan (Supriatma, 2009; Buehler, 2009). Seperti misalnya oligarki politik di Sumatera Utara, keluarga politik Chasan Sochib di Provinsi Banten, di Sulawesi Selatan dengan keluarga Yasin Limpo dan Qahhar Mudzakkar, atau revivalitas bangsawan (misalnya keraton dan karaeng), serta transformasi GAM di Aceh. Selain itu, masih banyak lagi di provinsi dan kabupaten/kota lain di Nusantara. Bab I: Pendahuluan Fenomena munculnya sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia dipahami sebagai hasil kombinasi tekanan politik sentripugal (sentralisasi) pada masa Suharto dan tekanan politik sentripetal (desentralisasi) pasca Suharto (Nordholt, 2005). Meskipun di awal-awal pelembagaan desentralisasi pola ini belum terlihat, akan tetapi memasuki dekade kedua pasca reformasi, kecenderungan pada semakin oligarkisnya kekuasaan politik lokal semakin terlihat nyata. Berbagai kesimpulan pun telah diajukan, bahwa transisi konstitusional ini bukanlah demokrasi (Robison & Hadiz, 2004). Kehadiran keluarga misalnya, Thomas Meyer (2002: 50) menyebutkan bahwa kelompok kekuasaan berdasarkan keturunan adalah salah satu musuh demokrasi yang dapat menimbulkan ancaman struktural terhadap demokrasi. Budaya ataupun struktur sosial masyarakat adalah pemicu dalam konteks ini. Pada akhirnya, terkait dengan proses demokratisasi di Indonesia, kini para ilmuwan politik menemukan kritik telak terhadap demokrasi Schumpeterian, yang tidak melihat faktor budaya dan segmentasi masyarakat sebagai sumber legitimasi politik. Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (1990) sebetulnya sudah menjelaskan bekerjanya kekuatan “budaya” – misalnya kekerasan, patronase termasuk kekerabatan – yang menghasilkan demokrasi semu (pseudo democracy). Dalam logika tersebut, keberadaan lembaga politik demokrasi secara formal mengakibatkan dominasi kekuasaan menjadi tidak kasat mata (Dwipayana, 2004: 6, 154).1 Akan tetapi, desakan globalisasi dan dukungan modernisasi saat ini telah “memaksa” banyak negara mendemokratisasikan dirinya. David Held (2007) menguraikan bahwa walaupun saat ini banyak negara menganut paham demokrasi, tetapi sejarah politiknya mengungkapkan adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Dengan melihat sejarah Eropa pada abad ke-20, demokrasi merupakan sebuah sistem yang sulit untuk diwujudkan dan dijaga (Dahl, 2001: 197). Kesimpulannya, demokrasi dalam perjalanan sejarahnya membentuk berbagai macam varian-varian transisi yang berbeda. Mengutip istilah Huntington (1990), 1 “Juan Linz, Seymour Martin Lipset, and I term these regimes pseudo-democracies, because the existence of formally democratic political institutions, such as multiparty electoral competition, masks (often in part to legitimate) the reality of authoritarian domination.” Lihat Larry Diamond (2003), “Defining and Developing Democracy” dalam R. Dahl, I. Shapiro & J. A. Cheibub (eds) The Democracy Sourcebook, Cambridge: The MIT Press, halaman 37. 2 Bab I: Pendahuluan demokrasi dalam kaitannya dengan budaya di berbagai negara adalah sebuah clash of civilization. Pada akhirnya, perdebatan ilmiah mengenai demokrasi demikian berlanjut, dan dengan jawaban berbeda. Seymour Martin Lipset (1950), menghubungkan demokrasi yang stabil dengan kondisi latar belakang ekonomi dan sosial tertentu, seperti pendapatan per kapita yang tinggi. Almond dan Verba (1989) mengatakan sistem politik yang demokratis menuntut adanya keserasian budaya politik, misalnya sikap kewargaan. Robert A. Dahl (2001) berpendapat bahwa stabilitas demokrasi memerlukan komitmen untuk aturan lembaga demokrasi, bukan di masyarakat (pemilih), tetapi di antara elit politik profesional sebagai representasi politik melalui ikatan politik yang efektif, yang sering dia sebut sebagai poliarchy. Begitu halnya Guillermo O‟Donnell, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead (1993) yang cenderung pada pendekatan agensi, dimana demokrasi sangat tergantung pada peran dan kepentingan elit politik. Akhirnya, Aurel Croissant (2004), merangkum keseluruhan jawaban-jawaban tersebut melalui kesimpulannya tentang demokrasi di Asia, dimana stabilitas demokrasi dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi; budaya politik dan sejarah kolonial; kenegaraan dan pembangunan bangsa; dan lembaga-lembaga politik. Debat ilmiah ini memang berkelindan dengan kondisi praktik demokrasi negara-negara global south seperti Indonesia, yang seringkali disebut sebagai transisi demokrasi. Dalam konteks transisi demokrasi, kecenderungan para pengkaji politik saat ini memahami praktik dominasi dalam demokrasi, lebih pada perspektif aktor. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa aktor politik adalah penentu dari lahirnya dominasi. Gagasan ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah “kegagalan” praktik demokrasi, sejatinya disebabkan oleh aktor? Agensi dianggap sosok yang memiliki kekuatan “super” yang bisa merubah – menentukan pembukaan kesempatan ataupun sebaliknya – bagi praktik demokrasi (O‟Donnell et.al, 1993). Untuk itu, perlunya kita memikirkan kembali bahwa terdapat sisi lain yang juga memberi peluang kuatnya praktik dominasi dalam demokrasi. Ataupun memungkinkan bagi kita untuk sampai pada kesimpulan besar bahwa dalam konteks tertentu kedua hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perkembangan demokrasi. 3 Bab I: Pendahuluan Di Indonesia, kasus-kasus pasca reformasi menjadi sebuah “laboratorium” untuk teori demokrasi. Berbagai kesimpulan pun telah diajukan oleh ilmuwan politik dalam mengkaji demokrasi di Indonesia. Sebagian menyebutnya sebagai masa transisi demokrasi atau konsolidasi demokrasi, dan sebagian yang lain menolak pendapat tersebut. Defective Democracy, Deficit Democracy, Politicizing Democracy, Changing Continuities, dan Patronage-Based Democracy adalah sebagian dari berbagai gagasan untuk menjelaskan praktik demokrasi di Indonesia, baik dalam ranah nasional dan lokal (Croissant, 2004; Priyono et.al., 2007; Harris, et.al., 2005; Nordholt, 2005, 2007; Palmer, 2010). Untuk itulah, sampai saat ini kasus menguatnya oligarki politik dekade kedua reformasi khususnya dalam politik lokal, memberikan banyak pertanyaan bagi para peneliti untuk menjawab pengaruhnya terhadap perkembangan masa depan demokrasi Indonesia. Ketika ditelisik lebih jauh tentang studi politik lokal yang ada dalam domain modalitas politik, secara teoritis para keluarga/kerabat/kelompok politik menggunakan berbagai modal sebagai basis legitimasi kekuasaan. Pada umumnya, dari sekian banyak kesimpulan tersebut, mayoritas studi-studi di Indonesia lebih melihat pada pasca keberhasilan mereka (baca: oligarki) dan proses-proses tata kelola politik pemerintahan yang mereka lakukan – kepiawaian mengelola modal politik – sebagai pejabat, pengusaha, ataupun bangsawan (Dwipayana, 2004; Hidayat, 2007; Haboddin, 2010; Lutfillah 2012). Berangkat dari fenomena ini yang kemudian melatarbelakangi studi tentang Klan Qahhar Mudzakkar. Saya mencoba untuk melihat lebih kedepan lagi pada pertanyaan mengapa dan bagaimana mereka hadir? Selain itu, terdapat karekteristik yang berbeda dari kasus yang diteliti dalam studi ini dengan studi-studi yang telah dihasilkan, terkait bahwa hadirnya Klan Qahhar Mudzakkar yang menduduki jabatan politik di tingkat pusat dan daerah, bukan dari golongan bangsawan, pejabat, ataupun memiliki basis ekonomi yang kuat (pengusaha). Realita inilah yang menarik untuk diteliti, apa sumber daya yang menjadi modal politik klan tersebut dan bagaimana modal tersebut bekerja. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menemukan perspektif lain dalam memahami fenomena hadirnya oligarki politik di Indonesia. 4 Bab I: Pendahuluan B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana relasi hadirnya politik klan dengan demokrasi dalam kasus Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan pasca reformasi?” Adapun pertanyaan turunan adalah: 1. Apa sumber daya yang dimiliki oleh Klan Qahhar Mudzakkar? 2. Bagaimana sumber daya tersebut mereproduksi kekuasaan? 3. Bagaimana implikasi dari kehadiran mereka terhadap masa depan demokrasi Indonesia? Penelitian ini mengajukan beberapa misi utama. Pertama, menjelaskan kekuatan keluarga yang memperoleh kekuasaan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan. Kedua, menguraikan perkembangan karakteristik terbaru dalam politik lokal di Indonesia, terkait dengan reproduksi kekuasaan. Terakhir, sebagai perspektif lain dalam melihat demokasi dan masa depannya di Indonesia. C. Tinjauan Pustaka: Karakteristik Politik Lokal Terkait dengan karakteristik politik lokal di Indonesia, berikut ini akan diuraikan beberapa studi tentang hal tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan posisi tulisan ini dengan studi-studi sebelumnya. Selain itu dimaksudkan untuk melihat letak perbedaan dari karakteristik kekuasaan tersebut. Dari hasil penelusuran saya, setidaknya ada beberapa karya ilmiah akademis yang menyinggung secara langsung mengenai praktik politik lokal di beberapa didaerah pasca reformasi. Akan tetapi, sebelumnya marilah kita sedikit melihat kebelakang tentang studi dari John T. Sidel (2005) mengenai orang kuat lokal di Indonesia yang dia sebut dengan Bossism atau bos lokal. Dalam studi Sidel, secara umum bos lokal adalah local power broker yang memperoleh posisi monopoli terhadap kekerasan dan sumber daya ekonomi dalam wilayahnya masing-masing seperti: penguasaan atas kontrak infrastruktur, kontrak pertambangan atau penebangan kayu, perusahaan transportasi, aktifitas ekonomi ilegal termasuk diantaranya kemampuan untuk memobilisasi suara, dan vote buying. Konsep boss berbeda dari patron karena tingkat monopoli diperoleh melalui koersif sebagai pilar utama dan disisi lain otoritas bos tidak bergantung pada afeksi dan 5 Bab I: Pendahuluan status, melainkan atas dasar hasrat untuk bertindak. Sidel menyebut demokrasi di Indonesia merupakan mafia lokal, jaringan dan marga atau klan (2005: 85). Walaupun studi ini dilakukan pada tahun 2004, sebelum adanya liberalisasi politik di Indonesia dengan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung.2 Namun, satu hal yang menjadi ketepatan argumen Sidel bahwa dalam konteks Indonesia, dinasti politik atau orang kuat lokal diperkirakan akan muncul bersamaan dengan pemilihan langsung. Di lain hal yang menjadi kekurangan, seperti patrimonialisme yang kurang mendapatkan perhatian serius dalam analisa Sidel mengenai Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa dinasti dan oligarki politik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai patrimonial, telah terjadi di beberapa daerah (Nordholt dan van Klinken: 2007). Satu hal yang menjadi ide utama dalam studi Sidel adalah adanya liberalisasi politik (demokrasi) di Indonesia dengan pelaksanaan pemilihan umum lokal secara langsung, berkorelasi dengan hadirnya praktik politik: mafia, jaringan dan kekerabatan di tingkat lokal. Studi kedua mengenai politik lokal ditulis oleh Syarif Hidayat (2007). Dalam studi Syarif Hidayat yang berjudul “Shadow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten”, secara umum tulisan ini menjelaskan bagaimana praktik oligarki melalui pendekatan ekonomi politik. Bagaimana bekerjanya sektor informal dalam mempengaruhi proses politik dan pemerintahan dalam hal ini diperankan oleh kelompok Jawara yang di motori oleh TB.Chasan Sochib. Selain itu, monopoli terhadap kekerasan dan sumber daya ekonomi seperti penguasaan atas kontrak infrastruktur (premanisme proyek) merupakan cara-cara yang digunakan dalam langkah awal menjalankan dominasi politik di provinsi Banten. Kekurangan tulisan ini adalah tidak menjelaskan bagaimana kemudian keluarga Chasan Sochib membangun dinasti politik dengan menempatkan kerabatnya sebagai elit politik di beberapa daerah di provinsi tersebut. Informasi penting yang yang bisa dijadikan referensi adalah modal yang digunakan dan pola-pola reproduksi kekuasaan yang dilakukan melalui basis ekonomi dan kekerasan. Studi yang lebih spesifik tentang keluarga politik di provinsi Banten ditulis oleh Kiki Luthfillah (2012) dalam studinya “Demokrasi dan Kekuasaan dalam Politik Lokal: Dominasi Kekuasaan Keluarga TB. Chasan Sochib di Provinsi Banten 2 Diterbitkan pertama kali dalam buku dengan editor John Harriss, Kristian Stokke and Olle Törnquist (2004), “Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation”, Palgrave Macmillan. 6 Bab I: Pendahuluan pasca Reformasi.” Studi ini menjelaskan bagaimana dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh Chasan Sochib dengan menempatkan jaringan keluarganya pada jabatan politik dan pemerintahan. Secara kronologis studi ini menguraikan bagaimana kemudian keluarga Chasan Sochib menciptakan jaringan kekuasaan di provinsi Banten. Sejalan dengan tulisan Syarif Hidayat, studi ini banyak melihat dari perspektif ekonomi politik sebagai modal (sumberdaya) kekuasaan. Mengenai demokrasi, studi ini menyimpulkan bahwa di era demokratisasi, dominasi kekuasaan tersebut justru semakin kuat dan meluas. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kontrol publik terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Kesimpulannya adalah institusi yang lemah mengakibatkan aktor dapat leluasa mendominasi kekuasaan. Selanjutnya, studi dari Michael Buehler (2007) “Rise of the Clans: Direct Elections in South Sulawesi”, yang nampaknya merupakan kajian yang lebih dekat untuk menggambarkan politik kekerabatan di Sulawesi Selatan. Buehler menulis tentang kebangkitan dari keluarga Yasin Limpo melalui pendekatan aktor. Dengan metode etnografi, Buehler menguraikan bagaimana sistem dari negara dalam kaitannya dengan pemilihan umum, birokrasi, dan institusionalisasi partai mampu dimanipulasi oleh agen. Walaupun dalam tulisan Buehler menggunakankan kata “clans”, akan tetapi, keluarga Yasin Limpo lebih tepat disebut sebagai dinasti karena kekuasaan itu sudah ada sebelum desentralisasi politik tahun 2004. Selain itu kajian yang luput dari studi ini adalah institusi yang tidak dilihat dalam mempengaruhi aktor untuk menciptakan dominasi kekuasaan dan terkait juga dengan modal yang menjadi basis kuatnya jaringan dinasti Yasin Limpo sejak orde baru. Gagasan utama yang dapat disimpulkan mengenai sumber daya kekuasaan adalah berupa jaringan birokrasi, partai, premanisme, dan uang sebagai modal untuk mereproduksi kekuasaan. Studi ini menyimpulkan bahwa demokrasi dan desentralisasi mengakibatkan tidak ada “orang baru” yang memiliki kesempatan nyata untuk memenangkan pemilihan langsung di Sulawesi Selatan. Gagasannya tentang praktik demokrasi adalah “Old Elite, New Competition” yang menegaskan tesis Henk Schulte Nordholt tentang Changing Continuities. Masih berkaitan dengan Sulawesi Selatan, studi dari Muhtar Haboddin (2010) tentang “Karaeng dalam Pusaran Politik: Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan” adalah salah satu dari studi hadirnya bangsawan dalam institusi 7 Bab I: Pendahuluan politik lokal. Melalui pendekatan local strongmen, argumen utama yang ingin disampaikan dalam studi ini adalah dominasi bangsawan (dinasti politik) terjadi ketika desentralisasi dan liberalisasi politik yang berimplikasi pada aktor-aktor politik lokal. Studi ini juga mulai menyinggung modal kultural/budaya yang menjadi basis lahirnya kekuasaan yakni hubungan patron-klien, akan tetapi masih dalam perspektik ekonomi. Dalam konteks demokratisasi, studi ini menolak pandangan dominan bahwa demokratisasi dan desentralisasi telah membangkitkan sentimen primordial. Baginya keberhasilan aristokrat dalam menguasai institusi-institusi politik modern mestinya dibaca sebagai sebuah kreasi yang paling jitu dalam upaya menghadirkan agensi dalam kancah politik dan kenegaraan. Selain Haboddin, studi tentang kekuasaan bangsawan ditulis oleh Ari Dwipayana (2004) yang menjelaskan kembalinya para bangsawan di Surakarta dan Denpasar. Melalui pendekatan komparatif ruang dan waktu, studi ini menjabarkan bagaimana genealogi kekuasaan para bangsawan sejak masa kolonial, revolusi kemerdekaan, orde lama, dan orde baru serta tindakan survivalitas para bangsawan menghadapi masa transisi demokrasi. Dengan basis ekonomi, kultural, dan partai politik, para bangsawan di dua kota tersebut berhasil mereposisi kedudukan politiknya sebagai bentuk revivalitas di era demokratisasi. Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa kekuasaan tersebut menimbulkan kemungkinan “abuse of power”. Hadirnya para aristokrat pasca reformasi dengan kekuatan ekonomi, politik, kenegaraan (birokrasi) dan kultural yang digenggam dalam satu tangan dapat menjadi musibah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia atau dalam istilah Dwipayana, “aristokratisasi demokrasi”. Mencermati beberapa pustaka di atas, penelitian ini merupakan kajian terbaru yang akan fokus pada masyarakat untuk melihat bagaimana klan dapat hadir dalam politik lokal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih cenderung fokus pada pendekatan aktor. Lokus penelitian dalam studi ini digunakan untuk mempelajari bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam struktur sosial politik membentuk perilaku individu, dan bagaimana institusi informal atau budaya dipandang sebagai sistem aturan dan desakan yang didalamnya individu berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka. Pendekatan dalam studi ini menggunakan paparan deduktif yang berawal 8 Bab I: Pendahuluan dari dalil-dalil teoritis tentang cara institusi bekerja (institusionalis baru) (Mars dan Stoker, 2011: 113). Mungkin sebaiknya studi ini dipandang kurang lebih sebagai studi yang melengkapi fenomena kontemporer tentang demokrasi lokal. Studi ini juga bertujuan untuk menambah khasanah politik lokal di Indonesia yang selama ini dikenal dengan istilah bossisme, local strongmen, dan dinasti politik. D. Kerangka Teori Dalam upaya mengungkap sumber daya sehingga mampu menjadi basis kekuatan Klan Qahhar Mudzakkar, ada beberapa hal yang perlu dijadikan kerangka teori. Oleh karena itu, menggunakan beberapa konsep dari Pierre Bourdieu. Konsep habitus, modal, dan arena digunakan karena secara internal ketiga konsep tersebut terkait satu sama lain, dan masing-masing dapat mencapai potensi analisis yang penuh hanya apabila digunakan bersama-sama dengan yang lain. Sedangkan doxa merupakan bagian dari produk ketiga konsep tersebut (Wacquant, 2007: 270). Penggunaan konsep modal dan arena, dipinjam untuk menjelaskan bagaimana kedua konsep ini sebagai alat reproduksi kekuasaan, sedangkan untuk melihat sumber legitimasi kekuasaan digunakan konsep habitus dan doxa. Untuk menjawab implikasi terhadap demokrasi akan diuraikan perdebatan teoritik mengenai demokrasi Indonesia. Selain itu, beberapa argumentasi awal untuk memahami penggunaan konsep klan dalam studi ini. Mendefinisikan Politik Klan Penggunaan politik klan dalam studi ini bermaksud untuk menjelaskan politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah klan disini juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah oligarki politik dalam studi yang lain. Berdasarkan hasil penelusuran saya, belum banyak studi yang menjelaskan pengertian politik klan secara spesifik. Hal ini disebabkan oleh arti dari klan itu sendiri yang umumnya berarti keluarga/kelompok. Klan di gambarkan sebagai suku, yang dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia, clan berarti anak. Sementara itu, istilah klan lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai analisis sistem kekerabatan yang didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial yang permanen 9 Bab I: Pendahuluan berdasarkan keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama (Kirchhoff, 1955; Kontjaraningrat, 1974). Para antropolog menggunakannya sebagai analisis dalam studi masyarakat primitif. Namun, istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan masyarakat modern. Misalnya penggunaan istilah klan di negara pasca Soviet, cukup umum untuk berbicara tentang klan mengacu pada jaringan informal dalam bidang ekonomi dan politik (Kosals, 2007: 72). Penggunaan ini atas asumsi bahwa anggota mereka bertindak terhadap satu sama lain dalam cara yang sangat dekat dan saling mendukung kurang lebih sama dengan solidaritas di dalam keluarga. Selain itu, terdapat istilah yang biasa digunakan dalam menjelaskan fenomena keluarga politik, misalnya politik dinasti. Pada akhirnya, para akademisi lebih banyak menggunakan politik dinasti untuk menjelaskan bagaimana politik dalam lingkaran keluarga karena definisinya yang mudah dipahami. Kamus Oxford, Advanced Learner‟s Dictionary mendefinisikannya sebagai “a period of years during which members of a particular family rule a country”. Dinasti politik didefinisikan sebagai suatu periode tahun di mana anggota keluarga tertentu memerintah sebuah negara. Singkatnya bahwa politik dinasti adalah bagian dari produksi kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga dalam struktur sosial dan politik yang kemudian berlanjut secara turun-temurun. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana tujuan studi ini yang mencoba melihat bagaimana reproduksi kuasa – atau bagaimana keluarga dapat hadir dalam politik – keluarga Qahhar Mudzakkar, maka penggunaan istilah politik klan akan lebih tepat untuk menjelaskannya. Sementara itu, penggunaan istilah politik dinasti dalam tulisan ini dianggap kurang tepat, mengingat objek yang menjadi studi adalah keluarga Qahhar Mudzakkar yang secara historis belum dapat dikategorisasikan sebagai penguasa (pejabat publik) sebelum era reformasi. Walaupun secara harfiah politik dinasti dan politik klan cenderung memiliki kesamaan perspektif. Akan tetapi, politik dinasti lebih tepat diartikan sebagai hasil dari kekuasaan keluarga dalam garis keturunan langsung yang telah mendominasi dan dilakukan dengan turun temurun, sedangkan politik klan lebih tepat digunakan untuk mengartikan bagaimana keluarga menghadirkan kekuasaan. 10 Bab I: Pendahuluan Modal dan Arena: Alat Reproduksi Kekuasaan Pierre Bourdieu (1986) melihat dalam arena sosial selalu ada yang mendominasi dan didominasi. Kondisi ini tidak lepas dari situasi dan sumber daya capital (modal) yang dimiliki seseorang, dimana modal tersebut adalah sesuatu yang langka dan berharga dalam ruang sosial tertentu. Menurutnya, modal adalah akumulasi kerja, berupa barang baik material maupun simbolik yang apabila dialokasikan secara privat oleh agen atau kelompok agen, memungkinkan mereka untuk memperoleh kekuatan sosial (Bourdieu, 1986: 241). “Capital is accumulated labor (in its materialized form or its „incorporated,‟ embodied form) which, when appropriated on a private, i.e., exclusive, basis by agents or groups of agents, enables them to appropriate social energy in the form of reified or living labor.” “Modal adalah kerja yang terakumulasi (bentuk materi atau dalam bentuk yang mirip „badan hukum‟) yang ketika dialokasikan secara pribadi, yaitu, secara eksklusif, menjadi dasar oleh agen atau kelompok agen, yang memungkinkan menyediakan energi sosial yang sesuai dalam bentuk abstrak atau kerja kehidupan.” Pandangannya tentang modal dimaksudkan sebagai hubungan sosial, karena modal merupakan suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam arena perjuangan dimana modal memproduksi dan mereproduksi. Bourdieu menegaskan bahwa modal adalah hasil dari sebuah proses kerja yang perlu waktu untuk diakumulasikan, sebagai kapasitas potensi untuk menghasilkan keuntungan dan untuk mereproduksi dirinya sendiri dalam bentuk yang sama atau diperluas. Modal juga mengandung kecenderungan untuk bertahan dalam eksistensinya, sebagai kekuatan yang terkandung dalam obyektivitas sesuatu, sehingga semuanya tidak mungkin setara (Bourdieu, 1986: 241). Pertarungan tentang modal dalam konsepsi Bourdieu, tidak lepas dari sumbangsih pemikiran Marx dalam dialektika ketimpangan sosial (Field, 2011: 20). Jika Marx menekankan pada basis struktur dan ekonomi, maka Bourdieu kemudian menguraikan modal tidak sebatas pada ekonomi. Bourdieu mengatakan tidaklah cukup melihat modal dari aspek ekonomi saja, walaupun ia berpendapat bahwa 11 Bab I: Pendahuluan modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lain. Selain aspek ekonomi, modal budaya dan modal sosial juga merupakan aset sebagai representasi akumulasi kerja. Bourdieu beralasan bahwa mustahil memahami dunia sosial tanpa mengetahui peran modal dalam segala bentuknya (Field, 2011: 24). Artinya bahwa modal memiliki energi yang penting dalam arena sosial dan politik. Adapun ciri-ciri modal dalam pandangan Bourdieu dapat disimpulkan antara lain: (1) modal terakumulasi melalui investasi; (2) modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan dan; (3) modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya (Mutahir, 2011: 68). Modal secara prinsipil dibedakan menjadi empat kategori (Bourdieu, 1989: 17): modal ekonomi (berupa uang, kekayaan, properti); modal sosial (berbagai jenis relasi, jaringan); modal kultural (misalnya pengetahuan, kualifikasi pendidikan, gelar akademik, bahasa); dan modal simbolik (seperti prestise, kehormatan, karisma). Salah satu sifat yang paling penting adalah di mana memungkinkan satu bentuk modal dapat dikonversi ke modal yang lain, misalnya, kualifikasi pendidikan tertentu dapat diuangkan melalui pekerjaan yang menguntungkan. Modal-modal inilah yang kemudian memiliki kekuatan-kekuatan sosial yang fundamental (Bourdieu, 1987: 152): “…ces pouvoirs sociaux fondamentaux sont, d'apres mes recherches empiriques, le capital economique, sous ses differentes formes, et le capital culturel, le capital social et le capital symbolique, forme que revetent les differentes especes de capital lorqu 'elles sont percues et reconues comme legitimes.” “…kekuatan-kekuatan sosial yang fundamental ini, menurut penelitian empiris saya, pertama adalah modal ekonomi dalam berbagai bentuknya, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik yang merupakan bentuk lain dari kapital-kapital tersebut ketika dianggap dan diakui dengan sah atau terlegitimasi.”3 Bourdieu kemudian mendefinisikan modal-modal tersebut dalam pengertian yang berbeda-beda. Menurut Bourdieu, modal ekonomi merupakan modal yang paling cepat dan dapat langsung dikonversi menjadi uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak milik (Bourdieu, 1986: 242). Sedangkan, modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang bertambah pada seorang individu atau 3 Choses Dites telah diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul “Choses Dites: Uraian dan Pemikiran”, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011. 12 Bab I: Pendahuluan kelompok karena memiliki jaringan tahan lama melalui hubungan timbal balik dari perkenalan dan pengakuan yang kurang lebih terlembagakan (Bourdieu & Wacquant, 1992: 119). Dalam pandangan Bourdieu, modal sosial sederhananya merupakan kumpulan relasi-relasi sosial yang mengatur individu atau kelompok, dapat berupa jaringan informasi, norma-norma sosial dan kepercayaan yang melahirkan kewajiban-kewajiban dan harapan. Lain halnya dengan modal sosial, modal kultural merupakan konversi budaya, seperti pengetahuan ilmiah, kualifikasi pendidikan, ataupun fasilitas verbal (bahasa), dengan kata lain ingin menunjukkan bahwa budaya (dalam arti luas) dapat menjadi modal (Swartz, 1997: 43). Modal kultural bisa eksis dalam tiga bentuk: pertama, dalam keadaan diwujudkan (non-fisik), yaitu dalam bentuk disposisi tahan lama dari pikiran dan tubuh seperti cara berbicara (bahasa), cara berjalan, atau perilaku-perilaku lain; kedua, dalam keadaan materi, seperti dalam bentuk barang budaya (lukisan, buku, alat elektronik, mesin-mesin, dll), yang menunjukkan status sosial karena kepemilikan benda-benda tersebut; terakhir, dalam keadaan terlembagakan (institusional) seperti kualifikasi akademik, gelar atau ijasah yang berhubungan dengan kualitas intelektual (Bourdieu, 1986: 242). Modal ini berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Terakhir, modal simbolik didefinisikan sebagai bentuk yang sama atau lain dari jenis modal yang lainnya, diperoleh melalui kategorisasi persepsi yang mengakui logika tertentu, sehingga merupakan akumulasi kehormatan yang dimiliki oleh pelaku sosial. Modal simbolik disimpulkan sebagai sebuah pengakuan, dilembagakan atau tidak, yang diterima dari kelompok (Bourdieu, 1991: 72). Pada dasarnya modal simbolik adalah tidak lain dari modal lainnya ketika diketahui dan diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan, hubungan kekuasaan simbolis yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. (Bourdieu, 1989: 21). Singkatnya, modal simbolik adalah transformasi dari modal ekonomi, sosial, dan kultural kedalam bentuk yang baru, dan memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan modal simbolik yang sangat besar pada akhirnya akan menciptakan kuasa simbolik (symbolic power). Menurut Bourdieu, penguasaan modal simbolik 13 Bab I: Pendahuluan adalah salah satu syarat dibangunnya kekuasan simbolik, disamping sejauh mana visi yang ditawarkan berpijak pada realitas (Bourdieu, 1987: 164; 2011: 183). “Premierement, ...le pouvoir symbolique doit etre fondee sur la possession d'un capital symbolique...” “Deuxiemement, l'efficacite symbohque depend du degre auquel vision propose est fonde dans la realite.” “Pertama, …kekuasaan simbolik harus didasarkan pada kepemilikan modal simbolik…” “Kedua, efektivitas simbolik bergantung pada sejauh mana visi yang ditawarkan dapat berpijak dalam realitas.” Bourdieu mengambil dari gagasan Max Weber yakni karisma dan legitimasi untuk mengembangkan teori kekuasaan simbolik (Swartz, 1996: 76).4 Seperti Weber, Bourdieu berpendapat bahwa pelaksanaan kekuasaan membutuhkan legitimasi.5 Pada akhirnya, Bourdieu berkata untuk kekuasan simbolik adalah kekuasaan tak terlihat yang dapat dilaksanakan hanya dengan keterlibatan orang-orang yang tidak ingin tahu bahwa mereka tunduk atau bahkan mereka sendiri menjalankan itu (Bourdieu, 1991: 164). Pertanyaannya kemudian apa sumber dan efek dari kuasa simbolik? Bourdieu (1991: 168-170) menjawabnya dengan panjang lebar: sebagai instrumen dominasi, kuasa simbolik adalah menstrukturkan (karena ia terstruktur), yang merupakan sistem ideologis yang spesialis memproduksi kedalam dan perjuangan atas monopoli produksi ideologis yang terlegitimasi dalam bentuk tidak dikenali (misrecognizable), melalui perantaraan homologi antara arena produksi ideologis dan arena kelas sosial. Efeknya, kekuatan simbolik sebagai kekuatan yang diberikan melalui ucapan atau kata-kata (bahasa), membuat orang melihat dan percaya, mengkonfirmasi atau mengubah visi pandangannya tentang dunia, dan dengan demikian, tindakan pada dunia adalah dunia itu sendiri. Selain itu, merupakan magical power yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang 4 Lihat secara lengkap di Pierre Bourdieu (1991), “Language and Symbolic Power”, Cambridge: Polity Press, halaman 163-170. 5 Max Weber mengajukan tiga dasar legitimasi yakni rasional, tradisional dan karisma (Weber, 1947: 328). Menurut Weber, legitimasi rasional bertumpu pada kepercayaan legalitas melalui pola aturan normatif, dan hak atas kekuasaan itu di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah (kewenangan hukum). Legitimasi tradisional bertumpu pada keyakinan yang didirikan pada kesakralan tradisi yang telah lama bertahan, patron-klien misalnya. Sedangkan legitimasi karismatik bertumpu pada pengabdian khusus, kesucian, kepahlawanan atau karakter teladan dari seorang individu, yang kemudian menjadi nilai (otoritas karismatik). Dalam kasus otoritas karismatik, pemimpin memenuhi syarat untuk dipatuhi berdasarkan kepercayaan pribadi yang ada dalam diri, kepahlawanan atau kualitas teladan yang dimiliki secara individu. 14 Bab I: Pendahuluan setara dengan apa yang diperoleh melalui force, baik fisik maupun ekonomi, dan berdasarkan mobilisasi yang dapat dijalankan hanya jika diakui, tidak dikenali bahwa itu sewenang-wenang (misrecognized as arbitrary). Kesimpulannya, legitimasi dalam konsepsi Bourdieu adalah kuasa simbolik. Lebih konkret lagi, legitimasi dunia sosial bukanlah produk dari tindakan yang memang diorientasikan untuk propaganda atau pemaksaan simbolis, sebaliknya legitimasi ini hadir karena agen-agen mengaplikasikannya kedalam struktur obejektif itu sendiri, dan karenanya cenderung menggambarkan dunia itu sesuatu yang sudah terbukti dengan sendirinya (Bourdieu, 2011: 181). Untuk itu, dalam banyak tempat di studi ini, legitimasi akan digunakan secara bergantian dengan kuasa simbolik. Berdasarkan konsepsi Bourdieu tentang modal tersebut memungkinkan bagi studi ini untuk mengetahui modal apa saja yang dimiliki oleh Klan Qahhar Mudzakkar. Ketokohan Qahhar Mudzakkar bagi masyarakat Sulawesi Selatan memberikan pemahaman awal bahwa salah satu modal yang dimiliki adalah modal simbolik. Disamping itu konsep modal yang dikatakan Bourdieu terakumulasi dari proses panjang sehingga memiliki peran yang penting bagi kontestasi politik, mengajak kita untuk mengaitkan dan mengujinya dalam arena elektoral. Keberhasilan Klan Qahhar Mudzakkar untuk terpilih sebagai pejabat publik di pusat dan daerah adalah langkah awal untuk mengetahui karakteristik modal yang dimiliki klan tersebut. Menurut Bourdieu, modal adalah setiap sumber daya yang efektif di ruang sosial tertentu yang memungkinkan seseorang untuk memastikan adanya keuntungan khusus yang timbul dari partisipasi dan kontestasi di dalamnya. Modal tersebut berada dalam sebuah champ (bahasa Perancis) atau arena, dimana berbagai jenis modal itu diperebutkan, dipertahankan dan dipertukarkan. Arena secara sederhana dapat disimpulkan sebagai jaringan hubungan sosial, sistem terstruktur dari posisi sosial di mana perjuangan atau manuver perebutan sumber daya, wilayah dan akses – beberapa akan berusaha untuk mempertahankan status quo, sedangkan yang lain berusaha untuk mengubahnya. Bourdieu mendefinisikan arena sebagai: “A network, or configuration of objective relations between positions. These positions are objectively defined in their existence and in the determinations they impose upon their occupants, agents or 15 Bab I: Pendahuluan institutions, by their present and potential situation in the structure of the distribution of species of power (or capital) whose possession commands access to the specific profits that are at stake in the field, as well as by their objective relation to other positions (domination, subordinaton, homology, etc).” (Bourdieu & Wacquant, 1992: 97). “Suatu jaringan, atau konfigurasi hubungan antara posisi-posisi obyektif. Posisi ini secara objektif didefinisikan dalam eksistensinya dan dalam determinasi yang mereka paksakan atas para penghuninya, agen atau lembaga, oleh kehadirannya dan situasi potensial dalam struktur dari distribusi jenis kekuasaan (atau modal), yang memiliki akses mengendalikan keuntungan tertentu yang dipertaruhkan di arena, serta hubungan yang bertujuan untuk posisi lain (dominasi, subordinasi, homologi, dll).” Arena dilambangkan sebagai arena-arena produksi, sirkulasi dan perebutan barang kebutuhan, pelayanan, pengetahuan atau status, dan posisi kompetitif yang diperebutkan oleh agen-agen sebagai bentuk akumulasi dan monopoli jenis-jenis kapital yang beragam (Swartz, 1997: 117). Konsep arena merupakan tempat pertarungan kekuatan atau tempat mempertahankan dan mengubah struktur hubungan-hubungan kekuasaan. Sebagai contoh pertama, arena adalah sebuah ruang terstruktur dari posisi, dimana kekuatan arena menetapkan penentuan spesifik kepada semua orang yang memasukinya. Misalnya seseorang ingin berhasil sebagai seorang ilmuwan, maka dia tidak memiliki pilihan selain untuk mendapatkan minimal “modal ilmiah” yang diperlukan dan untuk mematuhi adat istiadat dan peraturan yang ditegakkan oleh lingkungan ilmiah tersebut. Dalam contoh kedua, arena merupakan “arena of struggle” di mana agen dan institusi berusaha untuk melestarikan atau membatalkan distribusi yang ada terhadap modal (Wacquant, 2007: 268). Arena dapat dianggap sebagai semacam pasar atau permainan (jeu), karena dalam arena, kita memiliki saham (enjeux), investasi (illusio), dan kita juga memiliki kartu truf (Bourdieu & Wacquant, 1992: 98). Arena ditempati oleh yang dominan dan yang didominasi, dua set aktor yang berusaha merebut, mengeluarkan, dan membangun monopoli atas mekanisme reproduksi arena dan jenis kekuasaan yang efektif di dalamnya (pp. 106). Namun, arena juga selalu relasional, mikrokosmos sosial yang dinamis. Mereka bergantung dan terus berubah, yang berarti bahwa untuk memikirkan arena, orang perlu untuk berpikir relasional atau secara dialektis (pp. 96). 16 Bab I: Pendahuluan Dalam upaya perjuangan perebutan kekuasaan di dalam arena, Bourdieu membedakan tiga jenis strategi yang dipakai oleh para agen (Swartz, 1997: 125). Pertama, conservation, yaitu strategi yang biasa dipakai oleh pemegang posisi dominan dalam sebuah arena. Kedua, succession, yaitu strategi yang bertujuan untuk mendapatkan akses terhadap posisi-posisi dominan didalam arena. Posisi dominan tersebut biasanya dikejar oleh para agen pendatang baru. Ketiga, subversion, yaitu strategi yang dipakai oleh mereka yang mengharapkan mendapat bagian kecil dari kelompok-kelompok dominan. Strategi ini mengambil bentuk kurang lebih perpecahan radikal dengan kelompok dominan dengan menantang legitimasi untuk menentukan standar arena. Penggunaan strategi oleh agen pelaku sosial adalah untuk mempertahankan posisi, memperbaiki posisi dan memperoleh posisi-posisi baru di dalam arena. Strategi ini menyangkut penempatan modal dan habitus dalam arena, sehingga individu atau kelompok kemudian memiliki posisi di bagian kelas atas, menengah atau bawah. Semakin besar kepemilikan modal, maka semakin tinggi posisinya dalam hirarki ruang sosial di masyarakat. Untuk mengetahui strategi dalam arena sosial, Bourdieu (1998: 5) mengajukan matriks analisa posisi individu dalam penempatan modal (lihat bagan 1). Hanya saja tipologi arena sosial tersebut berdasarkan pada realita masyarakat Perancis pada saat itu. Berdasarkan bagan tersebut, Bourdieu (1998: 6-7) mengatakan bahwa untuk pembacaan terhadap analisis hubungan antara posisi sosial (hubungan relasional), disposisi (habitus), dan pengambilalihan-posisi (strategi), yakni pilihan yang dibuat oleh agen-agen sosial dalam ranah dengan berbagai macam praktik, dalam makanan atau olahraga, musik atau politik, dan sebagainya. Selain itu, penempatan modal sangat penting untuk melihat posisi pelaku sosial di setiap kelas, menentukan gaya hidup dan selera (distinction). Arena dibangun sedemikian rupa sehingga agen atau kelompok berada sesuai dengan posisi mereka dalam distribusi statistik modal secara keseluruahan, dan didasarkan pada dua prinsip diferensiasi yakni modal ekonomi dan modal kultural. Dalam dimensi pertama (vertikal), agen didistribusikan sesuai dengan volume keseluruhan dari berbagai jenis modal (ekonomi, sosial, budaya dan simbolik) yang mereka miliki, dan dalam dimensi kedua (horisontal) berdasarkan 17 Bab I: Pendahuluan dengan struktur modal mereka, yakni sesuai dengan relativitas berbagai jenis modal ekonomi dan budaya, dalam bobot komposisi volume modal mereka. Bagan 1 Ruang Sosial (Arena) berdasarkan Strategi Penempatan Modal Dengan demikian, dalam dimensi pertama, yang paling utama (kelas atas) adalah para pemegang volume modal terbesar secara keseluruhan, seperti pengusaha, pegawai profesional, dan profesor universitas (intelektual). Sedangkan guru, sekretaris profesional atau teknisi berada di garis pembelah yang dikelompokkan di dalam kelas menengah. Sementara yang terendah (kelas bawah), dalam bentuk massa adalah mereka yang paling kekurangan modal, seperti pekerja tidak terampil dan petani. Akan tetapi, dari sudut pandang bobot modal kultural, profesor relatif kaya 18 Bab I: Pendahuluan modal budaya daripada modal ekonomi, sehingga berlawanan dengan pengusaha yang relatif kaya modal ekonomi daripada modal kultural. Dimensi kedua (horisontal), adalah sumber dari perbedaan dalam disposisi (habitus), sehingga sebagai cara pengambilalihan posisi (strategi). Misalnya pertentangan antara intelektual dan pengusaha atau pada tingkat yang lebih rendah dari hirarki sosial, antara guru sekolah dasar dan pedagang kecil. Jika dimensi vertikal berdasarkan pada distribusi modal, maka dimensi horisontal berdasarkan diferensiasi habitus, misalnya selera. Untuk menganalisa arena tersebut mencakup tiga hal yang diperlukan dan secara internal saling berhubungan (Bourdieu & Wacquant, 1992: 104-5). Pertama, kita harus menganalisis posisi-posisi arena kekuasaan yang saling berhadapan (vis-àvis). Kedua, kita harus memetakan struktur obyektif terhadap relasi antara posisi yang diduduki oleh agen-agen sosial atau institusi yang bersaing untuk mendapatkan bentuk-bentuk legitimasi dari otoritas tertentu atas sebuah arena. Ketiga, menganalisa habitus agen sosial, sistem-sistem disposisi yang berbeda, yang diperoleh diperoleh melalui internalisasi pengaruh dari kondisi ekonomi dan sosial, serta menemukan sebuah jalan/masa depan (trajectory) yang pasti kedalam arena atas pertimbangan kesempatan yang menguntungkan untuk dapat teraktualisasikan. Kesimpulannya, untuk melihat strategi adalah dengan cara “mapping” posisi agen di dalam arena berdasarkan akumulasi modal – khususnya ekonomi dan kultural – kemudian mengelompokkan secara bersama profil individu dan institusi yang memiliki karakteristik sama dan bertentangan – habitus – dimana sebuah peluang atau kesempatan dalam arena sangat mempengaruhi. Pada akhirnya, dunia sosial dengan pembagian kelas-kelasnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh para agen pelaku sosial untuk berkuasa – dalam artian politik. Dilakukan secara individu dan kolektif, dalam kerjasama dan konflik, dimana posisi yang diduduki dalam ruang sosial berdasarkan distribusi berbagai jenis modal, dan diferensiasi habitus, yang dapat digunakan sebagai senjata, penentu representasi dari arena, dan untuk pengambilalihan posisi, dalam upaya perjuangan untuk melestarikan atau mengubahnya (Bourdieu, 1998: 12). Konsep arena tersebut diatas digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertarungan modal yang dimiliki Klan Qahhar Mudzakkar. Seperti apa modal 19 Bab I: Pendahuluan tersebut digunakan oleh para agen untuk memperebutkan kekuasaan dalam arena politik. Seperti yang Bourdieu katakan, “capital does not exist and function except in relation to a field” (Bourdieu & Wacquant, 1992: 101). Arena yang dimaksud dalam studi ini adalah kontestasi demokrasi elektoral dalam ruang kekuasaan. Demokrasi elektoral, sama seperti arena, adalah ruang di mana permainan berlangsung, yang merupakan hubungan antara individu yang bersaing untuk keuntungan pribadi. Dalam arena demokrasi elektoral terdapat aturan dan batasan-batasan yang harus dilalui oleh para agen atau pelaku sosial (diluar dari pelaku sosial dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial).6 Habitus dan Doxa: Sumber Legitimasi Kekuasaan Konsep habitus digunakan dalam studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana disposisi7 individu ke dalam suatu praktik tertentu. Apakah individu cenderung mendisposisikan dirinya dalam skema praktik yang dikonstruksi oleh masyarakat ataukah sebaliknya. Bagaimana praktik sosial dipahami sebagai agregat perilaku individu ataukah sebagai sesuatu yang ditentukan oleh struktur supra individual. Sedangkan konsep doxa dipinjam untuk menjelaskan bagaimana wacana dominan yang diproduksi oleh institusi sosial dapat diterima sebagai kebenaran obyektif bagi masyarakat Sulawei Selatan. Dengan kata lain, doxa merupakan basis bagi Klan Qahhar Mudzakkar sebagai legitimasi wacana dominan yang diproduksi oleh institusi masyarakat. Dalam studi ini institusi yang dimaksud adalah institusi yang sifatnya informal. Mengenai habitus, Bourdieu ingin keluar dari dualisme obyektivisme dan subyektivisme, dan reaksi terhadap strukturalisme yang mereduksi agen hanya sekedar pelaksana bagi struktur (Bourdieu: 1990a: 52). Bourdieu telah melampaui jalan dari perdebatan dua kutub subyektivisme dan obyektivisme yang mewarnai ilmu sosial hingga sekarang. Subyektivisme melalui eksistensialisme yang melihat individu sebagai penentu utama dalam tindakan sosial, sedangkan obyektvisme 6 Dialectic of the internalization of externality and the externalization of internality (externality adalah struktur dan internality adalah pelaku sosial). Lihat Bourdieu (1995), “Outline of A Theory of Practice”, New York: Cambridge University Press, halaman 72. 7 Pengertian disposisi menurut Bourdieu memiliki tiga makna: (a) hasil dari suatu tindakan pengorganisasian, (b) suatu keadaan habitual/kebiasaan (terutama dari tubuh); (c) tendensi, niat, atau kecenderungan (Bourdieu, 1995: 214, no. 1; Jenkins, 2010: 110). 20 Bab I: Pendahuluan melalui strukturalisme menempatkan struktur sosial sebagai faktor dominan yang mempengaruhi sebuah tindakan. Bourdieu ingin mendamaikan pertentangan kedua pendekatan tersebut yang menurutnya “absurd opposition between individual and society”, sehingga kemudian melahirkan konsep habitus (Bourdieu, 1990b: 31). Bourdieu kemudian mendefenisikan habitus sebagai sesuatu yang tahan lama, disposisi yang dapat berganti, struktur yang distrukturkan, yaitu sebagai prinsip yang mengatur praktik dan gambaran representasi/perwakilan yang dapat disesuaikan secara objektif untuk mendapatkan hasil tanpa mensyaratkan akan tujuan akhir atau penguasaan atas operasi-operasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Secara obyektif “teratur” dan “berkala” tanpa harus menjadi hasil dari ketaatan kepada aturan, mereka dapat diatur secara kolektif tanpa terorganisir oleh pelaku (Bourdieu, 1990a: 53; 1995: 72). “Systems of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them. Objectively „regulated‟ and „regular‟ without being in any way the product of obedience to rules, they can be collectively orchestrated without being the product of the organizing action of a conductor.” Habitus berdasarkan dengan apa yang diterima, nilai, dan cara bertindak di dalam arena sosial. Bourdieu kadang menggambarkan habitus sebagai “logika permainan” sebuah “rasa praktik” yang mendorong aktor bertindak dan bereaksi dalam situasi spesifik dengan suatu cara yang tidak dikalkulasikan sebelumnya dan bukan sekedar kepatuhan sadar pada peraturan-peraturan (Johnson, 2012: xvi). Habitus sebagai sistem skema persepsi dan apresiasi dari praktik, struktur kognitif dan evaluatif yang diperoleh melalui pengalaman abadi pada posisi sosial (Bourdieu, 1989: 19). Habitus ada dalam bentuk mental dan skema jasmani, matriks persepsi, apresiasi, dan tindakan (Bourdieu & Wacquant, 1992: 16, 18). Kesimpulannya bahwa habitus bukan sesuatu yang alami atau bawaan melainkan pengalaman sosial ataupun pendidikan, dapat diubah oleh sejarah, yaitu dengan pengalaman baru, pendidikan atau pelatihan. Disposisi yang tahan lama yang 21 Bab I: Pendahuluan cenderung melanggengkan, untuk memperbanyak diri, tetapi tidak kekal. Setiap dimensi habitus sangat sulit untuk mengubah, tetapi dapat diubah melalui proses kesadaran dan usaha pedagogik (mendidik). Secara sederhana habitus dapat diartikan sebagai hasil dari proses keterampilan berupa tindakan praktis (sadar ataupun tidak disadari) yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Kita dapat memahami pengoperasian habitus dengan mengamati diberlakukannya disposisi dalam praktik. Praktik seseorang-kelompok “corporeal hexis” (jasmani) dan “style of expression” (mental) adalah manifestasi empiris dari disposisi yang terletak di habitus. Ketika orang masuk ke dalam ruang sosial, maka mereka membawa habitus dan berhubungan dengan tatanan sosial yang lebih luas, sehingga praktik individu dalam organisasi diinformasikan (tapi tidak menentukan) oleh habitus (terkait dengan posisi dalam tatanan sosial yang lebih luas). Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan tugas-tugas sosial dan politik, orang bertindak atas dasar tidak hanya aturan institusi, tetapi juga dari habitus. Berangkat dari konsep tiga serangkai (habitus, modal, dan arena), Bourdieu secara sosiologis kemudian menguraikan gagasan tentang doxa. Doxa adalah hubungan kepatuhan langsung yang didirikan dalam praktik antara habitus dan arena yang sangat menyesuaikan diri, dan sesuatu yang diterima begitu saja dari dunia yang mengalir dari pikiran (Bourdieu, 1990a: 68). Doxa hadir ketika kita mempertanyakan tentang legitimasi yang tidak muncul, ataupun perjuangan simbolik tidak bertarung. Hal ini terjadi pada masyarakat doxic, suatu masyarakat yang menetapkan tatanan kosmologi dan politik dianggap tidak sewenang-wenang, dan bukan urutan kemungkinan, tetapi sebagai perintah yang sudah jelas dan alami (Bourdieu, 1995: 166). Dalam masyarakat doxic kebutuhan subjektif dan akal sehat divalidasi oleh konsensus obyektif tentang memahami dunia. Gagasan doxa milik Bourdieu menunjukkan dua hal: pertama, bahwa sikap alami dari kehidupan sehari-hari yang membawa kita menerima dunia yang di yakini bergantung pada kesesuaian antara kategori subjektif dari habitus dan struktur tujuan dari setting sosial di mana orang bertindak. Kedua, bahwa setiap alam semesta relatif otonom mengembangkan doxa sendiri sebagai satu set pendapat bersama dan 22 Bab I: Pendahuluan keyakinan yang tidak diragukan lagi yang mengikat pelaku satu sama lain (Wacquant, 2007: 270). Mereka yang menduduki posisi dominan dalam arena, dan mereka yang berada dalam posisi terdominasi tunduk sebagai bentuk penerimaan di arena, sikap mereka di dalamnya berdasarkan dari aturan keterlibatan. Bourdieu menyebut sikap ini sebagai doxa. Bourdieu menggunakan istilah doxa untuk menunjukkan apa yang diterima begitu saja (taken for granted) dalam setiap masyarakat tertentu. Doxa, dalam pandangannya adalah pengalaman dimana dunia alam dan sosialnya muncul secara alami dan terbukti dengan sendirinya (the natural and social world appears as self-evident) (Bourdieu, 1995: 164). Bourdieu berangkat dari pandangan bahwa setiap tatanan yang mapan cenderung menghasilkan (untuk derajat yang sangat berbeda dan dengan cara yang sangat berbeda) naturalisasi kesewenang-wenangan tersendiri. Disebabkan oleh korespondensi antara kelas yang obyektif dan kelas yang diinternalisasikan, struktur sosial dan struktur mental, yang merupakan dasar dari kepatuhan. Artinya, nilai dan wacana yang dihasilkan oleh doxa merupakan sebuah kebenaran yang sah dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagan 2 Doxa, Heterodoxy dan Orthodoxy (Bourdieu, 1995: 168) universe of undispute (undisputed) doxa opinion heterodoxy - orthodoxy + universe of discourse (argument) Didalam doxa ini terdapat seperangkat nilai dan wacana, sebagai prinsipprinsip fundamental bagi arena, dimana kebenaran terkandung didalamnya. Doxic attitude (sikap) telah membuat tubuh dan ketidaksadaran menerima kondisi-kondisi 23 Bab I: Pendahuluan yang sebenarnya tidak masuk akal dan bersifat mengikat. Doxa beroperasi seolaholah itu adalah kebenaran obyektif di ruang sosial secara keseluruhan. Praktik dan persepsi individu (pada tingkat habitus) ke praktik dan persepsi dari negara dan kelompok sosial (pada tingkat arena) (Bourdieu, 1995: 165-8). Dengan demikian, doxa sesungguhnya merupakan kebenaran obyektif yang diterima dalam lintas ruang sosial, dari praktik dan persepsi individu menjadi praktik dan persepsi yang diterima kelompok atau institusi sosial lainnya (universe of undispute). Artinya, doxa dapat menciptakan legitimasi bagi wacana dominan yang diproduksi dan direproduksi oleh institusi yang ada dalam masyarakat. Sebagaimana ruang sosial (arena) yang selalu bergerak, didalam doxa terdapat pertarungan dunia wacana (universe of discourse) antara heterodoxy dan orthodoxy (lihat bagan 2). Heterodoxy adalah opini (wacana) yang berusaha memberikan penilaian negatif terhadap doxa, sedangkan orthodoxy adalah wacana yang terus berusaha mempertahankan (semakin membenarkan) doxa (Bourdieu, 1995: 168-9). Dalam konteks Klan Qahhar Mudzakkar ditemukan bahwa perolehan suara terbanyak dalam Pemilu dan Pemilukada di Sulawesi Selatan, berada pada wilayah gerakan Qahhar Mudzakkar pada masa lalu. Daerah-daerah tersebut terdapat jaringan pengikut Qahhar Mudzakkar yang loyal. Kepercayaan bahwa Qahhar Mudzakkar masih hidup, terpelihara dengan baik dalam pikiran dan perilaku masyarakat setempat, serta menjadikannya sebagai mitos. Konsepsi Bourdieu tentang habitus dan doxa digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut, sehingga memungkinkan untuk menjawab bagaimana individu memberikan legitimasi kekuasaan bagi Klan Qahhar Mudzakkar, yang juga menjadikannya sebagai modal yang signifikan bagi keberhasilan mereka dalam politik. Demokrasi Indonesia Diawali dari runtuhnya rezim Soeharto dan hadirnya reformasi, banyak ilmuwan mengatakan Indonesia memasuki masa transisi demokrasi (Emmerson, 2001; Mishra, 2002; Webber, 2005). Demokrasi pluralis dan Pemilu kompetitif kemudian diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1999. Hal ini ditandai dengan transisi dari otokrasi terpusat ke pemilihan demokrasi dibantu oleh transformasi elit 24 Bab I: Pendahuluan politik, langkah-langkah membangun kontrol sipil atas aparat keamanan, sejumlah undang-undang tentang desentralisasi, pembentukan komisi independen untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dan pencegahan korupsi, kebebasan pers, dan pembentukan pengadilan niaga (Mishra, 2002). Salah satu bagian dari transisi yang dimaksud, misalnya, sebagai bagian dari proses desentralisasi, pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini membuat tata pemerintahan demokratis: lebih transparan (local accountability), partisipatif (political equality) dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi (local responsiveness) (Hasanuddin, 2003). Pada akhirnya, Indonesia disebut sebagai negara yang sedang mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan ilmuwan lain, cenderung menggambarkan reformasi kedalam bentuk transisi dari “orde ke dis-orde” atau changing continuities, yakni dengan adanya penguasaan elit lama terhadap institusi pemerintahan lokal baru (Robison & Hadiz, 2004; Slater, 2006); desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi lokal, melainkan keberlanjutan masa lalu (Nordholt & van Klinken, 2007). Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Indonesia bukanlah berjalan pada trek demokrasi yang sesungguhnya. Singkatnya, reformasi telah mengundang debat akademik tentang demokrasi Indonesia dan masa depan dari demokrasi itu sendiri. Saya memulai perdebatan ini dari argumen sebagian ilmuwan yang menampilkan Indonesia ke dalam sistem politik yang demokratis, setelah satu dekade reformasi politik, administrasi dan beberapa putaran pemilihan yang dinilai kompetitif. Mereka optimis menyebut Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang paling bersemangat di dunia. Demokrasi Indonesia jika diukur terhadap negaranegara lain pada tahap perbandingan demokratisasi, Indonesia adalah contoh yang mengesankan dari keberhasilan transisi menuju demokrasi pada periode kontemporer, dengan catatan-catatan didalamnya (Aspinall dan Mietzner, 2010: 17). Mengenai catatan-catatan empirik yang terkandung dalam demokrasi Indonesia yang dikemukakan oleh penganut teori konsolidasi demokrasi, mengatakan bahwa bagaimanapun, konsolidasi demokrasi di Indonesia akan terus membingungkan karena pelembagaan yang buruk dalam hal supremasi hukum, kekerasan dan peran militer yang tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Konsolidasi akan terjadi sampai elit dan pejabat pemerintah (aktor) diperkirakan 25 Bab I: Pendahuluan dapat diandalkan untuk menegakkan lembaga-lembaga demokrasi, dan tunduk pada hukum itu sendiri adalah jawaban untuk masa depan demokrasi di Indonesia (Davidson, 2009; Freedman, 2007). Dari kalangan ilmuwan Indonesia sendiri, menyimpulkan bahwa mandek atau tidaknya demokrasi Indonesia pasca reformasi bergantung pada elit politik, sebagaimana yang telah terjadi pada demokrasi liberal tahun 1950-an (Bakti, 2004: 206). Menurutnya, Indonesia telah berjuang dengan demokrasi selama beberapa dekade dengan tiga jenis demokrasi, yang semuanya gagal. Demokrasi Parlementer (1949-1957), Demokrasi Terpimpin (1957-1965), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) adalah kegagalan yang dimaksud. Sebagai kesimpulan, tidak adanya demokrasi di kalangan elit politik, dan kecenderungan militer untuk melihat dirinya sebagai “the guardian of the state”, mengancam transisi demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, penjelasan tersebut dijawab oleh dua ilmuwan Australia, Andrew MacIntyre dan Douglas E. Ramage. Mereka menjelaskan bahwa reformasi sipil-militer cukup berhasil di terapkan di Indonesia. Keluarnya militer dari politik telah membantu untuk memastikan konsolidasi demokrasi yang relatif stabil dan terutama mengenai kesepakatan perdamaian yang berhasil di Aceh (Macintyre & Ramage, 2008: 17). Kesimpulan yang sedikit berbeda dihasilkan dalam dua survei Demos (sejak tahun 2003-2007). Mereka menyimpulkan bahwa walaupun pada awalnya, demokrasi Indonesia mengalami defisit, akan tetapi telah bergerak pada kemajuan demokrasi yang mengesankan (Samadhi & Asgart, 2009: 53). Hal ini berdasarkan indikasi adanya perkembangan relasi aturan-aturan dan perundang-undangan dengan instrumen-instrumen operasional tata pemerintahan demokratis. Namun, disisi lain selama dekade awal reformasi, demokrasi juga dibarengi dengan kemunduran dan stagnasi. Demokrasi Indonesia dibayangkan sebagai bangunan yang berdiri diatas pasir, tidak mempunyai pondasi yang kuat (Samadhi & Asgart, 2009: 55). Mereka pada prinsipnya optimis dengan masa depan demokrasi yang telah bekerja dan berhasil, dan relatif lebih baik dengan pengalaman negara lain seperti Thailand dan Filipina. Berbagai teorisasi – terdapat juga prediksi – diatas, menggunakan perspektif prosedural demokrasi dalam menjelaskan demokrasi Indonesia. Ketersediaan tools demokrasi beserta dengan kemandirian aktor adalah jawaban atas masa depan 26 Bab I: Pendahuluan demokrasi. Merangkum dari keseluruhan teori diatas, bahwa pengalaman demokrasi dekade awal telah menjadi contoh yang menjanjikan terhadap konsolidasi demokrasi yang bertahap: sistem Pemilu, kemapanan elit politik, maupun aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan politik. Transisi demokrasi ataupun konsolidasi demokrasi merupakan jawaban dari dominannya pendekatan aktor dalam memahami realita demokrasi Indonesia. Hal yang akan selalu dikritik oleh penganut strukturalis. Kubu yang berseberangan berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah sebuah proses transisi demokrasi (Robison & Hadiz, 2004; Nordholt & van Klinken, 2007; Boudreau, 2009; Choi 2009). Pemahaman transisi demokrasi yang diiringi dengan proses desentralisasi, sebagai harapan untuk tata pemerintahan yang lebih transparan dan kompetitif perlu untuk dikaji ulang. Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter, tidak secara pasti diiringi dengan demokrasi yang bermutu di ranah lokal. Selain itu, desentralisasi yang dipraktikkan pada dasarnya, mengembalikan penguasa-penguasa lama dan kelompok-kelompok kepentingan dapat mengambil peran dan bahkan menjadi raja-raja kecil di daerah. Salah satu penggagas politik strukturalis Indonesia, Richard Robison dan Vedi R. Hadiz (2004) menyatakan oligarki politik masa lalu masih berkuasa pasca reformasi, meskipun pemerintahan otoriter Orde Baru telah tumbang dan digantikan dengan lembaga-lembaga yang secara formal demokratis. Elemen oligarki tersebut, kini telah menciptakan kembali diri mereka sendiri, dan berusaha untuk mempertahankan posisi mereka dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara dan sumber daya dalam format baru demokratisasi dan desentralisasi (Heryanto & Hadiz, 2005: 270). Henk Schulte Nordholt bahkan menyebut pasca reformasi sebagai changing continuities (2005, 2007: 2). Kontinuitas perubahan yang dimaksud adalah struktur berpikir dan tindakan masa lalu, mempengaruhi secara terus menerus praktik politik kontemporer, dan menghambat kemungkinan terjadinya perubahan (demokrasi). Menurut mereka, pemahaman kontemporer yang mengatakan bahwa Indonesia berada dalam fase transisi, dari masyarakat otoritarian tertutup menuju masyarakat yang terbuka merupakan teori yang keliru. Kecenderungan pada basis aktor dengan menekankan unsur-unsur kebetulan (accidents), pilihan aktor dan dilema-dilema etis yang muncul dalam periode ketidakpastian politik yang terbatas, 27 Bab I: Pendahuluan tidak cukup kuat sebagai dasar untuk menganalisa kesinambungan hubunganhubungan kekuasaan yang mendasarinya. Institusi-institusi baru yang terbentuk bersamaan dengan runtuhnya otoritarian lama, tidak menghilangkan kepentingankepentingan dalam kontestasi kekuasaan para elit lama (Hadiz, 2005: 238). Salah satu gagasan utama dari ilmuwan mazhab ini, bahwa terbentuknya pola-pola baru dari penggunaan kekuasaan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam politik lokal adalah cara yang dilakukan oleh kepentingan-kepentingan lama untuk bertahan dan menguasai lembaga-lembaga demokrasi Indonesia melalui aliansi dan kesepakatan baru (Hadiz, 2005: 237-9). Pada kesimpulannya bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Filipina, terkait dengan besarnya peluang rent-seeking melalui perebutan akses menuju posisi aparatur negara untuk tujuan pribadi oleh aktor-aktor lama. Tradisi yang panjang dan berurat akar dalam masyarakat lokal, seperti misalnya kekerasan, politik uang dan patronase yang kemudian menyesuaikan diri dengan koalisi-koalisi dan aliansialiansi baru di dalam lembaga baru demokrasi, adalah salah satu penyebab dari kenyataan tersebut. Pasca transisi, praktik-praktik otoriter bertahan dan dibentuk oleh rezim transisi dalam proses pemilihan dan kebijakan, serta pola represi menunjukkan cara di mana otoritarianisme dapat bertahan dalam transisi rezim yang merusak janji demokrasi (Boudreau, 2009: 233). Selain itu, perubahan-perubahan institusional tidak mampu mengubah konfigurasi kekuasaan di daerah, dimana demokrasi dan desentralisasi di Indonesia telah memungkinkan elit lokal yang telah mengakar untuk meningkatkan basis kekuasaan mereka dan akses ke sumber daya, dan yang paling penting, memberikan mereka peluang baru untuk berkontestasi dalam pemerintahan (Choi, 2009: 162). Kesimpulannya adalah kenyataan politik dari berbagai studi diatas menjadikan tidak adanya jalan pasti, Indonesia menuju sebuah demokrasi yang ideal. Pengalaman Indonesia yang demikian, memerlukan cara lain untuk memahami lintasan pasca otoriter yang berbeda dari yang ditawarkan dalam literatur tentang teori transisi dan konsolidasi demokrasi yang tidak memuaskan (Hadiz, 2009: 536). Masa depan demokrasi Indonesia dari teorisasi beberapa ilmuwan diatas, dapat dilihat sebagai pijakan awal untuk menjelaskan demokrasi pasca reformasi yang telah memasuki masa dekade kedua. Berbagai teorisasi tersebut merupakan 28 Bab I: Pendahuluan hasil dari praktik demokrasi yang telah terjadi pada masa awal reformasi. Hal utama yang perlu diingat dari perdebatan diatas adalah penganut agensi atau lebih dikenal dengan penganut teori transisi demokrasi yang berfokus pada badan elit politik (Harris et.al., 2005: 8), menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang muncul dalam kaitannya dengan desentralisasi dan demokrasi, didasarkan pada produk yang dirancang dengan buruk (aturan) ataupun implementasi dari kerangka kebijakan itu sendiri. Sedangkan kaum strukturalis menyimpulkannya sebagai produk dari jenis kepentingan sosial yang sudah berurat akar pada masa lalu, memimpin lembagalembaga pemerintahan daerah kontemporer pasca reformasi. Saya menyimpulkan secara lebih sederhana bahwa ada dua hal yang berbeda dari perdebatan tersebut. Satu sisi begitu optimistik dalam menapaki masa depan demokrasi Indonesia, sedangkan yang lainnya cenderung untuk pesimistik dengan demokrasi yang akan terjadi. Namun pada dasarnya mereka semua sepakat bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia tidaklah seperti harapan dari demokrasi yang terjadi di Barat. Untuk itu, studi ini sebagai kesimpulan terbaru dari serangkaian kajian yang menjelaskan seperti apa demokrasi kontemporer dan masa depannya dalam dekade kedua reformasi dalam kasus kehadiran Klan Qahhar Mudzakkar dalam politik lokal. E. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (case study). Metode studi kasus adalah metode pengumpulan informasi yang cukup secara sistematis tentang orang tertentu, pengaturan sosial, peristiwa, atau kelompok untuk memungkinkan peneliti memahami secara efektif bagaimana hal tersebut beroperasi atau berfungsi (Berg, 2001: 224). Studi kasus digunakan untuk mengetahui dan memahami kasus hadirnya Klan Qahhar Mudzakkar dalam politik lokal di Sulawesi Selatan terkait dengan setting social yang berlangsung dan berfungsi dalam demokrasi lokal. Studi kasus dipilih karena karakteristik kekuasaan dari hadirnya keluarga/kerabat Qahhar Mudzakkar yang menduduki jabatan politik merupakan cara yang berbeda. Berkaca pada studi aktor politik lokal yang ada, dimana secara teoritis para keluarga/kerabat/kelompok politik menggunakan berbagai modal sebagai basis legitimasi kekuasaan: sebagai pejabat; pengusaha; ataupun bangsawan. Namun 29 Bab I: Pendahuluan berbeda dengan Klan Qahhar Mudzakkar, yang hadir bukan dari golongan tersebut. Kesimpulannya, tampilnya aktor ini, bukanlah karena hasil pengolahan modal tersebut. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, Qahhar Mudzakkar adalah tokoh yang dikagumi, bahkan dibeberapa daerah, Qahhar Mudzakkar telah menjadi mitos. Keyakinan mitos (setting social) inilah yang terus terpelihara, sehingga fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti. Apa sumber daya yang menjadi modal politik klan tersebut, sehingga dimungkinkan untuk menemukan perspektif lain dalam memahami fenomena hadirnya klan politik di Indonesia. Metode studi kasus ini juga digunakan untuk menggabungkan sejumlah langkah pengumpulan data dari studi lapangan dan data pustaka. Penelitian ini ingin mengetahui “nature” kasus hadirnya Klan Qahhar Mudzakkar secara lebih mendalam dengan cara mendekatinya, kemudian dilanjutkan dengan menciptakan proposisi dan model untuk memprediksi masa depan demokrasi di Indonesia. Dalam studi kasus ini akan menggunakan jenis instrumental, dimana kasus diselidiki secara mendalam, semua aspek dan kegiatan yang rinci, tetapi tidak hanya untuk menjelaskan kasus semata, melainkan tujuannya adalah untuk membantu peneliti lebih memahami beberapa pertanyaan teoritis yang lebih luas (Berg, 2001: 229). Jenis studi kasus ini digunakan untuk mendukung/merevisi konsepsi tentang reproduksi kuasa dan demokrasi berdasarkan kasus hadirnya Klan Qahhar Mudzakkar dalam politik lokal. Lokasi Penelitian Studi ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian akan difokuskan pada daerah utara Sulawesi Selatan. Daerah utara secara administratif terdiri dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. Wilayah utara dipilih karena merupakan tanah kelahiran dan basis gerakan Qahhar Mudzakkar, dimana para pendukungnya sangat banyak diwilayah ini. Kedua, daerah ini memiliki kesamaan struktur sosial dan budaya. Selain itu, daerah utara merupakan mayoritas arena kontestasi politik bagi Klan Qahhar Mudzakkar dalam pemilihan elektoral. 30 Bab I: Pendahuluan Teknik Pengumpulan Data Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pencarian data meliputi data lapangan dan data pustaka. Sumber datanya berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, benda, arsip, dan dokumen. Strategi pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui field study (studi lapang), peneliti berinteraksi langsung dengan realita yang sedang ditelitinya sehingga dapat diperoleh data primer, yaitu data yang berasal langsung dari informan berupa hasil pengamatan berperan serta (observasi partisipatif) maupun berupa hasil wawancara mendalam (indepth interview). 1) Pengamatan Berperan Serta (Observasi Partisipatif) Penggunaan teknik observasi partisipatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjaring informasi atau data mengenai konteks penelitian yang meliputi: manusianya; kondisi sosial budaya, politik, dan lingkungan; kegiatan program dan aktor yang terlibat, interaksi informal yang digunakan dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Berbagai realita tentang Qahhar Mudzakkar dalam masyarakat, dengan melihat, mendengarkan serta merasakan apa yang terjadi, dimana, kapan, siapa yang terlibat, dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Hal ini dapat berupa berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kampanye, pembicaraan keseharian masyarakat yang berkaitan dengan Qahhar Mudzakkar, dan kehidupan keseharian masyarakat Sulawesi Selatan. 2) Wawancara Mendalam Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, meliputi: pengalaman, pendapat dan kepercayaan/keyakinan, pengetahuan mengenai program, norma, nilai, sikap, harapan, orientasi pandangan dan tanggapan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan Qahhar Mudzakkar dan klannya, seperti misalnya perjalanan hidup subjek. Dalam pelaksanaan wawancara, dilakukan secara formal dan non-formal. Untuk itu, peneliti menyusun desain penelitian sebagai pedoman wawancara (map interview guide) agar wawancara tetap terarah pada fokus penelitian. Adapun informan dari studi ini dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, masyarakat setempat yang tinggal dibeberapa daerah di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. Pengambilan populasi ini dengan dasar bahwa 31 Bab I: Pendahuluan wilayah tersebut merupakan daerah basis Qahhar Mudzakkar dengan DI/TII. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan data terkait dengan hubungan-hubungan yang terjadi antara individu, item sosial dan peristiwa yang terjadi di masyarakat berupa wacana, perilaku memilih, pemilu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan studi ini. Kedua, tokoh masyarakat yang mengetahui budaya dan sejarah masyarakat Sulawesi Selatan dan Qahhar Mudzakkar. Tokoh yang dimaksud antara lain, akademisi, peneliti, budayawan, purnawirawan TNI, dan keluarga DI/TII, yang mengetahui tentang sejarah Qahhar Mudzakkar dan Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih luas maupun sebagai perbandingan terhadap penelitian sebelumnya. Ketiga, aktor politik yakni Klan Qahhar Mudzakkar yang berhasil menduduki jabatan publik di Sulawesi Selatan, beserta dengan para jaringan organisasi Klan Qahhar Mudzakkar. Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan antara realita yang ada dimasyarakat terhadap pola perilaku individu/aktor. Pandangan dan sikap mereka terhadap Qahhar Mudzakkar, demokrasi, reformasi, dan masyarakat. Pemilihan informan ini sebagai salah satu cara menghubungkan keterkaitan antara individu dan struktur sosial. Mengenai daftar nama dan biodata informan dapat dilihat pada bagian lampiran. Kedua, melalui analisis teks, yang merupakan eksplorasi dari studi-studi yang telah dihasilkan (studi pustaka). Hal ini dipilih untuk membantu menemukan bagaimana dinamika realitas sosial mengenai Qahhar Mudzakkar dan bagaimana mengkerangkai realitas tersebut berdasarkan data-data pendukung yang telah ada. Data-data pendukung tersebut merupakan data penunjang, yaitu data-data tertulis yang terkait dengan Sulawesi Selatan dan masyarakatnya, Qahhar Mudzakkar dan klannya, dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud berupa rekapitulasi suara pemilu, dokumen tertulis, data statistik, laporan penelitian, tulisan-tulisan ilmiah dan liputan media yang merupakan dokumen penting untuk memperkaya data yang dikumpulkan. Analisis Data Penelitian ini menggunakan proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data (flow model of analysis) atau model analisis interaktif (Miles dan Haberman, 1992). Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti 32 Bab I: Pendahuluan membuat catatan singkat dengan kata-kata kunci, misalnya mengenai mitos Qahhar Mudzakkar yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya dari deskripsi singkat tersebut dikembangkan menjadi deskripsi lengkap, dilanjutkan dengan refleksi (metode, teori, analisis). Deskripsi data dengan refleksinya tersebut disusun dalam fieldnote. Setelah unit data lengkap, dilanjutkan dengan tiga komponen analisis yaitu: (1) reduksi data, yang isinya rumusan singkat dari setiap jenis temuan fieldnote; (2) sajian data, yang berawal dari pokok-pokok temuan dalam reduksi data, penulisan mengenai kondisi sesuai dengan konteks yang diteliti; (3) penarikan kesimpulan, dilakukan berdasarkan uraian yang telah dibuat dalam sajian data. Dari hasil ini selanjutnya meneruskan dan melakukan pemantapan dengan verifikasi. Artinya, guna meningkatkan validitas data yang diperoleh dan demi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna penelitian, maka penelitian ini menggunakan pengolahan data yang bersifat triangulasi. Metode triangulasi dipakai guna memperoleh validitas data yakni menggunakan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis atau sama serta digunakan untuk mengorganisir informasi yang ada. Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari enam bagian. Bab Satu (I) seperti yang telah kita lewati, berisi seputar penjelasan kepada pembaca tentang masalah mendasar dari penelitian, termasuk didalamnya mengapa masalah penelitian ini penting untuk dikaji pada masa sekarang. Bab Dua (II) akan memuat bagaimana penegasan dari bertahannya budaya dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Tujuan utamanya menguraikan karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan yang culture oriented. Pada bab ini, alur argumentasi akan dimulai dari menjelaskan secara singkat setting sosial politik Sulawesi Selatan, kemudian mengkategorisasikan beberapa konsep budaya yang dijadikan sebagai orientasi politik masyarakat Sulawesi Selatan. Pengkategorisasian ini meminjam konsep dari Bourdieu mengenai arena, habitus dan doxa. Bab Tiga (III) mengambil topik dengan judul klan, merupakan deskripsi halhal yang berkaitan dengan Qahhar Mudzakkar beserta dengan anggota klannya yang ada dalam politik. Tujuan utamanya adalah menguraikan tingkah laku politik Klan Qahhar Mudzakkar berdasarkan profil sosiologis dan jaringan-jaringan yang mendukung kehadiran klan. Bab ini juga menampilkan modal yang dimiliki oleh 33 Bab I: Pendahuluan klan seperti jaringan dan ketokohan Qahhar Mudzakkar dalam pandangan masyarakat Sulawesi Selatan. Secara garis besar bab ini menguraikan modal simbolik dan modal sosial Klan Qahhar Mudzakkar. Bab Empat (IV) mengambil topik tentang reproduksi kuasa klan, bagaimana keberhasilan dan kegagalan para anggota klan dalam reproduksi kuasa tersebut. Bab ini menampilkan pertumbuhan kuasa klan yang terbentuk secara struktural maupun kultural. Bagaimana masa reformasi menjadi titik awal reproduksi kuasa juga diperbincangkan dalam bab ini. Selain itu, bab ini menjelaskan bagaimana budaya politik yang terbangun sejak lama mampu menghasilkan sebuah otoritas politik, melalui strategi yang dilakukan oleh anggota klan ataupun dari hasil legitimasi kultural. Bab Lima (V) mengajukan topik tentang demokrasi Indonesia dalam kaitannya dengan oligarki politik. Pada bagian awal bab ini, mendiskusikan bagaimana sudut pandang dalam demokrasi dilihat secara prosedural dan kultural. Setelah itu, mencoba mengaitkan dengan hasil studi yang telah ada. Demokrasi yang dibahas disini akan cenderung dalam perspektif kultural, dimana budaya politik lokal kemudian berdampak pada proses demokrasi Indonesia. Setelah melihat dampak tersebut kemudian menyimpulkan secara hipotetik masa depan demokrasi Indonesia terkait dengan praktik demokrasi dengan kehadiran klan dalam politik lokal. Bab ini juga mengajukan beberapa tawaran mengenai masa depan demokrasi Indonesia, sebut saja salah satunya mengenai bagaimana menghabituasikan demokrasi. Sedangkan pada Bab Enam (VI) adalah bab terakhir yang merupakan rekapitulasi argumen berupa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. *** 34