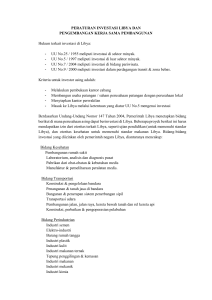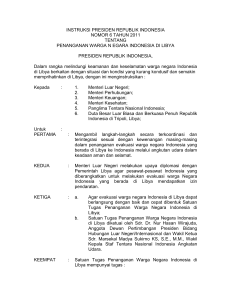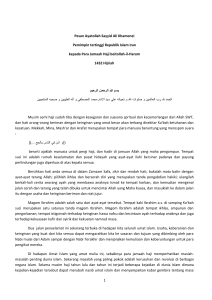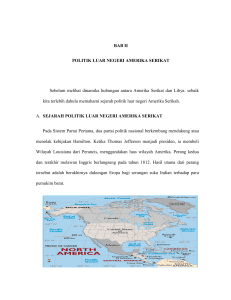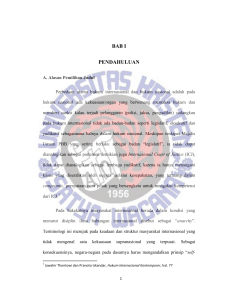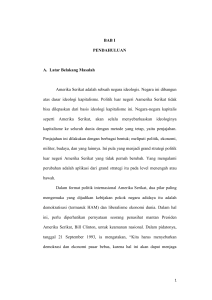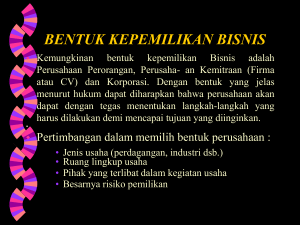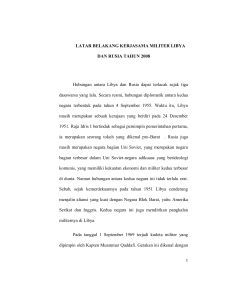Perang untuk Minyak: Kapankah dunia ini bermoral?
advertisement

Perang untuk Minyak: Kapankah dunia ini bermoral? “Tidaklah mengejutkan, bentrokan nyata pertama demi memperebutkan minyak selama Perang Dingin terjadi di belahan dunia yang menyimpan paling banyak minyak, yaitu Timur Tengah” –John Perkins “After Iraq and Libya, Teheran will be the next destination..Be careful” ‐AJB Belum lagi selesai musibah tsunami Jepang yang menimbulkan tangis dan kekhawatiran dunia akan ancaman nuklir Jepang, kita kembali dipertontonkan oleh serangan sekutu (Prancis, AS, dan Inggris) ke Libya, melalui “Operasi Fajar Odyssey” dengan tujuan mempertegas zona larangan terbang dan melumpuhkan kekuatan pasukan Khadafy. Perang di Libya, mengingatkan beberapa pemimpin negara, seperti Vladimir Putin dan Ayatolah Ali Khamenei, akan perang salib, perang agama antara umat Islam dan Kristen, meskipun terlalu berlebihan, jatuhnya bom nuklir di wilayaj kedaulatan Libya adalah bagian proyek “New Middle East” atau Timur Tengah Baru yang digagas oleh AS. Perang selalu menarik untuk dianalisis, karena selain melibatkan biaya yang sangat besar (catat: Perang Irak telah menghabiskan trilyunan dollar AS), memakan banyak korban jiwa, perang juga identik dengan transisi kekuasaan disertai perebutan kepentingan‐kepentingan strategis. Jutaan dollar AS dikucurkan selama perang, jumlah yang sangat menganggu sustainabilitas anggaran AS (catat: AS sedang recovery pasca krisis). Selain itu, jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit dan pasti memiliki motif. Pengembalian biaya perang adalah kata kunci. Kita semua tahu bahwa AS mengeluarkan uang 300 juta dollar untuk perang Libya dan tentunya there is no free lunch (tidak ada makan siang yang gratis). Terbentak tanya di benak kita: Untuk kepentingan siapakah perang yang didesain dan diprakarsai oleh AS dan sekutunya? Benarkah untuk penegakan demokrasi dan kebebasan yang bermartabat dan bermoral? Atau Untuk kepentingan strategis penguasaan sistem politik dan sumber daya strategis negara Timur Tengah? Adakah kejujuran yang terkandung dalam resolusi PBB selama ini, sehingga tidak mampu mencegah pertumpahan darah masyarakat sipil tak berdosa? Konspirasi AS Bagi pihak yang percaya teori konspirasi, dapat dipastikan bahwa serangkaian gejolak politik dan perang Libya tak ubahnya seperti suatu konspirasi. Pemain konspirasi dituduhkan kepada pihak asing, terutama AS, yang sangat berkepentingan atas kestabilan pasokan minyak di Timur Tengah dan keamanan Israel, sebagai domain utama politik AS. Kepentingan minyak dan keamanan Israel tentunya harus dijaga dengan baik dan sustainable, jika perlu digunakan cara‐cara keji seperti fitnah, propaganda, dan invasi militer. Teknologi dan kapabilitas militer kelas satu AS, bergabung dengan sekutu dekatnya seperti Inggris, Spanyol, Australia, dan terakhir Prancis, semakin menyulitkan dunia dan berpotensi membawa kita pada perang nuklir berkepanjangan. Ibarat ledakan, serangan ke Libya adalah pemicu ledakan‐ledakan berikutnya di kemudian hari. Setiap serangan pasti memiliki tujuan, begitu pula konspirasi. Gelombang revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara bukanlah sesuatu yang terjadi secara dadakan atau spontan. Berbagai pihak yang sangat percaya bahwa ini adalah konspirasi Barat, menyatakan bahwa AS dan sekutunya sengaja mendesain rangkaian aksi‐aksi anti pemerintah. Peralihan sistem politik dan kekuasaan, dari tirani ke demokrasi, status quo ke pihak oposisi, dinasti penguasa ke pihak yang dapat disetir oleh AS dan sekutu, adalah tujuan utama. Praktik konspirasi memunculkan rasa tahu sama tahu dan melibatkan kerjasama strategis antara pihak yang diuntungkan dari jatuhnya rezim dengan pihak Barat sebagai polisi dunia yang berlindung dibawah alasan “penegakan demokrasi, kedamaian, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. AS juga telah terlibat ratusan konspirasi penting dunia. Pengakuan John Perkins, dalam serial “Economic Hitman” menyadarkan dunia betapa dinas intellijen AS, yaitu CIA, seenaknya mengacak‐acak sistem perpolitikan, kedaulatan, bahkan mengatur pemberontakan dan penggulingan kekuasaan suatu negara. Dalam menguasai dan melebarkan pengaruhnya di belahan dunia lain, AS memiliki tiga pendekatan utama. Pertama, melalui program yang disebut “mafia ekonomi”, dimana para ekonom‐ekonom AS terlibat dalam usaha pembangkrutan negara, melalui cara‐cara langsung seperti terlibat dalam mempengaruhi proses negosiasi penggelembungan kontrak dan pengucuran hutang melalui lembaga‐lembaga yang tidak lain adalah representasi AS, seperti World Bank dan IMF atau keterlibatan secara tidak langsung, melalui “pembaptisan” ekonom‐ekonom dan pengambil kebijakan negara‐negara berkembang dengan tujuan melakukan “cuci otak”, sampai pada akhirnya para ekonom tersebut berhasil melakukan makelarisasi dan pembangkrutan negara, baik disadari atau tidak. Program mafia ekonomi inilah yang telah menjerat sebagian besar negara pada rantai kemiskinan tak berujung, kesenjangan tingkat pendidikan yang tinggi, serta kebodohan absolut mayoriats rakyatnya sebagai dampak bersatunya kejahatan korporatokrasi dan kleptokrasi secara bersamaan, karena sentral kekuasaan dipegang oleh kaum elite minoritas yang memiliki akses politik penting dan kekuatan uang, untuk menguasai sumber strategis kekayaan negara dalam upayanya memperkaya diri. Dengan pola ini (kombinasi korporatokrasi dan kleptokrasi) negara sudah pasti dibangkrutkan pelahan tapi pasti, ketika bangkrut dan terlilit hutang dapat dipastikan bahwa negara tersebut telah ada digenggam dan relatif mudah dikendalikan. Indonesia, adalah contoh terbaik dalam hal ini. Terlihat betapa kebijakan publik kita telah dirusak bukan saja oleh Barat, melainkan oleh ekonom kita sendiri. Kebijakan pembangunan tidak tepat sasaran, intervensi kontrak minyak dan tambang mineral, makelarisasi hutang dan proyek‐proyek BUMN, kebobrokan institusi dan lembaga negara, praktik suap merajalela bahkan di entitas yang dianggap malaikat sekalipun, deregulasi perbankan yang tidak ditinjau ulang (catat: Kepemilikan asing maksimal 99%, alias jauh lebih liberal dibanding AS yang hanya memperbolehkan maksimal 30%), divestasi merugikan pasca restrukturisasi, privatisasi BUMN, serta penguasaan sektor‐sektor strategis seperti pertambangan, telekomunikasi, perbankan, dan kini kesehatan, adalah rangkaian paket perluasan pengaruh dan hasil karya kerja keras “mafia ekonomi” dalam suatu sistem konspirasi di Indonesia. Hasilnya, kita bukan hanya terlilit jumlah hutang yang sedemikian besar, tetapi juga memiliki ketergantungan sangat tinggi atas aspek dan ranah‐ranah Barat, seperti film, makanan, budaya, lifestyle, dan pola konsumtif lainnya. Meskipun hal tersebut memang tidak dapat dihindari dengan adanya globalisasi, namun mengikuti globalisasi tanpa aturan adalah suatu kecelakaan bagi kelangsungan integritas dan moralitas bangsa ini. Kedua, ketika upaya pendekatan “mafia ekonomi” menemui jalan buntu, maka AS menggunakan cara lain yaitu jackal, yaitu suatu upaya pembunuhan pemimpin negara secara terang‐terangan atau tersembunyi tanpa meninggalkan jejak faktual. Upaya jackal dilakukan umumnya ketika pemimpin suatu negara dan aparatur pemerintahannya tidak dapat diintervensi dan tidak mudah untuk tunduk dan sepakat pada aturan‐aturan yang dibuat oleh AS. Pembunuhan keji Anwar Sadat di Mesir, dalam parade militer, yang akhirnya menaikkan Husni Mubarak ke tampuk pimpinan, dan pembunuhan Omar Torrijos dalam kecelakaan pesawat mengenaskan, berbagai upaya pembunuhan proklamator RI. Ketiga, ketika cara “mafia ekonomi” dan “jackal” menemui jalan buntu, maka AS melancarkan pendekatan strategi terakhir yaitu perang. Dalam memutuskan perang, tentunya mereka terlebih dahulu melakukan perhitungan matang, khususnya terkait kalkulasi biaya perang dan manfaat yang ditimbulkan setelah perang (cost‐benefit calculation). Mereka juga mempertimbangkan kekuatan politik dalam negeri dan konstelasi kekuatan politik global, termasuk dalam upaya mereka bagaimana perang tersebut dapat mendatangkan manfaat tidak hanya bagi AS sendiri melainkan kepentingan yang dibelanya, seperti Israel dan para sekutu terdekat AS. Perang terhadap rezim Saddam Hussein di Irak, Perang Vietnam, Afganistan, adalah bukti bahwa AS tidak segan‐segan memporakporandakan suatu negara dengan bom‐bom nuklir miliknya, membiarkan nyawa masyarakat sipil melayang, serta melegalisasi upaya pertumpahan darah yang lebih deras. Dengan perang yang dimenangi, mereka memperoleh berbagai keuntungan masa depan, seperti pengaruh politik yang lebih luas, keuntungan finansial melalui kerjasama dan penguasaan aset strategis suatu negara, sampai perusakan perlahan budaya dan adopsi “westernisasi” yang menguntungkan mereka. Serangan ke Libya memiliki pola relatif berbeda dengan serangan ke Irak dan Afganistan, karena tidak adanya mobilisasi angkatan darat AS dan sekutu. Serangan ini juga tidak ditujukan untuk menjatuhkan rezim Khadafy. Namun, serangan tersebut terbukti telah memperkuat basis pertahanan pihak opisisi dan perlahan tapi pasti akan melumpuhkan basis kekuatan pasukan Khadafy, dan kini alurnya mudah ditebak: Penggulingan kekuasaan secara tidak langsung. Selain tiga pendekatan strategi yang dieksplorasi diatas, AS juga lihai memainkan strategi propaganda, berstandar ganda, dan melakukan negosiasi‐negosiasi melalui komunikasi intensif dan pembentukan citra positif sebagai negara adidaya, bermoral melindungi kebebasan, dan menjunjung tinggi HAM, sehingga membentuk persepsi khalayak bahwa hampir semua negara tergantung dan diuntungkan atas kehadirannya. AS, juga lihai meneriakkan slogan demokrasi, sebagai upaya pembenaran atas berbagai langkahnya yang tak kenal kemanusiaan. Mereka bersuara keras tentang demokrasi di seberang sana, namun di sisi lain perilaku mereka bahkan telah mengkhianati semangat utama demokrasi yang menegakkan moral sama tinggi dengan kebebasan bertindak. Perang untuk minyak Ketimbang melabeli perang ini sebagai upaya penegakkan demokrasi dan stabilisasi politik Timur Tengah dan Afrika Utara, penulis dan mungkin juga lainnya lebih nyaman untuk melabeli perang ini sebagai “perang untuk minyak”, dimana serangan ke Libya menjadi titik awal invasi AS dan sekutu untuk melebarkan pengaruhnya, mensukseskan program “New Middle East”, dan terutama menguasai kepentingan minyak di Timur Tengah. Terlepas dari alasan apa yang mendasari operasi ini (penegakkan larang perang atau perjuangan menciptakan demokrasi) dan jenis perang seperti apakah yang nantinya akan terjadi (apakah perang asimetris, konvensional, atau non‐konvensional) yang jelas ada jutaan minyak diperebutkan disana (catat: produksi minyak Libya mencapai 1,65 juta barel per hari), dan setelah sukses menginvasi Irak (meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya karena ketidakstabilan politik yang masih terjadi), AS dan sekutunya rupanya terinspirasi oleh tokoh Jengis Khan, sehingga berkehendak membentuk imperialisme baru, khususnya penguasaan atas minyak. Melalui strategi masuk (entry strategy) yang “cantik” di Mesir dan Tunisia (yang notabene adalah sekutu terdekat mereka setelah Saudi Arabia), serangan ke Libya adalah intermediasi penting untuk serangan yang sangat penting, yaitu Teheran, Iran. Selain karena Iran dianggap mengancam keamanan Israel di Timur Tengah, rangsangan utama invasi ke Teheran adalah adanya 4,03 juta barrel per hari dan Iran kini tercatat sebagai produsen minyak nomor 3 setelah Saudi Arabia dan Kanada, Sejalan dengan Alan Greenspan, yang menyatakan bahwa sebagian besar alasan perang Irak adalah karena minyak, semua pihak termasuk rakyat AS sekalipun kini menentang garis kebijakan Washington dan sekutunya. Kebijakan yang bukan hanya menimbulkan hutang lebih dalam bagi rakyat AS, melainkan juga mengancam keselamatan warga negara AS dan sekutunya di negara lain. Kebijakan yang juga menyiratkan kepada kita bahwa AS tetaplah AS, siapapun pemimpinnya, entah Partai Republik atau Demokrat, etnis minoritas atau mayoritas, murah senyum atau berpenampilan dingin, mereka tetap berada pada garis kebijakan yang tidak berubah (unchangeable). Solusi dunia internasional Reaksi dunia beragam tentang operasi Libya ini. Dua dari lima anggota tetap PBB menyatakan abstain dan sisanya tiga anggota tetap –AS, Inggris, dan Prancis menyetujui. China dan Rusia memilih abstain dan menyatakan memilih cara‐cara damai untuk menyelesaikan krisis Libya. Terakhir, perselisihan juga terjadi diantara dua pemimpin Rusia, Presiden Dimitry Medvedev mengecam komentar Vladimir Putin mengenai konflik Libya yang dianggapnya “mengingatkan abad pertengahan akan perang salib” dan berujar bahwa “semua akan menjadi lebih buruk dibandingkan apa yang terjadi sekarang dan setiap orang harus mengingat itu”, artinya Medvedev mengingatkan bahwa upaya “provokasi” harus dihindari. Perseteruan dua serangkai inipun juga sempat menjadi pembicaraan berbagai media, dimana keretakan dan komentar saling berlawanan baru pertama kali terlihat. Meskipun sulit untuk menduga bahwa Rusia kini telah terpecah menjadi dua kubu, yang jelas jawaban Medvedev secara tegas justru menekankan pentingnya mempertahankan dua serangkai dan tidak terpengaruh oleh isu kampanye dan persaingan politik dalam pemilu. China, bahkan terlihat seperti paranoid, melihat perlawanan rakyat di Tunisia, Mesir, dan Libya, pemerintah China menekan warga minoritas etnis Uighur, aparat keamanan China telah membuat kota‐kota bagian barat China, seperti Kashgar dan Urumqi, seperti zona perang. Penggeledahan dan penahanan etnis tersebut telah menunjukkan bahwa China bereaksi keras dan tidak membiarkan satu percikan api pun menyala yang dapat mengancam keamanan dalam negerinya. Selain Rusia dan China, kalangan internasional khususnya negara‐negara yang tergabung dalam forum perdamaian perserikatan bangsa‐bangsa (PBB) harus bersikap tegas dan secara simultan menyerukan penghentian perang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak berkepanjangan. Ratusan US dollar yang digelontorkan AS dan sekutunya juga memunculkan kekhawatiran akan timbulnya dampak lain seperti gangguan keseimbangan ekonomi dunia, karena disaat bersamaan dunia juga dihadapkan oleh krisis nuklir Jepang (catat: Jepang memiliki besaran ekonomi nomor 3 dunia), peningkatan harga minyak dunia, persengketaan semenanjung Korea, dan kondisi ekonomi yang belum stabil di AS dan Eropa. Penulis khawatir prediksi Nouriel Roubini, dalam bukunya Crises Economics (2010), yang menyatakan bahwa krisis ekonomi dunia akan berbentuk W (double dip crises), dimana pasca pemulihan dunia akan kembali terjerembab dalam krisis ekonomi, akan benar‐benar terjadi. Pemicunya adalah pelebaran defisit anggaran karena perang. Oleh karenanya, dunia internasional melalui komunitas strategis harus bersama mencegah pertumpahan darah yang lebih banyak dan pergolakan politik yang diikuti pergolakan ekonomi dan sosial, serta melakukan penindakan tegas atas upaya negara manapun yang ingin menodai dan merusak isi piagam perdamaian dunia hak asasi manusia (HAM) tanpa pandang bulu. Solusi setidaknya menitiberatkan dua hal penting, yaitu kedudukan yang sama di mata internasional bagi suatu negara tanpa terkecuali dan adanya jaminan bagi setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri, mempertahankan kedaulatan, dan melakukan pergaulan politik secara mandiri, bebas intervensi, dan penuh tanggung jawab. Namun, jika pembentukan solusi hanya terlihat ideal pada secarik kertas kesepakatan, artinya tidak diimplementasikan secara konsisten dan bias ke salah satu pihak terkuat, maka pembentukan solusi tersebut tidak akan memberikan hasil apapun selain ketidakseimbangan politik, krisis ekonomi berkelanjutan, dan kemelaratan tak berujung. Dalam dunia yang telah terkoneksi secara kompleks sebagai cerminan globalisasi, tentunya kita tidak dapat menghindari bahwa kejadian di satu titik dapat dengan cepat menjalar dan menimbulkan dampak ke titik lainnya, tanpa terkecuali. Globalisasi adalah suatu keniscayaan, pilihannya “ikut” atau “tidak”. Kini rasanya tidak ada satu negarapun yang dapat menghindarnya dan secara sukarela atau terpaksa harus mengikuti arus globalisasi. Meminjam istilah Charles Darwin dalam survival for the fittest bahwa bukanlah makhluk terkuat dan terbesar yang akan bertahan, melainkan makhluk yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya, maka dalam lingkup global, kepandaian suatu negara dalam melakukan adaptasi berperan penting bagi tercapainya kemajuan negara tersebut dan dari sinilah kedewasaan kita sebagai bangsa benar‐benar diuji. Bagi Indonesia, perang Libya dan perubahan peta politik di Timur Tengah dan Afrika Utara ini memberikan banyak pelajaran, khususnya terkait aspek penting seperti kedaulatan dan ketahanan militer, yang dapat dijadikan refleksi seberapa mampu kita bertahan dan beradaptasi dalam pergaulan global dengan tetap menjujung tinggi integritas, mandiri, dan tidak kehilangan identitasnya. Indonesia juga selayaknya mampu berdaulat secara utuh, di bidang ketahanan militer, pangan, energi, dan sosial budaya, tidak ada ruang untuk melakukan “plagiarisme” Barat, tidak ada tempat yang strategis untuk budaya barat, dan tidak ada kesempatan yang lebih berarti selain kesempatan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh penghidupan, pendidikan, dan pekerjaan lebih layak, bukan hanya kesempatan bagi anak Presiden, Pengusaha, dan Pejabat Negara lainnya. Memperhatikan rakyat dengan lebih baik, menjunjung tinggi semangat demokrasi bermoral, dan menunjukkan pengabdian dalam bentuk karya nyata bagi kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, perang memberikan kita pelajaran berharga bahwa hanya ada satu kepentingan utama dan abadi di dunia ini, yaitu kepentingan atas uang. Keberadaan uang telah mengubah perilaku dan peradaban manusia pada umumnya, dimana faktor‐faktor penting lainnya, seperti birokrasi, kesepakatan perdamaian, dan ayat suci agama sekalipun menjadi tidak berarti dan relevan ketika kekuatan uang merajalela. Jika dibiarkan seperti ini, berarti kita semua telah membiarkan dunia ini tenggelam kepada kebobrokan moral yang sangat dan sebagai bangsa Indonesia kita seakan telah membiarkan bangsa ini terkubur dalam catatan sejarah buruk dimana kita tidak memiliki kemandirian dan harga diri sebagai bangsa besar. Terakhir, jika perang ini dibiarkan terus berlanjut, penulis teringat akan operasi Barbarosa (suatu operasi Jerman dipimpin Hitler untuk menguasai Rusia yang kala itu dipimpin oleh Stalin), dimana operasi tersebut menjadi titik awal meletusnya perang dunia ke II. Semoga kita mampu mencegahnya sebelum Tuhan marah kepada kita semua karena telah membentuk dunia tanpa moral. Penulis: Aji Jaya Bintara, MSM Founder of Strategic Development Institute (SDI)