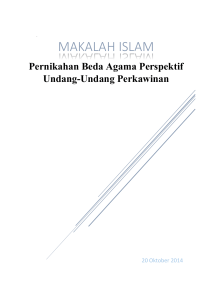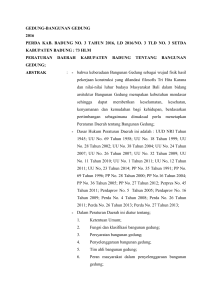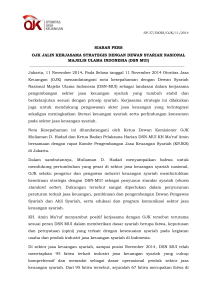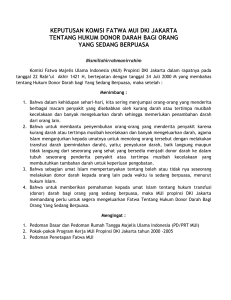EMPAT Konstruksi Baru Kebebasan Beragama
advertisement

!" #$ #% &' ($)*+, --.$//"#012/030+ 4$5"6$$ !! "# ! " " # "$% ! & $"$ $ !%% & ! ' ( ')*+ # , !& $ "$ $"$ ! $ ! ( $ "$ -.! %% ! '/ ( /00+ 11 '2! "-" "$ % # #! & # # ! - $ #! "" - !( &3(! $! ! ! " " ! # #! !!"#$%&' (#$%)#$#*+, -#$#&#$#)#%,+. / "!!"#%,&#%,)#%#+# $ "!!"#$%&'(#%#) *+/ 0 ''- /$ 1'' $/ 011''$/ 12' '' $# ''34 '. 011. 1''' 4'.$ / ' 4 '.5 )''1 67 !8)''1 7)' . 0 2'"1 ''# #5 -172 1''// 0 7-'1 '''4 '/ '-9'' :''$$ 11 ;9'':' %5 / 124 4 41'': '4%# " 1'' ' 4'.. SATU Hak Asasi Manusia Sebagai sebuah konsep, HAM telah memiliki akar sejarah yang panjang, termasuk dalam hal ini adalah ideologi1 universalisme dan partikularisme berkaitan dengan budaya dan kemanusiaan itu sendiri. Perdebatan dalam rentang pemikiran HAM ini merupakan salah satu akar perdebatan yang cukup panjang terkait kebebasan 1 Terma ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Idea berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Secara prinsipil terdapat tiga arti utama dari istilah ideologi. Pertama, ideologi sebagai kesadaran palsu. Dalam arti ini, ideologi biasanya teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Kedua, ideologi dalam arti netral. Dalam pengertian ini, ideologi dipahami sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilainilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Ketiga, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Dalam pengertian ini, ideologi umumnya digunakan dalam dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan-persoalan moral-etis, asumsiJimly Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, Makalah, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 1-2. Telusuri lebih lanjut dalam, Franz Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Jakarta, 1992, hlm. 230. Bandingkan dengan, Martin Hewitt, Welfare, Ideology, and Need: Developing Perspectives on the Welfare State, Harvester Wheatsheaf, Maryland, 1992, hlm. 1 dan 8. Sementara yang dimaksud dengan ideologi dalam buku ini adalah dalam bingkai pengertian pertama, yakni sebagai kesadaran palsu. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 1 beragama. Oleh karena itu, agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan radikal, dalam bab awal ini penulis mengajak pembaca untuk menelisik akar sejarah HAM berkaitan dengan konsep kebebasan beragama. Bab ini akan dimulai dengan sejarah HAM, HAM di berbagai konstitusi yang pernah kita gunakan sampai hak kebebasan beragama dalam berbagai peraturan yang pernah ada. A. Potret HAM dalam Lintasan Sejarah dan Pemikiran HAM merupakan terjemahan dari istilah menselijkegrondrechten dalam bahasa Belanda dan fundamental human rights dalam bahasa Inggris.2 Pengertian mengenai istilah HAM sangat beragam. Wolhof menjelaskan, ”Manusia mempunyai hak-hak yang sifatnya kodrat. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga, dan tidak dapat dipindahtangankan dari manusia satu ke manusia lain.”3 Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa hak asasi ini adalah sejumlah hak yang mengakar dalam tabiat kodrati setiap pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.4 HAM juga dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut: a. Soetandyo Wignyosoebroto: “HAM adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologis sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan legal kepada setiap manusia itu untuk kebebasan dari setiap bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang 2 Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia,UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 15. 3 Ibid, hlm. 16. 4 Harum Pudjiarto, Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 26. 2 Dr. Rohidin, M. Ag menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.”5 b. Arief Budiman: “HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dan HAM.”6 c. Majda El Muhtaj: “HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia dan melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi intrinsiknya.”7 d. Donelly: “Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang universal, bukan keuntungan, tanggungjawab, keistimewaan, atau beberapa bentuk pemberian lainnya tetapi diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.”8 e. Franz-Magnis Suseno: “Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia, berdasarkan harkat yang diterimanya dari Sang Pencipta, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.”9 dikutip Harum Pudjiarto, memberi batasan HAM sebagai berikut: 5 Dikutip dari Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, loc.cit. 6 Harum Pudjiarto, op. cit., hlm. 25. 7 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM:Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 14. 8 Jack Donnelly, “Human Right and Human Dignity: An Anallytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Right”, The American Political Science Review, Vol. 76, No. 2., dalam http://links.jstor.org, (Diakses pada tanggal 20 Desember 2010). 9 Franz Magniz-Suseno, Rechtsstaat, Bukan Machsstaat, dalam Mencari Makna Kebangsaan, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 58. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 3 “Hak itu ditemukan dalam hakikat manusia, demi kemanusiaannya semua orang satu persatu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapa pun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri, karena hak itu bukan sekadar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas berkesadaran moral). Manusia makhluk ciptaan Tuhan merupakan makhluk ciptaan tertinggi daripada makhluk ciptaan lainnya, yang di dalam hidupnya manusia dikaruniai Tuhan berupa hak hidup yang merupakan hak asasi paling pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan.”10 Konsep HAM secara alamiah bisa berasal dari berbagai sumber baik berupa ajaran agama, budaya, atau sifat dasar suatu masyarakat tertentu. Jika merujuk kepada sejarahnya, dapat kita lihat bahwa HAM internasional banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat di negara-negara Barat yang lebih mengedepankan hak-hak sipil dan politik dari individu-individu di dalam suatu negara. Hakhak tersebut cenderung membatasi kekuasaan negara terhadap masyarakatnya; hak individu untuk berekspresi, beragama, partai politik tertentu atau ikut serta di dalam sistem pemerintah, misalnya. Penggunaan kata “asasi” dalam istilah HAM, sebagaimana diungkapkan oleh Padmo Wahjono, menimbulkan kesan bahwa hak-hak tersebut termasuk (kewajiban-kewajiban) bersifat mutlak adanya. Adanya hak-hak tersebut merupakan identitas yang tidak terpisahkan dari keberadaan dirinya sebagai manusia.11 Pada akhirnya, karena sifat HAM adalah universal, maka hak tersebut tidak saja harus diberikan kepada semua individu, melainkan juga ada kewajiban universal bagi seluruh individu untuk memperlakukan dengan baik individu-individu yang kehilangan haknya. Kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun 10 Harum Pudjiarto, op. Cit., hlm. 26. 11 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 33. 4 Dr. Rohidin, M. Ag seseorang, melainkan harus dilaksanakan dengan persamaan hak bagi sesama manusia.12 Pemikiran tentang HAM pada dasarnya telah ada sejak era Yunani kuno. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran Solon sebagai pencetus “konsepsi hak” yang kemudian diadopsi oleh hukum modern.13 Konsepsi tersebut telah mengakhiri era aristokratis dengan diserahkannya kekuasaan kepada sekelompok kecil orang yang kira-kira terdiri dari seribu orang laki-laki kaya. Solon juga memperkenalkan hak untuk banding kepada pertemuan Majelis (Ekklesia). Dalam sistem ini, semua warga negara yang dipandang baik dan hadir di Phonyx berhak untuk memberikan suaranya, tetapi praktik demokrasi ini belum memasukkan kelompok perempuan, budak, orang asing, dan orang-orang yang tidak bisa membuktikan dirinya anak warga negara. Bahkan, perempuan tidak diperbolehkan untuk pergi ke tempat-tempat umum. Oleh karena itu, keadaan sosio-politik masyarakat Yunani masa itu belum bisa dikatakan telah memenuhi standar “demokrasi modern”.14 Dalam tradisi Yunani, pasca-Alexander the Great, kaitannya dengan persoalan HAM setidaknya masih ada dua aliran utama, Stoik dan Epikurean. Kelompok Stoik menekankan pentingnya kemuliaan (virtue), sebagai tandingan dari kenikmatan duniawi (hedonis). Ajaran Stoik dapat dipandang sebagai ajaran yang paling 12 Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010. hlm. 80. 13 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual, IMR Press, Cianjur, 2010, hlm. 98. 14 Seiring dengan menguatnya individualisme, peran perempuan dan budak juga membaik. Ajaran kaum Stoik menolak pandangan inferioritas moral dan intelektual kaum perempuan. Kaum Stoik merupakan salah satu Yunani. Mereka disebut juga dengan Stoicin atau Stoa. Disebut demikian karena pelajaran diberikan di lorong bertonggak dan bertembok (stoa) yang disampaikan oleh Zeno (336-264 SM). Zeno memberi gambaran cukup luas tentang hukum alam yang bersifat universal. Akal merupakan pusat kendali untuk mengungkapkan dan mengetahui segala hal termasuk HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Hukum (Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 2. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 5 kosmopolitan yang dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu. Zeno sebagai perintisnya merangkul persaudaraan umat manusia sebagai ajaran dasarnya. Maka dalam ajaran Stoik semua manusia dipandang sederajat. Tidak ada batas-batas yang berupa budak, status sosial, ataupun hal-hal lainnya yang dijadikan sebagai dasar superioritas satu bangsa terhadap yang lainnya, sehingga dalam pandangannya manusia dimungkinkan untuk membentuk kerajaan dunia.15 Stoa atau kelompok Stoik ini, alam semesta diatur oleh logika/ilmu tentang berpikir (logos/ prinsip rasional), di mana umat manusia memilikinya. Karena itu, manusia akan menaati hukum alam dan tidak mungkin melanggarnya, selama ia melakukan tindakan-tindakan di bawah kontrol akal atau nalar yang berarti mengikuti kehendak alami.16 Sementara dalam pandangan kelompok Epikurean berlaku hal sebaliknya. Ajaran kelompok ini menyatakan bahwa kenikmatan badaniah merupakan tujuan utama untuk dicapai dalam menjalani kehidupan, kebaikan bagi masyarakat tidak mendapatkan tempat yang penting, tetapi kepentingan individu yang harus menjadi prioritas. Dalam bermasyarakat kepentingan individu dibatasi oleh undang-undang. Penyusunan undang-undang harus mendapat persetujuan tiap individu, sehingga tidak merugikan kepentingan individu itu sendiri. Konsep persetujuan dan kesepakatan warga masyarakat yang dikembangkan oleh Epicurus (341-271 SM) menjadi embrio teori perjanjian masyarakat selanjutnya.17 Pada era selanjutnya, Romawi sebagai pewaris kebudayaan Helenisme secara langsung juga menerima konsep hukum alam sebagai bagian peradabannya. Konsep philantropia/philantropus Yunani terbawa pula menjadi konsep humanitas Romana. Konsep humanitas ini kemudian menjadi payung bagi nilai moral, termasuk 15 Lihat, Ibid., hlm. 102-103. 16 op. cit., hlm. 2. 17 Embrio perjanjian masyarakat tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Marsillius (1270-1340), yang menekankan pentingnya peran individu. Renaisans, Thomas Hobbes (1588-1679) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Lihat, A. op. cit., hlm. 3-4. Bandingkan dengan Pranoto Iskandar, op. cit., hlm. 102-103. 6 Dr. Rohidin, M. Ag dan pietas. Karena hal tersebut bangsa Romawi dapat menerima moralitas universalisme, selaku cikal bakal HAM. Pengaruh tradisi hukum alam ini sangat memengaruhi konsepsi hukum yang diterapkan di Romawi. Marcus Tullius Cicero dalam the Laws menyatakan bahwa “Hukum adalah budi tertinggi, termuat dalam alam, yang memerintah apa yang harus dilakukan dan yang dilarang. Budi ini, yang tertanam kuat dan berkembang penuh dalam pikiran manusia, adalah hukum”. Dalam buku tersebut ia mendasarkan argumennya pada hukum alam dan hakhak alamiah manusia. Lebih jauh ia mendukung akan ide “kesatuan warga negara selayaknya sebuah kota”. Sumbangan yang cukup menarik berkaitan dengan konsep HAM diberikan oleh Cicero dalam karyanya de Legibus. Dalam karya tersebut Cicero berbicara mengenai hubungan antara hukum alam dan hukum positif, ia berkesimpulan hukum positif harus didasarkan pada hukum alam. Jadi, ketika hukum positif bertentangan dengan hukum alam maka yang pertama haruslah batal. Argumentasi ini memberikan sumbangan yang cukup besar bagi HAM mengingat pada masa itu HAM identik dengan hak-hak alamiah.18 Pasca-runtuhnya imperium Romawi Barat, Gereja Kristen mulai memegang kendali. Meskipun begitu pengaruh dari Romawi masih berlanjut, seperti dipertahankannya bahasa Latin. Hal tersebut, secara langsung atau tidak, memberi jalan bagi diadopsinya tradisi hukum Romawi oleh para rohaniawan Gereja.19 Dalam tataran praktis penerapan hukum Romawi dalam bidang 18 Ibid., hlm. 106-107. 19 Misal St. Augustine yang melakukan “Kristenisasi” terhadap pemikiran Plato dalam Republic. Di samping itu, ia juga mengembangkan doktrin “perang adil”, di mana dalam doktrin tersebut dapat dijumpai penekanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Sementara Thomas Aquinas berpendapat bahwa perang yang didasarkan pada nafsu pribadi semata adalah dosa. Di berbagai daerah Jerman, seperti Kerajaan Visigoth dan Burgundi, hukum Romawi masih diterapkan bagi warga non-Jerman. Bahkan Alaric II, Raja Visigoth, mengadopsi Lex Romana Wisighothorum, yang memuat ringkasan dan komentar atas Codex Theodosianus dan berbagai sumber hukum Romawi lainnya. Hal tersebut oleh Zwiegert dan Kort dipandang sebagai sumbangan bagi keberlangsungan hukum Romawi. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 7 perdata, perkawinan, dan pewarisan masih dipertahankan oleh gereja. Konversi kepada agama Kristen oleh para penduduk Romawi memberikan konsekuensi yang cukup luas. Pengaruh utamanya adalah dikedepankannya konsep moralitas dalam segala aspek kehidupan. Keyakinan atas moralitas pun mendapat sambutan dari masyarakat umum yang telah putus asa terhadap pejabatpejabat yang dikenal korup. Atas dasar ini pula Augustinus mendorong pemerintah supaya campur tangan secara langsung dalam persoalan pemberian sumbangan bagi kaum miskin karena hanya mendasarkan rasa kasihan dianggap tidak cukup. Ia juga berpandangan praktik perbudakan adalah hal yang salah. Gereja kuno juga mengutuk hukuman mati dan tindak penyiksaan dalam proses hukum. Ini sangat tegas didukung oleh Paus Innocent I.20 Pada abad ke-11 dalam bidang pemikiran hukum terdapat pertentangan antara kaum Legist dan Kanonist. Kaum Legist sangat mengagumi hukum-hukum peninggalan Romawi, sedangkan kaum Kanonist merupakan kelompok yang condong pada ajaran-ajaran Paus. Pertentangan dua kelompok ini meliputi masalah besar yakni hubungan antara kekuasaan duniawi dan Ilahi.21 Pada masa Pemerintahan Papal, bangunan kenegaraan di Eropa yang didasarkan pada Reformasi Gregorian, khususnya Diktat Gregori 1075, menjadikan kekuasaan pemerintahan ada di Gereja. Paus adalah kepala gereja; orang-orang Kristen lainnya adalah Gereja. Paus memiliki kewenangan penuh (plenitudo auctoritatis) dan kekuasaan penuh (plenitudo potestatis). Meskipun pada awalnya kewenangan Paus bersifat terbatas tetapi sejak Gregori VII, Paus menjadi pembuat hukum tertinggi, administrator tertinggi, dan hakim tertinggi. Ia dapat membuat hukum, menerapkan pajak dan menghukum pelaku kejahatan.22 20 Ibid., hlm. 111. 21 Ibid., hlm. 114-115. 22 Konstruksi kenegaraan di atas tidak berlaku bagi bangsa Germania. Bangsa ini memiliki keyakinan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hal yang penting. Ini dibuktikan dengan menjadikan individu sebagai satuan, bukan komunitas. Walaupun kekuasaan negara terpusat sebagai akibat dari pengaruh 8 Dr. Rohidin, M. Ag Pada abad dua belas dan tiga belas mulai terdapat kecenderungan baru untuk mengganti majelis dengan dewan. Para anggota dipilih untuk masa tugas beberapa tahun, tetapi kemudian terjadi kooptasi yang mengubahnya menjadi pemerintahan aristokrat.23 Pada masa ini terdapat pemikir yang sangat berpengaruh Thomas Aquinas. Dalam teori hukum kodratinya, Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.24 Aquinas menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat memperkembangkan kepribadiannya dengan mempergunakan rasio yang diberikan oleh alam kepadanya. Sebagai konsekuensi logis, maka diperlukan kestabilan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, karena itulah diperlukan penguasa. Manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bermasyarakat untuk mencapai keinginannya, untuk itu dibutuhkan pemimpin. Jika pemimpin tersebut tidak mengejar dari Romawi, mereka memiliki badan-badan perwakilan. Badan-badan perwakilan inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi parlemen Inggris. Raja merupakan hasil dari proses pemilihan dan hukum dipandang sebagai pernyataan kesadaran mereka. Ibid., hlm. 115. 23 Menurut Berman pada akhir abad kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas terdapat sebuah komunitas politik yang memiliki delapan karakteristik. Pertama, Raja tidak lagi sebagai pemimpin spiritual tertinggi, tetapi sebatas sebagai pemimpin sekuler, dalam bidang spiritual ia merupakan bawahan dari Gereja Roma, yang dikepalai oleh Paus. Kedua, Raja tidak lagi hanya sebagai orang pertama di antara orang-orang bijak, para ksatria dan para tuan tanah, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk mengatur langsung semua subjeknya yang berada di wilayah kekuasaannya. Ketiga, sebagai penguasa temporal atas subjeknya tugas utama raja adalah menjaga perdamaian dan melakukan keadilan, dalam praktiknya diartikan sebagai untuk mengontrol kekerasan dan mengatur hubungan sebagai akibat dari penguasaan tanah. Keempat, tugastugas tersebut dilakukan oleh sekelompok pejabat kerajaan yang profesional bukan lagi berdasarkan keturunan. Kelima, Raja mendapatkan ketegasan akan hak dan kewajibannya untuk membentuk hukum yang dianggap perlu. Keenam, negara-negara kerajaan memiliki hukumnya sendiri sebagaimana negaranegara kota yang dikepalai walikota atau negara eklesiatik yang dikepalai Paus. Ketujuh, secara teori kekuasaan raja dibatasi oleh berbagai komunitas yang ada di kerajaannya. Kedelapan, kerajaan terdiri dari profesional elit bersifat internasional yang pada umumnya memiliki hubungan darah. Ibid., hlm. 116117. 24 Rhona K. M. Smith (dkk.), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 12. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 9 kepentingan umum maka ia digolongkan zalim. Karena kezaliman dapat merusak masyarakat, maka rakyat memiliki hak untuk menurunkannya bersama-sama. Agar tidak menjadi penguasa zalim, maka ia harus seorang hamba Tuhan yang selalu mengharap anugerah-Nya.25 Sejalan dengan kaum Stoik, Aquinas percaya bahwa hukum manusia (human law), yang bertentangan dengan hukum alam (nature law) bukanlah hukum yang benar.26 Sepanjang sejarah, terutama pada abad ke-17 dan 18, berbagai pemikiran mengenai HAM merupakan hal yang sangat menonjol berbagai instrumen untuk memberi kekuatan hukum. Legitimasi hukum ini berfungsi untuk menjamin keberadaan hak asasitiap individu, melindunginya dari berbagai pelanggaran yang mungkin timbul dari individu lainnya atau bahkan dari pemerintah sendiri. Bermula dari Deklarasi Hari Kemerdekaan (Declaration of Independence Day) pada tanggal 4 Juli 1776, sebagai buah keberhasilan revolusi di Amerika, HAM mendapat perhatian serius. Awal revolusi dipicu oleh tingginya pajak yang dikenakan di Amerika tanpa melibatkan pimpinan di Amerika. Reaksi tersebut disampaikan sebagai pembenaran teori kontrak sosial John Locke antara lain menyatakan: “...bahwa manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan; bahwa untuk menjamin hak-hak tersebut orang-orang mendirikan pemerintahan....”. Perumusan hak asasi manusia tersebut kemudian secara resmi menjadi dasar konstitusi negara Amerika Serikat pada tanggal 4 Maret 1789.27 Keberhasilan revolusi Amerika menjadi salah satu pemicu meletusnya revolusi Prancis. Jika di Amerika revolusi bertujuan untuk memerdekakan negara dari penjajahan Inggris, di Prancis 25 Harum Pudjiarto, op. Cit., hlm. 29. 26 op. Cit., hlm. 2. 27 Pranoto Iskandar, op. Cit. Taufani S. Evandri, op. Cit., hlm. 40. 10 Dr. Rohidin, M. Ag revolusi bertujuan untuk menumbangkan orde lama (ancient regime). Pikiran-pikiran John Locke, Montesqiueu, dan J.J. Rousseau mewarnai dan mempercepat revolusi tersebut. Keberhasilan revolusi Prancis tersebut ditandai dengan diikrarkannya Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) tahun 1789. Isi deklarasi tersebut antara lain menyatakan, “Kebahagiaan sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari hak-hak manusia yang suci, tidak dapat dicabut dan kodrati...”. Sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut adalah kebebasan (liberty), kepemilikan harta (property), keamanan (safety), dan perlawanan terhadap penindasan (resistance to oppresion ).28 Sebagaimana tampak dalam uraian di atas, bahwa HAM pada dasarnya lebih sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan pokok berupa penghargaan dan penghormatan terhadap manusia. Gagasan ini membawa kepada satu tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya tuntutan moral tersebut merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (al) dari tindakan zalim dan semena-mena dari mereka yang kuat dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Konsep HAM tersebut menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Karenanya, sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki 28 op. Cit., hlm. 41. Lihat juga, Majda El Muhtaj, op. Cit., hlm. 9. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 11 sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak berkumpul, serta hak beragama, dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip kesetaraan,29 persamaan, dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Secara umum DUHAM yang diumumkan PBB tahun 1948 mengandung empat hak pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak seperti: hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak, dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, wama kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh lakilaki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak untuk mogok; hak atas pendidikan: hak untuk bebas dari kelaparan. Berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) regional maupun 29 Prinsip ini oleh Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Pranoto, dinyatakan sebagai setiap manusia, semenjak ia dilahirkan, memiliki nilai-nilai yang dengan sendirinya memiliki atribut yang berbeda, terpisah dan obyektif setara. Sebagai konsekuensinya, melalui prinsip ini manusia dituntut untuk tidak menyakiti orang lain hanya demi kesenangan pribadi atau kelompoknya sendiri. Lebih lanjut telusuri dalam, Pranoto Iskandar, op. Cit., hlm. 68. 12 Dr. Rohidin, M. Ag internasional memberikan perlindungan dan pengakuan atas kebebasan beragama tanpa memberi batasan atas apa yang disebut sebagai agama dalam berbagai instrumen HAM ini tidaklah aneh, karena berbagai konstitusi di negara-negara dunia, termasuk Indonesia, memuat hak beragama tetapi tiada memberi batasan pasti apa yang dimaksud dengan agama. Di dalam hukum internasional modern, DUHAM30 adalah instrumen internasional hak asasi manusia pertama yang mengatur tentang kebebasan beragama. Deklarasi tersebut ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi No. 217 A (III) pada 10 Desember 1948.31 Dalam DUHAM sendiri, terdapat empat elemen yang patut untuk dijadikan sebagai penekanan: (i) difokuskan pada hak; (ii) pembatasan hanya diberikan pada hak; (iii) keseimbangan antara hak sipil dan politik di satu pihak dan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya di pihak lain; (iv) letak tanggungjawab bagi implementasi ada di tingkat nasional.32 Dalam instrumen internasional, hak kebebasan beragama diatur pada Pasal 18 DUHAM, yang menyatakan bahwa: 30 “HAM” dan yang menyebutkan secara jelas hak-hak itu yang bersifat universal. Dokumen ini adalah kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh para pihak (negara) yang menjadi anggota PBB. Walaupun demikian, kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum (not legally binding) dan tidak menyediakan perlindungan yang dapat dipaksakan. 31 United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (Online) dalam http://www.un.org/en/documents/udhr/, (Diakses pada 23 Desember 2010). Di dalam hierarki hak asasi manusia internasional, kedudukan Majelis Umum adalah sebagai lembaga tertinggi yang membawahi beberapa lembaga lainnya seperti Dewan HAM, dan Komite HAM. Oleh karena itu, Majelis Umum merupakan lembaga internasional yang mempunyai otoritas resmi untuk menginterpretasikan pasal-pasal yang ada dalam DUHAM. Interpretasi atau penjelasan dari lembaga tersebut juga merupakan sumber hukum di dalam hukum internasional yang harus diperhatikan oleh negara-negara di dalam mengimplementasikan norma-norma yang dikandung di dalam deklarasi tersebut. Lihat, Al-Khanif, op. Cit., hlm. 6. 32 Pranoto Iskandar, op. Cit., hlm. 359. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 13 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.33 Meskipun hak kebebasan beragama telah diatur sebagaimana di atas, namun ternyata tidak mudah mengatur hak tersebut secara komprehensif karena adanya perbedaan perspektif yang sangat besar dari negara-negara yang mendukung dan menentang norma kebebasan beragama. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa konsep dasar HAM dan khususnya hak kebebasan beragama seringkali bertentangan dengan hukum suci agama. Tidak jarang anggapan seperti itu kemudian menjadi pemicu bagi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama yang seringkali berujung pada radikalisme agama yang terjadi di berbagai negara. Pro-kontra terhadap keberadaan Pasal 18 di atas, sebagaimana dilansir Paul Seighart dan dikutip oleh Al-Khanif, sebenarnya telah ada sejak awal rapat pleno Majelis Umum PBB pada saat menyusun draft pasal tersebut. Sampai pada saat ditetapkan, deklarasi tersebut disetujui oleh 48 anggota PBB dengan tidak ada satu pun negara anggota yang menolak. Akan tetapi terdapat 8 negara yang memilih abstain, di antaranya adalah Saudi Arabia. Adapun alasan Saudi Arabia mengambil opsi abstain adalah karena negara tersebut tidak menyetujui aturan yang ada dalam Pasal 18 yang mengatur tentang hak kebebasan beragama.34 Selanjutnya, sebagai upaya untuk lebih mengokohkan kembali penegakan HAM, rumusan tentang hak kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam instrumen DUHAM tersebut 33 Tore Lindholm, et.al (ed.), Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, Leiden: Lorenzen, 2008, hlm. 874. 34 14 Al-Khanif, op. cit. Dr. Rohidin, M. Ag dielaborasi dalam ICCPR.35 Jaminan atas hakkebebasan beragama tersebut ditegaskan, di antaranya dalam Pasal 18 ICCPR yang menyatakan:36 (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. (3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. (4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Ketentuan tentang hak dan kebebasan beragama, baik dalam DUHAM maupun ICCPR, telah menimbulkan beberapa reaksi. 35 ICCPR merupakan salah satu dokumen hukum internasional—bersama dengan ICESCR dan DUHAM—yang membentuk UUhukum internasional. Di samping itu, ICCPR juga merupakan elaborasi lebih lanjut atas berbagai kebebasan dan hak sipil dan politik yang sebelumnya dimuat dalam DUHAM. Bahkan ada yang berpandangan bahwa ICCPR merupakan pernyataan atas kewajiban HAM dalam Piagam. Lihat, Pranoto Iskandar, op. Cit., hlm. 438. Lebih lanjut tentang proses perancangan ICCPR dalam Ibid., hlm. 432-437. 36 http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#art18 (Diakses pada tanggal 27 Desember 2010). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 15 Beberapa negara Islam mengkritik DUHAM, karena dianggap telah gagal untuk mempertimbangkan konteks agama dan budaya dari negara-negara Islam. Pada tahun 1982, perwakilan Iran untuk PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengartikulasikan posisi negaranya mengenai DUHAM, dengan mengatakan bahwa DUHAM merupakan “pemahaman sekuler tentang tradisi Yudeo-Kristen”, yang tidak dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa pelanggaran terhadap hukum Islam.37 18 ICCPR dalam kerangka Pasal 18 DUHAM dengan memasukkan kalimat, “hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau keyakinan”, menghadapi perbedaan pendapat terutama dari negara-negara muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yaman, dan Afghanistan, yang memaksakan pencoretan tentang penafsiran atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, yang mencakup kebebasan mengganti agama atau bahkan menganut pandangan-pandangan ateistik mencuatkan kontroversi. Perbedaan pandangan tersebut akhirnya menimbulkan suatu kompromi untuk mengubah bahasanya menjadi, “hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri”, yang lantas diambil secara bulat tanpa syarat. Rumusan ini didasarkan pada usulan-usulan yang diajukan oleh perwakilan dari Brazil, Filipina, dan Inggis.38 Meskipuntelah terjadi kesepakatanatas teks tentang kebebasan beragama dalam Pasal 18 ICCPR, namun penafsiran atas teks tersebut masih belum menemukan kesamaan pemahaman. Komite HAM mengindikasikan bahwa kebebasan “untuk menganut atau menerima” mencakup kebebasan “untuk mengganti agama atau kepercayaannya yang sedang dianut dengan yang lain atau menganut pandangan-pandangan ateistik, sebagaimana juga mencakup 37 Littman, David. “Universal Human Rights and Human Rights in Islam”, Midstream, February/March 1999, dalam, http://web.archive.org/ web/20060501234759/http://mypage.bluewin.ch/ameland/Islam.html, (Diakses pada tanggal 11 Desember 2010). 38 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Manusia, Jakarta, 2003, hlm. 121-122. 16 Dr. Rohidin, M. Ag kebebasan mempertahankan agama atau kepercayaan seseorang”.39 Penafsiran Komite HAM tersebut tentu saja, berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh negara-negara Muslim. Sebagai kritik atas dominasi HAM Barat yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam, sekaligus sebagai alternatif pandangan tentang hak kebebasan beragama, negara-negara Muslim yang tergabung dalam OKI pada 5 Oktober 1990 mengikrarkan Deklarasi Kairo, sebuah deklarasi tentang kemanusiaan yang sesuai dengan syariah Islam. Kemudian pada 30 Juni 2000, negara-negara Muslim yang menjadi anggota OKIsecara resmi memutuskan untuk mendukung Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam, sebuah dokumen alternatif yang mengatakan orang memiliki “kebebasan dan hak untuk hidup yang bermartabat sesuai dengan syariah Islam”.40 Deklarasi Kairo tahun 1990 tersebut memuat 24 pasal tentang HAM yang dirumuskan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Dalam penerapan dan realitasnya, Deklarasi Kairo memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan DUHAM yang dideklarasikan PBB pada tahun 1948.41 Kebebasan untuk mewujudkan satu agama atau kepercayaan dapat tunduk hanya pada pembatasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak mendasar dan kebebasan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan argumen para sarjana Muslim kontemporer dan beberapa negara Muslim, bahwa yang dilarang oleh hukum Islam bukanlah pindahnya seseorang dari agama itu semata-mata, melainkan penampakannya dalam bentuk yang mengancam keamanan publik, moral masyarakat, dan kebebasan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan pelaksanaan HAM sebagaimana yang tercantum dalam DUHAM Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan:42 39 40 Ibid., hlm. 122. http://en.wikipedia.org/wiki/UDHR, Desember 2010). (Diakses 41 42 pada tanggal 23 op. Cit., hlm. 261. Tore Lindholm, et.al (ed.), op. Cit., hlm. 875. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 17 “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.” B. HAM dalam Konstitusi Negara Hukum Indonesia Dalam memahami hakikat konstitusi terdapat dua pandangan, yaitu pandangan normatif yuridis dan pandangan sosiologis empiris. Pandangan sosiologis empiris beranggapan bahwa konstitusi tidak terbatas pada norma hukum dasar yang tertulis dalam satu kitab, melainkan juga tersebar dalam praktik atau konvensi ketatanegaraan. Sedangkan menurut pandangan normatif yuridis, konstitusi sama dengan UUD, yaitu kumpulan dari norma-norma hukum dasar yang tertulis dan terangkum dalam satu kitab.43 Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Hal tersebut diperlukan oleh rakyat agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Secara substantif, konsensus yang diwujudkan dalam konstitusi meliputi tiga hal:44 1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. 43 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 33. 44 Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional dalam Pluralisme Indonesia dalam, Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi: Tinjauan Konstitusional Praktik Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Publikasi SETARA Institute, Jakarta, 2009, hlm, 47. 18 Dr. Rohidin, M. Ag 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi prosedur-prosedur ketatanegaraan. dan Konstitusi yang berlaku dalam Negara Hukum Indonesia saat ini adalah UUD 1945. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 berisikan norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati yang bersifat mengikat, baik bagi pemerintah maupun bagi setiap warga negara Indonesia di mana pun ia berada.45 Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Republik Indonesia telah memiliki tiga UUD dengan empat kali masa berlaku, yaitu:46 (1) UUD 1945, pertama kali berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat, mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, (3) UUDS 1950, mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, dan (4) UUD 1945, berlaku untuk kedua kalinya sejak tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang. Keempat konstitusi tersebut memiliki karakteristik yang berbedabeda, karena kemunculannya memang dipengaruhi oleh konteks yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, maka secara konseptual juga terjadi perbedaan rumusan materi tentang HAM yang dimuat oleh UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1950. Bahkan UUD 1945 yang berlaku pertama kali dengan UUD 1945 yang berlaku saat ini juga terdapat perbedaan yang disebabkan oleh adanya empat kali perubahan, terhitung sejak tahun 1999 sampai 2002. 45 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD ’45 dalam Paradigma Reformasi, 46 Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat, hlm. 41-42. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 19 Dalam konteks jaminan atas HAM, konstitusi memberikan arti penting bagi terciptanya paradigma negara hukum, sebagai hasil dari proses dialektika demokrasi. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kehendak rakyat harus mampu memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh sebab itu, jaminan konstitusi terhadap HAM merupakan bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.47 1. HAM dalam Periode UUD 1945 (Pemberlakuan I [1945-1949]) Diskursus mengenai HAM dalam sejarah Indonesia telah mencuat sejak proses pembentukan negara Indonesia sedang gencargencarnya diperjuangkan. Perdebatan ini terekam jelas dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang membahas draftKonstitusi Negara Indonesia yang akan dibentuk.48 UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Para tokoh perumus konstitusi tersebut adalah Radjiman Wedyodiningrat, Ki Bagus Hadi Koesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Suryo Hamidjojo, Soetardjo Kartomihardjo, Soepomo, Abdul Kadir, Mohammad Amir (Sumatera), Abdul Abbas (Sumatera), Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Latuharhary, Pudja (Bali), A.H. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Mohammad Hassan (Sumatera).49 47 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 94. 48 BPUPKI atau Dokuritzu Zyunbi Tjoosakai merupakan badan bentukan Jepang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat yang kemudian setelah dibubarkan dibentuk kepanitiaan yang bernama PPKI atau Dokuritzu Zyunbi Iinkai dengan diketuai oleh Soekarno. Lihat, Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, 116-117. 49 20 A. Ubaidillah (dkk.), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Dr. Rohidin, M. Ag Moh. Hatta dalam pembicaraan mengenai dasar negara dalam sidang kedua BPUPKI mengusulkan supaya UUD yang akan dibuat juga memuat tentang adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Usul tersebut disetujui oleh Muh. Yamin. Berbeda dengan mereka, Soekarno dan Soepomo menolak usul tersebut dengan alasan bahwa anggota BPUPKI telah sepakat mengenai asas kekeluargaan yang dianut di dalam negara yang akan dibentuk. Penolakan Soekarno dan Soepomo tersebut didasarkan pada pandangan mereka tentang dasar negara—dalam istilah Soekarno disebut dengan “ ” dan Soepomo memakai istilah “Staatsidee”—yang tidak berlandaskan pada paham liberalisme dan kapitalisme. Menurut pandangan Soekarno, jaminan perlindungan hak warga negara berasal dari revolusi Prancis yang merupakan basis dari paham liberalisme dan individualisme yang telah menyebabkan lahirnya imperialisme dan peperangan antar-manusia. Pandangan ini secara tegas dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945,50 sebagai berikut:51 “…saya minta dan menangis kepada Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya buanglah sama sekali paham individualisme itu. Janganlah dimasukkan dalam UUD kita yang dinamakan ‘rights of citizens’ yang sebagai dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya…”. “….buat apa kita membikin grondwet. Apa gunanya grondwet yang ada berisi, ‘droits e el homme et du citoyen’, itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati. Maka oleh karena itu, jikalau kita betulbetul hendak mendasarkan negara kita kepada paham-paham Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 86. 50 Rhona K. M. Smith, (dkk.), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 238. 51 Dikutip dari Pidato Soekarno pada tanggal 15 Juli 1945 di depan BPUPKI berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM. AB. Kusuma dalam RM. AB. Kusuma (penghimpun), Lahirnya UUD 1945, Badan Penerbit Fak. Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm. 352. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 21 kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotongroyong, dan keadilan sosial, nyahkan tiap-tiap pikiran, tiaptiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Sementara itu, Soepomo dengan semangat yang sama, menolak dimasukkannya hak-hak warga negara dalam UUD dengan mendasarkan pada pandangannya mengenai ide negara integralistik (staatside integralistik), yang menurutnya sesuai dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia.52 Menurut paham tersebut, negara harus bersatu dengan seluruh rakyatnya, sehingga tidak ada pertentangan antara susunan hukum staat dan susunan hukum individu, karena individu tidak lain adalah bagian organik dari staat. Berdasarkan dari hal tersebut, maka hak individu menjadi tidak relevan dalam paham negara integralistik, yang justru relevan adalah kewajiban asasi kepada negara.53Lebih lanjut Soepomo menyatakan: “Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya: ‘Apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu?’. Pandangan Soekarno dan Soepomo tersebut ditentang oleh Moh. Hatta. Penolakan Hatta ini didasari oleh kekhawatiran jika tidak ada hak tersebut dalam UUD akan menjadikan negara yang baru dibentuk menjadi negara kekuasaan. Dalam sidang BPUPKI tersebut secara tegas Hatta menyatakan: 22 52 Subandi Al Marsudi, op. Cit., hlm. 129. 53 Rhona K. M. Smith (dkk.), op. Cit., hlm. 239. Dr. Rohidin, M. Ag “Memang kita harus menentang individualisme... Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi suatu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kapada rakyat dalam UUD yang mengenai hak mengeluarkan suara... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan.” Senada dengan pendapat Moh. Hatta, Muhammad Yamin bersikukuh memperjuangkan agar hak dan kebebasan warga negara dimasukkan secara jelas dalam UUD. Dalam pendapatnya Yamin mengatakan: “Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam UUD seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya... Saya hanya meminta perhatian betul-betul karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik; misalnya mengenai yang tertuju kepada warga negara yang akan mendapat hak, juga penduduk akan diperlindungi oleh republik ini.” Pendapat Moh. Hatta dan Muhammad Yamin tersebut juga didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan untuk drukpers dan onschendbaarheid van woorden (pers cetak dan kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan). Mereka sangat menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yang terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia II, apabila dalam negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga negara.54 54 Ibid., hlm. 240. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 23 Perdebatan-perdebatan di antara para founding fathers Negara Indonesia di atas masih diwarnai konsepsi dikotomi budaya Barat dan Timur. Dikotomi tentang konsep negara, antara negara berdasarkan kontrak sosial dan negara berdasarkan kekeluargaan.55 Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 16 Juli 1945 persidangan dalam BPUPKI menghasilkan kompromi sehingga beberapa ketentuan tentang hak diterima untuk dimasukkan dalam UUD.UUD RI yang telah dirancang oleh BPUPKI tersebut, dengan beberapa perubahan dan tambahan, akhirnya disahkan dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.56 UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada dasarnya hanya bersifat sementara, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Aturan Tambahan yang menyatakan: “Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD”. Pada waktu itu para penyusun UUD 1945 memperkirakan sebelum HUT RI Ke-1, sudah dapat tersusun UUD permanen yang dibuat oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Namun situasi politik nasional ternyata lebih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan, maka rencana tersebut belum sempat terlaksana.57 Dalam UUD 1945, meskipun dianggap telah memasukkan rumusan tentang hak, namun istilah HAM tidak dicantumkan secara eksplisit, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya. Menurut Mahfud MD, UUD 1945 hanya sebatas membahas mengenai hak asasi warga, padahal antara hak asasi manusia dan hak asasi warga negara jelas berbeda. HAM berdasarkan pada paham bahwa secara kodrati manusia, di 55 B. Hestu Cipto Handoyo, op. Cit., hlm. 276. 56 B. Hestu Cipto Handoyo, op. Cit., hlm. 276. Lihat juga, Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 76-77. Ketika disahkan oleh PPKI, UUD 1945 baru meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh, sedangkan Penjelasan baru dicantumkan, setelah naskah resminya dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946. Lihat, Subandi Al Marsudi, op. Cit., hlm. 129. 57 Baca, Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983. 24 Dr. Rohidin, M. Ag manapun, mempunyai hak-hak bawaan yang tidak dapat dipindahkan, diambil, atau dialihkan, sedangkan hak asasi warga negara hanya mungkin diperoleh ketika seseorang memiliki status sebagai warga negara.58 Sejalan dengan pandangan tersebut Bambang Sutiyoso juga menyatakan analisisnya bahwa dalam UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas tentang hak dan kewajiban warga negara dan hak-hak DPR.59Penggunaan konsep hak warga negara (right of citizens) bukan HAM (human rights) tersebut mengandung pengertian bahwa secara implisit paham natural rights yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena ia lahir sebagai manusia tidak diakui. Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut maka negara diposisikan sebagai regulator of rights, bukan sebagai guardian of human rights sebagaimana diposisikan oleh sistem Perlindungan HAM.60 Jaminan dan perlindungan atas hak asasi bagi warga negara ditegaskandalam UUD 1945 akhirnya tertuang pada Pasal 27, 28, 29 ayat (2), 30 ayat (1), 31 ayat (1), dan Pasal 34. Hak-hak yang dirumuskan dalam UUD 1945 tentang hak atas persamaan di muka hukum (rights of legal equality) adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”61 Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”62 58 Mahfud MD, “Undang-undang Politik, Keormasan dan Instrumentasi di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, UII Press No. 10, vol. 5. 1998. 59 Bambang Sutiyoso, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia”, dalam UNISIA, Yogyakarta, UII Press No. 10, vol. 5. 1998. 60 Rhona K. M. Smith (dkk.), op. Cit., hlm. 240. 61 Ayat ini menunjukkan adanya pengakuan dan jaminan atas persamaan hak semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality), tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, atau pun bentuk diskriminasi lainnya. 62 Ayat ini menunjukkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap martabat manusia (human dignity). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 25 Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 31 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tidak dicantumkannya rumusan tentang HAM secara tegas dalam UUD 1945 memang telah memicu timbulnya berbagai interpretasi terhadap kualitas muatan dan jaminan UUD 1945 atas HAM. Meskipun begitu, menurut Majda, ada hal yang patut untuk mendapatkan apresiasi positif, yaitu keberhasilan founding fathers Negara Indonesia dalam memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional dalam jangka waktu yang sangat terbatas dikarenakan kejaran waktu agar UUD dapat selesai sebagai syarat minimal berdirinya sebuah negara. Pada masa itu, UUD 1945 telah dapat dikategorikan sebagai konstitusi modern yang di dalamnya mengatur perihal lembaga-lembaga kenegaraan berikut mekanisme ketatanegaraan, serta jaminan atas hak, jauh sebelum masyarakat internasional merumuskan HAM dalam DUHAM pada forum PBB, 10 Desember 1948.63 2. HAM dalam Konstitusi RIS 1949 (1949-1950) Kondisi sosial politik yang belum kondusif pasca-proklamasi, dalam tataran implementatif, berakibat UUD 1945 pada masa permulaan diberlakukannya tidak berjalan efektif. Pada masa itu 63 26 Majda El-Muhtaj, op. Cit., hlm. 100-101. Dr. Rohidin, M. Ag tindakan maupun pemikiran bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi NKRI. Era 1945-1949, yang dalam istilah Arthur dikatakan sebagai establishment of a federal form government.64Kekalahan Jepang atas Sekutu memberikan implikasi politik bagi Indonesia. Belanda dengan segala cara berupaya menancapkan kembali politik kolonialismenya di Indonesia. Bahkan ancaman atas kedaulatan negara Indonesia tersebut tidak hanya dari rongrongan Pemerintah Belanda, namun juga dari tindakan-tindakan separatis dari dalam negeri yang muncul secara sporadis. Konfrontasi yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda tersebut akhirnya membuat Perserikatan BangsaBangsa (PBB) turun tangan. PBB mendesak kedua belah pihak agar menyelesaikan melibatkan pihak ketiga yakni BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg), sebuah ikatan negara-negara bagian bentukan Belanda. Sebagai upaya untuk mewujudkan resolusi PBB tersebut, pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 dilaksanakan konferensi di Den Haag, Belanda, yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB menghasilkan tiga keputusan mendasar. Pertama, pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS. Ketiga, pembentukan UNI-RIS-Belanda.65 Sebagai dasar berdirinya RIS hasil KMB, delegasi RI bersama dengan BFO merancang sebuah UUD yang diberi nama Konstitusi RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949 jam 10.17 pagi, di hadapan ketiga delegasi Ratu Juliana menandatangani Akta Penyerahan Kedaulatan. Peristiwa tersebut membawa konsekuensi pada berlakunya semua persetujuan hasil KMB dan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Dengan berdirinya RIS, maka posisi RI hanya sebagai salah satu “Negara Bagian” dalam RIS, dengan wilayah kekuasaan sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Renville. Demikian juga dengan berlakunya Konstitusi RIS, maka UUD 1945 hanya berlaku dalam 64 Ibid., hlm. 72. 65 Ibid., hlm. 74. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 27 Negara Bagian RI. Secara anatomik, Konstitusi RIS tersusun atas dua bagian, yakni Pembukaan dan Batang Tubuh yang memuat 6 bab dan 197 pasal, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan UUD 1945. Konstitusi tersebut sebenarnya hanya dimaksudkan untuk bersifat sementara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat”.66 Menariknya, Konstitusi RIS memberi penekanan yang Dalam Konstitusi RIS butir-butir HAM tidak hanya disebut secara eksplisit, tetapi cakupannya juga lebih luas jika dibandingkan dengan UUD 1945. Ada 35 pasal (Pasal 7 hingga Pasal 41) yang memberi jaminan konstitusional atas HAM. Rumusan tentang HAM dalam konstitusi tersebut diatur dalam bagian tersendiri, yakni Bab I, Bagian 5 Hak-hak dan Kebebasankebebasan Dasar Manusia, tercantum dalam 27 pasal. Bahkan Konstitusi RIS juga mengatur tentang kewajiban asasi negara dalam hubungannya dengan penegakan HAM, yakni pada Bab I, Bagian 6 Asas-asas Dasar, yang terbentang pada 8 pasal.67 Rumusan HAM tersebut ditempatkan mendahului bagian-bagian lain yang mengatur lembaga negara dan kewenangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi HAM dalam Konstitusi RIS lebih diutamakan daripada kekuasaan negara. Konstruk HAM dalam tubuh konstitusi RIS yang tercantum dalam bagian 5 Hak dan Kebebasan Dasar Manusia tersebut bisa digambarkan sebagai berikut: “Penekanan terhadap penegakan dan jaminan atas HAM dalam Konstitusi RIS secara historis sangat dipengaruhi oleh DUHAM, yang diikrarkan pada 10 Desember 1948. Diseminasi HAM versi PBB tersebut dalam konteks internasional pada 28 66 Lihat, Ibid., hlm. 74-75. 67 Ibid., hlm. 102. Dr. Rohidin, M. Ag waktu itu sangat mempengaruhi konstitusi-konstitusi negara di dunia, termasuk Konstitusi RIS.68 3. HAM Dalam UUDS 1950 (1950-1959) Konstitusi RIS yang dinyatakan berlaku pada 27 Desember 1949 ternyata tidak berusia panjang. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Ke-5 RI, 17 Agustus 1950 menandakan sebuah era baru bagi iklim ketatanegaraan Indonesia. Pada saat itu Konstitusi RIS dengan segala konsekuensinya berubah menjadi UUDS 1950.UUDS 1950 merupakan bukti historis kembalinya Indonesia kepada bentuk NKRI. Perubahan dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dilatarbelakangi oleh desakan rakyat yang menghendaki negara kesatuan. Bentuk negara serikat di mana wilayah-wilayah Indonesia berada dalam negara-negara bagian ternyata telah mengakibatkan disharmoni di kalangan masyarakat. Bahkan tidak jarang era Pemerintahan Federal Indonesia telah menciptakan 69 Kembalinya bentuk negara kesatuan tersebut juga tidak lepas dari upaya golongan unitaris yang menghendaki Indonesia menjadi negara kesatuan kembali dengan menyarankan kepada negara-negara bagian agar mau bergabung dengan RI yang berkedudukan di Yogyakarta. Usaha tersebut berhasil, terbukti mulai bulan Mei 1950 anggota RIS tinggal tiga negara bagian yaitu RI, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur.70 68 Ibid., hlm. 102. 69 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, Jakarta, 1983, hlm. 82. Bandingkan dengan, Majda El-Muhtaj, op. Cit., hlm. 76. 70 Upaya penggabungan negara-negara bagian tersebut sebenarnya harus dilakukan dengan UU Federal, sesuai dengan konstitusi RIS, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44; “Perubahan daerah sesuatu daerah bagian, demikian pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh sesuatu daerah ... menurut aturan-aturan yang ditetapka dengan UU Federal .... Kenyataannya, penggabungan tersebut tidak berdasarkan UU Federal. Maka, penggabungan tersebut disahkan dengan UU Darurat No. 11 tahun 1950 yang dikeluarkan dengan berlandaskan pada Pasal 139 KRIS yang menyatakan; (1) Pemerintah Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 29 Keputusan beralihnya Konstitusi RIS kepada UUDS 1950 terjadi sesudah diadakan perundingan antara Pemerintah Negara Bagian RI dengan Pemerintah Pusat Federal yang telah diberikan kuasa oleh Negara Bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur.71 Dalam perundingan tersebut disepakati sebuah alternatif sebagai dasar untuk menuju NKRI, yaitu pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasalpasal yang bersifat kesatuan. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950, berhasil ditandatangani Piagam Persetujuan yang secara pokok memuat pernyataan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai jelmaan dari RI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.72 Berkaitan dengan persetujuan tersebut maka diperlukan perubahan atau penggantian Konstitusi RIS. Meskipun Konstitusi RIS tersebut bersifat sementara, namun belum dimungkinkan untuk melakukan “penggantian”, karena sesuai dengan Pasal 186 Konstitusi RIS, penetapan sebuah konstitusi sebagai pengganti Konstitusi RIS hanya bisa dilakukan olehKonstituante (sidang pembuat undang-undang) bersama pemerintah, sedangkan Konstituante sendiri harus dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang tentunya akan memakan waktu lama. Sehubungan dengan itu maka dilakukan “perubahan” Konstitusi RIS. Perubahan konstitusi ini dapat dilakukan dengan lebih cepat, karena cukup dilakukan dengan UU Federal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 190 Konstitusi RIS. Berpijak pada hal tersebut diterbitkanlah UU Federal No. 7 Tahun 1950, tentang Perubahan Konstitusi Sementara berhak atas kuasa dan tanggungjawab sendiri menetapkan UU Darurat... (2) UU Darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa UU Federasi...Lihat, B. Hestu Cipto Handoyo, op. Cit., hlm. 64. 71 Dalam bagian “Menimbang” UUDS 1950 tercantum penjelasan penggantian Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 berdasarkan pertimbangan: Ini adalah kehendak rakyat dan dilaksanakan kehendak rakyat ini, adalah, setelah terlebih dahulu dilakukan pembicaraan di antara pemerintah Negara RI dengan Pemerintah Negara RIS yang mewakili Negara-negara Bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Dan pembicaraan-pembicaraan ini menghasilkan suatu persetujuan pendapat mengenai penggantian UUD Konstitusi 1949 dengan UUDS RI No. 7 Tahun 1950. Ramdlon Naning, op. Cit., hlm. 82. 72 30 B. Hestu Cipto Handoyo, op. Cit., hlm. 65. Dr. Rohidin, M. Ag RIS menjadi UUDS RI. Perubahan konstitusi ini pada intinya hanyalah penggantian sebagian pasal-pasal di dalamnya.73 Menurut catatan Mahfud MD, dilihat dari sudut bentuk, UUDS 1950 merupakan bagian dari UU Federal No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS RI.74 Dengan demikian fungsi UU No. 7 Tahun 1950 hanya memberlakukan UUDS, atau lebih tegasnya hanya mengubah Konstitusi RIS menjadi UUDS, sehingga ketika UUDS 1950 berlaku maka tugas UU No. 7 Tahun 1950 telah selesai. Secara anatomik, UUD 1950 terdiri atas 6 Bab dan 146 pasal. Sebagaimana telah ditegaskan diatas UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS 1949, maka perihal HAM secara umum juga memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaanperbedaan yang prinsipil. Menurut Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Majda, setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar antara UUDS 1950 dengan Konstitusi RIS 1949 dalam penegasan tentang HAM. Pertama, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama dan keyakinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Konstitusi RIS 1949 tidak lagi ditegaskan dalam UUDS 1950. Kedua, hak berdemonstrasi dan hak mogok kerja yang tidak terdapat pada Konstitusi RIS 1949 diatur dalam Pasal 21 UUDS 1950. Ketiga, pengadopsian dasar perekonomian pada Pasal 33 UUD 1945 dalam Pasal 38 UUDS 1950.75 UUDS 1950 tidak hanya memberi penegasan mengenai hakhak asasi secara individu, tetapi juga memberi penekanan kepada fungsi dan manfaat sosial. Hal tersebut tampak dalam penjelasan tentang hak milik dalam Pasal 26 ayat (3) yang secara eksplisit menyatakan, “hak milik itu adalah fungsi sosial”.76 73 Ibid., hlm. 65-66. 74 Majda El-Muhtaj, op. Cit., hlm. 77. 75 Ibid.,hlm. 107-108. 76 Ibid., hlm. 109. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 31 4. HAM Dalam UUD [1959-Sekarang]) 1945 (Pemberlakuan II Keberadaan UUDS 1950 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ternyata juga tidak berusia panjang. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menyatakan UUDS 1950 sudah tidak efektif lagi dan beralih kembali kepada pemberlakuan UUD 1945. Kenyataan ini berimplikasi kepada materi muatan konstitusi itu sendiri. Sehingga apa yang pernah dimuat dalam UUD 1945 pada awal berlakunya dinyatakan berlaku kembali. Berdasarkan hasil pemilu 1955, sebenarnya Konstituante diberi kewenangan untuk melakukan penyusunan UUD yang tepat bagi Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Bab V Pasal 134 UUDS 1950. Namun selama persidangan Majelis Konstituante sejak tanggal 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959, telah terjadi perdebatan sengit dalam tiga agenda sidang, yakni: dasar negara (1957), HAM (1958), dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Ide tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 muncul mengingat UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan liberal, supaya diperoleh kembali pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan, maka UUD 1945 menjadi pilihan terbaik. Meskipun begitu, kemunculan ide ini mengundang reaksi di kalangan Majelis Konstituante.77 Sementara itu, di luar Konstituante, Presiden Soekarno melalui Rapat Dewan Menteri pada tanggal 19 Februari 1959 di Bogor telah mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ( ) di bawah Soekarno dengan menegaskan kembali ke UUD 1945. Keputusan Dewan Menteri ini merupakan langkah awal pemberlakuan kembali UUD 1945. UUD 1945 dalam keputusan tersebut dipertahankan sebagai keseluruhan, sedangkan mengenai perubahannya dikembalikan pada Pasal 37 UUD 1945.78 77 Ibid., hlm. 80. 78 Keputusan Dewan Menteri ini menjadi alat mobilisasi kekuatan di luar Konstituante, sehingga persidangan dalam Majelis Konstituante menjadi tidak kondusif. Bahkan tekanan secara politik dilakukan oleh kekuatan Angkatan Darat yang mendesak secepatnya untuk kembali kepada UUD 1945. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah yang seharusnya tidak 32 Dr. Rohidin, M. Ag Keadaan ini diperkeruh dengan suasana perpolitikan yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai pemberontakan sebagai artikulasi politik yang tidak terakomodasi bermunculan. Atas dasar kondisi tersebut maka Presiden Soekarno menyatakan negara dalam keadaan darurat (Staat van Oorlog en Beleg) dan kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan:79 a. Pembubaran Konstituante. b. Pemberlakuan kembali UUD 1945. c. Penarikan kembali UUDS 1950 dan dalam waktu sesingkatsingkatnya mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945. Sejak diberlakukannya UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959, praktis secara yuridis UUD 1945 belum pernah mengalami perubahan. Meskipun begitu, dalam praktik kenegaraan sebenarnya sudah mengalami perubahan berulangkali, walapun hanya dalam tataran penafsiran. Pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, baik dalam era Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru) ternyata hanya merupakan retorika politik dari pemegang kekuasaan masing-masing era tersebut.80 Materi HAM dalam UUD 1945 tidak mengalami perubahan 1945 Indonesia. Jika mendapatkan tempat dan implementasi yang relatif proporsional, tetapi jika boleh terjadi.Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang terpusat di tangan Soekarno mengakibatkan lemahnya kontrol atas pemerintahan. Hal tersebut membuatPemerintahan Indonesia mengalami suasana tidak kondusif dan memprihatinkan yang berpuncakpada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Lihat, Ibid., hlm. 81. 79 Ibid., hlm. 82. 80 B. Hestu Cipto Handoyo, op. Cit., hlm. 278. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 33 akan mendapat perlakuan yang buruk.81 C. Hak Kebebasan Beragama dalam Konstruksi Regulasi di Negara Hukum Indonesia Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturanaturan normatif tidak serta-merta indah pula dalam kenyataannya. Ada sebagian warga negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Prinsip kebebasan beragama di Indonesia di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM, juga mengacu kepada konstitusi dan sejumlah undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penjaminan HAM. Di antaranya, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Kovenan Internasional tentang pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari seluruh warga negara tanpa kecuali. Kovenan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui UU No. 11 Tahun 2005. Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah dalam menegakkan hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya, termasuk kebebasan beragama di Indonesia. Jaminan konstitusional terkait hak kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 81 34 Majda El-Muhtaj, op. Cit., hlm. 112. Dr. Rohidin, M. Ag 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Secara eksplisit, pasal ini mengikuti prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dalam soal kebebasan sipil (civil liberties). Jaminan kebebasan beragama adalah sebuah keniscayaan, namun Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 membatasi hak tersebut dengan menetapkan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Implikasi dari ayat ini adalah bahwa agama dan kepercayaan yang tidak ber“Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dijamin haknya oleh negara. Dengan kata lain, negara tidak menganggap seseorang sebagai warga negara bila ia “tidak ber-Ketuhanan Yang Maha Esa” dan karena itu ia tidak memperoleh perlindungan negara.82 Senada dengan pasal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketetapannya No. VII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 13 juga menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Penjaminan yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Keberadaan kedua pasal tersebut (Pasal 28E dan Pasal 29), tidak saja menjadi konstruksi legal yang memberikan perlindungan konstitusional bagi warga negara untuk mempraktikkan kebebasan beragama dan keyakinan, namun juga memberi pengakuan sosiologis atas fakta keberagamaan 82 Rocky Gerung “Agama dan Negara” dalam Ahmad Suaedy (dkk.), Beragama, Berkeyakinan dan Berkonstitusi: Tinjauan Konstitusional Praktik Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Publikasi Setara Institute, Jakarta, 2009, hlm. 186. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 35 dan kebhinekaan yang telah lama tumbuh dan berkembang serta menjadi modal sosial terbentuknya bangsa Indonesia.83 Selanjutnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Pasal 22 ditegaskan: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (baca: Pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Kebijakan tentang jaminan kebebasan beragama juga terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18, yang berbunyi: 83 M. Atho Muzhar berpendapat bahwa kebebasan beragama yang diatur dalam kedua pasal tersebut bukanlah kemerdekaan yang tidak ada batasnya. Hak-hak asasi manusia dalam beragama dan dalam hal-hal lainnya bukanlah cek kosong yang dapat diisi dengan apa saja atau dengan common sense, melainkan senantiasa dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain dan karena itu dapat dibatasi oleh undang-undang. Lihat, Ahmad Suaedy (dkk.), Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, The WAHID Institute, Jakarta, 2009, hlm. 43-44. 36 Dr. Rohidin, M. Ag 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini menyangkut kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadat, ketaatan pengamalan dan pengajaran. 2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Sementara terkait dengan persoalan penyalahgunaan atau penodaan agama, pemerintah mengaturnya dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada Penjelasan Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa: “Agamaagama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka selain mendapatkan jaminan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, mereka juga mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.”84 Jika ditelusuri lebih lanjut, aspek-aspek yang dibatasi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 1/PNPS/1965 masih sangat luas, tidak saja mencakup kebebasan eksternal,85 tetapi juga kebebasan internal.86 Ketentuan semacam ini oleh sebagian 84 Siti Musdah Mulia “Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi” dalam Elza Peldi Taher (ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Efendi, ICRP, Jakarta, 2009, hlm. 341. 85 Kebebasan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan, secara individu maupun dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi, untuk memanifestasikan agama dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengamalan, dan peribadatannya. 86 Kebebasan pada level ini ingin menegaskan bahwa setiap orang Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 37 kalangan dirasa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain seperti Pasal 28E, Pasal 28I UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39/1999 dan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil Politik yang menganut pemisahan antara kebebasan internal dan eksternal. Dalam konteks inilah dapat kita lihat bahwa problematika mendasar tentang persoalan kebebasan beragama ini adalah terkait dengan masih adanya ketidakharmonisan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya sehingga melahirkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstatasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh undang-undang itu sendiri yang menyatakan bahwa: “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya…”. Karenanya, menjadi satu keharusan bagi setiap agama, keyakinan, dan kepercayaan apapun yang hidup di negeri ini untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa melihat ada tidaknya pengakuan legal dari negara tentang keberadaannya. Mengacu kepada dokumen HAM internasional, konstitusi, dan sejumlah undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka bagi Musdah kebebasan beragama harus dimaknai sebagai berikut:87 1. Kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadat menurut agama dan keyakinan masing-masing. mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya. 87 Ibid., hlm. 6-8. 38 Dr. Rohidin, M. Ag 2. 2. Kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan caracara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu. 3. Kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apapun yang diyakininya dapat membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragama. 4. Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebolehan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau berbeda sekte atau berbeda faham keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Artinya, perkawinan itu bukan dilakukan untuk tujuan perdagangan perempuan dan anak ( in women and children) yang akhir-akhir ini menjadi isu global. 5. Kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama manapun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut peserta didik. Demikian juga, kebebasan untuk memilih tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Akan Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 39 tetapi, lembaga pendidikan dapat mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan karakter warga negara yang baik. 6. Kebebasan beragama memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham, dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak menggangu ketenteraman umum dan tidak pula melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti perilaku kekerasan, penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama. 7. Kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasiorganisasi keagamaan untuk maksud meningkatkan kesalehan warga, meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau keyakinan sebagai syarat. Konsekuensinya, negara atau otoritas keagamaan apa pun tidak boleh membuat fatwa atau keputusan hukum lainnya yang menyatakan seseorang sebagai label terhadap suatu paham, sekte, aliran keagamaan atau kepercayaan tertentu sebagaipaham sesat. 8. Kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak boleh memihak kelompok keagamaan tertentu dan mendiskriminasikelompok lainnya. Dalam konteks ini seharusnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak ada istilah penganut agama samawi dan non-samawi. Demikian juga tidak perlu ada istilah agama induk dan agama sempalan. Jangan lagi ada istilah agama resmi dan tidak resmi atau diakui dan tidak diakui pemerintah. Setiap warga negara mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya. 40 Dr. Rohidin, M. Ag Dalam kenyataannya, “potret buram” perjalanan terkait implementasi jaminan hak kebebasan beragama dalam konstruksi peraturan perundangan di Indonesia ternyata juga tidak luput dari sorotan Komite Anti Penyiksaan PBB. Salah satu keprihatinan yang menjadi sorotan Komite Anti Penyiksaan PBB atas laporan pelaksanaan Pasal 19 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan oleh Pemerintah Indonesia adalah terkait dengan isu agama “resmi” dan ”tidak resmi”. Dalam hal ini, Komite melihat adanya pembedaan serius—sebagaimana termuat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan—antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dengan agama dan aliran kepercayaan lainnya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Komite selanjutnya merekomendasikan agar Negara Pihak memperlakukan dengan sama semua agama dan kepercayaan, menghargai kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama berbagai kelompok etnis minoritas dan/atau masyarakat indigeneous (indigeneous peoples). Komite ini juga merekomendasikan agar kolom agama dalam KTP dan Akte Kelahiran dihapuskan. Menindaklanjuti hal ini, Dewan HAM PBB (Human Rights Council) di Geneva mengeluarkan laporan tertanggal 16 Februari 2009 bertajuk Report of the Special Rapporteur on Freedom on Religion or Belief yang memuat komentar Asma Jahangir berjudul “Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Rights to Development.” Dalam komentarnya, Asma mengingatkan kembali akan kewajiban negara Indonesia untuk melindungi dan menjamin kelompok minoritas apapun yang hidup di wilayah yurisdiksinya. Dia mengingatkan akan kandungan Pasal 18 ayat (2) ICCPR yang berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”88 Dari pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan beragama di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa meski secara 88 Ahmad Suaedy (dkk.), op. Cit., hlm. 8-9. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 41 konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih terdapat ragam kelemahan. Bahkan ada kesan, paradigma dan perspektif pemerintah dalam melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segisegi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang. 42 Dr. Rohidin, M. Ag DUA Konsep Dasar Kebebasan Beragama A. 1. Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Arti dan Cakupan Konsep Kebebasan Beragama Istilah kebebasan beragama merupakan frasa yang tersusun dari dua kata “kebebasan” dan “beragama”. Secara etimologi kebebasan berakar dari kata bebas, yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang dan terganggu sehingga boleh bergerak, berbicara, dan berbuat dengan leluasa).Selain itu, bebas juga memiliki arti lepas dari kewajiban, tuntutan, tidak terikat atau terbatas oleh aturanaturan, dan merdeka.1 Sedangkan secara terminologis, Isaiah Berlin membagi kebebasan dalam bentuk positif dan negatif. Kebebasan dalam bentuk positif berarti ‘apa atau siapa’, yang bertindak sebagai sumber hukum yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan, atau mendapatkan suatu kebebasan, sementara dalam bentuk negatif bersinggungan dengan ruang lingkup di mana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.2 Dalam Kamus Hukum Black’s, kebebasan diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari beragam bentuk larangan, kecuali 1 Dendy Sugono (red.), Kamus Bahasa Indonesia, Depdiknas, Jakarta, 2008., hlm. 153. 2 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, dalam David Miller (ed.), Liberty, Oxford University Press, Oxford, 1991, hlm. 34. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 43 larangan yang telah diatur di dalam undang-undang.3 Pengertian kebebasan yang diutarakan dalam kamus tersebut merupakan kebebasan dalam bentuknya yang positif. Sesuai dengan pengertian tersebut, kebebasan manusia tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh peraturan hukum. Kebebasan dalam bentuk positif merupakan kebebasan dalam sebuah bingkai aturan, sehingga dalam tataran praktis setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu, selama hal tersebut tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lain halnya dalam bentuk negatif, yang mana kebebasan tersebut bersinggungan dengan ruang lingkup, di mana seseorang harus dihormati dan dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.4 Kebebasan dalam bentuk negatif ini dapat dilihat dalam kamus John Kersey, yang mengartikan kebebasan sebagai kemerdekaan meninggalkan atau bebas meninggalkan. Jadi, manusia bebas untuk tidak melakukan atau meninggalkan suatu hal.5 Sedangkan kata kedua (beragama) memiliki akar kata yang berupa agama. Banyak istilah yang digunakan untuk kata agama, sesuai dengan tradisi bahasa yang digunakan, seperti religion dalam masyarakat yang memiliki tradisi bahasa Inggris atau juga dalam masyarakat dengan tradisi bahasa Arab. Baik istilah agama, religion, maupun secara umum memiliki kesepadanan makna. Secara lexical meaning agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan antarmanusia dan manusia beserta lingkungan dengan kepercayaannya. Sehingga, beragama, sebagai bentuk kata kerjanya, 3 Henry Campbell (ed.), and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern,West Publishing Co, St. Paul, 1990, hlm. 918. 4 Baca, Isaiah Berlin, “Two Concept of Liberty”,loc. Cit. 5 Telusuri selengkapnya dalam, Jay Newman, On Religious Freedom, (E-Book), University of Ottawa Press, hlm. 18, dalam http://books.google. &sig=v_ONZVSgZrVp1jV39xYlnKXaNJk (Diakses pada tanggal 12 Desember 2010). 44 Dr. Rohidin, M. Ag berarti menganut (memeluk) agama, mematuhi segala ajaran agama, dan taat kepada agama.6 Meskipun demikian, bagi kalangan tertentu agama merupakan objek dari HAM yang paling sulit untuk agama memiliki arti yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.7 Bahkan, beberapa instrumen internasional, seperti ICCPR, hanya merumuskan tentang kebebasan beragama agama itu sendiri. Setiap agama memiliki pengertian sendiri tentang agama dan unsur-unsur yang ada dalam agama tersebut. Selama ini agama dari para pemeluk agama. Setiap pemeluk agama mempunyai keyakinan dan cara memanifestasikan keyakinan tersebut secara berbeda-beda. Namun demikian, terdapat acuan yang bisa digunakan untuk agama, yaitu dengan mengkaji Pertama, adanya kepercayaan terhadap Tuhan. Kedua, agama secara psikologis memengaruhi pemahaman manusia yang mempercayainya. Ketiga, agama merupakan kekuatan budaya dan sosial dari simbol-simbol yang melekat padanya.8 agama belum kebebasan beragama tidak bisa dirumuskan dan dijalankan. dikaitkan dengan konteks kehidupan beragama, maka kebebasan beragama mengandung pengertian bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk maupun tidak memeluk suatu agama. Sejalan dengan pengertian ini, Al Khanif menyatakan bahwa: “Pengertian kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan, di mana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama, baik yang bersifat theistik 6 Dendy Sugono (red.), op. Cit., hlm. 17. 7 Timothy Macklem, ” Faith as a Secular Value”, February 2000, hlm. 10. 8 , Ibid., hlm. 106. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 45 maupun yang non-theistik, dan untuk memanifestasikan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam hak asasi manusia internasional.”9 Jika konsep kebebasan beragama secara umum dihubungkan dengan konsep kebebasan dalam kamus Black’s—sebagaimana terurai di atas—maka kebebasan beragama tidak bersifat mutlak, tetapi terdapat batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah melalui konstitusi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak warga negara lainnya, menjaga ketertiban umum, dan menjaga kedaulatan negara. Secara substansial, tidak jarang agama atau kepercayaan cenderung menjadi konglomerasi dari berbagai nilai-nilai, klaim, dan hak. Kebebasan beragama itu sendiri memiliki beberapa dimensi. Sebuah agama tidak hanya menyangkut kepercayaan seseorang, akan tetapi terkait juga dengan pengajaran, nilai, kepercayaan, dan beribadat yang sama hubungannya dengan manifestasi dari nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Terdapat kecenderungan yang kuat di antara berbagai agama untuk memasukkan ajaran dan aturannya menuju sebuah ketundukan yang sempurna, dan dalam prosesnya, mereka kadang memengaruhi banyak aspek dari kehidupan manusia, termasuk sistem kekerabatan, pernikahan, hubungan keluarga, pengawasan anak, keturunan, aturan publik, makanan dan pola diet, serta kebebasan berekspresi dan berserikat. Salah satu kesulitan dari ajaran agama atau kepercayaan adalah munculnya monopoli tentang kebenaran yang mutlak. Agama dan kepercayaan cenderung kaku dan para pengikutnya tidak mampu mentolelir terhadap kompetisi nilaiagama lain. Sebagaimana dikemukakan Macaulay, tindakan intoleransi ini dapat menggiring pengikutnya pada sebuah anggapan bahwa; “Aku yang benar dan kamu yang salah. Jika kamu kuat, maka kamu harus mentolelir aku dan seperti itulah kewajibanmu untuk mentolelir 9 46 Al Khanif, op. Cit., hlm. 108. Dr. Rohidin, M. Ag kebenaran. Tetapi jika aku kuat, maka aku akan menghukummu sebab seperti itulah kewajibanku untuk menghukummu”. Intinya, bagi penganutnya, agama adalah moralitas itu sendiri dan pondasi dasar yang bersifat transendental yang lebih tegas dalam hal kewajiban daripada rival sekuler, atau ajaran agama-agama lain.10 Berkaitan dengan hal itu, muncul tiga pandangan yang berupa; pertama, universal absolut. Menurut pandangan ini, HAM merupakan nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional, ICCPR misalnya. masing bangsa tidak diperhitungkan, seperti yang tercantum dalam yang di antaranya menyebutkan bahwa; “As human rights are of universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights can not be considered to be an encroachment upon national sovereignity”. Rumusan tersebut menyatakan bahwa kedudukan HAM sebagai persoalan dan memiliki nilai universal, di samping pembelaannya. Sehingga, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan nasional suatu bangsa.11 Maka, berdasarkan pada pandangan ini hak kebebasan beragama seperti yang telah ditetapkan dalam ICCPR juga berlaku secara mutlak tanpa mempertimbangkan sosio-kulturalsuatu negara. Kedua, universal relatif. Konsep ini berpandangan bahwa HAM merupakan persoalan universal. Namun demikian, pengecualian dan pembatasan—sebagimana terdapat dalam DUHAM dan ICCPR—yang didasarkan atas asas-asas hukum nasional tetap diakui keberadaannya. Pandangan ini selaras dengan Pasal 29, ayat (2) dalam DUHAM, yaitu: Javaid Rehman, “Accommodating Religious Identities in an Islamic State: International Law, Freedom of Religion and the Rights of Religious Minorities” dalam International Journal on Minority and 7: 2000, hlm. 147-148. 10 11 Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 78. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 47 “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society”. Artinya, batasan-batasan tersebut sangat ditentukan oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mengapresiasi hak-hak dan kebebasan orang lain, di samping pemenuhan aspek, moral, norma, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, partikular. Bagian ini terbagi dalam dua bentuk, yakni absolut dan relatif. Partikular-absolut berpandangan bahwa HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberi alasan kuat, khususnya dalam melakukan penolakan tehadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini kerap menimbulkan kesan chauvinist. Sementara partikularrelatif berpandangan bahwa konsep HAM, di samping dilihat sebagai masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa masing-masing. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan pada masingmasing bangsa untuk bersikap defensif, tetapi di lain pihak juga aktif mencari perumusan dan pembenaran (vindication) terhadap karakteristik HAM yang dianutnya. Pandangan ini tampak terlihat dalam The Jakarta Message, Butir 18, yang di antaranya berbunyi: human rights and fundamental freedom are of universal validity... No country however, should use its power to dictate its concept of democracy and human rights or to impose conditionalities on others. In the promotion and the protection of these rights and freedoms, we emphasize the interrelatedness of the various categories, call for the balanced relationship between individual and community rights, uphold 48 Dr. Rohidin, M. Ag the competence and responsibility of national government in their implementation.” HAM dan kebebasan dasar manusia bersifat universal. Meski demikian, suatu negara tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap negara lain dalam dua persoalan tersebut. Dalam hal ini, keseimbangan peran tiga elemen suatu negara, yakni hak individu, masyarakat, dan negara, sangat dibutuhkan. 2. Konsep Negara Hukum Pancasila sebagai Pola Prismatik Berkaitan dengan Kebebasan Beragama Istilah negara secara lexical meaning berarti organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.12 Sementara hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara). Ia juga bisa diartikan denganundangundang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, di samping juga bisa diartikan denganpatokan (kaidah atau ketentuan) mengenai suatu peristiwa yang tertentu.13 Penyebutan negara hukum untuk RI selama ini telah populer di masyarakat Indonesia. Namun demikian, secara konseptual istilah negara hukum masih menuai kontroversi yang belum berakhir. Secara umum, istilah tersebut dianggap terjemahan dari dua istilah, yakni; rechtsstaat dan the rule of law. Kedua istilah tersebut secara konseptual kerap dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, karena keduanya tidak terlepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Akan tetapi, secara mendasar keduanyamempunyai latar belakang dan pelembagaan 12 Dendy Sugono (red.), op. Cit., hlm. 1069 13 Ibid., hlm. 559. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 49 yang berbeda, meskipun secara esensial sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM melalui lembaga peradilan yang bebas dan independen. Rechtsstaat merupakan konsep negara modern yang populer di Eropa sejak abad XIX dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Istilah tersebut dikampanyekan oleh beberapa tokoh terkemuka, seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fitche. Konsep tersebut lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Konsep tersebut banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law atau modern roman law, yang memiliki karakteristik administratif. Menurut Stahl, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, elemen penting yang dicakup oleh konsep tersebut berupa (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata usaha negara.14 Mengenai istilah the rule of law mulai poluler dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn 14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 148. Dalam perkembangannya, konsep rechtsstaat mengalami transformasi dari bentuk klasik ke bentuk modern. Berdasarkan sifatnya, konsep rechtsstaat klasik disebut dengan “Klassiek liberale en democratischerechtsstaat”, yang sering disingkat dengan “Democratische Rechtsstaat”. Konsep klasik ini menurut S.W. Couwenberg dalam karyanya Westers Staatsrecht als Emancipatieproces memiliki lima asas dan prinsip-prinsip dasar yang meliputi sepuluh bidang. Lima asas tersebut berupa: asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggungjawaban, dan asas publik. Sedangkan 10 prinsip tersebut adalah (1) pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil, pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan antara hukum publik dan hukum privat, (2) pemisahan antara negara dengan gereja, (3) adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil, (4) persamaan terhadap undang-undang, (5) adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum, (6) pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem “chek and balances”, (7) asas legalitas, (8) ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral, (9) prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsipprinsip tersebut diletakkan dengan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis; dan (10)prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun disentralisasi). Lihat, Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 74-77. 50 Dr. Rohidin, M. Ag Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to the Study of the Law of the Constitution.15 Konsep tersebut banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem common law, yang memiliki karakteristik judicial. Unsurunsur penting yang dimiliki oleh konsep tersebut menurut Dicey, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, adalah (1) supremacy of law, (2) equality before the law, dan (3) due process of law.16 Jika dilihat dari ciri-cirinya, kedua konsep tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar. Persamaannya, kedua konsep tersebut menitikberatkan pada upaya memberikan perlindungan pada hak asasi manusia, sehingga untuk mencapai hal tersebut harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Dengan cara ini pelanggaran atas hak asasi manusia dapat diminimalisasi, dan bahkan dicegah. Adapun perbedaan kedua konsep tersebut terlihat pada pelembagaan dunia peradilannya, di mana keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep the rule of law tidak terdapat lembaga peradilan administrasi, sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Di dalam konsep tersebut semua orang dianggap memiliki kedudukan yang setara di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun bagi pemerintah harus disediakan peradilan yang sama. Dilihat dari ciri-ciri tersebut, terlihat jelas betapa peranan pemerintah hanya sedikit, karena dalam konsep tersebut terdapat dalil “pemerintahan yang paling sedikit yang paling baik”. Karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik itulah, negara hanya diposisikan sebagai nachtwachterstaat (negara penjaga malam). Sebagai nachtwachter, pemerintah memiliki ruang gerak yang sangat sempit tidak hanya di wilayah politik, tetapi juga pada sektor ekonomi, dengan dalil laisses faire, laissez aller (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing). 15 Ibid., hlm. 72. 16 Jimly Asshiddiqie, op. Cit., hlm. 148. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 51 Konsep negara hukum (formal) tersebut secara perlahan mendapatkan gugatan menjelang pertengahan abad XX, tepatnya setelah Perang Dunia. Beberapa faktor yang menyebabkannya menurut Miriam Budihadjo, sebagaimana dikutip Mahfud MD, antara lain adalah ekses-ekses dalam industrialisasi dan sisitem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.17 Konsep yang memasung peran pemerintah dalam mengatur persoalan sosial-ekonomi rakyatnya bergeser pada konsep baru bahwa negara harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus bersifat aktif dan tidak boleh diposisikan sebagai nachtwachter dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan mengatur sektor tatanan sosial dan perekonomian. Demokrasi, dalam konsep baru ini, diperluas agar dapat menjangkau dimensi ekonomi dengan sistem, yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama kemampuan dalam mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan warga negaranya. Konsep baru tersebut dikenal dengan istilah welfaartsstaat (negara hukum material), yang kemudian dikenal dengan verzorgingsstaat.18 17 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 25. 18 Welfaartsstaat dan verzorgingsstaat merupakan konsep-konsep sosiologi dan ilmu politik. Pada masa Kabinet Loebers, di Belanda konsep verzorgingsstaat dirasakan terlalu mahal untuk dilaksanakan, sehingga ia menjalankan kosep warborgstaat. Dengan konsep tersebut, pemerintah menyediakan minimum warborg dan kekurangannya diserahkan kepada rakyat untuk mengusahakannya secara individu melalui asuransi partikelir. Dalam konsep yuridis, A.M. Denner, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa sosiale rechtsstaat lebih baik daripada istilah welfaartsstaat. Akan tetapi, S.W. Couwenberg berpandangan jika sosiale rechtsstaat merupakan varian dari liberal-democratischerechtsstaat. Varian tersebut di antaranya adalah (1) interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya serta dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari wet dan wetgeving, (2) kebebasan dan persamaan, yang dalam konsep klasik bersifat formal-yuridis, dalam konsep sosiale rechtsstaat ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat, bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang lain. Hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural mendapat perhatian utama, (3) legitimasi kekuasaan politik tidak 52 Dr. Rohidin, M. Ag Dengan meluasnya kampanye dan mulai diterimanya konsep baru tersebut, ciri-ciri negara hukum yang digagas oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau kembali sehingga dapat menggambarkan peranan aktif pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dalam sebuah konferensi yang digelar di Bangkok pada tahun 1965, International Commmision Jurist menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat, harus diakui pula adanya hak-hak sosial-ekonomi, sehingga standarisasi dasar sosial-ekonomi perlu dibentuk. Dalam kesempatan itu pula, komisi tersebut merumuskan unsur-unsur pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law, yaitu:19 a. Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. c. Pemilihan umum yang bebas. d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. e. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. f. Pendidikan kewarganegaraan. lagi merupakan masalah pokok, tetapi kekuasaan ekonomi dalam masyarakat kapitalis yang liberal dan kaitan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik, (4) kepentingan umum sebagai asas hukum publik, tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai kepentingan negara sebagai basis masyarakat dari hukum liberal, (5) watak undang-undang, yang dalam konsep klasik bersifat restriktif, dan stabiliserend, mulai luntur karena fungsi wetgeving hanyalah sebagai formeel-juridische basis van een sosialgeorenteerd overheidsbeleid. Dengan demikian, undang-undang dengan watak ratio scripta direduksi menjadi een juridis instrument ter realisering van dit beleid. Lihat,Philipus M. Hadjon, op. Cit., hlm. 77-78. 19 Lihat, Moh. Mahfud MD, op. Cit., hlm. 26. dan Sri Sumantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Conference of Jurist, Bangkok, Februari, 15-19, 1965, The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age, International Commission of Jurist, 1965, hlm. 30-50. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 53 Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan di atas serta melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum, Jimly Asshiddiqie merumuskan dua belas prinsip pokok, sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah:20 a. Supermasi hukum (supremacy of law). b. Persamaan dalam hukum (equality before the law). c. Asas legalitas (due process of law). d. Pembatasan kekuasaan. e. Organ-organ penunjang yang independen. f. Peradilan bebas dan tidak memihak. g. Peradilan tata usaha negara. h. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). i. Perlindungan hak asasi manusia. j. Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat). k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat). l. Transparansi dan kontrol sosial. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, gagasan mendasar tentang pembentukan negara adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum. Adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum. Maka, ketika para pendiri Negara Indonesia bermusyawarah guna menyusun sebuah konstitusi berarti secara sadar mereka telah memilih konsep negara hukum. Hal tersebut dilakukan karena adanya konstitusi berfungsi membatasi secara hukum kekuasaan pemerintah, 20 54 Jimly Asshiddiqie, op. Cit., hlm. 150. Dr. Rohidin, M. Ag sehingga penggunaannya tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan di dalam konstitusi tersebut. Naskah UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI secara umum menjelaskan dengan mengatakan bahwa Indonesia Negara berdasar atas hukum (rechtsstaat). Akan tetapi, UUD 1945 tidak memuat pernyataan yang jelas tentang konsep negara hukum yang mana, yang dianut di Indonesia, bahkan istilahnya pun tidak disebut secara eksplisit, baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuhnya. Konsep yang kemudian muncul di negara ini adalah Negara Hukum Pancasila. Jika ditelusuri dari latar belakang sejarahnya, baik konsep the rule of law maupun konsep rechtsstaat lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa. Berbeda dengan Negara RI, sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan dan absolutisme. Oleh karenanya, jiwa dan Negara Hukum Pancasila seyogianya tidaklah begitu saja mengalihkan konsep the rule of law ataupun konsep rechtsstaat. Terlebih lagi jika dilihat melalui kandungan UUD 1945 tentang HAM, di mana dalam proses pembuatannya didasarkan pada konsepsi negara hukum itu sendiri yang berintikan pada perlindungan HAM yang harus dikawal oleh adanya lembaga peradilan yang bebas. Artinya, pemilihan atas konsepsi negara hukum disebabkan oleh pilihan lebih dahulu pada pengakuan dan perlindungan HAM. Perdebatan antara Soekarno-Soepomo, di satu sisi, dan Hatta-Yamin, di sisi yang lain, dalam proses pembuatannya pada akhirnya menghasilkan kompromi dengan dimuatnya secara terbatas ketentuan-ketentuan tentang HAM pada Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31.21 Masuknya pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa konsepsi negara hukum dari tradisi Anglo Saxon yang berinisial rule of law tersebut inheren di dalam UUD 1945, misalnya pada Pasal 7 yang menentukan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan terlihat penggunaan istilah dalam bingkai rechtsstaat dan pelembagaan dunia peradilan administrasi negara sebagai 21 Lihat cuplikan perdebatan tersebut dalam, Moh. Mahfud MD, op. Cit., hlm. 135-136. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 55 cermin dari penganutan atas konsep negara hukum yang bersumber dari tradisi Eropa Kontinental. Selain itu, ketentuan tersebut juga menciptakan pemahaman bahwa konsepsi Negara Hukum Pancasila berakar pada individualisme yang lebih mengutamakan hak sipil dan politik, sebagaimana yang dikenal dalam konsep negara hukum formal yang berakar pada legisme. Namun demikan, pada saat yang bersamaan tampak ciri-ciri negara hukum material yang sangat kental mewarnai UUD 1945. Adanya tujuan negara yang dengan tegas mengharuskan pembangunan ‘kesejahteraan umum’ dan menjadikan ‘keadilan sosial’ sebagai salah satu prinsip kehidupan bernegara tidak dapat memberi kesimpulan selain penegasan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum material yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum, melainkan juga bertugas menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila.22 Kaitannya dengan ambiguitas tersebut, Sjahran Basah mengatakan bahwa mengingat Pancasila telah dijabarkan di dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945, seperti pasal 27, 28, 29, 30, dan 34, maka di Negara Hukum Indonesia terdapat hak dan kewajiban asasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan, tetapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan kepentingan keselamatan bangsa, serta moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Konsepsi yang demikian tersebut, hak perorangan menjadi diakui, dijamin, dan dilindungi namun dibatasi oleh dua hal, yakni fungsi sosial, yang dianggap melekat pada hak milik; dan corak masyarakat Indonesia, yang membebankan manusia perorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga masyarakat, dan sesamanya.23Sementara menurut Philipus M. Hadjon, Negara 22 Lihat, Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dielaborasikan pada Batang Tubuh, seperti tergambar pada Pasal 22, Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34. Pada Pasal 22 mempertegas adanya pengaruh konsep negara hukum material yang berintikan pada pembangunan kesejahteraan umum sebagai tugas pemerintah. Pada Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 23 56 Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Dr. Rohidin, M. Ag Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:24 a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasaan negara. c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari empat ciri tersebut, lanjut Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pemerintah seyogianya diarahkan kepada:25 a. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum yang preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan hukum yang represif. b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah. c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remidium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan haruslah mencerminkan suasana damai dan tenteram—terutama melalui hukum acaranya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsep Negara Hukum Pancasila, yang menjadi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 149. 24 Philipus M. Hadjon, op. Cit., hlm. 90. 25 Ibid., hlm. 90. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 57 dasar hukum Negara Indonesia, merupakan konsep sintesis dari berbagai konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Secara substantif, konsepsi sintesis Negara Hukum Pancasila mewakili semangat demokrasi dan hukum yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Istilah tersebut dipakai guna mengakomodasi berbagai karakter dan nilai yang tumbuh di Indonesia, seperti kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keserasian. Karena hukum diformulasikan dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat, maka hukum harus sesuai dengan hukum dan akar budaya masyarakat Indonesia.26 Nilai-nilai khas tersebutlah yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya sehingga muncul istilah hukum Pancasila yang jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik.27 Konsep ini menurut Riggs, 26 Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, dalam Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 10. 27 Istilah konsep hukum prismatik yang digagas oleh Mahfud MD dalam memahami konsepsi Negara Hukum Pancasila, sebenarnya diilhami oleh teori optik garapan Fred W. Riggs. Teori tersebut mengiaskan pesan sebagai cahaya yang masuk ke prisma (segi tiga). Selain sebagai pemantul cahaya, prisma juga memantulkan dirinya sendiri sebagai pelakunya. Dalam teori tersebut, Riggs membagi masyarakat menjadi tiga varian:tradisional, prismatik, dan modern. Riggs menilai masyarakat tradisional (memusat) sebagai masyarakat askriptif, partikularistik, dan kekaburan. Menurutnya, model masyarakat tradisional cenderung memandang dunia hanya dari sudut pandang kekeramatan, supranatural, pandangannya hirarkis, dan lingkungannya dipenuhi upacaraupacara. Adapun masyarakat modern (memencar), dalam pandangan Riggs, merupakan hubungan antarpribadi yang bersifat terbuka, proliferasi, dan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Sedangkan masyarakat prismatik, oleh Riggs diletakkan di antara dua model masyarakat sebelumnya, di mana pluralitas budaya dan sosial dalam masyarakat prismatik akan memantulkan pesan dari bentuk memusat menuju memencar. Masyarakat jenis demikian, dalam penilaian Riggs tidak lagi mempertontonkan perilaku secara dikotomis. Relevansi istilah teori optik ini dengan konsep Negara Hukum Pancasila adalah terletak pada varian masyarakat prismatik. Sebagaimana telah dijelaskan, Riggs memosisikan varian masyarakat prismatik di antara masyarakat tradisional dan modern, sementara konsep hukum prismatik merupakan kombinasi atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial petembayan. Lihat, Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 23. 58 Dr. Rohidin, M. Ag sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, merupakan kombinasi atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan.28 Dua nilai sosial ini saling memengaruhi warga masyarakat, yakni kalau nilai sosial paguyuban lebih menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan lebih menekankan kepada kepentingan dan kebebasan individu.29 Nilai prismatik diletakkan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosio-kultural masyarakat yang bersangkutan.30 Senada dengan teori masyarakat prismatik ini, H.L.A. Hart menteorikan bahwa masyarakat itu terdiri atas tatanan yang Primary rules of obligation dan Secondary rules of obligation. Lihat, H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, London, 1972, hlm.89-96. Bandingkandengan, Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, t.t., hlm. 43-45. Masyarakat yang berada pada peringkat primary rules of obligation ditandai dengan kondisi seperti berikut: (1) komunitas kecil, (2) didasarkan pada ikatan kekerabatan, (3) memiliki kepercayaan dan sentimen umum, dan (4) berada di tengah-tengah lingkungan yang stabil. Dalam kondisi seperti itu masyarakatnya tidak mengenal peraturan terperinci, hanya mengenal standar tingkah laku, dan tidak ada diferensiasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum. Penyelesaian sengketa pada masyarakat semacam ini relatif masih sangat sederhana. Hal itu disebabkan masyarakatnya berupa komunitas kecil yang didasarkan atas kekerabatan, sehingga mekanisme kontrol sosial yang ada telah dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Sedangkan pada masyarakat dengan peringkat secondary rules of obligation, masyarakatnya mempunyai kehidupan terbuka, luas, dan kompleks. Kondisi tersebut menandai lahirnya dunia hukum dan ditinggalkannya dunia pra-hukum, bersamaan dengan munculnya tiga macam kaidah, yaitu: (1) rules of recognition, (2) rules of change, dan (3) rules of adjudication. Masing-masing kaidah (rules) tersebut memegang otoritas untuk menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Lihat, Esmi Warassih Pujirahayu, “Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum”; dalam Masalah-Masalah Hukum No. 2 Tahun 1995, hlm. 20. 28 Ibid., hlm. 20. 29 Ankie M. Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat sedang Berkembang, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 87. 30 Ibid., hlm. 176. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 59 Ragaan. 2.1. Konsep Masyarakat Prismatik. Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs Masyarakat Prismatik (HukumPrismatik) Masyarakat Tradisional (Hukum Tradisional) Masyarakat Modern (Hukum Modern) Menurut Mahfudz MD., setidaknya ada empat hal supaya prismatika hukum dapat diwujudkan. Pertama, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan negara hukum yang menekankan pada civil law, dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum the rule of law, yang menekankan pada common law, dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law, as tool of social engineering) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law). Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau mengendalikan suatu agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan tanpa agama (karena bukan negara sekuler). Di sini negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasarkan pertimbangan 60 Dr. Rohidin, M. Ag mayoritas dan minoritas.31 Konsep Negara Hukum Pancasila yang bersifat prismatik inilah yang bisa dijadikan titik tolak pemikiran dalam merekonstruksi hukum kebebasan beragama di Indonesia. B. 1. Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Arti dan Cakupan Konsep Kemanusiaan Istilah kemanusiaan (humanity) berasal dari kata dasar manusia, yang diartikan dengan makhluk yang berakal budi. Secara lexical meaning kata kemanusiaandiartikan dengan: sifat-sifat manusia, secara manusia, sebagai manusia, dan perikemanusiaan, segala sesuatu yang layak bagi manusia.32 Noor Ms. Bakry mengikuti analisis logis, yang memasukkan manusia dalam kelompok jenis hewan, yaitu organisme yang berindra, sedang ciri pembeda bagi manusia untuk membedakan hewan yang lain, karena manusia mempunyai akal budi yang dapat mengatasi perjuangan hidupnya.33 Dari kata manusia muncul istilah kemanusiaan, yang dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran, sikap, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan universal. Nilai-nilai ini dapat berupa pertimbanganpertimbangan tentang baik-buruk secara naluriah yang tertanam dalam hati nurani manusia. kemanusiaan sebagai pandangan atau sikap hidup yang mengakui bahwa manusia khusus, karena manusia memiliki struktur tersendiri, mempunyai tendensi-tendensi tersendiri serta sikap dan hubungannya terhadap dunia dan sesamanya yang tersendiri pula. Karenanya, cara hidup, Mahfud MD, “Mimpi Demokrasi dari Bung Karno”, Jawa Pos, 27September 2006. 31 32 Dendy Sugono (red.), op. Cit., hlm. 987. 33 Noor Ms. Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberti, Yogyakarta, 2001, hlm. 102. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 61 cara berbahagia, caranya bekerja sama yang melekat pada diri manusia mempunyai ciri-ciri yang khas, dan tidak terdapat di luar lingkungan manusia.34 Hal demikian tersebut secara teknis diatur oleh sumber daya kejiwaan, yaitu: akal, rasa, dan kehendak. Akal terfokus pada kebenaran, rasa terfokus pada keindahan, dan kehendak terfokus pada kebaikan. Ketiganya saling memengaruhi, sehingga berbasis pada keterpaduan tiga elemen tersebut, manusia dapat mengerti nilai-nilai hidup manusiawi yang sesuai dengan ide kemanusiaannya. Secara praktis konsep kemanusiaan dipahami bahwa setiap manusia memiliki hak yang asasi untuk mendapat penghidupan sedemikian rupa, sehingga ia bebas dari kesengsaraan, kekangan, dan paksaan. Setiap manusia harus mempunyai mental yang mengakui hak-hak itu. Karenanya, konsep kemanusiaan memiliki tuntutan berupa usaha bersama untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dengan saling menghormati hak-hak insani, dengan saling menghormati kebebasan manusia. Kepentingan bersama tersebut sekaligus mengindikasikan pengertian bahwa kekuasaan negara adalah untuk kepentingan warga negaranya. Bagi Driyakara, pemerintah yang merepresi kemanusiaan adalah pemerintah yang inhuman. Pemerintah diberi kekuasaan menyelenggarakan tata tertib umum, supaya menciptakan kondisikondisi yang diperlukan untuk berbagai macam usaha manusia.35 Sebagai sebuah organisme, secara hakikat manusia memiliki unsur-unsur monodualis sebagai berikut:36 34 A. Sudiarja (ed.), Karya Lengkap Driyakara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dengan Perjuangan Bangsanya, Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, dan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 708-709. 35 Ibid., hlm. 712. 36 Disarikan dari: Noor Ms. Bakry, op Cit., hlm. 16-19. dan Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa , Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 162167. 62 Dr. Rohidin, M. Ag a. Susunan Kodrat Manusia Pada hakikatnya manusia tersusun dari jiwa dan raga. Keduanya berkait berkelindan satu sama lain, tanpa raga bukanlah manusia, demikian juga tanpa jiwa. Jiwa manusia ini tersusun atas sumber daya akal, rasa, dan kehendak, sementara raga manusia tersusun atas: zat benda mati, zat nabati, dan zat hewani. Apabila dalam kehidupannya manusia hanya mementingkan aspek kejiwaannya saja, maka akan sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan duniawi yang bersifat jasmani. Hal senada juga berlaku pada saat manusia hanya mementingkan aspek raganya saja, maka akan sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan rohani. Artinya, keseimbangan keduanya merupakan harga mati dalam kehidupannya. Berkaitan dengan statusnya sebagai warga Negara Indonesia, keseimbangan Pancasila. Sehingga, tujuan negara yang berdasarkan Pancasila adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera, baik lahir maupun batin. b. Sifat Kodrat Manusia Pada hakikatnya manusia memiliki dua sifat mendasar berupa individu dan sosial. Hal ini dapat terlihat pada inkonsistensi dominasi sifat tersebut dalam sikap dan perbuatannya seharihari, sewaktu-waktu sifat individualnya yang lebih mendominasi dan sewaktu-waktu sifat sosialnya yang lebih dominan. Dua sifat kodrati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai unsur kodrat manusia. Jika dalam kehidupannya manusia selalu didominasi oleh sifat individu saja, maka ia akan terlihat individualis atau liberalis. Demikian juga sebaliknya, jika dalam kehidupannya manusia hanya didominasi oleh sifat sosial saja, maka ia akan terlihat sosialis atau kolektif. Artinya, dalam pola hidup yang manusiawi keseimbangan keduanya adalah harga mati.Berkaitan dengan statusnya sebagai warga Negara Indonesia, Pancasila. Sehingga, tujuan negara yang berdasarkan Pancasila adalah untuk mewujudkan masyarakat yang penuh kebahagiaan dengan basis relasi manusia dengan masyarakatnya yang selaras, Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 63 serasi, dan seimbang, masyarakat yang berpaham kebersamaan dan kekeluargaan. c. Kedudukan Kodrat Manusia Pada hakikatnya manusia berkedudukan sebagai pribadi mandiri dan juga sebagai makhluk Tuhan. Hal tersebut tampak bahwa manusia adalah pribadi berdiri sendiri yang mampu untuk berkreasi dan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri dan juga menyadari dirinya sebagai makhluk Tuhan. Dua hal ini tidak dapat dimungkiri karena memang demikian kenyataanya. Jika dalam kehidupannya manusia, baik secara pribadi maupun bersama-sama, selalu menampakkan dirinya sebagai pribadi yang berdiri sendiri terlepas dari pengaruh Tuhan, maka kelompok manusia yang seperti ini hanya tampak mengandalkan kemampuan akalnya, sehingga manajemen kehidupan bersamanya diatur atas dasar pola pemikirannya sendiri tanpa adanya pengaruh dari ajaran Tuhan. Hal senada juga terjadi, jika manusia dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun bersama, selalu menampakkan sebagai makhluk Tuhan tanpa memerhatikan manusia sebagai pribadi yang mandiri, maka kelompok manusia yang seperti ini dalam kehidupan bersamanya selalu mengandalkan ajaran dari Tuhan dengan tafsiran yang dangkal tanpa menggunakan pertimbangan akal budi. Artinya, keseimbangan akan dua kesadaran tersebut adalah harga mati bagi manusia dalam menjalani hidup. Berkaitan dengan warga Negara Indonesia, keseimbangan dua unsur ini Pancasila. Hal tersebut tampak jelas pada lima pasalnya. 2. Konsep Kebebasan Beragama Berbasis manusiaan yang Adil dan Beradab Ke- Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, bahwa kebebasan beragama di Indonesia secara yuridis-normatif telah diatur secara mapan melalui sila pertama Pancasila sebagai kerangka dasarnya. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti bebas tanpa batas hingga membentur hak dan kebebasan orang lain. Dengan 64 Dr. Rohidin, M. Ag kata lain, hukum kebebasan beragama di Indonesia didasarkan pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Unsur yang terkandung dalam sila tersebut adalah berupa: adil dan beradab serta keadilan dan keadaban.37 Sebagai pribadi yang mandiri, hubungan manusia antarsesama secara individu, dengan masyarakat secara komunal, dengan negara secara administratif, dan dengan setiap manusia secara universal, mempunyai hak dan kewajiban. Secara praktis, hubungan keduanya seimbang, di mana tidak ada penekanan kepentingan atas salah satu dari dua hal tersebut. Hak-hak yang dimiliki setiap individu manusia dalam bernegara dan bermasyarakat di antaranya adalah: hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak perlindungan atas kesehatan, hak jaminan sosial di hari tua, dan hak beragama dan (ber)-keyakinan. Hak-hak tersebut wajib dihormati dan diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masing-masing manusia dengan tetap memerhatikan statusnya sebagai makhluk sosial. Jika pelaksanaan hak-hak tersebut hanya terbatas pada pemenuhan dirinya sebagai makhluk individu belaka, maka yang akan terjadi adalah seseorang cenderungmerugikan kepentingan manusia yang lain, baik disadari ataupun tidak. Meskipun demikian, kepemilikan hak-hak tersebut tidak berarti secara mutlak ia bebas untuk melaksanakan haknya, melainkan dibatasi oleh adanya kewajiban terhadap sesama manusia, masyarakat, maupun negara. Artinya, kata adil dalam sila kedua dari Pancasila tersebut dipahami sebagai bentuk kewajiban bagi pemerintah maupun manusia, secara individu maupun komunal masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia agar dapat hidup layak sebagaimana manusia seutuhnya. Hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia tidak boleh dirampas oleh pihak lain. Karena itu, pemaksaan untuk mengikuti kehendak pihak lain dengan menggunakan kekerasan tidak dapat ditoleransi, karena secara mendasar pemaksaan secara kekerasan atas manusia 37 Noor MS Bakry, Pancasila: YuridisKenegaraan, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 65 merupakan suatu bentuk pembudakan. Karenanya, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak setiap manusia. Pemenuhan kewajiban tersebut, baik terhadap lingkungan masyarakatnya maupun terhadap pemerintah dan negaranya, sebagai konsekuensi logis atas statusnya sebagai makhluk sosial. Ketentuan yang berlaku dengan pengertian sila kedua di atas, sebagaimana telah dilansir sebelumnya, adalah bahwa setiap manusia diakui memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban, dan selaras dengan prinsip keadilan. Karenanya, apa yang telah menjadi hak setiap manusia, terlebih persoalan keberagamaan yang menjadi fokus buku ini, secara individu adalah objek penghormatan bagi siapa pun. Penghormatan di sini mesti diimbangi pula dengan pemenuhan kewajiban oleh setiap pribadi manusia terhadap lingkungannya, karena manusia tidak hanya mempunyai pengertian sebagai makhluk individu saja tetapi juga sebagai makhluk sosial. Namun demikian, pengertian perikemanusiaan atau internasionalisme di atas juga mesti diimbangi dengan kesadaran bahwa manusia yang merupakan satu umat itu, duduk di berbagai bagian dari muka bumi yang satu sama berbeda dalam keadaan tanah dan iklimnya, dan lain-lain, sehingga perbedaan sifat dalam diri masing-masing manusia adalah keniscayaan. Perikemanusiaan atau internasionalisme dalam konteks Indonesia di sini sudah barang tentu terkait erat dengan kultur masyarakatnya. Dengan melihat konteks masyarakatnya yang terumuskan dalam slogan “Bhineka Tunggal Ika”, sila pertama dan kedua dalam Pancasila sebagai dasar negara, dan status religious nation state yang berbasis pada hukum, maka konsep kebebasan beragama di Indonesia dapat dirumuskan dengan pola jaminan perlindungan atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama serta keyakinan dan agama itu sendiri yang berbasis pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian, untuk menuju masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban tersebut diperlukan pembumian konsep civil society dalamkehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa basis itu, kiranya mustahil bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang bebas beragama dengan basis keadilan dan berkedaban. 66 Dr. Rohidin, M. Ag 3. Membumikan Civil Society: Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Berkeadaban a. Tinjauan Umum tentang Konsep Civil Society Sebagai sebuah wacana kontemporer, hingga saat ini belum ada satu kesepakatan mengenai rumusan teoretis dan konsep yang baku tentang civil society, civil society sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa di mana konsep tersebut akan diterapkan. Sebagai titik tolak, civil society dari berbagai pakar di berbagai negara yang menganalisis dan mengkaji fenomena tersebut.38 Pertama, latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Ia mengatakan yang dimaksud dengan civil societyadalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubunganhubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Oleh karenanya, yang dimaksud civil society adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara dalam civil society ini diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni individulisme, pasar (market) dan pluralisme. Batasan yang dikemukakan oleh Rau ini menekankan pada adanya ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada dalam civil society, yakni individulisme, pasar (market), dan pluralisme. 38 Dalam konteks Indonesia, konsep civil society ini mengalami penerjemahan yang berbeda-beda dan dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, dan civil society itu sendiri. Lebih lanjut lihat dalam, A. Ubaidillah (dkk.), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 138-141. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 67 Kedua, latar belakang kasus Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa civil society merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela terbesar dari sebuah negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersamasama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidarlitas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini. Konsep yang dikemukakan oleh Han ini menekankan pada adanya ruang publik (public sphere) serta mengandung empat ciri dan prasyarat bagi terbentuknya civil society, yaitu (1) diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara, (2) adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa pun dalam mengartikulasikan isu-isu politik, (3) terdapat gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu, dan (4) terdapat kelompok inti di antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial-ekonomi. Ketiga, Kim Sunhyuk, masih dalam konteks Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan civil society adalah suatu satuan yang terdiri atas kelompokkelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakangerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan dasar dari (re)-produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pada adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang relatif memosisikan secara otonom dari pengaruh dan kekuasaan negara. Eksistensi organisasi-organisasi ini mensyaratkan adanya ruang publik (public sphere) yangmemungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. 68 Dr. Rohidin, M. Ag Berbagai batasan dalam memahami terma civil society di atas, jelas merupakan suatu analisis dari kajian kontekstual terhadap performa yang diinginkan dalam mewujudkan civil society. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan penekanan (aksentuasi) dalam mensyaratkan idealisme civil society. Akan tetapi, dari ketiga batasan di atas secara global dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan civil society adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Dengan kata lain, meskipun belum dapat dikatakan telah terjadi semacam pembakuan konseptual hingga saat ini, setidaknya ada beberapa esensi dari makna civil society tersebut. Pertama, adanya individu dan kelompok-kelompok mandiri dalam masyarakat (politik, ekonomi, dan kultur). Kemandirian ini diukur terutama ketika mereka berhadapan dengan kekuatan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai tempat wacana dan kiprah politik bagi warga negara. Ruang publik inilah yang menjamin proses pengambilan keputusan berjalan secara demokratis. Ketiga, kemampuan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara, kendati tidak melenyapkannya secara total. Negara, bagaimanapun juga tetap diperlukan kehadirannya sebagai pengawas dan pelerai penjamin keamanan internal dan perlindungan eksternal.39 Adanya fakta keragaman pada aspek pemahaman tentang makna civil society tersebut bukan saja disebabkan karena teori tentang civil society terus mengalami perkembangan, namun juga karena konteks di mana teori-teori itu dikembangkan mengalami banyak perubahan. Perdebatan mengenai civil society yang terjadi akhir-akhir ini, sebagian besar muncul dari perbedaan perspektif teoretis yang digunakan serta kemampuan dalam melakukan kontekstualisasi dalam ruang sejarah dan masyarakat tertentu. Tokoh-tokoh seperti Ernest Gellner, Norberto Bobbio, dan Serif 39 Muhammad A.S. Hikam, Islam: Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. x. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 69 Mardin, merupakan sebagian nama dari para pakar yang telah menunjukkan beberapa kesulitan dan problematika penerapan konsep civil society dalam beragam konteks masyarakat. Kendati demikian, kesulitan-kesulitan dan problematika tersebut tidak serta-merta harus diterjemahkan dengan tertutupnya kemungkinan.40 Konsep civil society sendiri telah mengalami perubahan pemahaman selama lebih dari dua abad terakhir, mulai dari era hingga akhir abad kedua puluh ketika konsep tersebut “ditemukan” kembali oleh para aktivis pro-demokrasi. Dalam rentang waktu tersebut, setidaknya konsep civil society telah dipergunakan dalam beberapa pengertian, yaitu: (1) sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat, (2) sebagai sistem kenegaraan, (3) sebagai sebuah elemen ideologi kelas dominan, dan (4) sebagai kekuatan penyeimbang dari tegaknya sebuah negara. b. Karakteristik Civil Society 1) Free Public Sphere Free public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang yang bebas, individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksitransaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Hannah Arendt dan Habermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoretis bisa diartikan sebagai wilayah, di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara 40 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hefner, bahwa upaya untuk melaksanakan gagasan dan kiprah civil society bukanlah hal yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh sebuah “insting peradaban lama.” Justru sebaliknya, ia ditentukan oleh budaya dan lembaga yang senantiasa membutuhkan perubahan-perubahan dan ia masih berada dalam jangkauan manusia untuk melakukannya. Lihat, Robert Hefner, “A Muslim Civil Society?: (ed.), History and Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal, Transaction Press, New Brunswiek, 1998, hlm. 286. 70 Dr. Rohidin, M. Ag merdeka setiap menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta memublikasikan informasi kepada publik. Sebagai prasyarat untuk mengembangkan dan mewujudkan civil society dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena ruang publik yang bebas dalam tatanan civil society, maka akan memungkinkan terganggunya aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiran dan otoriter. 2) Demokrasi Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak implementasi civil society dalam kehidupan. Salah satu asumsi yang dapat dikemukakan adalah bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu sebuah sikap demokratis dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Dengan kata lain, demokrasi bahkan merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan civil society. Penegakan demokrasi di sini mencakup berbagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Sedikit bergeser ke wilayah wacana demokrasi dalam konteks Islam, menarik jika kita membaca pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang demokrasi. Baginya, konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Menurut Gus Dur, terdapat beberapa alasan mengapa Islam dikatakan sebagai agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan ( ). Artinya, adanya tradisi bersama dalam membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.41 41 Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi, PT Remaja Rosdakarya, Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 71 Masih dalam konteks demokrasi, prisma pemikiran Gus Dur yang lain juga terkait pembelaan terhadap minoritas. Undangundang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat terkait kebebasan berpendapat, hak mendapatkan keamanan, serta hak memilih dan berpindah agama, di mana Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas. Lebih jauh, ia mengatakan:42 “…merupakan pengingkaran hakikat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak akan pernah tercapai.” Dalam konteks ke-Indonesia-an yang pluralis, hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memosisikan syariah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya, seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan rule of law. Dari sini, dapat dibaca bahwa pemikiran demokrasi Gus Dur menunjukkan bahwa ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh ᏕL\Ɨ¶DO'ƯQ5D¶LV43 Bandung, 1999, hlm. 85. Meski banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang inkonsisten karena sering membuat manuver dan ide-ide yang membingungkan dan dianggap menyesatkan umatnya, namun justru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan bahwa ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmennya dalam menyuarakan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, termasuk pembelaan terhadap perempuan), serta keadilan bagi setiap warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi. 42 Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia,LKiS, Yogyakarta, 1995, hlm. 111. 43 72 Dikutip dari, Ibid., hlm. 115. Dr. Rohidin, M. Ag “Saya bersedia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak memperdulikan kutipan dari Injil atau Bhagawad Gita, kalau benar maka harus kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat-ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, tetapi sudah pemikiran.” Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Singkatnya, rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual. 3) Toleransi Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persolan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak, antara berbagai kelompok yang berbedabeda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani (civil society) lebih dari sekadar gerakan-gerakan pro-demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu pada kehidupan yang berkualitas dan tamaddan (civility). Sipilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandanganpandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 73 4) Pluralisme Sebagai sebuah prasyarat penegakan civil society, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu dengan penilaian positif sebagai bentuk rahmat Tuhan. Menurut Nurcholish Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani (civil society). Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities with in the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check andbalance). Dengan demikian pluralisme di sini dapat kita pahami sebagai pandangan yang menghargai kemajemukan serta menghormati pihak lain (other), membuka diri terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi (sharing), serta keterbukaan untuk saling belajar (inklusivisme). Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monopolitik. Jadi, tidak ada masyarakat yang tunggal, monopolitik, yang sama dan sebagun dalam segala segi. 5) Keadilan Sosial (Social Justice) Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat.Seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). 74 Dr. Rohidin, M. Ag Selain kelima karakteristik sebagaimana telah dikemukakan di atas, masih ada satu elemen penting yang dari awal juga harus menjadi dasar pemikiran, yaitu adanya pengakuan terhadap hak-hak kemanusiaan. Tanpa didasari oleh elemen pengakuan ini, niscaya kelima karakteristik di atas akan sulit—untuk tidak mengatakan mustahil—untuk dapat terlaksana.44 c. Pilar-Pilar Penegak Civil Society Yang dimaksud dengan pilar penegak civil society adalah institusiinstitusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritik kebijakan-kebijakan pihak penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan civil society, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat. Pilarpilar tersebut antara lain adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik. 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu LSM dalam konteks civil society juga bertugas mengadakan empowering (pemberdayaan) kepada 44 Sebagaimana kita pahami bersama, istilah kemanusiaan (humanity) berasal dari kata dasar manusia, yang diartikan dengan makhluk yang berakal budi. Dalam kamus kata tersebutdiartikan dengan:sifat-sifat manusia, secara manusia, sebagai manusia, dan perikemanusian, segala sesuatu yang layak bagi manusia. Lihat, Dendi Sugono (red.), op. Cit., hlm. 987. Sementara Driyarkara kemanusiaan sebagai pandangan atau sikap hidup yang mengakui bahwa manusia itu merupakan makhluk yang tersendiri mempunyai tendensi-tendensi tersendiri serta sikap dan hubungannya terhadap dunia dan sesamanya yang tersendiri pula. Karenanya, cara hidup, cara berbahagia, caranya bekerja sama yang melekat pada diri manusia mempunyai ciri-ciri yang khas, dan tidak terdapat di luar lingkungan manusia. A. Sudiarja (ed.), op. Cit., hlm. 708-709. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 75 sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi programprogram pembangunan masyarakat. 2) Pers Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan civil society.Pers punya kemampuan untuk mengkritik dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisis serta memublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan. Sebagaimana diketahui, lewat pers—terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya—kita dapat mengetahui berbagai informasi lebih cepat. Maka tidak berlebihan kiranya jika kemudian Ilham Prisgunanto mengatakan bahwa pers adalah tonggak kekuatan kelima bagi suatu bangsa, sebab tanpa pers negara menjadi tidak transparan dan rakyat akan buta dengan kinerja pemerintah.45 Lebih dari itu, pers, sebagaimana ditulis Yenrizal dan Rus’an Rusli, diyakini bisa masuk ke dalam semua ruang yang selama ini tertutup rapat tak terjamah (untouchable)46 dan juga memiliki tanggungjawab dan keberpihakan kepada suara kebenaran masyarakat (social responsibility). Selain itu, pada tataran ideal, pers juga memiliki peran sebagai kontrol sosial, yaitu dengan memberitakan hal-hal yang sifatnya pengawasan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sehingga dengan sendirinya, pers mampu membentuk opini publik serta mampu memberikan tekanan terhadap pihak-pihak yang berbuat kesalahan. 45 Ilham Prisgunanto, Praktik Ilmu Komunikasi dalam Kehidupan Seharihari, Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 11. 46 dalam Suyitno (ed), Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 234. 76 Dr. Rohidin, M. Ag Menurut Burhan Bungin, dalam menjalankan paradigmanya sebagai institusi pelopor perubahan, pers memiliki peran:47 a) Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu sebagai media edukasi. b) Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. c) Sebagai media hiburan sekaligus institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan serta katalisator perkembangan kebudayaan. 3) Supremasi Hukum Setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar-warga negara dan antar-warga negara dengan pemerintahan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tinggi. Selain itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar normanorma hukum serta segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpola bentuk kehidupan yang civilized. 4) Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi (PT) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat dan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Dengan catatan, gerak yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memosisikan diri pada rel dan realitas yang betul-betul 47 Lihat, Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 85-86. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 77 objektif dan menyatakan kepentingan masyarakat (public). Sebagai bagian dari pilar civil society maka PT memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruksi untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Di sisi lain, PT memiliki “Tri Dharma PT”, yang harus dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat (public). Menurut Riswanda Immawan, PT memiliki tiga peran yang strategis dalam mewujudkan civil society. Pertama, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupanpolitikyang demokratis. Kedua, membangun political safety net, yakni dengan menggambarkan dan memublikasikan informasi secara objektif dan tidak manipulatif. Political safety net ini setidaknya dapat mencerahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi. Ketiga, melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis, serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarkis. 5) Partai Politik Partai Politik (parpol) merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politik dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warganegara, maka parpol menjadi prasyarat bagi tegaknya civil society. Berkaitan dengan upaya penguatan civil society di Indonesia, maka Muslim sebagai pihak mayoritas menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Upaya penguatan civil society di Indonesia tidak bisa mengabaikan pentingnya faktor umat Islam. Bahkan, dalam beberapa hal tertentu, bisa dikatakan bahwa keberadaan Muslim merupakan basis perubahan politik dan sosial di Indonesia. Mereka memiliki potensi yang sangat besar dalam menentukan format dan kehidupan politik Indonesia. Begitu pula dalam upaya 78 Dr. Rohidin, M. Ag penguatan civil society, Muslim menduduki posisi terdepan yang bisa diharapkan menjadi pengimbang dari kekuatan negara yang cenderung dominatif. Dengan ungkapan lain, Muslim Indonesia memiliki prasyarat—setidaknya secara kuantitatif—bagi pertumbuhan dan penguatan civil society di Indonesia. Dalam hal ini, menurut Dawam Raharjo ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan civil society di Indonesia. Pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi. Kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Ketiga, strategi yang memilih membangun civil society sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu, strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.48 Ketiga model strategi pemberdayaan civil society tersebut di atas dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target grup yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan serta 48 Dawam Raharjo, “Masyarakat Madani: Demokrasi, Kemajuan dan Keadilan.” Makalah dalam seminar “Strategi Penguatan Civil Society di Indonesia,” 23-25 Oktober 1998 di Bogor. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 79 mahasiswa adalah mutlak adanya, karena merekalah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdayaan tersebut.49 Penanaman pola hidup berbasis civil society ini menjadi penting dalam kehidupan beragama di Indonesia karena di dalamnya sarat dengan masyarakat yang penuh dengan sikap toleran dan berkeadilan. Bahkan, dengan membuminya konsep tersebut, bisa jadi Indonesia tidak membutuhkan lagi bentuk regulasi tentang kehidupan beragama. Sebaliknya, dengan bentuk regulasi semapan apapun jika civil society tidak tertanam dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara maka jaminan kehidupan beragama hanya akan menjadi mimpi belaka. Namun demikian, untuk menuju kehidupan yang berbasis civil society, baik sistem, aparatur pemerintah, maupun masyarakat harus sama-sama menopangnya dengan penuh kesungguhan. Dengan tanpa kebersamaan tiga elemen tersebut sangat sulit kiranya civil society akan membumi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 49 80 A. Ubaidillah (dkk.), op. Cit., hlm. 157. Dr. Rohidin, M. Ag TIGA RENTANG BASIS IDEOLOGI KEBEBASAN BERAGAMA Sebagai bagian dari HAM, kebebasan beragama tidak bisa dilepaskan dari pertarungan beberapa ideologi. Dalam rentang sejarah perdebatan HAM terdapat setidaknya dua basis ideologi dalam memandang universalitas HAM dan kebebasan beragama. Dua basis ideologi ini berada pada dua titik ekstrem yang saling bertolak belakang. Titik ekstrem pertama adalah ideologi partikular-absolut yang memahami HAM dan juga kebebasan beragama bersifat partikular secara absolut. Kebebasan beragama di satu tempat tidak bisa diterapkan di tempat yang lain. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan agama yang benar-benar bebas dan berlaku untuk setiap tempat, kondisi, dan masa. Titik ekstrem kedua adalah ideologi universal absolut yang memahami HAM dan kebebasan beragama berlaku secara universal penuh. Ideologi ini memahami bahwa sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia semenjak lahir di dunia, kebebasan beragama tidak mengenal batasan apa pun dan pembatasan oleh siapa pun. Ideologi ini mengambil posisi berlawanan penuh terhadap ideologi pertama tadi. Nah, di antara dua titik ekstrem ini penulis akan berupaya menghadirkan jalan tengah. Untuk konteks Indonesia, penulis menawarkan ideologi Pancasila untuk menghadirkan titik tengah. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 81 A. Ideologi Partikular-Absolut Persepsi Eksklusif Basis Pembentukan Pandangan partikularisme menyangkut HAM dilatarbelakangi bahwa setiap bangsa memiliki latar belakang ideologi, sosial, dan budaya masing-masing yang sudah barang tentu memiliki perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain.1 Dengan universalisme HAM kepada seluruh lapisan bangsa adalah mustahil. Terlebih lagi, universalisme HAM tersebut tidak lain merupakan produk budaya Barat yang sudah barang tentu mengandung banyak perbedaan dengan budaya Timur, yang nota bene banyak didiami dan dianut oleh negera-negara berkembang. Sistem kebersamaan (communal), yang telah lama ada dan menjadi warisan dari generasi awal mereka merupakan prinsip fundamental dan sistem masyarakat Timur. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan cara pandang masyarakat Barat yang cenderung berbasis pada prinsip individualistik. Bagi masyarakat Timur, prinsip keadilan sosial dibentuk bukan berdasarkan HAM yang setara, melainkan status sosial yang tidak setara dan gabungan “privilese” dengan tanggung jawab, bahkan kelompok partikularisme mengatakan bahwa keberadaan masyarakat tradisional adalah untuk menentang universalisme HAM yang sudah menjadi asumsi.2 Penolakan masyarakat tradisional terhadap individualismeini menyatukan mereka ke dalam misi bersama untuk menghadapi resiko kehancuran budayanya. Pada saat masyarakat yang merupakan bagian dari budaya-budaya yang diromantisasi ini dianggap bukan sebagai individu yang riil—yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan nafsu—melainkan sebagai benda pameran antropologi yang hidup, maka HAM bisa terlewatkan dan tidak mungkin memiliki keinginan yang terkonstruksi secara 1 Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat: Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 115. 2 82 Rhoda E. Howard, HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, terj. Dr. Rohidin, M. Ag sosial dalam hal HAM seperti yang dimiliki masyarakat Barat, sebagai masyarakat yang dianggap beradab dan tetap terisolasi. Masyarakat tradisional tidak bisa perpikir abstrak, keluar dari lingkungannya untuk meninjau hakikat kehidupan sosial atau etika kelompoknya. Dengan demikian, memasukkan pandangan ideal HAM, bahkan ke dalam wacana lisan dengan masyarakat tradisional, adalah tindakan imperialis, menimbulkan proses perubahan sosial yang akan merusak tatanan sosial pribumi.3 Masyarakat Barat sendiri pada mulanya adalah masyarakat “tradisional”. Mereka telah mengalami proses perubahan sosial selama berabad-abad, bukan merupakan konsekuensi dari penegakan HAM bercorak indivisualistik secara tiba-tiba. Masyarakat tradisional yang masih ada dianggap sebagai asalusul manusia modern. Masyarakat Barat memerlukan masyarakat tradisional, bahkan ketika organisasi sosial mereka mengeksploitasi, atau kejam terhadap banyak anggotanya agar mereka bisa menikmati kemurnian masa lalu yang penuh dengan mitos. Integralistik organis masyarakat tradisional, kesatuannya dengan alam, tekanan terhadap pilihan individu mendorong keinginan Barat akan dunia khalayan yang lebih bersahaja. Masyarakat tradisional adalah komunitarian terbaik, yang tidak dicemari oleh individualisme. Dalam masyarakat mereka, tidak seorang pun mempertanyakan aturan; setiap orang, bahkan yang paling rendah, hidup harmonis dengan yang lain dan dengan penguasa.4 Para kritikus universalisme HAM dari kelompok partikularis mencari dunia yang tidak ada lagi. Kalau pun pernah ada, hal itu tidak lebih sebagai suatu dunia komunitas, dunia individu-individu yang bersatu dalam kelompok dan dunia yang terpadu dan menyatu dengan alam. Pembelaan kelompok partikularis terhadap budayabudaya pribumi yang menentang HAM, yang telah mengalami proses universalisasi hingga pada tingkat tertentu, merupakan konsekuensi dari rasa khawatir mereka bahwa universalisme HAM akan mendorong munculnya dunia sosial yang terindividualisasi, atomistis, dan kompetitif. Kelompok partikularis mengidealisasikan 3 Ibid., hlm. 109. 4 Ibid., hlm. 109-110. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 83 komunitas Dunia Ketiga yang memberi teladan bagi budaya Barat tentang masyarakat tradisional yang aman dan tenteram dan telah hilang darinya, sekalipun Dunia Ketiga memperlihatkan banyak pelanggaran HAM pada awal modernisasi.5 Cara hidup tradisional mengisyaratkan jiwa cemas orang Barat mengingatkan mereka pada asal-usul kolektif asli yang merupakan asal-muasal mereka. Individu-individu yang hidup dalam masyarakat tradisional, pra-kapitalis komunitarian, seperti orang-orang yang diminta Levi-Straus untuk tinggal di hutan, tidak diperbolehkan berubah atau berpikir tentang apa yang mereka inginkan dalam kehidupan. Sudah barang tentu jika mereka tidak diperbolehkan menolak impian utopia dengan mengadopsi ideide Barat.6 Suku-suku masyarakat tradisional di Dunia Ketiga kini tidak diperbolehkan tertarik mengadopsi atau mendukung pandangan-pandangan individualis tentang otonomi pribadi atau HAM. Mereka yang berbuat demikian segera disingkirkan karena dianggap berubah “menjadi Barat”, yaitu tidak asli, merusak peran psikologis yang mereka jalankan untuk orang Barat. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa gagasan Barat tentang HAM sejauh yang dinyatakan oleh elit-elit politik Dunia Ketiga, mencerminkan “westernisasi” elit ini.7 Oleh karena itu, meskipun masyarakat Barat menghargai kebebasan intelektual dalam tradisi mereka, mereka menolak hal itu bagi kaum intelektual dari tradisi lain; kaum intelektual dari tradisi lain dianggap sebagai teladan konservatif, bukan penentang radikal nilai-nilai budaya mereka sendiri.8 Dengan demikian, kelompok partikularisme absolut memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan 5 Ibid., hlm. 110. 6 Ibid., hlm. 110-111. 7 Penyeragaman cara pandang berdasarkan Komentar Umum ( Common) dari PBB atau bahkan penuntutan penggunaan paradigma yang biasa dipakai kaum liberal (baca: universal-absolut) untuk membatasi atau mengukur hak kebebasan yang ada di Negara Hukum Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk intervensi (intoleransi) luar atau Barat juga. Simak pertanyaan Munarman, sebagai Pihak Terkait dari Pemerintah, terhadap Siti Juhro dalam Sidang Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965 pada hari Rabu 17 Maret 2010 di Gedung MK Jakarta. 8 84 Ibid., hlm. 111. Dr. Rohidin, M. Ag alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen/instrument-instrumen hukum internasional berkaitan dengan HAM, sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensif, dan pasif tentang HAM. Cara pandang di atas kemudian melahirkan kelompok yang memiliki persepsi eksklusif terhadap HAM. Kelompok ini memandang bahwa HAM tidak bisa digunakan untuk kebebasan beragama. Amirsyah, seorang anggota MUI misalnya, berpendapat bahwa HAM tidak boleh merusak kedaulatan suatu agama, sebab jika atas nama HAM kemudian merusak nilai-nilai agama, jelas hal itu tidak benar.9 Senada dengan Amirsyah adalah pernyataan Jainal Abidin, Pengurus MUI D.I. Yogyakarta,menurutnya HAM harus dipahami sebagai produk budaya, karena ia tidak bisa dilepaskan dari nilaiHAM Barat, sementara Islam berangkat dari wahyu. Karena perbedaan itulah, maka HAM di Barat dan Timur, termasuk Indonesia, itu berbeda. Berkaitan dengan fatwa MUI, menurut Jainal tidak bisa atas dasar HAM kemudian merusak nilai-nilai agama. Apa yang terjadi pada kasus Ahmadiyah, sesungguhnya Ahmadiyah-lah yang melanggar HAM, bukan MUI-nya, karena dalam ajaran Ahmadiyah sendiri banyak yang mendeskriditkan kelompok misalnya.10 Lebih tegas dari Jainal adalah pernyataan Sobri Lubis, Sekjen FPI, baginya mereka (baca: Ahmadiyah) telah halal darahnya (baca: boleh dibunuh), karena telah merusak akidah Islam yang benar. “Persetan kitab HAM, tai kucing kitab HAM”, tegas Lubis saat mengaitkan kasus Ahmadiyah dengan persoalan HAM.11 Mendekati 9 Wawancara dengan Amirsyah, anggota MUI pada tanggal 1 Februari 2010. 10 Wawancara dengan Jainal Abidin, Pengurus MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis, 18 Agustus 2011. 11 Ungkapan ini disampaikan oleh Sobri Lubis dalam sebuah Tabligh Akbar di Kota Bogor pada tanggal 14 Februari 2008. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 85 Jainal dan Lubis adalah pernyataan Adian Husaini, baginya dunia Islam tidak menjadikan DUHAM sebagai “kitab suci”, dan tidak bersedia begitu saja mengadopsi sepenuhnya pasal-pasal dalam DUHAM. Bahkan, seseorang yang mempercayai piagam ini, bagi Adian, sesungguhnya telah meletakkannya di atas al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Dengan demikian, sesungguhnya mereka telah menjadikan teks piagam lebih tinggi kedudukannya dari teks kitab suci umat Islam.12Artinya, nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang bersifat partikular-absolut lebih dijunjung daripada universalisme individumanusia berkaitan dengan HAM. Oleh karena itu, bagi mereka, apa yang dilakukan MUI, sudah berada di jalur yang tepat. Jika kita bertolak dari teori persepsi Blumer, dapat dipahami bahwa persepsi eksklusif terhadap fatwa MUI tentang aliran sesat berkaitan dengan konsep kebebasan beragama terkonstruk sebagai pengaruh dari penggunaan ideologi partikular-absolut dalam memandang HAM. Sehingga sangat wajar jika agama, sebagai bagian dari partikularisme, lebih dijunjung daripada universalisme yang cenderung individualistik. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan ideologi partikular-absolut berkaitan dengan HAM ini tampak kurang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Konstruksi demikian tampak bersifat theosentris, dengan tanpa melihat unsur kemanusiaan sebagai realitas psikis dari pemeluk agama itu sendiri. B. Ideologi Universal-Absolut Persepsi Inklusif-Liberal Basis Pembentukan Asal mula dan perkembangan HAM tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral.13 Sejarah perkembangan 12 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2005, hlm. 84. 13 Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral secara rasional. Asal-muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan 86 Dr. Rohidin, M. Ag HAM dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus yang, meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang “benar” dan yang “konvensional”. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia di antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. “Hukum alam” ini sudah ada menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada “reason”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga. Dasar dari doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Penikmatan kita atas kepentingan mendasar tersebut dijamin oleh hak-hak alamiah yang kita miliki. Hukum alam ini seharusnya menjadi dasar dari sistem sosial-politik yang dibentuk kemudian. Oleh sebab itu, hak alamiah diperlukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Dengan demikian hak alamiah adalah valid tanpa perlu pengakuan dari pejabat politis John Locke, yang menyampaikan argumennya dalam karyanya, Two Treaties (1688). Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik mana pun, Locke melanjutkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan jurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani monarki atau sistem. Lihat, Knut D. Asplund (dkk.) (ed.), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 19-20. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 87 Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dimungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.14 Dalam model partikularisme, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih, dan persamaan. Perihal yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negara-negara tersebut mengacuhkan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep nation state dari Barat dan tujuan moderenisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi. Pemahaman HAM dari sudut pandang univeralisme lebih dilatarbelakangi oleh terbentuknya instrumen-instrumen hukum internasional berkaitan dengan HAM. Secara mendasar hak fundamental manusia terletak pada dua hal. Pertama, hak asasi manusia (human rights), yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Hal ini erat kaitannya dengan eksistensi hidup manusia, bersifat statis dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Wujud hak ini di antaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan emansipasi wanita. Kedua, hak undang-undang (legal rights), yaitu hak yang diberikan undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undangundang.15 Sebagai instrumen perundang-undangan, HAM kemudian 14 Ibid., hlm. 20. 15 I Gede Arya B. Wiranta, “Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis”, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, 88 Dr. Rohidin, M. Ag masyarakat agar masyarakat mengetahui dan berupaya untuk mengembangkan sarana-sarana pendukung agar apa yang terkandung dalam HAM dapat ditaati. Hal demikian membawa dampak pada perundang-undangan HAM yang dapat berlaku secara efektif, untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya pencanangan perundang-undangan HAM dengan baik, pelaksana dalam menunaikan tugasnya dapat searah dan senafas dengan bunyi serta penafsiran yang telah disepakati, penegak HAM harus menuntut para pelanggarnya.16 Cara pandang di atas sampai pada tataran tertentu menjadi basis bagi terbentuknya persepsi kelompok inklusif-liberal. Betapa tidak, bagi mereka perbedaan penafsiran dalam bingkai keagamaan adalah suatu keniscayaan. Otoritas tafsir tidak hanya dimiliki oleh seseorang atau lembaga tertentu, oleh karena itu kebenaran tafsir bersifat relatif dan tidak pernah serta tidak akan pernah ada tafsir 16 G.G. Howards dan Rummers, Law It’s Nature and Limits, New Jeresey Prestic Hall, 1999, hlm. 4647. Instrumen-instrumen hukum intemasional menyangkut HAM adalah sebagai berikut: The Universal Declaration of Human Rights, 1948 (DUHAM); The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); The International on Economic, Social and Cultural Rights,1966 (Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya); The Optional Protocol on Civil and Political Rights, 1967 (Protokol Tambahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); The International Convention on 1948 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dari Pemberian Hukuman Kejahatan Genosida); The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1969 (Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial); The International Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women, 1981 (Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan); The International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi Internasional Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Bermartabat); The International Convention on the Rights on the Child, 1989 (Konvensi Internasional Tentang Hak Anak); The International Convention Relating to the Status of Refuges, 1951 (Konvensi Internasional yang Berhubungan dengan Status Pengungsi); dan The International Protocol Relating to the Status of Refuges,1967 (Protokol Internasional yang Berhubungan dengan Status Pengungsi). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 89 tunggal. Pemahaman ahli ilmu tafsir dan keislaman selalu beragam, bahkan bisa jadi saling bertentangan. Dalam keadaan seperti ini justru, Nabi Muhammad saw., menggambarkan sebagai situasi yang penuh rahmat, dengan catatan setiap pihak bersedia untuk berdialog dan membangun toleransi keagamaan bagi kemuliaan kemanusiaan, bukan mengubah keyakinan dengan cara klaimklaim sepihak seperti sekarang ini.17 Lebih dari itu, fatwa MUI tentang aliran sesat kegamaan, bagi mereka, telah melanggar basis-basis moral Islam universal serta bertentangan dengan HAM, khususnya hak dan kebebasan beragama. Kebebasan beragama yang bersifat bebas tanpa batas, bagi mereka, hanya ada pada forum internum, sementara kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinannya digolongkan dalam kebebasan bertindak (freedom to act).18 Kebebasan beragama dalam bentuk ini dapat dibatasi dan diatur hanya berdasarkan undang-undang. Artinya, nilai-nilai universalisme berkaitan dengan HAM, khususnya dalam hal beragama, menjadi titik tolak pembentukan persepsi mereka. Individu manusia menjadi prioritas utama mereka dalam memandang fatwa berkaitan dengan kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM. Pola pikir semacam ini sudah barang tentu sangat antroposentris, bahkan unsur-unsur teosentris dalam agama menjadi kabur. Dengan demikian, unsur-unsur partikular yang terdapat dalam setiap agama tidak mereka indahkan. Akibatnya, pandangan mereka berkaitan dengan kebebasan beragama justru tercerabut dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang terakumulasi dalam konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dengan basis kemanusiaan yang adil dan beradab. 17 Wawancara dengan Munir Mulkhan pada tanggal 4 Mei 2010. Telusuri lebih lanjut dalam “Kala Fatwa jadi Penjara”, hlm. 169. 18 Wawancara dengan Hanick, Aktivis ICRP, pada tanggal 2 Februari 2010 di Jakarta. 90 Dr. Rohidin, M. Ag C. Ideologi Pancasila Sebagai Solusi atas Disharmoni Persepsi dalam Bingkai Kebebasan Beragama Perdebatan tentang HAM, baik yang bersifat universal maupun partikular (cultural relativism), sudah lama berlangsung, dan sudah barang tentu jika kedua pandangan tersebut disatukan merupakan hal yang sangat sulit, sebab masing-masing berdiri pada posisinya. Perdebatan keduanya tidak akan berakhir jika masing-masing pandangan berakar pada titik tolak yang berbeda, terutama dalam hal ideologi dan sosial-budaya dari sistem masyarakat yang berbeda. Pandangan universalitas HAM didasari dari pandangan yang bersifat individual, terutama adanya tuntutan kebebasan individu (warga negara) yang muncul dari sistem masyarakat yang liberal. Hal ini dapat dibuktikan dari perjalanan panjang sejarah HAM di Barat, baik yang terjadi di Inggris, Amerika, maupun Prancis, yang pada waktu itu menuntut adanya pembatasan kekuasaan bagi penguasa (Raja). Tuntutan kebebasan dan perlunya pembatasan kekuasaan bagi penguasa pada waktu itu, dengan perjalanan yang panjang membuat masyarakat Barat meracik konsep HAM tersebut lahirnya Piagam Magna Charta, Deklarasi Virginia, Deklarasi Independen, Bill of Rights, dan Declaration des Droits del’homme et du Citoyen. Piagam-piagam tentang HAM ini dijadikan dasar tentang adanya tuntutan tentang kebebasan dari warga negara dan adanya pembatasan bagi penguasa terutama dalam menjalankan sistem pemerintahan. Baru pada abad ke-19, setelah berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional terhentak untuk kembali secara bersama-sama merumuskan konsepsi-konsepsi dasar HAM ini dalam bentuk aturan yang bersifat hukum internasional yang akan diberlakukan ke seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia ini. Keinginan ini dilakukan mengingat sebagai akibat dari adanya Perang Dunia II tersebut, di mana banyaknya korban umat manusia serta hancurnya peradaban mereka, sehingga perlu dibangun secara bersama peradaban umat manusia tersebut dengan tetap menghormati harkat martabat manusia (dignity). Akhirnya, pada tahun 1948 dirumuskanlah konsepsi HAM tersebut dalam sebuah deklarasi sebagaimana yang dikenal dengan UDHR, yang kemudian Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 91 diikuti dengan aturan-aturan hukum internasional yang lain, yaitu: ICCPR, ICESCR (1966), serta Protokol Tambahan ICCPR (1967). Keseluruhan instrumen hukum internasional ini sudah menjadi bagian hukum positif internasional yang akan diberlakukan secara universal dan mengikat bagi bangsa-bangsa dan negara-negara Mereka yang berpaham partikularisme (cultural relativism) menyangkut HAM tentunya sangat sulit menerima paham universal HAM produk Barat tersebut. Hal ini terjadi karena HAM Barat tersebut tidak sesuai dengan paham ketimuran, terutama bagi negara-negara berkembang. HAM yang ada dan lahir di Barat tidak sama dengan HAM yang ada di Timur. Sebab masyarakat Timur selalu mengedepankan kepentingan kebersamaan (sense communal), sehingga berbeda dengan masyarakat Barat yang mengedepankan kepentingan individu. Dalam pandangan ketimuran,prinsip keadilan sosial bukan berdasarkan HAM yang setara, melainkan status sosial yang tidak setara dan gabungan privilese dengan tanggung jawab. Sehingga masyarakat ketimuran menentang universalitas HAM sebagaimana yang dimiliki Barat. Berkaitan dengan disharmoni di atas—dalam konteks kebebasan beragama—penggunaan ideologi Pancasila dapat dijadikan sebagai solusinya. Hal demikian dianggap relevan mengingat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai representasi dari budaya bangsa, terkandung di dalamnya. Unsur yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila tersebut adalah berupa: adil dan beradab serta keadilan dan keadaban. Hal demikian dapat disederhanakan dalam ragaan sebagai berikut: 92 Dr. Rohidin, M. Ag Ragaan 3.1. Penggunaan Ideologi Pancasila sebagai Solusi atas Disharmoni Persepsi dalam Bingkai Kebebasan Beragama HAM Universalisme Partikularisme Universal-Absolut Universal-Relatif Universal-Absolut Antroposentris Theo-Antroposentris Theosentris Humanistik Kolektivisme Individualisme PANCASILA Konsep Kebebasan Beragama Berbasis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Fatwa MUI Persepsi Eksklusif Persepsi Inklusif-Moderat Persepsi Inklusif-Liberal Pancasila, bagi Kaelan, merupakan ruh dari budaya bangsa. Berkaitan dengan fatwa dan kebebasan beragama, sebagai bagian dari HAM, Pancasila memuat unsur-unsur theo-antroposentris. Di samping Pancasila menjamin hak-hak individu, Pancasila juga melindungi agama itu sendiri. Artinya, warga negara berhak dan bebas dalam hal memeluk keyakinan atau agama, tanpa adanya intervensi, tetapi ia juga harus menghormati keberadaan keyakinan atau agama lain, tegas Kaelan.19 19 Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2011 di UGM Yogyakarta. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 93 Sebagai individu yang mandiri, relasi antar sesama manusia secara individu, dalam bingkai masyarakat secara komunal, dengan negara secara administratif, dan dengan antar manusia secara universal, mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan keduanya secara praktis seimbang, di mana tidak ada intervensi apapun atas salah satu dari dua hal tersebut. Hak-hak yang dimiliki setiap personal manusia dalam bernegara dan bermasyarakat, tarmasuk hak beragama dan berkeyakinan, wajib dijamin, dihormati, dan diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh setiap personal manusia dengan tetap memerhatikan statusnya sebagai makhluk sosial. Jika pemenuhan hak-hak tersebut hanya terbatas pada dirinya, sebagai makhluk individu belaka, maka yang terjadi adalah kecenderungan untuk merugikan kepentingan manusia lain, disadari ataupun tidak. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak tersebut tidak berarti secara mutlak ia bebas untuk melaksanakan haknya, melainkan dibatasi oleh adanya kewajiban terhadap sesama manusia, masyarakat, maupun negara. Artinya, kata adil dalam sila kedua dari Pancasila tersebut dipahami sebagai bentuk kewajiban bagi pemerintah maupun manusia, secara individu maupun komunal masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia agar dapat hidup layak sebagaimana manusia seutuhnya. Pemahaman tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa penghormatan atas setiap pribadi manusia merupakan kewajiban tersendiri bagi seseorang, sebagai pribadi, kelompok masyarakat, maupun bagi pemerintah. Hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia tidak boleh dirampas oleh pihak lain. Karena itu, pemaksaan untuk mengikuti kehendak pihak lain secara kekerasan tidak dapat ditoleransi, karena secara mendasar pemaksaan dengan kekerasan atas manusia merupakan suatu bentuk pembudakan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak setiap manusia. Pemenuhan kewajiban tersebut, baik terhadap lingkungan masyarakatnya maupun terhadap pemerintah dan negaranya, adalah konsekuensi logis atas statusnya sebagai makhluk sosial. 94 Dr. Rohidin, M. Ag Ketentuan yang berlaku dengan pengertian sila kedua di atas, sebagaimana telah dilansir sebelumnya, adalah bahwa setiap manusia diakui memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban, dan selaras dengan prinsip keadilan. Karenanya, apa yang telah menjadi hak setiap manusia, terlebih persoalan keberagamaan, secara individu adalah objek penghormatan bagi siapa pun. Penghormatan di sini mesti diimbangi pula dengan pemenuhan kewajiban oleh setiap pribadi manusia terhadap lingkungannya, karena manusia tidak hanya mempunyai pengertian sebagai makhluk individu saja tetapi juga sebagai makhluksosial. Namun demikian, pengertian perikemanusiaan atau internasionalisme di atas juga mesti diimbangi dengan kesadaran bahwa manusia yang merupakan satu umat itu, duduk di berbagai bagian dari muka bumi yang satu sama berbeda dalam keadaan tanah dan iklimnya, dan lain-lain, sehingga perbedaan sifat dalam diri masingmasing manusia adalah keniscayaan. Perikemanusiaan atau internasionalisme dalam konteks Indonesia di sini sudah barang tentu terkait erat dengan kultur masyarakatnya. Model demikiantampaknya menjadi basis ideologi dari terbentuknya persepsi inklusif-moderat. Sehubungan dengan itu, Kaelan mengungkapkan bahwa berkaitan dengan fatwa tentang aliran sesat, MUI memang memiliki hak untuk melakukan penilaian. Jika ada suatu kelompok yang melakukan penodaan terhadap agama maka negara harus menghukumnya, karena penodaan terhadap agama memang diatur dalam perundangundangan. Namun demikian, tegas Kaelan, tidak serta-merta fatwa MUI menjadi landasannya, karena fatwa hanya bersifat legal opinion, bahkan, dalam kasus Ahmadiyah misalnya, MUI harus berhati-hati. Lebih-lebih jika MUI membiarkan fatwanya dipersepsikan (pen.mewujud) dalam bentuk tindakan anarkis.20 Sejalan dengan Kaelan adalah Wawan, baginya dalam sejarah perjalanan Islam, kelompok mainstream selalu memiliki otoritas untuk menilai sebuah ajaran itu menyimpang atau tidak. Asalkan argumentasinya jelas, hal itu tidak masalah. Justru menjadi masalah ketika sudah disesatkan lantas hak-hak sipil mereka dibatasi atau 20 Ibid. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 95 bahkan dilanggar. Sehingga, ragam sebagai akibat dari fatwa, tandas Wawan, harus benar-benar dicegah, baik oleh MUI sendiri, lebih-lebih oleh negara, sebagai pelindung agama dan kelompok keagamaan.21 HAM dalam perspektif Pancasila, dengan demikian, di samping mengamini nilai-nilai universal juga menghormati keberadaan nilai-nilai partikular yang dimiliki oleh setiap bangsa. Artinya, HAM dalam perspektif Pancasila sejalan dengan pandangan universalisme-relatif. Pandangan ini meyakini bahwa persoalan HAM merupakan perihal universal, namun menyangkut pula tentang pengecualian (exeptions) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional untuk tetap diakui keberadaannya. 21 96 Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2010 di Sleman Yogyakarta. Dr. Rohidin, M. Ag EMPAT Konstruksi Baru Kebebasan Beragama Problem intoleransi dalam ranah keagamaan di Indonesia bisa dikatakan cukup marak. Hal ini tampak dalam berbagai aksi yang terjadi mulai dari bersifat lunak hingga menggunakan pemerintah, pemuka agama, elit politik, dan aparat penegak hukum ternyata tidak satu visi. Mereka justru terbelah ke dalam dua kubu yang saling bertolak belakang bahkan cenderung berseteru. Fakta menunjukkanbahwa tak jarang tindak intoleransi satu pihak memicu tindak intoleransi pihak lain dalam skala yang lebih luas. Sebab itulah, kita perlu menghadirkan konstruksi baru kebebasan beragama yang bisa menjembatani dua kubu tersebut sekaligus sesuai dengan Pancasila sebagai norma dasar Negara Hukum Indonesia. A. Potret Intoleransi Keagamaandi Indonesia Dilihat dari perspektif agama, Indonesia merupakan negara keberagamaan masyarakat terbagi ke dalam lima agama lain: Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun demikian, secara ideologis dan religio-politis Indonesia bukanlah “Negara Islam,” Indonesia tetap menjadi negara yang didasarkan kepada ideologi resmi, yang dikenal dengan Pancasila: (1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau monoteisme; (2) kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) persatuan Indonesia; (4) Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 97 demokrasi; dan (5) keadilan sosial. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, telah menawarkan lima dasar dalam Pancasila tersebut sebagai bagian dari modus vivendi antara nasionalisme sekuler yang diwakili oleh kaum nasionalis-sekuler dan gagasan negara Islam yang diwacanakan oleh kaum nasionalis-Islam.1 Dari sini, dapat dilihat bahwa negara memiliki peran yang sosial, termasuk di dalam wilayah kehidupan beragama setiap warga negaranya. Meskipun demikian, agama dan negara bukanlah dua entitas yang menyatu dan juga tidak berarti sama sekali terpisah, namun keduanya memiliki peranan yang berbeda dalam mengatur kehidupan manusia dalam bidangnya masing-masing. Negara mengatur manusia dalam hubungannya dengan pemerintah dan mengatur hubungan manusia sebagai subjek hukum dengan sesama subjek hukum lainnya, sementara agama mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesama dalam pergaulan dan hubungan dengan Tuhannya. Sehingga, dalam posisi ideal, negara dapat bekerjasama dengan agama, dan lebih jauh dengan berbagai aliran kepercayaan yang ada, untuk kemudian secara tegas menciptakan kerukunan dan kedamaian di antara masyarakat dan menegakkan hukum yang berlaku serta, pada titik tertentu, menentang segenap tindakan anarkisme atas nama agama. Akan tetapi, pada dimensi faktualnya, di Indonesia— sebagaimana juga yang terjadi di wilayah negara lain—seringkali agama dan negara (baca: politik) menjadi entitas yang tumpang tindih. Sebagai akibatnya, agama kerapdijadikan sebagaialat legitimasi dan manipulasi untuk kepentingan dan target politik. Di era pemeritahan Soeharto, misalnya, seringkali negara mengkooptasi Islam untuk mengontrol kekuasaannya. Hal ini 1 Selain melewati perjalanan yang cukup panjang, penetapan lima dasar dalam Pancasila tersebut juga tidak sepi dari perdebatan dan tarik-ulur kepentingan yang berakhir pada penghapusan tujuh kata yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Lihat, misalnya, dalam Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 37-43. Bandingkan dengan Siti Musdah Mulia “Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi” dalam Elza Peldi Taher (ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Efendi, ICRP, Jakarta, 2009, hlm. 335. 98 Dr. Rohidin, M. Ag berujung pada pembentukan beberapa organisasi keagamaan berbasis kelembagaan oleh pemerintah seperti MUI, yang kemudian dijadikan sebagai legitimasikebijakan politik pemerintah. Efek lain dari hal ini adalah intervensi negara yang terlampau jauh masuk dalam ranah garapan agama dan urusan moral seperti persoalan keyakinan (akidah) warganya dalam memilih dan memeluk agama dan kepercayaan tertentu yang berakhir pada pembatasan kebebasan warganya dalam beragama melalui beragam aturan hukum.2 Seiring dengan berjalannya waktu, beragam produk hukum yang membatasi dan melarang kebebasan warganya untuk menganut agama dan keyakinannya ini, ternyata telah melahirkan beragam pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (violation of right to freedom of religion or belief).3 Sebagai contoh adalah fenomena kekerasan seputar kebebasan beragama di Indonesia yang dari tahun ke tahun justru semakin memburuk jika dibandingkan dengan era sebelum reformasi. Praktik kekerasan—baik dalam bentuk pengusiran, penghancuran tempat ibadat, maupun intimidasi dan pemaksaan, baik secara 2 Intervensi yang dilakukan negara ini tentu dirasa berlebihan mengingat persoalan akidah dan keyakinan merupakan hak setiap warga negara yang justru harus dilindungi dan mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana yang telah digariskan dalam undang-undang. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Presiden Soeharto di hadapan peserta Rapat Kerja Depag (sekarang Kemenag) pada tanggal 24 Maret 1984, bahwa: “Negara dan pemerintah kita menghormati kebebasan beragama bagi setiap penduduk dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama adalah masalah keyakinan, dan tidak ada satu kekuasaan duniawi yang mampu dan berhak mencampuri keyakinan hati seseorang. Apa yang harus kita lakukan adalah melayani hajat kehidupan beragama bangsa kita sebaik-baiknya dan seadil-adilnya…. Kita ingin kebebasan beragama benar-benar dilaksanakan sehingga tidak ada golongan agama, betapapun kecilnya jumlah mereka, yang merasa tertekan atau dibatasi kebebasan beragama mereka.” 3 Adalah setiap bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama dan keyakinan. Lihat, Ismail Hasani (ed.), Siding and Acting Intolerantly: Intolerance by Society and Restriction by the State in Freedom of Religion/ Belief in Indonesia, SETARA Institute, Jakarta, 2009, hlm. 14. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 99 agama minoritas atau sekte-sekte tertentu—menyebar semakin luas dan liar tidak terkendali. Bahkan tidak jarang di beberapa daerah, justru aksi kekerasan tersebut didukung oleh aparatur pemerintah seperti polisi. Di tengah upaya pemerintah era reformasi yang sedang berusaha untuk terus membumikan pelaksanaan HAM di negeri ini, tentu berbagai aksi anarkis berbasis agama tersebut menjadi sebuah anomali tersendiri. Dalam konteks ini, yang tampak kemudian adalah negara terkesan ambigu dan lemah dalam meregulasi wacana dan praktek kebebasan beragama di negeri ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan porsi dan proporsinya yang tepat. Ambiguitas ini salah satunya tampak dalam sikap negara yang terlalu jauh melakukan intervensi terhadap urusan akidah dan keyakinan seseorang atau sekelompok warga negara yang menganut keyakinan tertentu. Akan tetapi pada sisi yang lain, dalam beberapa kasus, kriminalitas dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang beragama terhadap kelompok lainnya dibiarkan begitu saja oleh negara tanpa ada tindakan hukum yang jelas. Padahal, dalam perspektif HAM kebebasan beragama atau berkeyakinan diletakkan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya (non derogable rights).4 Dalam konteks yang lain, jika kita mengacu kepada instrumen HAM, terdapat dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran: (1) dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan/atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama atau berkeyakinan (by commission); (2) dengan cara 4 Selain kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak-hak yang juga terkandung dalam prinsip non derogable rights ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas berpikir, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, setiap tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak di atas dari diri seseorang atau sekelompok orang, maka dapat digolongkan sebagai sebuah pelanggaran HAM. Ismail Hasani (ed.), op. Cit., hlm. 13-14. 100 Dr. Rohidin, M. Ag membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum (by omission).5 Sementara pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya secara garis besar mencakup: (1) tindakan kriminal berupa pembakaran rumah ibadat, intimidasi, intoleransi. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh negara, Ghufron Mahmudi menyatakan bahwa pelanggaran tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengambil jarak terhadap persoalan agama yang muncul di masyarakat. Kebebasan beragama dan keyakinan merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik yang dikategorikan sebagai hak negatif (negative rights)—berbeda dengan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang dikategorikan sebagai hak positif (positive rights), yang bisa terpenuhi jika negara ikut berperan aktif memajukannya. Sebaliknya, hak negatif bisa diwujudkan bila negara tidak terlalu banyak mencampuri urusan agama dan keyakinan tersebut.6 Pada tataran yuridis-formal, Indonesia sebenarnya telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. II/1978 tentang Pedoman Penghayat dan Pengamal Aliran Kepercayaan. 5 Wawancara dengan Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham UII), pada tanggal 20 Agustus 2011. Dalam beberapa kasus, terlihat sikap aparat keamanan yang membiarkan dan tidak melakukan pencegahan sehingga mendorong sekelompok orang untuk tetap melakukan aksinya seperti menutup tempat ibadat atau menyerangkelompok kepercayaan lain. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban di masyarakat, aparat keamanan seharusnya menindak pelaku kekerasan tersebut. Tetapi tidak jarang aparat keamanan membiarkan, seakan tindakan pelaku kekerasan dibenarkan. Tindakan pembiaran ini tentu tidak dapat dibenarkan karena sama halnya negara tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lihat, Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan”, Makalah dalam Annual Converence on Islamic Studies (ACIS) Ke-10 di Banjarmasin, 1-4 November 2010, hlm. 722. 6 Ibid., hlm. 722. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 101 Jaminan ini kemudian diperkuat dengan langkah pemerintah HAM yang mengatur jaminan kebebasan beragama dan keyakinan yaitu ICCPR khususnya Pasal 7 Tidak berhenti sampai di sini, berbagai produk kebijakan turunan, baik dalam bentuk Keppres, Perpres, Keputusan Bersama, dan fatwa melalui lembaga keagamaan, juga terus muncul sebagai upaya menjamin hak warga dalam beragama dan keyakinan. Dengan adanya konsep yang mapan dalam Konstitusi sebagaimana terurai sebelumnya, bagi penulis hal itu sudah cukup untuk menjadi referensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama secara menyeluruh. Sebab, secara normatif hal tersebut memang dapat dikatakan sudah cukup ideal (baca: indah). Akan tetapi, idealisme tersebut masih mengandung kesenjangan di ranah implementasi. Hal ini terbukti dengan masih maraknya praktik kekerasan berbasis agama yang dialami oleh kelompokkelompok minoritas, terlebih yang diklaim “sesat.” Pada bagian ini, akan dilihat tingkat keberhasilan implementasi berbagai peraturan tersebut dan sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya untuk menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan mengemukakan sekian tindak kekerasan8 yang terjadi 7 Pasal tersebut mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadat, penataan, pengamalan, dan pengajaran, (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya, (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban dan kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain, dan (4) Negara-negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Ismail Hasani (ed.), op. Cit., hlm. 8-9. 8 kepada manusia maupun barang dengan tujuan menghancurkan, merusak, atau melukai. Termasuk ke dalam kategori kekerasan ini adalah berbagai perusakan dan penyegelan secara ilegal terhadap sebuah tempat atau aset 102 Dr. Rohidin, M. Ag dalam era reformasi, yang kemudian akan dilakukan pada era Orde Baru dan Orde Lama.Data-data pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan di sini penulis kutip dari berbagai sumber, baik dalam bentuk buku maupun laporan penelitian berkala seperti yang dilakukan oleh SETARA Institute, The Wahid Institute, CRCS UGM maupun lembaga-lembaga lain. Dalam buku ini, dari seluruh bentuk-bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan munculnya fatwa tentang aliran sesat dari berbagai lembaga keagamaan dan/ atau yang mengandung unsur-unsur penyesatan yang disajikan secara kronologis dalam bentuk tabel. Penyajian berbagai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang hanya dibatasi pada konteks fatwa-fatwa ini sendiri bertujuan untuk menunjukkan bahwa keluarnya fatwa yang sedianya dimaksudkan untuk meredam maraknya berbagai aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas, justru dipersepsikan secara berlebihan oleh sebagian masyarakat melalui tindakan anarkis “berkedok” agama. Meskipun fatwa bukanlah satu-satunya alasan bagi terciptanya sebuah persepsi dalam bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM di masyarakat, namun paling tidak dapat dilihat bahwa ternyata pengeluaran fatwa penyesatan terhadap sebuah kelompok keyakinan/keagamaan bukanlah satu-satunya upaya rekonsiliasi yang tepat karena fatwa-fatwa tersebut masih memunculkan multi-tafsir di kalangan umat. yang dimiliki oleh sebuah kelompok keagamaan. Lihat, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008 CRCS, hlm. 11. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 103 Tabel. 4.1. Dinamika Kebebasan Beragama dan Keyakinan Berkaitan dengan Fatwa MUI Waktu 7 Mei 2005 16 Mei 2005 29 Juli 2005 104 Tempat Keterangan Kepanjen, Malang, Jatim - MUI Malang dan MUI Jatim mengeluarkan fatwa klaim sesat terhadap Muhammad Yusman Roy dalam kasus salat dua bahasa. - Bupati Malang mengajukan Yusman Roy ke Pengadilan dengan tuduhan penodaan agama. - Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen memvonis Yusman 2 tahun penjara. Desa Krampilan, Kec. Besuk, Kraksaan, Probolinggo MUI Kab. Probolinggo mengeluarkan fatwa penyesatan terhadap M. Ardhi Husein, Pimpinan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) Desa Krampilan, karena dianggap menyebarkan aliran sesat melalui bukunya Menuju Terang 2.” Husein diajukan ke pengadilan dengan tuduhan penodaan agama. Brebes Kepolisian dan Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes membubarkan kelompok Kanjeng Patih Kala Jenggel pimpinan Kasnawi, setelah dinyatakan sesat oleh MUI setempat. Dr. Rohidin, M. Ag 4 September 2005 14 November 2005 29 Desember 2005 Jl. Utan Kayu 68 H, Matraman, Jakarta Timur. Kurang lebih 30-an orang mendatangi Komunitas Utan Kayu dengan membawa spanduk bertuliskan “Kami Mendukung Fatwa MUI dan Mendesak Muspika Matraman untuk Mengusir JIL dan antek-anteknya”, “JIL Haram, Darah Ulil Halal”, dan lain-lain. Mereka juga menuntut agar JIL diusir dari Utan Kayu. Paseh, Kab. Sumedang - MUI Kecamatan Paseh menyesatkan kelompok Husnul Huluq. - Massa membakar rumah pengikut ajaran tersebut. Jakarta - Pada tanggal 22 Desember 1997 MUI memfatwa bahwa kelompok keyakinan pimpinan Lia Aminuddin sesat-menyesatkan. - Lia Aminuddin alias Lia Eden ditahan Polda Metro Jaya atas sangkaan melakukan penodaan terhadap agama dan menghasut atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya. Ia dijerat pasal 156a, 157, 335, dan 336 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 105 Januari 2009 11 Januari 2009 106 Perum Parahyangan Kencana, Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung Desa Jajar, Kec. Talun, Kab. Blitar Dr. Rohidin, M. Ag - Sekitar seratus massa dari Gerakan Reformis Indonesia (Garis) melakukan demo menyatakan kelompok Amanah Keagungan Ilahi (AKI) adalah sesat, mencoreng nama Islam, dan meresahkan masyarakat Muslim. - Perwakilan AKI, Garis, dan MUI melakukan negosiasi. Akhirnya perwakilan AKI menandatangani pernyataan menghentikan segala aktivitas dan kegiatan yang dinilai Garis menyimpang dari syariah Islam. - PAKEM melakukan kajian terhadap AKI dan memutuskan bahwa AKI pimpinan Wahyu Kurnia/Syamsu di Cangkuang tidak sesat. Sedangkan AKI versi Andreas sesat karena mencampuradukkanantara agama Islam dan agama lain. - Sekretaris MUI Blitar menyatakan bahwaaliran Tiket Masuk Surga (aliran Dununge Urip) yang dipimpin oleh Suliyani telah berkembang di Blitar beberapa bulan sebelumnya. Aliran ini mewajibkan seluruh pengikutnya menandatangani kesanggupan membayar sejumlah biaya untuk jaminan masuk surga dari Rp. 3 juta hingga Rp. 7 juta. - Ketua MUI menyatakan aliran ini sesat karena menyalahi syariah Islam dan polisi bisa menjerat pelaku dengan pasal penodaan agama. MUI meminta warga untuk tidak bertindak anarkis. Kapolres Blitar akan berkoordinasi dengan MUI untuk mengkaji aliran ini dan kalau terbukti sesat, aparat akan membubarkannya. Februari 2009 Sangkapura, Kab. Gresik - Menurut beberapa pihak, Ali Akbar aliasSoleh Akbar adalah Dukun Kampung yang membuka praktik pengobatan. Menurut MUI, Ali Akbar mempraktekkan aliran sesat. Menurutnya, Ali meminta pasiennya untuk memuja sebagai Tuhan, mengajarkan syahadat bahwa dirinya adalah Allah dan sekaligus Rasulullah serta menginjak-injak al-Qur’an. - Untuk menghindari amuk massa, pada tanggal 10 Februari 2009, polisi membawa Ali ke Polsek Sangkapura. Di Polsek, Ali membantah telah menginjakinjak al-Qur’an. Setelah ditahan 24 jam, kepolisian membebaskan Ali karena tidak memiliki bukti kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. - Menindaklanjuti kasus ini, MUI, para tokoh agama, dan Muspika Sangkapura menetapkan Ali Akbar harus keluar dari Sangkapura. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 107 6 Februari 2009 9 Juni 2009 Juni 2009 108 Kec. Diwek, Kec. Jombang, dan Kec. Tambelang di Jombang - Pengurus MUI Jombang menyatakan aliran Noto Ati adalah sesat. Menurutnya, aliran ini mengutamakan wirid dan mengabaikan al-Qur’an, menolak tradisi sungkeman Idul Fitri, fanatisme berlebihan terhadap guru, larangan bertakziyah, dan larangan terhadap anak-anak untuk bersekolah dan berinteraksi sosial. - Depag menerima laporan kajian MUI, namun Depag menyatakan aliran ini telah membubarkan diri. Luwu, Sulsel MUI Luwu mengeluarkan fatwa penyesatan melalui SK No. 2/MUS/ MUI-LW/VI/2009 berisi larangan paham keselamatan Ambo (dkk.) di Dusun Pandada. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi sebelumnya yang kemudian oleh Kejari Balopa akan diteruskan ke Bakorpakem Pusat sebagai landasan pelarangan. Desa Air Batu, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin Dr. Rohidin, M. Ag - Tarekat Naqsabandiyah mulai dianut luas di Air Batu sejak tahun 2005.Sebagian warga melaporkan ada 20 prinsip ajaran dalam ajaran Tarekat Naqsabandiyah di Air Batu yang menyesatkan seperti Tuhan Beranak, malaikat tidak pernah ada dan bila iman sudah sempurna, salat tidak wajib lagi. - Ketua MUI Merangin menyatakan pada dasarnya ajaran Tarekat Naqsabandiyah tidak sesat, tetapi praktiknya di Air Batu adalah sesat. - Pada 23 Juni 2009 diadakan pertemuan di kantor Depag (sekarang Kemenag) antara MUI dan pengikut Tarekat Naqsabandiyah. Hadir pula dalam pertemuan tersebut kepala Depag, Kasat Intel Polres, Camat, dan Kapolsek. MUI dalam pertemuan tersebut menyatakan aktivitas tarekat Naqsabandiyah segera dihentikan dan melarang guru Tarekat Naqsabandiyah Ali Wardana masuk ke Desa Air Batu. Juni 2009 Kawasan hutan lindung Kab. Luwu - Sejak tahun 2007, Ambo menyebarkan aliran Maddina Lekko Pini Bunda Maryam. Pengikutnya meyakini aliran ini sebagai salah satu agama yang diturunkan Allah SWT sebagai pelengkap ajaran Islam. - MUI mengadakan pertemuan di Kejari Belopa yang dihadiri oleh Muspida Kab. Luwu untuk membahas ajaran Ambo. Pertemuan berikutnya diadakan di Depag. Kemudian MUI menetapkan secara resmi dengan surat keputusan bahwa aliran yang dibawa Ambo menyesatkan karena tidak sesuai dengan agama dan adat di wilayah itu. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 109 - Kejari Belopa meneruskan fatwa ini ke Bakorpakem Pusat. Bersamaan menunggu keputusan Bakor Pakem Pusat, Bakorpakem Luwu mengawasi aktivitas pengikut paham ini. Ambo diperiksa oleh polisi pada akhir Juni 2009. Sebaliknya, 20 pengikut Ambo menyatakan bertaubat di depan aparat Kab. Luwu. 14 Oktober 2009 OktoberNovember 2009 110 Madiun, Jawa Timur Warga Dusun Tawangrejo Kec. Gumarang, Madiun yang tergabung dalam Forum Keadilan Masyarakat Babadan (FKMB) melaporkan ke MUI setempat bahwa ajaran yang dikembangkan Sukarno sesat. Sebelumnya warga juga menggerebek rumah Sukarno yang waktu itu kosong. Kelurahan Kranggan, Gg. 5, Mojokerto, Jatim - Pada Oktober 2009, MUI Mojokerto menyatakan bahwa Aliran Ilmu Kalam Santriloka pimpinan Anwar aliasAchmad Nafan aliasMbah Aan adalah sesat. Aliran ini memublikasikan VCD dan buku berjudul Wind of Change.Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Mojokerto pada 31 Oktober mendukung pernyataan MUI dan secara simbolis membakar buku dan VCD Santriloka. Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur juga berpendapat serupa. Dr. Rohidin, M. Ag - Menurut pihak-pihak yang tidak setuju dengan Santriloka di atas, Santriloka telah menistakan agama seperti mengajarkan puasa Ramadhan dan salat bukan suatu kewajiban. Al-Qur’an yang asli bukan berbahasa Arab, melainkan bahasa Kawi, Sansekerta, dan Jawa Kuno. - Pada 28 Oktober 2009, Mbah Aan mengajarkan ajaran-ajarannya di sebuah padepokan di Kelurahan Kranggan. Aliran ini memiliki pengikut sekitar 700 orang. Paginya, setelah malamnya memberikan pengajaran di padepokan tersebut, Mbah Aan ditangkap polisi dan dibawa ke kantor Polres Kota Mojokerto. Setelah 7 hari ditahan, pada 5 November, Mbah Aan ditetapkan sebagai tersangka. 12 November 2009 Desa Kauman, Kec. Kota, Kudus, Jateng - Diisukan Sabdo Kusumo alias Kusmanto Sujono menulis buku Syahadat Makrifat yang menyatakan Syahadat: “…dan saya bersaksi bahwa Sabdo Kusumo utusan Allah” (dalam bahasa Arab). - MUI mengumpulkan berkas tertulis ajaran Sabdo Kusumo dan membuat surat pernyataan ke Polres Kudus bahwa aliran yang memiliki pengikut sekitar puluhan orang tersebut sesat melalui surat pernyataan bernomor K.30/MUI/ XI/2009. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 111 - Depag memanggil Sabdo Kusumo untuk dimintai keterangan. Dia membantah telah menulis buku Syahadat Makrifat. Dia mengaku mengarang buku Sabdaning Suma: Kaweruh Sangkan Paraning Dumadi Ngalam Pernataning Itu pun yang menulis kata-katanya adalah temannya, Kholiq dan Abdul Latief. Sabdo Kusumo mengaku, yang juga ditegaskan istrinya, bahwa dia tidak bisa membaca dan menulis bahasa Arab. - Pada 12 November 2009 di depan pejabat Depag di Kantor Depag Kudus, Sabdo Kusumo menandatangani surat pernyataan tidak pernah menyebarkan ajaran menyesatkan sebagaimana tercantum dalam buku Syahadat Makrifat. 2 Desember 2009 112 Sumatera Selatan Dr. Rohidin, M. Ag Komisi fatwa MUI Sumatera Selatan menyatakan aliran Amanat Keagungan Illahi (AKI) sesat dan dilarang berkembang di daerah ini. Pelarangan dikeluarkan melalui fatwa bernomor A-003/SKF/MUISS/XII/2009 tentang ajaran AKI kelompok ini dinilai meniadakan kewajiban salat dan puasa bagi pengikutnya. Tabel. 4.2. Kekerasan Berbasis Identitas Keagamaan dan Perbedaan Pandangan atau Praktik Keagamaan Peristiwa Penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid Waktu (2008) 22 Januari Tempat Keterangan Kelurahan Bangan, Deli, Medan - 2 orang kritis, puluhan luka-luka. - Kelompok penyerang berupaya menghancurkan tempat pengajian Satariah Sahid. - Argumen penganut Satariah Sahid: “Meneruskan ajaran Syekh Abdurrahman Singkil, seorang penyebar agama Islam di masa lalu”. - Argumen penyerang: “Ajaran Satariah Sahid melenceng dari ajaran Islam”. - Akhirnya Camat Medan Belawan membekukan kegiatan Satariah Sahid untuk sementara waktu. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 113 Penyerangan terhadap fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa di Lombok Timur Bentrokan antara pengikut MMI dan umat Muslim di Lombok Timur 114 7 Maret 14-15 Maret Dr. Rohidin, M. Ag Desa Karleko, Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB Dusun Tereng, Desa Karleko, Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB - Sekelompok orang menyerang dan merusak fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa. - Pihak Darusy Syifa tidak bisa penyerang tersebut. - Pihak Darusy Syifa merasa tidak memiliki musuh dan masalah dengan lingkungan di sekitarnya. - Kasus ini telah dilaporkan ke Komnas HAM. - 1 orang luka parah di bagian kepala, beberapa korban luka-luka ringan, dan dua rumah terkena lemparan batu. perbedaan tata cara penyelenggaraan salat Jumat. Pengikut MMI menggunakan satu kali azan dan warga Muslim lainnya dua kali azan sebagaimana tradisi yang telah lama dipraktikkan. - Polisi menahan 3 anggota MMI. Bentrokan antara anggota Laskar Umat Islam (LUI) dan warga di Solo 17 Maret Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, Solo - 2 orang warga meninggal dunia dan 1 orang luka parah. - Belasan pemuda meminum minuman keras. Sekitar 100 anggota LUI menyerangnya. Beberapa pemuda meminta bantuan warga lainnya dan bentrokan semakin sengit sampai jatuh korban. - Poltabes Solo menetapkan 7 tersangka dalam bentrokan tersebut. - Atap 2 rumah tokoh - Dakwah kelompok Pengusiran warga terhadap tokoh aliran Lombok Barat 12 Mei Dusun Mesanggok, Gapuk, Geruk, Lombok Barat warga sering mendiskreditkan paham keislaman warga dengan menganggapnya bidय़ah dan sesat. - Puluhan warga mendatangi dan melempari rumah H. Mukti, tempat pengajian kelompok melempari rumah H. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 115 - Polisi mengevakuasi pengikutnya saat peristiwa terjadi. - Hasil musyawarah yang juga didatangi oleh Kadus Mesanggok, Kades Gapuk, Kapolsek, Kakandepag dan Ketua MUI Lobar memutuskan warga dan H. Mukti pindah dari kampung mereka. Penyerangan terhadap aksi damai Aliansi Kebangsaan danKebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas 116 1 Juni Dr. Rohidin, M. Ag Monumen Nasional (Monas), Jakarta - Tidak kurang dari 70 orang AKKBB terluka. - Massa dari Komado Laskar Islam (KLI) yang terdiri dari FPI dan HTI menyerang kelompok AKKBB yang sedang memperingati hari kelahiran Pancasila. - KLI menuduh AKKBB membela Ahmadiyah. - Polisi menangkap 59 aktivis KLI, menjadikan 8 orang di antaranya tersangka dan memvonis Rizieq Shihab dan Munarman 1,5 tahun penjara. Dari waktu ke waktu berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh kelompok yang diklaim sesat atau menyimpang semakin kasus kekerasan yang terjadi, Ahmadiyah menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran kekerasan dari berbagai kelompok di luar Ahmadiyah. Sebagaimana yang telah disaksikan, beragam aksi anarkis yang terjadi di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah ini justru semakin memburuk pasca-dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 3/2008, KEP-033/A/ JA/6/2008 pada 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat. Akibat dari dikeluarkannya SKB tersebut, tentu Ahmadiyah semakin terpojok untuk melakukan segala aktivitasnya karena adanya ancaman dari kelompok-kelompok penentangnya yang merasa mempunyai dasar hukum berdasarkan SKB untuk melarang segala jenis perkumpulan Ahmadiyah yang menjurus pada syiar keagamaan mereka. Selain itu, penganut Ahmadiyah juga tidak bisa bebas berkumpul dan berserikat dengan sesama anggota Ahmadiyah karena adanya ‘kecurigaan’ para penentang mereka.9 9 Hal ini tentu telah melenceng jauh dari apa yang ada di dalam SKB, sebab dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa semua jenis manifestasi keagamaan boleh dilakukan oleh Ahmadiyah sejauh hal itu tidak mengganggu keamanan, kesehatan, ketertiban, dan moralitas umum. Al-Khanif, op. Cit., 257. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 117 Tabel. 4.3. Potret Intoleransi dan Persekusi yang Dialami oleh Kelompok Ahmadiyah Waktu Tempat Keterangan 15 Juli 2005 Parung, Bogor - Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Umat Islam (GUI) yang dipimpin oleh Habib Abdur Rahman Assegaf merusak dan menyerang kampus Mubarak milik JAI. - Ratusan anggota JAI dievakuasi. 04 Februari 2006 Dusun Gegelang, Desa Gegerung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Penyerbuan perkampungan milik Jemaat Ahmadiyah oleh warga. 17 Februari 2006 Bulukumba Penyegelan tempat ibadat Jemaat Ahmadiyah oleh Bupati atas desakan massa Laskar Jundullah dan Ormas Islam yang tergabung dalam Ikatan Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba. 5 Maret 2008 Jl. Nagarawangi No. 71, Kota Tasikmalaya, Jabar Sekelompok orang berpeci putih melemparkan batu ke balai pertemuan aset JAI. Akibatnya 12 kaca jendela dan 1 set pintu kaca pecah. 27 April 2008 Parakan Salak Rt. 02 Rw. 02, Sukabumi, Jabar Massa membakar Masjid alFurqon dan Madrasah milik JAI. 118 Dr. Rohidin, M. Ag 30 April 2008 Citareun Udik, Cibungbulang, Bogor Puluhan warga membongkar masjid Ahmadiyah. Pembongkaran ini disaksikan oleh aparat dan Polres Bogor. 13 Juni 2008 Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor Ribuan massa dan 14 organisasi Islam menyegel sekertariat JAI. 18 Juni 2008 Desa Sukadana dan Desa Penyairan, Campaka, Cianjur, Jabar Sekitar 100 massa menyegel 6 masjid milik Ahmadiyyah. 20 Juni 2008 Jl. Anuang No. 112, Makassar, Sulawesi Selatan FPI Silawesi Selatan menyegel Masjid An-Nusrat dan Sekretariat Pengurus Wilayah Ahmadiyah Sulsel. 20 Juni 2008 Jl. Dr. Muwardi, Cianjur, Jabar Ratusan massa menyegel Masjid Ahmadiyah. 8 Agustus 2008 Kebon Muncang dan Kebon Kelapa, Parakansalak, Sukabumi Warga merusak Masjid Baiturrahman dan Musola Baitud Do’a milik Ahmadiyah. 19 Agustus 2008 Jl. Raya Bukit Indah Ciputat, Tangerang, Banten Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muslim Ciputat menyegel Masjid Baitul Qoyyum. 5 Oktober 2008 Tanjung Medan, Pujod, Rakon Hilir, Riau Masjid Mahoto dihancurkan. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 119 2 Januari 2009 7 Februari 2009 120 Pondok Pesantren Soko Tunggal, Sendangguwo, Semarang Polwiltabes Semarang dan Kepolisian Resort Semarang Selatan membubarkan Pengajian JAI Semarang di Pondok Pesantren Soko Tunggal secara paksa dengan alasan bahwa kegiatan ini belum mendapatkan izin pelaksanaan. Pihak kepolisian hanya menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Pesantren. Jakarta Ketua MUI Pusat, Kholil Ridwan, mendesak pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang aliran sesat. Hal itu disampaikan ketika ia menjadi narasumber dalam bedah buku Nabi-Nabi Palsu di arena Islamic Book Fair di Istora Senayan Jakarta. Kholil juga mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan pemerintah untuk segera mengeluarkan keputusan pembubaran Ahmadiyah dan mengingatkan umat Islam agar pembubaran Ahmadiyah terus didengungkan di setiap pengajian. Dr. Rohidin, M. Ag 13 Maret 2009 19 Maret 2009 21 Maret 2009 Depok, Barat Jawa Ketua FPI Kota Depok Jawa Barat, Habib Idrus al-Gadri menyatakan, “FPI Kota Depok memutuskan untuk tidak memilih (golput) dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang karena hingga saat ini belum ada calon legislatif ataupun calon pemimpin yang bertekad membubarkan Ahmadiyah”. Jakarta Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Amin Djamaluddin, melaporkan Pemimpin, Ketua Umum, dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah ke Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian terkait ulang tahun Ahmadiyah di Kuningan. Amin menganggap kegiatan itu melanggar SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah dan larangan mengadakan kegiatan. Jakarta Selatan Dalam sebuah kampanye, Salim bin Umar al-Attar dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) berjanji melarang atau membubarkan kelompok yang dianggap telah menodai Islam seperti Ahmadiyah jika calegnya berhasil memperoleh kursi di DPR RI. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 121 25 Maret 2009 25 Maret 2009 122 Kota Bandung, Jawa Barat Aksi unjuk rasa sekitar seribu massa Garis, FPI Kota Bandung, AGAP, FUI, Aliansi Gerakan Anti Maksiat (A-GAM) Majalengka, PAS Indonesia, Forum Penyelamat Akidah Umat Kec. Kadungora Garut dan Forum Pemberdayaan Masjid Sumedang di Gedung Sate Bandung menuntut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, segera melakukan pelarangan serta pembubaran Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat Ratusan orang dari berbagai organisasi Islam, di antaranya kader FPI mendatangi Gedung Sate dan menuntut gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menerbitkan SK pembubaran Ahmadiyah. Massa juga menuntut pembersihan antekantek Yahudi dan Zionis Israel seperti Rotary Club di Jabar. Dr. Rohidin, M. Ag 1 April 2009 Jakarta Ribuan umat Muslim gabungan ormas-ormas Islam seperti FPI, Laskar Aswaja, Gerakan Cinta Nabi, FUI, Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API), gabungan Majelis Ta’lim se-Jabotabek serta gabungan Pondok Pesantren se-Indonesia berunjuk rasa di depan istana untuk menyuarakan agar Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pembubaran Ahmadiyah. Dalam aksi ini, KH. Nur Iskandar SQ. sebagai juru bicara menyatakan: “Jika presiden tidak bisa membubarkan dan/atau menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam, maka para kiai se-Indonesia akan menyerukan pada umat Islam untuk tidak memilih Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009”. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 123 13 Mei 2009 Surabaya, Jawa Timur Ketua Musyawarah Ulama seJawa Timur, Helmy Basaiban, menuntut Jusuf Kalla dan Wiranto membubarkan Ahmadiyah jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu. Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam pertemuan Musyawarah Ulama Jawa Timur di Rumah Makan Agis, Surabaya. Tetapi, dalam jawabannya Jusuf Kalla tidak menjawab secara tegas: “Untuk aliran sesat tentu harus diluruskan secara syari’at juga. Namun jika secara syariah juga tidak bisa, maka kewajiban negara untuk menegakkan hukumnya”. 6 Juni 2009 Jl. Ciputat Raya, Gg. Sekolah No. 18 Rt. 001/Rw. 01 Kebayoran Lama, Jakarta Masjid Ahmadiyah di Jakarta Selatan dibakar oleh dua orang tidak dikenal saat beberapa orang Jemaat Ahmadiyah melaksanakan salat Subuh berjamaah. Bandung, Jawa Barat Pernyataan ketua MUI Pusat, KH. Cholil Ridwan: “Belajar dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. Masak Gubernur Jawa Barat yang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah.” 7 Juni 2009 124 Dr. Rohidin, M. Ag 2 Juli 2009 FUI dan FPI berdemonstrasi di depan Kantor Depag Pusat untuk menyoal keberatan mereka atas tidak efektifnya SKB. Kepada pengendara yang melintas, Jakarta dan selebaran berisi dukungan kepada pasangan Jusuf KallaWiranto dalam Pilpres 2009 dan pembubaran Ahmadiyah. 11 Agustus 2009 11 Desember 2009 Sumatera Barat Depag Sumatera Barat menyetujui larangan Jemaat Ahmadiyah beribadat haji yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Kepala Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf Kantor Depag Sumatera Barat, Japeri Jarap, menghimbau instansi seperti RT atau lurah, agar melaporkan jika ada warganya dari Ahmadiyah yang ikut mendaftar ibadat haji. Jakarta Selatan Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, menyegel sebuah rumah ibadat sekaligus tempat tinggal milik sekelompok pengikut ajaran Ahmadiyah. Penyegelan terhadap rumah ibadat berlantai dua ini berlangsung tanpa keributan. Warga berpendapat para Jemaat Ahmadiyah ini melanggar SKB tiga menteri karena tetap melakukan kegiatan keagamaan. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 125 Jika ditelusuri lebih dalam, berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada era reformasi di atas sebenarnya tidak terlepas dari warisan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah era Orde Baru, dan lebih jauh oleh pemerintah era Orde Lama.10 Sebagaimana diungkapkan oleh Musdah Mulia, selama 32 tahun masa kekuasaannya, rezim Orde Baru nyaris sempurna melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama di tanah air. Intervensi itu, menurut Musdah, setidaknya mengambil tiga bentuk. Pertama, campur tangan negara terhadap keyakinan dan kehidupan keberagamaan warga. Intervensi jenis ini diwujudkan dalam bentuk pelarangan terhadap buku, perayaan, atau kelompok keagamaan tertentu yang dinilai dapat mengganggu dan memunculkan perlawanan atas kekuasaan. Keberhasilan intervensi ini dibuktikan dalam bentuk pelarangan terhadap lebih dari seratus aliran kepercayaan atau kebatinan yang berhaluan kiri oleh Pemerintah Orde Baru hanya dalam kurun dua tahun awal masa kekuasaannya. Kedua “agama resmi” dan ”agama tidak resmi”.11 rezim Orde Baru hanya melakukan kontrol terhadap kelompok di 10 Embrio dari warisan ini berawal dari munculnya berbagai aliran kebatinan, baik dalam ranah politik maupun sosial, yang kemudian melahirkan dua perkakas hukum yaitu Bakorpakem, yang terdiri dari Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri dan UU No. 1/PNPS/1965. Dalam perkembangannya, PNPS yang berisi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama tersebut digunakan sebagai alat untuk membentengi “agama-agama resmi” dari “serangan” aliran-aliran sempalan. Hal ini tentu saja menjadi intervensi nyata dari pemerintah terhadap kehidupan warga negaranya. Intervensi negara ke dalam wilayah privat (baca:keberagamaan) masyarakat ini sendiri disinyalir terjadi setelah adanya kegagalan partai-partai Islam memperoleh suara mayoritas dari kelompok-kelompok minoritas ini pada Pemilu 1955. 11 Pada dataran wacana, pernyataan Musdah ini terlihat berseberangan dengan pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan. Dengan mengacu kepada penjelasan TAP MPR tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemerintah tidak mencampuri masalah intern keagamaan, baik yang berkaitan dengan masalah penafsiran, pengamalan, maupun pelembagaan agama dari masing-masing umat beragama. Dalam kesempatan yang lain, Presiden Soeharto menandaskan bahwa di Indonesia tidak mengenal agama yang diakui dan tidak diakui. Lihat, Djohan Efendi “Jaminan Konstitusional Bagi Kebebasan beragama di Indonesia” dalam Nurcholish Madjid, (dkk.), Passing Over: Melintas Batas Agama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 111. 126 Dr. Rohidin, M. Ag luar “agama resmi” yang dianggap mengancam kekuasaannya lewat tangan agama-agama resmi. Salah satu efek yang ditimbulkan dari intervensi jenis kedua ini, agama-agama yang dianggap resmi kemudian seolahmenjadi perpanjangan tangan dari penguasa (baca:pemerintah) karena mereka diberikan kewenangan untuk mengontrol berbagai bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan oleh masyarakat. Ketiga,intervensi yang diwujudkan dalam bentuk proses kolonialisasi agama-agama mayoritas terhadap kelompok kepercayaan atau agama-agama lokal melalui islamisasi atau kristenisasi sebagai efek dari intervensi jenis kedua.12 Beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan yang terjadi pada era Orde Baru di antaranya sebagaimana yang tampak pada tabel berikut ini: Tabel. 4.4. Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Keyakinan pada Era Orde Baru Waktu Agustus 1968 Kasus H.B Jassin: Cerpen “Langit Makin Mendung” dalam Majalah Sastra, Th. VI. No. 8, Edisi Agustus 1968 Gambaran - Cerpen yang ditulis oleh seorang tokoh bernama Ki Panjikusmin tersebut dianggap melecehkan Islam. Akibatnya, ratusan eksemplar majalah Sastra disita di berbagai toko, agen, dan pengecer di kota Medan. - Kantor majalah Sastra didatangi 50 pemuda yang mencoret-coret dinding kantornya dengan berbagai macam penghinaan, “H.B Jassin Kunjuk!” (baca: Kunyuk), “H.B Ini Kantor Lekra, Majalah Sastra: Anti Islam”, misalnya. 12 Siti Musdah Mulia, op. Cit., hlm. 335. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 127 - H.B Jassin selaku Redaktur Majalah Sastra diseret ke pengadilan. Namun, di muka pengadilan ia bersikeras tidak mengungkap identitas Ki Panjikusmin dengan berpegang pada UU Pers 1966. - H.B Jassin dikenai Pasal 156a KUHP karena dianggap melakukan penodaan agama dan dihukum satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Arswendo Atmowiloto dalam Oktober Publikasi 1990 Hasil Angket Tabloid Monitor, 1990 128 Dr. Rohidin, M. Ag - Pada Senin, 15 Oktober 1990, Tabloid Monitor menurunkan hasil angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan Nabi Muhammad menempati urutan kesebelas sebagai tokoh yang paling dikagumi, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Monitor yang menempati peringkat kesepuluh. Publikasi tersebut menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam. - Monitor dianggap melecehkan Nabi Muhammad dan membangkitkan kembali sentimen suku, agama, dan ras. - Arswendo Atmowiloto dikenai Pasal 156a KUHP dengan tuduhan penodaan agama dan dihukum lima tahun penjara. A p r i l 1996 Saleh bin Abdul Kadir alias Hamid, Situbondo, 1996 13 - Saleh, seorang penjaga masjid, menyatakan kepada K.H. Achmad Zaini, pimpinan pondok Nurul Hikam, bahwa Allah adalah makhluk biasa dan K.H. As’ad Situbondo dan tokoh NU yang sangat dihormati, meninggal tidak sempurna (Madura: mate takacer). - Saleh dikenai Pasal 156a KUHP dengan tuduhan penodaan agama dan dihukum lima tahun penjara. Tanpa bermaksud mengabaikan landasan-landasan hukum yang lain, dari sekian produk kebijakan terkait jaminan dalam beragama dan berkeyakinan yang telah disebutkan di atas, tindak kekerasan di atas sebagian diakibatkan karena adanya inkonsistensi dari pemerintah dalam mematuhi landasan hukum nasional, dan 1413 Selain itu, pemerintah juga terkesan bersikap tebang pilih dalam menghukum para pelaku kekerasan. 13 Kasus yang menimpa Saleh ini terus merambat menjadi semakin besar yang kemudian berujung dengan terjadinya peristiwa kerusuhan di Situbondo. Telusuri lebih lanjut terkait kasus ini dan beberapa kasus kekerasan lain yang kental dengan nuansa SARA yang terjadi dalam di tahun 1995-1996 dalam, A. Made Tony Supriatma (ed.), 1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1997, hlm. 54-75. 14 Di dalam hukum internasional, sebuah sebuah instrumen internasional harus menunjukkan kepatuhan terhadap negara juga harus memerhatikan aturan hukum yang diatur oleh deklarasi internasional yang telah menjadi norma-norma absolut yang tidak bisa ditangguhkan dalam keadaan apapun juga seperti genosida, perbudakan, dan hak untuk hidup. Norma tersebut harus dijalankan sebagai bagian dari kepatuhan negara terhadap moralitas yang dikandung dalam hak tersebut. Lihat Al-Khanif, op. Cit., hlm. 210. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 129 Selain karena faktor kegamangan pemerintah tersebut, , sebagian juga diakibatkan karena adanya kesan diskriminasi yang tercermin dalam fatwa-fatwa yang (di antaranya) dikeluarkan oleh lembaga MUI, baik yang berada di tingkatan daerah maupun pusat.14 Fatwa-fatwa MUI yang sejatinya hanya bersifat legal opinion tersebut kemudian dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai legal binding untuk membatasi kebebasan beragama.15 Kekuatan “legalitas” fatwa-fatwa MUI tersebut paling tidak disebabkan karena adanya kedekatan dan keterkaitan MUI dengan pemerintah. Hal ini karena semenjak awal didirikannya, MUI dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya seperti Walubi, PGI, KWI, Hindu Dharma Indonesia, dan Matakin, dimaksudkan untuk menjadi bagian dari instrumen rezim otoriter Orde Baru untuk menyangga kekuasaan dan menjinakkan (baca:mengontrol) setiap bentuk gerakan keagamaan dari “agama-agama tidak resmi” dan masyarakat atau kelompok masyarakat pada umumnya. Kondisi ini tentu mengajak kita untuk kembali bersikap kritis terhadap fatwa ataupun pendapat yang bisa memancing emosi massa. Meski secara tekstual, dalam materi fatwa MUI, tidak ada diktum atau klausul untuk menyerang dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok atau aliran yang dianggap “sesat”, “ umat Islam, fatwa bermodel seperti itu adalah jenis fatwa yang paling efektif dalam menggerakkan nalar dan emosi masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan dan main hakim sendiri.16 14 Telusuri lebih lanjut tentang berbagai fatwa MUI dalam kurun 19762010 di bidang akidah dan aliran keagamaan dalam, MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jakarta, 2010, hlm. 35-123. 15 Yang perlu menjadi penekanan dalam hal ini adalah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal fatwa di dalam hierarki perundangundangan negara. Fatwa bukanlah hukum positif sehingga keberadaan fatwa tidak mengikat melainkan berisi subjektivitas moral dari organisasi-organisasi Islam yang mendukungnya. Sehingga, ketika sebuah fatwa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Pancasila, maka sudah seharusnya fatwa tersebut tidak boleh dikeluarkan. Al-Khanif, loc. Cit. 16 Bagaimanapun, fatwa-fatwa otoriter diduga kuat berpotensi menimbulkan tindakan anarki dan kekerasan. Peristiwa terbunuhnya ᦰUᒱ ᦰ ” karena dianggap melampaui 130 Dr. Rohidin, M. Ag Pada dasarnya semua warga negara yang beragama mendapatkan jaminan. Tetapi jaminan tersebut dibelah menjadi “jaminan penuh” dan “jaminan seadanya”. “Jaminan penuh” dalam pengertian bahwa agama-agama itu selain dijamin oleh UUD juga mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari serangan pemahaman-pemahaman di luar mainstream. Sementara “jaminan seadanya” adalah kosakata untuk menggambarkan model jaminan negara tanpa adanya pengakuan yang melindunginya.17 Di sinilah kiranya setiap entitas di negeri ini perlu untuk terus mengupayakan pencarian kebenaran yang lapang dan terbuka serta tidak membelenggu jiwa, dan ini hanya dapat diperoleh dengan merealisasikan dialog konstruktif yang terbuka untuk mencapai kata mufakat ( ). Dialog di sini tentu bukanlah sebuah polemik tempat orang beradu argumentasi lewat pena, bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran wewenang sebagai Pemimpin umat Islam yang digariskan Allah dan Rasulᦰ ᐅ setelah dituduh percaya kepada “hukum manusia” mungkin dapat dijadikan sebagai satu gambaran. Dalam konteks sejarah umat Islam modern, gambaran kembali dapat kita lihat dari peristiwa yang menimpa Syekh Muhammad murtad dan oleh ᦰ Farag Fouda ditembak mati di halaman rumahnya oleh pengikut kelompok radikal setelah atasannya menjatuhkan fatwa dan murtad kepadanya. Novelis Naguib Mahfouz mengalami percobaan pembunuhan setelah ada fatwa bahwa novelnya, $ZOƗG ᏡDUDWLQƗ, bertentangan dengan Islam.Pemikir Islam Sudan, Ustad Muhammad Mahmoud Thahadigantung sampai mati setelah divonis murtad. Dalam konteks ini, Analisis Tindak Ujar (speech act analysis) sebagai sebuah kerangka teoretis, sebagaimana dikembangkan oleh Austin (1962), penulisanggap relevan jika digunakan sebagai alat bantu untuk melihat korelasi antara fatwa-fatwa sesat MUI dan tindak kekerasan oleh masyarakat. Dalam kerangka teoretis speech act analysis ini, setiap tindak ujar selalu memiliki dan melibatkan dua pihak, yakni penutur sebagai pihak yang mengeluarkan ujaran dan petutur sebagai pihak yang menerima ujaran. Dalam hubungan antara penutur dan petutur tersebut, secara kategoris, terdapat tiga macam. Pertama, tindak lokusi (locutionary act), yang merupakan tindak ujar untuk menyatakan sesuatu. Kedua, tindak ilokusi (illocutionary act), yang merupakan tindak ujar yang dilahirkan dan dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, tindak perlokusi (perlocutinary act), yang merupakan tindak ujar yang memiliki dampak, daya dorong, serta pengaruh kuat bagi yang menerima atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. 17 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil, RaSAIL Media Group, Semarang, 2009, hlm. 163. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 131 pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain, dan bukan pula sebuah apologi sehingga orang berusaha mempertahankan kepercayaannya karena terancam. Namun, dialog di sini pada hakekatnya adalah suatu percakapan bebas, terus terang, dan bertanggung jawab, yang didasari oleh sikap saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan umat, baik material maupun spiritual, sehingga perlu dikembangkan prinsip “agree in disagreement” (setuju dalam perbedaan).18 Dengan perspektif yang berbeda, dialog dapat pula kita tafsirkan sebagai implementasi konkret dari semangat multikulturalisme, di mana orientasinya adalah kehendak untuk membawa masyarakat dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada. Mengacu kepada pemaparan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan mendasar terkait dinamika kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Pertama, dinamika kebebasan beragama di negeri ini ternyata berbanding lurus dengan dinamika perpolitikan yang sedang berjalan. Kedua, dari sekian jumlah kasus kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang terjadi dalam kurun reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama—di samping fakta kekerasankekerasan lain yang belum termaktub dalam tulisan ini—sebagian besar akibat dari persepsi yang berlebihan atas dikeluarkannya fatwa tentang aliran sesat oleh lembaga keagamaan berupa MUI serta adanya klaim-klaim sesat lain dari masyarakat, ormas Islam, dan aparat pemerintah.19 18 Dengan bahasa yang berbeda, Hans Khung, seorang Teolog Kristen, sebagaimana dikutip Komaruddin Hidayat, menyatakan bahwa dialog merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya hidup damai dalam suatu negara. Ia mengatakan,“No peace among the nations without peace among religions; no peace among religions without dialogue between the religions; no dialogue between religions without investigation the foundation of the religions”. Komaruddin Hidayat, “Membangun Teologi Dialogis dan Inklusivistik”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over, Melintasi Batas Agama, Jakarta: Gramedia, 1998 hlm. 37. 19 Terlepas dari adanya distingsi pada wilayah implementasi, beragam klaim penyesatan yang merebak ini tentu berlawanan dengan pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Ramah Tamah dengan peserta Rapat Kerja MUI pada 8 Maret 1984. Pada kesempatan tersebut, Soeharto sempat menyatakan, 132 Dr. Rohidin, M. Ag Kembali kepada fakta yang telah penulis kemukakan di awal, meskipun Negara Indonesia telah meletakkan dasar-dasar penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan sebagaimana tertuang dalam berbagai produk legislasi yang secara normatif sudah tampak ideal, ternyata hal itu belum sepenuhnya menjaminimplementasi hak asasi beragama kepada warga negara. Konklusi ini bisa dilihat dari masih suburnya berbagai pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan yang dilakukan oleh aparat negara, dan juga berbagai tindakan intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Mengacu kepada pembahasan bab ini, terlihat bahwa toleransi yang hingga saat ini gencar diwacanakan, ternyata masih sebatas jargon politis semata, sebab agama masih dipahami sebatas simbol, ritus, dan seremoni belaka dengan mengabaikan spiritualitas dan kemanusiaan. Bagaimanapun, hak setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan bukanlah pemberian negara atau pemberian golongan tertentu, sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR No. II/1978, dan hak ini tentu tidak mungkin dapat ditaklukkan dengan kekuasaan (negara). Karenanya, dengan berkaca kepada maraknya aksi pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan yang hingga saat ini masih terus bergulir, maka rekonstruksi wacana tentang relasi agama dan negara kiranya perlu kembali dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. B. Relasi Agama dan Negara Perspektif Pancasila Berkaitan dengan Konsep Kebebasan Beragama Ketika mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, founding fathers tidak hanya didukung oleh organisasi sosial dan politik, tetapi juga didukung oleh institusi lain bernama “Hendaklah disadari bahwa negara kita menganut kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masingmasing. Prinsip ini hendaknya menjadi anutan dan pegangan, bukan saja oleh negara melainkan juga oleh lembaga keagamaan masyarakat kita. Masingmasing kita, perorangan atau kelompok maupun lembaga, bahkan negara sekalipun, tidak berhak memaksakan suatu paham, baik dalam keyakinan, bentuk, dan pelaksanaan ibadat, maupun dalam pelembagaan.” Lihat, Djohan Efendi, op. Cit., hlm. 119. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 133 agama. Tidak satu pun lembaga keagamaan yang ada di Indonesia menentang aspirasi founding fathers. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat berlangsung secara cepat dan berjalan mulus. Proses mendirikan Negara Indonesia diwarnai oleh faktorfaktor rasional-objektif. Hal semacam ini terlihat dalam berbagai macam perundingan para wakil BPUPKI. Kesepakatan bersama yang diwarnai oleh faktor-faktor rasional-objektif itu menekankan Negara Indonesia berdasarkan pada nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa demi membangun kemanusiaan Indonesia dan persaudaraan segala bangsa.20 Proses me-negara yang ditentukan oleh faktor-faktor rasional-objektif tersebut menekankan pada kebangsaan sebagai ideologi yang memperjuangkan kesatuan bangsa.21 Berdirinya Negara Indonesia yang dilandasi Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh founding fathers, memfungsikan agama-agama turut aktif memperjuangkan dan menegakkan nilainilai kemerdekaan, kerakyatan, keadilan, dan kesatuan. Identitas masing-masing agama tidak dilenyapkan, tetapi agama-agama diletakkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu bahwa agamaagama perlu mengadakan kontekstualisasi ajaran-ajarannya di Indonesia. Dengan kata lain, ideologi kebangsaan menjadi semacam konteks yang tidak dapat ditiadakan oleh agama-agama. Kerangka kesatuan bangsa itulah yang menjadi semacam norma dasar negara Indonesia yang digunakan untuk meniadakan gerakan-gerakan agama yang berusaha memanfaatkan negara demi kepentingan agama tertentu dalam arti kelompok tertentu, seperti gerakan DI/TII.22 Dalam hal ini, agama dimengerti oleh founding fathers sebagai suatu institusi yang tidak pernah berusaha 20 M. Hatta, “Ke Arah Indonesia Merdeka?”, dalam Miriam Budiharja (ed.), Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 21-54. 21 A.M.W. Pranarka,Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, CSIS, Jakarta, 1985, hlm. 47-48. 22 Anhar Gonggong dan Abdul Qahhar Mudzakar, Dari Patriot Hingga Pemberontak, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 123-124. 134 Dr. Rohidin, M. Ag menggantikan konstitusi negara. Mengapa? Karena agama yang dipahami itu sebagai suatu institusi yang memiliki semangat kesetiakawanan, kemanusiaan, kerukunan, kesalehan, ketakwaan, dan tentu saja kebangsaan. Di Indonesia kepentingan agama senafas dengan kepentingan negara, yaitu menegakkan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, dan kesatuan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah peran agama-agama dan negara menuju tingkat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Pertanyaan semacam ini perlu diajukan karena dalam tingkat ‘negara’ peranan tingkat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa faktor-faktor emosional subjektif sangat berperan. Bukankah agama-agama yang datang ke Indonesia memiliki klaim-klaim kebenaran ajarannya tersendiri? Dengan demikian, agama-agama itu menggalang perasaan solidaritas kelompok secara lebih riil dan memadai jika dibandingkan dengan perasaan solidaritas kebangsaan Indonesia. Perasaan solidaritas kelompok yang padat semacam ini secara langsung dan tidak langsung mendorong agama-agama menuntut perannya sebagai ‘anak emas’ di Indonesia. Permasalahan yang timbul di Indonesia adalah tidak ada satu agama pun yang berhak menyandang gelar anak emas. Agama-agama dipaksa oleh ideologi kebangsaan Indonesia berperan sebagai anak bangsa.23 Teori tentang hubungan agama dan negara secara garis besar dibedakan menjadi trikotomi paradigma pemikiran, yaitu:24 23 John Titaley, “Pluralisme Agama dan Nasionalisme, Peranan Agama dalamPembentukan Dasar Kehidupan Berbangsa di 1ndonesia,” Makalah, dalam SeminarAgama-agama X11, Bogor/Tugu, September 1992, hlm. 16. 24 Disarikan dari: Dede Rosyada (dkk.), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Jakarta, Jakarta, 2003, hlm. 61., Hani Astika, “Hubungan Agama dan Negara dalam Islam”, dalam Jurnal al-Manahij, vol. 2, No. 1, Januari-Juni, 2008, hlm. 68-70., Gunarto, “Pemikiran Munawwir Syadzali tentang Islam dan Negara dalam Perbandingan Penafsirannya antara T.B. Simatupang dan Eka Darmaputra dari Perspektif Kehidupan Beragama dan Pancasila”, dalam Jurnal Teologi Stulos, vol. 6, No. 1, April 2007, hlm. 53-70. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 135 1. Paradigma Integralistik Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik sekaligus. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Ilahi” (divine sovereignty), karena pendukung konsep ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama. Sebaliknya, memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. Dengan model seperti ini, negara sangat potensial melakukan otoritarianisme dan kesewenang-wenangan. Alasannya, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang dapat berlindung di balik agama. 2. Paradigma Simbiotik Dalam paradigma simbiotik dinyatakan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan adanya negara maka agama akan dapat berkembang secara lebih baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Hanya saja, dalam tataran praktis, persetubuhan agama dan negara yang terjadi justru negara menelikung agama. Ajaran Islam, misalnya, yang semestinya mengatur kehidupan politik dari sektor etika, justru diatur oleh elit-elit politik, sehingga tetap cenderung menuju konsep ”Islam adalah agama dan negara”.25 25 Bagi Arif Hidayat, paradigma simbiosis ini mengandaikan terpenuhinya empat prinsip, yakni theokrasi, demokrasi, nomokrasi, dan ekokrasi. Hubungan keempat prinsip tersebut bersifat berkait berkelindan satu sama lain, dalam 136 Dr. Rohidin, M. Ag 3. Paradigma Sekularistik Menurut pandangan paradigma sekularistik, agama dan negara harus dipisahkan dengan tegas. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam. Atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Negara Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, pun juga demikian agama dan keyakinan yang dianut oleh warganya. Kekayaan di sektor keagamaan tersebut mengakibatkan Indonesia mendapat predikat sebagai bangsa multireligi. Dari sejumlah agama dan keyakinan yang ada, Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara. Meskipun demikian, pada kenyataannya Islam tidak diposisikan sebagai dasar negara. Negara demokrasi model Barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia, negara komunis lazimnya bersifat atheis, yang menolak agama dalam suatu negara, sedangkan negara agama memiliki konsekuensi kelompok agama tertentu akan menguasai negara dan di Indonesia dalam hal ini Islam. Oleh karena itu, founding fathers tampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar Negara tersebut tidak dipahami sebagai prinsip dalam konteks teologis, melainkan prinsip hidup bersama dalam suatu Negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki arti tidak bisa mengunggulkan sebagiannya dan mengabaikan sebagian yang lain. Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2011 di Semarang. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 137 keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal demikian dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban. Konsekuensi logis dari penggunaan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara adalah bahwa kehidupan agama tidak dipisahkan sama sekali, melainkan justru agama mendapatkan legitimasi sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung dalam sila pertama Indonesia, bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam hal hubungan negara dan agama. Peraturan perundang-undangan Indonesia bukan mengatur ruang akidah umat beragama, melainkan mengatur ruang publik warga negara dalam hubungan antar manusia. Dengan demikian, bertolak dari tiga paradigma relasi agama dan negara di atas maka Indonesia termasuk negara yang menggunakan paradigma simbiotik. C. Ƥ Kebebasan Beragama Berbasis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Bingkai Hukum Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, bahwa kebebasan beragama di Indonesia secara konseptual-normatif telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Konsepsi normatif tersebut jika dihubungkan dengan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian dan pengakuan akan penghargaan terhadap sesama manusia, di mana asal-usul, keyakinan, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, jumlah harta milik maupun pandangan politiknya, adalah sama, dalam artitidak ada perbedaan di antara masing-masing individu manusia dan tidak ada manusia yang diciptakan dengan nilai yang lebih tinggi dari manusia yang lain. Seluruh manusia diciptakan dengan nilai yang sama rata. Persamaan derajat di antara manusia ini bersifat universal. Atas dasar pandangan tersebut, muncul pengakuan rasa persaudaraan, 138 Dr. Rohidin, M. Ag di mana masing-masing individu manusia merasa menjadi saudara dari manusia yang lain, dan berada dalam satu wadah besar keluarga umat manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama.26 Namun demikian, asumsi kerangka normatif yang mapan tersebut tidak serta-merta mapan pula dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Sebaliknya, hal tersebut kerap menimbulkan kekecewaan, karena pengakuan kuatnya jaminan kerangka normatif di atas ternyata belum menjadi realita yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Banyak warga Negara Indonesia yang masih merasa dibelenggu kebebasannya dalam hal kebebasan mengekspresikan keagamaan dan keyakinannya. Demikian juga dalam realitas kehidupan masyarakatnya, ragam pelanggaran dan tidak adanya ketaatan serta penghormatan terhadap konstitusi merupakan potret faktual. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam kerangka pemikiran bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud terdiri atas tiga komponen, yakni komponen struktur hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu dikonsepsikan sebagai law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.27 Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini kerap disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan 26 Noor MS Bakry, op. Cit., hlm. 46. 27 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989, hlm. 51. Mochtar Kusumatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 11. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 139 hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.28 Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa UUD 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.29 Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Dengan kata lain, kebijakan perundangundangan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang erat kaitannya dengan kondisi dan kepentingan pembuatnya. Menurut James Anderson, sebagaimana dilansir sebelumnya, kebijakan merupakan arah tindakan yang bermaksud untuk ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep demikian berimplikasi pada tiga hal. Pertama, orientasi kebijakan publik adalah tujuan, bukan perilaku secara serampangan. Kedua, kebijakan adalah pola tindakan aparatur pemerintah, bukan keputusan-keputusan secara tersendiri. Ketiga, kebijakan adalah perilaku pemerintah dalam mengatur perihal teknis, bukan keinginan pemerintah. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka sifat kebijakan publik berkaitan dengan hukum kebebasan beragama dapat 28 Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 483. 29 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 53. 140 Dr. Rohidin, M. Ag dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa sebagai representasi dari kasus kebebasan beragama di negeri ini, maka kategori-kategori tersebut antara lain adalah tuntutantuntutan kebijakan; keputusan-keputusan kebijakan; pernyataanpernyataan kebijakan; hasil-hasil kebijakan; dan dampak-dampak kebijakan, yang kesemuanya berkaitan dengan Ahmadiyah. Sistem politik yang terdiri atas badan-badan legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi); partai-partai politik, kelompok kepentingan (aktivis pro-HAM dan aktivis gerakan Islam-radikal), media massa; anggota masyarakat non-Ahmadiyah, tokoh-tokoh masyarakat (MUI, NU, Muhammadiyah, dan akademisi, misalnya), struktur birokrasi; prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan, semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah inputs, yang beragam berkaitan dengan kasus Ahmadiyah, menjadi outputs, kebijakan mengenai Ahmadiyah. Proses pembentukan kebijakan berkaitan dengan kasus Ahmadiyah, sebagai contoh, tersebut dapat dijelaskan melalui ragaan berikut: Ragaan. 4.1. Teori Kebijakan Publik Berkaitan dengan Hukum Kebebasan Beragama dengan Contoh Kasus Ahmadiyah Intra (MUI, NU, Muhammadiyah, akademisi, aktivis pro HAM, aktivis gerakan Islam-radikal, media massa, dan anggota masyarakat non Ahmadiyah) Extra (ICCPR, Deklarasi Kairo, OKI, dan DUHAM) Demokrasi DPR dan Presiden I N P U T S deman G support Information feedback Conversion of deman into output Information feedback A U T H O R Kebijakan tentang I Ahmadiyah (output) T H I E S The flow of effects from the environment intra-societal environment: x sistem ekologis x sistem biologis x sistem personalitas x sistem sosial Feedback loop extra-societal environment: x sistem politik internasional x sistem ekologi internasional x sistem sosial internasional Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 141 Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban to adapt the law to this changed society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undangundang.30 Sehingga, konstruksi pembentukan (kebijakan) hukum berkaitan dengan kasus Ahmadiyah sebagaimana tergambar di atas sejatinya sangat ditentukan oleh pembuatnya. Namun demikian—sebagaimana telah berkali-kali diungkap— meskipun dalam kerangka normatif jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah mapan tidak serta-merta mapan pula dalam aplikasinya. Pelaksanaan hukum kebebasan beragama bukan dibebankan hanya pada satu elemen negara, pemerintah saja, misalnya, melainkan seluruh aspek yang berkepentingan dengannya. Dengan bertolak dari teori bekerjanya hukum Seidmen dan Chambliss, maka hukum kebebasan beragama akan berhasil jika memenuhi beberapa hal. Pertama, masing-masing elemen menempatkan dan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaik mungkin sebagaimana fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut adalah (a) hukum kebebasan beragama yang ada, (b) sanksi-sanksi hukum kebebasan beragama, (c) aktivitas lembaga penerap sanksi, seperti: pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, dan (d) seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang memengaruhinya. Kedua, jika hukum kebebasan beragama sudah berhasil menggerakkan perilaku anggota masyarakat, 30 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundangundangan, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 12. 142 Dr. Rohidin, M. Ag maka keadaan itu merupakan sesuatu yang bersifat khas dalam masyarakat tersebut. Ketiga, penggunaan hukum kebebasan beragama bersifat sama, berikut sanksinya, dan ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Oleh karenanya, pelaksanaan hukum kebebasan beragama tersebut untuk waktu dan tempat yang berbeda dan juga dengan lembaga penerap sanksi yang berbeda serta kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang memengaruhi pemegang peran yang berbeda pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pemegang peran yang sama dengan yang terjadi di tempat asal dari hukum tersebut. Berikut ragaan teori bekerjanya hukum berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia: Ragaan. 4.2. Bekerjanya Hukum Kebebasan Beragama Kekuatan Sosial dan Personal Tuntutan Masyarakat Umpan Balik DPR, Presiden, Menteri Norma Norma Kegiatan Penerapan Sanksi MK dan MA KekuatanKekuatan Sosial dan Personal Umpan Balik MUI, Muhammadiyah, NU, dll Umpan Balik KekuatanKekuatan Sosial dan Personal Dari beberapa tawaran konseptual dan sedikit gambaran berkaitan dengan Ahmadiyah, analisis penegakan dan kebijakan hukum di atas tampaknya dapat disederhanakan dalam tiga komponen. Pertama substansi hukum itu sendiri, kedua adalah komponen penegak serta pembuat hukumnya dan ketiga adalah komponen Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 143 budaya hukum. Ketiga komponen inilah yang mesti dilihat dalam rangka tegaknya asas kebebasan beragama di Indonesia. 1. Ambiguitas Produk Regulasi Jaminan Kebebasan Beragama: Problem Substansi Hukum Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa meskipun secara kerangka normatif-yuridis konsep kebebasan beragama sangat mapan, tetapi pada tataran legislasi dan peraturan penunjangnya masih mengandung banyak persoalan. Berikut beberapa bentuk legislasi dan peraturan yang penulis nilai sarat dengan ragam persoalan: a. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama Pokok-pokok penting dalam undang-undang ini sesungguhnya adalah pelarangan melakukan penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.31 Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa: “Pada KUHP diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: ‘Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 31 Pasal 1. Pada penjelasan pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan agama tersebut adalah enam agama di Indonesia. Bagi Nicola Corlbran, Undang-undang tersebut menandakan bila persepsi negara tentang agama masih didominasi oleh pemahaman arus utama yang menyatakan bahwa suatu agama harus memiliki Tuhan, Nabi, dan kitab suci. Nicola Corlbran, ”Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Secara Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, dalam Tore Lindholm (dkk.), Kebebasan Beragam atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh? Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 690. 144 Dr. Rohidin, M. Ag perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.’ Perundangan itu, bagi sebagian pegiat HAM, selain dianggap bertentangan dengan semangat kebebasan beragama sebagai amanat Konstitusi, juga dinilai sebagai bentuk intervensi negara yang sebenarnya tidak perlu—dan bahkan tidak boleh— dilakukan.32 Regulasi tersebut pada dasarnya lahir dalam konteks yang berbeda dengan realitas Indonesia yang dihadapi sekarang. Saat itu, demokrasi terpimpin adalah sistem kepemerintahan yang sedang demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik, dan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Sehingga, produk-produk hukum yang keluar pun tidak dapat keluar dari suasana politik tersebut, yakni otoritarian dan sentralistik.33 Artinya, konstruksi hukum dalam undang-undang 32 Menarik kategorisasi yang dibuat oleh As’ad Said Ali, menurutnya kewenangan negara dalam mengatur keagamaan dapat dipetakan menjadi lima hal. Pertama, kehadiran negara bisa bermakna wajib untuk menjalankan kesempurnaan pelaksanaan syariah Islam, keberadaan wali hakim dalam persoalan nikahnya umat muslim, misalnya. Kedua, kehadiran negara bisa bermakna menjadi syarat kesempurnaan ibadat, persoalan haji, misalnya, Ketiga, hampir sama dengan poin kedua. Kehadiran negara bisa memperlancar pelaksanaan ibadat, namun tingkat keterlibatan negara tidak seintensif poin kedua di atas, misalnya persoalan zakat. Keempat, mubah. Negara bisa dan juga bisa tidak hadir, misalnya, dalam hal perbaikan dan pengelolaan tempattempat ibadat, lembaga pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Kelima, negara terlarang masuk dalam urusan agama bila menyangkut peribadatan. Otoritas masalah tersebut adalah para pemuka agama. Jika muncul silang sengketa menyangkut ibadat, negara harus bertindak adil dan dan tidak terlibat dalam pokok masalahnya. Namun, negara harus tetap berupaya keras menjaga kerukunan atau tertib sosial. Lihat, As’ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa, LP3ES, Jakarta, 2009, hlm. 198-202. 33 Sebagaimana terlansir dalam Surat Permohonan Pemohon Judicial Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 145 tersebut juga sangat kental dengan nuansa politis semacam itu. Sementara, Indonesia yang dihadapi sekarang berbeda, terlebih kaitannya dengan kehidupan beragama, yang cenderung partikular dalam arti tergantung pada kelompok keagamaannya masingmasing. Pelarangan di atas secara tidak langsung berimplikasi pada asumsi adanya kebenaran tafsir yang bersifat tunggal. Padahal, kebenaran dalam agama dan keyakinan secara mendasar bersifat relatif. Relativitas yang selaras dengan semangat pluralisme ini kemudian dianggap dikebiri begitu saja oleh asumsi kebenaran tunggal di atas. Bagaimana tidak, benar dan tidaknya sebuah tafsir keagamaan oleh negara dikembalikan kepada Depag (Sekarang Kemenag). Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenag telah membentuk lembaga otonom yang salah satu tugasnya adalah memberikan pandangan (baca: fatwa) tentang kebenaran suatu tafsir keagamaan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah: MUI, KWI, PGI, Walubi, PHDI, dan Matakin.34 Review UU No. 1 PNPS/ 1965 bernomor: 140/PUUVII/2009 tertanggal 20 Oktober 2009. Lebih dari itu, Ahmad Fedyani Syaifuddin mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut dibuat dalam semangat positivistik, integrasi, pencegahan kekacauan politik, dan benturan kepercayaan masyarakat. Pernyataan Ahmad Fedyani Syaifuddin dalam Sidang Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965 pada Jumat, 19 Maret 2010 di Gedung MK, Jakarta. Sementara itu, menurut Moeslim Abdurrahman secara historis undang-undang tersebut muncul dalam situasi politik yang kacau, yakni banyaknya pertikaian antara Islam dan Komunis. Pernyataan Moeslim Abdurrahman dalam Sidang Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965 pada Rabu, 24 Maret 2010 di Gedung MK, Jakarta. 34 Meskipun Kemenag menyerahkan kewenangannya pada lembagalembaga bentukannya, dalam konteks hukum pidana apa yang menjadi putusan lembaga-lembaga tersebut bagi penulistidak bisa serta-merta dijadikan dasar dalam merespons persoalan aliran sesat. Seharusnya, ragam ambiguitas di atas harus diperjelas sedemikian rupa, termasuk apa yang dimaksud dengan penafsiran menyimpang dan pokok-pokok ajaran agama. Karena, hal ini akan sangat tergantung kepada mazhab mainstream yang dianut oleh si penafsir. Sedangkan jika negara merumuskan pokok-pokok ajaran agama dan berpihak pada satu mazhab dari ajaran tersebut, maka negara sudah terjebak pada model negara agama. Oleh karena itu jika undang-undang ini masih ingin dipertahankan, maka rumusan-rumusan pasalnya harus diperbaiki. Mengingat pemidanaan seseorang atau suatu kelompok tidak bisa dilakukan berdasarkan suatu opini, melainkan harus memenuhi empat prinsip, sebagaimana diungkap oleh Machteld Boot dengan mengutip pendapat Jescheck dan Weigend. Pertama,nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinya, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Kedua,nullum 146 Dr. Rohidin, M. Ag Oemar Senoadji, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa teori-teori delik agama pada intinya terdapat tiga hal sebagai berikut:35 1) Religionesschutz-theorie (teori perlindungan agama). Menurut teori ini, agama itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 2) (teori perlindungan perasaan keagamaan). Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang beragama. 3) Friedensschutz-theorie (teori perlindungan perdamaian/ ketentraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah crimen, nulla peona sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga,nullum crimen nulla poena sine lege certa. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Keempat,nullum crimen noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Lihat, Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 4-5. Dengan demikian, setiap tindakan yang akan dikriminalisasi atau dijadikan perbuatan pidana, seharusnya dirumuskan secara jelas dan tegas, tidak kabur dan ambigus. Hal ini semata-mata untuk menegakkan rasa keadilan dan menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa, yang dalam hal ini penegak hukum. Hal senada juga dinyatakan oleh Andi Hamzah bahwa rumusan delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perbuatan pidana. Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila ada undang-undang yang melarang perbuatan pidana tersebut terlebih dahulu. Asas tersebut dianggap kurang memadai karena banyak undang-undang karet (baca: multitafsir), sehingga semua orang bisa menafsirkannya. Oleh karena itu, muncullah asas berikutnya yang berbunyi, nullum crimen sine lege scripta, yang berarti tidak ada delik tanpa undang-undang yang ketat sebelumnya. Pernyataan Andi Hamzah, sebagai Ahli, dalam Sidang Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965pada Rabu, 3 Maret 2010 di Gedung MK, Jakarta. 35 Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, hlm. 2. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 147 “kedamaian/ketentraman beragama interkonfessional (di antara pemeluk agama/kepercayaan). Dengan kata lain, ketertiban umum merupakan tujuan dari teori ini. Bertolak dari tiga teori tersebut, lanjut Senoadji, adanya Pasal 156a KUHP tersebut dapat dipahami bahwa dilihat dari status dan penempatannya yang terletak pada bab V (Kejahatan dan Ketertiban Umum) maka ia termasuk delik terhadap ketertiban umum, di mana tujuannya bermaksud untuk melindungi ketentraman orang beragama. Jadi, objek yang dilindungi adalah “rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum”. Namun demikian, berbeda jika dilihat secara redaksional teksnya, penodaan agama tersebut sudah dapat dipidanakan tanpa harus mengganggu ketenteraman orang beragama dan tanpa mengganggu/membahayakan ketertiban umum, sekalipun dilakukan di hadapan orang-orang yang tidak beragama.36 Dengan kata lain, yang menjadi objek perlindungan adalah agama itu sendiri, bukan pemeluknya (ketertiban umum). Hal demikian merupakan salah satu bentuk ambiguitas dalam undang-undang ini.37 Hingga saat ini, banyak gagasan yang muncul bahwa persoalan agama dan/atau penodaan agama tidak perlu diatur oleh negara. Dengan kata lain, negara tidak semestinya mencampuri urusan keyakinan warga negaranya. Kebijakan pemerintah yang hanya mengakui enam agama “resmi” membuat para penganut agama lain tidak mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Bahkan, muncul pendapat yang mengatakan bahwa kehidupan 36 Ibid., hlm. 5. 37 Pada saat undang-undang ini di-judicial review, Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri mengakui bahwa baik dalam lingkup formal maupun secara substansial harus lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Namun demikian, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional atau cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi undangundang tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, MK tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. MK, Risalah Sidang Pengujian UU No. 1/PNPS/1965, MK, Jakarta, 2010, hlm. 304-305. 148 Dr. Rohidin, M. Ag agama di Indonesia lebih baik bila tanpa negara. Artinya, negara tidak perlu ikut campur mengatur kehidupan beragama sebab negara justru membuat kehidupan agama menjadi tidak baik. Menanggapi persoalan ini, Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip Mahfud MD, berpendapat bahwa negara tidak berhak mencampuri urusan agama, terlebih lagi melakukan pengakuan terhadap agama tertentu.38 Argumen yang mendukung gagasan itu, negara mesti bersikap netral terhadap semua agama dan tidak boleh melarang timbulnya suatu aliran kepercayaan atau agama apapun. Jika terdapat suatu kelompok yang ingin mendirikan agama sendiri, artinya tidak bisa dilarang oleh negara. Menurut pendukung gagasan tersebut, ketentuan yang menunjukkan intervensi negara terhadap agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 tidak lagi diperlukan. Kebebasan berpikir dan berkeyakinan melekat, tidak boleh dibatasi, tidak dapat ditunda, dan tidak patut dirampas. Berkaitan dengan intervensi tersebut—dan kontroversi Ahmadiyah sebagai konteksnya—muncul SKB No. 3/2008, Kep033/A/JA/6/2008 dan No. 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Juni 2008, dan merupakan hasil kontroversi panjang yang melelahkan. Meskipun di dalam SKB tersebut tidak terdapat istilah “pembekuan” atau “pelarangan dan pembubaran” JAI, seperti yang dituntut mereka yang anti terhadap Ahmadiyah, keluarnya SKB ditengarai merupakan salah satu titik panas dalam rangkaian tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di seluruh pelosok negeri ini. Sebagaimana telah dilansir sebelumnya, kasuskasus kekerasan terhadap anggota Ahmadiyah ini sangat mewarnai masa-masa setelah keluarnya SKB. Beberapa bulan setelah diterbitkannya SKB tersebut, diterbitkan pula Surat Edaran Bersama (SEB) No. SE/SJ/1322/2008; 38 Mahfud MD, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi”, Makalah, disampaikandalam Konverensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, diselenggarakan oleh ICRP pada tanggal 5 Oktober 2009. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 149 SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008; dan SE/119/921/D.III/2008, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. Dalam SEB tersebut ditegaskan bahwa absahnya SKB sebagai tindak lanjut dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No. 5/1969, dengan mengacu pada pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006, No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Pada tahun 2006, Pemerintah (cq. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan Peraturan Bersama No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Aturan perundangan ini menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDN-MAG Tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadat. SKB tersebut dianggap belum mengatur secara rinci prosedur pendirian tempat ibadat, dan oleh karena itu adalah salah satu penyebab penutupan, perusakan, dan penyerangan tempat ibadat. Menurut PBM di atas, pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.39 Sebelum didirikan, pemohon harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi; daftar nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau 39 150 Pasal 13 ayat (1). Dr. Rohidin, M. Ag propinsi; dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi rertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berkaitan dengan PBM tersebut, ada beberapa persoalan yang menurut penulis justru kurang sesuai dengan amanat konstitusi. Pertama, aturan perundangan tersebut menitikberatkan pada pembatasan pendirian rumah ibadat, padahal konstitusi, dan bahkan Kovenan Internasional, telah mengamanatkan bahwa suatu pembatasan dilakukan harus berdasarkan atau ditetapkan dengan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang, bukan dalam bentuk kebijakan berupa PBM. Kedua, yang dimaksud dengan rumah ibadat dalam peraturan tersebut adalah “bangunan… yang dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama”, yakni agama resmi. Sementara itu, ragam kepercayaan yang tidak termasuk dalam agama tersebut juga hidup di negeri ini dan berhak untuk menjalankan kepercayaannya secara bebas dan aman. Namun demikian, dengan adanya aturan tersebut, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa mereka tidak berhak untuk mendirikan tempat ibadat. Ketiga, kuantitas pemeluk agama di setiap daerah berbeda, ada yang berjumlah banyak dan tidak sedikit yang hanya beberapa orang. Aturan kuantitas dalam aturan di atas tampaknya tidak mampu mengakomodasi minoritas pemeluk agama dalam suatu komunitas. Kaum Muslim di Manokwari, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali dan Sulawesi Utara, misalnya, mayoritas daerah tersebut adalah non-muslim, sementara komunitas muslimnya adalah minoritas yang berjumlah kurang dari standart minimal di atas.40 40 Lihat, “Umat Islam juga Sulit Membangun Masjid”, dalam http:// www.berita2.com/nasional/umum/7070-umat-islam-juga-sulit-membangunmasjid.html, (Diakses pada tanggal 30 Maret 2011). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 151 c. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) ICCPR merupakan salah satu intrumen internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku efektif pada tanggal 23 Maret 1976. Secara mendasar hak-hak sipil dan politik ini merupakan hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hakhak dan kebebasannya dalam bidang sosial dan politik. Pascadisahkannya kovenan tersebut, negara-negara anggota PBB tidak bahkan meminta Sekretaris Jenderal untuk mendesak negara-negara anggota untuk melaporkan secara periodik mengenai kemajuan pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan Sekretaris Jenderal untuk mengumumkan teks kovenan seluas mungkin.41 Berkaitan dengan hal itu, Indonesia, melalui UU No. 12 Tahun 2005, telah turut serta menjadi bagian dari 192 states parties dikatakan bahwa kovenan ini memiliki tingkat universalitas yang sangat tinggi bila dibanding dengan perjanjian internasional HAM lainnya. Sebagai sebuah produk deklarasi internasional, sudah barang tentu nilai-nilai universalitas yang berbasis pada humanisme (individualistik) sangat kental dalam kandungannya. Artinya, tidak serta-merta jika kovenan tersebut diaplikasikan dalam sebuah negara tertentu akan relevan dengan akar budayanya, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia. Secara umum, memang terdapat kesesuaian antara konstitusi dengan kovenan tersebut, tetapi tampaknya terdapat beberapa poin yang dalam pandangan penulis kurang sesuai dengan Pancasila. Salah satu bentuknya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). 41 Ahmad Suaedy (dkk.), Islam, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama, dan Berkeyakinan di Indonesia, The Wahid Institute, Jakarta, 2009, hlm. 17. 152 Dr. Rohidin, M. Ag Secara sepintas, Pasal 18 ayat (1) tampak tidak memiliki masalah dan sejalan dengan konstitusi, karena di dalamnya sarat dengan muatan jaminan atas hak seseorang dalam berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Namun demikian, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama tersebut termasuk pula kebebasan untuk tidak beragama (baca: atheis).42 Sementara itu, dengan jelas disebutkan dalam Pancasila bahwa Negara Indonesia pertama-tama berasaskan “Ketuhanan yang Maha Esa”, selain memang secara sosio-kultural keberagamaan dan/atau keberkeyakinan merupakan bagian di dalamnya.43 42 Lihat, Komentar Umum 22 untuk Pasal 18, Komite HAM, 1993. 43 Kasus yang sama, dalam pandangan penulis, juga tampak pada Pasal 18 ayat (4), yang berbunyi: “Negara Pihak dalam Kovenanini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri”. Ayat ini memberikan kepada orangtua jaminan untuk menentukan dan menjamin pendidikan agama dan moral anakanak mereka. Hal ini ditambahkan pada tahapan terakhir dalam perancangan. Hak ini merupakan bagian lingkup budaya dan sosial yang menjadi bagian dari kovenan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan ada dalam kaitan dengan hak tentang pendidikan (Pasal 13 ayat [3]). Sebagai state parties, mestinya Indonesia membebaskan orangtua untuk memutuskan pendidikan agama dan moral apa yang ingin mereka berikan kepada anak-anak mereka. Negara jelas tidak berkewajiban untuk mengarahkan sekolah-sekolah umum Kovenan ini tidak mengatur bagaimana dan di mana pendidikan religius ataupun moral seharusnya diadakan, apakah sebaiknya di dalam sekolah atau luar sekolah. Negara juga tidak dituntut untuk mendanai pendidikan religius, tetapi hanya sebatas memberi toleransi apabila para orangtua ingin menyediakan atau mendanai sendiri pendidikan religius dan moral tersebut. Lihat, Karl Josef Partsh, “Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Kerpolitik”, dalamIfdhal Kasim (ed.), Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 246-247. Jika demikian pemahamannya, maka bagi penulisperundangan tersebut bertentangan dengan budaya bangsa, di mana masyarakat Indonesia, hingga saat ini, masih mendambakan pendidikan agama. Di samping itu, berkaitan dengan pilihan jenis agama di masyarakat masih mengenal dan mengidamkan kesamaan, meskipun dalam beberapa kasus tidak demikian halnya. Dengan kata lain, para orangtua masih menghendaki pendidikan keagamaannya anaknya dijamin dan diatur oleh pemerintah, dan penentuan pilihannya pun masih tergantung sama kehendak orangtua. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 153 d. Perda-perda Bernuansa Syariah Sejak awal tahun 2000-an, isu formalisasi agama menyeruak ke publik, meskipun ini bukan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Isu tersebut berbentuk apa yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda) syariah Islam. Sejauh ini terdapat beberapa argumentasi yang bisa direkam sebagai landasan adanya perda-perda bernuansa agama (Islam). Pertama, umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, namun sepanjang sejarahnya umat Islam (tepatnya, Islam politik) belum pernah mengembalikan bangsa ini. Kedua, sejak tahun 1997 Indonesia diterpa krisis multidimensi dan hingga kini krisis itu belum dilalui dengan baik. Semua cara sudah dicoba, tetapi ternyata Indonesia belum sembuh dari penyakit “krisis”. Islam sebagai alternatif yang bisa mengobati krisis multidimensi belum pernah dicoba, hingga sekaranglah saatnya menerapkan sistem Islam itu. Ketiga, momentum otonomi daerah memberi keleluasaan daerah untuk membuat perda yang sesuai dengan karakteristik daerah. Keempat, para perumus perda itu juga berlindung di balik konstitusi, Pasal 29 UUD 1945, di mana negara memberi jaminan kepada warganya untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya. Singkatnya, perda bernuansa agama dianggap sebagai bagian dari ekspresi kebebasan beribadat. Saat buku ini disusun, tidak kurang dari 22 daerah (kabupaten/ kota) telah menetapkan jenis perda bernuansa agama. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada dasarnya telah mempersoalkan puluhan perda yang mayoritas bernuansa syariah. Perda-perda bermasalah tersebut berjumlah hingga mencapai 96.44 Jenis-jenis perda tersebut paling tidak dapat dipetakan menjadi empat kategori.45Pertama, jenis perda yang terkait dengan isu 44 Kemenkumham, Peraturan Daerah yang Dipermasalahkan, dalam http://www.kemenkumham.go.id, (Diakses pada tanggal 23 Februari 2011). 45 yang dibuat oleh Ahmad Suaedy. Dalam karyanya, Perpektif Pesantren: Islam perdaperda syariah menjadi tiga jenis. Pertama, perda-perda yang berkaitan dengan isu keprihatinan publik (public order) atau pengaturan moral masyarakat, seperti perda anti perjudian, anti prostitusi, dan anti minuman keras. Kedua, perda-perda yang berkaitan dengan keterampilan beragama dan kewajiban ritual keagamaan. Aturan ini seperti aturan tentang kewajiban baca al-Qur’an, 154 Dr. Rohidin, M. Ag moralitas masyarakat secara umum. Meski menyangkut moral, namun perda jenis ini sebenarnya menjadi concern semua agama. Perda jenis ini, terutama diwakili oleh perda anti pelacuran, perizinan yang ada hampir di semua daerah, di mana istilah generiknya adalah perda anti kemaksiatan.46Kedua, jenis perda yang terkait dengan fashion dan mode pakaian lainnya seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu. Perda jenis ini juga banyak sekali muncul di berbagai daerah. Berbeda dengan yang pertama, perda fashion ini jelas sangat sebagai perda syariah Islam. Siapa pun akan mengatakan bahwa dalam jilbab ada kepentingan untuk menunjukkan identitas keislaman.47Ketiga, jenis perda yang terkait dengan keterampilan Islam. Ketiga, perda yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan, seperti kewajiban memakai jilbab bagi perempuan dan baju koko bagi laki-laki pada hari Jumat. Ahmad Suaedy, Perpektif Pesantren: Islam Sosial Baru Islam Demokrasi, The Wahid Institute, Jakarta, 2009, hlm. 146-147. 46 Lihat misalnya, Perda Kota Tangerang No. 08 Tahun 2005 Seri E, Perda Kota Bengkulu No. 24 Tahun 2000, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001, Perda Kota Bukittinggi No. 10 Tahun 2003, Perda Kota Solok No. 6 Tahun 2005, Perda Kab. Padang Pariaman No. 2 Tahun 2004, Perda Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002, Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004, Perda Kab. Lahat No. 3 Tahun 2002, Perda Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2005, Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2002, Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005, Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 1999, Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Tasikmalaya No. 28 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 10 Februari 2005, Perda Kab. Depok 28 April 2005, Perda Kab. Jember No. 14 Tahun 2001, Perda Kab. Gresik No. 7 Tahun 2002, Perda Kota Kupang No. 39 Tahun 1999, Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005, dan Perda Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2003. 47 Seperti yang tergambar dalam Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 5 Tahun 2003. Dalam Perda tersebut, salah satunya, siswi, diwajibkan “Memakai kerudung yang menutupi rambut telinga, leher, dan tengkuk serta dada”. Jika siswi bersangkutan tidak mengindahkan aturan tersebut, sanksi yang diberikan melalui tahapan; (1) ditegur secara lisan, (2) ditegur secara tertulis, (3) diberitahukan kepada orangtua, (4) tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran di sekolah, (5) dikeluarkan/dipindahkan dari sekolah. Sementara itu, pendidikan adalah hak bagi setiap warga, terlebih mereka yang berumur wajib belajar, bagimana mungkin kewajiban warga negara yang berupa belajar justru dipasung dengan sanksi dari pelanggaran terhadap perda yang dapat dikatakan justru kontraproduktif dengan konstitusi tersebut. Selain Perda Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut adalah; Perda Kab. Agam No. 5 Tahun 2005; Perda Kab. Sawahlunto/Sijunjung No. 2 Tahun 2003; Perda Kab. Pasaman No. 22 Tahun 2003; Perda Kota Solok No. 6 Tahun 2002; Perda Kota Batam No. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 155 beragama, seperti keharusan bisa baca tulis al-Qur’an sebagaimana terdapat di Indramayu, Bulukumba (Sulsel), dan sebagainya. Pada tingkat tertentu, perda keharusan di Madrasah Diniyyah Awwaliyah dapat digolongkan sebagai perda keterampilan beragama. Perda jenis ini juga sangat tipikal dengan Islam sehingga tampak sekali kepentingan Islam mendominasi munculnya perda tersebut. Perda keterampilan baca tulis al-Qur’an dan Madrasah Diniyyah ini dikaitkan dengan aktivitas lain. Keterampilan baca tulis al-Qur’an menjadi syarat untuk nikah, naik pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan ijazah Madrasah Diniyyah dijadikan syarat untuk dapat meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lulusan Sekolah Dasar (SD) yang akan melanjutkan ke Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) harus menyertakan ijazah MadrasahDiniyyah.48Keempat, perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat melalui perda zakat, infak, dan sedekah. Beberapa perda jenis ini antara lain Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat di Sukabumi, Perda No. 9 Tahun 2002 di Lombok Timur NTB, Perda No. 4 Tahun 2001 Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah di Cilegon dan lain sebagainya.49 Perda jenis ini merupakan respektasi aktual atas pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi undangundang. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 6 Tahun 2002; Perda Kab. Enrekang No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Maros No. 15 Tahun 2005; dan Perda Bulukumba No. 5 Tahun 2003. 48 Lihat, misalnya, Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2003, Perda Kab. Sawahlunto/Sijunjung No. 1 Tahun 2003, Perda Kab. Pasaman No. 21 Tahun 2003, Perda Kab. Pesisir No. 8 Tahun 2004, Perda Kota Solok No. 10 Tahun 2001, Perda Kota Padang No. 3 dan 6 Tahun 2003, Perda Kab. Banjarmasin No. 10 Tahun 2001 dan No. 4 Tahun 2004, Perda Kab. Enrekang No. 6 Tahun 2005, Perda Kab. Gowa No. 7 Tahun 2003, Perda Kab. Bulukumba No. 4 dan 90 Tahun 2003, dan Perda Kota Gorontalo No. 22 Tahun 2005. 49 Perda-perda lain dalam kategori ini di antaranya adalah Perda Kab. Pesisir Selatan No. 31 Tahun 2003, Perda Kab. Bukittinggi No. 29 Tahun 2004, Perda Kab. Solok No. 13 Tahun 2003, Perda Provinsi Banten No. 4 Tahun 2004, Perda Kab. Cilegon No. 4 Tahun 2001, Perda Kab. Serang No. 6 Tahun 2002, Perda Kab. Tangerang No. 24 Tahun 2004, Perda Kab. Cianjur No. 7 Tahun 2000, Perda Kab. Karawang No. 10 Tahun 2002, Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2003, Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2005, Perda Kab. Lombok Timur No. 9 Tahun 2002, Perda Kab. Banjarmasin No. 9 Tahun 2003, Perda Kab. Maros No. 17 Tahun 2005, dan Perda Kab. Bulukumba No. 2 Tahun 2003. 156 Dr. Rohidin, M. Ag kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam kasus di Lombok Timur, sebagaimana dilansir Rumadi, perda ini menuai protes dari para guru. Mereka menolak zakat profesi dengan memotong sebanyak 2.5% setiap bulan. Setelah terjadi gelombang demonstrasi para guru di Lombok Timur, akhirnya perda ini dibekukan. Kemarahan dan penolakan para guru ini bisa dipahami, karena gaji mereka yang pas-pasan justru menjadi “sapi perahan” birokrasi atas nama agama. Mereka ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai (orang yang berhak menerima zakat) dan bukan (orang yang wajib mengeluarkan zakat).50 2. Kerapuhan Aparatur Penegak Hukum dalam Mengawal Jaminan Kebebasan Beragama: Problem Struktur Hukum Friedman dalam teori three elements law system, menyatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum salah satunya ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (legal structure), yakni merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum adalah institusi dan penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, dan hakim. Dalam kasus kebebasan beragama, penulis akan menggeneralkan dengan istilah alat-alat negara, karena pada kenyataannya yang merespons kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan beragama bukan hanya empat elemen tersebut. Namun demikian, dalam hal ini penulis tidak akan mengupas satu persatu bagaimana fungsi dan tugas catur wangsa tersebut, melainkan hanya akan melihat respons mereka yaitu tindakan aktif (by commission) dan pembiaran (by omission). Kategori pelanggaran tindakan represif dan pembiaran dalam kerangka hukum kebebasan beragama merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, karena negara 50 Baca, Rumadi, “Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara”, dalam Ahmad Suaedy (dkk.), op. Cit., hlm. 29. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 157 merupakan state parties yang terkait secara hukum maupun terikat Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, di mana Pasal 18 menegaskan tentang kewajiban negara menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan. Mengingat konstitusi Indonesia juga menegaskan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan (Pasal 28E), negara juga dianggap telah melakukan pelanggaran konstitusional atas jaminan hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama atau berkeyakinan, termasuk menjalankan ritual ibadatnya. Dua dibuat oleh Setara Institute dalam Laporan Kondisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2008. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa di tahun 2008 negara telah melakukan 99 pelanggaran tindakan aktif yang dapat dikategorikan dalam 17 bentuk, sementara 89 pelanggaran negara berbentuk tindakan pembiaran atas aksi kekerasan dan pembiaran tidak memroses secara hukum atas tindakan kriminal. Pelanggaran tindakan aktif tersebut di antaranya berjumlah 8 dalam bentuk pelarangan ibadat dan aktivitas keagamaan. BupatiSukabumi, sebagai Aparatur Negara, pada tanggal 29 April 2008 melarang aktivitas di enam tempat ibadat Ahmadiyah di Sukabumi: Masjid al-Furqan Parakansalak; Masjid Mubasirin di Kampung Ciletung Desa Lebak Sari Kec. Parakansalak; Masjid Ar-Rahman di Kampung Cigombong, Desa atau Kec. Warung Kiara; Masjid Al-Barokah di Kampung Panjalu Desa Kerawang, Kec. Sukabumi; Masjid Al-Huda di Kampung Bojong Lowa, Desa Sukamantri, Kec. Cisaat; dan Masjid Al-Fadhol di Kampung Simpang Sangit, Desa Bojong Jengkol Kec. Jampang. Pada tanggal 25 Juni 2008, Kejari Tasikmalaya melarang Ahmadiyah melakukan salat Jumat dan mengadakan kegiatan di masjid. Pada tanggal 10 Juni 2008, Wali Kota Cimahi H. M. Itoh Tochija meminta agar Ahmadiyah di Kota Cimahi menghentikan aktivitasnya dengan dalih tidak sesuai dengan SKB. Wali Kota juga meminta Muspida di Kota Cimahi lebih tegas dan melakukan tindakan nyata jika terjadi pelanggaran di lapangan. Pada tanggal 19 Juli 2008, di Tangerang, Banten, Ketua RT, Lurah, dan Camat Kec. Tangerang melarang 158 Dr. Rohidin, M. Ag warga Ahmadiyah beribadat dan menghentikan secara paksa kegiatan Jemaat Ahmadiyah Kec. Tangerang. Pada tanggal 30 April 2008 di Cianjur, Jawa Barat, Kapolsek Ciranjang Cianjur melarang Jemaat Ahmadiyah melakukan ibadat secara berbeda. Pada tanggal 14 Juni 2008, di Kalimantan Tengah, Kakanwil Depag Kalimantan Tengah, H. Anshari meminta kepada Jemaat Ahmadiyah agar menghentikan penyebaran keyakinannya. Pada tanggal 25 Juni 2008, di Tasikmalaya, Kejari Tasikmalaya melarang Ahmadiyah melakukan salat Jumat dan kegiatan di Masjid. Pelanggaran tindakan pembiaran tersebut di antaranya berjumlah 3 dalam bentuk pembakaran tempat ibadat. Pada tanggal 13 Januari 2008 di Lombok Barat,NTB, terjadi pembakaran Pura Sangkareang milik umat Budha. Pada tanggal 28 April 2008 terjadi pembakaran Masjid dan Madrasah Al-Furqon milik JAI di Kampung Parakan Salak RT 02/RW 02 Desa atau Kecamatan Parakan Salak, Kab. Sukabumi oleh Forum Komunikasi Jam’iyatul Mubalighin (FKJM) Parakan Salak. Pada tanggal 20 Mei 2008 di Purwakarta Jawa Barat, terjadi pembakaran gedung sarana pendidikan dan rumah yang difungsikan sebagai Gereja Jemaat Protestan. 3. Krisis Kepercayaan dan Minimnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Kebebasan Beragama: Problematika Budaya Hukum Yang dimaksud dengan budaya hukum (legal culture), sebagaimana dikatakan di atas, adalah keterlibatan masyarakat berkaitan dengan hukum, yang dalam hal ini adalah kebebasan beragama. Keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ideide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan hukum kebebasan beragama tampak dalam dua aspek, yakni sikap dan harapan. Berkaitan dengan sikap, sebagaimana terlihat dalam perundangundangan bahwa terdapat perbedaan mendasar yang berpotensi memunculkan tindakan berlebihan. Perbedaan tersebut terletak Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 159 pada batasan kebebasan. Di dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang bebas dalam berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Cakupan hak ini adalah menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadat, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 18 ayat (3), kebebasan tersebut hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Mendekati hal tersebut adalah UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2). Kebebasan dalam perundangan ini dibatasi oleh nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Berbeda dengan UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1, di mana di dalamnya justru melarang penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang dari pokok ajaran agama. Persoalan menyimpang dan tidak menyimpang dalam hal beragama atau berkeyakinan adalah suatu keniscayaan, dan jika yang berhak menentukan benar dan tidaknya suatu bentuk penafsiran keagamaan atau kepercayaan adalah pihak tertentu, bukan pemeluknya, sebagaimana tampak dalam penjelasan pasal demi pasal, maka hal tersebut merupakan pembatasan yang justru bertentangan dengan dua perundangundangan sebelumnya. Perbedaan batasan tersebut ditanggapi masyarakat secara parsial dan kerap dijadikan legitimasi oleh masing-masing kelompok untuk mengabsahkan tindakannya, yang cenderung mengganggu hak dan kebebasan pihak lain dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Contoh yang kerap muncul adalah kasus Ahmadiyah. Dengan menyandarkan diri pada UU No. 1/PNPS/1965, pihak MUI melalui fatwa tentang aliran sesatnya mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. Fatwa tersebut yang ditambah dengan penyandaranpada UU No. 1/PNPS/1965 dijadikan legitimasi (baca: dipersepsi) oleh banyak kelompok untuk melakukan (dalam bentuk) penyerangan secara brutal kepada pihak Ahmadiyah. Bahkan, beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berisi tentang beberapa larangan beraktivitas bagi JAI, seperti SK Gubernur Jawa Timur 160 Dr. Rohidin, M. Ag No. 188/94/KPTS/013/2011. Dengan keluarnya SK, yang disinyalir sebagai kepanjangan tangan dari SKB No. 3/2008, Kep-033/A/ JA/6/2008 dan No. 199/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Juni 2008, tersebut masyarakat kemudian beraksi dengan beragam cara, menurunkan papan nama salah satu Kantor Cabang Ahmadiyah di Madiun, misalnya.51 Hal yang sama juga terjadi di Pusat Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur, sebagaimana dilakukan oleh Polisi setempat.52 Demikian juga yang tampak pada demonstran anti Ahmadiyah yang menyuarakan aspirasinya agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah tersebut dengan mentendensikan argumentasinya pada UU No. 1/ PNPS/1965, sebagaimana yang terjadi di Kuningan.53 Lain MUI dan masyarakat anti Ahmadiyah, lain pula para aktivis HAM, dengan mentendensikan dirinya pada UU No. 12 Tahun 2005, mereka justru mengkritik terbitnya SKB dan Perda-perda turunan SKB tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Komnas HAM.54 Sementara itu, selaras dengan harapan masyarakat terkait rasa keadilan yang didapatkan, sebagaimana di atas, bisa kita ambil contohkasus Ahmadiyah. Pada saat munculnya SKB Tiga Menteri, Ahmadiyah seharusnya mengajukan gugatan hukum, karena secara jelas SKB tersebut kurang sesuai dengan semangat konstitusi. Perihal peninjauan kembali terhadap perundang-undangan pernah dilakukan oleh aktivis HAM, yakni mengajukan peninjauan 51 http://www.seruu.com/index.php/2011030242453/utama/nasional/ penurunan-plang-ahmadiyah-uu-kalah-dengan-perda-42453/menu-id-691. html, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). 52 http://surabaya.detik.com/read/2011/02/28/174700/1581502/466/ papan-nama-pusat-kegiatan-ahmadiyah-jatim-dicopot, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). 53 Lihat, http://www.seruu.com/index.php/2011030242377/kota/regional/ maraknya-perda-anti-ahmadiyah-picu-aksi-massa-di-kuningan-42377/menuid-759.html;, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). 54 http://www.komnasham.go.id/2010-10-03-02-09-01/66-hot-news/647komnas-ham-sk-larang-aktivitas-ahmadiyah-harus-dikaji-ulang-dengan-uu, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 161 ulang atas UU No. 1/PNPS/1965 yang mereka nilai bertentangan dengan semangat konstitusi, namun pengajuan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.55 Demikian juga dengan kasus perdaperda larangan Ahmadiyah untuk beraktivitas, sebagai organisasi yang terdaftar secara sah, Ahmadiyah seharusnya melakukan peninjauan ulang atas perda-perda tersebut, meskipun hingga buku ini dituliskan wacana tersebut telah bergulir,56 meski dengan jelas banyak turunan perundang-undangan diajukan untuk ditinjau ulang yang ditolak dengan beragam alasan. Budaya hukum di masyarakat pada dasarnya akan berjalan dengan baik jika konsep civil society dapat tertanam dengan baik dalam kehidupan bermasyakat. Sikap kaum Muslim awal yang tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat dapat dijadikan pedomannya. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (tawaڍڍu )ڒdalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja. Dalam konteks negara, selain dianggap memiliki kapasitas sebagai kekuatan penyeimbang (balancing force) dari kecenderungan-kecenderungan dominatif dan intervensionis negara, civil society juga dinilai mampu melahirkan kekuatan kritis ) di dalam masyarakat. Itulah sebabnya civil society dianggap sebagai sebuah prasyarat menuju kebebasan (condition of liberty). Kebebasan di sini dapat diartikan sebagai 55 Bagi MK, para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terkait permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil. Pertentangan norma antara Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti menurut hukum. Karena itu, MK memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan. Telusuri lebih lanjut dalam, MK, op. Cit., hlm. 306. 56 Lihat, http://surabaya.detik.com/read/2011/02/28/205935/1581618/466/ ahmadiyah-akan-gugat-keputusan-gubernur-jatim. (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). 162 Dr. Rohidin, M. Ag kebebasan dari (freedom from) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan, dan kebebasan untuk (freedom for) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional.57 Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan tersebut tentu hanya bisa terwujud dalam suatu sistem kekuasaan yang demokratis.58 Masyarakat dalam konsep civil society adalah masyarakat yang “biasa-biasa” saja, dan karenanya tidak lepas dari kontradiksi internal. Hal itu terjadi karena di dalamnya terdapat masalah-masalah kelas, entitas, dan juga gender, yang—pada titik tertentu—berpotensi merusak civil society. Dalam konsep civil society, permasalahan-permasalahan di atas bukan untuk dihindari, tetapi yang diinginkan dari realitas itu adalah adanya kemampuan untuk melakukan tawar-menawar lewat dialog antar unsur tersebut dalam suatu ruang publik yang bebas (free public sphere). Dengan demikian, inhern di sana tidak untuk dirusak tapi dapat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme yang bersifat setara. Paling tidak, terdapat empat sebab internal yang bisa ditunjuk mengapa kohesivitas antar elemen masyarakat belum maksimal.59Pertama, masih belum terciptanya solidaritas yang kuat antar elemen progresif dalam civil society, karena masih belum pudarnya pengaruh primordialisme atau trauma masa lalu. Antar kelompok agama, etnis, dan kelompok masih cenderung tercipta kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Kedua, belum terlihat jelas adanya platform umum (common platform) yang bisa dipakai oleh kelompok pekerja demokrasi secara bersama-sama. Isu-isu yang dibangun belum benar-benar dimuarakan untuk kepentingan bersama, tetapi hanya 57 Lihat dalam Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, Mizan, Bandung, 1995. 58 Khusus dalam hubungannya dengan negara, paling tidak civil society dapat melakukan salah satu dari tiga fungsi pokoknya. Pertama, civil society berdiri sebagai perisai bagi masyarakat dari perilaku negara yang cenderung hegemonik, otoritarian, dan represif. Kedua, jika negara tidak hegemonik, civil society muncul sebagai mitra negara dalam melaksanakan kepentingan publik. Ketiga, bila kehidupan publik telah diakomodasi secara baik oleh negara, maka civil society dapat memainkan fungsinya secara komplementer, di mana ia muncul untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. 59 Muhammad A.S. Hikam, op. Cit., hlm. xiii. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 163 sekadar simbolisme dan penonjolan kelompoknya masing-masing. Ketiga, masih lemahnya kepemimpinan dalam civil society— secara kualitatif maupun kuantitatif—yang mampu menandingi pengaruh aparat negara. Kelima, masih kuatnya orientasi elitis dalam kelompok pekerja demokrasi sehingga belum mampu menggalang simpati massa. Isu-isu yang dibangun banyak yang mubazir, karena bahasa dan logika yang digunakan sangat elitis dan cukup jauh dengan tingkat pemahaman dan kesadaran psikologis massa bawah. Dalam civil society, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama (public good). Karena itu, tekanan sentral civil society terletak pada independensinya terhadap negara (vis a vis the state). Dari sinilah kemudian civil society dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi. Hubungan antara civil society dengan demokrasi (demokratisasi), sebagaimana dikemukakan oleh Dawam Raharjo, ibarat dua sisi mata uang yang bersifat ko-eksistensi. Hanya dalam civil society yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah civil society dapat berkembang secara wajar. Metafor tentang hubungan antara civil society dengan demokrasi juga dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Menurutnya, civil society merupakan ‘rumah’ persemaian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan rahasia. Namun demokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus memiliki “rumah”, maka rumahnya adalah civil society. Dalam konteks keterkaitan antara civil society dengan demokratisasiini, Larry Diamond secara sistematis menyebutkan bahwa terdapat enam kontribusi civil society terhadap proses demokratisasi. Pertama, ia menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat Negara. Kedua, pluralisme dalam civil society, bila diorganisasi akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis. Ketiga, memperkaya partisipasi politik dan 164 Dr. Rohidin, M. Ag meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Keempat, ikut menjaga stabilitas negara. Kelima, tempat menggembleng pimpinan politik. Keenam, menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim. Lebih jauh, Diamond menegaskan bahwa suatu organisasi betapapun otonomnya, jika ia menginjak-injak prosedur demokrasi—seperti toleransi, kerja sama, tanggung jawab, keterbukaan dan saling percaya—maka organisasi tersebut tidak akan mungkin menjadi sarana demokrasi.60 Dengan demikian, kebebasan beragama di negara ini hanya akan terwujud jika demokrasi telah benar-benar berjalan dengan baik. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengutip 61 adalah: Mungkinkah demokrasi tegak di tengah masyarakat yang tidak civilized (madani)? Mungkinkan civil society dapat ditegakkan di dalam sistem yang tidak demokratis? Dua pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam mengaktualisasikan dan mewujudkan masyarakat yang bebas beragama sebagai salah satu kondisi yang mesti ada dalam sebuah tatanan masyarakat, dan lebih jauh tatanan negara, yang demokratis. Dengan kata lain, untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang bebas beragama dalam konteks civil society, prasyarat yang terlebih dahulu dipenuhi adalah teraktualisasinya demokrasi secara menyeluruh dalam sebuah negara. Apa yang telah tergambar dalam tiga aspek tersebut menunjukkan betapa problem kebebasan beragama di Indonesia ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Jika problem tersebut dibiarkan berlarut-larut sudah barang tentu akan mengganggu jalannya proses pembangunan. Tidak hanya itu, pembiaran yang berkelanjutan tersebut bisa jadi akan mengancam stabilitas Pemerintahan, dan bahkan eksistensi negaranya, karena—diakui atau tidak—persoalan agama adalah persoalan sensitif yang tidak 60 A. Ubaidillah (dkk.), op. Cit., hlm. 152. 61 Civil Society di NegaraNegara Arab” dalam Bernard Lewis, et. al., Islam, Liberalisme, Demokrasi: Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 233. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 165 serta-merta dapat diselesaikan dengan mudah oleh suatu negara. D. Proses dan Konstruksi Baru Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Indonesia adalah negara yang tidak perlu lagi diragukan dalam hal menerima dan mengakui kebebasan beragama, bahkan menempatkannya sebagai sesuatu yang konstitutif dan mengikat. Namun demikian, sebagaimana kerap diungkap di muka bahwa kemapanan konseptual tersebut tidak sejalan dengan produk regulasi turunannya dan realitas pandangan masyarakat, termasuk intelektual Muslimyang berkaitan dengan fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan. Buku ini hendak melakukan rekonstruksi ragam problem tersebut agar sejalan dengan konsep normatifnya, Pancasila. Artinya, objek rekonstruksi ini adalah ketidaksepahaman sebagaian masyarakat berkaitan dengan konsep kebebasan beragama kaitannya dengan fatwa MUI tentang aliran sesat di Negara Hukum Indoneisa. Adapun basis rekonstruksinya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi salah satu nilai fundamental Pancasila. Pemilihan nilai dari Pancasila sebagai basisnya ini lebih ragam unsur atas konsep-konsep, yang beberapa elemen pokok partikularnya bertentangan. Sebagai sebuah titik temu dari beragam unsur, Pancasila—dalam pandangan Mahfud MD.— sebenarnya merupakan perwujudan dari konsep prismatik. Sebagai konsepsi prismatik, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Dengan demikian, paling tidak, ada dua hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun konsep kebebasan beragama dengan basis prismatik ini. Pertama, memuat unsur yang baik dari pandangan kolektivisme, yang berbasis pada ideologi partikular-absolut, dan individualisme, yang berbasis pada ideologi 166 Dr. Rohidin, M. Ag ǦǤǡakar ǦǤ beragamnya suku dan budaya. Namun demikian, pluralitas tersebut dapat disatukan dalam semboyan, “Bhineka Tunggal Ika”. Artinya, Ǧ yang berbeda tersebut. Kedua, Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut paham religious nation state, dalam arti bukan negara agama dan bukan pula negara Ǥ , aturan mengenai keberagamaan dan/atau keagamaan dapat dikonstruksi dalam bingkai hukum yang ǡ bukan agama. Dua hal tersebut dapat disederhanakan dalam ragaan sebagai berikut: Ragaan. 4.3. Kecenderungan: Mengutamakan kepentingan kolektif Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia (Religious Nation State) Existing: Eksklusif Berbasis partikular absolut Kecenderungan: Mengutamakan kepentingan individualisti Existing: Liberal Berbasis universal absolut NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Hal demikian itu pada dasarnya tampak jelas dalam sila pertama ǡ Ǥ rechtsidee konsep kebebasan beragama di Indonesia—sebagaimana telah diungkap sebelumnya—nilai dasar yang termuat di dalamnya tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga politis. Implikasinya adalah Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 167 bahwa nilai dasar itu menuntut orang untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar-pemeluk agama dan/atau kepercayaan yang beragam terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Berikut gambaran dialektika dua persepsi di atas beserta proses prismatiknya, sehingga menjadi bahan pertimbangan konstruksi baru konsep kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia: Tabel 4.5. Dialektika Kondisi Existing Problem Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berkaitan dengan Persepsi Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Titik Perbedaan Kolektivisme Individualisme Bentuk Persepsi Eksklusif Inklusif-Liberal Basis Nilai Agama Humanisme Basis Ideologi Partikular-Absolut Universal-Absolut Dasar Legitimasi UU No. 1/PNPS/1965 UU No. 12 Tahun 2005 168 Dr. Rohidin, M. Ag Pandangan atas Fatwa MUI tentang Aliran Sesat berkaitan dengan Kebebasan Beragama 1. Pemerintah harus melindungi agama dan pemeluknya. 1. Pemerintah harus melindungi pemeluk agama dan pengikut suatu keyakinan (aliran kepercayaan), bukan agama dan keyakinan itu sendiri. 2. Aliran sesat bukan termasuk bagian dari problem kebebasan beragama (sebagai bagian dari HAM). 2. Aliran sesat termasuk bagian dari problem kebebasan beragama (sebagai bagian dari HAM). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 169 170 3. Suatu keyakinan atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat bukan bagian dari hak kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM, justru ia telah melanggar HAM. 3. Semua aliran atau keyakinan adalah bagian dari hak kebebasan beragama yang merupakan bagian dari HAM. 4. Kebenaran tafsir keagamaan dapat ditentukan secara kolektif (mainstream). 4. Tafsir keagamaan tidak memiliki kebenaran mutlak, artinya ditentukan oleh keyakinan individu. 5. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, memang bersifat legal opinion tetapi karena kolektivitasnya maka kebenarannya bersifat mutlak. 5. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, bersifat legal opinion. Karena itu, ia sejajar dengan bentuk tafsiran lain yang mungkin bertentangan. 6. Berkaitan dengan kasus persekusi, aliran sesatlah yang menjadi pemicunya. 6. Berkaitan dengan kasus persekusi, aliran sesat bukan sebagai pemicunya. Dr. Rohidin, M. Ag Konsekuensinya Pemerintah harus tegas untuk membubarkan dan melarang aliran yang dianggap sesat oleh MUI. Pemerintah harus menindak tegas para pelaku persekusi, dan wajib melindungi para penganut suatu keyakinan atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat oleh MUI. Tabel 4.6. Konstruksi Baru Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berkaitan dengan Persepsi Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Bentuk Persepsi Inklusif-Moderat Basis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Pancasila) Basis Ideologi Universal-Relatif Dasar Legitimasi UUD 1945 Pandangan atas Fatwa MUI tentang Aliran Sesat berkaitan dengan Kebebasan Beragama 1. Pola perlindungan dan penjaminannya ditekankan pada pemeluk agama atau penganut suatu keyakinan (aliran kepercayaan) beserta agama dan keyakinan (kepercayaan) itu sendiri dalam batasan-batasan tertentu. 2. Aliran sesat termasuk bagian dari problem kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM, selama ia secara konstitusional dapat dikatakan demikian. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 171 3. Suatu keyakinan atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat dapat dikatakan melanggar hak kebebasan beragama yang merupakan bagian dari HAM jika memang secara konstitusional dapat dikatakan demikian. 4.Tafsir keagamaan memang tidak memiliki kebenaran yang bersifat mutlak, akan tetapi tidak sertamerta kemudian seseorang dengan bebas melakukan penafsiran dengan tanpa metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, bersifat legal opinion dan bisa menjadi referensi dalam menentukan kebijakan kasus aliran sesat, tetapi bukan merupakan satusatunya referensi. 6.Berkaitan dengan kasus persekusi, jika secara konstitusional pelakunya dapat dikatakan melanggar hukum, baik itu dari pihak aliran yang dianggap sesat maupun pelaku persekusi, maka keduanya bisa jadi dikatakan sebagai pemicu. 172 Dr. Rohidin, M. Ag Konsekuensi Pembentukan regulasi turunan yang dapat mengakomodasi jaminan perlindungan atas individu pemeluk agama atau penganut suatu keyakinan (aliran kepercayaan) beserta agama dan keyakinan (kepercayaan) itu sendiri dalam batas-batas tertentu yang selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah konsekuensi bagi pemerintah. Batasan-batasan yang dimaksud dalam tabel 4.6. contohnya adalah apa yang diistilahkan dengan blashphemy.62 Hal demikian menjadi lazim karena, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, Indonesia adalah Religious Nation State63 dan didasarkan atas hukum yang berisi nilai-nilai Pancasila, bukan agama. Sementara itu, kenyataan yang ada adalah bahwa produk regulasi turunan tentang sosial-keagamaan satu sama lain tampak kontraproduktif, dan bahkan kontradiktif. Sehingga, re-evaluasi dan harmonisasi 62 Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa yang dimaksud dengan blashphemy adalah; “Any oral or written reproach maliciously cast Book of Common Preyer, intended to wound the feelings of mankind or to excite contempt and hartred against the church by law established, or to promote immorality”. Hanry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, hlm. 171. Artinya, agama dan seperangkatnya dapat dilindungi oleh negara hanya dalam batasan untuk tidak direndahkan dalam bentuk penghinaan. Sementara itu, pada wilayah penafsiran keagamaan, negara tidak memiliki hak untuk mengaturnya. Di samping karena secara fundamental agama memang berpotensi untuk ditafsiri secara beragam, juga tidak akan ditemukannya general terminology yang akomodatif dari ragam perbedaan dalam dunia penafsiran. Mendekati pola semacam itu adalah pandangan Kaelan, menurutnya regulasi tentang kebebasan beragama harus bertumpu pada jaminan perlindungan atas pemeluk keyakinan atau agama sekaligus institusi keyakinan atau keagamaan itu sendiri. Berkaitan dengan tafsir keagamaan, Kaelan berpandangan bahwa hal tersebut menjadi sah selama tidak dianggap menghina institusi keyakinan atau keagamaan lain. Wawancara dengan Kaelan, Guru Besar UGM, di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2011. Bandingkan dengan, Barda Nawawi Arif, op. Cit., hlm. 65-66. 63 Hal senada juga diungkapkan oleh Amidhan, Pihak Terkait, dalam Sidang Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965 pada hari Kamis, 4 Februari 2010 di Gedung MK Jakarta. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 173 adalah konsekuensinya. Agenda tersebut dapat dijalankan secara konsisten mengacu pada Pancasila yang telah menggariskan empat kaidah penuntun hukum nasional. Kaidah-kaidah ini tidak terlepas dari kedudukan Pancasila yang menjadi citra hukum (rechtsidee) dan merupakan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Berkaitan dengan konsep kebebasan beragama, maka kaidahkaidah penuntun itu dapat dijabarkan dalam bentuk: 1. Hukum kebebasan beragama di Indonesia bertujuan dan menjamin integrasi bangsa. Konsep hukum tersebut tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. 2. Hukum kebebasan beragama di Indonesia dirumuskan dengan pola yang selaras dengan cita pembangunan demokrasi dan nomokrasi. Konsep hukum tersebut tidak dibuat berdasar paradigma keagamaan mainstream semata, dan prosedur yang benar. 3. Hukum kebebasan beragama di Indonesia diproduk dalam rangka membangun keadilan sosial. Tidak bisa dibenarkan jika produk hukum tersebut berpotensi mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial karena eksploitasi oleh golongan mainstream terhadap minoritas tanpa perlindungan Negara. Selain itu, konstruksi hukum kebebasan beragama juga diarahkan untuk menjaga agar minoritas tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak mainstream yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang mainstream. 4. Hukum kebebasan beragama di Indonesia diproduk dalam rangka membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Konsep hukum tersebut tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama dan/atau keyakinan (yang mendasarkan pada satu agama atau keyakinan tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tidak peduli atau hampa spirit keagamaan). Konsep hukum negara tidak dapat 174 Dr. Rohidin, M. Ag mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Dalam menyusun aturan soal agama, kaidah pertama dan keempat di atas mesti diperhatikan, karena hukum Indonesia bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, dan pada saat bersamaan membangun toleransi beragama serta berkeadaban. Harus disadari, agama dalam arti keyakinan secara fundamental merupakan wilayah privat, sehingga negara memiliki kewenangan untuk mengaturnya hanya dalam batas-batas tertentu atas kepentingan ketertiban sosial, bukan kepentingan agama itu sendiri. Sehingga, pengaturan terbatas pada bagimana masing-masing orang mengekspresikan keyakinannya supaya tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Aturan hukum sebaiknya hanya mengatur kehidupan bersama, interaksi, dan interelasi antar warga negara yang berbeda agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, hukum diproduk bukan dalam rangka mengatur kegiatan dan keagamaan secara individual dan internal komunitas pemeluk agama, apalagi mengatur kegiatan keagamaan yang terkait dengan pengalaman, sakralitas, dan ritualitas menurut keyakinan masing-masing agama atau suatu keyakinan. Tidak boleh, misalnya, negara membuat aturan hukum yang mewajibkan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh agama atau suatu keyakinan, atau sebaliknya melarang sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang agama atau suatu keyakinan. Selain itu, nilai-nilai humanitas juga mesti terkandung di segala produk hukum. Bertolak dari gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo—sebagaimana telah diungkap dalam kerangka pemikiran—maka diproduknya sebuah hukum ditujukan untuk manusia, dalam arti bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak beragama tetap menjunjung nilai-nilai humanitas. Jika suatu produk hukum berkaitan dengan hal tersebut kurang dianggap relevan, UU No. 1/PNPS/1965 misalnya, maka pihak berwenang mestinya tidak Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 175 gamang untuk merevisinya. Karena, segala produk hukum sejatinya selalu berada pada status “law in the making”, yakni selalu berproses dan menjadi. Bertolak dari ragam persoalan dan kerangka prismatika tersebut, maka konsep kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia dapat dirumuskan dalam pola jaminan perlindungan atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama serta keyakinan dan agama itu sendiri yang berbasis pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan pola semacam ini, tidak bisa dengan serta-merta seseorang memaksakan kehendak keyakinan atau keberagamaannya kepada orang lain, termasuk dalam hal penafsiran. Seseorang juga tidak bisa dengan sesuka hati melakukan penghinaan terhadap suatu agama atau keyakinan, termasuk pula ritus-ritus yang menyertainya. Selain itu, seseorang juga dilarang untuk mengganggu prosesi upacara suatu agama atau keyakinan, apalagi melakukan perusakan-perusakan terhadap tempat-tempat peribadatan keagamaan atau suatu keyakinan. Pola semacam ini dapat disederhanakan dalam ragaan sebagai berikut: 176 Dr. Rohidin, M. Ag Ragaan. 4.4. Negara Hukum Indonesia Berbasis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab UniversalAbsolut Antroposentris PartikularAbsolut Universalisme Individualisme HAM PANCASILA Partikularisme UniversalRelatif Theosentris Kolektivisme TheoAntroposentris Humanistik Bhineka Tunggal Ika Ketuhanan YME Kemanusiaan yang Adil dan Beradab PASAL 28 DAN 29 UUD 1945 Regulasi HAK: 1. Berpikir dan berpendapat terkait persoalan agama atau keyakinan. 2. Memeluk agama atau keyakinan. 3. Mendapatkan jaminan atas kebebasan berpikir dan berpendapat terkait persoalan agama atau keyakinan. 4. Mendapatkan jaminan atas kepemelukan seseorang terhadap agama atau keyakinan. 5. Mendapatkan perlindungan atas keagamaan atau keyakinan seseorang. 6. Mendapatkan perlindungan atas tempattempat peribadatan, termasuk ritus dan upacara upacara keagamaan atau keyakinan, yang dimiliki. KEWAJIBAN: 1. Menghormati hak kebebasan berpikir dan berpendapat terkait persoalan agama atau keyakinan. 2. Menghormati agama atau keyakinan orang lain. 3. Menghormati keberadaan tempattempat peribadatan, termasuk ritus dan upacara upacara agama atau keyakinan. LARANGAN: 1. Menghina suatu agama atau keyakinan, termasuk halhal yang terkait di dalamnya. 2. Menghasut seseorang untuk meniadakan keyakinan terhadap Tuhan. 3. Melakukan persekusi terhadap suatu agama atau keyakinan, baik fisik maupun mental. 4. Mengganggu upacara upacara agama atau keyakinan. 5. Merusak tempattempat peribadatan suatukeagamaan atau keyakinan. Terkait dengan kehidupan beragama, penulis merekomendasikan lima agenda besar sebagai solusi dari problem utama kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia. Lima agenda tersebut adalah sebagai berikut: 1. Ǧ ǡ Ǧ beragama. perlu disesuaikan dengan semangat Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 177 perlindungan dan jaminan, termasuk pula re-evaluasi dan harmonisasi atas ketentuan-ketentuan dalam kovenan internasional tentang kebebasan beragama, baik dari segi materinya itu sendiri maupun tentang kelembagaan dan peradilannya. 2. Melakukan inventarisasi, mengevaluasi, dan mengkaji seluruh produk hukum, yang berlaku dan kurang sesuai dengan semangat Pancasila. Ada beberapa pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang kurang sesuai dengan semangat Pancasila. 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansiinstansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan kebebasan beragama. Sebagaimana tampak dalam pembahasan problematika hukum kebebasan beragama, rendahnya kapasitas sistem peradilan juga turut andil dalam meningkatnya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. 4. Sosialisasi dan pemahaman tentang konsep kebebasan beragama dengan basis Pancasila itu sendiri, khususnya di kalangan pemerintah, utamanya di kalangan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masalah kebebasan beragama. Sosialisasi pemahaman ini terkait dengan penegakan profesionalisme aparat di dalam melaksanakan bidang kerjanya. Gamangnya aparat pemerintah dalam mengurusi dan berurusan dengan masyarakat yang partisipasi politik dan daya kritisnya makin tinggi ini disebabkan, antara lain karena mereka umumnya kurang dapat melaksanakan rambu-rambu profesionalismenya. Ini berlaku bagi aparat sipil maupun aparat keamanan. 5. Kerjasama dengan kalangan di luar pemerintahan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap penegakan hukum kebebasan beragama. Langkah ini juga dirancang guna mensosialisasikan pemahaman tentang kebebasan beragama secara merata di dalam masyarakat. Karena, 178 Dr. Rohidin, M. Ag diakui atau tidak, munculnya masyarakat juga kerap dilandasi dengan pengetahuan yang dangkal tentang kebebasan beragama. Namun demikian, perlu menjadi titik tekan, betapapun produk hukum dianggap mapan, kebebasan beragama tidak akan teraplikasikan jika sektor aparatur penegak hukum dan budaya masyarakatnya belum siap. Sebaliknya, betapapun produk hukum tidak dianggap mapan, tetapi jika budaya masyarakatnya sangat mapan, maka kebebasan beragama akan berjalan dengan sendirinya secara sempurna. Dengan kata lain, problem kebebasan beragama sesungguhnya dengan sendirinya akan teratasi jika civil society telah membumi dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 179 180 Dr. Rohidin, M. Ag LIMA Penutup Kebebasan beragama dan keyakinan (freedom of religion and belief) merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara kodrati melekat pada diri manusia serta bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, ia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Hak ini selain tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terdapat juga dalam berbagai dokumen historis HAM lainnya, seperti dokumen Magna Charta (1215), Bill of Rights England (1689), Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791), Rights of Russian People (1917), dan International Bill of Rights (1966). Pada perkembangannya, kebebasan ini kemudian lebih rinci diatur dalam Pasal 18, 20 ayat (2), dan Pasal 27 Instrumen InternationalCovenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap penjaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tampak semakin terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada amandemen kedua UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memasukkan satu bab yang secara khusus memberi landasan penjaminan HAM bagi setiap warga negara, yakni BAB XA. Pada bab ini, terdapat sepuluh pasal tentang HAM yang hampir seluruhnya mengadopsi prinsip-prinsip DUHAM dan ICCPR. Salah satu hak asasi yang diatur dalam bab ini menyangkut hak kebebasan beragama dan keyakinan bagi setiap warga negara, seperti yang Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 181 diatur dalam Pasal 28E UUD 1945. Pasal ini menegaskan tentang cakupan hak kebebasan beragama dan (ber)-keyakinan—yakni hak untuk memeluk agama, hak untuk menganut satu keyakinan, dan hak untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya. Konsekuensinya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam ketiga aspek tersebut. Jaminan konstitusi mengenai hakhak tersebut diperkuat oleh beberapa peraturan perundangundangan di bawah UUD 1945, antara lain Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 4, Pasal 12, dan Pasal 22. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni dalam Pasal 6 dan Pasal 43 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, terutama yang diatur dalam Pasal 18, 20, dan 27. ICCPR yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini bukan sekadar sebagai bentuk pengadopsian prinsip internasional hak sipil dan politik ke dalam hukum nasional, Indonesia ke dalam suatu kedudukan dan kewajiban tertentu. Dengan Indonesia memutuskan kebijakannya untuk menempatkan dirinya dalam pemantauan badan internasional, khususnya terkait hak sipil dan politik. Hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (right to freedom of thought, conscience, and religion) merupakan salah satu hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (nonderogable rights). Ini berbeda dengan kebebasan menjalankan agama atau keyakinan yang dapat dibatasi (derogable rights), karena hak ini berkaitan dengan hak-hak orang lain. Meskipun pembatasan kebebasan beragama sudah diatur secara jelas, yakni untuk melindungi lima keamanan yang diperlukan oleh masyarakat, di dalam UUD 1945 Pasal 28J ditambah satu aspek lagi, yakni meletakkan kesesuaian dengan moral dan nilai-nilai agama sebagai pertimbangan. Pasal inilah yang kemudian dipersoalkan oleh pembela HAM universal-absolut, kaitannya dengan moral seperti apa serta nilai-nilai apa saja dari agama itu yang dijadikan pertimbangan. Problematika pertimbangan dalam pembatasan seperti ini dapat dipahami, karena bagi pembela HAM universal- 182 Dr. Rohidin, M. Ag absolut yang terpenting adalah melindungi individu-individu pemeluk agama atau keyakinannya, bukan pada agama atau suatu keyakinan yang dipeluk atau dianut. Berbeda dengan pandangan tersebut, bagi sebagian masyarakat yang lain pembatasan seperti itu masih dimungkinkan sepanjang diatur oleh undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Jika cara pandang yang digunakan adalah perspektif sebagian masyarakat yang menyetujui adanya pertimbangan tersebut, maka Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya sejalan dengan berbagai Indonesia. Pola pemikiran demikian berimplikasi pada cara pandang terhadap UU No. 1/PNPS/1965 sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang. Dengan adanya peluang yang diberikan oleh Pasal 28J tersebut, maka UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana tampak pada namanya, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, semula adalah Penetapan Presiden (PNPS) yang dikeluarkan tahun 1965. Pada perkembangannya, PNPS tersebut ditetapkan menjadi undangundang (baca: diperundangkan) melalui UU No. 5 Tahun 1969. Latar belakang yang mendasari dikeluarkannya UU No. 1/ PNPS/1965 tidak terlepas dari aspek ideologis, integralitasnasionalis, dan aspek sosial kemasyarakatan keagamaan atau sosial-religius. Dengan kata lain, menjadi ironis jika sebuah negara yang masyarakatnya beragama tidak ada perangkat hukum yang menjamin dan melindungi agama dari perbuatan menyimpang dan menodai agama, bahkan ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang banyak menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bagi agama serta ketenteraman beragama. Pasal 1 dari undangundang tersebut berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 183 yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Kalimat “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” berarti mengandaikan adanya institusi atau lembaga yang berwenang untuk menentukan tafsir mana yang benar dan mana yang menyimpang. Dalam penjelasan undangundang tersebut dikatakan bahwa “Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama [Kemenag]) yang untuk itu mempunyai alat-alat/caracara untuk menyelidikinya”. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa saat ini komposisi Kemenag lebih didominasi oleh personperson manajerial yang bukan dari kalangan agamawan (Islam: ulama), sementara kalangan yang dianggap dapat mengetahui adanya unsur penyimpangan dari pokok ajaran agama (Islam) hanyalah para ahli agama (Islam), ulama. Di Indonesia terdapat organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari namanya saja, sekilas dapat dipahami bahwa person yang terlibat di dalamnya berstatus sebagai ulama, meskipun pada bagian-bagian tertentu terdapat person-person yang bukan ulama. Secara struktural, elite MUI memiliki komposisi yang beragam, dalam pengertian diduduki oleh ragam ulama yang berasal dari lintas Ormas Islam. Komposisi demikian ini kemudian dianggap sebagai keterwakilan dari masingmasing Ormas. Anggapan keterwakilan inilah yang kemudian memberi nilai tawar tersendiri bagi MUI di mata pemerintah dan sebagian masyarakat. Namun demikian, bukan berarti pemerintah selama ini selalu mengekor kepada MUI. Dalam kasus penodaan agama, pertimbangan ulama bagi pemerintah adalah suatu keniscayaan referensial. Untuk saat ini, bagi pemerintah, suara MUI dapat dinilai representatif dan dapat dikatakan sebagai . Kenyataannya memang demikian, dalam arti bahwa umumnya kasus pembubaran atau pelarangan aliran sesat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai implikasi dari adanya fatwa MUI. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada saat ini 184 Dr. Rohidin, M. Ag amanat dalam undang-undang tersebut kerap dilimpahkan kepada MUI. Sejak didirikan pada 1975, MUI pusat telah mengeluarkan delapan fatwa tentang aliran sesat. Delapan fatwa tersebut ditujukan untuk aliran-aliran sebagai berikut: (1) Islam Jamaah atau Darul Hadis; (2) Munkir al-Sunnah (Kelompok Penolak Sunnah/Hadis Rasul); (5) Darul Arqam; (6) Kelompok Salamullah; (7) Ahmadiyah (Qadiyan dan Lahore); dan (8) Al-Qiyadah al-Islamiyah. Beragam aliran lain juga pernah dinyatakan sesat oleh beberapa MUI Daerah. Kelompok Husnul Huluq, misalnya, aliran ini dinyatakan sesat oleh MUI Kecamatan Paseh, Kab. Sumedang pada tahun 2005. Demikian juga beberapa aliran lain, seperti: sebuah aliran salat dua bahasa pimpinan Yusman Roy yang dinyatakan sesat oleh MUI Jawa Timur pada tahun 2005, aliran Amanat Keagungan Ilahi yang dinyatakan sesat oleh MUI Sumatera Selatan pada tahun 2009, aliran Ilmu Kalam Santriloka yang dinyatakan sesat oleh MUI Mojokerto pada tahun 2009, dan aliran Sabda Kusuma yang dinyatakan sesat oleh MUI Jawa Tengah pada tahun 2011. Berkaitan dengan kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM, ragam fatwa (baca: penilaian sesat) yang dikeluarkan oleh MUI—baik pusat maupun daerah—tersebut ditanggapi secara beragam oleh kalangan intelektual Muslim. Ada yang mengakuinya sebagai kebenaran hingga harus dikawal sedemikian rupa meskipun sebagian persepsi mereka kemudian mewujud dalam tindakan anarkis, ada yang mengakuinya sebagai kebenaran tetapi tidak wajib untuk mengikutinya apalagi mengawalnya, ada pula yang justru menganggap MUI telah melanggar HAM karena telah menilai mereka sebagai aliran sesat. Artinya, terjadi dialektika antara fatwa MUI dan konsep kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM yang telah terbingkai dalam konstruksi hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum. Pada saat dialektika ini mewujud dalam tindak intoleransi keberagamaan, maka pada saat itu juga persepsi tersebut berkaitberkelindan dengan persoalan HAM dan hukum. Persepsi intelektual Muslim terhadap fatwa MUI tentang aliran sesat ini menjadi pintu Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 185 masuk dalam mengkaji problematika konsep kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia. Pasalnya, mengupas persoalan fatwa MUI tentang aliran sesat kaitannya dengan HAM dan hukum tidak hanya berada dalam dataran praksis, lebih dari itu dataran teoretis juga menjadi pewarnaannya. Dialektika tersebut mengandaikan adanya relasi beberapa elemen penting, yakni Negara Hukum Indonesia beserta sistemnya, masyarakat beraliran mainstream beserta elite agamawannya, MUI beserta fatwanya, dan kelompok keagamaan atau keyakinan (kepercayaan) minoritas yang dicap sesat, namun titik tekan di sini utamanya adalah fatwa MUI, Negara Hukum Indonesia, dan HAM. Kelompok yang menggunakan ideologi HAM partikularabsolutmenganggap benar apa yang dilakukan oleh MUI, di samping karena komitmen keagamaan yang mereka pegang dan jalankan juga melegitimasi persepsinya dengan UU No. 1/ PNPS/1965. Namun, karena pemerintah tidak tegas dalam meresponnya sebagian di antara mereka kemudian berreaksi secara berlebihan dengan melakukan berbagai bentuk persekusi. Sedangkan kelompok yang menggunakan ideologi HAM universalabsolut menganggap fatwa MUI bertentangan dengan HAM mentendensikan persepsinya pada UU No. 12 Tahun 2005. Artinya, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa bentuk regulasi berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama di Indonesia masih terdapat permasalahan. Inti permasalahan regulatif tersebut pada dasarnya terletak pada ambiguitasnya. Di satu sisi kebebasan beragama mendapatkan jaminan konstitusional sebagai bagian dari HAM. Namun di sisi lain,konstitusi serta instrumen perundanganundangan lainnya masih membatasi hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama sebagai hak kodrat yang dimiliki setiap manusia. Kontradiksi persepsi intelektual Muslim terhadap fatwa MUI tentang aliran sesat berkaitan dengan konsep kebebasan beragama di Indonesia dapat teratasi jika ambiguitas regulasinya dapat diatasi dengan baik. Untuk itu, sudah saatnya dirumuskan konsep kebebasan beragama dalam bingkai hukum berdasarkan kesepakatan hakikat negara ini yang menyatakan bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Sekalipun oleh sebagian 186 Dr. Rohidin, M. Ag masyarakat hasil kesepakatan tersebut dijadikan ruang silang pendapat yang cukup tajam mengenai kebebasan beragama. Bahkan, dapat dikatakan bahwa masalah kebebasan beragama adalah masalah rumit dan kompleks, yang tidak hanya dalam rumusan regulasinya, tetapi juga masalah pelaksanaannya di lapangan. Setidaknya terdapat tiga ranah masalah yang muncul dari konsep kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia. Pertama, ranah struktur hukum yang dalam hal ini negara atau pemerintah dengan berbagai aparaturnya (polisi, jaksa, dan hakim). Kedua, ranah substansi hukum, yakni tentang adanya berbagai jenis peraturan perundangan yang kontradiktif satu sama lain. Ketiga, ranah budaya hukum, sebab, meski keduanya telah mapan, hak kebebasan beragama tidak akan berjalan dengan baik jika budaya hukumnya tidak kondusif, terlebih jika persepsi kontradiktif sebagaimana di atas tidak dapat disatukan. Buku ini berupaya mencari solusi dari problem konseptual kebebasan beragama berbasis nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai salah satu sila dari Pancasila. Dalam buku ini, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori black box kebijakan publik David Easton, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori bekerjanya hukum dalam masyarakat ChamblissSeidman, dan teori prismatik Fred W. Riggs digunakan untuk menjawab persoalan tersebut. Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa fatwa MUI berkaitan dengan aliran sesat keagamaan ditanggapi secara beragam oleh kalangan intelektual Muslim. Ragam persepsi ini dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu eksklusif, inklusifmoderat, dan inklusif-liberal.Kelompok eksklusif memandang bahwa fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan di Indonesia tidak melanggar HAM, khususnya hak kebebasan beragama. HAM, bagi mereka tidak identik dengan kebolehan merusak kedaulatan suatu agama, karena jika atas nama HAM, kemudian merusak nilainilai agama, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena itu, dalam konteks fatwa tentang aliran sesat keagamaan, bagi mereka, MUI sudah berada pada jalur yang benar. Sementara itu, dalam konteks Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 187 status dan otoritas fatwa berkaitan dengan tata hukum di Indonesia, bagi mereka, sekalipun fatwa hanya bersifat legal opinion, tetapi akan menjadi sumber rujukan ketika dikaitkan dengan UU No. 1/ PNPS/1965. Kelompok inklusif-moderat memandang bahwa sebagai representasi dari elit agamawan dalam Islam, MUI memiliki hak untuk menilai suatu kelompok kegamaan seimannya yang berbeda dalam persoalan akidah. Namun demikian, sebagai sebuah legal opinion, fatwa juga mengandung dissenting opinion. Adanya potensi ini berimplikasi pada keharusan MUI untuk menerima dissenting opinion tersebut dan mempertanggungjawabkannya di hadapan publik guna menuai predikat otoritatifnya.Sementara itu, dalam konteks status dan otoritas fatwa berkaitan dengan tata hukum di Indonesia, bagi mereka, MUI berhak meminta dukungan negara, tetapi tidak berhak untuk memaksanya agar mengikuti hasil fatwanya dengan cara melarang penyebaran aliran yang dinyatakan sesat, membekukan organisasi, serta menutup semua aktivitas dan tempat kegiatannya. Demikian ini, bagi mereka, karena adanya keharusan negara untuk bersikap netral. Dalam persoalan kebebasan beragama, bagi mereka, negara hanya memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjamin keamanan setiap pemeluk agama dan/atau penganut suatu keyakinan, bukan mengintervensinya. Kelompok inklusif-liberal memandang bahwa fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan telah melanggar basis-basis moral keislaman universal serta bertentangan dengan HAM, dan bahkan konstitusi, terlebih lagi jika MUI kemudian “memaksa” negara untuk mengikuti hasil fatwanya dengan cara melarang penyebaran aliran yang dinyatakan sesat, membekukan organisasi, serta menutup semua aktivitas dan tempat kegiatannya. Berkaitan dengan persoalan kebebasan beragama, bagi mereka bebas tanpa batas hanya ada pada forum internum, sementara kebebasan dalam bingkai “tindakan” boleh untuk dibatasi berdasarkan undangundang. Namun demikian, pembatasan dengan model UU No. 1/PNPS/1965, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1, termasuk pelanggaran nilai-nilai dasar HAM. Karena, perbedaan penafsiran dalam sebuah agama adalah keniscayaan, dan otoritas kebenaran 188 Dr. Rohidin, M. Ag tafsir tidak bisa dimiliki atau ditentukan oleh perorangan atau lembaga tertentu.1 Dari tiga bentuk persepsi tersebut, dua di antaranya (eksklusif dan inklusif-liberal) dinilai kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut disebabkan karena persepsi mereka berbasis pada dua ideologi HAM yang bertolak belakang. Jika persepsi eksklusif berbasis pada ideologi HAM partikular-absolut, sementara inklusif-liberal berbasis pada ideologi HAM universal-absolut. Dari kenyataan demikian, penulis memberikan solusi untuk kembali menggunakan ideologi Pancasila dalam memandang fatwa MUI tentang aliran sesat berkaitan dengan kebebasan beragama. Hal demikian menjadi penting mengingat di dalamnya, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melihat demikian itu, konsep kebebasan beragama dapat dikonstruksikan dengan berbasis pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ideologi HAM-nya didasarkan pada model universal-relatif. Adapun dasar legitimasi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dalam memandang fatwa MUI tentang aliran sesat berkaitan dengan kebebasan beragama, yang dilindungi dan dijamin pemerintah adalah pemeluk agama atau penganut suatu keyakinan (aliran kepercayaan) dan agama serta keyakinan itu sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Aliran sesat termasuk bagian dari problem kebebasan beragama (sebagai bagian dari HAM) selama ia secara konstitusional dapat dikatakan demikian. Aliran kepercayaan atau keyakinan yang dianggap sesat dapat dikatakan melanggar hak kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM jika memang secara konstitusional dapat dikatakan demikian. Tafsir keagamaan memang tidak memiliki kebenaran yang bersifat mutlak karena ia merupakan produk manusia, akan tetapi tidak serta-merta kemudian seseorang dengan 1 Terkait persepsi intelektual muslim terhadap fatwa MUI ini lihat Rohidin, Mendebat Fatwa MUI; Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2013. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 189 bebas melakukan penafsiran dengan tanpa metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, bersifat legal opinion dan bisa menjadi referensi dalam menentukan kebijakan kasus aliran sesat, tetapi bukan merupakan satu-satunya referensi. Berkaitan dengan kasus persekusi, jika secara konstitusional pelakunya dapat dikatakan melanggar hukum, baik itu dari pihak aliran yang dianggap sesat maupun pelaku persekusi, maka keduanya bisa jadi dikatakan sebagai pemicu. Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan regulasi turunan yang dapat mengakomodasi jaminan perlindungan atas individu pemeluk agama atau penganut suatu keyakinan (aliran kepercayaan) beserta agama dan keyakinan (kepercayaan) itu sendiri dalam batas-batas tertentu yang selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah konsekuensi bagi pemerintah. Berikut gambaran sederhana dialektika dua persepsi kontradiktif beserta bentuk prismatikanya sebagai konstruksi baru konsep kebebasan beragama: Tabel 5.1 Dialektika Kondisi Existing Problem Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berkaitan dengan Persepsi intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Titik Perbedaan Kolektivisme Individualisme Bentuk Persepsi Eksklusif Inklusif-Liberal Basis Nilai Agama Humanisme Basis Ideologi Partikular-Absolut Universal-Absolut Dasar Legitimasi UU No. PNPS/1965 UU No. 12 Tahun 2005 190 Dr. Rohidin, M. Ag 1/ 1. Pandangan atas Fatwa MUI tentang Aliran Sesat berkaitan dengan Kebebasan Beragama 1. Pemerintah harus melindungi pemeluk agama dan pengikut suatu keyakinan (aliran kepercayaan), bukan agama dan keyakinan itu sendiri. 1. Aliran sesat termasuk bagian dari problem kebebasan beragama (sebagai bagian dari HAM). 1. Semua aliran atau keyakinan adalah bagian dari hak kebebasan beragama yang merupakan bagian dari HAM. Pemerintah harus melindungi agama dan pemeluknya. 2. Aliran sesat bukan termasuk bagian dari problem kebebasan beragama (sebagai bagian dari HAM). 3. Suatu keyakinan atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat bukan bagian dari hak kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM, justru ia telah melanggar HAM. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 191 4. Kebenaran tafsir keagamaan dapat ditentukan secara kolektif (mainstream). 5. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, memang bersifat legal opinion tetapi karena kolektivitasnya maka kebenarannya bersifat mutlak. 6. Berkaitan dengan kasus persekusi, aliran sesatlah yang menjadi pemicunya. Konsekuensinya 192 Pemerintah harus tegas untuk membubarkan dan melarang aliran yang dianggap sesat oleh MUI. Dr. Rohidin, M. Ag 1. Tafsir keagamaan tidak memiliki kebenaran mutlak, artinya ditentukan oleh keyakinan individu. 1. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, bersifat legal opinion. Karena itu, ia sejajar dengan bentuk tafsiran lain yang mungkin bertentangan. 1. Berkaitan dengan kasus persekusi, aliran sesat bukan sebagai pemicunya. Pemerintah harus menindak tegas para pelaku persekusi, dan wajib melindungi para penganut suatu keyakinan atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat oleh MUI. Tabel 5.2 Konstruksi Baru Konsep Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia Berkaitan dengan Persepsi Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Bentuk Persepsi Inklusif-Moderat Basis Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Pancasila) Basis Ideologi Universal-Relatif Dasar Legitimasi UUD 1945 1. Pola perlindungan dan penjaminannya ditekankan pada pemeluk agama atau penganut suatu keyakinan (aliran kepercayaan) beserta agama dan keyakinan (kepercayaan) itu sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Pandangan atas Fatwa MUI tentang Aliran Sesat berkaitan dengan Kebebasan Beragama 2. Aliran sesat termasuk bagian dari problem kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM, selama ia secara konstitusional dapat dikatakan demikian. 3. Suatu keyakinan atau aliran kepercayaan yang dianggap sesat dapat dikatakan melanggar hak kebebasan beragama yang merupakan bagian dari HAM jika memang secara konstitusional dapat dikatakan demikian. 4. Tafsir keagamaan memang tidak memiliki kebenaran yang bersifat mutlak, akan tetapi tidak sertamerta kemudian seseorang dengan bebas melakukan penafsiran dengan tanpa metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 193 5. Fatwa MUI, sebagai contoh tafsir keagamaan, bersifat legal opinion dan bisa menjadi referensi dalam menentukan kebijakan kasus aliran sesat, tetapi bukan merupakan satusatunya referensi. 6. Berkaitan dengan kasus persekusi, jika secara konstitusional pelakunya dapat dikatakan melanggar hukum, baik itu dari pihak aliran yang dianggap sesat maupun pelaku persekusi, maka keduanya bisa jadi dikatakan sebagai pemicu. Konsekuensi Pembentukan regulasi turunan yang dapat mengakomodasi jaminan perlindungan atas individu pemeluk agama atau penganut suatu keyakinan (aliran kepercayaan) beserta agama dan keyakinan (kepercayaan) itu sendiri dalam batas-batas tertentu yang selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah konsekuensi bagi pemerintah. Hemat penulis, saat ini problematika kebebasan beragama di Indonesia dalam bingkai hukum terletak pada tiga aspek, yakni: substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada aspek substansi, terdapat beberapa produk regulasi yang kontradiktif, dan bahkan kontraproduktif dengan konstitusi yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa bentuk regulasi tersebut di antaranya adalah UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Pasal 1, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (1), UU No. 12 Tahun 2005 (ICCPR) Pasal 18 ayat (1), dan beberapa Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah. Sementara pada aspek struktur, kerapuhan aparatur penegak hukum kentara dalam mengawal jaminan 194 Dr. Rohidin, M. Ag kebebasan beragama. Kerapuhan ini berimplikasi pada bentuk tindakan aktif (by commission) dan pembiaran (by omission). Sehingga, aparatur pemerintah, yang sejatinya menjalankan amanah dan mengawal konstitusi berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru—dalam beberapa kasus—tampak bertolak belakang dengan (untuk tidak mengatakan menghianati amanah)—konstitusi. Melihat kerapuhan yang berkepanjangan tersebut, krisis kepercayaan pun akhirnya muncul dalam sebagian benak masyarakat. Implikasi yang muncul kemudian adalah timbulnya ragam intoleransi, dan bahkan persekusi. Pihak pelaku melegitimasi tindakannya pada bentuk regulasi yang sesuai, demikian juga para korban yang mencoba melakukan pembelaan dengan melegitimasikan pada bentuk regulasi lain yang selaras pula, dan tidak mau ketinggalan para pembela pelaku maupun korban, yang sama-sama melegitimasikan pembelaannya pada bentuk regulasi yang selaras. Artinya atomisme dalam pemahaman hukum muncul dari bentuk regulasi kontradiktif-kontraproduktif di atas, di samping minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya supremasi hukum. Inilah beberapa bentuk problem yang terdapat pada aspek budaya. Jika ketiga aspek tersebut berfungsi dan bergerak sebagaimana mestinya, niscaya problem kebebasan beragama akan dapat teratasi dengan baik. Melihat hal demikian itu, penulis memberikan blue print bahwa konsep kebebasan beragama di Indonesia dalam bingkai hukum mesti dikonstruksikan dengan tidak keluar dari empat kaidah penuntun, berupa (a) bertujuan dan menjamin integritas bangsa, (b) bersamaan dalam misi membangun demokrasi dan nomokrasi, (c) membangun keadilan sosial, dan (d) membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Bertolak dari hal tersebut, maka konsep kebebasan beragama dapat dikonstruksikan dengan pola jaminan perlindungan atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama serta keyakinan dan agama itu sendiri yang berbasis pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan pola semacam ini, tidak bisa dengan serta-merta seseorang memaksakan kehendak keyakinan atau keberagamaannya kepada orang lain, termasuk dalam hal penafsiran. Seseorang juga tidak bisa dengan sesuka hati menghinasuatu agama atau keyakinan, termasuk pula Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 195 ritus-ritus yang menyertainya. Selain itu, seseorang juga dilarang untuk mengganggu prosesi upacara suatu agama atau keyakinan, apalagi melakukan perusakan-perusakan terhadap tempat-tempat peribadatan keagamaan atau suatu keyakinan. Namun demikian, betapapun produk hukum dianggap mapan, kebebasan beragama tidak akan teraplikasikan jika sektor aparatur penegak hukum dan budaya masyarakatnya belum siap. Sebaliknya, betapapun produk hukum tidak dianggap mapan, tetapi jika budaya masyarakatnya sangat mapan, maka kebebasan beragama akan berjalan dengan sendirinya secara sempurna. Dengan kata lain, problem kebebasan beragama sesungguhnya dengan sendirinya akan teratasi jika civil society telah membumi dalam kehidupan masyarakat. Pilihan terhadap konsep kebebasan beragama berbasis pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengambil kasus persepsi intelektual Muslim terhadap fatwa MUI tentang aliran sesat berimplikasi pada beberapa aspek berkaitan konsep kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia. 1. Implikasi Paradigmatik Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa hingga saat ini kebebasan beragama dikonsepsikan oleh sebagian intelektual Muslim dengan basis yang kurang sesuai dengan Pancasila. Di satu sisi mereka mengkonsepsikan kebebasan beragama dengan berbasis pada HAM universalabsolut, yang cenderung antroposentris, sedang sisi yang lain mengkonsepsikannya dengan basis HAM partikularabsolut, yang cenderung theosentris. Implikasi yang muncul kemudian adalah persepsi yang bertolak belakang terkait kebebasan beragama. Sehubungan dengan itu, maka kebebasan beragama dikonsepsikan dengan menggunakan Pancasila sebagai basisnya. Pemilihan Pancasila sebagai basis konseptual menjadi relevan mengingat ia merupakan staatfundamentalnorm. Selain itu, Pancasila juga merupakan perwujudan dari ideologi HAM universal- 196 Dr. Rohidin, M. Ag relatif, yang cenderung theo-antroposentris. Dengan demikian, maka agama atau keyakinan beserta pemeluknya dapat dijamin dan dilindungi dengan baik. 2. Implikasi Teoretis Secara teoretis Pancasila merupakan perwujudan dari prismatika antara nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Jika nilai sosial paguyuban lebih menekankan pada kepentingan bersama, sementara nilai sosial patembayan lebih menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Sehubungan dengan itu, selama ini kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia dikonsepsikan dalam bingkai nilai sosial paguyuban dan patembayan. Jika nilai sosial paguyuban terwujud dalam kelompok eksklusif, sementara nilai sosial patembayan terwujud dalam kelompok liberal-inklusif. Kebebasan beragama oleh kelompok eksklusif dikonsepsikan dalam pengertian bebas untuk memilih dan mengekspresikan suatu agama atau keyakinan. Kebebasan untuk memilih memiliki pengertian adanya larangan atas warga negara yang tidak beragama atau berkeyakinan. Sementara kebebasan untuk mengekspresikan tidak bersifat mutlak, dalam arti bahwa ekspresi keberagamaan atau keyakinan seseorang tidak bisa melenceng dari mainstream. Artinya, agama atau keyakinan secara institusional mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga jika ada tafsir keagamaan atau keyakinan yang diaggap menyimpang, misalnya, negara diwajibkan untuk memproteksinya. Kelompok inklusif-liberal mengkonsepsikan kebebasan beragama dalam pengertian bebas untuk memeluk dan mengekspresikan suatu agama atau keyakinan, termasuk tidak memeluk agama atau menganut suatu keyakinan, dan bahkan penafsiran terhadap suatu agama atau keyakinan. Kebebasan di sini tidak bersifat mutlak, dalam arti dapat Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 197 dibatasi oleh undang-undang yang jelas dan komprehensif. Namun demikian, pembatasan ini hanya boleh dilakukan dalam ranah ketertiban sosial. Artinya, konsep tersebut dikonstruksikan dengan berlandaskan pada nilai-nilai humanistik, di mana perlindungan terhadap individu kemanusiaan lebih diutamakan daripada kolektivisme berbasis agama. Bertolak dari teori Riggs di atas, maka kebebasan beragama di Negara Hukum Indonesia dapat dikonsepsikan dalam pengertian jaminan perlindungan atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama serta keyakinan dan agama itu sendiri yang berbasis pada nilai kemanusiaan yang adil dan individu yang tidak beragama atau berkeyakinan. Sementara pengertian berekspresi adalah menjalankan agama atau keyakinannya, dan termasuk pula penafsirannya. Namun demikian, kebebasan di sini dapat dibatasi oleh undangundang yang jelas dan komprehensif dalam koridor perlindungan atas suatu agama atau keyakinan secara institusional yang berkaitan dengan ketertiban umum. Konsepsi tersebut merupakan perwujudan dari prismatika dua nilai di atas. Konsepsi tersebut menegaskan bahwa relasi antara negara dan agama di Indonesia bersifat simbiosis, keduanya bersifat timbal-balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan adanya negara maka agama akan dapat berkembang secara lebih baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Hal demikian tentu berbeda dengan bentuk relasi yang bersifat integralistik, yangmenganggap bahwa keduanya merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, demikian juga sama berbedanya dengan bentuk relasi yang bersifat sekularistik, yang memandang bahwa negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga 198 Dr. Rohidin, M. Ag keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Sehubungan dengan itu, maka Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi religious nation state. 3. Implikasi Praktis Problem kebebasan beragama tidak akan larut dari negeri ini jika produk regulasinya banyak yang bersifat kontradiktif-kontraproduktif. Tidak berhenti pada perbaikan bentuk regulasi, peningkatan penegakan hukum juga sangat urgen untuk segera dijalankan. Namun, keduanya tidak akan berjalan jika kesadaran masyarakatnya tidak mendukung. Artinya, ranah substansi, struktur, dan budaya hukum mesti sama-sama bergerak menuju perubahan untuk mencapai hak kebebasan beragama yang benar-benar terjamin. Dengan ditegakkannya hak kebebasan beragama dengan basis nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, niscaya praktik-praktik intolerance religious yang kerap mengganggu proses pembangunan akan dapat diminimalisir dengan baik. persepsi intelektual Muslim terhadap fatwa MUI tentang aliran sesat dan penegakan hukum tentang kebebasan beragama, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Fatwa MUI tentang aliran sesat berkedudukan sebagai legal opinion, yang berpotensi mengandung dissenting opinion. Intelektual Muslim, dan bahkan seluruh masyarakat, mesti mempersepsikannya dengan berlandaskan pada Pancasila, terutama sila kedua. Baik yang mengamini maupun yang menolaknya, masyarakat secara umum dilarang keras untuk mengawal dan menanggapinya secara berlebihan, apalagi dengan melakukan persekusi. Demikian juga dengan negara, tidak bisa serta-merta menjadikan Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 199 fatwa MUI sebagai referensi yang paling utama. Dalam mengeluarkan kebijakan terkait aliran sesat, kebijakan negara mesti didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 2. MUI berhak untuk menilai sesat dan tidaknya suatu aliran, akan tetapi dalam merumuskannya mesti menggunakan metodologi yang tepat dan akurat. Selain itu, sebelum fatwa tersebut disahkan, MUI disarankan untuk melakukan uji publik terkait dengan produk fatwanya di hadapan kelompok akademisi, tokoh-tokoh agama non-MUI, dan masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari mereka, sehingga pada akhirnya fatwa tersebut betul-betul memiliki otoritas yang sangat kuat. 3. Konsep kebebasan beragam merupakan bagian dari HAM, yang diilhami dari dua semangat berbeda berupa partikularisme dan universalisme. Pancasila, sebagai ideologi yang lahir dalam bingkai kebhinekaan, mengakomodasi dua semangat tersebut yang terkonstruksi dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian, pada kenyataannya terdapat beberapa produk regulasi turunan yang tidak konsisten dan koheren dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut sebagaimana tampak pada UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Pasal 1 dan UU No. 12 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1). Melihat demikian itu, maka disarankan agar regulasi turunan tentang kebebasan beragama berkaitan dengan aliran sesat beserta kebijakan-kebijakan yang menjadi turunannya segera ditinjau ulang dan direvisi untuk kembali ditarik pada semangat Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28 dan 29. 4. Mengingat betapa krusialnya problem keberagamaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disarankan untuk segera membentuk dan/atau mengesahkan regulasi komprehensif yang sejalan dengan semangat konstitusi. Konsep yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut: a. Hak Hak-hak keberagamaan seseorang dapat diformulasikan 200 Dr. Rohidin, M. Ag dalam bentuk hak untuk (1) berpikir dan berpendapat terkait persoalan agama atau keyakinan, (2) memeluk agama atau keyakinan, (3) mendapatkan jaminan atas kebebasan berpikir dan berpendapat terkait persoalan agama atau keyakinan, (4) mendapatkan jaminan atas kepemelukan seseorang terhadap agama atau keyakinan, (5) mendapatkan perlindungan atas keagamaan atau keyakinan seseorang, dan (6) mendapatkan perlindungan atas tempat-tempat peribadatan, termasuk ritus dan upacara-upacara keagamaan atau keyakinan, yang dimiliki. b. Kewajiban Kewajiban-kewajiban warga negara dalam hal keberagamaan dapat diformulasikan dalam bentuk kewajiban untuk (1) menghormati hak kebebasan berpikir dan berpendapat terkait persoalan agama atau keyakinan, (2) menghormati agama atau keyakinan orang lain, dan (3) menghormati keberadaan tempat-tempat peribadatan, termasuk ritus dan upacara-upacara agama atau keyakinan. c. Larangan Larangan-larangan dalam hal keberagamaan dapat diformulasikan dalam bentuk larangan untuk (1) menghina suatu agama atau keyakinan, termasuk hal-hal yang terkait di dalamnya, (2) menghasut seseorang untuk meniadakan keyakinan terhadap Tuhan, (3) melakukan persekusi terhadap suatu agama atau keyakinan, baik agama atau keyakinan, dan (5) merusak tempat-tempat peribadatan suatu keagamaan atau keyakinan. [] Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 201 202 Dr. Rohidin, M. Ag DAFTAR PUSTAKA A. Buku Al Marsudi, Subandi, Pancasila dan UUD ’45 dalam Paradigma Reformasi, Ali, As’ad Said, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa, Jakarta: LP3ES, 2009. Alim, Muhammad, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, Yogyakarta: UII Press, 2001 Civil Society di NegaraNegara Arab” dalam Bernard Lewis, et. al., Islam, Liberalisme, Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, Jakarta: Paramadina, 2002. Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010. Arief, Barda Nawawi, Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010. Asplund, Knut D. (dkk.) (ed.), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010. Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006 ___________, UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional dalam Pluralisme Indonesia dalam, Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi: Tinjauan Konstitusional Praktik Kebebasan Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 203 Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: Publikasi SETARA Institute, 2009. Baderin, Mashood A., Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003. Bakry, Noor MS, Pancasila: YuridisKenegaraan, Yogyakarta: Liberty, 1985. ___________, Orientasi Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Liberti, 2001. Basah, Sjahran, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1985. Budiharja, Miriam (ed.), Masalah Kenegaraan, Jakarta: Gramedia, 1980. Bungin, Burhan, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Kencana, 2007. Campbell, Henry (ed.), Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul: West Publishing Co, 1990. Dendy Sugono (red.), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdiknas, 2008. HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Hukum (Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. El Muhtaj, Majda, Dimensi-dimensi HAM:Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Press, 2008. ___________, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana, 2007. 204 Dr. Rohidin, M. Ag Gellner, Ernest, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, Bandung: Mizan, 1995. Gonggong, Anhar dan Abdul Qahhar Mudzakar, Dari Patriot Hingga Pemberontak, Jakarta: Gramedia, 1992. Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2001. Handoyo, B. Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003. Hartono, C.F.G. Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991. Hasani, Ismail (ed.), Siding and Acting Intolerantly: Intolerance by Society and Restriction by the State in Freedom of Religion/ Belief in Indonesia, Jakarta: SETARA Institute, 2009. Hefner, Robert, (ed.), History and Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal, New Brunswiek: Transaction Press, 1998. Hewitt, Martin, Welfare, Ideology, and Need: Developing Perspectives on the Welfare State, Harvester Wheatsheaf, Maryland, 1992. Hiariej, Eddy O.S, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009. Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over, Melintasi Batas Agama, Jakarta: Gramedia, 1998., Hikam, Muhammad A.S., Islam: Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 205 Hoogvelt, Ankie M., Sosiologi Masyarakat sedang Berkembang, Jakarta: Rajawali Press, 1985. Howard, Rhoda E., HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, 2000. Howards, G.G. dan Rummers, Law It’s Nature and Limits, New Jeresey Prestic Hall, 1999. Husaini, Adian, Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005. Iskandar, Pranoto, Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual, Cianjur: IMR Press, 2010. Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa, Yogyakarta: Paradigma, 2002. Kholiludin, Tedi, Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009. Kusuma, RM. AB. (penghimpun), Lahirnya UUD 1945, Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2004, Kusumatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1986 Madjid, Nurcholish, (dkk.), Passing Over: Melintas Batas Agama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. Mahfud MD, Moh., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999. ___________, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: ___________, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2006. Manan, Bagir, Kedaulatan Rakyat: Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996. Miller, David (ed.), Liberty, Oxford: Oxford University Press, 1991. 206 Dr. Rohidin, M. Ag MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: MUI, 2010. Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat, Aditama, 2005. Naning, Ramdlon, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983. Pound, Roscoe, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Bhratara, 1989. Pranarka, A.M.W.,Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, Jakarta: CSIS, 1985. Prisgunanto, Ilham, Praktik Ilmu Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta: Teraju, 2004 Pudjiarto, Harum, Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999. Rohidin, Mendebat Fatwa MUI; Silang Perspektif Intelektual Muslim terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013. Rosyada, Dede (dkk.), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2003 Saleh, Roeslan, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Jakarta: Bina Aksara, 1979. Smith, Rhona K. M. (dkk.), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010. Sofyan, Ahmad A. & M. Roychan Madjid, Negara & Islam, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003. Suaedy, Ahmad (dkk.), Beragama, Berkeyakinan dan Berkonstitusi: Tinjauan Konstitusional Praktik Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia Jakarta: Publikasi Setara Institute, 2009. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 207 ___________, (dkk.), Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta: The WAHID Institute, 2009. ___________, Perpektif Pesantren: Islam Baru Islam Demokrasi, Jakarta: The Wahid Institute, 2009. Sudiarja, A. (ed.), Karya Lengkap Driyakara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dengan Perjuangan Bangsanya, Yogyakarta: Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, dan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia, 2006. Sumantri, Sri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989. Supriatma, A. Made Tony (ed.), 1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia, Jakarta: YLBHI, 1997. Suseno, Franz Magnis, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Jakarta: Kanisius, 1992. ___________, Rechtsstaat, Bukan Machsstaat, dalam Mencari Makna Kebangsaan, Yogyakarta: Kanisius, 1998. Suyitno (ed), Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi, Yogyakarta: Gama Media, 2006. Taher, Elza Peldi (ed.), Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Efendi, ICRP, Jakarta, 2009. Ubaidillah, A. (dkk.), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000. Wahid, Abdurrahman, “Agama dan Demokrasi”, Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 1995. ___________, Membangun Demokrasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999. Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. 208 Dr. Rohidin, M. Ag Weber, Max dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Jakarta: Sinar Harapan, 1988. B. Laporan Penelitian, Jurnal, Makalah, dan Surat Kabar Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan”, Makalah dalam Annual Converence on Islamic Studies (ACIS) Ke-10 di Banjarmasin, 1-4 November 2010. Asshiddiqie, Jimly, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, Makalah, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Astika, Hani, “Hubungan Agama dan Negara dalam Islam”, dalam Jurnal al-Manahij, vol. 2, No. 1, Januari-Juni, 2008. CRCS, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2008. Donnelly, Jack, “Human Right and Human Dignity: An Anallytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Right”, The American Political Science Review, Vol. 76, No. 2., dalam http://links.jstor.org, (Diakses pada tanggal 20 Desember 2010). Gunarto, “Pemikiran Munawwir Syadzali tentang Islam dan Negara dalam Perbandingan Penafsirannya antara T.B. Simatupang dan Eka Darmaputra dari Perspektif Kehidupan Beragama dan Pancasila”, dalam Jurnal Teologi Stulos, vol. 6, No. 1, April 2007. Macklem, Timothy, ” Faith as a Secular Value”, February 2000. , Mahfud MD, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi”, Makalah, disampaikandalam Konverensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, diselenggarakan oleh ICRP pada tanggal 5 Oktober 2009. ___________, “Mimpi Demokrasi dari Bung Karno”, Jawa Pos, 27September 2006. Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 209 ___________, “Undang-undang Politik, Keormasan dan Instrumentasi di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, UII Press No. 10, vol. 5. 1998. Pujirahayu, Esmi Warassih, “Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum”; dalam Masalah-Masalah Hukum No. 2 Tahun 1995. Raharjo, Dawam, “Masyarakat Madani: Demokrasi, Kemajuan dan Keadilan.” Makalah dalam seminar “Strategi Penguatan Civil Society di Indonesia,” 23-25 Oktober 1998 di Bogor. Rahardjo, Satjipto, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, dalam Kompas, 2003, hlm. 10. Rehman, Javaid, “Accommodating Religious Identities in an Islamic State: International Law, Freedom of Religion and the Rights of Religious Minorities” dalam International Journal on 7: 2000. Februari, 15-19, 1965, The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age, International Commission of Jurist, 1965. Sutiyoso, Bambang, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia”, dalam UNISIA, Yogyakarta, UII Press No. 10, vol. 5. 1998. Titaley, John, “Pluralisme Agama dan Nasionalisme, Peranan Agama dalamPembentukan Dasar Kehidupan Berbangsa di 1ndonesia,” Makalah, dalam SeminarAgama-agama X11, Bogor/Tugu, September 1992. C. Perundang-Undangan dan Peraturan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11/MUNAS VII/ MUI/15/2005 Tentang Ahmadiyah. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) MK, Risalah Sidang Pengujian UU No. 1/PNPS/1965, Jakarta: MK, 2010. 210 Dr. Rohidin, M. Ag Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) The Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief (EAIDRB). The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 [Amandemen Kedua] Undang Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Undang Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian. United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (Online) dalam http://www.un.org/en/documents/udhr/, D. Internet http://en.wikipedia.org/wiki/UDHR, (Diakses pada tanggal 23 Desember 2010). http://surabaya.detik.com/read/2011/02/28/174700/1581502/46 6/papan-nama-pusat-kegiatan-ahmadiyah-jatim-dicopot, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). http://surabaya.detik.com/read/2011/02/28/205935/1581618/466/ ahmadiyah-akan-gugat-keputusan-gubernur-jatim. (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). http://www.komnasham.go.id/2010-10-03-02-09-01/66-hotnews/647-komnas-ham-sk-larang-aktivitas-ahmadiyahharus-dikaji-ulang-dengan-uu, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). http://www.seruu.com/index.php/2011030242377/kota/regional/ maraknya-perda-anti-ahmadiyah-picu-aksi-massa-dikuningan-42377/menu-id-759.html;, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 211 http://www.seruu.com/index.php/2011030242453/utama/ nasional/penurunan-plang-ahmadiyah-uu-kalah-denganperda-42453/menu-id-691.html, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2011). http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#art18 (Diakses pada tanggal 27 Desember 2010). Kemenkumham, Peraturan Daerah yang Dipermasalahkan, dalam http://www.kemenkumham.go.id, (Diakses pada tanggal 23 Februari 2011). Littman, David. “Universal Human Rights and Human Rights in Islam”, Midstream, February/March 1999, dalam, http://web. archive.org/web/20060501234759/http://mypage.bluewin. ch/ameland/Islam.html, (Diakses pada tanggal 11 Desember 2010). Newman, Jay, On Religious Freedom, (E-Book), University of Ottawa Press, dalam http://books.google.co.uk/books/id=Z ig=v_ONZVSgZrVp1jV39xYlnKXaNJk (Diakses pada tanggal 12 Desember 2010). E. Narasumber Wawancara Amirsyah, anggota MUI pada tanggal 1 Februari 2010. Arif Hidayat pada tanggal 17 Oktober 2011 di Semarang. Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham UII), pada tanggal 20 Agustus 2011. Hanick, Aktivis ICRP, pada tanggal 2 Pebruari 2010 di Jakarta. Jainal Abidin, Pengurus MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis, 18 Agustus 2011. Kaelan, Guru Besar UGM, di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2011. Munir Mulkhan pada tanggal 4 Mei 2010. Wawan pada tanggal 10 Agustus 2010 di Sleman Yogyakarta. 212 Dr. Rohidin, M. Ag INDEKS A B Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 71 adil 7, 12, 40, 63, 65, 66, 73, 86, 87, 90, 92, 94, 97, 138, 142, 145, 166, 173, 176, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 199, 200 agama 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 60, 66, 71, 72, 81, 85, 86, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 157, 160, 163, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 210 agama resmi 40, 126, 127, 151 Ahmadiyah 85, 95, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 142, 143, 149, 158, 159, 160, 161, 162, 185, 210 aliran sesat keagamaan 166, 187, 188 Aquinas 7, 9, 10 Bakorpakem 108, 110, 126 Barat 4, 7, 17, 24, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 115, 118, 121, 122, 124, 125, 137, 155, 159 beradab 65, 66, 73, 83, 86, 90, 92, 97, 138, 166, 173, 176, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 199, 200 BPUPKI 20, 21, 22, 23, 24, 134 Budaya 3, 82, 89, 159, 162, 204, 206 budaya Barat 24, 82, 84 budaya Timur 82 C civil society 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 162, 163, 164, 165, 179, 196 common law 51, 60 D Deklarasi Kairo 17 demokrasi 5, 20, 58, 70, 71, 72, 73, 79, 98, 136, 137, 140, 145, 163, 164, 165, 174, 195 demokrasi terpimpin 145 Dewan HAM PBB 41 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 213 200 DUHAM 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 28, 47, 86, 89, 181 E eksklusif 85, 86, 187, 189, 197 Eropa Kontinental 50, 56 F fatwa MUI 85, 86, 90, 95, 112, 130, 166, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 196, 199, 200 FPI 85, 116, 119, 121, 122, 123, 125 FUI 122, 123, 125 G grondwet 21, 23 H hak 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 75, 77, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 129, 133, 140, 148, 152, 153, 155, 158, 160, 170, 172, 173, 175, 176, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 195, 198, 199, 200, 201 hak beragama 12, 13, 65, 94 HAM 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 67, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 100, 102, 103, 114, 129, 130, 141, 145, 152, 153, 154, 157, 214 Dr. Rohidin, M. Ag 161, 169, 170, 171, 172, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 196, 200, 204, 206, 208 hukum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 36, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 71, 75, 77, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 117, 126, 129, 130, 131, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 194, 195, 196, 199 hukum Islam 16, 17 Hukum Islam 16, 204 Hukum Pancasila 49, 55, 56, 57, 58, 61 human 2, 10, 25, 47, 48, 88 humanisme 152 I ICCPR 15, 16, 41, 45, 47, 92, 102, 152, 181, 182, 194, 211 ideologi 1, 70, 72, 81, 82, 86, 91, 92, 95, 97, 134, 135, 166, 186, 189, 196, 200 ideologi Pancasila 81, 92, 189 Immanuel Kant 50 imperialis 83 imperialisme 21, 88 individu 4, 6, 8, 10, 11, 22, 31, 37, 45, 49, 52, 53, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 138, 139, 170, 173, 183, 190, 192, 194, 197, 198 individualisme 5, 21, 22, 23, 56, 60, 83, 88, 166 Indonesia 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 90, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 122, 123, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210 integralistik 22, 136, 198 intoleransi 46, 84, 97, 99, 101, 133, 185, 195 J JAI 117, 118, 119, 120, 149, 159, 160 jaksa 157, 187 jaminan 2, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 65, 66, 77, 80, 99, 101, 102, 106, 129, 131, 139, 142, 153, 154, 158, 173, 176, 178, 186, 190, 194, 195, 198, 201 jaminan kebebasan 34, 36, 102, 142, 158, 186, 194 jaminan penuh 38, 131 jaminan seadanya 131 Jimly Asshiddiqie 1, 18, 50, 51, 54 K kafir 40, 85, 130 kapitalis 52, 53, 84 kapitalisme 21 keadilan 9, 22, 56, 60, 65, 66, 72, 73, 82, 87, 92, 95, 98, 134, 135, 147, 161, 174, 183, 195 keadilan sosial 22, 56, 82, 92, 98, 134, 174 kebebasan beragama 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 61, 64, 65, 66, 81, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 126, 127, 130, 132, 133, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 kebijakan publik 140, 187 kejaksaan 142 kemanusiaan 1, 7, 11, 17, 25, 39, 61, 62, 65, 66, 75, 86, 87, 90, 92, 97, 133, 134, 135, 138, 164, 166, 173, 176, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 199, 200 kemanusiaan yang adil dan beradab 65, 66, 86, 90, 92, 97, 138, 166, 173, 176, 187, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 199, 200 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 154 kepolisian 107, 120, 142 ketertiban sosial 175, 198 Kim Sunhyuk 68 kolektif 12, 36, 63, 84, 170, 192 kolektivisme 60, 166, 198 Komnas HAM 114, 161 Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 konflik 27, 69, 130, 163, 179 Konstitusi 1, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 50, 54, 58, 102, 141, 145, 148, 149, 152, 162, 203, 204, 206, 208, 209 Konstitusi RIS 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 215 Kovenan 15, 34, 36, 38, 89, 102, 151, 152, 153, 158, 182 Kristen 7, 8, 16, 37, 132 KWI 130, 146 L legal opinion 95, 130, 170, 172, 188, 190, 192, 194, 199 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 75 liberal 32, 52, 53, 72, 84, 89, 91, 187, 188, 189, 197 liberalisme 21, 22 M Mahfud MD 20, 24, 25, 31, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 149, 166, 206, 209 Mahkamah Konstitusi (MK) 148 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 35, 181 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 184 Matakin 130, 146 menteri 121, 125 Moh. Hatta 21, 22, 23 Montesqiueu 11 Muhammadiyah 58, 110, 141 Muhammad saw 90 N Nabi 90, 120, 123, 128, 144 negara 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 124, 126, 216 Dr. Rohidin, M. Ag 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 197, 198, 199, 200, 201 Negara Hukum 18, 19, 34, 43, 49, 55, 56, 57, 58, 61, 82, 84, 97, 166, 167, 168, 171, 176, 177, 185, 186, 187, 190, 193, 196, 197, 198, 206 nilai 1, 6, 7, 12, 46, 47, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 96, 134, 135, 138, 144, 152, 159, 160, 162, 166, 167, 168, 173, 175, 176, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 O otoriter 42, 71, 130, 145, 165 P Pancasila 1, 19, 33, 40, 49, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 81, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 116, 126, 130, 133, 134, 135, 138, 142, 145, 152, 153, 166, 167, 171, 173, 174, 177, 178, 187, 189, 193, 196, 197, 199, 200, 203, 204, 206, 207, 209 paradigma 20, 42, 84, 135, 136, 137, 138, 174 partai politik 4, 75, 141 partikular 48, 81, 86, 90, 91, 96, 146, 166, 186, 189, 196 partikular-absolut 81, 86, 166, 189, 196 partikularisme 1, 82, 84, 86, 88, 92, 200 PBB 12, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 41, 84, 152 pemerintah 4, 8, 10, 19, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 65, 66, 74, 76, 77, 80, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 120, 126, 127, 129, 130, 132, 140, 142, 148, 152, 153, 160, 161, 173, 178, 184, 186, 187, 189, 190, 194, 195 pendidikan 12, 15, 35, 39, 40, 65, 71, 79, 145, 153, 155, 156, 159 penegakan hukum 139, 157, 178, 199 perda 154, 155, 156, 157, 161, 162, 211, 212 perda syariah 154, 155 pers 23, 75, 76, 77 persekusi 96, 170, 171, 172, 186, 190, 192, 194, 195, 199, 201 persepsi 85, 86, 89, 90, 95, 103, 132, 144, 168, 185, 186, 187, 189, 190, 196, 199 pesantren 114 PGI 130, 146 PHDI 146 pidana 99, 144, 146, 147 pluralisme 67, 68, 74, 146, 164 polisi 100, 107, 110, 111, 157, 187 Presiden 32, 33, 98, 99, 123, 126, 132, 141, 145, 149, 183, 209, 211 R rechtsstaat 49, 50, 51, 52, 54, 55 rekonstruksi 133, 166 Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 Romawi 6, 7, 8, 9 ruang publik 68, 69, 70, 71, 138, 163 rule of law 18, 49, 50, 51, 53, 55, 60, 72 S Salamullah 185 sekularistik 137, 198 simbiosis 136, 198 simbiotik 136, 138 Siti Musdah Mulia 37, 98, 127 SKB 117, 121, 125, 149, 150, 158, 161 Soeharto 98, 99, 126, 132 Soekarno 20, 21, 22, 32, 33, 55, 98, 145 Soepomo 20, 21, 22, 31, 55 staat 22 Stoik 5, 6, 10 struktur hukum 139, 157, 187 substansi hukum 139, 143, 187 Sunnī 85 supremasi hukum 75, 77, 178 Susilo Bambang Yudhoyono 123 T tertib 62, 145 Timur 22, 24, 29, 30, 67, 82, 85, 92, 105, 110, 114, 124, 151, 156, 157, 161, 185 toleransi 73, 90, 133, 153, 165, 174, 175, 195 U UDHR 17, 91, 211 Universal 13, 16, 86, 89, 168, 171, 181, 190, 193, 211, 212 universal-absolut 84, 167, 182, 186, 189, 196 universalisme 1, 7, 82, 83, 86, 88, 90, 96, 200 universal-relatif 189, 196 UUD 1945 18, 19, 20, 21, 24, 25, Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 217 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 53, 55, 56, 101, 138, 140, 142, 154, 162, 171, 181, 182, 183, 189, 193, 200, 203, 204, 206, 207, 208 UUDS 1950 19, 29, 30, 31, 32, 33 W Walubi 130, 146 warga negara 3, 5, 7, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 46, 51, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 91, 93, 99, 100, 101, 131, 133, 137, 138, 139, 148, 155, 158, 164, 175, 181, 182, 197, 201 218 Dr. Rohidin, M. Ag Y Yamin 21, 23, 55 Yunani 5, 6 TENTANG PENULIS Rohidin kelahiran Subang Jawa Barat, 06 Maret 1967, anak dari pasangan H. Syafei dan Hj. Sawinah adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Masa kecil dilalui di kampung halamannya, tepi Pantai Pondok Bali, Pamanukan, Subang, dengan menimba pendidikan Sekolah Dasar hingga lulus pada 1980. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Persatuan Islam Benda Tasikmalaya, selesai 1986. Pada 1991, Rohidin menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Studi Strata 2 (S2) ditempuh di Program Kerjasama UI-IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selesai 1997. Pada 2007 ia melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selesai pada 19 Maret 2013. Alumnus Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga ini telah menulis beberapa artikel di Jurnal seperti “Pemikiran Hukum Islam “White Crime Collar dalam Perspektif Islam” (Jurnal Hukum FH UII) dan “Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat terhadap Otoritas Fatwa MUI” (Jurnal Hukum FH UII), “Fatwa Sesat MUI terhadap Aliran Keagamaan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM” (Jurnal Hukum FH Unnes Semarang). Konstruksi Baru Kebebasan Beragama 219 Di antara beberapa penelitian yang pernah dilakukannya adalah: “Qiyas sebagai Metode Penemuan Hukum Islam” (Penelitian di Fakultas Hukum UII), “Internalisasi Beberapa Ketentuan Hukum Waris Adat ke dalam Kompilasi Hukum Islam” (penelitian individual, Penelitian di Lembaga Penelitian UII), “Pengaruh Lokal terhadap Kompilasi Hukum Islam” (Penelitian Individu, Penelitian di Lembaga Penelitian UII), “Sebab-sebab Perceraian di Yogyakarta” (Penelitian Lembaga Penelitian UII), “Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Penyandang Cacat ke dalam Mainstream Masyarakat” (Penelitian Lembaga Penelitian UII), “Kawin Siri di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” (Penelitian di Fakultas Hukum), “Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Paradigma MUI dalam Mengeluarkan Fatwa Sesat dan Kaitannya dengan Prinsip-Prinsip HAM”, (Penelitian di Lembaga Penelitian UII), “Persepsi Masyarakat terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan” (Penelitian DP2M Dikti), dan “Corak Berpikir Keagamaan dan Toleransi: Studi Kasus Mahasiswa Aktivis Islam di DIY” (Penelitian di DP2M Dikti). [] 220 Dr. Rohidin, M. Ag