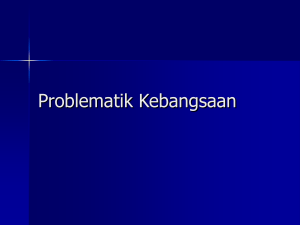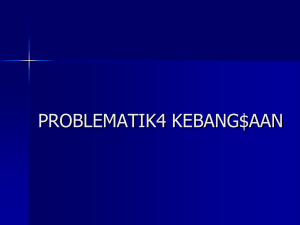s_sej_053657_BAB II
advertisement

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bagian ini merupakan hasil tinjauan pustaka dan telaah berbagai referensi yang berhubungan dengan perjalanan historis tentang hubungan antara Islam dengan politik negara. Kajian kepustakaan berguna sebagai landasan dalam mengambil posisi terhadap objek kajian. Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan bab ini, peneliti membagi menjadi dua bagian. Pertama, kajian tentang hubungan antara Islam dengan politik negara dalam konteks global. Kedua, kajian tentang hubungan antara Islam dengan politik negara dalam konteks keindonesiaan. A. Kajian Tentang Hubungan Antara Islam Dengan Politik Negara dalam Konteks Global Sepanjang sejarah peradaban manusia, termasuk dalam sejarah perkembangan Islam, agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh tehadap kehidupan umat manusia. Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula tidak jarang demi negara, seseorang tidak keberatan membela jiwa dan raganya. Konsep ‘syahid’ dalam ajaran Islam dan konsep ‘pahlawan’ yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia. 14 Berkaitan dengan perbedaan dua institusi di atas; agama dan negara, Kuntowijoyo menyatakan: Agama dan negara adalah dua satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (basyiran wa nadzira), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (coercion). Agama punya khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara punya birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama (collective conscience), negara mempunyai pengaruh sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar (Kuntowijoyo, 1997: 191-192). Sementara itu, Hasan al Bana, pendiri dan tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin (Mesir) memandang bahwa persoalan kenegaraan merupakan bagian integral dari Islam. Ia mengungkapkan: Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan da’wah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia juga aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih (Ridha. 2004: 49-50). Terkait dengan persoalan hubungan agama dan negara, Abdul Azis Thaba menggolongkannya ke dalam beberapa jenis (Thaba: 240-304). Pertama, hubungan yang cenderung didasarkan atas rivalitas dan antagonistik di antara keduanya, di mana masing-masing berupaya untuk saling menghancurkan. Turki, pada masa tumbangnya imperium Utsmani, 1924, menggambarkan jenis hubungan demikian. Demikian pula apa yang terjadi pada dekade 1980-an, di mana negara cenderung menafikan peran agama (Islam) atau setidaknya menjadikan agama (Islam) sebagai terpinggirkan, sehingga representasi hubungan 15 antara agama dan negara cenderung bersifat antagonistik dan didasarkan atas rivalitas. Kedua, hubungan yang saling mendukung antara agama dan negara. Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai hubungan simbiotik (Wahid, 1996: 34). Sebagai contoh, model hubungan semacam ini terjadi pada Kerajaan Saudi Arabia ketika pertama kali didirikan. Kolaborasi antara Raja Saud yang mendirikan negara Arab Saudi dengan Abdul Wahhab yang merintis ajaran wahhabiyah dapat dikelompokan ke dalam jenis hubungan simbiotis ini. Raja Saud, pendiri Kerajaan Saudi Arabia, di satu pihak, bekerja sama dengan Abdul Wahhab, yang membawa paham baru yang kemudian dikenal sebagai sekte wahhabi. Dalam konteks semacam di atas, Kuntowijoyo melukiskan bagaimana agama berfungsi sebagai legitimasi kepada negara, sebagai berikut: Agama menunjang politik dengan memberikan legitimasi kepada negara, partai dan perorangan. Legitimasi kepada negara sudah lama dilakukan oleh Islam. Dalam babad diceritakan bahwa walisanga adalah penasihat raja-raja, ketika raja dan kerajaan tidak dapat dapat dipisahkan. Raja-raja Mataram adalah khalifah (wakil Tuhan, kinarya wakil Hyang Agung) dan panatagama (penata agama). Kiranya hal yang sama terjadi sekarang. Legitimasi itu ada pada ideologi Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekalipun tidak jelas benar, tapi umat Islam dapat mengartikanya sebagai tauhid. Juga pelarangan terhadap komunisme dan Islam saling bermusuhan. Departemen agama, tindakan terhadap ajaran Islam yang menyimpang, penyelenggaraan haji yang diurus Negara, MTQ, MUI, Bank Muamalat dan seterusnya tekad negara untuk menjadi panatagama. “Upah” yang diharapkan adalah bahwa negara akan mendapat legitimasi (Kuntowijoyo, 1997: 195-196). Dalam konteks perkembangan politik Indonesia kontemporer, pada dekade 1990-an, hubungan antara agama dengan negara memperlihatkan 16 kecenderungan simbiotik ini. Dengan menggunakan perspektif Kuntowijoyo, agama memberikan legitimasi kepada (penguasa) negara dan sebaliknya negara memberikan perlindungan kepada agama (Islam). Setidaknya agama tertentu dan dari sekte tertentu pula. Bagaimana sebagian umat memberikan dukungan kepada penguasa saat itu dan sebaliknya kelompok tersebut mendapatkan perlindungan dari penguasa yang ada dapat dipahami dari perspektif hubungan yang saling mendukung ini. Pola dan bentuk hubungan negara dan agama, telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari nama yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW bagi kita kota hijrahnya itu menunjukan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah negara. Negara Madinah pimpinan Nabi itu adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. 1. Negara Madinah Hijrah, dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW adalah sebuah metamorphosis dari “gerakan” menjadi “negara”. Tiga belas tahun sebelumnya, Rasulullah Saw. melakukan penetrasi sosial yang sangat sistematis; di mana Islam menjadi jalan hidup individu, di mana Islam ‘memanusia’, dan manusia kemudian ‘memasyarakat”. Sekarang, melalui hijrah, masyarakat itu bergerak linear menuju 17 negara. Melalui hijrah gerakan itu “menegara” dan Madinah adalah wilayahnya (Matta, 2006: 2). Jika individu membutuhkan aqidah, maka negara membutuhkan perangkat sistem. Begitulah setelah komunitas Muslim menegara, dan mereka memilih Madinah sebagai wilayahnya, Allah SWT menurunkan perangkat sistem yang mereka butuhkan; maka turunlah ayat-ayat hukum dan berbagai kode etik sosial, ekonomi, politik dan keamanan lainnya. Lengkaplah sudah susunan kandungan sebuah negara: manusia, tanah, dan sistem. Apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW sebenarnya relatif mirip dengan semua yang dilakukan para pemimpin politik yang baru mendirikan negara. Ridha (2003: 59-60) memaparkan: pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol perangkat utamanya. Kedua, menciptakan kohesifitas sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas darah yang berbeda tapi menyatu sebagai komunitas agama, antara sebagian komunitas “Quraisy” dan “Yatsrib” menjadi komunitas “Muhajirin” dan “Anshar”. Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat pluralistik yang mendiami wilayah yang sama, melalui piagam Madinah. Keempat, merancang sistem pertahanan negara melalui konsep Jihad fi Sabilillah. Lima tahun pertama setelah hijrah dipenuhi oleh kerja keras Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup negara Madinah. Dalam kurun waktu itu, Rasulullah SAW ttelah melakukan lebih dari 40 kali peperangan dalam berbagai skala. 18 Perang Khandaq merupakan peperangan terbesar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Setelah itu, tidak ada lagi perang yang terjadi di sekitar Madinah, karena semua peperangan sudah bersifat ekspansif. Negara Madinah membuktikan kekuatan dan kemandiriannya, eksistensinya dan kelangsungannya. Di sini kaum Muslimin telah membuktikan kekuatannya, setelah sebelumnya kaum Muslimin membuktikan kebenarannya. Pada dasarnya, Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan negara Yatsrib atau negara Madinah, sebab bukan kedaulatan wilayah yang menjadi tujuan utama gerakan Nabi. Negara yang hendak dibangun Islam adalah negara yang memberi ruang pada kedaulatan aqidah (ideologi) dan fikrah (paradigma). Ketika beliau hijrah meninggalkan Makkah bukan bermaksud untuk menegakkan kekuasaan Madinah. Banyak ahli sejarah yang menamakan negara yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW sebagai Negara Madinah hanya karena pusat pemerintahannya di Madinah. Negara Madinah akhirnya disamakan dengan city state (Negara kota) seperti Athena dan Sparta di masa purba (Thohari, www.Hidayatullah.com, 18 Februari 2009). Pada dasarnya, menyangkut perihal hubungan antara negara dan agama atau keberadaan kedua institusi tersebut, maka ‘Negara Madinah’ merupakan prototype bagi terciptanya hubungan ideal dan harmonis antara negara di satu pihak dan agama di pihak lain. Negara Madinah adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Hanya saja, perkembangan zaman dengan segala macam aspeknya yang semakin kompleks menjadikan cara pandang terhadap ‘Negara Madinah’ menjadi berbeda satu sama lain. Dengan kata 19 lain, perbedaan tafsir terhadap pesan-pesan agama, dalam hal ini menyangkut kehidupan bukan keagamaan, menjadi faktor cara pandang yang berbeda pula dalam melihat ‘Negara Madinah.’ Menurut analisis Prof. Dhiauddin Rais (www.isnet.org, 18 Februari 2009), sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw. dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah, jika dilihat dari segi praktis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Di sisi lain, Ashgar Ali Engineer, seseorang pemikir muslim kenamaan kelahiran India yang sedikit banyak menjadi rujukan para penganut mazhab substantifistik Indonesia, menggambarkan kondisi masyarakat Madinah sebagai berikut: The Medeinese Arabs had not yet entered into the “civilized society” and belonged to the “savage stage” wherein the fruits of their industry were not appropriated by their superiors. So as a repressive state apparatus was not need to ensure collection of rent taxes. What, in fact, neccessated a supra-tribal authority like the one established by the Prophet was the inter-tribal war which resulted in meaningless blood-shed without any let or hindrance. And hence the Prophet, at the most, could claim the position of arbitrer and not of an unchallenged ruler., to begin with. It was only much later that he acquired a unique position. (Penduduk Arab Madinah belum masuk pada tahap “masyarakat beradab” dan masih berada dalam “tahap barbar” di mana hasilhasil produksi mereka tidak dirampok oleh para superior mereka. Oleh karena itu, aparat negara yang represif tidaklah diperlukan untuk melakukan pemungutan pajak. Sebenarnya, sesuatu yang memerlukan otoritas yang menguasai suku-suku sebagaimana diciptakan Nabi Muhammad adalah perang antar suku yang berakibat pada timbulnya pertumpahan darah yang tidak bermakna dengan tanpa adanya penghalang atau penghambat. Dalam pada itu, Nabi Muhammad, paling banter, hanya dapat mengklaim sebagai penengah, bukan seorang penguasa/pemimpin yang tidak tertandingi, untuk pertama kalinya demikian. Bahwasannya Nabi 20 menduduki posisi unik merupakan perkembangan lain di kemudian hari) (Sofyan dan Madjid: 2003: 22). Konsekuensinya, dikaitkan dengan eksistensi “Negara Madinah” sebagai sebuah “Negara” yang baru berdiri maka Ashgar menyatakan sebagai berikut: Hence to begin with there was no theocratic state in Medina. All the Prophet did was to recognize the existing reality and accord complete autonomy to the Medinesetribes. He also allowed the non-muslim in Medina to follow their religion and coexist with his followers provided they honoured the terms of the agreement and did not endanger the security of Medina by conspiring with the opponent of the Prophet from Mecca. Various laws wihich became the integral part of Islamic Yurispundence which revealed much later through different verses of a period of time. At that time, these laws, which revealed later, could not have become the basis of the state. (Dalam pada itu, untuk pertama kalinya, di Madinah tidak ditemukan satu bentuk negara teokratis. Semua yang dilakukan Nabi adalah mengenali realitas yang berkembang dan memberikan otonomi sepenuhnya kepada suku-suku yang ada di Madinah. Beliau juga membiarkan non-muslim di Madinah untuk tetap menganut agamanya dan hidup berdampingan sepanjang mereka menghormati ketentuan-ketentuan perjanjian dan tidak mengganggu keamanan Madinah dengan melakukan konspirasi dengan musuh Nabi dari Makkah. Beragam aturan yang menjadi bagian integral hukum Islam diungkapkan jauh kemudian melalui beragam ayat. Pada saat itu, hukum-hukum demikian, yang diturunkan kemudian, tidak dapat menjadi basis negara) (Sofyan dan Madjid: 2003: 22). Namun demikian, perkembangan-perkembangan sosial masyarakat mutakhir pada saat itu menuntut adanya satu perangkat ketentuan dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Dengan adanya aturan-aturan baru itulah maka lahirlah sebuah Negara Islam untuk pertama kalinya. 21 2. Negara Nasional dalam Peradaban Islam Dalam pandangan Ibnu Khaldun, antara negara dengan kekuasaan memiliki hubungan dengan umat antara satu sama lainnya, karena keduanya tidak dapat dipisahkan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Seperti yang telah ia sampaikan sebagai berikut: Adalah satu kenjataan, bahwa daulah (negara) dan mulk (kekuasaan wibawa) itu mempunjai hubungan jang sama terhadap umran (peradaban atau masjarakat) sebagai hubungan bentuk dengan benda. Bentuk adalah rupa jang mendjaga adanya benda dengan perantaraan potongan tertentu dari bangunan jang diwakilinya. Di dalam ilmu filsafat telah ditetapkan, bahwa jang satu tak dapat ditjerai-pisahkan dari jang lainnya. Kita sungguh tak dapat membajangkan suatu daulah tanpa umran, sedang satu umran tanpa daulah dan mulk adalah tidak mungkin, karena umat manusia menurut wataknja haruslah saling bantu-membantu, dan ini meminta adanja satu kewibawaan (Ar. Al-wazi). Maka kepemimpinan politik, jang didasarkan atas kekuasaan Sjari’at ataupun diradja, adalah satu keharusan sebagai pemegang wibawa itu. Inilah jang dimaksudkan dengan daulah. Oleh karena keduanja itu tidak dapat ditjerai-pisahkan, maka kehantjuran salah satunja itu akan mempengaruhi jang lainnya, sebagaimana djuga tak adanja jang satu akan mengakibatkan tak adanja jang lainnja itu (Raliby. 1965: 162). Dalam pandangan Ibnu Khaldun, antara negara dengan rakyat (umat) layaknya tangan kiri dan tangan kanan. Kehancuran pada salah satunya berarti merupakan sebuah kepincangan. Disinilah Ibnu Khaldun secara implisit menerangkan urgensi sebuah negara pemerintahan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pernyataan Ibnu Khladun juga menerangkan bahwa kehancuran negara berarti kehancuran rakyat, dan tak adanya negara berarti tidak adanya rakyat. Dengan kata lain, tanpa negara, atau kehancuran negara, niscaya masyarakat akan terjatuh dalam sebuah kehancuran yang bernama anarki. Secara khusus, keberadaan negara pun sudah 22 tentu dibutuhkan di tengah-tengah dunia Islam, namun cara pandang mengenai negaranya itu sendiri masih berbeda-beda di tengah umat Islam sendiri. Sebagaimana tidak dikenalnya secara baku tentang adanya konsep negara Islam, masyarakat Islam tidak mengenal konsep adanya negara bangsa atau nasional. Pada awalnya, setidaknya sampai dengan zaman pra-modern, masyarakat muslim hanya mengenal dua konsep territorial politik religious dar al Islam (wilayah damai), yaitu wilayah kaum muslimin dan dar al harb (wilayah perang) yaitu wilayah non-muslim. (Azra, 1996: 12). Oleh karena itu, konsep negara nasional (nation-state) seringkali menciptakan ketegangan historis dan konseptual, misalnya berbenturan dengan kekhalifahan. Pada awalnya konsep negara bangsa atau negara nasional dalam Islam dikenal sejak era Imperium Utsmani, bersamaan dengan lahirnya nasionalisme Turki. Menurut Sofyan dan Madjid (200: 28) dalam praktiknya, apa yang disebut sebagai nasionalisme Arab tidak pernah terwujud secara kongkrit dan stabil. Perbedaan-perbedaan mendalam di antara bangsa Arab dalam hal geografis, adat-istiadat dan tradisi lokal, dan orientasi sosio-ekonomis mengatasi kesamaan bahasa dan bahkan Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas bangsa Arab. Nasionalisme Arab sesungguhnya adalah ideologi semu. Di samping nasionalisme Arab, pada saat relatif bersamaan di dunia Arab lahir pula nasionalisme lokal dan lebih terfokus pada kawasan tertentu, tidak mencakup seluruh dunia Arab. Gerakan Nasionalisme lokal ini disebut dengan gerakan wataniyyah atau gerakan patriotisme/gerakan cinta tanah air. Berbeda dari gerakan qawmiyyah, gerakan patriotisme atau gerakan qawmiyyah, gerakan 23 patriotisme atau gerakan cinta tanah air yang lebih memfokuskan pada masingmasing kawasan di dunia Arab bukan seluruh dunia Arab. Semua gerakan nasionalisme Arab ini lahir sebagai sebuah bentuk ketidakpuasaan terhadap pemerintahan Turki Utsmani dan dan perlawanan terhadap imperialisme Eropa (Lenczowski, 2003: 32). Dalam khazanah budaya Arab, patriotisme atau cinta tanah air mempunyai akar yang dalam; tetapi karena pengaruh Barat, kini mendapatkan nuansa baru, khususnya pengaruh Revolusi Perancis. Di Mesir, Rifa’at al Tahtawi mengintrodusir gagasan menyangkut tanah air sebagai obyek pengorbanan, dan menegaskan bahwa persaudaraan atas dasar kesamaan tanah air (watan) sama dengan persaudaraan atas karena kesamaan agama. Muhammad Abduh, seorang reformis Islam, menyatakan bahwa watan merupakan basis bagi kehidupan politik; dan mengembangkan gagasan tentang hak dan kewajiban yang membatasi individu untuk tanah airnya. Di Suriah, alternatif lain terhadap sektarianisme adalah wataniyyah yang lebih bernuansa lokal dibandingkan dengan nasionalisme Arab. Wataniyya adalah produk nasionalisme tetapi selangkah lebih maju. Dia tidak menjadikan bangsa Arab secara keseluruhan sebagai basis kesetiaan, tetapi lokalitas atau propinsi tertentu Jadi, jika Mesir, Aljazair, dan Tunisia berada di bawah kolonialisme Eropa, maka wataniyya, di Negara-negara tersebut, berbentuk nasionalisme Mesir, nasionalisme Aljazair dan nasionalisme Tunisia. Sementara qaumiyya dimaksudkan untuk melawan terutama imperium Utsmani, wataniyya lahir sebagai gerakan melawan imperialisme Eropa (Sofyan dan Madjid, 2003: 29-30). Ringkasnya, dalam sejarah peradaban Islam konsep nasionalisme yang 24 secara otomatis melahirkan konsep ‘negara bangsa’ atau ‘negara nasional’ merupakan fenomena modern yang lahir pada akhir kejayaan imperium Turki Utsmani. Namun demikian, pada saat konsep negara nasional tidak sepenuhnya mendapatkan tempat di kalangan umat Islam dan bahkan memunculkan ketegangan historis dan kultural, konsep Negara Islam pun belum dicapai kata sepakat di kalangan umat. Sebagaimana yang ditulis Azra (1996: 22) umat Islam tidak mempunyai model Negara Islam yang jelas dan kongkrit dalam sejarah. Tidak adanya konsensus menyangkut konsep Negara Islam ini disebabkan beberapa faktor antara lain; pertama, Negara ideal Madinah (dibawah pimpinan Nabi dan keempat khalifah) tidak menawarkan rincian yang bisa mengilhami penerapannya di alam modern dan masa kontemporer. Kedua, praktek-praktek kekhalifahan yang belakangan, yakni periode Umayyah dan Abbasiyah, hanya menyediakan kerangka sistem lembaga politik, pajak dan sebagainya. Ketiga, kegagalan secara penuh mendirikan Negara Islam mengarah pada perumusan citacita ideal (hukum Islam dan teori politik) yang menggambarkan masyarakat utopia yang bersifat teoritis dan teridealisasi. Keempat, hubungan antara agama dan negara-seperti kebanyakan kepercayaan, praktek dan bahkan wahyu itu sendiri-selama berabad-abad menjadi subyek interpretasi. Dengan pertimbangan di atas, maka menarik mendiskusikan konsep Negara nasional di tengah makin meningkatnya tuntutan untuk revitalisasi Islam, kendati konsep Negara Islam itu sendiri, seperti baru saja dikemukakan, belum terjelaskan secara kongkrit. konsep ‘negara bangsa’ atau ‘negara nasional’ 25 dalam sejarah peradaban Islam muncul pada era imperium Turki Utsmani. Menurut Azra (1996: 30) konsep tersebut berasal dari rasa nasionalisme yang masing-masing dikembangkan bangsa Turki dan bangsa Arab. Di era imperium Utsmani, terdapat pemikir terkemuka tentang nasionalisme baik Turkisme maupun Arabisme yang saling bertentangan satu sama lain. Yang pertama adalah Ziya Gokalp dan yang kedua adalah Al-Kawakibi. Dan keduanya sama-sama berangkat dari realitas kejumudan (stagnasi) dan kemunduran umat Islam serta upaya untuk mengatasi persoalan yang melilit umat Islam. Al-Kawakibi berpijak pada perspektif teologis dan memperlihatkan nuansa lebih politis, sedangkan Gokalp menganalisisnya dari perspektif sosiologis dan lebih bercorak kultural. Al-Kawakibi berpendapat bahwa kaum muslimin seharusnya kembali kepada ajaran agama mereka yang sejati untuk mengembangkan nalar mereka dalam berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Ziya Gokalp menganjurkan pemisahan antara agama dan negara, diadopsinya peradaban Barat dan perbaikan sistem pendidikan nasional Turki harus sejalan dengan sistem pendidikan modern. Dua pandangan di atas mempengaruhi pemikiran umat Islam di kemudian hari dan tampaknya saling bersaing untuk membuktikan sebagai pemikiran yang benar dan aplikatif, termasuk di kalangan umat Islam Indonesia. Kendati mereka berdua berbeda pandangan dalam mengatasi krisis umat Islam, mereka sama-sama menganjurkan nasionalisme tentu dengan unsurunsur yang tidak sama. Dengan nasionalisme Arabnya, al-Kawakibi memasukan unsur-unsur Islam kedalam pemikirannya, sedangkan Ziya Gokalp lebih memilih jalan lebih liberal bahkan sekuler. Dengan kata lain, nasionalisme dan Negara 26 nasional mulai diakui dan diterima dalam komunitas umat Islam secara eksplisit sejak era imperium Turki Utsmani. B. Kajian Tentang Hubungan antara Islam dengan Politik Negara dalam Konteks Keindonesiaan 1. Perdebatan Negara Pada Masa Awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945, akhirnya, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa para founding fathers Republik Indonesia memilih satu bentuk atau format negara nasional sebagai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian dipilihnya Pancasila oleh para founding fathers sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui satu proses panjang dan tidak mulus. Perdebatan mengenai dasar negara terjadi dalam sebuah badan bernama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat (Maarif, 1984: 71). Masalah pokok yang diperdebatkan dalam BPUPKI berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan konstitusi bagi sebuah negara. Perdebatan dalam badan yang dibentuk Jepang itu berjalan lancar, kecuali menyangkut persoalan dasar negara. Perdebatan seputar dasar Negara dibuka, untuk pertama kali, oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Diantara anggota yang ternyata siap menjawab tawaran Radjiman adalah Ir. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno 27 menyampaikan sebuah pidato yang cukup panjang dan tanpa teks yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Sehubungan dengan persoalan lahirnya Pancasila ini, Douglas E. Ramage menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno merupakan upaya untuk menemukan jalan tengah antara dua kelompok berbeda yang menghendaki dasar negara yang berbeda pula. Kemudian memperhatikan suasana tegang terutama antara kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan kelompok nasionalis yang menolak gagasan tersebut, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Douglas E. Ramage menulis: In order to bridge the strongly held position between nationalist advocates of a secular state and those championing an Islamic state. Soekarno addressed the committee on June 1 1945 in a now famous speech known as Lahirnya Pancasila (the Birth of Pancasila) Soekarno sought provide an ideological foundation upon which a state coterminous with the boundaries or former Netherlands East Indies could be survive as a unified national state. (Dalam rangka menjembatani pandangan yang teguh dipegang oleh kaum nasionalis yang mendukung negara sekuler dan mereka yang mendukung Negara Islam, pada 1 Juni 1945 Soekarno memberikan pidatonya yang dikenal dengan lahirnya Pancasila di depan anggota Badan Penyelidik. Soekarno berupaya memberikan landasan dimana negara menjadi terputus/ tidak ada kaitan dengan bekas Negara Hindia Belanda dapat survive sebagai Negara nasional bersatu) (Ramage: 1995: 11). Apa yang dilakukan Soekarno saat itu yang dengan pidatonya yang menawarkan satu gagasan tentang dasar negara, dalam pandangan Douglas E. Ramage, merupakan satu upaya kompromi politik yang dia tawarkan kepada berbagai kelompok yang berbeda tentang dasar Negara untuk Indonesia merdeka. Ramage menulis: 28 The speech was clearly designed to establish a political compromise. Soekarno proposes that five principles-nationalism or Indonesian unity, humanitarianism, Indonesian democracy through consultation and consensus, sosial justice and belief in God – could form a common platform on which all competing ideologies could meet and yet not threaten the essential unity of Republic. National unity could be threatened, Soekarno implied, if one exclusive ideologi, Islam in particular, were to be enshrined as the basis of the state for all citizens. (Pidato tersebut ditujukan untuk menciptakan kompromi politik. Soekarno mengemukakan lima dasar/Pancasila-nasionalisme atau persatuan Indonesia, kemanusiaan, demokrasi Indonesia melalui musyawarah mufakat , keadilan sosial dan keTuhanan-dapat membentuk common platform di mana semua ideologi yang berkompetisi dapat bertemu dan tidak mengancam persatuan Indonesia, jelas Soekarno, jika satu ideologi eksklusif, khususnya Islam, dijadikan dasar negara untuk semua penduduk) (Ramage: 1995: 12). Kemudian dalam upaya membahas pidato Ir. Soekarno yang sedikit banyak mulai membicarakan persoalan dasar negara, maka dibentuklah sebuah komite kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Panitia ini dibentuk untuk merumuskan kembali isi pidato Soekarno. Panitia ini terdiri dari sembilan orang yang merepresentasikan golongan-golongan yang ada saat itu. Islam, Nasionalis dan Kristen. Kendati demikian, ketegangan antara dua kelompok berbeda yakni di satu pihak kelompok Islam yang terus berupaya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara bagi Indonesia merdeka dari kelompok nasionalis yang berjuang untuk menolak keinginan kelompok Islam terus berlangsung. Hanya saja, setelah Panitia Sembilan ini bekerja keras, akhirnya ditemukan satu solusi politik. Pada tanggal 22 Juni 1945 diusulkan satu bentuk piagam yang 29 mengakomodir keinginan pemimpin Islam saat itu. Satu piagam yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara diterima, tetapi sila Ketuhanan yang dalam pidato Soekarno diletakkan pada bagian paling akhir, oleh Panitia Sembilan ditempatkan pada bagian pertama dengan diikuti oleh anak kalimat sebagai berikut ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (Anshari, 1986: 29-68). Anak kalimat strategis ini ditempatkan tidak saja dalam UUD 1945, tetapi juga dalam pasal 29 ayat 1, Piagam Jakarta ini diterima secara aklamasi oleh semua anggota BPUPKI pada 16 Juli 1845. Saat itu terjadi perkembangan sejarah yang besar yang melahirkan perubahan besar pula terhadap perjalanan sejarah konstitusi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta memanggil tokoh-tokoh Islam untuk merespon perkembangan-perkembangan yang terjadi saat itu. Akhirnya, disetujui bahwa tujuh kata setelah sila Ketuhanan dihilangkan, tetapi atribut strategis “Yang Maha Esa” dikukuhkan sebagai penggantinya. Terkait dengan digantikannya tujuh kata setelah Ketuhanan dalam Piagam Jakarta dengan kata Yang Maha Esa, Mohammad Hatta menyatakan: Pada waktu itu kami menginsafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ketuhanan dengan mewajibkan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa……tiap-tiap peraturan dalam kerangka syari’ah Islam, yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana Undang-Undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu, lambat laun terdapat bagi umat Islam di Indonesia suatu sistem syari’ah yang teratur dalam 30 undang-undang, berdasarkan Qur’an dan Hadits yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang (Maarif, 1984: 45). Sehubungan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar Negara KH. Wahid Hasyim mengakui adanya keadilan kaum nasionalis untuk menjaga kesatuan negara Indonesia dan sepakat bahwa demi kesatuan Republik, Islam tidak harus mendapatkan perlakuan istimewa. Bagi Wahid Hasyim pertanyaan terpenting bagi umat Islam bukan “bagaimana tempat dan posisi umat Islam dalam Negara?” melainkan “dengan instrumen apa kita bisa menjamin posisi semua agama dalam Indonesia merdeka?” (Ramage: 1995: 14). 2. Perdebatan Dasar Negara Pada Masa Demokrasi Liberal Sepuluh tahun kemudian, ketegangan antara kelompok-kelompok pendukung Islam versus pendukung Pancasila mengemuka kembali. Setelah pemilu pertama tahun 1955, di bawah payung hukum UUDS 1950, perdebatan Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mengemuka kembali. Perdebatan ini terjadi dengan keras dalam majelis konstituante. Pemilu yang dilaksanakan pertama kali dalam sejarah republik yang baru merdeka ini dimaksudkan untuk membentuk parlemen dan Majelis Konstituante. Semula diharapkan bahwa Majelis Konstituante hasil pemilu akan mampu membuat sebuah UUD yang permanen untuk menggantikan UUD yang pernah dimiliki. Partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII, dan PTII) dalam Pemilu 1955 hanya berhasil meraih suara kurang dari 43,5 % suara dengan perolehan kursi 114 dari 257 kursi. Undang-undang pemilu yang berdasarkan UUDS 1950 menuntut bahwa suatu UUD barulah menjadi sah bila draftnya disetujui oleh 31 paling kurang 2/3 anggota yang hadir dalam rapat. Dengan ketentuan ini sebenarnya suatu Negara Islam atau negara berdasarkan atas Islam secara eksplisit menjadi tidak mungkin. Begitu juga untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara permanen pada waktu itu tidak mungkin sebab partai-partai pendukungnya antara lain PNI, PKI, PSI, PIR, Partai Katolik, Parkindo dan lain-lain hanyalah mengantongi suara lebih sedikit dari 50%. Adapun materi yang menjadi perdebatan Majelis Konstituante tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada BPUPKI. Ada tiga draft yang diusulkan oleh berbagai kekuatan berbeda saat itu, yaitu Pancasila, Islam dan sosial ekonomi. Sosial-ekonomi hanya didukung oleh dua partai kecil yang mempunyai pengikut rakyat kecil yakni Murba dan Partai Buruh (Maarif, 1985: 124). Jadi sejak semula sebenarnya sudah dapat diperhitungkan bahwa tanpa suatu kompromi, Majelis Konstituante akan berakhir dengan kegagalan. Tapi rupanya sebagaimana diharapkan oleh UU Pemilu, suatu perdebatan harus berlangsung lebih dulu baru suatu kompromi mungkin tercapai. Sayangnya sebelum kompromi itu menjadi kenyataan, ada intervensi dan kekuatan ekstra parlementer, yaitu militer bersama Soekarno yang kemudian membubarkan Majelis. Oleh karena itu yang akhirnya saling berhadapan adalah Pancasila dan Islam. Berbeda dari BPUPKI, di Majelis Konstituante ini, wakil-wakil umat Islam lebih siap, dan sekarang kombinasi kekuatan dunia pesantren dan dunia intelek berpendidikan mumum dikerahkan untuk memperjuangkan dasar Islam bagi Indonesia merdeka. Tokoh Islam yang menonjol antara lain: Mohammad Natsir, KH. Saefuddin Zuhri, Z.A. Ahmad, Osman Raliby, KH. Syukri Ghazali, 32 Muhammad Hasbi as Shiddiqi, KH. Masykur, Kasman Singodimedjo, Hamka, Muhamad Taher Abu Bakar, Syamsiah Abbas. Sedangkan dari kelompok pendukung terkemuka dasar Pancasila antara lain: Ruslan Abdul Gani, St. Takdir Alisyahbana, Soedjatmiko, Prof. Soeripto, Arnold Mononutu, Njoto, Karkono Protokusumo dan Suwirjo (Maarif, 1984: 75). Masing-masing golongan bekerja keras untuk mempertahankan pendiriannya, namun tidak mampu meyakinkan pihak lawan. Perdebatan tentang dasar ideologi negara dalam Majelis Konstituante berlangsung sampai sidangnya yang terakhir pada 2 Juni 1959, tanpa tercapainya satu keputusan. Dengan kenyataan ini pembuatan satu UUD yang permanen menjadi terhambat, sekalipun sudah 90% dari cara kerja majelis yang terselesaikan (Nasution, 1992: 78). Kemudian situasi setengah macet ini diatasi oleh Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 dengan membubarkan Majelis Konstituante serta menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Ini artinya Pancasila dinobatkan melalui Dekrit Presiden menjadi dasar negara yang permanen, tetapi tetap mempertimbangkan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 sebagai menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan UUD tersebut. Menurut Anshari (1986: 99), kebijakan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden lebih banyak disebabkan karena koalisi ABRI dengan Soekarno yang merasa kepentingan politiknya terancam jika demokrasi parlementer tetap diterapkan. Hal menarik dalam perkembangan yang terjadi pada sidang-sidang di Majelis Konstituante pandangan elit politi dalam memandang Pancasila bukan 33 sebagaimana dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Menurut kajian Douglas E. Ramage: However by the late 1950s Pancasila no longer represented a compromise or a meeting place for all ideologies originally envisioned by Soekarno. This was because Pancasila had been increasingly utilized as an ideological tool for delegitimizing Islamic demands for state recognition af Islam. (Namun demikian, pada akhir 1950-an Pancasila tidak lagi menjadi tempat kompromi atau meeting place, bagi semua ideologi yang ada sebagaimana untuk pertama kalinya digagas Soekarno. Ini karena Pancasila semakin digunakan sebagai instrumen ideologis untuk mendeligitimasi tuntutan umat Islam untuk memperjuangkan Negara Islam) (Ramage: 1995: 19). Bahkan Soekarno, orang yang menggagas Pancasila, tidak bisa menghindar dari menggunakan Pancasila untuk deligitimasi kelompok Islam. Douglas E. Ramage menceritakan: Soekarno himself explicitly used Pancasila in this fashion in a speech thatgenerated much Islamic anxiety and anti Pancasila sentiment. In 1953 Soekarno candidly voiced his fear of the negative implications for national unity if muslim Indonesian pressedtheir demand for an Islamic state, or for constitutional or for legal provision which would constitute formal recognition of Islam by the state. (Dengan eksplisit, Soekarno sendiri menggunakan Pancasila dalam kerangka ini dalam sebuah pidato yang melahirkan keprihatinan dari umat Islam sentimen anti Pancasila. Pada 1953, dengan terus terang Soekarno mengemukakan kekhawatirannya atas dampak negatif yang bakal muncul atas persatuan nasional jika umat Islam memaksakan tuntutannya untuk berdirinya satu Negara Islam, atau untuk aturan hukum atau konstitusi yang dapat melahirkan pengakuan formal terhadap Negara Islam) (Ramage: 1995: 17). Namun demikian, kaum pendukung Pancasila pun, terbelah menjadi dua kelompok berbeda dalam memahami Pancasila. Sofyan dan Madjid (2003: 48-49) menulis: kelompok pertama memandang Pancasila sebagai satu forum, titik temu semua partai dan kelompok yang berbeda. Pandangan seperti ini 34 dipegang oleh PNI (Partai politik terbesar saat itu), PKI (pemenang keempat pada pemilu 1955), Partai Katholik dan Partai Kristen. Sutan Takdir Alisjahbana (PNI) mengungkapkan: “….bahwa Pancasila hanyalah kumpulan paham-paham yang berbeda-beda untuk menentramkan semua golongan pada rapat-rapat” (Zuhri, 1980: 201). Dengan kata lain, kelompok-kelompok ini memandang Pancasila dalam terminology original sebagai satu kompromi politik. Kelompok kedua, melihat Pancasila sebagai satu-satunya ideologi politik yang memberikan jaminan atas persatuan nasional dan cocok dengan kepribadian Indonesia, dan oleh karenanya, menjadi satu-satunya dasar negara yang tepat untuk Indonesia. Pandangan semacam ini dianut oleh sekelompok kecil anggota Majelis Konstituante, termasuk Prof. Soepomo, proponen original paham integralistik. Pandangan demikian ini memandang Pancasila bukan sekedar kompromi politik, melainkan sebagai ekspresi ideologi dan politik budaya politik asli. Pandangan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional yang all-encompassing mendapat dukungan kalangan luar Majelis Konstituante terutama Presiden Soekarno dan militer. Dari dua kelompok pendukung Pancasila semasa Demokrasi Konstitusional, kelompok kedualah yang survive sampai pergantian sistem politik; dari sistem politik liberal ke dalam sistem politik yang dikenal sebagai didasarkan atas Demokrasi Terpimpin. Dengan kata lain, pandangan bahwa Pancasila merupakan satu ideologi yang all-encompassing berlanjut hingga era Demokrasi Terpimpin. 35 3. Perdebatan Dasar Negara Pada Masa Demokrasi Terpimpin Dalam era Demokrasi Terpimpin, perdebatan seputar dasar negara tidak mengemuka sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Melalui bekerjasama dengan militer (Angkatan Darat), Presiden Soekarno, Dekrit Presiden tahun 1959 berhasil menghentikan debat seputar dasar negara yang terjadi antara terutama kelompok Islam dan kelompok Pancasila. Selain itu, Menurut Thaba (1996: 178) Soekarno berhasil melakukan pendekatan kepada umat Islam seperti NU, Perti dan PSII. Partai-partai tersebut tetap diizinkan berdiri karena mendukung Demokrasi Terpimpin. Mereka tampil sebagai wakil kelompok agama dalam Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), yang merupakan jargon politik Soekarno dalam rangka menciptakan persatuan bangsa. NU pun ikut menyokong pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui Sidang MPRS tanggal 18 Mei 1963. K.H. Wahab Hasbullah, Rais Aam NU, memberikan keputusan agar NU masuk ke DPRGR (parlemen bentukan Soekarno sebagai pengganti parlemen hasil pemilu 1955) tanpa menunggu keputusan musyawarah wilayah yang berwenang mengambil keputusan tersebut. Ia berargumentasi sebagai berikut: Kita putuskan sekarang saja, kita masuk dulu dalam DPRGR setelah itu kita minta penegasan Musyawarah Antara Wilayah memutuskan kita masuk, kita sudah berada di dalam. Tetapi jika Musyawarah memutuskan menolak DPRGR, apa sulitnya kita keluar dari DPRGR. Akan tetapi kalau sekarang kita menolak duduk dalam DPRGR… lalu Musyawarah Antara Wilayah memutuskan kita harus masuk dalam DPRGR, kita sudah terlambat, pintu masuk sudah tertutup (Maarif, 1988: 91). 36 Masyumi menilai sikap NU yang ikut serta dalam demokrasi terpimpin merupakan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Sedangkan Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti) menganggapnya sebagai sikap realistis dan pragmatis. Sementara itu, Masyumi yang selalu melancarkan kritik tajam terhadap pemerintah dianggap sebagai penghalang revolusi Soekarno. Masyumi seringkali mengalami perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah. Sebagaimana dicatat oleh Thaba (1996: 178) pada tanggal 20 Maret 1960 untuk pertama kalinya Masyumi dikucilkan di DPRGR. Empat bulan kemudian, partai ini diperintahkan bubar dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya seperti Natsir, Syafrudin Prawiranegara ikut terlibat pemberontakan PRRI (Noer, 1987: 349357). Menurut George McTurnan Kahin keterlibatan antara Masyumi dengan PRRI masih bisa diperdebatkan (Kahin, 1978: 328-329). Berdasarkan dokumen politik, tidak ada indikasi keterlibatan Masyumi dalam PRRI. Tokoh yang terlibat secara pribadi seperti Natsir, Syafrudin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap lebih banyak berperan sebagai pemberi landasan bagi perjuangan menekan pemerintah pusat. Bahkan atas peran tokoh-tokoh tersebut, PRRI tidak berubah menjadi gerakan separatis (Suswanta, 1993: 155). Oleh karena itu, dibubarkannya Masyumi sebagai simbol perjuangan Negara Islam dan akomodasi Soekarno terhadap NU, PSII dan Perti telah menutup pintu untuk mendiskusikan kembali persoalan dasar negara. Pemusatan kekuasaan di satu tangan melalui demokrasi terpimpin menimbulkan konsekuensi bahwa perdebatan dasar negara oleh pemerintah sudah final, yaitu Pancasila. 37 Dengan tidak adanya satu sistem yang memberikan tempat bagi partai politik, kekuasaan politik pada era Demokrasi Terpimpin, berkisar di antara tiga kekuatan yakni Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI, di mana Soekarno berupaya menjadi faktor penyeimbang di antara dua kekuatan PKI dan AD yang saling bersaing itu (Thaba: 1996: 187). Akan tetapi kepentingan politik dan ideologis yang saling bersaing antara ketiga kekuatan di atas menciptakan satu sistem politik yang sangat rapuh dan tidak stabil yang pada akhirnya, sistem demikian ini berakhir dengan sistem baru pada tahun 1966. Satu sistem politik yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. 4. Perdebatan Dasar Negara Pada Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, penguasa terus melestarikan apa yang dilakukan Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin dengan menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai satu instrumen kompromi politik sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh Soekarno, melainkan sebagai sebuah ideologi yang allencompassing. Douglas E. Ramage menyimpulkan: The New Order focused upon Pancasila and enshrined it as the ideological pilar of the regime. It now emerged as the fully-flegged ideological justification of the ruling group, no longer simply a common platform where all ideologies could meet. (Orde Baru fokus pada Pancasila dan mentahbiskannya sebagai pilar rezim yang ada. Kali ini Pancasila tampil sebagai sebuah justifikasi ideologi yang benar-benar keramat bagi kelas penguasa, bukan lagi semata-mata sebuah common platform di mana semua ideologi yang ada dapat hidup berdampingan) (Ramage 1995: 24). Sebagai satu rezim baru, penguasa Orde Baru berupaya untuk mendapatkan legitimasi. Obsesi tersebut diupayakan oleh penguasa Orde Baru dengan berupaya 38 melakukan penataan-penataan dalam kehidupan ekonomi, politik dan bahan keamanan. Namun demikian, penguasa belum merasa yakin dengan kebijakan yang relatif memperlihatkan hasilnya sejak tahun-tahun pertama kekuasaannya. Dengan kata lain, penguasa Orde Baru tidak merasa aman dengan hanya mendapatkan legitimasi yang bersifat “material.” Penguasa Orde Baru berupaya pula untuk mendapatkan legitimasi yang bersifat ideologis dan jawabannya adalah Pancasila. Digunakannya Pancasila sebagai sebuah ideologi yang allencompassing oleh rezim Orde Baru, bukan sekedar satu instrumen untuk kompromi politik sebagaimana konsep awal yang dikemukakan Soekarno dalam sidang BPUPKI, mencapai puncaknya ketika rezim Orde Baru berhasil menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial politik yang ada; yakni dijadikannya Pancasila sebagai asas tunggal. Bagi Syamsudin (1993: 108), kebijakan asas tunggal merupakan bagian dari upaya rezim Orde Baru melakukan de-ideologisasi. Kebijakan deideologisasi ini meliputi antara lain: penggabungan partai-partai politik, diciptakannya kebijakan massa mengembang, ditetapkan P4 oleh MPR, dan puncaknya adalah dijadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Sedangkan Leo Suryadinata menganggap bahwa kebijakan asas tunggal memang ditujukan terutama terhadap umat Islam dalam menghadapi Pemilu 1987. Leo Suryadinata mengemukakan: 39 Strategi asas tunggal tidak lebih dari upaya de-islamisasi politik Indonesia. Ini dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi Pemilu 1987, setelah pemerintah melihat masih melekatnya pengaruh Islam dalam partai Islam (PPP) pada pemilu-pemilu sebelumnya (Suryadinata, 1992: 75). Dikaji lebih jauh, berpijak pada apa yang dinyatakan Suryadinata, maka dapat dipahami bahwa asas tunggal merupakan upaya subordinasi penguasa yang didominasi oleh kelompok nasionalis terhadap kelompok-kelompok Islam. Dengan kata lain, kebijakan asas tunggal merupakan puncak ketegangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang berakhir dengan “kemenangan” pada kelompok nasionalis. Dalam realitas politik demikian itu, maka hampir tidak ada ruang bagi kelompok-kelompok Islam yang mendukung Piagam Jakarta untuk menyuarakan kembali dukungannya terhadap Piagam Jakarta, sebagaimana dilakukan pada masa Demokrasi Konstitusional. Atau bahkan untuk sekedar menggunakan label Islam dalam organisasi-organisasi umat Islam. Memang pada tahun 1968, kalangan Islam pernah mencoba mengusulkan untuk kembali pada Piagam Jakarta, namun usul tersebut ditolak Penguasa. Namun demikian, umat Islam tidak putus asa menghadapi realitas politik yang tidak menguntungkan mereka. Fase ini juga ditandai dengan munculnya generasi pemikir Islam tahun 1970-an yang lebih bercorak substansialistik. Asas tunggal diterima oleh hampir semua mereka, kendati dengan alasan yang tidak persis sama kenyataan politik kemudian hari memperlihatkan bahwa umat Islam tidak terlalu kesulitan menghadapi realitas politik di atas. Bahkan mereka mampu berdapatasi dalam realitas yang relatif baru itu. 40 Isu-isu yang dikemukakan mereka pun tidak terpaku pada persoalan Piagam Jakarta. Pasca pemberlakuan asas tunggal, mereka mulai mengalihkan perhatiannya pada bagaimana mengamalkan ajaran Islam dengan segala macam interpretasinya dalam sebuah sistem politik yang didasarkan atas Pancasila, bukan Piagam Jakarta atau pendirian negara Islam. Azyumardi Azra tokoh pemikir dari generasi ini bahkan mengungkapkan: Gagasan dan upaya untuk membentuk Negara Islam di Indonesia, baik secara damai melalui parlemen seperti yang dilakukan Masyumi, maupun secara radikal yang dilakukan Kartosuwiryo, pada hakikatnya bertitik tolak dari romantisme yang sayangnya sangat samar-samar dan sering berdasarkan pada normativisme keagamaan belaka. Sebab itulah, gagasan dan upaya kalangan kaum Muslimin tertentu, baik di Indonesia maupun di bagianbagian dunia muslim lainnya, akan menemui kegagalan. (Azra, 2000: 173) Maka menjelang berakhirnya sistem politik Orde Baru, lahirlah organisasi seperti ICMI (terlepas dari berbagai kritik yang juga dilontarkan sesam umat Islam), yang dalam konteks tulisan ini dapat dipahami sebagai kekuatan penyeimbang atau tepatnya “pesaing” kekuatan nasionalis. Kemudian perubahan tatanan politik yang terjadi di era reformasi memberikan ruang kepada sebagian aktifis umat Islam untuk menyuarakan kembali Piagam Jakarta, sebagaimana diperlihatkan oleh para pendukung Mazhab formalis dalam memahami hubungan Islam dan negara. Partai-partai politik yang mendukung Piagam Jakarta antara lain PBB, PK, dan PPP dan sejumlah partai Islam lainnya. Selain dari partai politik, desakan untuk kembali pada Piagam Jakarta muncul dari berbagai organisasi umat Islam yang secara terus terang mendukung syariat Islam sebagai frame of reference kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 41




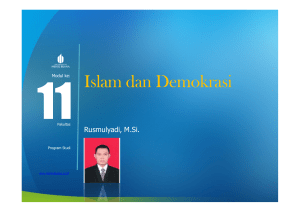

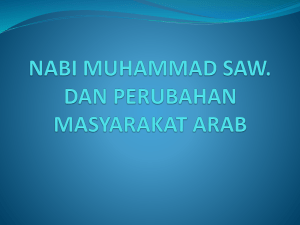
![Modul Agama [TM12] - Universitas Mercu Buana](http://s1.studylibid.com/store/data/000296276_1-33954cb90007e13aff298fe7ca956f57-300x300.png)