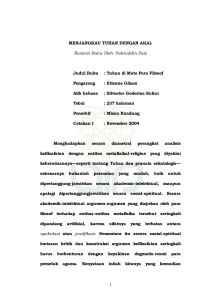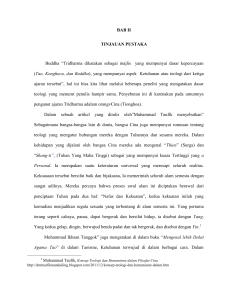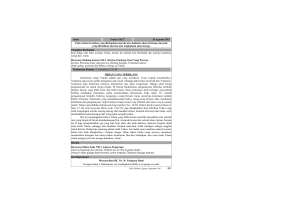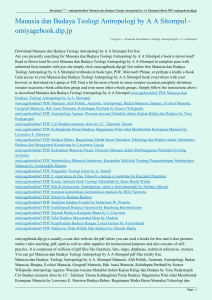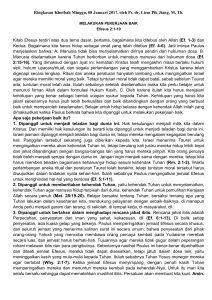wajah agama dalam hegemoni teologi
advertisement

WAJAH AGAMA DALAM HEGEMONI TEOLOGI BADARUS SYAMSI Abstrak Artikel ini melihat peran teologi yang merupakan salah satu aspek dari agama. Penulis melihat bahwa teologi mengambil peran sangat penting bahkan terpenting, yang oleh penulis disebut sebagai hegemoni. Peran ini tentu saja punya efek yang tak selamanya diharapkan. Teologi yang terlalu memfokuskan pada persoalan Tuhan, misalnya, sering membawa para teolog pada kebenarannya sendiri yang melangit dan abai melihat realitas. Di akhir, penulis mengusulkan dekonstruksi terhadap teologi yang telah menjadi hegemoni bagi agama tersebut. Kata Kunci: teologi, pemikiran keagamaan, hegemoni, dekonstruksi agama. Pendahuluan Bagi manusia, keinsyafan akan kehadiran kekuatan Maha Dahsyat itu bukan hanya mendatangkan ketenangan dan perlindungan, namun juga memberikan bimbingan dalam menemukan otoritas yang kepadanya manusia harus meyandarkan harapan dan cita-cita, demikian pula cinta dan dedikasi dalam hidupnya. Dengan keinsyafan semacam itu, maka kebesaran dan kekuasaan hanyalah karakter semu belaka yang melekat pada identitas kemanusiaan, kebesaran dan kekuasaan menjadi karakter yang mutlak dan total yang melekat pada identitas ketuhanan Sang Maha Dahsyat. Ketika ternyata, identifikasi manusia terhadap kekuatan Maha Dahsyat itu menghasilkan kesimpulan tentang sosok yang bernama Tuhan, maka dengan bangga dan rasa penuh kemenangan, manusia memproklamasikan ketundukan dan kepasrahan yang total kepada-Nya. Proklamasi itu mendorong manusia untuk memuja dan mengatasnamakan Tuhan dalam setiap kali ia mensiasati gerak hidup, dalam membangun perdamaian, juga dalam mengobarkan peperangan.1 1 M. Nasir Tamara, “Pengantar”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Tahar (ed.), 414 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 Gejala dan ekspresi keagamaan yang digambarkan oleh Nasir Tamara di atas merupakan hal yang terdapat di dalam setiap agama apa pun di dunia. Dengan kesadaran akan adanya wujud dan kekuatan Yang Maha Tinggi atau Supreme Being, manusia mulai memproyeksikan kekuatan tersebut di dalam kalbu dan feeling-nya. Kesadaran ini kemudian melahirkan dua aspek penting dalam kehidupan kegamaan manusia: aspek vertikal dan horisontal. Dengan kalbu dan feeling-nya, manusia membangun hubungan vertikal kepada Tuhan dengan ritualritual tertentu. Ritual-ritual tersebut kemudian berpengaruh pada level-level hubungan sosial-horisontal manusia dengan mengambil wujud institusionalisasi keyakinan dan institusionalisasi ritual-ritual, yang kemudian melahirkan komunitas-komunitas tertentu pula. Agama setidaknya mempunyai dua sisi, yaitu keyakinan agama atau teologi dan pelaksanaan ajaran agama atau syariah. Artikel ini akan melihat lebih jauh tentang sisi pertama dalam agama, yang cenderung lebih kuat atau “hegemonik” ketimbang sisi kedua. Agama, Teologi, dan Kalam Terdapat beberapa istilah yang akan diklarifikasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh. Istilah-istilah tersebut antara lain, agama, teologi, dan kalam serta hubungan agama dengan teologi atau kalam. Agama Dalam bahasa Eropa modern, agama merupakan istilah yang menunjuk kepada semua konsep mengenai kepercayaan kepada Tuhan dan sifatsifat ketuhanan seperti wujud spiritual atau hal-hal pokok transendental yang lain. Agama juga menunjuk kepada sebutan untuk intitusi atau badan-badan yang menampilkan konsep-konsep ketuhanan. 2 Agama sering juga diartikan sebagai institusi serta badan keanggotaan 2 Agama dan Dialog antar Peradaban, ( Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. xi-xii. John R. Hinnels (ed.), Dictionary of Religions, (Kanada: Penguin Book, 1995), hlm. 414. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 415 dimana para anggotanya berkumpul bersama secara tetap untuk beribadah serta menerima seperangkat konsep ajaran.3 Sedangkan seorang teolog Islam seperti Al-Jurjani mendefinisikan agama (al-din) sebagai aturan-aturan Tuhan yang menyerukan kepada orang-orang yang berakal untuk menerima apa-apa yang datang dari Rasul, sehingga jadilah hal itu sebagai syariat yang ditaati.4 Dari asal-usul bahasa yang lain, misalnya bahasa Sansekerta, sebagaimana menurut Endang Saifuddin Anshari, kata agama berasal dari penggalan kata “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Agama berarti tidak kacau, atau dengan kata lain agama juga berarti teratur dan tertib.5 Maka agama dalam tulisan-tulisan ini akan didefinisikan sebagai doktrin ajaran, aturan serta norma dari Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci, hal mana pelaksanaan terhadapnya telah melahirkan kelompok-kelompok dan institusi tertentu, di mana kemudian institusi tersebut dinamakan dengan agama tertentu. Misalnya, agama Islam, merupakan sebuah institusi dari doktrin atau peraturan serta norma-norma Islam, agama Kristen yang merupakan sebuah institusi dari doktrin atau peraturan serta norma-norma Kristen dan sebagainya. Teologi Istilah ini berasal dari bahasa Yunani “theos” yang berarti Tuhan dan “logos” yang berarti percakapan dan pertimbangan.6 Teologi sering diartikan pula sebagai “reflection on the natural being of God”, yakni pemikiran atas sifat-sifat dan wujud Tuhan.7 Sebagai sebuah disiplin 3 4 5 6 7 William L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, (New York: Humanities Press, 1996), hlm. 647. Al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Kairo: Dar al-Irsyad, 1991), hlm. 117-118. Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat dan Agama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 123. William L. Reese, Dictionary of Philosophy, hlm. 647. John Bowker, The Oxford Dictionary of Word Religion, (Amerika: Oxford University Press, 1995), hlm. 970. 416 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 ilmu di Barat, teologi telah diterima sebagai sebuah norma atau keterangan-keterangan yang logis dan rasional (masuk akal) yang menceritakan tentang Tuhan.8 Teologi merupakan usaha-usaha metodis untuk memahami serta menafsirkan kebenaran wahyu. Dan untuk tujuan ini, Teologi menggunakan sumber daya rasio, dengan bantuan ilmu sejarah dan filsafat.9 Dari segi istilah, istilah teologi itu sendiri sebenarnya secara lebih khusus berasal dari gereja, meski sebelumnya teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang terpisah. Dan dalam konteks gereja, teologi bukan hanya berarti pembicaraan tentang Tuhan, akan tetapi ia juga berisi pujian terhadap Tuhan.10 Dari uraian di atas, maka sebenarnya teologi merupakan istilah yang berasal dari dunia Kristen yang berarti ilmu ketuhanan, ilmu yang membahas tentang wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan, serta pujianpujian terhadap Tuhan dengan berlandaskan pada rasio dan akal. Dan lebih dari itu, penafsiran terhadap wahyu dan doktrin kitab suci juga merupakan teologi. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa akal dan rasio yang dimaksud dalam kontek ini hanya sebagai penguat atau rasionalisasi konsep ketuhanan. seorang teolog, sebagaimana yang pernah dicirikan oleh Thomas Aquinas, dalam upayanya menciptakan konsep-konsep keagamaannya berangkat dari wahyu terlebih dahulu sebagai landasan pijaknya, sedangkan pertimbangan rasionalitas dan empirik hanya mereka jadikan sebagai penguat yang berfungsi untuk memastikan adanya Tuhan.11 Jika teologi merupakan suatu ilmu yang secara metodis bertujuan membahas tentang ketuhanan dengan berlandaskan kepada wahyu kemudian diperkuat oleh akal, maka akan menjadi sebuah kelaziman manakala nantinya terdapat istilah teologi di dalam setiap agama. Demikian juga dalam aliran8 9 10 11 William L. Reese, Dictionary of Philosophy, hlm. 647. Gerald O’Collins, SJ. dan Edward G. Forrugia, SJ. (ed.), Kamus Teologi, (Yogyakarta: Kanisius 1996), hlm. 314. John Bowker, The Oxford Dictionary, hlm. 970. Frederick Copleston, S.J. History of Philosophy Medieval Philosophy, (New York: Image Books, 1962), hlm. 30. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 417 aliran di lingkungan internal suatu agama, terdapat teologi Kristen, teologi Islam, dan seterusnya. Kaitan antara Teologi dan Ilmu Kalam Dalam kaitannya dengan Islam, teologi sering dipadankan dengan kalam. Dalam tradisi pemikiran Islam, kalam berarti percakapan atau dialektik. Adapun isi percakapan atau dialektika itu berkisar pada analisa tentang konsep Tuhan, pembuktian akan eksistensi Tuhan melalui argumen ontologi dan argumen kosmologi, hubungan antara Tuhan dengan dunia, etika keadilan Tuhan, yang berkenaan dengan freewill dan predestination, kegunaan bahasa agama serta kekhasan fungsi pengajaran para nabi serta hubungan antara akal dan wahyu serta perannya dalam kehidupan masyarakat.12 Dalam sejarah Islam, istilah kalam secara umum diidentikkan dengan lahirnya aliran-aliran atau sekte-sekte keagamaan dalam bidang akidah, dengan konsep-konsepnya masing-masing serta melalui proses dialektika yang panjang, yang secara khusus hal itu muncul pada masa setelah kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib. Setidaknya terdapat kurang lebih lima aliran kalam dalam Islam, misalnya Khawarij, Murji’ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu’tazilah, dan Ahlussunnah wal Jama’ah (Asy’ariyyah dan Maturidiyyah). Aliran-aliran teologi tersebut secara keseluruhan memiliki konsep masing-masing yang diperkuat dengan dalil naqli (argumen wahyu atau teks kitab suci) dan dalil aqli (argumen akal dan rasio). Hampir keseluruhan isi pembahasan kalam menyangkut ketuhanan, sehingga orang sering menyamakan istilah kalam dengan teologi. Ilmu Kalam itu dalam tradisi pemikiran Islam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang dasar-dasar agama baik itu menyangkut ketuhanan ataupun keyakinan terhadapnya dengan menggunakan dalil aqli dan dalil naqli. Perlu ditegaskan di sini bahwa kaitan antara teologi dengan 12 John L. Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Word, (Amerika: Oxford University Press, 1995), hlm. 214. 418 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 kalam adalah kesamaan keduanya dalam hal kajian tentang pembicaraan Tuhan, dan kedua ilmu tersebut sama-sama menggunakan dalildalil naqli dan dalil aqli. Di sisi lain, seperti yang disebutkan di dalam The Concise Encyclopaedia of Islam, penggunaan istilah kalam ini agaknya mengikuti penggunaan kata Yunani yang dalam filsafat dikenal sebagai “logos”, yakni istilah yang digunakan untuk ilmu pemikiran. Para teolog sering disebut sebagai ahlul kalam atau mutakallimun.13 Dalam hal objek kajiannya serta metode pembahasannya, antara teologi dengan kalam memang tidak terdapat perbedaan, sehingga menyamakan kedua istilah tersebut misalnya adanya kelaziman istilah dalam kajian Islam seperti teologi Islam, kiranya tidak terlalu penting untuk dipersalahkan. Akan tetapi, dari aspek kelahirannya, kedua istilah tersebut memang berbeda. Teologi lahir dari dunia Kristen yaitu tepatnya pada tradisi gereja, sedangkan kalam lahir dari dunia Islam, tepatnya ketika lahir banyak aliran-aliran atau sekte keagamaan pascakepemimpinan Ali. Hubungan antara Agama dan Teologi (Kalam) Dengan mendefinisikan istilah-istilah pokok di atas, maka penting kiranya untuk dijelaskan hubungan antara agama dengan teologi atau kalam. Setelah memperhatikan pengertian istilah-istilah di atas, maka dapat dikatakan bahwa jika agama merupakan seperangkat doktrin yang di dalamnya disampaikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau informasi metafisika lainnya serta peraturan-peraturan agama yang selanjutnya hal itu akan membentuk institusi dan komunitas tertentu (ada komunitas atau institusi agama Islam, Kristen, Yahudi, dan seterusnya), maka teologi atau kalam merupakan ilmu yang berupaya menjelaskan hal itu semua secara rasional—meski rasionalitas itu nantinya akan berbeda di antara 13 Cyriil Glasse, The Concise Encyclopaedia of Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 202, entri “Kalam”. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 419 penjelasan dari orang atau kelompok tertentu dengan orang atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, teologi atau kalam menjelaskan doktrin agama baik mengenai Tuhan beserta informasi metafisik lainnya ataupun menjelaskan pula peraturan atau hukum-hukum agama. Maka secara otomatis, sebagaimana agama, teologi atau kalam akan menyebabkan lahirnya komunitas atau institusi teologis tertentu, misalnya teologi atau kalam Islam, teologi atau kalam Kristen, teologi atau kalam Yahudi, begitu juga dengan agama lainnya. Dapat dinyatakan pula bahwa apa dan bagaimana wajah sebuah refleksi keagamaan yang tampil ke panggung sejarah, akan banyak ditentukan oleh corak teologi yang terdapat di dalam agama tersebut. Sebuah refleksi keagamaan akan berwajah dan bersifat tradisional atau ortodoks manakala teologi yang dianutnya adalah teologi dengan corak tradisional dan ortodoks. Demikian juga pada kasus yang lebih kecil, bahwa tipe keagamaan seseorang akan tampak konservatif, rasional, atau liberal sekalipun, hal itu akan banyak ditentukan oleh apa dan bagaimana corak teologi yang dianutnya. Di sini teologi sangat memengaruhi dan membentuk karakter keberagamaan seseorang. Akan tetapi yang penting untuk dicatat bahwa teologi bukanlah Tuhan itu sendiri demikian pula teologi bukanlah agama itu sendiri secara orisinil, akan tetapi ia hanya releksi atau pemikiran serta tafsiran terhadap agama (baik pemikiran atau tafsiran mengenai Tuhan atau wahyu). Agama secara orisinal sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci adalah tetap dan pasti, akan tetapi teologi sebagai ilmu yang menafsirkan agama akan sangat dipengaruhi oleh setting historis kesejarahan manusia. Dengan demikian, tidak sebagaimana agama, teologi akan senantiasa mengalami perubahan dalam setiap tempat dan zaman. Setelah memaparkan beberapa istilah-istilah dan pendekatan di atas, maka yang maksud dari “pergulatan agama dalam hegemoni teologi” adalah pergulatan agama dalam sejarah kemanusiaan akan senantiasa disebabkan oleh hegemoni (kungkungan yang memengaruhi) teologi sebagai ilmunya. Teologi dapat disebut sebagai top maker 420 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 yang senantiasa memengaruhi perjalanan agama dalam persentuhan dan pergulatannya dengan kondisi kesejarahan manusia. Apakah agama akan cenderung inklusif, akomodatif, dan menjadi rahmatan lil alamin bagi setiap kondisi zaman, atau barangkali agama hanya pada proses kelahirannya yang menunjukkan kebaikan bagi alam semesta, sedangkan dalam perjalanannya akan cenderung menjadi penindas, tanyakan semua itu kepada teologi. Pendekatan Teologi terhadap Agama Melalui pendekatan teologi, ada beberapa variabel yang akan dikupas terlebih dahulu di dalam agama itu sendiri. Pertama, sikap teologi dan teolog terhadap agama. Kedua, agama dalam tradisi pemikiran teologi. Ketiga, dekonstruksi pemikiran teologi. Dengan tiga subtopik pembahasan tersebut, diharapkan ditemukan kejelasan mengenai bagaimana eksistensi agama manakala dipahami melalui pendekatam teologi. Sikap Teologi terhadap Agama (Dalam upaya memahami agama) kaum filsuf memulai dari dunia pengalaman dan berpendapat dengan akalnya untuk sampai kepada Tuhan sehingga dia dapat mengetahui penciptaan. Sedangkan teolog berangkat dari (konsep) Tuhan sebagaimana Dia telah mewahyukan diri-Nya. Sedangkan metode penelitian di dalam teologi (hanyalah) berfungsi untuk memastikan adanya Tuhan… Kaum teolog menerima prinsip-prinsip (agama atau keyakinan) sebagai (suatu hal) yang telah diwahyukan dan mempertimbangkan objek (kajian)-nya dengan pertimbangan wahyu. Sedangkan filsuf memahami prinsip-prinsip (agama) melalui akal dan mempertimbangkan objeknya bukan sebagai yang telah diwahyukan, akan tetapi sebagai objek yang dapat dipahami melalui akal… Sebagai contoh, filsuf berpendapat bahwa Tuhan sebagai pencipta, sebagaimana halnya kaum teolog menerima kenyataan juga bahwa Tuhan sebagai pencipta. Akan tetapi pengetahuan kaum filsuf tentang Tuhan sebagai pencipta datang dari kesimpulan-kesimpulan yang rasional, sedangkan teolog menerima pengetahuan tentang Tuhan sebagai pencipta itu dari wahyu.14 14 Frederick Copleston, S.J. History of Philosophy, hlm. 31. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 421 Kutipan yang agak panjang di atas sengaja diambil dari pandangan Thomas Aquinas tentang ciri-ciri filsuf dan teolog dalam memahami agama. Ada dua ciri utama kaum teolog dalam mendekati agamanya. Pertama, untuk mengetahui Tuhan, para teolog mempergunakan wahyu sebagai landasan epistimologinya. Kedua, prinsip-prinsip keagamaan, termasuk di dalamnya ekspresi keagamaan yang tecermin dalam pola pikir dan sikap seorang teolog yang berangkat dari pemahaman tekstualnya terhadap wahyu. Pada ciri yang pertama, seorang teolog dalam rangka untuk sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan menggunakan wahyu sebagai landasan teologinya. Seorang teolog memercayai dan meyakini bahwa wahyu merupakan berita dan informasi dari Tuhan yang berisi segala hal yang bersifat metafisik yang belum diketahui oleh manusia. Seorang teolog meyakini bahwa wahyu merupakan sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memecahkan segala persoalan yang tidak dapat dipecahkan manusia. Implikasi dari pemikiran ini adalah bahwa agama-agama (utamanya agama wahyu) merupakan keharusan kemanusiaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan demi keselamatan manusia. Di samping itu, adanya nabi sebagai penyampai agama Tuhan kepada manusia tersebut, juga merupakan keharusan. Satu hal yang penting dari uraian di atas adalah implikasi sosial yang muncul dari paradigma teologi yang mempergunakan wahyu sebagai landasan epistimologinya. Terdapatnya relativitas terhadap segala upaya untuk menggambarkan Tuhan sering berakibat lahirnya relativitas dalam ekspressi bahasa agama. Yang terjadi adalah bahwa ekspresi, bahasa agama utamanya tentang Tuhan sering menggambarkan perbedaan di antara agama-agama. Terjadi perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya. Klaim kebenaran yang bersifat subjektif sering berakibat adanya ketegangan antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya. Hal kedua yang lahir dari apa yang disampaikan oleh Thomas Aquinas adalah bahwa prinsip-prinsip keagamaan, termasuk di dalamnya ekspresi keagamaan yang tecermin di dalam pola pikir dan 422 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 sikap seorang teolog berpijak dari pemahaman tekstualnya terhadap wahyu. Apa yang melandasi pola pikir, prinsip-prinsip keagamaannya adalah wahyu. Jikalau seseorang mempergunakan akal atau ilmu dalam melandasi prinsip-prinsipnya, maka hal itu tidak lebih dari upaya untuk merasionalisasi prinsip-prinsip dan pemikiran keagamaannya. Sebagaimana dikatakan Thomas Aquinas di atas, seorang teolog mempertimbangkan objek kajiannya dengan pendekatan dalil teks suci (wahyu). Jika dihadapkan pada suatu permasalahan, para teolog langsung merujuk dan mencari jawabannya kepada wahyu. Bagaikan kamus populer, para teolog menjadikan wahyu (kitab suci) sebagai the key of answer. Akan tetapi manakala wahyu dirasa belum begitu cukup untuk menjawab permasalahan tersebut, kaum teolog akan memakai dalil akalnya untuk menguatkan dalil wahyu tersebut.15 Dalam teologi, khususnya ketika merespons firman atau teks wahyu, sebenarnya terdapat kecenderungan stagnasi di antara teolog. Sebetulnya kalau dikaji lebih jauh mengenai apa yang pernah disampaikan oleh filsuf Perancis Maurice Blondel, sebagaimana dikutip Amtsal Bahtiar, pernah menyatakan bahwa apa yang menjiwai teologi (dan sikap keagamaan teolognya) adalah tindakan percaya. Teologi sebagai ilmu iman betitik tolak atas kepercayaan akan wahyu Allah yang khusus. Karena berangkat dari iman, maka penekanan kepercayaan without reserve senantiasa mengiringi pemahaman teolog terhadap kitab sucinya, hal mana sering mengakibatkan seorang teolog lebih berpegang teguh kepada teks suci daripada memberi penafsiran yang liberal atau berani dan bebas terhadap teks-teks suci tersebut. 15 Hal ini bisa bisa dilihat di dalam fenomena yang dialami oleh Thomas Aquinas ketika membuktikan adanya Tuhan. Thomas Aquinas mempergunakan lima macam argumen untuk menguatkan bahwa Tuhan itu ada. Argumen tersebut antara lain argumen gerak, argumen sebab, argumen kemungkinan dan keharusan, argumen keteraturan alam, dan argumen tingkatan. Semua argumen tersebut merupakan argumen yang berangkat dari rasio akal. Untuk uraian lebih luas mengenai isi argumen tersebut. Lihat Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati sejak Thales sampai James, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 86. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 423 Dalam tradisi pemikiran teologi Islam, tercatat bahwa golongan Asy’ariyah terkenal sebagai golongan yang berpegang teguh kepada teks kitab suci. Tidak terlalu liberal menafsirkan teks-teks kitab suci. Sementara itu golongan Mu’tazilah terkenal sebagai golongan liberal dan cukup rasional dalam menafsirkan teks-teks wahyu. Dari fakta yang kecil ini, jika diperhatikan khususnya dalam hal inovasi pemikiran, peluang terjadinya stagnasi peran rasio akan terjadi pada golongan Asy’ariyah. Terlalu berpegang kepada wahyu secara ortodoks dapat menyebabkan seseorang mengalami stagnasi dalam kreatifitas pemikirannya. Agama dalam Tradisi Pemikiran Teolog Teologi sebagai ilmu iman, yang mengadakan pemikiran atas Tuhan dan sebagai upaya metodis untuk menafsirkan wahyu ilahi, keberadaannya bukanlah tanpa mengundang permasalahan bagi eksistensi hubungan antar agama maupun antarkomponen internal (misalnya aliran keagamaan) di dalam suatu agama itu sendiri. Dalam tradisi pemikiran teologi, agama setidaknya akan dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai ganda. Hal yang pertama bahwa di dalamnya merupakan seperangkat ajaran yang terdapat di dalam wahyu yang bersifat metafisis, terkadang irrasional dan bersifat mengikat para teolog, dalam arti harus diimani oleh teolog itu sendiri. Misalnya, keberadaan mengenai Tuhan, janji-janji kebaikan akan fasilitas Tuhan bagi siapa yang bertakwa atau bahkan ancaman-ancaman akan hukuman bagi mereka yang ingkar, yang semua sangat metafisis dan irasional. Sedangkan di sisi lain, menjadi tanggung jawab bagi para teolog untuk menyampaikan ajaran wahyu tersebut dengan artikulasi yang rasional. Bagaimana sebenarnya wajah agama dalam tradisi pemikiran teologi tersebut? Hal yang sangat mendasar adalah bahwa teologi akan melahirkan seorang teolog, yang menjelaskan atau memberikan tafsiran atau gambaran tentang Tuhan serta memberikan tafsiran-tafsiran rasional, meski terkadang ukuran rasional itu sifatnya relatif, hanya bagi kalangannya sendiri dan belum tentu terkesan rasional bagi orang lain, 424 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 atas firman Tuhan di dalam kitab sucinya. Persoalan yang sering muncul adalah bahwa bahasa agama yang merupakan cerminan dari tafsiran atau gambaran eksistensi metafisik itu terkadang menjadi embrio relativisme dan parsialisme kebenaran yang pada gilirannya sering mengundang konflik hubungan agama. Eksistensi metafisisk misalnya Tuhan, maupun pesan-pesan fiirman Tuhan yang juga bersifat metafisis, merupakan eksistensi yang transenden dan terlalu abstrak untuk ditafsirkan dan bahkan digambarkan dalam empirisme kemanusiaan manusia. Kekuatan akal manusia terlalu kecil untuk dapat menghadirkan gambaran Tuhan beserta pesan-pesannya yang sakral dalam kehidupan profan kemanusiaan.16 Inilah kemudian yang mengakibatkan adanya perbedaan penngambaran tentang eksistensi metafisik yang mau tidak mau hal ini akan berpengaruh pada ekspresi keagamaan manusia. Satu Tuhan ditafsirkan atau dibahasakan dalam banyak nama. Satu eksistensi digambarkan dalam banyak perwujudan. Dalam sejarah keagamaan manusia, relativisme bahasa keagamaan manusia terkadang sering menyebabkan konflik antaragama, atau bahkan konflik di dalam internal agama itu sendiri misalnya konflik antaraliran atau sekte dalam satu agama. Fanatisme bahasa agama terkadang menyebabkan seseorang hanya membenarkan ungkapan tentang Tuhan menurut versinya sendiri, sedangkan ungkapan bahasa tentang Tuhan orang lain adalah salah. Contoh kasus yang kecil barangkali adalah bahwa ungkapan ketuhanan dalam agama Kristen 16 Komaruddin Hidayat setidaknya mengklasifikasikan tiga macam bahasa agama. Pertama, ungkapan untuk menjelaskan objek yang bersifat metafisik. Kedua, bahasa kitab suci. Ketiga, bahasa ritual. Bahasa dalam kategori pertama memiliki keterkaitan tersendiri dengan pembahasan di atas. Bahasa dalam kategori pertama menurut Komaruddin digunakan untuk menjelaskan objek yang bersifat metafisikal, terutama tentang Tuhan. Persoalan pokoknya adalah mampukah akal dan bahasa manusia membuat deskripsi dan atribusi yang tepat mengenai Tuhan. Bukankah sejauh-jauh manusia berpikir dan berbahasa tetap di dalam kurungan wilayah pengalaman empiris dan inderawi. Jika pandangan ini diterima, maka Tuhan yang Maha Gaib dan berada di luar jangkauan nalar dan bahasa manusia tidak mungkin diungkapkan dengan bahasa manusia. Lebih lanjut Lihat Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, ( Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 6. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 425 yang tergambarkan di dalam bingkai trinitas sering kali mengganggu perasaan keagamaan orang islam. Yang sering terjadi adalah bahwa orang Islam mengklaim bahwa agama Kristen bukanlah agama monoteis akan tetapi penuh dengan syirik dikarenakan menggambarkan Tuhan itu dalam tiga person. Contoh lainnya adalah di dalam agama Islam sendiri, dimana terdapat perbedaan di dalam mengkonsepsikan Tuhan antara aliran Mu’tazilah dengan aliran Asy’ariyah. Sebagai aliran rasional dalam Islam, Mu’tazilah menolak manakala Tuhan itu dikonsepsikan dengan sifat-sifat tertentu, dengan alasan bahwa hal itu akan membawa pemahaman umat Islam kepada syirik. Sedangkan aliran Asy’ariyah sebagai aliran tradisional menganggap bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan syirik karena mengkonsepsikan Tuhan dengan sifat-sifat tertentu.17 Problem teologi khususnya dalam hal describing of God juga pernah disampaikan oleh filsuf Frithjof Schuon. Pertama-tama dia mengkritik kelemahan para teolog yang telah menggambarkan eksistensi yang tinggi dan tak terjangkau. Menurut Schuon, misteri yang tidak terselami (God) yang diajukan oleh para ahli teologi kadang-kadang tidak 17 Jelasnya, menurut Harun Nasution, Mu’tazilah mencoba menyelesaikan persoalan ini (Tuhan bersifat atau tidak) dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Definisi mereka tentang Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan al-Asy’ari, bersifat negatif. Tuhan tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai hajat dan sebagainya. Ini tidak berarti bahwa Tuhan bagi mereka tidak mengetahui, tidak bekuasa, tidak hidup dan sebagainya. Tuhan tetap mengetahui, berkuasa dan sebagainya, tetapi mengetahui, berkuasa dan sebagainya bukanlah sifat dalam arti sebenarnya. Arti “Tuhan mengetahui”, kata Abu al-Huzail, ialah Tuhan mengetahui dengan perantara pengetahuan dan pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Sedangkan dari kalangan Asy’ariyah, menurut al-Baghdadi, terdapat konsensus bahwa daya, pengetahuan, hayat, kemauan, pendengaran, penglihatan, dan sabda Tuhan adalah kekal. Sifat-sifat ini, kata al-Ghazali, tidaklah sama dengan esensi Tuhan, tetapi berwujud dalam esensi itu sendiri. Uraian-uaian ini juga membawa paham banyak yang kekal, dan untuk mengatasinya kaum Asy’ariyah mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah Tuhan tetapi tidak pula lain dari Tuhan. Karena sifat-sifat tidak lain dari Tuhan, adanya sifat-sifat tidak membawa kepada paham banyak yang kekal. Lebih jauh Lihat Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 135-136. 426 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 lebih dari perwujudan kekurangmampuan metafisika mereka, atau jika tidak demikian mereka mengacu kepada subjektifitas ilahi yang sama sekali tidak dapat diselami. Hal ini sama mustahilnya dengan mengobjektifkan dan memisahkan indera pemikiran dengan memerintahkan mata melihat saraf optik, tetapi kemustahilan mata untuk melihat saraf optik suatu saat tidak misterius. Menurut Schuon, sering sekali tesis tentang “misteri” hanya merupakan suatu penegasan tidak beralasan yang digunakan untuk menutupi kontradiksi teologi atau dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi.18 Dalam kerangka wacana ini, Schuon nampaknya kurang begitu meyakini otentisitas gambaran tentang supreme being yang digambarkan oleh para ahli teologi dalam setiap agama. Kritik kedua dari Frithjof Schuon dalam hal ini adalah terhadap prototipe paradigma teologi yang berkecenderungan untuk menyederhanakan sesuatu yang tak dapat digambarkan sebagaimana di atas. Hal ini menurut Frithjof bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara sublimisme mereka (para teolog) yang berkecenderungan kuat pada penyederhanaan dengan gagasan tentang maya pada tingkat keilahian atau gagasan tentang relativitas ilahi.19 Dalam hal ini, bisa dimaklumi manakala prototipe berpikir yang ditempuh oleh para teolog adalah penyederhanaan eksistensi. Akal dan rasio teolog memang tidak akan pernah mampu untuk menggambarkan secara pasti akan eksistensi supreme being yang bersifat metafisis. Sedangkan kritik ketiga dari Schuon terhadap teologi, sebagai akumulasi dari dua kritik di atas, adalah menganggap bahwa jalan berpikir kaum teolog adalah jalan berpikir yang salah. Teologi dengan membiarkan dirinya manampung pertentangan karena menjadi metafisika sentimental, dianggap telah membelokkan jalur yang lurus. Karena tidak peduli terhadap perbedaan aspek-aspek dan sudut-sudut pandang terhadap sesuatu, teologi harus bekerja atas dasar data-data yang kaku, yang pemecahannya hanya dapat dilakukan dengan jalan menyingkirkan kekakuan 18 19 Frithjof Schuon, Islam dan Filsafat Perennial, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 48. Schuon, Islam dan Filsafat, hlm. 48. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 427 palsu itu. Cara kerjanya didasarkan atas pandangan sentimental, dan ini digambarkan sebagai “pemikiran yang salah”.20 Kritik Schuon kepada teologi yang dianggap telah membelokkan jalur atau jalan yang lurus tersebut dapatlah dipahami bahwa betapa paradigma penyederhanaan—akan sesuatu yang besar dan sulit untuk digambarkan, sehingga yang lahir adalah gambaran metafisik yang sentimental dan bahkan emosional tersebut—dapat menyesatkan manusia. Berdasarkan hal itu, maka otentisitas gambaran tentang keilahian atau wujud supreme being itu patut diragukan. Selanjutnya, gambaran metafisika yang dilahirkan oleh teologi tersebut terkadang bersifat kaku dan ekslusif serta kurang bisa menerima perbedaan, merupakan salah satu pola pikir teologi yang patut disalahkan. Akan tetapi, belum ditemukan apa solusi dari Schuon dalam menghadapi dilemma paradigma tersebut. Barangkali dalam bingkai pluralisme, Schuon hanya ingin membuka cakrawala berpikir para teolog yang cenderung sentimentil, kaku, dan ekslusif, untuk dibawa kepada pemahaman yang inklusif dan pluralis. Dengan demikian, dalam tradisi pemikiran teologi sebenarnya terdapat problem yang besar dan menganga. Relativitas yang terekspresikan dalam keragaman pada satu sisi sering tampil indah dan menyenangkan, akan tetapi pada sisi lain—dan ini yang sering menonjol—akan menjadi ancaman yang serius. Terdapat banyak nama tentang Tuhan. Ada Allah, Yahweh, Brahman, dan sebagainya. Lantas Tuhan mana yang benar-benar Tuhan. Pada ahirnya barangkali akan lebih bijak kalau semuanya dikembalikan kepada sebuah wisdom yang mengatakan bahwa nama-nama tersebut hanya merupakan sarana belaka untuk sampai atau mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Pengakuan keberagamaan yang baik dalam hal ketuhanan ini adalah tidak semata-mata terhenti pada konsepsi-konsepsi formal teologi tersebut, akan tetapi lebih jauh lagi merambah pada tataran esensi yang berada di luar konsepsi-konsepsi formal tersebut. Pengakuan 20 Schuon, Islam dan Filsafat, hlm. 48. 428 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 ketuhanan yang hanya sampai pada tataran konsepsi-konsepsi formal teologi tersebut akan mengakibatkan suatu syirik, karena konsepsikonsepsi tersebut—meminjam istilah Schuon di atas—hanya merupakan penyederhanaan, bahkan bagi penulis merupakan penyempitan dan bukan yang sesungguhnya dari realitas asli Yang Sakral, Maha Tinggi, Maha Agung, dan Maha Sempurna. Terlepas dari persoalan bahasa agama di atas, persoalan lain yang dapat ditemukan dalam bahasan agama dalam tradisi pemikiran teologi adalah klaim-klaim kebenaran dan atau rasionalisme yang subjektif. Di setiap agama apapun di dunia ini akan ditemukan upayaupaya teolog yang gigih menyampaikan firman Tuhannya dengan tingkat rasionalitas tertentu. Pada waktu-waktu tertentu, kita dapat menyaksikan di layar kaca televisi, acara mimbar agama tertentu dengan tema-tema menarik serta dengan tokoh agama yang berpenampilan menarik pula. Dengan gigihnya seorang ulama, pastor ataupun biksu menjelaskan ajaran agamanya kepada penonton, dimana penjelasan-penjelasan tersebut terkadang juga disertai dengan penonjolan, pengagungan serta klaim kebenaran agama sendiri. Akan tetapi, jarang kita menemukan tafsiran mereka yang benar-benar rasional dan independen. Tafsiran rasional seorang teolog terhadap kitab sucinya sebetulnya hanya untuk keperluan penguatan kebenaran kitab sucinya—kalau tidak boleh dikata sebagai rasional subjektif yakni rasional hanya menurut ukuran sang teolog tersebut, yang bagi teologteolog lainnya barangkali bisa jadi sangat tidak rasional dan mengadaada. Mereka (teolog) mencoba menafsirkan dengan rasio dan menganggap bahwa tafsirannya tersebut rasional, padahal ending-nya tetap menguatkan atau bahkan tetap kembali kepada wahyu. Hal ini yang kemudian oleh Komaruddin Hidayat disebut sebagai perilaku dengan standar ganda dalam memahami kitab suci. Dalam memahami kitab suci, seseorang cenderung menggunakan standar ganda, yaitu berpikir dalam kapasitas dan berdasarkan pengalaman kemanusiaan namun diarahkan untuk suatu objek yang diimani yang berada di luar jangkauan nalar dan inderanya. Dengan ungkapan Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 429 lain dia berpikir dalam kerangka iman, dan dia beriman sambil mencoba mencari dukungan dari pemikirannya. Pada kondisi ini pula menurut Komaruddin terdapat wilayah remang-remang. Dikatakan remang-remang karena dalam sikap “beriman” terdapat hal-hal yang diyakini kebenarannya namun tidak diketahui dan tidak terjangkau oleh nalar. Maka dari kondisi seperti ini lahirlah apa yang kemudian dikenal dengan istilah “ilmu kalam”. Menurut Komaruddin, kata “ilmu” mengisyaratkan adanya aktivitas penalaran, sedangkan “kalam” atau firman Tuhan menunjukkan bahwa objek yang dikajinya berkaitan langsung dengan sifat dan aktivitas Tuhan yang tak terjangkau oleh nalar. Oleh karenanya tidak salah jika dikatakan bahwa ilmu kalam merupakan “nalar yang beriman” atau “iman yang bernalar”, yaitu penalaran tentang Firman Tuhan dalam rangka melayani iman atau beriman kepada Tuhan berdasarkan pertimbangan yang logis. Sehingga, dalam bingkai teologi, meskipun nalar telah berusaha memahami dan menafsirkan Firman Tuhan secara logis, pada ujungnya para teolog akan pasrah pada keputusan imannya ketika dihadapkan pada firman Tuhan yang sulit dicerna oleh akal.21 Jika tradisi pemikiran teologi mempunyai visi dan misi rasionalisasi agama, adakah rasionalitas sesungguhnya dalam agama itu? Kiranya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menantang para teolog. Bukankah dari awal teologi telah mengesankan dan menyisakan suatu pertanyaan fundamental yang penuh misteri yaitu adakah theos itu logis, atau dengan ungkapan lain adakah sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan yang metafisik itu logis atau rasional? Adakah hal itu hanya merupakan kebohongan kegamaan yang besar yang terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan di muka bumi? Sebetulnya sangat sulit bagi manusia-manusia pada umumnya untuk memercayai akan adanya Tuhan, apalagi eksistensi surga atau neraka atau mungkin kebangkitan kembali jasad-jasad manusia sesudah matinya di dunia. Akal manusia hanya mampu menangkap segala 21 Lebih lanjut lihat Hidayat, Memahami Bahasa, hlm. 6-7. 430 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 sesuatu yang rasional, empirik dan riil. Dalam kerangka pembahasan ini, kembali agama beserta teologi pernah kewalahan membendung arus sekulerisme. Di Barat, sebagai kelanjutan dari masa Renaisans dan humanisme, agama beserta teologi pernah kewalahan menghadapi pukulan sekulerisme bahkan ateisme. Rasionalitas manusia yang sudah sampai pada tahap yang tinggi, telah mengingkari realitas metafisika yang hal itu merupakan jantung dari agama dan pusaka teologi. Maka ketika realitas metafisika tersebut diingkari, agama telah terposisikan pada kondisi reduksionitas terendah, yang mengakibatkan konstruksi agama beserta teologi berada pada level terendah dan termarjinalkan dari benak manusia. Dus, fenomena yang sangat mengancam eksistensi agama adalah bahwa, sebagaimana fundamentalisme dan radikalisme beserta lainnya, sekulerisme bukan hanya tampil sebagai sebuah wacana, akan tetapi sekulerisme pernah menjadi sebuah ideologi pergerakan yang dapat memobilisasi gerakan untuk menentang dan bahkan menghancurkan agama. Ini yang pernah dikatakan oleh Bert F. Breiner, yakni sekulerisme menguasai otoritas lembaga-lembaga tertentu untuk upaya-upaya mengembangkan sayap sekulerismenya.22 Fakta keagamaan sering menunjukkan kepada kita betapa sikap para teolog sering tidak adil dalam menghadapi gejolak rasionalisme 22 Uraian lebih jelas disampaikan oleh Bert F. Breiner. Menurutnya, manifestasi paling jelas tentang marginalisasi kepercayaan agama adalah fenomena sekularisme. Sekulerisme di sini berarti suatu keyakinan bahwa dunia atau alam semesta dipahami tanpa mengacu pada realitas yang transenden, tak ada yang lain selainnya. Meski demikian, sekulerisme merupakan “pusat dunia”. Jika ia tidak menolak eksistensi Tuhan atau beberapa realitas transendental, secara efektif tidak menolak keterpautan antara yang transenden dengan realitas kehidupan di dunia ini. Sejumlah studi sosiologi dan sejarah mempresentasikan perkembangan Eropa Barat dalam term-term ini secara tepat. Pengkultusan akal pada akhir abad ke-18 dipandang sebagai upaya membangun pengkultusan terhadap kemanusiaan di atas kehancuran transendentalisme kuno. Di Prancis melahirkan positivisme yang mengontrol secara ketat terhadap sejumlah otoritas lokal, khususnya sekolah-sekolah pada 1870-an dan 1880-an, sering menggunakan kekerasan kekuatan untk menghancurkan para rahib dan biara. Lebih lengkap lihat Bert F. Breiner, “Persoalan-persoalan Agama Kontemporer di Eropa”, dalam Mukti Ali, dkk., Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 55-56. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 431 kemanusiaan. terkadang, dunia teologi dengan para teolognya terhanyut dalam arogansi sikap keagamaan. Represi keagamaan dengan mengklaim kafir atau barangkali tidak beragama dan murtad bagi mereka yang bertindak meragukan atau bahkan tidak percaya terhadap eksistensi-eksistensi metafisik dan ghaib tersebut. Mereka (para teolog) tidak berpikir bagaimana mengakomodasi gejolak rasionalisme itu sehingga hal itu dapat diletakkan dalam bingkainya yang jelas, atau bahkan hal itu dapat bermanfaat bagi dunia agama dan teologi. Hal yang sering terjadi adalah para teolog menganggap gejolak rasionalisme sebagai ancaman yang besar bagi agama. Dan dalam sejarah, hal inilah yang menjadi sebab dari timbulnya gap yang diteruskan dengan konfrontasi yang panjang antara akal dan wahyu (agama) atau ilmu dan iman. Itulah fenomena sosial keagamaan yang sering dijumpai baik dari level masyarakat bawah jauh di pedalaman maupun pada masyarakat modern. Yang diharapkan dari sikap keagamaan teolog adalah bagaimana gejolak rasionalisme yang terkesan mengancam visi transendentalisme agama itu bisa dihadapi dengan kedewasaan sikap keagamaan para teolog dan bukan malah terkesan menghancurkan gejolak tersebut. Jika para teolog terlalu sering memaksakan visi dan misi transcendental untuk membungkam gejolak rasionlisme manusia dengan klaim-klaim kafir, tidak beragama atau murtad, maka sebenarnya yang sering terjadi—untuk menyebut pasti terjadi dan sudah turun-temurun—adalah pemaksaan kebenaran atau rasional subjektif ajaran agama dari para teolog kepada umat sebagai pemeluk agama. Dalam upaya rasionalisasi ajaran agama kepada umat sebagai penganutnya, para teolog menggunakan dan mewajibkan suatu “password keyakinan” kepada umatnya, yaitu wajib mengimani, memercayai, dan menaati without reserve terlebih dahulu. Bagi teolog hal yang pertama kali harus dimiliki bagi penganut agama adalah sikap percaya dan bukan meragukan atau menyangkal. Bahkan dalam kondisi tertentu, rasionalisme dalam wujudnya yang sering meragukan eksistensieksistensi metafisik tersebut merupakan suatu keharaman. Memercayai atau mengimani terlebih dahulu baru berpikir kemudian dan 432 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 bukan berpikir dahulu baru percaya atau beriman adalah motto teologi. Akankah keberagamaan dengan motto demikian akan menjadi keimanan dengan kesadaran penuh full understanding? Tidakkah motto tersebut justru mengindikasikan adanya pemaksaan pada permulaannya? Terkadang patut juga untuk direnungkan bahwa keberagamaan manusia sebagian besarnya bisa jadi merupakan keberagamaan dengan keimanan yang semu dan munafik karena merupakan hasil paksaan dari kaum teolog. Hal ini karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu beragama dengan tanpa kesadaran yang penuh yang benar-benar berangkat dari kebebasan perenungan pikirannya dan ketinggian kontemplasinya untuk sampai kepada Tuhannya. Dengan demikian, konsep Tuhan beserta segala hal metafisik yang berkait dengan-Nya adalah murni berangkat dari pengalaman dan pemahamannya sehingga menjadilah ia sebagai keimanan yang murni. Keimanan bukan sebagai hasil pemaksaan dan intimidasi teologi yang munafik dan arogan. Kita barangkali jarang untuk berpikir mungkinkah terdapat seorang teolog yang hanya memberikan jalan keagamaan yang umum tanpa mengharuskan seseorang untuk memercayai dan memegangi fatwa-fatwa teologisnya baik untuk sebuah afiliasi keagamaan ataupun gambaran-gambaran tentang eksistensi metafisik? Terlalu sering ditemui bahwa seorang teolog menganggap orang-orang biasa merupakan sasaran misi teologisnya, menganggap mereka lemah dan perlu untuk diselamatkan dengan cara memasukkan mereka ke dalam lingkungan system teologis yang dia (teolog) miliki. Ini sebenarnya yang merupakan embrio inti dari terjadinya pemaksaan agama. Terdapat upayaupaya islamisasi, kristenisasi, dan lainnya, yang semua merupakan fakta yang menunjukkan masih terjadinya pemaksaaan teologis dalam agama. Padahal sesungguhnya tidak terdapat pemaksaan dalam hal afiliasi keberagama tersebut. Sebenarnya, dalam level-level perenungan tertentu, kita dapat berpikir mungkinkah terlahir kepercayaan, keyakinan serta kesadaran keagamaan secara benar-benar murni dari manusia itu sendiri. Manu- Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 433 sia benar-benar sadar dalam agamanya karena memang merupakan hasil perenungannya yang tinggi sebagai kontinuitas fitrah dan naluri kemanusiaan yang cenderung untuk beragama. Yang sering terjadi, dan ini yang barangkali telah menjadi tradisi sejarah kemanusiaan, adalah agama sebagai hasil turun-temurun. Mengikuti cara teologi, agama itu diwahyukan dan bukan dicari. Agama membentuk manusia dan bukan manusia membentuk keagamaannya sendiri. Seorang ayah bisa berfungsi sebagai seorang teolog bagi anak-anaknya untuk memperkenalkan dan mewajibkan atas anak-anaknya suatu keyakinan agama tertentu. Pada kondisi seperti ini tidak terlalu salah manakala kita menyebut adanya hierarkisasi agama dalam sejarah keberagamaan manusia. Agama itu diturunkan sebagai tradisi sejarah keagamaan manusia dan bukanlah agama itu merupakan hasil pencarian yang panjang dari manusia itu sendiri. Premis-premis semacam itu merupakan premis yang pantas diklaimkan kepada dunia teologi. Semuanya merupakan perenungan dalam bingkai agama dalam tradisi pemikiran teologi. Sebagai percikan wacana terahir dari bingkai agama dalam tradisi pemikiran teologi, terdapat satu fenomena yang keberadaannya sering mewarnai keagamaan manusia. Agama dalam tradisi pemikiran teologi terkadang sarat dengan nuansa apologetika dari para teolog. Seorang teolog yang menyampaikan kebenaran-kebenaran wahyu serta tentang ketuhanan dalam agamanya dengan memakai akal untuk memperkuat kebenaran-kebenaran tersebut terkadang terkesan tak lebih dari seorang apolog. Seorang teolog, layaknya apolog, senantiasa membenarkan agamanya serta akan senantiasa memberikan perlawanan atau counter terhadap pihak-pihak luar yang menyerang agamanya. Hal ini karena setiap agama memiliki teologi. Klaim kebenaran parsial di setiap agama (sebagai kondisi pertama) tidak jarang menyebabkan seorang teolog dari satu agama tergoda untuk mengkritik dan bahkan menyalahkan ajaran agama lain (sebagai kondisi kedua). Kaum teolog, yang berposisi di atas sebagai maker of paradigm dengan khotbahkhotbahnya telah berhasil membangun wacana yang banyak 434 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 memengaruhi umat pada level bawah. Sekali lagi, yang perlu dipahami dari bingkai pemikiran teologi keagamaan adalah adanya relativisme; kebenaran teologi bukanlah kebenaran dari Tuhan, tetapi hal itu hanya merupakan tafsiran serta respons seorang terhadap ajaran kitab sucinya yang hal itu tentu akan sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu atau setting historis teolog tersebut. Teologi bukanlah Tuhan dan teologi bukanlah agama. Teologi hanya tafsiran belaka dari keduanya. Maka sebenarnya teologi beserta teolog dan tafsirannya adalah suatu kerelativan belaka, sedangkan kebenaran tertinggi hanya dari Tuhan saja. Hal ini yang oleh Nurcholis Madjid dinyatakan sebagai wewenang menetapkan hukum itu hanya pada Tuhan sedangkan apa-apa yang merupakan tafsiran manusia (teologi) adalah suatu yang relatif.23 Dekonstruksi Pemikiran Teologi Telah dipaparkan di atas bahwa agama dalam kungkungan teologi tidak jarang akan lahir sebagai agama dengan wajah subjektivisme, rasionalitas yang sering semu, sarat dengan klaim kebenaran parsial, ortodoksi, dan bahkan apologi. Terdapat dua problem fundamental agama dalam kungkungan pemikiran teologi dapat diklasifikasi ke dalam dua hal, secara internal dan eksternal. Pertama, secara internal dapat dinyatakan bahwa teologi terkadang memformulasi wacana atau kajian agama hanya pada wacana-wacana yang melangit atau metafisik 23 Nurcholish Madjid pernah menyatakan bahwa pandangan seseorang mengenai suatu agama tertentu diakui oleh yang bersangkutan sebagai yang paling tepat dan paling benar mengenai agama itu. Tetapi sebagai entitas mengenai entitas yang lain, masuk akal (absurd) untuk melihat kedua-duanya sebagai identik dan bisa saling tukar (interchangable). Jadi pemahaman seseorang atau kelompok tentang suatu agama bukanlah dengan sendirinya senilai dengan agama itu sendiri. Ini lebih-lebih lagi benar jika suatu agama diyakini hanya datang dari Tuhan (wahyu “agama samawi”) dan bukannya hasil akhir suatu proses historis dan sosiologis (dengan istilah “agama wahyu” atau “agama samawi”), maka wewenang menetapkan agama atau tasyri’ (seharusnya) hanya ada pada Tuhan atau berasal “dari langit”, sementara yang datang dari manusia atau dari arah bumi (juga seharusnya) dipandang sebagai relatif belaka. Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Menuju Tuhan, ( Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 242. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 435 yang tidak cukup aktual, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan jaman. Kedua, secara eksternal, agama dalam wajah-wajahnya yang subjektif, parsialis, apologis, dan ortodoks, sering menciptakan ketersekatan umat dengan wajah ekslusivismenya yang pada ending-nya tidak jarang menyebabkan konflik horisontal antarpemeluk agama atau perang urat syaraf para teolog dari berbagai agama. Pada hal yang pertama, yakni tinjauan internal, sebenarnya telah lama terjadi keluhan terhadap pemikiran dan wacana teologi—sering disebut juga sebagai teologi skolastik—dalam arti menampilkan wacana-wacana metafisik dan terkesan melangit, misalnya tentang Tuhan, sifat-Nya, hubungan-Nya dengan alam semesta. Dalam banyak hal sebenarnya keluhan itu berisi tentang tidak kontekstualnya atau bahkan tidak relevannya lagi pembahasan atau wacana-wacana teologi yang demikian itu. Munculnya upaya-upaya pembumian agama— yang kalau ditilik lebih jauh sebenarnya merupakan upaya pembumian teologi dari teologi langit ke teologi bumi, dan slogan yang sering dimunculkan misalnya, slogan-slogan teologi sosial, teologi transformasi, teologi keadilan, dan sebagainya. Hal itu semua sebetulnya merupakan ekspresi dari geliat kemanusiaan dalam upayanya untuk mengkontekstualisasikan teologi, dalam arti bagaimana bahasan atau wacana teologi lebih memerhatikan kebutuhan yang sedang berkembang, atau dengan kata lain akomodatif terhadap tuntutan zaman. Teologi pada saat ini lebih ditekankan kepada bagaimana bahasan, wacana, dan solusi teologi atas kemiskinan, ketidakadilan sosial, ketidakadilan gender dan sebagainya. Teologi tidak lagi terlalu terfokus terus-menerus pada pembahasan apa, siapa, di mana dan bagaimana Tuhan (meski itu semua tidak sepenuhnya harus dinafikan dari benak manusia). Sekilas, upaya-upaya yang berkenaan dengan pembumian teologi di atas terkesan positif, utamanya untuk menancapkan lebih dalam spiritualitas agama dalam kehidupan sosial, di dalam setiap dimensinya. Di dalam Islam, barangkali upaya-upaya seperti itu lebih menunjukkan intensitasnya yang tinggi. Banyak kasus yang sebenarnya 436 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 menarik untuk dikaji dalam fenomena agama Islam dalam kaitannya dengan pembumian teologi. Adanya teori politik Islam, ekonomi Islam, sains Islam, atau yang sering diklaim sebagai islamisasi ilmu, merupakan upaya-upaya yang berkenaan dengan hal di atas. Dalam kaitan ini, slogan-slogan serta indikasi-indikasi menguatnya proses agamaisasi setiap dimensi kehidupan sosial sebenarnya bisa ditilik dari dua tujuan. Pertama, sebagai upaya spiritualisasi agama bagi setiap dimensi kehidupan sosial. Kedua, selanjutnya hal itu merupakan upaya untuk membendung sekulerisme, yakni agama-agama akan termarjinalkan dan ditinggalkan oleh penganutnya karena dimensidimensi sosial manusia yang lain selain agama lebih memberikan daya tarik bagi manusia ditimbang agama. Dari tilikan atas dua tujuan tersebut, dapat disaksikan bahwa teologi dan teolog kontemporer sering mengkamuflase atau mengubah bentuknya dalam wajah fundamentalisme agama. Tentu istilah fundamentalisme agama di sini bukanlah dimaksudkan sebagai sebuah gerakan dalam Kristen Protestan di Amerika Serikat yang muncul pada pasca-Perang Dunia I, yang sarat dengan militansi tinggi, fanatisme, ekstremisme, dan radikalisme. Tetapi istilah fundamentalisme agama di sini lebih mengacu kepada semangat dan prototipe keagamaan fundamentalisme tersebut, yang cenderung untuk merealisasikan ajaran kitab suci ke dalam setiap dimensi kehidupan sosial.24 Upaya spiritualisasi agama ke dalam setiap dimensi kehidupan sosial manusia bisa dilihat dari adanya upaya-upaya agamisasi semua dimensi kehidupan sosial tersebut. Para teolog modern merasa khawatir kalau-kalau setiap dimensi kehidupan sosial manusia dijalankan terlepas dari nilai-nilai agama sebagaimana yang terdapat di dalam kitab sucinya. Indikasi yang paling sederhana dapat dilihat pada kasus upaya islamisasi ideologi negara oleh sebagian pemikir Muslim Indonesia. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menimbang 24 Lebih lanjut lihat M. Dawam Raharjo, “Fundamentalisme”, dan Yusril Ihza Mahendra, “Fundamentalisme: Faktor dan Masa Depannya”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, ( Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 34. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 437 apakah hal itu benar atau salah, perlu atau tidak, akan tetapi dalam kerangka kajian ini, hal itu dipandang sebagai bagian kecil dari indikasi adanya islamisasi atau pembumian teologi Islam modern ke dalam dimensi kehidupan politik masyarakat. Pada hal yang kedua, yakni faktor eksternal. Masih terdapat satu hal lagi yang menyangkut problem agama dalam kungkungan teologi sehingga menyebabkan perlunya dekonstruksi teologi, yakni agama dalam wajahnya yang subjektif, parsialis, apologis, dan ortodoks sebagai akibat dari ulah teologi, sering kali menyebabkan ketersekatan umat. M. Amin Abdullah dalam kaitan dengan hal ini menyampaikan: Bahwa hampir semua pengamatan sosial keagamaan sepakat bahwa pemikiran teologi sering kali membawa ke arah ketersekatan umat. Ketersekatan dan keterkotak-kotakan yang tidak dapat terhindarkan barangkali. Ibarat konsep “manusia” yang bersifat universal, kemudian tersekat oleh berbagai “bahasa” dan “warna kulit”. Suatu ketersekatan yang tidak dapat terhindarkan secara historis…. Teologi sebagaimana kita ketahui, tidak bisa tidak pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku—bukan sebagai pengamat—adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis.25 Apa yang disampaikan oleh M. Amin Abdullah di atas barangkali relevan dengan banyak fakta yang terjadi pada saat-saat ini. Dari faktafakta di atas, kecenderungan berpikir teologis terkadang banyak mengundang permasalahan. Karena merupakan refleksi atas Tuhan dan kitab suci, yang jelas hal ini akan memberi peluang yang besar bagi terjadinya perbedaan-perbedaan fundamental agama, dapat menjadi pemicu perbedaan teologi antaragama bahkan di dalam internal agama itu sendiri yang pada gilirannya menyebabkan perpecahan di antara komponen-komponen tersebut. Sementara pembumian teologi sebagai upaya aktualisasi dan kontekstualisasi teologi dalam era modern agar dapat memberikan sumbangan pada masyarakat modern, 25 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 13. 438 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 sering menyebabkan semangat baru mirip seperti fundamentalisme yang hal ini juga dapat memicu ketegangan hubungan antaragama. Sebelum mencarikan solusi atas permasalahan di atas, kaitannya dengan upaya dekonstruksi pemikiran teologi di atas, maka di sini akan dipaparkan terlebih dahulu corak pemikiran teologis yang bisa jadi menyebabkan teologi dewasa ini sering mengundang permasalahan. M. Amin pernah menyampaikan corak pemikiran teologis secara umum, sebagaimana yang dikatakannya: Setidaknya ada dua ciri yang menonjol dari corak pemikiran teologis. Pertama, pemikiran teologis diwarai oleh tingkat “personal commitment” (kesetiaan pribadi) yang sangat peka terhadap ajaran agama yang dipeluk seorang. Agama adalah persoalan hidup dan mati (ultimate concern) yang tidak dapat dengan mudah diganti, diubah seperti layaknya orang memakai dan mengganti baju. Pemeluk agama tertentu akan mempertahankan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya dengan gigih, sehingga bersedia untuk berkorban habis-habisan jika diperlukan. Agama menuntut keikutsertaan dan kesetiaan menyeluruh (totalistis) dari segenap pengikutnya… Bahasa yang dipergunakan oleh pemeluk agama adalah bahasa seorang “pelaku” atau “pemain” (aktor) dan bukannya bahasa seorang pengamat atau lebih-lebih bukan bahasa seorang peneliti yang datang dari luar (spectator) dengan begitu, seorang agamawan selalu involved (terlibat penuh) secara utuh dan total.26 M. Amin Abdullah di dalam memandang teologi, dalam kaitannya dengan upaya-upaya dekonstruksi pemikiran teologi, lebih menitikberatkan kepada prototipe pemikiran ala teologi terhadap agama. Kecenderungan involve atau terlibat dari pemikiran dan sikap teologi, lebih khusus adalah teolognya, mengakibatkan seorang teolog kurang memerhatikan kondisi luar dalam arti pemikiran lain di luar bingkai agama dan teologinya. Rasa kesetiaan pribadi yang parsial, menerima kebenaran parsial dan afiliasi pemikiran dan sikap keberagamaan yang parsial juga. Semua ini menyebabkan seorang teolog menjatuhkan pemihakannya kepada agamanya secara parsial dan bukannya kepada 26 M. Amin Abdullah “Teologi dan Filsafat dalam Perspektif Globalisasi Ilmu dan Budaya”, dalam Mukti Ali, dkk. (ed.), Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 271. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 439 kebenaran yang universal. Kesetiaan pribadi yang parsial mengakibatkan seorang teolog hanya setia kepada agamanya sendiri, tidak menjatuhkan kesetiaannya hanya kepada kebenaran, apa pun wujud dan darimana datangnya kebenaran tersebut. Kebenaran yang ia tanamkan di dalam benaknya kiranya hanya merupakan kebenaran parsial di dalam bingkai agama atau teologinya sendiri dan tidak memandang kebenaran universal, sehingga terkadang kurang mengakui kebenaran agama lain meskipun dalam pandangan rasionya di dalam agama atau teologi lain tersebut terdapat kebenaran. Dan yang pasti afiliasi pemikiran dan sikap keagamaannya adalah pada agama dan teologinya sendiri. Maka sebagai akibat dari hal ini semua adalah kecenderungan ekslusivisme kebenaran agama.27 Dan dalam sejarah keagamaan manusia, ekslusivisme kebenaran agama dalam banyak hal sering melahirkan ekspresi pemikiran dalam bentuk aksi-aksi maupun gerakan-gerakan yang mengancam masa depan agama-agama manusia itu sendiri, baik dalam wujud ekstremisme maupun radikalisme. Dari mempelajari corak pemikiran teologi beserta efek-efek yang sering ditimbulkannya tersebut, maka dalam ikhtiar yang sederhana kiranya dapatlah dijadikan pembuka wacana bagi upaya dekonstruksi teologi, bahwa pemikiran dan sikap teologi yang tecermin di dalam performance teolognya (yakni dengan kecenderungan kepada fanatisme, menjatuhkan kesetiaannya kepada kesetiaan parsial agama dan teologinya dan bukan kesetiaan universal, menerima kebenaran parsial agama dan teologinya dan bukan kebenaran universal serta memberikan afiliasinya hanya kepada agama serta sistem teologinya sendiri tanpa melihat pada kebenaran lain di luar agama dan teologinya sendiri), semua telah melahirkan ekslusivisme kebenaran agama, semua meru27 Nurcholiish Madjid mendefinisikan ekslusivisme kebenaran keagamaan sebagai suatu pandangan yang menganggap bahwa kebenaran agama (dan sistem teologi) itu hanya terdapat di dalam agamanya sendiri dan menganggap bahwa agama (dan sistem teologi) lain adalah salah dan bahkan menyesatkan. Nurcholish Madjid, “Pengantar”, dalam Tiga Agama Satu Tuhan, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. xix. 440 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 pakan pemikiran teologi yang perlu untuk didekonstruksi. Sebagai klarifikasi, yang dimaksud dekonstruksi teologi lebih mengacu kepada pergumulan teologi dengan kondisi-kondisi eksternal, dan bukan pada tataran internal. Pada pergumulan dengan kondisi eksternal dimana di dalamnya tercakup bagaimana hubungan antaragama satu dengan lainnya, demikian pula bagaimana hubungan antara satu teologi dengan teologi lainnya. Dalam pergumulannya dengan kondisi eksternal semacam ini, pola pemikiran serta sikap teologis para teolog wajib untuk ditanggalkan. Hal itu karena merupakan wilayah yang rawan konflik yang dapat mengancam eksistensi sebuah agama dan teologi secara keseluruhan. Dalam kondisi eksternal semacam ini, seorang teolog kiranya harus mampu berpikir dan bersikap inklusif dan pluralis.28 Sedangkan pada tataran internal, performance yang tergambar di dalam pemikiran serta sikap teolog di atas, kiranya masih perlu untuk dilestarikan. Hal ini karena pemikiran serta sikap-sikap teologi yang demikian itu dapat dikatakan sebagai jantung daripada agama, dalam arti bahwa tanpa pola pikir serta sikap-sikap keagamaan seperti itu, mustahil eksistensi sebuah agama akan dapat dipertahankan, utamanya dalam menghadapi goncangan-goncangan dari luar atau tantangantantangan jaman. Dekonstruksi internal sebuah teologi hendaknya diarahkan kepada bagaimana sebuah sistem teologi lebih memfokuskan diri terhadap solusi-solusi konkret atas permasalahan-permasalahan kontemporer zaman, seperti slogan pembumian agama atau pembumian teologi dengan memerhatikan pertimbangan proporsionalisme, yakni memahami ruang dan tempat gerak. Dengan pertimbangan ini, prebumisasi agama atau prebumisasi teologi tidak menimbulkan permasalahan baru seperti penindasan agama atau penindasan oleh teologi dalam wujudnya yang baru. 28 Madjid, “Pengantar”, hlm. xix. Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 441 Penutup Agama merupakan seperangkat konsep-konsep ajaran dan doktrin yang telah diciptakan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Agama dipenuhi oleh relativitas teologi yang mau tidak mau hal itu akan memengaruhi gerak langkah keberagamaan manusia. Teologi akan senantiasa menghegemoni agama, mengatur agama, dan menentukan corak agama. Bagaimana wajah agama yang akan tampil ke panggung sejarah kemanusiaan, tanyakan semua kepada corak teologinya. 442 | Media Akademika Volume 25, No. 4, Oktober 2010 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996). Abdullah, M. Amin, “Teologi dan Filsafat dalam Perspektif Globalisasi Ilmu dan Budaya”, dalam Mukti Ali, dkk. (ed.), Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, ( Jakarta, Tiara Wacana, 1997). Tafsir, Ahmad, Filsafat Umum: Akal dan Hati sejak Thales sampai James, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997). Al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Kairo: Dar al-Irsyad, 1991). Bowker, John, The Oxford Dictionary of Word Religion, (Amerika: Oxford University Press, 1995). Breiner, Bert F, “Persoalan-persoalan Agama Kontemporer di Eropa”, dalam Mukti Ali, dkk. (ed.), Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, ( Jakarta: Tiara Wacana, 1997). Copleston S.J., Frederick, History of Philosophy Medieval Philosophy, (New York, Image Book, 1962). Esposito, John L. (ed.), The Oxford Encyclopedia of The Modern Word, (USA: Oxford University Press, 1995). Glasse, Cyril, The Concise Encyclopaedia of Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika, ( Jakarta: Paramadina, 1996). Hidayat, Komaruddin, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, ( Jakarta: Paramadina, 1998). Hinnels, John R. (ed.), Dictionary of Religions, (Kanada: Penguin Books Press, 1995). Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1996). Madjid, Nurcholish, Pintu-pintu Menuju Tuhan, ( Jakarta: Paramadina, 1996). Madjid, Nurcholish, “Pengantar”, dalam Tiga Agama Satu Tuhan, Badarus Syamsi, “Wajah Agama dalam Hegemoni Teologi” | 443 (Bandung: Mizan, 1999). Mahendra, Yusril Ihza, “Fundamentalisme: Faktor dan Masa Depannya” dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, (Paramadina: Jakarta, 1996). Nasution, Harun, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan, ( Jakarta: UI Press, 1986). O’Collins S.J., Gerald, & Edward G. Forugia (ed.), Kamus Teologi, (Yogyakarta, Kanisius, 1996). Raharjo, M. Dawam, “Fundamentalisme”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, ( Jakarta: Paramadina, 1996). Roese, William L. (ed.), Dictionary of Philosophy and Religion, (New York: Humanities Press, 1996). Schuon, Fritchof, Islam dan Filsafat Perennial, (Bandung: Mizan, 1994). Tamara, M. Nasir, “Pengantar”, dalam M. Nasir Tamara & Elza Peldi Tahar (ed.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, ( Jakarta: Paramadina, 1996).