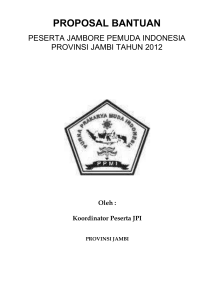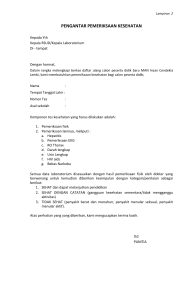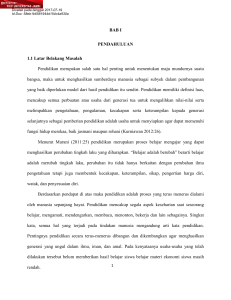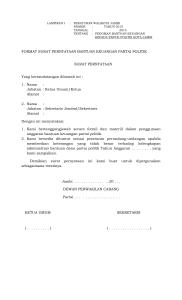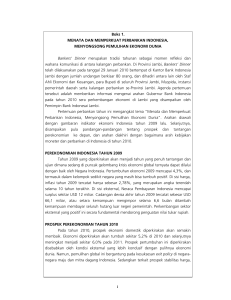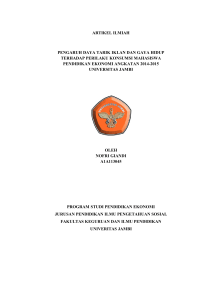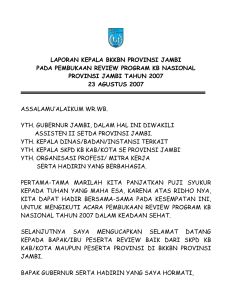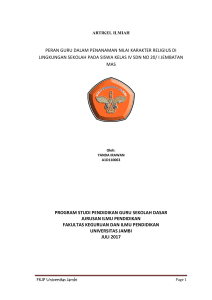1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kejatuhan
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kejatuhan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari tampuk presiden berimbas sangat besar terhadap industri media cetak di Indonesia. Kebijakan Reformasi yang segera menyusulnya membuat media-media tumbuh subur. Kalau pada akhir Orde Baru keseluruhan media cetak di Indonesia tidak sampai 300, setelah Reformasi angkanya melonjak tajam menjadi lebih dari 1.000 (Tabel 1.1). Tabel 1.1. Jumlah Media Cetak di Indonesia, 1997-2010 Tahun 1997 Maret 1999 1999 2001 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber: Lim (2011: 4). Jumlah Media Cetak 289 289 1.381 1.881 889 983 1.008 1.036 1.076 Banyak sarjana yang telah memberikan penjelasan atas fenomena pertumbuhan besar media cetak di Indonesia pasca-Reformasi. Nyaris keseluruhan analisis mereka mengerucut pada kesimpulan dicabutnya UU Nomor 21 Tahun 1982 yang digantikan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Poin penting perubahan regulasi tersebut, yang kemudian dianggap melempangkan jalan bagi tumbuhnya media cetak, adalah hilangnya ketentuan kepemilikan Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi penerbit media. Ketentuan tentang SIUPP diatur dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984, yang merupakan turunan dari UU Nomor 21 Tahun 1982. UU ini 1 menekankan kerja pers mestilah “bebas dan bertanggung jawab”, dan SIUPP merupakan sarana bagi pemerintah Orde Baru untuk mengontrol kebebasan-yangtidak-bertanggung-jawab. Ketika mendapati media keluar dari ketentuan tersebut, dengan mudah Orde Baru memainkan “kartu” SIUPP hingga mencabutnya. SIUPP ketika itu tak ubahnya nyawa bagi media, yang tanpanya sebuah media tidak dapat terbit. Perubahan kebijakan terkait penerbitan media yang tidak mengharuskan kepemilikan SIUPP, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 yang mengedepankan kebebasan pers, dengan sendirinya membuat penerbitan media menjadi bergairah.1 Kalau banyak penelitian terhadap peningkatan pesat jumlah media cetak di Indonesia dilakukan dalam skala luas dan menyeluruh di tingkat nasional, dengan kesimpulan sebagaimana di atas, bagaimanakah fenomena tersebut dijelaskan dalam konteks lokal? Pertanyaan ini penting diajukan setidaknya karena dua hal. Pertama, selain (Maret) 1999, sebetulnya ada satu tahun krusial lagi yang penting dilihat dari Tabel 1.1, yaitu 2006. Tahun-tahun tersebut menjadi titik terendah total media cetak di Indonesia setelah 1997 sekaligus tahun beranjak sebelum jumlahnya terus membesar dan mengalami kenaikan. Pertanyaannya, ada apa dengan tahun-tahun itu atau di sekitar keduanya? Sebagaimana telah disebut, untuk yang pertama jelas ada kejatuhan Soeharto dan Orde Baru pada Mei 1998, yang disusul oleh kebijakan Reformasi dan dibukanya kebebasan pers pada 1999. Banyak analisis terdahulu tampaknya hanya terpaku pada perubahan yang terjadi pada atau di sekitar tahun tersebut. Untuk yang kedua atau 2006, dua tahun sebelumnya, pemerintah mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai amanat UU ini, pada Juni 2005 untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan Analisis seperti ini misalnya diajukan Merlyna Lim, @Crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia, (Arizona: Participatory Media Lab dan Ford Foundation, 2011), hlm. 21-22; Krishna Sen dan David T. Hill (eds.), Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy, (London dan New York: Routledge, 2011); Herlambang Perdana Wiratraman, “Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study”, disertasi di Universiteit Leiden, 2014; Angela Romano, Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture, (London and New York: Routledge, 2003); Syamsul Rijal, “Media and Islamism in Post-New Order Indonesia: The Case of Sabili”, Studia Islamika, 12, 3, (2005), hlm. 421-474. 1 2 pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Kalau sebelum 2005 kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setelah Juni 2005 “dipilih dalam satu pasangan [kepala daerah dan wakil kepala daerah] secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”2 Walau kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memang dimulai pada 1999,3 sejak kebijakan pilkada langsung diberlakukan pada 2005, lanskap politik Indonesia berubah dengan kian pentingnya politik lokal.4 Sebagaimana 1999, perubahan kedua ini tentu saja menjadi konteks yang tak boleh diabaikan untuk melihat peningkatan media cetak di Indonesia pasca-Reformasi. Kedua, pentingnya daerah setelah 2005 menemukan pendasarannya dalam fakta bahwa penyumbang terbesar dari angka kenaikan jumlah media cetak pascaReformasi adalah media cetak lokal, sementara media nasional sebetulnya mengalami penurunan terutama setelah 2006. Pada 2010, menurut catatan Dewan Pers, jumlah media cetak lokal di Indonesia adalah 952, sementara keseluruhan media cetak berjumlah 1.076.5 Artinya, hampir 90 persen media cetak di Indonesia pasca-Reformasi adalah media cetak lokal. Kalau pada masa Orde Baru media lokal disebut oleh David T. Hill sebagai media yang marginal (marginal presses),6 setelah Reformasi keadaannya berbalik dan menjadi sangat dominan dari segi jumlah. Data media lokal di Jambi jelas sekali memperlihatkan pertumbuhan media cetak lokal pasca-Reformasi. Pada masa Orde Baru, hanya ada satu koran harian, yaitu Independent, yang sekarang berubah menjadi Jambi Independent. Saat ini, lebih dari 20 koran terbit setiap hari di Jambi. Tidak semua koran itu terbit dan beredar di ibukota dan di seluruh wilayah Provinsi Jambi, tetapi lebih dari separuh bahkan merupakan koran yang hanya berada di lingkup kabupaten. Sebagaimana 2 Pasal 24 (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi adalah amanat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 7 Mei 1999. 4 Nankyung Choi, Local Politics in Indonesia: Pathways to Power, (London dan New York: Routledge, 2011), hlm. 1 dan 10. 5 Petrus Suryadi Sutrisno, “Fenomena Kebangkitan Industri Pers Daerah/Media Lokal”, Jurnal Dewan Pers, 5 (2011), hlm. 88. 6 David T. Hill, The Press in New Order Indonesia, (Jakarta: Equinox, 2007), hlm. 111137. 3 3 tampak dalam Tabel 1.2, setelah keran kebebasan pers dibuka pada 1999 hingga 2004, hanya ada 4 koran lokal di Jambi. Pertumbuhan terbesar terjadi setelah kebijakan pilkada diperkenalkan pada 2005. Pada periode 2005-2010, muncul 14 koran lokal serta setelah 2011 terdapat 5 koran lokal baru lagi. Tabel 1.2. Jumlah koran lokal di Jambi, 1998-2014 Tahun 1998 1999 2002 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014 Jumlah Koran Lokal 1 2 3 4 9 12 14 18 19 20 23 Selain dari periode terbitnya sebagaimana di atas, pertumbuhan koran lokal di Jambi yang dipengaruhi oleh dinamika politik daerah juga dapat dilihat dari kepemilikan beberapa koran oleh pengusaha sekaligus aktor politik lokal, seperti Aksi Post, Jambi Today, dan Harian Jambi. Koran-koran ini tentu sulit untuk menghindari konflik kepentingan dan ambisi politik pemiliknya. Sementara itu, koran-koran yang pemiliknya “netral”, yakni koran-koran yang merupakan cabang atau anak usaha dari kelompok media nasional seperti Jawa Pos Group dan Kelompok Kompas Gramedia, masuk dalam pusaran politik daerah lewat iklan dan berita berbayar yang dipasang oleh pemerintah daerah, yang menjadi rawan digunakan untuk kepentingan politik pejabat kepala daerah.7 Ironisnya kemudian iklan-iklan oleh pemerintah daerah seperti itu menjadi pemasukan terbesar kebanyakan koran lokal di Jambi, yang memungkinkan mereka tumbuh dan 7 Burhanuddin & Jamaluddin, “Out of Frame: Studi Pemberitaan Pemilukada Provinsi Jambi 2010 oleh Media Lokal di Jambi”, laporan penelitian, (2010). 4 berkembang.8 Praktik tersebut persis kesimpulan Ignatius Haryanto ketika melihat pers lokal setelah sepuluh tahun Reformasi: Menjadi suatu praktik umum di mana media massa di berbagai wilayah tak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat, tidak profesional, dan menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada dinamika yang terjadi dalam politik lokal (mulai dari langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapan selamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya).9 Perkembangan industri pers yang terlihat kental dengan nuansa kepentingan tersebut, menarik dikaji dengan pendekatan ekonomi politik. Para teoretikus ekonomi politik melihat bahwa ada kelompok tertentu yang mengendalikan institusi ekonomi yang kemudian memengaruhi institusi sosial lainnya, termasuk media dan pers. Dengan kata lain, penguasaan institusi ekonomi akan berujung pada penguasaan nyaris seluruh aspek kehidupan, mulai hal kecil seperti cara makan hingga hal besar seperti perangkat komunikasi dan politik. Penguasaan itu dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi mereka. Meskipun praktik yang kental kepentingan tersebut berlaku umum di dalam industri pers daerah di Indonesia, menurut Haryanto, “tak mudah bagi masyarakat untuk mengetahui” apa yang sesungguhnya terjadi di sebaliknya.10 Tentu saja para peneliti dan sarjana yang mesti melihat fenomena tersebut lebih jauh. Sayangnya, tidak banyak peneliti yang melakukannya. Kenyataannya ada rangkap kekosongan akademis di sini. Pertama, kajian terhadap pers lokal sendiri bisa disebut minim. Haryanto menyebutnya sebagai “tidak ada data”.11 Penelitian kebanyakan dilakukan terhadap “pers nasional”,12 yang tentu saja ironis di tengah fenomena merebaknya industri pers lokal atau pers daerah.13 Kedua, telaah ekonomi politik untuk mengudar berbagai kepentingan yang berjalin-kelindan di balik sebuah kebijakan cukup lama absen dalam dunia 8 Wawancara dengan JR, 8 April 2015; wawancara dengan MU, 9 April 2015; wawancara dengan YJ, 10 April 2015; wawancara dengan HN, 19 Agustus 2015; wawancara dengan RH, 29 Oktober 2015. 9 Ignatius Haryanto, “Menilik Pers Lokal 10 Tahun Setelah Reformasi”, Jurnal Dewan Pers, 5 (2011), hlm. 19. 10 Haryanto, “Menilik Pers Lokal”, hlm. 19. 11 Haryanto, “Menilik Pers Lokal”, hlm. 21. 12 Misalnya David T. Hill & Krishna Sen, The Internet in Indonesia’s New Democracy, (London & New York: Routledge, 2007); Lim, @Crossroads; Lim, The League of Thirteen. 13 Sutrisno, “Fenomena Kebangkitan”. 5 akademik di Indonesia. Penyebabnya, menurut Vedy R. Hadiz, kekuasaan Orde Baru selama lebih-kurang 32 tahun melarang analisis-analisis kapitalisme dan kelas dengan pisau bedah Marxisme, padahal analisis terakhir ini merupakan basis dalam teori ekonomi politik. Analisis apa pun, ketika menggunakan pendekatan tersebut, dengan segera dianggap sebagai Kiri oleh Orde Baru. Ironisnya, saat itu kekuatan kapital sedang tumbuh di Indonesia,14 yang segera memicu para sarjana Indonesia melakukan analisis terhadapnya. Walhasil, dengan sedikit pengecualian, yang muncul kemudian adalah analisis-analisis yang disebut Hadiz sebagai “most banal forms and narrow behaviorism”.15 Untuk mengisi kekosongan akademik tersebut, tentu saja penting melakukan analisis ekonomi politik industri pers di daerah. Dalam konteks pasca-Reformasi yang dilanjutkan dengan kebijakan otonomi daerah, apa yang disebut “kapital” juga beralih dari pusat ke daerah.16 Para pemain industri media di tingkat nasional kemudian melebarkan sayap ke daerah. Mereka membikin cabang dari industri pers yang telah dimiliki di pusat atau membangun industri pers baru di tingkat lokal. Kecenderungan ini kemudian berjumpa dengan desentralisasi yang mengubah landskap politik Indonesia.17 Aktor politik lokal bermunculan d(eng)an memanfaatkan serta menguasai segala sumber daya milik daerah, termasuk sumber daya media atau pers. Hasil dari pergumulan antara kekuasaan politik dan industri media tersebut pada gilirannya menghasilkan apa yang disebut sebagai sistem pers (lokal). B. Rumusan Masalah Persoalan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa industri koran lokal di Indonesia tumbuh pesat pasca-Orde Baru. Dengan mengambil kasus Jambi serta untuk memudahkan tahapan analisis, persoalan tersebut Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, (Jakarta: Equinox, 2008 [edisi perdana terbit 1986]). 15 Vedi R. Hadiz, “Studies in the Political Economy of New Order Indonesia”, Kyoto Review of Southeast Asia, 1 (2002). 16 Edward Aspinall, “Kemenangan Modal? Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia”, Prisma, 32, 1 (2013), hlm. 27. 17 Nordholt & van Klinken, Renegotiating Boundaries. 14 6 dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana perkembangan industri koran lokal di Jambi pasca-Orde Baru? Bagaimana perkembangan itu dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah? Struktur apa yang mendasari perkembangan tersebut? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini berupaya mendapatkan penjelasan yang memadai tentang perkembangan industri koran lokal di Jambi pasca-Orde Baru, terutama dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan pada era baru tersebut, dinamika ekonomi-politik yang menyertainya, serta sistem pers yang tumbuh di Jambi. Argumen yang mendasarinya adalah bahwa konteks pasca-Orde Baru menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan industri pers lokal, seiring dengan tumbuh dan masuknya kapital ke daerah serta munculnya aktor-aktor politik lokal pasca-desentralisasi. D. Manfaat Penelitian Selain menyumbang pemikiran tentang praktik ekonomi politik dalam industri pers di Jambi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melihat realitas industri pers di tingkat lokal. Kalau Haryanto secara berlebihan menyebut “tidak ada data” tentang pers lokal di Indonesia,18 secara praktis gambaran realitas tentang industri pers yang dihasilkan penelitian ini tentu saja akan menyumbang data yang kosong tersebut. Lebih lanjut, data tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan terkait pers di tingkat lokal atau di Indonesia. E. Kerangka Teori 1. Koran dan Media Lokal Istilah koran yang menjadi topik penelitian ini mengacu pada surat kabar tercetak yang terbit setiap hari. Tak ada kesepakatan tentang dari mana kata “koran” berasal. Ada yang menyebut dari bahasa Arab “qurān” yang berarti bacaan. 18 Haryanto, “Menilik Pers Lokal”, hlm. 21. 7 Dalam sejarah Indonesia, relasi dengan Timur Tengah melalui para haji memang menginspirasi munculnya terbitan-terbitan berkala berbahasa Arab dan Pegon atau Jawi di beberapa daerah seperti Minangkabau dan Batavia.19 Ada pula yang mengatakan dari bahasa Belanda “krant” karena bagaimanapun pengaruh kolonial kuat sekali mewarnai sejarah awal koran modern di Indonesia.20 Sedikit yang lain berpendapat dari bahasa Prancis “courant” yang tampaknya merujuk sisi aktual (current dalam bahasa Inggris) dari terbitan ini. Dalam bahasa Indonesia, pembentukan sebuah istilah dengan mempertimbangkan hal seperti di atas memang sering terjadi. Koran sendiri acap disinonimkan dengan “harian” karena mengacu periode terbitnya yang setiap hari atau “surat kabar” saja sebab isinya yang lebih dominan kabar atau berita. Sebagai bagian dari media publikasi yang bersifat massal, koran memiliki sifat atau karakteristik berikut: (a) publisitas atau disebarkan untuk publik luas, (b) diterbitkan secara periodik, yakni setiap hari, (c) informasi yang dibawanya aktual, (d) universal atau tidak mengenai satu persoalan saja, dan (e) terbit secara kontinu. Koran juga termasuk salah satu dari media lama yang sering disebut sebagai lima besar (the big five of mass media), yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Salah satu fungsinya adalah fungsi informatif atau membawa kabar yang jauh menjadi dekat dan hadir di sini; jarak yang menjadi penghalang diruntuhkan oleh kehadiran media. Dengan fungsi melintas batas ruang seperti itu, menyebut dan mendefinisikan koran atau media lokal di masa sekarang sebetulnya problematis. Di dalam Understanding the Local Media, Meryl Alridge menyebut problem tersebut terutama terkait realitas dunia saat ini yang semakin mengglobal, ditandai dengan temuan-temuan teknologi modern yang mengatasi hambatan jarak yang sebelumnya menjadi pemisah. Globalisasi yang memungkinkan interaksi sosial Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma below the Winds, (London dan New York: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 142-151. 20 Ahmat Adam, “The Vernacular Press and the Emergence of National Consciousness in Indonesia”, Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 11, (1982), hlm. 1-2; Ahmat B. Adam, The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913), (Ithaca, New York: Southeast Asia Program, Cornell University, 1995), hlm. 178. 19 8 antarwarga dunia secara real-time, yang semakin menyempurnakan gagasan global village dari Marshall McLuhan, pada gilirannya mengubah kebudayaan manusia untuk tidak hanya berpikir tapi juga bertindak secara global.21 Dan koran atau media, sebagai sarana komunikasi massa, demikian Alridge, merupakan pemain paling penting yang mendorong terjadinya globalisasi.22 Dengan sifat dasarnya yang global, bagaimana mungkin kemudian ada yang dinamakan media atau koran lokal? Rupanya, menurut Alridge, di tengah gelombang globalisasi, kerinduan pada lokalitas juga menguat.23 Di samping dipengaruhi oleh berbagai faktor global, apa yang disebut kenyataan hari ini tidak bisa tidak dibentuk oleh lokalitas yang dekat (immediate locality). Dalam definisi globalisasi, misalnya yang dikemukakan Anthony Giddens, ditekankan pentingnya keterlibatan lokal (local involvement) dalam pembentukan sebuah kejadian, di samping tentu saja interaksi lintas jarak (interaction across distance) yang merupakan sumbangan global.24 Kerinduan akan lokalitas itu, menurut Alridge, menyebabkan preferensi masyarakat Inggris, negara yang dia teliti, terhadap media yang mengangkat berita lokal sangat kuat.25 Pemberitaan atau orientasi lokal, dalam pandangan Ashadi Siregar, merupakan salah satu ukuran untuk melihat apakah sebuah media bisa disebut media lokal atau tidak, di samping sirkulasi.26 Siregar membuat tiga “tingkatan” media berdasarkan orientasi dan sirkulasi tersebut, yang merupakan “tingkatan” keduanya: lokal, regional, dan nasional. Menurut Siregar, “nasional melingkupi seluruh wilayah negara; regional mencakup sebagian wilayah nasional, bersifat Meryl Alridge, Understanding the Local Media, (Berkshire dan New York: McGraw-Hill dan Open University Press, 2007), hlm. 7. Tentang global village, lihat Marshall McLuhan, War and Peace in the Global Village, (New York: Bantam, 1968). 22 Alridge, Understanding the Local Media, hlm. 5. 23 Alridge, Understanding the Local Media, hlm. 7-8. 24 Annabelle Sreberny, “The Global and the Local in International Communications”, M.G. Durham dan Douglas M. Kellner (eds.), Media and Cultural Studies: KeyWorks, (USA: Blackwell, 2006), hlm. 605. 25 Alridge, Understanding the Local Media, hlm. 15. 26 Ashadi Siregar, “Perkembangan Media Cetak Lokal”, makalah disampaikan dalam seminar Being Local in National Context: Understanding Local Media and Its Struggle, Surabaya, 14 Oktober 2002. 21 9 antar daerah; sedang lokal mencakup satu kota atau daerah terbatas.”27 Dengan kerangka seperti itu, terbuka kemungkinan sebuah koran misalnya berorientasi lokal namun diedarkan secara nasional atau sebaliknya berorientasi regional tapi sirkulasinya hanya lokal. Apa yang disebut koran atau media lokal, dalam pandangan Siregar, sejatinya adalah yang berorientasi lokal dan wilayah sirkulasinya juga lokal.28 Definisi Siregar tentulah terasa amat longgar jika dibandingkan definisi dari Bob Franklin yang mensyaratkan media atau koran lokal lokal “dimiliki orang lokal, diproduksi secara lokal, mempekerjakan jurnalis lokal, melaporkan apa yang menjadi konsen lokal, dan dibaca oleh penduduk lokal.”29 Kalau Siregar hanya menekankan orientasi pemberitaan dan wilayah edar, Franklin menambahkan pemilik, produksi, dan pekerja media mesti juga bersifat lokal. Meskipun membuat definisi ketat, Franklin pesimis semua syarat lokal itu bisa dipenuhi. Franklin sendiri menyebutkan, di masa sekarang, apa yang disebut media lokal tinggal nama semata. Pemilik koran lokal kerap kali adalah kelompok jaringan media yang tidak hanya memiliki media di suatu daerah tetapi juga di daerah lain, bahkan bisa jadi kelompok industri dari negara lain. Dengan kepemilikan yang demikian, produksi bisa berada di tempat yang jauh serta keputusan redaksional ditentukan dari wilayah lain. Hal yang paling mengkhawatirkan, sebagai konsekuensinya, adalah terputusnya relasi antara masyarakat suatu wilayah dan media atau koran yang beredar di sana.30 Sama halnya dengan pendapat Franklin, relasi kedua hal itu juga sangat penting bagi Siregar. Keduanyalah yang disebut Siregar sebagai orientasi dan sirkulasi, yang sesungguhnya menunjukkan dua fungsi atau peran media: sebagai institusi sosial dan institusi bisnis. Kata Siregar, 27 Siregar, “Perkembangan Media”, hlm. 1. Siregar, “Perkembangan Media”, hlm. 1-2. 29 Bob Franklin, “Local Journalism and Local Media: Contested Perceptions, Rocket Science and Parallel Universes”, Bob Franklin (ed.), Local Journalism and Local Media: Making the Local News, (London dan New York: Routledge, 2006), hlm. xxi. 30 Franklin, “Local Journalism”, hlm. xxi. Bandingkan dengan Granville Williams, “Profits before Product? Ownership and Economics of the Local Press”, Bob Franklin (ed.), Local Journalism and Local Media: Making the Local News, (London dan New York: Routledge, 2006), hlm. 83-92. 28 10 Sebagai institusi sosial, [media] berorientasi ke luar (outward looking) untuk kepentingan masyarakat. Sebagai institusi bisnis, media massa sama halnya dengan setiap korporasi, yaitu menjalankan operasinya dengan orientasi ke dalam (inward looking), untuk kepentingan sendiri.31 Dua peran tersebut dalam kenyataannya sulit seiring sejalan dan kerap menjadi dilema dalam kerja-kerja jurnalistik, termasuk bagi koran lokal. Dalam konteks Indonesia, perkembangan jumlah koran lokal yang luar biasa pascaReformasi,32 tidak hanya disebabkan oleh penghapusan SIUPP sebagai syarat penerbitan media, melainkan juga buah dari dinamika lokal seiring kebijakan desentralisasi.33 Perubahan lanskap politik Indonesia yang menjadikan kabupaten dan kota sebagai basis otonomi pada gilirannya membutuhkan ruang publik bersama yang berfungsi menghasilkan imajinasi komunitas dan identitas yang dicita-citakan.34 Dalam sejarah modern, penerbitan seperti koran dianggap mampu memenuhi tugas tersebut.35 Walhasil, meskipun merupakan institusi bisnis, koran lokal sejatinya tidak melupakan tugasnya sebagai institusi sosial. Dua peran tersebut seyogianya berjalan beriringan. Pertanyaannya, apakah koran-koran lokal di Jambi telah melaksanakan kedua tugas tersebut? 2. Koran sebagai Institusi Bisnis: Bagaimana Industri Koran Berkembang? Industri media cetak seperti koran pada umumnya bertumpu pada dua hal yang merupakan produk-produk utama mereka yang dijual ke pasar. Pertama, jumlah cetakan (volume) atau oplah yang sering disebut juga jangkauan edar atau sirkulasi. Kedua, pariwara atau iklan.36 Menurut Patrick Hendrics, sirkulasi menjadi aspek paling penting karena sifat koran yang massal (mass). Untuk melayani massa yang luas, koran yang terutama berisi pemberitaan harus diproduksi dalam jumlah besar. Walhasil media cetak masuk ke dalam apa yang disebut sebagai sistem produksi massal (mass 31 Siregar, “Perkembangan Media”, hlm. 2. Lim, @Crossroads; Lim, The League of Thirteen; Sutrisno, “Fenomena Kebangkitan”. 33 Siregar, “Perkembangan Media”, hlm. 3. 34 Nordholt dan van Klinken, Renegotiating Boundaries. 35 Lihat Benedict R. O’G. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (London: Verso, 1983). 36 W.B. Reddaway, “The Economics of Newspapers”, The Economic Journal, 73 (290), (1963), hlm. 201-202. 32 11 production system) dengan model industri yang berbasis jumlah cetak (volume atau copy). Jumlah cetak yang semakin besar, yang berarti pembacanya semakin banyak, menunjukkan bahwa media tersebut kian memiliki kemampuan melayani keinginan massa yang sesungguhnya sangat beragam; sebuah media pada dasarnya merupakan produk untuk memenuhi aneka fungsi dari beragam pembaca.37 Pendapatan berupa uang dihasilkan dari penjualan jumlah cetakan tersebut. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam penjualan cetakan. Pertama, area penjualan atau jangkauan edar. Sebagaimana dalam definisi yang sudah dikemukakan sebelumnya, koran yang menyebut diri sebagai koran nasional semestinya di samping pemberitaannya mencakup nasional, area distribusinya juga tidak terkonsentrasi di satu daerah tertentu. Demikian pula koran yang mendaku sebagai koran lokal, tentu tidak mudah untuk dipasarkan di luar wilayah yang menjadi fokus pemberitaannya. Kedua, periode terbit, yang berpengaruh terhadap waktu distribusi atau sirkulasi. Karena terbit setiap hari pada pagi hari, koran-koran punya waktu sangat terbatas dalam pemasarannya. Lewat tengah hari biasanya koran sudah dianggap terlambat dan beritanya menjadi basi.38 Untuk mengatasi problem sirkulasi yang waktunya sempit, korankoran dengan wilayah edar dan penjualan yang luas seperti koran nasional di masa sekarang memberlakukan teknologi cetak jarak jauh. Selain menjual jumlah cetakan, koran juga memasarkan ruang-ruang (spaces) untuk pariwara atau iklan. Di dalam lembaran koran, di samping berita yang biasanya lebih dominan, terdapat ruang iklan di mana publik bisa mengisinya untuk memasarkan produk atau jasa mereka agar diketahui oleh masyarakat luas, setidaknya setara dengan jumlah pembeli cetakan koran. Sama dengan cetakannya, iklan-iklan ini juga dijual secara terbuka kepada masyarakat. Dengan cara itu, siapa pun yang ingin menggunakan ruang koran untuk kepentingannya, mereka bisa membayar sesuai ketentuan periklanan yang Patrick Hendriks, Newspapers: A Lost Cause? Strategic Management of Newspaper Firms in the United States and the Netherlands, (Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1999), hlm. 15. 38 Reddaway, “The Economics of Newspapers”, hlm. 202. 37 12 diterapkan. Bagi koran atau media, pemasang iklan adalah mitra kerja yang menopang ekonomi mereka.39 Kalau oplah penting karena koran terutama berurusan dengan pemberitaan, sehingga idealnya penyiaran atas berita sedapat mungkin meluas, iklan dipercaya menjadi penyumbang utama pendapatan media. Dalam beberapa kasus bahkan penjualan koran atau media cetak tidak mampu menutupi biaya pencetakan, sehingga harus disubsidi oleh iklan-iklan yang dipasang di lembarannya.40 Pariwara di dalam sebuah koran mengandaikan koran tersebut memiliki khalayak atau kelompok pembacanya, yang kemudian menjadi titik tolak dalam penyajian informasi berupa berita. Ada berita-berita tertentu dari sebuah koran yang dipilih oleh khalayak tertentu, sementara berita dari koran yang lain disukai oleh khalayak yang berbeda. Khalayak pembaca yang berkelompok atau tersegmentasi itulah yang dipertimbangkan oleh pemilik produk atau jasa ketika memilih koran atau media untuk memasang iklan. Iklan produk tertentu bisa jadi hanya cocok untuk sebuah koran, sementara produk berbeda juga menjadi lebih dikenal jika diiklankan di koran yang lain.41 Karena pengiklan biasanya mempertimbangkan pembaca atau khalayak koran, maka di dalam teorinya pendapatan iklan berbanding lurus dengan jumlah pembaca atau sirkulasi media. Jumlah pembaca yang besar akan menjustifikasi naiknya harga iklan serta jumlah iklan yang dipasang. Ketika sirkulasi rendah dan jumlah pembaca jatuh, industri koran akan terimbas melalui dua jalan. Pertama, pendapatan dari jalur sirkulasi berkurang, walaupun sebetulnya biaya produksi cetak juga turun disebabkan jumlah cetakannya yang lebih sedikit. Kedua, pasar iklan koran tersebut melemah: jumlah pemasang iklan mengecil serta harga iklan akan tertekan lebih rendah.42 Hendriks, Newspapers, hlm. 16; Ashadi Siregar, “Periklanan sebagai Mitra Kerja Media”, makalah disampaikan dalam Seminar Periklanan sebagai Mitra Kerja Media di Surakarta, 22 Februari 1987. 40 Lawrence Solely dan R. Krishnan, “Does Advertising Subsidize Consumer Magazine Prices?”, Journal of Advertising, 16, 2 (1987), hlm. 4-9. 41 Siregar, “Periklanan sebagai Mitra”, hlm. 3. 42 Hendriks, Newspapers, hlm. 16. 39 13 Meskipun dalam teorinya demikian, kenyataannya terkadang terjadi penyimpangan. Misalnya, oplah cetak tinggi namun jumlah iklan yang dipasang sedikit, barangkali karena pembaca koran ini dianggap tidak potensial atau tidak menjadi target bagi banyak calon pemasang iklan. Sebaliknya bisa jadi ditemukan oplah cetak rendah tetapi halaman-halaman koran selalu penuh pariwara. Pemasang iklan menyukai misalnya karena pembaca koran ini berasal dari kelompok masyarakat berekonomi tinggi yang doyan belanja, sehingga berbagai produk yang diiklankan diperkirakan bakal dibeli. Yang jelas, untuk mendapatkan pemasukan yang tinggi, baik iklan maupun sirkulasi idealnya sama-sama berjumlah banyak. Demi mengejar pendapatan besar melalui keduanya, koran-koran tak jarang membuat pemberitaan yang menyenangkan pembacanya atau memilih memuat berita yang populer supaya dicari dan dibeli konsumen. Terkadang pula berita-berita di dalam koran yang semestinya objektif dikomodifikasi menjadi iklan. Muncullah kemudian beritaberita berbayar atau advertorial serta jenis-jenis iklan yang lain. Kerja sama dengan kekuatan-kekuatan politik dan penguasa kapital terkait iklan juga rentan dilakukan koran atau media untuk memaksimalkan pendapatan. 3. Koran dan Tanggung Jawab Sosial Selain sebagai institusi bisnis yang sebagian besar dimiliki oleh pribadi maupun badan usaha swasta, koran atau media massa sejatinya juga merupakan sebuah institusi sosial. Logika yang mendasarinya adalah bahwa informasi yang berkembang di dalam masyarakat merupakan milik masyarakat tersebut. Media seperti koran kemudian memfasilitasi untuk mempermudah penyampaian informasi-informasi yang berkembang di dalam masyarakat.43 Dengan demikian, masyarakat di sini bukan sekadar konsumen yang melahap berita atau menjadi target pemasangan iklan semata, melainkan juga pemilik sah informasi. Begitu juga media semestinya tidak hanya menjalankan peran untuk mencari keuntungan David Croteau dan William Hoynes, Media/Society: Industries, Images, and Audiences, 5th edition, (London: Sage, 2014), hlm. 18-19. 43 14 ekonomi semata, tetapi juga menjadi institusi yang mewadahi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Peran sosial tersebut semakin penting di dalam masyarakat luas yang kompleks, yang berbeda dari sebuah negara kota (city state) sebagaimana yang pernah ada pada masa Yunani kuno dan sering menjadi nostalgia. Saat itu, dengan jumlah penduduk yang terbatas, masyarakat Yunani kuno secara langsung dapat berpartisipasi di dalam komunikasi publik dengan setara (homoioi). Persoalanpersoalan sosial-kemasyarakatan didiskusikan bersama dengan bebas tanpa banyak hambatan.44 Karena komunikasinya bersifat langsung, tentu saja tidak membutuhkan media, melainkan kemampuan orasi yang mumpuni, yang kemudian diwadahi oleh sistem pendidikan untuk membentuk orator ulung. Kondisi sekarang berbeda sekali dan jauh lebih kompleks. Wilayah negara bisa sangat luas mencakup ribuan pulau. Model demokrasi dan komunikasi langsung seperti pada masa Yunani kuno menjadi mustahil diterapkan. Kalau di dalam politik ada istilah demokrasi tak langsung melalui perwakilan (representative), sebagaimana yang populer diterapkan saat ini, media seperti koran menjadi sarana atau saluran untuk mendukung sistem tersebut. Menurut Pippa Norris di dalam A Virtuous Circle: Political Communication in PostIndustrial Societes (2000), setidaknya ada tiga peran yang bisa dimainkan media di dalam demokrasi, yaitu media sebagai forum kewargaan (civic forum), sebagai pengawas pemerintah atau lembaga-lembaga publik, dan sebagai agen mobilisasi untuk mendapatkan suatu jabatan atau posisi politis.45 Sebagai forum kewargaan, media hadir di dalam sebuah ruang publik (public sphere) yang semestinya jernih dan tidak didominasi oleh kekuatankekuatan politik dan kapital tertentu.46 Tanpa dominasi tersebut, bukan saja masyarakat bisa mengangkat berbagai persoalan publik dan mendiskusikannya Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, terj. Thomas Burger dan Frederick Lawrence, (Cambridge: The MIT Press, 1991), hlm. 3-4. 45 Dikutip dari I Gusti Ngurah Putra, “Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia”, Jurnal Ilmu Komunikasi, 3, 2, (2004), hlm. 135. Penjelasan di bawah banyak diambil dari sumber ini. 46 Tentang gagasan ruang publik ini, lihat lebih lanjut Habermas, The Structural Transformation. 44 15 bersama tanpa dihantui oleh ketakutan, tetapi juga media menjadi mungkin untuk mewadahi setiap perdebatan. Dengan bantuan media, perdebatan publik yang tentu saja terbatas jika dilakukan secara langsung, bisa melibatkan masyarakat dari wilayah yang luas. Tentu di dalam masyarakat yang plural dari segi budaya dan politik, media juga mesti mewadahi semua keragaman yang ada. Seharusnya pula tak ada yang menjadi minoritas dan mayoritas atau difavoritkan di dan oleh media, apalagi kalau kemudian itu dilakukan media karena tekanan dari pihak tertentu atau godaan suatu kekuatan kapital.47 Dalam perannya sebagai pengawas pemerintahan dan lembaga-lembaga publik, media ibarat anjing penjaga (watchdog) yang siap menyalak jika terjadi praktik penyimpangan oleh para pemegang kekuasaan. Dalam istilah yang populer, media merupakan kekuatan demokrasi keempat setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam trias politica-nya Montesquieu. Media mendapatkan mandat untuk mengawasi ketiga lembaga tersebut agar menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Harapan itu digantungkan kepada media karena baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif bisa tidak saling mengawasi atau menjalankan fungsi check and balance, melainkan bisa juga bekerja sama dalam sebuah permufakatan jahat yang merugikan negara dan publik.48 Sementara sebagai agen mobilisasi, media menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam proses-proses politik seperti pemilihan umum. Dalam prinsip demokrasi ala Schumpeterian, partisipasi publik dalam kontestasi jabatan politik penting karena saat itulah publik menjalankan fungsi pengawasan yang sebenarnya. Kalau menilai pemimpin atau pejabat lama tidak sesuai dengan harapan, publik menghukumnya dengan tidak memilih lagi dalam pemilihan umum. Begitu juga bila punya harapan atau keinginan, publik menitipkan gagasannya lewat kandidat yang sesuai dengan kriterianya. Selain 47 48 Putra, “Demokrasi dan Kinerja”, hlm. 135-137. Putra, “Demokrasi dan Kinerja”, hlm. 137-139. 16 menjamin proses politik berjalan baik dengan mendorong keterlibatan warga, media juga menjadi pendamping bagi pendidikan politik.49 4. Sistem Media: Bergerak di Antara Institusi Bisnis dan Sosial Ada beberapa cara yang digunakan para peneliti untuk melihat kenyataan dan sistem pers di sebuah negara. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm di dalam buku mereka yang telah menjadi klasik, Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do (1963), menganjurkan untuk mengkaji pandangan-dunia (worldview, welltanschauung) yang dianut warga negara itu. Mereka berpendapat bahwa pandangan-dunia tersebut akan memengaruhi dan pada gilirannya tecermin di dalam media. Mereka mengatakan, Untuk melihat sistem sosial dalam hakikat hubungannya dengan pers, seseorang harus mengulik nilai-nilai dasar dan asumsi menyangkut masyarakat dan negara, relasi-relasi negara, serta pengetahuan dan kepercayaan dasariah.50 Pendapat Siebert, Peterson, dan Schramm tersebut telah banyak dikritik terutama karena terlalu normatif dan ahistoris,51 bias Barat terutama ketika menggambarkan pers Uni Soviet,52 serta kunonya teori tersebut sehingga tidak relevan lagi digunakan setelah Uni Soviet runtuh pada 1980-an.53 Yang sangat mendasar dari banyak kritik itu sesungguhnya mempersoalkan teori mereka yang sangat deduktif: bila sistem yang dianut negara adalah A, maka sistem pers yang ada di negara itu juga A. Model penalaran silogis yang ada dalam pendapat Siebert dkk, oleh para pengkritiknya, dianggap mengabaikan kenyataan atau fakta pers yang kerap berbeda dengan sistem besar negara. 49 Putra, “Demokrasi dan Kinerja”, hlm. 139. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do, (Urbana: University of Illinois Press, 1963), hlm. 1. 51 Misalnya Jay G. Blumler, Jack M. McLeod, Karl Erik Rosengren (eds.), Comparatively Speaking: Communication and Culture Across Space and Time, (California: Sage Publications, 1992); Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini, Comparing Media System: Three Models of Media and Politics, (Cambridge dan New York: Cambridge University Press, 2004), hlm. 7-15. 52 Antara lain Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960, (Oxford: Oxford University Press, 1994); Everett M. Rogers, A History of Communication Study: A Biographical Approach, (New York: Free Press, 1994). 53 Robert G. Picard, The Press and the Decline of Democracy: The Democratic Socialist Response in Public Policy, (Connecticut: Greenwood Press, 1985). 50 17 Achmad Zaini Abar, salah seorang pengkritik empat teori pers ala Siebert, Peterson, dan Schramm, menyatakan bahwa kenyataan yang berbeda tersebut sering terjadi terutama di negara dunia ketiga. Di dalam bukunya, Kisah Pers Indonesia: 1966-1974, Abar menunjukkan bahwa di Indonesia, yang merupakan negara dunia ketiga, pers jauh dari apa yang dicita-citakan oleh demokrasi Pancasila, sistem yang digadang-gadang oleh Orde Baru. Di bawah Orde Baru, pers Indonesia adalah pers yang terkungkung dalam hegemoni dan ketakutan sebab sewaktu-waktu pembredelan bisa terjadi bila pemberitaannya tak memeroleh restu rezim.54 Setidaknya ada dua kelemahan dalam kritik Abar terhadap Siebert dkk. Pertama, persoalan sebenarnya bukanlah apa yang dibilang oleh Abar sebagai inkonsistensi sistem dan kenyataan, melainkan bahwa demokrasi Pancasila benarbenar dijadikan sebagai sistem oleh Orde Baru juga masih bisa diperdebatkan. Belakangan lebih banyak yang menyebut sistem pemerintahan Orde Baru adalah otoritarianisme. Walhasil, bila pendapat terakhir ini dipegangi, sistem pers di bawah Orde Baru sesungguhnya sesuai dengan sistem yang dianut negara.55 Di sini inkonsistensi yang merupakan titik kritik Abar untuk Siebert dkk dengan sendirinya tidak tepat dan malah menguatkan pendapat mereka. Kedua, pendapat Abar bahwa inkonsistensi sistem negara-sistem pers terjadi di negara dunia ketiga jelas sangat bias Barat. Di dalam ilmu sosial cara pandang ini disebut orientalisme: melihat timur atau dunia ketiga sebagai jelek dan barat sebagai maju dan berperadaban. Cara pandang yang digunakan Abar ini mengabaikan banyak fakta inkonsistensi yang juga terjadi di negara maju. Di Italia di masa kepemimpinan Perdana Menteri Silvio Berlusconi, misalnya, pers dimiliki dan digunakan oleh penguasa untuk kepentingan politiknya. Fakta bahwa sistem pers yang dianut negara-negara maju tidak sama, meskipun mereka mengklaim diri sebagai penganut demokrasi, dengan sendirinya menunjukkan bahwa di sana juga terjadi ketidaksamaan sistem negara dan pers. Paling tidak itu Lihat lebih lanjut Akhmad Zaini Abar, Kisah Pers Indonesia, 1966-1974, (Yogyakarta: LKiS, 1995). 55 Di dalam teori Siebert, Peterson, dan Schramm disebut pers otoritarian. 54 18 memperlihatkan bahwa sistem pers di negara maju tidaklah monolitik dan tidak mengikut saja, untuk mengatakan sesuai dengan, sistem yang dianut negara. Meskipun kritiknya mengandung kelemahan, usulan Abar terkait pendekatan untuk melihat sistem pers di suatu negara menarik disimak lebih lanjut. Abar menyebut pendekatan usulannya sebagai pendekatan struktural. Pendekatan yang dipinjam dari analisis-analisis ilmu sosial, yang mulai marak pada 1970-an, itu berupaya melihat lebih jauh dinamika hubungan pers dengan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun menjelaskan panjanglebar soal pendekatan struktural yang diusulkannya, Abar abai menunjukkan variabel yang meyakinkan yang dia gunakan dalam melihat sistem pers Indonesia.56 Bukunya kemudian nyaris bercerita lepas terkait sejarah pers di paruh awal Orde Baru. Pada titik itu, apa yang ditulis Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini melengkapi pendekatan yang dimaksud Abar. Sama dengan Abar, Hallin dan Mancini juga mengkritik empat teori pers yang mereka sebut sebagai normatif. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan pendekatan yang lebih historis, dengan tujuan-tujuan yang dijelaskan sebagai berikut: Kami di sini bukan ingin untuk mengukur sistem-sistem media melawan yang ideal dan normatif, tapi hendak menganalisis perkembangan historisnya sebagai institusi dalam konteks sosial tertentu. Kami ingin memahami mengapa sistem-sistem itu berkembang dalam cara yang unik; apa peran yang mereka mainkan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi; dan pola-pola relasi mereka dengan institusi sosial lainnya. Model jurnalisme kami merupakan model yang empiris, bukan normatif.57 Berbeda dengan Abar, Hallin dan Mancini menjelaskan variabel yang digunakan untuk melihat sistem pers tersebut, yang seluruhnya ada empat variabel. Pertama, industri pers, yang ditekankan pada kuat atau lemahnya sirkulasi media. Kedua, paralelisme politik, yaitu hubungan media dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di masyarakat; sistem media merefleksikan kekuatan politik. Ketiga, profesionalisme jurnalis. Keempat, pemerintah terhadap pers.58 Lihat bab dua bukunya, Kisah Pers Indonesia. Hallin dan Mancini, Comparing Media System, hlm. 14. 58 Lihat Hallin dan Mancini, Comparing Media System, hlm. 21 dan seterusnya. 56 57 19 intervensi Dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya bahwa media mempunyai dua orientasi, yaitu orientasi ke dalam atau bisnis dan orientasi ke luar atau sosial, empat variabel dari Hallin dan Mancini dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam dua orientasi tersebut. Industri pers dan paralelisme politik, misalnya, masuk ke orientasi pertama atau bisnis. Memang paralelisme politik sekilas tak berhubungan dengan bisnis, tetapi di dalam industri media dengan sirkulasi rendah, hubungan media dengan kekuatan politik dan modal cenderung tinggi. Pengikat hubungan itu tak lain adalah aliansi untuk mendapatkan keuntungan uang bagi media dan manfaat politik bagi partai atau pemerintah.59 Sementara itu, variabel profesionalisme jurnalis dan intervensi pemerintah terhadap pers digolongkan ke dalam orientasi ke luar atau sosial. Kalau media yang profesional dalam pandangan Norris mestilah memerankan diri sebagai forum kewargaan, pengawas pemerintah, dan agen mobilisasi, ketiga peran itu dapat dirusak atau dilemahkan oleh intervensi yang dilakukan pemerintah. Dengan perbandingan berbagai teori yang sudah dikemukakan di atas, dapat ditarik konsep, definisi, dan variabel yang akan digunakan penelitian ini, sebagaimana tampak dalam Tabel 1.3. Sementara penerapannya dalam penelitian ini tampak dalam Gambar 1.1. Tabel 1.3. Konsep, definisi, dan variabel yang digunakan dalam penelitian Konsep Koran lokal Industri koran Tanggung jawab sosial koran Sistem media Definisi Surat kabar tercetak yang terbit setiap hari dengan sirkulasi dan orientasi pemberitaan lokal Aspek bisnis koran untuk menghasilkan pendapatan guna membiayai operasional perusahaan dan memeroleh keuntungan Koran sebagai institusi sosial dengan orientasi untuk kepentingan masyarakat Sistem yang mendasari kenyataan media di sebuah negara 59 Hallin dan Mancini, Comparing Media System, hlm. 67. 20 Variabel - Surat kabar cetak - Terbit harian - Orientasi berita lokal -Mayoritas sirkulasi lokal - Oplah atau sirkulasi - Iklan - Sumber pemasukan lain - Forum kewargaan - “Anjing penjaga” - Alat mobilisasi sosial - Sirkulasi - Paralelisme politik - Profesionalisme jurnalis - Intervensi pemerintah Gambar 1.1. Sistem pers dalam perbandingan dengan teori-teori yang lain serta penerapannya dalam penelitian industri koran lokal Meskipun yang ditekankan Hallin dan Mancini dengan menggunakan empat variabel yan mereka usulkan adalah perbandingan sistem pers di beberapa negara, pendekatan yang digunakan jelas sekali memadai dipakai untuk melihat sistem pers di sebuah wilayah. Bahkan dengan menggunakannya untuk membandingkan sistem pers di banyak negara, pendekatan Hallin dan Mancini berarti telah dipakai dan memadai untuk melihat pers di wilayah-wilayah yang berbeda. Alasan inilah yang membuat penelitian ini memilih pendekatan Hallin dan Mancini. Memang ada kritik bahwa pendekatan mereka terlalu mempertimbangkan faktor politik, sebagaimana anak judul buku mereka, three models media and politics, namun, sebagaimana kasus Jambi yang diteliti, kaitan keduanya sangatlah erat. 21 Tinggal persoalannya, kalau Halllin dan Mancini melihat pers dalam konteks politik negara, apakah bisa pendekatannya dipakai untuk melihat pers di sebuah provinsi di suatu negara? Apakah tidak cukup melihat sistem pers di tingkat negara lalu kemudian menderivasinya ke dalam sistem pers di daerah? Pasca-Reformasi, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah secara berlebihan di Indonesia. Banyak hal yang sebelumnya diatur oleh dan menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian didelegasikan dan menjadi hak daerah. Kebijakan desentralisasi ini, dalam pandangan banyak pengamat, mengubah secara total landscape politik Indonesia.60 Aktor-aktor politik lokal bermunculan d(eng)an memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah, termasuk sumber daya media. Meskipun urusan tentang regulasi media masih berada di pusat, kenyataan media di pusat atau daerah bisa berbeda sama sekali. Ini alasan pentingnya melihat pers atau media di daerah di Indonesia terutama pascaReformasi, sebagaimana dilakukan penelitian ini. F. Metodologi Penelitian 1. Paradigma dan Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Peter Golding dan Graham Murdock membedakan perspektif ekonomi politik ke dalam dua paradigma, yaitu paradigma liberal dan kritis. Kalau paradigma liberal melihat kebebasan individu di hadapan pilihan komoditas yang ditawarkan pasar, sehingga semakin banyak pilihan komoditas akan semakin besar kebebasan untuk menentukan pilihan; paradigma kritis memandang ketidakberdayaan publik disebabkan upaya sistematis dan terstruktur dari kapitalis untuk menguasai mereka. Dengan cara pandang demikian, penelitian yang menggunakan perspektif ekonomi politik dengan paradigma kritis dicirikan oleh tiga hal: holistik, fokus pada dominasi kapitalis, dan berkaitan dengan persoalan moralitas berkaitan dengan publik.61 Lihat misalnya Nordholt dan Van Klinken (eds.), Renegotiating Boundaries. Obet, “Relasi Kapitalisme dengan Organisasi Media”, www.koranpembebasan. wordpress.com-/2013/11/13/relasi-kapitalisme-dengan-organisasi-media/, diunduh pada 12 Desember 2014. 60 61 22 Untuk sampai pada ketiga ciri tersebut, penelitian ini menggunakan metode historis atau sejarah. Metode ini memandang realitas tidak saja dalam satu tahapan waktu atau sinkroni tertentu, melainkan dalam suatu proses diakronis yang panjang. Sebagaimana metode dalam ilmu sosial lainnya, sejarah berupaya menghadirkan cerita (description) dan penjelasan (explanation). Dalam penceritaan dan memberikan penjelasan, metode historis menuturkan suatu objek atau ide (ideographic) dan mengangkatnya sebagai gejala tunggal 62 (singularizing). Masa setelah runtuhnya Orde Baru dan lahirnya Reformasi pada 1998 dijadikan sebagai babakan awal melihat perkembangan media lokal di Jambi. Reformasi dianggap penting karena mengubah struktur politik Indonesia secara signifikan dari sentralisme ke otonomi daerah, yang kemudian memicu pertumbuhan media-media lokal, termasuk di Jambi. Rentang waktu perkembangan koran lokal di Jambi yang panjang dibatasi hingga 2015. 2. Objek Objek penelitian ini adalah media-media lokal di Jambi. Tidak semua media di Jambi menjadi objek penelitian ini, melainkan hanya media berbentuk koran. Pada masa Orde Baru, hanya ada satu koran di Jambi, yakni Jambi Independent, dan setelah Reformasi terdapat 23 koran.63 Semua koran itu menjadi objek penelitian ini. Pertanyaannya, mengapa koran? Dengan sifatnya yang tercetak, arsip koran relatif lebih bisa diakses dibanding jenis media lainnya seperti radio dan televisi, di samping koran dianggap sebagai wujud pelaksanaan praktik jurnalisme yang sebenarnya. Lalu mengapa semua koran yang ada di Jambi? Sebagaimana nanti akan dipaparkan lebih lanjut, meskipun beberapa bisa diakses, banyak data media sulit sekali didapatkan. Selain arsip koran lama yang tak lengkap, beberapa perusahaan Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 2-9. Ke-23 koran tersebut adalah Jambi Independent, Radar Sarko, Radar Bute, Harian Tanjab, Radar Kerinci, Jambi Ekspres, Posmetro Jambi, Bungo Pos, Radar Tanjab, Radar Kerinci, Jambi Ekspres, Posmetro Jambi, Bungo Pos, Radar Tanjab, Sarolangun Ekspres, Jambi Star, Kerinci Pos, Tanjab Ekspres, Batanghari Ekspres, Timur Ekspres, Bute Ekspres, Merangin Ekspres, Aksi Post, Tribun Jambi, Jambi Today, Jambi One, dan Jambi Raya. 62 63 23 koran juga tidak membuka diri selebar-lebarnya kepada peneliti. Selalu ada datadata tertentu yang disembunyikan. Mereka beralasan perusahaan mereka adalah perusahaan privat, sehingga sah saja mereka tidak terbuka. Saya menyadari sepenuhnya hal tersebut menjadi kelemahan penelitian ini. Karena itu, saya memutuskan menjadikan seluruh koran lokal di Jambi sebagai objek, dengan harapan bila ada data dari koran tertentu yang tidak lengkap, akan tertutupi oleh data dari koran lain. Jelas di sini saya mengandaikan adanya pola umum dalam sistem pers di Jambi, hal yang sebetulnya ingin dipahami oleh atau menjadi tujuan dari penelitian ini. 3. Data Data-data penelitian ini terutama terdiri atas dua jenis. Pertama, data-data koran lokal sebagai institusi ekonomi atau “organisasi industri dan komersial yang memproduksi dan mendistribusikan komoditas”.64 Untuk itu, penelitian ini mengumpulkan data tentang jumlah cetakan atau oplah, jalur distribusi atau sirkulasi, jumlah iklan atau pendapatan, serta mekanisme pencarian iklan.65 Kedua, data-data koran lokal sebagai aparatus ideologis yang merupakan “dimensi ideologis produksi media massa”, yang tidak hanya menuntut pengumpulan datadata ekonomi sebagaimana yang pertama, tetapi juga data menyangkut struktur politik yang bekerja di seputar media. Data terakhir ini “penting untuk mendemonstrasikan bagaimana ideologi diproduksi dalam praktik yang nyata.”66 Data jenis ini berkenaan dengan struktur dan praktik politik lokal (partai dan aktor yang menguasai politik lokal), peran yang dimainkan koran lokal dalam politik daerah, hubungan antara keduanya, serta bagaimana politik memengaruhi koran lokal. 64 Graham Murdock dan Peter Golding, “For a Political Economy of Mass Communications”, R. Miliband dan J. Saville (eds.), The Socialist Register 1973, (London: Merlin Press, 1974), hlm. 205-206. 65 Pengumpulan data-data ekonomi media ini misalnya disarankan oleh Douglas Gomery, “Media Economics: Terms of Analysis”, Critical Studies in Mass Communication, 6 (1989), hlm. 43-60. 66 Murdock dan Golding, “For a Political Economy”, hlm. 206. 24 Data-data tersebut dikumpulkan dalam kesempatan yang luas. Saya telah memulainya sejak saya bekerja sebagai redaktur bahasa di Jambi Independent pada 2008-2010. Saya melibatkan diri dalam pergaulan dengan para wartawan serta melihat dari dekat mereka meliput dan menulis berita, tidak saja wartawan dari institusi tempat saya bernaung tetapi juga dari media lain. Relasi yang tetap saya jaga bahkan setelah 2010 ketika saya tak lagi bekerja di media tersebut memudahkan saya menggali tidak saja data jenis pertama, tetapi juga dana jenis kedua. Lebih khusus saya mengumpulkan data untuk keperluan penulisan tesis dalam beberapa kesempatan saya berkunjung atau pulang ke Jambi. Yang pertama pada Januari-Februari 2014. Saat itu saya sudah mulai berancang-ancang memilih koran lokal di Jambi sebagai topik tesis saya. Fokus pengumpulan data lebih lanjut berlangsung pada Maret hingga Desember 2015 dan Februari hingga Juni 2016. Dalam kesempatan yang luas itu, saya mengunjungi semua kantor koran serta kantor humas pemerintah daerah yang ada di sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Jambi. Saya mendatangi perusahaan percetakan koran serta melihat bagaimana koran-koran dicetak, yang berguna sekali untuk memastikan berapa oplah koran yang sebenarnya. Demi mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sirkulasi dan distribusi koran lokal ke daerah-daerah di Jambi, saya ikut mobil ekspedisi pengantar koran yang berangkat tengah malam dan harus sampai di tujuan sebelum matahari terbit. Saya juga ikut dalam mobil ekspedisi estafet atau lanjut untuk daerah yang jauh seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh pada pagi harinya. Di dua daerah itu, target kedatangan koran adalah tengah hari. Di sela pengumpulan data lapangan itu, pada Mei-Juni 2015 saya memeroleh fellowship di Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore (NUS). Kesempatan berharga itu saya gunakan untuk mengumpulkan banyak data kepustakaan, yang bermanfaat sekali bagi pemahaman saya akan sejarah perkembangan media di Indonesia dan perubahan politik dari rezim otoritarian Orde Baru ke Reformasi. Di ARI, saya juga mendiskusikan topik ini 25 dengan beberapa peneliti, menulis studi pendahuluan, serta mempresentasikan temuan awal dalam sebuah konferensi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, utamanya wawancara, dokumentasi, pembacaan terhadap arsip, dan pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap insan media, mencakup pemimpin media, wartawan, serta personel koran yang lain seperti sales iklan, menyangkut pengalaman mereka bekerja di koran lokal, cara mereka mengelola media, serta sistem kerja yang berlaku. Banyak insan media yang masih aktif menjawab diplomatis bahkan tertutup ketika wawancara mulai memasuki wilayah “dapur” perusahaan mereka. Sementara itu, mereka yang sudah tidak lagi bekerja di media, yang cukup banyak saya wawancarai, biasanya berlaku sebaliknya. Mereka menjadi sangat terbuka dan banyak membuka “rahasia” koran bekas tempat mereka bekerja. Wawancara juga dilakukan terhadap insan yang sering berhubungan dengan koran, seperti pejabat atau pegawai pemerintah daerah, pemimpin organisasi wartawan, dll. Wawancara dengan pemerintah daerah berguna untuk mengetahui cara mereka berhubungan dengan koran lokal, relasi yang dibangun, jumlah langganan mereka, serta anggaran pemerintah daerah untuk koran lokal. Dua hal terakhir ini biasanya berlanjut dengan permintaan beberapa dokumen pendukung seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Perubahan (APBDP), atau laporan penggunaan anggaran untuk tahun yang sudah lewat. Meskipun segala prosedur penelitian di daerah sudah saya penuhi, data-data anggaran tidak selalu mudah saya dapatkan. Saya sering kali harus bolak-balik ke Bagian Humas (yang mengelola anggaran untuk media), Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) atau yang sejenisnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), atau ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketika prosedur resmi sering tak membuahkan hasil, pertemanan dengan beberapa staf instansi-instansi tersebut serta “jalur tak resmi” sering menjadi solusi dan memudahkan pencarian dokumen anggaran tersebut. Total tak kurang 50 wawancara saya lakukan terhadap mereka. Terkadang, ketika satu sumber telah saya wawancarai, saya harus mengulang pada waktu 26 yang lain untuk melakukan pendalaman serta menggali topik lebih lanjut. Saya bahkan memiliki kontak elektronik pribadi nyaris semua sumber yang saya wawancarai, yang kerap saya gunakan untuk mengonfirmasi beberapa temuan penting terutama pada saat proses penulisan hasil penelitian. Sementara itu, beberapa arsip dikumpulkan dari kantor koran, disortir berdasarkan isu-isu yang relevan dengan penelitian, dan didokumentasikan untuk keperluan penulisan. Teknik pengumpulan data ini berguna sekali untuk mengonfirmasi beberapa temuan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Saya misalnya membaca semua koran beberapa bulan bahkan setahun sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jambi 2010 dan 2015 untuk memastikan berapa jumlah iklan yang dipasang oleh pemerintah daerah yang kepala daerahnya menjadi kandidat. Di dalam wawancara misalnya dikatakan mereka tak banyak memasang iklan, begitu juga angka di dalam anggaran, tetapi kenyataannya iklan yang dipasang di koran sangat besar. Kroscek data melalui pembacaan arsip penting untuk memastikan keabsahan data. Harus diakui bahwa banyak koran di Jambi buruk sekali dalam mengelola arsip koran lama mereka. Koran-koran lama kebanyakan diikat dan ditumpuk begitu saja di gudang. Beberapa koran yang besar, seperti Jambi Independent, Jambi Ekspres, dan Tribun Jambi, jelas lebih unggul soal pengarsipan tersebut. Koran-koran tersebut juga memiliki arsip daring yang bisa diakses publik, meskipun terbatas untuk beberapa tahun terakhir. Kecuali dari mereka, Perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi punya arsip yang rapi untuk beberapa koran lokal, yang lebih bisa saya andalkan. Saya juga mengunjungi dan mencoba mencari arsip koran lokal Jambi di Museum Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, namun data-data di sana tak banyak membantu penelitian saya. Sebagaimana telah disinggung, wawancara, pembacaan arsip, dan pengamatan lapangan dalam penelitian ini bukan sekadar metode untuk mengumpulkan data, melainkan juga teknik yang digunakan untuk melihat keabsahan data yang telah dikumpulkan. Terbuka kemungkinan hasil wawancara berbeda dengan data arsip atau hasil pengamatan. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan awak koran, acap dikatakan bahwa koran mereka dicetak 27 dalam jumlah angka yang tinggi sekali. Kenyataan yang ada di lapangan ternyata jumlahnya tak setinggi angka yang disebutkan dan berada jauh di bawahnya. Untuk itu, dalam pengumpulan data juga ditekankan upaya verifikasi dan falsifikasi data yang telah terkoleksi. Semua data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara memilahmilah dan menyeleksinya berdasarkan sub-subtopik penelitian. Proses ini tidak sebentar, terutama untuk data keuangan pemerintah daerah di bidang media. Ada banyak data keuangan yang tidak selalu sama, misalnya yang bersumber dari anggaran murni, anggaran perubahan, dan laporan penggunaan anggaran. Saya harus mendiskusikan dengan orang yang mengetahuinya untuk memastikan sumber mana yang mesti saya gunakan. Dari hasil seleksi tersebut, beberapa data yang tidak relevan dengan penelitian kemudian dibuang. Data-data hasil seleksi dan sudah terbukti valid selanjutnya diinterpretasi. Untuk menghindari kesalahan, sekali lagi saya mengandalkan interpretasi silang antarsumber data. Dalam banyak kasus, saya juga mengonfirmasikan interpretasi saya atas data kepada sumbersumber yang pernah saya wawancarai melalui sambungan elektronik pribadi. Proses selanjutnya adalah penyajian data hasil penelitian. Secara umum, penulisan deskriptif menjadi teknik penyajian yang banyak digunakan. Di beberapa tempat, untuk memeroleh pemahaman atas asal-usul atau genealogi, misalnya ketika membahas sejarah industri koran lokal di Jambi, saya mengombinasikannya dengan penulisan kronologis. Di lain tempat, karena tuntutan analisis yang digunakan, teknik argumentasi juga cukup mewarnai. 4. Analisis Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa yang dikenal di dalam ilmu sosial sebagai analisis ekonomi politik. Dipilih karena melihat data yang telah dikumpulkan tidak sekadar sebagai deskripsi kenyataan atau fakta sosial, analisis ekonomi politik mengulik lebih lanjut berbagai kepentingan di balik datadata tersebut. Pada awalnya, analisis ini merupakan kritik terhadap analisis ekonomi konvensional yang menekankan keseimbangan (equilibrium). Adam Smith, 28 pencetus teori ekonomi klasik tersebut, berpendapat bahwa kepemilikan uang atau modal akan menyebar dengan sendirinya melalui mekanisme yang murni pasar berdasarkan prinsip pertukaran (exchange). Dengan prinsip ini, menggenggam semua uang dan melepas seluruh barang hanya akan membuat harga jatuh, sebaliknya mengambil semua barang dan melepas uang akan membuatnya naik. Kedua sudut ekstrem itu tidak mungkin terjadi dan uang akan dengan sendirinya menyebar, yang pada akhirnya membuat keseimbangan antara kepemilikan uang dan barang. Salah satu kritik terhadap ekonomi klasik ini adalah pengabaiannya terhadap berbagai faktor di luar ekonomi seperti struktur sosial, akses informasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, ekonomi tidak mempertimbangkan relasi kuasa yang hendak mengontrol pasar dan produksi sekaligus. Sebagai kritik terhadap ekonomi konvensional, karena itu, ekonomi politik didefinisikan sebagai “relasi sosial, khususnya relasi kuasa, yang membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya”.67 Komunikasi tentu saja tidak berbeda dari dan termasuk sumber daya tersebut, sehingga produk komunikasi seperti koran dan distribusinya serta pilihan konsumen atasnya juga dibentuk dan dipengaruhi oleh relasi kuasa. Dengan tekanannya pada relasi kuasa, ekonomi politik banyak disumbang oleh tradisi Marxis. Menurut teoretikus ekonomi politik, ada empat karakteristik analisis ekonomi politik, yakni historis, multidisiplin, penekanan pada moral, dan praksis. Penjelasan singkat atas keempatnya adalah bahwa berbagai kekuatan yang membentuk sebuah fakta sosial tidak begitu saja bisa dipahami dalam suatu babakan waktu tertentu, karena itu perlu dilihat dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang. Demikian pula, suatu fakta sosial itu tidak cukup hanya dilihat dari suatu sudut atau teori saja, melainkan perlu penggunaan banyak teori. Asumsinya adalah sebuah fakta sosial itu kompleks dan total. Berbeda dari analisis lain yang “normal”-nya hanya untuk kepentingan ilmu, ekonomi politik fokus pada relasi Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, 2nd edition, (London, California, New Delhi, dan Singapore: Sage, 2009), hlm. 24. 67 29 sosial yang timpang yang merugikan publik, yang hasilnya tidak sekadar refleksi, tetapi praktis dan dapat digunakan atau berguna bagi publik.68 Dengan karakteristiknya yang historis dan multidisiplin, pendekatan di dalam analisis ekonomi politik menjadi sangat luas. Banyak analis ekonomi politik kemudian menyarankan tiga pintu masuk, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Pada intinya ketiganya melihat relasi kuasa yang: membentuk perubahan nilai dan fungsi sumber daya (komodifikasi), memengaruhi dinamika ruang di mana sumber daya berada (spasialisasi), dan mengatur praktik sosial dari sebuah sumber daya (strukturasi).69 Analisis ekonomi politik di dalam penelitian ini tidak secara rigid menggunakan tiga pintu masuk tersebut. Mengandalkan data historis yang sangat luas, analisis pertama-tama dilakukan secara deskriptif dengan fokus mencari relasi kuasa yang menyebabkan industri koran lokal berkembang di Jambi. Deskripsi seperti itu penting karena data sejarah butuh penjelasan lebih lanjut menyangkut konteks dan struktur (kekuasaan) yang menggerakkannya.70 Berangkat dari detail penjelasan-penjelasan historis tersebut, secara induktif analisis berusaha menemukan pola-pola atau praktik umum yang terjadi dalam industri koran lokal di Jambi. Di sini kemudian, pada akhirnya banyak temuan analisis tampaknya menginformasikan praktik-praktik komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Jadi, meskipun tidak berangkat dari tiga pintu masuk dalam analisis ekonomi politik media sebagaimana banyak disarankan teoretikus ekonomi politik, penelitian ini tidak juga mengabaikannya. Secara induktif bahkan analisis yang digunakan menemukan banyak detail praktik ketiganya yang mungkin unik dan berbeda dari komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi di tempat lain. Mosco, The Political Economy, hlm. 26-36. Antara lain Mosco, The Political Economy; Murdock dan Golding, “For a Political Economy”, hlm. 205-234; Nicholas Garnham, “Contribution to a Political Economy of Mass Communication”, Fred Inglis (ed.), Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of Information, (London: Sage, 1990), hlm. 20-55. 70 Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah, hlm. 2-9. 68 69 30 G. Sistematika Mempertimbangkan pendekatan dan analisis yang digunakan serta keluasan objek dan data yang dicakup oleh penelitian ini, hasilnya ditulis ke dalam sembilan bab yang diorganisasikan dengan sistematika berikut. Setelah Bab I Pendahuluan yang mengantarkan penelitian ini, Bab II Koran Lokal, Desentralisasi, dan Persebaran Kapital: Telaah Historis memberikan perspektif yang lebih luas tentang penelitian ini. Dilihat dari sudut sejarah, maraknya koran lokal pasca-Orde Baru jelas merupakan kelanjutan dari sejarah panjang pers Indonesia. Bab ini juga memberikan pengantar tentang desentralisasi, keadaan-keadaan yang mendahuluinya, serta konsekuensinya bagi akumulasi modal di daerah. Sejarah ringkas tentang bagaimana modal bekerja dan bergerak (mobile) juga akan dipaparkan. Bab ini coba menyambungkan tiga konsep penting dalam penelitian ini: koran lokal, konteks pasca-otoritarianisme Orde Baru, dan modal. Bab III Provinsi Jambi Pasca-Reformasi: Konteks Ekonomi Politik menyediakan diri bagi konteks yang lebih spesifik di mana penelitian ini dilakukan. Bab ini fokus pada keadaan-keadaan di Jambi pasca-Reformasi, berupa kebangkitan lokalitas, munculnya elite-elite lokal baru, akumulasi modal di daerah, serta konsekuensi yang tak diharapkan berupa penyebaran korupsi di daerah. Konteks seperti itulah yang menjadi latar belakang bagi muncul dan berkembangnya koran lokal di Jambi, yang dibahas lebih lanjut di dalam Bab IV Genealogi Koran Lokal di Jambi. Setelah memaparkan secara diakronis munculnya koran-koran di Jambi pasca-Reformasi, bab ini melihat bagaimana koran-koran itu mengembangkan diri melalui aliansi bisnis yang dibangun dan relasinya dengan politik lokal. Sudut pandang industri terkait pertumbuhan cepat koran lokal di Jambi dibahas dalam Bab V Dua Menara Kembar Industri: Sirkulasi dan Iklan. Sebagaimana judulnya, bab tersebut fokus melihat sirkulasi dan iklan sebagai nyawa utama industri koran. Lebih jauh, kaitan iklan dengan politik lokal dipaparkan dalam Bab VI Iklan dan Politik: Kisah Dua Pemilu Lokal. Mengambil dua kasus Pemilihan Gubernur Jambi 2010 dan 2015, bab ini secara spesifik melihat iklan-iklan politik jelang perhelatan keduanya. Iklan-iklan yang semakin 31 besar nilainya jelang dua pemilihan kepala daerah langsung tersebut sebetulnya menggambarkan relasi patrimonial antara koran dan pemerintah daerah. Ketika kepala daerah akan maju lagi dalam kontestasi, dia menggunakan banyak sekali anggaran daerah untuk menyosialisasikan dirinya. Pada Pemilihan Gubernur 2010, lima kandidat dari empat pasangan calon adalah para bupati aktif, sementara pada Pemilihan Gubernur 2015 tiga kandidat dari dua pasangan calon juga merupakan para petahana atau pejawat (incumbent) dan bupati. Anggaran daerah yang diperuntukkan bagi koran lokal dibahas dalam Bab VII Anggaran Daerah untuk Koran Lokal: Korupsi yang Legal?. Fokusnya adalah unit atau lembaga yang mengelola anggaran untuk koran lokal, jumlah anggaran, serta bagaimana siasat yang dilakukan ketika anggaran yang ada tak mencukupi “kebutuhan”. Anggaran yang disediakan tersebut, sekali lagi, memperlihatkan relasi yang erat antara koran lokal dan pemerintah daerah. Namun, relasi itu tidak selalu berjalan mulus, sebagaimana dibahas dalam Bab VIII Dinamika Hubungan Koran Lokal-Politik Lokal. Beberapa kali muncul riak yang sempat mengganggu. Hanya, setiap kali memburuk, selalu ada upaya kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan mereka, memperlihatkan keduanya yang saling tergantung. Koran membutuhkan pemerintah daerah, dan pemerintah memerlukan koran. Bab IX Penutup yang merupakan bab terakhir terutama berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini. Keterbatasan penelitian juga akan dipaparkan, diakhiri dengan kemungkinan penelitian lanjutan yang bisa dilakukan.[] 32