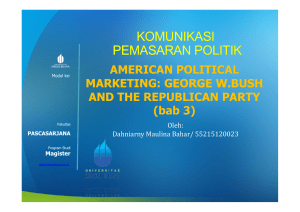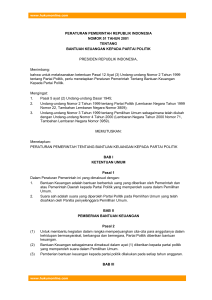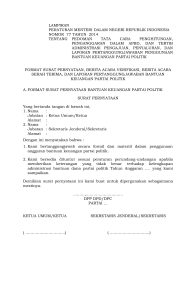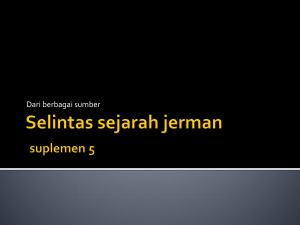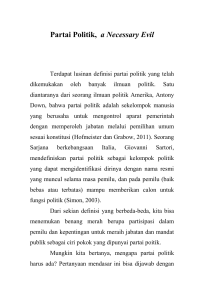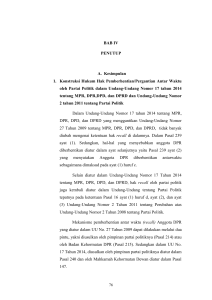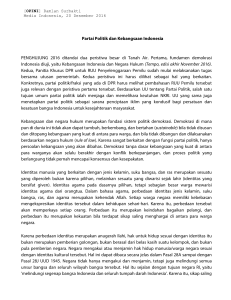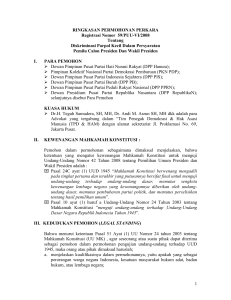BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. REFLEKSI
advertisement

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. REFLEKSI TEORITIS Partai Demokrat didirikan berdasarkan kalkulasi rasional oleh para pendirinya. Pendiri Partai Demokrat menilai mendirikan partai baru merupakan pilihan alternatif yang paling efisien dan menguntungkan dalam mengusung SBY sebagai presiden dibandingkan mengusung SBY lewat partai lain. Namun rasionalitas pendiri Partai Demokrat tidaklah seperti yang dikonsepsikan oleh pendukung rational choice clasik tetapi lebih mendekati dengan konsepsi Herbert A Simon (1995) tentang bounded rasionality. Hal itu bisa dilihat dari beberapa hal. salah satunya perbedaan perhitungan antara Subur Budhisantoso dengan Venje Rumangkang. Subur Budisantoso masih memandang perlu didirikanya Partai Demokrat seandainya pemilihan presiden masih lewat MPR. Sebab peluang SBY menjadi presiden lewat MPR juga tidak kecil. Sedang Venje memandang tidak perlu. Sebab peluangnya SBY menjadi presiden sangat kecil lewat pemilihan di MPR, seperti yang dialami SBY saat maju dalam pemilihan wakil presiden pada 2001. 195 Selain itu, keputusan mendirikan Partai Demokrat diambil karena para pendiri meyakini partai yang akan didirikan nanti memiliki peluang mendapatkan dukungan dari pemilih pada pemilu 2004. Peluang itu didasarkan pada kinerja partai lama yang tergabung dalam koalisi partai pemerintah dinilai buruk oleh sebagian besar masyarakat. Buruk kinerja partai lama ini menimbulkan isu baru yang memungkinkan menuculnya Partai Demokrat sebagai partai baru untuk menawarkan diri sebagai alternatif pilihan pemilih saat pemilu. Tavit (2007) melihat gejala ini (buruknya kinerja partai) sebagai akibat dari banyaknya permasalahan pelik yang tidak mudah diatasi dalam waktu singkat yang sangat jamak (lumrah) terjadi di negara yang sedang mengalami transisi demokrasi. Namun buruk kinerja partai hasil pemilu 1999 di Indonesia lebih disebabkan oleh pertikaian antar elit dalam merebut kekuasaan dan penyalagunaan kekuasan yang dilakukan oleh elit politik dalam maraih kentungan untuk partai ataupun untuk kepentingan pribadi. Buruknya kinerja partai lama tersebut pada saat yang sama berdampak pada turunya loyalitas pemilih terhadap partai politik hasil pemilu 1999 secara signifikan. Hal ini mengindikasikan turunya identitas kepartaian pasca reformasi lebih bertalian dengan hasil evelausi pemilih terhadap partai sebagaiamana konsepsi Anthony Down (1957) dan kurang bertalian dengan perpecahan atau memudarnya sosial cleavages yang menjadi basis dukungan 196 partai lama sebagaiamana diasumsikan para pendukung pendekatan sosiologis. Selain itu juga menunjukan gejala yang berbeda dengan konsepsi Margit Tavits (2007) dan Cox (1997). Menurut keduanya pada fase awal transisi demokrasi dukungan terhadap partai penuh dengan ketidak-pastian. Ketidak-pastian ini menjadikan setiap peserta pemilu merasa memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mendapatkan suara dan dukungan publik saat pemilihan umum. Meskipun demikian konsepsi Margit Tavits (2007) dan Cox (1997). tersebut barangkali tepat untuk menggambarkan situasi antara masa reformasi 1997 sampai menjelang pemilu 1999. Buruknya kinerja partai lama tersebut diperkuat oleh absennya partai oposisi yang kuat. Partai Keadilan yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtrah merupakan satu – satunya partai oposisi pada saat itu. Namun PK / PKS pada saat itu merupakan partai berhaluan kanan ekstrim. Kondisi tersebut menyulitkan PK / PKS untuk mendapatkan limpahan suara masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai lama. Sebab pada umumnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang moderat. Melihat hal ini Partai Demokrat dirancang oleh para pendirinya sebagai partai tengah. Hal ini dimaksudkan agar Partai Demokrat mendapatkan dukungan masyarakat dari berbagai kalangan. 197 Meskipun demikian, buruknya kinerja partai lama dan absenya partai oposisi yang kuat bukanlah variable atau faktor independen yang berpengaruh terhadap dukungan bagai partai baru. Variable ini sangat tergantung pada keberadaan tokoh utama partai yang mampu sebagai magenet electoral atau merarik pemilih yang kecewa terhadap kenerja partai lama. Pendiri Partai Demokrat meyakini keberadaan SBY sebagai tokoh utama dan ikon Partai Demokrat akan bisa memikat dan menarik pemilih untuk memilih Partai Demokrat. Keyakinan itu di dasarkan pada dua hal. Pertama, SBY merupakan salah satu kandidat calon wakil presiden yang paling populer versi poling yang dilakukan oleh beberapa media massa pada saat itu. Kedua, sebagian karakteristik pemilih Indonesia dalam memilih partai politik masih melihat kualitas tokoh utama yang dimiliki dan dijual oleh partai dalam pasar pemilu. Hasil pemilu 1999 menyiratakan pesan bahwa tokoh utama yang dimiliki oleh partai merupakan salah satu alat tukar untuk mendapatkan (membeli) suara pemilih dalam pasar pemilu yang cukup efektif. Temuan dalam tesis ini mengkonfirmasi konsepsi Barnes, Mc Donough, dan Pina, (1985) Liddle dan Mujani (2000) dan studi yang dilakukan oleh Mujani, Liddle dan Ambardi (2012). 198 Menurut Harmel dan Robertson (1985) dan Hug (2001), negara yang memiliki populasi yang lebih beragam dan lebih besar cenderung memiliki kebutuhan representasi yang lebih kompleks dan dalam banyak hal menghasilkan masalah baru yang memungkinan masuknya partai baru. Namun konsepsi tersebut tidak didukung oleh bukti dalam penelitian ini. Partai Demokrat secara sengaja didirikan tidak sebagai artikulator kelompok sosial, ideologi atau masyarakat di wilayah tertentu dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buktinya pengurus dan calon anggota legislatif maupun DPR terpilih, kepala daerah dari Partai Demokrat berasal dari berbagai berbagai kelompok. Selain itu, isu dan kebijakan yang diusung dalam kampanye bukan isu segmented melainkan isu yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, Partai Demokrat sengaja tidak ditempatkan pada salah satu klaster pembilahan sosial (cleavages) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Secara tekstual Partai Demokrat memang memiliki ideologi. Namanya nasionalis - religius. Namun ideologi tersebut bukan terjemahan dari ideologi atau cita – cita kelompok sosial tertentu. Partai Demokrat merupakan partai otonom (dari berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat). Partai Demokrat berusaha mencari dukungan masyarakat dari semua segmen (nasionalis – religius) untuk mendapatkan kekuasaan sebesar - besarnya. Partai Demokrat pada kenyataanya juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dari berbagai segmentasi. 199 Sistem pemilu sebagaimana asumsi Taagepera (1999) dan Octavio Amorim Neto dan Gary W Cox (1997) berpengaruh terhadap peluang keberhasilan partai untuk mendapatkan kursi dalam pemilu. Semestinya ini menjadi pertimbangan aktor dalam mendirikan partai politik. Namun sistem pemilu tidak menjadi basis rujukan penting bagi berdirinya Partai Demokrat. Sebab sistem pemilu baru diputuskan setelah Partai Demokrat didirikan dan dideklarasikan. Elit seringkali mendirikan partai sebagai sarana untuk menduduki kursi presiden (eksekutif) seperti konsepsi Andreas Ufen (2006) tentang munculnya partai presiden (presidentialized party) atau partai pribadi (personal party) sebagaimana konsepsi Koichi Kawamura (2013). Ketika peluang tokoh utama partai untuk menjadi presiden kecil atau tidak ada, mendirikan bisa dipandang tidak lagi penting. Pendiri Partai Demokrat dalam kenyataanya tidak hanya menghitung peluang Partai Demokrat dalam mendapatkan dukungan tetapi juga peluang SBY dalam mendapatkan dukungan sebagai presiden di pemilu 2004. Hal ini didasarkan pada tinnginya hasil poling saat SBY menjadi calon wakil presiden maupun hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Subur Budisantoso. Selain itu, potensi SBY sebagai calon presiden alternatif juga karena SBY memiliki karakter yang dingingkan public dan kepiawaian SBY dan timnya dalam membagun komunikasi dengan publik. SBY sampai batas tertentu mampu 200 memunculkan diri sebagai sosok yang cerdas, santun dan bersih. Potensi ini sudah mulai tampak dimata public sejak SBY mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pada saat yang sama peforma tokoh utama partai lain, utamanya yang memiliki potensi menjadi capres pada pemilu 2004 memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat dan memiliki kelemahan dari sisi komunikasi publik. Faktor ongkos yang murah untuk biaya mendirikan dan operasional partai serta biaya mengikuti pemilu merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan didirikanya Partai Demokrat. Hanya saja perhitungan pendiri Partai Demokrat berbeda dengan hasil studi para peneliti sebelumnya yang mengkaji kemunculan partai politik dalam rumpun rational choice. Para peneliti sebelumnya seperti Tavits (2006, 2007) dan Simon Hug (2001) lebih banyak menyoroti penilaian atau perhitugan aktor terhadap ogkos mendirikan partai dan mengikuti pemilu dari sisi faktor institusional, seperti pertalian biaya mendirikan partai dengan aturan mendirikan partai dan aturan pendanaan partai serta hubungan antara biaya mengikuti pemilu dengan sistem pemilu. Faktor ketokohan SBY di Partai Demokrat tidak hanya dinilai oleh para pendiri Partai Demokrat sebagai vote getter tetapi juga sebagai money gatter. Pendiri Partai Demokrat meyakini Keberadaan SBY di Partai Demokrat akan membuat masyarakat dari berbagai kalangan bersimpati dan membantu pendanaan Partai Demokrat. Selain itu, keberadaan SBY juga akan membuat beberapa tokoh 201 potensial ikut bergabung dan mendanai Partai Demokrat. Implikasinya pendanaan Partai Demokrat bisa ditanggung secara gotong royong. Sumbangan masyarakat dan pendaan secara gotong royong dipandang pendiri Partai Demokrat sebagai faktor yang membuat biaya mendirikan partai dan biaya mengikuti pemilu yang semula mahal menjadi ringan. Pendiri Partai Demokrat tidak menjadikan aturan pendaftaran partai sebagi basis dalam menghitung besaran dana dan komponen pembiayaan yang dipersiapkan untuk mendirikan Partai Demokrat sebab Partai Demokrat didirikan sebelum Undang – Undang Partai Politik dan sistem pemilu disahkan oleh negara. Besaran pendanaan lebih bertalian dengan kebutuhan eksistensi partai di masa yang akan datang, seperti pembentukan DPD, DPC dan KTA anggota. Menurut Cox (1997) jika disiplin kepartaian lebih longgar, maka semakin kecil munculnya partai baru. Elit politik akan lebih senang bergabung dengan partai yang sudah mapan untuk mengejar atau mewujudkan kepentingan sendiri dari pada mendirikan partai baru. Sebab pilihan tersebut dipandang lebih murah dan menguntungkan. Tesis Gary W Cox tersebut dalam batas tertentu berbeda dengan kalkulasi orang – orang yang terlibat sebagai pendiri Partai Demokrat. Keputusan mendirikan partai baru untuk mengantarkan SBY menjadi presiden dinilai lebih murah dibandingkan mengusung SBY lewat partai orang lain meskipun seandainya peluang mengsung SBY menjadi presiden lewat partai 202 orang lain ada. Sebab partai orang lain tersebut diyakini akan meminta uang sewa yang lebih tinggi dari ongkos yang dibutukan untuk mendirikan partai baru. Pendiri sangat yakin dalam rentang waktu sejak reformasi sampai dengan pemilu 2004 media akan banyak menyorot SBY karena SBY figur besar dan menjadi pejabat publik. Hal itu dinilai sebagai iklan gratis bagi Partai Demokrat dan SBY. Hal ini menguatkan konsepsi Carina (2011) bahwa sentiemen positif media terhadap partai baru bisa mengurangi ongkos biaya kampanye secara signifikan. Keputusan beberapa orang untuk mendirikan Partai Demokrat tersebut menunjukan faktor ongkos menjadi basis pertimbangan yang cukup penting dalam mendirikan sebuah partai baru pasca reformasi di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan hasil studi yang dilakukan oleh Harmel & Robertson (1985: 516-17) terhadap 233 partai baru di 19 negara demokrasi di Eropa Barat dan Anglo Amerika. Menurut Harmel & Robertson (1985: 516-17) variable biaya untuk mendapatkan suara tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya partai politik baru di negara tersebut. Temuna dalam tesis ini berani menyimpulkan, faktor ketokohan seseorang atau figur utama merupakan variable independen dalam mempengaruhi murah dan mahal ongkos mendirikan partai baru dan mengikuti pemilu. 203 Beberapa akademisi berbeda pendapat terkait dengan apa yang dimaksud keuntungan bagi partai politik. Menurut Jonathan Hopkin (2000) kekuasaan politik bagi partai sama dengan keuntungan moneter bagi perusahaan. Hal itu diperjelas lagi oleh Margit Tavits. Menurut Tavits (2006:104) di dalam kekuasaan selalu melekat keuntungan matriil dan prestise. Keuntungan ini tidak bergantung pada sistem yang sedang berlaku di suatu negara. Pendiri Partai Demokrat sebagai mana yang telah dinyatakan oleh Sutan Bhatugana tidak mengelak kalau didalam kekuasaan itu ada beberapa keuntungan matriilnya, seperti gaji, tunjangan, prestise, subsidi dana partai dari negara dan sejenisnya. Namun Sutan Bhatugana menekankan, pendiri Partai Demokrat tidak memiliki tujuan untuk meraih keuntungan lewat cara – cara yang tidak benar sebagaimana yang telah dilakukan oleh kader – kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi. Keuntungan matriil yang diperoleh oleh partai politik dalam kenyataanya tidak hanya di dapatkan melalui jalan yang legal. Hal itu bisa terjadi kerena pemerintah Indonesia memiliki kendali yang sangat besar dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang langkah, seperti lisensi pengelolaan sumber daya alam. Kasus suap di SKK Migas merupakan salah satu dari sekian banyak contoh bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan DPR dalam 204 mengelola sumber daya ekonomi tidak diberikan secara gratis kepada pengusaha yang membutukan. Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai proyek proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang nilai ratusan triliyun rupiah dalam setiap tahun. Proyek – proyek tersebut dalam kenyataanya tidak diberikan secara cuma – cuma kepada pihak kontraktor atau pemenang tender. Kasus Hambalang dan Wisma Atelit yang melibatkan kader Partai Demokrat merupakan salah satu contoh dari sekian banyak contoh bahwa proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara transparan dan diperjual-belikan untuk mendanai partai maupun untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh partai politik lewat jalur ilegal ini luar biasa besar dibandingkan lewat keuntungan yang diperoleh lewat jalur legal. Sistem pemilu presiden secara langsung dianggap oleh sebagian pendiri Partai Demokrat sebagai sistem yang cukup menguntungkan untuk mendirikan partai sebagai sarana untuk mengusung SBY sebagai presiden. Vence mangakui jika pemilihan presiden secara langsung juga merupakan salah satu alasan penting didirikanya Partai Demokrat. Sebab tokoh utama Partai Demokrat pada waktu itu sedang digandrungi oleh masyarakat sehingga peluang Partai Demokrat dalam mengantarkan Pak SBY menuju istana sangatlah besar. “Kalau sistem pemilihanya seperti tahun 1999, meskipun Popularitas Pak SBY tinggi di mata masyakat, potensi untuk dikalahkan oleh calon presiden dari partai besar yang 205 telah mapan sangat besar. Perhitungan itu sesuai dengan konsepsi Bollin. Menurutnya (2007) pemilihan presiden secara langsung memberi kesempatan yang lebih baik bagi partai baru dalam menapatkan kekuasaan. Namun faktor ini tidak kuat, sebab sebagian pendiri (Subur Budhisantoso) menilai Partai Demokrat tetap akan didirikan sebab peluang Partai Demokrat untuk mengantarkan SBY menjadi presiden dalam sistem pemilihan presiden lewat anggota MPR tidak otomatis tertutup. Kondisi perpolitikan di Indonesia menunjukan peluang partai baru dalam mendapatkan kekuasaan di eksekutif lewat voting di MPR atau lewat pemilu secara langsung sama – sama bagus. Konsepsi dasar Negara Indonesia menurut Undang – Undang Dasar 1945 adalah presidensial tetapi perebutan kekuasaan di Indonesia tidak mengenal istilah the winner takes all (Pemenang mengusai semua jabatan). Kekuasaan di eksekutif dan di legislatif didistribusikan secara proporsional ke pada partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian fakta politik di Indonesia pasca reformasi dalam batas tertentu bertolak belakang dengan tesis Charles Hauss dan David Rayside (1978). Menurutnya, sistem presidensial mencegah pembentukan partai baru. Sifat sistem presidensial the winner takes all (Pemenang mengusai semua) akan mendorong partai politik untuk berkolaborasi dan merger untuk memenangkan kekuasaan di pemerintahan daripada mendorong munculnya partai baru. 206 Partai Demokrat dilahirkan dalam sistem presidensial yang memungkinkan jabatan di eksekutif dan di DPR dibagi secara merata ke berbagai partai politik. Menurut asumsi Carina (2011) hal ini lebih memudakan bagi partai baru untuk mendapatkan akses dalam rangka untuk mempengaruhi sistem kekuasaan yang memungkinkan kekuasaan dapat dibagi lebih luas di antara beberapa partai dan parlemen memainkan peran yang lebih besar dalam check and balance. Tetapi hal itu tidak menjadi basis pertimbangan didirikanya Partai Demokrat. Dengan demikian temuan dalam tesis ini juga berbeda dengan konsepsi Carina S. Bischoff. Selain itu temuan dalam tesis ini juga menunjukan gejala negative terhadap tesisnya Simon Hug. Sebab jika dilihat dari fakta di atas menunjukan bahwa kondisi perpolitikan di Indonesia tidak terkosentrasi pada satu titik lembaga dan satu partai politik melainkan menyebar ke beberapa lembaga dan partai politik. Menurut Konsepsi Hug kondisi tersebut tidak kondusif bagi munculnya partai baru. Kenyataanya Partai Demokrat dan beberapa partai baru lainya tetap muncul. Menurut Margit Tavits (2006) pengaruh kelompok non electoral yang sangat kuat dalam mempengaruhi kebijakan membuat keuntungan mendirikan menjadi berkurang. Hal bisa membuat politisi kurang tertarik untuk membentuk partai 207 baru. Namun Carina (2011), kelompok non eletoral terkadang menjadi sumber dukungan bagi partai politik. Pendiri Partai Demokrat tidak menjadikan pengaruh kelompok non electoral dalam kebijakan sebagaimana yang diasumsikan Tavits dan juga tidak menjadikan dukungan kelompok non electoral sebagai yang di asumsikan Carina S. Bischoff sebagai basis pertimbangan didirikanya Partai Demokrat. Dididrikanya Partai Demokrat sebagai sarana untuk mengusung SBY sebagai presiden juga didasari oleh perhitungan mengusung Pak SBY menjadi presiden 2004 lewat partai sendiri lebih menguntungkan daripada mengusung Pak SBY lewat partai orang lain. Jika lewat partai orang lain, orang lain yang akan menentukan berbagai pos jabatan strategis dan lain sebagainya. Tetapi kalau lewat partai sendiri, mereka sendiri yang menentukan. Hal ini tentu lebih menguntungkan mengusung SBY lewat partai sendiri. Melihat fakta di atas menunjukan pendiri Partai Demokart tidak memiliki perhitungan yang terinci mengenai keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dan hal apa saja yang akan mengurangi keuntungan mendirikan partai baru sebagaimana konsepsi atau temuan beberapa akademisi yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Ini menunjukan perhitungan mengenai manfaat memegang jabatan menjadi skunder. Sedangkan peluang untuk meraih dukungan pemilih untuk memperoleh jabatan menjadi perhitungan pokok. Hal 208 ini karena keuntungan selalu melekat dalam kekuasaan. Kekuasaan bisa menjadi senjata bagi elit untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain semakin tinggi peluang untuk memperoleh jabatan, maka otomatis semaking tinggi potensi keuntungan yang akan diraih. Kondisi ini seperti yang dikatakan oleh Tavits (2006) jika peluang dukungan cukup besar perhitungan elit terkait manfaat memegang jabatan menjadi skunder. Sebalinya, jika peluang dukungan terhadap partai baru kecil pehitungan elit terhadap manfaat memegang jabatan menjadi perhitungan pokok bagi elit. B. IMPLIKASI Kehadiran Partai Demokrat (PD) di Indonesia pasca reformasi merupakan hasil dari kalkulasi, preferensi dan strategi individu dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau tujuaanya. Meskipun demikian, dalam batas tertentu kehadiran Partai Demokrat masih memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahtraan masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti kenaikan pendapatan perkapita, penurunan persentase penganguran dan kemiskinan. Ukuran ini bertumpuh pada asumsi keberhasilan atau kinerja pemerintah adalah program atau kenirja partainya. Selebinya dapat dilihat dalam tebel di bawah ini. Tabel 10. Persentase Pendapatan Perkapita, Pengangguran dan Kemiskinan Pertahun Pendapatan Persentase Persentase Tahun Perkapita pengangguran Kemiskinan 10,4 10,25 16,66 2004 209 12,4 11,89 15.97 2005 14,7 10,93 17.75 2006 17,2 10,01 16,58 2007 21,0 9,39 15,42 2008 23,6 8,96 14,15 2009 28,8 8.32 13,33 2010 30,4 7,70 12,49 2011 33,3 7,24 11,66 2012 Sumber BPS, dalam Data Dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004 -2012 BPS – Bapenas 2013 ; 5,13. Menurut Sutan Bhatugana, jika pada pemilu 2004, kami hanya mengandalkan figur SBY tetapi setelah itu kami mengandalakan program – program, utamanya dalam peningkatan kesejahtraan masyarakat agar Partai Demokrat dipilih oleh rakyat.59 Itu artinya peningkatan kesejahtraan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bertumpuh pada sikap alturistik60 tetapi bertumpuh pada self interes atau dalam terminology Herbert A Simon disebut sebagai reciprocal alturism61. Hal ini bisa terjadi karena bekerjanya hukum “invisible hand”. Kebijakan bagi politisi dan rakyat sama dengan barang konsumsi bagi pedagang dan konsumen. Perilaku pedagang hanya termotivasi untuk mencari keuntungan sebesar – besarnya bagi dirinya sendiri, namun kemampuan mereka untuk memperoleh keuntungan bergantung pada kemampuan mereka memproduksi barang-barang yang lebih murah dan lebih berkualitas dibandingkan para pesaingnya. Begitu juga dengan politisi, pada umum mereka termotivasi untuk mencari kekuasaan sebesar – besarnya dalam pasar pemilu, namun kemampuan politisi dalam 59 . Wawancara dengan Sutan Bhatugana. Jakarta. 10/10/2013. Pukul 13.47 – 14. 41 WIB . Sikap relah berkorban (waktu, tenaga dan sejenis) demi keuntungan orang lain. 61 Menurut Herbert A Simon (1995:55) reciprocal altruism adalah tindakan berkorban demi orang lain dengan asumsi akan mendapatkan balasan dalam waktu jangka panjang. 60 210 mencari kekuasaan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mengeluarkan kebijakan yang populis bagi pemilih, utamanya yang bertalian dengan hajat hidup banyak orang (kesejahtraan). Jika mereka gagal, maka pesaingnya (oposisi atau partai baru) yang dinilai oleh pemilih mampu menawarkan alternatif kebijakan yang populis yang akan dipilih dalam pemilu. Hal itu semakin menguatkan hipotesis Anthony Down. Menurut Downs (1957b:137) partai politik dalam negara demokrasi merumuskan kebijakan sebagai sarana untuk mendapatkan suara. Mereka tidak berusaha untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu atau untuk melayani setiap kelompok kepentingan tertentu, melainkan mereka merumuskan kebijakan dan melayani kelompok kepentingan untuk mendapatkan jabatan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populis, seperti kenaikan BBM, pemerintah pada saat yang sama mengeluarkan kebijakan stimulus berupa uang konpensasi seperti BLT, BLSM dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko atau dampak negatif kebijakan pada saat pemilu. Atas dasar itu, pemerintahan SBY pernah memintah persetujuan anggran BLSM diputus terlebih dahulu sebelum keputusan kenaikan harga BBM disetujui oleh DPR. Fakta itu menunjukan Partai Demokrat merasa hawatir jika kenaikan BBM terlanjur disetujui oleh DPR sementara BLSM tidak disetujui. 211 Selain BLT dan BLSM pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan populis lainya yang bersifat jangkah pendek, seperti beras untuk warga miskin (Raskin), asuransi kesehatan untuk warga miskin (Askeskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kompor gas gratis, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan sosial (Bansos). Program – program tersebut menjadi andalan kampanye Partai Demokrat sebagai partai pemerintah. Persaingan dalam mendapatkan suara yang begitu sengit di dalam sistem multi partai mengharuskan Partai Demokrat untuk membuat program – program populis sebanyak mungkin agar bisa mendapatkan kekuasaan sebanyak – banyaknya. Pada sisi yang lain perilaku kader Partai Demokrat tidak selamanya selaras dengan peningkatan kesejahtraan masyarakat. Terungkapnya kasus korupsi Wisma Atelit dan Hambalang adalah salah satu contoh perilaku kader Partai Demokrat yang tidak selaras dengan agenda peningkatan pembangunan dan kesejahtraan rakyat. Itu menunjukan hukum “invisible hand” dalam praktik politik sulit terlaksana seratus persen atau sepenuhnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka bergabung dengan partai, berinvestasi, mengeluarkan tenaga, pikiran dan sejumlah uang. Sebagian besar mereka bukan relawan yang dengan tulus masuk partai dalam rangkah memperjuangkan cita – cita atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, mereka membutukan imbalan dan keuntungan materi yang riil setelah kekuasaan sudah didapatkan. Mereka tidak hanya sekedar 212 membutukan prestise. Implikasinya, dua kaki partai akan berkerja ke arah yang berbeda dengan tujuan yang sama atau satu tujuan. Satu kaki partai akan berkerja untuk memuaskan kepentingan matriil anggota partai. Sedangkan kaki yang lainya akan berusaha menjalankan fungsi agregasi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kedua gerakan kaki partai tersebut sama – sama untuk memenuhi self – interes anggota partai. Kader partai tidak jarang mendistorsi atau membajak lembaga demokrasi seperti DPR, DPRD, Kementrian, dinas, lembaga hukum (MK, MA, Kejaksaan) sebagai alat untuk untuk memobilisasi dana untuk kepentingan partai sekaligus memperkaya diri. sebagai contoh, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan Kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjumlah 318 orang di Indonesia sejak diterapkan pilkada langsung (Indopos /15/02/2014). Secara umum, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami perbaikan dalam setiap tahun. Hanya pada tahun 2009 – 2010 dan 2012 – 2013 mengalami stagnasi. Meskipun demikian, Indonesia merupakan negara terkorup di dunia. Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara pada tahun 2013. Tabel di bawah ini menunjukan, nilai atau skor korupsi masih jauh dari ideal. Skor 213 tertinggi atau yang paling dianggap bersih adalah 100 (10,0) sedangkan sampai dengan tahun 2013 skor Indonesia hanya 32 (3,2). Tabel 11. Indeks Persepsi Korupsi Versi Transparency International (TI) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Skor 20 22 24 23 26 28 28 30 2013 32 32 Sumber: Corruption Perceptions Index, Transparency International Meskipun kader partai kerap kali mendistorsi lembaga demokrasi namun secara kuantitatif pemerintah masih berfungsi dengan baik. Itu artinya dalam batas tertentu perilaku partai politik masih kompatibel dengan kualitas demokrasi. Hal itu bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 12 Indek Kualitas Demokasi Indonesia versi the Economist Intelligence Unit’s Tahun Ukuran atau Indikator Kualitas Demokrasi Proses Fungsi Partisipasi Budaya Kebebasan Pemilu dan Pemerintah Politik Politik Sipil Pluralisme /Warga 2006 6,92 7,14 5,00 6,25 6,76 2008 6,92 6,79 5,00 5,25 6,76 2010 6,92 7,50 5,56 5,63 7,06 2012 6,92 7,50 6,11 5,63 7,65 Sumber; diolah dari laporan the Economist Intelligence Unit’s 2007:4, 2008:5, 2010:4, 2013:5 Skor Rata Rata 6,41 6,34 6,53 6,76 Lima ukuran kualitas demokrasi yang dirilis oleh the Economist Intelligence Unit’s yang paling bersinggungan secara langsung dengan kinerja partai politik 214 adalah fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintah mendapatkan skor 7.5 dari 10. Baiknya indikator fungsi pemerintah ini kemungkinan disebabkan oleh berkerjanya hukum “invisible hand” meskipun tidak secara penuh dan adanya persaingan di antara aktor politik electoral maupun control dari aktor non electoral. Aktor akan berusaha dan mencari cara agar berbagai kejahatan yang akan maupun telah dilakukan tidak sampai didengar, dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Namun tidak selamanya tangan aktor mampu menutupi kejahatan yang akan atau telah dilakukan. Persaingan electoral yang begitu ketat di antara berbagai aktor dan control dari berbagai aktor non electoral di alam demokrasi memungkinkan terkuaknya berbagai kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh aktor yang sedang berkuasa. Terkuaknya sekandal kasus Century dan kemudian diputus oleh rapat paripurna DPR sebagai kebijakan yang menyimpang dan direkomendasikan untuk diselidiki potensi tindak korupsinya oleh lembaga hukum merupakan salah satu indikasi, bahwa di antara partai politik tidak selalu bekerjasama untuk mencapai kepentingan ekonomi dan kekuasaan tetapi juga berkompetisi dan saling kontrol. Sedangkan terkuaknya kasus korupsi Wisma Atelit, Hambalang dan batalnya rencana renovasi Gedung DPR merupakan buah dari control aktor non electoral. 215 Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup baik dalam memberantas korupsi juga tidak terlepas dari dorongan dan pengawasan dari aktor non electoral yang sangat masif. Aktor non electoral selalu mengawal dan mengawasi kinerja KPK sejak proses seleksi anggota KPK yang dilakukan oleh panitia seleksi sampai dengan pelaksanaan tugas dalam setiap hari. Pengawasan dari aktor non electoral ini dalam batas tertentu meminimalisir adanya potensi intervensi yang dilakukan oleh kekuatan partai politik baik di DPR maupun di pemerintah (eksekutif) terhadap kinerja KPK. Sebab proses seleksi anggota KPK yang melibatkan pemerintah (melalui pansel) dan DPR memungkinkan kekuatan partai politik yang ada di eksekutif dan di DPR untuk mengintervensi KPK dengan menempatkan orang – orang yang setia pada kepentingan partai politik untuk duduk sebagai anggota KPK. Media massa (TV, Koran, radio dan sejenisnya) merupakan salah satu arena atau instrumen penting yang murah (bahkan menguntungkan) yang digunakan oleh aktor non electoral dalam melakukan kontrol terhadap kinerja KPK. Kompetisi atau kontrol di antara aktor politik electoral maupun control dari aktor non electoral akan menjadi informasi penting yang murah bagi pemilih untuk menilai kinerja partai. Kondisi ini membawa implikasi, jika ada kader partai yang terlibat kasus korupsi dan sudah diketahui oleh publik, partai politik akan berusaha melokalisir tindakan koruptif yang dilakukan oleh kader partai sebagai tindakan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan partai. 216 Kasus korupsi yang ditudukan ke Nazaruddin dan Anas selalu dicoba dilokasir oleh kader Partai Demokrat lainya sebagai tindakan pribadi. Ini merupakan bagian dari strategi untuk meminimalisir resiko electoral saat pemilu. Kompetisi atau tindakan saling kontrol di antara aktor politik electoral dan control dari aktor non electoral pada kenyataanya hanya menghambat dan tidak menghentikan langkah koruptif partai. Ketua KPK (Abraham Samad) sering mengatakan dalam berbagai kesempatan, modus korupsi semakin canggih dan sulit dicari bukti hukumnya. Sebab korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa dalam membuat hukum dan keputusan – keputusan penting yang sangat vital. Mereka tahu cela korupsi yang sulit dilacak bukti hukumnya. Tidak mengherankan jika beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tertentu membutukan waktu bertahun – tahun. C. REKOMENDASI Kajian tesis ini hanya berhasil membuktikan kemunculan Partai Demokrat saja dalam prespektif rational choice. Dengan demikian hasil kajian dari tesis ini belum bisa memastikan apakah kemunculan partai yang lain, termasuk partai baru yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen pasca refomasi bisa didekati dengan prespektif rational choice. 217 Penulis sangat mengharapkan ada penelitian lain yang mengkaji kemunculan partai politik selain Partai Demokrat yang muncul pasca reformasi dalam prespektif rational choice. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui apakah teori atau prespektif rational choice bisa digunakan untuk menjelaskan kelahiran semua partai politik pasca reformasi atau hanya Partai Demokrat saja. DAFTAR PUSTAKA 1. A, Denny J. 2006. Jejak – Jejak Pemilu 2004. Yogyakarta. LKiS 2. Ambardi, Kuskridho. 2009. Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia. 3. Amorim Neto, Octavio dan Gary W Cox. 1997. “Electoral Institutions, Cleavage Structures, and the Number of Parties,” American Journal of Political Science 41: 149 - 174. 4. Baroma, Suhendro. 2010. Sejarah Dan Kemenangan Partai Demokrat. Jakarta. Jala Permata. 5. Barnes, Samuel H., Peter McDonough, dan Antonio Lopez Pina, 1985. The development of partisanship in new democracies: The Case of Spain.” American Journal of political science 29/4:695-720. 218