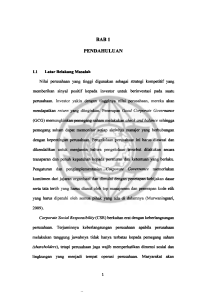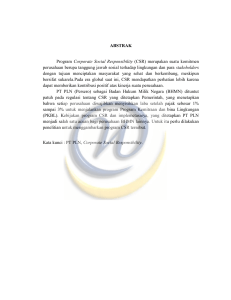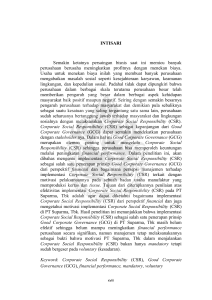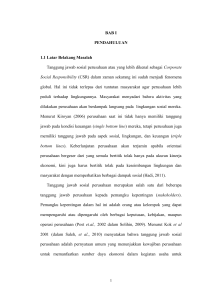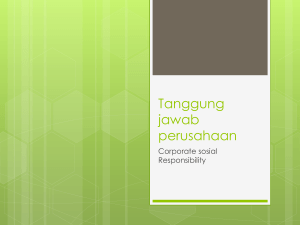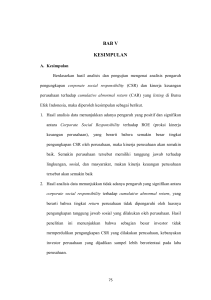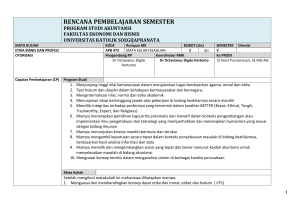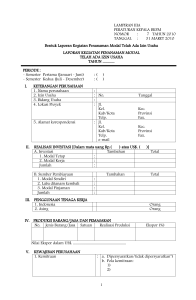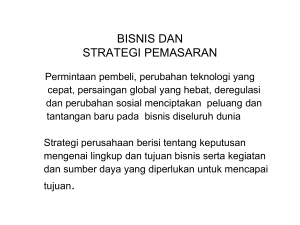Jurnal Hukum.indd - Universitas Udayana Repository
advertisement

KERTHA PATRIKA Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Volume 34 Nomor 1, Januari 2010 Penanggung Jawab: Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,SH.,MH. Pemimpin Redaksi: Prof. Dr. I Wayan P. Windia, S.H.,M.Si. Dewan Redaksi: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon,SH. (Unsakti) Prof. Dr. Nindyo Pramono,SH.,MS. (UGM) Prof. Dr. Hikmahanto Juwana,SH.,LLM. (UI) Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti,SH.,MS (Unud) Prof. Dr. I Nyoman Sirtha,SH.,MS. (Unud) Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani,SH.,MS. (Unud) Prof. Dr. I Made Pasek Diantha,SH.,MS. (Unud) Prof. Dr. I Ketut Mertha,SH.,M.Hum. (Unud) Prof. Dr. Ibrahim R. SH.,M.Hum. (Unud) Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan,SH.,M.Hum. (Unud) Sekretaris Redaksi: I Ketut Sudantra,SH.,MH. IGN Parikesit Widiatedja,S.H.,M.Hum. Administrasi: I Gede Yusa,SH.,MH. Cok Istri Anom Pemayun,SH.,MH. AA Istri Ari Atu Dewi,SH.,MH. Cokorda Dalem Dahana,SH.,M.Kn. Kadek Sarna,SH.,M.Kn. Bendahara: Ni Luh Gede Astariyani,SH.,MH. Distribusi: Luh Putu Sri Arwati,SE. Ni Nengah Serni Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Bali No.1 Denpasar, Bali Telp.(0361) 222666, Fax (0361)222666 [email protected] Daftar Isi Pengantar Redaksi ................................................ 2 A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ni Ketut Supasti Dharmawan .......................... 3 - 13 Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan ........................................... 14 - 26 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Dewa Suartha ................................................... 27 - 38 Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia I Ketut Westra ................................................... 39 - 48 Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam AwigAwig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi ..................... 49 - 64 Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung .................................... 65 - 77 Fenomena Cyber Terrorism I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti ........... 78 - 87 Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya ........................... 88 - 100 Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Cokorda Istri Anom Pemayun........................... 101-110 Petunjuk Bagi Penulis .......................................... Pracetak: Udayana University Press Kampus Unud Sudirman Gedung Pascasarjana Lt.1 R1.1 Jl. P.B. Sudirman, Denpasar-Bali Telp. (0361) 9173067 Design & Layout: I Putu Mertadana 111 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 1 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Pengantar Redaksi Edisi perdana di tahun 2010 ini tampak mengalami berbagai perubahan. Dari sisi tampilan, kulit muka (cover) Kertha Patrika berupaya menampilkan ciri, identitas dan jati diri suatu jurnal hukum tanpa mengesampingkan aspek seni dan estetika yang ada. Format penulisan pun juga telah disesuaikan dengan mengikuti standar-stándar yang ada. Dari sisi personil, Kertha Patrika juga mengalami pergantian staf redaksi untuk melakukan proses penyegaran dan meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi substansi, ada sesuatu yang membanggakan di edisi kali ini. Telah nampak suatu kesadaran dan kegairahan untuk menulis yang ditunjukkan dengan banyaknya naskah yang diterima oleh redaksi dan datang dari beberapa bagian yang ada di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hampir seluruh bagian menyumbangkan tulisannya di edisi ini. Bagian Perdata diwakili oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan dengan A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia, I Wayan Wiryawan dengan Implementasi Prinsip Tri Hita Karana Dalam Kontrak Konstruksi, I Ketut Westra dengan Implementasi Good Corporate Governance dalam Perusahaan Publik di Indonesia, dan I Gusti Nyoman Agung dengan Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundangundangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum, Absentee) Dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/ Pembaruan Agraria. Dewa Suartha mewakili Bagian Acara dengan tulisannya mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.Bagian Hukum Administrasi Negara diwakili oleh Cokorda Istri Anom Pemayun dengan tulisannya Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi mewakili Bagian Hukum dan Masyarakat dengan tulisan Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-awig dalam kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman. Bagian Hukum Pidana diwakili oleh I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, SH dengan tulisannya Fenomena Cyber Terrorism. Sebagai pamungkas, Bagian Internasional diwakili langsung oleh ketua bagiannya I Gede Pasek Eka Wisanjaya melalui tulisan Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Semoga dengan relatif seimbangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh para penulis dari beberapa disiplin hukum yang berbeda, dapat menyumbangkan segala konsep, ide, teori, dan pemikiran hukum dengan melihatnya dari beragam sudut pandang dan fokus kajian. Pada gilirannya, proses ini akan memperkaya khazanah keilmuan hukum yang ada khususnya bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Udayana. Redaksi 2 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia1 oleh: Ni Ketut Supasti Dharmawan (Bagian Hukum Perdata FH-Unud) Abstract There is different way to enforce a CSR in developed countries such as in Europe and America, they enforce the CSR voluntary, otherwise in Indonesia, and it is enforced mandatory based on the Act No. 40 Year 2007 and the Act No. 25 Year 2007. Alternatively, a Hybrid Framework can be employed as solution for further enforcement of CSR in Indonesia instead of mandatory based. Through a hybrid framework, the corporation may contribute better corporate social responsibility that flexibly adopting their programs by reflecting the local genuine problem. Key words: CSR, Voluntary based, Mandatory Based, A Hybrid Framework. I. PENDAHULUAN Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) , khususnya Pasal 74, dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM), maka CSR ( Corporate Social Responsibility ) di Indonesia secara resmi terkonstruksi melalui bentuk Perundang-Undangan dengan sebutan ”Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan” pada UUPT, dan ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ” pada UUPM. Sehubungan dengan keberadaan ”Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan” dan ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” dalam kedua Undang-Undang tersebut di atas, ternyata telah mengundang pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Konsep CSR di pergaulan dunia internasional lebih dikenal sebagai konsep yang pelaksanaannya melalui framework ”voluntary based”, atau tim peneliti dari Komisi Hukum Nasional (KHN) menyebutkan bahwa dalam praktik CSR berlangsung melalui mekanisme soft law ( deregulasi) seperti code of conducts. Mekanisme soft law ini,2 telah menjadi ciri tersendiri dari pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi.3 Meskipun dalam praktek korporasi di negara-negara maju seperti misalnya 1 2 3 Makalah ini disajikan sebagai bahasan atas Makalah Utama yang disajikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro,SH,MH dengan tema: “CSR ( Corporate Social Responsibility) dalam peraturan Perundang-undangan”, yang disampaikan dalam Acara DISEMINASI REKOMENDASI BAGI PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA, Kerjasama Komisi Hukum Nasional RI dengan FH UNUD Bali, Ina Sindhu Beach Sanur Bali, 16 November 2009. Soft law is collectively rules that are neither strictly binding nor completely lacking in legal significance. In international law , soft law : Guideline, police declarations, or codes of conduct that set standards of conduct but are not legally binding. See Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Thomson West Publishing Co, USA, page 1426. Mardjono Reksodiputro( Tim Peneliti KHN), CSR ( Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Desiminasi, 2009, hal 4. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 3 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 di Amerika dan Uni Eropa, CSR diatur melalui mekanisme soft law, namun keberadaan CSR di Indonesia secara tegas diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan (UUPT dan UUPM). Sehubungan dengan penomena tersebut, CSR dari konsep awalnya voluntary based bergeser ke mandatory based, ternyata telah menimbulkan perdebatan dan diskusi hangat, pro dan kontra mempertanyakan tentang ketidaklaziman pengaturan CSR (secara mandatary) yang berbeda dengan praktek-praktek di negara maju. Dalam acara Desiminasi Rekomendasi KHN, fokus kajian dan rekomendasi lebih diarahkan untuk mengkaji keberadaan CSR di Indonesia yang tidak sama dengan kelazimannya di negara-negara seperti Eropa dan Amerika, juga mengkritisi tentang apakah ”Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” serta ”Tanggung jawab Sosial Perusahaan” memiliki konsep yang sama dengan CSR di negara-negara maju ? serta bagaimanakah keberadaan Pasal 74 U.U. No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang ”Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” apakah keberadaan pasal tersebut tidak tumpang tindih (inkonsisten) dengan perundang-undangan lainnya? atau bahkan inkonsisten dalam Undang-Undang itu sendiri. Sehubungan dengan tema sentral kajian tersebut diatas, melalui kertas kerja / makalah ini saya mencoba untuk ikut menyumbangkan pemikiran dan rekomendasi. Pokok-pokok pembahasan dalam tulisan ini hanya akan difokuskan pada perbedaan model pendekatan dan argumentasi pendukungnya, serta luas cakupan konsep CSR di Indonesia yang tertuang dalam UUPM dan UUPT dan perbandingannya dengan CSR di Eropa dan negara maju lainnya. Dalam tulisan ini, digunakan studi kepustakaan4 yaitu dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji dan membahas keberadaan CSR di Indonesia dan perbandingannya dengan konsep dan teori CSR di negara-negara maju. II. PEMBAHASAN 1. Studi Perbandingan Tentang CSR Dalam Dunia Korporasi Di Negara Maju Dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam UUPT dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada UUPM Keberadaan dan perkembangan CSR secara yuridis formal dengan menyebut secara tegas istilah ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (CSR) memang masih sangat dini di Indonesia, yaitu melalui pendekatan mandatory diatur dalam UUPT 2007 dan UUPM 2007. Namun demikian, dalam bentuk dan ”nama lain” CSR sudah dikenal sejak lama di Indonesia, misalnya dalam bentuk ”peran serta perusahaan” terhadap pembangunan di masyarakat sekitarnya. Kemudian dengan diundangkannya UUPT dan UUPM perusahaan-perusahaan besar atau perusahaanperusahaan multinasional mulai mengembangkan program dan konsep CSR. Praktek perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika Serikat ( perusahaan transnasional) menunjukkan bahwa norma-norma CSR dicantumkan dalam code of conduct, dan merupakan satu tipe regulasi internal yang mampu diterapkan atau diberlakukan pada perusahaan yang globalised. Konsep CSR atau pertanggungjawaban sosial di negara-negara maju seperti di Eropa dan AS diberlakukan dan bersifat sukarela atau voluntary.5 CSR diterapkan secara sukarela (voluntary based) di negara-negara maju tentu saja menjadi 4 5 In legal research, case law, treaties and statutes constituted as part of primary source, otherwise such mass media and textbooks fall within secondary sources. See The Staffs of George Washington University Journal of International Law and Economic, 1993. Guide to International Legal Research, Second Edition, Butterworth Legal Publishers, United States, page 37. Ibid, hal 12 4 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ni Ketut Supasti Dharmawan wajar-wajar saja dan tidak terlalu istimewa, terutama jika praktek tersebut dikaitkan dengan berbagai definisi tentang CSR yang dapat dijumpai dari berbagai literatur. Seperti misalnya menurut World Bank, CSR didefinisikan sebagai ”the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both and good for business development.”6 Senada dengan World Bank, Danette Wineberg and Philip H Rudolph mengemukakan definisi CSR adalah “the contribution that a company make in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy.”7 Mencermati adanya konsep Corporate Philanthropy (CP), yaitu kedermawanan perusahaan dan komitmen perusahaan dalam memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (tempat perusahaan beroperasional), sekali lagi menjadi sangat wajar jika praktek penerapan CSR di negara-negara maju diterapkan secara sukarela atau voluntary. Keberadaan CSR di Indonesia sekarang ini, selain kontroversial yaitu perdebatan seputar voluntary based v. mandatory based, juga persoalan lain yang juga dipertanyakan adalah mengapa perusahaan atau korporasi yang harus melakukan tanggung jawab sosial ? mengapa bukan pihak lainnya ? mengapa tanggung jawab sosial harus dibebankan kepada perusahaan ?. Jawabannya akan menjadi sangat sederhana jika mengacu pada legal term “CSR” adalah kepanjangan dari Corporate Social Responsibility, tentu saja dari istilah dan konsep tersebut menentukan perusahaan atau korporasi yang mempunyai tanggung jawab sosial. Sehubungan dengan mengapa korporasi atau perusahaan harus bertanggungjawab dan seberapa besar tanggungjawab social yang harus dilakukan oleh perusahaan, dalam ranah keilmuan di kenal empat (4) teori yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan yaitu: 8 • Maximizing Profits theory, berdasarkan teori ini, yang lebih dikenal sebagai teori atau pandangan tradisional tentang tanggung jawab sosial, mengemukakan bahwa sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan dari shareholders (pemilik saham perusahaan). Menurut Milton Friedman, seorang pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi melalui teorinya menambahkan bahwa memaksimalkan profit diartikan sepanjang dilakukan dalam jalur yang tepat (rule game) dalam skema persaingan bebas tanpa suatu kecurangan. Teori ini banyak dikecam karena hanya menekankan pada tanggungjaab dan kewajiban meningkatkan keuntungan bagi shareholders. • Moral Minimum theory, konsep tanggung jawab sosial menurut teori yang ke dua ini adalah bahwa perusahaan wajib untuk menghasilkan keuntungan dalam operasinya, namun jangan sampai merugikan atau membahayakan pihak lainnya. Sebagai contoh dalam teori ini jika suatu perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan, maka perusahaan tersebut wajib memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Jika kemudian pihak perusahaan telah memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan tersebut , maka perusahaan tersebut telah melakukan tanggung jawab sosial yaitu memenuhi moral minimum konsep CSR. Teori ini pun banyak menuai kritik karena tanggung jawab sosial hanya berorientasi pada program pemulihan keadaan setelah terjadi negatif effects . 6 7 8 Johannes Simatupang, Memeriksa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, http://johannessimatupang.wordpress.com/2009/06/08/, diakses 8 Nopember 2009, hal 1. Mardjono Reksodiputro, op. cit, hal 2. Henry R. Cheeseman, 2003. Contemporary Business & E-Commerce Law, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, page186-192. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 5 KERTHA PATRIKA • • • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Stakeholder Interest Theory, menurut teori ini perusahaan harus mempertimbangkan efek dari kegiatan operasionalnya terhadap kepentingan stakeholder (karyawan, konsumen, kreditor, masyarakat setempat). Kritik terhadap teori ini adalah bahwa tidak mudah mengharmonisasikan kepentingan stakeholder yang satu dengan stakeholder lainnya, misalnya suatu tindakan mungkin akan mememenuhi kepentingan stakeholder dari kalangan para kreditor, namun belum tentu memenuhi keinginan dan kepentingan stakeholder pegawai/ karyawan maupun masyarakat setempat. Corporate Citizenship theory, menurut teori ini, tanggung jawab sosial berarti perusahaan berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik (to do good) baik untuk perkembangan perusahaannya sendiri maupun keseluruhan stakeholders termasuk didalamnya lingkungan, perusahaan bertanggungjawab untuk membantu memecahkan masalah sosial, mensubsidi mendirikan sekolah-sekolah maupun mendidik anak-anak. Teori ini kemudian banyak diikuti berkaitan dengan penerapan CSR dalam praktek. Senada dengan Corporate Citizenship theory, berkembang konsep CSR dengan tiga piramida dasarnya berdasarkan konsep triple bottom lines yaitu : profit, people, dan planet (3P), keberadaan perusahaan ataupun korporasi tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan, akan tetapi sejak awal sudah turut melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, orangorang, atau stakholdernya dan lingkungan. Konsep CSR di Eropa dan AS, jika dikaitkan dengan CSR yang tercantum dalam UndangUndang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007 ) dan Undang-Undang PT (UU No. 40 Tahun 2007 ) memang terlihat ada perbedaan. Konsep dan teori-teori CSR sebagaimana tersebut diatas, khususnya dari “pemaksaan” pelaksanaannya dan luas cakupan dari CSR itu sendiri. Sekali lagi di negara-negara maju mekanisme pelaksanaannya CSR adalah voluntary based, sedangkan di Indonesia adalah mandatory atau kewajiban hukum, kewajiban tersebut sangat tegas dicantumkan melalui ketentuan Pasal 15 dan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa : setiap Penanam Modal (perseroan ataupun perusahaan berbadan hukum ataupun bukan badan hukum) berkewajiban untuk: 1. Menerapkan prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik 2. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan 3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal 4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal 5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan ( Pasal 5 UU No 25 Tahun 2007 )9 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur sanksi secara tegas mengenai pelanggaran terhadap kewajiban CSR yaitu: 1. Peringatan tertulis 2. Pembatasan kegiatan usaha 3. Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal dan 4. Pencabutan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal. Sementara itu CSR dalam UU PT yang kemudian lebih dikenal sebagai Tanggung Jawab 9 Jamin Ginting, 2007,. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 98. 6 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ni Ketut Supasti Dharmawan Sosial Dan Lingkungan, melalui ketentuan Pasal 74 U.U. No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 5. Penjelasan Pasal 74 UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan ”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Dengan mencermati bunyi Pasal 74 UUPT dan kemudian membandingkannya konsep CSR di negara-negara maju, saya sependapat dengan tim peneliti dari KHN bahwa bahwa konsep dasar Tanggung Jawab Sosial Korporasi dalam Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan yaitu dari konsep dasar ’tanggung jawab sosial” (social responsibility) menjadi ”kewajiban hukum” (legal obligation). Meskipun konsep CSR kemudian mengalami perubahan ketika diterapkan di Indonesia, kiranya itu bukan suatu kesalahan. CSR sebagai suatu konsep, sebagai suatu pemahaman seperti halnya perkembangan teori-teori CSR tersebut diatas, bukanlah sesuatu yang vacuum melainkan senantiasa progress dan berubah. Dengan demikian bukan merupakan sesuatu yang sangat aneh jika dalam penerapannya di Indonesia konsep CSR berubah dari social responsibility menjadi legal obligation, jika memang perubahan pemahaman atas konsep CSR tersebut lebih tepat untuk mengakomodir tidak hanya kepentingan perusahaan, akan tetapi juga seluruh stakeholders perusahaan seperti: masyarakat setempat, karyawan, konsumen, investor, dan pemerintah. CSR sebagai salah satu perwujudan best practice dari GCG (Good Corporate Governance), jika memang dalam kontekstualnya di Indonesia lebih tepat diformulasikan melalui bentuk Undang-Undang, mengapa tidak ? Indonesia harus berani berbeda karena memang situasi dan kondisi indonesia berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Sebagaimana telah dikemukakan, Indonesia harus berani berbeda dengan negara-negara maju dalam penerapkan CSR jika memang itu diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, melindungi, melestarikan dan merabilitasi lingkungan hidup manusia serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Secara singkat, konsep CSR idealnya tetap dikaitkan dengan konsep Community Development (CD). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengaturan dan pengimplementasian CSR di Indonesia, adalah suatu progress step dan langkah yang sangat berarti bagi perkembangan Indonesia ke depan dengan berani ”bertegur sapa” dengan pluralism approach, terutama jika memang pendekatan itu yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia (masyarakatnya, lingkungannya, dan juga alamnya). Melalui mekanisme mandatory based, kepastian bahwa keberadaan perusahaan tidak JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 7 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 hanya akan memikirkan perkembangan perusahaan itu sendiri akan tetapi sama pentingnya dengan berkontrubusi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat setempat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Secara etis moral, perusahaan dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakatnya. Untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial itu terlaksana dengan baik, pendekatan legal obligation atau konsep pertanggungjawaban sosial yang bersifat mandatory kiranya tidak berlebihan diterapkan di Indonesia. Archie B. Carrol, mengembangkan piramida CSR yaitu sebagai suatu kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lones : profit, people, dan planet ( 3P), konsep piramida CSR haruslah difahami sebagai suatu kesatuan. Dalam pemahaman CSR sebagai suatu kesatuan, maka penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. Karenanya CSR bukan saja sebagai tanggungjawab, tetapi juga sebuah kewajiban.10 Kontroversi tentang pengaturan CSR dalam Undang-Undang di Indonesia kiranya juga sah-sah saja, sebab baik yang pro maupun yang kontra, mereka mempunyai argumentasi yang kuat untuk mendukung pendapatnya. Seperti halnya pandangan yang mengkritisi legalisasi CSR ke dalam Undang-Undang yang khusus mengatur tentang korporasi, memandang legalisasi seperti itu malah akan membebankan pihak pengusaha. Kelaziman praktek CSR juga menjadi argumentasi yang relevan untuk mengkritisi pengaturan CSR ke dalam bentuk Undang-Undang. Praktek CSR yang berlangsung lewat mekanisme soft laws ( deregulasi) seperti code of conducts telah menjadi ciri tersendiri pelaksanaan CSR di dunia hukum korporasi, karenanya setiap upaya untuk menstransformasikan CSR dalam hukum perusahaan (regulasi) akan selalu memunculkan permasalahan dan preseden regulasi. CSR dengan ciri khasnya yang terformulasikan dalam bentuk soft law sesungguhnya berada di luar wilayah hukum formal. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep CSR dengan demensinya (lingkungan, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, organizational governance, isu konsumen, dan praktek bisnis yang sehat), pelaksanaannya sangat beragam dan sangat bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela yang didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena penerapan CSR dalam prakteknya selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakatnya. Pendekatan regulasi (dalam bentuk UU) sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness, seperti mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan, yang tidak hanya pelaporan tentang aspek keuangan, akan tetapi juga pelaporan yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.11 Namun demikian keberadaan CSR dalam bentuk Undang-Undang juga akan dapat menjadi dasar hukum bagi sektor bisnis agar mampu menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab dan bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban para pebisnis atas berbagai malpraktek yang dilakukannya selama ini dan berdampak sangat merugikan tidak hanya masyarakat setempat, lingkungan, dan bumi Indonesia. Di negara Eropa, situasi kontroversi sehubungan dengan penerapan CSR juga terjadi seperti yang dialami di Indonesia. Meskipun kelazimannya CSR diterapkan secara sukarela di Eropa, 10 11 Bing Bedjo Tanudjaja, Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia, http://www.petra.ac.id/ , diakses 8 November 2009, hal.93. Mohamad S. Hidayat, Pandangan Dunia Usaha Terhadap Undang-Undang, http://www.madani-ri.com/2007/10/31 , diakses 7 Nopember 2009, hal 3. 8 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ni Ketut Supasti Dharmawan namun dewasa ini, seiring dengan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, seperti pelanggaran HAM12, keinginan untuk menerapkan konsep CSR melalui pendekatan Undang-Undang mulai tumbuh secara progress dan umumnya disuarakan oleh kalangan akademisi dan Non Government Organization (NGO). Kalangan ini berargumen bahwa tanggungjawab korporasi terutama yang berdimensi human rights terlalu riskan dan amat penting jika hanya dibiarkan dikelola oleh korporasi. Menurut pandangan para akademisi dan NGO ini, kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh korporasi sudah sewajarnya diimbangi dengan serangkaian tanggungjawab berbasis hukum, terutama korporasi-korporasi dari kalangan Foreign Direct Investment (FDI) yang memiliki serentetan hak-hak yang sangat mendominasi, mengapa harus takut membebani mereka dengan kewajiban hukum. Namun demikian dalam kenyataannya suara-suara mereka belum cukup kuat jika dibandingkan dengan kekuatan korporasi, sehingga di Eropa, CSR masih diterapkan sesuai konsep awalnya yaitu dalam bentuk social responsibility yang voluntary based.13 Di Eropa, starting point tentang perdebatan CSR antara regulatory atau voluntary, khususnya tanggung jawab perusahaan terkait human rights, social and environmental responsibilities, dapat disebutkan berawal dari the EU’s Corporate Social Responsibility Police: The European Commission’s Green Paper On CSR of 2001. Mengkaji proses perkembangannya, The Green Paper 2001 mendifinisikan CSR sebagai sebuah konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap stakeholders nya dengan basis voluntary atau secara sukarela, namun tetap mempertimbangkan peran aktif dari otoritas publik. Perkembangan selanjutnya tentang CSR adalah pada tahun 2002, melalui the EU Multi-Stakeholder Forum dan the Lisbon Strategy review pada tahun 2005 yang nampaknya masih didominasi oleh para pebisnis (korporasi), karenanya CSR pendekatannya masih pada ranah voluntary. Di sisi lain, pandangan dari the European Parliement agak kontras (berbeda) dengan the EU Multi-Stakeholder Forum maupun the Green Paper 2001, dengan mengedepankan konsep a mixed approach, yaitu suatu kombinasi voluntary dan regulatory. Meskipun European Parliement dan juga NGO yang pada awalnya berkeinginan agar CSR diterapkan dalam format regulatory, namun dalam perkembangannya ternyata suara korporasi yang masih tetap unggul, dan sebagai hasil akhirnya sudah dapat dipastikan bahwa CSR tetap dalam format voluntary approach14. Proses perdebatan dan kontroversi tentang pendekatan CSR di Eropa, kiranya juga dapat dijadikan perenungan bahwa meski di negara maju seperti Eropa, konsep CSR tidak begitu saja harus diterapkan dalam format voluntary, akan tetapi ada juga keinginan untuk mengaturnya dalam format regulatory, atau pendekatan yang lebih memadai dengan mixed framework A mixed framework atau a hybrid framework adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan antara pelaksanaan CSR secara voluntary dan regulatory. Dalam pendekatan hybrid ini tidak melihat keduanya terpisah secara ekslusif, akan tetapi melihatnya sebagai dua hal yang saling melengkapi. Dengan adanya suatu usaha legislasi, itu bukan berarti menganggap inisiatif voluntary sebagai suatu hal yang tidak penting, melainkan usaha atau pemasukan konsep CSR ke dalam Undangundang lebih dimaksudkan sebagai salah satu faktor yang akan dapat lebih mempengaruhi 12 13 14 Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terkait dengan keberadaan Korporasi (MNC) seperti misalnya dalam kasus Filartiga v. Pena-Irala case, Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co Case, Doe I v Unocol Corp Case, dll . penomena seperti itu telah menarik banyak experts untuk melakukan penelitian terkait dengan tanggungjawab perusahaan. Lihat Menno T. Kamminga and Saman Zia-Zarifi, 2000, Liability of Multinational Corporations Under International Law, Kluwer Law International, The Netherlands, page 3. Jan Wouters, Leen Chanet, Corporate Human Rights Responsibility : A European Perspective, http://www.law.nortwestern.edu/ journals/jihr/v6/n2/3 , diakses 8 Mei 2009, hal 3. Ibid, hal 7-12. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 9 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 ketaatan prilaku korporasi dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya. Dalam banyak hal, di luar pendekatan regulatory framework, justru sangat diharapkan korporasi lebih dapat menjalankan tanggungjawab sosialnya melebihi dari apa yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Melalui alternatif hybrid model ini, secara yuridis setiap perusahaan sebagaimana pengertian perusahaan dalam UUPT dan UUPM wajib menjalankan CSR, (mandatory based), namun dari aspek mekanisme pelaksanaanya yang berkaitan dengan apakah perusahaan secara langsung atau harus bermitra dengan pemerintah untuk melaksanakannya, begitu juga jenis-jenis kegiatan apa saja yang menjadi cakupan dari CSR, apakah harus dalam bentuk rekrtmen pegawai, pemberian beasiswa, pola pendampingan usaha, model-model pelestarian lingkungan, partisipasi aktif ke masyarakat, dan lain sebagainya, kiranya pelaksanaannya dilakukan dalam sekema voluntary based, dengan berorientasi pada local genuine problem. Model hybrid framework inilah yang kiranya cukup memadai digunakan dalam penerapan CSR di Indonesia ditengah-tengah kontroversi CSR antara voluntary dan regulatory ( mandatory). Dalam kaitannya dengan persoalan apakah konsep CSR yang berlaku secara umum di dunia korporasi sama dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam UUPT No. 40 Tahun 2007, dapat dikemukakan bahwa dari segi pendekatan yang digunakan memang berbeda. CSR yang berlaku secara umum di dunia korporasi berbasis social responsibility yang voluntary, sementara itu dalam UU No. 40 Tahun 2007 tanggung jawab sosial yang berbasis ”kewajiban hukum” atau legal obligation. Namun demikian, sebagaimana dengan model pendekatan a hybrid framework seperti tersebut diatas, penerapan CSR dalam perundang-undangan hendaknya tidak dilihat sebegai suatu yang berbenturan akan tetapi suatu pendekatan yang saling melengkapi. Jikapun harus dilihat sebagai suatu yang berbeda, sekali lagi pencantuman konsep CSR dalam format Undang-Undang bukan suatu ”kesalahan” melainkan suatu ”kebutuhan”. Mencermati mengapa CSR dalam prakteknya (kelazimannya) di negara-negara maju dilakukan secara voluntary, mungkin jawabannya karena ”kebutuhan” mereka seperti itu. Umumnya korporasi-korporasi ”MNE”, holding company- nya berasal dari Eropa maupun Amerika. Dalam situasi seperti itu penerapan CSR lebih menguntungkan jika dilakukan dengan pendekatan voluntary. Jika negara negara maju posisinya ditukar, mereka berposisi seperti negara Indonesia yang lingkungannya dan sumber daya alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan operasional bisnis para korporasi, akankah kebutuhan mereka tetap menginginkan CSR diterapkan dengan pendekatan voluntary ? atau jangan-jangan dengan bargaining position mereka yang lebih kuat, pihaknya akan memaksakan agar CSR dimasukkan dalam framework regulatory. Dalam perkembangan globalisasi sekarang ini, negara-negara maju yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat senantiasa sangat concern memperjuangkan framework regulatory jika menyangkut ”kebutuhannya”, seperti halnya dalam pengimplementasian WTO dengan berbagai Annex- nya yang senantiasa menuai kontroversial. Bagi negara maju, globalisasi ekonomi dan international trade tentunya sangat menguntungkan, namun belum tentu situasinya sama bagi negara-negara berkembang. Oleh karenanya penerapannya mesti dibarengi dengan good governance dan bantuan secara berkesinambungan dari negara-negara maju, sebab jika tidak kehadiran perangkat regulasi ini lebih akan menjadi kutukan atau nestapa (a curse ) dari pada berkah (a blessing to humankind).15 Dalam hal ’kebutuhan” berkorelasi dan menyangkut ”keadilan” masyarakat manusia dan alam lingkungannya, kiranya bertegur sapa dengan pendekatan pluralisme bukanlah sesuatu yang tabu. 15 Peter Van Den Bossche,2008. The Law And Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press, page 71. 10 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ni Ketut Supasti Dharmawan 2. Perbandingan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (UU No. 25 Tahun 2007) dan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (UU No. 40 Tahun 2007) Dengan Konsep CSR di Eropa Dan Amerika. Sehubungan dengan keberadaan Pasal 15 huruf b UUPM serta penjelasannya tentang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Ayat 1 UUPT berkaitan dengan kewajiban perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ( TJSL), kiranya memang konsep yang diakomodirnya tidak sama persis dengan CSR di Eropa dan AS. CSR baik dalam UUPM maupun UUPT hanya mengedepankan kewajiban perusahaan untuk menciptakan dan memelihara bina lingkungan yaitu berinteraksi dan menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Konsep CSR seperti yang lazim dipraktekkan di Eropa dan Amerika cakupannya lebih luas juga mencakup kewajiban perusahaan untuk mematuhi standar internasional di bidang ketenagakerjaan, pemenuhan kepuasan, atau kebutuhan pemangku kepentingan seperti misalnya konsumen.16 Secara eksplisit cakupan yang seluas CSR di negara maju memang tidak diatur baik dalam UUPM maupun UUPT. Mengingat CSR merupakan salah satu bentuk perwujudan dari best practice GCG, kiranya kedepannya akan sangat relevan dalam UUPM maupun UUPT mengatur secara eksplisit prihal kewajiban mematuhi standar internasional di bidang ketenagakerjaan, seperti halnya yang lazim dalam praktek di Eropa dan Amerika, begitu juga kewajiban tanggungjawab sosial ( pemenuhan kepuasan dan kebutuhan ) pemangku kepentingan seperti konsumen. Perbedaan konsep CSR dalam UU di Indonesia dengan CSR di negara maju, selain dalam UUPM maupun UUPT tidak mengakomodir secara eksplisit elemen-elemen penting dari CSR sebagaimana konsep CSR di negara maju, saya sependapat dengan tim peneliti dari KHN bahwa keduanya tidak secara tegas mencantumkan dan menjelaskan apakah konsep CSR dalam Undang-Undang tersebut mencakup bidang ketenagakerjaan dan hak asasi manusi seperti CSR di negara maju. Dalam UUPT Pasal 1 angka 3 hanya menyebutkan : ”Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.” Selain itu, saya juga sependapat dengan pemakalah, bahwa CSR dalam UUPT terkesan diskriminatif, yaitu karena hanya mewajibkan TJSL kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. Idealnya CSR diterapkan pada perseroan dalam semua lini. Konflik norma tampak jelas mewarnai keberadaan CSR dalam UUPT, terutama pada Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74. pada Pasal 1 ayat 3 UUPTmenyebutkan ”tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”, sementara itu pada Pasal 74 UUPT mengemukakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, dengan mendasarkan pada konstruksi hukum yang dikemukakan oleh Lawerence Friedman, dimana sistem hukum ( legal system) terdiri dari tiga 16 Mardjono Reksodiputro, OpCit, hal 10. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 11 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 unsur yaitu legal substance ( substansi hukum ), legal structure ( struktur hukum ) dan legal culture ( budaya hukum),17 idealnya suatu produk hukum mengakomodir sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman agar dalam penerapannya tidak bermasalah. Jika dalam tatanan legal substance (substansi hukumnya) terjadi konflik norma maupun norma kabur, tentu saja dalam proses penegakan hukumnya akan menyulitkan dan akan menjadi sebagai salah satu faktor penyebab tidak efektifnya hukum dalam ranah penegakannya. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah untuk mencermati kembali keberadaan pasal 1 ayat 3 dan relasinya dengan Pasal 74 UUPT . III. PENUTUP Simpulan Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa penerapan konsep CSR di negara Eropa dan Amerika tidak sama dengan di Indonesia, dimana di negara maju tersebut CSR diterapkan dengan mekanisme voluntary based sedangkan di Indonesia melalui UUPT dan UUPM diterapkan dengan mandatory based. 2. Pendekatan hybrid framework relevan sebagai suatu alternatif penerapan konsep CSR dalam situasi kontekstual, terutama pada kondisi kontroversial antara pendekatan regulatory (legal obligation) seperti dalam UUPM dan UUPT dengan voluntary based sebagaimana penerapan CSR di negara-negara maju. 3. Konsep CSR yang dituangkan dalam UUPM dan UUPT cakupannya lebih sempit dari konsep CSR di negara maju seperti Eropa dan Amerika. Baik UUPM maupun UUPT tidak secara tegas mengakomodir kewajiban tanggungjawab sosial yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan hak asasi manusia, serta tidak secara eksplisit menentukan adanya kewajiban tanggungjawab sosial (pemenuhan kepuasan dan kebutuhan ) pada pemangku kepentingan seperti konsumen. 4. Pengaturan CSR dalam UUPT selain diskriminatif juga diwarnai dengan konflik norma, sehingga substansi hukum seperti itu akan dapat menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasiannya. Rekomendasi 1. 2. 17 Hendaknya pendekatan regulatory berkaitan dengan CSR di Indonesia tidak dibenturkan dengan tajam dengan pendekatan voluntary, melainkan dipahami sebagai suatu pendekatan yang saling melengkapi. A Hybrid Framework dapat dijadikan sebagai suatu alternatif solusi .dalam penerapan CSR di Indonesia Perlu pengkajian lebih mendalam tentang substansi hukum dalam UUPT agar tidak terjadi konflik norma. Lawrence Friedman, 2001, American law : An introduction, 2nd edition, diterjemahkan oleh Wisnu basuki, Tatanusa, bandung, hal 6-12. 12 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ni Ketut Supasti Dharmawan DAFTAR PUSTAKA Bryan A. Garner.2004. Black’s Law Dictionary..USA: Thomson West Publishing Co. Henry R. Cheeseman. 2003. Contemporary Business & E-Commerce Law. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River. Jamin Ginting. 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Bandung: Citra Aditya Bakti. Lawrence Friedman. 2001. American law: An introduction, 2nd edition. Diterjemahkan oleh Wisnu Basuki.Bandung: Tatanusa. Menno T. Kamminga and Saman Zia-Zarifi. 2000. Liability of Multinational Corporations Under International Law. The Netherlands: Kluwer Law International. Peter Van Den Bossche 2008. The Law And Policy of the World Trade Organization. Cambridge University Press. The Staffs of George Washington University Journal of International Law and Economic.1993. Guide to International Legal Research, Second Edition. USA: Butterworth Legal Publishers. Mardjono Reksodiputro.2009. CSR ( Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundangundangan. Makalah Desiminasi. Bing Bedjo Tanudjaja, Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia, http://www.petra. ac.id/ Jan Wouters, Leen Chanet, Corporate Human Rights Responsibility : A European Perspective, http:// www.law.nortwestern.edu/journals/jihr/v6/n2/3 Johannes Simatupang, Memeriksa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, http://johannessimatupang. wordpress.com/2009/06/08/ Mohamad S. Hidayat, Pandangan Dunia Usaha Terhadap Undang-Undang, http://www.madaniri.com/2007/10/31 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 13 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi.1 Oleh: I Wayan Wiryawan (Bagian Hukum Perdata FH-Unud) Abstract The Tri Hita Karana literally means three things that cause welfare, as an expression of relating pattern in harmony and equitability bears universal values, it means could be implemented by everyone in live activities or in contractual related between each individual and others. Relating to the construction contract, the form and function of Tri Hita Karana which are reflected in scope of construction works are covered of planning construction works, implementing construction works and controlling construction works. Keywords: Implementation, Tri Hita Karana, Construction Contract. I. PENDAHULUAN Dalam pembangunan nasional, bidang usaha jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lain, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, usaha jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.2 Bidang usaha jasa konstruksi diharapkan mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan ekektif. Struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya pola kemitraan yang sinergis antara pengguna jasa dan penyedia jasa baik yang berskala besar, menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil. Untuk itu perlu diwujudkan pola ketertiban penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. 1 2 Disampaikan Pada Seminar Pekan Ilmiah Dalam Rangka HUT Ke- XLV Dan Badan Kekeluargaan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar ,9-10 Oktober 2009. Penjelasan Umum Undang-Undang Jasa Konstruksi (angka 1). 14 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan Dengan demikian pengaturan jasa konstruksi mempunyai tujuan untuk: a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.3 Dalam kaitannya dengan tujuan pengaturan jasa konstruksi tersebut untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, perlu dikemukakan jenis usaha jasa konstruksi, yaitu: usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksana konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi. Adapun bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi adalah yang disebut pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Pengaturan hubungan kerja para pihak tersebut dituangkan ke dalam bentuk kontrak konstruksi.4 Salah satu syarat dalam kontrak konstruksi itu mencakup uraian mengenai kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk tanggungjawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia.5 Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan termasuk kepatuhan para pihak yakni pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengikatan dalam hubungan kerja kontrak konstruksi di dalam implementasinya selain dilandasi oleh Undang-undang Jasa Konstruksi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999) dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000), juga memperhatikan ketentuan mengenai prinsip dan norma hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau tempat di mana penyelenggaraan kontrak konstruksi itu diselenggarakan. Pada wilayah provinsi Bali, prinsip dan norma hukum yang dimaksud tertuang dalam aturan tentang pemanfaatan tataruang wilayah yang dikenal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (disingkat RTWRP) Bali dan tertuang pula dalam aturan mengenai persyaratan arsitektur bangunan, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tataruang wilayah provinsi Bali yakni Perda RTRWP Bali Nomor 3 Tahun 2005 yang saat ini perubahannya masih dalam pembahasan, dan Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Penyelenggaraan kontrak konstruksi di Bali sudah sepatutnya memperhatikan ketentuan peraturan daerah yang dimaksud, karena kedua peraturan daerah tersebut, baik Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 maupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 pada azasnya berdasarkan pada landasan filosofis yang dikenal dengan Tri Hita Karana. Hal ini penting untuk dikemukakan, sebab Tri Hita Karana telah menjadi landasan keharmonisan hidup masyarakat 3 4 5 Pasal 3 Undang-Undang Jasa Koonstruksi. Pasal 22 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Pasal 22 Undang-Undang Jasa Konstruksi jo Pasal 23 ayat (1) Huruf m PP No. 29/2000 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 15 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Bali. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimanakah wujud, fungsi dan implementasi Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi di Bali serta penegakan hukumnya (dari aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis). II. PEMBAHASAN 1. Wujud dan Implementasi Tri Hita Karana Berdasarkan etimologi, Tri Hita Karana terdiri dari kata: Tri artinya tiga, Hita artinya kemakmuran, dan Karana artinya penyebab atau sebab musabab. Jadi, Tri Hita Karana diartikan sebagai tiga unsur penyebab kebahagian atau kemakmuran. Tiga unsur yang dimaksud adalah: Unsur pertama yang disebut dengan Parhyangan (Ida sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa); Unsur yang kedua yang disebut dengan Pawongan (Umat manusia); dan Unsur yang ketiga yang disebut dengan Palemahan (Alam lingkungan). Konsepsi filosofis Tri Hita Karana tercantum dalam Kitab Suci agama Hindu (Bhagawadgita: III.10) yang pada intinya menyebutkan bahwa Tri Hita Karana adalah ”membangun kebahagiaan dengan mewujudkan sikap hidup yang seimbang dan harmonis antara ber-bhakti (ketulusan) pada Tuhan, mengabdi pada sesama dan menyayangi alam berdasarkan yadnya (ritual, korban suci)”.6 Harmonisasi dan keseimbangan berdasarkan yadnya dari tiga unsur tersebut sebagai sebab (Karana) datangnya kebahagiaan atau kesejahteraan hidup (Hita). Dengan demikian harmoni dan seimbang merupakan faktor yang menghasilkan keharmonisan dan keseimbangan sehingga membentuk satu prinsip yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem budaya untuk menuju pada intergrated balance harmony. Menurut A White, suatu sistem budaya terbentuk atau terdiri atas tiga elemen pokok yaitu: teknologi, sosiologi dan ideologi.7 Di dalam elemen teknologi terdiri atas peralatan termasuk cara penggunaan atau pemakaiannya. Pada elemen sosiologi meliputi adat kebiasaan (customs), pranata atau lembaga sosial (institution), dan peraturan (codes). Sedangkan pada elemen idiologi mencakup ide-ide atau konsep-konsep dan kepercayaan. Ketiga elemen sistem budaya itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Masing-masing hanya bermakna kalau berkolerasi satu dengan yang lain dalam satu kesatuan sistem secata keseluruhan. Dalam konteks pengertian Tri Hita Karana, sistem budaya pada masyarakat Bali pada hakekatnya adalah merupakan implementasi dari unsur Parhyangan yang analog dengan subsistem budaya atau pola pikir, unsur Pawongan yang analog dengan subsistem sosial dan unsur Palemahan yang analog dengan subsistem teknis atau kebendaan termasuk lingkungan alam.8 Berdasarkan konsepsi tersebut, Tri Hita Karana secara aplikatif merupakan ekspresi pola-pola hubungan yang serasi, harmonis dan seimbang yang bersifat universal dalam arti dapat diterapkan oleh setiap manusia dalam aktivitas kehidupannya ataupun dalam hubungan kontraktual antara individu satu dengan individu lainnya. Sifat universal dari pola hubungan yang serasi, harmonis dan seimbang tersebut tercermin di dalam pengaturan jasa konstruksi yang berlandaskan pada asas keserasian dan keseimbangan, di samping asas kejujuran dan 6 7 8 I.B. Mantra, 2004. Bhagawadgita (Alih Bahasa Dan Penjelasan), Upada Sastra, Denpasar, h.22. Periksa: I Made Titib, Veda (Sabda Suci) Pedoman Praktis Kehidupan, Paramita, Surabaya, 2004, h. 224. Periksa juga: I Ketut Wiana, 2004.Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif (Tri Hita Karana Sehari-hari), Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 264-265 A. White, The Concept of Culture System, Columbia University Press, New York. Wayan Windia, Transformasi Sistem Irigasi Subak yang berlandaskan Konsep Tri Hita Karana, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2006, Cetakan Pertama, h. 28. 16 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan keadilan, manfaat, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan.9 Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk berkualitas dan bermanfaat tinggi. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya serta menjamin terpilihnya penyedia jasa secara proporsional oleh pengguna jasa. Sejalan dengan asas keseimbangan dalam kaitannya dengan hubungan kontraktual, patut disimak pendapat Herlin Budiono yang menyatakan bahwa: ”asas keseimbangan difungsikan sebagai pembenaran daya ikat suatu perjanjian di samping tiga asas pokok lainnya dalam hukum kontrak yakni asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak”.10 Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembenaran daya ikat suatu perjanjian itu diekstrasi dari cara pikir khas Indonesia. Keterikatan kontraktual itu dilandaskan pada faktor idiil dan riil sebagai ”bahan dasar” (bouwstenen) yang mencakup pandangan hidup atau wawasan tertentu (pemahaman tentang hukum, falsafah hukum dan cita hukum) serta realitas (kondisi faktual) suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian asas keseimbangan memiliki tujuan utama yaitu kepatutan sosial (social gezindheid) untuk menjamin tercapainya keseimbangan antara individu satu dengan individu lainnya atau individu dan masyarakatnya.11 Oleh karena itu, wujud dan implementasi Tri Hita Karana dalam konteks penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dituangkan ke dalam bentuk kontrak konstruksi fokus pada perwujudan dari unsur keserasian dan keseimbangan hubungan antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa (sebagai unsur sesama manusia/pawongan dalam hubungan kontraktual), di samping perwujudan dua unsur lainnya yaitu unsur keserasian dan keseimbangan hubungan dengan Tuhan/Parhyangan, dan unsur keserasian dan keseimbangan hubungan dengan alam lingkungan/Palemahan yang realisasinya diwujudkan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan.12 2. Fungsi Tri Hita Karana Dalam Kontrak Konstruksi Kajian tentang fungsi Tri Hita Karana dengan ketiga unsur yang terkandung di dalamnya yakni: pertama, unsur Parhyangan (Tuhan) yang perwujudannya menunjuk pada fungsi ruang sebagai tempat yang bernilai kesucian termasuk kawasan suci atau tempat-tempat suci. Kedua, unsur Pawongan (manusia) yang perwujudannya menunjuk pada fungsi ruang sebagai tempat tinggal di dalam suatu wilayah atau teritorial. Ketiga, unsur Palemahan (alam lingkungan) yang perwujudannya menunjuk pada fungsi ruang yang menempatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, mencegah terjadinya eksploatasi terhadap potensi sumber daya alam. Dalam konteks ini, faktor fungsi mempunyai peranan penting. Pengertian fungsi dalam natuurwissenschaft (ilmu pengetahuan alam) mempunyai empat arti, yaitu: 9 10 11 12 Pasal 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Herlin Budiono, 2006. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Adtya Bakti, Bandung, h. 507 Ibid., h.413 Pelaksanaan pekerjaan konstruksi “Pengamanan Pura Tanah Lot” dalam kontrak paket III No.001/PKK/Ar.01/DPB.2000 dengan spesifikasi pekerjaan (scope of work) meliputi pembuatan artificial reef di lepas pantai untuk mereduksi energi gelombang, rehabilitasi areal pura, dan penataan lingkungan kawasan puraTanah Lot. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 17 KERTHA PATRIKA (1). (2). (3). 4). • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Bergantung pada; Tugas; Hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan; dan Kerja (werking).13 Dalam terminologi hukum, fungsi diartikan sebagai ”tugas khusus dari suatu jabatan”.14 Dengan demikian fungsi baru menampakan arti yang benar jika dihubungkan dengan suatu masalah.15 Permasalahan yang dimaksud dalam konteks kontrak konstruksi diantaranya syaratsyarat kontrak yang memuat tentang kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan bentuk tanggungjawab mengenai lingkungan dan manusia.16 Pembangunan proyek panas bumi yang dikenal dengan proyek ”Geothermal Bedugul” di kabupaten Tabanan pada tahun 1998 yang dilaksanakan oleh PT Pertamina dengan Bali Energi Ltd. yang sampai saat ini masih dipermasalahkan dari aspek sosiologisnya yaitu terkait dengan adanya penolakan masyarakat atas proyek yang dimaksud, dan dari aspek yuridisnya yaitu tidak dipatuhinya ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2005 bahwa lokasi proyek tersebut berada dalam areal kawasan suci dan kawasan hutan lindung. Merujuk pada pendapat bahwa fungsi berarti bergantung pada dan hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan, sangat relevan pada permasalahan proyek panas bumi tersebut. Peranan fungsi dari ketiga unsur Tri Hita Karana telah diabaikan sehingga mengakibatkan proyek tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya disampaikan fungsi Tri Hita Karana dalam konteks ruang lingkup atau obyek kontrak yakni lingkup pekerjaan perencanaan konstruksi, lingkup pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan lingkup pekerjaan pengawasan konstruksi. Ketiga lingkup pekerjaan konstruksi tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan pada fungsi unsur-unsur dari Tri Hita Karana sebagai berikut: 1). Unsur Parhyangan yang diimplementasikan sebagai tempat yang mempunyai kekuatan magis (supranatural) berfungsi sebagai media untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Unsur ini wajib diperhatikan oleh pihak penyedia jasa (kontraktor) berkait dengan tata letak dan fungsi bangunan yang akan dikerjakan. Ketentuan mengenai tata letak dan fungsi bangunan merujuk pada Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung dan berdasarkan Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu Tentang Arsitektur Bali, maka ketentuan untuk membangun atau tempat bangunan berpedoman pada pustaka yang disebut dengan Asta Bumi, ketentuan untuk bangunan atau konstruksinya berpedoman pada pustaka Asta Kosala-Kosali, dan ketentuan untuk bahan-bahan atau material yang akan digunakan berpedoman pada Asta Dewa.17 Sedangkan pedoman untuk kawasan bangunan yang berfungsi sebagai tempat suci berdasarkan ”pola pewilayahan” yang disebut dengan Tri Mandala (Tri=tiga, Mandala=wilayah) yakni: Utama Mandala yang berarti berada pada wilayah yang utama, Madya Mandala yang berarti berada pada wilayah tengah, dan Nista Mandala, yang berarti berada pada 13 14 15 16 17 Sjachran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico Bandung, 1986, h. 18-19. Periksa: Sjachran Basah, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangannya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34-35 IPM Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 301 Koesnoe Goesniardi S, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya,2006, h.25-26 Pasal 23 Huruf m PP No.29/2000 Ida Pedanda Mpu Jaya Wijayananda, 2004. Tata Letak Tanah Dan Bangunan (Pengaruhnya Terhadap Penghuninya), Paramita, Surabaya, h.6-9. Periksa: I Made Bidja, Asta Kosala-Kosali, Asta Bumi, Pustaka Bali Post, Denpasar, h.13 18 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan wilayah paling belakang.18 Berdasarkan konsep form follows function (bentuk mengikuti fungsi),19 maka bangunan yang akan dibangun akan disesuaikan dengan fungsinya terlebih dahulu, baru kemudian bentuk bangunannya mengikuti fungsi tersebut. Apabila fungsi bangunan tersebut sebagai tempat peribadatan atau tempat suci, maka bentuk bangunannya akan disesuaikan dengan kaidah atau norma yang berlaku berdasarkan arsitektur bangunan atau berdasarkan tafsir terhadap aspek agama Hindu mengenai arsitektur Bali. (2). Unsur Pawongan yang diimplementasikan sebagai teritorial atau wilayah yang mengatur ruang pribadi, ruang transisi, dan ruang bersama dalam kebersamaan fungsi sebagai tempat untuk mengadakan kesepakatan atau perjanjian dalam hubungan kontraktual dan saling menghormati hak dan kewajiban pihak satu dan pihak lainnya. Dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi, unsur pawongan ini merupakan media atau sarana untuk saling berinteraksi antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa yang dituangkan dalam syarat-syarat sahnya kontrak. Dari unsur pawongan ini tercermin beberapa prinsip dasar yang perlu dikemukakan, antara lain: a. Prinsip ”kerja keras” yakni mengerjakan pekerjaan dengan tekun dan disiplin. Dalam Bhagawadgita disebutkan: ”tanpa kerja, orang tidak akan mencapai kebebasan dan kesempurnaan. Hanya orang-orang yang giat bekerja, tulus dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam hidup”.20 b. Prinsip ”kerjasama”. Dalam pustaka Hindu (Yayur Weda dan Rig Weda) disebutkan: ”manusia harus membantu orang lain yang mengalami kesulitan atau ditimpa kemalangan. Tuhan akan selalu memberi karunia kepada orang yang selalu berusaha untuk menciptakan dan memelihara keharmonisan yang selaras diantara sesama”.21 Dalam konteks ini, prinsip ”kerjakeras” dan ”kerjasama” tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang ”Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak konstruksi” yang meliputi: 1). Hak dan kewajiban pengguna jasa; 2). Hak dan kewajiban penyedia jasa.22 Penjabaran lebih lanjut dari prinsip ini tercermin pula pada ketentuan yang mengatur bagian ”Pelaksanaan Kontrak” yang tercantum dalam Bab II Huruf D 1 a Lampiran I Keppres No.80/2003 memuat tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bahwa: ”selambat-lambatnya empatbelas hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, pihak pengguna jasa sudah harus menerbitkan SPMK”. Ini artinya prinsip ”kerja keras” sebagaimana dimaksud telah dapat dilakukan oleh penyedia jasa setelah menerima perintah mulai kerja dari pengguna jasa. Demikian pula pada ketentuan yang mengatur tentang ”Pemeriksaan Bersama” yang menyatakan: ”pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, pihak pengguna jasa bersama-sama dengan pihak penyedia jasa melakukan pemeriksaan bersama”. Implementasi prinsip ”kerjasama” sebagaimana dimaksud nampak dengan dilakukannya pemeriksaan secara bersama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ikatan kerjasama yang dilakukan dapat menciptakan suasana yang serasi dan harmonis. 18 19 20 21 22 Ibid Eko Budiharjo, 1997. Arsitektur & Kota Di Indonesia, Alumni, Bandung, h.31 B.Ashrama, 2003.Buku Panduan (Handbook) Tri Hita Karana, Tourism Award&Accreditation Bali Travel News, Cet.Pertama, h.7 Ibid Pasal 23 ayat (1) Huruf e PP No. 29/2000 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 19 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 (3). Unsur Palemahan yang diimplementasikan dalam bentuk-bentuk penataan ruang bagi kehidupan yang heterogen, profesional dan struktural, yang berfungsi untuk mengatur kegiatan pemanfaatan alam. Berdasarkan kenyataan, unsur palemahan ini berhubungan dengan aspek fisik suatu konstruksi bangunan. Ketinggian suatu bangunan tidak melebihi dari limabelas meter atau setinggi pohon kelapa, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari limabelas meter seperti menara pemancar, mercusuar, bangunan pertahanan dan keamanan dan bangunan keagamaan.23 Implementasi dari unsur palemahan ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan kualitas lingkungan sesuai dengan pemanfaatannya dan sekaligus berfungsi sebagai salah satu syarat untuk dapat tidaknya suatu pekerjaan konstruksi diselenggarakan. Di samping itu hal ini penting untuk diperhatikan, karena pelanggaran terhadap ketentuan normatif dari pemanfaatan ruang dan ketentuan yang berlaku memungkinkan terjadinya pekerjaan konstruksi tidak dapat dilanjutkan.24 3. Penegakan Hukum Penegakan hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah penegakan hukum dalam konteks implementasi prinsip Tri Hita Karana dalam peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2005. kedua peraturan daerah tersebut pada prinsipnya di arahkan untuk mewujudkan pembangunandi wilayah Provinsi Bali seseuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Pada kenyataannya, pembangunan yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah di Provinsi Bali tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang di dalam peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu penegakan hukum dalam hal ini perlu tegas dan konsisten terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: a. kepastian hukum (rechtssicherheit); b. kemanfaatan (zweckmassiheit); dan c. keadilan (gerechtigheit).25 Kepastian hukum merupakan perlindungan masyarakat terhadap tindakan sewenangwenang. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknnya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Demikian pula penegakan hukum harus memperhatikan keadilan. Sebab hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.26 Secara konsepsional, esensi dari arti penegakan hukum (dari aspek filosofisnya) adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah atau 23 24 25 26 Pasal 30 ayat (1) Huruf e angka 2 Perda No.3/2005 Kasus penataan Loloan Yeh Poh di Desa Kuta Utara, Kabupaten Badung Tahun 2007 yang dilakukan oleh PT Bali Unicorn Corporation selaku pihak kontraktor, pengerjaan proyek tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung No.637/2003: Loloan termasuk daerah limitasi yang tidak dapat dikembangkan untuk pembangunan. Sudikno Mertokusumo, 1993.Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, , h. 1 Ibid 20 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan norma yang mantap dan diimplementasikan pada sikap tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.27 Dengan demikan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagar pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menuju pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan. Sejalan dengan konsepsi di atas, pada saat hukum akan ditegakan untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka akan ada kemungkinan rasa keadilan masyarakat akan terganggu, sehingga dalam situasi yang demikian ada konflik atau benturan kepentingan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat.28 Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus kajian penegakan hukum (aspek yuridisnya) adalah dalam kaitannya dengan penerapan prinsip Tri Hita Karana dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. 3.1. Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2005. Potensi dan daya dukung alam Bali yang terbatas menimbulkan permasalahan pada tataruang Bali. Permasalahan itu dapat dilihat pada pembangunan fisik disepanjang jalan arteri sehingga dapat mengurangi dayatarik keindahan alam sekitarnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, ketimpangan pembangunan antar kabupaten, tumpang tindih pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya, serta ancaman terhadap pelestarian budaya daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadikan semakin rumitnya persoalan tataruang Bali yang menurut Ketua Badan Perencana Pembangunan Daerah Bali (Bapeda Bali) pada waktu itu, disebabkan oleh lemahnya kesadaran hukum serta kemampuan aparat dalam menegakan hukum sehingga belum mampu menjadikan hukum sebagai panglima dalam pembangunan.29 Secara sosiologis dari akibat lemahnya kesadaran hukum dan kemampuan aparat dalam menegakan hukum dapat mengakibatkan munculnya persoalan pada daerah kawasan baru pembangunan jalan, munculnya pembangunan fisik dan pelanggaran jalur hijau, mencerminkan tidak terkendalinya pemanfaatan ruang yang potensial merusak fungsi lingkungan. Telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibat pula telah terjadi ketidakserasian dan ketidakseimbangan hubungan sebagaimana tercermin dari unsur-unsur Tri Hita Karana. Kasus yang menjadi sorotan berbagai pihak adalah Vila Bukit Berbunga dan sejumlah Rumah Makan bermunculan di kawasan penyangga danau Beratan, Desa Bedugul, Kabupaten Tabanan. Demikian juga pelanggaran kawasan jalur hijau dan peruntukan tataruang disepanjang jalan Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Permasalahan menjadi semakin rumit karena pengelolaan dan kewenangan penataan ruang dilakukan secara parsial oleh masingmasing kabupaten dan kota. Hal ini terbukti dari pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang baru sebagai pengganti RTRWP Bali Tahun 2005 yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Pembahasan menjadi alot karena kecenderungan pemerintah kabupaten dan kota menggali sumberdaya alam dengan mendorong pembangunan semata-mata untuk mengejar 27 28 29 Soerjono Soekanto,1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5 Muchammad Zaidun, 2006. Tantangan Dan Kendala Kepastian Hukum Di Indonesia (Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, h.120 Putu Sujana Cahyanta, 2004. Lemahnya Penegakan Hukum, Penyimpangan Peruntukan Ruang (Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita), Pustaka Bali Post, h. 168 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 21 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 target Pendapat Asli Daerah (PAD), sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pemanfaatan tataruang dan mengakibatkan pula terjadinya ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tataruang wilayah. Penegakan hukum dalam persoalan konflik kepentingan yang dirasakan saat ini perlu pengkajian secara cermat. Dalam konteks ini, terhadap semua tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku harus dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Berbagai pelanggaran di dalam pemanfaatan tataruang selama ini tidak mendapat tindakan secara proporsional sehingga terus berlangsung dan cenderung meningkat. Berdasarkan kenyataan sebagaimana dimuat dalam media surat kabar dengan judul: ”Pelemahan Bali Nan Terkoyak”, antara lain ditulis bahwa bangunan vila tidak hanya menyerbu kawasan suci sekitar Pura Uluwatu di Desa Pecatu Kabupaten Badung, di daerah persawahan di Desa Canggu dan Desa Kerobokan, juga di kawasan hulu seperti lereng, danau di Kabupaten Tabanan mulai dirambah pembangunan vila. Ironisnya pembangunan vila-vila tersebut tidak lagi mengindahkan pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah yang berlaku saat ini. Kawasan hulu yang diharapkan mampu menyediakan air untuk kawasan hilir, secara perlahan mulai digerogoti dengan adanya alih fungsi lahan.30 Secara spesifik penegakan hukum di wilayah kabupaten Badung belum berjalan secara optimal. Masih banyak pelanggaran tataruang dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas. Penegakan aturan tataruang pemerintah kabupaten Badung dinilai ”ompong”.31 Penegakan aturan itu tidak berdaya karena tidak adanya pengenaan sanksi. Sesungguhnya penjatuhan sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelanggar tataruang sebagaimana di atur dalam Pasal 42 Perda RTRWP Bali, yang selengkapnya berbunyi: Ayat (1) : setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 Perda ini (yakni wajib memelihara kualitas ruang dan wajib menaati rencana tataruang yang telah ditetapkan), diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) : tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran. Ayat (3) : selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seyogyanya pemerintah kabupaten Badung lebih serius memperhatikan penegakan hukum tersebut untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan hubungan sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana. Pemerintah kabupaten Badung harus meningkatkan pengawasan terhadap pengaturan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian tataruang. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, lebih menekankan pentingnya penjagaan lingkungan termasuk pengenaan sanksinya. Berdasarkan undang-undang tersebut, para pelanggar aturan dapat dikenakan sanksi denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.32 Sanksi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 jauh lebih berat dibandingkan sanksi yang di atur dalam Peraturan Daerah tersebut. Dengan payung hukum yang lebih tegas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, tentunya pemerintah kabupaten Badung tidak ragu-ragu lagi dalam penegakan hukum. 30 31 32 Harian Umum Bali Post, Jumat 25 April 2008, h. 2 Harian Umum Bali Post, Kemis 21 April 2008, h. 2 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 22 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan Dari persoalan lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus sebagaimana dipaparkan di atas, perlu ada komitmen dari semua pihak khususnya dari aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan konsisten menjadikan hukum sebagai panglima dalam pembangunan terutama penegakan aturan sebagaimana di atur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku yang dilandasi oleh prinsip Tri Hita Karana. 3.2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 yang mengatur tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (selanjutnya disingkat Perda No.5/2005) pada prinsipnya adalah menjamin keselamatan pengguna dan lingkungan serta mengakomodir nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan prinsip Tri Hita Karana. Menjadi persoalan, bagaimanakah penegakan hukum dari peraturan daerah ini dengan tidak adanya kejelasan atau tidak dicantumkannya ketentuan tentang sanksi bagi persyaratan arsitektur bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut? Patut dicermati bahwa di dalam Pasal 23 Perda No.5/2005 hanya menentukan: “arsitektur bangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana di atur dalam Perda ini”. Demikan pula di dalam ”Penjelasan” pasal ini disebutkan ”Cukup jelas”. Oleh karena itu, Perda No.5/2005 sudah sepatutnya direvisi dan diberdayakan terutama dalam penegakan hukumnya. Sebab, sesuai dengan fungsi penegakan hukum, bahwa Perda ini harus dapat menciptakan kepastian hukum agar pelaksanaan persyaratan arsitektur bangunan gedung menjadi tertib. Selanjutnya dengan terciptanya kepastian hukum, Perda ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat pengguna dan lingkungannya. Demikian pula dengan adanya Perda ini rasa keadilan akan terwujud dengan sanksi yang akan dikenakan bagi setiap pelanggarnya. Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disingkat UU No.28/2002) dalam Bab IV, Bagian Ketiga, Paragraf 3 Pasal 14 di atur mengenai Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Dengan adanya aturan tersebut, maka bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan saksi. ”Setiap pemilik atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana”.33 Pengenaan sanksi tidak membebaskan pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 28/2002 ini patut dijadikan acuan dalam penjatuhan sanksi, karena sanksi yang di atur dalam perda No.5/2005 tidak tegas. Sanksi administratif yang dimaksud adalah sanksi yang diberikan oleh administrator (pemerintah) kepada pemilik atau pengguna bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan, meliputi beberapa jenis tergantung pada tingkat kesalahannya. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.34 Selain pengenanaan sanksi administratif, dapat juga dikenakan sanksi denda paling banyak 10 %0 (per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Nilai bangunan yang 33 34 Pasal 44 UU No.28/2002 Pasal 45 ayat (1) UU No.28/2002 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 23 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 dimaksud adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun. Bagi yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi, dihitung berdasarkan nilai keseluruhan bangunan gedung yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri. Sedangkan sanksi pidananya ditujukan kepada setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, di ancam pidana mulai dari tiga tahun hingga lima tahun tergantung dari akibat kerugian yang ditimbulkan.35 Dari ketentuan di atas, nampak jelas perbedaan ancaman hukuman yang dikenakan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana pada UU No.28/2002. Sebaliknya di dalam Perda 5/2005 tidak di atur atau tidak jelas ancaman hukuman yang dikenakan baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidananya. Walaupun Perda No.5/2005 tidak menyebutkan sanksi secara jelas, namun dapat ditafsirkan bahwa Perda No.5/2005 itu merupakan penjabaran dari UU No.28/2002, karena UU No.28/2002 mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk peraturan daerah.36 Dengan demikian, apabila pengenaan sanksi pada Perda No.5/2005 tidak mengatur secara jelas, dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur dalam UU No.28/2002 dengan merujuk pada produk hukum yang lebih tinggi berdasarkan asas perundang-undangan yakni Lex superiori derogat legi inferiori (”peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah”). Guna meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam ruang lingkup berlakunya Perda No.5/2005, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah Tim Pengendali Arsitektur Tradisional Bali (disingkat TPATB) sebagaimana dicetuskan oleh Ketua Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) Cabang Bali.37 Tim ini dibentuk dalam kerangka kepedulian terhadap upaya-upaya mewujudkan tataruang Bali yang lestari melalui pengembangan arsitektur tradisional Bali yang kontekstual, namun tetap menghormati nilai-nilai luhur dan konsisten dalam penegakan hukumnya. Dengan upaya ini diharapkan ada komitmen yang sama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menyelamatkan Bali melalui arsitektur tradional Bali yang disusun oleh para leluhur dan dengan rambu-rambu pengendali sebagaimana di atur dalam Perda No.5/2005 yang berlandaskan Tri Hita Karana. 35 36 37 Periksa: Pasal 46 ayat (1), (2), (3), UU No.28/2002 Bagian Umum Penjelasan Atas UU No.28/2002 IGN Adnyana dalam: Alit Sumerta, 2004. Perlu Tim Pengendali Arsitektur Tradisional Bali (Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita), Pustaka Bali Post, Denpasar, h.179-180. 24 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Prinsip Tri Hita Karana dalam Kontrak Konstruksi I Wayan Wiryawan III. PENUTUP 1. Simpulan 1.1. Asas keserasian dan asas keseimbangan sebagai landasan pengaturan jasa konstruksi sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi, seiring dan sejalan dengan prinsip Tri Hita Karana dengan ketiga unsurnya yakni Parhyangan, Pawongan dan Palemahan, merupakan pola hubungan keterikatan para pihak (pengguna jasa dan penyedia jasa) dalam hubungan kontraktual dan dikaji dari asas hukum kontrak merupakan prinsip dan norma hukum yang mengikat (pacta sunt servanda). 1.2. Implementasi prinsip Tri Hita Karana dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi tercermin dalam wujud dan fungsinya pada setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan perencanaan konstruksi, pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan pengawasan konstruksi. Ketiga ruang lingkup pekerjaan konstruksi tersebut merupakan obyek dari kontrak konstruksi, yang di dalam pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan aturan pelaksanaannya, juga tunduk pada kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan perundang-undangan lain termasuk peraturan daerah. 1.3. Penegakan hukum dalam rangka untuk meminimalkan bahkan meniadakan terjadinya pelanggaran atas pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian tataruang Bali, pengenaan sanksinya merujuk pada Perda No. 3/2005 Tentang RTRWP Bali jonto UU No. 28/2007 Tentang Penataan ruang, sedangkan pengenaan sanksi bagi setiap pemilik atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan dan atau penyelenggaraan bangunan gedung, merujuk pada Perda No.5/2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung jonto UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Saran 2.1. Pola hubungan kontraktual sebagai pencerminan dari prinsip Tri Hita Karana diyakini sebagai suatu sistem keharmonisan hidup masyarakat (Bali) yang berasal dari kearifan lokal, seyogyanya dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi dalam implementasinya pada skala yang bersifat universal untuk menuju pada integrated balance harmony. 2.2. Implementasi prinsip Tri Hita Karana dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi, idealnya perlu dicantumkan dalam suatu klausula kontrak guna mengakomodir unsur-unsur dari Tri Hita Karana. 2.3. Segera dilakukan revisi pada peraturan daerah yang pengenaan sanksinya masih lemah dan tidak jelas dengan merujuk pada produk hukum yang lebih tinggi agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 25 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 DAFTAR PUSTAKA Buku Ashrama, B., 2003. Buku Panduan (Hand Book) Tri Hita Karana, Tourism Award & Accreditation Bali Travel News, Cet. Pertama. Basah, Sjachran, 1986. Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung. Bija, I Made, 2000. Asta Kosala-Kosali, Asta Bumi, Bali Post, Denpasar. Budiono, Herlin, 2006. Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Mantra, IB., 2004. Bhagawadgita, Alih Bahasa Dan Penjelasan, Upada Sastra, Denpasar. Mertokusumo, Sudikno,1996. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. White, A., 1975. The Concept of Culture System, Columbia University Press, New York. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, LNRI Tahhun 1999 No. 53, TLNRI No. 3833. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4. 26 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia oleh : Dewa Suartha (Bagian Hukum Acara FH Unud) Abstract The acceptance of corporation as subject of criminal act brings problem to criminal law policy in corporation criminal act respnsibility. There are two principle problems in this study : 1) How is the current criminal law policy in corporation criminal act responsibility ? 2) How is criminal law policy upon the corporation criminal act responsibility in insconstituendum perspective? The result of the research : 1) criminal code has not regulates corporation as the subject of criminal act that is accountable for criminal law, nevertheless it is partial but inconsistent; 2) criminal code bill 19992000 has clearly and completely regulated corporation as subject of criminal act and is accountable for criminal law and accept unconditional criminal responsibility as well as substitute criminal responsibility, although with the exception to solve difficult problem ini order to prove mistakes mide by corporation. Keywords : policy on corportion, criminal act I. PENDAHULUAN Konsep badan hukum, pada mulanya timbul dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan akan lebih berhasil. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya tiada lain sekedar ciptaan hukum yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu bdan, dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, disamping subyek hukum yang berujud “manusia alamiah” (natuurlijk persoon). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan yang sekalipun badan sekedar suatu badan, namun dianggap badan ini bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi, manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan hukum yang bersangkutan1. Menurut Chaidir Ali, Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing2. Di Indonesia dikenal berbagai bentuk badan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), ada pula dalam bentuk perkumpulan yang diatur dalam titel IX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbentuk 1 2 H. Setiojono, 2002, Kejahatan Korporasi Analisis Vikti mologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Overasi Press, Malang, hal. 4 Chaidir Ali.1987. Badan Hukum. Bandung: Alumni,h.64 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 27 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992, berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 joncto UndangUndang No. 6 Tahun 1969 juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 dan Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001. Sebagai suatu kenyataan sosiologis peranan badan hukum (korporasi) dalam aktivitas ekonomi sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Sejalan dengan perkembangan IPTEK yang berpengaruh pula pada dinamika ekonomi, sehingga sepak terjang korporasi yang saat ini lazim dikenal dengan sebutan perusahaan-perusahaan multi nasional (multi nasional corporation) yang tidak saja berdampak positif, melainkan yang negatifpun tidak kalah bahayanya yang sangat merugikan masyarakat luas. Pada awal tahun 1960 mulai menjadi perhatian para akhli sosial ekonomi dan kriminologi. Fenomena dan sepak terjang korporasi itu telah berlangsung sebelum perang dunia ke-2, namun study yang sistimatis dan mendalam baru dimulai pada awal tahun itu, sementara itu dikalangan kriminologi, study kritis terhadap peranan korporasi sudah dimulai sejak tahun 1939, melalui suatu pidato bersejarah Edwin H. Suter Land di depan : “The American Sosiological Association” Ia mengemukakan konsep “White Collar Crime (WCC) yang didefinisikan sebagai : a crime committed by a person of respectability and high social status in the cowese of hisaccuption3. Perhatian masyarakat Internasional terhadap korporasi secara jelas nampak pula dari usaha dunia Internasional untuk menangkal prilaku negatif dari perusahaan-perusahaan multi nasional (multi nasional enter prise). Usaha tersebut merupakan hasil kerjasama Internasional dalam bentuk code conduct of Transnasional Corporation (UN Ecosoe, 1977) yang antara lain mengatur : (1) Aktivitas Transnational Corporation (TNC), (2) Treatment of TNC dan (3) Intergovernmental co-operation4. Di Indonesia kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap korporasi harus dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kenyataannya bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi sebagai subyek hukum tidak diatur dalam KUHP secara tegas, mengingat hukum pidana nasional di desain untuk menghadapi prilaku individu manusia alamiah (natuurlijk person), sedangkan beberapa perundang-undangan di luar KUHP telah ada mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi, tetapi masih bersifat parsial dan tidak konsisten, sehingga sangat sulit penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia. Mengingat pertanggungjawaban tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia cenderung kepada pelaku manusia sebagai subyek hukum, sedangkan korporasi sebagai subyek hukum yang juga bisa melakukan tindak pidana tidak pernah mendapat perhatian dalam praktek peradilan kiranya perlu dibahas selanjutnya menyangkut hal-hal sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kebijakan Hukum Pidana saat ini dalam pertanggung jawaban tindak pidana korporasi ? 2. Bagaimanakah kebijakan Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban tindak pidana korporasi dalam perspektif ins constituendum? 3 4 Shofic Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Prilaku Korporasi, Ghalia Indonesia Jakarta, hal. 20. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undil, Semarang, hal. 6 28 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Dewa Suartha II. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI 1. Pengaturan dalam KUHP KUHP berlandaskan pada azas bahwa hanya manusia (natuurlijk persoon) yang dapat dituntut sebagai pelaku (dader) dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan, maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari, antara lain : a. Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum dimaksudkan kepada orang atau manusia secara pribadi. Perumusan yang lain adalah : seorang ibu (Pasal 341, 342 KUHP), Perempuan (346 KUHP) Guru (Pasal 294 KUHP), Pemula Agama (Pasal 530 KUHP), Nahoda (Pasal 93, 325 KUHP), Tabib (Pasal 267 KUHP), Pedagang (Pasal 392, 397 KUHP), Pengurus atau Komisaris Perusahaan (Pasal 398, 399, 403 KUHP), seorang pemborong (Pasal 387 KUHP), Panglima Tentara (Pasal 413 KUHP), Pegawai Negeri (Pasal 414 s/d 419 KUHP), Hakim (Pasal 420 KUHP), Mucikari atau Germo (Pasal 506 KUHP). Jadi keseluruhan perumusan pasal-pasal tersebut bukan untuk badan hukum (Korporasi). b. Sistem Pidana yang dianut, khususnya pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan pada manusia pribadi dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau korporasi. c. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. d. Tidak ada prosedur khusus dalam Hukum Acara Pidana untuk korporasi. e. Sesungguhnya dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang kelihatannya menyangkut korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi ancaman pidananya ditujukan kepada orang atau manusia pribadi bukan korporasi, misalnya Pasal 169, 398, 399 KUHP. 2. Pengaturan dalam Perundang-Undangan di luar KUHP Sebagai upaya untuk mengetahui pengaturan pertanggung jawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ternyata korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana dalam perkembangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sudah dikenal sejak 1951 dan mulai dikenal secara luas pada tahun 1955 yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah : a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Tenaga Kerja No. 12 untuk seluruh Indonesia. b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 untuk seluruh Indonesia. c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan perburuhan untuk seluruh Indonesia. d. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. e. Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. f. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Jo Undang-Undang No. 26 tahun 1957 tentang JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 29 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 penyelesaian perburuhan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Undang-Undang No. 38 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu. i. Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi j. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapora ketenaga kerjaan di Perusahaan. k. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar perusahaan l. Undang-Undang No. 14 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular m. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. n. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup o. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika p. Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika q. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. r. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen s. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. t. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) u. Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. g. h. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, nampaknya ada keinginan untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi mengenai pertanggungjawabannya tidak jelas arah perkembangannya. Jika diklasifikasikan maka akan tampak ada beberapa cara pembuat Undang-Undang dalam merumuskan kedudukan korporasi sebagai pelaku dan pertanggungjawabannya sebagai berikut : a. Hanya pengurus sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggung jawab kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Rumusan yang demikian dapat dilihat dalam pasal 169, 398, 339 KUHP. Dalam hal perumusan yang demikian, (maka berlakulah syarat-syarat umum tentang perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terahdap orang atau manusia pribadi. b. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggung-jawaban pidananya kepada pengurus. Pendapat ini berdasarkan kepada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh manusia secara fisik dalam keadaan nyata dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Rumusan seperti tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 UU No. 3 Tahun 1958, Pasal 34 UU No. 7 Tahun 1981, pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982, pasal 15 Tahun 1984. Ketentuan ini menganut prinsip pelimpahan tanggungjawab secara tanpa syarat. Disebut demikian karena menempatkan pengurus korporasi sebagai pihak yang harus menerima pelimpahan tanggung jawab pidana dengan mengabaikan apakah yang bersangkutan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Dalam hal ini beban 30 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Dewa Suartha c. tanggung jawab pidana dari pengurus seakan-akan hanya sebagai konskuensi dari suatu jabatan yang telah ditetapkan oleh peraturan intern korporasi. Jadi disini sama sekali tidak disyaratkan bahwa pengurus tersebut harus ebagai pemberi perintah atau pemimpin didalam perbuatan tersebut. Dengan demikian “asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang merupakan dasar dari ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana telah dikecualikan. Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pengurus menurut kewenangannya berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut, maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana itu diidentikkan dengan apa yang diatur dalam hukum perdata, khususnya tentang perbuatan “intravires” dan “ultra vires”. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak (badan hukum) adalah perbuatan “intra veres” sebaliknya setiap perbuatan yang dilakukan berada di luar lingkup kecakapan bertindak di Perseroan Terbatas (PT) atau diluar maksud dan tujuan badan hukum adalah perbuatan “ultra veres” yang karenanya tidak sah dan tidak mengikat PT. Korporasi Diakui Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dapat di pertanggunjawabkan dalam hukum pidana. Dimuat dalam rumusan pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun 1955, Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 70 UU No. Tahun 1997, Pasal 80 UU No. 22 Tahun 1997, Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002. III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM 1. Pengaturan Dalam Rancangan KUHP 1999/2000 Dalam ruang lingkup pembentukan KUHP Nasional Indonesia, muncul perhatian khusus mengenai perlindungan sosial terhadap aktivitas korporasi yang bersifat merugikan masyarakat, sehingga korporasi dipandang perlu untuk dirumuskan sebagai pelaku dan yang bertanggung jawab. Konsep korporasi dan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dirumuskan oleh Tim Penyusun Naskah Rancangan KUHP 1999/2000 Pasal 162 dan Pasal 44 sampai dengan pasal 49. Bunyi rumusan pasal-pasal tersebut adalah, sebagai berikut : Pasal 162 : Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan. Pasal 44 : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak Pasal45 : Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya Pasal 46 : Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Pasal 47 : Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi di batasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Pasal 48 Ayat (1) : Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 31 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dari pada menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Ayat (2) : Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim. Pasal 49 : Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi. Mengenai kedudukan sebagai pelaku dan sifat pertanggung jawaban korporasi disebutkan dalam penjelasan Pasal 46 Rancangan KUHP 1999/2000 sebagai berikut : a. Pengurus korporasi sebagai pelaku dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab. b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi menurut Rancangan KUHP 1999/2000 hanyalah “pidana denda” dengan ancaman maksimum pidana denda lebih berat dibandingkan pidana denda terahdap orang, yaitu katagori lebih tinggi berikutnya. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 5 tahun adalah denda katagori V dan mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah denda kategori VI. Sedangkan pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah denda katagori IV (Pasal 75 ayat (4), (5) & (6). Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi (Pasal 84 ayat (2). 2. Relevansi Penerimaan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korporasi dalam hukum Pidana. Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran, kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan “Mens Rea”. Doktrin Mens Rea itu dilandaskan pada maxim “actus non facit comisi mens sit rea” yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam hukum pidana Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan “an act does not make a person quilty unsless the mind is legally blame worthy”. Berdasarkan asas tersebut, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu : (1) ada perbuatan lahiriah yang terlarang (actus rens) dan (2) ada sikap bathin jahat atau tercela lahiriah yang terlarang (mens rea). Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealfaan. Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu, sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam mempertanggung32 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Dewa Suartha jawabkan pelaku delik karena telah melakukan perbuatan pidana. Asas tersebut juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pelaku delik. Pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu5. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan, misal : Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan, Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan di dalam KUHP, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya mengidentifikasikan dianutnya asas kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealfaan. Disamping itu juga dalam hukum pidana dikenal suatu asas yang tidak tertulis yang berbunyi : “geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Dengan perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, maupun dunia usaha, muncul perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sifatnya ringan, namun sangat membahayakan bagi masyarakat umum (public welfare offences). Kejahatan dalam bentuk ini kadang-kadang tidak disertai dengan niat jahat sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain, seperti : pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Kejahatan ini juga kadang kala hanya berupa pelanggaran peraturan yang berdampak pada membahayakan masyarakat (regulatory offences), misalnya yang berkaitan dengan minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang, pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan sebagainya. Dalam rangka mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Alasan utama untuk menerapkan pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu, seperti tindak pidana korporasi sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu: (a) pertanggungjawaban mutlak, (b) pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban korporasi. Ad. a. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak Pertanggungjawaban pidana mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pelaku sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap bathinnya. Asas ini diartikan dengan istilah “Liability Without Foulty”, Unsur pokok dalam strict liability adalah : perbuatan (actus rens), sehingga yang harus dibuktikan hanya actus rens, bukan mens rea. Landasan penerapan strict liability, antara lain: 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial. 2) Perbuatan terbenar-benar bersifat melawan hukum (unlawful) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan. 5 Roeslan Saleh , 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 33 KERTHA PATRIKA 3) 4) • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang, karena dikatagorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesepakatan, keselamatan dan moralik (a particular activity potential danger of public health, safety, or moral). Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (unreasonable preausions)6. Dalam persefektif ius constituendum, sistem pertanggung-jawaban pidana mutlak juga sudah dirumuskan dalam Rancangan KUHP, Pasal 32 ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut: Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Latar belakang dan alasan dicantumkannya asas tersebut dalam Rancangan Konsep KUHP 1999-2000 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan suatu perkecualian. Oleh karena itu tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh UndangUndang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau “strict liability”. Secara teoritis, asas tanggung jawab mutlak (strict liability) telah diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-19. Di Indonesia sendiri, pengetahuan mengenai asas strict liability tidak hanya terbatas di kalangan teoritis atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Sebab, asas strict liability sesungguhnya telah diterapkan sejak lama dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum lalu lintas dalam hal terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan7. Ad. b. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggung-jawaban seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata, kemudian berkembang akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasuskasus pidana dalam sistem precedent, seperti: Inggris dan Amerika. Asas pertanggungjawaban pidana pengganti dikenal “Vicarious Leability”, yaitu prinsip pendelegasian (the delegation principle” dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (the servant’s act is the master’s act in law)8. (1) Prinsip pendelegasian (the delegation prinsiple) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain (2) Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (the servant’s act is the master’s act in law). Seseorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh buruhnya atau pekerjaannya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. Jadi apabila si pekerja sebagai permbuat matriil/ fisik (auctor ficiens) dan majikan sebagai pembuatan intelektual (auctor intellectualis). 6 7 8 Yahya, Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya bakti Badung, hal. 37-38. Barda Nawawi Arief , 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 237 Marcus Flacher.1990. A-Level Principle of English Law, 1st Edition. London. HLT Publication, hal.194. 34 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Dewa Suartha Rancangan KUHP 1999/2000 juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana pengganti ini dalam pasal 32 ayat (2) yang rumusannya menyatakan bahwa: “Dalam hal-hal tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang”. Ad.c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Korporasi disebut sebagai legal personality, artiya korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam perkara perdata sehingga timbul pertanyaan apakah korporasi dapat dituntut/dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ? Pada mulanya orang menoleh untuk mempertanggungjawab dan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia, sehingga ia tidak mungkin melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikirn untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau berupa tindakan lain, seperti : tindakan tata tertib atau tindakan administratif9. Sehubungan hal tersebut pertanyaan yang muncul adalah : sampai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai relevansi untuk diterapkan di Indonesia ? Dengan kata lian, sampai sejauhmana relevansinya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia ? Dengan kata lain, sampai sejauhmana relevansinya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada beberapa tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembenar, yaitu : (1) dasar pembenar teoritis, (2) dasar pembenar sosiologis, (3) dasar pembenar filosofis. Ad. 1: Dasar Pembenar Teoritis Relevansi teoritis ini perlu dikemukakan dengan pertimbangna apakah berlakunya suatu kaedah hukum tidak bertentangan dengan kecenderungan perkembangan pemikiran global. Relevansi Teoritis ini juga kasus dikaitkan dengan jalan pemikiran ilmiah di kalangan akademis hukum, artinya apakah kaedah hukum yang baru di introdusir itu dapat diterima atau ditolak oleh kalangan ilmiah hukum dengan berbagai alasan dan argumentasi yang di kemukakan. Alasan dan argumentasi para akhli hukum tersebut di samping didasarkan pada pemikiran yang abtrak, juga didasarkan pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Lebih karena itu pembahasan mengenai relevasi teoritis ini tidak dapat dilepaskan dari realitas yang ada dalam masyarakat, baik mengenai perundang-undangan, mmaupun realitas penegakan hukumnya melalui putusan penyidikan (Yuriprudensi). Barda Nawawi Arief berpendapat, penyesuaian pangan tidak alas kesalahan, jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (Contralietensi), tetapi juga harus dilihat sebagai pelengkap (complement) dalam mewujudkan asal keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, keseimbangan antara kedua kepentingan itulah oleh beliau dinamakan sebagai asas monodualistik10. Pembenaran penyimpangan terhadap kesalahan dalam pertanggung jawaban tindak pidana berporasi dapat di kaji atas dasar tujuan 9 10 Sue Titus Reid, Criminal Low, 3 Edition, Prentici Hall, New Jersey, hal. 51 Barda Narawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti, Bandung, hal.112-113 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 35 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat integretif dalam rangka perlindungan sosial, yaitu : (1) pencegahan umum dan khusus, (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan atau pengimbangan. Alasan perlunya perumusan “Strict Leability” dan “Vicarious Liability” dalam pemidanaan korporasi merupakan refleksi dalam menjaga kepentingan sosial. Ad 2 : Dasar Pembenar Sosiologis Relevansi sosiologis ini dibutuhkan untuk menilai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua teori yang dikenal, yaitu teori pengakuan dan teori kekuasaan. Kedua teori tersebut digunakan oleh Soerjono Soekanto dalam menilai keberlakuan hukum adat di Indonesia, juga akna dipergunakan dalam menilai sejauhmana penyimpangan asas kesalahan itu dapat diberlakukan atau tidak dalam masyarakat Indonesia11. Menurut teori pengakuan, berlaku tidaknya suatu norma hukum itu ditentukan oleh sejauhmana masyarakat menerima dan mengakui sebagai norma yang ditaati. Secara ekstrim menurut pandangan teori pengakuan, suatu ketentuan hukum baru boleh dianggap sebagai hukum apabila ia diakui secara sah oleh masyarakat sendiri. Sedangkan menurut teori kekuasaan, berlaku tidaknya suatu norma itu dilihat sejauhmana norma itu diberlakukan oleh suatu kekuasaan tertentu. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa dalam pandangan teori kekuasaan, suatu norma hukum itu berlaku karena kekuatannya sendiri yang bersifat perintah, terpisah dari pertimbangan ada tidaknya pengakuan dari masyarakat yang diaturnya. Menurut hukum adat pidana, dalam masalah pertanggung-jawaban pidana, tidak sematamata menganut asas kesalahan sebagai unsur yan mutlak yang harus ada dalam suatu delik. Hukum adat pidana juga menuntut seseorang untuk bertanggungjawab, walaupun tidak ada kesalahan sama sekali. (seperti strict liability)12. Tindakan reaksi atau koreksi itu tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabat atau keluarganya atau mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangna yang terganggu (seperti vicarious liability)13. Penyimpangan asas kesalahan ini dengan pembatasanpembatasan yang ketat dapat saja diberlakukan atau tidak diberlakukan di Indonesia, bergantung pada bagaimana sikap pembentuk undang-undang untuk menentukannya14. Melihat hukum pidana dalam perspektif (us constituendum) penyimpangan asas kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk Rancangan KUHP 1999-2000. Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat yang diikuti perkembangan bentuk dan modus operensi kejahatan yang semakin kompleks. Penerimaan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi merupakan refleksi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 11 Soerjono Soekanto.1979. Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat. Jakarta: Akademika, hal 5-6. 12 13 14 I Made Widnyana, 1993, Kapita Selekta Hukum Adat, PT. Ereco, Bandung, hal. 19-27 Ibid. Jimly Asshiddiqi, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Angkasa Bandung., hal. 216-217. 36 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia Dewa Suartha Ad. 3 Dasar Pembenar Filosofis Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang diikuti pula perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, yaitu munculnya perbuatan melawan hukum yang sifatnya ringan namun sangat membahayakan masyarakat, maka pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban korporasi sangat sulit dalam praktek penegakan hukumnya. Adanya keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan (terutama unsur kesengajaan) dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi cenderung akan memberi peluang kepada korporasi untuk memperoleh profit (menguntungkan) dengan tidak mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang bertujuan untuk memelihara kepentingan sosial. Akibatnya kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam. Oleh karena itu diambil jalan tengah, yaitu penyimpangan asas kesalahan diterima, namun dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana tertentu yang mengatur kepentingan umum atau yang sifatnya ringan. Apabila kebijakan seperti itu dijalankan, maka berarti salah satu prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi (asas monodualistik) telah dijalankan. Penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, penyimpangan asas kesalahan itu mempunyai relevansi filosofis. IV. SIMPULAN Dalam mengakhiri tulisan ini, dapat dikemukakan beberapa simpulan berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yaitu : 1. KUHP tidak dapat menjaring korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipidana, karena masih menganut prinsip subyek hukum hanyalah manusia alamiah. Sedangkan peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah mulai sejak 1951 menempatkan korporasi. Sebagai subyek hukum pidana dan masalah pertanggungjawaban pidananya. Namun cara merumuskannya masih bersifat parsial dan tindak konsisten. 2. Dalam perspektif ius constituendum subyek tindak pidana korporasi dan pertanggunjawaban pidananya telah dirumuskan secara tegas dan terperinci dalam naskah rancangan KUHP 1999/2000, Pasal 162, Pasal 44 s/d Pasa 49. Dan Rancangan KUHP 1999/2000 tersebut telah menerima dan merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan konsep pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarions liability), sebagai eksepsional atau menyimpangi asas mensria yang merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana, walaupun masih merupakan perkecualian terhadap tindak pidana tertentu saja, misal : tindak pidana korporasi. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 37 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 DAFTAR PUSTAKA Barda Narawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Barda Narawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti, Bandung. Chaidir Ali.1987. Badan Hukum. Bandung: Alumni. Widnyana I Made, 1993, Kapita Selekta Hukum Adat, PT. Ereco, Bandung. Jimly Asshiddiqi, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Angkasa Bandung. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undil Semarang. Marcus Flacher.1990. A-Level Principle of English Law, 1st Edition. London. HLT Publication. Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Setiojono, H, 2002, Kejahatan Korporasi Analisis Vikti mologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Overasi Press, Malang. Shofif Yusuf, 2002, Pelaku Usaha dan Tindak Prilaku Korporasi, Ghalia Indonesia jakarta. Sue Titus Reid, Criminal Low, 3 Edition, Prentici Hall, New Jersey. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya bakti Badung. Soerjono Soekanto.1979. Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat. Jakarta: Akademika. 38 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia Oleh : I KETUT WESTRA (Bagian Hukum Perdata FH-Unud) Abstract Intrisically,Good Corporate Governance is a comprehensive mechanism which regulates managing a corporate company based on compulsory requirement such as articles of association, law concerning limited liability company and other regulations in related with company activities of doing business. It also has a cardinal role to manage a company that can bring investor trust institutionally. Beside that, GCG is marketable internalization need and financial modernization of investor which provides basic concept for the development of company value in pertinent with business landscape, independent, transparent, profesionalism and social responsibility principle. The implementation of Good Corporate Governance principle in public company in Indonesia has not been efective yet. It can be denoted from several problems comprising a protection of minority shareholders, low performance of audit committee, and cultural as well as historical problem. Key words: implementation, good corporate governance, public company I. PENDAHULUAN Good Corporate Governance (GCG) merupakan bagian dari salah satu prinsip ideal yang harus terangkum dalam setiap penerapan Corporate governance (CG) pada setiap perusahaan. Saat ini Indonesia menjadi perhatian bagi berbagai kalangan, mulai dari pelaku bisnis, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Besarnya perhatian terhadap GCG, menurut pandangan dari berbagai kalangan dikarenakan penerapan GCG yang lemah pada perusahan-perusahaan dinilai turut serta memberikan kontribusi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 hingga saat kini.1 GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, supplier, dan stakeholder lainnya. Istilah corporate governance pertama kali digunakan pada tahun 1970-an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat, dan beberapa tindakan perusahaanperusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat, dan budaya korupsi, kegagalan perusahaan- perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan, dan krisis-krisis ekonomi diberbagai Negara, telah membuat banyak perusahaan memusatkan 1 . Tjager.N. Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komonitas Bisnis Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2003,h 99. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 39 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 perhatiannya pada pentingnya penerapan corporate governance.2 Laporan penelitian yang dilakukan oleh Asia Development Bank menyebutkan bahwa cikal bakal dari konsep GCG muncul dari adanya keinginan untuk memisahkan aspek pemilikan atas perseroan dari pengendalian terhadap perseroan. Hal ini didasari oleh suasana rumit yang sering dihadapi direksi dan jajaran manajemen perseroan, yaitu upaya menjalankan perseroan untuk mencapai kepentingan perseroan sendiri dengan tuntutan untuk memenuhi kepentingan dari para pemegang saham.3 Untuk memahami konsep GCG, tidak dapt dipisahkan dari pemahaman tentang corporate governance (CG). CG mulai diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992. Komite ini dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury yang saat itu menjabat sebagai Direktur Bank England dan Mantan CEO Grup Cadbury. Istilah CG dipergunakan dalam laporan tahunan mereka yang kemudian dikenal dengan istilah Cadbury Report. Cadbury Committee menyebutkan CG merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.4 Corporate Governance (CG) mengatur aspek-aspek yang terkait dengan keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu RUPS, Komisaris, dan Direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal), dan pemenuhan tanggung jawab sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder, yang mencakup hal-hal yag terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholder. Disamping itu latar belakang pelaksanaan Good Corporate Governance juga didorong oleh perkembangan perekonomian modern yang telah mempengaruhi perekonomian nasional sehingga menuntut adanya pemisahan manajemen dan pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemegang saham sebagai pemilik perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada tenaga-tenaga professional, yang bertugas untuk kepentingan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Perkembanngan perekonomian juga mengakibatkan semakin banyaknya perusahaan yang bergantung pada modal ekstern yang berasal dari equity capital, dan pinjaman yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatanya, melakukan investasi, dan mengembangkan usahanya. Untuk kepentingan tersebut, perusahaan perlu memberikan kepastian kepada pemegang saham dan penyandang dana ekstern, bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan efisien, serta manajemen pengelola yang ditunjuk oleh perusahaan bertindak yang terbaik untuk kepentingan prusahaan. Kepastian yang dimaksud hanya dapat diberikan apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam GCG, karena dengan tercapainya GCG perusahaan akan dapat menciptakan lingkungan kondusif terhadap pertumbuhan usahanya yang efisien dan berkesinambungan.5 Beberapa tindakan penyalahgunaan corporate governance yang dilakukan oleh para organ perusahaan tidak hanya dapat menyesatkan pemegang saham mengenai prospek dan kinerja perusahaan, tetapi juga pihak lain yang terkait seperti stakeholder, karyawan, kreditor dan 2 3 4 5 Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, PT Indek Kelompok Penerbit GRAMEDIA, Jakarta, 2004, h 2.. Tjager.N. Op Cit, h 97. A Sofyan Djalil, Good Corporate Governance, Komite Nasional Corporate Governance , 200, h 3 .Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Rafika Aditama, Bandung, 2006, h 71. 40 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia I Ketut Westra masyarakat. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada menurunnya harga saham perusahaan, para pekerja kehilangan pekerjaan, dan yang lebih ekstrim adalah perusahaan tersebut menjadi pailit.6 Penerapan GCG di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan. Dengan menerapkan GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan juga para stakeholder yang lain. GCG merupakan suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stake holder. Sejak Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi, maka GCG menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan korporasi. GCG pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masingmasing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. GCG juga mengatur hubungan antara unsur-unsur perseroan secara intern, dan juga unsur-unsur perseroan dengan unsur-unsur diluar perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak, masyarakat luas yang meliputi para investor public, dan stake holder.7 Good Corporate Governance (GCG) awalnya memang didorong tuntunan eksternal agar setiap perusahaan tidak melakukan pembohongan kepada publik. Tekanan ini semakin memuncak sejak terkuaknya kasus skandal akuntasi di Enron dan beberapa perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1990-an, yang merupakan praktik manipulasi data keuangan yang banyak dilakukan perusahaan. Hal ini jelas merugikan publik dan dianggap sebagai tindakan illegal, sehingga lahirlah aturan hukum yang dikenal Sarbanes Oxley Act (SOX). Undang-undang ini didesain untuk mencegah adanya praktik illegal sejenis yangn dilakukan di internal perusahaan yang dapat merugikan publik dan investor.8 Mengingat pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporte Governance pada pengelolaan perusahaan, dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian modern yang bersifat global, serta untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG dan paraktikpraktik illegal dalam perusahaan, maka dapat dikemukakan beberapa isu-isu hukum antra lain: 1. Apakah prinsip-prinsip GCG sudah terimplementasi dalam pengelolaan perusahaan publik di Indonesia ? 2. Mengapa prinsip-prinsip GCG begitu penting dalam pengelolaan suatu perusahaan Publik ? II. PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Secara teoritis konsep GCG bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi, tetapi di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi sejak pasca krisis tahun 1998. Awalnya konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery pasca krisis. GCG merupakan suatu konsep tentang suatu tata kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stakeholder) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali 6 7 8 Daniel .J.H.Greenwood, Enronities WhyGood Corporate Go Bed, Columbia Business Law review, 2004, h 774., Sutan Remy Sjahdeini, Peranan Fungsi Kepengawasan bagi pelaksana Good Corporate Governance, “ pada perusahaan Repormasi Hukum di Indonesia sebuah Keniscayaan , R M Talib Puspokusum, ed , Tim Pakar Hukum Departemen kehakimandan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000, h 2. Ridwan Khairandy, Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembagan Pemikiran dan Implementasinya di Indeonesia dalam Persefektif Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h 116. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 41 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 investasinya.9 Amin Wijaya Tunggal : Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya.10 Hesel .Nogi.S Tangkilisan : Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha dalam menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stake holder, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.11 Forum For Corporate Governance Indonesia (FCGI): Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Organization For Economic Co Operation and Development (OECD) : Corporate Governance sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. The 1992 Report of The Committee of the Financial Aspect of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance sebagai “the system by which companies are directed and controlled” dari difinisi tersebut dapat dikatakan bahwa corporate governance bermakna sebagai suatu sitem di mana perusahaan itu diarahkan dan dikendalikan. The OECD Corporate Governance Principles of 1999 mendefinisikan corporate governance dengan “ Corporate Governance involves a set of relationshipbetween a company s management, its board, its shareholder and other stakeholder, Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined” Menurut Vanderloo mendifinisikan corporate governance adalah: Corporate governance refer to those procedures established within a company s organization that allow director oversight of key officer decisions, provide disclosure of materialfact to investors and other stakeholders, and allow for efficient and accurate decision making within the organization, Corporate governance describes “ the legal rules relating to the perspective powers and duties of director, officer, and shareholder”. 12 Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No KEP-23/M-PM.BUMN/2000 tgl 31 Mei 2000, Pasal 2 menyatakan GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan 9 10 11 12 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h 60. Amin Wijaya Tunggal, Komite Audit ( Audit Committee , Jakarta, Harvarindo, 2003, h 9. Hessel Nogi Tangkilan, Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance , Yogyakarta, Balairung, 2003,h 12. Nicolai Lazerev, “ an Certain Issues of the Modern Corporate Governance Reform in Rusia “ International Company and Commercial Law Review, Volume 17, 2006, h 143. 42 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia I Ketut Westra yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Bank Dunia sebagaimana dikutip Tangkilisan; mendefinisikan GCG sebagai sekumpulan hukum, peraturan, dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham, maupun masyarakat secara keseluruhan.13 Dengan demikian, corporate governance berarti seperangkat aturan yang dijadikan acuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar, dan penuh integritas, serta membina hubungan dengan para stakeholder, guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang menaungi perusahaan tersebut seperti Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), dan aturan – aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. III. PRINSIP-PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka GCG adalah : 1. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ-organ perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and proper test, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. 2. Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yangn baik. 3. Transparansi (Transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses pengembilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan stakeholder dan publik secara benar dan tepat waktu. 4. Pertanggungjawaban (Respossibility), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undanngan yang berlaku,dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. 5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip- prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkret dengan melakukan pemisahaan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan terhadap organ-organ perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, serta menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi secara jelas. 13 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Op Cit, h 43. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 43 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang merupakan forum perkumpulan dari asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi menjabarkan bentuk-bentuk konkret dari prinsip- prinsip GCG sebagai berikut :14 1. 2. 3. 4. 5. Hak-hak para pemeganng saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusankeputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut dalam memperoleh keuntungan perusahaan. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan para pemegang saham, kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dari perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholder). Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen, dan pertanggungjawabankepada perusahaan IV. TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG). Tujuan Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan setidaknya dapat mencapai 4 (empat) situasi ideal yang hendak dicapai yaitu :15 1. Existence of fair business: efficient market, efficient regulation, and efficient contract. 2. Information garding the (fair) price and specification of goods and services being exchange is available to all parties. 3. Each party ia able is willing to comply to the rules and regulation, and term andcondition in contract. 4. Judicial processes axist and are able to implement the rules and to executie punishment to the noncompliant of the contract. Diterjemahkan secara bebas sebagai beriukut : 1. Keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisiensi pasar, efisiensi regulasi, dan efisiensi kontrak. 2. Adanya informasi tentang harga dan spesifikasi dari barang dan jasa yang menjadi objek pertukaran para pihak. 3. Kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan regulasi, syarat-syarat, dan kondisi dalam kontrak, dan 4. Adanya proses peradilan, kepastian hukum ,dan pelaksanaan hukuman bagi pihak yang tidak melaksanakan kontrak. 14 15 Forum for Corporate Governance in Indonesia Of Cit. Hasnati , Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perusahaan Perseroan Terbatas Good Corporate Governance, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis ,Volume 22, Nomor 6, 2003, h 20. 44 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia I Ketut Westra Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG). 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value; 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia; 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden. Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Dalam Perusahaan Publik. Penerapan prinsip-prinsip GCG membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus, lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab serta pengawasannya. GCG memiliki andil besar dalam meningkatkan performa perusahaan secara keseluruhan. Penerapan GCG yang tepat merupakan modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah, investor, calon investor, dan stakeholder, lainnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG harus dicapai dengan standar yang tinggi untuk mendukung tujuan bisnis, baik pertumbuhan usaha, profitabilitas, nilai tambah untuk stakeholder, serta meningkatkan kemampuan agar kelangsungan usaha jangka panjang dapat tercapai. Walaupun kehadiran GCG di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan berusaha yang kondusif dan dapat menghindarkan segala bentuk skandal dalam suatu perusahaan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan budaya korupsi yang sangat tinggi. Dalam kenyataannya GCG hingga saat ini belum dapat diterapkan sepenuhnya. GCG tampaknya masih dirasakan seperti sebuah slogan, harapan, atau cita-cita yang ideal. Di Indonesia sendiri penerapan GCG dapat dikatakan belum begitu baik. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, Mc Kinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia , yang menyimpulkan bahwa praktik GCG di Indonesia masih rendah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA), Pricewaterhouse Coopers, dan McKinsey& Co menemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan GCG di Indonesia al : 1. Praktek-praktek perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri, serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. 2. Dominasi pemegang saham. 3. Tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan. 4. Lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor. Disamping itu, penerapan GCG di Indonesia sangat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor budaya, maupun historis. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen kemasyarakatan. Faktorfaktor tersebut merupakan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor kesulitan lain dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep-konsep manajemen atau pengelolan perusahaan yang baik. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 45 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia khususnya pada perusahaan publik belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat Internasional Pentingnya Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Pada Suatu Perusahaan. Agenda Indonesia untuk menerapkan GCG dibagi menjadi tiga aktivitas, yakni menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta. Dewasa ini seberapa jauh suatu perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG menjadi demikian penting. Artinya makin dekat suatu entititas bisnis atau perusahaan menjalankan prinsip GCG, maka akan semakin dekat yang bersangkutan dengan akses dana. Penerapan GCG kini semakin penting sebagai faktor bagi keputusan investasi. Kecendrungan tersebut kian terlihat saat ini, perusahaan yang menjalankan prinsip Corporate Governance sudah menjadi karakter investasi Internasional. Karakter tersebut ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana diseluruh dunia. Intinya penerapan GCG menjadi demikian penting bagi perusahaan yang ingin memperoleh manfaat dari Pasar Modal global dalam menarik dana jangka panjang. Pelaksanaan GCG dianggap sebagai terapi yang paling baik untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal beserta kreditornya, sehingga pemasukan modal dapat direalisasikan, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Secara formal penerapan GCG sebenarnya hanya ditujukan bagi perusahan yan statusnya merupakan perusahaan publik. Secara sederhana bentuk GCG dalam perusahaan publik dapat dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum dengan direksi dan komisaris sebagai pengurus kepada para pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan kewajiban untuk mengelola perusahaan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh akuntabilitas. Untuk lebih mengefektifkan penerapan GCG pada perusahaan maka, Komisi Nasional GCG kemudian merumuskan Pedoman Good Corporate Governance (Code For Good Corporate Governance) yang memuat hal-hal : perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholder, keterbukaandan trasparansi, serta peranan direksi perusahaan. Disamping itu juga dimuat tentang terciptanya hubungan yang fair, seimbang, transparan, diantara para organ yang terdapat dalam PT.16 Penerapan GCG berperanan penting dalam perusahaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :17 1. Pihak investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki GCG. Bahkan investor tersebut menempatkan prinsip GCG sebagai salah satu kriteria utama disamping kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan. 2. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di Negara-negara Asia akhir abad 20 disebabkan lemahnya penerapan prinsip GCG dalam perusahaan di negara-negara tersebut. Hal itu terlihat dari tindakan-tindakan manajemen keluarga, berkolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi pemerintah, budaya suap, dan korupsi. 16 17 Ridwan Khairandy, Camelia Malik, Op Cit, h 123. .Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82. 46 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia I Ketut Westra 3. 4. Penerapan prinsip GCG sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar termasuk juga modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para investor bersedia menanamkan modalnya. Prinsip GCG telah memberi dasar bagi berkembangnya value perusahaan yang sesuai dengan landscape bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat mengedepankan nilainilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Simpulan 1. 2. 3. 4. Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang menaungi perusahaan tersebut. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu : pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, kedua adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan publik dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan investor, terutama pemegang saham, mendorong tumbuhnya mekanisme check and balance dalam lingkungan kinerja perusahaan. Penerapan Prinsip-prinsip GCG pada perusahaan publik di Indonesia dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat diterapkan, hal mana dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang muncul seperti perlindungan pemegang saham minoritas yang belum maksimal, kinerja komite audit yang belum efektif, adanya faktor-faktor budaya dan historis yang juga merupakan kendala penerapan prinsip-prinsip GCG. Good Corporate Governance berperanan sangat penting dalam pengelolaan suatu perusahaan, karena GCG dapat memberikan kepercayaan investor institusional, GCG merupakan kebutuhan dalam Internasionalisasi pasar dan modernisasi pasar finansial terhadap investor, GCG memberi dasar bagi berkembangnya value perusahaan yang sesuai landscape bisnis, nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial perusahaan. DAFTAR PUSTAKA Amin Wijaya Tunggal.2003. Komite Audit (Audit Committee).Jakarta: Harvarindo. A Sofyan Djalil.2000. Good Corporate Governance. Jakarta: Komite Nasional Corporate Governance. Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini.2004. Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, Jakarta: PT Indek Kelompok Penerbit GRAMEDIA. Daniel .J.H. dan Greenwood, Enronities.2004. WhyGood Corporate Go Bed, Columbia Business Law Review. Hessel Nogi Tangkilan.2003. Mengelola Kredit berbasis Good Corporate Governance . Yogyakarta: Balairung. Johannes Ibrahim.2006. Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum. Bandung: Rafika Aditama. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 47 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Munir Fuady.2006. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung:Citra Aditya Bakti. Nindyo Pramono.2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ridwan Khairandy, Camelia Malik.2007. Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. Sutan Remy Sjahdeini. Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perusahaan dalam R M Talib Puspokusum, ed.2000. Reformasi Hukum di Indonesia sebuah Keniscayaan. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen kehakiman dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tjager.N. 2003. Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komonitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo. Hasnati.2003. Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perusahaan Perseroan Terbatas Good Corporate Governance. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6. Nicolai Lazerev. An Certain Issues of the Modern Corporate Governance Reform in Rusia. International Company and Commercial Law Review. Volume 17, 2006. 48 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awigawig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Oleh : Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Bagian Hukum dan Masyarakat Abstract Kasepekang (expelation) is customary sanction which is exist in customary village in Bali. It can be sentenced to people who are pressumed violating a customary law. This research has revealed that Kasepekang is not always exist in customary law of customary village in written form. Nontheless, due to customary law character, it can be executed promptly based on consensus of member in customary village. Key words: Existency,Customary Sanction, Customary law, Customary Village I. PENDAHULUAN Sanksi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sanksi merupakan salah satu ciri dari hukum. Tanpa adanya sanksi maka hukum tidak akan memiliki wibawa untuk ditaati oleh masyarakat. Secara umum istilah sanksi sering disamakan dengan istilah hukuman atau tindakan. Dalam kamus bahasa Indonesia sanksi diartikan sebagai tindakan-tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau apa-apa yang sudah ditentukan1. Sanksi pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seorang warga atau warga mentaati norma-norma yang berlaku. Adapun tugas sanksi adalah : 1. merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan. 2. agar norma hukum ditaati. 3. merupakan akibat hukum bagi seseorang melanggar norma hukum2. Menurut Soeroso bahwa sanksi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan apakah hukum yang ada dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah-kaidah hukum lainnya3, sedangkan Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa sanksi merupakan kreteria yang hakiki dari keputusan hukum, namun harus disadari bahwa sanksi itu dapat saja berbentuk non fisik. Misalnya sanksi-sanksi yang bersifat biologis seperti pengucilan,cemohan-celaan, tidak ditegur sapa atau tidak diberi bantuan 1 2 3 Ahmad A.K. Muda, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher , hal 474. SR Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, hal 30. R Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal 189. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 49 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 yang merupakan sanksi-sanksi yang halus sifatnya dan sangat informal, tetapi bisa lebih efektif dari hukuman tubuh4. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang dikenal dengan desa pakraman diikat dengan aturan-aturan adat dan hukum adat yang hidup , tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Aturan- aturan itu disebut awig-awig. Awig-awig merupakan pedoman dalam berprilaku dan bertingkah laku yang mengandung sifat mengatur dan memaksa demi terciptanya keserasian dan kentraman dalam masyarakat adat setempat. Setiap pelanggaran aturan adat (awig-awig) akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran aturan adat harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Apabila keseimbangan itu terganggu, hukum adat mengenal upaya-upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang berupa reaksi adat (adatreactie) atau masyarakat umum mengenalnya dengan istilah sanksi adat. Pandecten van het Adatrecht, bagian X yang terbit tahun 1936, seperti dikutip oleh R Soepomo, memuat jenis-jenis reaksi adat diberbagai masyarakat hukum adat di Indonesia, yaitu: 1. pengganti kerugian “immaterieel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan; 2. bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani; 3. selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib; 4. penutup malu, permintaan maaf; 5. pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati; 6. pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum5. Berbagai jenis sanksi juga dikemukakan oleh Pospisil dan Paul Bohannan untuk masyarakat Kapauku di Irian Jaya sebagaimana dikutip oleh Wirtha Griadhi yang mengelompokkan jenisjenis sanksi sebagai berikut : 1. Corporal sanctions (hukuman badan) 2. Economic sanctions (denda/pembayaran) 3. Psycological sanctions (teguran/peringatan) 4. Supernatural sanctions (sanksi dari alam gaib) 5. Self Redress (sanksi langsung dari korban)6. Jenis-jenis sanksi yang dikemukakan diatas adalah berkaitan dengan jenis pelanggaran adat yang dilakukan. Pada prinsipnya pelanggaran adat yang dilakukan akan mengakibatkan keseimbangan alam (sekala dan niskala) terganggu. Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat dapat dipandang sebagai perbuatan yang menggangu ketertiban masyarakat. B. Ter Haar pernah menulis dalam kepustaan hukum adat sebagai berikut: di masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imatereel orang seorang, atau dari pada orang-orang 4 5 6 H. Hilman Hadikusuma, 2004, Pengantar Antropologi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 115. R.Soepomo, 1977, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta,hal 94. I Ketut Wirta Griadhi, 2008, ”Kasepekang Dalam Perspektif Hukum Adat”, Makalah disajikan dalam semiloka Kasepekang Dalam Perspektif Hukum dan Ham, diselenggarakan oleh Bali Shanti ( Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali), Denpasar, hal 4. 50 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan); tindakan itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat – ialah reaksi adat (adatreactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang)7. Menurut R. Soepomo, dalam sistem hukum adat dirumuskan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum, jika hukum itu diperkosa8. Rumusan-rumusan di atas mengandung arti bahwa suatu perbuatan atau pelanggaran yang merupakan delik adat apabila ada unsur terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Bali keseimbangan itu senantiasa dipelihara yang merupakan unsur-unsur dari tri hita karana, yaitu: kesimbangan hubungan manusia dengan sesamanya (pawongan), keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (palemahan), dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta (parhyangan. Demikianlah pola hubungan yang dikehendaki mengenai hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan menurut alam pikiran masyarakat Bali. Semua itu ditujukan agar dapat dicapainya kehidupan yang harmonis antara kesejahteraan lahir dan bathin (sukerta sekala niskala). Apabila ditelusuri kepustakaan hukum adat di tanah air, alam pikiran demikian ternyata tidak hanya berlaku lokal dalam masyarakat Bali, melainkan merupakan alam pikiran universal yang dianut dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Soepomo menyatakan bahwa alam pikiran orang Indonesia adalah bersifat kosmos, artinya selalu mencari keseimbangan dengan alam. Dalam alam pikiran masyarakat Indonesia, eksistensi alam kosmos selalu dibedakan menjadi alam nyata dengan alam tidak nyata (alam gaib). Kedua alam ini tidak bisa dipisahkan melainkan merupakan suatu totalitas. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat9. Oleh karena pelanggaran adat (delik adat) dapat menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan nyata maupun tidak nyata, maka dalam hukum adat Bali dikenal penggolongan sanksi adat yang menyangkut perbaikan kehidupan alam nyata dan tidak nyata (sekala niskala) pula. Dalam hukum adat Bali, sanksi adat dikenal dengan istilah danda atau pamidanda. Ada tiga golongan pamidanda yang dikenal dengan sebutan tri danda, yang terdiri dari: 1. artha danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang); contoh dosa atau dedosan yaitu hukuman denda berupa pembayaran sejumlah uang 2. jiwa danda, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis); seperti kasepekang, kanohrayang dan lain sebagainya. 3. sangaskara danda, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama) seperti maprayascita , nyarunin desa yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan leteh atau kekotoran gaib10. 7 8 9 10 B Ter Haar, 2001, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K.Ng.Soebakti Poeponoto), Cetakan Ketigabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 226. R Soepomo, Op. cit, hal 110. I Made Widnyana, 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Eresco Bandung, hal 19. I Made Swastawa Darmayuda, 2001, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Propinsi Bali, Upada sastra, hal 145. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 51 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Pada prinsipnya, pamidanda atau danda yang dijatuhkan sebagai tindakan hukum bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggar hukum, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan dunia nyata (sekala) maupun dunia tidak nyata (niskala) sesuai dengan filosofi tri hita karana. II. KONSEP KASEPEKANG Kasepekang merupakan salah satu bentuk dari sanksi adat (pamidanda) yang dikenal di Bali. Sebagai sanksi adat, kasepekang merupakan sanksi yang sangat ditakuti dan tergolong sanksi adat yang berat, namun demikian akhir-akhir ini sanksi adat kasepekang banyak mendapat perhatian dari kalangan masyarakat. Antusias perhatian masyarakat terhadap sanksi kasepekang ini dikarenakan banyaknya kasus-kasus adat yang terjadi dan berujung pada penjatuhan sanksi adat kasepekang. Kasepekang dalam terminologinya dapat diartikan sebagai pengucilan. Istilah lain dari kasepekang adalah kemenengan, tan polih arah-arahan, kagedongin, kapuikin dsea, kapuikin gumi dan tan polih suaran kulkul. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan untuk penyebutan sanksi adat ini, namun dalam kehidupan masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah kasepekang. Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa istilah kasepekang sudah merupakan istilah yang umum digunakan baik oleh media cetak maupun media elektronik dan bahkan awig-awig desa pakraman juga mencantumkan istilah kasepekang sebagai salah satu bentuk pamidanda. Menurut Kersten sebagaimana dikutip oleh P Windia11 menyatakan kasepekang berasal dari kata sepek yang mengandung arti mempermasalahkan dihadapan orang. Koti Cantika12 menyatakan bahwa kasepekang ini berasal dari kata Ka sepi ikang yang mengandung arti dikucilkan. Dalam konteks sanksi adat, kasepekang menurut Koti Cantika sejatinya adalah mereka yang dijatuhi sanksi adat kasepekang tidak diladeni dalam aktivitas suka dan duka dengan tidak mendapat pemberitahuan, tidak mendapat suara kentongan dan tidak mendapat pelasksanaan persembahyangan serta tidak mendapat gotongan dalam penguburan, namun demikian mereka tetap berhak melakukan persembahyangan di pura serta melaksanakan penguburan di kuburan (setra) milik desa. Nyoman Serikat Putra Jaya13 sebagaimana dikutip dari hasil penelitian Tjokorda Istri Putra Astiti menyatakan bahwa sanksi kasepekang adalah tidak diajak bicara oleh krama banjar/desa karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik / melanggar peraturanperaturan di desa/ banjar. Sanksi adat kasepekang ini merupakan sanksi adat yang sangat berat bukan hanya sekedar tidak diajak bicara oleh krama desa melainkan akan berbuntut panjang , seperti sampai tidak dilayani segala urusan yang berhubungan dengan desa pakraman bahkan sampai tidak bisa menggunakan kuburan atau setra. I Made Suasthawa Dharmayuda14 berpendapat bahwa sanksi adat kasepekang adalah sanksi yang dikenakan kepada krama desa pakraman yang pada intinya tidak mendapat pemberitahuan (tan polih arah-arahan), tidak mendapat layanan kentongan (tan polih suaran kukul), dan tidak 11 12 13 14 I Wayan P Windia, 2008, “Konflik Adat dan Sanksi Kasepekang Di Desa Adat Bungaya Kabupaten Karangasem Bali : Perspektif Kajian Budaya”, Disertasi Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Udayana, hal 31. I Wayan Koti Cantika, 2007, “Tata Cara Penerapan Pamidanda” Dalam I Ketut Sudantra dan Anak agung Oka Parwata, Editor Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Upada sastra Denpasar Bekerjasama Dengan Bagian Hukum dan MAsyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 94. Serikat Putra Jaya, Nyoman 2005, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Citra Aditya bakti Bandung, hal 186. I Made Swastawa Dharmayuda, Op.cit, hal 145. 52 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi mendapat bantuan banjar (tan polih penyanggran banjar). Dari rumusan diatas maka pada prinsipnya kasepekang itu adalah salah satu bentuk sanksi adat yang berupa pengucilan yang dikenakan kepada warga desa (krama desa pakraman) dimana telah melanggar ketentuan-ketentuan adat dan terhadap pelanggar tersebut dikenakan sanksi kasepekang yang pada intinya tidak mendapat pemberitahuan (tan polih arah-arahan), tidak mendapat layanan kentongan (tan polih suaran kukul), dan tidak mendapat bantuan banjar (tan polih penyanggran banjar) dan mereka masih tetap berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh desa pakraman seperti kuburan (setra) dan pura sebagai tempat persembahnyangan. Namun penerapan sanksi adat kasepekang sekarang ini tidak lagi berjalan pada prinsip semula melainkan sudah mengarah kepada perbuatan anarkis atau perbuatan kesewenang-wenangan desa pakraman kepada krama (warga) desa pakraman seperti tidak dijinkan untuk menggunakan setra, pura bahkan tidak dilayani secara administrasi (kedinasan). III. EKSISTENSI YURIDIS SANKSI ADAT KASEPEKANG Untuk melihat dasar hukum dari sanksi adat kasepekang maka sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu pengaturannya dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan suatu aturan hukum yang levelnya paling tinggi dalam hukum nasional15 . Terkait dengan eksistensi secara yuridis sanksi adat kasepekang maka terlebih dahulu akan dikaji dari konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NKRI Tahun 1945). Istilah sanksi adat kasepekang secara teknik yuridis belum ada pengaturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian istilah sanksi adat kasepekang sering digunakan dalam sistim hukum adat khususnya sistem hukum adat di Bali yaitu diatur dalam awig-awig desa pakraman. Desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan secara tegas dalam UUD NKRI tahun 1945 khususnya Pasal 18 B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Rumusan Pasal tersebut di atas menunjukan adanya perhatian dan pengakuan yang kuat terhadap hukum adat yang didalamnya termasuk sanksi adat kasepekang sebagai hukum yang tidak tertulis yang hidup dan masih berlaku dalam masyarakat hukum adat disamping hukum tertulis, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam Undang-undang. Dari uaraian diatas dapat digarisbawahi bahwa eksistensi sanksi adat kasepekang mempunyai landasan yuridis yang kuat karena telah mendapat pengakuan berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI tahun 1945. Pengaturan tentang eksistensi sanksi adat kasepekang dalam peraturan perundang-undangan nasional tidak diatur secara eksplisit, tetapi secara implisit eksistensi secara yuridis hukum adat dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundnag-undangan nasional diantaranya: UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diwajibkan menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pernyataan 15 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamh Konstitusi RI, Jakarta, hal 110. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 53 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 ini menegaskan bahwa dalam hal hakim memutus suatu perkara hendaknya seorang hakim memperhatikan dan wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (living law). Mochtar Kusumaatmadja 16 sebagaimana dikutip Otje Salman Soemadiningrat melihat bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif yaitu keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga merupakan gejala sosial yang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam bahwa landasan yuridis yang dapat dijadikan dasar bagi eksistensi hukum adat adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakantindakan Sementara Untuk Penyelenggara Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan, khususnya Pasal 5 ayat 3b yang menyatakan sebagai berikut: Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana materiil sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: bahwa untuk suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sipil, maka dengan dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum; bahwa, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran Hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. Dari rumusan Pasal 5 ayat 3b Undang-undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 dapat disarikan sebagai berikut : 1. perbuatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai perbuatan atau delik adat tetapi tidak diatur dalam peraturan prundang-undangan adalah tetap diakui keberadaanya sebagai perbuatan pidana meskipun tidak dirumuskan dalam Undnag-undang (hukum tertulis). 2. delik adat yang telah dijatuhi sanksi adat oleh masyarakat hukum adat dan tidak ditaati oleh yang terkena sanksi adat maka dapat diancam dengan pidanatidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda Rp. 500,- sebagai hukuman pengganti. 3. sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku yang menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan dan dendadiatas, karena kesalahannya kepada pelaku dapat dikenakan 16 Otje Salman Soemadiningrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer, Alumni Bandung, hal 22. 54 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi 4. hukuan pengganti sepuluh tahun penjara. hukum adat yang tidak selaras dengan perkembangan jaman hendaknya diganti. Rumusan Pasal 5 ayaut 3 (b) Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 secara eksplisit tidak mengatur mengenai eksistensi sanksi adat khusunya sanksi adat kasepekang. Namun dalam rumusan yang berbunyi ”...hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum....”. Dari ketentuan itu dapat ditafsirkan bahwa Undnag-undang mengakui keberadaan sanksi adat dan penjatuhan sanksi adat oleh prajuru adat sepanjang ditaati oleh masyarakat dan pelaku, danapabila tidak ditaati dapat diganti dengan sanksi pidana. Eksistensi sanksi adat kasepekang juga mendapat pengakuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003. Walaupun secara eksplisit istilah ”sanksi adat kasepekang” tidak disebutkan di dalam Peraturan Daerah tersebut, namun dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa prajuru desa pakraman bertugas melaksanakan awig-awig desa pakraman dan mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa. Rumusan Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut dapat ditafsirkan bahwa desa pakraman dalam hal ini prajuru desa pakraman bertugas melaksanakan awig-awig termasuk penerapan sanksi adat yang telah diatur dalam awig-awig. Prajuru desa pakraman juga diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa. Pernyataan ini menunjukan adanya kewenangan dari prajuru desa pakraman dalam penerapan sanksi adat. Pengakuan terhadap sanksi adat ini penting sebab dengan ini eksistensi sanksi adat khususnya sanksi adat kasepakang mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam hukum tertulis. Dalam awig-awig Desa Pakraman, eksistensi sanksi adat kasepekang mendapat pengakuan yang sangat jelas. Sebagai contoh awig-awig Desa Pakraman Kerobokan, Baturiti, Tabanan dalam Pawos 67 tentang Pamidanda menentukan sebagai berikut : Bacakan pamidanda luire : a. Panukun kasisipin b. Danda arta c. Rerampagan d. Kasepekang e. Penyangaskara f. Kasuwudang mebanjar/madesa adat Selain itu awig-awig desa pakraman Padonan Kuta Utara Badung juga menggunakan istilah kasepekang sebagai salah satu bentuk dari pamidanda, seperti terdapat dalam Pawos 82 kaping (4) yang menyebutkan penggolongan sanksi adat (pamidanda) antara lain : 1. Danda arta miwah panikel-panikelnia 2. Pengampura/Nyewaka 3. Upakara Panyangaskara 4. Kasepekang makrama. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 55 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Eksistensi sanksi adat kasepekang juga terdapat dalam Pedoman/teknis penysunan awigawig Propinsi Bali, khususnya Pawos 61 kaping 3 yang menyebutkan: Bacakan pamidanda luire ; ha. Ayahan panukun kasisipan; na. Danda arta (dosa, danda saha panikel-nikelnya miwah panikel-nikel urunan); ca. Rarampagan; ra. Kesepekang; ka. Kewusang mekrama kewaliang pipilnyane; da. Penyangaskara17. IV. PENGATURAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DALAM AWIG-AWIG Dalam awig-awig desa pakraman khususnya bab wicara lan pamidanda (masalah dan sanksi) umumnya diatur mengenai sanksi adat. Penjatuhan sanksi adat kepada krama dimaksudkan apabila krama melakukan pelangaran adat, seperti yang dinyatakan Hilman Hadikusuma18 yaitu apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan maka akan dikenakan suatu sanksi adat. Sanksi adat dalam terminologi adat Bali disebut pamidanda (danda). Sanksi adat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Sangaskara danda, artha danda dan jiwa danda. Sanksi adat pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan apabila terjadi gangguan keseimbangan yang berkaitan dengan parhyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), pawongan (hubungan manusia dengan manusia lainnya) dan palemahan (hubungan manusia dengan alam lingkungannya). Namun dilihat dari pengaturan sanksi adat (pamidanda) dalam awig-awig , ketiga istilah pamidanda tersebut tidak dimuat dan diatur dalam awig-awig. Pengaturan sanksi adat (pamidanda) dalam awig-awig desa pakraman sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya akan dibuat dalam tabel mengenai pengaturan sanksi adat (pamidanda) dalam awigawig desa pakraman. Awig-awig yang akan diteliti adalah beberapa awig-awig desa pakraman yang ada di Kabupaten Gianyar. 17 18 Biro Hukum Setda Propinsi Bali, 2001, Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-Awig Dan Keputusan Desa Adat, Denpasar, hal 44. Hilman Hadikusuma, Op.cit. hal.20, lihat juga R. Soepomo , Op.cit., hal 112. 56 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Tabel 1.7 Pamidanda dalam awig-awig desa pakraman Awig-awig desa pakraman Pengaturan Pamidanda/Sanksi adat Awig-awig desa pakraman Pawos 83 menyatakan : Jero Kuta Batubulan (1) Desa utawi banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa utawi banjar sane sisip (2) Paniwak inucap kemargiang olih Bendesa utawi Klian banjar (3) Bacakan pamidanda luire : Ha. Ayahan panukun sisip Na. Danda arta (desa, danda panikel-nikelnya miwah panikel-nikel urunan) Ca. Rerampagan Ra. Kenorayang Ka. Kawusang mekrama kewaliang pipilnyaane Da. Penyangaskara. (4) Pamidanda katiwakang patut masor singgih manut ring kesisipane utamanya ngemanggehang kasudamalan desa. (5) Jinah utawi raja brana pamidanda, ngeranjing dados druwe desa utawi banjar. Awig-awig desa pakraman Pawos 75 menyatakan : Jasan Tegalalang (1) Desa/Banjar wenag niwakang pamidanda ring warga Desa sane sisip. (2) Tetiwak inucap kelaksanayang olih bendesa utawi klian banjar (3) Bacakan pamidanda luire : 1. Ayahan panukun sisip 2. Danda arta (dosa, kagenda miwah panikel) 3. Rerampasan 4. Kedaut karang ayahan 5. Penyangaskara (4) Pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane. (5) Jinah utawi arta brana pamidanda punika, ngeranjing dados druwen desa. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 57 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Awig-awig desa pakraman Pawos 68 menyatakan : Payangan Desa, Payangan (1) Desa/Banjar wenang niwakang pamidanda ring warga Desa sane sisip (2) Paniwak inucap kelaksanayang olih Bendesa/Klian Banjar. (3) Bacakan Pamidanda luwire: a. Ayahan panukun sisip b. Data Arta (dosan sahapanikel-nikelnya miwah panikel urunan) c. Kadaut karang ayahan d. Kanohrayang e. Panyangaskara (4) Pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane. (5) Jinah utawi raja brana pamidanda ngranjing dados drewen desa/banjar. Awig-awig desa pakraman Pawos 76 menyatakan : Ubud (1) Prajuru desa/banjar lan Bendesa wenang niwakin pamidanda ring krama desa pakraman sane sisip (2) Agung alit pamidanda manut kasisipanya, tan maren ngupasi dharma kawelas asihan kariinin antuk pamarisuda (3) Bacakan pamidanda luwire : Ha. Atma danda (nunas pangampura ring paruman). Na. Sangaskara danda (melarapang antuk ngemargiang pemarascita). Ca. Artha danda (nawur antuk brana) Ra. Panukun ayah (nawur kaisisipan antuk ayah) (4) Jinah utawi artha brana pamidanda, ngeranjing dados druwe desa/banjar. 58 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Awig-awig desa pakraman Pawos 99 menyatakan : Sayan Ubud (1) Desa utawi banjar wenang niwakin pamidanda ring warga desa sane sisip. (2) Yanin sampun janten kasisipang (kapastika iwang) ring klian Banjar, olih sang mawicara kebandingan ke desa, tur antuk Bendesa kapastika iwang, patut keni pamidanda nikel ring pamidanda sane katiwakin ring Kelihan Banjar. (3) Peniwak inucap kelaksanayang olih Bendesa utawi Kelihan banjar nnggal-nunggal utawi sinarengan manut dudonan. (4) Agung alit pamidanda manut sor singgih kesisipan, tan maren ngupadi dharma keolas arsan pinih ajeng make buatan kasudamalan desa. (5) Bacakan pamidandane sakeluwire : 1. Dange arta muah panikel-panikelnye; 2. Nunas pangampura 3. Upakara pangaskara 4. Kenoroyang mekrama (6) Jinah utawi arta brana pamidanda ngranjing dados druwen desa utawi banjar. Awig-awig desa pakraman Pawos 70 menyatakan: Gitgit, Gianyar (1) Desa/banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa/banjar sane sisip. (2) Paniwak inucap kelaksanayang olih Bendesa/Klian Banjar (3) Bacakan Pamidanda luwire : Ha. Ayahan panukun sisip Na. Danda Artha Ca. Kanorayang Ra. Panyangaskara (4) Pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane (5) Jinah utawi raja brana pamidanda dados druwen Desa/banjar. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 59 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Awig-awig desa pakraman Pawos 73 menyatakan: Pakudui Tegalalang (1) Desa/banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa/banjar sane sisip. (2) Paniwak inucap kelaksanayang oleh Bendesa/Klian Banjar. (3) Bacakan Pamidanda luire: Ha. Ayahan panukun sisip Na. Danda artha Ca. Kanorayang Ra.Panyangaskara (4) Pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipanne (5) Jinah utawi raja brana pamidanda ngaranjing dados druwen desa /banjar Awig-awig desa pakraman Pawos 67 menyatakan : Samplangan Gianyar (1) Desa utawi banjare wenang niwakang pamidanda ring wong desane sane sisip. (2) Tetiwak inucap kelaksanayang olib bendesa adat utawi Kelian Banjar. (3) Bacakan Pamidanda luire : a. Ayahan panukun kasisipan b. Danda arta c. Panikel-panikel urunan utawi panikel dedandan. d. Upakara panyangaskara e. Kanorayang makrama Beberapa model awig-awig desa pakraman yang telah diteliti menunjukan bahwa pengaturan mengenai sanksi adat (pamidanda) tampaknya sudah mengacu pada pedoman penyuratan awigawig yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Bali. Secara tegas pengaturan sanksi adat (pamidanda) terdapat dalam Pawos 61 Pedoman penyusunan awig-awig, yang menyatakan ; (1) Desa utawi banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa utawi banjar sane sisip. (2) Paniwak inucap kemargiang olih Bendesa utawi Klian Banjar. (3) Bacakan pamidanda luire : Ha. Ayahan panukun sisip; Na. Danda arta ( dosa, danda saha panikel-panikelnya miwah panikel-nikel urunan); Ca. Rarampagan; Ra. Kasepekang; Ka. Kewusang mekrama kewaliang pipilnyane; Da. Penyangakara; (4) Pamidanda sane katiwakang patut mesor singgih manut ring kesisipane utamanya ngemanggehang kesudamalan desa. (5) Jinah utawi raja brana pamidanda, ngranjing dados druwe desa utawi banjar. 60 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Berkaitan dengan pengaturan sanksi adat kasepekang dalam awig-awig desa pakraman, ternyata dari awig-awig yang diteliti tidak ada mengatur tentang sanksi adat kasepekang. Namun secara implisit dalam awig-awig desa pakraman ubud mengatur mengenai atma danda. Atma danda merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan jiwa danda (denda yang dikenakan secara pisik maupun psikis). Salah satu katagori jiwa danda adalah kasepekang. Mendukung penyataan di atas I Made Widnyana menyatakan bahwa sanksi adat jiwa danda sama dengan atma danda. Namun demikian, atma danda yang ada dalam awig-awig desa pakraman ubud mempunyai makna yang berbeda yaitu meminta maaf pada paruman desa jika membuat suatu kesalahan (nunas pangampura ring paruman). Beberapa model awig-awig diatas dilihat dari substansi hukum (legal substance) bahwa mengenai sanksi adat kasepekang tidak diatur secara eksplisit dalam awig-awig, baik istilah, rumusan atau pengertian kasepekang serta prosedur dalam penjatuhan sanksi adat kasepekang. Prosedur yang dimaksud adalah mekanisme dan proses pentahapan (tahap-tahap) sampai suatu perkara dijatuhkan sanksi adat kasepekang. Ini dapat diartikan bahwa ada kekosongan hukum terhadap pengaturan sanksi adat kasepekang dalam awig-awig desa pakraman . V. ANALISA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADAT KASEPEKANG YANG TIDAK BERDASARKAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN Dalam kepemerintahan Desa Pakraman di Bali, penjatuhan sanksi adat umumnya selalu berdasarkan pada awig-awig desa pakraman yang ada. Awig-awig yang merupakan patokanpatokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman) dengan Tuhan, antar sesama krama Desa Pakraman maupun krama dengan lingkungannya19yang secara yuridis dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman/ banjar pakraman masing-masing. Awig-awig tersebut termasuk substansi hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman adalah aturanaturan, norma-norma yang berada dalam persekutuan masyarakat hukum termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh masyarakat hukum adat setempat termasuk keputusan-keputusan masyarakat hukum adat. Untuk mengetahui bahwa dalam penjatuhan sanksi adat kasepekang berdasarkan awigawig atau tidak, maka dalam forum ilmiah ini akan diungkapkan beberapa hasil penelitian penelitian mengenai penjatuhan sanksi adat kasepekang. Hasil penelitian yang diungkapkan adalah penjatuhan sanksi adat kasepekang di desa pakraman Samplangan dan desa pakraman Pakudui. Hasil penelitian yang di dapat dari dua lokasi di Gianyar yaitu di desa pakraman Samplangan dan desa pakraman Pakudui, bahwa dalam penjatuhan sanksi adat kasepekang, desa pakraman tersebut tidak berdasarkan pada awig-awig yang ada. Terhadap penjatuhan sanksi adat kasepekang banyak kalangan baik masyarakat maupun pemerintah menyatakan bahwa sanksi adat kasepekang pada 19 Astiti, Tjok Istri Putra, 2005, Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hokum Universitas Udayana, hal 19. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 61 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 dasarnya tidak bisa dijatuhkan (diterapkan) karena tidak ada dasar untuk menjatuhkan sanksi adat kasepekang tersebut (awig-awig tidak mengatur mengenai sanksi adat kasepekang). Penjatuhan sanksi adat kasepekang tersebut juga sangat terkait dengan wujud awig-awig yang ada pada masing-masing desa pakraman. Mengenai wujud awig-awig di desa pakraman Samplangan dan Pakudui sudah dalam bentuk tercatat (tertulis). Pada dasarnya Awig-awig dalam bentuk tertulis akan sangat meringankan tugas dari pengurus (prajuru desa pakraman) dalam menerapkan aturan hukum dan bersifat pasti bagi semua kalangan (pasti bagi prajuru desa, pasti bagi masyarakat dan pasti bagi pemerintah). Namun yang unik adalah eksistensi awig-awig desa pakraman Pakudui dimana awig-awig desa pakraman pakudui wujudnya sudah dalam bentuk tercatat namum belum disahkan dan dicatatkan pada kantor Bupati Gianyar. Terhadap hal ini, masyarakat memandang bahwa awig-awig tersebut belum bisa diterapkan dengan alasan belum disahkan oleh pejabat Pemerintah. Mengenai tangapan masyarakat terhadap pencatatan dan pengesahan awig-awig dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang menyatakan : (1) Awig-awig desa pakraman dibuat dan disahkan oleh krama desa pakraman melalui paruman desa pakraman. (2) Awig-awig desa pakraman dicatatkan di kantor bupati/walikota masing-masing. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dijelaskan dua (2) poin penting yaitu sahnya awig-awig dan pendaftaran awig-awig secara administrasi di kantor Bupati/Walikota. Bahwa sahnya awig-awig desa pakraman apabila ada suatu kesepakatan krama desa melalui suatu paruman desa. Sehingga awig-awig yang telah disahkan melalui kesepakatan dalam paruman tersebut baru dapat diberlakukan kepada krama desa pakraman. Mengenai pencatatan awigawig pada kantor Bupati/Walikota berdasarkan pasal 12 ayat (2) diatas, hanya memenuhi unsur administrasi birokrasi pada kantor Bupati/Walikota. Tidak menjadi suatu keharusan untuk mencatatkan awig-awig desa pakraman tersebut mengingat, sekalipun awig-awig desa pakraman tidak dicatatkan secara administrasi di kantor Bupati/Walikota sepanjang sudah disahkan oleh krama desa melalui paruman maka awig-awig desa pakraman bisa berlaku dan mengikat bagi krama desa pakraman. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencatatan awig-awig desa pakraman di kantor Bupati/walikota hanya bersifat administrasi saja. Berdasarkan hasil penelitian awig-awig yang terkait dengan penjatuhan sanksi adat kasepekang, bahwa tidak diaturnya sanksi adat kasepekang dalam awig-awig, tidak berarti sanksi adat kasepekang tidak bisa diterapkan (dijatuhkan) pada krama desa pakraman. Mengingat dalam hukum adat salah satu karakter hukum adat adalah kesepakatan dalam arti pengambilan keputusan dalam hukum adat adalah dengan kesepakatan bersama melalui paruman desa pakraman. Oleh karena itu dapat diartikan, sanksi adat kasepekang dapat dijatuhkan (diterapkan) sepanjang keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama melalu paruman desa pakraman. Analisa yang lain juga sangat mendukung terhadap hal ini diantaranya adalah bahwa hukum adat tidak mengenal asas legalitas, sehingga sanksi adat kasepekang tidak mutlak ada pengaturannya terlebih dahulu dalam awig-awig dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi adat kasepekang di desa pakraman. 62 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Eksistensi Sanksi Adat Kasepekang dalam Awig-Awig dalam Kaitan dengan Penjatuhan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Pakraman Anak Agung Istri Ari Atu Dewi SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian diatas, mengenai pengaturan sanksi adat kasepekang dalam awigawig Desa Pakraman ternyata tidak diatur secara eksplisit. Yang menjadi pokok permasalahan yaitu ketika sanksi adat kasepekang dijatuhkan dan tidak berdasarkan pada awig-awig (sanksi adat kasepekang tidak diatur dalam awig-awig) sehingga banyak kalangan yang berpendapat bahwa sanksi adat kasepekang tidak bisa dijatuhkan, dengan alasan bahwa sanksi adat kasepekang tidak diatur dalam awig-awig desa pakraman. Terhadap hal ini dapat dikemukakan analisa yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi adat kasepekang tersebut. Analisa yang dikemukakan terhadap penjatuhan sanksi adat kasepekang yang tidak ada pengaturannya dalam awig-awig desa pakraman adalah bahwa sesuai dengan salah satu karakter hukum adat yaitu kesepakatan dan tidak mengenal asas legalitas sehingga sanksi adat kasepekang dapat dijatuhkan pada krama desa pakraman walaupun tidak ada pengaturan secara eksplisit dalam awig-awig desa pakraman. Jadi yang dipakai dasar dalam penjatuhan sanksi adat kasepekang adalah kesepakatan bersama krama desa melalui paruman desa pakraman atau pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat krama desa melalui paruman desa pakraman dan bukan pengambilan keputusan dengan suryak siu, karena hukum adat tidak mengenal asas suryak siu. DAFTAR PUSTAKA Astiti, Tjok Istri Putra, 2005, Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hokum Universitas Udayana. Ahmad A.K. Muda, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher . Biro Hukum Setda Propinsi Bali, 2001, Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-Awig Dan Keputusan Desa Adat, Denpasar Hadikusuma, H. Hilman, 2004, Pengantar Antropologi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Isntitut Hindu Dharma, 1986, Keputusan Seminar XII Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu, Proyek Daerah ingkat I Bali. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamh Konstitusi RI, Jakarta Koti Cantika, I Wayan 2007, “Tata Cara Penerapan Pamidanda” Dalam I Ketut Sudantra dan Anak agung Oka Parwata, Editor Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Upada sastra Denpasar Bekerjasama Dengan Bagian Hukum dan MAsyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer, Alumni Bandung. Sianturi SR, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta Soeroso R, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Soepomo R., 1977, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta Serikat Putra Jaya, Nyoman 2005, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Citra Aditya bakti Bandung. Ter Haar B, 2001, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K.Ng.Soebakti Poeponoto), Cetakan Ketigabelas, Pradnya Paramita, Jakarta. Wirta Griadhi, I Ketut, 2008, ”Kasepekang Dalam Perspektif Hukum Adat”, Makalah disajikan JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 63 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 dalam semiloka Kasepekang Dalam Perspektif Hukum dan Ham, diselenggarakan oleh Bali Shanti ( Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali, Denpasar. Widnyana, I Made, 1993, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Eresco Bandung. Windia, I Wayan P, 2008, “Konflik Adat dan Sanksi Kasepekang Di Desa Adat Bungaya Kabupaten Karangasem Bali : Perspektif Kajian Budaya”, Disertasi Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Udayana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Penyelenggara Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman 64 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria Oleh : I GUSTI NYOMAN AGUNG (Bagian Hukum Perdata FH-Unud) Abstract To renew the agrarian affairs as stated in Tap.MPR RI No. IX/2001 (the Decisions made by the People`s Advisory Assembly), some provisions with regard to land reform as included in UUPA and the regulations regulating its implementation should be reviewed. What can be recommended as far as the excessive ownership of land the minimum limit of ownership of land and the absentee ownwership of land (as part of the substance of the land reform program) are concerned is as follows: 1. The maximum limit ownership of land: (a) the indicator used for classifying areas should be reviewed; (b) the decree made by the Agrarian Minister No. 978/Ka/1960 should be adjusted to the current situation and condition of the areas; (c) the provision determining the maximum limit of ownership of land for non agricultural purpose needs to be immediately realized. 2. The minimum limit of ownership of land: (a) the reduction of the minimum limit of ownership of land should accurately and thoroughly taken into account; (b) solution to the fragmentation of agricultural land (due to inheritance) should be sought after and should be regulated in the form of rules and regulations (Peraturan Perundang-undangan abbreviated as PP). 3. The provisions regulating the absentee ownership of land is still relevant; however, some should be made more perfect. Those which should be made more perfect are: (a) the criterion of “kecamatam” (the creterion that head of a district can determine the absentee ownership of land) needs to be reviewed; (b) it would be advisable that the exception for the maximum limit of absentee ownership of agricultural land refers to the minimum limit of ownership of land. Key word: action of making UUPA more perfect, renewal of agrarian affairs, land reform, maximum limit, minimum limit, absentee. I. PENDAHULUAN JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 65 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah berusia setengah abad, melewati masa orde lama, orde baru dan saat ini berada dalam era reformasi. Jauh sebelumnya wacana tentang penyempurnaan UUPA/pembaruan agraria telah digulirkan. Tuntutan-tuntutan pembaruan ini semakin hari semakin kuat dan pada akhirnya mencapai puncaknya pada tgl. 9 Nopember 2001 yang ditandai dengan terbitnya Tap.MPR No. IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia1. Dalam pada itu arah dan kebijakan pembaruan agraria ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Tap.MPR.RI No. IX/MPR/2001 yang dalam butir tiga-nya menetapkan: “melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat”. Pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut pembaruan agraria ini ditugaskan kepada DPR bersama Presiden, termasuk mengubah dan/atau mengganti semua UU dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan MPR tersebut.2 Terbitnya Tap.MPR.RI No.IX/MPR/2001 mendapat sambutan hangat dari pelbagai kalangan dan diyakini akan membawa angin segar bagi penyempurnaan UUPA/pembaruan agraria. Dalam pada itu sikap para cendekiawanpun beragam, paling tidak ada tiga pemikiran yang berkembang antara lain: (1) golongan pertama menginginkan perubahan mendasar dengan membuat UU baru sebagai pengganti UUPA; (2) golongan kedua menginginkan amandemen terhadap pasal-pasal tertentu dari UUPA; dan (3) golongan ketiga berpendapat hanya sebatas penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam hal menanggapi penyempurnaan UUPA/ pembaruan agraria sebagaimana disebutkan di atas maka yang jelas adalah, bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan landreform sebagai salah satu substansi hukum dibidang agraria perlu mendapat pemikiran kembali secara mendalam lebihlebih dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 6 Tap. MPR. RI No. IX/MPR/2001 di atas. Berhubung ruang yang tersedia sangat terbatas, maka materi Peraturan perundang-undangan landreform yang akan dibahas dalam tulisan ini berkisar pada: (1) pemilikan/penguasaan tanah melampaui batas; (2) batas minimum pemilikan tanah; dan (3) pemilikan tanah pertanian secara absente/guntai; II. PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH MELAMPAUI BATAS 1 2 Pasal 2 Tap. MPR.RI No. IX/ MPR/ 2001. Pasal 6 Tap.MPR. RI No. IX/2001. 66 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung Pemilikan dan/atau penguasaan tanah melampaui batas maksimum diatur dalam Pasal 7 dan 17 UUPA. Pasal 7 UUPA menetapkan: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 UUPA menetapkan: (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum. (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat. (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 dan 17 UUPA, ditetapkanlah UU No.56 Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini mengatur tentang: (1) penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian; (2) penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil; dan (3) penebusan tanah pertanian yang digadaikan. Dengan demikian maka UU tersebut khusus mengatur mengenai soal tanah pertanian saja sedangkan untuk tanah non pertanian akan diatur sendiri dengan PP (Pasal 12 UU No.56 Prp/1960). Sampai saat ini PP termaksud belum diterbitkan, yang ada hanya berupa Instruksi Mendagri No. 21/1973 dan No. 27/1973 yang mendeteksi adanya penguasaan tanah yang melampaui batas kebutuhan usaha sesunguhnya dan menegaskan kembali pengawasan sebagaimana diatur oleh Pasal 19 dan 44 PP No.10/1961. Disinyalir oleh Abdurrahman, bahwa pada saat ini telah terjadi meluasnya wabah lapar tanah untuk perumahan oleh karena itulah ketentuan Pasal 12 UU No.56 Prp/1960 perlu segera direalisir. 3 Sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 UU No.56 Prp/1960, Maria S.W. Sumardjono, 2008: 13-14 menyatakan, apabila dicermati ketentuan Pasal 12 UU No.56.Prp/1960 maka ukuran maksimum tanah bangunan didasarkan pada luas dan jumlah tanah. Hal ini berarti bahwa bila sudah ditentukan maksimum untuk daerah tertentu seyogyanya dibedakan antara daerah yang dinilai mempunyai arti strategis bagi pembangunan dan daerah yang kegiatan pembangunannya belum berlaku secara intensif, maka kriterianya dapat dipilih antara: (1) menentukan batas luas tertentu (baik untuk tanah yang sudah ada bangunannya maupun yang belum ada), misalnya 5.000 M2 bagi daerah strategis dan 10.000 M2 bagi daerah lain dengan penentuan bidang tanah sekitar lima atau sepuluh bidang, atau (2) hanya menentukan batas luas tertentu tanpa menentukan bidang tanahnya. Selanjutnya dikatakan bahwa alternatif kedua tampaknya lebih fleksibel mengingat adanya kemungkinan penetapan luas kapling tanah yang diatur oleh 3 Abdurrahman, 1985, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni, Bandung, hal 89-90. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 67 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk berbagai penggunaan. Pada dasarnya Pasal 7 UUPA menegaskan dilarangnya suatu asas groot grondbezit untuk mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan tertentu saja. Pemilikan dan/ atau penguasaan tanah yang melapui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubung dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya di daerah-daerah yang padat penduduknya, hal ini menyebabkan menjadi sempitnya kalau tidak dapat dikatakan hilangnya sama sekali kemungkinan bagi banyak petani untuk memiliki tanah sendiri4. Yang dilarang oleh Pasal 7 UUPA bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi penguasaan tanah. Dalam pengertian penguasaan tidak terbatas pada penguasaan dengan hak milik saja tetapi juga dengan hak-hak lainnya seperti hak gadai, sewa dan sebagainya. Penentuan batas maksimum memakai dasar keluarga, walaupun yang berhak atas tanahnya mungkin orang seorang. Menurut Penjelasan Pasal 17 UUPA yang dimaksud dengan keluarga adalah suami, istri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar tujuh orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga. Selanjutnya ditegaskan melalui Instruksi Bersama Mendagri dan Otonimi Daerah dengan Menteri Agraria dalam suratnya No. 9/1/2 tgl. 5/1/1961 yang pada butir 5a-nya menyatakan: keluarga adalah sekelompok orang-orang yang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan. Namun demikian dalam prakteknya masih terjadi kesulitan sebagaimana diungkap oleh Boedi Harsono, 2007: 374, yang mempermasalahkan: apakah seseorang yang beristri lebih dari satu dianggap berkeluarga satu atau lebih? Dalam peraturan tersebut hal ini tidak diberi penjelasan. Sehubungan dengan itu ia berpendapat, kiranya yang menentukan adalah kenyataan dalam penghidupannya dan bagaimana pendapat umum di daerah ybs. Kalau masing-masing istri serta suami bersama itu pada kenyataannya merupakan kelompok sendiri dalam kehidupannya misalnya tinggal di tempat yang berlainan, mempunyai sumber nafkah sendiri-sendiri -- kiranya masing-masing itu dapat dianggap sebagai satu kesatuan keluarga. Terlepas dari pandangan Boedi Harsono di atas maka penulis memandang perlu adanya aturan yang memberi ketegasan yang lebih rinci terhadap pengertian keluarga termaksud. Dalam pada itu jumlah anggota keluarga ditetapkan tujuh orang termasuk kepala keluarga (yang dapat laki-laki atau wanita). Apabila jumlah satu keluarga lebih dari tujuh orang maka kelebihan anggota keluarga diperhitungkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.56 Prp/1960 yang antara lain menetapkan: (1) Jika jumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang maka keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 1 untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering. (2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 UU No.56 Prp/1960, Maria S.W. Sumardjono, 1990: 4 Efendi Peranginangin, 1979, Hukum Agraria I, Sari Kuliah (2), Jurusan Notariat, FH UI, Jakarta,hal.53. 68 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung 87 menyatakan, untuk masa yang akan datang mungkin dapat dipikirkan tentang penyesuaian jumlah anggota keluarga dalam kaitannya dengan batas maksimal yang ditentukan berdasarkan pertimbangan ekonomis agar dapat menunjang kehidupan yang layak bagi petani beserta keluarganya yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerahnya saat ini serta perkiraannya dimasa yang akan datang. Menurut Penjelasan Umum butir (7) a UU No. 56 Prp/1960 luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II dengan memperhatikan keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut: (1) tersedianya tanah yang masih dapat dibagi; (2) kepadatan penduduk; (3) jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak; (4) besarnya usaha tani yang sebaikbaiknya (the best farm size) menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani; dan (5) tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini. Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor lainnya, maka luas maksimum ditetapkan sebagai berikut: Di daerah-daerah yang 1. Tidak padat 2. Padat a. kurang padat b. cukup padat c. sangat padat Sawah (hektar) atau Tanah kering (hektar) 15 20 10 7,5 5 12 9 6 Beberapa faktor yang dipakai sebagai tolok ukur untuk mengklasifikasikan suatu daerah ke dalam daerah padat dan tidak padat perlu mendapat sorotan, diantaranya: Luas daerah; yang dipakai sebagai perhitungan oleh UU adalah luas keseluruhan tanah yang ada si suatu daerah yang bersangkutan. Apakah perhitungan luas tanah secara keseluruhan ini dapat dianggap memadai? Menurut hemat penulis cara perhitungan ini kurang tepat oleh karena, yang diatur oleh Undang-Undang adalah mengenai tanah pertanian dan oleh karenanya lebih proporsional apabila yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah luas tanah pertanian yang ada di daerah yang bersangkutan. 1. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daerah; apakah tepat kalau yang dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan (tanpa membedakan klasifikasi pekerjaan) dengan luas tanah secara keseluruhan dalam suatu daerah? hal ini juga memerlukan pemikiran. Penulis berpendapat bahwa secara rasional yang kiranya tepat dibandingkan adalah jumlah petani yang ada dalam suatu daerah dengan jumlah luas tanah pertanian sehingga diperoleh perbandingan yang lebih realistis. 2. Selanjutnya pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UU No.56 Prp/1960 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Agraria No. Sk 978/KA/1960 tentang penegasan luas maksimum tanah pertanian. Apakah ketentuan ini masih relevan untuk dipertahankan? Dalam perkembangannya seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar. Peta daerah yang pada mulanya ditetapkan sebagai JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 69 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 daerah yang tidak padat bisa berubah menjadi daerah padat, daerah yang kurang padat bisa berubah menjadi daerah yang cukup padat bahkan bisa dikatagorikan sebagai daerah yang sangat padat lebih-lebih di beberapa daerah telah mengalami pemekaran. Dengan demikian apa yang ditetapkan oleh Menteri Agraria setengah abad yang lalu tidak realistis dimasa sekarang ini dan oleh karenanya mutlak perlu ditinjau kembali, meskipun penetapan yang dilakukan kemudian tidak bisa dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang. III. PENETAPAN BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH Selain batas maksimum, UUPA memandang perlu menetapkan batas minimum pemilikan tanah dengan tujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (4) UUPA. Menurut Penjelasan Pasal 17 UUPA ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecahbelahan (versplintering) tanah lebih lanjut. Disamping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya, transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi supaya batas minimum itu dapat dicapai secara berangsur-angsur. Ketentuan lebih lanjut tentang batas minimum pemilikan tanah diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU No.56 Prp/1960. Pasal 8 UU No. 56 Prp/1960 menetapkan: Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 ha. Pasal 9 UU No. 56 Prp/1960 menetapkan (1) Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau sipenjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus. (2) Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, di dalam waktu satu tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1). (3) Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain. (4) Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit maka pertanyaannya adalah apakah batas minimum ini (baik untuk sawah/ tanah kering) masih bisa dipertahankan? Sehubungan dengan masalah ini Abdurrahman5 5 Abdurahman, op.cit.,h.85. 70 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung menyatakan: ada yang beranggapan bahwa batas tersebut harus diturunkan menjadi satu hektar saja sekalipun sebenarnya dua hektar tersebut sudah sangat minim dan kurang memungkinkan kelayakan hidup bagi seorang petani, tetapi apa yang hendak dikata tanah mana yang harus diberikan kepada mereka yang jumlahnya selalu bertambah sedangkan jumlah tanah relatif tetap tidak bertambah. Terhadap masalah ini penulis berpendapat bahwa diperlukan kajian yang mendalam, penuh hati-hati dan landasan pijakannya tidak terlepas dari tujuan UUPA itu sendiri yaitu kemakmuran rakyat (terutama petani). Sehubungan dengan itu untuk menetapkan batas minimum ini apakah tidak perlu dipikirkan klasifikasi jenis tanah pertanian (sawah atau tanah kering), tingkat kesuburan tanah di masing-masing daerah, jenis tanaman yang bisa ditanam di atas tanah tersebut disamping kemampuan seorang petani mengerjakan tanah dalam luas tertentu. Dalam pada itu pernyataan beberapa pejabat dan para akhli ternyata telah memperkuat adanya fragmentasi tanah pertanian yang semakin meluas. Data terbaru mengenai hal ini belum ditemukan, akan tetapi bercermin dari realita yang diungkap sekitar dua puluh tahun yang lalu dapat ditunjukkan melalui uraian berikut: Sunandar Priyosudarmo (mantan Gubernur Jawa Timur) dalam pertemuan pimpinan AMPI se-Jawa Timur menyatakan rata-rata pemilikan tanah pada akhir Tahun 1979 akan menururn dari 0,3 Ha. Tahun 1974 menjadi 0,1 Ha. Pada Tahun 1979. Demikianlah fragmentasi berlangsung tanpa dapat dikontrol. Seirama dengan gambaran di atas, Soeharto (mantan Presiden RI) dalam pidato kenegaraan tgl. 18 Agustus 1982 menyatakan: masalah yang terasa semakin gawat yaitu meningkatnya jumlah petani gurem; (1) selama tujuh tahun (1973-1980) jumlah petani meningkat dari empat belas juta menjadi tujuh belas juta atau 2,8% pertahun; (2) petani yang amat miskin yang menggarap tanah kurang dari 0,5 hektar yang juga sering disebut petani gurem jumlahnya naik dari 6,6 juta menjadi sebelas juta orang; (3) jumlah petani penggarap (penduduk pedesaan miskin tak bertanah) meningkat selama periode yang sama dari 490.000 menjadi dua juta orang. Dalam pada itu Sayogyo menyatakan; ratio antara petani yang memiliki tanah dua hektar lebih dan mereka yang memiliki kurang dari dua hektar adalah satu berbanding lebih dari delapan. Demikian juga halnya dengan pernyataan Tampubolon, berdasarkan sensus pertanian Tahun 1983, penguasaan lahan usaha tani rata-rata per keluarga petani adalah 1,05 hektar untuk seluruh Indonesia, dan + 0,67 hektar untuk Pulau Jawa dan Bali, bahkan mungkin sudah berada dibawah 0,50 hektar. Untuk Pulau Jawa dan Bali rata-rata penguasaan lahan beririgasi berkisar antara 0,1 – 0,2 hektar per keluarga.6 Pernyatan-pernyataan di atas sangat memprihatinkan dan olehkarenanya perlu mendapat perhatian khusus. Apabila fragmentasi ini berlangsung terus maka proses kemiskinan dikalangan petanipun akan terus berlangsung. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya fragmentasi adalah pewarisan tanah. Beberapa pendapat muncul menanggapi masalah ini, ada yang menyarankan agar diadakan pembatasan mengenai pewarisan tanah yang luasnya kurang dari batas minimum, akan tetapi ada juga yang kurang sependapat karena menyangkut sendi-sendi yang fundamentil dalam sistem hukum kewarisan dibidang spiritual.7 6 7 Maria S.W. Sumardjono, 1990, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cet. pertama, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, h.87 Abdurrahman, 1985, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Bandung: Alumni,h.149 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 71 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Terlepas dari silang pendapat sebagaimana dipaparkan di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU No. 56/Prp/1960 tentang pengaturan lebih lanjut bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar dalam bentuk PP maka perlu adanya beberapa alternatif pemecahan yang dalam uraian ini dapat disebutkan sebagai berikut: 1. Maria S.W. Sumardjono mengemukakan: pengaturannya lebih lanjut perlu mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 56 Prp/1960 yakni menunjuk salah seorang diantara akhli waris yang akan memiliki tanah itu atau memindahkannya kepada pihak lain dalam jangka waktu satu tahun setelah diterimanya warisan tersebut. Tidak kalah pentingnya dalam masalah fragmentasi ini adalah upaya non yuridis berupa penyediaan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja pertanian ini ke sektor lain.8 2. Dengan menyitir pandangan Sayogyo yang menyatakan, bahwa landreform hanya dikenakan pada golongan yang paling gurem maka cara pemecahan masalah adalah sebagai berikut: misalnya yang menguasai kurang dari 0,2 hektar, tanah mereka dibeli Pemerintah kemudian dititipkan sebagai tanah negara yang harus diurus oleh Badan Usaha Buruh Tani (BUBT) di desa. Uang pembelian tanah itu sebagian dijadikan modal BUBT baik modal untuk usaha bersama maupun modal yang dipinjamkan kepada anggota untuk usaha perseorangan. Atas dasar gagasan apa untuk mengkomunalkan tanah yang paling gurem itu ? Secara tersendiri-sendiri usaha di atas tanah yang sesempit itu mereka tidak mempunyai masa depan yang layak, daripada membiarkan mereka terombang-ambing dalam nasib, lebih tepat dengan sadar memiliki kebijaksanaan untuk mempersatukan mereka di satuan-satuan badan usaha setiap desa di bawah tokoh-tokoh pilihan mereka yang diberi tempat sebagai anggota baru pamong desa pelaksana program. Pembinaan BUBT dalam fase permulaan seyogyanya adalah Departemen Dalam Negeri (Cq Agraria dan PMD) dengan dukungan Dep. Nakertranskop.9 3. Alternatif lain diajukan oleh Parlindungan yang memperkenalkan suatu konsep tentang larangan fragmentasi secara tuntas dan land consolidation. Keduanya dapat dituangkan dalam suatu produk hukum. Larangan fragmentasi harus dengan tegas dilaksanakan dan termasuk masalah mengenai pewarisan. Bebarapa negara seperti Jepang menetapkan anak tertua yang mewarisi tanah sedangkan bagi anak-anak lainnya sejumlah uang yang menjadi bagiannya dan untuk keperluan itu bank akan memberikan pinjaman. Sedangkan land consolidation dicapai dengan cara menghimpun semua tanah-tanah, baik tanah yang tersebar maupun tanah-tanah yang kecil-kecil untuk dihimpun dan kemudian dibagi lagi dengan kavling yang memenuhi syarat untuk menjadi lahan keluarga (lahan yang dapat memberikan kehidupan yang layak kepada satu keluarga). Selanjutnya dikatakan, hak akhli waris tidak diganggu namun hak untuk mendapatkan tanah perlu ditata dan tanah tidak boleh dipecah-pecah lagi dalam lahan-lahan yang tidak lagi sebagai lahan ukuran keluarga yaitu lebih kurang dua hektar (menurut versi UU No. 56 Prp/1960) dan sekaligus dilaksanakan land consolidation atas tanah yang terpecah-pecah sehingga tidak lagi ekonomis dan juga atas tanah-tanah milik seseorang yang tersebar di beberapa lokasi.10 Ketiga alternatif yang diajukan oleh para akhli di atas dalam rangka usaha mencegah dan 8 9 10 Maria S.W. Sumardjono,op.cit.,h.88 Abdurrahman,op.cit.,h.66 Parlindungan, A.P., 1987, Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Bandung: Alumni,h. 66 72 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung menanggulangi fragmentasi tanah pertanian sangat menarik untuk disimak. Catatan penulis atas pandangan Sayogyo adalah, apakah Pemerintah mempunyai cukup dana untuk membeli tanah milik petani ? dan bagimana pula mengenai penetapan harganya ? IV. PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE Pasal 10 ayat (1) UUPA menetapkan: “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Ditegaskan lebih lanjut oleh Penjelasan Umum II butir (7) bahwa, ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) adalah merupakan suatu perumusan asas yang menjadi dasar perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut landreform atau agraria reform yaitu bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Sehubungan dengan itu maka diadakanlah ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan tanah pertanian secara absentee/ guntai (yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar tempat tinggal yang empunya). Tindak lanjut ketentuan Pasal 10 UUPA diatur oleh Pasal 3 PP No. 224/1961 dan Pasal I PP No. 41/1964. Pada dasarnya kedua pasal tersebut melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat tanahnya. Pemilikan tanah absentee menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya dan pengangkutan hasilnya. Disamping itu dapat juga menimbulkan sistem penghisapan misalnya orang-orang yang tinggal di kota memiliki tanah di desa yang digarapkan kepada para petani-petani yang ada di desa itu dengan sistem bagi hasil. Hal ini berarti bahwa petani yang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanya mendapat sebagian saja dari hasil tanah yang dikerjakan, sedang pemilik tanah yang tinggal di kota yang kebanyakan juga sudah mempunyai mata pencaharian lain dengan tidak perlu mengerjakan tanahnya mendapat bagian dari hasil tanahnya pula. Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, agar tanah itu dapat dikerjakan sendiri. Batas daerah diambil kecamatan karena jarak dalam kecamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnya secara efektif. Meskipun pemilikan tanah pertanian secara absentee tidak diperkenankan oleh UU akan tetapi dimungkinkan juga adanya pengecualian-pengecualian. Sangat menarik pandangan Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan bahwa, perlu adanya perhatian terhadap beberapa aspek tertentu berkaitan dengan pemilikan tanah secara absentee antara lain11: 1. Alasan jarak antara tempat tinggal dan letak tanahnya mengingat kemajuan dalam bidang komunikasi dan transportasi saat ini (Pasal 3 PP No. 224/1960). 2. Pengecualian yang diberlakukan bagi PNS/ABRI atau yang dipersamakan, pensiunan PNS/ ABRI dan janda PNS/ABRI/pensiunan (PP No. 4/1977), mengingat bahwa pengecualian itu didasari atas penyediaan jaminan di hari tua. a. kemungkinan yang dapat mengadakan pembelian adalah mereka yang relatif mampu yang mungkin tidak perlu menggantungkan diri pada perolehan nafkah di bidang pertanian. Justru mereka yang mungkin lebih dapat memanfaatkan hasil pertanian sebagai sumber kehidupan di hari tuanya, secara finansial kurang/tidak mampu 11 Maria S.W. Sumardjono,op.cit,h.88 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 73 KERTHA PATRIKA b. c. d. • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 melakukan pembelian tanah pertanian. Bila istri yang berstatus PNS/ABRI, apakah ketentuan ini berlaku terhadap duda/ PNS/ABRI ? Apakah tidak seyogyanya ditegaskan keharusan untuk pindah ke tempat pertaniannya sesudah ybs. pensiun, mengingat bahwa pengecualian dari asas yang termuat dalam Pasal 10 UUPA itu sifatnya temporer ? Terlepas dari ketiga hal tersebut, mungkinkah ketentuan tentang pemilikan tanah absentee ini kelak dihapuskan ? Masalah No. 1 sebagaimana diungkap di atas nampaknya sangat tepat. Sehubungan dengan itu sudah saatnyalah untuk meninjau kembali produk hukum yang berkaitan dengan jarak tempat tinggal dengan tanah untuk disesuaikan dengan kemajuan dibidang komunikasi, teknologi dan transportasi. Diilhami oleh masalah sebagaimana disebutkan di atas maka penulis merasa perlu juga untuk mempermasalahkan, apakah daerah kecamatan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan pemilikan tanah absentee masih relevan ? hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa kemungkinan seseorang memiliki tanah di luar kecamatan yang tidak berbatasan dengan kecamatan tempat tinggalnya akan tetapi masih memungkinkan untuk dikerjakan secara efisien (bila dihitung berdasarkan jarak). Sehubungan dengan itu, apakah tidak lebih tepat untuk menentukan absentee atau tidaknya pemilikan tanah dipakai kabupaten/kota atau kalau menemui kasus seperti tersebut di atas tetap dipakai ukuran kecamatan tetapi apabila masih memenuhi kriteria jarak yang ditentukan bisa juga dikecualikan ? Masalah No. 2a kiranya perlu mendapat perhatian yang seksama. Apabila yang disinyalir itu benar maka perlu kajian yang lebih mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehingga harapan yang terkandung dalam PP termaksud sasarannya tepat. Oleh karena itu penulis mengacu pada tujuan UUPA dan penetapan batas minimum pemilikan tanah. Salah satu tujuan UUPA adalah untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat terutama rakyat tani. Penetapan batas minimum bertujuan agar tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk mencapai taraf penghidupan yang layak. Bertumpu pada alasan yang telah diungkap di atas maka penulis berpendapat bahwa, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemilikan maksimal tanah pertanian secara absentee bagi PNS/ABRI dan yang dipersamakan, pensiunan PNS/ABRI dan janda PNS/ABRI/pensiunan perlu ditinjau kembali dan menurut hemat penulis batas maksimum berpatokan pada luas minimum (yaitu dua hektar) bukan 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota). Hal ini didasarkan pada pemikiran berikut: (a) PNS/ABRI dan janda PNS/ ABRI sudah mempunyai penghasilan tetap (gaji/pensiunan); (2) perlakuan terhadap petani pada umumnya dengan PNS/ABRI, pensiunan PNS/ABRI dan janda PNS/ABRI hendaknya tidak menunjukkan gap terlalu tajam agar tidak memicu kecemburuan sosial. Terhadap masalah 2b tentang kemungkinan diberlakukannya ketentuan untuk janda PNS/ABRI terhadap duda PNS/ABRI. Penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap istilah janda yang dalam pengertiannya yang luas istilah janda tercakup didalamnya janda perempuan dan janda laki/duda. Istilah janda laki sebagai sinonim istilah duda dipakai oleh Surojo Wignjodipuro, 1973: 233, dan pakar hukum adat lainnya. Dari Penjelasan Umum angka 7 PP No. 4/1977 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan janda adalah terbatas pada seorang istri yang ditinggal suami karena meninggal dunia. Dengan demikian tidak termasuk mereka yang berstatus janda sebagai akibat perceraian. Motif apa yang mendorong Pemerintah 74 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung menetapkan hanya janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia saja yang bisa memiliki tanah pertanian secara absentee tidak pernah diungkap oleh PP itu sendiri. Dengan mendasarkan diri pada interpretasi ekstensif dan mengacu ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.56 Prp/1960 penulis berpendapat bahwa, terhadap duda PNS/ABRI dapat juga diberlakukan ketentuan untuk janda PNS/ABRI. Terhadap masalah 2c, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: (1) Apakah alasan yang diungkap dalam PP termaksud masih relevan? Penulis berpendapat bahwa alasan yang dimuat dalam PP termaksud masih bisa diterima. Bukankah untuk pindah ke tempat letak tanah memerlukan biaya yang cukup tinggi? Bagaimana pula dengan anakanaknya yang masih memerlukan bimbingan/perhatian orang tua disamping kemungkinan adanya kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana/situasi dan kondisi lingkungan yang baru. (2) Kalaupun pensiunan PNS/ABRI bisa pindah ke kecamatan letak tanahnya belum tentu ia dapat mengerjakan sendiri tanahnya secara aktif apalagi yang bersangkutan tidak mempunyai ketrampilan dibidang pertanian, faktor usia, disamping UU masih memungkinkan untuk menyerahkan pengusahaan tanahnya kepada orang lain (bagi hasil). (3) Tidak pindahnya pensiunan PNS/ABRI ke kecamatan letak tanahnya justru kurang menguntungkan pensiunan itu sendiri. Bukankah pemilikan tanah absentee dibatasi (hanya sampai 2/5 dari batas maksimum)? (4) Ditinjau dari umur rata-rata orang Indonesia, maka bagi pensiunan tidak lama lagi menikmati hidupnya, sehingga setelahnya ia meninggal dunia terjadilah proses pewarisan, hal mana berarti berakhirnya pemilikan tanah pertanian absentee. Terhadap masalah 2d tentang kemungkinan penghapusan ketentuan pemilikan tanah absentee, menurut hemat penulis diperlukan pemikiran yang cermat. Ada beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: 1. Adanya kesulitan untuk melacak/memonitor pemilikan/penguasaan tanah seseorang dalam kaitannya dengan penetapan pemilikan batas maksimum (seandainya memiliki tanah terpencar). 2. Pemilikan/penguasaan tanah secara terpencar menimbulkan penggarapan yangtidak efisien dan optimal, dus ini berarti kurang menguntungkan petani itu sendiri. 3. Memperluas terjadinya pemerasan oleh golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah yang tersalur dalam bentuk sewa, bagi hasil dsb. 4. Memberikan peluang kepada segolongan orang tertentu untuk menyimpang dari ketentuanketentuan landreform. Atas dasar pertimbangan di atas maka ketentuan tentang pemilikan tanah pertanian secara absentee belum saatnya dihapus. V. SIMPULAN JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 75 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik simpulan berikut: 1. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah melampaui batas: a. Kriteria yang digunakan untuk membedakan daerah padat dan tidak padat berdasarkan indikator sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum butir (7) UU No. 56 Prp/1960 perlu dikaji ulang. b. Sementara belum ditetapkan penggolongan daerah berdasar peraturan perundangundangan baru maka, Keputusan Menteri Agraria No. Sk 978/ Ka/1960 hendaknya diperbarui, disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang ada pada saat ini. c. Pemilikan batas maksimum untuk tanah non pertanian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 12 UU No. 56 Prp/1960 perlu segera direalisir untuk mencegah terjadinya spekulasi dibidang pertanahan. 2. Pemilikan batas minimum a. Penurunan batas minimum pemilikan tanah pertanian perlu pertimbangan yang cermat. Nampaknya penetapan yang sifatnya bervariasi dirasa lebih rasional dan adil. b. Fragmentasi tanah pertanian yang disebabkan karena pewarisan hendaknya jangan dibiarkan terus berlanjut, untuk itu perlu dipikirkan jalan keluarnya sekaligus dalam rangka merealisir Pasal 9 UU No. 56 Prp/1960. 3. Pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai a. Dalam rangka penyempurnaan UUPA/pembaruan agraria, ketentuan-ketentuan mengenai pemilikan tanah pertanian secara absentee masih relevan oleh karena itu hendaknya dipertahankan, namun beberapa hal diantaranya perlu dikaji ulang. b. Kecamatan sebagai kriteria penetapan pemilikan tanah secara absentee perlu ditinjau kembali. Kiranya ukuran yang lebih tepat adalah Kabupaten/ Kota. c. Batas pemilikan tanah pertanian secara absentee khusus bagi mereka yang dikecualikan, sebaiknya mengacu pada pemilikan batas minimum. Demikianlah uraian penulis, semoga dalam penyempurnaan UUPA/ pembaruan agraria buah pikiran ini ada manfaatnya. DAFTAR PUSTAKA 76 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Tinjauan Kritis atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum dan Absentee) dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria I Gusti Nyoman Agung Abdurrahman, 1985, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni, Bandung. Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet. kesebelas (edisi revisi), Djambatan, Jakarta. Efendi Peranginangin, 1979, Hukum Agraria I, Sari Kuliah (2), Jurusan Notariat, FH UI, Jakarta. Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cet. pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. _______, 1990, Penggunaan Tanah di Pedesaan Menyongsong Era Industrialisasi, Makalah pada Seminar Nasional Tri Dasa Warsa UUPA kerjasama Fakultas Hukum UGMBPN, 24 September, Yogyakarta. Parlindungan, A.P., 1987, Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Alumni, Bandung. Surojo Wignjodipuro, 1973, Pengantar dan Asas-azas Hukum Adat, Alumni,Bandung. Ketetapan MPR RI No. IX / MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Peraturan Pemerintah No. 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah No.41/1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No.224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah No. 4/1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai/ Absentee Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2/1961 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 56 Prp/1960. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 77 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Fenomena Cyber Terrorism oleh : I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti (Bagian Hukum Pidana FH-Unud) Abstract For Indonesian socities, cyber terrorism is not so famous like other crimes eventhough the phenomenon of this crime was exist one time in Indonesia criminal lifestyle. Terrorism via cyber space also do not take a lot of attention because of less knowledge about cyber space. In addition crime via cyber space in every kind of its doesn’t have a rule of law to solve its. Keywords: Cyber terrorism I. PENDAHULUAN Peradaban dunia masa kini ditandai dengan adanya kemajuan dibidang teknologi khususnya teknologi informasi atau umum disebut juga sebagai teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi atau teknologi telekomunikasi ini telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan dengan manusia lain pada komunitas yang berbeda dengan mudah. Interaksi sosial pada masa kini dapat dilakukan dengan tanpa melakukan perpindahan komunitas asal atau tempat dimana ia tinggal, interaksi ini bahkan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Teknologi informasi atau teknologi telekomunikasi disadari telah membawa manusia pada suatu peradaban baru dimana masyarakat konvensional akan berkembang menuju masyarakat informasi internasional yang memiliki struktur global dengan sistem tata nilai yang global universal. Hal ini mengandung arti sekat-sekat wilayah suatu negara perlahan mulai memudar (state borderless) dan terjadi perubahan besar pada nilai, norma, moral serta kesusilaan. Ditambah kemudian dengan terjadinya konvergensi antara komputer, telekomunikasi dan media yang melahirkan internet sebagai suatu sarana baru yang memudahkan masyarakat melakukan interaksi sosial, semakin membawa masyarakat pada suatu fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan. Pada awal penemuannya internet hanya ditujukan untuk kepentingan dunia pendidikan dan lembaga penelitian semata. Namun sejak internet mulai diperkenalkan kepada publik pada tahun 1995 ternyata internet telah membawa banyak kemudahan-kemudahan bagi manusia, seperti misalnya manusia dengan mudah mengakses informasi melalui world wide web (www) yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee dan mulai banyak bermunculan aplikasi-aplikasi bisnis melalui internet yang menunjukkan adanya aspek finansial. Contohnya melalui internet manusia bisa memesan tiket penerbangan, pembayaran rekening telepon, listrik dan lain sebagainya dimana semuanya itu dapat dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat-tempat transaksi yang nyata. Penemuan internet memang membawa banyak kemudahan bagi manusia. Akan tetapi kemudian disadari bahwa internet juga membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan 78 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Fenomena Cyber Terrorism I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Sh manusia. Kini melalui media internet banyak kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang terjadi seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan (hacking), penyerangan melalui virus sampai dengan cyber terrorism. Berbicara mengenai cyber terrorism, di Indonesia kejahatan jenis ini memang belum pernah terjadi namun dengan berkembangnya infrastruktur berbasis komputer potensi kejahatan terorisme yang difasilitasi teknologi informasi sangat rentan terjadi. salahsatu contoh yang telah nyata, dari laptop Imam Samudra (salah seorang terpidana mati Bom Bali I) yang disita oleh penyidik dapat diketahui adanya hubungan yang kuat antara aksi terorisme dengan tindak pidana berbasis teknologi informasi. Dimana internet dijadikan sarana untuk melakukan komunikasi, propaganda, serta carding untuk memperoleh dana bagi pembiayaan teror. Cyber terrorism memang belum cukup dikenal di Indonesia namun apa yang terjadi dengan Imam Samudra ini sekiranya dapat dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk tetap waspada akan bahaya terorisme yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mengenai cyber terrorism dalam kehidupan masyarakat awam sehingga penting rasanya untuk mengulas sedikit mengenai cyber terrorism. Diharapkan dengan adanya tulisan ini akan lahir tulisan-tulisan lain yang lebih luas wawasannya dalam memandang permasalahan cyber crime khususnya mengenai cyber terrorism. II. TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN TERORISME Sebelum membahas mengenai cyber terrorism maka terlebih dahulu akan diulas sedikit mengenai terorisme. Hal ini dilakukan karena cyber terrorism merupakan bentuk lain daripada aksi terorisme yang umum kita kenal. Terorisme berasal dari kata teror. Sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom dari Franz Magnis-Suseno, Istilah “teror” diinkorporasi ke dalam kosakata politik pada saat Revolusi Perancis. Maximillan Roberspierre (1758 - 1794), ”Imam Agung” teror besar dalam Revolusi Perancis, pemimpin agung Revolusi Perancis memaklumatkan ”la grande terreur”, teror agung terhadap setiap lawan politiknya. Pengagum berat Jean-Jacques Rousseau ini menghukum mati siapa saja yang dicurigai sebagai antirevolusi tanpa proses pengadilan yang wajar. Menurut Roberspierre, kecurigaan rakyat selalu benar1. Diungkapkan pula oleh Oka Metria dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul “Terorisme Internasional Dalam Kerangka Teori Hukum Internasional (Suatu Analisis Teori)”, di Eropa sendiri kata “teror” baru dikenal pada akhir abad ke-18, lima abad setelah tumpasnya sekte “assassin” itu. Dengan Revolusi Perancis, kekuasaan teror telah berhasil menangkap pasling kurang 300.000 orang tertangkap dan 17.000 orang telah dipenggal kepalanya dengan gillotine dan banyak lagi tindakan kekerasan telah terjadi di luar hukum tanpa melalui proses peradilan2. Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom juga mengatakan bahwa teror merupakan fenomena yang cukup tua dalam sejarah kehidupan manusia. Aksi kekerasan berbau teror dapat ditelusuri dari tulisan Xenophon (431-350) mengenai perang psikologis, kekerasan bangsa Roma yang terjadi di Spartacus pada tahun 73 SM, juga peristiwa di sekitar tahun 14 – 34 Masehi dan 37 – 41 Masehi tatkala Kaesar Tiberius dan Caligula dari Romawi mengeksekusi musuhnya tanpa 1 2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.49 Oka Metria K, 1988, Terorisme Internasional Dalam Kerangka Teori Hukum Internasional (Suatu Analisis Teori), Majalah Ilmiah Universitas Udayana, Pusat Penelitian Univ. Udayana, Denpasar, hal.119. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 79 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 melalui saluran hukum atau pengadilan, melakukan penangkapan-penangkapan, perampasan harta benda, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya3. Hal demikian telah membawa kehidupan rakyat pada masa itu penuh dengan rasa takut dan cemas, penuh dengan pertanyaan kapan akan dirampas harta benda jiwanya oleh Kaesar (penguasa). Oka Metria dalam tulisannya kemudian menambahkan munculnya kelompok “assassin” pada masa itu terutama awal abad ke-12 yang telah menyebar keberbagai daratan di Eropa seperti ke Suriah, Persia dan Asia Tengah, yang sekarang dikenal sebagai orang Khojas, keadaan “great fear ” antar negara dan bangsa menjadi berkembang Sebagai tambahan diungkapkan juga bahwa diakhir abad 19, awal abad ke 20 dan menjelang PD II, ” terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi dan dapat dilakukan negara. Sebagai contoh rezim Stalin pada tahun 1930-an yang dianggap sebagai “pemerintahan teror”. Mengenai pengertian terorisme sendiri masih terdapat perbedaan pemahaman antara para pakar dimana masing-masing pakar mengungkapkan pengertian terorisme sesuai dengan teori yang melandasi dan kepentingan politis masing-masing. Sebagaimana juga diungkap oleh I Wayan Parthiana, perbedaan definisi ini disebabkan karena pandangan dan kepentingan negaranegara terhadap terorisme itu sendiri yang beraneka macam yang sulit untuk dikompromikan antara satu dengan lainnya4. Negara-negara yang sedang berkembang tidak setuju jika usaha kelompok bangsa-bangsa terjajah dalam memperjuangkan hak-haknya yang kadang-kadang dengan tindakan kekerasan, diisebut sebagai kelompok teroris, suatu posisi yang berlawanan dengan negara-negara maju. Sekelompok negara menolak jika tindakannya yang mendukung ataupun membantu terorisme digolongkan juga sebagai tindakan teror, berhadapan dengan negara-negara yang mengklasifikasikan tindakan semacam itu sebagai terorisme dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu juga diketahui bahwa kesulitan dalam memberikan definisi terorisme terjadi karena kejahatan ini memiliki kompleksitas yang cukup rumit misalkan mengenai latar belakang peristiwa dan pelaku, target sasaran yang kerap kali tidak pandang bulu serta bentuk-bentuk terorisme yang terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan jaman. Peraturan perundang-undangan mengenai terorisme yang ada di dunia sendiri masih belum secara jelas memberikan definisi terorisme. Liga Bangsa-Bangsa (the league of nations) pernah memberikan definisi terorisme dalam Konvensi Jenewa 1937 yaitu “terrorisme is all criminal acts directed against a state amd intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public.” Akan tetapi yang disayangkan konvensi ini (Konvensi Jenewa) tidak pernah dinyatakan berlaku sebagai hukum internasional positif, sebab karena tidak memenuhi persyaratan untuk berlakunya karena jumlah negara yang meratifikasinya tidak mewakili. Oleh karenanya dalam Resolution F Statuta International Criminal Court disebutkan bahwa sangat disesalkan tidak ada definisi kejahatan terorisme yang dapat diterima secara umum. Dalam prakteknya kemudian, masyarakat internasional mengupayakan definisi daripada terorisme dengan membuat konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang kejahatankejahatan yang substansinya berkaitan dengan terorisme dan kejahatan tertentu lainnya sebagai wujud terorisme. Di Indonesia ketidakjelasan mengenai definisi terorisme juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan bangsa kita yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme, Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU No. 3 4 Ibid. I Wayan Parthiana, 2004, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Widya, Bandung, hal. 74 80 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Fenomena Cyber Terrorism I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Sh 15 Tahun 2003 menyebutkan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam perppu ini. Jika berdasarkan pasal ini maka tidak terdapat kejelasan pengertian mengenai terorisme bahkan bunyi pasal terkesan mendua dan multitafsir. Ini dapat dilihat dalam pernyataan “ segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana”, jadi perbuatan yang bagaimana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini tidak dijelaskan. Kemudian bila menunjuk unsur-unsur yang terkandung dalam pasalpasal lainnya seperti pada pasal 5, 6, 7, 9,11, 12 dan 14 yang mengandung delik formil dan material maka akan semakin nampak sifat ambigu dan multitafsir yang dikandung oleh UU No. 15 Tahun 2003. Pada pasal-pasal ini juga tidak terdapat kejelasan yang dapat memberikan kepastian mengenai pengertian tindak pidana terorisme. Akan tetapi meskipun terdapat kesulitan dalam memberikan definisi dari terorisme, beberapa literatur telah mencoba memberikan pegangan mengenai pengertian terorisme dengan mengemukakan beberapa pendapat antara lain : 1. Ayatullah Sheikh Muhammad Al Taskhiri menyatakan bahwa “terrorism is an act carried out to achieve on in “human and corrupt objective and involving threat to security of mankind, and violation of rights acknowledge by religion and mankind” . 2. FBI menyatakan bahwa “terrorism is the unlawful use of violence “against persons or property to intimidate or coerce a governed, civilian populations, or any segment threat, in furtherance or political or social objective.” 3. Sebuah forum bersama (brain stroming) antara para akademisi profesional, pakar, pengamat politik dan diplomat terkemuka pada pertemuan bersama di kantor Menko Polkam tanggal 15 September 2001 berpendapat bahwa terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separtatis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum. 4. T.P. Thornton dalam bukunya Terror as a Weapon of Political Agitation yang ditulis pada tahun 1964 menyatakan bahwa terorisme merupakan penggunaan teror sebagai tindakan simbolis untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Menurut Thornton, terorisme dapat dibagi menjadi dua macam yaitu enforcement terror dan agitational terror. Bentuk pertama adalah teror oleh penguasa untuk menindas yang melawan kekuasaannya, sedangkan bentuk kedua yaitu teror yang dilakukan untuk mengganggu tatanan politik yang mapan untuk kemudian dikuasai. 5. Igor Primoratz menyatakan bahwa “terrorism is best defined as the deliberate use of violence, or threat of its use, against innocent people, with the aim of intimidating some other people into a course of action they otherwise would not take” 6. F. Budi Hardiman menyatakan bahwa dalam mendefinisikan secara objektif mengenai terorisme harus dilihat unsur kualitas aksinya. Kualitas aksi tersebut adalah adanya penggunaan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan ketakutan yang meluas. Menurut Hardiman, pendefinisian dengan melihat kualitas aksi atau peristiwa lebih menguntungkan karena dapat mengidentifikasi pola-pola yang luas dari aksi, dapat mengenali kecenderungan dimasa depan dan dapat mengetahui pertumbuhan terorisme serta menemukan penyebarannya di dunia5. 5 Seluruhnya dikutip dari Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom, op.cit., hal.62 – 63. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 81 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Bila diperhatikan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat dilihat bahwa terorisme adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan dengan tujuan sosial politik, menjatuhkan pemerintahan, pemaksaan, yang menyerang masyarakat sipil, orang-orang tidak berdosa sampai dengan objek-objek vital strategis yang memiliki peranan penting bagi kemanusiaan.. Kekerasan yang dimaksud dipertegas dengan bentuknya yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain secara meluas (ancaman) dan bentuknya yang nyata (tindakan yang dilakukan oleh badan). III. PENGERTIAN CYBER TERRORISM Sebagaimana telah diungkap di atas, cyber terrorism merupakan bentuk lain dari terorisme. Sebagai bentuk lain dari terorisme, cyber terrorism adalah terorisme yang dilakukan di dunia maya memiliki sedikit kesamaan dengan terorisme, yaitu sama-sama kejahatan atau tindak pidana yang menyerang objek-objek vital strategis hanya saja pelaksanaan cyber terrorism umumnya lebih mudah dan lebih sedikit memerlukan biaya. Cyber terrorism sendiri lahir sebagai akibat dari proses globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya sistem informasi.yakni internet. Oleh Andi Widjajanto dalam F. Budi Hardiman sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom, kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi dan informasi menjadi sarana penerapan strategi perlawanan teroris secara tidak langsung (indirect strategy). Karena sifatnya yang tidak dibatasi ruang dan waktu maka aksi teror dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sebab distribusi geografisnya mencakup seluruh dunia, tidak ada pusat kontrolnya dan kecepatan beroperasi sesuai waktu sesungguhnya (real time speed). Mengenai pelaksanaan teror melalui dunia cyber ini juga sulit untuk diberi definisi selayaknya terorisme yang sampai saat ini masih belum memiliki satu definisi yang jelas dan tegas. Beberapa definisi pernah disebutkan guna memperoleh satu pandangan mengenai cyber terrorism, definisi tersebut antara lain yang diberikan oleh: 1. NPA yang merumuskan cyber terrorism sebagai “serangan elektronik melalui network komputer terhadap infrastruktur kritis yang berpotensi besar mengganggu aktifitas sosial dan ekonomi bangsa/negara”. 2. The U.S. Department of Justice menyatakan “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for it’s preparation, investigation or prosecution”. 3. OECD menyatakan “any ilegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and/or the transmission of data”. 4. Cahyana Ahmadjayadi yang menyatakan bahwa terorisme pada dasarnya sudah terjadi jika seseorang atau kelompok orang melakukan kegiatan ilegal melalui teknologi informasi. Menurutnya, penyusupan kedalam sistem komputer yang duproteksi miliki orang lain dan mencuri data atau merusak data maupun informasi digolongkan sebagai “terorisme informasi”. 5. James A. Lewis mendefiniskan cyber terrorism sebagai “the use of computer network tools to shut down critical national infrastructures (such as energy, transportation, government operations) or to coerce or intimidate a government or civilian population”. 6. Dorothy E. Denning memberikan definisi cyber terrorism secara luas dan menekankan aspek target, motivasi, tujuan dan pelakunya. Menurut Dorothy, istilah cyber terrorism adalah : “...is 82 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Fenomena Cyber Terrorism I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Sh generally understood to mean a computer-based attack or threat of attack intended to intimidate or coerce governments or societies in pursuit of goals that are political, religious, or ideological. The attack should be sufficiently destructive or disruptive to generate fear comparable to that from physicl acts of terrorism. Attacks that lead to death or bodily injury, extended power outages, plane crashes, water contamination, or major economic losses woukd be examples. Depending on their impact, attacks against critical infrastructures such as electric power or emergency services could be acts of cyber terrorism. Attacks that disrupt nonessential services or that are mainly costly nuisance would not”6. Berdasarkan beberapa pemahaman-pemahaman di atas mengenai cyber terrorism sekiranya dapatlah dipahami bahwa cyber terrorism adalah jenis tindak pidana terorisme yang paling mudah, cepat dan murah karena hanya menggunakan media komputer / laptop yang telah dilengkapi dengan sistem internet kejahatan telah dapat terlaksana. Selain itu dapat pula dipahami bahwa terorisme yang “tadinya” dilakukan hanya di dunia nyata kini beralih dapat dilakukan di dunia maya (cyber). Dimana internet menjadi salahsatu media untuk melakukan perancangan sekaligus media untuk melaksanakan serangan terhadap pihak musuh dengan melakukan penyerangan melalui objek-objek sasaran yang memiliki sistem komputer. Jadi teror dapat dilakukan terhadap infrastruktur yang strategis sepanjang berhubungan dengan sistem komputer dan memiliki hubungan dengan internet. Adapun perbedaan tipisnya dengan terorisme konvensional adalah mengenai proses pelaksanaan kejahatannya. Apabila dalam terorisme konvensional tindakan kejahatan umumnya lebih nyata melukai perasaan jiwa dan tubuh seseorang maka dalam cyber terrorism yang dilukai adalah sistem dari data atau infrastruktur yang berbasis komputer dan internet yang juga bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Apabila dalam terorisme konvensional bentuk kejahatannya adalah perusakan yang menyeluruh baik manusia maupun objek vital strategis maka dalam cyber terrorism bentuk-bentuk kejahatannya adalah perusakan terhadap objek vital strategis yang berbasiskan komputer dan internet. IV. BENTUK-BENTUK CYBER TERRORISM Telah diketahui bersama sehebat apapun suatu teknologi tetap saja memiliki kelemahankelemahan atau kekurangan-kekurangan demikian juga dengan komputer atau internet. Tidak ada satu pun sistem jaringan dalam internet yang tidak memiliki kelemahan, hampir setiap sistem komputer memiliki tingkat keamanan yang rendah sehingga teroris yang pintar mengoperasikan dan tahu seluk beluk komputer dapat mengeksploitasinya dengan mudah. Oleh karena itu ada beberapa bentuk-bentuk kegiatan dalam dunia cyber dapat digunakan dalam kegiatan terorisme seperti : a. Unauthorized Acces to Computer System and Service merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. b. Carding atau yang disebut credit card fraud merupakan tindakan memanfaatkan kartu kredit orang lain untuk berbelanja di toko-toko online guna membeli peralatan terorisme dan pembiayaan operasional. Teroris mencari nomor-nomor credit card orang lain melalui chanel di IRC, melalui CC Generator, meng-hack toko online dan masuk data basenya, membuat 6 Seluruhnya dikutip dari Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom, op. cit., hal. 65-66. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 83 KERTHA PATRIKA c. d. e. f. g. h. • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 website palsu mengenai validitas kartu kredit seperti pada umumnya di situs-situs porno. E-mail. Teroris dapat menggunakan email untuk menteror, mengancam dan menipu, spamming dan menyebar virus ganas yang fatal, menyampaikan pesan di antara sesama anggota kelompok dan antara kelompok. Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Cyber Sabotage and Extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Membajak media dengan menunggangi satelit dan siaran-siaran TV Kabel utuk menyampaikan pesan-pesannya. Selain itu, teroris dapat mencari metode-metode untuk menyingkap “penyandian” signal-signal TV Kabel yang ada dan menyadap siarannya. Contoh kasus demikian adalah kasus “Captain Midnight” memanipulasi siaran HBO yang berjudul “The Falcon and Snowman”. Phreaker, merupakan Phone Freaker yaitu kelompok yang berusaha mempelajari dan menjelajah seluruh aspek sistem telepon misalnya melalui nada-nada frekwensi tinggi (system multy frequency). Pada perkembangannya setelah perusahaan-perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat menggunakan komputer untuk mengendalikan jaringan telepon, para phreaker beralih ke komputer dan mempelajarinya seperti hacker. Sebaliknya para hacker mempelajari teknik phreaking untuk memanipulasi sistem komputer guna menekan biaya sambungan telepon dan menghindari pelacakan. Hacking untuk merusak sistem dilakukan melalui tahap mencari komputer (foot printing) dan mengumpulkan informasi untuk mencari pintu masuk (scanning). Setelah menyusup, penjelajahan sistem dan mencari akses keseluruh bagian (enumeration) pun dilakuka. Kemudian, para hacker membuat backdoor (creating backdoor) dan menghilangkan jejak7. Selain hal-hal tersebut di atas Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom juga menambahkan pernyataan dari Michael Vatism yang menyatakan bahwa ada tiga cara komputer dapat dimanfaatkan oleh kaum teroris untuk melakukan aksinya. Pertama, komputer digunakan sebagai alat (tool). Kedua, sebagai penerima atau alat bukti dan yang ketiga sebagai target. Contoh komputer dijadikan sebagai alat (tool) adalah membuat home page sebagai sarana propaganda, rekruitmen, mengumpulkan data (informasi) dari sektor privat atau data rahasia dam mengadakan hubungan dengan kelompok teroris lainnya. Di Indonesia bentuk kegiatan dunia cyber yang digunakan untuk melancarkan aksi terorisme ditemukan dalam laptop milik Imam Samudra pelaku Bom Bali I, disinyalir Imam Samudra melakukan propaganda, komunikasi, pendanaan terorisme melalui internet. Oleh karena itu Indonesia rasanya perlu untuk waspada terhadap munculnya fenomena kejahatan terorisme yang menggunakan komputer berbasis internet sebagai alat melancarkan aksi terorisme. 7 Cahyana Ahmadjayadi, makalah tahun 2003 “Dampak Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Kegiatan Terorisme”; dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom, op.cit., hal. 65-66. 84 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Fenomena Cyber Terrorism I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Sh V. MENYIKAPI FENOMENA CYBER TERRORISM Cyber terrorism mungkin memang belum muncul sebagai kejahatan biasa selayaknya kejahatan konvensional yang ada. Cyber terrorism sampai saat ini masih merupakan fenomena kecil dari kejahatan cyber yang harus diwaspadai. Yang menjadi inti dari tulisan ini sesungguhnya adalah mengenal sedikit mengenai cyber terrorism kemudian berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya kejahatan terorisme yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salahsatu alat untuk melancarkan kejahatan. Mengingat penanggulangan terorisme telah menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Oleh karenanya perang terhadap terorisme dengan segala bentuknya haruslah dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat nasional maupun internasional. Hal tersebut patut untuk dilakukan dalam upaya menciptakan iklim masyarakat nasional maupun internasional yang tidak mengijinkan adanya terorisme tumbuh dan berkembang. Di lain sisi, penggunaan komputer (khususnya disini laptop) yang berbasis internet adalah merupakan hak setiap manusia yang mampu untuk itu. Ini berkaitan dengan apa yang namanya hak atas kebebasan informasi dan komunikasi yang memperoleh jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional seperti UDHR 1948, the European Convention on Civil and Political Rights 1950; the International Covenant in Civil and Political Rights (ICCPR), the American Convention on Human Rights 1969 dan the African Charter on Human and People’s Rights 1986. Akan tetapi meskipun demikian kebebasan akan informasi dan komunikasi ini tidaklah bersifat mutlak. Ini dilihat dari ajaran aliran filsafat hukum kodraf mengenai hak milik yang dikembangkan oleh Sonny Keraf dimana dalam ajaran tersebut diungkapkan hak untuk melakukan komunikasi dan hak atas informasi sebenarnya merupakan kewajiban sekaligus hak manusia untuk mempertahankan hidup manusia. Kodrat individual harus harmonis dengan kodrat sosial. Hak individual harus bersifat fungsi sosial dan tidak merusak atau merugikan individu lain dan masyarakat. Oleh karena itu sepatutnya dunia cyber haruslah dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya untuk menciptakan komunikasi dan informasi yang positif bukan sebaliknya menjadikan dunia cyber sebagai sarana untuk melakukan kejahatan terhadap individu lain. Hal ini nampaknya bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari aksi terorisme yang lebih mengarah pada timbulnya ancaman perusakan fisik maupun non fisik yang merusak kelangsungan hidup orang lain dengan alasan mempertahankan hidup individu dan kolektif kelompoknya. Oleh karena itu penting rasanya untuk menciptakan suatu hukum ataupun peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan terorisme termasuk di dalamnya cyber terrorism. Berbicara mengenai hukum mengenai terorisme khususnya cyber terrorism, dunia internasional memang belum berhasil memiliki satu peraturan yang bersifat global yang dapat digunakan oleh semua bangsa sebagai pedoman. PBB memang pernah mengadakan suatu kongres di Havana sekitar tahun 1990 yang mengantarkan lahirnya Manual on the Prevention and Control of Computer Related Crime dan Vienna Declaration on Crime and Justice pada tahun 1994 dan Masyarakat Ekonomi Eropa juga mengeluarkan sebuah Council of Europe’s Convention on Cybercrime pada tahun 2001 yang sekiranya dapat dipergunakan untuk sementara bagi bangsa-bangsa yang ada didunia untuk menegakkan hukum bagi terorisme yang berbasis teknologi komputer dalam melaksanakan aksinya. Sedangkan jika menurut hukum nasional Indonesia, UU No. 15 Tahun 2003 tentang JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 85 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 terorisme sampai saai ini adalah satu-satunya undang-undang yang dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber terrorism guna menghindari terjadinya kekosongan hukum ( ini dapat kita temui dalam pengaturan pasal 6, 7, 9 dan pasal 11 serta pasal 12. cat. pen ). Undang-undang terorisme ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan aksi terorisme dan dapat dijatuhi hukuman walaupun tindak pidana terorisme belum terjadi atau baru hanya sampai pada tahap maksud atau merencanakan. Dengan demikian dalam rangka menyikapi fenomena cyber terrorism di Indonesia, bilamana dikemudian hari terjadi cyber terrorism aparat penegak hukum dapat mempergunakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme sebagai hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan demi menjaga kepentingan orang banyak dan menghindari terjadinya kekosongan hukum mengenai cyber terrorism. Di sisi lain ada suatu pengharapan besar bahwa pemerintah akan melahirkan sebuah undang-undang mengenai cyber law yang nantinya dapat menjadi peraturan hukum bagi dunia cyber. VI. PENUTUP Simpulan Berdasarkan wacana di atas, penulis menemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang dapat membantu mempermudah pemikiran mengenai Cyber Terrorism yaitu : 1. Cyber Terrorism di Indonesia belum pernah terjadi namun indikasi kearah itu sudah pernah ada. Ini dapat dilihat dari ditemukannya upaya komunikasi teroris melalui internet dan propaganda dalam laptop Imam Samudra salah seorang pelaku Bom Bali I. 2. Permasalahan Cyber Terorrism tidak dapat dipandang dengan sebelah mata mengingat kemajuan teknologi dan sistem informasi yang terus berkembang dengan pesat. Teknologi dan sistem informasi yang maju dipandang dapat membantu atau memudahkan pelaksanaan daripada aksi terorisme. 3. Tidak adanya pemahaman yang sama mengenai terorisme menyulitkan juga dalam memberikan pemahaman terhadap Cyber Terrorism. Yang dapat dipahami adalah cyber terrorism merupakan bentuk lain dari terorisme yang mempergunakan teknologi dan sistem informasi ( komputer dan internet) sebagai alat untuk melancarkan aksi terorisme . Dengan kata lain Sebagai bentuk lain dari terorisme, cyber terrorism memiliki sedikit kesamaan dengan terorisme, yaitu sama-sama kejahatan atau tindak pidana yang menyerang objek-objek vital strategis hanya saja pelaksanaan cyber terrorism umumnya lebih mudah dan lebih sedikit memerlukan biaya. 4. Tidak adanya peraturan mengenai dunia cyber/Cyber Law menjadi salahsatu faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan dalam dunia cyber. Hal ini juga menjadi faktor penentu terjadinya Cyber Terrorism. 5. Untuk saat ini UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme adalah satu-satunya peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan terhadap tindak pidana Cyber Terrorism. 86 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Fenomena Cyber Terrorism I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Sh Saran Ada beberapa saran yang ingin penulis sertakan berkaitan dengan wacana ini yaitu : 1. Bangsa Indonesia hendaknya jangan melupakan ideologi bangsa yakni Pancasila yang merupakan pedoman falsafah hidup bangsa Indonesia yang mempersatukan seluruh manusia Indonesia dalam suatu bangsa meski ada dalam perbedaan suku dan agama. 2. Cyber Terrorism memang belum pernah terjadi di Indonesia tetapi sekiranya hal ini perlu diwaspadai oleh kita bangsa Indonesia mengingat adanya pernyataan bangsa kita saat ini menjadi surganya para teroris. Jangan sampai kelemahan karena ketiadaan undang-undang menjadi dasar teroris untuk berani melakukan aksi terorisme di Indonesia. Oleh karena itu menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk melahirkan suatu peraturan mengenai dunia cyber yang mencakup segala aspek hukum yang ada. DAFTAR PUSTAKA Alvin Toffler, Kejutan Masa Depan “Future Shock”, PT. Pantja Simpati, Jakarta, 1992 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT. Refika Aditama, Bandung, 2005. Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005. Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, CV. Yrama Widya, Bandung, 2004. Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1984. Oka Metria, K, Terorisme Internasional Dalam Kerangka Teori Hukum Internasional (Suatu Analisis Teori), Majalah Ilmiah Universitas Udayana, Pusat Penelitian Univ. Udayana, Denpasar, 1988 Oppenheimer-Lauterpacht, International Law, A Treaties, Vol. 1: Peace, Longmans, London, 1960. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 87 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional Oleh: I Gede Pasek Eka Wisanjaya (Bagian Hukum Internasional) Abstract Children are very important in every family which have rights and dignity. Nonetheless, in fact a lot of children are afflicted by violence treatment that mainly come neither their own family nor outside. Daily news in news paper or television have shown its gloomy phenomenon. State has a duty to be a shelter of our children from violence which has been strictly regulated in national law. This duty is derived from international law such as convention concerning protection of children which has been ratified by the state concern. Key words: protection, children’s rights, national, international, law I. PENDAHULUAN Akhir-akhir ini media dihebohkan dengan maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anakanak. Dalam berbagai berita dikesankan bahwa seolah-olah kekerasan seperti itu meningkat drastis. Berita-berita tersebut makin marak karena semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita politk dan sosial yang mengisi wahana informasi publik. Apakah pemberitaan itu juga mencerminkan perhatian publik yang makin serius dengan persoalan ini? Hal ini susah diukur, karena sejak lama kita telah disuguhi dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang tingkat kesadisannya bervariasi, tetapi komunitas terpelajar dan pengembang kebijakan tenang-tenang saja, seperti menderita sindroma ketakberdayaan. Jauh sebelum kasus Arie Hanggara tahun 1983, ada paradigma keliru tentang anak di kalangan banyak orangtua. Seolah anak adalah hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan, kekerasan pada anak tidak mengenal strata sosial. Dikalangan menengah ke bawah, kekerasan pada anak karena faktor kemiskinan. Dikalangan menengah ke atas, karena ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah, di masyarakat, termasuk selebritis cilik agar bisa tampil di televisi. Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas Perlindungan Anak mencatat, anak (9 tahun) korban kekerasan akhirnya ingin membunuh ibunya jika ia bertemu. Ini semua akibat tindak kekerasan pada anak. Paradigma keliru yang menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orang tuanya, harus diakhiri. Sudah saatnya orang tua menyadari, anakanak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal; 88 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak. Hak anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990, disusul disahkannya UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak. Bahkan, Pasal 13 UU Perlindungan Anak menyebutkan, orangtua diposisikan pada garda paling depan bagi upaya perlindungan anak, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak akan ditambah sepertiga jika yang melakukan adalah orang tuanya sendiri. Hal itu harus terus disosialisasikan oleh pemerintah, media, LSM, lembaga pendidikan, perorangan maupun organisasi yang memiliki akses kepada ibu dan keluarga, untuk mengubah paradigma keliru tentang anak. Selama ini, pembicaraan soal hak anak hanya muncul menjelang Hari Anak Nasional, lalu dilupakan.1 Diberlakukannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak seolah menjadi antiklimaks dari banyak aktivis perlindungan anak. Padahal UU ini saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak. UU ini juga belum dapat diharapkan untuk mempunyai efek deteren karena belum banyak dikenal oleh aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak akan tetap berlanjut dan jumlah kejadiannya tidak akan menurun karena sikon hidup saat ini sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu berbagai ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak-pihak yang paling lemah dalam keluarga itu. Anak adalah pihak yang paling lemah dibanding anggota keluarga yang lain. Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, misalnya selain UU perlindungan anak dan KDRT yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah sistem deteksi dini, rujukan, penanganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasaan. Di Malaysia sejak awal tahu 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota timnya terdiri dari relawan, masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tahu apa yang mereka harus perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasaan terhadap anak. Di Indonesia sistem seperti itu belum ada, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasaan seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan ? tetapi peranan mereka tidak diatur dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk meyelamatkan anak. Oleh karena itu jangan heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka perbuat, takut, atau ragu-ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan tehadap anak.2 Sudah menjadi hal yang “lumrah” di zaman sekarang ini kita mendengar berita seorang anak dibunuh oleh ibunya dengan cara dibakar, seorang bapak yang memperkosa anak gadisnya sendiri, seorang anak bunuh diri karena sering dipukuli kakaknya, dan masih banyak lagi hal-hal 1 2 Seto Mulyadi, Kekerasan Pada Anak, http://www.mail-archive.com, diakses 19 Agustus 2008. Irwanto, Pelaku Kekerasan Pada Anak : Apakah Hukuman Saja Cukup?, http://himpsijaya.org, diakses 19 Agustus 2008. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 89 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 “lumrah” yang sering kita dengar yang membuat bulu kuduk manusia normal merinding. Entah sudah berapa banyak kasus yang ditangani polisi mengenai kasus-kasus tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lebih spesifik lagi adalah kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2008, yaitu seorang ayah di Asahan, Sumatra Utara tega menganiaya anaknya. Akibatnya, Amar Ma`ruf yang baru berusia delapan tahun terluka pada pelipis kanan dan lengan kiri, memar di bagian wajah serta bengkak di kakinya. Korban mengaku, penganiayaan dilakukan saat menanyakan tas sekolah. Bukan jawaban yang diterima, tapi penganiayaan. Tubuh kecil Amar juga diempaskan ke halaman rumah hingga dua kali yang membuat korban pingsan. Warga yang melihat kejadian ini tak tinggal diam. Mereka melapor ke polisi. Sang ayah, Kisman, lalu ditangkap. Sedangkan Amar dibawa ke klinik. Kisman mengaku tega menganiaya karena kesal dengan ulah anaknya. Dari keterangan warga, Kisman sudah bercerai dengan istrinya empat tahun lalu. Diduga karena perceraian mengakibatkan Kisman sering memukul istrinya. Perceraian membuat kisman menjadi orangtua tunggal bagi dua anaknya. Demikian juga seorang ayah di Bengkulu tega menganiaya anaknya yang baru berusia tiga tahun. Revina, si bocah cilik harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka memar dan bengkak di pipi serta kepala. Perut, dada, dan tangan Revina lecet. Dan yang paling mengenaskan, kemaluan Revina tidak luput dari penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan dokter, penyiksaan yang dialami Revina ternyata sering terjadi karena bekas-bekas luka lama masih terlihat. Alasan Rudi Hadmoko, ayah Revina sungguh di luar kewajaran. Pemicu kejadian terakhir ternyata lantaran buah hatinya itu buang air besar di ruang tamu. Revina pun tidak luput dari amarah sang ayah. Karena masih rewel, bocah malang tersebut menerima penganiayaan dari Rudi, yaitu dengan menggigit, mendorong, hingga membentur dinding. Atas penganiayaan ini, Rudi terancam hukuman lima tahun penjara. Kekerasan terhadap anak termasuk dari orang-orang terdekat seperti orangtua mereka semakin memprihatinkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2008, 43 juta anak di 33 provinsi mengalami tindakan kekerasan mulai fisik, psikis, maupun seksual. Angka ini naik 50 persen dibandingkan tahun lalu (tahun 2007).3 Anak bukanlah objek, itu yang dikemukan banyak organisasi wanita yang memperjuangkan hak-hak anak. Anak bukanlah objek, bukanlah permainan, dan bukanlah milik siapa-siapa termasuk orang tuannya sendiri. Orang tua bertugas membimbing anak tersebut dan bukannya menyiksa anak tersebut atau bahkan membunuhnya. Anak memiliki hak-hak sewajarnya, hakhak sebagai manusia. Melihat masalah yang cukup pelik ini, pemerintah sudah mengesahkan undang-undang mengenai “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang biasa disingkat UU KDRT. Dalam undangundang ini masalah-masalah yang berhubungan dengan kekerasan yang terjadi di rumah tangga, termasuk kekerasan anak sudah resmi menjadi bagian dari perbuatan kriminal. Maka bagi para orang tua bisa ditangkap dan dipenjara jika melakukan kekerasan terhadap anak. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah, walaupun UU KDRT sudah resmi disahkan tetap saja masalah kekerasan dalam rumah tangga meningkat dengan jumlah yang tidak signifikan.Tetap saja setiap hari ada kasus di mana anak-anak menjadi korban dari penganiayaan yang mengerikan dan bahkan yang menganiaya anak tersebut adalah orang terdekatnya dan lebih parahnya lagi adalah orang tua dari anak tersebut. 3 http://www.liputan6.com, diakses 19 Agustus 2008. 90 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya Berdasarkan fakta, tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta yang tidak tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, dan seksual), selain tidak tersembunyikan lagi, juga membawa dampak yang permanen dan berjangka panjang. Serta di sisi lain, berbagai macam dan ragamnya pelanggaran terhadap hak anak yang semakin tidak terkendali, mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.4 II. PEMBAHASAN Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus citacita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hakhak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. non-diskriminasi; b. kepentinganyang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan; d. penghargaan terhadap pendapat anak. 4 Seto Mulyadi, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Stop Kekerasan Pada Anak, http://www.eramuslim.com, diakses 19 Agustus 2008). JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 91 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Dasar yuridis dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain: 1. Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28I ayat (4), (5) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immedeiate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Perbincangan tentang hak kodrati atau hak asasi manusia memang sudah sering dikalangan filsuf dan ahli hukum, namun baru pada beberapa dekade belakangan gagasan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari kosakata masyarakat luas di sebagian besar kawasan dunia (James W. Nickel, 1996: xi). Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi. Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia. Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku. Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan. Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia internasional. Lebih 92 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi pada era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) Internasional menentukan adanya Jus Cogen yang dikualifikasikan sebagai a peremtory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character.5 Sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen Hukum Internasional setidak-tidaknya telah melampauai tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah: Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era ‘enlightenment’ di Eropah, meningkat menjadi dokumen-dokumen Hukum Internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada persitiwa penandatangan naskah Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggeris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan Decalaration of Independence, dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya ‘International Couvenant on Economic, Social and Cultural Rights’ pada tahun 1966. Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau ‘rights to development’. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.6 Terkait dengan perkembangan generasi hak asasi manusia tersebut, bahwasannya perlindungan hak asasi anak dari tindakan kekerasan sejatinya adalah penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, karena konsep perlindungan hak asasi manusia tidak mengenal batas usia, ras, agama, warna kulit, dan status sosial. Penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia ini termasuk kedalam perkembangan hak asasi manusia generasi pertama. Sejarah menunjukkan bahwa puncak perkembangan hak asasi 5 6 vide Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990: 108 dalam Artidjo Alkostar 2007, http://pushamuii.org, diakses 18 Agustus 2008. Jimly Asshiddiqie, Dimensi Konseptual Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, http://www.theceli.com, diakses tahun 2006. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 93 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 manusia generasi pertama ini adalah pada persitiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi PBB tahun 1948 ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Lahirnya deklarasi ini mencerminkan bahwa negara-negara (masyarakat internasional) yang ada di dunia sangat sadar bahwa harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi, dalam arti harus dihargai, dihormati, serta dilindungi. Mukadimah naskah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 menyebutkan beberapa hal penting, yaitu: Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa, Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan, Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan, Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas, Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka, Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia: Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. 94 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya Secara spesifik perlindungan individu dari tindakan kekerasan terdapat dalam Pasal 5 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948, yang menyatakan: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Pernyataan pasal di atas menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, seperti misalnya disiksa, dianiyaya, dihukum secara tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya, dengan tidak mengenal batas usia, ras, warna kulit, agama, dan status sosial. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan kekerasan yang diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948 ini sangat terkait dengan perlindungan hak asasi anak dari tindakan kekerasan. Penyiksaan atau penganiyaan kepada anak-anak dapat mengambil bermacam-macam bentuk: mungkin dilakukan dengan sengaja, tak terelakkan atau karena situasi.7 Secara spesifik perlindungan hak asasi anak dari tindakan kekerasan telah pula diatur dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989. Dalam mukadimah Konvensi Hak-hak Anak ini, disebutkan beberapa hal penting antara lain: Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain, Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan BangsaBangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus, Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya didalam masyarakat, Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian, Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas, 7 Peter Davies (ed), 1991, Human Rights, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Hak-hak Asasi Manusia, penerjemah: A. Rahman Zainuddin,Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1994, h.63. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 95 KERTHA PATRIKA - - - • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak, Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, ”anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”, -Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata, Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang. Bukan orang dewasa saja yang mempunyai hak, anak-anakpun mempunyai hak. Hakhak untuk anak-anak ini telah diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa, memiliki 4 (empat) hak dasar yaitu : • Hak Atas Kelangsungan Hidup Termasuk di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perwatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. • Hak Untuk Berkembang Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. • Hak Partisipasi Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orangtua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak. • Hak Perlindungan Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur.8 8 (http://yuwielueninet.wordpress.com, diakses 18 Agustus 2008). 96 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya Penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak asasi anak dari tindakan kekerasan atau penganiyayaan secara tegas diatur dalam Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak Anak dalam pasal-pasal sebagai berikut: - Pasal 2 Konvensi: 1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak. 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak. - Pasal 19 Konvensi: 1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, lukaluka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. 2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedurprosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yagn digambarkan sebelum ini, dan sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan. - Pasal 37 Konvensi: Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: (a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan... Dari paparan beberapa pasal konvensi tersebut, terlihat jelas bahwa negara termasuk juga warga negara (masyarakat) wajib memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak dari tindakan kekerasan baik yang bersihat pisik maupun psikis. Penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang diatur dalam instrumen Hukum Internasional (Deklarasi dan Konvensi PBB) tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa instrumen hukum nasional kita dalam bentuk undang-undang, diantaranya adalah dengan diterbitkannya UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengoptimalkan pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap seluruh umat manusia yang ada di Indonesia. UU No. 39 Th. 1999 mengatur juga tentang hak anak, bahwasannya anak harus mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, termasuk dari tindakan kekerasan. Hak anak diatur dalam Pasal 52 UU No. 39 Th. 1999 yang menyatakan: JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 97 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan terhadap hak asasi anak, khususnya perlindungan dari tindakan kekerasan secara lebih lengkap diatur didalam UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: - Pasal 1, angka 2: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. - Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. - Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. - Pasal 13: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Anak mempunyai posisi yang sangat mulia sesuai dengan penjelasan No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-undang 98 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional I Gede Pasek Eka Wisanjaya Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih memerlukan suatu undangundang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. III. SIMPULAN Anak mempunyai posisi yang sangat mulia karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap hak asasi anak sangat jelas diatur dalam instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Dalam instrumen hukum internasional diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 tentang Hak Anak, demikian pula dalam instrumen hukum nasional diatur dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam beberapa undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak IV. SARAN 1) 2) Pemerintah harus secara kontinyu mensosialisasikan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami isi atau substansi dari undang-undang tersebut, sehingga hal ini akan mencegah atau meminimalisasi tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Lembaga atau komisi perlindungan anak harus terus tanggap dan bekerja secara efektif dan maksimal dalam melindungi hak asasi anak serta memonitor pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak di masyarakat, sehingga harkat dan martabat anak benar-benar terjaga dan terlindungi. DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Artidjo Alkostar, 2007, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia, Cetakan ke: I, PUSHAMUII, Yogyakarta, http://pushamuii.org/index.php?lang=id&page=buku&id=22, diakses 18 Agustus 2008. James W. Nickel, 1987, Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection On The Universal Declaration Of Human Rights, University Of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 99 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Universal Hak Asasi Manusia, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, 1996, Jakarta. Peter Davies (ed), 1991, Human Rights, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Hak-hak Asasi Manusia, penerjemah: A. Rahman Zainuddin,Yayasan Obor Indonesia, 1994, Jakarta. B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. C. Artikel Gde Made Swardhana, Upaya Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, makalah disampaikan pada Lokakarya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Bali, untuk Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, yang diselenggarakan Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali di Denpasar, 18 Oktober 2005. http://www.liputan6.com/news/?id=162531&c_id=3, diakses 19 Agustus 2008. http://yuwielueninet.wordpress.com/2008/08/05/ hak- hak- anak/, diakses 18 Agustus 2008. Irwanto, Pelaku Kekerasan Pada Anak : Apakah Hukuman Saja Cukup?, http://himpsijaya. org/2006/10/21/ pelaku- kekerasan- pada- anak- apakah-hukuman-saja-cukup/, diakses 19 Agustus 2008. Jimly Asshiddiqie, Dimensi Konseptual Dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, Makalah Dalam Rangka Diskusi Terbatas Tentang Perkembangan Pemikiran Mengenai Hak Asasi Manusia, Yang Diadakan Oleh Institute For Democracy And Human Rights, The Habibie Center, April 2000, http://www.theceli. com/dokumen/produk/jurnal/jimly/j009.htm, diakses tahun 2006. Seto Mulyadi, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Stop Kekerasan Pada Anak, http://www. eramuslim.com/berita/nas/8721114129 -kak- seto- stop -kekerasan- pada-anak.htm, diakses 19 Agustus 2008. Seto Mulyadi, Kekerasan Pada Anak, http://www.mail-archive.com/dharmajala@yahoogroups. com/msg03716.html, diakses 19 Agustus 2008. 100 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Oleh : Cokorda Istri Anom Pemayun (Bagian Hukum Administrasi Negara FH-Unud) Abstract The implementation of decentralization and deconcentration principle in province underlied by law number 32 year 2004 has engendered a governor in two rules comprising head of province all at once as central government representatives. In his rules a central government representative, emerged subordination relation beetwen governor and major. Key words ; Implementation, Governor Position, subordination relation I. PENDAHULUAN Sejalan dengan maksud pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pasang surut dalam beberapa dekade penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi dan dekonsentrasi adalah azas utama pemerintahan daerah. Desentralisasi selalu bermakna penyerahan sejumlah urusan kepada daerah atau pengakuan bahwa daerah dapat menyelenggarakan sejumlah urusan yang bukan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dekonsentrasi bermakna pelimpahan wewenang kepada pejabat pemerintah di daerah. Dekonsentrasi juga dapat bermakna sebagai penyebaran fungsi-fungsi (pemerintah) secara berjenjang dan meluas pada organisasi yang bernaung di bawah jenjang itu (seperti instansi vertikal pada masa lalu).1 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepada wilayah. Azas ini menjadi dasar pembentukan wilayah, sebagai lingkungan kerja perangkat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Secara hierarkhis yang dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi terdiri dari provinsi, kabupaten/kotamadya, kota administratif dan kecamatan. Wilayah administratif pada tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya berhimpitan (fused model) dengan daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Wilayah-wilayah administratif yang dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi itu adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 secara eksplisit mengatur dan membangun konsep dekonsentrasi sebagai suatu azas yang menjadi dasar pembentukan wilayah kerja pemerintah pusat di daerah yang melaksanakan 1 Ateng Syafrudin, 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, Bandung: Tarsito,h. 14 JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 101 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 tugas pemerintahan umum. Urusan-urusan dekonsentrasi adalah urusan-urusan pemerintahan umum, yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, pembinaan politik dalam negeri, koordinasi, pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak menjadi urusan rumah tangga daerah dan bukan menjadi urusan instansi vertikal.2 Konsep pemerintahan umum yang dikonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sesungguhnya telah berakar sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda (dezentralisatie wet 1903) yang dikenal sebagai algemeen bestuur, yang berhubungan dengan tugas-tugas aparatur negara, tidak menjadi urusan departemen tertentu, tetapi fungsi dan tugas gewestelijke bestuurshoofden (kepala wilayah) yang bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Pembentukan instansi-instansi vertikal di daerah terutama setelah ditetapkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tidak menghilangkan fungsi-fungsi pemerintahan umum, tetapi telah membatasi ruang lingkup urusan pemerintahan umum yang sebelumnya bersifat bebas (vriijbestuur). Urusan kepolisian dan justisi pada masa pemerintahan Hindia misalnya, kemudian dipisahkan dari pemerintahan umum dengan terbentuknya lembaga-lembaga kepolisian dan peradilan. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, adakalanya kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan umum diinkorporasikan dalam badan-badan daerah otonom atau diserahkan kepada daerah. Jika penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menganut azas dekonsentrasi sebagaimana terdapat pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, maka tugas-tugas pemerintahan umum dilaksanakan oleh kepala daerah. Meskipun dalam prakteknya pejabat pamong praja tetap melaksanakan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat yang melaksanakan juga tugas-tugas pemerintahan umum.3 Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut azas desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan pada semua jenjang pemerintahan. Dalam undang-undang ini secara lengkap diatur bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup dekonsentrasi. Konstruksi dekonsentrasi yang dianut sebenarnya tetap relevan dalam pergeseran politik desentralisasi yang terjadi. Akan tetapi, konstruksi ini tidak berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bahkan undang-undang ini, meskipun menyebut dekonsentrasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, tetapi tidak mengaturnya secara eksplisit. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi mengatur tentang ruang lingkup urusan-urusan dekonsentrasi, tidak memiliki dasar pengaturan cakupan dekonsentrasi sehingga penetapan ruang lingkup dekonsentrasi tidak tepat sasaran, karena di dalamnya tidak sepenuhnya memuat aspek-aspek pemerintahan umum yang disebut sebagai kewenangan dekonsentrasi. Bahkan pada Peraturan Pemerintah ini terdapat kejanggalan karena urusan otonomi dimasukkan sebagai aspek dekonsentrasi seperti pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengulangi kesalahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam ketentuan umum dijelaskan pengertian dekonsentrasi, tetapi sama sekali tidak mengaturnya dalam batang tubuh undang-undang. Undang-undang ini tidak mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas dekonsentrasi. Ada kecenderungan menafsirkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagian diatur pada pasal 217 sebagai urusan dekonsentrasi. Akan tetapi, hendaknya dipahami bahwa pembinaan dan pengawasan itu hanya salah satu aspek dalam dekonsentrasi yang termasuk dalam pemerintahan umum. Formulasi atas urusan-urusan dekonsentrasi perlu dilakukan agar pelaksanaannya efektif. 2 3 Kansil, C.S.T.,1979. Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Aksara Baru,h. 47 Ibid,h. 22 102 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Cokorda Istri Anom Pemayun Meskipun tidak terdapat kaidah pengaturan yang menjadi dasar penyusunan aturan pelaksanaan, tetapi kehadiran suatu peraturan pemerintah sangat urgen dan mendesak. Urgensi ini mendorong pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan pemerintah ini selain kurang memiliki konsep yang jelas tentang dekonsentrasi, juga tidak tampak secara eksplisit hubungan antara dekonsentrasi dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah. Oleh karena itu, perlu pengaturan kedudukan gubernur sebagai pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. II. URGENSI PENGATURAN 1. Urgensi normatif Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur kedudukan kepala wilayah (gubernur, bupati/walikota dan camat) sebagai wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan pemerintahan umum, meliputi pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Pada penjelasan undang-undang ini, tugas dan wewenang kepala wilayah dirinci secara jelas, sehingga urgensi pengaturan dalam suatu peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatnya tidak lagi diperlukan. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meskipun gubernur tetap dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat karena azas dekonsentrasi dianut di provinsi, tetapi tidak mengatur secara lengkap tugas dan kewenangan gubernur dalam konteks dekonsentrasi. Bahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya mencantumkan azas dekonsentrasi di dalam ketentuan umum dan tidak mengaturnya dalam batang tubuh undang-undang. Pengaturan tentang dekonsentrasi yang tidak lengkap pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menimbulkan ketidakjelasan konstruksi dekonsentrasi yang berimplikasi pada pengaturan dekonsentrasi yang kurang tepat dan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat dielaborasi secara lengkap dengan hanya menggunakan pengaturan yang terbatas dalam undang-undang. Urgensi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi telah mendorong pemerintah pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, di tengah ketiadaan dasar pengaturan. Seharusnya pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi dasar pengaturan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh gubernur, dan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dilihat dalam konteks dekonsentrasi. Oengan demikian, tidak perlu pengaturan yang khusus tentang dekonsentrasi dalam suatu peraturan pemerintah yang berbeda dengan pengaturan tentang kedudukan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat. Pasal 38 ayat (4) mengatur bahwa tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain urgensi normatif pengaturan menurut pasal ini, peraturan pemerintah tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dapat meletakkan hubungan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam konteks dekonsentrasi, sehingga terdapat keterkaitan yang tidak sating meniadakan atau tidak saling bertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 dengan peraturan pemerintah tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang akan ditetapkan kemudian. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 103 KERTHA PATRIKA 2. • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Urgensi Politik. Secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menggeser pola hubungan pusat dan daerah dari dominasi pusat ke diskresi daerah. Perubahan format hubungan ini kemudian menimbulkan berbagai ekses dalam implementasinya yang menimbulkan ketidakserasian hubungan antara pusat dan daerah. Pusat beranggapan bahwa pergeseran format itu telah menimbulkan egosentris daerah yang cenderung mengancam hubungan antar pemerintahan, sedangkan daerah beranggapan bahwa pemerintah pusat masih tidak berubah dan cenderung sentralistik. Penataan hubungan antara pusat dan daerah urgen dilakukan agar hubungan yang proporsional dan serasi dapat dipelihara. Meskipun hubungan daerah terhadap pusat tetap berada dalam subordinasi, tetapi pengaturan interaksi antara pusat dan daerah yang saling mempercayai secara timbal balik (reciprocal trust) perlu dibangun.4 Penataan hubungan pemerintah dengan gubernur sebagai wakil pemerintah, selain dapat menghindari terjadinya salah pengertian yang menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang cenderung terjadi saat ini, juga akan menjamin efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang selama ini cenderung terbengkalai. Dalam hubungan antar daerah, pengaturan kedudukan gubemur sebagai wakil pemerintah pusat akan memberi kejelasan hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota yang cenderung tidak harmonis. Kabupaten/kota beranggapan bahwa pemerintah provinsi memasuki area urusan otonomi kabupaten/kota, sementara pemerintah provinsi beranggapan bahwa pemerintah kabupaten/kota lepas kendali. Hal ini disebabkan kevakuman aturan pelaksanaan yang cukup lama di dalam penyelenggaraan azas dekonsentrasi yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota. Sebagai daerah otonom, provinsi dan kabupaten/kota adalah setara. Konsekunsi kedudukan yang setara adalah pengakuan bahwa masing-masing daerah otonom merupakan organisasi yang otonom. Masing-masing daerah otonom memiliki kedudukan yang mandiri (zelf-standing). Hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota tidak bersifat hierarchische gebondenheid dan pejabat-pejabat yang ada di kabupaten/kota tidak dapat dianggap berada pada posisi arnbtelijk ondergeschikt kepada pejabat-pejabat provinsi. Dianutnya azas desentralisasi dan dekonsentrasi di provinsi menempatkan gubernur pada posisi dua peran (dual role) yaitu sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, terbentuk hubungan subordinasi antara gubernur dengan bupati/walikota.5 Hubungan yang terbentuk berdasarkan azas dekonsentrasi yang diletakkan pada provinsi menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota yang bersifat fungsional. Kewenangan yang melekat pada gubernur sebagai wakil pemerintah tidak identik dengan campur tangan gubernur terhadap urusan otonomi kabupaten/kota, tetapi hubungan yang terbentuk bersifat hirarkhis, subordinasi karena gubernur menjalankan fungsi pemerintah pusat terhadap kabupaten/kota. 3. Urgensi administrasi 4 5 Kavanagh, 1985. British Politics Continuities and Change, Oxford University Press, h.116. Peter Blau, M., & Richard A.S.1971.The Structure of Organization, New York: Basic Books, Inc,h. 115. 104 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Cokorda Istri Anom Pemayun Dari perspektif administrasi pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan memberi kejelasan ruang lingkup tugas dan wewenang, pengorganisasian dan pembiayaan. Ketidakjelasan ruang lingkup tugas dan wewenang akan dapat menimbulkan ketidakpastian tindakan yang dapat berakibat gubernur memasuki ranah urusan otonomi kabupaten/kota atau tugas yang seharusnya dijalankan dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat tidak terlaksana dengan baik. Tugas dan wewenang hanya akan terlaksana dengan efektif jika diikuti dengan pengorganisasian yang relevan. Fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi menjadi dasar pengorganisasian ke dalam satu unit kerja yang fungsional, dan secara spesifik melaksanakan tugas-tugas yang dielaborasi dari fungsi-fungsi yang ada. Urgensi administrasi terletak pada pengaturan fungsi-fungsi ke dalam satuan kerja yang melaksanakan tugas-tugas yang didekonsentrasikan kepada gubernur, bukan ke dalam unit kerja yang melaksanakan urusanurusan daerah. Selain menghindari terjadinya duplikasi, pengorganisasian ke dalam satuan kerja yang berbeda dengan SKPD, juga akan lebih menjamin efektivitas kinerja pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Pada aspek pembiayaan, urgensi pengaturan terletak pada jaminan pelaksanaan tugas-tugas secara berkelanjutan dengan dukungan anggaran yang pasti dan sepadan. III. LANDASAN NORMATIF PENGATURAN Pembagian wilayah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 didasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen). Penjelasan pasal 18 menunjukkan bahwa daerah-daerah yang dibentuk bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka. Daerah yang dibentuk berdasarkan azas desentralisasi disebut daerah terdiri dan daerah tingkat I dan daerah tingkat II, sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi disebut wilayah yang tersusun secara vertikal merupakan lingkungan kerja pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Kepala daerah menjalankan dua fungsi (dual role), yaitu fungsi sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah, dan fungsi kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Kedudukan gubernur sebagai kepala wilayah yang menyelenggaran tugas-tugas pemerintahan umum, tetap relevan dan menjamin konstruksi pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah. Tugas dan wewenang yang dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah terbentuk karena urusan dekonsentrasi yang diletakkan pada provinsi, tugas dan wewenang dimaksud adalah tugas dan wewenang yang termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara jelas mengatur tugas pemerintahan umum sebagai dekonsentrasi tetapi pengaturan tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah harus diletakkan dalam konteks pemerintahan umum. Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan dekonsentrasi karena tidak ada perintah dalam kedua pasal tersebut yang mengharuskan pengaturan dekonsentrasi. Kedua pasal dimaksud lebih tepat menjadi kaidah pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan mestinya pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dipahami sebagai dekonsentrasi. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 105 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Urgensi normatif pengaturan terletak pada mendudukan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam konteks dekonsentrasi. Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus dipahami sebagai pengaturan tentang dekonsentrasi yang member! kedudukan pada gubernur untuk menjalankan tugas dan wewenang pembinaan, pengawasan dan koordinasi atas jalannya pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sebagai aspek-aspek pemerintahan umum. IV. ASPEK-ASPEK YANG DIATUR Pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mencakup aspek-aspek ruang lingkup tugas dan kewenangan, pengorganisaian, dan pembiayaan. 1. Tugas dan Kewenangan. Berdasarkan konstruksi tugas dan wewenang yang melekat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, baik yang melekat (atributif) maupun yang dilimpahkan kepada gubernur (delegatif), aspek-aspek kewenangan yang perlu diatur meliputi kedua bentuk tugas dan kewenangan dimaksud. a. Tugas dan kewenangan atributif Tugas dan kewenangan atributif adalah tugas yang dapat dikategorikan sebagai tugastugas yang diserahkan kepada gubernur karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah. Tugas ini tidak didasarkan pada pelimpahan tetapi melekat pada jabatan gubernur, meliputi tugas dan kewenangan sebagai berikut. 1) Pembinaan politik dalam negeri, mencakup segala upaya pembinaan ideologi negara, politik dalam negeri, dan kesatuan bangsa sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi kegiatan: upaya-upaya pengamanan dan pengamalan ideologi negara, upaya-upaya menciptakan politik dalam negeri yang stabil, upaya-upaya pembinaan kesatuan bangsa. 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, mencakup segala upaya untuk menciptakan suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur sesuai kebijakan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan pemerintah, meliputi kegiatan: upaya-upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap bentuk pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggungan ketentaram dan ketertiban masyarakat. upaya-upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh bencana. upaya-upaya pengaturan untuk mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. upaya-upaya pengaturan kegiatan dalam rangka penaggulangan bencana. 3) Koordinasi, mencakup segala upaya untuk menciptakan integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intansi vertikal dan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai dayaguna dan hasilguna yang optimal, meliputi kegiatan: 106 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Cokorda Istri Anom Pemayun - 4) 5) membentuk forum bersama antara gubernur dengan instansi vertikal dalam rangka pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan urusan-urusan instansi vertikal dan urusan pemerintah provinsi. membentuk forum bersama antara gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi. Pengawasan, mencakup segala upaya membimbing dan mengarahkan agar tercipta keserasian antara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berhasilguna dan berdayaguna, meliputi kegiatan: Pengawasan umum, yaitu upaya-upaya untuk menjamin tertib pemerintahan agar tercipta keserasian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan preventif, yaitu tindakan melakukan pengesahan terhadap produk hukum daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengawasan represif. yaitu tindakan melakukan penangguhan atau pembatalan terhadap produk hukum daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Tampungtantra (vrijbestuur), mencakup segala tindakan yang dilakukan terhadap pelaksanaan suatu tugas yang nyata-nyata tidak menjadi tugas atau tidak dapat dilaksanakan oleh instansi vertikal dan tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tampungtantra, dengan alasan keterbatasan jangkauan terhadap pelaksanaan tugas tampungtantra, gubernur dapat menunjuk pejabat yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tampungtantra dimaksud. Aspek Kewenangan delegatif Kewenangan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh departemen teknis, meliputi aspek-aspek pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan urusan-urusan daerah menurut bidang-bidang departemen teknis, maupun pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Tugas dan kewenangan delegatif meliputi: 1) Pembinaan, mencakup kegiatan fasilitasi, supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota. a) Supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan: Memberi arah bagi keterpaduan perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota. Memberi bimbingan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa. b) Asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan: pemberian bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk bimbingan teknis perencanaan, pengorganisasian dan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 107 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 - 2) 2. pemberian bantuan administratif kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk penyebarluasan norma dan standarisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan sistem pelaporan. c) Fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, instansi vertikal, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan: Menyediakan sarana pendukung dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota yang berdayaguna dan berhasilguna. Melakukan kegiatan dalam bentuk forum-forum bersama antara instansi tingkat provinsi, antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar kabupaten/kota. Membantu memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas instansi vertikal, dan penyelenggaraan tugas-tugas urusan pemerintah kabupaten/kota, serta pelaksnaaan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa. d) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, instansi vertikal, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan: 1. melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan strandar penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 2. melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota dan desa. 3. melakukan penilaian terhadap penerapan norma dan strandar, dan penilaian kesesuaian antara rencana dengan hasil, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, dan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota dan desa. Pengawasan delegatif dapat berbentuk represif maupun preventif terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota menurut norma dan standar penyelenggaraan bidang-bidang yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, meliputi: upaya-upaya untuk menjamin tertib penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan norma dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. upaya-upaya untuk mengambil tindakan penyesuaian terhadap penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak berdasar pada norma dan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pengorganisasian Penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat hanya dapat efektif jika didukung yang relevan. Dalam melakukan pengorganisasian didahului dengan identifikasi terhadap fungsi-fungsi yang melekat pada kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menurut pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, fungsifungsi dimaksud mencakup pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Ketiga fungsi dimaksud menjadi dasar pengorganisasian ke dalam satu unit kerja yang fungsional, dan secara spesifik melaksanakan tugas-tugas yang dielaborasi dari fungsi-fungsi yang ada. Dalam pengorganisasian hendaknya didasarkan pada pertimbangan departementasi fungsi. 108 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Implementasi Yuridis Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Cokorda Istri Anom Pemayun Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan kesamaan sifat atau kesamaan dalam pelaksanaannya. Dalam departementasi fungsi perlu diperhatikan pengelompokan aktivitas ke dalam satuan-satuan organisasi berdasarkan kesamaan sifat dan kesamaan pelaksanaannya, menghindari pembentukan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi ganda. Berdasarkan argumen ini, pengorganisasian dilakukan terhadap fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi ke dalam satuan kerja. Fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi berdasarkan argumen dekonsentrasi dapat berbentuk fungsi yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Fungsi atributif, berarti tugas dan kewenangan gubernur yang dapat dikategorikan sebagai tugas-tugas yang melekat pada gubernur karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, meliputi pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pengawasan, dan koordinasi. Fungsi bersifat delegatif mencakup tugas dan kewenangan yang didasarkan pada pelimpahan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dalam bentuk pembimaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengorganisasian hendaknya dilakukan ke dalam dua bentuk pilihan. Pertama, tugas dan kewenangan yang bersifat atributif tidak dimasukan ke dalam unit kerja yang melaksanakan urusan-urusan daerah, atau bukan menjadi SKPD, untuk menjamin pengelompokan aktivitas ke dalam unit kerja yang memiliki kesamaan sifat dan kesamaan pelaksanaan dan menghindari terjadinya fungsi ganda (duplikasi). Pengorganisasian tersediri akan lebih menjamin efektivitas kinerja pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Pembentukan organisasi di luar SKPD dimungkinkan menurut pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang mengatur bahwa daerah dapat membentuk lembaga lain untuk melaksanakan peraturan perundangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. Kedua, tugas dan kewenangan yang bersifat delegatif diintegrasikan ke dalam unit kerja pelaksana urusan daerah (operating core) yang memiliki kesamaan sifat. Berdasarkan pertimbangan pengorganisasian yang relevan dan departementasi fungsi serta peluang pengorganisasian tersediri, satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka pengorganisasian dilakukan dalam bentuk direktorat-direktorat, sebagai unit kerja baru yang dibentuk untuk melaksanakan dua jenis tugas. Pertama, tugas-tugas pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pelimpahan urusan dari departemen teknis (delegative), berupa supervisi, asistensi dan fasilitasi. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebenarnya telah terdapat unit kerja yang ditempatkan sebagai bagian dari SKPD, yaitu badan kesatuan bangsa. Agar pengorganisasian dekonsentrasi menjadi jelas, maka Badan Kesbang direposisi dari SKPD menjadi satuan kerja dekonsentrasi (SKD) dengan sebutan direktorat pembinaan kesatuan bangsa yang melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan pembinaan politik dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pembinaan ketentraman dan ketertiban dibentuk direktorat pembinaan ketentraman dan ketertiban. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk direktorat bina pemerintahan daerah. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 109 KERTHA PATRIKA • VOLUME 34 NOMOR 1 • JANUARI 2010 Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang didasarkan pada pelimpahan dalam bentuk pembinaan teknis penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah kabupaten/kota tidak didasarkan pada pembentukan unit kerja direktorat baru, tetapi dikoorporasikan ke dalam SKPD yaitu ke dalam tugas pokok dinas dan lembaga teknis daerah (existing). Tugas-tugas yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat hanya mencakup pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten/kota dan atas tugas pembantuan. Seluruh tugas dimaksud menjadi tugas pokok tambahan dalam rangka dekonsentrasi dinas dan lembaga teknis yang melaksanakan fungsi sejenis atau serumpun. V. PENUTUP Kebutuhan pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah urgen segera dilakukan agar tugas-tugas pemerintah pusat di daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Pada sisi lain, pengaturan ini diharapkan akan dapat dipedomani dalam tautan hubungan provinsi dengan kabupaten/kota yang akhir-akhir ini cenderung mengarah pada konflik. Pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah mencakup pengaturan tugas dan wewenang gubernur yang bersifat atributif dan delegatif. Konstruksi tugas dan wewenang ini menjadi dasar pengaturan pengorganisasian satuan kerja dekonsentrasi yang selama ini telah menimbulkan kerancuan yang berakibat pada ketidakjelasan pelaksanaan dekonsentrasi dan alokasi pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu pengaturan peraturan pemerintah tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu segera dilakukan. DAFTAR PUSTAKA Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, Tarsito, Bandung, 1976. Kavanagh, British Politics Continuities and Change, Oxford University Press, 1985. Kansil, C.S.T., Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1979. Lemans, A.F., Changing Pattern of Local Government, The Hauge, IULA, 1971. Peter Blau, M., & Richard A.S., The Structure of Organization, Basic Books, Inc., New York, 1971. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, FKAIIP, Jakarta, 2004. 110 • JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM Petunjuk Bagi Penulis 1. 2. 3. 4. 5. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas A4, panjang 15-20 halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah dan CD dengan pengelolaan kata MS Word, font Times New Roman, size 12. bahasa Inggris dengan standar penggunaan bahasa yang baik dan benar. Artikel yang dibuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hokum, baik sebagai hasil penelitian atau artikel ilmiah konseptual. Tulisan hasil penelitian/tesis/disertai disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) nama pengarang (disertai identitas diri), (c) abstrak (bahasa Inggris untuk tulisan berbahasa Indonesia atau bahasa Indonesia untuk tulisan berbahasa Inggris) , berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), (d) kata-kata kunci, (e) pendahuluan, berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan-tujuan penelitian, (f) metode penelitian, (g) hasil dan pembahasan, (h) simpulan dan saran, (i) daftar pustaka. Tulisan artikel ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) Judul, (b) nama pengarang, (c) abstrak (bahasa Inggris untuk tulisan berbahasa Indonesia atau bahasa Indonesia untuk tulisan berbahasa Inggris) berisi pemadatan tujuan penulisan dan hasil pembahasan (50-100 kata), (d) pendahuluan, berisi latar belakang dan perumusan masalah, (e) pembahasan, (i) daftar pustaka. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dalam tulisan dengan sistem foot note. Contoh : Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm .26 Suparman Marzuki, “Hukum Modern dan Institusi Sosial”, artikel dalam Jurnal Hukum, No. 7 hlm.35. Erman Radjaguukguk, ”Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak”, makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departeman Kahakiman, 1996, hlm.5. ”Jurnal BUMN Diciutkan Jadi 50”, Republika, 19 Oktober 2005. Prijono Tjiptoherijanto, ”Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia”, http://www.pk.ut. ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2006. Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan dari De Structuur de Rechstwetenschap, Alih Bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003) , hlm.9. 6. 7. 8. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan jumlah minimal 10 judul. Penulis melampirkan biodata singkat penulis yang berisi: nama lengkap dengan gelar, alamat rumah, tempat bekerja, dan alamat e-mail. Tulisan dialamatkan kepada: Sekretariat Jurnal Hukum Kertha Patrika, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Jl. Bali Denpasar. Contact Person: Kadek Sarna, HP. 081578555 atau IGN Parikesit Widiatedja, HP. 081803861749 Atau dikirim melalui email ke alamat: [email protected]. JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM • 111