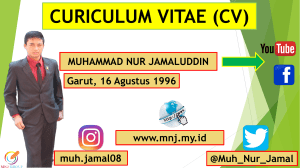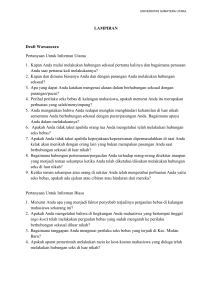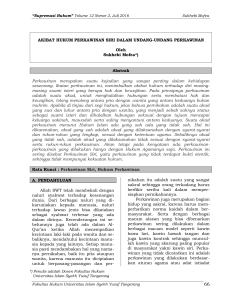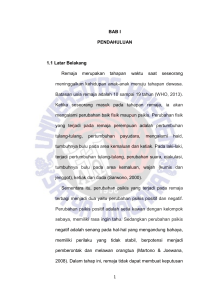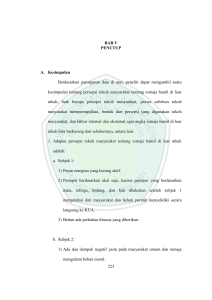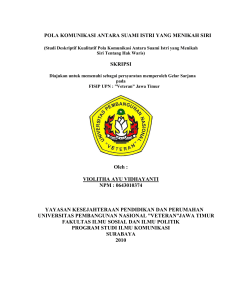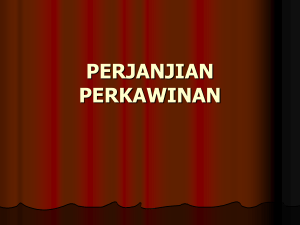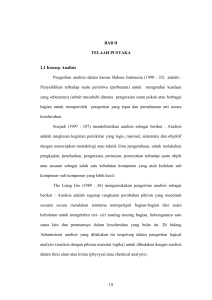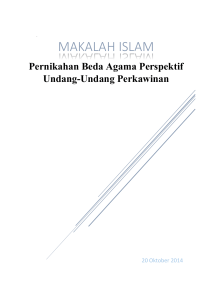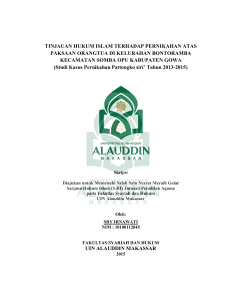praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri
advertisement

PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK SERTA HARTA KEKAYAANNYA (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Oleh: M. Mashud Ali NIM 107043203400 KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2014 M ABSTRAK M. Mashud Ali. NIM 107043203400. PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK SERTA HARTA KEKAYAANNYA (ANALISIS PERBANDINGAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF). Konsentrasi Perbandingan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2014 M. IX + 63 halaman. Masalah utama dari penelitian ini adalah tentang akibat perkawinan siri. Dari hasil penelitian, perkawinan siri memiliki banyak akibat negatif, misalnya bagi status istri, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah di mata hukum yang berakibat pada hak-hak istri tidak terjamin secara hukum. Begitu juga dengan anak, di mata hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya. Adapun tujuan yang diharapkan dapat dijangkau dan dihasilkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fikih atau hukum Islam terhadap status perkawinan siri, pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap status perkawinan siri dan akibat hukum dari perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, serta harta kekayaannya. Sedangkan penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini secara spesifik adalah penelitian deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan masalah hukum yang ada, sistem hukum dan kemudian mengkajinya secara sistematis. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kata Kunci : Perkawinan Siri, Akibat Hukum, Istri, Anak, Harta Kekayaan. Pembimbing : Dr. H. Abd. Wahab Abd. Muhaimin, Lc., MA. Daftar Pustaka: Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2011. KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Rabbi al-‘Alamin, penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan dan membukakan hati serta pikiran penulis untuk menyelesaikan setiap proses dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita dapat merasakan indahnya Islam, iman dan ihsan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir dari penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. selaku mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 2. Bapak Dr. H. JM Muslimin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag. dan Bapak Fahmi Ahmadi, M.Si. selaku mantan Ketua dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. 4. Bapak Dr. Khamami Zada, MA. dan Ibu Siti Hanna, S.Ag., Lc., MA. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. 5. Bapak Dr. H. Abd. Wahab Abd. Muhaimin, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan hingga selesainya skripsi ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan mencurahkan tenaga serta pikirannya untuk mendidik kami. i 7. Pimpinan dan segenap staff Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini. 8. Ayahanda H. Ali Muhsin Zaini dan Ibunda tercinta Hj. Sufiyah sebagai tonggak semangat penulis, mereka yang tak kenal lelah terus memberikan doa, dukungan, nasehat, bimbingan serta motivasinya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi di perkuliahan ini dari awal hingga akhir. 9. Buat kakak-kakak yang selalu penulis banggakan, yaitu; Nur Azizah Ali beserta Ali Mahfud, Agus Abdillah Ali beserta Ida Fitri Royani, Malik Afan Ali beserta Diyah Sholihah, dan semua keponakan yang cantik-cantik dan lucu-lucu. 10. Buat para senior yang banyak mengajarkan tentang makna kehidupan (ngaji urip), antara lain; Uray Mashuri Abdurrahman, Uday Mashudi Abdurrahman, Nanang Syaiful Ghozi, Haji Silahuddin, Abdul Wahab, Zafar Sodik, Fuad Hadziq, dan Anang Lukman Afandi. 11. Buat teman-teman yang sempat hadir dalam kehidupan penulis yang penuh suka cita dan kebahagiaan, antara lain; Abd. Muktadir, Heri Sofyan Saury, Annisul Muttaqin, Akmaludin Siddiq, Ahmad Farhan, Abdul Rozak, Muhammad Masrur, Rofik Hidayat, Qiraatu Taslimah, Riyan Hidayat, Shofika Nurul Laili, Iza Zulfa Nuraini, Shohifatus Syifa, dan Salmi Hayati Alizar. 12. Buat teman-teman KAMAWANGI (Keluarga Besar Mahasiswa Banyuwangi), PMII Ciputat, Kelas PH 2007, KKN 80 2010, Keluarga Besar Mahasiswa PMH, Eljalabiyya Club dan semua teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan sumbangsihnya dicatat oleh Allah SWT sebagai bentuk amal kebaikan. Amin. Jakarta, 30 Desember 2014 M 8 Rabiul Awwal 1436 H Penulis ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 6 D. Studi Review Terdahulu ................................................................... 7 E. Metode Penelitian ............................................................................. 8 F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 9 BAB II : PERKAWINAN DALAM PANDANGAN FIKIH ......................... 11 A. Perkawinan Menurut Fikih ............................................................. 11 B. Hukum Perkawinan Menurut Fikih ................................................ 14 C. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fikih ................................... 17 D. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Fikih ............................ 21 BAB III : PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA ....................................................................................... 25 A. Perkawinan Menurut Hukum Positif .............................................. 25 B. Syarat dan Sahnya Perkawinan dalam Hukum Positif ................... 26 1. Syarat Perkawinan .................................................................... 26 2. Sahnya Perkawinan ................................................................... 28 iii C. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif ............................... 29 BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAANNYA .............................................................................. 38 A. Status Perkawinan Siri Menurut Fikih ........................................... 38 B. Status Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif ............................ 40 C. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta kekayaannya Menurut Fikih dan Hukum Positif ........... 42 1. Kedudukan Istri .......................................................................... 42 2. Kedudukan Anak ....................................................................... 45 3. Kedudukan Harta Kekayaan ...................................................... 51 BAB V : KESIMPULAN ................................................................................. 58 A. Kesimpulan .................................................................................... 58 B. Saran ............................................................................................... 60 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 61 iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.1 Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 1 Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 56. 1 2 keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.3 Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasangpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49: Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49) Dari mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dengan berpasangpasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa’, ayat 1: 2 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 40. 3 Sayyid Mujtaba Musavi Lari, Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 15. 3 Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1) Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.4 Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk 4 13. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 4 menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah.5 Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undangundang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan perkawinan siri. Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya 5 Muhammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 114. 5 nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. 6 Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak. Bagi suami perkawinan siri juga dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapat warisan. Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut. Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Sehingga penulis berinisiatif menulis skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan Siri serta Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)”. 6 Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 71. 6 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Mengingat begitu luasnya masalah perkawinan siri tersebut, penulis membatasi dengan pokok permasalahan, yaitu tentang perkawinan siri serta akibat yang terjadi terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya. Adapun perumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan, antara lain: 1. Bagaimana pandangan fikih terhadap perkawinan siri? 2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perkawinan siri? 3. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini, antara lain: 1. Mengetahui pandangan fikih terhadap perkawinan siri. 2. Mengetahui pandangan hukum positif terhadap perkawinan siri. 3. Mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini antara lain: 1. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang fikih dan hukum positif dalam hal perkawinan siri serta dampak hukumnya terhadap terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya. 7 2. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literatur serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan. 3. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang ingin melakukan perkawinan siri. D. Studi Review Terdahulu 1. Tindakan Perkawinan Siri di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, sebuah skripsi yang disusun oleh Achmad Husairi pada tahun 2010. Skripsi ini meneliti tentang perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Karang Tengah, berisi tentang faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, dampaknya bagi keluarga serta tindakan dan argumentasi masyarakat terhadap perkawinan siri. 2. Dampak Poligami Melalui Nikah Siri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sarua Indah Ciputat), disusun oleh Mirzan Ghulammahmad pada tahun 2009. Sebagaimana yang tercatat dalam judul, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sarua Indah Ciputat, yang meneliti dan mengkaji masalah poligami yang dilakukan dengan perkawinan siri serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. 3. Pengaruh Nikah Siri terhadap Kewarisan “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 921/Pdt. G/2007/PAJT”, yang disusun oleh Elluyah Al’aros pada tahun 2010. Skripsi ini mengkaji secara 8 detail Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor Perkara 921/Pdt. G/2007/PAJT tentang Sengketa Waris. Ketiga skripsi di atas, meskipun bertema serupa akan tetapi berbeda secara prinsip dan pembahasan dengan skripsi yang akan penulis bahas. Pertama, skripsi ini membahas tentang perkawinan siri dari segi fikih sekaligus hukum positif Indonesia. Kedua, analisis perbandingan perkawinan siri antara fikih dan hukum positif Indonesia. E. Metode Penelitian Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.7 Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: 1. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu terdiri dari Al-Quran, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini). 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain; tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini. 7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13. 9 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan library research atau studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif secara kualitatif yaitu membandingkan tinjauan fikih dan hukum positif terhadap permasalahan yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi yang ditertibkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press. F. Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab. Secara sistematis bab-bab itu terdiri dari: BAB I Pendahuluan Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi review terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Perkawinan dalam Pandangan Fikih Bab ini menguraikan tentang perkawinan menurut fikih, hukum perkawinan menurut fikih, rukun dan syarat perkawinan dalam fikih, serta pencatatan perkawinan dalam pandangan fikih. 10 BAB III Perkawinan dalam Pandangan Hukum Positif Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang perkawinan menurut hukum positif, syarat dan sahnya perkawinan dalam hukum positif, dan pencatatan perkawinan dalam hukum positif. BAB IV Analisis Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang status perkawinan siri menurut fikih, status perkawinan siri menurut hukum positif, dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, kedudukan anak serta kedudukan harta kekayaan menurut fikih dan hukum positif. BAB V Penutup Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran. BAB II PERKAWINAN DALAM PANDANGAN FIKIH A. Perkawinan Menurut Fikih Perkawinan atau pernikahan asal dari kata nikah, secara bahasa berarti himpunan (adh-dhamm), kumpulan (al-jam’u), atau hubungan intim (al-wath’u). Secara denotatif kata nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif kata nikah merujuk pada makna hubungan intim. Adapun nikah secara syar’i adalah akad yang membolehkan adanya hubungan intim dengan menggunakan kata menikahkan, mengawinkan, atau terjemah dari kedua kata tersebut.1 Sulaiman Rasjid menuturkan bahwa dalam hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fikih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”.2 Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami atau istri), sehingga status kepemilikan akibat akad tersebut bagi suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh yang lainnya, yang dalam term fikih disebut milku al-intifa’, yakni hak memiliki 1 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur’an dan Hadits, terj. Muhammad Afifi (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), hlm. 449. 2 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1993), hlm. 355. 11 12 penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (dalam hal ini adalah istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri. Bagi perempuan (istri), sebagaimana suami, ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologis yang sama. Akan tetapi, tidak bersifat khusus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini istri boleh menikmati secara biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri yang lain). Sehingga kepemilikan di sini hak berserikat antara para istri. Lebih jelasnya, poliandri tidak dipermasalahkan lagi hukumnya, yakni haram, dan sebaliknya poligami masih ada celah diperbolehkan secara syar’i.3 Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.4 Dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, 3 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan Antar Madzhab (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1. 4 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, hlm. 356. 13 hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberi jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.5 Oleh karena itu, perkawinan menurut hukum Islam merupakan sebuah ikatan lahir batin yang suci dan mulia antara pasangan pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yakni keluarga yang penuh ketenangan, penuh cinta kasih dan selalu mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Selain itu perkawinan merupakan sebuah ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. 5 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 2, hlm. 5. 14 B. Hukum Perkawinan Menurut Fikih Segolongan fuqaha, yakni Jumhur ulama, berpendapat bahwa nikah itu sunah hukumnya. Golongan Zhahiriy berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedang para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah bagi sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya lagi. Silang pendapat ini disebabkan, apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini harus diartikan wajib, sunah ataupun mubah.6 Perkawinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat, hukumnya termasuk anjuran (mustahab) bagi orang yang membutuhkan atau ingin berhubungan seksual dengan syarat mempunyai biaya nikah dan bertujuan demi menjaga agama, melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab serta mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:7 ّﯾﺎ ﻣﻌﺸﺮاﻟﺸّﺒﺎب ﻣﻦ اﺳﺘﻄﻊ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺒﺎءة ﻓﻠﯿﺘﺰوّج ﻓﺎءﻧّﮫ اﻏﺾ ﻟﻠﺒﺼﺮ واﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮج وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺼﻮم ﻓﺎءﻧّﮫ ﻟﮫ (وﺟﺎء )ﻣﺘّﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ Artinya:“Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan 6 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 222. 7 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur’an dan Hadits, hlm. 452. 15 memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat mengekang syahwat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Substansi dari hadis di atas secara nyata telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menikah dan menjaganya. Demikian pula, para sahabat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan melakukan pernikahan dan menjaganya, dan kebiasaan itu diikuti pula oleh umat beliau. Meneladani atas semua perbuatan yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa perkawinan menempati posisi hukum sunah. Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunah pula dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikit pun tidak dibenarkan Islam. AlThabarani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah SAW bersabda:8 (ان ﷲ اﺑﺪﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮّھﺒﺎﻧﯿّﺔ اﻟﺤﻨﻔﯿّﺔ اﻟﺴّﻤﺤﺔ )رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ Artinya:“Sesungguhnya Allah SWT menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”. (HR. At-Thabarani) Adapun jika seseorang tidak butuh menikah, tapi mempunyai biaya yang tidak bermasalah, sementara dia juga tidak serius dalam beribadah, nikah baginya lebih utama daripada tidak. Tujuannya agar waktu kosong tidak 8 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, hlm. 7. 16 membuatnya terjerumus dalam perbuatan keji (al-fawahisy). Akan tetapi nikah tidak dianjurkan bagi orang yang tidak punya biaya, justru orang tersebut dianjurkan tidak menikah dahulu.9 Sebagaimana firman Allah SWT dalam AlQuran Surat An-Nur ayat 33: Artinya:”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nur: 33) Dengan demikian, hukum perkawinan dalam Islam adalah sunah, tapi jika dikaitkan dengan kondisi seseorang maka hukum sunah tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi orang tersebut. Sebagaimana pandangan para 9 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur’an dan Hadits, hlm. 453. 17 ulama mutaakhkhirin (belakangan) dari mazhab Maliki yang berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah, dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Pendapat ini juga diikuti oleh pengikut Imam Syafi’i dan pengikut Imam Ahmad bin Hambal. 10 C. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fikih Suatu perkawinan atau pernikahan dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang jelas. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti menutup aurat untuk sholat. Adapun rukunnya nikah ada 5 (lima), yaitu shighat, calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan wali.11 1. Shighat Akad Nikah Shighat akad nikah adalah perkataan yang diucapkan pihak calon suami dan pihak calon istri pada waktu melakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan qabul ialah 10 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 1. 11 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur’an dan Hadits, hlm. 453. 18 pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi calon istrinya. 12 Shighat akad nikah harus diucapkan secara jelas (sharih), lengkap dengan ijab dan qabul sebagaimana akad yang lainnya. Shighat yang diucapkan wali misalnya adalah “aku kawinkan kamu dengan putriku” atau “aku nikahkan kamu dengannya”. Sedangkan shighat yang diucapkan suami adalah “aku kawini”, “aku nikahi”, atau “aku terima nikahnya atau kawinnya”.13 2. Calon Suami Adapun syarat-syarat calon suami antara lain: a. Beragama Islam. b. Bukan mahram dari calon istri dan calon suami tersebut jelas halal kawin dengan calon istri. c. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. d. Orangnya diketahui dan tertentu. e. Calon mempelai laki-laki tahu pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. f. Calon suami rela (tidak dipaksa atau terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri. 12 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 76. 13 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur’an dan Hadits, hlm. 454. 19 g. Tidak sedang melakukan Ihram. h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. i. Tidak sedang mempunyai istri empat. 3. Calon Istri Adapun syarat-syarat calon istri antara lain:14 a. Beragama Islam. b. Tidak ada halangan syar’i, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah. c. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci). d. Wanita itu tentu atau jelas orangnya. e. Tidak dipaksa (merdeka dan atas kemauan sendiri). f. Tidak sedang ihram haji atau umrah. 4. Dua Orang Saksi Syarat untuk dua orang saksi adalah merdeka, laki-laki, adil meski hanya dari segi dzahir, bisa mendengar, dan bisa melihat. Persaksian budak, wanita, orang fasik, orang tuli, maupun orang buta itu tidak sah, sebab pernyataan hanya bisa ditangkap dengan adanya fungsi penglihatan dan pendengaran yang normal. Syarat adil di atas sudah mencangkup syarat beragama Islam.15 14 Muhammad Abdul Tihami, Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm. 33. 15 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur’an dan Hadits, hlm. 458. 20 Kewajiban adanya saksi ini tidak lain untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Dan di sinilah saksi itu dapat memberikan kesaksiannya. 5. Wali Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari beberapa pendapat tersebut tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ibnu Rusyd:16 a. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan Syafi’i juga menyatakan demikian. b. Abu Hanifah, Zufar, Sya’bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan. 16 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 14-15. 21 c. Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda. Ia berkata, disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda. d. Berdasarkan riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat ke empat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya. Dia juga mensunahkan agar seorang janda mengajukan kepada walinya untuk menikahkannya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan dalam nikah). D. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Fikih Salah satu tujuan dari syariat Islam (maqashidu syari’ah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan mudharat kepada istri, anak, dan harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dipandang sebagai masalah dharurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat 22 berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis atau maqashidu syari’ah, dengan berdasarkan kaidah fiqhiyah:17 ﺗﻐﯿﺮاﻻﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﯿﺮاﻻﺣﻮال واﻷزﻣﻨﺔ Artinya:“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.” Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.18 Di samping itu ada pula yang menjadikan maslahah mursalah sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat. Berdasarkan cara berfikir tersebut, pencatatan perkawinan sangat dianjurkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya, karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya. Para perancang ordonansi perkawinan di Pakistan mendasarkan fikiran mereka pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti utang piutang saja hendaknya 17 Huzaemah Tahido Yanggo, Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam (Jakarta: GT2 dan GG Pas), hlm. 22. 18 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 57. 23 selalu dicatatkan, apalagi perkawinan yang bahkan lebih penting dari utang piutang.19 Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: ... Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.” (QS. Al-Baqarah: 282) Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat AnNisa’ ayat 21, yang berbunyi: 19 Fathurrahman Djamil, Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya terhadap Anak dan harta (Jakarta: GT2 dan GG Pas, Mei 2007), hlm. 38. 24 Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 21) Setidaknya terdapat 2 (dua) manfaat dari pencatatan perkawinan, yaitu manfaat represif dan manfaat preventif. Manfaat represif dari pencatatan perkawinan adalah terbentuknya kesempatan itsbat nikah (penetapan nikah) bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Sedangkan manfaat preventif dari pencatatan nikah adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum perundang-undangan, dengan ini dapat dihindari pelanggar terhadap kompilasi relatif pegawai pencatat perkawinan atau menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.20 20 hlm. 111. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), BAB III PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA A. Perkawinan Menurut Hukum Positif Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Selanjutnya, menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan sebuah rumah tangga yang damai, teratur, penuh cinta kasih serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.1 1 Mahmuda Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), hlm. 110. 25 26 Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk adanya pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan umat manusia, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan manusia dalam berumah tangga. Dengan demikian perkawinan merupakan pertalian yang seteguhteguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antara suami dan istri, melainkan juga ikatan saling kasihmengasihi pasangan hidup tersebut, yang natinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masingmasing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan seorang dapat terpelihara terhadap keganasan dan kebinasaan hawa nafsunya. B. Syarat dan Sahnya Perkawinan dalam Hukum Positif 1. Syarat Perkawinan Tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka perkawinan dilakukan dengan syarat yang ketat. Apabila memperhatikan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka syarat perkawinan terbagi atas: a. Syarat formil yaitu meliputi; 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)); 2) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat (1)); 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9). b. Syarat materiil yang berlaku khusus, yaitu bagi perkawinan tertentu saja, antara lain; 1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2). Apabila telah dipenuhi syarat-syarat tersebut di atas, baik syarat materiil maupun syarat formil, maka kedua calon mempelai telah resmi menjadi suami istri. Akan tetapi, bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang berakibat batalnya suatu perkawinan. Kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 28 tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas; b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri; d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan; e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 2. Sahnya Perkawinan Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 29 Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaanya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.2 Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yakni perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.3 Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuanketentuan agama, maka perkawinan tidak sah, demikian juga sebaliknya. C. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal yang menyangkut proses administratif, sehingga perkawinan harus dicatatkan 2 M Ridwan Indra, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 1. 3 Wahyono Darmabrata, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 101. 30 sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pencatatan ini, akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain; 1. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum 31 perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); 2. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974); 3. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); 4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masingmasing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. 32 Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami istri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah. Kelembagaan pencatat perkawinan di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, berdasarkan agama Islam dan agama non Islam. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi perkawinan di luar agama Islam melibatkan 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu lembaga agama (yang berwenang menikahkan) dan lembaga pencatatan sipil (yang akan mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama). 33 Berdasarkan pencatatan sipil tersebut kemudian dikeluarkan kutipan akta perkawinan.4 Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang 4 hlm. 16. K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 34 dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Penghulu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan. Terkadang ada salah tafsir bahwa penghulu itu menikahkan. Tapi, dia juga bisa bertindak menjadi naibul wali ketika wali menyerahkan untuk memimpin kewaliannya itu. Namun itu harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya. Tidak bisa dia mengangkat dirinya menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu, yang tidak ada surat keputusannya sebagai penghulu. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah, tetapi tidak di hadapan hukum dan negara. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu 35 kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan. Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan sebagai salah satu komponen administrasi kependudukan berada pada fungsi pencatatan sipil yang secara struktural berada di bawah pembinaan Direktorat Pencatatan Sipil Depdagri. Peran yang diberikan dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) antara lain berupa penyajian data perkawinan sesuai dengan komposisi yang diperlukan, yakni melalui pemberian input data secara proporsional terhadap 36 sistem yang ada. Melalui input yang lengkap dan benar akan dapat disajikan data perkawinan sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat data perkawinan tersebut antara lain: 1. Untuk mengetahui jumlah penambahan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga dan dijadikan komponen lembaga terkecil bagi pembentukan SDM berkualitas; 2. Untuk pengelolaan data berkaitan dengan rencana program pembinaan rumah tangga dan advokasi penduduk pra nikah; 3. Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang telah memiliki akta perkawinan sebagai tolok ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam aspek administrasi kependudukan. Dengan melihat pada fungsi data perkawinan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 37 Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pelaporan tersebut disampaikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil. BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAANNYA A. Status Perkawinan Siri Menurut Fikih Perkawinan merupakan perbuatan mulia yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam sosial kemasyarakatan. Mengenai perkawinan siri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i sepakat bahwa tidak boleh melakukan perkawinan secara rahasia (sirri). Mereka berbeda pendapat jika mendatangkan saksi 2 (dua) orang, lalu keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah perkawinan tersebut termasuk perkawinan siri atau bukan, Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah nikah secara rahasia dan harus dibatalkan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia.1 Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini merupakan hukum syar’i atau maksud 1 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 31. 38 39 dari kesaksian tersebut adalah menutup jalan perselisihan atau pengingkaran. Ulama yang menyatakan bahwa itu adalah hukum syar’i mengatakan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat sah, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk pembuktian mengatakan bahwa kesaksian termasuk syarat kesempurnaan.2 Adapun dalam perkembangannya, perkawinan siri yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam. Namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah.3 Perkawinan siri juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada pula yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).4 Sementara dalam pandangan KH. Ma’ruf Amin, Forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa, sengaja memakai istilah nikah bawah tangan. Selain untuk membedakan perkawinan siri yang sudah dikenal oleh masyarakat, istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurutnya penyebutan dengan istilah nikah bawah tangan untuk membedakan dengan perkawinan siri yang berkonotasi lain. Kalau nikah siri dalam pengertian nikah yang dilakukan hanya 2 3 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 32. Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm 65. 4 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17. 40 berdua saja, tidak memakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan perkawinan semacam ini tidak sah.5 Dengan demikian, status hukum dari perkawinan siri menurut fikih atau hukum Islam adalah sah sebagaimana perkawinan pada umumnya, selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, yakni adanya akad, calon suami, calon istri, dua orang saksi dan adanya wali. Hanya saja dalam pelaksanaannya perkawinan siri tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. B. Status Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif Perkawinan siri merupakan akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuanketentuan agama Islam semata tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah. Perkawinan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.6 Pemerintah secara tegas telah mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 5 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 147. 6 Ali Uraidy, Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, (Jurnal Ilmiah Fenomena, November 2012), hlm. 982. 41 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut jelas dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundangan yang berlaku. Adapun prosedur lebih detailnya termuat dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pada asasnya tiap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah berporos pada kemaslahatan bersama (mashlahah ‘ammah). Ada banyak hal yang melatarbelakangi pembentukan peraturan tersebut. Termasuk aturan perkawinan yang mulai diperhatikan jauh setelah kemerdekaan Indonesia dicapai. Jadi di balik semua itu tersirat manfaat besar yang diharapkan akan tercapai tatkala masing-masing individu melaksanakannya. Oleh karena itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, yakni setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. 42 C. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Menurut Fikih dan Hukum Positif 1. Kedudukan Istri a. Menurut Fikih Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya perkawinan siri yang memenuhi setiap syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam merupakan perkawinan sah. Kedudukan istri dalam perkawinan adalah seimbang dengan suami, begitu pula dengan akibat hukumnya, tidak berbeda dengan perkawinan yang pada umumnya terjadi di dalam Islam. Allah SWT berfirman: Artinya:“...Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isteri-isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. AlBaqarah: 228) Para ulama sepakat bahwa akibat dari sebuah perkawinan adalah timbulnya hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, yaitu nafkah dan pakaian.7 Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran: ... 7 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 106. 43 Artinya:”dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf (baik)...“ (QS. AlBaqarah: 233) Kemudian akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:8 1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut. 2. Mahar atau mas kawin yang diberikan menjadi milik sang istri. 3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. 4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anak yang sah. 5. Timbul kewajiban dari suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama. 6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua. 7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda. 8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. 9. Bila di antara suami istri ada yang meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya. 8 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49. 44 b. Menurut Hukum Positif Mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.9 9 Nurul Huda Haem, Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007), hlm 104. 45 Akibat negatif yang muncul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. Dengan akta nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan haknya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan wanita sebagai istri. Secara hukum, wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perceraian. 2. Kedudukan Anak a. Menurut Fikih Kedudukan anak sebagai hasil dari perkawinan merupakan bagian yang penting dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak sah. Seorang anak sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam 46 hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan atas nama Allah SWT yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Para ulama sepakat bahwa anak yang terlahir kurang dari 6 (enam) bulan tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya, baik terlahir pada waktu akad, maupun pada waktu dukhul (setelah senggama). Meskipun begitu, para ulama berbeda pendapat dalam penetapan nasab karena keputusan qafah (ahli nasab), yaitu dua orang yang melakukan persetubuhan dalam satu masa suci, baik karena sebab perbudakan atau karena sebab pernikahan. Gambaran hukum qafah ini terdapat pada anak pungut yang diakui oleh dua orang atau tiga orang. Qafah menurut bangsa Arab adalah suatu kaum yang memiliki pengetahuan tentang garis keturunan yang mirip antara sesama manusia, untuk saat ini seperti dibuktikan dengan tes DNA. Para ulama yang berpegang pada putusan qafah tersebut adalah Imam Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur dan Al-Auza’i, sedangkan para ulama Kufah dan mayoritas ulama Irak menolak putusan qafah.10 Perkawinan siri dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga 10 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 718-719. 47 ayahnya serta mendapatkan hak waris dan nafkah dari orang tuanya. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan dan perlindungan dari orang tuanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran: Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233) 48 Kemudian, anak hasil dari perkawinan siri sebagai anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi semua hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdur Rozak di dalam bukunya “Hak Anak dalam Islam”, bahwa hakhak anak antara lain:11 a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan. b. Hak anak dalam kesucian keturunannya. c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik. d. Hak anak dalam menerima susuan. e. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, perawatan dan pemeliharaan. f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya. g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam perkawinan siri. Selama perkawinan memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah sah dan begitupun dengan anak hasil perkawinan tersebut berkedudukan sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah. 11 21. Abdur Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 49 b. Menurut Hukum Positif Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sebagai anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin.12 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 (enam) bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Mengenai anak sah maupun anak luar kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya dalam Pasal 42, 43 dan 44, yaitu: Pasal 42 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 12 J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 50 Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, dalam Pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.13 Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) 13 Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin (www.jimlyschool.com) 51 kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan di dalam Pasal 272 jo Pasal 283 KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mendapatkan waris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata. Dengan demikian, bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata bukan hanya dengan ibunya saja, tapi dengan ayah dan keluarga ayahnya, apabila hubungan darahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain. Sehingga hubungan perdata dengan ayah atau ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum. 3. Kedudukan Harta Kekayaan a. Menurut Fikih Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya bagi diri mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan 52 hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.14 Harta benda yang timbul karena perkawinan ada dua jenis, yaitu harta benda yang dibawa dari luar perkawinan yang telah ada pada saat perkawinan dilaksanakan atau harta bawaan dan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan atau disebut sebagai harta bersama. Secara umum, hukum Islam (Al-Quran, Hadis dan fikih) tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan istri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.15 Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, menerangkan tentang hak milik pria atau wanita secara terpisah yang keduanya memiliki harta bendanya sendiri-sendiri, yaitu: 14 15 hlm. 175. J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 53 Artinya:“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 32) Ayat tersebut bersifat umum, tidak ditujukan terhadap suami atau istri saja, tetapi semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing. Sedangkan dalam hukum waris, ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita punya hak untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua.16 Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwasanya hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu 16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 126-127. 54 tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.17 Hal senada disampaikan pula oleh Khoiruddin Nasution, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain, yakni tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.18 Kemudian apabila dalam majelis akad perkawinan dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau istri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Akan tetapi harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, adanya akad syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.19 17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 101. 18 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), hal 192. 19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 176. 55 Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta bersama dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara lebih terperinci, sehingga masih terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan penggalian hukum dengan metode qiyas. Dengan demikian, dari beberapa pandangan pakar tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan Islam memisahkan harta kekayaan suami istri tersebut sebenarnya akan memudahkan pasangan suami istri sendiri apabila terjadi proses perceraian, karena prosesnya menjadi lebih mudah dan tidak rumit. b. Menurut Hukum Positif Salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah adanya harta benda dalam perkawinan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa setelah terjadinya perkawinan maka harta benda yang dihasilkan selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama suami istri. Mengenai harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan, Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Bab XIII, Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami atau istri (Pasal 85). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan 56 dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86). Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 89). Adapun jika terjadi perceraian, bagian masing-masing mantan suami istri berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97). Berkaitan dengan harta bersama atau harta gono-gini ini diatur dalam perundangan di Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana harta bersama diatur dalam satu bab, yaitu Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang terdiri dari tiga pasal, Pasal 35, 36 dan 37, sebagai berikut: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. 57 Jika dilihat dari uraian di atas, penyelesaian pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia selain dengan jalan musyawarah juga bisa ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, apabila tidak dapat dicapai kesepakatan di luar pengadilan. Dengan demikian, harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan siri tidak dapat diajukan ke pengadilan, kecuali sebelumnya telah dilakukan itsbat nikah (penetapan nikah). BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akhirnya membuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkawinan siri menurut fikih atau hukum Islam adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. 2. Perkawinan siri menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri tidak dikenal, hanya disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan, antara lain: a. Kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan, akan tetapi negara tidak mengakuinya. Pengakuan ini penting bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya pengakuan negara dan tanpa adanya akta nikah menjadikan posisi istri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum, yakni berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri dan hak- 58 59 hak lain bila ditinggalkan suami, diceraikan suami atau suami meninggal. Penegak hukum termasuk pengadilan hanya berpegang pada bukti yang sah (akta nikah) untuk memproses setiap tuntutan, gugatan atau perselisihan suami istri tersebut. b. Kedudukan anak di dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama seperti halnya dalam perkawinan yang dicatatkan. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, dengan tidak adanya akta nikah orang tua, akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang melahirkan tapi tidak tercantum nama ayah. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga hak-haknya tidak didapatkan sebagaimana anak-anak yang lain. c. Kedudukan harta di dalam perkawinan siri menurut hukum Islam diperhitungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi jika dihadapkan dengan hukum negara, biasanya istri yang akan menjadi korban apabila suami dengan itikad tidak baik melakukan pengingkaran dan mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut milik dirinya sendiri. Istri tidak akan bisa menuntutnya di pengadilan, hanya mediasi dan musyawarah untuk mufakat di luar pengadilan adalah jalan satu-satunya. 60 B. Saran 1. Melihat akibat hukum dari perkawinan siri yang begitu luas, hendaknya harus ada upaya-upaya dari berbagai pihak, seperti pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para praktisi hukum, penegak hukum, dan lainlain untuk lebih aktif mensosialisasikan arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara. 2. Pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum seharusnya membuat kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan mengitsbatkan setiap perkawinan yang diketahui telah dilakukan secara siri, agar supremasi hukum di negara ini dapat lebih ditegakkan. DAFTAR PUSTAKA Al-Quran Al-Kariim Abbas, Ahmad Sudirman. Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan Antar Madzhab, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006. Abdullah, Abdul Ghani. Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta: Intermasa: 1991. Ali Uraidy, Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmiah Fenomena, November 2012. Anwar, Moch. Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan, Bandung: CV Diponegoro, 1991. Asmawi, Muhammad, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, Yogyakarta: Darussalam, 2004. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004. Darmabrata, Wahyono. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Gitama Jaya, 2003. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Djamil, Fathurrahman. Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuensinya terhadap Anak dan Harta, Jakarta: GT2 dan GG Pas, Mei 2007. Fachruddin, Fuad Mohd. Masalah Anak dalam Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990. Haem, Nurul Huda. Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar hingga Perselingkuhan, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007. Hazairin. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Tinta Mas, 1985 Husein, Abdur Rozak. Hak Anak dalam Islam. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992. 61 62 Indra, M Ridwan. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994. Junus, Mahmuda. Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989. Lari, Sayyid Mujtaba Musavi. Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993. Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknisi Administrasi dan Teknisi di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: 4 April , 2006. Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005. Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogjakarta: Graha Ilmu, 2011. Muhdlor, A. Zuhdi. Memahami Hukum Pernikahan. Bandung: Al-Bayan, 1994. Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir; Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997. Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005. Prawirohamidjojo, Soetojo. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 1986. Ramulyo, Idris. Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam, Jakarta: Attahiriyah, 1993. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. 63 Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1983. Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980. Satrio, J. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. Sholeh, Asrorun Ni’am. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: Elsas, 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Sofyan, Syafran. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin, www.jimlyschool.com. Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002. Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005 Tihami, Muhammad Abdul. Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Press, 2009. Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007. Yanggo, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshari Az, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah Hukum Nikah, Surabaya: Terbit Terang, 2006. Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQuran dan Hadits, terj. Muhammad Afifi, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.