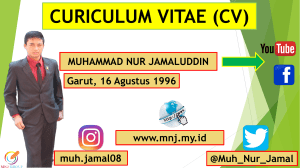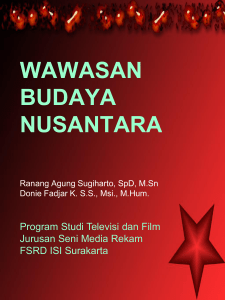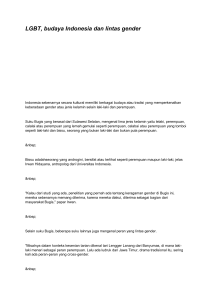TOLERANSI DALAM TRADISI KEARIFAN LOKAL
advertisement

TOLERANSI DALAM TRADISI KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT BUGIS
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Oleh
Firdaus
NIM: 1110032100022
JURUSAN STUDI AGAMA AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H./2017 M.
i
TOLERANST trALAIW TRAI}ISiI KEARIFAFI LOKAL
JI{ASYARAI(AT BUGIS
SKRITS_i
Diajr*aa Ur&ft Mernenrrhi Persymatan Memperctetr
Gel.r Sejffi, ^&gffiE Iski €S-r+g)
Oleh:
F€EftEEffigffffi
Pembimbi4g:
z*%4
I)w'Hil)*rmdlMA
ritB- 1ffi39' 1gl5&3 t g&'t
JURUSA1T STUDI AGAMA
AGAMA
FAI(IILTAS ffiffULIMI}M{
{TNTYERSITAS ISI,AIVI NEGERI
SYARIS'trIIBAYATI}LLAII
JAKARTA
1438 lf,.J20t7
t{"
LEMBAR PENGESAIIAN PANITIA UJIAN SIDANG
Skripsi berjudul "TOLERANSI DALAM TRADISI KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT BUGIS)" telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas
Ushuluddin UIN Syarif hidayatullah Jakarta, pada 8 Mei
2Afi. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada
Program Studi Agama-Agama.
Jakarta,8 Mei 2017
Sidang Munaqosah,
Ketua Merangkap Aqggota,
Sekretaris
Anggota,
!vr
MA
1975t019 200312
NrP. 19s90413 t99603 2 001
1
Angggta,
Penguji
I
/hc.9"*
Dr. M. Amin Nurdin" MA
NrP. 19550303 198703
I
NIP.
003
Pembimbing,
Drs.Dadi Darffi
NIP. 19690707 199503 1 001
u
198603 2001
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1.
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk mernenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata
I
di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
ini
telah
saya
di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika ditemukan kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya
asli saya atau merupakan hasil plagiat dari karya orang lain maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta,2T
Maret2}l7
irtt
iit:
ilii'i,
i19r)
Firdaus
lll
KUTIPAN
“Jangan pernah berbicara tentang ketuhanan kalau kau masih menghujat
perbedaan, jangan pernah mengklaim kebenaran bila sikapmu tak manusiawi, dan
jangan pernah mengaku baik jika lisanmu tak terkontrol.
Penulis : Firdaus
iii
ABSTRAK
Firdaus
1110032100022
Toleransi Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bugis
Toleransi merupakan hal sangat mendasar untuk menuju kemajuan bangsa
Indonesia. Keragaman suku, budaya, ras, kelompok dan agama yang ada sangat
rentan untuk dibenturkan dengan isu-isu yang sangat mudah menyulut konflik
dikalangan masyarakat. Pencegahan sikap intoleransi sampai resolusi konflik telah
ditawarkan oleh para ahli dari berbagai kajian keilmuan. Dalam hal ini penulis
fokus pada hasil pemikiran Mukti Ali, Alwi Shihab, dan juga Abdurahman Wahid
(Gus Dur) yang menurut penulis beliau merupakan tokoh-tokoh yang toleran dan
juga sekaligus pernah menjadi pejabat tinggi dalam struktur pemerintahan
tertinggi di Indonesia.
Dengan buah pemikiran para tokoh di atas tentang toleransi. Penulis,
menilai bahwa hakikat nilai toleransi adalah suatu sikap yang memanuisakan
manusia tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada. Dari nilai toleransi itu
sangat tanpak jelas dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia, yang menjunjung
nilai-nilai moral dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.
Dalam skripsi ini penulis mencoba menggali nilai toleransi kearifan lokal
masyarakat Bugis. Dimana masyarakat Bugis menekankan prinsip siri’ dan pesse
yang pada hakikatnya menjunjung nilai tau sipakatau, sepakalebbi, dan
sipakainge’, selain dari pada itu terdapat pula pedoman-pedoman kehidupan yang
terdapat dalam pangederreng, dan juga konsep assimellereng sebagai konsep
kesetiakawana sosial dalam masyarakat Bugis.
Kata Kunci
: Pluralisme, Toleransi,
Pangederreng, Bugis.
iv
Kearifan
Lokal,
Siri’,
Pesse,
KATA PENGANTAR
بسم هللا الر حمن الرحيم
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada
junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para
pengikutnya yang senantiasa berkorban menyebarkan dakwah Islam kepada
seluruh umat sampai hari kiamat.
Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata
1 (S.1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Membahas
dan menyusun skripsi ini bukan hal yang mudah, dibutuhkan semangat,
kesungguh-sungguhan dan kerja keras serta keikhlasan dalam menjalani setiap
rintangannya.
Di samping itu, penulis juga banyak mendapatkan motivasi, petunjuk dan
bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung
sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai
dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
v
2. Bapak Dr. Media Zainul Bahri MA. Selaku Ketua Program Studi, Studi
Agama-Agama dan Ibu Dra. Halimah Mahmudy, MA. Selaku Sekretaris
Program Studi Studi Agama-Agama, dan Bapak Hakim, MA.
3. Bapak Dr. Dadi Darmadi, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang
senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan
serta koreksi yang sangat berarti dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Para dosen-dosen Fakultas Ushuluddin Jurusan Studi Agama-Agama yang
telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan
bermanfaat serta menjadi berkah bagi penulis, serta para pimpinan dan staf
perpustakaan baik Perpustakaan Utama maupun Perpustakaan Fakultas
Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan guna menyelesaikan skripsi
ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda H. Abd. Gaffar
dan Ibunda Hj. Syarifah, yang telah bersusah payah mengasuh dan mendidik
penulis dengan kasih sayang, semoga sehat selalu dan panjang umur.
Kemudian untuk saudara-saudara penulis tersayang, Masna, Zulkifli,
Zulkarnain, Abdul Hadi dan kakak ipar penulis Anas Anda Ganesa, serta
keponakanku tercinta Nurul Mekka Shidqia. Juga kepada sepupu penulis
Kolonel Inf. Bahman dan om Letkol. Rasli, ST. Terimakasih telah
menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Awaluddin Kuo. Terkhusus para
dewan pengajar dan staff, Serta kepada kawan-kawan alumni 2010. Menjadi
vi
santri merupakan pengalaman terbesar dan penuh pelajaran yang berharga
yang sekaligus menjadi modal utama penulis untuk bertahan dan
menyelesaikan studi di Jakarta.
7. Teruntuk senior-senior yang telah membimbing dan berbagi pengalaman
dengan penulis diantaranya, Prof. Dr. Mashadi Said, M. Saleh Mude, Nur
Amin Syam, Dr. Saifuddin Zuhri MA. Adli Bahrun, Arjan Sila, Andika Ulil
Amri, Awaluddin Jenne, Amiruddin Wata. Terima kasih atas segala atas
kerendahan hatinya mau membantu penulis.
8. Kepada kewan-kawan Jurusan Studi Agama-agama angkatan 2010
khususnya Bang Iman Abdulrahman, Bang Tauhid, Bang Faiz Ramadhan
dan Kang Yusuf Ambar Firdausy, serta Daeng Kurniawan. Dan tak terlupa
kepada kawan ku Kacung Arisma dan Reza Nata Suhandi. Terimakasih
telah menjadi patner yang baik selama ini.
9. Senior-senior Alumni dan Saudara-saudara seperjuangan Pengurus IKAMI
Sul-Sel Cab. Ciputat. terkhusus IKAMI Sul-Sel Cab. Ciputat periode 2013
terlebih Fahri Husain, Andi Firman, M. Sapril, dan juga Inggrit Pratiwi.
Terimakasih telah mengajarkan menjadi team yang komplit.
10. Teman-teman seperjuangan I.C.I (Insan Cendekia Indonesia), ada bang
Muamar Midan dan bang H. Muslim selaku senior yang selalu memberikan
arahan dalam setiap perjalanan I.C.I, kanda Moh. Farid Chair, Rizal Mampa,
Laila Nihayati, Abdullah el Sahar, Firman Faisal, M. Sapril, Arif Hidayat,
Ceceng Holilullah, Anis Fahmi, Abdul Khalid, M. Ihsan, Nur Muhaimin, M.
Fauzan Chair, M. Fadli Imam, Hifdzil Farazdaq, Al Ghazali, M. Amar, dll.
vii
11. Kawan-kawan Pengurus Besar IKAMI SUL-SEL periode 2016.
12. Kepada Senior-senior Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD KKSS
TANGSEL), bapak Andi Djalal Latif, Kakanda Saifuddin Zurhi, bapak
Mudatsir, bapak Hasanuddin, dan lain-lainnya. Serta BPW KKSS
BANTEN, dan BPP KKSS.
13. Kawan-kawan Sandeq Sul-Bar, Ketum Arwin, Mabrur, Rosita, Asrul,
Samad, Abangda Aco. Dan lain-lain.
14. Saudara-saudara seperjuangan FKPM Mamuju, ada Siswadi, Ocit, Lita,
Wahyu, Aksin, Rahman, Najam, Ulin, UU’, Amrin, Dul’, Rijal, Irda, Tika,
dan Ila.
Demikianlah ucapan terima kasih yang penulis haturkan atas semua bantuan
baik itu moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Mudah- mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah
diberikan. Amin.
Jakarta, 5 Maret 2017
Penulis
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................
i
LEMBAR PERNYATAAN ...........................................................................
ii
KUTIPAN .......................................................................................................
iii
ABSTRAK .....................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................
v
DAFTAR ISI ...................................................................................................
x
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
B. Identifikasi Masalah ...............................................................
15
C. Batasan Masalah .....................................................................
15
D. Rumusan Masalah ..................................................................
15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................
16
F. Metode Penelitian ...................................................................
17
1. Sumber Data .....................................................................
17
2. Jenis Penelitian ..................................................................
17
3. Teknik Pengumpulan Data ...............................................
17
4. Teknik Penulisan ...............................................................
18
G. Sistematika Penulisan .............................................................
18
TOLERANSI BERAGAMA
A. Pengertian Toleransi Beragama .............................................
21
B. Perkembangan dan Teori Toleransi Agama di Indonesia ......
24
ix
BAB III
1. Pluralisme .........................................................................
26
2. Inklusifisme ......................................................................
27
3. Dialog ...............................................................................
28
C. Pendapat Para Tokoh .............................................................
28
1. Mukti Ali ...........................................................................
29
a. Singkretisme ...............................................................
29
b. Rekonsepsi .................................................................
30
c. Sintesis ......................................................................
31
d. Penggantian ...............................................................
32
e. Agree in Disagreement ..............................................
33
2. Alwi Shihab ......................................................................
34
a. Saling Mengenal .. ......................................................
34
b. Keberaganaman Keyakinan ........................................
34
c. Keberaganaman Etnis ................................................
35
3. Abdurahman Wahid .........................................................
36
a. Pribumisasi Islam .......................................................
36
d. Humanisme dan Demokrasi .......................................
38
e. Pluralisme dan Toleransi .............................................
41
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUGIS
A. Perkembangan Masyarakat Bugis ..........................................
43
B. Siri’ Dan Pesse Prinsip Kehidupan Masyarakat Bugis ..........
44
1. Siri’ ....................................................................................
45
2. Pesse .................................................................................
52
x
C. Pangederreng Masyarakat Bugis’..........................................
55
1. Ade’ ...................................................................................
59
2. Bicara ...............................................................................
60
3. Rapang ..............................................................................
65
4. Wari ...................................................................................
67
D. Assimellereng sebagai Konsep Kesetiakawan Masyarakat
Bugis .....................................................................................
BAB IV
BAB V
69
ANALISA
A. Pandangan Umum Toleransi ..................................................
75
B. Analisa Toleransi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bugis
79
PENUTUP
A. Kesimpulan ...........................................................................
92
B. Saran-saran ............................................................................
94
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
96
xi
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................
i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SIDANG ...........................
ii
LEMBAR PERNYATAAN ...........................................................................
iii
KUTIPAN .......................................................................................................
iv
ABSTRAK .....................................................................................................
v
KATA PENGANTAR ...................................................................................
vi
DAFTAR ISI...................................................................................................
x
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..........................................................
1
B. Identifikasi Masalah ...............................................................
15
C. Batasan Masalah ....................................................................
16
D. Rumusan Masalah ..................................................................
16
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........................................
16
F. Metode Penelitian ..................................................................
17
1. Sumber Data .....................................................................
17
2. Jenis Penelitian ..................................................................
18
3. Teknik Pengumpulan Data ...............................................
18
4. Teknik Penulisan ...............................................................
18
G. Sistematika Penulisan ............................................................
19
TOLERANSI BERAGAMA
A. Pengertian Toleransi Beragama .............................................
22
B. Perkembangan dan Teori Toleransi Agama di Indonesia ......
25
1. Pluralisme .........................................................................
27
2. Inklusivisme .....................................................................
28
3. Dialog ...............................................................................
29
C. Pendapat Para Tokoh ............................................................
29
1. Mukti Ali ...........................................................................
30
a.
Sinkretisme ................................................................
30
b. Rekonsepsi .................................................................
31
c. Sintesis ......................................................................
32
d. Penggantian ...............................................................
33
e. Agree in Disagreement ..............................................
34
2. Alwi Shihab
BAB III
...................................
35
a. Saling Mengenal ........................................................
35
b. Keberagaman Keyakinan ...........................................
35
c. Keberagaman Etnis ...................................................
36
3. Abdurahman Wahid .........................................................
37
a. Pribumisasi Islam .......................................................
37
d. Humanisme dan Demokrasi .......................................
39
e. Pluralisme dan Toleransi .............................................
42
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUGIS
A. Perkembangan Masyarakat Bugis ..........................................
44
B. Siri’ Dan Pesse Prinsip Kehidupan Masyarakat Bugis ..........
45
1. Siri’....................................................................................
46
2. Pesse .................................................................................
53
C. Pangederreng Masyarakat Bugis’ .........................................
56
1. Ade’ ...................................................................................
60
2. Bicara ...............................................................................
61
3. Rapang .............................................................................
66
4. Wari ...................................................................................
68
D. Assimellereng sebagai Konsep Kesetiakawan Masyarakat
Bugis .....................................................................................
BAB IV
BAB V
70
ANALISA
A. Pandangan Umum Toleransi ..................................................
76
B. Analisa Toleransi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bugis .
80
PENUTUP
A. Kesimpulan ...........................................................................
93
B. Saran-saran ............................................................................
95
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
97
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan budaya.,
Indonesia dapat diketegorikan sebagai negara majemuk. Kemajemukan ini
menjadi titik perhatian dari founding fathers kita, sehingga dirumuskanlah konsep
yang menaungi segala bentuk kemajemukan itu yang dikenal dengan semboyan
“Bhineka Tunggal Ika”. Konsep ini merupakan tata nilai moral yang hidup jauh
sebelum adanya Indonesia.
Konsep kemajemukan ini kemudian diperkokoh
dengan sumpah pemuda, yang dicirikan sebagai alat persatuan dalam menghadapi
penjajah.
Kemajukan masyarakat seyogyanya menjadi kekuatan yang disadari oleh
masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, segala bentuk keanekaragaman bisa
menjadi kekayaan yang bisa digunakan sebagai kontribusi pembangunan negara
apabila dikelola dengan baik.
Namun demikian, seringkali timbul ancaman yang dapat mengganggu
stabilitas dan keutuhan NKRI. Dapat dilihat dari sejarah negara Indonesia, yaitu
pasca jatuhnya Orde Baru dari tampuk kekuasaannya, mulai bermunculan kasus
yang berbau etnis dan agama di berbagai wilayah Indonesia. Seperti kasus
Ambon, Poso, Sampit, dan Aceh. Kesemuanya ini bukan persoalan yang remeh,
sebab bila tidak segera ditanggulangi, akan mewabah ke daerah lain. Padahal,
pada kasus-kasus tersebut, agama hanyalah menjadi objek tertuduh mendalangi
1
2
semua permusuhan itu, dan bila dirunut jauh, pada hakikatnya kejadian tersebut
dilatarbelakangi oleh kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Inilah yang
menjadi bukti, bahwa perhatian terhadap kesadaran perbedaan haruslah
diperhatikan dengan seksama.
Pemerintah memang telah memberikan perhatian terhadap tata kelola
kehidupan keagamaan di Indonesia. Salah satunya melalui UU Pasal 29 ayat (2)
bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tipa-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”1 Aturan ini sebagai upaya dari pemerintah untuk
menciptakan suasana kondusif dan toleransi antar umat beragama di Indonesia.
Namun demikian, tetap saja konflik-konflik keagamaan masih terjadi di
Indonesia.
Melihat fenomena itu, Mukti Ali, Alwi Shihab, Abdurahman Wahib,
Ahmad Wahib dan lainnya, menawarkan beberapa jalan alternatif yang bisa
ditempuh terkait dengan konflik-konflik yang terjadi. Diantaranya adalah wacana
pluralisme dan menyegarkan ulang ingatan kita tentang multikulturalisme bangsa
Indonesia yang pernah menjadi payung kokoh dalam sejarah bangsa Indonesia.
Dengan memahami pluralisme serta multikultaralisme, diharapkan akan
mereduksi gejolak dan konflik-konflik yang terjadi serta membawa dampak yang
lebih baik bagi bangsa. Bahkan ada juga yang berpendapat pluralitas itu menjadi
prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi dalam masyarakat modern. 2
1
UU Pasal 29 ayat 2
Asep Syaefullah, Kerukunan Umat Beragama (studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang
Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Penerbit Gragindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 142.
2
3
Pemahaman akan pluralisme pada hakikatnya adalah membiarkan mereka
yang berpikir lain atau berpandangan lain tanpa menghalang-halangi. Pluralisme
menurut filsafat agama, sering diartikan sebagai keyakinan akan kebenaran semua
agama yang ada. Istilah pluralisme sudah dikembangkan dibeberapa ruang
lingkup seperti pluralisme sosial, pluralisme budaya, dan pluralisme etika dan
kemudian muncullah pluralime agama.
Gunawan
Adnan
yang
dikutip
dalam
buku
Pluralitas
Agama
menyebutkan ada dua macam bentuk pluralisme agama. Pertama pluralisme
eksternal agama adalah keyakinan akan kebenaran semua agama, baik dalam
kapasitas yang sama maupun dengan kapasitas kebenaran yang berbeda-beda.
Kedua, pluralisme internal agama adalah keyakinan akan kebenaran semua sekte
atau mazhab dalam satu agama tertentu, dimana letak perbedaan sekte atau
mazhab adalah disebabkan perbedaan perbedaan penafsiran (heurmeneutika)
terhadap konteks agama.3
Selain itu istilah pluralisme ada beberapa tokoh yang mengguankan istilah
toleransi merupakan konsep memahami perbedaan itu, dengan mengambil contoh
satu agama misalnya Islam memandang toleransi sebagai persamaan hak manusia,
semua manusia mempunyai hak yang sama, tidak membedakan antara orang kulit
putih, berkulit hitam, berkulit kuning, dan kulit merah atau antara si kaya dan si
miskin.4
3
Y.B. Mangunwijaya dkk., Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman (Jakarta:
Kompas, 2001), h. 24.
4
Musthafa Muhammad Syak’ah, Islam Tanpa Mazhab (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h.
24.
4
Kemudian apabila toleransi ditinjau dari kacamata sejarah, toleransi
dibedakan antara toleransi formal dan toleransi material. Toleransi formal berarti
membiarkan pandangan-pandangan dan praktik-praktik politik atau agama yang
tidak sesuai dengan pandangan umum sejauh itu tidak mengganggu hak orang
lain.
Toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif
yang mungkin terkandung dalam pemahaman yang berbeda itu.5 Kedua bentuk
toleransi di atas dengan jelas memberikan gambaran toleransi yang semestinya
digunakan di Indonesia, sehingga apabila terjadi konflik tidak lagi mengangkat isu
yang mengandung SARA.
Selain itu penyadaran kembali atas keragaman masyarakat Indonesia ini
diharapkan bisa menghindari konflik dan menyadarkan kita bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari perbedaan yang ada. Aksi
radikalisme agama atau apapun bentuknya hanya akan menggerogoti nafas
pluralisme yang telah menjadi perekat bangsa kita dan pada gilirannya akan
mengancam integritas nasioal. Inilah arti pentingnya menumbuhkan kembali dan
memupuk multikulturalisme sebagai bagian dari kerja membangun Indonesia
yang lebih baik.
Multikulturalisme pada hakikatnya merupakan mekanisme kerjasama dan
reciprocity (saling memberi) dengan mana setiap individu dan komponen
masyarakat sanggup memberikan tempat, merenggangkan perbedaan dan bahkan
5
Elza Peldi Taher, ed., Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun
Djohan Effendi (Jakarta: ICRP & Buku Kompas, 2009), h. 81.
5
membantu individu dan kelompok yang lainnya yang ada dalam masyarakat
tersebut.
Nilai-nilai
toleransi,
keterbukaan,
inklusivitas,
kerjasama
dan
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan mekanisme yang
terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Ia
mencegah adanya individu atau kelompok masyarakat yang merasa diri paling
benar, dan dengan mengatasnamakan kebenaran, mengembangkan prilaku ekslusif
yang mengabaikan hak-hak orang lain.
Dengan demikian multikulturalisme berperan menjaga harmoni sosial,
yang didefinisikan sebagai kemampuan sebuah masyarakat untuk mengatur
sumber daya dan memproduksi serta mereproduksi tatanan sosial dan lainnya
yang ia butuhkan untuk eksis.6 Ini tidak akan mungkin terjadi apabila faham
radikalisme menjadi tembok yang kokoh untuk menghadang dan menutup ruang
dialog dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Dimana radikalisme yang
menghambat tumbuhnya harmoni sosial dan saling percaya (trust) dalam
kehidupan bermasyarakat.
Radikalisme agama merupakan cerminan dari lemahnya hubungan sosial.
Dari sudut pandang sosiologis, gejala semacam ini berhubungnan dengan ekspansi
meodernisasi yang menciptakan kondisi dunia modern yang sangat paradoksal
dan ini menimbulkan tekanan terhadap sistem disposisi berkelanjutan individual
6
Taher, Merayakan Kebebasan Beragama, h. 81.
6
yang mengintegrasikan pengalam-pengalaman masa lalu dan berfungsi sebagai
matriks persepsi dan tindakan.
Sampai di sini, dapat dilihat bahwa substansi dari multikulturalisme adalah
adanya penghayatan akan kesadaran setiap indivindu di dalam masyarakat.
Setidaknya itulah pendapat para pakar yang bisa disimpulkan saat ini.
Pengahayatan tersebut sebenarnya telah ada jauh sebelum terbentuknya Indonesia
seperti saat ini. Dalam artian bahwa, kesadaran akan nilai keragaman telah
dipahami oleh para pendahulu bangsa Indonesia.
Menerapkan konsep toleransi dan multikultural dari beberapa pendapat
tokoh setelah Mukti Ali. Tetapi konsep pluralisme dan multikultural yang
mengakui atas perbedaan sebenarnya sudah ada dalam adat dari suku masyarakat
jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.
Modernisasi yang telah membawa arus informasi demikian begitu cepat,
sehingga menimbulkan kompleksitas yang tidak terkontrol, dimana suatu
pemahaman akan budaya-budaya luar begitu cepat bertrasnformasi dan merubah
pemahaman budaya lokal. Sehingga, menimbulkan pembauran nilai budaya yang
tidak terstruktur bahkan kadang rancu.
Pandangan masyarakat luar tentang multikulturalisme seperti pengalaman
negara-negara
Eropa
Barat,
Australia,
dan
Selandia
Baru,
bahwa
multikulturalisme baru akan tumbuh dalam suatu tatanan masyrakat apabila
ditunjang oleh syarat-syarat berikut:
1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
7
2. Negara dengan pengamanan sosial yang kuat dan redistribusi kekayaan
secara baik melalui sistem pajak yang progresif.
3. Tidak ada kelas bawah terpingkirkan atas garis etnisitas.
4. Negara netral yang tidak berpihak pada kelompok dominan tertentu.
5. Perkawinan antar-ras dan etnik serta agama yang bebas.
6. Akses pendidikan yang merata termasuk bagi perempuan.
7. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada nilai kosmopolitanisme dan
keragaman budaya.
8. Legislasi yang efektif unutk menghukum provokator yang menebar
kebencian antar- agama dan golongan.
9. Pengalaman bersama dalam aktifvittas-aktivitas sosial dan olahraga.
10. Ideologi patriotik yang menghadang loyalitas kedaerahan dan etnis. Akses
terbuka untuk naturalisasi.
11. Rule of law dan jaminan kesamaan didepan hukum.
12. Agama berfungsi menciptakan solidareitas, sosial, bukan perpecahan.7
Uraian di atas adalah hasil dari pengalaman-pengalaman “budaya luar”
yang tidak selalu tepat jika dipraktekkan di wilayah Indonesia. Sebab suatu
budaya merupakan suatu kekayaan nilai yang dimiliki oleh suatu daerah dan
apabila budaya yang berkembang di suatu daerah dipaksa diterapkan ke suatu
daerah yang lain maka tentunya tidak akan menghasilkan suatu yang baik secara
maksimal. Bukannya hendak mengucilkan atau meremehkan nilai “budaya luar”,
namun betapa tidak adilnya jika hanya melihat sesuatu hanya dari beberapa bagian
7
Taher, Merayakan Kebebasan Beragama, hal. 203.
8
kecil aspek saja. Terlebih bila dihadapakan pada konteks keindonesian yang mana
lebih banyak memiliki ragam budaya yang ada.
Sering kali budaya luar diterima oleh masyarakat yang secara mentahmentah menimbulkan problematika yang baru dalam kehidupan bangsa kita saat
ini misalnya globalisasi, liberalisasi dan hedonisme, yang mana mendorong
masyarakat menjadi individualistis, tidak lagi peduli terhadap individu lainnya.
Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi nilai “gotong royong” dan rasa
empati terhadap orang lain sudah mulai tergerus sehingga dengan tidak disadari
ini dapat menggerus identitas bangsa, sehingga nantinya Indonesia tidak lagi
menjadi sebuah bangsa seperti apa yang telah diwariskan dan dicita-citakan oleh
para founding fathers kita dulu.
Masuknya budaya luar dalam kehidupan masyarakt Indonesia begitu
menghebohkan masyarakat, sehingga tanpa tersadari masyarakat melupakan
budaya leluhurnya. Bahkan dalam beberapa hal budaya yang menjadi identias keIndonesiaan dilupakan karena dianggap tradisional dan kolot.
Mengikuti budaya barat yang tanpa mempertimbangkan apakah budaya
yang datang dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks
Indonesia saat ini. Semestinya kita bisa mensinergikan antara budaya yang datang
dari luar dengan budaya Indonesia sendiri, sehingga Indonesia tetap mempunyai
identitas yang kuat dalam bersaing dengan negara modern lainnya,
apalagi
Indonesia kaya keanekaragama budaya, sumber daya manusia, dan sumber daya
alam yang dimilikinya.
9
Kita bisa lihat kemajuan bangsa Jepang misalnya yang mana dalam
pandangan umum sejajar dengan bangsa modern lainnya yang sampai saat ini
mereka tetap mempertahankan kebudayaan nenek moyang yang diwariskan
kepada mereka yang pekerja keras dan mempertahankan budaya malu. Walaupun
mereka tetap menjaga tradisinya tapi mereka juga tetap melaju menuju bangsa
modern lain yang tetap menonjolkan identitas sebagai bangsa Jepang.
Dalam konteks Indonesia yang tergolong dalam negara berkembang saat
ini sangat rentan dengan pola ikut-ikutan (follower) dari bangsa yang maju yang
tanpa filterasi dengan baik dalam masyarakat yang semestinya mengambil nilai
positif dan meninggalkan budaya negatif dari budaya bangsa luar yang maju,
Sejalan dengan itu, Prof. Dr. Ridwan Lubis menjelaskan bagaimana tujuan
pesantren pada awal didirikan oleh para ulama yaitu, “meninggalkan yang tidak
baik dan melanjutkan yang baik”, ini bisa menjadi contoh dalam mengadopsi pola
kehidupan dari budaya luar, bagaimana mengadopsi budaya dari luar tanpa
menghilangkan budaya sendiri yang baik dalam masyarkat kita.8
Melihat dari kondisi di atas ada dua macam respon terhadap budaya luar
yang akan beredar dikalangan masyarakat kita seperti yang digambarkan Fuad
Hasan yaitu, pertama budaya-tandingan (counter culture) budaya ini biasanya
tampil melalui perilaku dan penampilan, gaya berujar, penggunaan kata sandi, dan
lain sebagainya; sedangkan yang disebut budaya tandingan tampil dengan ciri
negativisme, sikap protes, ungkapan pembangkan, dan sebagainya. Kedua, budaya
8
Penjelasan Prof. Dr. Ridwan Lubis pada mata kuliah Islam dan Kristen di Indonesia,
pada tahun 2013 di Fakultas Ushuluddin.
10
sandingan (sub-culture) berbeda dengan budaya-tandingan yang budaya
sandingan mengarahkan untuk bagaimana kita bisa mensinergikan
dan bisa
berjalan beriringan dengan budaya realitas tersebut.9
Dari kedua macam respon yang akan terjadi dalam masyarakat kita
terlebih karena kondisi Indonesia yang bergerak manuju negara maju, budaya
sandingan menjadi alternatif yang untuk menerima budaya kuar yang akan
berpengaruh positif di kalangan masyarakat Indonesia, kemudian budaya
tandingan yang positif (bukan dengan sikap pembangkang yang arogan) akan
tetapi menawarkan suatu konsep budaya yang positif dalam kehidupan
bertoleransi masyarakat yaitu prulalisme yang selama ini para pakar tawarkan
berdasarkan pada teori yang bermunculan di negara-negara Eropa yang selama ini
diterapkan Indonesia.
Ada beberapa pakar pluralisme menggunakan dalil-dalil agama sebagai
dasar dalam teorinya, yang mana hasilnya belum begitu signifikan dalam
mewujudkan toleransi sebagai bangsa yang multikultur. Padahal sebelum
kemerdekaan permasalahan multikulturalitas, pluralitas, dan toleransi sudah
terwujud dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika” yang selalu didengungkan dari
Sabang sampai Merauke
Dalam hal ini penulis merasa bahwa untuk menciptakan kesadaran dan
penghayatan yang mendalam dalam masyakat Indonesia dibutuhkan aspek budaya
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Mengingat akan kesadaran
9
Fuad Hasan, Renungan Budaya (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet..I, h .85.
11
multikulturalitas, pluralitas, dan toleransi telah terbungkus dengan rapi dari nilainilai kearifan lokal masing-masing suku sebelum Indonesia menjadi sebuah
negara yang utuh.
Saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dalam intern
suatu suku bahkan bagaimana hidup rukun dari sekian banyak perbedaan dari
masing suku di suatu daerah seperti hidup rukunnya suku atau masyarakat Minang
yang diidentikan Islam dengan masyarakat Melayu yang juga diidentikan Islam,
dan dengan masyarakat Batak yang diidentikan dengan Kristen yang ada di pulau
Sumatera dimana pertemuan dan pergesekan yang akan berakibat fatal dalam
masyarakat meskipun begitu bisa diredam dan terselesaikan dengan baik.
Kemudian perbedaan yang sama antara masyarakat suku Makassar, Bugis,
Mandar yang diidentikan dengan Islam, dan sementara Toraja yang diidentikan
dengan Kristen yang mana demikian ini melihat dari perbedaan-perbedaan yang
begitu menonjol dari masing-masing suku, baik itu dari segi adat-istiadat, nilainilai budaya, dan kepercayaan (agama) akan tetapi semua dari semua perbedaan
itu mereka bisa
bekerja sama dan bersanding dengan baik, hidup rukun.
Bagaimana dulu budaya dan tradisi mengatur kehidupan manusia yang
mengutakan keharmonisan hubungan manusia, baik hubungan manusia dengan
penciptanya, lingkungan, kehidupan sosial, maupun dirinya sendiri, 10 sehingga
dapat membuat sebuah peradaban yang besar.
10
Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis (Jakarta: Pro leader, 2016), h. 3.
12
Apabila kita mengingat kondisi saat itu teori normatif tentang
multikulturalisme dan pluralisme belum pernah terdengar dan diketahui oleh
suku-suku tersebut, melainkan sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masingmasing suku tersebut melihat perbedaan yang ada. Kehidupan yang toleran dalam
masyakat bangsa Indonesia sudah terletak sejak lama dalam nilai-nilai budaya kita
sendiri.
Masyarakat Bugis mempunyai peradaban yang tinggi dalam tataran
masyarakat Sulawesi Selatan yang bisa membuat masyarakat Bugis dikenal yang
cepat menyesuaikan dan pantang menyerah akan cita-citanya. kekayaan sumber
daya alamnya saat itu sehingga banyak neraga yang melakukan perdagangan
dengan masyarakat Bugis, baik itu dari pedangan Nusantara, Cina, India, serta
banyak negara samudra Hindia lainnya11, begitu pulat kapal pedagang Wajo
sampai ke Singapura.12
Menurut penelitian antropologi yang dikemukakan oleh A. Mattulada
dalam disertasinya berjudul “Latoa, suatu lukisan analisis terhadap antropologi
politik orang Bugis” yang juga dikutip oleh Laica Marzuki mengatakan bahwa
manuskrip lontara karya klasik gubahan La Mellong membuktikan bahwa siri
mendinamisasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap pangederreng sebagai
wujud totalitas kebudayaan beserta dengan isinya.13 Pangederreng menjadi
sebuah budaya yang tinggi dalam masyarakat Bugis selama ini dengan beberapa
11
Cristian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 356.
Pelras, Manusia Bugis h. 362.
13
M. Laica Marzuki, Siri: Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar sebuah
telaah filsafat hukum (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 25.
12
13
unsurnya yaitu, Ade’ (kaedah hukum, adat-istiadat, kebiasaan), Bicara (Peradilan,
putusan hakim atau raja), Rapang (rujukan, yurisprudinsil), Wari’ (aturan
kekerabatan, protokoler, pengaturan silsilah menurut garis keturunan), dan Sara’
(syariat). Dari pengederreng bagaimana kehidupan orang Bugis diatur sedemikian
rupa agar mencapai kemajuan dalam hidupnya, dari pangederreng itu terangkum
dalam “Siri na Pesse”.
Siri na Pesse adalah dua suku kata yang terdiri dari kata “Siri”dan kata
“Pesse”. Siri diartikan sebagai malu, harga diri atau martabat diri seseorang,
peneliti Auckland University, Selandia Baru Leonard Y Andaya. yang dikutip oleh
Mashadi Said,
bahwa Siri’ itu dua makna yang kontradiktif, pertama Siri’
diartikan sebagai shame (malu) kedua yaitu makna self respect, self esteem, selfworth (harga diri).14
Seseorang Bugis akan menyerahkan segalanya bahkan nyawanya
sekalipun untuk menegakkan Siri’-nya dan dianggap mulia dan terhormat apabila
seseorang bisa menegakkan siri’-nya meskipun dia membunuh sekalipun, dalam
hal ini masyarakat Bugis banyak yang menggangap bahwa logika orang Bugis itu
tidak baik dan salah karena menghargai dan memuliakan pembunuh. Akan tetapi
di lain sisi kondisi psikologis masyarakat Bugis “sangat peka” dimana sikap
saling mengormati dan saling menghargai begitu dijunjung tinggi yang mana akan
berakibat fatal bagi pribadi yang tidak menghormati dan menghargai orang lain
sebagai manusia.
14
Said, Jati Diri Manusia Bugis, hal. 38.
14
Kemudian kata “Pesse” yang berarti pedas seperti cabe atau merica yang
menganding rasa pedas yang mengigit. Pesse juga bisa diartiakan, pesse perru’
atau bebbua contoh dalam ungkapan mapesse perru’na (perih hatinya) maka
artinya adalah perasaan kasihan, iba hati atau rasa empati terhadap orang lain yang
juga merupakan suatu panggilan hati.15 Ini menunjukan kepekaan masyarakat
Bugis untuk memanusiakan manusia lainnya.
Untuk menciptakan kondisi yang toleran dan solidaritas dalam masyarakat
Bugis pada Zaman dahulu dikenal dengan istilah Assimellereng yang terdapat
dalam Pangaderreng yang kini menjadi prinsip paling dijunjung dalam kehidupan
sehari-hari.
Assimellereng
mengadung
makna
kesehatian,
kerukunan,
kesatupaduan antara satu keluarga dengan yang lainnya, antara suatu masyarakat
dengan masyarakat lainnya.16
Realisasi dari Assimellereng ini terdapat dalam tiga (3) sipa’ (sifat) yaitu,
Sipakatau
(saling menghormati),
sipakalebbi’
(saling menghargai), dan
sipakainge’ (saling mengingatkan) yang kemudian dikenal dengan falsafah 3-S
dalam masyarakat Bugis.
Sehubungan itu penulis ingin menjadikan budaya lokal sebagai salah sudut
pandang untuk menciptakan kesadaran dan penghayatan menuju masyarakat
Indonesia yang toleran dalam skiripsi penulis dengan judul “Toleransi dalam
Kearifan Lokal Masyarakat Bugis”. Sebagaimana yang telah ada tergambar dalam
nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bugis secara idea.
15
Marzuki, Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, h. 135.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 204.
16
15
B. Identifikasi Masalah
1. Selama ini masalah intoleransi di Indonesia kebanyakan timbul dari sudut
pandang agama dan selalu diselesaikan menggunakan teori toleransi yang
diambil dari dalil agama-agama, dalil filsafat Timur dan Barat yang
tentunya berbeda dari segi history dan budaya yang ada di Indonesia.
2. Memberikan ruang kepada kearifan lokal di Indonesia untuk berbicara
dalam permasalahan intoleransi khususnya kearifan lokal masyarakat
Bugis.
3. Indonesia menuju masyarakat yang unggul dan berperadaban memiliki
masalah yang kompleks termasuk perbedaan itu bisa terselesaikan dan
membentuk peradabannya baru.
C. Batasan Masalah
Dalam proposal ini penulis membatasi penelitian secara merinci pada isuisu intoleransi baik daerah dan nasional yang solusinya sudah diwariskan oleh
leluhur masyarakat Bugis:
1. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Bugis Menyikapi perbedaanperbedaan yang ada, baik itu di internal masyarakat Bugis dan
masyarakat di luar dari masyarakat Bugis.
D. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam pembahasan skripsi dengan judul
“toleransi dalam kearifan lokal masyarakat Bugis” sebagai berikut:
1. Bagaimana pesan toleransi dalam kearifan lokal masyarakat Bugis ?
E. Tujuan dan Manfaat penelitian
16
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui dan mendalami konsep toleransi dalam masyarakat
Bugis.
2) Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
3) Setidaknya menjadi sebuah kontribusi kecil untuk mewujudkan bangsa
Indonesia yang toleran.
4) Dan menjadikan budaya lokal salah satu unsur untuk mewujudkan
bangsa Indonesia yang toleran.
2.
Manfaat Akademis
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan
strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Manfaat Praktis
Menambah wawasan mahasiswa pada umumnya, dan bagi penulis pribadi
pada khususnya bahwa ada sebuah etika toleransi yang wariskan para
leluhur kita khususnya masyarakat Bugis kepada kita masih eksis dan
dapat diterapkan dengan baik sesuai cita-cita bangsa yaitu masyarakat
yang toleran. Dan diharapkan memberi sumbangan wacana civitas
akademika bagi jurusan Perbandingan Agama dan Fakultas Ushuluddin.
F. Metode Penelitian
1.
Sumber Data
17
Penelitian ini menggunakan referensi utama buku-buku yang berkaitan
dengan kehidupan masyarakat Bugis di antaranya: Manusia Bugis17, Jati Diri
Manusia Bugis18, I La Galigo19, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis20, dan
Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassa.,21
Adapun data sekunder yang digunaka mungkin dari Jurnal-jurnal, Majalah,
atikel dan koran-koran yang kiranya berhubungan dengan pembahasan etika
secara umum dan toleransi secara umum pula yang bisa memperlancar
pembahasan toleransi dalam kearifan lokal masyarakat Bugis.
2.
Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan
secara terperinci terkait dengan masalah yang hendak diteliti kemudian
menganalisis setiap masalah untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif.
3.
Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk penelitian library research, maka teknik
pengumpulan data dilakukan di sebagian besar perpustakaan, baik perpustakaan
Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan Freedom
Institute, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional, maupun
perpustakaan pribadi yang menyediakan literatur berkaitan dengan tema pada
penelitian ini. Semua buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini
17
Cristian Pelras, Manusia Bugis, Jakarta: Forum Jakarta-Paris.2006.
Marhadi Said, Jati Diri Manusia Bugis, Jakarta: Pro leader, 2016.
19
R.A. Kern, I LA GALIGO Cerita Bugis Kuno Edisi Indonesia, (Jogja: Gadjah Mada
University Press, cetakan pertama, 1989).
20
Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Ujung Pandang: Hasanuddin
Universitas Press, 1992).
21
M. Laica Marzuki. Siri: Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (sebuah
telaah filsafat hukum) (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995).
18
18
dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan relevansi terhadap pembahasan
penelitian ini. Setelah semua buku telah diklasifikasi maka langkah selanjutnya
adalah dibaca dan diteliti dan pada akhirnya dimasukkan pada pembahasan
penelitian yang diangkat.
4.
Teknik Penulisan
Teknik penulisan pada penelitian ini mengacu pada buku “Pedoman
Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”
tahun 2010-201122.
G. Sistematika Penulisan
Pembahasan penelitian ini disusun dalam lima BAB, BAB I adalah
pendahuluan. Di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah dan
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Di dalam bagian ini juga
dikemukakan secara umum tentang toleransi dalam kearifan lokal masyarakat
Bugis.
Pada BAB II, diuraikan toleransi agama meliputi pengertian toleransi
agama yang memberikan definisi-definisi toleransi yang selama ini berkembang.
Perkembangan dan teori toleransi di Indonesia, menjelaskan bagaimana proses
toleransi berkembang dan beberapa teori toleransi yang berkembang di Indonesia
pendapat tokoh-tokoh muslim tentang toleransi: 1. Mukti Ali, beliau sebagai
peletak batu pertama toleransi dalam institusi perguruan tinggi di Indonesia. 2.
Alwi Shihab merupakan tokoh yang cukup diperhitungkan dengan 2 kali menjadi
kabinet pemerintah, selain itu beliau juga menulis beberapa karya tentang
22
Jamhari, dkk., Pedoman Akademik Program Strata 1, 2010/2011 (Jakarta: UIN Syarif
Hiduatullah Jakarta, 2010.
19
toleransi sehingga penulis merasa tertarik meneliti karya beliau. 3. Abdurahman
Wahid, beliau adalah satu-satunya presiden ke-4 Republik Indonesia yang
bergelar Kiyai Haji yang mempuanyai pemikiran yang cerdas dengan argumentasi
sederhana dan rasional serta dilengkapi oleh rasa humanisme yang kuat di setiap
sikapnya terhadap perbedaan.
Pada BAB III, pada bab ini pembahasannya mengenai Perkembangan
mayarakat Bugis meliputi sejarah tentang Bugis kemudian perkembangan
masyarakat Bugis sampai sekarang, kearifan lokal masyarakat Bugis, membahas
bagaimana masyarakat Bugis bisa mengendalikan dan menyelesasikan masalah
yang terjadi dalam masyarakt. Siri na Pesse prinsip hidup masyarakat Bugis,
Prinsip yang menjadi pegangan pokok dalam masyarakat Bugis dalam menyikapi
segala bentuk persoalan.
Pangederreng masyarakat Bugis adalah suatu identitas yang sudah
ditanamkan kepada masyarakt Bugis, meliputi: 1. Ade’, ade’ merupakan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bugis di semua ruang lingkup kehidupan. 2.
Bicara, bicara adalah aturan-aturan peradilan yang normatif yang mengatur
kehidupan masyarakat Bugis, sama hal Pengadilan Negeri yang ada sekarang ini.
3.
Rapang,
rapang
perumpamaan,
contoh,
kesamaan,
atau
sebagai
yurisprudensial, suatu ketentuan yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan
atau kejadian-kejadian yang pernah dilakukan pada waktu yang lalu.23 4. Wari,
wari Wari merupakan suatu sistem yang mengatur tentang batas-batas
23
Mattulada, LATOA : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,
(Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h.334.
20
kewenangan dalam masyarakat, membedakan antara satu dengan yang lainnya
dengan ruang lingkup penataan sistem kemasyarakatan
5. Assimellereng merupakan konsep sehatian, kerukunan, kesatupaduan,
solidaritas antara satu dan lainnya, antara satu keluarga dengan keluarga lain dan
antara manusia sesama manusia yang lainnya.
Pada BAB IV, analisis toleransi dalam masyarakat Bugis, bagaimana
masyarakat menyikapi atas perberdaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat sesuai dengan konsep kearifan lokal masyarakat Bugis.
Pada BAB V, merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang
berisikan Kesimpulan dan Saran penulis yang dianggap penting terhadap toleransi
dalam kearifan lokal masyarakat Bugis ini.
21
BAB II
TOLERANSI BERAGAMA
A. Pengertian Toleransi Beragama
Toleransi berasal dari bahasa Latin “tolerantia” yang artinya menahan.
Ketika seseorang memiliki “toleransi yang tinggi pada rasa sakit”, berarti dia bisa
“menahan rasa sakit”. Dengan demikian toleransi adalah istilah sebuah sikap
untuk menahan dari hal-hal yang dinilai negatif, khususnya dalam hal perbedaan
sikap dan tingkah laku dalam suatu intraksi dalam kehidupan bermasyarakat.1
Menurut definisi Gerald O’Colins SJ dan Edward JFarrugia SJ toleransi
adalah membiarkan dalam damai orang-orang yang mempunyai keyakinan dan
praktik hidup yang lain.2 Menurut Soejorno Soekanto bahwa toleransi adalah
suatu sikap yang merupakan perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak
lain yang tidak disetujui.3
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran,
secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional dan kelapangan
dada. Sedangkan secara terminologi, toleransi yaitu bersifat atau bersikap
menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat,
1
Abd Muqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis alQuran (Depok: Katakita, 2009), h. 5.
2
Gerald O’ Collins SJ dan Edward G. Farrugia SJ, Kamus Teologi (Yogyakarta: Kanisius,
1996), h. 335.
3
Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Royandi, 1985), h. 518.
21
22
pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda dan atau bertentangan dengan
pendiriannya.4
Dalam istilah agama-agama seperti dalam agama Islam (bahasa Arab)
toleransi
biasanya dikatakan ikhtimal, tamaamukh yang artinya, sikap
membiarkan, lapang dada, samakha-tasaamakha: lunak berhati ringan atau ada
yang memberi arti tolerantie itu dengan kesabaran atau membiarkan, dalam arti
menahan diri walaupun diperlakukan senonoh.5
Dalam bahasa Inggris toleransi berasal dari kata tolerate yang berarti
memperkenankan atau sabar tanpa protes terhadap perilaku orang atau kelompok
lain. Ia juga berarti saling menghormati, melindungi, dan kerja sama terhadap
yang lain.6 Bahasa Yunani toleransi disebutkan dengan istilah sophrosyne yang
artinya adalah moderasi atau mengambil jalan tengah.
Dari semua penjelasan di atas toleransi dimaksudkan adalah adanya sikap
untuk saling menghasgai dan menghormanti orang lain, dan menjaga sikap dalam
memutuskan langkah yang dilakukan setelah adanya suatu tindakan yang
menuinggung perasaan dari kelompok yang berbeda.
Jadi, apabila toleransi yang telah dikemukakan di atas, ditimbahkan
dengan kata “beragama” maka yang terpikirkan adalah sikap sabar dan menahan
diri untuk tidak menganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan
4
Binsar A. Hutabarat, Kebebasan Beragama VS Toleransi Beragama,
http://www.toleran.com, di akses pada tanggal 28 Oktober 2016.
5
Djohan Efendi & Ismet Natsir, ed., Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad
Wahib (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 55.
6
Sufa’at Mansur, Toleransi dalam agama Islam (Yogyakarta: Harapan Kita, 2012), h. 1.
23
dan ibadah penganut agama-agama lain. Toleransi berarti sikap lunak,
membiarkan dan memberi keleluasaan kepada penganut agama lain untuk
memenuhi hak dan kewajiban atas agama yang dianutnya.
Dalam hubungan antar agama, toleransi dapat berupa toleransi ajaran atau
toleransi dogmatis dan toleransi bukan ajaran praksis.7 Dengan toleransi dogmatis
maka pemeluk agama tidak menonjolkan keunggulan ajaran agamanya masingmasing. Toleransi praksis maka pemeluk agama akan membiarkan pemeluk
agama yang lain melaksanakan keyakinan mereka masing-masing. Pemahaman
demikian ini akan melahirkan konsep damai dalam kehidupan manusia.
Menurut Thogir senada dengan M. Natsir yang mengatakan man is born as
social being (manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial). Sebagai akhluk sosial
manusia tidak bisa melepaskan komunikasi dan hubungan pergaulan terhadap
sesama. Pada tataran ini akan terjadi proses pembaruan yang tidak mungkin
dihindari.8
Toleransi dalam beragama bukan berarti seseorang boleh dengan bebas
menganut agama tertentu dan esok harinya berpindah atau menganut agama yang
lain. Sehingga nantinya seseorang itu dengan bebasnya mengikuti ibadah dan
ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi,
toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan dan saling hormat
terhadap perbedaan yang ada.
7
A.M Hardjana, Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik (Yogyakarta:
Kanisius, 1993), h. 115.
8
Thohir Luth, Masyarakat Madani: Solusi Damai dalam Perbedaan (Jakarta: Mediacita,
2006), h.76.
24
B. Perkembangan dan Teori Toleransi Agama di Indonesia
Perkembangan tentang toleransi diikuti oleh perkembangan globalisasi dan
modernitas yang ada, tidak bisa lagi memaksakan kehendak pribadi dan suatu
kelompok yang tentunya akan menghambat suatu kemajuan. Sehingga bisa
dikatakan bahwa apabila suatu kelompok yang intoleran maka akan mengalami
stagnansi dari segala sendi kehidupan. Kemudian toleransi dalam keagamaam
mulai dilirik dan dikembangkan melalui doktrin yang tentunya belandaskan kitab
suci.
Toleransi agama-agama yang diakui di Indonesia berjalan sesuai dengan
pemahaman keagamaan dalam setiap agama itu sendiri. Misalnya dalam Gereja
katolik Roma, beberapa keputusan Konsili Vatikan II telah menumbuhkan sikap
yang lebih positif terhadap keberadaan agama-agama lain. Sedangkan dalam
kalangan Protestan selama tahun 1970-an Dewan Gereja-Gereja dunia
menganggap semakin penting artinya dalam upaya menggalakkan dialog yang
sekarang tetap menjadi pembahasan dalam setiap Gereja yang menjadi
anggotanya, kemudian umat Kristen mulai meninggalkan sikap eksklusifnya 9
Dalam ajaran Protestan diajarkan hidup yang rukun beragama adalah
seperti yang diajarkan dalam Alkitab yaitu hukum cinta kasih. hukum kasih yang
mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, bagi
Kristen Protestan adalah hukum utama di dalam kehidupan orang Kristen.
Sedangkan dalam Kristen Katolik seperti yang telah dikatakan sebelumnya,
9
Norbert Ama Ngongu, “Pluralisme Dalam Perspektif Agama Katolik”artikel diakses
pada tanggal 4 September 2016 dari http://norbertang.blogspot.co.id/2008/03/pluralisme-dalamperspektif-agama.html
25
bahwa kerukunan antar umat beragama terkandung dalam konsili Vatikan II
tentang sikap gereja terhadap agama lain.
Perkembangan yang ada memaksa setiap manusia untuk hidup toleran dan
makin hari makin erat bersatu, hubungan antar bangsa menjadi kokoh, gereja
lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama
dan karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan
juga di antara para bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan
secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk
hidup berkawanan.10
Toleransi agama bukan sekedar wacana yang berkembang pada saat ini,
tetapi sudah terbentuk dalam berbagai formulasi yang terus berkembang. Semua
agama pada dasarnya menjunjung tinggi nilai toleransi ini, Islam mengajarkan
(amar ma’ruf nahi mungkar), Kristen mengajarkan cinta kasih, Hindu
mengajarkan dharma dan Budha mengajarkan jalan kebenaran yang semuanya
menuntut pemeluknya untuk menebarkan perdamaian dan sikap toleran kepada
pemeluk agama lain. Dalam perkembangan toleransi beragam memuat beberapa
konsep yaitu:
1. Pluralisme
Pluralitas yang berarti majemuk atau berbeda identitas. Sebagaimana
dinyatakan Alwi Shibab pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan
10
Wijaya, Spiritualitas Baru, h. 9.
26
adanya kemajemukan, namun yang terpenting adalah keterlibatan aktif menyikapi
fakta pluralitas itu. Dengan kata lain, pluralisme agama berarti setiap pemeluk
agama dituntut untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi turut serta
dalam usaha memahami perbedaan ajaran masing-masing dan persamaan
kedudukan pemeluknya dalam pergaulan kehidupan di masyarakat demi
tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.11
Dari sikap yang aktif untuk memahami perbedaan akan tumbuh
kesadaraan dan akan menjunjung nilai-nilai yang perbedaan. Bila komunitas
agama menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme maka akan menghasilkan potensi
besar yang membangun toleransi dalam kehiduapan sehari. Sebaliknya potensi
destruktif akan dominan jika komunitas agama tidak mau menghargai perbedaan
bahkan menganggap superior agamanya dan memandang inferior agama lain.12
Menurut Muhaimin pluralistik adalah Sikap pluralistik (kemajemukan)
dalam hidup bukan berarti mengajak seseorang untuk beragama dengan jalan
sinkretisme, yakni semua agama adalah sama, dan mencampurbaurkan segala
agama menjadi satu.13
Demikian juga bukan mengajak seseorang untuk melakukan sintesis
(campuran) dalam beragama, yaitu menciptakan agama baru yang elemenelemennya diambilkan dari berbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap
pemeluk agama merasa bahwa dalam agama sintesis (campuran) itu menjadi
11
Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka (Bandung: Mizan, 1999), h. 34.
Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai – Nilai Al-Qur’an dalam Pendidikan
Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 122.
13
Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan,
Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press,
2009), h. 317.
12
27
solusi dari permasalahan agama-agama yang ada sebelumnya. Agama sintesis
tidak mungkin dapat diciptakan, karena tiap-tiap agama mempunyai latar
belakang sejarahnya sendiri yang tidak begitu saja diputuskan dan tiap-tiap agama
terikat kepada hukum-hukum sejarahnya sendiri.
2. Inklusivisme
Inklusivisme yaitu pemikiran atau sikap yang memandang bahwa
kebenaran yang di anut oleh suatu agama adalah juga dianut oleh agama lain.
Oleh karena itu inklusivisme memandang kebenaran yang universal yaitu
memandang bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai universal yang bisa diakui
dan dianut oleh siapa saja dan dari pemeluk mana saja. Dalam pemikiran ini
terdapat titik temu antara agama-agama yang ada dalam aspek tertentu dari ajaranajarannya.
Menurut Amin Abdullah membagi wilayah sosial keberagamaan umat manusia,
ada wilayah yang disebut normatifitas dan sakralitas, dan pada saat yang sama
juga ada wilayah historitas dan profanitas.14
3. Dialog
Dialog agama sangat diperlukan di era keterbukaan ini. Dialog agama
bukanlah untuk mencari kebenaran agama masing-masing, tetapi menjembatani
segala perbedaan yang ada dan memuaskan semua komunitas yang berdialog.
Oleh karena itu hendaknya bahasa yang didialogkan adalah bahasa-bahasa sosial,
14
Ahmad Norma Permata, ed., Metodologi Studi Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000), h. 5.
28
kepentingan bersamaan nilai-nilai profan yang ada dalam agama bukan
sebaliknya mendialogkan hal-hal yang normatif dan dogmatif yang memang
sebenarnya dimiliki dan diakui oleh penganutnya masing-masing. W.C. Smith.15
Keduanya harus terkadang bercampur aduk dan sangat erat kaitannya. Oleh
karena itu inklusif sangat dibutuhkan sehingga meminimalisir bias keagamaan
dengan menonjolkan emosi keagamaan dan simbol-simbol keagamaan yang
destruktif.
C. Pendapat Tokoh-Tokoh Muslim tentang Toleransi
Melihat penomena intoleran yang semakin membesar dan meluas
dikalangan masyarakat Indonesia para tokoh intelektual muslim khususnya
Indonesia sendiri mencari jalan keluar dari keresahan ini. Adapun solusi yang
ditawarkan oleh para tokoh di Indonesia antara lain sebagai berikut :
1.
Mukti Ali
Mukti Ali adalah tokoh Indonesia pertama yang membawa Ilmu
Perbandingan Agama untuk dipelajari dikalangan Mahasiswa. Menurut beliau
bahwa alasan paling pokok untuk melibatkan diri dalam studi Ilmu Perbandingan
Agama adalah untuk meningkatkan hubungan antara pemeluk agama, keterbukaan
terhadap agama-agama lain, juga menumbuhkan toleransi aktif dalam menyikapi
perbedaan.16 Dalam penelitian agama-agama Mukti Ali memberikan pendekatan
baru yang menggabungkan pendekatan lintas disiplin dan interdisiplin yang
15
Permata, Metodologi Studi Agama, h. 91.
Singgih Basuki, Pemikiran keagamaan Mukti Ali (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h.
16
242.
29
disebut dengan pendekatan sintetis.17 Ada 4 hal yang diprioritaskan dalam upaya
para ahli lainnya merumuskan formulasi sehingga diharapkan akan mencapi
masyarakat toleran.
a. Sinkretisme
Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah
sama. Sinkretisme berbendapat bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai
wujud dan manifestasi dari keberadaan azali (zat), sebagai pancaran dari terang
azali yang satu, sebagai ungkapan dari subtansi yang satu, dan sebagai ombak dari
samudra yang satu.18 Paham ini secara tidak langsung menyatukan semua unsurunsur yang ada pada tiap-tiap agama.
Mukti Ali bagaimana mengkaji agama tanpa hanya melihat dari satu sudut
pandang saja akan tetapi melihat suatu penomena agama yang timbul dalam
masyarakat akan keliru apabila hanya menggunakan satu sudut pandang saja
seperti hal para orientalis memandang Islam hanya dari ajarannya saja, atau juga
para ulama menggunakan pendekatan doktriner yang dihubungkan dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat.19 Melihat agama yang hanya dari satu sudut
pandang saja menurut Mukti Ali akan menghasilkan kesimpulan yang keliru dan
tidak utuh pada suatu agama, sehingga dibutuhkan ilmu pengetahuan yang
lainnya.20
b. Rekonsepsi
17
Basuki, Pemikiran keagamaan Mukti Ali, h. 243.
Mukti Ali, Agama dan Keagamaan di Indonesia (Jakarta: Biro Humas Departemen
Agama RI, 1972), h. 118.
19
Singgih, Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali, h. 244.
20
Mukti Ali. Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia (Yogyakarta: Jajasan Nida,
1971), h. 76.
18
30
Agama adalah suatu keyakinan mengenai cara hidup yang benar, kegiatan
ini adalah desakan atau tuntutan alam semesta. Keinginan yang timbul menjadi
inti dari agama yang bersifat pribadi dan universal, artinya agama merupakan
pengalaman seseorang tetapi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan umum dari
hati manusia. Untuk itu disusun agama universal yang memenuhi segala
kebutuhan dengan merekonsepsi, menata, dan meninjau ulang agama masingmasing dalam konfrontasi dengan agama-agama lain.21
Ini menjadi sebuah konsep yang akan berkembang dari kondisi paham
keagamaan yang terus menerus menimbulkan konflik dikalagan pemeluk agama.
Dimana paham ini memandang bahwa masing-masing agama harus mempunyai
celah yang rasioanal untuk meredam dan mengasilkan sebuah terobosan solutif
dari konflik-konflik agama yang ada. Sehingga dari semua agama menghasilkan
pandangan yang sama dari semua unsur agama yang berbeda.
Agama adalah seperangkat doktrin, kepercayaan, atau sekumpulan norma
dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenaranya. Adapun
kebeagamaan adalah penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap
doktrin, kepercayaan atau ajaran-ajaran Tuhan itu, yang tentu saja menjadi relatif
dan sudah pasti kebenarannya menjadi bernilai relatif pula.22
c.
Sintesis
21
Khairah Husin, “Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Agama di
Indonesia,” Jurnal Ushuluddin UIN RIAU, Vol. XXI, No.1 (Januari 2014), h. 109.
22
Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 20.
31
Sintesis yakni membuat agama baru dengan formulasi yang diambil dari
berbagai pada setiap agama-agama yang ada. Sehingga pemeluk dari suatu agama
merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke
dalam agama sintesis tadi, dari agama sintesis ini orang-orang akan menganggap
bahwa toleransi dan kerukunan antar umat beragama akan tercipta dengan baik.
dalam hal ini Mukti Ali berpandangan seperti berikut :
“Agama sintesis sendiri tidak bisa diciptakan karena setiap agama
memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat
diputuskan begitu saja. Dengan kata lain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan
kuat kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.”23
Mukti Ali menawarkan sintesis yang berusaha menggabungkan kedua
kecenderungan melalui gagasan yang menggunakan pendekatan religio-scientific
(ilmiah-agamais) atau scientific-cumdoktrinair dalam studi agama.
Jadi metode sintesis merupakan cara memahami agama yang memadukan
antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dengan
metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk memahami agama
yang tampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis, sedangkan metode
normatif digunakan untuk memahami agama yang terkandung dalam kitab suci.
Melalui metode teologis normatif ini seseorang memulainya dengan memahami
agama sebagai agama yang mutlak benar. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat
agama sebagaimana norma ajaran yang berkaitan dengan berbagai aspek
kehidupan manusia yang secara keseluruhan diyakini amat ideal.
23
Mukti Ali, “Setuju dalam perbedaan,” Majalah Mawas Diri, no. 1 (Maret 1972), hal. 6.
liat juga Faisal Ismail, Republik Bhineka Tunggal Ika:Mengurai Isu-isu Konflik Multikulturalisme,
Agama, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keragamaan, 2012), h. 9.
32
Dari metode ilmiah religius ini memungkin terjadinya sikap fanatik radikal
dari suatu kelompok agama disebabkan oleh kebenaran yang dianggapnya mutlak,
dimana suatu ajaran agama atau dogma secara ilmu pengetahuan telah
membuktikan kebenarannya. Metode ini rawan untuk diterapka dalam
menciptakan kondisi rukun bagi pemeluk antar umat agama.
d. Penggantian
Pandangan ini menyatakan bahwa untuk mewujudkan toleransi maka
semua agama akan melebur menjadi satu, dan agama itulah yang benar. Seraya
berupaya keras agama para pengikut agama-agama lain memeluk agamanya, Ia
tidak rela melihat orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda
dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama lain itu haruslah
diganti dengan agama yang dia peluk. Dengan jalan ini ia menduga bahwa
kerukunan hidup umat beragama dapat tercipta dan dikembangkan. 24
e. Agree in Disagreement
Dalam mewujudkan kondisi kehidupan toleransi, dialog antaragama,
damai dan harmoni dalam masyarakat yang berbeda-beda Mukti Ali memberikan
konsep berupa bentuk prinsip setuju dalam ketidaksetujuan “agree in
disagreement” yang mana ketidaksepahaman yang terjadi dalam masyarakat,
karena kondisinya yang majemuk semua setuju dalam perbedaan itu dan
mengesampingkan perbedaan yang ada sehingga tercipta kehidupan yang
harmonis antar umat beragama.
24
Ali, “Setuju dalam perbedaan,” Majalah Mawas Diri, no. 1 (Maret 1972), h. 9.
33
Prinsip ini menekankan pengakuan dari para pemeluk agama, pengakuan
bahwa ada hal dasar yang menjadikan agama memiliki persamaan dan
perbedaan.25 Dari pengakuan ini yang dapat menumbuhkan sikap saling
menghargai dan saling menghormati, sehinga harmonisasi lebih mudah untuk
diwujudkan antar agama, suku, ras, dan kelompok.
Dari kelima konsep di atas tepat dikembangkan untuk membina dan
mengembangkan toleransi di Indonesia, karena tercermin beberapa sikap yang
rela untuk meluangkan dan juga kesadaran yang ditimbulkan apabila dari kelima
konsep diatas di pegang teguh setiap masyarakat dan kelompok agama. Dari
konsep sinkretisme yang notabenenya dibutuhkan sikap rendah hati untuk
mengatakan bahwa semua agama berangkat dari asali yang satu.
2.
Alwi Shihab
a. Saling Mengenal
Sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab, bahwa umat Islam dihadapkan
kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang
pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik internal atau antar agama
25
Mukti Ali, Agama dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Biro Humas Departemen
Agama RI, 1972), h. 118.
34
adalah fenomena nyata.
26
Sebagaimana ketentuan dalam firman Allah yakni QS.
al-Hujurat ayat 13, Alwi Shihab mengemukakan ayat Al-Quran yang berbunyi:
َّ َعارفُىا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد
َ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ لَ ْقنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثى َو َج َع ْلنا ُك ْم ُشعُىبا ً َوقَبائِ َل لِت
َِّللا
َّ أَ ْتقا ُك ْم إِ َّن
َّللاَ َعلِي ٌم خَ بِي ٌر
Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku suku supaya kamu saling kenal-menganal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.27
b. Keberagamaan Keyakinan
Keberagamaan keyakinan menurut Alwi Shihab adalah sebagai peristiwaperistiwa kekerasan baik terhadap individu maupun terhadap kelompok.
Penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa keagamaan dengan
mengatasnamakan agama ataupun Tuhan. Fenomena intoleransi anatara umat
beragama tersebut masih terus berlangsung sampai detik ini. Padahal kalau kita
perlu meyakini, Alwi Shihab tidak mengajarkan sesuatu yang berbau kekerasan
yang mengatasnamakan agama.
Alwi sendiri memaknai keberagamaan keyakinan adalah sikap pasrah dan
tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang patuh dan tunduk kepada
Tuhan disebut Muslim, bentuk jamaknya adalah “muslimin”. Dalam kepasrahan
ini terkandung keyakinan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus
disembah, dipuja, dan diagungkan. Ajaran ini dalam Islam disebut Tauhid. Ini
26
Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka, h. 39.
QS. Al-Hujurat, Ayat 13.
27
35
adalah inti dan prinsip tertinggi serta ajaran utama bukan hanya bagi agama yang
dibawa Oleh Rasulullah SAW, tetapi juga dalam semua agama yang ada.
c. Keberagamaan Etnis
Keberagamaan etnis menurut Alwi Shihab adalah kebudayaan sebagai
sesuatu yang mandiri, utuh dan statis sesungguhnya mereduksi makna kebudayaan
sebagai proses kemanusiaan. Artinya, sebagai proses kemanusiaan, kebudayaan
dimanapun, kapanpun selalu mengalami perubahan dan perkembangan secara
terbaru. Bahkan bisa jadi ia menjadi sekedar fosil pada saatnya. Itulah sebabnya,
keinginan untuk menyatukan kebudayaan tanpa dibarengi dengan kesadaran
multikultural sifatnya tidak permanen. Karena yang terjadi kemudian adalah (kita)
hanya seolah menghimpun kebudayaan dalam satu simbol kebudayaan nasional.28
3.
Abdurrahman wahid
a. Pribumisasi Islam
Islam pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di Jazirah Arab
dan dilanjutkan para sahabat-sahabat nabi beserta para tabi’in sampai saat ini
tersebar di seluruh dunia, akan tetapi dengan datang Islam di Jazirah Arab tidak
serta merta menolak semua tradisi Arab pra-Islam (tradisi masyarakat Arab praIslam). Inti budaya, tradisi dan adat setempat tidak bertentangan secara diametral
dengan Islam sehingga itu menjadi ciri khas dari fenonema Islam di tempat
28
Listiyono Santoso, Mewacanakan Nalar Agama yang Inklusif dalam konteks Kemanusiaan dan
Kemajemukan Indonesia, diakses pada 15 November 2016 dari
https://www.academia.edu/8554403/Mewacanakan_Nalar_Agama_yang_Inklusif_dalam_konteks
_Kemanusiaan_dan_Kemajemukan_Indonesia,
36
tertentu.29 Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia, tidak serta
merta menghapus semua tradisi, budaya dan adat masyarakat setempat yaitu
masyarakat Nusantara pada saat itu.
Mayoritas masyarakat menganggap bahwa agama dan budaya bagaikan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Islam bersumberkan al-Qur’an,
wahyu yang bersifat normatif maka cenderung permanen. Sedangkan budaya
ciptaan manusia, dimana budaya sendiri dalam perkembangannya mengikuti
zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi
kemungkinan
manifestasi
kehidupan
beragama
dalam
bentuk
budaya.30
Sederhananya bahwa Islam mengandung nilai normatif dan universal, sedangkan
budaya atau tradisi akan selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan
struktur masyarakat dan juga perkembangan zaman.
Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus menerus
sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak
gersang. Kekayaan budaya memungkinkan adanya hubungan antar berbagai
kelompok atas dasar persamaan. Dalam hal ini Gus Dur membedah antara agama
dan budaya menambah kreatifitas manusia dalam memahami apa yang diberikan
oleh Allah.
Selanjutnya Gus Dur lebih menawarkan bahwa pribumisasi bukan
merupakan suatu upaya yang kalah dari kuat suatu kebudayaan di suatu daerah
akan tetapi bagaimana hukum Islam bisa menjadi solusi dari permasalahan
29
Umarudin Masdar, Membaca Pememikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi
(Yogyakarta Pustaka Pelajar), h. 141.
30
Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta:
Desantara, 2001), h. 117.
37
kontemporer dalam masyarakat Islam. pribumisasi Islam dilakukan agar kita tidak
tercabut dari akar budaya.31 Sebaliknya, kecenderungan “Arabisasi” bukan saja
membuat kita jadi terasing dengan budaya sekitar, tetapi dalam banyak hal sering
tidak bersesuaian bahkan bertentangan dengan keperluan masyarakat di Indonesia.
Pribumisasi
juga
bukan
upaya
untuk
menghindarkan
timbulnya
perlawanan dari kekuatan budaya setempat, tetapi justeru agar budaya itu tidak
hilang. Lalu, bagaimanakah proses pribumisasi berlangsung dan dapat dikawal,
Gus Dur menawarkan pola yang cukup sederhana, yaitu dengan mempergunakan
variasi pemahaman nash dengan tetap memberikan peranan kepada usul fiqh dan
qaidah fiqhiyah.32
Qaidah fiqhiyah seperti al- cadat al-muhakkamah (adat istiadat menjadi
hukum) dan al-muhafazatu bi qadimi al- sahih wa akhazu bi al-jadid al-aslah
(memelihara yang lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).33
misalnya boleh menjadi petunjuk untuk mendorong, mengawal, dan sekaligus
mengevaluasi gerak pribumisasi ini.
Dalam upaya mewujudkan pribumisasi Islam ini, menurut Gus Dur bahwa
umat Islam tidak perlu melihat budaya Arab, tapi Islam yang dilihat dari sisi
agamanya bukan berkembang dari budaya Arab karena Islam diturunkan pertama
kali di Arab. Sehingga Islam bisa menjadi ways of life dengan kondisi budaya
yang jauh berbeda dengan budaya Arab, konsep Islam yang dinamis sangat
31
Abdurahman Wahid, Islam Ku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara
Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 245.
32
Wahid, Islam Ku, Islam Anda, Islam Kita, h. 246.
33
Muhammad Bakir dan M. Zaid Mahyudi, Gus Dur: Santri Par Exellence (Teladan Sang
Guru Bangsa “Abdurahman Wahid Ketegaran Pluralisme Akar Rumput) (Jakarta: Kompas, 2010),
h. 200.
38
dibutuhkan sekarang ini melihat bahwa konteks keberagamaan seseorang
kebanyaka hanya sebagai formalitas semata.
b. Humanisme dan Demokrasi Gus Dur
Gus Dur dikenal sebagai seorang tokoh humanis dikalangan masyarakat,
apa yang diperjuangkannya merupakan nilai kemanusiaan tanpa adanya embelembel yang menjadi dinding pembatas untuk menegakkan hak kemanusiaan yang
dimiliki oleh seseorang. Gus Dur dalam praktik keagamaannya sering kali
melebih batasan dalil-dalil agama yang statis, menengakkan nilai-nilai
kemanusiaan yang universal adalah intisari dari semua ajaran agama yang mana
toleransi dan hidup damai merupakan tujuan semua agama.34
Masuknya Islam di Nusantara secara historis pada saat itu mayoritas
masyarakatnya telah berkembang kepercayaan Hindu, Budha dan ajaran agamaagama lokal di setiap daerah, akan tetapi penyebaran Islam pada saat itu masih
diberi tempat sehingga Islam bisa menjadi agama mayoritas dianut masyarakat
Indonesia. Dengan ini Gus Dur menganggap bahwa sangat ironi ketika sekarang
ini penganut agama Islam yang mayoritas menjadikan Islam yang tidak toleran
atas hak-hak kemanusia orang lain yang minoritas.35
Kaum minoritas hakikatnya hanya ingin diperlakukan selayak manusia
yang bebas untuk memperoleh hak sebagai manusia dan warga negara Indonesia
tanpa harus membedakan kelompok, agama, etnis ataupun budayanya.
Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi
dari perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Baginya konsep demokrasi adalah
34
Ali Masykur Musa, Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2002), h. 120.
35
Musa, Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur, h. 121.
39
konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran
Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama,
Islam adalah agama hukum, dengan pengertian bahwa agama Islam yang
mempunyai nilai hukum dimana dalam hal ini hukum berlaku bagi semua orang
tanpa memandang ras, suku, kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas.
Terkait dengan kaum minorits Gus Dur menganggap bahwa dengan
penerapan demokrasi yang sehat dan baik akan memberikan tempat bagi para
kaum minoritas untuk bernaung, memperoleh hak dan juga berekspresi
sebagaimana masyarakat lainnya, secara sederhanya dikenal dengan prinsip
kesetaraaan.36
Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (amruhum syuraa
bainahum), artinya adanya tradisi bersama membahas dan mengajukan pemikiran
secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam
selalu berpandangan memperbaiki kehidupan, menguatkan inspirasi dan juga
sekaligus menjadi kekuatan moral dalam masyarakat37
Ide demokratisasi Gus Dur muncul karena ia melihat ada kecenderungan
umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai
“inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Maksudnya bahwa selama ini Islam selalu
dijadikan sebagai alternatif dari permasalahan yang ada dalam masyarakat dimana
pada praktiknya juga tidak berjalan baik, sehingga menurut Gus Dur agama
semestinya menjadi inspirasi.
36
Listiono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta: Ar-Ruszz Media, 2004), h.190.
Santoso, Teologi Politik Gus Dur, h.199.
37
40
Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan yang tidak boleh
dilupakan dan diabaikan yaitu tentang “kemanusiaan”. Pada dasarnya hakekat
demokrasi itu adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri.
“dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kesediaan untuk memperjuangkan
kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan
itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas dalam kehidupan bangsa
dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang terlibat dengan
penderitaan rakyat di bawah”.38
Berangkat dari kedua alasan ini bahwa dengan humanisme dan
demoktatisme yang dimilikinya tergambar dari ide untuk mencabut ketetapan
MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang baginya substansi gagasan itu merangkum
nilai cinta yang universal non-diskriminasi terhadap suatu kelompok yang telah
dihilangkan hak demokrasinya.39
c. Pluralisme dan Toleransi
Pluralisme dalam pandangan Gus Dur menjadi sebuah keniscayaan dalam
sebuah negara yang dianugrahkan dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan terus
menghiasi kemajemukan Indonesia sampai kapan pun.40 Menurut pendapat Gus
Dur bahwa UUD 1945 dan Pancasila bentuk jaminan atas sikap toleransi dan juga
mengandung nilai Islam “kekuatan inspratif”.
38
Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999), h.
190.
39
Limas Susanto, Gus Dur: Santri Par Exellence, h. 165.
Bakir dan Mahyudi, Gus Dur: Santri Par Exellence, h.199.
40
41
Selain itu nilai toleransi yang beliau dapatkan melihat bahwa dari sekian
banyak perbedaan pendapat dalam tradisi keilmuannya bahwa perbedaan itu tidak
sedikit pun mengurangi penghormatan terhadap pendapat lain, dan juga dari
penghormatan itu tidak mengurangi sedikit pun keyakinan atas pendapat yang lain
meskipun jelas berbeda. Bahkan sejak dari kecil Gus Dur sudah menadapatkan
pembelajaran tentang kesetaraan (semua agama dipandang sama dan harus
dihormati) dari semua pemeluk agama saat ayahnya menjadi Menteri.41
pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan ini muncul karena dipengaruhi
beberapa faktor di antaranya adalah konflik berkepanjangan yang terus terjadi dari
hari ke hari sampai sekarang ini baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang
mengatasnamakan agama di berbagai daerah di Indonesia.
Konflik
berkepanjangan
ini
menunjukkan
bahwa
belum
adanya
penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan mudahnya orang dengan main
hakim sendiri. Sehingga situasi yang seperti ini perlunya melibatkan tokoh agama,
birokrat, penegak hukum, pendidik, dan tokoh masyarakat berperan dalam
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara menanamkan nilai-nilai agama
yang berkaitan dengan moralitas guna menyadarkan pluralitas masyarakat.
Khususnya adalah kelompok minoritas agama, etnis dan gender lainnya,
karena ia memang telah mengkampanyekan toleransi agama dan kerukunan hidup
sejak lama. Bahkan, Gus Dur memasukkan beberapa anggota kabinet dari
kelompok Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Dalam kapasitasnya sebagai
presiden, Gus Dur melanjutkan aktifitasnya dalam mempromosikan toleransi dan
menunjukan komitmennya terhadap kebebasan beragama dengan memanggil para
pemuka agama Hindu, Buddha, Shikh dan lainnya dalam festival agama-agama.
41
Abdurahman Wahid dan Daisaku Ikeda, Dialog Peradaban untuk Toleransi dan
Perdamaian (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 44.
42
43
BAB III
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUGIS
A. Perkembangan Masyarakat Bugis
Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang menempati bagian selatan
pulau Sulawesi. Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan biasanya disebut dengan to
Ogi, to Bugi atau to Ugi, yang kebanyakan menurut beberapa ahli kata ugi atau
ogi diambil dari kata La Sempugi. La Sempugi sendiri adalah sebuah nama dari
bapak La Wicudai yang kemudian menjadi mertua dari Sawirigading.1
Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk
beberapa kerajaan dan kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara,
dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain
Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang.
Suku Makassar dan Mandar terdapat hubungan melalui proses pernikahan
oleh Keturunan raja-raja Bugis sehingga adanya pertalian darah suku terdekat dari
pemukiman masyarakat Bugis. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa
Kabupaten yaitu: Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai dan
Barru.2
Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba,
Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar
adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya
1
Sawirigading merupakan tokoh yang menjadi manusia pertama di dalam Lontara’ suku
Bugis.
2
Hamid Abudullah, Manusia Bugis Makassar (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1985), h. 12.
43
44
beberapa perang diantara perang melawan penjajah dan juga perang saudara yang
memaksa beberapa masyarakat Bugis harus meninggalkan kampung halamannya
(ri akkanropangi tanah) dan pergi ke beberapa daerah seperti di Kalimantan,
Jawa, dan Sumatera.3
B. Siri Na Pesse Prinsip Hidup Masyarakat Bugis
Dalam kebudayaan masyarakat Bugis perbuatan seseorang tidak bisa
dipisahkan oleh seseorang yang lainnya, ini disebabkan karena masyarakat Bugis
dilandasi pada suatu prinsip pemuliaan harkat dan martabat seseorang sebagai
manusia,
disebutkan
dalam
bahasa
Bugis
“tau-sipakatau”
yang
bisa
diterjemahkan dengan “memanusiakan manusia sebagai layaknya manusia yang
sesungguhnya”.
Mashadi Said dalam bukunya “Jati Diri Manusia Bugis” menyebutkan
bahwa “manusia secara individual harus memiliki dua keutamaan yaitu siri’ dan
pesse. Siri’ dan pesse yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan
dijadikan sebagai prinsip bagi masyarakat Bugis”.4 Kedua prinsip ini merupakan
pola hidup yang menentukan bentuk perilaku dan semua intraksi dalam praktik
hidup bermasyarakat. Tuntutan prinsip itu selalu didasari oleh masyarakat Bugis
sebagai suatu hal yang menjadi landasan dalam bertingkah laku. Siri’ merupakan
adat kebiasaan yang melembaga dan masih besar pengaruhnya dalam kehidupan
masyarakat Sulawesi Selatan (Bugis).5
3
Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis (Jakarta: Prodeleader, 2016), h. 36.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 98.
5
Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Ujung Pandang: Hasanuddin
Universitas Press, 1992), h. 168.
4
45
1. Siri’
Ada banyak pendapat tentang siri’ dalam pembahasan ini Mattulada yang
dikutip oleh Laica Marzuki menyebutkan bahwa siri’ adalah “kesadaran tentang
nilai martabat yang didukung oleh tiap-tiap orang dalam tradisi kehidupan
masyarakat Bugis” dikatatan, siri’ juga merupakan kesadaran kolektif yang amat
peka, dibebankan kepada tiap-tiap orang anggota persekutuan hidup untuk
membangunya, untuk mempertahakan dan menegakkannya.6
Nilai siri’ dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural yang
memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku
itu dapat diamati sebagai pernyataan ataupun wujud kehidupan masyarakat Bugis.
Apabila kita mengamati pernyataan nilai siri’ ini atau lebih konkritnya
mengamati kejadian-kejadiannya berupa tindakan, perbuatan atau tingkah laku
yang katanya dimotivasi oleh siri’, maka akan timbul kesan bahwa nilai siri’ itu
pada bagian terbesar unsurnya dibangun oleh perasaan sentimental atau
sejenisnya. Cara pandang seperti ini jelas merupakan sebuah cara pandang yang
kurang lengkap terutama apabila hendak mengamatinya dari sudut pandang
kebudayaan. Sebab hal tersebut merupakan sebuah nilai yang bukan hanya
6
M. Laica Marzuki. Siri: Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (sebuah
telaah filsafat hukum) (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 36.
46
sekedar memiliki nilai kebudayaan akan tetapi juga merupakan sebuah prinsip
atau falsafah hidup manusia.7
Kemudian, hakikat kebenaran dari falsafah inilah yang mulai surut dalam
setiap tingkah laku maupun tindakan kolektif masyarakat Bugis Sebagai seorang
masyarakat Sulawesi Selatan, penulis melihat, missinterpretasi semacam ini sudah
lama terjadi.
Bagaimana rasa malu yang tidak ditempatkan pada tempat semestinya,
mendahulukan rasa amarah ketimbang sikap rasional dalam memahami suatu
permasalahan. Jika berkaca pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah saat
ini, mulai dari demonstrasi yang selalu berakhir dengan kerusuhan, sampai kepada
perilaku bermasyarakat
yang kebanyakan berujung
pada konflik
yang
menimbulkan korban jiwa. Ini disebabkan karena siri yang sekarang dipahami
masyarakat mengalami pergeseran makna.
Disintegrasi seperti inilah yang kemudian berpotensi melahirkan
ketidakstabilan
dalam
kehidupan
sosial
masyarakat
sehingga
seringkali
menimbulkan konflik. Dimana siri’ pun harus timbul pada diri seorang yang telah
berbuat zalim, khianat dan curang atau yang berakibat akan merugikan orang lain
dalam suatu kelompok masyarakat.8 Maksudnya siri’ juga harus timbul dari dalam
diri seseorang untuk menjaga siri’ orang lain dalam bentuk berbuat baik, amanah,
dan menghargai orang lain.
7
Mattulada, LATOA : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis
(Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 62.
8
Nurhayati Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas (Makassar: La Galigo Press, 2012), h.
175.
47
Apabila
kita
ingin
mendalami
makna
siri’
dengan
segenap
permasalahannya, antara lain dapat diketahui dari lontara‟ La Toa, Dimana dalam
lontara ini berisi paseng (pesan atau amanat) dan pappanngaja (nasehat-nasehat)
yang merupakn kumpulan petuah untuk dijadikan sebagai suri tauladan.9
Kata Latoa sendiri sejatinya memiliki arti petuah-petuah, dimana juga
memiliki hubungan yang erat dengan peranan siri’ dalam pola hidup atau adat
istiadat masyarakat Bugis. Misalnya dapat dilihat pada beberapa point dalam
lontara‟ tersebut: Siri’ sebagai harga diri atau pun kehormatan, mapappakasiri’
artinya menodai kehormatannya, ritaroang siri’ yang artinya ditegakkan
kehormatannya, passampo siri’ yang artinya penutup malu, siri’ sebagai
perwujudan sikap tegas demi sebuah kehormatan hidup.10
Ungkapan sikap yang mencerminkan siri’ yang harus dijaga masyarakat
Bugis yang termanifestasikan lewat kata-kata taro ada’ taro gau (selarasnya kata
dengan perbuatan), merupakan tekad atau cita-cita dan janji yang telah diucapkan
pastilah dipenuhi dan dibuktikan dalam perbuatan nyata. Hal tersebut juga sejalan
dengan prinsip-prinsip abattireng ripolipukku (asal usul leluhur senantiasa
dijunjung tinggi, semuanya ku abadikan demi keagungan leluhurku).11 Pada
pernyataan di atas tergambar bahwa siri’ bukan hanya tercermin dari sikap
masyarakat Bugis semata tapi juga melalui ucapan yang harus dibuktikan melalui
perbuatan. Karena membuktikan perbuatan selama apapun itu menandakan bahwa
seseorang itu mempunyai harga diri dan naluri kebaikan.
9
Mattulada, LATOA, h. 85.
Mattulada, LATOA, h. 64.
11
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 95.
10
48
Pembagian makna siri’, Mattulada memamaparkan hal yang sependapat
dengan C.H. Salam Basjah dan Sappena Mustaring yang memberikan penjelasan
atas kata siri’ dalam tiga golongan pengertian yaitu:12
1. Siri’ sama artinya dengan malu, isin (Jawa), shame (Inggris)
2. Siri’merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh,
mengasingkan, mengusir dan hukuman lainnya terhadap apa atau siapa
saja yang telah menghilangkan kehormatan diri orang lain, atau
melakukan hal yang salah dalam masyarakat. Hal ini merupakan
kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yaitu berupa
hukuman dari norma-norma jika tidak dilaksaanakan.
3. Siri’ sebagai penyemangat atau daya pendorong yang bisa juga ditujukan
kearah pembangkitan tenaga untuk suatu pekerjaan atau usaha.
Adapun makna siri’ menurut La Side budayawan Bugis dalam buku
Mashadi Said mengatakan bahwa konsep siri’ mengandung tujuh makna yaitu:13
1. Siri’ dalam makna malu-malu, dapat dilihat dari kalimat “ adeppeki’ mai,
aja’ na tu masiri’, nasaba tania ki tau laing” yang berarti mendekatlah
kemari, janganlah malu, karena anda bukan orang lain (yang sudah kenal
maupun yang sudah akrab).
2.
Siri’ bermakna malu dapat dilihat dari kalimat berikut ini “de’na
kuissenggi siri’ku nasaba risenge ri tenggana tau maegae” artinya “tak
terkira maluku karena saya ditagih ditengah orang banyak”, kata siri’
12
Mattulada, LATOA, h. 62.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 101.
13
49
diatas menunjukan malu seseorang karena ditagih utangnya diantara
orang banyak.
3. Siri’ dalam makna takut dapat dilihat dari kalimat berikut “temmasiriki
matti ri Nabitta na de’ta turussiewi panggaja’na” artinya tidakkah anda
merasa takut kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak menuruti
nasehat dan ajarannya” kata siri’ di atas menujukan kata takut.
4. Siri’ dalam makna hina atau aib, dapat dilihat dari kalimat “ Masseroa”
napakasiri naleppa’ riolo na tau maegae” artinya betapa ia menghina
saya, menampar saya di depan orang banyak. Siri’ di sini bermakna
penghinaan atau aib.
5. Siri’ dalam makna iri hati atau dengki terlihat dari kalimat berikut ini “
masiri ati wi ri iyya, na saba ubettai menre pangka’” artinya dia iri hati
terhadap saya karena mendahuluinya naik pangkat. Siri’ di sini bermakna
iri hati.
6. Siri’ dalam makna harga diri atau kehormatan, dilihat dari kalimat “ na ia
tau matanre e siri’ na tenna pojiwi minreng tenna poji mellau” artinya
orang mempunyai harga diri adalah orang tidak suka berhutang dan tidak
suka meminta.
7. Siri’ dalam makna kesusilaan bisa dilihat dari kalimat „ ia pasilainggi tau
na olo’ kolo’ e iana ritu siri’e” artinya yang membedakan manusia
dengan binatang ialah kesusilaan.
Dari tulisan di atas dapat disederhanakan menjadi dua macam sikap reaktif
dari siri’ yaitu pertama, Siri Ripakasiri bersifat eksternal reaktif, yang disebabkan
50
oleh penyerangan kehormatan (martabat) yang datang dari luar pribadi seseorang
pihak yang mengalami perlakuan penyerangan kehormatan berkewajiban untuk
melakukan tindakan pemulihan, karena orang telah diserang kehormatannya
disebut dengan mate siri’, orang yang mate siri‟nya tidak lagi dianggap sebagai
manusia, melainkan binatang (olokolok) yang menyerupai manusia (rupa tau).
sehingga harkat kemanusiaan yang telah Mate Siri’ pulih kembali seperti semula,
siri’ ripakasiri terjadi apabila orang lain di hina atau dipermalukan.14 Siri’ yang
dimaksudkan di sini adalah siri’ yang datang dari luar diri seseorang.
Kedua, itu Siri’ Masiri terjadi karena adanya reaksi siri’ datang dari dalam
diri pribadi seseorang, yang dilandasi kehendak untuk mencapai prestasi yang
lebih baik dalam kehidupannya. Siri’ masiri bersifat internal, bertujuan mencapai
serta meningkatkan prestasi demi siri pribadi, siri keluarga, dan siri masyarakat.15
Tidak hanya itu tapi juga harus ditanamkan siri’ mappakasiri maksudnya
seseorang harus mempunyai kesadaran siri’ untuk menjaga dan menegakkan siri’
yang timbul karena kesadaran ingin mamanusiakan manusia yang lainnya.
Layaknya sebuah tradisi, maka secara turun temurun konsep nilai ini
senantiasa akan menjadi pegangan serta pedoman dalam kehidupan masyarakat
Bugis. Bilamana pada suatu generasi penafsirannya meleset, maka akan
berdampak ke generasi berikutnya. Jika terjadi disintegrasi terhadap penafsiran
tentang nilai Siri’ ini, maka tentunya akan berdampak kepada kelanjutan
eksistensi kepada generasi yang akan datang.
14
15
Marzuki, Siri’ Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, h. 53.
Marzuki, Siri’ Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, h. 54.
51
Dasar falsafah hidup yang menjiwai dan menjadi pegangan masyarakat
Bugis untuk senantiasa hidup baik di negeri sendiri atau negeri orang lain adalah
menjadi manusia yang perkasa dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia
keturunan Bugis dituntut harus memiliki keberanian, pantang menyerah
menghadapi tantangan ataupun ujian hidup. Itulah sebabnya maka setiap orang
yang mengaku sebagai masyarakat Bugis memiliki orientasi yang mampu
menghadapi apapun.
Hakekat prinsip tersebut bersumber pada leluhur masyarakat Bugis yang
tersimpul dengan “duai temmallaiseng, tellui temmasarang” (dua bagian yang tak
terpisahkan dan tiga bagian yang tak terceraikan). Yaitu siri na pesse dan tiga
sifat sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi (yaitu siri’ dan pesse serta tiga
sifatnya yaitu saling memanusiakan, saling mengingatkan atau menyeru pada
kebaikan, dan saling menghormati juga menghargai.16dengan demikian konsep
siri’ memberikan pengarahan yang cukup jelas bagi kehidupan masyarakat Bugis
lebih baik.
Siri’ adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dalam diri manusia yang
tidak terjadi secara sepintas sehingga secara langsung akan bereaksi apabila
terjadi sesuatu, siri‟ disejajarkan dengan akal pikiran yang baik karena bukan
timbul dari kemarahan, dengan peradilan yang bersih karena tidak dilakukan
16
Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h.154.
52
secara sewenang-wenang, dengan perbuatan kebijakan yang tidak menjengkelkan
sesama manusia secara tak patut.17
2. Pesse
Kata pesse secara harfiah dapat berarti pedih, yang menyerap dalam kalbu
seseorang, karena melihat penderitaan orang lain.18 Pesse yang lengkapnya pesse
bebbua yang berarti ikut merasakan penderitaan orang lain dalam perut sendiri,
mengindikasikan adanya perasaan haru (empati) yang dalam terhadap tetangga,
kerabat, atau sesama kelompok sosial.19 Sehingga ini dimaknai sebagai rasa
solidaritas yang dimiliki masyarakat Bugis dalam berbagai hal, baik suka maupun
duka. Lebih luas lagi, ungkapan pesse ini menunjukkan rasa simpati yang
mendalam, atau perasaan empati terhadap sesama anggota kelompok komunitas
masyarakat.20
Kata pesse juga selalu disandingkan dengan siri’, sebagaimana Laica
Marzuki kemukakan pesse merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan oleh siri’.
Pesse juga menurut dalam sebuah panggilan nurani untuk menyatakan sikap
untuk melarutkan diri setiap pribadi pendukung siri’ guna kepentingan bersama.
Pesse berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, kebersamaan serta
pemuliaan manusia (sipakatau).21 sehingga mendorong seseorang untuk saling
tolong menolong, saling menghormati, dan turut membela harkat dan martabat
17
Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h.169.
Marzuki, Siri’ Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, h. 132.
19
Cristian Pelras, Manusia Bugis, Jakarta: Forum Jakarta-Paris.2006, h. 252.
20
Rahmawati, “Integrasi Nilai Budaya Siri’ dan Pesse Masyarakat Bugis Makassar
dalam Pelajaran IPA, Jurnal Pendidikan Nusantara Indonesia, vol.1, 2015, (Unismuh Makassar),
hal. 92.
21
Marzuki, Siri’ Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, h. 132.
18
53
orang lain untuk menegakkan kembali siri’ (martabat seseorang). Pesse menjadi
hal yang tidak terpisahkan dari manusia seperti disebutkan dalam Lontara:
“Iya sempugi’ku, rekkua de’na siri’na, engka messa pessena”
Artinya “Kalaupun saudaraku sesama Bugis (sempugi’ku) tidak menaruh
siri’ atasku, paling tidak, dia pasti masih menyisakan pesse.”
Maksudnya dari pernyataan di atas adalah apabila seseorang tidak
mempunyai rasa hormat terhadap orang lain tapi orang Bugis pasti memiliki rasa
empati atau rasa kasihan terhadap orang lain.22 Dengan kata lain bahwa pesse
adalah panggilan hati untuk merasakan penderitaan orang lain dalam hati nurani
masyarakat Bugis.
Pesse mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa
mementingkan diri sendiri dan golongan inil adalah salah satu konsep yang
membuat suku Bugis mampu bertahan dan disegani diperantauan, pesse
mengeskpresikan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban dan
penderitaan orang lain, orang lain di sini meliputi semua orang yang di luar dari
diri orang yang bersangkutan. tepatnya, siapapun yang menjadikan dirinya larut
oleh endapan perasaan pesse.
Perasaan pesse dikala melihat orang lain menderita karena diperlakukan
(ripakasiri) menjadikan konsep pesse selalu tampil berpadanan, bagi orang Bugis
manusia tanpa siri’ dipandang sebagai sama dengan binatang, tapi apabila
manusia tanpa endapan pesse menjadikan dirinya lebih rendah derajatnya dari
22
Pelras, Manusia Bugis, h. 253.
54
binatang. Sehingga pesse yang timbul dari dalam diri sesorang inilah yang akan
membantu baik secara langsung dan tidak langsung dalam mengembalikan dirinya
menjadi Tau (manusia yang semestinya).23 Maksudnya menjadi makhluk yang
paling biadaplah apabila ada seseorang yang tidak mempunyai sebuah pesse
dalam hati nuraninya, karena binatang sekali sekalipun masih mempunyai rasi
kasihan dan empati terhadap sesamanya binatang.
Tidak hanya dalam hal orang lain yang telah diperlakukan tidak terhormat
(mate siri’) tetapi pesse dijadikan sumber yang mengeratkan anggota kelompok
sosial.24 Misalnya penderitaan siapa saja dalam kelompok sosial yang sedang
dalam keadaan serba kekurangan, berduka, mengalami musibah, atau menderita
sakit. Maka diwajibkan untuk membantu sekuat dan semampunya kita sebagai
manusia.
Bahkan pesse dijadikan sebagai hutang budi pada seorang yang telah
berbuat baik kepadanya, tentunya tidak hanya ditunjukan dalam ucapan
“terimakasih” saja melainkan ditunjukan dengan sesuatu perbuatan yang setara
atau lebih dari apa yang telah diterimanya.25
Dalam pesse bertumpuhnya sebuah solidaritas yang menunjukan
persaudaraan di kalangan masyarakat Bugis dan di sebutkan dalam lontara bahwa
: Iya padecengi assijingeng: 1. Sianrasa-ranggange na sipammase-mase, 2.
23
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 131.
Pelras, Manusia Bugis, h. 252.
25
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 136.
24
55
Sipakario-rio, 3. Tessicarinnainggeng ri sitinajae, 4. Sipakainge’ ri gau patujue,
na siaddampengeng pulanae.26
Artinya, yang melestarikan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat
yaiu: 1. sependeritaan dan saling mengasihi, 2. Saling menggembirakan, 3. Rela
merelakan harta dalam batas sepantasnya, 4. Saling memperingati dalam
kebaikan, dan 5. saling memaafkan dengan penuh keikhlasan.
Inti budaya siri' na pesse mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat
Bugis, karena siri' na pesse merupakan jati diri dari orang-orang Bugis. Dengan
adanya falsafah dan ideologi siri' na pesse maka keterikatan antar sesama dan
kesetiakawanan menjadi lebih kuat baik dengan sesama suku, maupun dengan
suku yang lain.
Konsep siri' na pesse bukan hanya menjadi prinsip oleh kedua suku ini
(Bugis dan Makassar), tetapi juga dianut oleh suku-suku lain yang mendiami
daratan Sulawesi seperti, suku Mandar dan Toraja, hanya kosakata dan
penyebutannya saja yang berbeda, tetapi falsafah ideologinya memilikii kesamaan
dalam berinteraksi dengan sesama.
C. Pangederreng Masyarakat bugis
Pangaderreng menurut La Tadamperreng Puang ri Manggalatung27 (arung
Matoa Wajo) dalam Lontara Sau Wae (LSW) bahwa “ Naia riaseng e
26
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 133.
56
pangaderreng tellu toi: seuani, allelengeng elempu’, madduanna to mappalaleng
malempu’, mattellunna to mallaleng malempu’ aga ennassarang pura onro, pura
llaloe” adapun yang disebut pangederreng ada tiga: pertama, tempat berjalan
(peraturan Hukum) yang lurus; kedua, orang yang menyuruh untuk menjalani
(penguasa pemerintah pelaksana hukum) yang lurus dan orang yang disuruh
menaati yang lurus maka ia tidak akan dipisahkan dari peraturan yang telah
diterapkan lebih dahulu, yang tak boleh diubah lagi”.28
Panngaderreng menurut Mattulada mengatakan bahwa panngaderreng
bukan hanya meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan-aturan
adat, yaitu hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, juga meliputi
hal-hal dimana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri
dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih
jauh daripada itu, ialah adanya semacam perasaan bahwa seseorang adalah bagian
integral dari pangederreng29.
S.H. Alatas dan Nurhayati Rahman mendefinisikan pangederreng sebagai
keseluruhan falsafah sosial dan budaya masyarakat Bugis, mencakup hidup
politik, keadilan, ekonomi, adat, keluarga, dan lain-lainnya.30
Sehingga bisa dikatakan pangederreng adalah suatu bagian yang tidak
terpisahkan dari personal seseorang dalam keterlibatannya secara total dalam
27
La Tadamperreng Puang ri Manggalatung adalah raja dari kerajaan Wajo di kabupaten
Wajo, Sulawesi Selatan.
28
A. Zainal Abidin Farid, dkk., Siri’ Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar:
“Siri, Pesse Dan Were’ Pandangan Hidup Orang Bugis” (Makassar: Arus Timur, 2014), h. 37.
29
Mattulada, LATOA, h. 339.
30
Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h. 175.
57
kehidupan bermasyarakat yang tentunya memiliki tolak ukur baik dan buruknya
perilaku manusia dalam kehidupan masyarakatnya.
Pangedereng meliputi semua pikiran-pikiran yang baik, perbuatanperbuatan atau tingkah laku yang baik.31 Lebih lanjut pangederreng menunjukan
nilai-nilai dari kebiasaan yang terdapat dari perilaku seseorang, masyarakat dan
juga pemerintah (Kerajaan) yang akan mengharmoniskan serta akan memberikan
manfaat bagi harkat dan martabat manusia.
Secara rinci pangederreng berbeda dengan adat yang dimaksudkan dalam
konsep kebudayaan, adat mengandung pengertian umum sedangkan pangederreng
mengandung pengertian terbatas. Adat meliputi adat makan-minum dengan
keluarganya, atau yang adat yang melembaga dalam suatu keluarga seperti, tidur,
bangun, berpakaian dan sebagainya. Semua contoh yang disebutkan diatas tidak
masuk dalam ruang lingkup pangederreng, namun pangederreng berbicara boleh
atau tidak boleh, baik dan buruknya sesuatu dalam kehidupan masyarakat.32
Apabila pangederreng adalah kebiasaaan atau aturan-aturan yang sudah
dibiasakan saja maka akan menghilangkan satu aspek terdapat dari hakikat
pengederreng, yaitu memelihara dan menumbuhkan harkat dan nilai-nilai
kebaikan yang justru menjadi tulang punggung untuk tegaknya pangederreng.
Sehingga apabila suatu masyarakat menerima kebiasaan atau aturan-aturan
yang diadatkan berupa kekerasan dan penindasan sebagai satu aspek sosial, selaku
adat kebiasaan, aturan yang dibiasakan, tentu dapat disebut adat tapi bukan
31
Mattulada, LATOA, h. 128.
Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h.137.
32
58
pangederreng dalam arti essensial. Adat yang demikian akan ditentang oleh
pangederreng, karena pangederreng membangun harkat dan martabat manusia.33
Dan unsur pangederreng memberi tempat yang sangat tinggi kepada 1) Hak-hak
asasi manusia, 2) kedaulatan rakyat, dan 3) pejabat sebagai abdi rakyat.34
Mattulada mengidentifikasi bahwa aspek-aspek panngederreng mengandung 4
azas yang menjadi latar belakang yaitu:
1. Azas mappasilasa’e, diwujudkan dalam manifestasi ade‟ agar terjadi
keserasian
dalam
sikap
dan
tingkah
laku
manusia
di
dalam
memperilakukan dirinya dalam pangederreng. Dalam tindakan-tindakan
operasionalnya ia menyatakan diri dalam usaha-usaha pencegahan
(preventif) sebagai tindakan-tindakan penyelamat.
2. Azas mappasisaue, diwujudkan dalam manifestasi ade’ untuk hukuman
deraan pada tiap-tiap pelanggaran ade’ yang diyatakan dalam bicara.
3. Azas mappasenrupae, diwujudkan dalam manifestasi untuk memelihara
kelangsungan aturan-aturan dahulu yang sudah ada.
4. Azas
mappallaiseng,
diwujudkan
dalam
manifestasi
ade
untuk
memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan
lembaga-lembaga sosialnya, dimana ini adalah upaya agar manusia
terhindar dari hal negatif dalam masyarakat.
33
Mattulada, LATOA, h. 141.
Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h. 176.
34
59
Para ahli kebudayaan Bugis menjelaskan ada empat unsur yang terkait
kelangsungan kehidupan moral manusia Bugis, yaitu ade’, rapang, bicara, wari.35
ini berdasarkan apa yang telah diwariskan oleh Kajao La Liddo dari tanah Bone
sekitar abad ke 16 M. Aspek ideal dalam pangederreng juga terbagi dalam
beberapa kategori dibawah ini.
1.
Ade’
Ade’ merupakan salah satu aspek pangaderreng menurut Kajao La Liddo36
yang dikutip Anwar Ibrahim bahwa ade’ yang memperkuat kebesaran raja,
menjadi pagar dalam perbuatan orang-orang berbuat semaunya dan sandaran bagi
orang-orang lemah.37 Ade’ bisa dikatakan sebuah norma adat dalam bahasa
Indonesia yang juga dimiliki semua suku-suku dimana adat berisi tentang aturanaturan bermasyarakat.
Ade’ adalah penjelmaan sesuatu aspek kebudayaan, baik dalam bentuk
nilai-nilai ideal berupa perilaku. Adat dan lain-lain disebut singkeruang,
kelakuan-kelakuan yang disebut barangkau‟, maupun dalam bentuk fisik yang
disebut abbaramparangeng38. Sehingga bisa dikatakan bahwa ade’ merupakan
nilai kebaikan secara konsep dan juga sekaligus menjadi sebuah nilai
implementasi dari konsep di atas.
35
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 69.
Kajao La Liddo atau Kajao berarti orang pintar dan La Liddo adalah nama desa
asalnya. Nama sebenarnya La Mellong, dia salah satu penasehat kerajaan Bone pada abad XVI
yang terkenal dengan kecerdasannya.
37
Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal
(Makassar: Lembaga penerbit Universitas Hasanuddin, 2003), h.12.
38
Mattulada, LATOA : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,
h. 340.
36
60
Ade’ diucapkan Arung Bila39 terbagi dalam beberapa jenis yaitu:40
a. Ade’ pura Onro, yaitu norma yang bersifat permanen atau menetap
dengan sukar untuk diubah.
b. Ade’ Abiasang, yaitu sistem kebiasaan yang berlaku dalam suatu
masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan hak-hak asasi
manusia.
c. Ade’Maraja, yaitu norma baru, apabila ada fenomena yang belum
pernah ada dalam pranata sosial masyakarat maka parewa ade’41 berhak
menentukan seperti apa solusi yang terhadap fenomena tersebut.
Dari ketiga Jenis ade’ ini adalah kerangka yang menata kehidupan
masyarakat dimana ade’ maraja adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh yang
sedang menjabat untuk memperlancar urusan untuk menciptakan keadilan dan
ketentraman bagi rakyatnya.
2.
Bicara
Bicara adalah aturan-aturan peradilan yang normatif dalam arti luas.
Dengan demikian maka
bicara itu adalah aspek
pangederreng
yang
mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam
interaksi kehidupan bermasyarakat. Tujuan bicara adalah menyelesaikan
persengketaan orang yang berselisih.42 Memberikan jaminan hukum bagi
masyarakat atas perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.
39
Arung Bila adalah raja dari kerajaan bila yang terdapat di kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan.
40
Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Essay Demokrasi dan Kearifan Lokal (Makassar:
Lembaga Penerbit universitas Hasanuddin 2003), h.110.
41
Parewa ade‟ merupakan seperangkat pemangku adat.
42
Ibrahim, Sulesana, h. 12.
61
Dalam Lontara’ Latoa, Mattulada menjelaskan secara spesifik tentang
makna adil seperti yang biasa kita pahami dalam bahasa Indonesia, akan tetapi
keadilan atau adil dalam bahasa Bugis lebih dikenal dengan istilah tongeng atau
tongengge, bila diartikan secara harfiah (tongeng) berarti “benar” dan (tongengge)
diartikan “kebenaran” Bicara lebih bersifat refresif, menyelesaikan sengketa yang
mengarah kepada keadilan dalam arti peradilan bicara senantiasa berpijak kepada
objektivitas, tidak berat sebelah.
Apabila kita memandangnya dari sudut hukum adat, maka akan lebih
memudahkan pemahaman, bicara mempersoalkan masalah hukum, sebagai
hukum ada, yang lazim kita kenal dalam gelanggang ilmu pengetahuan hukum di
Indonesia.43
Kini bicara menjadi sebuah disiplin yang jelas sebagai aspek
pangederreng yang berfungsi representatif terhadap pelanggaran tata tertib dalam
masyarakat, bicara memberikan batasan bagi anggota masyarakat dan juga
menentukan baik buruknya perbuatan dan hukuman apa yang akan diberikan
kepada si pelanggar ade’ dan pangederreng. Bicara sekaligus menjadi
mappasisaue (memulihkan atau penyembuhan agar seseorang bisa kembali
menjadi tau tongeng (orang yang benar).44
Dalam penetapan hukum Tomabbicara45 tidak semena-mena dalam
menetapkan hukuman seperti apa yang akan dijalani oleh seseorang yang
melanggar aturan karena dalam pangederreng menganggap bahwa manusia pada
43
Mattulada, LATOA, h. 359.
Mattulada, LATOA, h. 363.
45
Tomabbicara adalah orang yang bertugas menangani perkara atau peradilan, lihat
Nurhayati Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas, h. 131.
44
62
dasarnya tau tongeng, sehingga membutuh kejelasan akar atas suatu permasalahan
yang terjadi.
Dalam ade’ mengajarkan bahwa untuk menetapkan hukuman atas
kesalahan seseorang adalah tomabbicara dan pakketenni ade’ mempunyai
pertimbangan dan kebijaksanaan terhadap pelaku, kemudian tomabbicara
diupayakan memperhatikan bila hukuman itu diberikan kepada dirinya sebelum
menentukan hukuman yang diberikan (bagamana aku terhadap dia, dan begitu
pula dia terhadapku) dalam Lontara’ disebutkan dalam landasan dalam
menetapkan hukuman.46
“takaranku kupakai menakar, timbanganku ku pakai menimbang, yang
rendah kutempatkan di bawah, yang tengah kutempatkan di tengah, yang tinggi
ku tempatkan di atas”.
Jadi dalam menetapkan hukuman pada terdakwa maka pabbicara harus
mempertimbangkan bila hukuman itu terjdi pada diri pabbicara. Apakah
pabbicara sanggup untuk menjalankan hukuman itu bila dia menjadi terdakwa.
sehingga dibutuhkan musyawarah dalam menentukan hukuman seseorang.
memusyawarakan hukuman itu menjadi sangat sangat penting sebagaimana
dijelas pula dalam Lontara’47:
“tentang bicara yang paling dipuji oleh dewata (Sang pencipta), untuk
menetepkan bicara, yang mengambil contoh pada dirinya, artinya apabila engkau
sudi memlalui (sesuatu jalan), barulah engkau menyuruh orang lain melaluinya,
46
Mattulada, LATOA, h. 363.
Mattulada, LATOA, h. 363.
47
63
karena itulah to-riolo berkata, bersepakatlah engkau sanggup melaluinya,
barulah engkau menjajak orang lain untuk melaluinya”.
Maksdunya dalam menjalankan ketentuan-ketentuan bicara pangederreng
menekankan adanya kesadaran dari pelaksana kekuasaan peradilan, bahwa apa
yang ditetapkan akan berguna bagi penerima hukuman tapi juga berguna bagi
orang lain, oleh karena itu pelaksana peradilan (tomabbicara) harus sanggup
membebaskan diri perasaan senang, perasaan marah dan perasaan segan dalam
melaksanakan peradilan terhadap siapa pun, sekalipun yang dihukum itu raja yang
bersalah.
Dalam penetapan hukum selain yang di atas pabbicara juga harus pegang
teguh pada48:
a. Bicara tongengtellue (tiga kebenaran hukum)
1. Pengakuan kesalahan dan kebenaran kedua belah pihak
2. Pengakuan kesalahan dan kebenaran menurut ade’
3. Kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya (bukti-bukti kongkrit)
b. Melepaskan diri dari :
1. Kemarahan
2. Kegirangan
3. Keseganan
4. Maksud-maksud yang mengadung tujuan lain, dan
5. Keharuan.
Penjelasan ini telah pernah terjadi sebagai mana dicontohkan dalam Lontara’
48
Mattulada, LATOA, h. 365.
64
“karena adapun ade’ itu, sedangkan raja pun harus diturunkan dari
tahtanya apabila ia tak mau berjalan menurut pangederreng dan jadikanlah
Arungpone Matinroe ri-addenenna, yang berani melakukan perbuatan-perbuatan
yang tidak menurut pangederreng sebagai rapang, sehingga orang pun
bersepakat membunuhnya di atas tangganya, dan disebut Arungpone yang berada
di atas tangganya”.
Ini menjadi contoh bahwa apabila pangederreng dilanggar maka pelaku
harus mengakui kesalahnya sesuai dengan ketentuan ade’ dan juga ikut sertakan
bukti-bukti dari kesalahannya dalam hal ini raja sekalipun. Dari contoh di atas
juga menunjukan bahwa dalam penetapan hukum tidak semesternya seorang
pabbicara terinterpensi oleh rasa kasihan, rasa marah, dan rasa bahagia, sehingga
dalam kesepakatannya Arungpone yang melanggar pangederreng harus dibunuh di
bawah tangga rumah kerajaan.
Bagian terpenting dalam pelaksanaan bicara adalah sanksi hukuman yang
bertujuan untuk menegakkan hukum tanpa menunda-nunda, sebagai pembelajaran
kepada masyarakat lainnya bahwa ade’ tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul
ke atas. Adapun jenis-jenis hukuman yang telah ada dalam lontara sebagai
berikut49 :
1. Dibunuh (Ri uno)
2. Hukuman pengasingan (Pali‟)
3. Hukuman deraan badan (Calla)
4. Hukuman sita (Rappa)
5. Hukuman tawanan (Ri reppung)
6. Hukum jual (Ri balu).
49
Mattulada, LATOA, h. 65.
65
3. Rapang
Rapang secara istilah bisa disebut juga dengan perumpamaan, contoh,
kesamaan, atau sebagai yurisprudensial, suatu ketentuan yang diambil
berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kejadian-kejadian yang pernah dilakukan
pada waktu yang lalu.50 Rapang juga diartikan sebagai contoh, perumpamaan,
ibarat, kias, atau juga perumpamaan yang dapat mengokohkan negara atau yang
ditetapkan setelah membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau
membandingkan dengan keputusan adat yang berlaku di negeri tetangga.51 Pada
salinan Lontara’ misalnya yang dikutip Fredericy (1933) dan ditetapkan sebagai
kata pembukaan dari Erste Hoofdstuk dari buku De Standen bij De Boegineesen
en Makassaren, kata rapang itu digantikan dengan “oendang”52.
Abdul Razak Daeng Patunru juga dalam bukunya Sejarah Gowa yang
dikutip Mattulada tidak menyebutkan rapang, tetapi menyebutnya undangundang.53 Sementara menurut Mattulada penggantian rapang menjadi undangundang menunjukan bahwa undang-undang yang disebutkan oleh Daeng Patunru
adalah kata yang bisa menggambarkan rapang secara singkat, Akan tetapi
undang-undang dalam bahasa Indonesia yang tertentunya mempunyai batasan
sebagaimana pengertiannya, yakni hukum tertulis, sedangkan rapang lingkupnya
sangat luas daripada undang-undang.
50
Mattulada, LATOA, h. 334.
Mattulada, LATOA, h. 377.
52
Oendang yang dimaksudkan adalah kata undang-undang dalam bahasa Indonesia.
53
Mattulada, LATOA, h. 378.
51
66
Menurut fungsinya rapang sebagai: 1. Stabilisator; seperti undang-undang
yang ketetapan, keseragaman, dan konstintensi kebijakan atas suatu permasalahan
dalam masyarakat dari masa ke masa. 2. Bahan perbandingan suatu (tidak ada
atau
belum
adanya
norma-norma
dan
undang-undang
yang
mengatur
permasalahan baru, berdasarkan ketetapan di masa lampau), 3. Alat pelindung dari
pamali, yang berfungsi untuk melindungi milik umum dan seseorang dari mara
bahaya.54
Sehubungan dengan fungsi rapang untuk memberikan penguatan bagi
negara atau kerajaan. Sehingga dibutuhkan sikap magetteng ri rapangnge (sikap
keras terhadap masyarakat untuk menegakkan rapang sebagai undang-undang
negeri, dimana rapang adalah suatu hukum yang objektif dan konkrit di masa lalu
yang mana rapang mengandung makna mappasenrupa yaitu memberi hukuman
yang sama atas permasalahan yang sama berdasarkan masa lalu.
Rapang memberikan kejelasan atas sanksi yang sesuai dengan apa yang
telah dijadikan sanksi di masa lalu, juga sekaligus menjadi perbandingan atas
suatu sanksi yang belum pernah ada sanksi dari permasalahan baru didapatkan
dalam masyarakat. Sehingga pabbicara bisa mengambil sebuah kebijakan yang
tidak merugikan bagi kerajaan dan masyarakat yang ada. Contohnya apabila
rapang tidak ditegakkan maka akan terjadi banyak mala petaka, meluasnya
perselisihan pada masyarakat. Sehingga dengan ini negara akan maju.
4.
Wari
54
Mattulada, LATOA, h. 378.
67
Wari adalah perbuatan mappalaisengge (yang tau membedakan) atau
pengelompokan jenis, yang membedakan satu yang lain dengan yang lainnya.
Wari merupakan suatu sistem yang mengatur tentang batas-batas kewenangan
dalam masyarakat, membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan ruang
lingkup penataan sistem kemasyarakatan, hak, dan kewajiban setiap orang.
Menurut friedericy menerjemahkan wari dengan “de indeeling in standen”
berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta menentukan
hubungan kekerabatan.55 Lebih dari pada itu wari tidak hanya menjelaskan
masalah keturunan dan pelapisan masyarakat semata-mata, melainkan mempunyai
fungsi-fungsi lain yang cakupan lebih luas.
Dengan demikian umumnya wari’ berfungsi :
a. Menjaga jalur dan garis keturunan yang membentuk pelapisan masyarakat
atau mengatur tentang tata keturunan melalui hubungan perkawinan.
b. Menjaga atau memelihara tata susunan atau tata penempatan sesuatu
menurut urutan semestinya.
c. Memelihara tata susunan hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri
dengan negeri lainnya, sehingga dapat ditentukan mana yang lebih tua,
mana yang muda dalam tata pengederreng.
Dalam kegunaannya wari bertujuan untuk penataan pangederreng dan
penertibannya meliputi: 1. Wari’tana ialah tata kekuasaan dan tata pemerintahan
dalam
hal
55
mengenal
dasar-dasarnya,
Mattulada, LATOA, h. 380.
bagaimana
raja
bersikap
kepada
68
masyarakatnya dan bagaimana sikap rakyat kepada rajanya, 2. Wari asseajingeng,
ialah tata tertip yang menentukan garis keturunan dan kekeluargaan sehingga bisa
dibedakan mana keturunan raja-raja (anakarung), masyarakat biasa (maradeka)
dan mana yang termasuk dalam budak (ata), atau dalam bahasa Jawa kita kenal
dengan kata “abdi dalem”, 3. Wari’ pangoriseng ialah mengenai tata urutan dari
hukum yang belaku dalam sistem hukum. Inilah yang menjadi tolak ukur berlaku
atau tidaknya suatu rapang atau undang-undang.56
Selain itu wari berfungsi sebagai suatu pedoman yang mengatur sikap
manusia dari sekian banyak perbedaan yang ada dalam masyarakat, mangajarkan
bagaimana layaknya seorang masyarakat berhubungan dengan kerajaan,
tomabbicara dengan raja. Bagaimana hubungan suatu kerajaan dengan kerajaan
lainnya yang tentunya mengedepankan nilai kebaikan selayaknya fitrah
manusia.57 Demikian lah wari memberikan antara oposisi-oposisi yang
berlawanan dengan pangederreng dan kerajaan dalam masyarakat.
D. Assimellereng sebagai Konsep Kesetiakawanan Masyarakat Bugis
Assimellereng secara istilah memiliki arti yang hampir sama dengan
konsep pesse di awal pembahasan bab ini, akan tetapi assimellereng diambil dari
kata melle’ yang berarti “keterikatan” sesuatu dengan yang lainnya, kata melle’
juga kebanyakan selalu disandingkan dengan kata perru berarti usus atau isi
dalam perut seorang manusia. sebagaimana ungkapan melle’ perru ri padanna
rupa tau artinya memiliki rasa keterikatan kepada sesama manusia. Secara
56
Mattulada, LATOA, h. 380.
Mattulada, LATOA, h. 382.
57
69
mendalam melle‟ perru dimaksudkan bahwa adanya rasa kasih yang besar kepada
orang lain.
Menurut Mashadi Said Assimellereng merupakan konsep sehatian,
kerukunan, kesatupaduan antara satu dan lainnya, antara satu keluarga dengan
keluarga lain dan antara manusia sesama manusia yang lainnya dalam masyarakat
Bugis.58 Memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, kesetiakawanan, cepat
marasakan penderitaan orang lain, dan tidak tega membiarkan kesulitan
saudaranya yang lain yang berada dalam penderitaan dan cepat dalam mengambil
tindakan untuk membantu saudaranya yang terkena musibah.
Dalam assimellereng terdapat konsep yang dikenal dengan “sipa’depurepu” yaitu (saling memelihara, saling kasih mengasihi). Dan bette’ perru (tega)
yang dimaksudkan adalah orang yang tidak memperdulikan kesulitan sanak
keluarganya, tetangganya, atau orang lain, ini ada antitesa dari assimellereng yang
peka terhadap orang lain.59 Selain itu dalam bahasa Bugis lain yang sepadan
dengan bette perru yaitu pettu perru yang juga berarti sikap seseorang tidak lagi
ada rasa welas kasih dan tidak lagi memiliki empati terhadap orang lain, sekalipun
itu kepada keluarganya.
Dalam kehidupan sehari hari penerapan assimellereng atau melle disebut
dalam ungkapan Bugis “tejjalli tettappere banna mase-mase” artinya tanpa tikar
dan permadani kecuali kasih sayang. ungkapan ini biasanya diucapkan ketika tuan
rumah kedatangan tamu, karena keinginan menjamu tamunya dengan baik, tuan
58
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 204.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, hal. 204.
59
70
rumah menunjukan kepada tamunya layanan sebaik-baiknya, bahwa apabila
seorang tamu sudah berada di dalam rumah maka sang tamu akan merasa aman,
tentram, terlindungi dan kasih sayang dari tuan rumah.60
Dengan penuh kerendahan hati tuan rumah akan menatakan “kami tidak
mempunyai apapun untuk kami suguhkan kepada tuan. Kami tidak mempunyai
permadani atau sofa yang empuk untuk tuan duduki, kami tidak memiliki
makanan yang enak untuk kami suguhkan. Yang kami miliki hanyalah kasih
sayang”. Dengan demikian bukan berarti tuan rumah tidak mempunyai apa-apa
yang bisa di hidangkan atau tidak menjamu tamunya, akan tetapi hanya memberi
informasi kepada tamu bahwa tuan rumah kemungkinan tidak mempunyai sesuatu
yang sama apabila bertamu di tempat lain.
Dikalangan masyarakat Bugis menghargai dan melayani tamu sebaik-baiknya
adalah sebuah kewajiban dan juga adalah untuk menunjukan solidaritas yang
tinggi terhadap sesama manusia.61
Dalam lontara‟ dijelaskan untuk memperoleh hubungan baik kepada sesama
manusia, masyarakat Bugis harus berpegang pada 5 syarat berikut yaitu62 :
a. Sianrasa-rasang
na si
ammase-masei
(Sependeritaan
dan saling
mengasihi). Maksudnya adalah apabila ada anggota keluarga yang
mengalami penderitaan maka anggota keluarga yang lainnya harus
membantunya dengan ketulus-ikhlasan dan kasih sayang.
60
Said, Jati Diri Manusia Bugis, hal. 204.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 205.
62
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 206.
61
71
b. Sipakario-rio
(sama-sama
bergembira)
apabila
kita
merasakan
kegembiraan, kita patut berbagi kepada orang lain atas kegembiraan yang
kita rasakan. Misalnya dalam keseharian leluhur orang Bugis apabila
pulang dari melaut maka hasi tangkapannya akan dibagikan kepada
tetangganya yang lain. Ini yang dimaksudkan berbagi kegembiraan.
c. Tensicarinnainggeng ri sitinajae (kerelaan berkorban yang semestinya)
maksudnya kalau ada keluarga atau kawan yang memerlukan bantuan
maka kita berkewajiban dalam untuk membantu sesuai dengan kemanpuan
kita.
Contohnya dalam pernikahan masyarakat Bugis apabila keluarga lelaki
belum memncukupi atas permintaan pinangan (Sompa atau Panaik) keluarga
perempuan, maka semua keluarga perempuan berkewajiban dalam memenuhi
sompa tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing.
d. Sipakainge ri gau patujue (saling mengingatkan kepada kebaikan) saling
mengingatkan kepada kebaikan, disini menjadi kewajiban apabila melihat
keluarga atau orang lain sebelum dan setelah melakukan kesalahan. Juga
disebutkan Malilu Sipakainge “saling mengingatkan tak kala sedang lupa”
e. Siaddampengeng pulanae (selalu saling memaafkan) memberi maaf atas
kesalahan yang orang lain pernah lakukan kepada kita.
Dari kelima syarat di atas bahwa menunjukan hubungan yang semestinya
dimiliki oleh sebuah keluarga atau kelompok masyarakat sehingga keharmonisan
dalam masyarakat semakin melekat.
72
Soal kesetiakawanan orang Bugis selalu akan membuka diri untuk
menegakkan persahabatan. Orang Bugis rela mengorbankan apa yang dia miliki
termasuk nyawanya sendiri untuk mempertahankan kesetiakawanan tersebut
sebagaimana ungkapan dalam Lontara’ disebutkan.63
Tessiakkakeng tigerro
tessicalekeng tange (LPT: 12)
Artinya :
Tidak saling mencekik leher
Tidak saling menutupkan pintu.
Dalam hal tolong menolong dalam tradisi masyarakat Bugis selalu
membuka diri, bahkan tak dimintai pertolongan dan dilakukannya secara dengan
sukaria sebagaimana penyataan di atas.
Artinya apabila seseorang memerlukan bantuan dan diri kita terasa sanggup
untuk membantunya maka kewajiban untuk membuka diri untuk membantu.
Dalam Lontara’ juga disebutkan64:
Tessisampoang uring loa,
tessipaopangeng pamuttu (LPT:10)
Artinya :
tidak saling menutup belanga,
tidak saling menutupkan kuali.
Selain daripada itu belanga dan kuali dalam masyarakat Bugis merupakan
simbol kesejateraan keluarga. Untuk membantu dalam suatu kebajikan, saling
63
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 205.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 206.
64
73
membukakan jalan dalam kesempitan, rasa solidaritas ditandai dengan saling
membantu dalam permasalahan yang ada, saling mengingatkan agar terhindar dari
sesuatu yang tidak diinginkan yang bisa menghambat kebajikan. Dalam
mempertahankan hubungan masyarakat Bugis berpegang pada hal berikut ini.
Rebba sipatokkong
Mali siparappe
Siwata’menre tessirui no’
Malilu sipakainge
Mainge’ pi mu paja
Artinya :
Rebah, saling menegakkan
Hanyut saling mendamparkan
Saling menarik ke atas bukan saling menarik turun
Hilaf, saling mengigatkan
Tak henti sampai ia menyadarinya.
Inilah gambaran kesetiakawanan dalam masyarakat Bugis yang dipegang
teguh sehingga kemudian mampu untuk memberikan hidup yang baik dalam
bermasyarakat. Dengan demikian secara otomatis bahwa toleransi yang
sebagaimana cita-cita oleh para semua agama dan pemerintah untuk hidup damai
dan berdampingan.
75
BAB IV
ANALISA
A. Pandangan Umum Toleransi
Toleransi menjadi hal yang penting pada masa sekarang. Mengingat
semakin melebarnya jurang perdebatan yang mencari-cari perbedaan dalam
keyakinan, hingga yang terparah adalah adanya perang fisik yang diakibatkan oleh
dorongan membela kebenaran agama, maka toleransi sudah menjadi perihal
mutlak dikedepankan. Karena itu, tidak sedikit para tokoh memberikan argumen
dan pendepatnya untuk merealisasikan toleransi antar umat beragama saat ini.
Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran sedikit dari tiga tokoh yaitu:
Mukti Ali, Alwi Sihab, dan Gus Dur.
Mukti Ali memberikan dua argumen mendasar dalam hal toleransi.
Pertama, dengan menawarkan sintesis. Metode ini menggabungkan dua
kecenderungan melalui gagasan pendekatan. Lebih jelasnya, metode ini berusaha
memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya seperti rasional, objektif,
kritis, dengan metode teologis normatif.
Metode ilmiah digunakan memahami agama dari sisi historis, empiris,
sosiologis. Sedangkan metode normatif digunakan untuk memahami agama
sebagaimana yang terkandung dalam kitab sucinya masing-masing, dengan
membawa dogma awal bahwa agamanya sudah mutlak kebenarannya. Barulah
setelah itu agama dilihat sebagai norma ajaran yang amat terkait dengan aspek
75
76
kehidupan sosial, yang mana dengan kaca mata agama, arahan yang bersentuhan
dengan aspek sosial adalah ideal sebab telah tercantum dalam kitab sucinya.1
Kedua, Mukti Ali memaparkan konsep agree in disagreement. Konsep ini
dapat diartikan dengan setuju dalam ketidaksetujuan. Konsep ini ideal
menurutnya, bila diterapkan dalam tatanan masyarakat yang majemuk dan plural.
Masyarakat yang dalam kondisi seperti ini, tentu terdapat setuju dan
ketidaksetujuan dalam memandang suatu hal. Maka ketidaksetujuan atau
perbedaan ini disepakati dan diakui oleh masing-masing pemeluk agama. Dengan
adanya pengakuan perbedaan maka diharapkan akan terciptanya kondisi yang
harmonis antara umat beragama, sebab semua hal tidak harus sama.2
Setelah Mukti Ali, adalah Alwi Sihab. Tokoh ini memberikan
pandangannya berkenaan realisasi toleransi dalam masyarakat. Berbeda dengan
Mukti Ali, Alwi Sihab berangkat dari ajaran agama Islam. Menurutnya, sebuah
masyarakat majemuk dan plural adalah pasti dalam sebuah kebudayaan. Sebab,
tidak ada satu kebudayaan pun yang luput dari sebuah perubahan, dan perubahan
itu mengandaikan adanya kemajemukan.
Dia menyebutnya dengan “proses
kemanusiaan”. Lantas bila terjadi pristiwa kekerasan yang mengatasnamakan
agama dan keyakinan, misalnya agama Islam, maka sudah keluar dari garis ajaran
agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, diajarkan kepatuhan dan tunduk kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Sikap kepatuhan itu dilalui dengan jalan menaati
11
Mukti Ali, “Setuju dalam perbedaan,” Majalah Mawas Diri, no. 1 (Maret 1972), hal. 6
liat juga Faisal Ismail, Republik Bhineka Tunggal Ika:Mengurai Isu-isu Konflik Multikulturalisme,
Faisal Ismail, Paving The War For Interreligion Dialogue, Tolerance, and Harmoni Following, h.
Agama, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keragamaan, 2012), h. 174.
2
Mukti Ali, Agama dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Biro Humas Departemen
Agama RI, 1972), h. 118.
77
ajarannya, dimana ajaran agama Islam tidak melegalkan kekerasan atas nama
agama.
Tokoh terakhir adalah Gus Dur. Tokoh ini merupakan sosok yang
dipandang sebagai orang yang sangat mengerti konsep toleransi. Berbagai
kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinannya, merupakan bukti nyata
bahwa beliau adalah sosok yang kosmopolit yang mendalami keberagaman.
Landasan awalnya dalam meneguhkan toleransi antara umat beragama di
Indonesia, dengan melihat bahwa keberagaman dalam negara adalah suatu
kenyataan sosial. Menolak salah satunya merupakan bukti mengesampingkan
nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, bila kita mencermati, jauh hari dalam peradaban
umat manusia, mengutamakan nilai kemanusiaan adalah tujuan yang hendak
dicapai sehingga kadang menimbulkan perang fisik.
Demokrasi lahir bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan,
dengan menempatkan manusia sebagai subjek dari demokrasi itu. Begitu pula
dengan ajaran Islam memiliki asas permusyawaratan, adalah instrumen untuk
menempatkan nilai kemanusiaan sebagai tujuan.3 Sehingga, instrumen-intrumen
pengantar menuju nilai kemanusiaan ini akan menempatkan manusia memiliki
derajat yang sama, serta tidak memandang ada yang lebih tinggi dan ada yang
lebih rendah.
Demikianlah pendapat para tokoh dalam memberikan pandangannya.
Partisipasi
mereka
dalam
memberikan
pandangannya,
mengingat
pengejawantahan dari toleransi adalah sebuah keharusan. Bila tidak, sungguh
3
Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi, h. 85.
78
situasi yang harmonis dan tentram tidak akan pernah tercapai. Terlebih lagi, akan
menghambat sebuah kebudayaan dan kemajuan bangsa.
Penulis melihat pandangan para tokoh di atas sikap penuh pendewasaan
dalam melihat keragaman dan juga keuniversalitasan suatu agama, suku, ras,
maupun kelompok bahwa dengan menunjukan sikap yang ramah, saling
menghormati, dan saling menghargai karena melihat seseorang sebagai manusia
yang memiliki hak-hak dasar.
Oleh karena itu, penulis berusaha mengeneralisir secara terperinci
bagaimana sikap atau pun cara mendasari terciptanya toleransi dalam masyarakat
dari beberapa pandangan para tokoh di atas sebagai berikut:
1. Pluralisme
Pluralisme sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa suatu sikap untuk
mengakui eksistensi dan hak-hak atas agama, suku, ras, maupun kelompok
lain sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal ini menurut penulis untuk
melihat pluralisme dibutuhkan suatu sikap sikap empati dan rasa memiliki satu
sama lain guna melihat perbedaan yang ada dalam masyarakat.
2. Inklusivisme
Inklusivisme yaitu pemikiran atau sikap yang memandang bahwa
kebenaran yang di anut oleh suatu agama adalah juga dianut oleh agama lain.
Dalam hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat harus mempunyai sikap
terbuka secara aktif oleh setiap pribadi masyarakat, bahwa kebenaran
sesungguhnya tidak harus mengabaikan atau mengesamping norma-norma
kemanusiaan.
79
3. Dialog
Dialog agama sangat diperlukan di era keterbukaan ini. Dialog agama
bukanlah untuk mencari kebenaran agama masing-masing, tetapi menjembatani
segala perbedaan yang ada dan memberikan ruang kepada semua komunitas yang
berdialog.
B. Analisa Toleransi Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bugis
Meskipun demikian, di samping pandangan para tokoh yang telah
disebutkan sebelumnya, sebenarnya terdapat konsep toleransi dalam masyarakat
Bugis yang sudah lama dipraktikkan dan terpelihara dan terlembaga dalam
kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan (Bugis). Lebih jauh, sebenarnya toleransi
dalam masyarakat Sulawesi Selatan adalah bentuk luar yang bersifat empiris dan
dapat
diamati, namun
sebenarnya
mempunyai
landasan filosofis
yang
mendorongnya dari dalam.4 Landasan filosofis tersebut tidak empiris, melainkan
sesuatu sifat sentimental dan perasaan yang sangat dalam. Dengan kata lain,
landasan tersebut menjadi prinsip hidup yang begitu sangat kuat mengakar dalam
pribadi masing-masing masyarakat Sulawesi Selatan.
Landasan hidup yang termanifestasi menjadi filosofi inilah yang penulis
coba uraikan dengan hati-hati. Disebut dengan “hati-hati” karena dalam mengurai
prinsip hidup ini, penulis sendiri merupakan generasi belakangan yang sudah
dilanda misinterpretasi dalam memahami prinsip tersebut.
4
Mattulada, LATOA: Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,
(Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 62.
80
Prinsip hidup masyarakat suku Bugis adalah siri’ dan pesse’. Memaknai
kata siri’, sungguh telah banyak budayawan baik lokal maupun luar, memberi
batasan pengertian tentang siri’. Siri’ dapat diartikan dengan kehormatan. Bagi
Mattulada, siri’ dimaknai dengan kesadaran tentang nilai martabat yang didukung
oleh tiap-tiap orang dalam tradisi kehidupan masyarakat Bugis. 5 Artinya, dengan
kehormatan yang tegak, merupakan sikap hidup yang harus dan mesti dijaga.
Selain permaknaan itu, pada bab sebelumnya dijelaskan siri’ tidak lain
akibat yang kemudian timbul jika salah satu nilai kemanusia dilanggar. Seseorang
tidak hanya merasa masiri’ karena telah diperlakukan tidak jujur, dipandang
enteng, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Tetapi siri’ juga sekaligus harus
sebab yang timbul dari dalam diri seorang manusia untuk selalu menjaga sikap,
saling mengormati, saling menghargai, memperaktekkan panggederreng, dan juga
menjadi semangat untuk meraih kesuksesan.6 Nilai siri’ harus menjadi tingkah
laku nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, siri’ juga sebagai sikap aktif untuk menjaga harkat dan martabat
orang lain karena masyarakat Bugis sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya
bahwa apabila seseorang tidak mempunyai siri’ maka hanya dianggap sebagai
mayat hidup dan juga binatang. Seperti yang dijelaskan dalam Lontara’:
Siri’e tu ri aseng tau, na rekko de’i siri’na,
tania i tau, rupa tau mani
Artinya:
Kerena siri’lah seseorang disebut sebagai manusia,
5
M Laica Marzuki, Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (Sebuah
Telaah Filsafat Hukum) (Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1995), h. 36.
6
Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Ujung Pandang: Hasanuddin
Universitas Press, 1992), h. 174.
81
manakala seseorang tidak mempunyai siri’,
maka bukan lagi manusia tetapi menyerupai manusia.
Ungkapan lainnya:
Naia tau de’e siri’na,
de’i laenna olok-kolok
Artinya: Jikalau manusia tidak mempunyai siri’,
mereka itu tidak lain dari pada binatang.
Pesan dari ungkapan Bugis di atas memberikan tanda bahwa selain
perbuatan melanggar siri’ akan menghilangkan nilai atau hak-hak kemanusiaan
seseorang dalam suatu kelompok sosial, tetapi Si pelanggar juga akan dianggap
bersikap paling menjengkelkan, menjijikan seperti sikap binatang karena tidak
lagi memperlakukan seorang manusia yang selayaknya.
Rahman Rahim menyebutkan si pelanggar siri’ adalah orang yang telah
tertelanjangi dari moralitas dan dalam Lontara’ binatang itu seperti binatang tikus,
dimana kerusakan yang ditimbulkannya, tidak terbatas pada sawah, tetapi juga
pada padi yang sudah di simpan di lumbung akan digerogoti juga. Bahkan setelah
menjadi beras tikus tetap saja menggerogotinya dan sampai sudah menjadi nasi
tikus masih saja memperetelinya. Begitu lah ungkapan kekejian seseorang yang
tidak mempunyai siri’ dalam dirinya.7
Lebih dari pada tikus yang menjijikan di atas sikap yang dianggap
melebihi binatang apabila dalam hati seseorang tidak terdapat nilai pesse. Dimana
pesse merupakan rasa empati yang timbul dari dalam hati seorang manusia, ibah
hati, rasa yang menyatuh antara seseorang dengan orang yang lainnya, rasa untuk
peduli akan kesulitan yang orang lain alami.
7
Rahman Rahim, Nilai-Nilai Kebudayaan Bugis, h. 170.
82
Pesse’ dapat diartikan sebagai “obbi”, yaitu panggilan hati nurani untuk
ikut merasakan penderitaan orang lain dalam perut sendiri. Ini mengindikasikan
adanya perasaan haru atau empati yang dalam terhadap tetangga, kerabat, atau
sesama kelompok sosial. Disebutkan dalam Lontara’ bahwa setiap manusia harus
mempunyai rasa pesse dalam dirinya jika menjadi lebih mulia dibandingkan
orang-orang lainnya, dan agar tidak dianggap keji melebihi binatang.8
Selain dari pada itu, hakikat siri’ dan pesse adalah menitik-beratkan sikap
sipakatau,
sipakalebbi, dan sipakainge’. Sipakatau adalah sikap saling
menghormati sesama manusia yang notabene sesama makhluk Tuhan, sipakalebbi
adalah sikap saling memuliakan dari semua kelompok masyarakat yang ada, dan
sipakainge’ menekankan sikap pesse untuk saling mengingatkan dalam hal
kebaikan, saling memperingati untuk menjauhi hal-hal yang bisa merugikan diri
peribadi dan orang lain. tentunya dilakukan dengan cara yang baik dari hati nurani
manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Lontara’ sebagai berikut:
“akkita tau mu madeceng kalawing ati, apak iya sininna deceng enrengge
upe’ e, kumanenggi pole riatau madeceng kalawing ati e. Apa’ iyyanaritu
tau rilalenna tauwe. Aja iya mualai pompola tomapperumae, apa’ iyatu
mata e, dauccilie. Lilae, inge’e, majeppu tomapperuma ritu. Majeppu iyana
ritu tau pole ri lalenna tauwe. Iyatona pakkita matae, iya tona
perengkalingae dauccilie, iya tona pakedo lilae, iyamuto parimmau. Iyato
makkita tekkemata-mata, iya muto maringkalinga tekkeculing-culing.
Iyamuto makkeda takkelessuk-lessuk, iyatona maremmau tekke emammau-
8
M Laica Marzuki, Siri’ Sebagai Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, h. 134.
83
emmau. Makkedai namatane’ to; makkitai nasellempik. Maringkalinga ri
sillalennae. Mainge’i pua na pugau’. Enrengge pura napoadae, kuaettopa
pura naegkalingae. Aga nainge;e ritu naonroi lampek paringgerrang.
Nariaseng tau to mainge’”.
artinya: Berpandanganlah sebagai manusia dan perbaiki sikap hatimu.
Sebab, semua kebaikan dan keberuntungan sumbernya berasal dari orang
yang baik dari dalam hati, itulah yang disebut kemanusiawian yang dimiliki
seseorang. Jangan jadikan perioritas, penghuni rumah yang menumpang
padamu. Sebab, adapun mata, telinga, lidah, hidung itu adalah hanya
menumpang. Sesungguhnya ia adalah tamu dalam diri manusia. Itulah yang
menjadikan mata melihat. Menjadikan telinga mendengar, ia menjadikan
lidah bergerak. Ia juga penciuman. Ia yang tidak melihat sembarangan,
mendengar sembarangan, tidak sembarangan berkata-kata, menjaga
penciuman, ia juga tidak sembarangan bergerak. Bergeraknya ia sepatutnya
dan mendengar sewajarnya. Sadar akan apa yang dilakukakan, dikatakan
disertai pendengaran. Kesadaran itu tempatnya ingatan. Maka disebutlah
orang itu adalah orang yang penuh kesadaran.
Ini menunjukan sikap yang baik dan akan membuat manusia lebih
beruntuk dari manusia yang lainnya apabila memiliki bawaan hati nurani yang
baik, dengan bawaan hati yang baik ini menjadikan seseorang mempunyai nilai
kemanusiaan dalam dirinya, nilai kemanusiaan yang tidak mengikuti hawa nafsu
karena nilai pokok dari manusia adalah nilai kebaikan.
84
Manusia yang madeceng kalawing ati dan ininnawa tau, disertai nilai
paramata mattappa’: yaitu lempu’, ada tongeng, sibawa tette’, siri’ sibawa
getteng, yang terwujud dalam perilaku (barang-kau’), hati (ati), lidah (lila), dan
usaha atau jerih- payah (reso).9 Maksudnya adalah orang yang mempunyai
bawaan hati nurani dan rasa kemanusiaan harus disertai dengan sikap “permata
yang terlihat” yaitu, kejujuran, perkataan benar yang konsisten, harga diri dengan
keteguhan hati, dan harus terbukti lewat perilaku, hati, lidah untuk selalu berkata
benar dan baik, serta dari usaha-usaha yang seorang manusia kerjakan.
Selain dari pada itu kejujuran dan kesucian hati menjadi hal utama yang
diajarkan para pendahulu orang Bugis yang diabadikan dan karya sastra klasik
atau yang dikenal dengan istilah elong-kelong, berikut ini:
Dua kuala sappo,
Unganna panasae, na belo kanuku
Artinya : Dua hal ku jadikan pagar,
yaitu bunga nangka (kejujuran) dan hiasan kuku (hati yang penuh kesucian)
Ungkapan di atas mempunyai makna yang sangat dalam karya sastra orang
Bugis, dua hal yang dijadikan pagar atau pelindung dari kehidupan. Kejujuran
diumpamakan dengan bunga nangka, karena bunga nangka tidak perna
membengkok dan selalu lurus. Itulah mengapa bunga nangka yang lurus itu
diartikan kejujuran. Kemudian hiasan kuku dalam masyarakat Bugis dikenal
dengan istilah pacci atau paccing, yang berarti bersih dan tak bernoda. Sehingga
diartikan sebagai kesucian.
9
Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Essai Tentang Demokrasi Dan Kearifan Lokal, h.
104.
85
Dengan semua penjelasan diatas tadi bahwa dari siri dan pesse yang
menjadi prinsip masyarakat Bugis yang menekankan sikap sipakatau, sipakalebbi
dan sipakainge’ guna untuk menjaga harga diri atau hak kemanusiaan dari hati
nurani yang suci dari seseorang sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis
dalam masyarakat. Dalam masyarakat Bugis Seseorang tidak dapat dipisahkan
dengan individu lainnya, karena prinsip harkat dan martabat manusia (manusia
saling memanusiakan), seseorang dikatakan manusia apabila menempatkan
dirinya dan orang lain sebagai tau “pesona”, yang berarti bahwa hati, ucapan, dan
perilaku mempraktikan manusia yang sesungguhnya.
Beranjak kekonsep berikutnya bahwa pangederreng memberikan pesanpesan untuk hidup yang tentram, damai, dan kemajuan dalam masyarakat.
Menurut Mattulada, Pangedderreng bukan hanya meliputi aspek-aspek yang
disebut sistem norma dan aturan-aturan adat, yaitu hal-hal dimana seorang dalam
tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bukan saja
merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu adanya
semacam perasaan bahwa seseorang adalah bagian internal dari pangedderreng’.10
Penekanan pada kata harus berarti pengedderreng adalah sesuatu yang sangat
dihayati dan didalami. Adanya semacam ikatan yang bila ditinggalkan selain
terkena sanksi, juga perasaan penyesalan yang amat mendalam.
Pangedderreng merupakan kebiasaan berbentuk peraturan yang terdapat
dalam perilaku seseorang, masyarakat dan juga pemerintah. Kebiasaan tersebut
10
Mattulada, LATOA, h. 339.
86
mencakup hanya pada perbuatan atau prilaku yang mengharmoniskan serta
memberikan manfaat bagi harkat dan martabat manusia.11
Selain pangederreng memberikan panduan yang bersifat normatif dalam
bentuk petunjuk dan arahan menuju ke jalan yang benar guna mendapatkan
ketenangan dan kebahagiaan hidup bagi setiap manusia dalam masyarakat,12juga
mengandung tiga tujuan utama dalam kehidupan masyarakat. Pertama, Tuhan
titik sentral bagi manusia. Kedua, sikap jujur. Ketiga, sebagai unsur keadilan dan
kebijaksanaan. Ini terlihat dari Pangederreg pada hakikatnya mengandung 4 azas
dasar yaitu:13
Pertama, Azas Mappasilasa’e terangkum dalam Ade’, sebagian maknanya
adalah adat. Namun adat di sini, sebagaimana yang telah diterangkan, memiliki
aspek yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Ade’ adalah aturan yang
diberikan oleh raja dan juga harus dipatuhi oleh raja.
Kedua, Azas mappasisau e diwujudkan dalam bicara yang konkritnya saat
ini, adalah lembaga peradilan. Bedanya, bicara yang dalam porsinya memberikan
keadilan dan kebenaran kepada masing-masing pihak yang bersengketa,
menggunakan pijakan objektivitas, dimana tomabbicara (hakim) tidak semenamena dalam memberikan sanksi. Karena pada dasarnya manusia dianggap sebagai
tau tongeng (orang yang baik), sehingga tomabbicara terlebih dahulu akan
menanyakan kepada dirinya, apakah sanksi yang diberikan kepada orang lain,
dapatkah ia tanggung, dalam artian, apabila seorang pabbicara melanggar hukum
11
Nurhayati Rahman, Suara-Suara dalam Lokalitas (Makassar: La Galigo Press, 2012), h.
137.
12
Mashadi Said, Jati Diri Manusia Bugis (Jakarta: Prodeleader, 2016), h. 73.
Said, Jati Diri Manusia Bugis, h. 69.
13
87
dan dihukum seperti yang akan dihukumkan kepada seseorang pabbicara
dianggap sanggup, maka hukuman itu boleh dijalankan.
Ini merupakan landasan objektif yang dalam Lontara’ disebut sebagai
pijakan hukum. Selain itu, penegak hukum juga harus berpegang pada tiga hal
yaitu, Bicara tongengetellue (tiga kebenaran hukum): pengakuan kesalahan dan
kebenaran kepada kedua belah pihak, pengakuan kesalahan menurut ade’ (adat
atau hukum), kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya atau bukti-bukti kongkrit.
Setelah ketiganya tercapai, raja sekalipun dijatuhkan hukuman, bila perbuatannya
melanggar ade’ dan proses penjatuhan hukumannya dilaksanakan dengan Bicara.
Ketiga,
azas mappasenrupae yang diwujudkan dalam rapang. Dalam istilah
disebut dengan perumpamaan.
Rapang dalam dunia hukum saat ini dapat
diartikan dengan yurisprudensi, yaitu suatu ketentuan yang diambil dari
ketentuan-ketentuan dan kejadian-kejadian yang pernah dilakukan di waktu yang
lalu. Dengan rapang, suatu keputusan negara tetangga dapat dibandingkan dengan
keputusan berdasarkan ade’.14 Sementara menurut pendapat yang lain, lebih
mendefenisikan rapang masuk dalam kategori undang-undang.
Hal ini yang perlu diluruskan, sebab makna rapang lebih luas dari hanya
sekedar undang-undang. Adapun fungsi rapang antara lain: sebagai stabilisator,
sebagai bahan pembanding terhadap norma yang belum terdapat aturannya, dan
sebagai alat pelindung dari pamali-pamali.
Keempat, azas mappallaiseng e diwujudkan dalam wari yaitu suatu sistem
yang mengatur tentang batas-batas kewenangan. Fridericy mengartikan wari
14
Mattulada, LATOA, h. 334.
88
sebagai fungsi yang mengatur tata susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta
menentukan kekerabatan. Jenjang atau lapisan yang terdapat dalam masyarakat
suku Bugis, menimbulkan mana yang menjadi hak dan kewajibannya diukur
sesuai hirarkinya.15 Kekerabatan yang dimaksud di sini, dimana raja yang
menikahkan anaknya dengan raja lain, yang berada dalam satu koalisi. Hubungan
kekerabatan ini, dapat dirujuk pada pangedderreng, sehingga dapat ditentukan
mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Klasifikasi ini, memudahkan
dalam menentukan tata pengedderreng yang berlaku.
Dari keempat azas ini memiliki tugas-tugas tersendiri seperti yang
disebutkan dalam Lontara’ dari percakapan antara La Kajao La liddo dengan raja
Bone yang dikutip oleh Anwar Ibrahim sebagai berikut.16
Iyanaritu adek-e, Arumpone, peesseriwi arajanna arung-mangkauk-e iyatona
sappoipangkaukenna topegaubawannge, iyatona nasanresi tomadodonnge; naiya
bicarae, iyana passaranngi assisalangenna tomangkagaek-e; naiya rapang, iyana
passiajinngi
tana-masseajinnge.
Nakko
marusakni,
Arumpone,
adek-e,
temmassekni,rituarajangna arung-mangkauk-e, masolang-toni tanae; narekko
temmagettengni bicarae, masolang ritu jemma-tebbek-e; narekko temagettengni
rapange, iyanaritu, Arumpone, mancaji assisalangeng, gagaenna ritu mancaji
musuk. Musuk-ena ritu mancaji assiuno-unong: Sabak makkuanna naro,
Arumpone, rieloreng riyatututi adek-e, kuwaetopa bicarae, enrennge rapannge,
sibawa warik-e.
15
Matuulada, LATOA, h. 380.
Ibrahim, Sulesana, h. 31.
16
89
Artinya: Adapun ade’ itu, Arumpone, akan memperkuat kebesaran Arung
Mangkau’17; itulah juga yang memagari perbuatan orang yang berbuat semenamena; itulah juga yang menjadi sandaran orang lemah. Adapun bicara itu ialah
menyelesaikan perselisihan orang yang bertengkar. Adapun rapang itu, ialah yang
membina kerukunan kekeluargaan negeri yang sekeluarga. Kalau menjadi rusak,
Arumpone, ade’ itu, tak kuatlah sebesaran Arung Mangkau’, rusak pulalah negeri;
kalau tak tegas bicara itu, akan rusaklah rakyat banyak; dan kalau tak tegas
rapang itu, itulah Arumpone, menjadi perselisihan. Dan perselisihan itulah,
menjadi permusuhan; dan permusuhan itu yang menjadi penyebab saling bunuhmembunuh. Oleh karena itulah Arumpone, maka dikehendaki terpeliharanya ade’
itu, demikian juga bicara, beserta rapang dan wari’.
Dari kutipan di atas bisa disimpulkan bahwa apabila ade’, bicara, rapang,
dan wari tidak tegakkan dalam masyarakat, maka akan menimbulkan kekacauan
dan saling membunuh antar masyarakat karena tidak ada lagi becci18 atau ukuran
dalam bersikap dan berperilaku.19
Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, paseng dan pappaseng para
leluhur mengajarkan agar apa yang telah dijanjikan, harus direalisasikan. Bila
tidak, derajatnya tidak lebih dari hewan. Begitu pula paseng dan pappaseng yang
ditulis dalam lontara’ yaitu: Tessiakkekeng tigoro,Tessicalekeng tange, yang
artinya, tidak saling mencekek leher, tidak saling menutupkan pintu.
17
Arung Mangkau’ adalah sebutan bagi seorang raja yang sedang menjabat pada kerajaan
Bugis di Sulawesi Selatan.
18
Becci secara harifiah adalah alat pengukur, yang digunakan untuk melihat lurus atau
tidaknya suatu tanaman dengan menggunakan tali, akan tetapi becci dalam hal di atas bermakna
aturan-aturan atau pedoman yang telah diatur dalam kehidupan masyarakat Bugis.
19
Ibrahim, Sulesana, h. 13.
90
Konsep
ini
sangat
sepadan
dengan
konsep
assimellereng
(kesetiakawanan), dimana mengajarkan saling membantu, saling membukakan
jalan dalam kesempitan, dan saling membantu dalam menghadapi permasalahan
yang ada. Bila kemudian rasa kesetiakawanan ini hilang dari lubuk hati orang
Bugis, maka dikatakan, Siri’-nya sudah hilang, bersamaan dengan hilangnya
kehormatannya. Dengan demikian, siri’ sebenarnya adalah instrumen pendorong
untuk melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, saling menghargai, dan saling
mengasihi, dimana pada ujungnya
akan
menciptakan
kondisi,
dimana
penghargaan manusia ditempatkan sebagai manusia, dengan cara mengajukan
sikap toleran antar sesama manusia. Sebab, manusia pada sifat asalnya melekat
kebaikan (tau tongeng).
Assimellereng (kesetiakawanan) adalah untuk mewujudkan persatuan
masyarakat (masseuwani tauwe) dalam masyarakat apabila seluruh komponen
dalam masyarakat bersatu maka kedamaian dan keharmonisan. Sehingga
kemudian kehidupan masyarakat tercipta kehidupan yang sejahtera. Dalam
mewujudkan persatuan (masseuwani tauwe) menurut Anwar Ibrahim mengutip
pemikiran To Maccae ri Luwu20 sebagai berikut.21
Delapan sifat yang perlu dipelihara untuk menciptakan persatuan, yaitu:
1. Massituru’i ri lalempanua, seiya-sekatanya masyarakat dalam suatu
negeri.
20
To Maccae ri Luwu adalah orang yang bijak sekaligus penasehat kerajaan Luwu,
Sulawesi Selatan. Beliau hidup sekitar tahun 1530 an, sekitar 50 setelah lahirnya Kajao La
Mellong penasehat kerajaan Bone. Lihat Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Essai Tentang
Demokrasi Dan Kearifan Lokal, h. 33.
21
Ibrahim, Sulesana, h. 41.
91
2. Siallempurenggi, kejujuran kepada sesama masyarakat.
3. Siakkeda tongenggi, saling berkata benar diantara masyarakat.
4. Sia-sirikenggi, Saling memelihara siri’.
5. Ja’ na uru’, deceng na uru’, bersatu dalam duka dan bersatu dalam suka.
6. Sitereng ri bulu’e, tessinoreng ri lompo’e, ke gunung sama mendaki, tidak
saling menurunkan ke lembah.
7. Tessicarinnaianggi ri silasanae, tidak segan-segan membantu sesama
masyarakat.
8. Sipatonggi ri akkunae, saling membenarkan dengan apa adanya.
Dari cerita di atas menjelaskan bagaimana masyarakat akan mendapatkan
kesejahteraan dengan mengedapankan persatuan melalui sikap konsistennya
perkataan dan perbuatan, berkata jujur dan benar, saling menghargai, bersatu
dalam suka dan duka, saling menyanjung dan tidak saling menjatuhkan, menghina
seta menjelek-jelekan, tidak segan dalam membantu atas kesusahan yang dialami
oleh orang lain dan juga membenarkan apa yang memang pantas untuk
dibenarkan.
Dalam toleransi dalam masyarakat berdasarkan apa yang telah dijelaskan
oleh para tokoh sebelumnya bahwa selalu dibutuhkan dialog untuk melihat
dengan jelas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Berdialog dengan
mengedepankan rasa hormat dan saling menghargai. Dalam masyarakat Bugis
berdialog dikenal dengan istilah tudang sipulung atau bermusyawarah untuk
memperjelas persoalan yang terjadi dalam masyarakat.22 Adapun hasil dialog atau
hasil musyawarah tidak boleh dilanggar oleh raja karena ketetapan itu adalah hasil
dari ketetapan masyarakat banyak.
22
Ibrahim, Sulesana, h.156.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Toleransi dan keharmonisan sangat dibutuhkan dalam masyarakat guna
untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkemajuan dalam suatu
negeri. Indonesia yang kondisi masyarakat yang beragam dan kekayaan alam yang
berlimpah, mempunyai potensi besar untuk menjadi negara adidaya diantara
negara-negara lainnya apabila masyarakatnya bersatu dengan mengesampingkan
perbedaan yang ada.
Konflik yang selama ini terjadi, terlebih lagi konflik yang benuansa SARA
kebanyakan berangkat
dari kepentingan kelompok
yang mempropokasi
masyarakat. Kemudian dibumbuhi dengan anggapan isu-isu yang subjektif tanpa
mempertimbangkan benar dan baiknya. Dalam hal ini penulis melihat konflik
yang sudah perna terjadi khusus konflik yang membawa isu perbedaan agama
sesungguhnya menghancurkan harapan para founding fathers dan batang tubuh
dari dasar negara kita yaitu Pancasila.
Para tokoh telah menawarkan konsep toleransi dalam masyarakat. dalam
hal ini, penulis membahas toleransi menurut Mukti Ali, Alwi Shihab, dan
Abdurahman Wahid (Gus Dur). Dimana dari hasil analisis menulis yang secara
hati-hati menganggap bahwa Mukti Ali lebih menekankan penerimaan perbedaan
pendapat atas perbedaan yang ada dalam masyarakat. Alwi Shihab menekankan
keterbukaan dalam kehidupan beragama tanpa harus mempermasalahkan klaim
92
1
93
kebenaran suatu agama, maksudnya setiap orang akan mengatakan agama yang
dianutnya adalah agama yang paling benar dan tidak harus menghakimi
ketidakbenaran agama orang lain. Kemudian Abdurahman Wahid (Gus Dur)
menitik-beratkan
toleransi dari sisi kemanusiaannya, bahwa setiap orang
mempunyai hak-hak dalam kehidupannya, terlebih lagi undang-undang telah
mengatur hak-hak masyarakat untuk bebas memilih agama dan menjalankan
ajaran agama yang dianutnya.
Dari ketiga tokoh tersebut secara umum penulis memandang bahwa
toleransi menempatkan hak-hak kemanusiaan sebagai objek tertinggi. Ini sejalan
dengan konsep karifan lokal masyarakat Indonesia dalam hal ini penulis
mengambil objek toleransi yang terdapat dalam kearifan lokal masyarakat Bugis.
Dalam masyarakat Bugis bahwa prinsip siri’ adalah bagaimana seseorang
manusiakan seseorang yang lainnya (tau sipakatau), saling menghormati dan
saling menghargai (sipakalebbi), dan saling mengingatkan (sipakainge’).
Kemudian pesse yang menenkankan empaty atau jiwa sosial yang harus ada
dalam hati setiap orang. Karena seseorang akan dianggap lebih hina daripada
binatang (olok-kolok) apabila tidak terdapat pesse di dalam dirinya.
Begitu pula dengan panggederreng yang secara sederhana merupakan
serangkaian pedoman hidup masyarakat Bugis yang terdiri dari ade’, bicara,
rapang, dan wari. Dari keempat pedoman itu menjadi acuan masyarakat untuk
membedakan yang pantas atau tidak pantas seorang manusia lakukan. Niat,
perkataan dan perbuatan harus selalu dikontrol sehingga sesaui dengan ajaran
94
panggederreng, yang hakikatnya menjaga dan melestarikan siri’ dalam seseorang,
masyarakat, dan negara.
Kemudian yang terakhir konsep assimellereng (kesetiakawanan sosial)
dalam masyarakat bugis yang secara harfiah diambil dari kata “melle” yang berarti
bersambung atau terhubung. Masyarakat Bugis juga biasanya mengganti
assimellereng dengan kata “melle perru” yang bermakna rasa yang menyatuh
dengan orang lainnya, yang secara kongkrit berupa rasa kasihan, dimana itu
menjadi keharusan.
Demikian kesimpulan penulis melihat kearifan lokal masyarakat Bugis
yang mengandung nilai-nilai toleransi dan keharmonisan sebagaimana apa yang
telah penulis analisis dari teori Mukti Ali, Alwi Shihab, dan Abdurahman Wahid
(Gus Dur).
B. Saran-saran
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari berbagai
keterbatasan dan kekurangan, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal
mungkin. Toleransi merupakan pendukung terbesar untuk menciptakan Indonesia
negara yang maju. Mempermasalahkan perbedaan hanya membuang waktu saja.
Maka dari itu mari hidup damai dalam perbedaan, pada hakikatnya semua agama
mengajarkan kebaikan.
Semoga kajian toleransi dalam nilai-nilai kearifan lokal menjadi salah
satu aspek tinjauan dalam mewujudkan toleransi di Indonesia dan semoga
menambah luas peranan jurusan Studi Agama-Agama dalam menciptakan
95
akademisi yang toleran, serta bisa terjun langsung dalam masyarakat banyak. Ini
merupakan langkah awal dari penelitian yang telah penulis kaji. Oleh karena itu,
penulis berharap agar dapat melanjutkan penelitian ini, yang masih memiliki
banyak kekurangan dalam segi khasana keilmuan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin dan Norma Permata, Ahmad. (ed), Metodologi Studi Agama,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
Abudullah, Hamid. Manusia Bugis Makassar, Jakarta: PT Inti Idayu Press, Cet. I.
1985.
Agil Husin Al Munawar, Said. Aktualisasi Nilai – Nilai Al-Qur’an dalam
Pendidikan Islam, Jakarta, 2005.
Ali, Mukti. Agama dan Keagamaan di Indonesia, Jakarta: Biro Humas
Departemen Agama RI, 1972.
Ali, Mukti. Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia, Yogyakarta: Jajasan
Nida, 1971.
Ali, Mukti “Setuju dalam perbedaan” dalam Majalah Mawas Diri No. 1 TH. 1
Maret 1972, hal.6. liat juga Faisal Ismail, Republik Bhineka Tunggal
Ika:Mengurai Isu-isu Konflik Multikulturalisme, Agama, Sosial, dan
Budaya, Jakarta: Puslitbang Kehidupan keragamaan, 2012.
Ali, Mukti. Agama dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Biro Humas
Departemen Agama RI, 1972.
Bakir, Muhammad dan Zaid Mahyudi, M.
Gus Dur: Santri Par Exellence
(Teladan Sang Guru Bangsa “Abdurahman Wahid Ketegaran Pluralisme
Akar Rumput), Jakarta: Kompas, Cet. I, 2010.
Basuki, Singgih. Pemikiran keagamaan Mukti Ali, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
1
93
Ghofur, Abdul. Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia : Studi
Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Hardjana, A.M. Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik,
Yogyakarta, Kanisius, 1993.
Hasan, Fuad. Renungan Budaya, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-I, 1989.
Husin, Khairah. Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Agama di
Indonesia, RIAU: jurnal Ushuluddin UIN RIAU, Vol. XXI, No.1 Januari
2014.
Ismail, Faisal. Paving the War For Interreligion Dialogue, Tolerance, and
Harmony Following, Mukti Ali’s Path, hal. 174Mukti Ali, “Setuju dalam
perbedaan” Majalah Mawas Diri No. 1 TH. 1 Maret 1972
Ibrahim, Anwar. Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan
Lokal, Makassar: Lembaga penerbit Universitas Hasanuddin, 2003.
Kern, R.A. I LA GALIGO Cerita Bugis Kuno Edisi Indonesia, Jogja: Gadjah
Mada University Press, 1989, Cet.I.
Laica Marzuki, M. Siri Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar
(Sebuah Telaah Filsafat Hukum), Ujung Pandang, Hasanuddin University
Press, Cet. I, 1995.
Luth, Thohir. Masyarakat Madani: Solusi Damai dalam Perbedaan, Jakarta:
Mediacita, 2006.
Mangunwijaya, Y.B, dkk. Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman,
Jakarta: Kompas, 2001.
Mansur, Sufa’at. Toleransi dalam agama Islam, Yogyakarta; Harapan Kita, 2012.
94
Masdar, Umarudin. Membaca Pemikiran Gusdur dan Amin Rais tentang
Demokrasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Masykur Musa, Ali. Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur, Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2002.
Mattulada, LATOA : Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang
Bugis, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press Cet.II, 1995.
Muchtar Ghazali, Adeng. Ilmu Studi Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan,
Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran,
Jakarta: Rajawali Pres, 2009
Muhammad Syak’ah, Musthafa. Islam Tanpa Mazhab, Solo: Tiga Serangkai
2008.
Muqsith Ghazali, Abd Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi
Berbasis al-Quran, Depok: Katakita, 2009,
Norma Permata, Ahmad (Ed.), Metodologi, Yogyakarta: UII Press, 2003.
O’ Collins SJ, Gerald dan G. Farrugia SJ, Edward. Kamus Teologi, Yogyakarta:
Kanisius, 1996.
Pelras, Cristian. Manusia Bugis, Jakarta: Forum Jakarta-Paris, Cet. I,2006.
Peldi Taher, Elza., ed., Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 tahun
Djohan Effendi, Jakarta: ICRP & Buku Kompas, 2009.
Rahim, Rahman. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, Ujung Pandang:
Hasanuddin Universitas Press, 1992.
95
Rahmawati, Jurnal Pendidikan Nusantara Indonesia “Integrasi Nilai Budaya Siri’
dan Pesse Masyarakat Bugis Makassar dalam Pelajaran IPA Vol.1.No,
2015, (Unismuh Makassar)
Rahman, Nurhayati. Suara-Suara dalam Lokalitas, Makassar: La Galigo Press,
2012
Said, Marhadi. Jati Diri Manusia Bugis, Jakarta: Pro leader, 2016.
Santoso, Listiono. Teologi Politik Gus Dur, Jogjakarta: Ar-Ruszz Media, 2004.
Santoso, Listiyono. Mewacanakan Nalar Agama yang Inklusif dalam konteks
Kemanusiaan dan Kemajemukan Indonesia
Susanto, Limas. Dkk. Gus Dur: Santri Par Exellence “Psikoterapi Abdurahman
Wahid”, Jakarta: Kompas, Cet. I, 2010.
Shihab, Alwi. Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka, Bandung: Mizan, 1999.
Soekanto, Soerjono. Kamus Sosiologi, Jakarta: Royandi, 1985.
Syaefullah, Asep. Kerukunan Umat Beragama (studi Pemikiran Tarmizi Taher
tentang Kerukunan Umat Beragama, Jakarta: Penerbit Gragindo Khazanah
Ilmu. 2007.
Wahid, Abdurahman. dan Ikeda, Daisaku. Dialog Peradaban untuk Toleransi dan
Perdamaian, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Wahid, Abdurrahman. Tuhan Tidak Perlu Dibela, Yogyakarta: LKiS, Cet. 1,1999.
Wahid, Abdurrahman. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Jakarta:
Desantara, Cet.I, 2001.
Wahid, Abdurahman. Islam Ku, Islam Anda, Islam Kita (Agama Masyarakat
Negara Demokrasi), Jakarta: The Wahid Institute, Cet. I, 2006.
96
Wahib, Ahmad. Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib,
Jakarta: LP3ES, 1981.
Zainal Abidin Farid, A. dkk, Siri’ Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja, mandar
“Siri, Pesse Dan Were’ Pandangan Hidup Orang Bugis”, Makassar: Arus
Timur, 2014.
Sumber Internet
Norbert Ama Ngongu, “Pluralisme Dalam Perspektif Agama Katolik”artikel
diakses pada tanggal 4 September 2016,
http://norbertang.blogspot.co.id/2008/03/pluralisme-dalam-perspektif-agama.html
Listiyono Santoso, Mewacanakan Nalar Agama yang Inklusif dalam konteks
Kemanusiaan dan Kemajemukan Indonesia, diakses pada 15 November 2016 ,
https://www.academia.edu/8554403/Mewacanakan_Nalar_Agama_yang_Inklusif
_dalam_konteks_Kemanusiaan_dan_Kemajemukan_Indonesia,