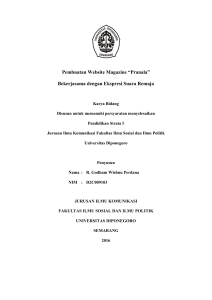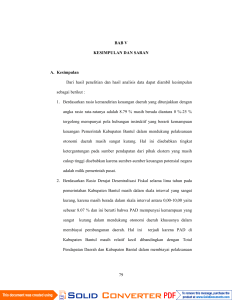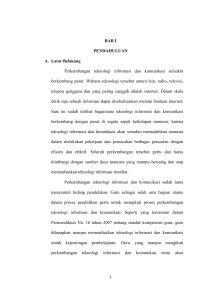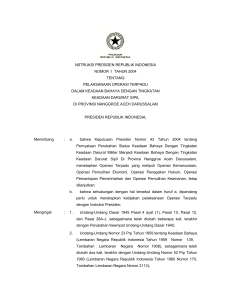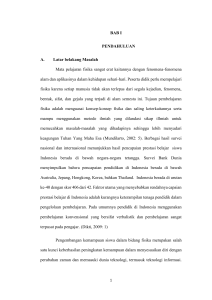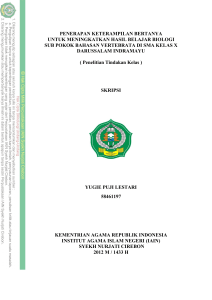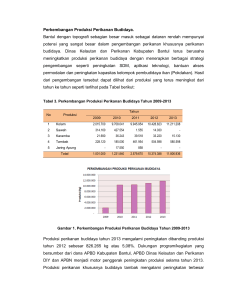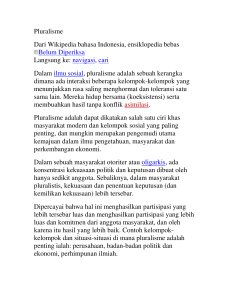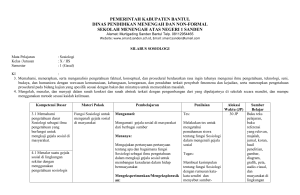advertisement
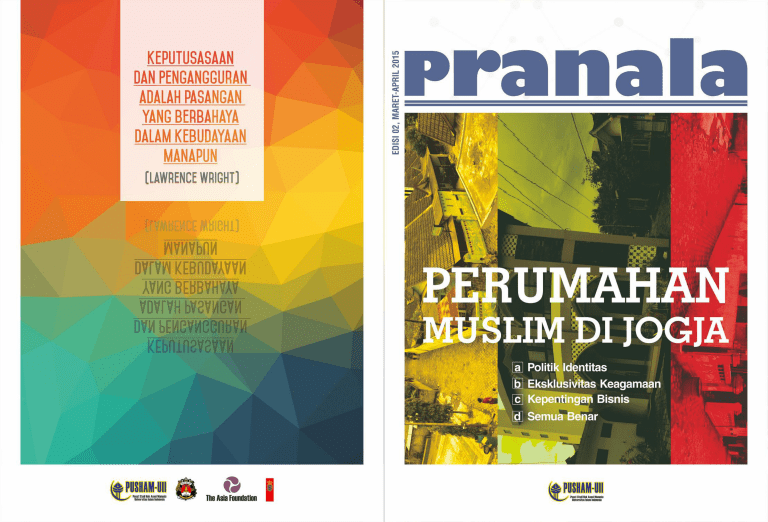
@Surat Pembaca
Film dan Masa Lalu Bangsa
Menarik membaca majalah Pranala edisi perdana, yang
mengangkat topik utama gagalnya pemutaran film Senyap
di berbagai tempat di Yogyakarta. Setidaknya ada dua hal
yang bisa dilihat dari peristiwa ini.
Pertama, terjadinya tindakan kekerasan oleh kelompokkelompok tertentu yang tidak sepakat dengan film ini. Situasi
ini semakin menguatkan opini publik bahwa di Yogyakarta dari
hari ke hari sudah tidak aman dan nyaman bagi warganya.
Kekerasan selalu saja menjadi jalan keluar dari setiap
perbedaan yang terjadi. Aparat Kepolisian seolah diam
membiarkan kekerasan itu terjadi, tanpa proses hukum
kepada pelaku. Tentu saja situasi seperti ini jika dibiarkan
terus menerus akan mengancam semangat hidup bertoleransi
di tengah-tengah masyarakat, yang selama ini melekat pada
kota Yogyakarta.
Kedua, secara keseluruhan isi dari majalah Pranala
edisi perdana ini bisa menjadi pintu bagi masyarakat untuk
berdiskusi tentang sejarah masa lalu bangsa. Ada banyak
catatan kelam sejarah bangsa yang secara sistematis
sengaja dihilangkan dalam ingatan masyarakat kita. Salah
satunya adalah seputar peristiwa 65. Film Senyap ini
sebenarnya bisa digunakan sebagai media alternatif untuk
melihat dan mengurai kembali apa yang sesungguhnya
terjadi di masa lalu.
Wahyu Warsito, Gowongan
Soal Spanduk Syi’ah
Di beberapa sudut jalan di Yogya belakangan ini banyak kita
jumpai spanduk-spanduk tentang bahaya Syi’ah. Entah siapa
yang memasangnya. Agak aneh rasanya, karena selama ini
khususnya di Yogya tidak ada aktifitas dari komunitas Syi’ah
yang cukup menonjol. Terlepas dari siapa dan bagaimana
Syi’ah, munculnya spanduk-spanduk ini tentu menimbulkan
keprihatinan, karena dikhawatirkan akan memunculkan
potensi kekerasan yang mengarah pada konflik bernuansa
agama. Dalam lima tahun terakhir kasus-kasus kekerasan di
Yogyakarta meningkat tajam. Baik kekerasan yang bernuansa
agama maupun kekerasan karena tindak kriminal murni.
Pemerintah daerah dan aparat kepolisian dan semua lapisan
masyarakat sudah seharusnya menyikapi masalah ini sejak
dini dengan serius.
Noviandi Ramadhan, Lempuyangan
Cara Mendapatkan Pranala
Mau tanya kepada redaksi. Gimana, ya cara untuk
mendapatkan majalah Pranala? Apakah dijual secara bebas?
Dimana bisa kami dapatkan ? Saya membutuhkan sekitar 20
buah untuk perpustakaan karang taruna di kampung saya.
Mohon informasinya.
Pratiwi Kusuma, Wates
Daftar Isi
2 EDITORIAL
Belajar dari Jeffrey Lang
4 LAPORAN UTAMA
Pertumbuhan Perumahan Melesat Pesat
8 LAPORAN UTAMA
Perumahan Muslim Dilembah Mejing
23 WAWANCARA
Arie Sudjito, Sisiolog Universitas Gadjah
Mada, "Kultur Masyarakat Jawa Tidak
Menyuburkan Garis Keras dalam Agama"
26 RESONANSI
Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme
Indonesia
14 LAPORAN UTAMA
31 TAGAR
17 LAPORAN UTAMA
33 RESENSI
20 WAWANCARA
36 PERSPEKTIF
Resiko Pembangunan Perumahan Muslim
Tak Ada Larangan Membuat Perumahan Muslim
Sugeng Bayu Wahyono, Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta,
"Kraton Cukup Khawatir dengan Keberadaan Islam Bercorak Timur
Tengah yang Menjadi Matahari Baru"
Netizen Pertanyakan Toleransi di Indonesia
Jalan Raya; Sebuah Jalan Menuju Toleransi
Tindak Kekerasan dalam PersPektif
Masyarakat Konsumtif
Editorial
BELAJAR DARI
JEFFREY LANG
Oleh: Puguh Windrawan
A
da yang menarik dari tulisan Jeffrey Lang
pada sebuah buku yang inspiratif. Buku itu
diterbitkan oleh Serambi pada tahun 2008, bertajuk “Aku Beriman, Maka Aku Bertanya”. Jeffrey Lang
adalah seorang profesor di sebuah perguruan tinggi
di Amerika. Setidaknya, ketika saya membaca buku
itu, Prof. Lang masih menjadi Guru Besar Matematika
di Universitas Kansas, Amerika. Saya merasa, bagian
paling menarik dari pengalaman Prof. Lang adalah
ketika suatu saat ia sedang berjalan dengan Jameela,
putrinya yang masih kecil. Kemudian terjadilah dialog
diantara mereka.
Intinya, Jameela ingin bertanya kepada ayahnya.
Bagaimana seandainya ia kemudian berpindah agama,
dari semula muslim ke Kristen? Sebagai penganut Islam,
tentu saja Prof. Lang terperanjat. Alasan Jameelah, sebagai seorang anak kecil sangat sederhana. Ia merasa
berat dengan apa yang harus dijalankan untuk menjadi
kewajiban seorang muslim. Bahkan ia bertanya kepada
ayahnya.
“Aku sekedar ingin tahu, apakah Ayah akan marah
padaku. Apakah nenek dan kakek memarahi ayah ketika engkau keluar dari agama Kristen dan kemudian
memeluk Islam?”
Prof. Lang agaknya mulai mengenang masa lalunya.
Agaknya, anaknya sudah mulai kritis dengan berbagai
hal yang muncul di sekitarnya, termasuk dalam dirinya
sendiri. Yang menarik adalah, ia sama sekali tak bisa
menyalahkan pemikiran Jameelah, yang kala itu masih
berusia 9 tahun. Ia merasa bahwa apa yang dipikirkan
2
PRANALA { Maret - April 2015 }
Jameela pernah muncul dalam dirinya sendiri. Anaknya
adalah refleksi dari pemikirannnya di masa lalu. Prof.
Lang mengerti, bahwa pertanyaan ini hanyalah sebuah bentuk awal dari apa yang disebutnya sebagai fase
kritik dan proses dalam perkembangan keagamaan.
Tanpa tendensi untuk menyalahkan sedikitpun, ia
kemudian berkata kepada Jameelah. Sebuah perkataan
bijak, yang luarbiasa. Prof. Lang mengatakan bahwa
ia sangat menyayangi anaknya itu. Mulai dari saat
menimang membuatnya seakan berada dia atas langit.
Sebuah kosakata untuk mengatakan bahwa memilik
Jameelah adalah sebuah anugerah yang luarbiasa.
“Dan setelah dewasa kelak, engkau juga harus melakukan apa yang kau yakini benar. Ayah akan selalu
mendampingi, membantu, dan menasehatimu, tetapi
pada akhirnya engkau sendirilah yang harus memutuskan apa yang kaunggap baik, bahkan ketika ayah
dan ibumu tak setuju dengan keputusanmu. Aku hanya
berharap, bahwa engkau mesti menentukan pilihanpilihan dengan penuh pertimbangan yang cerdas dan
matang,” kata Prof. Lang.
Siapa yang tidak terkejut mendapatkan pertanyaan
dari sang anak. Apalagi menyangkut agama. Bagaimana
jika ini terjadi dengan anak Anda? Saya terkadang berpikir, jika saya tidak dilahirkan oleh orang tua saya,
maka saya saat ini sedang berada dimana? Kebetulan,
saya lahir di keluarga muslim, jadinya tertera dengan
jelas bahwa orang tua saya memilihkan agama untuk
saya; Islam. Ini saya.
Tetapi, mungkin bisa jadi Anda berbeda. Anda lahir
di lingkungan keluarga Kristen, yang secara otomatis
membuat agama Anda menjadi Kristen. Saya tak pernah
menemukan hal ini. Ketika ada seseorang yang lahir
dari kedua orang tua yang muslim, ternyata orang tua
memilihkan anak itu beragama Kristen. Sebaliknya,
kedua orang tuanya Kristen, kemudian anaknya yang
lahir dijadikan beragama Islam. Saya belum pernah
mendengar itu.
Bukan hanya agama. Kita sendiri tak berdaya saat
dipilihkan sebuah nama oleh kedua orang tua kita.
Ketidakbedayaan membuat kita belum bisa mengambil
jalan sendiri. Pilihan orang tua, menjadi pilihan awal
yang sama sekali tak bisa ditolak. Memang, suatu saat
kita punya pemikiran sendiri. Setelah lama bergelut
dengan pengalaman-pengalaman, lantas kita bisa merujuk kepada identitas yang akan kita pikul. Akan tetapi,
landasan awal, baik tentang agama ataupun persoalan
pemilihan nama tetap pada orang tua masing-masing.
Ini juga masalah kesadaran tentang makna identitas itu. Kita itu sama-sama tak berdaya di hadapan
Tuhan, dan ketika Tuhan menjadikan kita manusia di
muka bumi, ada saat dimana kita sama sekali tak bisa
memilih. Ini yang harus dijawab, mengapa Tuhan memilihkan kita berada di tempat ini dan tidak di tempat
itu? Mengapa Tuhan menjadikan kita bertemu dengan
orang tua ini dan bukan dengan orang tua itu? Mengapa
Tuhan memberikan kita latar belakang kemiskinan dan
bukan memberikan kita kepada keluarga yang berlatar
belakang kekayaan?
Inilah yang harus dijawab. Tuhan pasti punya rencana untuk ini. Pastilah ada makna dan keterangan
Pranala
yang bisa ditelisik. Tuhan itu Maha Adil. Kita sepakat
untuk ini. Kita sepakat bahwa Tuhan bukan mahluk.
Dia-lah yang menguasai segenap alam, lalu mengapa
menjadikan kita berbeda satu sama lain? Dilahirkan
berbeda agama dan berbeda keyakinan. Apakah lantas
dengan itu semua membuat kita justru memberangus
perbedaan tersebut?
Awalnya sudah berbeda. Tak mungkin ada
kesamaan. Tuhan-lah yang membuat itu. Bukan hak
manusia dan bukan kewenangan manusia untuk menaklukan perbedaan. Bagaimana mungkin menaklukan
perbedaan sedang dari ‘sono-nya’ kita sudah berbeda?
Apa ada yang salah ketika kita dilahirkan di tengah keluarga Muslim, Yahudi atau Kristen? Itu bukan pilihan
kita. Kita hanya bisa memilih ketika kita sudah punya
pengalaman untuk memilih. Kita bisa menentukan
identitas kita setelah kita punya wawasan dan mengerti
tentang kehidupan.
Agama itu keyakinan, bukan sekedar pemberian.
Jika itu pemberian, maka Tuhan bisa dikatakan tidak
adil, karena menjadikan agama kita berbeda, karena
orang tua yang memilihkan kita untuk itu. Tapi saya
yakin dan mungkin Anda juga sepakat untuk itu; bahwa
Tuhan bukanlah entitas yang sembarangan. Ia disembah karena Ia punya kelebihan dibanding mahluk dan
bahkan menciptakan mahluk.
Lantas, apa yang membuat kita semua membenci
orang yang sama sekali berbeda keyakinan dengan
kita?
Diterbitkan Oleh
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta
Penaggung Jawab: Eko Riyadi | Pemimpin Redaksi: Puguh Windrawan | Reporter: Kamil Alfi
Arifin, Kelik Sugiarto, Prayudha Maghriby | Kontributor: Ahmad Alwajih, Mohammad Fathoni |
Fotografer: Gibbran Prathisara | Layout: Arief Mizuary
Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jeruk Legi RT. 13 RW. 35 Gang Bakung No.517 A, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta 55198 | Telpon: 0274-452032 | Fax: 0274-452158 | Website: www.pusham.
uii.ac.id Email: [email protected]
PRANALA { Maret - April 2015 }
3
Laporan Utama
Pertumbuhan
PERUMAHAN
MELESAT PESAT
Oleh: Prayudha Maghriby Foto: Gibbran Prathisara
Kebutuhan perumahan di Jogja saban tahun meningkat secara signifikan.
Ini diikuti dengan perkembangan wilayah yang juga semakin pesat.
Awalnya didesain sederhana, hanya beberapa wilayah yang bisa dijadikan perumahan.
Kebutuhan yang meningkat membuat desain awal tersebut terabaikan.
A
zizah sudah sekian kali melewati lampu
lalu lintas. Terik matahari yang memancar
sempurna di siang itu membuat perjalanannya terasa semakin panjang. Dari SD tempatnya
mengajar hingga rumahnya di Pajangan terbilang cukup
jauh. Itu sekitar 20 kilometer. Wajar jika ibu muda berusia 25 tahun itu kemudian mengeluh di status BBM-nya.
“Lampu merah bikin bad mood. Kapan nyampainya?”
Cuaca Jogja di bulan-bulan ini memang terbilang
cukup ekstrim. Jika siang panasnya menyengat dan
di sore harinya hujan turun lebat. Azizah belum sepenuhnya terbiasa dengan perjalanan panjang menuju
tempat kerja. Ini karena dia baru beberapa minggu
pindah. Sebelumnya ia tinggal di kontrakan dekat SD
tempatnya mengajar. Keputusan pindah itu diambil
setelah ia dan suaminya bisa mengumpulkan dana untuk
uang muka perumahan. Sebagai keluarga muda, ia tak
punya banyak pilihan soal lokasi perumahan. Ia mesti
4
PRANALA { Maret - April 2015 }
memilih perumahan dengan uang muka dan angsuran
yang terendah.
Beruntung, sebuah Perumahan Nasional (Perumnas)
baru saja di bangun. Namanya Perumnas Bumi Guwosari.
Namun demikian, lokasi perumahan terbilang cukup
jauh dari pusat kota. Harga murah tentunya tidak bisa
dicapai jika lokasi perumahan berada di kota. Harga jual
tanah di Jogja saat ini sudah sangat tinggi.
Perkembangan lokasi perumahan di Jogja yang begitu pesat itu sebenarnya telah diprediksi. Dikutip dari
sebuah tesis di Universitas Gadjah Mada yang ditulis
oleh Wahyu Nur Harjadmo pada tahun 1996, berjudul
“Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan
Perkotaan Yogyakarta”, bahwa sebenarnya pada tahun
1988, pemerintah DIY telah menyiapkan desain pengembangan kota yang bernama Yogyakarta Urban Development
Project (YUPP). Desain ini digagas atas kerjasama
Pemda DIY dengan Swiss. Melalui SK Gubernur Kepala
Laporan Utama
membutuhkan 39.742 unit rumah. Pada 2033, jumlah kebutuhan rumah di Bantul diproyeksi mencapai 174.254
unit. Sebagian rumah dapat dipenuhi dalam bentuk
perumahan. Pertumbuhan perumahan tersebut terutama
akan ada di wilayah YUPP.
Wilayah Banguntapan, Sewon, dan Kasihan sebagai
daerah penyangga utama memiliki kepadatan penduduk
cukup tinggi. Akibatnya, jumlah kebutuhan perumahannya cukup tinggi. Namun demikian, dalam perhitungan
Bappeda Bantul, jumlah ketersediaan lahan pemukiman
bisa mengimbangai pertumbuhan jumlah penduduk
hingga tahun 2033. Semakin padat sebuah lokasi, harga
jual tanahnya juga akan semakin naik. Untuk tetap bisa
membangun perumahan dengan harga yang masuk akal,
sejumlah pengembang mulai melirik wilayah Piyungan,
Pleret dan Pajangan untuk dijadikan perumahan.
Wilayah Pajangan menjadi lokasi yang baru-baru ini
mulai dikembangkan. Meski lokasinya relatif jauh dari
Jogja, kepadatan penduduk di Pajangan masih relatif
rendah dibanding lokasi penyangga lainnya. Perumnas
yang Azizah tempati juga berada di kecamatan yang terkenal dengan keberadaan Goa Selarongnya ini. Cukup
sulit untuk bisa menyediakan perumahan yang relatif
murah di wilayah penyangga lainnya.
****
TINGKAT PENGHASILAN
MERUPAKAN KRITERIA DALAM PENGAJUAN
KREDIT PERUMAHAN.
SESEORANG ATAU SEBUAH
KELUARGA DIANGGAP
MAMPU UNTUK MENGANG
SUR PERUMAHAN JIKA
MEMILIKI PENGHASILAN
RP.900 RIBU HINGGA
RP. 1,5JUTA.
6
PRANALA { Maret - April 2015 }
Setelah hampir satu jam berpacu di jalanan kota, motor Suzuki Smash milik Azizah kini mendapat tantangan
baru. Mesin 110 cc di motor itu mesti menaklukan tanjakan 45 derajat. Azizah menurunkan gas dan terpaksa
diganti ke gigi satu. Gas sedikit digeber dan ibu muda
bertinggi badan kurang lebih 150 cm itu melaju. Seluruh
motor bergetar termasuk barang belanjaan di motornya.
Saat mencapai puncak, Azizah segera menikung
tajam ke arah kanan. Roda gigi motor dinaikan ke angka 2. Segera saja ia memasuki sebuah kebun jati yang
rimbun. Di balik rerimbunan itulah tempat perumahan
Azizah berdiri. Lokasinya tepat di titik tertinggi puncak,
tepatnya di Desa Guwosari. Sebagian besar unit yang ada
telah rampung. Beberapa lainnya masih dalam proses
finishing.
Baru saja mesin motor berhenti, Azka, anak Azizah
membuka pintu. Ia berlari ke arah Azizah sembari berteriak, “Ummi, mana chiken-nya?”
Azizah punya kebiasaan membeli lauk untuk makan siang. Ia cukup kewalahan jika mesti masak untuk
makan siang.
“Awas knalpot. Ini sayang. Abi mana?” ujar Azizah,
memanggil suaminya.
Keluarga kecil Azizah kemudian makan siang bersama di rumah tipe 29 itu, tipe rumah terkecil di Perumnas.
Sebuah kipas angin menjaga mereka untuk tetap nyaman. Azka makan dengan lahap dan tak bisa diam. Ia lari
keluar masuk ruang rumah yang terdiri dari dua kamar,
satu kamar mandi, dan ruang tamu itu. Sang suami, Ali,
tetap pendiam namun juga terus lahap makan. Setelah
makan, Ali mesti berangkat kerja di sebuah restoran
sebagai juru masak.
Pasangan ini sama-sama bekerja. Namun untuk soal
penghasilan, Azizah tak mau begitu terus terang. Jika
keduanya digaji UMR Kota Jogja sebesar Rp. 1.302.500,
maka penghasilan keluarga itu sebesar Rp. 2.605.000,-.
Penghasilan itu termasuk dalam golongan menengah,
jika mengikuti kriteria BPS.
Tingkat penghasilan merupakan kriteria dalam
pengajuan kredit perumahan. Seseorang atau sebuah
keluarga dianggap mampu untuk mengangsur perumahan jika memiliki penghasilan Rp. 900 ribu hingga
Rp. 1,5 juta. Dengan penghasilan sebesar itu seseorang
dikatakan bisa mendapatkan rumah dengan ukuran 21
m2 – 36 m2. Keluarga Azizah masuk dalam kriteria menengah. Dengan demikian, ia seharusnya bisa mendapatkan
rumah yang lebih besar.
Perumahan sendiri dapat dibagi menjadi dua berdasarkan penyedianya; oleh masyarakat, serta oleh swasta
dan pemerintah. Bagi seorang pendatang seperti Azizah,
mengakses perumahan dari swasta dan pemerintah lebih
masuk akal dari pada mesti membangun sendiri. Azizah
adalah perantau dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan
suaminya berasal dari Tulang Bawang, Lampung. Cukup
sulit bagi Azizah dan suami untuk memiliki tanah di
Jogja. Apalagi untuk membangun rumahnya sendiri.
Pemda Bantul memperkirakan jika pembangunan
perumahan oleh masyarakat dapat memenuhi 25% kebutuhan rumah. Perumahan yang dibangun masyarakat
diperkirakan mencapai 57.452 unit hingga tahun 2033.
Kebutuhan rumah selanjutnya mesti dipenuhi oleh pengembang baik swasta maupun negara. Hingga tahun
2033, swasta dan negara harus bisa mencapai target
pembangunan 172.356 unit rumah di Bantul.
Bagi pengembang properti, target pembangunan
rumah bukan semata beban, tetapi juga peluang bisnis.
Sejumlah pengembang ramai-ramai mengajukan izin
pembangunan. Tercatat ada 29 perumahan yang telah
mendapatkan ijin pembangunan perumahan. Beberapa
pengembang telah memulai pembangunan dan beberapa
lainnya masih dalam proses pembebasan lahan.
Beberapa perumahan memiliki blok pengembangan
yang cukup luas. Dengan demikian, izin yang diajukan
juga lebih banyak. Dari 29 perumahan tersebut, tercatat izin pembangunan yang dikeluarkan oleh Dinas
Perizinan Bantul mencapai 1.046 pada 2012. Angka itu
belum termasuk pengembang yang masih dalam proses
pengajuan izin. Perum Padma Residence yang terletak
di Bangunjiwo, Kasihan, tercatat mengantongi izin
terbanyak yakni 135 perizinan. Sementara itu, Perum
Perumnas, tempat Azizah menetap, telah mengantongi
73 izin. Perizinan paling sedikit dimiliki oleh Perumahan
Pesona Tamanan Asri, yakni sebanyak 7 izin pembangunan.
Nama Pengembang yang Telah Mendapatkan Izin
No.
Nama Perumahan
Jumlah Izin
1.
Taman Pleret Asri
62
2.
Graha Banguntapan
53
3.
Metro Harmony Residence 2
18
4.
Graha Nirmala
54
5.
Perum Kaliurang
20
6.
Kharisma Cepoko
11
7.
Pesona Tamanan Asri
7
8.
Kadipiro Indah
28
9.
Griya Prima Baru
14
10.
Purimas Tamansari
41
11.
Perumnas Guwosari
73
12.
Pesona Tamanan Asri
16
13.
Dalem Banguntapan Asri
8
14.
Kavling Bangunjiwo
33
15.
Potorono Residence
17
16.
Kavling Cikalan
7
17.
Puri Tamanan Indah
11
18.
Pondok Permai Kadipiro
72
19.
Padma Residence
135
20.
Pesona Nirmala
12
21.
Kuantan Regency Soragan
14
22.
Azzafira
57
23.
Ruko Sonosewu
11
24.
Pesona Kuantan
10
25.
Graha Sedayu Sejahtera
50
26.
Villa Banguntapan
50
27.
Laguna Spring Jogja
55
28
Sawit Asri Residence
58
29.
Puri Sakinah
49
Jumlah
1.046
Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bantul per Mei 2012
PRANALA { Maret - April 2015 }
7
Laporan Utama
PERUMAHAN MUSLIM
DI LEMBAH
P
engeras suara berbunyi nyaring, tepat pada jam 4
sore. Suaranya membelah perumahan di lembah
yang dikelilingi sungai dan hutan bambu itu.
“Teman-teman sudah jam 4, loh. Belajar TPA, yuk?”
ucap suara anak melalui pengeras suara.
Anak-anak yang tadinya asyik bermain sepeda segera menuju sumber suara. Suara itu berasal dari sebuah
masjid di tengah lembah. Kubah dan menara masjidnya
berwarna keemasan dan menjulang hingga bisa disak-
8
PRANALA { Maret - April 2015 }
sikan dari semua penjuru.
Di saat yang sama, anak-anak laki-laki di kampung
sebelah utara perumahan masih asyik bermain sepak
bola. Beberapa anak perempuan sibuk menggarisi tanah
untuk bermain engklek. Lokasi bermain itu tepat di depan Masjid Al Hidayah. Di tembok masjid tertera jika
pada jam itu seharusnya TPA —sebagaimana di masjid
perumahan— telah dimulai. Kampung itu berada tepat
di atas lembah.
Oleh: Prayudha Maghriby
Foto: Gibbran Prathisara
H MEJING
Perumahan khsusus berbasis keyakinan
semakin banyak berdiri.
Salah satunya adalah Perumahan
Muslim Darussalam.
Akankah perumahan eksklusif seperti ini
mengurangi seamangat keberagaman?
Jalanan kampung saat itu mulai ramai dilintasi mobil. Sempat ada Nissan Grand Livina keluaran terbaru
melintas menuju lembah. Merek lain seperti Suzuki APV
Arena juga tampak melintasi jalan menurun nan sempit
itu. Mereka adalah para penghuni perumahan yang baru
pulang dari tempat kerja.
Sebaliknya, aktivitas bekerja justru tengah di mulai di kampung sebelah utara lembah. Seorang lelaki
bertelanjang baju tampak mengangkat ember besar
bekas cat tembok. Air di ember itu lantas disiramkan
ke lantai sebuah kandang. Anak-anak anjing tampak
berkejar-kejaran di sekeliling kandang. Mungkin karena
terganggu, hewan peliaraan di kandang itu mencuatkan
kepalanya. Telinga hewan itu pendek. Kulitnya berwarna pink. Rupanya itu adalah kandang babi. Kandang
semacam itu ternyata hampir ada pada tiap rumah di
kampung utara lembah.
Perumahan dan kampung-kampung yang mengitari
PRANALA { Maret - April 2015 }
9
Laporan Utama
lembah itu terhitung masih dalam wilayah Pedukuhan
Mejing Wetan, Ambar Ketawang, Sleman. Waljiati,
seorang penduduk asli kampung menuturkan, jika perumahan itu baru didirikan pada 2004 silam. Lokasi
perumahan sebelumnya adalah hamparan sawah milik
salah satu warga kampung.
“Dulu kepunyaan orang kaya di sini. Dia tanahnya
ada di mana-mana,” ujar wanita 49 tahun ini.
Karena tepat di sisi sungai yang berhulu di Merapi,
tanah di lembah itu bercampur dengan pasir. Sawah
menjadi kurang subur dan sang pemilik akhirnya memutuskan untuk menjualnya. Singkat cerita, berdirilah
perumahan yang kemudian dikenal sebagai Perumahan
Muslim Darussalam. Jumlah rumah di kompleks itu terus bertambah. Beberapa warga kampung mau melepas
tanah untuk dijadikan lokasi pengembangan perumahan. Hingga kini, perumahan Darussalam terdiri dari 3
Rukun Tetangga (RT) dan 99 unit rumah.
****
Darussalam nampak lengang di Ahad siang. Seorang
satpam tampak siaga di posnya. Matanya terus mengawasi tiap kendaraan yang melewati pintu masuk
perumahan. Setelah bisa memastikan tidak ada yang
perlu dicurigai, satpam itu melempar senyum kecil sembari menganggukan kepala. Artinya, sang pengunjung
bisa terus masuk.
Saat memasuki gang-gang Darussalam, tampak mo-
10
PRANALA { Maret - April 2015 }
bil-mobil menepi di sisi-sisi gang. Rumah-rumah sepi.
Sedikit aktifitas hanya tampak di salah satu persimpangan gang. Seorang lelaki paruh baya, berperawakan
kurus, dengan rambut yang hampir memutih sepenuhnya tengah memanjat tiang listrik dengan tangga. Di
bawahnya tampak tiga orang lelaki yang lebih muda
berdiri sembari mengawasi.
Lelaki paruh baya itu namanya Subari. Usianya 55
tahun.
“Ini saya pasangi empat sensor surya di empat titik.
Saya paralelkan jaringannya,” ucap Subari sembari memasukan sebatang rokok ke mulutnya.
Pemasangan sensor itu agar lampu jalan bisa mati
otomatis di saat gelap. Ada masalah soal lampu penerangan jalan. Tagihan listrik masjid membengkak
karenanya. Karena penghuni perumahan sibuk, seringkali lampu jalan tetap menyala meski hari telah terang.
“Kabel optik internet sekalian saya perbaiki. Kalau
pakai wireless mesti ada repeater dan access point,”
tambahnya.
Subari yang hari itu mengenakan setelan kaus oblong dan celana jeans yang dipotong selutut itu tampak
sangat menguasai istilah dalam teknologi informasi.
Rupanya dia adalah mantan pegawai Telkom. Saat ini
ia mengelola usaha jasa yang terkait dengan IT. Ia sendiri telah menjadi
penghuni Darrussallam dari perumahan itu pertama dibangun. Sebelumnya
ia tinggal di perkampungan tempat kelahirannya, Sosrowijayan. Karena
kurang nyaman dengan lingkungannya, ia dan isteri memutuskan pindah
ke Darussalam.
Subari dan isteri mendapat informasi perumahan dari sebuah koran.
Suatu hari di tahun 2003 isterinya menemukan iklan rumah berharga sekitar Rp. 60 juta. Terbilang cukup murah untuk ukuran
saat itu. Meski sedikit tak percaya, Subari memutuskan
untuk menelusuri info itu. Ia khawatir jika itu hanya
bentuk penipuan. Sampai di lokasi ia mendapati fondasi-fondasi bangunan telah ada. Tak pikir panjang ia
pun bergabung menjadi salah satu dari 99 pembeli perumahan itu.
Di balik iklan Perumahan Darussalam itu ada tiga
serangkai: Mansur Fahmi, Agus Prayitno, dan Salim.
Ketiganya adalah alumnus Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional (STPN) Yogyakarta. Berawal dari keinginan
memiliki rumah sendiri, mereka kemudian merancang
sebuah perumahan. Agar daya tawar ke pihak pengembang kuat, mereka lantas mengumpulkan calon
pembeli terlebih dahulu. Iklan yang mereka sebarkan
mampu menarik sejumlah calon pembeli.
Pada akhir 2003, sekitar 50 calon pembeli kemudian dikumpulkan di Masjid STPN. Sebuah pengembang
akhirnya tertarik untuk membangun 99 unit rumah
di Dusun Mejing. Perumahan itu terbagi ke dalam
Darussalam 1 dan 2. Direktur pengembang, Bambang,
rupanya dengan tanpa seizin Mansur, Agus, dan Salim
membangun Darussalam 3 di Condongcatur. Belakangan
diketahui jika Bambang baru saja keluar penjara atas
tindak penipuan terkait Darussalam 3.
Mansur menuturkan, jika tidak ada rencana khusus untuk menjadikan Darusalam sebagai perumahan
muslim yang eksklusif. Penggunaan nama Darussalam
juga lebih karena ia dan Agus Priyatno punya kenangan
dengan nama itu saat masih di kampung halamannya,
Purbalingga.
“Masjid di sana (Purbalingga-red) namanya
Darussalam. Jadi sesedarhana itu,” ujar pria kelahiran
1973 ini.
Ia juga menampik jika ada ketentuan khusus agar
Darussalam menjadi perumahan muslim. Menurutnya,
tidak ada ketentuan khusus soal identitas keagamaan
bagi calon pembeli perumahan saat itu.
“Tidak ada batasan semisal yang kristen tidak boleh
beli,” tambah Mansur yang kini bertugas di kantor Badan
Pertanahan Umum (BPU) Purwodadi ini.
Namun demikian, Mansur tidak mengelak jika konsep perumahan yang islami memang menjadi konsep
sedari awal. Pada kesepakatan yang dibuat bersama
pengembang, Mansur dan kedua rekannya meminta
agar fasilitas masjid menjadi hal utama. Konsep islami
itu yang kemudian menjadi salah satu daya tarik bagi
PRANALA { Maret - April 2015 }
11
Laporan Utama
pembeli.
“Kita punya cita-cita. Karena muslim, yah,” ucap
Mansur.
Dalam perencanaannya, Mansur mencoba memenuhi
syarat perumahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang
diyakininya. Mansur mencontohkan, jika ia memiliki
ruangan khusus bagi tamu, terpisah dengan rumah utama. Toilet pada tiap rumah juga diusahakan agar tidak
menghadap kiblat.
Terkait dengan kehidupan sosial perumahan,
Darussalam juga disetting agar sesuai dengan keyakinan yang mereka peluk. Sebuah masjid bernama Masjid
Darussalam menjadi pusat kegiatan perumahan. Rapat
dan pengajian rutin dilaksanakan di masjid yang diresmikan langsung oleh Sri Purnomo, Bupati Sleman kala
itu. Mansur sendiri saat ini dipercaya sebagai ketua
takmir masjid. Tepat di samping masjid berdiri sebuah
bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain
sebagai tempat pendidikan, PAUD juga berfungsi untuk
menitipkan anak-anak dari penghuni perumahan selama mereka beraktifitas. Rencana selanjutnya, Mansur
dan pengurus masjid akan mengambangkan program
tahfidzul qur’an.
Uniknya, selain memiliki ketua RT, Darussalam
juga memiliki Amir. Amir menjadi semacam pemimpin
perumahan. Sosok Ahmad Sumiyanto, mantan anggota
DPRD DIY dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
didaulah menjadi Amir hingga kini. Terkait dengan
konsep keamiran, Mansur menampik jika itu menjadi
simbolisasi negara Islam atau semacamnya. Amir perumahan dipilih untuk memudahkan koordinasi warga.
“Kami tidak membuat padukuhan sendiri. Itu untuk menjaga hubungan baik dengan warga kampung,”
ujarnya.
Amir diharapkan bisa memaksimalkan kordinasi
kerja antara dua RT di Darussalam. Ahmad Sumiyanto
dipilih karena dianggap memiliki kapasitas.
“Pak Totok (Ahmad Sumiyanto-Red) dipilih karena
beliau bisa diterima semuanya,” tambah Mansur, sembari menampik jika pemilihan Amir dilatarbelakangi
kepentingan politik praktis tertentu.
****
12
PRANALA { Maret - April 2015 }
Dadang Winarko mengamati pemasangan sensor
surya oleh Subari. Sesekali ia melempar canda untuk
mencairkan suasana. Sosok berperawakan tinggi besar
ini belum begitu lama menjadi ketua RT 12. Sebagaimana
Subari, ia juga menjadi penghuni Darussalam sejak awal.
“Karena murah dan kalau orang Jawa bilang sudah
pulung (keberuntungan),” ungkap Dadang menjelaskan
alasan utamanya memilih Perumahan Darussalam sebagai tempat tinggal.
Mengurus warga RT 12 Darussalam menurut Dadang
tidak terlalu sukar. Sebagian besar warganya memang
cukup sibuk. Warganya kebanyakan adalah kaum profesional. Tidak sulit menemukan dokter bahkan dosen
di Darussalam.
“Ini yang lelaki dosen psikologi UGM dan isterinya
dosen psikologi UAD,” ujar Dadang sembari menunjuk
sebuah rumah di samping tempatnya berdiri.
Kesibukan warganya luar biasa padat, sehingga ia
perlu mensiasati jika ingin membuat pertemuan warga.
Tidak semua warga ia kenali. Ini karena beberapa dari
mereka adalah penghuni kontrak. Bahkan, ada rumah
yang dari pertama dibangun hingga kini belum sempat
ditengok oleh si pemilik.
“Mungkin untuk investasi atau apa saya tidak tahu,”
tambah pria kelahiran Kentungan, Surabaya, 1973 silam ini.
Terkait investasi, Dadang menceritakan jika rumah tipe 36 —ukuran asli perumahan saat awal— di
Darussalam kini bisa mencapai kisaran Rp. 300 juta.
Harga itu berbeda jauh dengan harga awal yang hanya
Rp. 60 juta-an.
Sebagai perumahan yang memakai tageline Islam,
Dadang berpendapat jika secara tidak langsung penghu-
KERENTANAN KONFLIK
DADANG SADARI JUGA BISA
MUNCUL DARI PERBEDAAN
KARAKTERISTIK ANTARA
PENGHUNI PERUMAHAN
DENGAN WARGA KAMPUNG.
POTENSI KONFLIK YANG
TERKAIT DENGAN KELAS
SOSIAL, KELAS EKONOMI,
DAN JUGA IDEOLOGIS.
ni Darussalam memang spesifik. Ada pemisahan secara
alami dari sisi keyakinan. Dadang tidak menampik jika
pernah terjadi konflik terkait itu. Peristiwa itu terjadi
beberapa tahun silam. Satu keluarga mengontrak salah
satu rumah. Mereka penganut Kristiani. Dadang dan
hampir seluruh warga cukup kaget. Penghuni baru itu
tidak mendapat banyak kesempatan untuk bergaul dengan warga.
Ini karena sebagian besar kegiatan dipusatkan di
masjid. Mungkin karena tidak nyaman, penghuni itu
akhirnya memutuskan untuk pindah. Kepindahan itu
pun tidak sepengetahuan pengurus RT dan Keamiran.
Selain kejadian itu, ada juga penghuni mu’alaf yang
mengontrak salah satu rumah. Dia membawa serta keluarganya yang notabene penganut Kristiani. Untuk
kejadian ini Dadang tidak terlalu mengikuti. Yang jelas
saat ini, penghuni itu sudah tak lagi ada di Darussalam.
Kerentanan konflik Dadang sadari juga bisa muncul
dari perbedaan karakteristik antara penghuni perumahan dengan warga kampung. Potensi konflik yang
terkait dengan kelas sosial, kelas ekonomi, dan juga
ideologis. Sebelum ada perumahan, lokasi Darussalam
dikenal sebagai pusat peternakan babi. Perlahan peternakan babi mulai surut. Kini tersisa beberapa rumah di
utara perumahan yang masih memlihara babi.
“Ada seorang warga tengah menarik babi. Tiba-tiba
ada anak kecil bertanya, Pak babi itu, kan, haram,” ujarnya mengingat sebuah cerita jenaka.
Untuk soal ini, pihak Darussalam melihatnya sebagai
ladang dakwah. Ada pengajian yang turut serta mengundang warga kampung.
“Pernah ada ibu-ibu izin pengajian karena babinya
melahirkan,” kenang Dadang menyulut tawa.
Selain itu, Darussalam juga rutin mengadakan bakti
sosial seperti pengobatan gratis dan pemberian sembako.
Agoes Erwin Sulaiman, pria yang juga memperhatikan usaha Subari memasang sensor surya menambahkan
beberapa keterangan. Darussalam juga telah beberapa
kali mengadakan peringatan hari besar bersama-sama
dengan warga Kampung Mejing. Menjelang bulan
Ramadhan, anak-anak dari Darussalam dan kampung
berkolaborasi menggelar karnaval islami. Para penghuni
Darussalam yang memiliki pengetahuan seputar Islam
juga kerap menjadi pengkhotbah di pengajian atau acara
keagamaan lainnya di kampung. Erwin yang sehari-hari
bekerja sebagai staf di Fakultas Ilmu Budaya UGM ini
juga menuturkan pernah ada kegiatan unik. Pernah sesekali ada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia
yang perlombaannya tidak lazim.
“Ada itu peringatan 17-an, tapi lombanya itu qiroaah
dan hafalan qur’an,” canda pria asli Bandung ini.
Kepala Dukuh Mejing Wetan, Sudaryono, mengamini jika Darussalam cukup membantu warga kampung.
Ini terutama soal keagamaan. Menurutnya, para
penghuni Darussalam telah banyak mengubah wajah
kampungnya.
“Tidak ada yang salah. Kami justru merasa sangat
terbantu sejak kehadiaran Perumahan Darussalam terutama soal agama,” kata pria 52 tahun ini.
Terkait dengan adanya anggota DPRD di Darussalam,
Sudaryono tidak begitu melihatnya sebagai masalah.
Ketika Pemilu, tidak ada hal yang dalam penilainnya
mengganggu. Semua partai dapat kesempatan untuk
memaparkan visi dan misinya.
“Aman mas. Di sini semua boleh kampanye,” tukas
kepala dusun dari salah satu wilayah di kecamatan
Ambar Ketawang yang pada Pemilu 2009 dimenangkan
oleh PKS ini. Sudaryono berharap jika hubungan baik
antara Perumahan Muslim Darussalam dengan warga
kampung Mejing Wetan terus terjaga dengan baik.
PRANALA { Maret - April 2015 }
13
Laporan Utama
RESIKO PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
MUSLIM
Oleh: Kamil Alfi Arifin
Foto: Gibbran Prathisara
Perumahan-perumahan muslim
kian merebak.
Kemunculannya menciptakan
fenomena kantong-kantong
pemukiman eksklusif.
Buktinya, warga non-muslim
tak boleh membeli dan tinggal di
dalamnya.
S
ejumlah warga di kompleks perumahan muslim Djogja Village Plosokuning IV, Sleman,
kasak-kusuk, bergosip tak sedap, ngrasani, dan mempersoalkan penghuni baru, yang
baru saja masuk dan tinggal di perumahan muslim ini. Sebabnya, tetangga baru itu
ditemukan memiliki identitas agama lain yang berbeda dari seluruh warga yang tinggal di
dalamnya. Bagi warga, hal ini dipandang sebagai sesuatu yang ganjil dan sama sekali tidak lazim
dalam lingkungan mereka.
Kejadian itu berawal saat seorang pemilik salah satu
rumah di kompleks perumahan muslim Djogja Village
Plosokuning IV, terpaksa meninggalkan rumahnya karena harus pindah ke luar kota. Dari pada tak ditempati,
pemilik rumah berpikir untuk menyewakan saja rumah
14
PRANALA { Maret - April 2015 }
itu. Rumah terurus, juga dapat keuntungan sewa. Begitu
pikirnya. Namun, yang kemudian menjadi persoalan,
rumah itu disewakan kepada orang yang dianggap tidak
tepat, yakni keluarga non-muslim.
Sontak, hal tersebut menjadi sumber kasak-kusuk
warga. Mereka mengaku kecolongan atas kasus tinggalnya warga non-muslim di kompleks perumahan muslim
ini. Demikian yang diceritakan Firdaus, salah seorang
warga, sekaligus mantan Ketua RT, di kompleks perumahan muslim Djogja Village Plosokuning IV, saat
ditemui di kediamannya. Menurut Firdaus, warga perumahan muslim Djogja Village Plosokuning IV, mempersoalkan “tinggalnya warga non-muslim” di kompleks
perumahan muslim yang mereka tempati, lantaran kasus
tersebut memang melanggar aturan sebagaimana yang
sudah ditetapkan.
“Dulu pernah terjadi, entah karena pemiliknya
mengabaikan atau tidak perduli, dia mengontrakkan
rumahnya ke non-muslim. Sempat jadi…ya, kita komunikasikan. Waktu itu kita jadi pengurus RT. Terus kita
sampaikan ke yang bersangkutan bahwa ada peraturan
seperti ini. Sebenarnya kita sendiri, warga internal perumahan ini, tidak masalah. Cuma khawatirnya, dengan
warga yang di luar gitu, loh. Kalau kita, sih, enggak apaapa. Sepanjang tidak mengganggu dan melanggar normanorma yang umumlah,” ujar Firdaus panjang lebar.
Perumahan muslim Djogja Village ini, terletak di sebuah perkampungan muslim Plosokuning IV, di mana
semua warganya adalah muslim. Sejak adanya rencana
pembangunan perumahan oleh pengembang di perkampungan ini, kata Firdaus, ada tuntutan dari masyarakat
sekitar kampung untuk “memuslimkan” perumahan
yang hendak dibangun itu.
Akhirnya, berdirilah perumahan muslim Djogja Village ini. Berdasarkan tuntutan warga kampung sekitar,
pengembang perumahan muslim Djogja Village menetapkan satu persyaratan penting bagi calon pembeli dan
penghuninya, yakni yang bersangkutan harus muslim.
Perumahan muslim ini tidak boleh dihuni dan dijualbelikan kepada dan untuk warga non-muslim.
Ketua Dukuh Plosokuning IV, Yadidi, juga menegaskan hal yang serupa. Menurutnya, perumahan muslim Djogja Village Plosokuning IV ini memang khusus
muslim. Bahkan, persyaratan ini berlaku mengikat dan
memiliki kekuatan hukum. “Jadi yang jual tahu, dan yang
beli juga tahu, kalau (perumahan) ini muslim. (Ketentuan) ini sudah dinotariskan,” paparnya di waktu dan
tempat yang berbeda.
Peristiwa dikeluarkannya warga non-muslim di perumahan muslim Djogja Village Plosokuning IV bukan
kasus tunggal. Kasus yang hampir sama juga pernah
terjadi di perumahan muslim Darussalam 1 dan 2 di Sidoarum Godean. Menurut cerita yang dikisahkan Dadang,
salah satu warga di perumahan muslim ini, beberapa
tahun yang lalu, ada pemilik rumah yang juga sempat
mengontrakkan rumahnya kepada non-muslim. Akan
tetapi, warga non-muslim itu tidak diminta keluar.
Meski demikian, lanjut Dadang, warga non-muslim itu
tetap keluar dengan sendirinya tanpa sepengetahuan
warga sekitar.
“Enggak pamitan, tiba-tiba keluar dengan sendirinya.
Enggak ada yang tahu,” katanya.
Di perumahan muslim ini, memang tidak ada ketentuan dan persyaratan secara tertulis, bahwa pembeli
dan penghuni harus muslim. Di Jalan Imogiri Timur
Km 9, juga terdapat perumahan muslim Graha Taman
Asri. Sama halnya dengan perumahan muslim Djogja
PRANALA { Maret - April 2015 }
15
Laporan Utama
MUNCULNYA PERUMAHAN
MUSLIM BERESIKO BAGI
MASYARAKAT MULTIKULTUR.
INI KERUGIAN. RUANG
MENJADI EKSKLUSIF, DIKOTAKKOTAKKAN IDEOLOGI
Village Plosokuning IV, perumahan muslim Graha Taman Asri terletak di sebuah perkampungan muslim,
Jati Wonokromo.
Menurut keterangan ketua RT setempat, saat ada
pengembang masuk dan berencana membangun proyek perumahan di wilayah muslim ini, masyarakat
berkumpul dan sepakat meminta pihak pengembang
untuk membangun perumahan muslim, yang di dalamnya, tidak diperkenankan warga selain muslim tinggal.
“Bukan apa-apa, kasihan juga takut tidak kerasan.
Karena di sini masyarakatnya muslim,” kata Priyana.
Di kampung muslim ini, lanjut Priyana, sudah ada
peraturan yang sudah menjadi tradisi, yakni warga
non-muslim diwajibkan mengikuti kegiatan (bahkan
juga kegiatan keagamaan) yang diadakan masyarakat,
termasuk tahlilan. Sementara, warga non-muslim tidak diperkenankan mengadakan aktivitas keagamaan
mereka sendiri.
Tahun-tahun belakangan ini, perumahan-perumahan
muslim kian merebak. Perumahan-perumahan muslim
mudah ditemukan di sejumlah tempat di Yogyakarta.
Sejauh pantauan redaksi Pranala, empat kabupaten di
kota yang majemuk ini, yakni Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul, terdapat perumahan muslim di
dalamnya. Meskipun, di kabupaten Bantul, perumahanperumahan muslim lebih banyak dan dominan.
***
Menanggapi fenomena kian maraknya perumahanperumahan muslim di Yogyakarta ini, sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), S. Bayu Wahyono,
mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari semakin
mengentalnya proses islamisasi di tengah-tengah masyarakat. Dan mengentalnya islamisasi ini, ditangkap
16
PRANALA { Maret - April 2015 }
secara cerdas oleh para pengembang (developer) dengan
memasukkan konsep agama dalam bisnis properti yang
mereka garap. Orang-orang modern, kata dia, memang
seperti “belanja agama”. Padahal lanjut Bayu, untuk
konteks Yogyakarta sebagai “city of tolerance” dan “city of
pluralism”, perumahan-perumahan muslim sangat merugikan dan beresiko.
“Munculnya perumahan muslim beresiko bagi masyarakat multikultur. Ini kerugian. Ruang menjadi eksklusif, dikotak-kotakkan ideologi” ujarnya.
Di rumah joglonya yang asri dan nyaman, di Dusun
Terung, Wedomartani, Bayu menjelaskan panjang lebar
pandangannya terkait perumahan muslim dan keberagaman di Yogyakarta. Menurut Bayu, dalam ruang-ruang
yang dikotak-kotakkan ideologi, seperti perumahanperumahan muslim, masyarakat sangat mudah untuk
dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Sebab, interaksi mereka dengan yang lain terbatasi.
“Intertekstualitasnya rendah,” katanya.
Dengan pertimbangan seperti itu, Bayu kembali menegaskan, bahwa perumahan-perumahan muslim menjadi problem krusial bagi keberagamaan di Yogyakarta.
Interaksi menjadi semakin mampat.
“Ruang-ruang yang diideologisasi tidak produktif
untuk membangun masyarakat toleran,” tegas doktor
lulusan Universitas Airlangga (Unair) tersebut.
Meski demikian, lelaki yang juga mengajar di jurusan
Kajian Budaya dan Media di Sekolah Pascasarja UGM
tersebut mengaku tidak tahu pasti, mengapa pemerintah
daerah kurang menyadari masalah serius ini. Seolah-olah
terkesan begitu mudahnya memberikan Izin Membangun Bangunan (IMB) perumahan muslim di Yogyakarta
kepada para pengembang.
“Bisa jadi karena kuatnya daya tawar kelompok islam politik di jajaran pemerintahan daerah. Di birokrasi
terjadi santrinisasi. Bisa jadi,” kata Bayu.
Bayu hanya berharap, saat ini dan ke depan, Islam
ditampilkan secara lebih cerdas, agar tidak merugikan.
TAK ADA LARANGAN
MEMBUAT PERUMAHAN
MUSLIM
Oleh: Kamil Alfi Arifin Foto: Gibbran Prathisara
P
Tidak ada persoalan perizinan terkait
maraknya perumahan-perumahan muslim di Jogja.
Sekalipun perumahan-perumahan tersebut menuai kritik.
Dianggap merugikan dalam konteks Yogyakarta sebagai
kota yang majemuk dan toleran.
ukul 11.00 siang. Matahari bersinar hampir
nyaris tepat di atas kepala. Kota Bantul, siang
itu, begitu terik dan panas. Sedikit berdebu.
Namun, Sri Ediastuti terlihat tetap fokus bekerja di
ruangan kantornya yang lebar. Di atas mejanya, bertumpuk-tumpuk berbagai macam dokumen.
“Silahkan duduk di sini saja, mas. Saya sambil kerja,
ya?” ujarnya sambil menawarkan tim Pranala duduk di
atas dua kursi yang terletak di depan meja kerjanya.
Setelah dzuhur dan istirahat, dia mengaku ada agenda
rapat dengan bawahannya. Sehingga, dia tetap memilih
duduk di kursi kerjanya dibandingkan di kursi sofa berwarna hitam tempat dia biasa menerima tamu-tamunya,
hanya untuk menyiapkan bahan-bahan rapat berupa
data-data yang belum rampung dia bereskan.
Sri adalah Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
Melihat posisinya, maklum, jika pekerjaannya bejibun.
Semua perizinan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), di wilayah kabupaten Bantul berada di bawah tugas dan wewenangnya. Saat tim Pranala diminta mengutarakan dan menjelaskan kepentingan menemui dirinya,
Sri sempat bingung lantaran tim Pranala mengatakan
bahwa Pranala merupakan majalah Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII).
“Apa kaitannya, mas?” sergahnya.
Sri merasa tak mengerti, apa kaitan HAM dengan
tugas-tugasnya di Kantor Dinas Perizinan Kapubaten
Bantul.
Lulusan Magister Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut juga sempat bingung saat
tim Pranala menanyakan soal perumahan-perumahan
muslim yang kian marak di Yogyakarta.
“Tidak tahu saya,” tegas dia.
Sri tidak terlalu memperhatikan fenomena kian maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta
secara serius. Hanya saja, setelah mengingat-ngingat,
PRANALA { Maret - April 2015 }
17
Laporan Utama
Sri kemudian baru menyadari kalau dirinya beberapa
waktu yang lalu sempat mendengar soal adanya perumahan muslim. Tetapi, Sri tidak mendengar langsung
soal perumahan muslim ini dari orang-orang di kantornya. Padahal, kata dia, bawahan di kantornya, terutama tim teknis, bertugas setiap hari meninjau pendirian
bangunan di lapangan.
“Tahunya kita, ya, dengar dari orang luar. Cerita orang
saja,” ujarnya.
Menurut Sri, pihaknya juga tidak mempersoalkan
perumahan-perumahan muslim yang kian marak di
Yogyakarta tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya hanya
sekadar menilai dari segi kelayakan bangunan. Hal itu
sesuai dengan peraturan sebagaimana sudah ditetapkan.
“Kita, kan IMB itu dari sisi bangunan. Bukan dari sisi
muslim tidaknya,” terangnya.
Dalam buku panduan dan pedoman “Perizinan Dasar” yang diterbitkan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul,
berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
hanya tertulis: 1) Foto copy identitas diri/KTP pemohon.
2) Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan diwakilkan. 3) Fotokopi sertifikat tanah/
bukti kepemilikan tanah dengan status tanah pekarangan atau non-pertanian. 4) Surat pernyataan kerelaan
antar pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila
pemilik bangunan bukan pemilik tanah. 5) Surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan. 6) Surat pernyataan tidak
keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung. 7)
Gambar rencana bangunan dengan skala 1:100 atau 1:50
yang meliputi: situasi, denah, tampak (depan, belakang,
samping kanan, samping kiri) rencana (pondasi, atap,
sanitasi) potongan (melintang dan memanjang). 8) Gambar dan perhitungan konstruksi baja (untuk bangunan
yang menggunakan baja). 9) Gambar dan perhitungan
beton (untuk bangunan bertingkat dan menggunakan
struktur beton). 10) Hasil tes sondir (untuk bangunan
bertingkat >12 m). 11) SPPL/DPL (untuk bangunan gedung kepentingan umum dan komersial dengan luasan
ruang komersial >54 m2); 12) Untuk selain bangunan
rumah tinggal tidak bertingkat dilengkapi dengan: a)
18
PRANALA { Maret - April 2015 }
KALAU PERSYARATAN
TIDAK APA-APA. KIT
DENGAN PERATURA
Surat Keterangan Rencana Kabupaten dari DPU. b).
Pengesahan Dokumen Perencanaan dari DPU. 13) Untuk
perumahan dilengkapi dengan: a). Persetujuan site-plan
dari DPU. b). Dokumen Pengelolaan Lingkungan bila
luas lahan >5.000m2.
Dari segi mata rantai prosedur perizinan perumahan,
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini, merupakan puncak legalitas atau output akhir suatu perumahan bisa
disebut legal atau tidak. Bagi pengembang perumahan,
sebelum IMB bisa diterbitkan, terdapat beberapa izin
lain yang juga mesti dipenuhi. Untuk di Kabupaten Bantul, berikut berbagai ketentuan admintrasi yang harus
dipenuhi tersebut, tim Pranala kutip dan himpunkan
dari situs rumahjogjaindonesia.com.
Pertama, Persetujuan Prinsip kepada bupati. Persetujuan prinsip ini merupakan langkah awal yang harus ditempuh setiap pengembang sebelum melakukan
pembukaan lahan baru. Persetujuan prinsip ini berisi
rekomendasi dari Bupati Bantul, apakah lokasi yang
akan dibuka sebagai perumahan, secara Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, boleh digunakan sebagai pemukiman atau tidak.
Kedua, Aspek Tata Ruang kepada Kepala DPU. Setelah
mendapatkan persetujuan prinsip dari bupati, dalam
tahapan berikutnya, pengembang harus mengajukan
permohonan aspek kesesuaian tata ruang kepada DPU.
Ketentuan ini, dimaksudkan agar setiap pembangunan
perumahan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga akan terwujud penyelenggaraan bangunan perumahan yang tertib, andal, dan
serasi dengan arah kebijakan Kabupaten Bantul.
Ketiga, Klarifikasi (luas lahan 0,05 Ha s/d 1 Ha) kepada
Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan Ijin Lokasi
kepada Kepala Dinas Perijinan (luas lahan >1 Ha (10.000
m²). Setelah pengembang mendapatkan rekomendasi
aspek tata ruang, pengembang harus mengurus perijinan
FENOMENA KIAN MARAKNYA P
DI YOGYAKARTA MULAI MEND
BANYAK KRITIK. PERUMAHAN
SEMAKIN MEMPERTAJAM SEKAT
KANTONG EKSKLUSI
NNYA TERPENUHI, YA
TA NORMATIF, SESUAI
AN YANG BERLAKU,
berkaitan dengan proses tanah yang akan digunakan.
Untuk luas lahan dengan luasan antara 0,5 Ha sampai
dengan 1 Ha, harus mengajukan klarifikasi ke kantor pertanahan. Sedangkan, untuk lahan di atas 1Ha pengembang harus mengajukan ijin lokasi ke Dinas Perijinan.
Keempat, Pengesahan Site plan kepada Kepala DPU.
Site plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan
fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan,
jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan. Dalam site plan, diatur berbagai ketentuan yang
harus dilakukan pengembang, agar perumahan tersebut
tidak membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan serta dampak sosial lainnya.
Misalnya, soal prosentase penggunaan tanah, luas
tanah efektif maksimal 65% dari seluruh luas lahan, sementara sisanya 35% persen untuk fasilitas sosial (fasos)
dan fasilitas khusus (fasos).
Kelima, Dokumen Pengelolaan Lingkungan kepada
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pengembang
perumahan juga harus menyusun dokumen UKL/UPL
jika lokasinya di perkotaan dengan luas lahan 0,5 ha
sampai dengan 5 ha atau luas lantai bangunan kurang
dari 10.000 m2. Menyusun AMDAL jika lokasi di perkotaan, dengan luas lebih dari 5 ha atau kepadatan penduduknya 350 jiwa/ha atau luas lantai bangunan lebih dari
10.000 m2. Sedangkan, pembangunan perumahan di luar
perkotaan dengan luas lahan 0,5 ha sampai dengan 10
ha atau kepadatan penduduknya 150 jiwa/ha atau luas
lantai bangunan kurang dari 10.000 m2 wajib menyusun
dokumen UKL/UPL. Luas lahan lebih dari 10 ha atau luas
lantai bangunan lebih dari 10.000 m2 yang lokasinya di
luar perkotaan wajib menyusun AMDAL.
Setelah melewati berbagai ketentuan tersebut, baru
kemudian masuk ke dalam proses akhir yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dilihat dari prosedur perizinan perumahan dari instansi terkait di Kabupaten
PERUMAHAN-PERUMAHAN MUSLIM
DAPATKAN SOROTAN DAN MENUAI
N-PERUMAHAN MUSLIM DIANGGAP
T-SEKAT DAN MEMBUAT KANTONGSIF DI YOGYAKARTA.
Bantul, tidak terlihat adanya larangan membangun perumahan-perumahan berlabel agama yang peruntukannya
dikhususkan untuk pembeli dengan identitas agama
yang sama dalam bisnis properti, seperti perumahanperumahan muslim.
Kalau ada pengembang memohon surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengisi formulir dan memenuhi
semua persyaratannya, pihak perizinan akan memproses dan menerbitkan izinnya. Tidak jadi soal apakah
itu perumahan muslim, Kristen, Hindu, Budha dan lain
sebagainya.
“Kalau persyaratannya terpenuhi, ya tidak apa-apa.
Kita normatif, sesuai dengan peraturan yang berlaku,”
terang Sri.
Seorang pengembang perumahan muslim yang bernaung di bawah PT Arofa, Fajrianto, saat ditemui tim
Pranala di waktu dan tempat yang berbeda, juga menyatakan hal senada dengan Sri. Menurutnya, secara
perizinan, tidak masalah mendirikan perumahan dengan
label agama, seperti perumahan muslim.
Fajriyanto sendiri sudah cukup lama bermain dalam
bisnis properti perumahan. Pada tahun 2009 yang lalu,
Fajriyanto sudah mendirikan perumahan muslim Taman
Azmi di Kasongan, Bantul. Tahun ini, Fajriyanto kembali membangun proyek perumahan muslim Sidoarum
Harmony 2 di Godean Sleman.
Padahal, fenomena kian maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta mulai mendapatkan sorotan dan menuai banyak kritik. Perumahan-perumahan
muslim dianggap semakin mempertajam sekat-sekat
dan membuat kantong-kantong eksklusif di Yogyakarta.
Sebagai kota yang majemuk, kemunculan dan kian
maraknya perumahan-perumahan muslim dianggap
kontraproduktif bagi Yogyakarta terutama dalam agenda
membangun masyarakat multikultur. Di wilayah Bantul,
sejauh pantauan tim Pranala, cukup banyak perumahanperumahan muslim bila dibandingkan dengan di wilayah
kabupaten lainnya, seperti di Kulonprogo dan Gunung
Kidul. Menanggapi kritik tersebut, Sri tutup mulut.
“Enggak komen, karena saya dari sisi bangunannya,
ya?” tampiknya.
PRANALA { Maret - April 2015 }
19
Wawancara
Sugeng bayu Wahyono, SoSiolog univerSitaS negeri yogyakarta
“KERATON CUKUP
KHAWATIR DENGAN
KEBERADAAN ISLAM
BERCORAK TIMUR
TENGAH YANG BISA
MENJADI MATAHARI
BARU.”
Wawancara Oleh: Kelik Sugiarto
Di Yogyakarta marak pendirian perumahan
berlabel agama tertentu. Nyaris di setiap kabupaten bahkan sudah berdiri perumahan
muslim. Menurut Anda apa yang terjadi?
Fenomena ini memang tidak terlepas dari perkembangan sosial politik selama 20 tahun terakhir. Terutama
gerakan Islam politik di Indonesia. Gerakan Islam politik
berkembang cukup signifikan dan masuk ke dalam negara. Tentu ini bisa dikatakan sebagai awal kebangkitan
gerakan Islam. Gerakan Islam politik menyadari betul
bahwa di Indonesia ini negara mempunyai posisi yang
sangat penting, sehingga mereka bergerak mengembangkan diri lewat negara. Kalau bisa ya, merebut negara.
Gerakan Islam politik ini semakin mendapatkan momentum yang lebih baik ketika terjadi perubahan sistem
politik dari otoriter ke demokrasi.
Sebagai contoh, pada Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Dalam beberapa dekade terakhir ditempati
oleh kalangan islamis. Padahal dulu diisi dari kalangan
nasionalis. Media juga secara luar biasa memproduksi
wacana keislaman ini. Pada posisi itulah kemudian Islam
hadir membangun kelas menengah.
Dulu di jajaran birokrasi dari kalangan priyayi nasionalis Jawa, sekarang mengalami santrinisasi. Secara
ekonomi, kelas menengah ini potensial, sehingga ini
ditangkap oleh pasar sebagai peluang untuk dijadikan
20
PRANALA { Maret - April 2015 }
Foto Oleh: Gibbran Prathisara
lahan bisnis. Bagaimana pasar ini kemudian melayani
kelas menengah yang lebih santri, islami, yang mempunyai kesadaran beragama Islam yang lebih kuat. Ini
kemudian ada kaitannya dengan gaya hidup kelas menengah generasi muslim.
Apakah situasi ini bisa dihubungkan dengan fenomena kapitalisme yang juga semakin menguat?
Yang namanya kapitalis, bendera itu nggak penting.
Yang berlaku ya, pasar. Sebagai contoh, pasar ini kemudian melayani gaya hidup dalam hal fashion, misalnya busana muslim. Bersamaan dengan itu, di institusi
birokrasi, tren busana muslim ini kemudian bisa menggantikan busana nasional. Busana muslim sekarang ini
menjadi busana resmi. Itulah salah satu keberhasilan
pasar menangkap kebutuhan kelas menengah.
Logika sosiologis mengatakan, siapapun yang berada
dalam kelas menengah ini pasti mereka akan gelisah
dan sekuler. Mereka takut mati. Satu-satunya tawaran
alternatif untuk menetralisir kegelisahan itu ya, agama.
Agama menjadi penting untuk memapankan supaya
pencapaiannya dan kemapanannya tadi tidak terusik
dan terus diakui keberadaannya sebagai kelas menengah. Nah, dari situ muncullah kemudian apa yang di
namakan “belanja agama”. Salah satunya ya, perumahan
muslim itu tadi.
Apakah munculnya perumahan muslim ini
bisa mengancam semangat toleransi?
Fakta di lapangan penguatan identitas agama, entah itu
Islam, Kristen, memang cukup menguat, khususnya di
Yogyakarta ini. Orang merepresentasikan identitasnya
itu ke arah agama. Implikasinya, muncul ruang-ruang
mengikuti atau dibatasi oleh ideologi. Nah, kalau itu
yang terjadi, maka munculnya perumahan muslim itu
sebenarnya merupakan kerugian dalam upaya membangun masyarakat yang multikultur.
Apalagi bagi Yogyakarta sendiri yang berniat menjadi
“City of Tolerance” ini. Hal ini pasti menjadi masalah karena ruang itu menjadi eksklusif, terkotak-kotak oleh
identitas agama. Sekarang banyak muncul kos muslim,
sekolah muslim, salonpun ada yang muslim. Akibatnya,
masyarakat yang berada di ruang-ruang itu intelektualnya rendah dan akan makin ideologis, tapi mudah untuk
di mobilisasi. Makanya orang-orang PKS, Hizbut Tahrir
itu kan, intelektualnya rendah dan jadi lebih ideologis,
tapi mudah untuk digerakkan. Jadi munculnya perumahan muslim itu sebenarnya ya, bentuk dari ruang-ruang
ideologis tadi.
Jika memang keberadaan perumahan muslim ini dirasakan mengancam kehidupan
bertoleransi, mengapa pemerintah daerah
tetap memberikan izin pendiriannya?
Kalau pemerintah daerah konsisten dengan sebutan “City
of Tolerance”, maka seharusnya selektif dengan apapun
yang tidak produktif bagi terciptanya masyarakat yang
toleran. Bisa jadi ini karena kuatnya daya tawar kelompok Islam politik ini di jajaran birokrasi. Bisa juga karena sudah terjadi santrinisasi birokrasi, atau bisa juga
karena gigihnya developer dalam menawarkan produk
propertinya.
Sebenarnya keberadaan perumahan muslim ini berpotensi menjadi tidak produktif untuk membangun
masyarakat yang toleran.
Dulu Sultan pernah mencanangkan perkampungan
muslim di daerah Piyungan. Namun akhirnya tidak jadi.
Tapi toh, perumahan muslim ini kemudian tetap dibangun dan tersebar di seluruh kabupaten.
Ini bisa ditafsirkan bagaimana keraton membonsai
Islam. “Itu lho, wong mung sak kampung“. Sama halnya
dengan perumahan muslim tadi. Itu kan, sebenarnya
merugikan bagi umat muslim sendiri.
Pertama karena menjadi eksklusif, kedua mengandaikan yang di luar perumahan muslim berarti bukan
muslim. Yang muslim ya, yang berada di perumahan itu.
Yang lainnya bukan muslim.
Sama halnya kalau kita masuk ke kawasan tertib
lalu lintas. Itu kan, berarti di luar kawasan itu kita bisa
sakkarepe, to? Boleh nggak pakai helm, SIM, STNK. Kan,
tidak berada di kawasan tertib lalu lintas? Keberadaan
perumahan muslim ini maksudnya biar kelihatan islami,
tapi akhirnya malah kontra produktif bagi umat muslim
sendiri.
Kasus-kasus intoleransi marak terjadi di
Yogyakarta. Sultan sebagai pengayom masyarakat sepertinya tidak cukup baik merespon masalah ini. Menurut Anda?
Sebenarnya keraton cukup gelisah dan prihatin dengan
aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hanya saja keraton tidak cukup adaptif dengan perkembangan perilaku masyarakat yang cenderung lebih vulgar
dan dangkal. Politik keraton itu mengedepankan rasa.
Jadi menyikapi peristiwa intoleran ini dengan rasa itu
tadi. Tapi kan, itu dulu. Kalau sekarang ya, tidak bisa.
Harus dengan tindakan tegas.
Dulu kalau Sultan mengeluarkan statement yang sifatnya menyindir secara halus itu masih efektif bagi masyarakat. Kalau sekarang kan, tidak. Keraton sebenarnya
tidak diam. Hanya saja kemudian tidak mengambil
PRANALA { Maret - April 2015 }
21
Wawancara
tindakan dengan tegas dan masih menggunakan politik rasa. Bisa juga bagi keraton, masalah intoleransi ini
dianggap sebagai masalah biasa yang akan hilang dengan
sendirinya. Tapi harus diakui, politik keraton dalam
menyikapi masalah intoleran ini memang mengalami
penurunan.
Padahal dukungan kepada keraton jika mengambil
isu tentang toleransi beragama itu tinggi sekali. Kalau
dulu keraton mempunyai sumber daya yang cukup kuat
untuk membonsai agar Islam tidak masuk ke dalam ranah politik, caranya seperti apa?
Ya, pokoknya Islam itu mengurus orang mati dan
DALAM PEMIKIRAN SAYA,
KELAS MENENGAH MUSLIM INI
HARUS MEMBANGUN FASILITASFASILITAS PUBLIK SEBAGAI
WADAH BEREKSPRESI BAGI
BUDAYA LOKAL INI. DAN DENGAN
SENDIRINYA, YANG NAMANYA
RADIKALISME ITU AKAN PUDAR.
menikah saja. Kemampuan untuk memanage politik Islam
itu cukup canggih. Tapi sekarang nampaknya sudah
tidak bisa. Seperti penjelasan di awal, dalam 20 tahun
ini gerakan Islam politik ini sangat masif, bahkan negara pun tidak bisa membendung munculnya gerakangerakan ini.
Negara kesulitan membendung, apakah
ini artinya keraton juga memiliki kesulitan yang sama?
Pada sisi yang lain, keraton cukup khawatir dengan keberadaan Islam bercorak Timur Tengah yang bisa menjadi “matahari baru”. Dalam politik kekuasaan Jawa tidak
di kenal “matahari kembar”. Kalau ada potensi munculnya “matahari baru” pasti ditumpas. Dan yang paling
berpotensi ya, gerakan-gerakan Islam, terutama yang
dimobilisasi dari pesisir. Jadi pihak keraton memang
sudah sejak dulu mewaspadai gerakan-gerakan Islam.
Dalam penelitian saya ketika keraton bertindak sebagai penjaga toleransi dan kebudayaan Jawa, maka
resonansi kekuasaan keraton itu memudar. Seperti
gelombang radio, semakin jauh akan semakin lemah
sinyalnya. Tapi kalau isunya tentang persatuan, maka
22
PRANALA { Maret - April 2015 }
dukungan di daerah itu tidak pudar. Jadi walaupun
jauh secara teritori tapi punya kedekatan secara budaya, maka orang-orang di daerah itu akan mendukung
kebijakan keraton.
Jadi seperti orang abangan yang ada di Pacitan atau
di Ponorogo yang mempunyai kedekatan budaya dengan
keraton. Kalau untuk membangun toleransi mereka akan
mendukung. Sebaliknya, kalau dekat secara teritori, seperti Kauman, tetap bersikap kritis kepada keraton. Jadi
tetap ada potensi untuk berkompetisi secara politik
dengan keraton, dan yang paling menonjol ya kelompok
Islam ini.
Seperti yang saya katakan tadi, kalau keraton bersikap tegas terhadap masalah-masalah intoleransi, pasti
akan mendapat dukungan dari masyarakat. Hanya sepertinya masalah intoleransi ini memang uncontroling.
Bahkan institusi negara tidak cukup mampu mengatasi
masalah ini, termasuk keraton.
Anda bisa memberikan contoh?
Acara nonton film Senyap saja dibubarkan paksa. Ada
organisasi gay mengekspresikan identitasnya juga digrebek. Komunitas Ahmadiyah juga ditekan. Tradisi-tradisi lokal yang hidup di masyarakat dicap syirik, bid’ah.
Padahal kalau agama tidak disentuh dengan nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal, maka agama itu akan tampil
garang. Dan di situ pasti muncul intoleran dan akan
tergelincir pada tindakan yang lebih otoriter.
Maka di Nahdlatul Ulama (NU) itu bisa hidup berdampingan dengan kaum abangan tanpa ada masalah. Ini
karena Islam bisa bertemu dengan budaya-budaya lokal.
Sepanjang spirit lokalitas itu tetap diberi ruang untuk
berekspresi, maka itu akan menjadi habitat subur bagi
tumbuhnya toleransi. Tapi kalau ruang itu dimatikan,
maka yang lokal ini akan habis. Tidak punya daya tawar
lagi dalam hal toleransi agama.
Dalam pemikiran saya, kelas menengah muslim ini
harus membangun fasilitas-fasilitas publik sebagai
wadah berekspresi bagi budaya lokal ini. Dan dengan
sendirinya, yang namanya radikalisme itu akan pudar.
Tapi kelas menengah ini yang bermasalah. Sibuk dengan
dirinya sendiri. Akhirnya ya, belanja agama itu tadi. Perumahan muslim salah satunya.
arie Sudjito,SoSiolog univerSitaS gadjah mada
“KULTUR MASYARAKAT JAWA
TIDAK MENYUBURKAN
GARIS KERAS DALAM AGAMA.”
Wawancara oleh: Kamil Alfi Arifin
Foto Oleh: Gibbran Prathisara
Belakangan ini di Yogyakarta, semakin merebak perumahan-perumahan berlabelkan
agama, perumahan-perumahan muslim
atau perumahan-perumahan Islam. Ini fenomena apa?
Ini merupakan gejala makin menguatnya sentimen identitas di masyarakat, sektarianisme sebagai bagian dari
ekspresi pendangkalan relasi antar kelompok. Gejala ini
sebenarnya sudah agak lama, dalam berbagai bentuk.
Bukan saja mereproduksi identitas agama namun juga
etnik, afiliasi politik dan sejenisnya.
Ini sebagai sinyal menguatnya pola eksklusif masyarakat baru saat memahami perbedaan. Namun hal
semacam ini sebenarnya merupakan gejala yang dialami
kota-kota besar, dimana arus perubahan sosialnya pesat.
Hal ini tanpa dibarengi orientasi membangun kultur
kewargaan yang inklusif.
Kalau di Yogyakarta terus terjadi sektarianisme kelompok, berarti ada suasana “kohesi dan inklusi” yang
hilang. Hal demikian bisa jadi dampak pembangunan
dan kebijakan pemerintah yang keliru, ataukah juga
karena masyarakat yang makin pragmatis dan kurang
peduli atas situasi seperti ini.
Menurut Anda, perumahan-perumahan
muslim ini hanya sekedar bentuk eksploitasi kapitalisme (bisnis properti) terhadap
agama? Atau semacam penguatan identitas
keislaman dan upaya kontrol terhadap ruang yang dilakukan oleh kelompok tertentu
untuk kepentingan ideologi tertentu?
Hal tersebut perpaduan antara bagian menguatnya
sentimen identitas sektarianisme di satu sisi, dengan
hasrat komodifikasi para pemilik modal yang berupaya
memanfaatkan hal seperti itu untuk kepentingan bisnis.
Namun yang namanya kapitalisme itu, apa saja dijadikan
komoditas. Mereka selalu berupaya mencari untung,
bahkan dengan cara merusak sekalipun. Itulah kenapa
kapitalisme itu membahayakan, persis juga bahayanya
sektarianisme agama atau etnik.
PRANALA { Maret - April 2015 }
23
Wawancara
Dalam konteks toleransi, apakah fenomena
merebaknya perumahan-perumahan muslim ini tidak “mengganggu”, karena hanya
membuat kantong-kantong pemukiman
yang tertutup?
Kalau pembentukan komunitas itu diikuti oleh sentimen
kuat kelompok dan mereproduksinya secara eksklusif,
ini akan problematik dalam interaksi antar identitas.
Agama apapun atau etnik apapun potensi eksklusif selalu ada. Namun ruang interaksi untuk terbuka saling
belajar dan bekerjasama sangat dibutuhkan dalam masyarakat plural seperti Indonesia.
Apalagi di Yogyakarta, sikap inklusif dan kerjasama
dalam perbedaan sangat diperlukan untuk membangun
toleransi. Paling tidak itu bagian dari pertanggungjawabannya sebagai daerah istimewa dalam pengertian
positif. Kecenderungan sekat itu, membutuhkan jalan
keluar agar tidak mengarah tubrukan atau gesekan yang
negatif.
Adalah makin diperlukannya ruang publik untuk
kerjasama, berdebat dan berdialog dalam kebijakan, dalam praksis kebudayaan maupun cara-cara apapun yang
memiliki misi kerjasama dan dialog yang bermartabat.
Di perumahan muslim, salah satu persyaratannya harus muslim. Bahkan ini sudah diaktanotariskan oleh pihak pengembang. Sementara
warga non-muslim tidak boleh membeli dan
tinggal di dalam perumahan muslim. Ada semacam eksklusi, pengeluaran non-muslim dari
ruang sosial. Apa ini cermin dari semakin intolerannya masyarakat Jogja sekarang?
24
PRANALA { Maret - April 2015 }
PEMERINTAH DAERAH MEMANG
KURANG PEKA. IMAJINASI
MEREKA SOAL HUBUNGAN
ANTAR KELOMPOK SANGAT
PRAGMATIS SAJA, TIDAK MEM
PERTIMBANGKAN VALUE ATAU
SPIRIT MENGELOLA KEBER
AGAMAN DIKAITKAN DENGAN
PRAKTIK KEBIJAKAN.
Sebenarnya gejala eksklusif beberapa kelompok masyarakat di Yogyakarta sudah nampak lama. Baik itu
komunitas berbasis kesamaan agama, kesamaan kelas
orang kaya, kesamaan etnik dan sejenisnya. Nah, reproduksi hal semacam ini memang potensial konflik,
saat berinteraksi dengan kelompok lain jika diikuti rasa
saling curiga identitas.
Mengapa pemerintah daerah seolah-olah
tidak menyadari dan membiarkan masalah
ini? Melalui dinas perizinan dan badan penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu, misalnya. Mengapa proses perizinannya tidak dipersulit?
Pemerintah daerah memang kurang peka. Imajinasi mereka soal hubungan antar kelompok sangat pragmatis
saja, tidak mempertimbangkan value atau spirit mengelola keberagaman dikaitkan dengan praktik kebijakan.
Dalam hal informalitas, pemerintah mungkin peduli soal
pluralitas, namun urusan kebijakan kadang mereka tidak menyadari bahwa kebijakannya itu menjadi pintu
terbentuknya sekat-sekat eksklusif.
Atau dalam beberapa hal sadar soal itu, tetapi lebih
sadar kepentingan pragmatis ekonomi politik saja. Ini
perlu menjadi bahan refleksi pemerintah dan masyarakatnya saat ini dan jangka panjang. Kalau soal perijinan
itu instrumen. Tentu hanya mengikuti ideologinya apa.
Perumahan-perumahan muslim menimbulkan dampak. Bukan hanya pada persoalan
toleransi dan keberagaman, melainkan juga
dampak lingkungan, seperti pembangunan
mal, hotel dan apartemen yang belakangan dipersoalkan publik. Menurut Anda,
bagaimana seharusnya pemerintah daerah
bersikap?
Sebenarnya kalau soal maraknya kehadiran mal dan
apartemen mewah di Yogyakarta itu memang bentuk
keserakahan kapitalisme. Itu juga merupakan ekspansi
modal yang menguasai arena kebijakan tata ruang kabupaten, kota, juga provinsi. Jadi nggak perlu dan nggak
ada kaitannya dengan urusan sentimen yang berasal dari
agama. Jangan salah kaprah.
Intinya, kapitalisme di Yogyakarta berbentuk pembangunan mal dan apartemen makin merusak kohesi
sosial dan tata ruang Yogyakarta. Selain memiskinkan,
juga membuat potensi konflik stuktural kian membesar.
Yogyakarta menyimpan bom waktu soal pembangunan yang makin tidak ramah lingkungan dan mengancam
keadilan sosial jika dibiarkan berlarut-larut soal tata
ruang. Mulai marginalisasi, kemacetan, polusi, dan ketimpangan yang dialaminya. Sementara itu, kalau soal
watak eksklusif terkait sentimen agama dan etnik juga
masalah tersendiri yang memprihatinkan. Ironi jika daerah istimewa justru menghadapi masalah soal relasi
perbedaan antar kelompok.
warganya sesuai konstitusi. Sebagai daerah istimewa,
memang Sultan sebagai pemimpin masyarakat Yogyakarta menjadi ikon tokoh yang menjaga itu.
Namun ingat, itu tugas negara dengan alat-alatnya
agar bisa memastikan warga negara tidak diintimidasi,
tidak direpresi, serta tidak ada diskriminasi oleh kelompok manapun. Kita memang masih berharap Sultan sebagai simbol yang bisa menjaga pluralitas sebagai
identitas keistimewaan dengan baik, sekalipun sekarang
kian menyusut kecenderungannya.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana membangkitkan emansipasi warga dan pemimpin komunitas sebagai pilar-pilar penting. Ini untuk mengatasi
potensi anarkisme dengan berbagai strategi. Baik wacana, edukasi dan tindakan praksis kemanusiaan yang
mencerminkan Yogkarta benar-benar istimewa terkait
konteks kerukunan dalam perbedaan.
Ricklefs dalam penelitiannya yang terakhir
mengemukakan bahwa pasca reformasi,
Jawa semakin “hijau”. Semakin terislamkan. Bahkan kata dia, tidak ada penentangan
yang signifikan terhadap semakin mengentalnya proses islamisasi ini? Anda setuju?
Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Konsep keislaman itu secara kontekstual terbuka di Indonesia, termasuk
masyarakat Jawa juga Islamnya plural. Sekalipun ada
gejala pengentalan kelompok tertentu yang berhaluan
keras dalam Islam, toh hal itu tidak mainstream. Struktur dan kultur masyarakat Jawa tidak memungkinkan
menyuburkan garis keras dalam agama. Bahkan harus
dicatat, sikap kritis banyak dan kuat bermunculan dari
golongan Islam moderat dan Islam kultural dalam merespon gejala sektarianisme kelompok keras.
Di Jogja, banyak sekali tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok
tertentu. Keberadaan Sultan sebagai tokoh
masyarakat kemudian dipertanyakan. Bagaimana pandangan Anda?
Sebenarnya semua pemimpin formal sebagai representasi negara seperti gubernur, bupati dan walikota beserta aparatnya, harus bertanggung jawab melindungi
PRANALA { Maret - April 2015 }
25
Resonansi
POLITIK IDENTITAS
DAN MASA DEPAN
PLURALISME
INDONESIA
Orasi Ilmiah pada Nurcholis Majied Memorial Lecture III (NMML III)
Judul Orasi “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme di Indonesia”.
Source Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H2FvFQbPHqc
Oleh: Ahmad Syafii Maarif
D
ilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru
tertarik kepada isu politik identitas pada 1970an. Bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas,
dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa
terpinggirkan, merasa teraniaya. Dalam perkembangan
selanjutnya, cakupan politik identitas ini meluas kepada
masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural
yang beragam.
Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan
masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingankepentingan lokal, yang diwakili pada umumnya oleh
para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan
pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu
wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan
dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam
wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati
atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal
untuk tampil sebagai pemimpin? Ini merupakan masalah
yang tidak selalu mudah dijelaskan.
Pertanyaannya kemudian adalah; apakah politik identitas ini akan membahayakan posisi nasionalisme dan
pluralisme Indonesia di masa depan? Jika berbahaya,
26
PRANALA { Maret - April 2015 }
kira-kira dalam bentuk apa, dan bagaimana cara mengatasinya? Makalah ini akan mendiskusikannya lebih
jauh. Tetapi sebelum pembicaraan menukik kepada
permasalahan yang muncul di negeri kita, sebagai bahan perbandingan yang cukup relevan dengan situasi
Indonesia, kita juga akan melihat berbagai tipe politik
identitas di berbagai tempat dan di kalangan diaspora
muslim di Barat.
Adalah L.A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan
hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (The Student Nonviolent Coordinating
Committee). Sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di
Amerika Serikat di awal 1960-an. Siapa sebenarnya yang
menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali
masih kabur sampai hari ini. Tetapi secara substantif,
politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggotaanggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas
dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah
bangsa atau negara.
Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi
sangat relevan. Di Amerika Serikat, para penggagas teori
politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasanlah
yang membangun kesadaran golongan yang diperas.
Khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang
berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa
terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal, yang umumnya dikuasai golongan
kulit putih tertentu.
Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme
di Indonesia
Setelah kita menyoroti tipe-tipe politik identitas di
negara-negara lain, tibalah saatnya kita turun ke nusantara untuk mencoba meneropong isu serupa. Ini didasarkan pada pengalaman sejarah dalam rentang waktu
100 tahun terakhir. Dengan uraian ini, nanti saya ingin
mengukuhkan posisi intelektual Profesor Nurcholish
Madjid dalam kaitannya dengan gagasan besarnya tentang Pancasila yang mungkin dapat diangkat menjadi
kalimatun sawâ’ (prinsip/pegangan/proposisi dasar bersama) bagi Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa depan.
Dengan Pancasila yang dipahami dan dilaksanakan
secara jujur dan bertanggungjawab, semua kecenderungan politik identitas negatif-destruktif yang dapat meruntuhkan bangunan bangsa dan negara ini pasti dapat
dicegah. Pluralisme etnis, bahasa lokal, agama, dan latar
belakang sejarah, kita jadikan sebagai mozaik kultural
yang sangat kaya, demi terciptanya sebuah taman sari
Indonesia yang memberi keamanan dan kenyamanan
bagi siapa saja yang menghirup udara di nusantara ini.
Secara historis, pembentukan Indonesia sebagai
bangsa baru terjadi tahun 1920-an, dilakukan melalui
kegiatan intensif Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, kemudian dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda 1928.
Semua peristiwa penting ini terjadi di zaman kolonial
periode akhir. Selanjutnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah negara baru yang juga bernama Indonesia, muncul ke atas peta dunia, sekalipun Belanda
dibantu Inggris sama sekali tidak rela dengan cetusan
kemerdekaan rakyat terjajah ini. Seperti sudah disinggung di atas, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa saja tertunda sekiranya PD II tidak meledak.
Belanda sebagai penjajah memang tidak pernah siap
untuk melihat sebuah kemerdekaan bagi nusantara yang
sebagaian wilayahnya sudah cukup lama dikuasainya.
Indonesia adalah negara kepulauan yang terluas di
muka bumi. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000, etnisitas, sub-kultur, dan bahasa lokalnya ratusan. Bahkan di
Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan
bahasa khasnya masing-masing. Dari sisi keragaman
budaya (pluralisme) ini saja, jika Indonesia bisa bertahan
dalam tempo lama, maka menurut saya adalah mukjizat
sejarah yang bernilai sangat tinggi.
Oleh sebab itu, apa yang bernama politik identitas
yang sering muncul ke permukaan sejarah modern Indonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh
nalar historis yang dipahami secara benar dan cerdas.
Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 70 juta. Sekarang di awal abad ke-21 sudah menjadi
sekitar 235 juta, membengkak lebih tiga kali lipat sejak
1945, telah muncul sebagai bangsa terbesar keempat di
dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat.
Modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa
itu sudah kita miliki, yaitu; pengalaman sejarah berupa
pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, Pancasila,
dan adanya tekat bulat untuk mempertahankan dan
membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah
gerakan sosial keagamaan, ada Muhammadiyah dan NU,
dua sayap besar umat Islam, yang telah mengukuhkan
dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di
Indonesia. Sekalipun sering digerogoti oleh kelakuan
politisi salah tingkah dalam berbagai periode sejarah
pasca proklamasi, toh, sudah lebih enam dasawarsa, Indonesia masih bertahan dengan segala keberuntungan
dan malapetaka yang dialaminya.
Tantangan lain yang cukup serius terhadap keutuhan
bangsa datang dari berbagai gerakan sempalan agama
dengan politik indentitasnya masing-masing. Mereka ini
semua anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan anti-pluralisme. Bentuk ekstrem dari gerakan sempalan ini yang
sering melakukan bom bunuh diri di Indonesia punya
akar transnasional pada al-Qaedah dengan tokoh utamanya Osama bin Laden (Saudi) dan Ayman al-Zawahiri
(Mesir). Indonesia sangat terganggu oleh perilaku nekat
bom bunuh diri ini. Peran Densus 88 yang pada akhirnya
bisa menghabisi beberapa tokoh puncak bom bunuh diri
ini, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top (keduanya
PRANALA { Maret - April 2015 }
27
Resonansi
warga Malaysia), dan beberapa pengikutnya warga Indonesia, patut diberi apresiasi yang tinggi.
Di atas sudah dikatakan bahwa politik identitas di
Indonesia lebih bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi
politik. Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), dan Gerakan Papua Merdeka (GPM),
sebagai misal, adalah perwujudan dari kegelisahan etnis-etnis ini terhadap politik sentralistik Jakarta yang
dirasa sangat tidak adil, khususnya bagi Aceh dan Papua. Gerakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat, Aceh, dan
Sulawesi Selatan, menggunakan agama sebagai payung
ideologi politik identitas mereka. Kecuali GPM yang
masih seperti api dalam sekam sampai hari ini, gerakangerakan politik identitas lain seperti tersebut di atas,
relatif telah dapat diatasi melalui kekerasan senjata atau
diplomasi persuasif.
Selain itu, masih di era pasca-proklamasi, Indonesia
juga pernah diancam oleh Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Pemberontakan PRRI/Permesta di akhir
1950-an dan awal 1960-an. PKI menggunakan ideologi
Marxisme sebagai politik identitasnya, sedangkan PRRI/
Permesta lebih merupakan gerakan protes terhadap politik Presiden Sukarno yang dinilai telah melanggar UUD
1950 dan sikap pro-PKI yang dirasakan pada periode itu.
Untuk Pemberontakan G30S 1965, politik identitas apa
yang memicunya, masih kontroversial sampai hari ini.
Pemerintahan Soeharto, yang didukung oleh pendapat beberapa penulis domestik dan asing, mengatakan
bahwa PKI-lah sebagai otak utama tragedi itu. Penulispenulis kiri berpendapat sebaliknya. Jika pun ada unsur
PKI terlibat, partai ini hanyalah terseret arus oleh persaingan dalam tubuh Angkatan Darat (AD). Sedangkan di
mana posisi Presiden Sukarno dalam tragedi itu, masih
perlu dikaji lebih jauh. Karena masalah ini sudah banyak
dikupas oleh berbagai kalangan, sekalipun belum juga
tuntas, saya tidak ingin untuk saat ini berbicara banyak
tentang peristiwa berdarah yang terjadi di kalangan sesama anak bangsa ini.
Sekarang saya beralih kepada realitas politik Indonesia kontemporer. Yang menjadi burning issues dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak 11 tahun
terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau
28
PRANALA { Maret - April 2015 }
setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Sebagaimana partner mereka di bagian dunia lain, gerakangerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan
sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme.
Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan
pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula
berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian
dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh jagat.
Untungnya di Indonesia, sebagian besar masjid masih
di bawah pengawalan Muhammadiyah dan NU, sekalipun ada beberapa yang terinfiltrasi oleh virus ideologi
serba radikal itu.
Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari
berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama; pelaksanaan Syariah Islam
dalam kehidupan bernegara. Faksi-faksi yang ingin
kita bicarakan di sini ialah Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI), Front Pembela Islam (FPI) , dan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI). Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), yang sesungguhnya adalah partai Islamis yang
sangat dipengaruhi oleh cita-cita al-Ikhwan al-Muslimun (Persaudaraan Muslim), bentukan Hassan alBanna tahun 1928 di Mesir, menempuh jalan demokrasi
untuk mencapai tujuannya.
Apakah cara-cara demokrasi itu sebagai taktik PKS
sebelum menjadi kekuatan politik besar atau memang
telah menerima demokrasi sebagai sebuah sistem politik,
belum dapat dikatakan sekarang. Kita akan kembali lagi
ke PKS ini pada bagian akhir makalah ini. Tetapi satu
hal yang pasti adalah bahwa semua gerakan Islam yang
sedang kita sorot ini telah menjadikan Islam sebagai
politik identitas mereka. Bedanya adalah MMI, FPI, dan
HTI, tidak menyebut diri sebagai gerakan politik, sekalipun melakukan fungsi politik, sedangkan PKS jelas-jelas
sebuah partai politik dan sekaligus partai dakwah.
Kita bicarakan sekadarnya tentang MMI, FPI, dan
HTI. Sebenarnya literatur sudah tersedia yang membahas faksi-faksi Islam radikal ini. Seperti sudah dikatakan,
semua faksi ini bersikeras untuk pelaksanaan syariah
dalam kehidupan bernegara. MMI misalnya sangat
menyesalkan tersingkirnya Piagam Jakarta, khususnya
pencoretan tujuh kata dari sila pertama Pancasila yang
berbunyi ”dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” pada 18 Agustus 1945 atas
prakarsa Hatta. Bagi MMI, penolakan arus besar umat
Islam Indonesia terhadap pelaksanaan syariah secara
konstitusional dengan sendirinya dapat masuk dalam
kategori ”kafir, fasiq, dan zalim.”
Berikutnya, kita lihat FPI yang didirikan 17 Agustus
1998 di Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kyai. Tentang latar belakang kelahirannya, dikatakan bahwa umat Islam telah
lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku
di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan
Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat
keadilan. Tetapi ada sebuah ironi di sini. Tersiar berita
bahwa ada oknum tentara hadir dalam pertemuan itu,
bahkan memberikan bantuan dana dan latihan militer.
Apa artinya ini? Tidak lain; oknum militer sedang
main api yang dapat membakar Indonesia untuk jangka panjang. Sekiranya kelompok-kelompok radikal ini
dibiarkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan
atas nama agama, seperti yang dilakukan atas gereja,
Ahmadiyah, dan lain-lain, sementara aparat tidak mencegah perbuatan kriminal mereka. Bagi FPI, segala tindakan kekerasan itu dinilai sebagai bagian dari prinsip
nahi munkar (mencegah kemungkaran). Yang biadab adalah bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan dengan
cara-cara yang munkar oleh aparat swasta.
Kemudian kita lihat selintas HTI. Berbeda dengan
MMI dan FPI yang bercorak lokal Indonesia, HTI adalah
gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas
antara lain oleh Taqiyuddin al-Nabhani, sempalan dari
Ikhwan. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah
terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh
dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI,
khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan
dengan kehendak Syariah.
Salah seorang tokoh HTI, M. Shiddiq al-Jawi, dalam
sebuah diskusi buku di Padepokan Musa Asyarie (PADMA) Yogyakarta beberap waktu yang lalu, dengan nada
optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri tahun 2020. Tidak dijelaskan
bagaimana semuanya itu akan terjadi. Tokoh HTI yang
lain, Farid Wadjdi, ketika menyoroti demokrasi dengan
prinsip ke daulatan rakyatnya, tegas-tegas mengatakan
bahwa demokrasi itu sistem kufur.
Menurut HTI, kekhilafahan juga sebagai realisasi
negara syariah. Oleh sebab itu, formalisasi syari’ah harus dilakukan oleh negara. Sedangkan dalam sebuah
negara-bangsa, seperti Indonesia, cita-cita ke arah realisasi syari’ah menjadi tidak mungkin. Dalam perspektif
ini, bagi HTI, konsep-negara bangsa itu tidak lain hasil
rekayasa penjajah yang kafir.
Kesimpulan kita tentang HTI. Sekalipun diembeli
dengan perkataan Indonesia, organisasi ini jelas bercorak
transnasional, di mana bangunan negara-negara bangsa
harus dilebur. Bukankah angan-angan semacam ini tidak
lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari
kenyataan? Tetapi kritik HTI terhadap praktik demokrasi di berbagai tempat, bukan substansinya yang menempatkan setiap warga pada posisi yang setara dalam
sebuah negara, mengandung beberapa unsur kebenaran.
Pertanyaan saya adalah; mengapa HTI menutup mata
terhadap praktik busuk ”kekhilafahan” yang dipaksakan
PRANALA { Maret - April 2015 }
29
Resonansi
PANCASILA SEBAGAI DASAR
FILOSOFI NEGARA TIDAK
DIBIARKAN TERGANTUNG DI
AWANG-AWANG, TETAPI DI
HAYATI DAN DILAKSANAKAN
DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH
DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.
dalam berbagai periode sejarah Muslim? Bukankah sistem khilafah selama berabad-abad telah membunuh
prinsip egalitarian yang diakui dalam demokrasi, yang
begitu tegas dinyatakan dalam al-Qur’an? Pandangan
yang ahistoris semacam inilah yang mengkhawatirkan
saya; bahwa HTI berangan-angan menciptakan sebuah
”imperialisme agama” pada skala global, yang menurut
Shiddiq al-Jawi akan menjadi kenyataan pada tahun
2020. Tinggal 11 tahun lagi dari sekarang.
Kelompok-kelompok radikal ini, dengan kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai
faksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi
termasuk dalam kategori mazhab Zha hiriyyah baru
dengan enam ciri yang menonjol; pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong
terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan
pendapat, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat
dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah. Kita
turunkan salah satu ciri saja, yaitu mudah mengkafirkan
orang yang berbeda pendapat.
Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang
berlainan pendirian ini menyebar, maka sudah bisa
dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin
buyarnya suasana persaudaraan muslim yang memang
sudah lama rusak. Dengan kata lain, ”Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu; menghancurkan peradaban dengan memakai
lensa kacamata kuda!”
Akhirnya untuk menutup bagian ini, kita kembali
kepada PKS. Dalam dokumen resmi partai disebutkan
bahwa PKS tidak menolak demokrasi, pluralisme, dan
nasionalisme Indonesia. Bahkan, menurut dokumen itu,
dengan berpedoman kepada Piagam Madinah, PKS menerima kenyataan pluralitas agama dalam masyarakat
30
PRANALA { Maret - April 2015 }
Indonesia. Lalu untuk meredam pengaruh gerakan radikalisme Islam, umat Islam perlu memiliki gerakan Islam
politik dalam sistem demokrasi. Tentu yang dimaksud
dengan gerakan Islam di sini adalah PKS sendiri. Sekalipun belum ada kupasan yang agak mendalam tentang
pluralisme dan nasionalisme, PKS secara tertulis menerima kedua prinsip itu.
Persoalannya kemudian adalah; apakah penerimaan
ini sebagai siasat politik sementara atau memang PKS
telah menyesuaikan perjuangannya dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia? Jawabannya tidak mungkin diberikan sekarang. Kita masih harus menunggu
sampai suatu ketika sekiranya PKS pegang kekuasaan
dan telah membesar. Bila partai ini konsisten dengan
apa yang dikatakan dalam dokumen resminya, maka
corak Islamis yang menjadi ciri utama Gerakan Ikhwan
di negara-negara Arab dan di negara-negara lain telah
mengalami perubahan orientasi mendasar di tangan PKS.
Yang dimaksud dengan corak Islamis ialah suatu
cita-cita politik untuk melaksanakan Syariat Islam
dalam sistem kenegaraan dengan mencantumkannya
dalam konstitusi sebuah negara. Dengan kata lain, terciptanya sebuah negara Islam atau negara berdasarkan
Islam, sebagaimana yang dulu pernah diperjuangkan
oleh kekuatan politik Islam dalam Majelis Konstituante
(1956-1959) di Indonesia. Posisi PKS belum terlalu jelas,
apakah sudah menerima Pancasila sebagai sesuatu yang
sudah final atau masih berfikir untuk alternatif yang lain.
Akhirnya
Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan
membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa
depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda
yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila
sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung
di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang sering benar
dipermainkan oleh orang yang larut dalam pragmatisme
politik yang tuna-moral dan tuna-visi. Sikap semacam
inilah yang menjadi musuh terbesar bagi Indonesia, dulu,
sekarang, dan di masa datang.
Tagar
Netizen
Pertanyakan Toleransi
di Yogyakarta
Oleh: Kamil Alfi Arifin
Para netizen menggugat dan mempertanyakan toleransi
di Yogyakarta. Ini seiring dengan banyaknya tindakantindakan anarkis yang terjadi.
Mereka juga memandang perlu adanya ruang publik yang
lebih bisa menghormati perbedaan.
Dalam beberapa tahun belakangan, toleransi di Yogyakarta mulai digugat dan dipertanyakan oleh publik. Saat tindakan-tindakan
anarkis dan intoleran semakin marak terjadi
dan berulang-ulang, sebutan “City of Tolerance” untuk kota ini hanya dianggap sebagai
mitos. Bisa dianggap ini sebagai sekadar
slogan kosong yang semakin menjauh dari
realitasnya.
Begitu mudah menyebut banyaknya tindakan anarkis dan intoleran tersebut. Sebut saja
misal beberapa di antaranya; pembubaran
diskusi bersama Irshad Manji yang diadakan
LkiS, penyerangan terhadap Julius Felicianus,
pembubaran diskusi dan seminar tentang
gay di kampus Sanata Dharma, pembubaran
paksa nonton bareng film Senyap dan masih
banyak yang lainnya. Atas tindakan-tindakan
kekerasan itu, publik kecewa dan mempersoalkan toleransi di Yogyakarta. Ini juga terjadi di
dunia sosial media.
“Kemana perginya toleransi?? ,”
tulis Yuviana Lestari di twitternya
denganakun @uv_ana saat merespon
kasus penyerangan pada Julius Felicianus
beberapa waktu lalu, sambil membagikan
tautan berita Kompas yang berisi sikap
Komnas HAM yang mengecam
para pelaku biadab itu.
Senada dengan Yuviana, salah seorang
netizen lain, Astri Kusumawardani dengan
akun @astricyrene, juga mempertanyakan
hal yang serupa. “Kenapa di Jogja jadi
banyak kekerasan… kenapa kekerasan di
Jogja makin banyak..toleransi hilang dan
orang-orang semena-mena,” keluhnya.
Ancaman terhadap toleransi memang
sedang menguat di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Hal itu diteguhkan
oleh sebuah LSM Inggris, Christian Solidarity
Worldview (CSW) belum lama ini. Menurut
lembaga tersebut, seperti dilansir media online
KBR, pluralisme dan toleransi di Indonesia
sedang berada dalam ancaman serius. Dalam
laporan CSW tahun 2014, setidaknya terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan mengapa
pluralisme dan toleransi berada dalam bahaya
dan tindakan-tindakan anarkis yang intoleran
meningkat cukup signifikan.
Pertama, penyebaran ideologi ekstrimis
melalui pendidikan, ceramah dan penyebaran
literatur, penerbitan pamflet dan buku-buku,
DVD, dan CD, melalui internet.
Kedua, kasus intoleransi juga dipicu penerapan undang-undang dan peraturan yang
PRANALA { Maret - April 2015 }
31
diskriminatif. Hal ini diperparah dengan
lemahnya penegakan hukum oleh polisi dan
pengadilan.
Ketiga, ketidakmampuan mayoritas Islam di Indonesia untuk menolak intoleransi.
Dalam konteks di Yogyakarta, netizen makin
sedih. Terutama saat menyadari jika Yogyakarta saja yang selama ini dijadikan parameter
dan rujukan bagi kota-kota lain dalam mengembangkan masyarakat yang multikultur
dan toleran, tak terhindarkan dari adanya
ancaman tindakan-tindakan anarkis. Pertanyaannya, bagaimana dengan kota-kota yang
lain, yang memang dikenal sebagai kota yang
eksklusif dan tak terbuka?
Seorang netizen dengan akun @Okky
Soetanto meratap, “Oh Jogja kenapa seperti
ini…di daerah yang toleransi kuat…masih
saja ada aksi intoleransi,” ujarnya.
Tindakan-tindakan anarkis dan intoleran di
Yogyakarta tersebut, oleh sebagian kalangan,
dipandang tidak melulu merupakan masalah
teologis, apalagi dipersempit dan dilokalisir
sebagai konflik islam dengan agama lain.
Melainkan kadang, kata mereka, problemnya
adalah masalah sosiologis. Sebuah lembaga
studi yang bergiat dalam persoalan pluralisme
dan multikulturalisme di Yogyakarta (Impulse),
dalam status facebooknya menegaskan hal itu.
Lembaga itu merespon kasus penyerangan jamaat yang sedang berdoa rosario. Penyerangan yang dilakukan oleh ormas tertentu.
“Massa yang mengenakan atribut
mirip anggota Front Pembela Islam (FPI),
menyerang sekelompok jemaat yang
sedang berdoa rosario. Penyerangan ini,
seakan merupakan konflik dua agama;
Kristen vs Islam. Tapi hati-hati, anggapan
seperti itu terlalu simplistis. Serangan yang
memang marak terjadi oleh kalangan
mengatasnamakan ormas Islam, bukanlah
perang teologi. Hal itu sebab utamanya,
karena perebutan lahan semata. Artinya,
konflik berada pada ranah sosiologis,
bukan teologis,” tulisnya.
32
PRANALA { Maret - April 2015 }
Dalam status facebooknya yang lain, Impulse Jogja juga menegaskan perlunya membangun dialog antar etnis dan antar agama
untuk meminimalisir tindakan-tindakan anarkistis. Upaya membangun dialog lintas iman
dan kesukuan ini, harus mutlak dibarengi juga
dengan dibangunnya ruang-ruang publik yang
bisa diakses oleh semua pihak.
“Tampaknya di Yogya yang toleran ini
tidak punya ruang publik, yang gratis,
dan mampu diakses oleh semua publik
di Yogyakarta,” kritiknya.
Impulse menegaskan bahwa persoalan
intoleransi tidak harus selalu menyangkut
persoalan agama, melainkan masalah “keruangan” di Yogyakarta. Di jalan raya, misalnya,
orang biasa berebut satu sama lain, saling
sikut dan bahkan misuh-misuh. Hal ini merupakan sebuah potret sikap intoleransi masyarakat
Yogyakarta di jalan raya. Yogyakarta sudah
mengalami banyak perubahan, terutama perubahan demografi penduduknya.
Seorang antropolog, Agus Indianto, dalam
sebuah diskusi bertajuk “Perubahan Demografi
Masyarakat Terhadap Dinamika Perbedaan di
Yogyakarta”, yang diadakan di kampus UKDW
oleh sebuah lembaga lintas agama, Interfidei,
juga memandang urgennya Yogyakarta memiliki ruang publik untuk mengurangi konflik
perbedaan. Menurutnya, perubahan demografi
penduduk di Yogyakarta menimbulkan masalah-masalah serius yang mesti disikapi dengan
serius pula.
“Perubahan penduduk di Jogja
menimbulkan 3 potensi: konflik
keruangan, hilangnya ruang sosial,
intoleransi. Jogja perlu ruang simbolik
untuk orang saling berbicara dengan
bahasa yang sama agar terjadi
interaksi, saling memahami,” ujar
Indianto, seperti dikutip oleh akun
@Dian_Interfidei di twitternya.
Resensi
JALAN RAYA;
SEBUAH JALAN
MENUJU TOLERANSI?
Oleh: Ahmad Alwajih
Mahasiswa Program Magister Ilmu
Komunikasi Universitas Gadjah
Mada (UGM)
Berbicara mengenai toleransi, sebenarnya tidak
melulu gagasan besar yang hanya bisa dijumpai di
puncak menara gading ilmu pengetahuan.
Ia adalah “ruang” nyata dan tertangkap panca
indera tanpa kita sadari.
Ruang itu bernama “jalan raya”.
Tengoklah Jalan Kaliurang, Yogyakarta Pada
jam-jam berangkat-pulang kerja, hampir seluruh
Judul Buku
Penulis
Penerbit
Cetakan
Tebal
: Negara di Persimpangan Jalan Kampusku
: Hani Raihana
: Kanisius
: Kelima, Tahun 2011
: 158 Halaman
ruas jalanan kota macet oleh kendaraan bermotor. Hingar-bingar bunyi klakson, entah marah
atau tergesa, memaksa mereka yang ada di depan
untuk menyingkir secepatnya. Hampir semua
kendaraan bermotor melakukan hal yang sama.
Belum lagi bicara tentang semakin sesaknya
dada akibat polusi dari knalpot kendaraan bermotor.
Kesemua itu adalah fragmen pemandangan yang kini
seakan lumrah dalam siklus keseharian warga Yogyakarta. Seiring bertambahnya waktu, pemandangan ini
semakin memadati kedua mata kita. Dan bagaimana
dengan nasib pesepeda dan pejalan kaki?
PRANALA { Maret - April 2015 }
33
Resensi
Meski usia terbitnya buku ini sudah usang, yakni
di tahun 2007 silam, tetapi agaknya fragmen kehidupan di Jalan Kaliurang tersebut masih pantas disimak.
Isu dalam buku Hani Raihana ini masih hangat untuk
diperbincangkan. “Negara di Persimpangan Jalan Menuju Kampusku” adalah sebuah upaya merefleksikan
gagasan tentang jalan, di luar makna ia hanya sekedar
menjadi bagian dari prasarana transportasi.
Benar apabila ada yang mengatakan jalan adalah
tempat kendaraan berlalu-lalang. Namun, kesimpulan
ini terlalu tergesa-gesa dan teramat reduktif. Sebab,
jalan di sisi yang lain adalah ruang penuh makna juga.
Seperti diungkapkan Marco Kusuma Wijaya dalam
sekapur sirih buku ini, jalan memiliki banyak arti seperti “jalan kebenaran”, “jalan simpang”, “jalan buntu”,
dan “jalan terbuka.”
Oleh karena tidak bisa direduksi semata prasana
angkutan itulah, maka jalan seharusnya bisa menjadi
ruang publik. Ia tempat bertemunya berupa-rupa
gagasan. Di sini satu isu menarik yang hendak dibidik
adalah garis penghubung antara jalan, negara, dan
toleransi para penggunanya. Sementara konteks yang
dipilih adalah Yogyakarta, terkenal akan kota para
pesepeda dan predikatnya sebagai “city of tolerance”.
Minimnya Toleransi Sesama
Pengguna Jalan
Pada bagian-bagian awal pembahasan, Hani menyeret
ingatan kita ke kondisi jalan Yogyakarta di masa lalu.
Dulu, ketika jalan belum diramaikan oleh kendaraan bermotor, orang masih bisa saling bertemu sapa sekaligus
berbagi informasi. Gambaran ini tampak pada momen
ketika sepeda masih mendominasi jalan di Yogyakarta.
Para pekerja berangkat beriringan dari Bantul dan berpencar di Gondomanan ke tempat kerja masing-masing,
lalu bertemu kembali di persimpangan saat sore, saling
bersisian, bercanda, dan berkeluh kesah.
Jika dilihat secara historis, asal muasal konsep
tentang jalan sebenarnya sudah dibangun sejak
kolonial, yang membuka jalan fisik dari Anyer
34
PRANALA { Maret - April 2015 }
sampai Panarukan. Logika yang dipakai tentunya
pertimbangan ekonomi-politik eksploitatif kolonial.
Tidak hanya memakan korban, tetapi juga ada yang
tertinggal sejak proses itu dimulai, yaitu edukasi.
Pembangunan fasilitas fisik ternyata tidak berimbang
dengan penyiapan-penyiapan mental yang mendidik
para manusianya untuk menggunakan jalan.
Itulah kenapa masih kerap dijumpai tidak hanya
pelanggaran lalu lintas, tetapi juga arogansi dari
masing-masing pengguna jalan. Celakanya, kondisi ini
kerap tidak disadari (atau diabaikan?) oleh pemerintah sebagai pihak pemegang otoritas jalan, sehingga
logika pembangunan fisik masih menjadi tolok ukur
kemajuan suatu daerah. Maka kesemrawutan di jalan
adalah wajah pemerintah juga.
Di sinilah Hani memaknai jalan sebagai ranah perjuangan, tempat bagi individu dan modal berinteraksi
UNTUK MEREDAKAN GEJOLA
SUDAH ADA BEBERAPA SOLUS
PELEBARAN JALAN DI BEBE
JUAN UNTUK MENGURANGI K
INI CENDERUNG PROBLEMA
PULA OLEH PENGENDALIAN
TOR DI JALAN YANG
dan berjuang hingga menentukan posisi. Sepeda
memiliki modal kebal dari peraturan lalu lintas, motor
dengan kegesitan dan iritnya, dan mobil dengan segala
kenyamanannya. Mobil memberi ruang kepada motor,
motor memberi ruang kepada sepeda, dan seterusnya,
sampai pemberian ruang kepada pejalan kaki.
Faktanya, para pengguna jalan ini justru menganggap jalan itu arena perebutan ruang. Sepeda wajib
mengalah kepada motor, motor harus memberi jalan
pada mobil, dan mobil dengan segala modal yang
dimilikinya menjadi penguasa tunggal jalanan. Maka,
mereka ini diibaratkan para pelaku yang sadar tentang aturan main, tetapi menghendaki ruang untuk
dapat eksis, bahkan kalau bisa menguasainya. Lalu
dimanakah makna “city of tolerance”?
Toleransi bukan semata soal penerimaan akan
agama, budaya, atau etnis yang berbeda. Dari kondisi
di jalan, kita akan tahu bahwa toleransi juga persoalan
kenyataan sehari-hari yang lekat dengan saling kelindan sosial-ekonomi-budaya-politik. Di jalan, toleransi
adalah dengan memberi ruang pada pengguna jalan
lain untuk hidup berdampingan berdasarkan nilai dan
tujuan bersama, selayaknya bertetangga.
Lebih jauh lagi, carut-marutnya kondisi lalu lintas
di Yogyakarta bisa dilihat sebagai cermin tentang
kondisi umat beragama. Jangan-jangan selama ini
agama hanyalah simbol idelogis belaka dan belum
menyentuh hakikat kehidupan pemeluknya? Janganjangan inilah wajah toleransi dan multikulturalisme
yang selama ini diidealkan, tak mau tahu, hipokrit,
dan sikap kesemau-gue-an, antara satu individu dengan
yang lain? (hal:132-134)
AK DI JALAN, SEBENARNYA
SI YANG LUMAYAN. SEMISAL,
ERAPA TEMPAT YANG BERTU
KEMACETAN. NAMUN, SOLUSI
ATIS KARENA TAK DIIKUTI
JUMLAH KENDARAAN BERMO
SEMAKIN BERTAMBAH.
Tentu ironis. Jangankan memberi ruang, bahkan
di jalan, kita seakan sudah tak mampu lagi berdialog.
Komunikasi antar pengguna jalan hanyalah bersifat
simbolik belaka. Antara lain terwujud dari nyalak bunyi klakson, lampu-lampu sein, dan sesekali umpatan.
Bagaimana dengan Pengguna Jalan yang Lain?
Jika dicermati lebih teliti, sebenarnya pengguna
jalan tidak sebatas pada pengendara motor, mobil, pesepeda, maupun pejalan kaki. Di sana masih dijumpai
para pedagang kaki lima, warung-warung, pengamen,
polisi, tukang parkir, sampai yang kerap terpinggirkan selain pesepeda adalah kaum difabel.
Namun, kita tak boleh melupakan, bahwa jalan
tak hanya sesak oleh manusia, tetapi juga simbolsimbol kapitalisme, yang kesemuanya seakan berebut
perhatian dari para pengguna jalan. Jalan akhirnya
menjadi arena kontestasi simbol, dimana yang paling
banyak menyedot perhatianlah yang akan menang.
Akibat dari kurangnya kontrol terhadap logika ini,
maka ukuran papan reklame semakin bertambah dari
hari ke hari. Akhirnya kerap terdengar kabar tentang
papan reklame berukuran raksasa yang jatuh dan melukai para pengguna jalan ketika hujan disertai angin
kencang tengah melanda.
Ruang-ruang kota Yogyakarta disulap menjadi
roda penggerak ekonomi belaka karena adanya pergeseran dari masyarakat produktif menuju masyarakat yang semakin konsumtif. Dalam logika ini, jalan
kemudian dipandang sebatas penghubung kegiatan
kapitalisme. Bukan lagi sarana yang memprioritaskan
manusia atau memberi kesempatan pada interaksiinteraksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Mencari Titik Terang Dalam Konteks
Saat Ini
Sampai di titik ini, buku Hani tidak hanya mengajak
untuk kritis terhadap kondisi jalan. Namun memancing
sebuah pencarian solusi secara konkret. Ada dua isu
yang ditawarkan.
Pertama, solusi dari segi fisik. Untuk meredakan
gejolak di jalan, sebenarnya sudah ada beberapa solusi
yang lumayan. Semisal, pelebaran jalan di beberapa
tempat yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Namun, solusi ini cenderung problematis karena
tak diikuti pula oleh pengendalian jumlah kendaraan
bermotor di jalan yang semakin bertambah.
Maka, alternatif kedua, sebagaimana sering disinggung oleh Hani, adalah meng-upgrade dari segi nonfisik, sebutlah edukasi mentalitas pengguna jalan.
Tentu dibutuhkan studi-studi lanjutan yang mendalam. Harus ditemukan cara terbaik untuk menggugah
kesadaran para pengguna jalan, agar jalan tidak lagi
dilihat sebagai arena perebutan kuasa semata. Jalan
adalah ruang tempat bertemunya “dialog-dialog”
manis, agar antar pengguna jalan mau belajar bersikap
toleran terhadap sesamanya.
PRANALA { Maret - April 2015 }
35
Tindak Kekerasan
dalam Perspektif
Masyarakat Konsumtif
Oleh: Moh. Fathoni, M.A ( Direktur Karimata Institute )
Dewasa ini, konflik dan kekerasan cenderung sering terjadi. Terbukanya ruang publik,
kebebasan, dan terbentuknya organisasi masyarakat sipil tidak selalu berkorelasi dengan
tiadanya kekerasan. Sedangkan kampaye nir-kekerasan di Indonesia tampaknya belum
berhasil. Di pihak lain, kekerasan yang terorganisir menunjukkan kematangan dalam
logikanya sendiri. Tulisan ini akan membahas persoalan tindak kekerasan dari cara
pandang aktor kekerasan dalam rangka untuk memahami persoalan toleransi dan
kekerasan, dengan asumsi; 1) bahwa tindak kekerasan yang mereka lakukan rasional,
2) rasionalitas mereka sejajar dengan logika konsumen dalam perspektif masyarakat
konsumtif, dan 3) kedua hal tersebut mengandaikan adanya kondisi, dimana toleransi
sulit diwujudkan jika mengabaikan kondisi masyarakat konsumtif.
36
PRANALA { Maret - April 2015 }
Kekerasan Terorganisir
Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)
melaporkan jumlah korban akibat kekerasan selama
2014 di 34 provinsi, yakni sekurang-kurangnya 2.943
korban tewas dan 22.118 cedera dari 27.775 insiden
dan 26 persen adalah konflik.1 Jumlah ini sangat
memprihatinkan. Sebelumnya, pada 2012, Center for
Strategic and International Studies (CSIS) melakukan
survei yang menunjukkan bahwa pemeluk agama
tertentu tidak nyaman hidup berdampingan dengan
pemeluk agama lain.2 Belakangan di beberapa daerah
terjadi intimidasi dan intoleransi terhadap minoritas
atau pihak yang berbeda agama, kepentingan, dan
beragam perbedaan lainnya.
Dalam melakukan aksinya, aktor kekerasan tersebut
berorganisasi dan berafiliasi dengan kelompok tertentu
serta mengatasnamakan aksinya. Diantaranya, aktor
tersebut seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum
Ukhuwah Islamiyah (FUI), Gerakan Reformis Islam
(GARIS), Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI),
Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS),
Forum Anti-Komunis Indonesia (FAKI) dan lainnya.
Motif atau pesan yang diangkat oleh aktor kekerasan
tersebut adalah persoalan agama dan paham komunisme.
Persoalan tersebut tampak pada pernyataan, tanda dan
identitas yang sengaja dimunculkan, seperti muslim
sejati, Islam kaffah, anti-maksiat dan pemurtadan/ sesat,
atau yang terkini misalnya; masyarakat madani. Hal ini
menandakan bahwa terdapat pergeseran isu dan pesan
yang digunakan sesuai dengan kondisi tertentu.
Dalam aksinya organisasi-organisasi tersebut juga
secara progresif menyebarkan pesan intoleransi dan
kebencian yang berujung pada kekerasan terhadap
pihak yang tidak hanya minoritas, tapi juga pihak yang
sudah mereka tandai. Organisasi juga memiliki logika
dan moralitas sendiri sehingga tindakan yang dilakukan
bukan berarti irrasional dan tidak beralasan. Bahkan
organisasi tersebut juga memiliki akses, mendapat
sponsor, dan berpartner dengan pihak keamanan, FPI
misalnya.3 Ketika anggota organisasi ini ditangkap polisi
karena bertindak kekerasan, mereka hanya dituntut dan
dihukum ringan.4
Dengan demikian, insiden-insiden kekerasan tersebut
tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan logika
dan cara pandang, sensitifitas dan mentalitas, dan
moralitas sekelompok orang “menyerang” orang atau
pihak lain yang tidak hanya dianggapnya berbeda, tapi
juga yang sudah mereka jadikan sasaran atau target
tertentu, sehingga aksinya berhasil dan pesan yang
mereka usung sampai pada publik.
Organisasi yang mengatasnamakan “masyarakat
madani” dapat dikatakan mengusung pesan bahwa
“masyarakat madani” itu anti-demokrasi, atau “agama”
menolak demokrasi. Apa yang dilakukan organisasi
tersebut telah membentuk penafsiran “masyarakat
madani” dan “demokrasi”, sesuai dengan perspektif
mereka. Maka, secara tidak langsung mereka berhasil
mengacaukan dan memberi makna baru terhadap
“masyarakat madani” dan “demokrasi”, termasuk “agama
Islam” dan “Pancasila”.
Yang menarik lagi, bahwa aksi anti-Komunisme, antiAhmadiyah dan anti-Syiah dipandang sebagai sebuah
pesan. Sebuah tanda bahwa terdapat masyarakat yang
menentang paham komunisme dan aliran Islam tersebut
sehingga regulasi-regulasi yang legal dan fatwa atau
opini yang sejalan dengan penentangan tetap memiliki
relevansi dengan pekerjaan mereka.5
PRANALA { Maret - April 2015 }
37
Perspektif
Tindak Kekerasan Sebagai Pekerjaan
Keberhasilan dan relevansi tersebut bukan terjadi
karena kebetulan. Di atas disebutkan bahwa organisasi
ini memiliki relasi dengan pihak tertentu, termasuk
otoritas dan keamanan misalnya.6 Maka diasumsikan
bahwa mereka menjadi “pekerja” untuk mengerjakan
suatu “tugas” tertentu, atau yang jelas bahwa mereka
memiliki visi dan misi sendiri yang sejalan dengan
kepentingan tertentu. Mereka juga memiliki moralitas
atau etika baru, sehingga yang dilakukan merupakan
“sebagian dari perjuangan”.7
Dalam perkembangannya, organisasi ini menggunakan
isu dan pesan yang menjadi trend kekinian. Pada 2005,
setahun setelah bangkit yang sebelumnya sempat beku
(2002-2004), seorang anggota FPI mengatakan bahwa
nasionalisme dan kebangsaan sudah ketinggalan zaman,
kini anti-kemaksiatan atas nama Islam jauh lebih seksi.8
Maka, dapat dikatakan bahwa organisasi ini mengalami
pergeseran visi; dari bela bangsa ke persoalan simbolik,
tetapi cara bertindak mereka tetap konsisten, kecuali
mereka tetap melakukan tindakan intimidasi, ancaman,
perusakan, pembakaran, atau kekerasan lainnya yang
mengatasnamakan bangsa (dulu) atau agama (kini).
Sebagaimana logika dan moralitas mereka, tindak
kekerasan yang mereka lakukan tersebut adalah
benar. Benar dalam artian sesuai dengan acuan moril
organisasi. Benar dalam pengertian bahwa tindakan
mereka dipandang sebagai “perjuangan” (dulu) atau
“jihad”, “saleh”, “muslim sejati” (kini). Apabila mereka
melakukan tindak kekerasan mereka seperti orang yang
dianggap semacam “pahlawan”.
Pahlawan adalah sebuah tanda yang dilekatkan
secara sosial sesuai dengan moral yang menjadi acuan
mereka. Maka, jika mendapatkan identitas tersebut
mereka akan bangga, dihargai dan dihormati diantara
sesama mereka. Hal ini semacam pencapaian prestisius,
seperti pemenang dari sebuah persaingan. Sayangnya,
persaingan tersebut hanya sebatas di antara kelompok
mereka sendiri.
Artinya, di luar mereka, tindakan tersebut belum
tentu disebut prestisius dan belum tentu mendapat
pengharagaan sebagaimana di dalam logika mereka.
Sebab, mereka termasuk kelompok yang menganut
38
PRANALA { Maret - April 2015 }
DALAM LOGIKA KON
SUMEN, SESEORANG HARUS
BEKERJA KERAS UNTUK
MEMILIKI PENDAPATAN YANG CUKUP AGAR
DAPAT MEMBELI SUATU
PRODUK. MEREKA HARUS
BEKERJA KERAS UNTUK
MENDAPATKAN TANDA
KEISTIMEWAAN, YANG
PRETISIUS, DAN ME
MENANGKAN PERSAINGAN.
logika tertutup; toleransi dan keberagaman yang
dikampanyekan oleh beberapa pihak di bawah payung
demokrasi pun dianggap menjadi tantangan kerja.
Mereka tampak seperti tenaga kerja yang terlatih (skilled
labour).
Selain itu, dalam logika produksi masyarakat
konsumtif, produk juga dapat digunakan sebagai
komoditas yang bernilai komersial dan menghasilkan
keuntungan—keuntungan dipahami tidak hanya
berupa materiil atau finansial, tapi juga keuntungan
sosial, politik, dan kultural, yang akhirnya adalah upaya
pencapaian nilai tukar. Maka, masyarakat konsumsi juga
bersifat proaktif dalam memproduksi tanda dan makna.
Tidak benar jika disebut konsumen itu pasif. Logika
produksi suatu barang bagi konsumen sebagaimana
produksi kekerasan, mereka mengonsumsi dan sekaligus
memproduksi kekerasan.
Dalam logika konsumen, seseorang harus bekerja
keras untuk memiliki pendapatan yang cukup agar
dapat membeli suatu produk. Mereka harus bekerja
keras untuk mendapatkan tanda keistimewaan, yang
pretisius, dan memenangkan persaingan. Tetapi, dalam
keadaan demikian beroperasi pula kekuatan modal
dan kuasa pasar yang mempengaruhi dan sistem sosial,
menggeser tata nilai sekelompok orang atau masyarakat,
dan kemudian membentuk sistem sosial baru.
Menariknya, sistem yang baru tersebut tidak
memiliki kemampuan reflektif dan tidak terkendali,
sebab kebenaran dan moralitas yang mereka anut hanya
semacam sistem nilai yang dibentuk dan dipengaruhi
oleh kondisi dan kepentingan sosial-politik,9 yang tidak
jauh berbeda dengan perilaku konsumen.
Sebuah Prakondisi atau Prasyarat Toleransi
Di pihak lain, untuk menghadang dan mengatasi
gerakan kekerasan tersebut dilawan dengan wacana
toleransi baik dalam kerangka demokrasi maupun dalam
kearifan, kebhinnekaan dan nasionalisme. Wacana yang
terakhir ini mendorong pendekatan dalam penafsiran
lain mengenai keragaman, kemanusiaan (HAM), antikekerasan, dan sebagainya. Yang perlu dicatat adalah
upaya menghalau kekerasan dengan pendekatan
toleransi dan keragaman tersebut mengasumsikan
bahwa masyarakat Indonesia diandaikan: 1) terdapat
perbedaan, 2) yang mestinya dipandang sebagai
keragaman.
Keragaman disini berarti cara pandang sekaligus
konsep nilai yang mengutamakan sikap saling
menghargai, menghormati, atau yang disebut tenggangrasa. Keragaman memerlukan prakondisi yang
mengakui bahwa terdapat perbedaan. Sedangkan dalam
masyarakat konsumtif pada dasarnya menyembunyikan
perbedaan. Di mata konsumsi antara orang kaya dan
miskin tidak dilihat dan dipersoalkan. Orang yang
pendapatan rendah dan tinggi dianggap sama. Pekerjaan,
pendidikan, budaya, dan jenis kelamin dianggap sama.
Buruh dan bos dinilai mempunyai keinginan yang sama
dalam konsumsi. Pengangguran dan politikus samasama memiliki keinginan membeli kendaraan, televisi,
alat komunikasi, dan seterusnya. Orang Islam dan kafir
sekalipun sama. Siapapun orangnya adalah sama, sebagai
konsumen.
Namun, kesamaan dalam konsumsi ini di sisi
lain menyimpan dan menyembunyikan perbedaan,
kebutuhan, kemampuan, termasuk budaya, negara,
bahasa, bahkan ideologi. Kesamaan dalam konsumsi
adalah membonceng keseragaman dan mengabaikan
KONSUMEN HIDUP...MEMBEDAKAN DIRI, SELALU
MENJADI BENTURAN UNTUK
MENDIRIKAN KELOMPOK
YANG SECARA TOTAL BER
BEDA, LANGSUNG, NYATA
DALAM MASYARAKAT...
(MEREKA) MENANDAI TING
KATAN-TINGKATAN DALAM
PERBEDAAN GOLONGAN,
MELALUI PEMBENARAN
GOLONGANNYA SENDIRI
hubungan satu orang dengan yang lain, sebagaimana
disebut sebelumnya. Sehingga, kesadaran terhadap
keragaman sulit dipahami. Kesadaran ini dalam
konsumsi adalah strategi keinginan dan ketidakpedulian.
“Ini adalah pengingkaran kenyataan,” kata Baudrillard,
seorang pemikir berkebangsaan Perancis.10
Kesadaran relasi sosial diganti dengan relasi
konsumsi. Maka, ketidakpedulian yang dimaksud
berangkat dari relasi sosial logika konsumsi bahwa
hubungan manusia dengan manusia lain diandaikan
dengan sebuah produk—yang pertama adalah
persaingan, seperti dijelaskan di atas—memperlakukan
orang lain sebagaimana memperlakukan produk.
Agama, Tuhan, keyakinan dan semacamnya adalah
produk kenyataan yang dipandang memenuhi kebutuhan
seseorang. Maka, mengikuti pandangan kelompok
keagamaan tertentu seperti halnya mengkonsumsi suatu
produk tertentu. “Konsumen hidup...membedakan diri,
selalu menjadi benturan untuk mendirikan kelompok
yang secara total berbeda, langsung, nyata dalam
masyarakat...(mereka) menandai tingkatan-tingkatan
dalam perbedaan golongan, melalui pembenaran
golongannya sendiri,” kata Baudrillard.11
Mereka menganggap dirinya “lebih” daripada yang
lain, yakni meninggikan pihaknya dan merendahkan
yang lain. Seseorang yang dapat memiliki atau
menggunakan produk yang bernilai prestis akan
mengganggap dirinya berbeda dengan orang lain. Dalam
logika konsumsi ini, produk (kekerasan) adalah bernilai
prestis (kesalehan atau perjuangan), sedang keragaman
tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Masyarakat
dalam pandangan tersebut dipandang seragam.
Mereka melihat keberadaannya seperti dalam medan
pertempuran, padahal mereka dalam persaingan pasar.
Tetapi, dalam medan yang disebut pasar sebuah
produk dipandang menarik dan memberikan dorongan
(terhadap kebutuhan, kepuasan, dan penyebaran nilainilai) yang sudah dipengaruhi citra atau promosi
yang beredar di dalam pasar. Situasi sosial-politik
memproduksi pemaknaan terhadap kekerasan yang
mereka lakukan. Relasi dengan pihak tertentu (otoritas
dan kemanan) membuat mereka berani melakukan
identifikasi dan pembedaan diri dengan yang lain.
***
PRANALA { Maret - April 2015 }
39
Perspektif
Dalam logika masyarakat konsumtif, tindak
kekerasan merupakan sebuah pekerjaan untuk
mencapai tanda. Mereka memproduki dan mengonsumsi
kekerasan. Konsumen membeli dan menggunakan
tanda untuk mencapai “keistimewaan” tertentu dan
itu menguntungkan bagi mereka. Hal ini disebabkan
oleh cara pandang yang berlaku dalam masyarakat
konsumsi bahwa; 1) relasi antar manusia diandaikan
seperti persaingan, dan persaingan tersebut mereka
ciptakan sendiri dan diseragamkan, sehingga mereka
melihat bahwa, 2) semua orang dianggap seragam,
seragam dalam kaca mata mereka dan tidak mengakui
perbedaan.
Hal ini adalah semacam prakondisi bagi toleransi dan
kesadaran keragaman yang nirkekerasan tampaknya
sulit dilakukan tanpa menggeser sistem masyarakat
konsumtif dan menghalau industrialisasi lanjut—tidak
berbeda jauh dengan seruan Gus Dur, perdamaian tanpa
keadilan adalah ilusi.12 Jika tidak demikian, maka “Saya
yakin bahwa di masa-masa yang akan datang, Polri
masih akan menghadapi konflik-konflik agama...” kata
Kapolri, Badrodin Haiti.13
(Endnotes)
1 Kriminalitas 59 persen, KDRT 8 persen, persoalan hukum 7 persen, dan konflik 26 persen.
Sedangkan dilihat dari jenis konflik; konflik
separatisme, konflik identitas, konflik sumber
daya, konflik pemilihan dan jabatan, konflik
tata kelola pemerintah, konflik main hakim
sendiri, selengkapnya lihat dalam www.snpkindonesia.com/.
2 Seperti dilaporkan oleh Direktur CSIS, Phillips Vermonte, sekitar 60 persen mengatakan
mereka tidak keberatan tinggal di sebelah
orang dari agama lain, lebih dari 33 persen
menyatakan ketidaknyamanan. Lebih dari 68
persen tidak ingin rumah ibadah selain agamanya dibangun di komunitas mereka. Penolakan
hampir sama tinggi di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan mereka yang berhenti
sampai SMP; Lihat, “Survei: Toleransi Beragama Orang Indonesia Rendah,” www.tempo.co, 5
Juni 2012.
3 Menurut Wilson, mereka mendapat akses
ke sumber daya dan manfaat ekonomi sering
lebih penting daripada komitmen ideologis.
Lihat, Ian Douglas Wilson, “As long as it’s
halal: Islamic Preman in Jakarta,” dalam Greg
Fealy and Sally White (eds.), Expressing Islam:
Religious Life and Politics in Indonesia (Singapura:
Institute of Southeast Asian Studies, 2008).
Fenomena kekerasan dan organisasi semacam
ini merupakan warisan Orde Baru. Orde Baru
memobilisasi preman dan pemuda untuk
menyerang komunis—seperti yang diperlihatkan dalam film dokumenter The Act of Killing
(2012)—dan kemudian mensponsori mereka
masuk ke organisasi seperti Pemuda Pancasila;
Lihat, David Brown & Ian Wilson, “Ethnicized
40
PRANALA { Maret - April 2015 }
Violence in Indonesia: Where Criminals and
Fanatics Meet,” Nationalism and Ethnic Politics,
Vol. 13, No. 3, (23 Agustus 2007), hlm. 373.
4 Seperti ketika pada kasus insiden Monas
pada 2008 atau aksi penusukan anggota HKBP
Ciketing pada 2010, anggota FPI dihukum
jauh dari maksimum yang ada di KUHP. Lihat
Sidney Jones, Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan
Masyarakat Madani di Indonesia (Jakarta: Pusad
Paramadina, 2015), hlm. 10-11. Mengenai hal
ini Nurcholish Madjid (Cak Nur) berpendapat
bahwa perlu upaya memutus keterkaitan aktor
negara dengan organisasi tersebut, serta memperkuat pluralisme. Dalam Laporan Wahid
Institute 2014 menyebutkan bahwa pemerintah pusat tidak banyak mendayagunakan
kekuasaanya untuk memajukan Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan. Terdapat sikap
yang mendua pemerintah. “SBY memilih
mendelegasikan kekuasaannya kepada kepala
daerah ketika terjadi perselisihan menyangkut
IMB di HKBP Filadelfia dan GKI Taman Yasmin. Pada kasus lainnya, kepala daerah tidak
ditegur karena mengabaikan perkara semacam
ini.” Lihat, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/
Berkeyakinan dan Inttoleransi 2014: “Utang” Warisan
Pemerintah Baru (Jakarta: The Wahid Institute,
2014), hlm. 19.
5 Lihat aksi anti-komunisme akan dianggap
relevan dengan dipertahankannya Ketetapan
MPRS RI No. XXV 1966; aksi anti-ahmadiyah
relevan dengan fatwa sesat atau SKB dua
menteri; anti-liberal atau anti-syiah dengan
keputusan ulama, dan sebagainya.
6 Pada April 2012, Forum Ulama Ummat
Indonesa (FUUI) mengadakan diskusi yang
7
8
9
10
11
12
13
bertajuk “Merumuskan Langkah Strategis
untuk Menyikapi Penyesatan dan Penghinaan
Para Penganut Syiah.” Hasil diskusi tersebut
menyimpulkan bahwa Syiah sesat dan bisa
tidak dianggap Muslim sejati. Salah satu tamu
diskusi tersebut antara lain Gubernur Jawa
Barat dan Walikota Bandung. Perlu dicatat
bahwa organisasi ini pada akhir 2002 silam
mengeluarkan fatwa mati terhadap Ulil Abshar Abdalla, Jaringan Islam Liberal; Lihat, “Pemerintah akan mengawasi gerakan anti-Syiah,”
dalam www.syiah.co/viewtopic.php?id=38.
Sidney Jones, hlm. 26.
Ian Douglas Wilson, 2008, hlm. 193.
Sidney Jones, hlm. 23
Lihat Jean P. Baudrillard, Masyarakat Konsumsi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004),
hlm. 18.
Ibid, hlm. 61.
Lihat, seruan Yenny Wahid dalam pawai
damai peringatan Wahid Institute dan Gus
Dur pada Hari Perdamaian Internasional, 21
September 2014, yang dilansir SCTV; Lihat
http://news.liputan6.com/read/2106366/yenny-wahidahok-bawa-keadilan-di-tengah-masyarakat.
Dalam sebuah pengantar laporan riset
mengenai “Pemolisian Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia pasca-Orde Baru” yang
dilangsungkan pada Januari 2012-September
2013. Lihat dalam Rizal Panggabean & Ihsan
Ali-Fauzi, Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia, Edisi Ringkas (Jakarta: Pusad Paramadina,
2014), hlm. V.