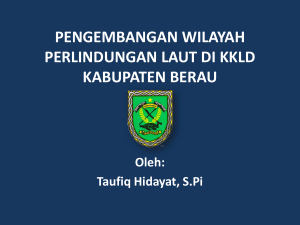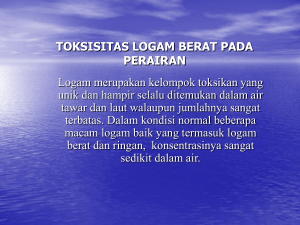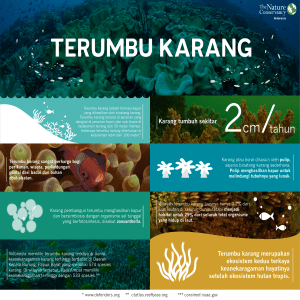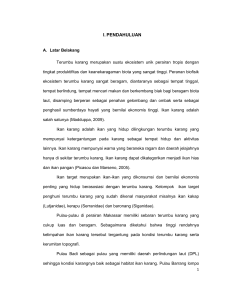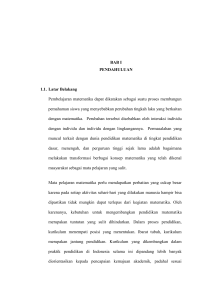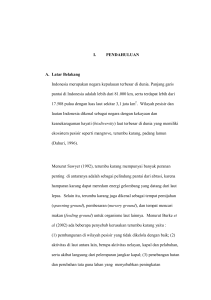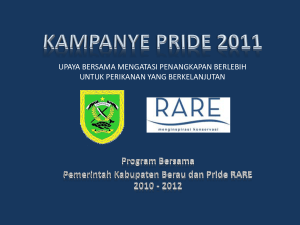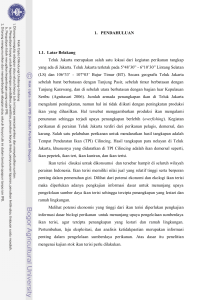sumber daya ikan di perairan teluk jakarta dan alternatif
advertisement

SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA Editor: Prof. Dr. Ali Suman Prof. Dr. Wudianto Drs. Bambang Sumiono, M.Si. Kerja sama: • • • • Balai Penelitian Perikanan Laut Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Editor: Prof. Dr. Ali Suman Prof. Dr. Wudianto Drs. Bambang Sumiono, M.Si. Copyright © 2011 Balai Penelitian Perikanan Laut Pencetakan buku Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya dibiayai dari dana APBN Balai Penelitian Perikanan Laut TA. 2011 Editor Bahasa Korektor Desainer Sampul Penata Isi : Elviana : Putri Komalasari : Sani Etyarsah : Ardhya Pratama dan Sani Etyarsah PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Bogor Cetakan Pertama: Desember 2011 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit ISBN: 000-000-000-000-0 Kata Pengantar Puji syukur ke hadirat Allah Yang Mahakuasa, atas perkenan-Nya buku dengan judul “Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya”, dapat diselesaikan. Buku ini merupakan karya ilmiah para peneliti Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL), Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Saya menyambut baik atas karya buku ini sebagai sumbangan ilmiah dalam menguak status pemanfaatan sumber daya ikan di Teluk Jakarta, sebagai salah satu daerah penangkapan ikan yang utama bagi nelayan ibu kota Republik Indonesia. Buku ini sangat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama sebagai bahan dasar pengelolaan sumber daya ikan di perairan ini yang mengacu pada pilar strategi pembangunan nasional yaitu pro-poor, pro-job, dan pro-growth serta pengembangan pilar pro-business. Makalah yang dimuat dalam buku ini sudah dipresentasikan dalam acara Forum Teluk Jakarta yang diadakan di Bogor pada tanggal 31 Oktober–1 Nopember 2011, dan telah dilakukan evaluasi oleh para editor, untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh penulis masingmasing. Atas usaha dan kerja keras dari para editor: Prof. Dr. Wudianto, Prof. Dr. Ali Suman, Drs. Bambang Sumiono, M.Si, dan para penulis dalam penyempurnaan makalah-makalah yang termuat dalam buku ini diucapkan terima kasih. Sebagai suatu karya ilmiah, saya mengharapkan buku ini dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di Teluk Jakarta secara berkelanjutan. Semoga Allah Yang Maha Esa Kata Pengantar senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua serta semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Jakarta, Desember 2011 Kepala Balai, Prof. Dr. Ali Suman iv Daftar Isi Kata Pengantar.......................................................................................iii Daftar Isi................................................................................................. v Daftar Tabel.......................................................................................... vii Daftar Gambar..................................................................................... xiii 1. Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu - Teluk Jakarta Oleh Sri Turni Hartati dan Amran Ronny Syam................................1 1. a. Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Oleh Khairul Amri dan Samsul B. Agus...................................35 2. Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Oleh Isa Nagib Idrus dan Sri Turni Hartati.....................................49 3. Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Oleh Sri Turni Hartati, Isa Nagib Idrus, Amula Nurfiarini dan Ina Juanita Indarsyah...............................................................65 4. Status Pemanfaatan dan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Oleh Siti Nuraini, Prihatiningsih, Wahyuningsih, dan Wedjatmiko..............................................................................91 5. Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus pelagicus linn) di Perairan Teluk Jakarta Oleh Bambang Sumiono, Karsono Wagiyo, Duranta D. Kembaren, dan Prihatiningsih........................................................................107 Daftar Isi 6. Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Oleh Adriani Nastiti, Masayu Rahmia A.P, dan Sri Turni Hartati...................................................................127 6. a.Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Oleh Suprapto, Duranta D. Kembaren, dan Pratiwi Lestari............147 7. Keragaan Sumber daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh M. Taufik, Tuti Hariati, dan M. Fauzi..................................179 8. Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya Oleh Hufiadi, Tri Wahyu Budiarti, Baihaqi, dan Mahiswara..........197 9. Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan : Framentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh Suherman Banon Atmaja......................................................211 10. Alternatif Pengelolaan Sumber daya Ikan di Teluk Jakarta Oleh Ali Suman............................................................................231 Daftar Pustaka.....................................................................................241 vi Daftar Tabel Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu - Teluk Jakarta Oleh Sri Turni Hartati dan Amran Ronny Syam Tabel 1. Kondisi terumbu karang di perairan Gosong Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu...................................................................6 Tabel 2. Kondisi terumbu karang di perairan karang Wak Rom, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu . ..........................................7 Tabel 3. Kondisi terumbu karang di perairan Kaliage Kecil, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu . .........................................7 Tabel 4. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu...................................................................8 Tabel 5. Kondisi terumbu karang di Pulau Opak kecil Kepulauan Seribu .................................................................9 Tabel 6. Kondisi terumbu karang di area perlindungan laut utara Pulau Tidung.......................................................................10 Tabel 7. Kondisi terumbu karang alami diperairan selatan Pulau Payung.......................................................................11 Tabel 8. Kondisi terumbu karang di daerah perlindungan laut selatan Pulau Pari..........................................................12 Tabel 9. Status kesehatan karang pada beberapa daerah perlindungan laut di wilayah Kepulauan Seribu . .................14 Tabel 10. Karakteristik beberapa terumbu buatan di perairan Kepulauan Seribu.................................................................15 Daftar Tabel Tabel 11. Komposisi ikan hasil tangkapan bubu yang didaratkan di Pulau Panggang bulan Maret 2007...................................23 Tabel 12. Komposisi ikan hasil tangkapan bubu yang didaratkan di Pulau Kelapa, Maret 2007................................................24 Tabel 13. Komposisi ikan hasil tangkapan muroami di perairan Kepulauan Seribu bulan Maret 2007....................................25 Tabel 14. Kelimpahan dan komposisi ikan hasil tangkapan muroami yang dioperasikan secara babangan dan didaratkan di Pulau Tidung ..................................................................25 Tabel 15. Kelimpahan ikan karang di perairan Kepulauan Seribu utara pada bulan Maret 2008.....................................29 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Oleh Khairul Amri dan Samsul B. Agus Tabel 1. Luasan daerah perlindungan luat di Kepulauan Seribu.........41 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Oleh Isa Nagib Idrus dan Sri Turni Hartati Tabel 1. Posisi lokasi transek .............................................................52 Tabel 2. Jenis-jenis karang yang teridentifikasi di Gugusan Pulau Pari, Teluk Jakarta......................................................54 Tabel 3. Persentase tutupan bentuk kehidupan karang yang diperoleh dengan cara RRA..........................................56 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Oleh Sri Turni Hartati, Isa Nagib Idrus, Amula Nurfiarini, dan Ina Juanita Indarsyah Tabel 1. Komposisi hasil tangkapan jaring rampus di perairan gugusan Pulau Pari pada tahun 2009....................................82 viii Daftar Tabel Tabel 2. Kelimpahan hasil tangkapan sero di Pulau Kongsi bulan Maret 2008.................................................................82 Tabel 3. Hasil tangkapan ekor kuning, upaya penangkapan, dan hasil tangkapan per unit upaya di Kepulauan Seribu, tahun 1969–1977.................................................................84 Tabel 4. Hasil tangkapan ekor kuning, upaya penangkapan, dan hasil tangkapan per unit upaya di Kepulauan Seribu, tahun 2001–2007.................................................................84 Tabel 5. Nilai Investasi pada beberapa jenis alat tangkap di Pulau Pari, November 2009.............................................87 Tabel 6. Kelayakan usaha penangkapan ikan pada beberapa jenis alat tangkap di Pulau Pari, November 2009.................88 Status Pemanfaatan dan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Oleh Siti Nuraini, Prihatiningsih, Wahyuningsih, dan Wedjatmiko Tabel 1. Hasil tangkapan (CPUE: kg/trip) nelayan garuk harian di perairan Tanjung Kait pada bulan Agustus–September 2011.....................................................99 Tabel 2. Lokasi pendaratan kerang, jumlah pengumpul dan perkiraan jumlah armada garuk di perairan Teluk Jakarta tahun 2011...................................................100 Tabel 3. Estimasi perkembangan produksi kerang Anadara dan kerang tahu di perairan Teluk Jakarta pada tahun 1995–2011......................................................100 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus pelagicus linn) di Perairan Teluk Jakarta Oleh Bambang Sumiono, Karsono Wagiyo, Duranta D. Kembaren, dan Prihatiningsih Tabel 1. Hasil tangkapan rajungan (Portunus Pelagicus) pada beberapa alat tangkap di Teluk Jakarta, April–Mei 2007 .................120 ix Daftar Tabel Tabel 2. Data lebar karapas dan berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan dan sero di perairan Teluk Jakarta, Maret–Agustus 2008..........................................................121 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Oleh Adriani Nastiti, Masayu Rahmia A.P, dan Sri Turni Hartati Tabel 1. Posisi geografis lokasi penelitian di Teluk Jakarta................130 Tabel 2. Parameter yang diukur selama pengamatan........................130 Tabel 3. Beberapa parameter sebagai kriteria pemilihan kawasan konservasi (Salm et al. 2000) yang dimodifikasi sesuai kondisi Teluk Jakarta............................132 Tabel 4. Klasifikasi calon kawasan konservasi asuhan udang.............134 Tabel 5. Nilai parameter perairan di lokasi penelitian Teluk Jakarta......................................................................136 Tabel 6. Pengelompokan parameter dan skor berdasarkan kriteria pemilihan kawasan konservasi (Salm et al. 2000)....137 Tabel 7. Estimasi luas kawasan asuhan juvenil udang.......................140 Keragaan Sumber daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh M. Taufik, Tuti Hariati, dan M. Fauzi Tabel 1. Sumber daya ikan pelagis kecil utama yang tertangkap di perairan Kepulauan Seribu tahun 2006–2008................183 Tabel 2. Komposisi gabungan hasil tangkapan payang sampel (Agustus, Oktober, dan Desember 2006) dari perairan Teluk Jakarta .......................................................189 Tabel 3. Laju tangkap ikan pelagis kecil dari payang pada tahun 2006 ...............................................................190 Tabel 4. Komposisi jenis ikan hasil tangkapan payang yang didaratkan di Pulau Kelapa pada bulan Maret 2007...........191 x Tabel 5. Komposisi ikan campuran tertangkap jaring rampus pada bulan Desember 2006................................................192 Tabel 6. Ukuran ikan yang dominan di dalam hasil tangkapan jaring rampus di perairan Teluk Jakarta pada bulan Desember 2006........................................................193 Tabel 7. Komposisi hasil tangkapan 4 kapal jaring kembung sampel di perairan Kepulauan Seribu bulan Mei 2007........193 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Framentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh Suherman Banon Atmaja Tabel. 1. Persentase penutupan terumbu karang untuk 2 pulau di Kepulauan Seribu....................................215 Tabel 2. Beberapa program intervensi/manipulasi lingkungan dari Suku Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu...................222 Tabel 3. Jenis alat tangkap berdasarkan hierarki perikanan...............226 Alternatif Pengelolaan Sumber daya Ikan di Teluk Jakarta Oleh Ali Suman Tabel 1. Kebutuhan data dan informasi bagi pemanfaatan secara berkelanjutan............................................................240 Daftar Gambar Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu - Teluk Jakarta Oleh Sri Turni Hartati dan Amran Ronny Syam Gambar 1. Jumlah jenis ikan karang pada 9 lokasi pengamatan di Kepulauan Seribu, April 2007............................................ 29 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Oleh Khairul Amri dan Samsul B. Agus Gambar 1. Lokasi daerah perlindungan laut di Kepulauan Seribu............ 40 Gambar 2. Persentase (%) penutupan kategori bentik terumbu karang pada empat DPL di Kepulauan Seribu................................... 42 Gambar 3. Indeks Keanekaragaman (H`), Keseragaman (E), dan Dominansi (C) pada empat DPL di Kepulauan Seribu.......... 44 Gambar 4. Kondisi potensi terumbu dan ikan karang di DPL Kepulauan Seribu (Sumber: Anonim 2010)........................... 45 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Oleh Isa Nagib Idrus dan Sri Turni Hartati Gambar 1. Peta gugus Pulau Pari yang menunjukkan lokasi penelitian 53 Gambar 2. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Kudus bagian utara...................................................... 58 Daftar Gambar Gambar 3. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Tikus bagian barat....................................................... 59 Gambar 4. Kondisi terumbu karang diperairan Pulau Pari Selatan-Timur....................................................... 60 Gambar 5. Status dan kondisi terumbu karang di perairan Pulau Pari bagian timur-utara.............................. 61 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Oleh Sri Turni Hartati, Isa Nagib Idrus, Amula Nurfiarini, dan Ina Juanita Indarsyah Gambar 1. Kepadatan stok ikan karang di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2007....................................... 68 Gambar 2. Komposisi jenis ikan karang di beberapa perairan Kepulauan Seribu.................................................................. 69 Gambar 3. Kepadatan ikan karang di gugusan Pulau Pari pada bulan Juni 2009............................................................. 70 Gambar 4. Komposisi kehadiran famili ikan karang konsumsi di beberapa wilayah perairan gugusan Pulau Pari pada bulan Juni 2009........................................... 71 Gambar 5. Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan bubu di Kepulauan Seribu.............................................................. 73 Gambar 6. Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan pancing ulur di Kepulauan Seribu . ......................................76 Gambar 7. Komposisi hasil tangkapan jaring muroami pada bulan April 2009 di perairan gugusan Pulau Pari........... 79 Gambar 8. Kelimpahan dan komposisi hasil tangkapan jaring gebur pada bulan Agustus 2009 di perairan gugusan Pulau Pari............................................... 81 Gambar 9. Komposisi hasil tangkapan jaring millenium di Pulau Tikus bulan Maret 2008.......................................... 83 xiv Daftar Gambar Gambar 10. Produksi kerapu di Kepulauan Seribu pada tahun 2008–2010.......................................................... 85 Gambar 11. Produksi kerapu di Kepulauan Seribu pada tahun 2010......... 86 Gambar 12. Produksi ikan kakatua di Kepulauan Seribu pada tahun 2008–2010.......................................................... 86 Gambar 13. Rantai Pemasaran Hasil Perikanan Pulau Pari....................... 89 Status Pemanfaatan dan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Oleh Siti Nuraini, Prihatiningsih, Wahyuningsih, dan Wedjatmiko Gambar 1. Lokasi stasion pengamatan pemantauan perairan Teluk Jakarta tahun 1995–2011............................................ 94 Gambar 2. Sebaran densitas Anadara spp. (ind/m2) di perairan laut Teluk Jakarta pada 1995–1997 .................... 96 Gambar 3. Komposisi jenis kekerangan di perairan Kamal-Tanjung Kait, Tangerang Banten pada bulan Agustus–September 2011....................................................... 97 Gambar 4. Garuk alat tangkap kekerangan yang digunakan di perairan Teluk Jakarta........................................................ 98 Gambar 5. Struktur ukuran dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang kerang bulu (Scaparca cornea) yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 28 mm)....... 102 Gambar 6. Struktur ukuran (a) dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang (b) kerang darah (Anadara nodifera) yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 24,33mm)... 103 Gambar 7. Struktur ukuran dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang kerang tahu, Phaphia undulata yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 43mm)........ 104 Gambar 8. Struktur ukuran dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang kerang batik (Meritrix lyrata) yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 33,9 mm).... 105 xv Daftar Gambar Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus pelagicus linn) di Perairan Teluk Jakarta Oleh Bambang Sumiono, Karsono Wagiyo, Duranta D. Kembaren, dan Prihatiningsih Gambar 1. Daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan bubu dan gillnet rajungan di perairan Teluk Jakarta...................................................... 112 Gambar 2. Daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan sero dan bagan di perairan Teluk Jakarta . .................................. 112 Gambar 3. Bubu rajungan yang digunakan perairan di Teluk Jakarta.... 114 Gambar 4. Rancang bangun 1 pis jaring kejer di daerah Muara Angke (Jakarta Utara)............................................... 115 Gambar 5. Rancang bangun sero jaring di perairan Teluk Jakarta ........ 116 Gambar 6. Satu unit bagan tancap yang beroperasi di perairan Pulau Lancang .................................................. 117 Gambar 7. Produksi daging rajungan menurut bagiannya dari pedagang pengumpul di Teluk Jakarta, 2002–2008............. 119 Gambar 8. Estimasi produksi rajungan dari pedagang pengumpul di Teluk Jakarta, 2002–2008............................................... 119 Gambar 9. Hubungan lebar karapas-berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan di perairan Teluk Jakarta, Maret – Agustus 2008................................... 122 Gambar 9. Hubungan lebar karapas-berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan di perairan Teluk Jakarta, Maret – Agustus 2008 (lanjutan)......................................... 123 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Oleh Adriani Nastiti, Masayu Rahmia A.P, dan Sri Turni Hartati.... Gambar 1. Lokasi penelitian (KU1-KU7).............................................. 129 Gambar 2. Evaluasi per stasiun di Teluk Jakarta.................................... 139 xvi Daftar Gambar Gambar 3. Lokasi yang dijadikan sebagai calon konservasi kawasan asuhan udang......................................................... 140 Gambar 4. Hubungan rekruitment juvenil terhadap estimasi luasan konservasi kawasan asuhan udang........................................ 141 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Oleh Suprapto, Duranta D. Kembaren, dan Pratiwi Lestari Gambar 1. Peta lokasi daerah pengamatan kualitas perairan di Teluk Jakarta................................................................... 150 Gambar 2. Pola sebaran mendatar rata-rata suhu permukaan laut (SPL) di perairan Teluk Jakarta pada musim angin yang berbeda pada tahun 1996–2011........................................... 154 Gambar 3. Pola sebaran mendatar salinitas permukaan laut di perairan Teluk Jakarta pada musim yang berbeda. . .......................... 157 Gambar 4. Pola sebaran mendatar rata-rata oksigen terlarut di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011........... 160 Gambar 5. Pola sebaran mendatar rata-rata pH air di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011....................... 163 Gambar 6. Variasi rata-rata indeks keanekaragam jenis bentos tiap stasiun penelitian di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011........................................... 165 Gambar 7. Variasi sebaran rata-rata kelimpahan fitoplankton di perairan Teluk Jakarta pada tiga musim yang berbeda pada tahun 1996–2011........................................................ 168 Keragaan Sumber daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh M. Taufik, Tuti Hariati, dan M. Fauzi Gambar 1. Peta lokasi penelitian........................................................... 181 Gambar 2. Peta lokasi pengamatan aktivitas bagan tancap di seluruh perairan Teluk Jakarta......................................... 184 xvii Daftar Gambar Gambar 3. Peta lokasi pengamatan aktivitas bagan tancap sampel di perairan barat Teluk Jakarta, bulan Mei 2006 (1–7 = Posisi bagan tancap yang diamati).......................... 185 Gambar 4. Daerah penangkapan ikan dengan bagan tancap di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu pada tahun 2007.................................................................. 186 Gambar 5. Komposisi ikan demersal, ikan pelagis, dan non ikan yang tertangkap payang bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2006 di perairan Teluk Jakarta..................... 190 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya Oleh Hufiadi, Tri Wahyu Budiarti, Baihaqi, dan Mahiswara Gambar 1. Trajektori efisiensi payang di perairan Teluk Jakarta............ 202 Gambar 2. Produksi aktual dan produksi potensial perikanan payang DKI Jakarta periode tahun 2001–2002................................ 203 Gambar 3. Trajektori efisiensi pancing di perairan Teluk Jakarta........... 204 Gambar 4. Produksi aktual dan produksi potensial perikanan pancing DKI Jakarta periode tahun 2001–2002................................ 204 Gambar 5. Trajektori efisiensi bubu di perairan Teluk Jakarta............... 205 Gambar 6. Produksi aktual dan produsi potensial perikanan bubu DKI Jakarta periode tahun 2001–2010 . ............................. 206 Gambar 7. Trajektori efisiensi muroami di perairan Teluk Jakarta......... 207 Gambar 8. Produksi aktual dan produksi potensial perikanan muroami DKI Jakarta periode tahun 2001–2010................................ 208 xviii Kata Pengantar Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Framentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh Suherman Banon Atmaja Gambar 1. Ekosistem Teluk Jakarta terdiri dari dua ekosistem pantai (coastal ecosystems), yaitu Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu atau Pulau Seribu Complex (sumber: Williams et al. 2000 dalam Arifin 2004).............................. 213 Gambar 2. Hubungan antara tutupan karang hidup dan jarak dari daratan (pengamatan 28 pulau di Kepulauan Seribu) (Sumber: Hutomo 1987 dalam Cesar 1996)............ 216 Gambar 3. Diagram illustrasi pergerakan ikan antara habitat mangrove, padang lamun, dan terumbu karang pada perbedaan tingkat daur hidup (adaptasi dari Mumby et al. 2003 dalam Unsworth 2007) ....................................................... 217 Gambar. 4. Dualistik kegiatan yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.............................................................. 219 xix Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan SeribuTeluk Jakarta Sri Turni Hartati 1) dan Amran Ronny Syam 2) Balai Penelitian Perikanan Laut dan Balai Penelitian Pemulihan Konservasi Sumber Daya Ikan 1) 2) Abstrak Upaya untuk merehabilitasi kerusakan terumbu karang di Kepulauan Seribu sudah banyak dilakukan, seperti penetapan daerah perlindungan laut, transplantasi karang, dan pengembangan terumbu buatan. Penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan rehabilitasi yang ada dan mengidentifikasi beberapa lokasi terumbu karang yang dapat direkomendasikan untuk direhabilitasi. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah karakteristik kondisi biogeofisik, meliputi kondisi kesehatan karang dan oseanografi perairan, stok sumber daya ikan dan karakteristik sosial budaya, serta ekonomi dan kelembagaan masyarakat yang terdapat di wilayah Kepulauan Seribu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai parameter oseanografi mendukung kehidupan ekosistem terumbu karang. Kesehatan terumbu karang dan komunitas ikan pada daerah perlindungan laut menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu pada ketegori baik dengan penutupan karang batu > 50%. Hal ini terindikasi dengan ditemukannya kembali ikan konsumsi ekonomis ekor kuning (Caesio cuning) dan ikan hias Amphiprion sp yang populasinya sudah mulai menurun di perairan Kepulauan Seribu pada periode sebelumnya. Tidak demikian halnya dengan kegiatan transplantasi karang dan pengembangan terumbu buatan, terlihat perkembangannya tidak signifikan. Sebagian besar transplan terlepas dari substratnya dan kehadiran Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya biota penempel relatif rendah. Hasil identifikasi habitat menunjukkan bahwa perairan Pulau Kotok Kecil, Gosong Air, Pulau Genteng, dan Pulau Harapan dapat direkomendasikan untuk direhabilitasi melalui pengembangan terumbu buatan. Kata kunci:Status pemulihan ekosistem terumbu karang, Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta Pendahuluan Perairan Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Laut Jawa, pada posisi paling selatan dari Paparan Sunda, yang terdiri dari beberapa ekosistem, antara lain perairan pantai yang relatif dangkal, terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, dan perairan lepas pantai. Perairan tersebut memiliki potensi beranekaragam ikan/biota dan beberapa jenis bernilai tinggi karena merupakan komoditas ekspor. Secara administratif kawasan Kepulauan Seribu merupakan kabupaten baru dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang juga merupakan salah satu perwakilan kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia yakni sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 162/Kpts-II/1995, tanggal 23 Maret 1995, luas Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah 107.489 hektare, terletak pada posisi geografis antara 106º 25’–106º 37’ BT dan 05º 23’–05º 40’ LS. Kepulauan Seribu terdiri dari 106 pulau-pulau kecil, membentang dari utara Laut Jawa, memiliki karakteristik perairan dangkal dengan dasar batu karang dan tercatat sebanyak 11 pulau yang berpenghuni. Dalam rangka pengelolaan cagar alam yang difungsikan sebagai kawasan Taman Nasional Laut, Direktur Taman Nasional dan Hutan Wisata, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan menetapkan pembagian perairan kawasan Kepulauan Seribu ke dalam empat zona, yaitu: Zona inti, Zona Perlindungan, Zona Pemanfaatan, dan Daerah Penyangga, melalui Surat Keputusan No. 02/VI/TN-2/SK/1986, yang pada tahun 1995 kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nasional. Dari kondisi ekosistem kepulauan yang bertebaran itu diduga bahwa sumber daya ikan yang cukup dominan adalah sumber daya ikan karang. Terumbu karang yang ada tampaknya sudah mengalami kerusakan baik 2 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta yang disebabkan oleh pencemaran ataupun kegiatan penangkapan. Data dan informasi yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, diduga sudah sangat berubah. Perubahan kondisi terumbu karang akan berpengaruh terhadap lingkungan, yang pada umumnya dapat menyebabkan kondisi sumber daya ikan dan biota lainnya berubah pula. Lingkungan terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif dan amat rentan terhadap perubahan lingkungan. Sejumlah hasil penelitian hidrologis yang menitikberatkan pada aspek oseanografi yang bersifat fisik (Physical oceanography) kawasan Kepulauan Seribu telah dilaporkan oleh Moosa et al. (1985). Data dan informasi yang diperoleh antara lain: data sebaran dan rata-rata suhu permukaan perairan (sea surface temperature), salinitas, oksigen, nitrat, fosfat dan silikat. Data dan informasi tentang biota laut meliputi alga bentik, karang batu, krustasea, moluska, dan ekhinodermata. Data dan informasi tentang potensi sumber daya sampai saat ini masih bersifat kualitatif. Penelitian kondisi terumbu karang di wilayah Kepulauan Seribu pada tahun 1999 menunjukkan kategori buruk sampai bagus, dan kondisinya didominasi buruk sampai sedang, dengan besara persentase penutupan karang hidup hanya pada kisaran 0 sampai 49,9% (Suharsono 1996). Upaya menanggulangi masalah kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia telah dilakukan melalui pengembangan terumbu buatan yang dirintis oleh Dinas Perikanan DKI pada tahun 1980–1988 dengan menenggelamkan bekas kerangka bis dan becak. Pada tahun 2002–2010 telah dilakukan rehabilitasi karang seluas 39.480 m2 atau sebanyak 6.241 buah modul terumbu buatan yang terbuat dari bahan beton berbagai bentuk (Suku Dinas Kelautan dan Pertanian 2011). Ditjenkan pada tahun 1990–1993 juga telah mengembangkan terumbu buatan dengan bahan ban mobil di 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Demikian pula dengan Puslitbang Perikanan telah mendukung pengembangan terumbu buatan tersebut dengan melakukan Penelitian Teknis Rehabilitasi Terumbu Karang di perairan Kepulauan Seribu, Bali, dan NTB. Pemasangan terumbu buatan menggunakan bahan beton berbentuk kubus berongga yang disusun dalam formasi piramida memberi dampak biologis dan ekologis yang lebih nyata, di antaranya mampu menarik biota dan jenis-jenis ikan karang. 3 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Bahan dan Metode Makalah ini merupakan himpunan beberapa hasil penelitian di sekitar Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dalam rangka kegiatan rehabilitasi terumbu karang yang berdampak pada pemulihan stok sumber daya ikan di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Hasil dan Pembahasan 1. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kondisi ekosistem terumbu karang di wilayah Kepulauan Seribu diamati pada beberapa lokasi, baik pada terumbu karang alami maupun yang sudah direhabilitasi melalui penetapan daerah perlindungan laut (DPL), transplantasi karang, dan pengembangan terumbu buatan. Beberapa lokasi yang diamati berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan wilayah Kepulauan Seribu Selatan. Wilayah Kepulauan Seribu Utara meliputi perairan Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Semak Daun. Wilayah Kepulauan Seribu Selatan meliputi perairan Pulau Pari, Pulau Tikus, Pulau Tidung, dan Pulau Payung. 1.1 Perairan Pulau Pramuka Pengamatan di perairan Pulau Pramuka dilakukan di 5 titik (stasiun), 4 titik berada di Gosong Pramuka yang terletak di sebelah barat laut dan merupakan daerah perlindungan laut (DPL) dan 1 titik berada di perairan sebelah barat daya. Stasiun 1 Stasiun 1 (perairan Gosong Pramuka) berada pada posisi geografi 05o,44’11,2” LS–106o,36’32,0” BT. Terumbu karang terdapat pada kedalaman 2–10 meter, terlihat kondisinya relatif baik pada lokasi dengan tingkat kemiringan lebih dari 30%. Rataan karang relatif sempit dan berada pada kedalaman 2 meter. Terumbu karang didominasi oleh jenis karang masif (Porites lutea) dan Millepora sp atau karang api. Kesehatan terumbu karang pada kategori sedang mendekati baik, dengan persentase penutupan karang batu (hard coral) mendekati 50%. 4 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta Stasiun 2 Stasiun 2 (perairan Gosong Pramuka) berada pada posisi geografi o 05 44’08,4” LS–106o36’35,1” BT. Rataan karang relatif sempit dan pada saat surut terendah tidak digenangi air. Terumbu karang terdapat pada kedalaman 1–12 meter, dengan tingkat kemiringan lebih dari 30%. Terumbu karang didominasi oleh jenis karang submasif (Porites nigrescens), karang foliosa (Montipora foliosa), dan karang bercabang (Acropora hydnopora). Kesehatan terumbu karang pada kategori sedang mendekati baik, dengan penutupan karang batu mendekati 50%. Pada kedalaman 15 meter, dasar perairan terdiri dari pasir berlumpur. Stasiun 3 Stasiun 3 (perairan Gosong Pramuka) berada pada posisi geografi o 05 ,44’,04,4” LS–106o, 36’,37,1” BT. Kesehatan terumbu karang pada kategori sedang, dengan persentase penutupan karang batu 30%. Terumbu karang didominasi oleh jenis karang masif (Porites sp., Favia sp., Goniopora sp.), Millepora sp., dan karang folios (Montipora foliosa) Stasiun 4 Stasiun 4 (perairan Gosong Pramuka) berada pada posisi geografi 05o 44’ 03,9” LS–106o 36’ 37,3” BT. Terdapat rataan karang relatif luas pada kedalaman 5 meter. Terumbu karang pada kedalaman 5–8 meter didominasi oleh jenis karang folios (Montipora foliosa), karang bercabang (Acropora sp, Pocillopora sp, dan Seriatopora sp), dan karang masif (Porites sp, Favia sp, Goniopora sp). Kesehatan terumbu karang pada kategori baik, dengan persentase penutupan karang batu 75%. Melalui RRI dapat terlihat bahwa keanekaragaman jenis karang relatif tinggi. Perairan Gosong Pramuka selain ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) dalam upaya konservasi, juga merupakan daerah yang direhabilitasi melalui pengembangan terumbu buatan dan transplantasi karang. Terumbu buatan ditemukan pada stasiun 3 dan 4. Pada stasiun 3 ditemukan sebanyak 4 unit, terbuat dari beton panjang disusun 3 dan di atasnya adalah bentuk piramida. Pada stasiun 4 terumbu buatan berbentuk beton kubus, berukuran relatif besar 120 x 120 meter, dan hanya terlihat 1 unit. Terumbu buatan berada pada kedalaman perairan 15 m. Pada terumbu buatan tampak biota penempel dalam jumlah relatif sedang, di antaranya juvenil Goniastrea sp. dan beberapa jenis karang 5 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya bercabang seperti Pocillopora sp. dan Acropora sp. Menurut informasi dari nelayan setempat, terumbu buatan diturunkan pada tahun 2004 pada kedalaman 15–25 meter. Kondisi terumbu karang pada beberapa stasiun pengamatan di perairan Gosong Pramuka disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Kondisi terumbu karang di perairan Gosong Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Lifeform Benthic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Stasiun 1 Stasiun 2 2,5% 2,4% 47,0% 46,5% 7,9% 8,8% 1,5% 1,5% 18,8% 18,8% 22,4% 21,9% Sedang Sedang Stasiun 3 5,0% 25,0% 30,0% 5,0% ,08% 20,0% Sedang Stasiun 4 15,0% 60,0% 3,0% 5,0% 12,0% 5,0% Baik Stasiun 5 Stasiun 5 (perairan barat daya Pulau Pramuka) pada posisi geografi o 05 45’ 00,3” LS dan 106o 36’ 31,6” BT. Terumbu karang terdapat pada kedalaman 2–5 meter dengan kondisi buruk. Topografi dasar perairan dengan tingkat kemiringan lebih dari 30%, dengan substrat pasir halus berlumpur. Pada stasiun 5 terdapat terumbu buatan yang lokasinya berdekatan dengan alur pelayaran kapal-kapal nelayan, dengan kedalaman perairan hanya 5–10 meter. Terumbu buatan berbentuk piramid pada bagian atasnya dan pada bagian bawahnya tersusun kubus panjang bersusun 4 (empat). Jumlah terumbu buatan kurang lebih 20 unit, sebagian susunannya pada kondisi berantakan. Kehadiran jenis-jenis biota penempel pada terumbu buatan relatif banyak, di antaranya karang masif (Porites sp) dan karang bercabang (Pocillopora sp., Seriatopora sp., dan Acropora sp.). Ukuran biota penempel sebagian sudah relatif besar, yaitu panjangnya mencapai kisaran 15–20 cm. 1.2. Perairan Pulau Kelapa Pengamatan terumbu buatan dilakukan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL), yaitu perairan karang Wak Rom dan perairan Kaliage Kecil. 6 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta (1) Perairan Karang Wak Rom Perairan karang Wak Rom sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) mempunyai rataan karang relatif luas, terletak pada posisi kekeringan pada saat surut terendah. Pada kedalaman perairan 3–5 meter. Kesehatan karang pada kategori sedang, dengan penutupan karang batu lebih dari 35% (Tabel 2). Terumbu karang didominasi oleh jenis karang masif (Favia sp., Goniastrea sp.), karang bercabang submasif (Porites rus, Porites nigrescen), dan karang foliosa (Montipora sp.). Tabel 2. Kondisi terumbu karang di perairan karang Wak Rom, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lifeform Benthic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-Acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Kehadiran 4,7% 30,8% 9,3% 25,3% 9,6% 27,4% Sedang (2) Perairan Kaliage Kecil Kondisi terumbu karang di perairan Kaliage Kecil pada kategori baik, dengan penutupan karang batu lebih dari 50%. Rataan karang terdapat pada kedalaman 1–3 meter, kemudian mulai 5 m tingkat kemiringan topografi dasar perairan lebih dari 30%. Kondisi terumbu karang pada 2 stasiun pengamatan di perairan Kaliage Kecil disajikan pada Tabel 3. Terumbu karang didominasi oleh jenis karang bercabang (Acropora sp.) dan karang folios (Montipora sp.). Tabel 3. Kondisi terumbu karang di perairan Kaliage Kecil, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu No Lifeform Benthic 1 Hard coral (Acropora) 2 Hard coral (Non-Acropora) 3 Dead coral Stasiun 1 33,3% 32,0% 6,0% Stasiun 2 22,0% 37,8% 13,0% 7 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 3. Kondisi terumbu karang di perairan Kaliage Kecil, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu (lanjutan) No Lifeform Benthic 4 Algae 5 Other fauna 6 Abiotik Kategori Stasiun 1 17,7% 11,0% 0,0% Baik Stasiun 2 13,0% 7,7% 6,5% Baik 1.3. Perairan Pulau Harapan Pengamatan dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL). Seperti di perairan karang Wak Rom (perairan Pulau Harapan) mempunyai rataan karang yang relatif luas terletak pada lokasi kekeringan saat surut terendah. Pada kedalaman 2–5 meter topografi dasar perairan mempunyai tingkat kemiringan lebih dari 30o. Kondisi terumbu karang pada kategori rusak dengan persentase penutupan karang batu kurang dari 25%. Jenis karang yang ditemukan berbentuk foliosa (Montipora foliosa) masif (Porites lutea) dan karang bercabang (Porites rus dan Porites nigrescen). Kondisi terumbu karang disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lifeform Benthic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-Acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Kehadiran 5% 19% 23% 5% 13% 34% Rusak 1.4. Perairan Pulau Opak Kecil Perairan Pulau Opak Kecil mempunyai rataan karang relatif sempit. Terumbu karang terdapat pada kedalaman 3–12 m dengan tingkat 8 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta kemiringan topografi dasar perairan lebih dari 30o. Kondisi terumbu karang pada kategori sedang dengan persentase penutupan karang batu 3950%. Jenis-jenis karang yang ditemukan di antaranya adalah karang foliosa (Montipora foliosa) karang bercabang (Porites nigrescen, Acropora sp., dan millepora). Untuk jenis fauna lainnya ditemukan kelompok echinoidea (bulu babi) dan kelompok lili laut. Daerah pengamatan mempunyai dasar perairan berlumpur dan berarus deras. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Opak Kecil disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Kondisi terumbu karang di Pulau Opak kecil Kepulauan Seribu No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lifeform Benthic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-Acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Kehadiran 0,0% 39,5% 11,5% 1,0% 14,5% 16,5% Sedang 1.5. Pulau Semak Daun Perairan Pulau Semak Daun mempunyai rataan karang relatif luas dan tidak tergenang air pada saat surut terendah. Terumbu karang terdapat pada kedalaman 2–10 m dengan tingkat kemiringan topografi dasar perairan lebih 30o. Kondisi terumbu karang pada kategori rusak, jenis karang didominasi oleh jenis foliosa (Montipora sp.) dan masif (Porites sp., Favia sp., dan Goniastrea sp.). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di perairan Pulau Semak Daun terlihat adanya terumbu buatan pada kedalaman 25 meter. Terumbu buatan terbuat dari bahan beton berbentuk kubah dengan ketinggian 50 cm dan panjang lingkaran 1 meter. Kondisi perairan lokasi terumbu buatan sangat keruh dengan dasar perairan berlumpur. Terumbu buatan tampak tidak berkembang, keseluruhan modul tertutup lumpur sehingga tidak terlihat adanya biota penempel. 9 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 1.6. Perairan Utara Pulau Tidung Perairan Pulau Tidung mempunyai luasan rataan karang yang memanjang dari barat sampai ke timur. Kondisi terumbu karang masih bagus dan merupakan area perlindungan laut yang luasnya mencapai 10 ha dan berjarak kurang lebih 200 m dari pantai. Rataan karang berada pada kedalaman 1–5 meter kemudian mulai kedalaman 7 meter tingkat kemiringan topografi dasar perairan lebih dari 30o. Pada kedalaman 20 m terlihat kembali rataan dengan substrat dasar pasir berlumpur dan sedikit karang yang hidup. Berdasarkan hasil analisis dari pengamatan LIT, kondisi terumbu karang pada kategori baik dan sangat baik dengan tutupan karang hidup 67,5% dan 81,0% (Tabel 6). Terumbu karang didominasi oleh jenis karang Montipora foliosa kemudian diikuti kelompok Acropora sp dengan berbagai bentuknya Pocillopora hysterik, Porites nigrescen, dan Seriatopora sp. Tabel 6. Kondisi terumbu karang di area perlindungan laut utara Pulau Tidung No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lifeform Benthic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-Acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Stasiun 1 1,0% 67,5% 9,0% 0,0% 2,0% 36,4% Baik Stasiun 2 0,0% 81,0% 0,0% 8,0% 0,0% 11,0% Baik sekali Berdasarkan data dari Dinas Perikanan DKI, di bagian utara Pulau Tidung terdapat dua kelompok terumbu buatan dari bahan beton yaitu pada posisi 05°47’37,8” LS dan 106°29’34,7” BT pada kedalaman 50 meter dan pada posisi 05°47’42,2” LS 106°30’8,5” BT pada kedalaman 40 meter. Kedua posisi tersebut merupakan daerah alur kapal kecil dan daerah pemancingan nelayan di sekitarnya. Penempatan kedua terumbu buatan tersebut dirasa kurang tepat karena tidak mengindahkan kajian pengembangan terumbu buatan yang sudah ada. Pada kedalaman 20 meter, kondisi perairan sudah terlihat gelap, pertumbuhan karang tidak 10 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta maksimal bahkan tidak tumbuh dan hanya jenis-jenis tertentu yang bisa hidup seperti kelompok alga jelatang dan beberapa jenis karang lunak (soft coral). Kegiatan transplantasi karang juga dilakukan di Daerah Perlindungan Laut (DPL) utara Pulau Tidung dengan substrat dari beton bentuk kubus bertangkai besi sebanyak 10 buah. Dari hasil pengamatan terlihat tidak berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan masih tersisanya 2 koloni karang dari jenis Acropora sp. 1.7. Perairan Pulau Payung Selatan Pulau Payung dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 1 km mempunyai rataan karang relatif luas pada kedalaman 2–5 meter. Kondisi terumbu karang pada kategori rendah sampai sedang dengan tutupan karang 21,3%–39,1% (Tabel 7). Pada kedalaman 6–10 m tingkat kemiringan dasar perairan mulai tajam yaitu lebih dari 30o. Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan DKI pada perairan ini terdapat terumbu buatan dari beton kubus pada posisi 05o 49’19,4” BT dan 106o 32’ 46,6” LS. Hasil pemeruman pada lokasi ini menunjukkan kedalaman lebih dari 50 m sehingga pengamatan kondisi terumbu buatan tidak perlu dilakukan karena alasan keselamatan. Penempatan terumbu karang buatan di lokasi ini tidak sesuai dengan kajian pengembangan terumbu buatan yang sudah ada. Jenis karang didominasi oleh Acropora hystrik, A. Formosa, A. Nobilis, Montipora hispida, Palauastrea sp., Porites lobata dan Galaxea sp. Fauna lain yang terlihat adalah bulu babi, bintang laut (Linkia sp.), teripang dan moluska. Tabel 7. Kondisi terumbu karang alami diperairan selatan Pulau Payung Lifeform Bentic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-Acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Titik 1 1,0% 38,1% 0% 12,5% 15,5% 33,9% Sedang Titik 2 1,0 % 21,4% 0,0 % 15,1 % 19,0 % 34,5 % Buruk Titik 3 8,6% 12,7% 0,0 5,6% 55,2% 18,0% Buruk 11 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 1.8. Perairan Pulau Pari Berdasarkan hasil pengamatan, di selatan Pulau Pari terdapat Daerah Perlindungan Laut (DPL) dengan luas 12 ha. Menurut informasi dari Dinas Perikanan DKI, di daerah ini terdapat terumbu buatan berbentuk kubus pada kedalaman 30 meter. Dengan penyelaman, keberadaan terumbu buatan tersebut tidak ditemukan. Hasil pengamatan terumbu karang dengan metode LIT (English et al. 1994) di bagian selatan Pulau Pari ditemukan tutupan karang hidup cukup baik yaitu 51% (Tabel 8). Tutupan karang hidup didominasi oleh jenis Montipora foliosa, Seriatopora hystrik, Pocillopora sp., Acropora sp., dan Fungia sp. Biota lain di antaranya sponge, Xestospongia sp., Petrosia sp., Liosina paradoxa, Calispongia sp., dan aaptos aaptos yang mempunyai kandungan zat bioaktif untuk obatobatan kanker. Tabel 8. Kondisi terumbu karang di daerah perlindungan laut selatan Pulau Pari No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lifeform Benthic Hard coral (Acropora) Hard coral (Non-Acropora) Dead coral Algae Other fauna Abiotik Kategori Kehadiran 0,5% 50,5% 0,0% 46,0% 3,0% 0,0% Baik 1.9. Perairan Pulau Tikus Pulau Tikus memiliki luas daratan yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di gugusan Pulau Pari yaitu kurang lebih 12 ha. Perairan selatan Pulau Tikus mempunyai goba dengan kedalaman 10 m dengan dasar perairan terdiri dari pasir sedikit berlumpur. Tidak ditemukan modul terumbu buatan dari ban berbentuk piramida yang dipasang oleh Puslitbang perikanan pada tahun 1992. Hasil dari LIT (Line Intercept Transect) menunjukkan bawa persentase penutupan karang 12 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta hidup rendah (di bawah 25%). Jenis karang didominasi jenis Palauastrea ramosa, Porites lobata, dan Goniopora sp. Kelompok lain yang hadir adalah makro algae, turf algae, coralin algae, dan Ascidian. 2. Transplantasi Karang Untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang juga dilakukan penanaman biota karang yang sering dikenal dengan transplantasi. Transplantasi ini umumnya dilakukan di daerah dengan kondisi terumbu karang yang tidak mengalami kerusakan berat. 3. Pengembangan Terumbu Buatan Selain berfungsi sebagai media penempelan biota sesil, penempatan terumbu buatan di suatu perairan juga berfungsi sebagai fish shelter rumpon atau tempat berlindung ikan. Dengan adanya terumbu buatan, diharapkan bisa terbentuk habitat baru yang menyerupai terumbu karang alami. Di seluruh dunia telah terpasang kurang lebih 500.000 bola beton berbagai ukuran sebagai terumbu buatan. Dana yang dibutuhkan mencapai puluhan juta dolar Amerika, tetapi hanya menghasilkan 2 km terumbu buatan padahal terdapat sekitar 300.000 km2 terumbu karang di dunia yang dapat menjadi sumber substrat. Masalahnya adalah sebagian besar terumbu tersebut tidak dikelola dengan baik atau telah rusak (Edwards dan Gomez 2007). Dalam rangka memperoleh informasi sejauh mana hasil kegiatan rehabilitasi terumbu karang di wilayah perairan Kepulauan Seribu melalui Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Jatiluhur selama tahun 2007 telah dilakukan kegiatan penelitian di beberapa lokasi rehabilitasi. Kegiatan tersebut bertujuan menetapkan lokasi yang tepat untuk direhabilitasi melalui pengembangan terumbu buatan. Kegiatan riset tersebut mengidentifikasi habitat di berbagai wilayah perairan karang Kepulauan Seribu. Hasil pemantauan pada beberapa wilayah perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) menunjukkan keberhasilan yang relatif signifikan. Status kesehatan karang pada beberapa wilayah daerah perlindungan laut tersebut disajikan pada Tabel 9. 13 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 9. Status kesehatan karang pada beberapa daerah perlindungan laut di wilayah Kepulauan Seribu No Lokasi DPL Tutupan karang batu (%) Status kesehatan karang 1. Gosong Pramuka 30–75 Sedang–Baik sekali 2. Karang Wak Rom > 35 Sedang 3. Kaliage Kecil 4. Pulau Harapan 5. Utara Pulau Tidung 6. Selatan Pulau Pari 60–65 Baik < 25 Rusak 68–81 Baik–Baik sekali > 50 Baik Pengamatan pada 6 lokasi yang ditetapkan sebagai daerah perlindungan laut menunjukkan penetapan DPL Pulau Harapan kurang tepat. Dengan kondisi terumbu karang yang rusak, lebih tepat jika dilakukan rehabilitasi melalui rekayasa habitat terumbu buatan, tentunya dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lainnya. Penetapan kelima daerah perlindungan laut lainnya berdampak positif terhadap perkembangan komunitas ikan. Melimpahnya kembali ikan ekor kuning berdasarkan sensus visual pada LIT di daerah perlindungan laut. Teridentifikasinya kembali jenis-jenis Amphiprion yang pada saat ini sudah mulai langka. Jenis ikan tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi. Demikian pula dari pengamatan hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan alat tangkap bubu dan muroami didominasi oleh jenis ekor kuning yang beberapa tahun terakhir menghilang dari Kepulauan Seribu. Evaluasi rehabilitasi kerusakan terumbu karang melalui rekayasa habitat dengan terumbu buatan dilakukan pada beberapa wilayah perairan di Kepulauan Seribu Utara dan Selatan. Dengan pertimbangan keselamatan dari 7 lokasi yang direncanakan, hanya 3 lokasi yang dapat teramati karena 4 lokasi lainnya berada pada kedalaman > dari 30 m. Kedalaman yang dipersyaratkan untuk lokasi terumbu buatan adalah pada kisaran 10–20 meter sehingga masih tertembus cahaya matahari serta tidak mengganggu alur pelayaran kapal nelayan dan mudah untuk diamati. Dari 3 lokasi yang teramati, hanya 1 lokasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi yaitu terumbu buatan di barat daya Pulau Pramuka. Spesifikasi beberapa terumbu buatan di wilayah Kepulauan Seribu dan karakteristik lainnya disajikan pada Tabel 10. 14 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta Tabel 10. Karakteristik beberapa terumbu buatan di perairan Kepulauan Seribu No Lokasi 1. Utara Gosong Pramuka 2. Barat Daya Pulau Pramuka 3. 4. 5. 6 7. Pulau Semak Daun Utara Pulau Tidung Selatan Pulau Pari Selatan Pulau Payung Goba Pulau Tikus Kedalaman Perairan (m) 15–25 5–10 25 > 30 > 30 > 50 ttd Bentuk Terumbu Kubus KubusPiramida Kubah ttd ttd ttd ttd Biota penempel Sedang Tinggi Rendah - Keterangan: ttd = tidak terdeteksi 4. Identifikasi Habitat untuk Pengembangan Terumbu Buatan Melihat keberhasilan rehabilitasi kerusakan terumbu karang melalui rekayasa habitat dengan pengembangan terumbu buatan di Kepulauan Seribu relatif rendah, telah dilakukan identifikasi untuk alternatif lokasi perairan karang yang tepat untuk direhabilitasi. 4.1. Persyaratan Kondisi Oseanografi Pemilihan lokasi bagi penempatan terumbu buatan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan ekologis, antara lain suhu, salinitas, oksigen, kecerahan, pH, dan arus. Pengamatan kondisi oseanografi yang dilakukan di perairan Kepulauan Seribu pada lokasi yang akan disarankan untuk direhabilitasi adalah sebagai berikut. 1. Suhu air Suhu air permukaan pada lokasi yang akan disarankan untuk direhabilitasi melalui pengembangan terumbu buatan berkisar 29,03 oC–29,95oC dan di dasar perairan berkisar 28,12 oC–29,16oC. Perbedaan antara suhu air di permukaan dengan suhu air di dasar tidak berbeda jauh, hal ini disebabkan air laut memiliki panas jenis 15 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya yang tinggi sehingga diperlukan panas yang tinggi untuk mengubah suhu air sebesar 1oC. Fluktuasi suhu di perairan Kepulauan Seribu < 1oC. Suhu air tertinggi terjadi pada musim peralihan dan terendah terjadi pada musim barat dan timur. Suhu tersebut sangat mendukung untuk pertumbuhan terumbu karang karena biota tersebut dapat tumbuh dengan baik pada suhu 25oC–30oC. Suhu yang baik untuk terumbu buatan adalah 28oC–30oC karena pada kisaran suhu tersebut memungkinkan organisme untuk melakukan metabolisme secara normal. 2. Salinitas Salinitas di permukaan dan dasar perairan berkisar 33,0 o/oo–33,5 o/ . Kondisi ini akan menunjang tumbuhnya biota terumbu karang oo dengan baik di perairan tersebut. Baku mutu salinitas untuk kehidupan karang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 adalah 33 o/oo–34 o/oo. Biota lainnya seperti fitoplankton dapat berkembang pada perairan dengan salinitas lebih dari 15 o/oo dan optimum pada salinitas 35 o/oo. Bagi fitoplankton, perubahan salinitas sekecil apapun dapat memengaruhi daya melayang fitoplankton (Anonim 2004). Fluktuasi salinitas di kepulauan seribu pada permukaan berkisar 30,5 o/oo–32,75o/oo dan di dasar berkisar 32,0 o/oo–33,5o/oo. 3. Oksigen terlarut 16 Konsentrasi oksigen terlarut pada lapisan permukaan perairan masing-masing lokasi berkisar 2,71–4,45 ml/l dan di dasar perairan 2,29–5,50 ml/l. Konsentrasi oksigen terlarut yang rendah terdapat di lokasi Pulau Panjang. Sedangkan di tiga lokasi lainnya, yaitu Pulau Genteng, Pulau Kotok Kecil, dan Pulau Gosong, air mempunyai konsentrasi oksigen yang dapat mendukung kehidupan terumbu karang. Tingginya konsentrasi oksigen terlarut ini disebabkan oleh proses fotosintesis yang berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh kecerahan yang hampir mencapai dasar perairan. Konsentrasi oksigen terlarut ini masih memenuhi baku mutu untuk kehidupan biota air. Nilai konsentrasi oksigen terlarut di dasar perairan umumnya lebih rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh dekomposisi bahan organik. Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta 4. Kecerahan Kecerahan di setiap lokasi penelitian umumnya mencapai dasar perairan yaitu berkisar 7,52–11,0 m. Kecerahan yang baik dapat mendukung terjadinya proses fotosintesis karena penetrasi cahaya matahari dapat mencapai perairan yang dalam. Cahaya yang masuk ke perairan dapat digunakan oleh alga sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Berdasarkan PP N. 51 Tahun 2004, kecerahan untuk biota laut khususnya terumbu berkisar lebih dari 5% dan kurang dari 10% dari perubahan kedalaman eufotik (Kementerian Lingkungan Hidup 2004). Untuk lokasi penempatan modul terumbu buatan tidak kurang dari 0,5 m. Kecerahan ini berperan untuk penetrasi cahaya dan menjaga jangkauan indra organisme. 5. Kedalaman Kedalaman di calon lokasi penempatan modul terumbu buatan berkisar 10–21 m. Letak kedalaman yang optimum untuk terumbu buatan berkisar 15–20 m. Kedalaman ini berhubungan dengan kemudahan peletakkan dan pemanfaatan terumbu buatan serta pertumbuhan biota penempel. Terumbu buatan masih dapat tumbuh dengan baik pada kedalaman 10 m. 6. Arus Arus berperan sangat penting dalam transportasi zat-zat hara untuk kebutuhan pertumbuhan fitoplankton. Selain itu juga sebagai media transportasi bagi larva dan sebagian biota di antaranya adalah biota yang hidupnya menempel pada substrat. Batas kecepatan arus maksimum untuk kehidupan biota di laut adalah 3 km/jam dengan arah yang bervariasi mengikuti pola pasang surut. Hasil pengamatan arus pada lokasi tersebut berkisar 5,7–15,1 cm/det dengan arah yang bervariasi. Persyaratan untuk penempatan terumbu buatan sebaiknya tidak lebih dari 50 cm/detik. Pengamatan pada perairan Gosong Air, kondisi arus tidak terdeteksi. 7. pH Calon lokasi penempatan modul terumbu memiliki nilai pH yang cenderung netral berkisar 7,34 –7,54. Nilai pH yang baik untuk 17 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya kehidupan biota air berkisar 6–9 (Effendi 2003) dan berdasarkan peraturan kementerian lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, baku mutu untuk kehidupan biota laut adalah 7– 8,5. 5. Kondisi Dasar dan Luasan Paparan. Berdasarkan kajian yang ada sebelumnya, ukuran volume terumbu yang ekonomis adalah 400 m3. Untuk memperoleh terumbu buatan sebesar 400 m3 tersebut dengan tiap 1 modul terumbu buatan yang berbentuk piramida 21,96 m2 membutuhkan luasan dasar perairan 11.600 m2. Berdasarkan pengamatan kondisi oseanografi, topografi dasar perairan dan luas paparan lokasi yang direkomendasikan untuk pengembangan terumbu buatan adalah perairan Pulau Kotok Kecil, Pulau Genteng, Pulau Gosong Air, dan bagian barat Pulau Harapan. Posisi geografi untuk lokasi pengembangan terumbu buatan di perairan Pulau Kotok Kecil adalah 5o 41’ 24”–5o 41’ 15” LS dan 106o 31’ 46,8”–106o 31’ 59,7” BT dengan luas rataan karang (reef flat) adalah ± 8 ha atau 80.000 m2 pada kedalaman 10–12 m. Posisi geografi lokasi pengembangan terumbu buatan di perairan Gosong Air adalah 5o 39’ 12” –5o 39’ 12,8 LS dan 106o 33’ 42”–106o 33’ 45,5” BT dengan luas rataan karang ± 12 ha atau 12.000 m2 pada kedalaman 17–21 m. Posisi geografi lokasi pengembangan terumbu buatan di perairan Pulau Genteng adalah 5o 36’ 42,5” –5o 36’ 50,6 LS dan 106o 32’ 2,8”–106o 32’ 57,4” BT dengan luas rataan karang ± 12 ha atau 12.000 m2 pada kedalaman 17–21 m dan untuk perairan Pulau Harapan terletak pada posisi 5o 39’ 23,9”–5o 39’ 30,8 LS dan 106o 33’ 21”–106o 33’ 22,8” BT dengan luas rataan karang ± 8 ha atau 80.000 m2 pada kedalaman 10–14 m. Berdasarkan luas rataan dasar perairannya yang lebih dari 8 ha pada kedalaman antara 10–20 meter, keempat wilayah tersebut secara ekonomis bisa dimanfaatkan untuk pengembangan terumbu buatan. Sebagian wilayah perairan Kepulauan Seribu merupakan perairan karang. Oleh karena itu, dasarnya terdiri dari pasir bercampur pecahan karang. Keadaan tersebut terdapat pada keempat lokasi pengamatan dengan dasar perairan terdiri dari pasir halus pasir kasar dan pecahan karang. Adanya pecahan karang menunjukkan bahwa pada lokasi pengamatan pernah terjadi penangkapan ikan dengan bahan 18 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta peledak. Dengan demikian, lokasi pengembangan terumbu buatan secara ekonomis layak dilakukan di perairan Pulau Kotok Kecil, Gosong Air, Pulau Genteng, dan Pulau Harapan. 6. Kondisi Oseanografi Pengamatan oseanografi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor oseanografi mendukung perkembangan Daerah Pelindungan Laut (DPL) melalui pengembangan terumbu buatan dan transplantasi karang di perairan Kepulauan Seribu. Parameter oseanografi yang diamati meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH, senyawa nitrat, nitrit, fosfat, bahan organik, total arus, dan kecerahan air. Selain di daerah terumbu karang, sampling oseanografi dilakukan juga pada lokasi yang pernah dilakukan restoking teripang. 6.1. Oksigen Terlarut Berdasarkan Pengamatan yang dilakukan April 2007 di perairan Kepulauan Seribu Utara menyatakan bahwa konsentrasi oksigen terlarut di permukaan perairan berkisar 2,55 – 4,25 ml/l dan di dasar perairan berkisar 3,64–4,19 ml/l. Konsentrasi oksigen terlarut tertinggi terdapat di stasiun pengamatan Pulau Pamegaran yang merupakan lokasi restoking teripang, sedangkan konsentrasi oksigen terlarut terendah terdapat pada lokasi pengamatan barat daya Pulau Pramuka yang merupakan daerah padat penduduk. Konsentrasi oksigen terlarut di dalam air laut tergantung pada kedalaman dan temperatur. Pada temperatur yang tinggi, kelarutan oksigen di dalam air laut menjadi rendah. Penurunan konsentrasi oksigen terlarut mungkin juga disebabkan penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Pada umumnya konsentrasi oksigen lebih rendah pada perairan yang lebih tercemar. Pengamatan pada Juli 2007 di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan menyatakan bahwa konsentrasi oksigen terlarut berkisar 3,57– 5,78 ml/l, konsentrasi tertinggi di perairan Pulau Tidung dan terendah di perairan Goba Pulau Tikus. Konsentrasi oksigen terlarut di perairan Kepulauan Seribu utara dan Kepulauan Seribu Selatan masih dapat mendukung untuk kehidupan biota karang. 19 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 6.2. Salinitas Salinitas di perairan Kepulauan Seribu utara pada bulan April 2007 berkisar 32 o/oo–32,5o/oo di permukaan dan dasar perairan pada kisaran 32o/ . Perbedaan nilai salinitas tersebut relatif rendah sehingga bisa dikatakan oo homogen. Kondisi ini disebabkan oleh semua daerah pengamatan jauh dari sumber air tawar (tidak ada muara sungai). Suhu air yang hampir sama juga menyebabkan laju evaporasi relatif sama. Demikian juga dengan nilai salinitas di perairan Kepulauan Seribu Selatan yang diamati pada bulan Juli 2007 berada pada kisaran yang hampir sama yaitu antara 32,5o/ –33,0o/oo. oo 6.3. Suhu Suhu sangat berperan dalam mengendalikan ekosistem akuatik karena perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap proses fisika kimia maupun biologi perairan (Effendi 2003). Suhu permukaan di perairan Kepulauan Seribu utara pada bulan April 2007 berkisar 29,5oC–30oC dan di dasar perairan berkisar 30oC. Seperti kondisi salinitas perairan, perbedaaan suhu juga relatif kecil sehingga dapat dikatakan homogen. Suhu di perairan Kepulauan Seribu selatan pada bulan Juli 2007 berkisar 29oC–30oC. 6.4. Kecerahan Kecerahan perairan di Kepulauan Seribu utara pada kedalaman 18– 45 m mencapai dasar perairan, sedangkan pada kedalaman 8,8–20,4 m berkisar 2–10 m. Kecerahan terendah terdapat di perairan Pulau Pamegaran yang disebabkan tingginya partikel terlarut. Daerah ini merupakan daerah yang dangkal dengan dasar pasir berlumpur sehingga sangat mudah terjadi pengadukan. Perairan ini sangat cocok untuk kehidupan biota teripang. Sedangkan untuk kehidupan biota karang membutuhkan perairan yang relatif cerah untuk proses fotosintesa. Kecerahan di perairan Kepulauan Seribu Selatan berkisar 7,5–13,5 m untuk kedalaman perairan 10–40 m. 6.5. pH pH perairan Kepulauan Seribu utara pada umumnya bersifat netralbasa yaitu pada kisaran 7,8–8,0 sehingga bisa dikatakan homogen. Pengamatan di perairan Kepulauan Seribu selatan mempunyai kisaran hampir sama yaitu antara 7,58–7,77. Biota air umumnya sensitif terhadap perubahan pH dan lebih menyukai perairan dengan pH antara 7– 8,5. 20 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta 6.6. Konduktivitas Konduktivitas di lokasi penelitian berkisar 3,12–5,05 dengan nilai tertinggi terdapat di perairan Gosong Pramuka. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya garam-garam terlarut yang terionisasi, yang ditandai oleh nilai salinitas yang mencapai 32o/oo. Ion Cl- merupakan penyusun utama dari salinitas yaitu 55,25% sehingga semakin tinggi nilai salinitas, semakin tinggi pula nilai konduktivitasnya. 6.7. Nitrat (N-NO3) Nitrat merupakan bentuk utama dari nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan alga dan tanaman. Nitrat mempunyai sifat mudah larut dalam air dan stabil. Senyawa ini dihasilkan oleh proses oksidasi sempurna nitrogen. Konsentrasi nitrat di lokasi penelitian di Kepulauan Seribu utara berkisar 0,198–0,846 mg/l. Konsentrasi nitrat tertinggi terdapat di perairan Wak Rom yang mungkin berasal dari dekomposisi bahan organik dari karang yang telah mati. Konsentrasi nitrat sangat tinggi di perairan Kepulauan Seribu selatan yang relatif lebih dekat dengan Teluk Jakarta yaitu berkisar 0,4–2,4 mg/l. Tingginya konsentrasi nitrat tersebut sangat berpengaruh untuk terjadinya ledakan (blooming) plankton. 6.8. Nitrit (N-NO2) Nitrit di perairan alami ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan nitrat. Hal ini dikarenakan nitrit merupakan bentuk peralihan antara nitrat dan ammonia sehingga mempunyai sifat yang tidak stabil dengan adanya oksigen. Konsentrasi nitrit yang lebih dari 0,05 mg/l dapat bersifat toksin bagi biota air. Konsentrasi nitrit di perairan Kepulauan Seribu utara berkisar 0,001–0,018 mg/l dengan rata- rata 0,007 mg/l dan tertinggi terdapat pada perairan Opak Kecil dan barat daya Pulau Pramuka yang mungkin berasal dari dekomposisi bahan organik dari karang yang telah mati. Konsentrasi nitrit di perairan Kepulauan Seribu selatan relatif lebih tinggi yaitu berkisar 0,006–0,039 mg/l. 6.9. Fosfat (P-PO4) Konsentrasi P-PO4 di Kepulauan Seribu utara berkisar 0,036–0,778 mg/l dengan rata-rata 0,148 mg/l dan tertinggi terdapat di stasiun Kaliage Kecil. Konsentrasi fosfat di perairan Kepulauan Seribu selatan relatif 21 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya lebih rendah yaitu pada kisaran 0,03–0,17 mg/l. Senyawa fosfor mungkin berasal dari perombakan enzimatik berbagai senyawa fosfat dalam sel- sel fitoplankton dan bakteri. 6.10. Bahan Organik Total Keberadaan bahan organik dapat berasal dari alam, yaitu dari pembusukan tanaman dan hewan ataupun dari aktivitas manusia, misalnya dari aktivitas pemeliharaan ikan di Keramba Jaring Apung. Konsentrasi bahan organik di perairan Kepulauan Seribu berkisar 3,037–5,182 mg/l dan tertinggi terdapat di daerah barat daya Pulau Pramuka. Hal ini mungkin disebabkan oleh pembusukan hewan-hewan yang telah mati. 6.11. Arus Kecepatan dan arah arus akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan lokasi, baik untuk pengembangan terumbu buatan maupun transplantasi karang dalam upaya rehabilitasi habitat. Kecepatan arus yang disyaratkan adalah tidak lebih dari 30 cm/detik. Pada waktu pengamatan, kecepatan arus di perairan Kepulauan Seribu berkisar 1,6–8 cm/detik. 6.12. Plankton Kelimpahan plankton dan komposisi genera di perairan Kepulauan Seribu terdiri dari 10 kelas yaitu: Bacillariophyceae (17 genera), Chloropeceae (1 genera), Dinophyceae (3 genera), Rotatoria (1 genera), Crustacea (8 genera), Ciliata (1 genera), Sarcodina (3 genera), Sagittoidea (1 genera), Hydrozoa (1 genera), dan Bivalvia (1 genera). Jumlah individu tertinggi di jumpai pada perairan Pulau Tidung dengan kelimpahan 41 x104 indv/m3. Kelimpahan tertinggi ini di dominasi oleh genera bacillariopecheae. Bacillariophyceae adalah salah satu jenis genus yang sering di jumpai melimpah baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada berbagai tipe perairan sungai, baik sebagai plankton maupun sebagai perifiton. Menurut Sachlan (1982), Bacillariophyceae adalah salah satu genus yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap kondisi ekstrem, mudah beradaptasi, dan mempunyai daya reproduksi yang tinggi sehingga rekruitmentnya juga tinggi. Sedangkan kelimpahan terendah terdapat pada perairan Pulau Pari dengan kelimpahan 2,3 x 104 indv/m3. 22 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta 7. Kelimpahan Stok Ikan Karang Data sampling hasil tangkapan dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk indeks kelimpahan stok atau hasil tangkapan per unit upaya. Data yang diperoleh tersebut baru merupakan satu titik. Dengan menggabungkan data dari sumber lain diharapkan dapat diperoleh gambaran dan perbandingan tentang besarnya indeks kelimpahan stok pada saat ini. Untuk melengkapi data indeks kelimpahan stok juga dilakukan pengamatan komunitas ikan karang secara langsung (sensus visual) dengan metode transek garis pada wilayah perairan terumbu karang dan terumbu buatan. 7.1. Kelimpahan Hasil Tangkapan Data hasil tangkapan nelayan diperoleh dari Balai Riset Perikanan Laut yang secara bersamaan mempunyai kegiatan riset di perairan Kepulauan Seribu. Data yang diacu adalah data hasil tangkapan dengan bubu dan Muroami yang penangkapannya dilakukan di perairan karang. Kelimpahan dan komposisi hasil tangkapan bubu yang didaratkan di Pulau Panggang dan Pulau Kelapa disajikan pada Tabel 11 dan 12. Hasil tangkapan per unit upaya bubu yang didaratkan di Pulau Panggang adalah 13,3 kg/kapal/trip/hari didominasi oleh ikan nuri (Choerodon anchorago). Hasil tangkapan yang didaratkan di Pulau Kelapa relatif sedikit yaitu 38 kg/kapal/trip/hari didominasi oleh ikan kerapu sunu halus (Plectropomus leopardus) yang bernilai ekonomis tinggi. Tabel 11.Komposisi ikan hasil tangkapan bubu yang didaratkan di Pulau Panggang bulan Maret 2007 No Jenis Ikan Jumlah (Ekor) (%) Berat (kg) (%) 1 Ekor kuning (Caesio cuning) 14 8,48 1.260 9,47 2 Nuri (Choerodon anchorago) 130 78,79 9.100 68,42 3 Pasir-pasir (Scolopsis margaritifer) 15 9,09 2.400 18,05 4 Kerapu minyak (Epinephelus ongus) 2 1,21 165 1,24 5 Kakatua (Scarus ghobban) 1 0,61 145 1,09 6 Kakatua (Scarus sp.) 2 1,21 140 1,05 7 Kurisi (Pentapodus sp.) Jumlah 1 0,61 90 0,68 165 100,00 13.300 100,00 23 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 12.Komposisi ikan hasil tangkapan bubu yang didaratkan di Pulau Kelapa, Maret 2007 No 1 2 Jenis Ikan Kerapu sunu halus (Plectopomus Leopardus) Kerapu minyak (Epinephelus ongus) Jumlah Jumlah (Ekor) (%) Berat (kg) (%) 11 64,71 2.300 60,53 6 35,29 1.500 39,47 17 100,00 3.800 100,00 Muroami merupakan alat tangkap yang produktif untuk ikan karang sehingga dapat menggambarkan kelimpahan stok ikan karang lebih akurat. Hasil tangkapan muroami di perairan Kepulauan Seribu relatif lebih tinggi daripada alat tangkap lainnya. Hasil tangkapan kapal muroami dengan 3 kali setting pada bulan Maret 2007 sebesar 100 kg/kapal/hari. Komposisi jenis ikan dari sampel sebanyak 70% seluruh hasil tangkapan berdasarkan jumlah dan beratnya didominasi oleh ikan ekor kuning (Caesio cuning) sebesar 45,7% dan 76,9% serta pisang-pisang (Pterocaesio digramma) masing-masing 36,7% dan 13,7%. Data komposisi ikan hasil tangkapan kapal muroami yang didaratkan di Pulau Pramuka disajikan pada Tabel 13. Hasil tangkapan yang diperoleh dari trip babangan (hari) pada bulan Januari–Maret rata-rata mencapai 500 kg/kapal/trip/minggu. Demikian juga dengan yang didaratkan di Pulau Tidung, hasil tangkapan diperoleh pada kisaran 100–700 kg/kapal/trip/minggu. Kelimpahan dan komposisi hasil tangkapan muroami yang dilakukan secara babangan dan didaratkan di Pulau Tidung pada bulan Mei 2007 disajikan pada Tabel 14. Dari Tabel 13 dan 14 terlihat bahwa ekor kuning adalah jenis yang mendominasi hasil tangkapan muroami di perairan Kepulauan Seribu. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir jenis ekor kuning sempat menghilang atau over fishing dari perairan Kepulauan Seribu. Dengan demikian, upaya rehabilitasi yang dilakukan sementara ini berdampak nyata terhadap pemulihan stok sumber daya ikan. 24 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta Tabel 13.Komposisi ikan hasil tangkapan muroami di perairan Kepulauan Seribu bulan Maret 2007. No Jenis Ikan 1 2 Ekor kuning (Caesio cuning) Pisang-pisang (Pterocaesio diagramma) Beronang susu (Siganus canaliculatus) Alu-alu (Sphyraena forsteri) Kakap batu Kakatua (Scarus sp.) Romon-romon Cumi-cumi (Loligo sp.) Jumlah 3 4 5 6 7 8 Jumlah (Ekor) 623 500 45,7 36,7 Berat (kg) 56.000 10.000 76,9 13,7 2 0,2 150 0,2 112 1 5 7 112 1362 8,2 0,1 0,4 0,5 8,2 100,00 5.000 265 600 395 400 72.810 6,8 0,4 0,8 0,5 0,5 100,00 (%) (%) Tabel 14.Kelimpahan dan komposisi ikan hasil tangkapan muroami yang dioperasikan secara babangan dan didaratkan di Pulau Tidung No Tanggal 1 08/01/2007 2 10/01/2007 3 4 5 Komoditas ikan Hasil tangkapan (kg) Total Hasil Tangkapan (kg) Ekor kuning (Caesio cuning) 210 Gebel (Platax batavianus) 172 Ekor kuning (Caesio cuning) 367 Kerapu lodi (Plectopomuleopardus) 30 16/01/2007 Ekor kuning (Caesio cuning) 219 219 17/01/2007 Ekor kuning (Caesio cuning) 100 100 Ekor kuning (Caesio cuning) 245 Kuwe 25 Kerapu lodi (Plectopomuleopardus) 12 20/01/2007 382 397 282 25 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 14.Kelimpahan dan komposisi ikan hasil tangkapan muroami yang dioperasikan secara babangan dan didaratkan di Pulau Tidung (lanjutan) No Tanggal 6 29/01/2007 7 04/02/2007 8 07/02/2007 Komoditas ikan Hasil tangkapan (kg) Ekor kuning (Caesio cuning) 93 Kerapu lodi (Plectopomuleopardus) 53 Ekor kuning (Caesio cuning) 149 Kerapu lodi (Plectopomuleopardus) 09 Ekor kuning (Caesio cuning) 242 Kerapu lodi (Plectopomuleopardus) 11 Bulat (Carangoides bajad) 12 Total Hasil Tangkapan (kg) 146 158 265 9 08/02/2007 Ekor kuning (Caesio cuning) 203 203 10 12/02/2007 Ekor kuning (Caesio cuning) 282 282 11 20/02/2007 Ekor kuning (Caesio cuning) 750 Kerapu lodi (Plectopomuleopardus) 76 12 25/02/2007 Ekor kuning (Caesio cuning) 208 826 208 Total 3.468 Rata-rata 289 7.2. Komunitas Ikan Karang Secara keseluruhan ikan karang yang teramati dari 9 stasiun (titik penyelaman) di perairan Kepulauan Seribu utara terdiri dari 18 Famili. Famili-famili ikan karang untuk kelompok ikan mayor yang ditemukan berjumlah 8 famili yaitu Apogonidae, Malacanthidae, Pomacanthidae, Synodontidae, Gobiidae, Labridae, Pinguipedidae, dan Pomacentridae. Ikan target yang ditemukan sebanyak 9 famili yaitu Caesionidae, Lethrinidae, Lutjanidae, Mullidae, Nemipteridae, Scaridae, Serranidae, Dasyatididae, dan Ephippidae. Sedangkan ikan indikator dari famili Chaetodontidae ditemukan sebanyak 6 spesies yaitu Chaetodon kleinii, Chaetodon oxycephalus, Coradion melanopus, Heniochus diphreutes, Parachaetodon ocellatus, dan Heniochus monoceros. Famili Chaetodontidae yang mengindikasikan kesehatan karang banyak dijumpai di perairan 26 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta timur Gosong Pramuka, selatan Gosong Pramuka, terumbu buatan di barat daya Pulau Pramuka, dan DPL Kaliage Kecil Pulau Kelapa. Hasil pengamatan kondisi terumbu karang juga menunjukkan bahwa persentase penutupan karang batu keempat perairan tersebut pada kategori baik. Ikan target dominan dan bernilai ekonomis adalah ekor kuning (Caesio cuning). Beberapa ikan target yang teridentifikasi juga bernilai ekonomis tinggi yaitu kelompok ikan kerapu (Famili Serranidae) seperti Chromileptes altivelis, Ephinephelus fasciatus, dan Ephinephelus fuscogutatus. Jumlah ikan terbanyak yang ditemukan selama pengamatan yaitu famili Pomacentridae (45%) dan Labridae (14%) dari kelompok ikan mayor dan famili Nemipteridae (10%) dari kelompok ikan target. Jumlah jenis ikan terbanyak ditemukan di ekosistem terumbu buatan barat daya Pulau Pramuka. Hal ini mungkin disebabkan oleh struktur terumbu buatan yang berbentuk piramida dan terdapat banyak rongga serta sudah tumbuhnya biota penempel sehingga dapat digunakan sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Berbeda dengan kondisi terumbu buatan di Pulau Semak Daun yang berbentuk kubah dengan rongga yang berdiameter kecil dan kehadiran biota penempel sangat rendah menyebabkan jumlah jenis ikan karang yang ditemukan sangat sedikit. Faktor kedalaman lokasi penempatan terumbu buatan (antara 20–25 m) dan tipe substrat dasar perairan pasir berlumpur menyebabkan ekosistem terumbu buatan tidak berkembang. Kegiatan monitoring juga dilakukan di utara Gosong Pulau Pramuka untuk memantau kondisi biota karang dan ikan karang pada ekosistem terumbu buatan dan daerah transplantasi karang yang sudah berumur 2 tahun. Terlihat bahwa biota karang pada transplantasi yang teramati belum dapat tumbuh secara optimal. Begitu pula dengan keberadaan ikan karang yang terpantau dalam jumlah yang sedikit. Sangat berbeda dengan kondisi kelimpahan ikan karang pada terumbu karang alami di timur dan selatan Gosong Pramuka yang berada tidak jauh dari lokasi terumbu buatan dan transplantasi karang relatif lebih banyak. Penetapan Gosong Pulau Pramuka sebagai Daerah Perlindungan Laut (DPL) berdampak positif, di mana aktivitas penangkapan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang alami dapat dicegah. Minimnya ikan karang pada lokasi terumbu buatan disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan lokasi. 27 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Jenis ikan yang teridentfikasi pada seluruh lokasi pengamatan adalah 61 jenis. Jumlah jenis terbanyak ditemukan di barat daya Pulau Pramuka yaitu sebanyak 39 jenis. Kemudian untuk DPL Kaliage Kecil, selatan Gosong Pramuka, dan DPL Karang Wak Rom berturut-turut memiliki jumlah jenis 27,26, dan 24. Jenis ikan relatif sedikit di perairan lainnya, seperti di timur Gosong Pramuka dan Pulau Opak Kecil masing-masing sebanyak 17 jenis. Famili Pomacentridae sebagai populasi terbanyak dan terdiri dari jumlah jenis yang paling banyak yaitu 13 jenis, hampir 25% dari seluruh jenis yang teridentifikasi. Keberadaan famili Pomacentridae sebagai ikan herbivor grazer pemakan alga tentunya menguntungkan dari segi ekologis. Ikan herbivor berperan dalam tiga proses penting di terumbu karang yaitu: (1) sebagai penyambung aliran energi dari produsen ke konsumen lainnya, (2) menentukan distribusi dan komposisi kelompok tumbuhan dalam lingkungan terumbu karang dengan proses grazing, tidak hanya pola distribusi dan ukurannya, tetapi juga rerata produksi dan komposisi internalnya sehingga membantu karang dalam persaingan mempertahankan ruangnya, dan (3) adalah interaksi antarikan herbivor sendiri dalam hal teritori yang telah digunakan sebagai dasar dalam penelitian mengenai demografi dan tingkah laku ikan karang secara umum (Sale 1980 dan Choat 1991). Kelimpahan jenis ikan karang di setiap lokasi pengamatan disajikan pada Gambar 1. Hasil sensus visual menunjukkan kelimpahan ikan di perairan karang Kepulauan Seribu utara berkisar 1–3 ind/m2. Kelimpahan yang relatif tinggi terdapat di perairan DPL Wak Rom, Pulau Kelapa, dan terumbu buatan barat daya Pulau Pramuka yaitu 3 ind/m2. Kelimpahan yang relatif rendah terdapat di perairan terumbu buatan Semak Daun, terumbu buatan utara Gosong Pramuka, dan transplatasi karang utara Gosong Pramuka yaitu 0–1 ind/m2. Kondisi tersebut disebabkan jumlah biota karang/penempel pada ketiga perairan sangat rendah. Untuk itu harus dipertimbangkan secara matang lokasi yang akan digunakan sebagai rekayasa habitat. Kelimpahan ikan karang pada setiap stasiun pengamatan di Kepulauan Seribu utara disajikan pada Tabel 15. 28 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta 40 1.Timur Gosong Pramuka 2. Selatan Gosong Pramuka 3. APL Karang Wak Rom 4. APL Kaliage Kecil 5. Pulau Opak Kecil 6. Pulau Semak Daun 7. Barat Daya Pulau Pramuka (terumbu buatan) 8. Utara Gosong Pramuka (terumbu karang buatan) 9. Utara Gosong Pramuka (karang transplantasi) 35 Ju m lah Jen is 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gambar 1.Jumlah jenis ikan karang pada 9 lokasi pengamatan di Kepulauan Seribu, April 2007 Tabel 15.Kelimpahan ikan karang di perairan Kepulauan Seribu utara pada bulan Maret 2008. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stasiun Pengamatan DPL Timur Gosong Pramuka DPL Selatan Gosong Pramuka DPL Karang Wak Rom DPL Kaliage Kecil Pulau Opak Kecil Pulau Semak Daun (TB) Barat Daya P. Pramuka (TB) Utara Gosong Pramuka (TB) Utara Gosong Pramuka (TK) Kelimpahan (ind/m2) 1,51 1,95 2,92 2,17 1,03 0,28 3,24 0,23 0,19 Analisis komunitas ikan karang menunjukkan nilai indeks keanekaragaman berkisar 1,9 hingga 3,2. Nilai tertinggi berada pada ekosistem terumbu buatan barat daya Pulau Pramuka dengan kondisi terumbu buatan tidak beraturan. Susunan teratas piramida banyak yang sudah terpisah, namun menguntungkan karena jumlah terumbu buatan relatif banyak. Keanekaragaman terendah terdapat di stasiun transplantasi 29 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya karang utara Gosong Pramuka. Terlihat bahwa perkembangan ekosistem pada transplantasi karang kurang optimal sehingga kurang berfungsi secara ekologis bagi ikan karang. Stasiun pengamatan lainnya menunjukkan indeks keanekaragaman nilai lebih dari 2 bahkan pada beberapa lokasi mendekati 3. Nilai indeks keseragaman menunjukkan kisaran yang relatif sempit yaitu antara 0,858 hingga 0,958. Nilai indeks keseragaman yang mendekati 1 mengindikasikan komunitas ikan karang dalam kondisi stabil. Tingginya indeks keseragaman juga ditunjukkan dengan rendahnya indeks dominansi antarspesies sangat rendah yaitu berkisar 0,055 hingga 0,163. Pengamatan di perairan Kepulauan Seribu selatan dilakukan pada 4 stasiun pengamatan yaitu DPL utara Pulau Tidung, perairan selatan Pulau Payung, DPL selatan Pulau Pari, dan Goba Pulau Tikus. Hasil pengamatan menunjukkan ikan karang yang teridentifikasi terdiri dari 14 famili. Kelompok ikan mayor sebanyak 6 famili yaitu Apogonidae, Malacanthidae, Pomacanthidae Synodontidae, Labridae, dan Pomacentridae. Kelompok ikan target sebanyak 7 famili yaitu Caesionidae, Lethrinidae, Lutjanidae, Mullidae, Nemipteridae, Scaridae, dan Serranidae. Kemudian kelompok ikan indikator yaitu famili Chaetodontidae ditemukan sebanyak 3 jenis yaitu Chaetodon kleinii, Chaetodon octofasciatus, dan Chaetodon ornatissimus. Jumlah ikan terbanyak yang ditemukan selama pengamatan yaitu dari famili Labridae, Pomacentridae, dan Caesionidae. Ikan yang teridentifikasi dari keseluruhan pengamatan terdiri dari 44 jenis. Jenis ikan terbanyak ditemukan di DPL selatan Pulau Pari (35) dan terendah di perairan Goba Pulau Tikus (15). Kelimpahan ikan berada pada kisaran 0,43 ind/m2–2,65 ind/m2 . Sesuai dengan dengan kelimpahan jenisnya, jumlah individu ikan terbanyak dijumpai di DPL selatan Pulau Pari dan terendah di Goba Pulau Tikus. (1) Utara Pulau Tidung 30 Berdasarkan hasil sensus visual pada terumbu karang di daerah perlindungan laut utara Pulau Tidung dengan kedalaman 5–7 meter teridentifikasi 17 jenis ikan, 8 jenis di antaranya merupakan famili Pomacentridae, 4 jenis dari famili Labridae, dan 5 jenis lainnya merupakan famili Malacanthidae, Caesionidae, Lutjanidae, Nemipteridae, dan Chaetodontidae. Pomacentridae dan Labridae Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta sebagai famili dengan jumlah populasi paling banyak dan termasuk dalam katagori ikan mayor. Katagori ikan mayor dijumpai sebanyak 69,29%, ikan target 25,98%, dan ikan indikator sebanyak 4,72%. Kelimpahan total diperoleh sebesar 0,85 ekor/m2. Indeks keanekaragaman sebesar 2,69, indeks keseragaman sebesar 0,95, dan indeks dominansi spesies sebesar 0,08. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunitas ikan karang di perairan utara Pulau Tidung berada dalam kondisi mendekati stabil. Hal ini juga didukung oleh persentase tutupan karang hidup sebesar 68,5 % dengan katagori baik sehingga dapat memberikan fungsi ekologis bagi ikan karang. (2) Selatan Pulau Payung Pengamatan komunitas ikan di terumbu karang selatan Pulau Payung teridentifikasi 18 jenis dengan kelimpahan total sebesar 2,29 individu/ m2. Famili Labridae termasuk dalam kelompoki ikan mayor ditemukan dengan populasi terbesar. Kelompok ikan mayor dijumpai sebanyak 76,45%, kelompok ikan target 17,73%, dan kelompok ikan indikator sebanyak 5,81%. Spesies Halichoeres, purpurescens, Halichoeres, melapterus, Apogon victoriae, dan Caesio cuning merupakan jenis yang banyak dijumpai. Hasil analisis struktur komunitas ikan menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman 2,52, indeks keseragaman 0,87, dan indeks dominansi 0,10. Telah disampaikan pada subbab sebelumnya bahwa persentase tutupan karang batu di selatan Pulau Payung pada kategori sedang mendekati baik, yaitu pada kisaran nilai 40%. (3) Selatan Pulau Pari Hasil pengamatan di Selatan Pulau Pari teridentifikasi 35 jenis dengan kelimpahan 2,65 individu/m2. Indeks keanekaragaman 2,69, indeks keseragaman 0,75, dan indeks dominansi 0,12. Gugusan Pulau Pari merupakan daerah perlindungan laut, meliputi Pulau Pari, Pulau Kongsi, Pulau Tengah, Pulau Tikus, dan Pulau Dua sehingga jalur migrasi ikan umumnya tidak terlalu jauh dan akan lebih memilih untuk menetap pada habitatnya. Persentase tutupan karang batu pada kategori baik atau lebih dari 50%. Dari data tersebut diketahui bahwa Pomacentridae dan Labridae adalah famili dengan populasi terbesar. Sedangkan Caesio cuning merupakan jenis ikan target yang dominan. 31 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Ikan mayor dijumpai sebanyak 75,57%, ikan target 19,40%, dan ikan indikator sebanyak 5,04%. Spesies Amphiprion ocellaris dan Amphiprion perideraion termasuk dalam kategori ikan mayor. Spesies ini merupakan ikan hias yang sangat menyukai anemon laut sebagai habitatnya, namun akhir-akhir ini populasinya semakin menurun. Di antara ikan target yang teridentifikasi di selatan Pulau Pari terdapat jenis yang bernilai ekonomis dan dominan yaitu ikan ekor kuning (Caesio cuning) dan ekonomis tinggi seperti kelompok ikan kerapu (Famili Serranidae) antara lain Cephalopolis boenack dan Ephinephelus fuscogutatus. Kelompok ikan kerapu tersebut hanya ditemukan dalam jumlah yang relatif rendah. Biota non ikan yang dijumpai di antaranya adalah sotong atau Sephia sp. Daerah perlindungan laut yang dimaksud adalah daerah yang ditutup secara permanen di mana semua kegiatan ekstraktif manusia dilarang terutama menangkap ikan dengan tujuan akhir untuk melestarikan sumber daya pesisir dan laut. Daerah perlindungan laut tersebut sudah diterapkan di beberapa wilayah perairan dan direncanakan akan ada di setiap kelurahan. Kesimpulan Rehablitasi habitat dalam upaya memulihkan ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu dilakukan melalui kegiatan pengembangan terumbu buatan, transplantasi karang, dan penetapan daerah perlindungan laut. Penetapan daerah perlindungan laut berdampak terhadap kondisi kesehatan terumbu karang pada kategori baik dan peningkatan stok ikan seperti pulihnya jenis ikan hias ekonomis tinggi yang populasinya sudah mulai menurun di Kepulauan Seribu (seperti Amphiprion sp.). Selain itu, kembali melimpahnya ikan konsumsi ekonomis penting seperti ekor kuning (Caesio cuning). Tidak demikian halnya dari hasil evaluasi kegiatan rehabilitasi habitat melalui pengambangan terumbu buatan dan transplantasi karang menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan. Pengamatan pada lokasi transplantasi karang menunjukkan bahwa sebagian besar transplan terlepas dari substratnya dan tidak berkembang. Demikian juga dengan pengembangan terumbu buatan dari beberapa lokasi yang diamati hanya di perairan barat daya Pulau Pramuka 32 Keragaan Rehabilitasi Terumbu Karang, Kondisi Oseanografi dan Sumber Daya Ikan Karang di Kepulauan Seribu-Teluk Jakarta yang dapat berkembang dengan baik. Dari identifikasi habitat dapat direkomendasikan bahwa rehabilitasi kerusakan karang dengan rekayasa habitat melalui pengembangan terumbu buatan dapat dilakukan di perairan Pulau Kotok Kecil, Gosong Air, Genteng, dan Pulau Harapan. Rekomendasi Berdasarkan evaluasi terhadap rehabilitasi habitat yang sudah dilakukan di perairan kepulauan Seribu dan identifikasi habitat yang dilakukan pada beberapa wilayah perairan, dapat direkomendasikan bahwa rehabilitasi kerusakan terumbu karang untuk meningkatkan daya dukung perairan dapat dilakukan di perairan Pulau Kotok Kecil, Gosong Air, Pulau Genteng, dan Pulau Harapan melalui rekayasa habitat dengan pengembangan terumbu buatan. Daftar Pustaka English SC Wilkinson and V Baker. 1994. Survey Manual for Tropical Marine Resources. Australian Institute of Marine Science. Townsville. Australia. Kuiter RH. 1992. Tropical reef-fishes of the Western Pacific Inonesa and Adjacent Waters. Jakarta: Gramedia. KPP-COREMAP. 2001. Buku panduan pengelolaan berbasis masyarakat (PBM)-COREMAP. COREMAP- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Lieske E and R Myers. 1997. Reef fishes of the World. Jakarta Indonesia: Periplus Edition. Ludwig JA and JF Reynolds. 1988. Statistical ecology. A primer on methods and computing. New York: Jhon Wiley and Son. Nontji A. 2000. Coral reefs of Indonesia. Prosiding Lokakarya Pengelolaan dan Iptek Terumbu Karang Indonesia. LIPI- COREMAP. Jakarta. Rahmat dan Yosephine. 2001. Software Percent Cover Benthic Lifeform Versi 5.1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi. LIPI. Jakarta. 33 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Romimohtarto K dan S Juwana. 2005. Biologi Laut. Ilmu Pengetahuan tentang biologi laut. Cetakan ke 2. Jakarta: Djambatan. Suharsono. 1996. Jenis-jenis karang yang umum dijumpai di Perairan Indonesia. Laporan Penelitian. Proyek Penelitian dan Pengembangan Daerah Pantai LIPI. Sukarno Hutomo M. Moosa M.K. & DarsonoP. 1983. Terumbu Karang di Indonesia; Sumber daya Veron JEN. 1986. Corals of Australia and The Indo-Pasific. Honolulu: Univ. of Hawaii Press. Wasilun K dan Suprapto. 1991. Study on coral rehabilitation techniques. The Project Report CRIFI Jakarta. Sachlan M. 1982. Planktonologi. Fakultas Peternakan dan Perikanan. Edwards A dan E Gomez. 2007. Konsep & Panduan Restorasi Terumbu: Memilih pilihan bijak di antara ketidakpastian. Coral Reef. Targeted Research & Capacity Building for Management. Suku Dinas Kelautan dan Pertanian. 2011. Program Budidaya dan Rehabilitasi Ekosistem Laut Kepulauan Seribu – DKI Jakarta. 34 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya *) Khairul Amri1) dan Samsul B. Agus2) Peneliti pada Pusat Penelitian Pengembangan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan, Ancol 2) Pengajar pada Dept. Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bogor *) Bagian dari Penelitian Kajian Potensi Sumber Daya Pertanian dan Kelautan, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2010 1) Abstrak Sebagian besar masyarakat Kepulauan Seribu yang berprofesi sebagai nelayan, secara langsung maupun tidak langsung, menggantungkan hidupnya pada keberadaan ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang memiliki peran penting mengingat fungsi ekologisnya sebagai habitat berbagai jenis biota benthic yang memiliki keterkaitan terhadap keberlangsungan hidup berbagai spesies ikan demersal, khususnya ikan karang, yang menjadi target penangkapan nelayan. Saat ini berbagai tekanan terkait aktivitas manusia seperti penambangan karang dan pasir untuk kebutuhan bahan bangunan serta penangkapan ikan karang menggunakan potas dan bahan peledak, telah merusak sebagian besar dari ekosistem terumbu karang yang ada di perairan ini. Untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang yang sudah terlanjur rusak dan memberikan perlindungan bagi ekosistem terumbu karang yang masih baik, telah dilakukan inisiasi pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Pola DPL yang dikembangkan di Kepulauan Seribu merupakan pola pengembangan berbasis masyarakat. Penelitian yang dilakukan melalui survei langsung ke beberapa lokasi sampel DPL, menunjukkan Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, bergantung pada faktor internal maupun eksternal yang memengaruhinya. Dukungan program lain seperti transplantasi terumbu karang dan penanaman fish shelter dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan upaya pemulihan kondisi terumbu karang di perairan ini. Kata Kunci: terumbu karang, Daerah Perlindungan Laut (DPL), Kepulauan Seribu Pendahuluan Kepulauan Seribu merupakan perairan laut di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup potensial. Perairan ini mencakup area seluas 6.997,5 km2, memiliki 110 pulau dan gosong terumbu karang yang berukuran relatif sangat kecil, 70% di antaranya memiliki luas kurang dari 10 ha. Kehadiran terumbu karang di perairan ini memiliki arti penting bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, karena merupakan daerah penangkapan ikan demersal. Selain itu, daerah tersebut merupakan lokasi aktivitas penambangan karang dan pasir untuk kebutuhan bahan bangunan. Kajian yang dilakukan Terangi (2007) mencatat sebanyak 72% masyarakat Kepulauan Seribu menggantungkan penghidupannya pada ekosistem terumbu karang. Namun di sisi lain, kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di perairan ini, melalui aktivitas penambangan karang dan pasir serta kegiatan penangkapan ikan menggunakan potas dan bahan peledak, telah merusak sebagian besar dari ekosistem terumbu karang yang ada (Suharsono 1998). Berdasarkan inventarisasi Terangi (2007), diketahui bahwa penutupan terumbu karang di Kepulauan Seribu pada tahun 2007 adalah 29%, menurun dari tutupan tahun 2005 yaitu 33,2%. Perusakan terumbu karang ini sudah berlangsung sejak lama, meskipun sebagian besar perairan di kawasan ini sudah dijadikan sebagai kawasan cagar alam di tahun 1970-an hingga kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut di tahun 1980-an. Dampak dari rusaknya ekosistem terumbu karang terlihat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Penurunan hasil tangkapan tidak 36 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya hanya terjadi pada ikan karang (demersal) terutama jenis-jenis kerapu, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil tangkapan ikan pelagis. Selain terjadinya penurunan jumlah hasil tangkapan, juga terjadi penurunan ukuran ikan hasil tangkapan. Secara ekonomi, hal ini berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena sebagian besar masyarakat di wilayah ini sepenuhnya menggantungkan penghidupannya dari produksi perikanan tangkap yang lokasi penangkapan (fishing ground) utamanya berada di perairan sekitar ekosistem terumbu karang. Menyadari pentingnya kelestarian terumbu karang, pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan diyakini tidak bisa hanya didekati dari aspek ekonomi saja. Pengalaman telah membuktikan bahwa pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang hanya dilihat dari aspek ekonomi menimbulkan kerusakan ekosistem yang pada gilirannya telah menyebabkan degradasi sumber daya perikanan yang ditandai dengan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan DKI Jakarta adalah pengembangan pengelolaan sumber daya perikanan dengan pendekatan ekosistem yang berbasis masyarakat melalui pencanangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) untuk melindungi ekosistem terumbu karang. Tujuan utama dari pengembangan DPL ini adalah untuk melindungi suatu ekosistem yang pada akhirnya juga sekaligus untuk sumber daya perikanan yang berasosiasi dengan ekosistem tersebut, seperti sumber daya ikan kerapu, khususnya pada saat mereka melakukan pemijahan hingga pengasuhan. Untuk mengatasi dan mencegah kerusakan lebih jauh terhadap kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Suku Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu sejak tahun 2004 telah menginisiasi program rehabilitasi sumber daya laut di Kepulauan Seribu melalui aktivitas penenggelaman terumbu buatan (fish shelter). Tulisan ini memaparkan hasil penelitian mengenai daerah perlindungan laut di Kepulauan Seribu sebagai upaya melestarikan ekosistem terumbu karang yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan dan kelestarian sumber daya ikan. 37 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Metodologi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data hasil survei lapangan di lokasi penelitian. Sementara data sekunder merupakan data pendukung terdiri dari peta dan citra satelit serta data pendukung terkait lainnya. Survei lapangan di lakukan pada bulan Maret–April (mewakili musim peralihan) dan Mei (mewakili musim timur) tahun 2010. Analisa data hasil penelitian dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi ekosistem terumbu karang dan perairan sekitar DPL. Perolehan data kondisi ekosistem terumbu karang dan substrat lain melalui survei lapangan di ekosistem terumbu karang, dilakukan dengan metode transek garis menyinggung (Line Intercept Transect), yang dimodifikasi dari English et al. (1997). Metode ini digunakan untuk mengestimasi penutupan karang hidup ataupun mati. Pada tiap stasiun, transek garis dengan menggunakan roll meter dibentangkan sepanjang 3x10 m yang diletakkan sejajar garis pantai mengikuti kontur kedalaman. Pengamatan dilakukan pada kedalaman antara 3 meter sampai 10 meter, sebagai perwakilan kondisi ekosistem terumbu karang dangkal sampai yang lebih dalam. Pengamatan dilakukan dengan cara mencatat dan mengukur kisaran penutupan bentuk pertumbuhan (lifeform) karang hidup, karang mati, biota lain, dan komponen abiotik lain yang ditentukan menyinggung di sepanjang transek garis. Pencatatan dilakukan dengan “sabak” bawah air dan pensil. Komposisi habitat terumbu karang yang diamati digolongkan berdasarkan komponen dasar penyusun ekosistem terumbu karang berdasarkan lifeform karang dan kode yang digunakan (English et al. 1997). Metode Rapid Reef Assessment (RRA) digunakan untuk mengetahui kelimpahan dan jenis ikan serta persentase tutupan karang hidup, karang mati, dan habitat lainnya seperti pasir, pecahan karang, alga, lamun dan lain-lain. Teknik ini dinilai cukup baik untuk dapat mengestimasi persentase masing-masing kategori bentik dan habitat dalam waktu yang relatif singkat. Waktu pengamatan RRA dibatasi selama 5–10 menit. Di tiap lokasi, 2 orang pengamat akan mengestimasi persen penutupan habitat dan kelimpahan tiap jenis ikan dalam satu ruang imajiner berukuran 10x10 m2. 38 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Hasil dan Pembahasan 1. Lokasi dan Luas Daerah Perlindungan Laut (DPL) Daerah perlindungan laut (DPL) yang dikembangkan untuk tujuan perbaikan dan perlindungan kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu merupakan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat. Kegiatan ini diinisiasi oleh pemerintah daerah yang berupaya mendorong masyarakat untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas ekosistem terumbu karang secara bersama-sama, Upaya ini selain diharapkan dapat memperbaiki dan melestraikan kondisi ekosistem terumbu karang, sekaligus juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya perikanan lainnya yang berasosiasi dengan terumbu karang. Secara lebih spesifik, area/daerah perlindungan laut memberi manfaat: (1) memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat tempat hidup, bertelur, dan memijah biota-biota laut, dan (2) memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat sekitarnya, sehingga terjadi keberlanjutan dan meningkatkan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan, baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari. Daerah Perlindungan Laut (DPL) ini tidak hanya sebagai alat untuk mengupayakan konservasi terhadap sumber daya yang ada, tetapi juga dapat dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya itu sendiri yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dengan ditetapkannya DPL, akan terjadi pembatasan pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada. Salah satu yang dapat dikembangkan yaitu dengan membuat zonasi pemanfaatan sumber daya. Terdapat pada tujuh (7) lokasi yang ditetapkan sebagai DPL di perairan Kepulauan Seribu yang terdata dan teridentifikasi sampai tahun 2010, yaitu DPL Gosong Pramuka (Kelurahan Pulau Panggang), DPL Karang Waroh (Kelurahan Pulau Kelapa), DPL Kaliage Kecil (Kelurahan Pulau Kelapa), DPL Pulau Harapan (Kelurahan Pulau Harapan), DPL Pulau Tidung (Kelurahan Pulau Tidung), serta terdapat 2 site DPL di Pulau Payung (Kelurahan Pulau Pari). Gambar 1 menunjukkan lima lokasi utama DPL dengan total luasan mencapai 122,1 hektare (Tabel 1). 39 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 05.25 05.30 05.35 05.40 05.45 U 05.50 106.25 106.30 106.35 106.40 106.40 106.45BT Gambar 1. Lokasi daerah perlindungan laut di Kepulauan Seribu Daerah perlindungan laut yang melibatkan masyarakat di Kepulauan Seribu pertama kali terbentuk tahun 2004. Dari citra satelit pada Gambar 1 terlihat wilayah DPL ini mencakup area paling selatan, yang terletak di Pulau Pari. Selanjutnya secara berurutan lokasi DPL lainnya yang berada ke arah utara meliputi ekosistem terumbu karang di perairan Pulau Tidung, Pulau Panggang, Pulau Karang Waroh, dan Pulau Harapan. Secara spesifik, luasan DPL pada masing-masing lokasi tersebut tertera pada Tabel 1. 40 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Tabel 1. Luasan daerah perlindungan luat di Kepulauan Seribu No DPL-BM Luas (ha) Tahun Terbentuk 1 Gosong Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang 16 2004 2 Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Harapan 12 2005 3 Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari 12 2005 4 Tidung Besar bagian utara, Kelurahan Pulau Tidung 10 2005 5 Karang Waroh, Kelurahan Pulau Kelapa 7 2006 6 Pulau Kaliage Kecil, Kelurahan Pulau Kelapa 60 2007 7 Pulau Payung, Kelurahan Pulau Tidung 5,1 2007 Total 122, 1 Seperti tertera pada Tabel 1, DPL yang berada di sekitar Pulau Kaliageh Kecil di Kelurahan Pulau Kelapa merupakan yang terbesar dengan luas area mencapai 60 ha. Sementara itu, DPL di perairan Pulau Payung yang berada di Keluruhan Pulau Tidung merupakan yang terkecil dengan luasan hanya sekitar 5 ha. 2. Kondisi DPL Berdasarkan data hasil pemantauan kondisi tutupan karang hidup dan biota benthic yang lakukan pada bulan Mei 2010 di empat lokasi DPL yaitu: DPL Pulau Harapan, Pulau Kelapa (Karang Waroh), Pulau Tidung dan Pulau Pramuka diperoleh kondisi terkini ekosistem terumbu karang dan lingkungan perairan sekitarnya di perairan ini. Pengamatan yang dilakukan pada bulan Mei (permulaan musim timur) menunjukkan tingkat sedimentasi perairan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan musim peralihan (Maret dan April). Adanya sedimentasi yang tinggi ditandai dengan tingkat kekeruhan perairan yang tinggi, diduga sebagai akibat pergerakan massa air dari arah timur yang membawa material terlarut yang cukup pekat dari biasanya. Pada saat monitoring, kondisi perairan (dalam hal ini gelombang laut) relatif tenang. Namun, arus massa air yang membawa material terlarut (sedimen) yang tinggi dari arah timur, menjadikan visibilitas yang rendah (< 20 m). 41 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Prosentase Luasan(%) Hasil pengamatan biota benthic dikelompokkan berdasarkan kondisinya, yaitu berupa kelompok karang keras hidup (HCL/hard coral live), karang lunak (SC/soft coral), dan Others (OT/others), serta abiotik dan alga. Hasil pengamatan ditampilkan pada Gambar 2, yang merupakan persentase penutupan kategori bentik pada ekosistem terumbu karang di DPL yang diamati. Hasilnya pengamatan menunjukkan persentase penutupan karang hidup di keempat DPL yang diamati berada dalam kisaran sedang sampai dengan sangat baik berdasarkan kriteria yang ditetapkan Gomez dan Yap (1988). Dari pengamatan tersebut diketahui tutupan karang hidup tertinggi berada pada DPL Pulau Pramuka dan terendah berada di DPL Pulau Harapan . Sementara itu, penutupan alga justru menunjukkan kondisi sebaliknya, yaitu yang tertinggi ditemukan DPL Pulau Harapan dengan persentase tutupan alga mencapai 40%, sementara penututupan alga yang terendah ditemukan di DPL Pulau Pramuka. Diduga kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan di Pulau Harapan lebih mendukung bagi kehidupan alga di perairan tersebut. Persentase penutupan soft coral, lebih tinggi di DPL yang berada di Pulau Pramuka dan yang terendah ditemukan di DPL Pulau Harapan. Sebaliknya, persentase penutupan akuatik di Pulau Harapan justru lebih tinggi dibandingkan dengan DPL di Pulau Pramuka. Gambar 2. Persentase (%) penutupan kategori bentik terumbu karang pada empat DPL di Kepulauan Seribu 42 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Variabilitas penutupan karang di setiap daerah perlindungan laut selain dipengaruhi oleh kondisi perairan yang berbeda, juga dipengaruhi oleh perbedaan jarak DPL dengan pemukiman pendududuk serta tingkat penjagaan yang dilakukan masyarakat. Dari penelitian ini terlihat, DPL yang lokasinya berada relatif lebih dekat dengan pemukiman penduduk, memiliki tutupan alga yang lebih tinggi di bandingkan dengan DPL yang berada lebih jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa DPL yang lebih dekat dengan pemukiman lebih terlindungi dari perusakan secara fisik oleh pihak luar. Tingkat penjagaan yang lebih baik akibat kesadaran masyarakat yang tinggi bagi kelestarian ekosistem DPL seperti dibangunnya floating buoy untuk bersandar kapal di Pulau Pramuka, sehingga kapal yang bersandar dan membuang sauh tidak merusak terumbu karang di bawahnya, menjadikan DPL di sekitar pulau tersebut memiliki penutupan karang hidup lebih tinggi dibandingkan dengan DPL di lokasi lainnya. Masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan ekosistem yang ada merupakan pelaku yang sangat penting untuk ikut melestarikan sumber daya tersebut. Tingginya penutupan alga di DPL Pulau Harapan diduga berpotensi mengurangi ketersediaan settlement place untuk juvenile karang sehingga jenis dan persentase tutupan akan cenderung stabil untuk beberapa periode waktu mendatang. Walaupun kondisi penutupan karang karena sedimentasi sepenuhnya bergantung pada keadaan alam dan pergerakan gelombang. Manajemen DPL sangat berperan dalam menjaga dan mengurangi tekanan manusia terhadap DPL. Pada saat keadaan tekanan lingkungan meningkat, terumbu karang sebagai sebuah ekosistem dapat merestorasi sistem dan mengembalikannya ke keadaan semula. 43 IndekKeanekaragaman Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Gambar 3. Indeks Keanekaragaman (H`), Keseragaman (E), dan Dominansi (C) pada empat DPL di Kepulauan Seribu Nilai Indeks keanekaragaman berkisar 1,53–2,22 dengan nilai tertinggi berada di daerah DPL Pulau Kelapa, dan nilai terendah berada di DPL Pulau Harapan. Nilai Indeks keseragaman relatif merata di semua daerah pengamatan dengan kisaran nilai 0,66–0,83. Pada kisaran nilai ini, semua daerah termasuk memiliki ekosistem yang stabil. Sementara itu, nilai indeks dominansi berada pada kisaran 0,13–0,37. Nilai terendah berada di DPL Pulau Kelapa dengan nilai tertinggi berada di DPL Pulau Harapan. Menurut Simpson (1949) dalam Magurran (1988), pada kondisi ini tidak terdapat spesies yang mendominasi spesies lainnya. Nilai indeks keseragaman dan nilai indeks keanekaragaman yang kecil biasanya menandakan adanya dominasi suatu spesies terhadap spesiesspesies lain. Dominasi suatu spesies yang cukup besar akan mengarah pada kondisi ekosistem atau komunitas yang labil atau tertekan (Odum 1971; Simpson 1949 dalam Magurran 1988). Gambar 4 merupakan salah satu contoh kondisi ekosistem terumbu karang di salah satu DPL di Kepualauan Seribu yang kondisinya terlihat baik dan terdapat beberapa spesies ikan karang. 44 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya Gambar 4.Kondisi potensi terumbu dan ikan karang di DPL Kepulauan Seribu (Sumber: Anonim 2010) 3. Upaya Pendukung Lainnya Mekanisme konservasi lain yang juga diharapkan mendukung kelestarian ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu adalah kegiatan transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan salah satu pendekatan untuk memperbaiki kondisi terumbu karang dengan menumbuhkan terumbu karang jenis-jenis tertentu secara buatan di dalam laut. Transplantasi terumbu dilakukan dengan metode penanaman dan penumbuhan koloni suatu jenis karang secara fragmentasi. Umumnya koloni transplantasi diambil dari satu induk koloni yang berukuran lebih besar dan terdapat di sekitar lokasi transplantasi berlangsung, dengan tujuan untuk mempercepat regenerasi dari komunitas karang yang telah mengalami kerusakan (Harriot dan Fisk 1988). Selain transplantasi karang, program rehabilitasi sumber daya laut lain yang telah berjalan adalah penenggelaman fish shelter. Fish shelter atau rumpon adalah struktur benda padat buatan manusia yang ditenggelamkan di perairan dengan tujuan menjadi tempat perlindungan dan berkumpulnya ikan di dalam atau di sekitar struktur tersebut. Fish shelter sering juga disebut sebagai terumbu buatan (artificial reef), merupakan suatu kerangka buatan manusia yang ditenggelamkan di dasar perairan untuk memengaruhi proses-proses fisik, biologi, atau sosioekonomi yang berhubungan dengan sumber daya hayati laut (Seaman 2000). 45 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Penenggelaman fish shelter di sejumlah lokasi di Kepulauan Seribu bertujuan untuk menyediakan “rumah baru” bagi ikan-ikan yang kehilangan habitat aslinya. Oleh karena itu, umumnya penenggelaman fish shelter dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang telah terdegradasi atau rusak. Selain itu, modul fish shelter juga secara alami akan ditempeli oleh organisme bentik (misalnya larva karang, sponge, dan lain-lain) yang bisa ditemukan di ekosistem terumbu karang alami. Diharapkan setelah bertahun-tahun penenggelamannya, modul fish shelter dapat membentuk suatu habitat kompleks yang mendukung program rehabilitasi terumbu karang dan bisa dijadikan tempat tujuan wisata.. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu (Anonim 2010), program transplantasi karang di sejumlah lokasi DPL telah berlangsung lebih dari lima tahun dan secara umum kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil karena survival rate-nya mencapai 80% untuk semua lokasi. Penggunaan modul mini fish shelter merupakan hal yang baik karena bisa menyediakan landasan bagi larva karang untuk menempel dan tumbuh berkembang jadi polip-koloni karang baru secara alami, selain meminimalkan perturbasi pesaing polip karang seperti alga dan sedimen. Lebih jauh lagi, modul tersebut juga berfungsi secara ekologis sebagai habitat perlindungan bagi ikan-ikan yang ada di area tersebut. Kesimpulan Peran penting ekologis terumbu karang sebagai habitat berbagai jenis biota benthic yang memiliki keterkaitan terhadap keberlangsungan hidup berbagai spesies ikan demersal, menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan di perairan Kepulauan Seribu. Apalagi sebagian besar masyarakat nelayan di perairan ini mengantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan karang. Upaya perlindungan seperti penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis masyarakat tampak lebih efektif dan menunjukkan hasil yang nyata bagi pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang rusak. Sampai tahun 2010, terdapat tujuh (7) lokasi DPL di Kepulauan Seribu. Berdasarkan pengamatan terhadap biota benthic yang terdapat di sana, menunjukkan terjadinya perbaikan kondisi ekosistem terumbu karang yang dijadikan sebagai DPL dalam persentase penutupan kategori kisaran sedang sampai dengan sangat baik. Indeks keanekaragaman 46 Kondisi Terumbu Karang dan Lingkungan Perairan Sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kepulauan Seribu serta Upaya Pelestariannya penutupan karang relatif merata di semua daerah pengamatan, yang berarti memiliki ekosistem yang stabil. Sementara itu, nilai indeks dominansi menunjukkan tidak terdapat spesies yang mendominasi terhadap spesies lainnya di semua DPL yang disurvei sebagai sampel. Selain itu, upaya transplantasi karang serta penenggelaman fish shelter, terbukti mampu mendukung pemulihan sumber daya perikanan. Pustaka Anonim. 2010. Laporan Kajian Potensi Sumber daya Pertanian dan Kelautan, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. English S, Wilkinson C, and Baker V. 1997. Survey Manual for Tropical Marine Resources, 2nd Edition. (Townsville: Australian Institute of Marine Science). Gomez ED dan HT Yap. 1988. Monitoring Reef Conditions. In : Kenchington, R. A and B. E. T. Hudson (eds). h. 187 – 196. Coral Reef Management Handbook. UNESCO Regional Office for Science and Technology for South-East Asia. Jakarta. Harriot VJ, Fisk DA (1988a) Accelerated regeneration of hard corals: a manual for coral reef users and managers. G.B.R.M.P.A.. Technical Memorandum 16. Magurran AE. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press. 192 p. Princeton, N.J. Odum EP. 1971. Fundamentals of ecology. 3rd ed. Saunders, Philadelphia and London. Seaman W. Jr 2000. Artificial reef evaluation – with applicationto related marine habitats. CRC Press/Springer-Verlag.246 pp. Simpson EH. 1949. Measurement of Diversity.Editor Charles H. Smith’s Note: This short but important paper is reprinted by permission from Nature 163 (1949): 688, Macmillan Publishers Ltd. Terangi. 2007. Buku Terumbu Karang Jakarta. Pengamatan Terumbu Karang Kepulauan Seribu Tahun 2003–2007. Yayasan Terangi. Jakarta 47 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Isa Nagib Edrus dan Sri Turni Hartati∗) Balai Penelitian Perikanan laut Abstrak Penelitian kesehatan terumbu karang dilakukan di beberapa wilayah perairan Gugusan Pulau Pari, yaitu wilayah perairan dengan ekosistem terumbu karang yang sudah terdegradasi. Secara geografis letak Gugusan Pulau Pari yang berdekatan dengan Kota Jakarta dan Tanggerang memengaruhimenyebabkan kawasan tersebut relatif rentan terhadap dampak buruk pembangunan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret dan November 2008 dengan menggunakan metode RRA dan LIT. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi keragaman dan kondisi kesehatan karang. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah jenis karang batu yang ditemukan sebanyak 56 spesies dan 4 suku. Status kesehatan terumbu karang di Gugusan Pulau Pari masuk pada kategori sedang. Kata kunci: Terumbu karang, Pulau Pari, Teluk Jakarta * Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Peningkatan kegiatan pembangunan di pesisir menyebabkan meluasnya kehilangan dan kerugian, mulai dari sisi produksi, genetik, sampai nilai-nilai konservasi. Untuk alasan tersebut pemerintah menaruh perhatian yang serius pada program perlindungan laut di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan. Sementara itu, cara-cara penangkapan yang merusak seperti pengeboman dan peracunan terus berlangsung. Pengeboman dan peracunan ikan sudah menjadi hal biasa. Kebiasaan tersebut semakin meluas terjadi di wilayah perairan karang tanpa dapat dipantau dan dilarang (Pet-Saode et al. 1996; Hopley dan Suharsono 2000). Ancaman kerusakan karang di Asia Tenggara diperkirakan sebesar 64% berasal dari penangkapan berlebih dan 56 % dari kegiatan penangkapan yang merusak (Burke et al. 2002). Laporan WWF menyebutkan bahwa lebih dari 6.000 penangkap ikan hidup telah menggunakan 150.000 kg potas dalam bentuk larutan disemprotkan ke-33 juta onggok karang setiap tahun. Jika praktik peracunan tersebut terus berlangsung, diperkirakan tahun 2020 semua terumbu karang akan rusak (Michael 2011). Beragam fungsi atau manfaat dapat diperoleh dari terumbu karang. Sekitar 25% GDP nasional berasal dari industri laut dan pantai, transportasi, perikanan dan pariwisata (Dahuri dan Dutton 2000). Terumbu karang di Indonesia menyediakan keuntungan ekonomi tahunan sebesar US$ 1,6 juta (Burke et al. 2002), tetapi tidak sedikit pula kerugian yang ditanggung oleh ekosistem tersebut. Usaha individual perikanan yang menggunakan racun (cyanide fishing) memperoleh keuntungan bersih 33.000 US$ per km2 dalam periode 20 tahun, tetapi total kerugian yang ditimbulkannya bagi usaha masyarakat dalam perikanan tangkap yang berkelanjutan dan usaha pariwisata mencapai 40.000 sampai 446.000 US$ per km2 dalam periode yang sama. Nilai tersebut belum terhitung kerugian dari sisi kehilangan biodiversity dan proteksi lingkungan (Cesar 1996; Burke et al. 2002). Berkaitan dengan kepentingan manusia pada terumbu karang, pemahaman fungsi dan peran biologi, ekologi, serta sosial ekonomi terumbu karang perlu ditingkatkan untuk memperbesar manfaatnya bagi 50 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta kesejahteraan manusia dan memperkecil risiko kerusakannya. Riset-riset biologi dan ekologi perlu dilakukan untuk memahami hidup karang dan hubungan timbal balik antara karang sebagai mahluk hidup dengan lingkungannya. Data kondisi kesehatan dan keanekaragaman sumber daya terumbu karang sangat dibutuhkan untuk pengaturan pengelolaan, ekploitasi, dan konservasinya. Jika perubahan-perubahan kondisi tersebut terukur sercara periodik, diakui mampu memprediksi adanya perubahan-perubahan lingkungan akibat tekanan pembangunan terhadap sumber daya terumbu karang. Kepuluan seribu tercatat sebagai salah satu kawasan yang mempunyai potensi kelautan cukup besar. Empat aspek potensi kelautan yang dimilikinya mencakup ekonomi, ekologi, pertahanan keamanan, pendidikan, dan riset. Pemenuhan kebutuhan DKI Jakarta terhadap aspek perikanan, pariwisata, pendidikan, dan riset sangat bergantung pada wilayah tersebut. Salah satu alternatif untuk mendukung pemerintah dalam usaha pengelolaan potensi itu adalah dengan menggali dan menyajikan informasi yang tepat mengenai potensi tersebut. Gugus Pulau Pari merupakan wilayah yang secara langsung memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran di sekitar teluk Jakarta. Monitoring kondisi karang sangat bermanfaat untuk kepentingan perbaikan manajemen dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data keragaman bentuk kehidupan bentik terumbu dan status kesehatan. Kesehatan karang dapat terukur dari persen tutupan masing-masing komponen bentuk kehidupan tersebut. Bahan dan Metode Penelitian dilakukan pada bulan Maret dan November 2008 di perairan Gugusan Pulau Pari (Tabel 1; Gambar 1). Pendekatan dalam pengambilan data dilakukan dengan RRA (Rapid Reef Assesment) dan LIT (Line Intercept Transek) (English et al. 1994; Gomez dan Yap 1984). RRA digunakan untuk menilai secara cepat, yaitu dengan cara time swimming 51 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya (per 15 menit). LIT digunakan untuk melihat kondisi secara lebih detail dengan menggunakan roll meter, di mana penyelam mencatat intercept lifeform karang yang di lewati pita ukur (roll meter). Setiap lokasi transek ditentukan posisi geografisnya (Tabel 1). Persen tutupan benthic lifeform terumbu karang dianalisis dengan menggunakan Lifeform Software Program berdasarkan standar UNEP yang berlaku untuk ASEAN-Australia (Rahmat dan Yosephine 2001). Penetapan kondisi karang batu (hard coral) mengacu pada kriteria kesehatan karang yang diukur menurut kategori persentase tutupan karang seperti sangat baik (excellent) >75%; baik (good) <75%–>50%; sedang (fair) <50–>25%; dan buruk (poor) <25% (Chou 1998). Tabel 1. Posisi lokasi transek Lokasi RRA 1 (Pulau Pari) RRA 2 (Pulau Pari) RRA 3 (Pulau Kudus) RRA 4 (Pulau Kogsi) RRA 5 (Pulau Tikus) RRA 6 (Pulau Tikus) RRA 7 (Pulau Pari) Lokasi (Locations) LIT 1 (Pulau Kudus) LIT 2 (Pulau Tikus) LIT 3 (Pulau Pari) LIT 4 (Pulau Pari) 52 Posisi Transek RRA Bujur Timur (BT) Lintang Selatan (LS) 05° 51,254’ 106° 38,333’ 05° 50,987’ 106° 37,696’ 05° 50,962’ 106° 35,905’ 05° 50,802’ 106° 35,849’ 05° 51,168’ 106°34,795’ 05° 51,539’ 106° 34,199’ 05° 51,902’ 106° 35,114’ Posisi Transek LIT 05° 50,962’ 106° 35,905’ 05° 51,539’ 106° 34,199’ 05° 51,902’ 106° 35,114’ 05° 51,186’ 106° 38,127’ Tikus Burung Tengah Kongsi Kudus RRA 3 / LIT 1 Pari RRA 7 / LIT 3 RRA 2 Gambar 1. Peta gugus Pulau Pari yang menunjukkan lokasi penelitian RRA / LIT = Lokasi Transek Keterangan : RRA 6 / LIT 2 RRA 5 RRA 4 RRA 1 LIT 4 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta 53 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Hasil dan Pembahasan 1. Keanekaragaman Karang Batu Jumlah jenis karang yang teridentifikasi di area penelitian dengan metode RRA dan LIT sebanyak 56 spesies dari 4 suku (Tabel 2). Karang keras didominasi oleh suku Acroporidae. Variasi bentik lifeforms cukup beragam, di antaranya ditemukan banyak karang bercabang (branching), karang meja (Tabulate), karang daun (foliose), karang otak (massive), karang merayap (encrusting), karang piring (mushroom), karang api (millepora), dan karang lunak (soft corals). Tabel 2. Jenis-jenis karang yang teridentifikasi di Gugusan Pulau Pari, Teluk Jakarta NO I SUKU dan JENIS ACROPORIDAE NO II SUKU dan JENIS AGARIICIDAE 1 Acropora aspera 39 Coeloseris mayeri 2 A. austera 40 Pavona decusata 3 A. brueggemanni 41 P. cactus 4 A. carduus 42 P. varians 5 A. microclados 43 P. venosa 6 A. diversa 44 Pachyseris speciosa 7 A. formosa 8 A. grandis 9 A. humilis 10 A. hyacinthus III CARYOPHYLLIIDAE 45 Euphyllia glabrescens 46 Physogyra lichtensteini 11 A. hebes 12 A. intermedia 54 IV FAVIIDAE 13 A. latistella 47 Caulastrea tumida 14 A. micropthalma 48 Echinopora gemmacea 15 A. nasuta 49 E. lamellosa 16 A. palifera 50 Favia pallida 17 A. pulchra 51 Favites aboita 18 Acropora sp 52 F. chinensis Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Tabel 2. Jenis-jenis karang yang teridentifikasi di Gugusan Pulau Pari, Teluk Jakarta (lanjutan) NO I SUKU dan JENIS ACROPORIDAE NO II SUKU dan JENIS AGARIICIDAE 19 A. splendida 53 F. rotundata 20 A. tenuis 54 Goniastrea pectinata 21 A. subulata 55 G. retiformis 22 A. listeri 56 Hydnopora exesa 23 A. valida 24 A. vanderhorsti 25 Montipora ehrenbergii 26 M. punctata 27 M. divaricata 28 M. foliosa 29 M. fructicosa 30 M. informis 31 M. levis 32 M. monasteriata 33 M. digitata 34 M. striata 35 Montipora sp 36 M. trabeculata 37 M. verrilli 38 M. verucosa Jumlah jenis hard coral yang ditemukan di Gugus Pulau Pari tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan wilayah terumbu yang sehat. Di perairan Halmahera yang kondisi perairannya relatif lebih baik, ditemukan sebanyak 84 spesies karang dari 16 suku (Anonimous 2006). 2. Kondisi umum kesehatan terumbu karang Hasil penilaian kondisi kesehatan terumbu karang diperoleh dengan metode RRA pada 7 lokasi transek. Kondisi kesehatan terumbu karang 55 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya diperlihatkan oleh besaran persen tutupan komponen karang batu yang diwakili oleh kelompok acropora dan non acropora (Tabel 3). Berdasarkan kriteria Chou (1998), semua lokasi metode RRA memiliki kondisi kesehatan dengan kategori “sedang”, kecuali lokasi transek 4 dalam kondisi “rusak”. Tabel 3 menunjukkan bahwa komponen karang mati yang ditutupi alga (Death Coral with Algae-DCA) cukup tinggi pada semua lokasi, sama kondisinya seperti komponen pecahan karang (rubbles). Banyaknya DCA ini menunjukkan bahwa kerusakan karang sudah cukup lama terjadi dan kontinu, seperti ditunjukkan oleh banyaknya fragmen patahan karang (rubbles). Tabel 3. Persentase tutupan bentuk kehidupan karang yang diperoleh dengan cara RRA NO BENTHIC LIFEFORMS I Lokasi Transek RRA 1 2 3 4 5 6 7 RATARATA Kelompok Biotik 1 Acropora 2 Non acropora 15 20 10 15 15 10 12,8 25 20 20 10 35 30 30 24,3 3 Soft Coral 5 5 5 5 10 5 7 6 4 Sponge 5 3 2 2 3 3 2 2,8 5 Makro Algae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 50 20 30 30 28,3 6 Seagrass 7 Death Coral With Algae (DCA) II 5 0 33 8 Death Coral 0 0 1 0 1 0 0 0,3 9 Other fauna 2 2 2 3 1 2 1 1,8 30 30 Kelompok Abiotik 10 Rubble 15 15 10 10 17 18,1 12 Sand 10 5 5 5 5 5 3 5,4 13 Rock 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Kondisi rinci terumbu karang Penilaian status dan kondisi terumbu karang dengan cara LIT dilakukan pada empat stasiun yang mewakali sisi Utara-Barat dan SelatanTimur gugus Pulau Pari. Stasiun-stasiun tersebut terdiri dari perairan 56 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Pulau Kudus bagian utara (LIT 1) dan Pulau Tikus bagian barat (LIT 2) yang mewakili sisi selatan-barat gugusan Pulau Pari. Kedua stasiun berada pada perairan yang sangat terbuka dengan gelombang dan arus cukup kuat serta dipengaruhi oleh musim barat. Stasiun Pulau Pari-Selatan-Timur (LIT 3) dan Stasiun Pulau Pari-Timur-Utara (LIT 4) merupakan stasiunstasiun yang mewakili sisi selatan-timur Gugus Pulau Pari dengan perairan yang relatif terlindung dan lebih dipengaruhi oleh musim timur. 3.1 Stasiun LIT 1 (Pulau Kudus bagian utara; 05° 50,987’ LS ; 106° 35,905’ BT ) Pulau Kudus terletak pada bagian sisi utara gugusan Pulau Pari, mempunyai rataan terumbu (fringing reef) dan lereng terumbu atau tubir (reef slope and cresh) yang merupakan ciri dari perairan karang yang ada di Gugusan Pulau Pari. Rataan terumbu pendek dengan jarak dari pantai lebih kurang 300 meter, didominasi oleh dasar berpasir dan patahan karang mati (rubbles) dengan ditumbuhi lamun dan makro alga. Lereng terumbu cukup landai dengan kedalaman mencapai 15–20 meter. Koloni karang ditemukan pada daerah tubir dan berkembang pada kedalaman antara 5 meter sampai 10 meter. Kelompok Acropora dengan area tutupan 5% berbentuk karang bercabang atau karang meja. Kelompok non Acropora dengan area tutupan 36%, berbentuk massive, sub masssive, dan encrusting. Fauna karang lain (other fauna) seperti lili laut (crinoid), tridacna, karang lunak (soft corals) dijumpai dengan area tutupan 2%. Karang yang masuk kategori baru mati (masih kelihatan putih) ditemukan sebesar 3%, sementara karang mati yang sudah cukup lama dan tergolong turf algae mendominasi persen tutupan terumbu (54%). Persen tutupan secara keseluruhannya diilustrasikan pada Gambar 2. Kondisi kesehatan karang ditentukan oleh Acropora 5% dan Non Acropora 36%, di mana jumlahnya 41%. Dengan demikian kesehatanan terumbu karang Pulau Kudus, menurut kriteria Chou (1998) berada dalam kondisi sedang. 57 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 36% Acrop pora 2%0% 5% Non Acropora A Dead Scleractinian 54% Algae 3% Others rs Abiotic Gambar 2. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Kudus bagian utara 3.2 Stasiun LIT 2 (Pulau Tikus bagian Barat: 05° 51,539’ LS ; 106° 34,199’ BT) f Stasiun LIT 2 berada pada sisi barat Pulau Tikus yang merupakan rataan terumbu (reef plate) dan lereng terumbu (reef slope). Perairan pada sisi timur dan selatan Pulau Tikus merupakan goba dan sedikit rataan terumbu yang dimanfaatkan sebagai lahan budi daya rumput laut dan perikanan tangkap, terutama dari alat tangkap sero dan bagan tancap. Rataan terumbu Pulau Tikus bagian barat sampai dengan utara cukup luas, panjangnya dari pantai antara 600–800 meter, memiliki dasar berpasir halus dan substrat keras dari karang mati. Antara pulau dengan rataan terumbu luar terdapat goba dengan kedalaman 10–15 meter. Lereng terumbu berakhir pada tubir yang dalamnya mencapai 20 meter, di mana terumbu berkembang pada kedalaman mulai dari 5 meter sampai 10 meter. Bentuk kehidupan terumbu didominasi oleh pertumbuhan alga (turf algae) dengan tutupan mencapai 39% (Gambar 3). Persen tutupan karang mati dalam terumbu sebesar 2% yang disebabkan oleh serangan bintang laut dan pemutihan karang (bleaching). Persen tutupan dari kelompok abiotik (pasir dan rubbles) sebesar 25%, hal ini menunjukkan adanya terumbu yang terpisah-pisah berupa bongkahan-bongkahan (path reefs). Biota lain yang berasosiasi dengan terumbu, seperti karang lunak dan makro bentos, jarang dijumpai dan tutupannya hanya mencapai 2%. Kelompok karang hidup yang menunjukkan kesehatan karang diwakili oleh adanya Acropora (2%) dan non acropora (30%), di mana jumlah 58 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta keduanya adalah 32%. Menurut kriteria kesehatan karang Chou (1998), persen tutupan karang batu sebesar 32% menunjukkan kondisi kesehatan sedang. Acropora Non Acropora a 2 2% 25% 30% % 2% 2% 39% Dead Scleracctinian Algae Others Abiotic Gambar 3. Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Tikus bagian barat 3.3 Stasiun LIT 3 (Pulau Pari bagian selatan timur: 05° 51,902’ LS ; 106° 35,114’ BT) Pulau Pari merupakan pulau terbesar di antara pulau-pulau yang berada dalam gugusan Pulau Pari, dengan luas mencapai 41,2 ha. Perairan sekitar Pulau Pari digunakan sebagai lahan budi daya rumput laut, lahan konservasi mangrove, Daerah Perlindungan Laut (DPL), serta lokasi perikanan tangkap (fishing ground). Stasiun pengamatan berada pada sisi selatan Pulau Pari dan merupakan area perlindungan laut. Area ini merupakan perairan karang terbaik dengan tutupan karang batu tertinggi, walaupun badan air mengalami kekeruhan pada waktu-waktu tertentu. Rataan terumbu cukup luas, kurang lebih 300 x 700 m2 dan memiliki dasar berpasir dan patahan karang mati yang ditumbuhi lamun dan makro alga. Dasar perairan di belakang tubir lebih didominasi oleh substrat keras dari bongkahan karang mati serta terdapat patahan karang yang mengeras dan menempel satu sama lain. Lereng terumbu landai sampai ke tubir dengan kedalaman 15 meter. Terumbu karang didominasi oleh kelompok non Acropora (50 %). Bentuk kehidupan bentik lainnya yang tergolong dominasi kedua adalah algae atau turf algae, di mana tutupan komponen ini mencapai 38%. Tutupan biota lain yang termasuk kelompok spon (other fauna) sangat rendah, yaitu hanya 1%. Tutupan karang mati dan abiotik masing-masing 6% dan 5%. Tutupan karang hidup (hard corals) yang dijumpai di area transek hanya diwakili oleh kelompok non 59 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Acropora (50%), sedangkan kelompok Acropora nihil (Gambar 4). Semua jenis bentuk karang bercabang di area ini tergolong non Acropora dan Millepora. Dengan demikian, kondisi kesehatan menurut kriteria Chou masuk dalam kondisi sedang mendekati baik. Acropora 1% 5% 0% Non Acropo ora 4 49% 39% % Dead Sclerractinian Algae 6% Others Abiotic Gambar 4. Kondisi terumbu karang diperairan Pulau Pari Selatan-Timur 3.5 Stasiun LIT 4 (Pulau Pari bagianTimur-Utara: 05° 51,186’ LS ; 106° 38,127’ BT) Stasiun pengamatan 4 berada pada sisi timur Pulau Pari dan merupakan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Rataan terumbu tidak terlalu luas, lebarnya dari pantai berkisar 300 sampai 400 meter. Dasar perairan dari rataan terumbu didominasi oleh pasir dan patahan karang mati yang ditumbuhi lamun dan makro alga. Tubir karang tidak terjal tetapi berangsur-angsur curam sampai kedalaman 20–25 meter. Bentuk kehidupan terumbu didominasi oleh tutupan karang keras (Gambar 5), yaitu kelompok Acropora (15%) dan non Acropora (40%). Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan terumbu karang di area ini tergolong dalam kondisi sedang. Tutupan alga golongan turf algae dan biota lain yang tergolong spon dan karang lunak masing-masing 6% dan 2%. Karang mati dijumpai cukup tinggi dengan tutupan sebesar 17%. Kelompok abiotik juga cukup tinggi (20%) yang menandakan bahwa rataan terumbu berupa gunduk-gundukan terpisah (path reef). 60 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Acropora 2% 20% 15% Dead Sclera actinian 6% 17% Non Acropora 4 40% Algae Others Abiotic Gambar 5. Status dan kondisi terumbu karang di perairan Pulau Pari bagian timur-utara Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Jumlah jenis karang yang teridentifikasi di gugusan Pulau Pari sebanyak 56 jenis dari 4 suku, di mana jumlah jenis tersebut relatif rendah. 2. Kesehatan terumbu karang pada semua stasiun pengamatan masuk pada kategori sedang, di mana persen tutupan karang batu berada pada kisaran nilai di bawah 50% dan di atas 25%. Saran 1. Melakukan perlindungan yang ketat pada perairan karang di semua lokasi gugus Pulau Pari dengan menetapkan DPL-DPL baru. 2. Melarang secara ketat cara-cara penangkapan yang merusak. 3. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan monitoring kondisi perairan karang. 4. Menetapkan kawasan penangkapan dan juga zona larangan penangkapan. 61 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Daftar Pustaka Anonimous. 2006. Kajian Analisis dan Data Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan: Penyusunan dan Pemetaan Perwilayahan Ekosistem Pesisir. Bappeda Maluku Utara dan BPTP Maluku Utara, Ternate, 169 hal. Burke L, E Selig and M Spalding. 2002. Reefs at Risk in Southeast Asia. World Resources Institute, Washington DC. 76 p. Cesar H. 1996. “Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs,” Working Paper Series ‘Work in Progress’, Washington, DC: World Bank. Chou LM. 1998. Status of Southeast Asian Coral Reefs. In: Status of Coral Reefs of the World: 1998. C. Wilkinson (Ed). Sida – Australian Institute of Marine Science – ICLARM Publ., Quensland, Australia. Dahuri R and IM Dutton, “Integrated Coastal and Marine Management Enters a New Era in Indonesia,” Integrated Coastal Zone Management (2000): 1, 11–16. English S, C Wilkinson and V Baker. 1994. Survei manual for Tropical marine Resources. Australian Institute of Marine Science, Townsville. Australia. Gomez ED and HT Yap. 1984. Monitoring Reef Condition. In: Coral Reef Management Handbook. R.A. Kenchingt6on and B.E.T. Hudson (Eds). Unesco Publisher, Jakarta, p. 171. Hopley D and Suharsono. 2000. The status and management of coral reefs in eastern Indonesia. The Australian Institute of Marine Science for the David & Lucile Packard Foundation, USA. 145 pp. Michael AW. 2011. Cyanide and Dynamite Fishing, Who’s really Responsible? Ocean N Environment Ltd. P.O. Box 2138, Carlingford Court Post Office Carlingford NSW 2118, Australia. email: [email protected]. http://www. Ocean Environment.com. au. Diunduh dari http://www.eepsea.org. Juli 2011. Pet-Soede L, H Cesar, and J Pet. 1996. “Blasting Away: The Economics of Blast Fishing on Indonesian Coral Reefs,” in H. Cesar, ed., Collected Essays on the Economics of Coral Reefs, pp. 77–84. 62 Kondisi Kesehatan Terumbu Karang di Perairan Gugus Pulau Pari, Teluk Jakarta Rahmat dan Yosephine. 2001. Software Percent Cover Benthic Lifeform versi 5.1. Pusat Penelitiaan dan Pengembangan Oseanologi LIPI. Jakarta. Lampiran Bentuk pertumbuhan bentik di gugusan Pulau Pari 63 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Sri Turni Hartati, Isa Nagib Edrus, Amula Nurfiarini, dan Ina Juanita Abstrak Tulisan ini menyajikan hasil kajian status perikanan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Seribu, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkesinambungan. Data dan informasi yang digunakan berasal dari kegiatan penelitian tahun 2007–2009 di perairan Kepulauan Seribu. Kepadatan stok ikan diperoleh melalui sensus visual pada transek garis dengan cara menyelam sepanjang 50 meter, dengan luas area jelajah dan pandang 50 x 5 m. Kelimpahan dan komposisi hasil tangkapan alat tangkap ikan karang diperoleh melalui observasi dengan mengikuti kegiatan nelayan. Produksi dan upaya penangkapan beberapa jenis ikan dominan dan ekonomis penting diperoleh dengan mengompilasi data statistik perikanan dari Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Data tentang nilai investasi dan pendapatan yang digunakan untuk analisis kelayakan usaha diperoleh dari hasil wawancara dengan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan ikan demersal dan karang di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2007 pada kisaran 42 ekor/250 m2 sampai 536 ekor/250m2, didominasi oleh Caesionidae, Nemipteridae, Pomacentridae, Labridae, dan Lethrinidae. Kepadatan ikan dalam kriteria sangat jarang berada pada kisaran 1–5 ekor/m2. Status pemanfaatan sumber daya ikan demersal dan karang di Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya perairan Kepulauan Seribu sudah menunjukkan tingkat kejenuhan (over fishing), yang terindikasi dari menurunnya terus indeks kelimpahan stok ikan tersebut. Usaha penangkapan ikan cukup menguntungkan dan layak untuk diusahakan, dengan tingkat kelayakan usaha bervariasi antara 1,31– 9,95. Kata Kunci: Perikanan, ikan karang, ikan demersal, Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta Pendahuluan Beberapa wilayah terumbu karang di perairan Kepulauan Seribu tampaknya sudah mengalami kerusakan baik yang diakibatkan oleh pencemaran ataupun kegiatan penangkapan ikan. Kesehatan terumbu karang di perairan Pulau Kelapa pada tahun 1999 menunjukkan kategori buruk sampai sedang, penutupan karang hidup pada kisaran 0% sampai 49,9% (Lazuardi dan Wijoyo 2000). Menurut Warsa dan Purnawati (2010), terumbu karang di Kepulauan Seribu yang ditetapkan sebagai daerah perlindungan laut, penutupan karang hidup berkisar 30%–75% . Kesehatan terumbu karang di gugusan Pulau Pari pada kategori sedang sampai baik, penutupan karang hidup berkisar 41%–55% (Hartati dan Edrus 2010) Beberapa kelompok ikan karang dominan dan bernilai ekonomis, bahkan di antaranya merupakan “icon” dari Kepulauan Seribu (seperti ikan ekor kuning, kerapu, lencam, beronang, kakap, dan kakaktua). Pengusahaan ikan karang di Kepulauan Seribu dimulai sejak tahun 60-an, dan mencapai puncaknya pada tahun 70-an, dengan produksi per tahun setiap jenisnya mencapai lebih dari 1.000 ton. Hasil penelitian Subani (1978), produksi ekor kuning pada tahun 1969–1977 mencapai kisaran 800–1.400 ton/tahun, sebaliknya pada tahun 2001–2007 hasil tangkapan hanya pada kisaran 1–34 ton per tahun (Anonim 2007). Wacana ikan kakaktua yang jenisnya relatif banyak dan melimpah di perairan Kepulauan Seribu dan bukan merupakan target utama penangkapan, akan dimasukan dalam daftar appendix CITES, harus diluruskan melalui rekomendasi dari hasil-hasil penelitian. Menurut Hartati et al. (2004), 66 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu hasil tangkapan bubu di perairan gugusan Pulau Kelapa dan sekitarnya didominasi oleh kelompok ikan kakaktua dan kerapu. Hasil sensus visual melalui transek garis di beberapa wilayah terumbu karang gugusan Pulau Pari, jenis ikan karang konsumsi yang dominan di antaranya kakaktua dan kerapu (Hartati dan Edrus 2010) . Tujuan penulisan adalah mengkaji status perikanan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Seribu, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkesinambungan. Bahan dan Metode Data dan informasi yang digunakan dalam penyajian makalah ini berasal dari kegiatan penelitian tahun 2007–2009 di perairan Kepulauan Seribu serta data statistik perikanan dari Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan penelitian yang dilakukan meliputi: • Observasi dengan mengikuti kegiatan nelayan menggunakan beberapa alat tangkap sebagai alat tangkap utama ikan karang dan demersal untuk mengetahui kelimpahan dan komposisi hasil tangkapan. Seluruh hasil tangkapan ditimbang kemudian disortir dan ditimbang kembali menurut jenis ikan. Identifikasi jenis ikan mengacu pada Thomas dan Kailola (1984), Lieske dan Myers (1994), dan Kuiter RH (1992). • Sensus visual pada garis transek (English et al. 1994), untuk mengetahui kondisi populasi ikan karang. Sensus visual dilakukan dengan cara menyelam pada garis transek sepanjang 50 meter, dengan luas area jelajah dan pandang 50 x 5 m. Jenis dan perkiraan jumlah ikan dicatat dalam data sheet kedap air. Identifikasi jenis ikan menggunakan buku petunjuk bergambar (Kuiter 1992; Lieske dan Myers 1994). • Kompilasi data perikanan melalui Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. • Wawancara dengan nelayanuntuk penangkapan mengetahui kelayakan usaha 67 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Hasil dan Pembahasan 1. Kepadatan Stok Kepadatan jenis-jenis ikan karang di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2007 berdasarkan sensus visual melalui transek garis berkisar 42 ekor/250 m2–536 ekor/250 m2. Kepadatan stok ikan karang tertinggi berada di perairan Pulau Genteng dan terendah di perairan Pulau Semak Daun (Gambar 1). Komposisi jenis ikan pada beberapa wilayah perairan menunjukkan bahwa kelompok ikan ekor kuning (Caesionidae) dan kurisi (Nemipteridae) adalah dominan. Jenis-jenis ikan lainnya dengan kehadiran relatif rendah adalah kerapu (Serranidae), kakaktua (Scaridae), kakap (Lutjanidae), lencam (Lethrinidae), dan kuniran (Mullidae). Komposisi jenis ikan pada beberapa wilayah perairan di Kepulauan Seribu disajikan pada Gambar 2. KepadatanIkan(ekor/250m2) 600 500 400 300 200 100 0 Stasiunpengamatan Gambar 1. Kepadatan stok ikan karang di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2007 68 3% 8% 27% 85% Nemipteridae Lutjanidae Caesionidae Mullidae Lethrinidae Lutjanidae Scaridae Caesionidae Serranidae Lethrinidae Nemipteridae Caesionidae Serranidae 76% Caesionidae Scaridae Lutjanidae Nemipteridae Lethrinidae Mullidae DPLP.Pari Serranidae 3% 3% 3% 8% 4% 3% 88% 1% DPLWakrom 4% 7% 1% Nemipteridae Lutjanidae Scaridae Caesionidae Serranidae 95% Nemipteridae Lutjanidae Caesionidae Serranidae PulauGenteng 3% 1% 75% 18% 3% DPLKaliage 2% 2% Gambar 2. Komposisi jenis ikan karang di beberapa perairan Kepulauan Seribu PulauPayung 12% 56% 2% DPLPramuka 4% 3% Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu 69 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Beberapa wilayah perairan menunjukkan bahwa kelompok ekor kuning (Caesionidae) hadir dengan persentase relatif tinggi, seperti DPL Pulau Payung, DPL Pulau Pari, dan Pulau Genteng, dengan persentase kehadiran 76%–95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa populasi ekor kuning sebagai “Icon” dari Kepulauan Seribu masih tinggi. Berbeda dengan kelompok ikan kerapu (Serranidae), yang kehadirannya relatif rendah (1%–7%). Hasil pengamatan yang dilakukan di beberapa perairan gugusan Pulau Pari pada tahun 2009, teridentifikasi 28 famili dan 125 jenis ikan karang. Kepadatan ikan pada kisaran 200 ekor/250m2–507/250m2, tertinggi di perairan selatan Pulau Pari dan terendah di barat Pulau Tikus (Gambar 3). Mengacu pada kriteria Ranks of Square Density (Djamali dan Darsono 2005), kepadatan ikan karang di perairan gugusan Pulau Pari dan Kepulauan Seribu pada umumnya dalam kriteria sangat jarang, yaitu pada kisaran 1–5 ekor/m2. Kepadatanikan(ekor/250m2) Jenis-jenis ikan yang kehadirannya melimpah di gugusan Pulau Pari adalah dari famili Pomacentridae dan Labridae, yaitu pada kisaran 39%– 50%, dan 13%–30%. Kepadatan jenis-jenis ikan kerapu (Serranidae) berkisar 1%–2%, ekor kuning (Caesionidae) 4%– 11%, dan kakaktua (Scaridae) 5%–13%. Beberapa famili ikan lainnya yang hadir adalah Apogonidae, Lutjanidae, Nemipteridae, Chaetodontidae, Siganidae, dan Carangidae (Gambar 4). 600 500 400 300 200 100 0 SelatanP.SelatanP.TTenggara TimurP. UtaaraP. BaratP. SelataanP. Burung Pari P.Pari Pari Ku udus Tikus Tiku us Stasiun nPengamatan Gambar 3. Kepadatan ikan karang di gugusan Pulau Pari pada bulan Juni 2009 70 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Scaridae 6% Apogoniidae 4% Serranidae 2% Caesiionidae 8% 8 Pomacen ntridae 44% % Labridae 30% lainnya 6% Nemipteridae 3% Lainnya 7% Serranidae 1% Lutjanidae 5% Caesionidae 5% nidae Sigan 7% % Scaridae e 7% Labridae 18% Pomacentridae 44% Lainnya 10% Serranidaae 1% Chaetodontidae 3% Scaridae 10% ae Caesionida 11% Pomacentridae 50% Labridae 13% Chaetod dontidae 5% 5 Serranidae 1% Apogoidae 4% Chaetodontidae 5% Carangidae C 5% Nemipteridae 7% Lainnyya 9% Pomacentridae 39% Labridae 17% Scaridae 13% St.4.Timu urPulauPari Gambar 4. Komposisi kehadiran famili ikan karang konsumsi di beberapa wilayah perairan gugusan Pulau Pari pada bulan Juni 2009 71 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Serranidae 1% haetodontidae Ch 3% Caessionidae 4% Apogonidae 4% Lainnyya 13% % Labrid dae 18% % Pomacentridae 48% Serraanidae 11% Scaridae 9% Caesionidae 7% Nemipteridae 8% Lainnya 5% Pomacentridae 48% Labridae 21% Scaridae 10% Gambar 4. Komposisi kehadiran famili ikan karang konsumsi di beberapa wilayah perairan gugusan Pulau Pari pada bulan Juni 2009 (lanjutan) 2. Alat Tangkap Ikan Karang Dari observasi mengikuti kegiatan nelayan, disajikan beberapa aspek alat tangkap utama ikan karang dan demersal, seperti bubu ikan, pancing ulur, jaring muroami, jaring rampus, jaring gebur, jaring millenium, dan sero • Bubu Ikan 72 Hasil tangkapan bubu ikan pada bulan Februari, April, dan Juli 2009 di gugusan Pulau Pari pada kisaran 3–4 kg/ hari. Pada bulan Februari tertangkap 11 jenis ikan sebanyak 21 ekor, didominasi oleh kelompok ikan lencam (Lethrinidae) dan pasir-pasir (Scolopsis ciliatus). Hasil tangkapan pada bulan April sebanyak 42 ekor terdiri dari 9 jenis ikan, Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu didominasi oleh Dischitodus perspicillatus (Pomacentridae). Pada pengamatan bulan Juli teridentifikasi sebanyak 16 jenis ikan dari 42 ekor yang tertangkap, didominasi oleh kakak tua (Scarus gobhan). Komposisi jenis ikan hasil tangkapan bubu di gugusan Pulau Pari berdasarkan bulan pengamatan disajikan pada Gambar 5. Komposisibubu(N) Februari2009 5% 10% 5% Lethrinusharax Lethrinusmicrodon Lethrinusornatus 20% Lethrinusminiatus 5% 10% Scolopsisciliate Pentapodustrivitatus 10% 5% 25% Lethrinuslentjam Choerodonanchorago 5% Epinephelusmelanostigma Lutjanusboutton Komposisibubu(W) Februari2009 Lethrinuslentjam Lethrinusharax Lethrinusmicrodon 3% 11% 5% Lethrinusornatus Lethrinusminiatus 21% 6% 6% 19% 20% 6% 3% Scolopsisciliate Pentapodustrivitatus Choerodonanchorago Epinephelusmelanostigma Lutjanusboutton Gambar 5.Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan bubu di Kepulauan Seribu 73 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Komposisibubu(N) April2009 3% 2% 5% 3% 2% 2% 5% Lethrinusornatus Ephinephelusmerra Plectropomusmaculatus Chephalopholisboenack Dischistodusperspicillatus 14% Scarusgobban Siganusvirgatus 64% Cheilinustrilobatus Hemigyhinusmelapterus Komposisibubu(W) April2009 5% 3% 3% Lethrinusornatus Ephinephelusmerra 6% Plectropomusmaculatus Chephalopholisboenack 3% Dischistodusperspicillatus 55% 21% Scarusgobban Siganusvirgatus 2% 2% Cheilinustrilobatus Hemigyhinusmelapterus Gambar 5.Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan bubu di Kepulauan Seribu (lanjutan) 74 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Komposisibubu(N) Juli2009 Siganuspunctatus Scarusgoban Cheilinustrilobatus 6% 9% 23% 9% Scolopsisciliatus Plectropomusquoyqnus 9% Siganusvirgatus 29% 6% 9% Balistocensidesvirides Abudedufsp Komposisibubu(W) Juli2009 Siganuspunctatus Scarusgoban Cheilinustrilobatus 11% 10% Plectropomusquoyanus 9% 6% 5% 4% 7% Scolopsisciliate 29% Siganusvirgatus Epibulusinsidiator Balistoidesviridescens 10% 9% Abudedufsp Cephalopholissexmaculata Gambar 5.Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan bubu di Kepulauan Seribu (lanjutan) Hasil tangkapan bubu di Kepulauan Seribu pada tahun 2003 pada kisaran 10 sampai 15 kg/5 bubu, didominasi oleh pasir-pasir (Scolopsis sp.), swangi (Sargocentron sp.), kerapu (Cephalopholis sp., Plectropomus sp., Epinephelus sp.), dan ekor kuning (Caesio sp.) masing-masing sebesar 22%, 13%, 12%, dan 11% (Hartati et al. 2004). Hasil tangkapan pada tahun 2007 berkisar 4 sampai 14 kg/5 bubu, rata-rata 2 kg/5 bubu. Komposisi jenis ikan hasil tangkapan bubu didominasi oleh ikan nuri (Choerodon anchorago). Hasil tangkapan tahun 2008 relatif lebih rendah, yaitu rata-rata 3 kg/5 bubu, didominasi oleh beronang (Siganus sp.) dan kakaktua (Scarus sp.). 75 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya • Pancing Ulur Kelimpahan hasil tangkapan pancing ulur pada bulan Februari, April, dan Juli 2009 di gugusan Pulau Pari berkisar 1–5 kg/perahu. Melihat hasil tangkapan pancing ulur pada bulan Februari dan April, dominasi jenis ikan hasil tangkapan tidak berbeda dengan hasil tangkapan bubu ikan, yaitu didominasi oleh kelompok lencam (Lethrinidae), dengan persentase mencapai 75%–80%. Hasil tangkapan pancing ulur dan bubu pada bulan Februari dan April menunjukkan bahwa keberadaan ikan lencam di gugusan Pulau Pari masih cukup melimpah. Berbeda dengan hasil tangkapan pancing ulur pada bulan Juli, selain kelompok ikan lencam, jenis ikan ekor kuning juga mendominasi hasil tangkapan. Komposisi hasil tangkapan pancing ulur disajikan pada Gambar 6. Komposisipancing(N) Februari2009 Lethrinusminiatus Lethrinuslentjam 10% Lethrinusharax 10% 10% 50% 10% Lethrinusornatus Epinephelussp. 10% Pentapodussp. Komposisipancing (W) Februari2009 Lethrinusminiatus Lethrinuslentjam 6% 4% 17% Lethrinusharax 49% Lethrinusornatus Epinephelussp. 17% 7% Pentapodussp. Gambar 6. Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan pancing ulur di Kepulauan Seribu 76 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Komposisipancing(N) April2009 Lethrinushypscloptinus Lethrinusornatus 13% 25% Lethrinusharax 13% 25% Lethrinusminiatus 12% 12% Epinephelus.ongus Choerodonanchorago Komposisipancing(W) April2009 Lethrinushypscloptinus Lethrinusornatus 4% 6% Lethrinusharax 28% Lethrinusminiatus 7% 44% 11% Epinephelus.ongus Choerodonanchorago Gambar 6. Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan pancing ulur di Kepulauan Seribu (lanjutan) 77 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Komposisipancing(N) Juli 2009 Lethrinushypscloptinus Lethrinusornatus 4% 6% 28% Lethrinusharax Lethrinusminiatus 7% 44% 11% Epinephelus.ongus Choerodonanchorago Komposisipancing(W) Juli2009 Caesiocuning 5% 3%2% Caesiocaerulaurea 25% Selaroidesleptolepis 65% Lethrinussp Nemipterussp Gambar 6. Komposisi jenis ikan karang hasil tangkapan pancing ulur di Kepulauan Seribu (lanjutan) 78 Kelimpahan hasil tangkapan pancing ulur yang didaratkan di Pulau Tidung pada bulan Maret 2007 berkisar 1 sampai 78 kg/perahu, dengan rata-rata 7 kg/perahu. Pada bulan April 2007 berkisar 1 sampai 101 kg/perahu dan rata-rata 7 kg/perahu, dan pada bulan Mei 2007 berkisar 1 sampai 87 kg/perahu, dengan rata-rata 11 kg/ perahu. Sampling pada bulan Mei 2007 teridentifikasi 13 jenis ikan. Berdasarkan jumlah individu dan berat, hasil tangkapan pancing didominasi oleh ikan kurisi (Nemipterus fruscosus) dengan persentase masing-masing 44,63% dan 38,01%. Hasil tangkapan pancing ulur di gugusan Pulau Pari pada tahun 2008 pada kisaran 6 sampai 50 kg/ perahu. Sampling pada bulan Mei didominasi oleh ekor kuning (Caesio cuning) sebesar 76%, jenis-jenis lainnya adalah Caesio caerulaurea, Selaroides leptolepis, Lethrinus sp., dan Scolopsis sp. Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu • Jaring Muroami Komposisi hasil tangkapan muroami dengan daerah penangkapan di sekitar perairan gugusan Pulau Pari pada bulan April dan Juli 2009 tersaji pada Gambar 7. KomposisiMuroami(W) April2009 Pterocaesiopisang 21% Caesiocuning 17% 62% Lainnya Komposisilainnya April2009 1% 1% 2% 2% 4% 4% 21% 5% 7% 17% 8% 11% 14% Scarusgobban Lutjanuscarponotatus Scarusniger Scarusfasciatus Cheilinusfasciatus Pterocaesiocaerulaurea Scolopsisfosmeri Sphyraenasp. Abudefdufsexfaciatus Amblyglyphidodonleucogaster Pentapodusemeryii Hemigenusmelapterus Amblyphlypidodonaureus Lutjanusbiqulatus Selaroidesleptolepis Gambar 7. Komposisi hasil tangkapan jaring muroami pada bulan April 2009 di perairan gugusan Pulau Pari 79 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya KomposisiMuroami(W) Juli2009 6% 4% 8% Caesiocuning Pterocaesiodigrama Caesiocaerulaurea 21% 61% Siganusvirgatus Lainnya KomposisilainnyaJuli2009 Selaroidesleptolepis 12% 4% 26% 18% Herklotsrchthyssp. Scarussp. Sphyraenaforsterii 17% 18% 5% Lethrinusvariegatis R.kanagurta Pentapodusemeryii Gambar 7. Komposisi hasil tangkapan jaring muroami pada bulan Juli 2009 di perairan gugusan Pulau Pari (lanjutan) 80 Hasil tangkapan muroami pada bulan April terdiri dari 19 jenis ikan, 546 ekor, dan total berat 11 kg. Jenis ikan yang mendominasi hasil tangkapan adalah pisang-pisang (Pterocaesio pisang) sebanyak 366 ekor (62%), ikan ekor kuning (Caesio cuning) sebanyak 139 ekor (17%), dan jenis lainnya 21%, di antaranya juga terdapat kelompok kakaktua dan kekakapan dalam jumlah yang kecil. Hasil tangkapan muroami pada bulan Juli teridentifikasi sebanyak 11 jenis, 415 ekor, dan total berat 20 kg. Ekor kuning (Caesio cuning) mendominasi hasil tangkapan muroami (61%), kemudian diikuti pisang-pisang (Pterocaesio digrama) sebesar 21%, Caesio caerulaurea sebesar 8%, Siganus virgatus sebesar 6%, dan jenis lain sebesar 4%, di antaranya Selaroides leptolepis. Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Hasil tangkapan rata-rata kapal muroami harian yang di daratkan di Pulau Pramuka pada bulan Maret 2007 sebesar 73 kg/kapal. Berdasarkan jumlah individu (n) dan berat (w), hasil tangkapan didominasi oleh ekor kuning (Caesio cuning) sebesar 45,74%(n) dan 76,91% (w), kemudian diikuti oleh ikan pisang-pisang (Pterocaesio digramma), sebesar 36,71% (n) dan 13,73% (w). Hasil tangkapan pada bulan Agustus relatif rendah yaitu 5 kg/kapal/trip/hari, didominasi oleh ekor kuning (Caesio cuning). • Jaring Gebur (Gillnet Dasar) Pengamatan hasil tangkapan jaring gebur dilakukan pada bulan Agustus dan Oktober 2009. Hasil tangkapan pada bulan Agustus 2009 sebanyak 18 kg, terdiri dari 17 jenis ikan, satu jenis tidak teridentifikasi, dan didominasi oleh kakatua (Scaridae). Hasil tangkapan pada bulan Oktober 2009 hampir 100% adalah lingkis (Siganus canaliculatus), sebanyak 98 ekor dan total berat kurang lebih 10 kg. Hasil tangkapan jaring gebur menunjukkan bahwa keberadaan lingkis dan jenis-jenis ikan kakatua (Scaridae) relatif melimpah di perairan gugusan Pulau Pari. Komposisi hasil tangkapan disajikan pada Gambar 8. UnIdentified Hippocarusharid Cheilinustrilobatus Epibulusinsidiator Lethrinussp. Lutjanusfulvihammus Scolopsislineatus Scolopsismonogramma Hemigymusmelanopterus Siganuspunctatus Chaerodonanchorago Pseudobalisteshavicuarginatus Scarruslongiceps Scarrussp Scarrusrivulatus Scarruspyrrhurus Scarusghobban 0 10 20 30 40 KomposisiHasilTangkapan(%) Gambar 8.Kelimpahan dan komposisi hasil tangkapan jaring gebur pada bulan Agustus 2009 di perairan gugusan Pulau Pari 81 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya • Jaring Rampus (Gillnet Dasar) Pengamatan kegiatan penangkapan dengan jarring rampus dilakukan pada bulan Februari, April, Juli, dan Agustus 2009. Kelimpahan hasil tangkapan pada kisaran 4–20 kg/kapal/trip/hari, didominasai oleh ikan beronang (Siganidae). Komposisi hasil tangkapan jaring rampus pada bulan Februari, April, Juli, dan Agustus disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Komposisi hasil tangkapan jaring rampus di perairan gugusan Pulau Pari pada tahun 2009 Jenis Ikan Jenis Ikan Siganus canaliculatus. Siganus virgatus Siganus punctatus Scarrus ghobban Pentapodus sp Komposisi (%) Februari April Juli 97,31 20,86 70 49,1 30 30,04 0,82 1,87 Agustus 93,83 6,17 • Sero Hasil tangkapan sero pada bulan Maret 2008 menunjukkan bahwa bahwa hasil tangkapan pada 1 unit sero hanya 1 jenis ikan, yaitu sembilang karang (Plotosus lineatus) pada posisi sero 1 dan ikan siro (Amblygaster sirm) pada posisi sero 2 (Tabel 2). Tabel 2. Kelimpahan hasil tangkapan sero di Pulau Kongsi bulan Maret 2008 Alat tangkap Sero 1 Sero 2 Jenis Ikan Plotosus lineatus Amblygaster sirm Nama Lokal Sembilang karang Ikan siro Berat (kg) 65 11 • Jaring Millenium 82 Pengamatan kegiatan penangkapan dengan jaring millenium disajikan pada Gambar 9. Hasil tangkapan kurang lebih 25 kg/kapal/trip/hari, terdiri lebih dari 8 jenis, didominasi oleh ikan kuwe (Caranx tille). Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu KomposisiMillenium(W) Maret 2008 Psettodecrumei 18% 44% 2% 1% Cynoglossusarel Diagrammapunctatum Carcharhinusleucas 15% Mustelusmanazo 11% KomposisiMillenium(N) Maret2008 Caranxtille Gnathanodonspeciosus Ariussp 10% 40% 20% 5% 5% Gnathanodonspeciosus Ariussp 7% 2% Caranxtille Psettodecrumei Cynoglossusarel Diagrammapunctatum 5% 5% 10% Carcharhinusleucas Mustelusmanazo Gambar 9. Komposisi hasil tangkapan jaring millenium di Pulau Tikus bulan Maret 2008 2. Produksi dan Upaya Penangkapan Beberapa Jenis Ikan Dominan dan Ekonomis Penting • Ekor Kuning Produksi ekor kuning dari Kepulauan Seribu pada tahun 1969– 1977 berkisar 793–1.339 ton, dan mencapai puncaknya pada tahun 1970–1974, lebih dari 1000 ton per tahun (Subani 1978). Dengan tingkat upaya penangkapan 17–26 unit muroami, hasil tangkapan per unit upaya (CPUE) adalah 34,48–69,94 ton/unit/tahun (Tabel 3). Kondisi pada periode tahun 1969–1977 berbeda dengan periode tahun 2001–2007 (Anonim 2007), yaitu hasil tangkapan menurun setiap tahun, pada kisaran 0,49–33,70 ton/tahun. Dengan tingkat upaya penangkapan relatif tinggi pada setiap tahunnya yaitu mencapai 53 unit muroami, CPUE menurun tajam, 0,64 ton/unit pada tahun 83 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 2001 dan 0,03 ton/unit pada tahun 2007. Pengurangan unit upaya penangkapan yang berlangsung mulai tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan hasil tangkapan (Tabel 4). Tabel 3. Hasil tangkapan ekor kuning, upaya penangkapan, dan hasil tangkapan per unit upaya di Kepulauan Seribu, tahun 1969–1977 Tahun 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Catch (ton) 890 1.157 1.189 1.304 1.339 1.016 793 919 938 Effort (unit muroami) 17 17 17 21 23 24 23 26 16 CPUE (ton/unit muroami) 52,35 68,06 69,94 62,10 58,22 42,33 34,48 35,35 58,63 Tabel 4. Hasil tangkapan ekor kuning, upaya penangkapan, dan hasil tangkapan per unit upaya di Kepulauan Seribu, tahun 2001–2007 Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 84 Catch (ton) 33,70 30,81 32,99 13,30 4,87 0,49 1,53 194 154 77 Effort (unit muroami) 53 53 53 53 53 53 53 15 15 10 CPUE (ton/unit muroami) 0,64 0,58 0,62 0,25 0,09 0,01 0,03 12,93 10,27 7,7 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Daerah perlindungan (MPA) merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengendalian sumber daya ikan yang lestari. Dengan adanya penetapan daerah perlindungan laut, peningkatan pengawasan secara terpadu diharapkan akan lebih efektif. Selama periode tahun 2008–2009, produksi ekor kuning mengalami peningkatan cukup tajam dengan upaya penangkapan hanya 15 unit armada penangkapan. • Kerapu Produksi kerapu di Kepulauan Seribu selama 3 tahun terakhir (2008– 2010) dari hasil observasi berfluktuasi pada setiap bulannya. Tahun 2008 produksi ikan kerapu 108 kg/tahun, kemudian tahun 2009 mengalami kenaikan yaitu mencapai 505 kg/tahun dan tahun 2010 menurun kembali menjadi 75 kg/tahun (Gambar 10). 30 20 Des Nop Okt Sept Agust Juli Juni Mei 2009 April 0 Mar 2008 Feb 10 Jan Produksi(Kg) 2010 Bulan Gambar 10. Produksi kerapu di Kepulauan Seribu pada tahun 2008–2010 Berdasarkan sumber data Suku Dinas Pertanian dan Kelautan Kepulauan Seribu, produksi ikan kerapu di Kepulauan Seribu disajikan pada Gambar 11. Produksi ikan kerapu pada tahun 2010 berfluktuasi pada setiap bulannya, pada kisaran 68 ekor/bulan–360 ekor/bulan dengan 954 kg/bulan–1.672 kg/bulan. 85 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Produksi(N) 400 300 200 100 0 Januari Febuari Maret April Mei Juni Tahun2010 Produksi(KG) 2000 1500 1000 500 0 Januari Febuari Maret April Tahun2010 Mei Juni Gambar 11. Produksi kerapu di Kepulauan Seribu pada tahun 2010 Sumber Data: Sudin Kelautan dan Perikanan Kab Kepulauan Seribu • Kakatua 1,500 1,000 500 2008 0 2009 Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des Produksi(Kg) Produksi kakatua di Kepulauan Seribu pada tahun 2008 sampai 2010 mengalami kenaikan, berturut-turut 2.359 kg/tahun, 2.795 kg/tahun, dan 3.269 kg/tahun. Produksi selama tahun 2008–2010 berfluktuasi pada setiap bulannya. Gambar 12 menunjukkan bahwa produksi relatif tinggi pada bulan Maret–April dan Oktober–November. 2010 Bulan Gambar 12. Produksi ikan kakatua di Kepulauan Seribu pada tahun 2008–2010 86 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu 4. Kelayakan Usaha Penangkapan dan Pemasaran Pada usaha penangkapan ikan di Pulau Pari, diketahui bahwa ratarata pendapatan yang diperoleh nelayan antara Rp10.000,- sampai Rp109.000,-/RTP/hari. Keragaman nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh musim, jenis, dan jumlah alat tangkap yang dimiliki. Investasi yang diperlukan dalam kegiatan usaha adalah alat tangkap dan alat transportasi, di mana rata-rata investasi yang dikeluarkan nelayan berkisar Rp700.000– Rp8.700.000 (Tabel 5). Hasil analisis pendapatan nelayan menunjukkan bahwa nelayan rampus, bubu bambu, dan nelayan jaring gebur memiliki pendapatan lebih tinggi dari nelayan dengan alat tangkap yang lain. Tingginya nilai pendapatan tersebut sangat berkaitan dengan jenis ikan hasil tangkapan dan jumlah hasil tangkapan. Tabel 5. Nilai Investasi pada beberapa jenis alat tangkap di Pulau Pari, November 2009 Kepemilikan (unit) Jenis Alat Tangkap Investasi (Rp) armada Alat tangkap 1. Pancing Tonda 1 15 8.000.000 75.000 8.075.000 2. Jaring Gebur 1 4 5.000.000 2.000.000 7.000.000 3. Jaring rampus 1 12 5.000.000 1.440.000 6.440.000 4. Bubu Lipat 1 60 5.000.000 900.000 5.900.000 5. Jaring Cendro 1 6 5.000.000 3.600.000 8.600.000 6. Pancing Ulur 1 100 5.000.000 100.000 5.100.000 7. Pancing cumi 1 5 3.500.000 75.000 3.575.000 8. Pengko 1 20 500.000 200.000 700.000 9. Bubu bambu 1 10 500.000 500.000 1.000.000 Armada Alat tangkap Nilai Investasi (Rp) 87 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 6. Kelayakan usaha penangkapan ikan pada beberapa jenis alat tangkap di Pulau Pari, November 2009 Jenis Alat Tangkap Rata-rata Hasil alat yang Tangkapan dioperasikan (kg/Trip) (Unit/RTP) Rp/hari Kelayakan Usaha Rp/Bulan (R/C ratio) Pendapatan 1. Pancing Tonda 3 14 27.850 696.180 1,31 2. Jaring Gebur 1 20,8 73.500 1.838.400 4,15 3. Jaring rampus 12 12,5 109.000 2.725.000 4,94 4. Bubu Lipat 47 4 35.000 875.000 2,43 5. Jaring Cendro 4 7 10.000 250.000 1,31 6. Pancing Ulur 100 3 10.000 250.000 1,90 7. Pancing cumi 5 1,5 10.000 271.000 2,07 8. Pengko 5 1,5 27.000 700.000 5,55 9. Bubu bambu 10 2 100.000 2.500.000 9,95 Sumber: data hasil lapang di olah, November 2009 Hasil analisis terhadap kelayakan usaha penangkapan menunjukkan bahwa pada beberapa jenis alat tangkap, usaha penangkapan ikan cukup menguntungkan dan layak untuk diusahakan, dengan tingkat kelayakan usaha bervariasi antara 1,31–9,95 (Tabel 6). Agar tidak mengalami kerugian operasional, hasil tangkapan yang diperoleh dengan alat tangkap pancing tonda harus lebih dari 8 kg/trip. Hasil tangkapan ikan oleh nelayan, hampir seluruhnya dipasarkan melalui pegepul setempat, dan sebagian kecil lainnya dipasarkan langsung oleh nelayan kepada pengepul di luar pulau pari, khususnya yang berupa ikan hidup (kelompok kerapu dan ikan hias). Di Pulau pari pengepul ikan berjumlah 2 orang. Hasil tangkapan ikan tersebut kemudian didistribusikan ke TPI muara saban, untuk kemudian dipasarkan kepada pengecer dan konsumen. Dengan demikian, saluran pemasaran produksi ikan di gugus pulau pari mengikuti skema berikut (Gambar 13). 88 Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu Produsen 95% Pengecer Pengepul Konsumen 5% Gambar 13. Rantai Pemasaran Hasil Perikanan Pulau Pari Kesimpulan 1. Kepadatan ikan demersal dan karang di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2007 pada kisaran 42 ekor/250 m2 sampai 536 ekor/250m2, didominasi oleh Caesionidae, Nemipteridae, Pomacentridae, Labridae, dan Lethrinidae. Kepadatan ikan dalam kriteria sangat jarang, yaitu pada kisaran kepadatan 1–5 ekor/m2 2. Status pemanfaatan sumber daya ikan demersal dan karang sudah menunjukkan tingkat kejenuhan (over fishing), yang terindikasi dari menurunnya indeks kelimpahan stok ikan tersebut. 3. Usaha penangkapan ikan cukup menguntungkan dan layak untuk diusahakan, dengan tingkat kelayakan usaha bervariasi antara 1,31– 9,95. Daftar Pustaka Anonim. 2007. Data Pendaratan Ikan. TPI Muara Angke. Sudin Kelautan dan Perikanan Jakarta Utara. English S, C Wilkinson and V Baker.1994. Survei manual for Tropical marine Resources. Australian Institute of Marine Science, Townsville. Australia. Hartati ST, Awalludin, dan SW Indar. 2004. Kelimpahan dan komposisi jenis ikan hasil tangkapan bubu di Perairan Gugusan Pulau Kelapa Kepulauan Seribu JPPI. Edisi Sumber Daya dan Penangkapn. Vol. 10 No.4 Tahun 2004. ISSN 0853-5884. 89 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Hartati ST dan IN Edrus. 2010 Struktur komunitas ikan dan kesehatan terumbu karang di beberapa wilayah perairan Gugusan Pulau Pari. Prosiding Nasional Ikan VI dan Kongres Masyarakat Iktiologi Indonesia III. Kuiter RH. 1992. Tropical Reef-Fishes of the Western Pacific Indonesia and Adjacent Waters. Gramedia, Jakarta. Lazuardi ME, NS Wijoyo, 2000. Perubahan kondisi terumbu karang di Gugusan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta. Pros. Lok. Pengelolaan & Iptek Terumbu Karang Indonesia. Jakarta. Lieske E and R Myers. 1997. Reef Fishes of the World. Jakarta: Periplus Edition. Subani W. 1978. Studi Perikanan Muroami Sebagai Penunjang Perikanan Rakyat. LPPL. Jakarta. Thomas GT and PJ Kailola. 1984. Trawled Fishes of Southern Indonesia and Northwestern Australia. Warsa A dan BI Purnawati. 2010. Kondisi Lingkungan dan terumbu Karang di Daerah Perlindungan Laut Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. BAWAL. Widya Riset Perikanan Tangkap. Vol 3 No. 2: 115–121. 90 Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Siti Nuraini*, Prihatiningsih*, Wahyuningsih dan Wejatmiko* Abstrak Kajian status sumber daya kekerangan didasarkan hasil penelitian Teluk Jakarta tahun 1995–2010 dan pada September 2011. Secara umum perikanan kekerangan bersifat skala kecil dengan alat garuk dan menyelam. Armada garuk dioperasikan oleh nelayan Cirebon dengan kapal berukuran 9x2x1 m dengan motor diesel dan tempel 17–24PK . Secara spasial, kekerangan dijumpai di bagian barat Teluk Jakarta yaitu di perairan Tanjung Kait, di bagian timur dijumpai di perairan Bendera dan Tanjung Kerawang. Di kawasan pesisir Kamal, Ancol, Marunda, dan Cilincing ke utara sudah tidak dijumpai kekerangan. Terlihat perubahan densitas benih kerang secara signifikan dalam waktu 2,5 dekade. Beberapa jenis kerang ekonomis penting sudah tidak dijumpai. Produksi dan kelimpahan kekerangan sangat menurun karena berkurangnya daerah penangkapan dan upaya penangkapan. Kata kunci : Status pemanfaatan, kekerangan, Teluk Jakarta * Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Teluk Jakarta secara geografis merupakan bagian dari Laut Jawa dan secara administratif mencakup tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Perairan Teluk Jakarta termasuk perairan yang terbuka dengan kedalaman maksimum sekitar 25 m dengan kemiringan dasar laut ke arah utara semakin dalam dan ke arah pantai semakin dangkal (± 2 m) serta pantai sekitar 21 mil laut. Perairan Teluk Jakarta bermuara di 13 sungai, empat di antaranya adalah sungai besar yaitu Sungai Cisadane di bagian barat, Sungai Ciliwung bagian tengah, Sungai Citarum dan Sungai Bekasi pada bagian timur. Endapan hasil sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai membentuk delta dengan topografi yang umumnya lumpur dan pasir. Kondisi topografi perairan pantai yang berlumpur serta melimpahnya nutrient yang berasal dari run off sungai-sungai yang bermuara di teluk Jakarta menjadikan kawasan pantai sebagai habitat yang sesuai bagi kehidupan berbagai jenis kekerangan. Kekerangan (Bivalvia) mempunyai mekanisme adaptasi yang besar untuk melangsungkan aktivitas kehidupannya sehingga dapat dijumpai pada berbagai ekosistem perairan laut. Selain pada ekosistem pantai lumpur berpasir (estuaria), kekerangan juga dijumpai di bakau dan terumbu karang. Secara ekonomi kekerangan mempunyai nilai ekonomis yang rendah, akan tetapi kekerangan dikenal mempunyai kandungan protein tinggi yang berguna bagi pemenuhan gizi masyarakat dengan harga relatif murah. Dengan semakin berkurangnya lapangan kerja yang berdampak meningkatnya pengangguran telah mendorong eksploitasi kerang di kawasan pantai. Peningkatan penangkapan dan penurunan kualitas perairan karena buangan limbah (domestik dan industri) di kawasan teluk menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya baik secara kuantitas maupun kualitas. Kekerangan merupakan biota yang menetap (sessile) di dasar perairan. Hidupnya sebagai pemakan plankton dengan menyaring (filter feeder). Sebagai biota yang tidak aktif bergerak dan menetap di suatu, kekerangan seringkali digunakan sebagai indikator pencemaran suatu perairan. Dari kajian kandungan logam berat (Pb, Hg, Cd, Cu, As) di dalam daging kerang dara (Anadara granosa) di Tanjung Kait menunjukkan bahwa kerang masih dalam batas aman untuk dikonsumsi (Murtini dan Ariyani 2005) 92 Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Kajian mengenai sebaran, kelimpahan bentos, plankton dan lingkungannya di perairan Teluk Jakarta sudah banyak dilakukan (Juanita et al. 2007). Informasi mengenai kelimpahan dan pemanfaatan SD kekerangan di perairan teluk Jakarta sangat sedikit. Lebih dari 30 jenis moluska dijumpai di perairan teluk. Saat ini kerang hijau (Perna viridis) merupakan jenis kerang potensial dan dibudidayakan di Teluk Jakarta (Anonimous 2005, 2006). Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sumber daya beserta pemanfaatannya di perairan Teluk Jakarta dan sekitarnya. Bahan dan Metode Lokasi Penelitian Perairan Teluk Jakarta merupakan perairan dangkal dengan kedalaman perairan di setiap stasiun pengamatan berkisar 7,5–25 m. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh bahwa sebaran suhu permukaan berkisar 27,45oC–9,30oC dengan rata-rata 28,20 ± 0,32oC. Pada perairan muara sungai suhu berkisar 28,14oC–30oC. Salinatas berkisar 27,45–31.98 ppm. Salinitas rendah di jumpai di muara sungai pada musim barat. Kecerahan di kawasan laut berkisar 1,5–5,5 m. Kecerahan rendah dijumpai dekat kawasan pantai dan muara sungai. Semakin ke utara, kecerahan semakin tinggi. Sumber data Kajian didasarkan hasil pemantauan Teluk Jakarta bekerjasama dengan BPLH, DKI dan BRPL tahun 1995–1997, 2004–2010 di perairan Teluk Jakarta, kajian P3O LIPI tahun 1975–1979 di perairan Teluk Jakarta dan Kajian BRPL tahun 2006, 2008 di Pulau Pari, Kepulauan Seribu serta dilengkapi dengan hasil updating data perikanan kerang pada bulan September tahun 2011 di Kamal dan Cilincing. Produksi kerang tahunan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pengumpul kerang di tempat pendaratan kerang di Kamal dan Cilincing serta buku bakul. Musim kerang diasumsikan tiap tahun hanya 3 bulan, dengan demikian produksi dihitung sebagai berikut. Produksi = Jumlah upaya (jumlah kapal kerang) x trip x tiga bulan. 93 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Gambar 1. Lokasi stasion pengamatan pemantauan perairan Teluk Jakarta tahun 1995–2011 Hasil 1. Jenis dan kelimpahan kekerangan di perairan laut Teluk Jakarta Hasil pengamatan tahun 1977–1978 di perairan Teluk Jakarta dengan beam trawl dijumpai 103 jenis (Kastoro et al, 1980). Jenis yang tertangkap antara lain Strombus, Conus, Anadara, Scaparca, Crassostrea, Paphia, Donax sp., Turitella sp.; jenis dominan tertangkap yaitu Strombus L. canarium (Gonggong/siput laut), Spondylus S. imperialis, dan Amusium pleuronectes. Hasil perhitungan keragaman jenis dari tahun 1977 sampai 1979 belum menunjukkan adanya penurunan jumlah jenis. Artinya, belum ada jenis yang punah dari perairan laut Teluk Jakarta. 94 Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Pemantauan makrozoobentos tahun 1995–1997 dengan menggunakan grab di perairan Teluk Jakarta diperoleh lebih dari 40 jenis makrozoobentos termasuk di dalamnya benih kerang (Anonimous 1995, 1997; Anonimous 2010). Benih kekerangan yang dijumpai antara lain kerang bulu dan kerang dara (Anadara spp.), tiram/mata tuju (Crassostrea sp.), Conus spp., dan kerang tahu (Paphia), Mendosa spp., Gonggong (Strombus spp.). Pada tahun 1995 sampai 1997, benih kerang (Anadara spp.) tersebar dan dijumpai pada kawasan pesisir sekitar muara sungai di sekitar perairan Tanjung Kait (stasion A1, A2, dan B1), muara Sungai Angke (C2), muara Sungai Ancol (stasion D3), muara Marunda (D6), dan sekitar Tanjung Gembong (Stasion B5 dan B6). Kepadatan tertinggi benih kerang darah di perairan teluk Jakarta pada tahun 1995 dijumpai di muara Sungai Ancol (stasion D3) dengan kepadatan 9.214 ind/m2. Pada stasiun lainnya, kepadatan berkisar 1 sampai 81 ind/m2. Pada tahun 1996 kepadatan tertinggi dijumpai pada stasion D3 perairan Ancol (81 ind/m2) dan pada tahun 1997 dijumpai di sekitar perairan Muara Gembong B6 (526 ind/m2). Rata-rata kepadatan kerang darah tahun 1995 diperoleh 415 ind/m2. Pada tahun 1996 rata-rata kepadatannya menurun sebesar 11,5 ind/m2 dan tahun 1997 turun sebesar 100 ind/m2. Pada tahun 2004 benih Anadara spp. hanya dijumpai di sekitar perairan Tanjung Kait (B1: 175 ind/m2), A3 (25 ind/m2) dan A4 (254 ind/ m2) serta di muara Ancol (D3:50 ind/m2). Pada tahun 2006 sampai 2010, benih kerang dara sudah tidak dijumpai lagi di semua stasion pengamatan. Sebaran kepadatan rata-rata benih kerang Anadara spp. tahun 1995–1997 disajikan pada Gambar 2. 95 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya -5.7 Laut Jawa -5.8 Tanjung Karawang Lintang Selatan -5.9 -6 Tanjung Gembong -6.1 Muara Gembong Kepadatan (ind./m2) -6.2 Muara Kamal Muara Cengkareng Muara Sunter Muara Angke Muara Karang Muara Marunda Muara Cakung Muara Ancol 4 to 10 10 to 14 14 to 25 -6.3 25 to 65 65 to 2367 -6.4 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur Gambar 2. Sebaran densitas Anadara spp. (ind/m2) di perairan laut Teluk Jakarta pada 1995–1997 Pada Pulau Kongsi dengan ekosistem habitat pasir dan pecahan karang, di dijumpai 17 jenis bivalvia, termasuk di dalamnya Arciidae, Lucinidae, Metlynidae, Pinnidae, Tellinidae, Veneridae, Vulsellidae, Cardidae, Mesodesmatidae, dan Fimbriidae (Supriadi 2003). Jenis yang mendominasi habitat pasir dan pecahan karang yaitu Arca avellana dan kerang buel (Codakia tigerina). Kepadatan tertinggi di perairan Pulau Kongsi dijumpai sebesar 128 ind/m2. Jenis lainnya yang dimanfaatkan oleh nelayan pesisir Pulau Kongsi dan kepulauan Seribu yaitu kima, Tridacna gigas, gonggong (Strombus urceus), kapak (Pinna bicolor), mata tuju, Crassostrea sp., kede (Lambis lambis), kerang bulu (Scaparca pilula, Isognomon perna, dan Scaparca indica). Berdasarkan hasil pencatatan harian hasil tangkapan nelayan kerang yang didaratkan di Dadap dan Kamal, diperoleh kerang bulu (Scaparca cornea) sebesar 46% dan kerang dara (Anadara nodifera) 39%. Jenis lainnya 96 Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya yang tertangkap yaitu jenis keong macan (Babylonia sp.), kerang Bambu Solen sp.), kerang darah (Anadara granosa), kerang gelatik (Anadara sp.), gonggong (Strombus urseus), Simping (Placuna placenta). Komposisi jenis hasil tangkapan garuk yang didaratkan di Kamal disajikan pada Gambar 3. 8% 1%2% 4% 46% 39% Scaparca cornea A. nodifera Anadara sp. Turritella sp. Strombus canarium Phaphia undulata Gambar 3. Komposisi jenis kekerangan di perairan Kamal-Tanjung Kait, Tangerang Banten pada bulan Agustus–September 2011 2. Aspek Penangkapan Kerang di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dijumpai pada habitat pasir, lumpur berpasir, dan pasir dengan pecahan karang. Usaha pemanfaatan kekerangan di perairan Teluk Jakarta dilakukan dengan alat tangkap garuk, dengan menyelam dan budi daya. Selanjutnya akan dibahas secara mendalam alat tangkap garuk sebagai alat tangkap utama kekerangan 2.1. Alat, Daerah, Musim Penangkapan dan Laju Tangkap Usaha penangkapan kerang di perairan Teluk Jakarta dilakukan oleh nelayan andon dari Cirebon. Daerah penangkapan armada garuk meliputi perairan Cirebon, Tangerang, Teluk Jakarta, Tanjung Kait, dan Tanjung 97 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Karawang (Bekasi), Serang (perairan Pontang, Bojonegara, Tengkurak, Pulau Burung, dan Pabean), dan Lampung. Lamanya trip penangkapan dalam satu hari (one day fishing) dari jam 05.00 sampai 14.00 atau 17.00. Dalam satu trip sebanyak 7 sampai 8 tawur. Kapal yang digunakan yaitu kapal kayu berukuran panjang 8–10 m x 1,8–2 m x 1 m. Mesin penggerak yang digunakan adalah diesel 16–24 PK. Jumlah ABK 3–4 orang. Garuk berbentuk segitiga samakaki dan terbuat dari bahan besi yang dilengkapi dengan kantong jaring dengan tinggi 70 cm. Mulut garuk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 175 cm tinggi 20 cm. Pada mulut garuk terdapat jari-jari besi dengan panjang 15 cm dan jarak masingmasing jari 2 cm (Gambar 4). Gambar 4. Garuk alat tangkap kekerangan yang digunakan di perairan Teluk Jakarta Penangkapan kerang dilakukan sepanjang tahun. Pola musim penangkapan dengan garuk tidak menentu, artinya penangkapan tidak selalu terjadi setiap tahun. Misalnya pada tahun 2009 dan 2010, populasi kerang kerang Anadara di perairan Teluk Jakarta tidak ada. Musim penangkapan berlangsung sekitar 3 bulan pada bulan Juli sampai Desember dengan puncak musim pada bulan Juli. 98 Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Laju tangkap (CPUE) dapat digunakan sebagai indeks kelimpahan sumber daya ikan (kerang) yang menunjukkan jumlah kerang yang tertangkap di suatu lokasi pada waktu tertentu. Berdasarkan pencatatan harian tangkapan nelayan garuk yang didaratkan di Dadap dan Kamal pada bulan Agustus sampai September 2011, dari 101 trip diperoleh hasil tangkapan sebesar 25,8 ton. Hasil tangkapan kerang per perahu berkisar 6–725 kg per trip dengan rata-rata tangkapan keseluruhan sebesar 255,04 kg/trip. Variasi hasil tangkapan per individu nelayan dapat dilihat pada Tabel 1 . Tabel 1. Hasil tangkapan (CPUE: kg/trip) nelayan garuk harian di perairan Tanjung Kait pada bulan Agustus–September 2011 Nelayan 1 2 3 4 5 6 7 Rata2 CPUE (kg/trip) 255,0 259,3 376,1 236,2 200,9 175,4 213,8 SD (kg/ CPUE CPUE trip) Maksimum Minimum 88,7143 398 115 113,6327 353 77 134,3870 725 181 100,9421 435 79 88,1069 329 6 104,2107 338,5 33 103,1566 371,5 74 Jumlah Trip 13 11 23 13 14 17 10 Selain dengan garuk, penangkapan kerang dilakukan dengan menyelam menggunakan kompresor. Lama trip penangkapan satu hari (one day fishing). Daerah penangkapan sekitar Tanjung Kait dan Marunda. Jenis kerang yang ditangkap yaitu kerang kepah/kerang batik (Meritrix meritrix, Phaphia undulata, Polimedosa) dan kerang bambu (Solen stritus). Hasil tangkapan harian berkisar 5 kg per trip. 2.2. Produksi Hasil tangkapan kerang dengan garuk dari perairan Tanjung Kait, Tanjung Karawang, Teluk Jakarta dan sekitarnya didaratkan di Tanjung Kait Dadap, Kamal, Tangerang, Tanjung Kait, Kali Adem, Marunda, 99 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Cilincing. Penangkapan kerang dikelola oleh pengumpul kerang. Jumlah armada garuk yang menangkap kerang sangat bervariasi jumlahnya. Pada saat produksi melimpah, jumlah armada meningkat dan sebaliknya. Jumlah pengumpul dan kapal yang digunakan disajikan pada Tabel 2 dan perkembangan produksi kerang disajikan pada Tabel 3. Tabel 2. Lokasi pendaratan kerang, jumlah pengumpul dan perkiraan jumlah armada garuk di perairan Teluk Jakarta tahun 2011 Lokasi Pendaratan Jumlah Pengumpul Dadap, Kamal Cilincing Kali Adem Tanjung Pasir 3 4 4 10 Jumlah Perahu Musim Tidak Musim 60 10 34 14 4 2 60 20 Didasarkan data hasil wawancara dengan pengumpul dan nelayan garuk di Kamal dan Cilincing, perkembangan produksi kerang Anadara dan kerang tahu pada tahun 1995 hingga 2011 menunjukan penurunan produksi yang signifikan (Tabel 3). Tabel 3. Estimasi perkembangan produksi kerang Anadara dan kerang tahu di perairan Teluk Jakarta pada tahun 1995–2011 Periode tahun 1995–2000 2001–2003 2004–2005 2006–2008 2011 100 Rata-rata perahu 100 100 100 50 30 Rata-rata Laju tangkap (kg/trip) 250–2.000 250–1.000 200–500 150–400 100–350 Produksi (ton) 12.850 6.530 2.740 1.205 310 Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Penurunan produksi kerang ini sejalan dengan berkurangnya jumlah benih kerang Anadara dari stasion pengamatan di perairan Teluk Jakarta. Pada tahun 1995–1997, benih masih tercatat melimpah. Menghilangnya benih kerang di perairan muara dan Teluk Jakarta pada tahun 2005–2006 diduga disebabkan tingginya intensitas penangkapan kerang. Pada 2–3 dekade yang lalu, hasil tangkapan kerang bulu di perairan Kamal dan sekitarnya dapat mencapai 2–3 ton per perahu per hari, hasil tangkapan menurun sebesar 400–500 kg per perahu per hari pada tahun 2005. Selain itu, penurunan produksi disebabkan berkurangnya daerah penangkapan karena konflik dengan nelayan jaring rajungan. Selain tekanan penangkapan, penyebab punahnya benih kerang di hampir semua perairan Teluk Jakarta diduga karena penurunan kualitas air (pencemaran limbah industri dan domestik). Penurunan kualitas air dapat menyebabkan kematian kerang karena kerusakan hati dan insang kerang hijau (BRPL 2006). 3. Struktur Ukuran Hasil analisis data frekuensi panjang jenis kerang dominan yaitu kerang dara (Anadara nodifera) dan kerang bulu A. cornea (synonym A. inaequivalvis), kerang batik/kerang tahu (Paphia undulata, Meritrix meritrix) diperoleh: • Kerang bulu (Scaparca cornea) (synonym A. inaequivalvis) Kerang bulu tertangkap di perairan Teluk Jakarta pada bulan September 2011 dengan ukuran 18,93–40,88 mm. Pada Gambar 5 terlihat 2 modus pada panjang 26 cm dan 32 cm. Berdasarkan kurva logistik sebaran frekuensi panjang, pada posisi 50% rata-rata ukuran tertangkap dengan garuk di perairan Tanjung Kait, Teluk Jakarta, Lc50% = 28 mm. 101 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Kerang bulu, Scaparca cornea 25 Frek (% ) 20 15 10 5 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Panjang (mm) Kerang bulu, Scaparca cornea % Cum catch 100 75 50 25 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Panjang (mm) Gambar 5. Struktur ukuran dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang kerang bulu (Scaparca cornea) yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 28 mm) • Kerang dara (Anadara nodifera) 102 Pada bulan September 2011, kerang dara (Anadara nodifera) merupakan jenis kerang yang banyak tertangkap di perairan Teluk Jakarta saat ini. Kerang yang tertangkap berukuran lebih kecil (21,95–28,03 mm). Modus dijumpai pada panjang 25 mm (Gambar 6). Berdasarkan kurva logistik sebaran frekuensi panjang, pada posisi 50% rata rata ukuran tertangkap dengan garuk di perairan Tanjung Kait, teluk Jakarta, Lc50% = 24,33 mm. (Gambar 6). Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya Kerang darah, Anadara nodifera (n:100) 30 F rek (%) 25 20 15 10 5 0 21 22 23 24 25 26 27 28 Panjang (mm) Kerang darah, Anadara nodifera Cu m m . C atch (% ) 100 75 50 25 0 21 22 23 24 25 26 27 28 Lebar (mm) Gambar 6.Struktur ukuran (a) dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang (b) kerang darah (Anadara nodifera) yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 24,33mm) • Kerang tahu (Paphia undulata) Kerang tahu merupakan kerang yang banyak tertangkap di perairan yang dangkal di kawasan Teluk Jakarta (Tanjung Kait, muara Sungai Blencong, Marunda). Kerang yang tertangkap berukuran 37,04– 51,02 mm. Modus dijumpai pada panjang 44 mm. Berdasarkan kurva logistik sebaran frekuensi panjang, pada posisi 50% rata rata 103 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya ukuran kerang tertangkap dengan garuk di perairan tanjung Kait, teluk Jakarta, Lc50% =43,0 mm. (Gambar 7). Kerang yang tertangkap di atas nilai Lm (length at first maturity). Phaphia undulata (88) 35 F rek (% ) 28 21 14 7 0 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Panjang (mm) Kerang tahu, Phapia undulata % C u m C atch 100 75 50 25 0 36 38 40 42 44 46 48 Panjang (mm) 50 52 Gambar 7. Struktur ukuran dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang kerang tahu, Phaphia undulata yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 43mm) • Kerang batik, Meritrix lyrata 104 Kerang batik Meritrix lyrata merupakan kerang yang hidupnya menggerombol yang banyak tertangkap di perairan yang dangkal di kawasan Teluk Jakarta (Tanjung Kait, muara S. Blencong, Marunda). Kerang yang tertangkap berukuran 31,27–41,87 mm. Modus dijumpai Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya pada panjang 33–35 mm. Berdasarkan kurva logistik sebaran frekuensi panjang, pada posisi 50% rata rata ukuran tertangkap dengan garuk di perairan tanjung Kait, teluk Jakarta, Lc50% =33,9 mm (Gambar 8). Kerang batik, M. lyrata (n:101) 25 F re k (% ) 20 15 10 5 0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Panjang (mm) Kerang batik, Meritrix lyrata Cum m . catch (% ) 100 75 50 25 0 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Panjang (mm) Gambar 8. Struktur ukuran dan % kumulatif sebaran frekuensi panjang kerang batik (Meritrix lyrata) yang didaratkan di Kamal pada bulan September 2011 (Lc50% = 33,9 mm) Kesimpulan 1. Jenis kerang mengalami penurunan jumlah, dari 103 jenis tahun 1977 menjadi 40 jenis pada tahun 1995. Jenis kerang dara dan kerang bulu (Anadara spp.) punah dari stasion pengamatan pada tahun 2006. 105 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 2. Indeks kelimpahan stok kerang di Teluk Jakarta telah mengalami penurunan dan hal ini mengindikasikan telah terjadi overfishing dalam pemanfaatannya. 3. Daerah penangkapan kerang pada saat ini semakin menyempit hanya di sekitar Tanjung Kait, yang diakibatkan karena pencemaran dan konflik dengan nelayan rajungan. Daftar Pustaka Andamari R dan W Ismail. 1983. Telaah produksi kerang hijau (Perna viridis, L.) di pantai Ketapang, Mauk, Tangerang. Lap. Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta, Vol.6 : 21–28 Anonimus. 1995–1997. Laporan Hasil pemantauan Perairan Teluk Jakarta dan Muara Sungai . Balai Penelitian Perikanan Laut. Laporan intern. Annimous. 2005–2010. Laporan Hasil Pemantauan Perairan Teluk Jakarta dan Muara Sungai. Balai Riset Perikanan Laut. Juanita II, ST Hartati dan Prihatiningsih. 2006. Perkembangan Kondisi Sumber daya Kerang Hijau (Perna viridis) di Perairan Teluk Jakarta. Kastoro W, A Djamali, dan SoedibyoBS. Penelahaan tentang Komunitas Moluska di Perairan Teluk Jakarta. Dalam Teluk Jakarta. Pengkajian Fisika, Kimia, Biologi dan Geologi tahun 1975-1979.hal.: 249–269 Murtini JT dan F Ariyani. 2005. Kandungan Logam Berat Kerang Dara (Anadara granosa) dan Kualitas Perairan di Tanjung Pasir, Jawa Barat. JPPI vol.11 no. 8 Supriadi D. 2003. Struktur komunitas Bivalvia di Daerah Pasang Surut Pulau Kongsi, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Skripsi. Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor.49 hal. 106 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Bambang Sumiono 1), Karsono Wagiyo 2), Duranta Kembaren 2), dan Prihatiningsih 2) Abstrak Perairan Teluk Jakarta merupakan salah satu daerah penangkapan sumber daya rajungan penting di pantai utara Jawa. Jaring insang dan bubu merupakan alat tangkap rajungan yang banyak digunakan. Penelitian tentang perikanan rajungan di perairan Teluk Jakarta telah dilakukan pada tahun 2007–2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang alat penangkapan, laju tangkap, ukuran individu dan beberapa faktor lingkungannya. Pengumpulan data dengan cara mengikuti kegiatan nelayan setempat dan pengumpul rajungan di pantai utara Tangerang dan Jakarta serta di Pula Lancang, Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa. Alat tangkap utama untuk menangkap rajungan adalah jaring rajungan (lokal: kejer) dan bubu lipat, sedangkan sero dan bagan digunakan untuk hasil tangkapan ikutan. Produksi rajungan cenderung menurun sejak tahun 2006. Pada bulan April–Mei 2007, laju tangkap rajungan tertinggi (23 kg/hari) terdapat pada bubu lipat, diikuti oleh jaring rajungan, sedangkan terkecil (3,25 kg/hari) terdapat pada bagan tancap. Rata-rata ukuran rajungan yang 1) Peneliti pada Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur. Jakarta-14440 2)Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut. Jln. Muarabaru Ujung. Jakarta-14430 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya tertangkap dengan jaring insang relatif lebih besar. Hubungan lebar karapasberat individu bersifat isometrik yang berarti pertambahan panjang sebanding dengan pertambahan beratnya. Kata Kunci: rajungan, alat tangkap, biologi, Teluk Jakarta Pendahuluan Rajungan (Portunus pelagicus Linn) tergolong hewan yang hidup di dasar laut dan berenang ke dekat permukan laut untuk mencari makan, sehingga disebut pula swimming crab atau blue swimming crab yang artinya kepiting perenang. Dalam perdagangan dibedakan dengan kepiting bakau (Scylla serrata) yang lebih banyak diam di dasar perairan sekitar bakaubakau. Stephenson (1962) dan Kailola et al. (1993) menyebutkan bahwa penyebaran rajungan terutama terdapat di daerah estuaria dan pantai di kawasan Asia dan Pasifik Barat. Menurut Bussiness News (1989), di antara berbagai jenis rajungan dan kepiting di Indonesia, Portunus pelagicus merupakan salah jenis yang mempunyai nilai ekspor yaitu dalam bentuk beku segar tanpa kulit atau daging rajungan dalam kaleng. Menurut DKP (2007), pada tahun 2000–2005 ekspor rajungan menempati urutan keempat dalam volume dan nilai ekspor perikanan dari Indonesia setelah komoditi udang, tuna, dan ikan lainnya. Peningkatan nilai ekspor rajungan rata-rata sebesar 8,79% per tahun. Sampai dengan akhir 2005, pangsa pasar utama komoditas perikanan Indonesia adalah Jepang, diikuti oleh Amerika (USA) dan Uni Eropa (UE). Ditinjau dari nilai ekspor menurut negara tujuannya, sejak tahun 2004 pangsa pasar ke USA lebih baik daripada Jepang. Data dan informasi tentang perikanan rajungan di Indonesia masih belum banyak diperoleh. Sementara menurut Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI), dalam lima tahun terakhir ini volume ekspor rajungan cenderung menurun yang diikuti oleh menurunnya ukuran (size) individu rajungan. Eksploitasi yang tidak terkontrol disertai dengan perubahan lingkungan perairan ditengarai penyebab menurunnya populasi rajungan di alam. Menurut Antara News (2008) produksi rajungan di daerah 108 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Cirebon cenderung menurun sejak tahun 2000. Penurunan itu diikuti oleh semakin banyaknya ukuran rajungan relatif kecil (lebih dari 100 ekor per kg). Penelitian oleh Moosa dan Juwana (1996) dan Sumiono (1997) menyebutkan daerah penyebaran rajungan di Indonesia terutama terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan Sulawesi Selatan. Perairan Teluk Jakarta merupakan salah satu penghasil rajungan yang cukup penting di utara Jawa selain Labuhan, Cirebon, Brebes, dan Rembang. Di Teluk Jakarta rajungan dikenal sebagai salah satu komoditas sumber daya yang dominan tertangkap setelah ikan petek, teri dan tembang, di mana kegiatan penangkapannya dilakukan oleh nelayan tradisional. Alat tangkap ikan yang telah berkembang di kawasan pantai Teluk Jakarta antara lain sero, bagan, jaring rampus, jaring dogol, jaring arad, sero, pukat, bubu, dan bondet (Karsono et al. 2006 ) Sesuai dengan sifat rajungan, bahwa sebagian besar suka berada di dasar atau dekat dasar perairan, alat tangkap yang digunakan adalah jenis alat yang dioperasikan sampai ke dasar perairan, antara lain jaring insang (gillnet), pukat pantai (beach seine), dan bubu (trap net). Efektivitas dan daya tangkap alat tangkap berbeda menurut desain alat tangkap, bahan baku dan cara pengoperasiannya (Nomura 1974; Sumiono dan Widodo 1987). Bangsa Krustasea yang terdiri dari udang, kepiting, dan rajungan dapat tertangkap oleh jaring karena terpuntal (gilled) oleh tonjolantonjolan atau gerigi pada permukaan tubuhnya. Daerah yang disenangi adalah habitat lumpur campur pasir. Selanjutnya Prasad dan Tampi (1953) dalam Moosa dan Juwana (1996) menyatakan bahwa rajungan dapat hidup di perairan dengan suhu dan salinitas yang bervariasi. Stadia burayak (yuwana) terdapat di daerah dengan kadar salinitas rendah dan seterusnya berkembang menjadi dewasa yang memerlukan salinitas relatif tinggi. Romimohtarto (1977) mengemukakan rajungan terdapat di perairan Teluk Jakarta dan Pulau Pari pada suhu rata-rata 29,18oC dengan salinitas rata-rata 31,36 ppt. Tulisan ini membahas secara ringkas tentang perikanan rajungan di perairan Teluk Jakarta meliputi aspek perikanan (dekripsi alat tangkap, laju tangkap, dan daerah penyebaran) dan aspek biologi (ukuran lebar karapas, berat individu, dan sex ratio). 109 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Bahan dan Metode Penelitian rajungan (Portunus pelagicus Linn) di perairan Teluk Jakarta dilakukan pada tahun 2007–2009. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan nelayan penangkap rajungan di laut dengan berbagai alat tangkap serta pengumpulan data dan wawancara dengan pengumpul rajungan di utara Tangerang, Jakarta, dan Kepulauan Seribu (Pula Lancang, Pulau Pramuka, dan Pulau Kelapa). Analisis hubungan lebar karapas-berat rajungan ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut (Bal dan Rao 1984): W = aLb. .............................................................................................. (1) Dimana : W = berat rajungan (gram); L = lebar karapas (mm); a = intercept (faktor kondisi) dan b = slope (koefisien pertumbuhan) Jika: b = 3 :Pertumbuhan bersifat isometrik (pertumbuhan panjang sebanding dengan pertumbuhan berat). b < 3 :Pertumbuhan bersifat alometrik negatif (pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertumbuhan berat). b > 3 :Pertumbuhan bersifat alometrik positif (pertumbuhan berat lebih cepat dari pertumbuhan panjang) Untuk mengetahui apakah nilai b yang diperoleh lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari 3 digunakan uji t: ¦d 2 S xy 110 ¦ xy ¦y x ¦ 2 2 xy 2 2 ¦d 2 xy n2 ................................................................ (2) . ................................................................................ (3) Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Sb 2 S 2 xy ........................................................................................ (4) ¦ x2 sb 2 .......................................................................................... (5) 3b . .................................................................................... (6) Thitung Sb Di mana: Sb Sb= simpangan baku dari b Uji tabel dalam taraf nyata 95% (n-2) Hipotesa Ho : b=3 (isometrik) Hi: b ≠ 3 (alometrik positif atau negatif) t hitung > t tabel = beda nyata (tolak Ho terima Hi) t hitung < t tabel = tidak berbeda nyata (terima Ho tolak Hi) Hasil dan Pembahasan 1. Daerah Penangkapan Penangkapan dengan bubu rajungan dilakukan di sekitar Muara Angke, perairan utara Cilincing, dan Kepulauan Seribu (sekitar Pulau Lancang, Pulau Pramuka). Penangkapan dengan gillnet monofilemen (lokal: jaring rajungan) dilakukan di perairan sekitar Pulau Onrust, Pulau Bidadari hingga ke Pulau Untung Jawa dengan kedalaman perairan antara 5–15m (Gambar 1). Daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan sero bambu dan bagan tancap lebih banyak terdapat di daerah pantai dengan kedalaman relatif lebih dangkal (Gambar 2). Menurut Kailola et al. (1993), rajungan dewasa dapat dijumpai pada kedalaman antara 30– 50m. 111 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 5.92 SKALA 1 : 50000 1 5 2 4 11 8 2 6.00 5 94 10 5 8 10 6.08 Lokasi aktivitas tangkap 6.17 106.67 Bubu. rajungan Gillnet rajungan 106.75 106.83 106.92 107.00 Gambar 1. Daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan bubu dan gillnet rajungan di perairan Teluk Jakarta Bagan Sero . Gambar 2. Daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan sero dan bagan di perairan Teluk Jakarta 112 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Perbedaan ukuran rajungan yang tertangkap erat kaitannya dengan lokasi daerah penangkapan rajungan. Lokasi sero dan bagan terletak di daerah muara sungai atau perairan pada kedalaman kurang dari 5 meter. Daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan bubu dan gillnet terletak lebih ke tengah (arah utara dari Teluk Jakarta) pada kedalaman lebih dari 30 m. Menurut Bellchambers dan de Lestang (2005), perairan Estuaria merupakan daerah asuhan rajungan, artinya rajungan yang tertangkap di perairan ini merupakan rajungan muda dan umumnya berukuran kecil. Dalam pertumbuhannya, rajungan akan beruaya ke perairan lebih dalam untuk melakukan pemijahan. 2. Alat Tangkap 2.1 Bubu lipat rajungan (collapsible traps) Kegiatan penangkapan rajungan dengan bubu dilakukan secara harian (one-day fishing) maupun lebih dari sehari (antara 4–5 hari). Kapal dengan panjang 6 m, lebar 2,8 m, tinggi 1,5 m dengan kekuatan mesin 22 DK digunakan untuk transportasi ke dan dari daerah penurunan bubu. Bahan utama bubu adalah kawat, jaring polyethelene (PE), dan tali (Gambar 3). Jumlah bubu dalam satu unit dapat mencapai 200 buah dengan jarak antar bubu sekitar 10 meter. Setiap 100 bubu diberi pelampung berbendera. Umpan yang digunakan adalah potongan ikan. 113 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Mulut bubu Gambar 3. Bubu rajungan yang digunakan perairan di Teluk Jakarta Keterangan: Merupakan setengah dari panjang bubu; (B) Lebar bubu ; (C) Tinggi bubu; (D) Jarak antara dasar bubu dengan tempat masuknya rajungan mulut bubu ; (E) Jarak antara atas ujung bubu dengan mulut bubu; (F) Jarak antara bawah ujung bubu dengan mulut bubu; (G) Tempat gantungan umpan; (H) Kunci penutup. 2.2 Jaring rajungan (Monofilament gillnet) Jaring rajungan (lokal: kejer) dengan mata jaring berukuran 4 inci, bersifat tidak selektif terhadap rajungan, karena prinsip tertangkapnya rajungan adalah secara terbelit/terpuntal (entangled) oleh adanya tonjolan atau duri-duri di sebagian tubuhnya. Sebaliknya, bila ditujukan untuk menangkap ikan, jaring kejer bersifat selektif (Hamley 1975; Nomura dan Yamazaki 1975; Fridman dan Carrothers 1986 ;Kawamura 1972; 114 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Matsuoka 1995). Menurut kriteria Sarman (1998) dalam Susanto (2007), gillnet yang ditujukan untuk menangkap rajungan atau kepiting dapat dikategorikan sebagai alat tangkap tidak ramah lingkungan. Deskripsi unit jaring rajungan milik nelayan Muara angke terdiri dari tali ris atas, tali ris bawah (bahan PE diameter 0,8–1,3 mm), badan jaring (nilon monofilamen berdiameter 0,20 mm) dengan ukuran mata jaring (mesh size) sebesar 4 inci (Gambar 4). Penangkapan pada umumnya berlangsung pada malam hari dengan setting sebanyak 4 kali. Trip penangkapan dilakukan selama satu hari (one-day fishing). 42m Pelampung karet n = 16 buah PA monofilament Mesh size 4,0 inci 0.8m Pemberat timah (n=20), Berat total 4 kg Gambar 4. Rancang bangun 1 pis jaring kejer di daerah Muara Angke (Jakarta Utara) 2.3. Sero (Guiding barrier) Sero jaring merupakan alat penangkapan ikan yang dioperasikan di daerah perairan pantai. Alat ini bersifat menetap (stationary) dan berfungsi sebagai perangkap (trap) bagi ikan-ikan yang melakukan gerakan ke pantai atau ikan-ikan yang habitatnya di pantai. Sero dipasang dengan cara ditancapkan menggunakan bambu, pada kedalaman antara 1,5 sampai 3 m. Bahan yang digunakan adalah waring ukuran 4 mm dan tali ris atas PE Ø 3mm (Gambar 5). 115 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Bambu Jarak 1 m 2.5 m Penaju 100 m 5m 1m Bambu Jarak 3 m 50 m Sayap 20 m 5m 5m Bunuhan 3m 2.5 m Gambar 5. Rancang bangun sero jaring di perairan Teluk Jakarta 2.4 Bagan (Lift nets) Bagan yang dioperasikan di perairan sekitar Pulau Lancang adalah bagan tancap. Rumah bagan terbuat dari kayu pinang berjumlah 50 batang yang saling diikat menggunakan tali tambang dan kawat, disusun membentuk piramida dengan sisi bidang atas 11 x 11 m, dan bidang bawah berukuran 10 x 10 m. Rumah bagan berdiri pada rakit bambu yang terdapat pada kedua sisi bawah yang berlawanan, dengan pelampung dari drum plastik dan pemberat sehingga posisi bagan tidak berpindah. Bidang datar bagian atas berupa pelataran yang berfungsi sebagai tempat nelayan melakukan kegiatan dan pada salah satu bagian sisinya disediakan alat penggulung (roller) untuk menurunkan dan mengangkat jaring (Gambar 6). 116 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta (Dokumentasi Hartati 2009) Gambar 6. Satu unit bagan tancap yang beroperasi di perairan Pulau Lancang 3. Pemanfaatan dan Produksi Pada umumnya bagian yang dimanfaatkan dari rajungan adalah dagingnya. Cangkang (karapas) rajungan dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan lantai keramik, barang hiasan atau campuran pakan ternak. Proses perebusan dan pengambilan daging rajungan serta pengepakan menurut bagian tubuh rajungan banyak dilakukan oleh tenaga kerja wanita. Menurut Romimohtarto dan Djamali (1998), sejak tahun 1992 proses perebusan rajungan sudah banyak dilakukan di desa Bondet, Cirebon. Daging rebus yang sudah dipisah menurut beberapa bagian rajungan di distribusikan ke perusahaan pengekspor daging rajungan. Produk daging rajungan terdiri dari beberapa macam, yaitu: • Collosal, adalah bagian paha rajungan paling atas, dagingnya kenyal, dan rasanya paling enak, mempunyai harga jual yang paling mahal. • Jumbo atau Super, adalah daging dari bagian badan yang berhubungan langsung dengan kaki renang, berwarna putih, rasanya manis, strukturnya padat dan kompak, mempunyai harga hampir sama dengan kategori collosa. 117 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya • Special adalah sisa daging berupa serpihan dari bagian cangkang rajungan, umumnya berwarna putih. • Clawmeat adalah daging rajungan yang diperoleh dari bagian kaki capit, kaki jalan atau kaki renang. Dagingnya berwarna khas yaitu merah terang atau kecoklatan. • Lump, adalah daging yang diperoleh dari bagian dada rajungan dan umumnya berwarna putih. Beberapa miniplan membagi lagi menjadi Lump Flower, Lump Backfin (bagian/pecahan dari daging Jumbo), dan Super Lump (bagian dada rajungan yang berwarna putih). Di wilayah Teluk Jakarta terdapat beberapa tempat pendaratan rajungan/pedagang pengumpul rajungan, antara lain terdapat di Rawa Saban (Tangerang), Muara Kamal, Kali Adem, Ancol, dan Cilincing. Di pulau Seribu antara lain terdapat di Pulau Lancang dan Pulau Kelapa. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI), produksi daging rajungan dari pedagang pengumpul Teluk Jakarta terdiri dari masing-masing bagian rajungan yang bervariasi setiap tahunnya. Bagian yang paling banyak diproduksi adalah clawmeat dan special meat. Pada tahun 2002–2008 total produksi daging rajungan bagian clawmeat mencapai 307.630,8 ton atau 43.947,3 ton/tahun (31,9% dari berat total daging rajungan). Sementara itu, produksi bagian special meat mencapai 218.067,3 ton atau 31.352,5 ton/tahun (22,6%). Perkembangan produksi daging rajungan menurut bagiannya selama tahun 2002–2008 dikemukakan pada Gambar 7. Menurut pengusaha (pedagang pengumpul) rajungan, nilai konversi dari daging rajungan terhadap berat seekor rajungan tidak sama untuk setiap lokasi penangkapan. Konversi dari berat daging rajungan terhadap berat seekor rajungan berkisar 30%–32%, artinya berat daging sekitar sepertiganya berat seekor rajungan utuh. 118 Produksi (kg) Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta 200,000 2 1 180,000 1 160,000 1 140,000 1 120,000 1 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Cocktail Claw w Clawmeat Special Super Lump Lump/ Flowerr i Lump/ Backfiin 20 002 2003 2004 2005 2006 2 2007 2008 Tahun Gambar 7. Produksi daging rajungan menurut bagiannya dari pedagang pengumpul di Teluk Jakarta, 2002–2008 Pada daerah dengan hasil tangkapan berukuran kecil, nilai konversi tersebut berkisar 20%–22%. Bila nilai konversi 30% digunakan untuk mengestimasi produksi rajungan di Teluk Jakarta, selama tahun 2002– 2008 produksi tertinggi (606 ton) terdapat pada tahun 2006, diikuti dengan penurunan pada tahun berikutnya (Gambar 8). 700.0 7 606,0 Produksi (ton) 600.0 6 500.0 5 400.0 4 537,7 529,5 515,1 439,0 301,1 300.0 3 200.0 2 283,0 100.0 1 0.0 2002 2003 2 2004 200 05 2006 2007 2008 Tahun Gambar 8. Estimasi produksi rajungan dari pedagang pengumpul di Teluk Jakarta, 2002–2008 119 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 4. Komposisi Jenis dan Laju Tangkap Hasil tangkapan bubu rajungan di perairan Kepulauan Seribu (Pulau Lancang, Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa) pada bulan April–Mei 2007 berkisar 2–80 kg/kapal/hari atau rata-rata 40 kg/kapal/hari. Hasil tangkapan bubu rajungan yang didaratkan di pantai utara TangerangJakarta lebih sedikit, berkisar 5,0–7,0 kg, atau rata-rata 6 kg/hari. Dengan demikian, laju tangkap rajungan di Teluk Jakarta berkisar 6–40 kg/hari. Rajungan yang tertangkap di perairan Pulau Lancang umumnya berukuran lebih besar (kualitas ekspor). Hasil tangkapan rajungan sekitar 80% dari total hasil tangkapan bubu. Selain rajungan, diperoleh tangkapan ikutan, antara lain ikan buntal (Lagocephalus inermis), kerapu (Epinephelus spp.), ikan lidah (Cynoglosus spp.), cumi-cumi (Loligo sp.), udang jerbung, dan udang kipas. Hasil tangkapan rajungan dengan gillnet monofilamen sebagian besar berkisar 5–11 kg/hari atau rata-rata 8 kg/hari. Hasil tangkapan ikan lainnya yaitu ikan petek (Leighnathus spp.), kembung (Rastreliger brachysoma), tembang (Clupeidae), beronang (Siganus spp.), dan gulamah (Johnius spp.). Hasil tangkapan rajungan pada alat sero berkisar 6–10 kg/unit/hari, sedangkan dengan bagan rata-rata kurang dari 5,0 kg/unit/hari (Tabel 1). Ukuran rajungan pada penangkapan dengan sero dan bagan relatif kecil. Tabel 1. Hasil tangkapan rajungan (Potunus Pelagicus) pada beberapa alat tangkap di Teluk Jakarta, April–Mei 2007 Jenis alat 120 Total Total rajungan tangkapan (kg/ (kg/unit/hari) unit/hari) Rata-rata rajungan (kg/ unit/hari) Ikan dan biota lain Sero 120 4,0–10,0 7,0 Ikan petek,baronang, udang Bagan 25,0 1,5–5,0 3,25 Petek, gulamah, kembung,cumi Bubu lipat 7,5–50 6,0–40,0 23,0 Ikan gulamah, kerapu, udang kipas Jr. rajungan 7–16 5,0–11,0 8,0 Ikan petek, gulamah, kembung Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta 5. Hubungan Sebaran Karapas dan Berat Pengukuran terhadap 3.843 ekor rajungan hasil tangkapan jaring rajungan (lokal: jaring kejer) dan 406 ekor rajungan hasil tangkapan sero pada tahun 2008 dikemukakan pada Tabel 2. Dari Tabel tersebut tampak secara umum ukuran rajungan hasil tangkapan jaring rajungan lebih besar daripada hasil tangkapan sero. Ukuran lebar karapas rajungan hasil tangkapan jaring rajungan berkisar 53–136 mm. Untuk hasil tangkapan garuk, ukuran lebar karapas rajungan berkisar 50–119 mm. Besar kecilnya ukuran rajungan yang tertangkap berkaitan dengan ukuran mata jaring (mesh size) alat tangkap yang digunakan dan lokasi penangkapan. Ukuran mata jaring pada jaring kejer sebesar 4 inci dan ukuran bagian kantong pada sero sebesar 2 mm (waring). Rajungan hasil tangkapan jaring umumnya sudah dalam stadia dewasa. Hubungan lebar karapas dan berat rajungan hasil tangkapan jaring kejer diperoleh nilai b = 3,089 untuk jenis jantan dan b = 3,052 untuk betina. Setelah dilakukan perhitungan nilai uji-t pada taraf 95% dengan derajat bebas (n-2), diperoleh nilai thitung masing-masing lebih kecil dari ttabel (significant), yang berarti tidak berbeda nyata (terima Ho). Dengan demikian, nilai b untuk rajungan sama dengan 3 (b=3) atau bersifat isometrik, artinya pertambahan lebar karapas sebanding dengan pertambahan beratnya (Gambar 9). Tabel 2. Data lebar karapas dan berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan dan sero di perairan Teluk Jakarta, Maret–Agustus 2008 Jaring rajungan (gillnet) Sero (guiding barrier) Parameter Jantan Betina Jantan Betina (Male) (Female) (Male) (Female) Jumlah sampel 2.228 1.615 279 127 Sex ratio 1,4 1 2,1 1 Lebar karapas (mm) Minimum 53 59 54 50,8 Maksimum 136 126 119,1 116 Rata-rata 94,2 93 81,9 85,2 Std. Dev. 0,98 1,05 15,41 14,76 121 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 2. Data lebar karapas dan berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan dan sero di perairan Teluk Jakarta, Maret–Agustus 2008 (lanjutan) Jaring rajungan (gillnet) Sero (guiding barrier) Jantan Betina Jantan Betina (Male) (Female) (Male) (Female) 10 10 10 180 122 100 49,5 45,6 37,2 17,39 15,69 22,61 Parameter Berat (gram) Minimum Maksimum Rata-rata Std. Dev. 200 JantanJantan 180 y = 0,053x3,037 r = 0,93 n = 2228 160 Berat (gram) 10 95 40 20 140 120 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 Lebar karapas (cm) Gambar 9. Hubungan lebar karapas-berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan di perairan Teluk Jakarta, Maret – Agustus 2008 122 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Betina Gambar 9. Hubungan lebar karapas-berat rajungan hasil tangkapan jaring rajungan di perairan Teluk Jakarta, Maret – Agustus 2008 (lanjutan) Secara keseluruhan, hubungan panjang (lebar) karapas dan berat rajungan masing-masing diperoleh nilai b = 3,037 untuk jenis jantan dan b = 2,845 untuk jenis betina. Setelah dilakukan perhitungan uji-t pada taraf 95% dengan derajat bebas (n-2), diperoleh nilai thitung masing-masing lebih kecil daripada ttabel (significant), yang berarti tidak berbeda nyata (terima Ho). Dengan demikian, nilai b untuk rajungan sama dengan 3 (b=3) atau bersifat isometrik, artinya pertambahan lebar karapas sebanding dengan pertambahan beratnya. Kesimpulan 1. Alat tangkap utama yang digunakann untuk menangkap rajungan di Teluk Jakarta adalah jaring rajungan (gillnet monofilamen, lokal: kejer), bubu lipat, sero, dan bagan tancap. Daerah pengoperasian jaring dan bubu terdapat di perairan lebih ke tengah, terutama di sekitar Pulau Lancang, Pulau Pramuka, dan Pulau Kelapa. 123 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 2. Produksi rajungan cenderung menurun sejak tahun 2006. Bagian rajungan yang paling banyak diproduksi adalah clawmeat (daging bagian kaki capit, kaki jalan atau kaki renang) dan special meat (serpihan daging dari bagian cangkang rajungan). 3. Pada bulan April–Mei 2007, laju tangkap tertinggi (23 kg/hari) terdapat pada bubu lipat dan terkecil (3,25 kg/hari) terdapat pada bagan tancap. 4. Ukuran rajungan yang tertangkap dengan jaring rajungan relatif lebih besar dibandingkan dengan sero dan hubungan lebar karapas-berat rajungan bersifat isometrik yang berarti pertambahan panjang sebanding dengan pertambahan beratnya. Daftar Pustaka Alverson DL, MH Freeberg, SA Murawski and JG Pope. 1994. A global assessment of fisheries by-catch and discards. FAO Technical Paper 339: 1–233 Antara News. 2008. Rajungan Cirebon Nyaris Punah Akibat Penggunaan Jaring Arad. Selasa 12 September 2008. Bal DV and KV Rao. 1984. Marine Fisheries. Tata Mc. Graw-hill Publishing Company Limited. New Delhi: 5–24. Bellchambers LM and S de Lestang. 2005. Selectivity of different gear types for sampling the blue swimmer crab, Portunus pelagicus L. Fisheries Research 73 (2005): 21–27 Brandt AV. 1972. Fish Catching Methods of the World. Fishing News (Books) Ltd. 110 Fleet Street, London. EC.4: 158–165 and 204– 214. Bussines News. 1989. Kepiting, Komoditas Penting Tapi Belum Digarap Serius. Terbitan No. 4863, tahun XXXIII, Senin 2 Oktober. Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002–2007. Statistik Ekspor Impor Hasil Perikanan 2000-2005. Pusat Data Statistik dan Informasi. Departemen Kelautan dan Perikanan. Diterbitkan setiap tahun. 124 Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus Pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta Fridman AL and PJG Currothers. 1986. Calculation of Fishing Gear Designs. FAO. United Nation Fishing News Books. Farnham, Surrey. 242 p. Hamley JM. 1975. Review on Gillnet Selectivity. Journal of Fisheries Research Board of Canada 32: 1942–1969. Kailola PJ, MJ Williams, PC Stewart, RE Riechelt, A McNee and C Grieve (Eds.). 1993. Australian Fisheries Resources. Bureau of Resource Sciences, Canberra: 422. Karsono W, ST Hartati, dan A Priatna, 2006. Sebaran, intensitas, produktifitas, komposisi dan kondisi biologi ikan hasil tangkapan alat tangkap pasif menetap di Teluk Jakarta. Pros. Seminar Nasional Ikan IV. Jatiluhur, 29–30 Agustus 2006: 13 hal. Kawamura G. 1972. Gillnet Mesh Selectivity Curve Developed From Length-Girth Relationship. Bulletin of Japanese Socity of Scientific Fisheries 38 : 1942–1969. Matsuoka T. 1995. A method to Calculate Selectivity of Gillnet With a Probability Model Based on Variation of Body Girths. Faculty of Fisheries. :Kagoshima University. Moosa MK dan S Juwana. 1996. Kepiting Suku Portunidae dari Perairan Indonesia (Decapoda, Brachyura). Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi – LIPI, Jakarta: 118 hal. Nomura M and TYamazuki. 1975. Fishing Techniques.Japan International. Cooperation Agency, Tokyo: 46–49 Nomura M. 1974. Gillnet Fishery. Japanesse Fishing Gear and Method. Text Book for Marine Fisheries Research Course. Overseas Technical Cooperation Agency. Government of Japan:103–129. Romimohtarto K. 1977. Hasil Penelitian Pendahuluan tentang Biologi Budidaya Rajungan, Portunus pelagicus (L), dari Teluk Jakarta dan Pulau Pari (Pulau-pulau Seribu). Prosiding Seminar Biologi V dan Kongres III Biologi Indonesia I: 199–216. 125 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Stephenson W. 1962. Evolution and ecology of portunid crabs, with special reference to Australian species. In: Leeper, G.W. (Ed.): The Evolution of Living Organisms. Melbourne University Press, Melbourne: 311– 327. Sumiono B. 1997. Fishing Activities in Relation to Commercial and Smallscale Fisheries in Indonesia. Proceeding of the Regional Workshop on Responsible Fishing. Bangkok, Thailand, June 24–27,1997. SEAFDEC, Samutprakarn, Thailand: 41-70 Susanto. 2007. Studi Alat Tangkap Kepiting Rajungan Ramah Lingkungan di Wilayah Perairan Kabupaten Pangkep.Jurnal Agrisistem Vol. 3(2): 76–73 126 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Adriani Sri Nastiti*), Masayu Rahmia Anwar Putri*) dan Sri Turni Hartati**) Abstrak Udang merupakan salah satu sumber daya ikan yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan di Teluk Jakarta. Apabila sumber daya udang ini terus menerus dieksploitasi dengan jumlah kapal penangkap ikan yang terus bertambah, akan terjadi penurunan produksi udang. Penelitian ini bertujuan untuk memilih calon kawasan konservasi udang sebagai salah satu langkah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya udang di Teluk Jakarta. Penelitian dilakukan selama tahun 2010 pada bulan April, Juni, Agustus dan Oktober di wilayah timur Teluk Jakarta. Pengumpulan data primer untuk pemilihan kawasan konservasi mencakup tiga parameter yaitu bioekologi, sosial, dan ekonomi. Data yang diperoleh dari ketiga parameter tersebut kemudian diolah berdasarkan kriteria pemilihan calon kawasan konservasi yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi Teluk Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan timur Teluk Jakarta yang sesuai untuk konservasi kawasan asuhan udang adalah Muara Grobak (KU 5), Muara Beuting, (KU 6) dan Muara Bungin (KU 7) dengan estimasi total luas kawasan asuhan sebesar 53,92 ha. KATA KUNCI: Pemilihan, Konservasi Udang, Teluk Jakarta Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Teluk Jakarta telah dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas domestik, industri, transportasi, dan penangkapan sumber daya ikan yang akhirnya akan memberi tekanan terhadap lingkungan perairan Teluk Jakarta. Aktivitas penangkapan sumber daya ikan yang tidak ramah lingkungan dan memiliki intensitas yang cukup tinggi merupakan kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi sumber daya ikan di Teluk Jakarta. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan habitat sumber daya ikan, penurunan produksi, hilangnya ikan jenis tertentu, penurunan kualitas sumber daya ikan, baik dari bobot ataupun genetik dan masih banyak dampak negatif lainnya. Udang merupakan salah satu sumber daya ikan yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan Teluk Jakarta karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perairan Teluk Jakarta memiliki potensi produksi sumber daya udang yang cukup tinggi, data produksi udang dari tahun 1997 sampai 2008 mencapai 18.617,09 ton dengan kenaikan rata-rata per tahun mencapai 5,75 % (Pemda DKI Jakarta 2009). Apabila sumber daya udang ini terus menerus dieksploitasi dengan jumlah kapal penangkap ikan yang terus bertambah, akan terjadi penurunan produksi udang. Wilayah penangkapan udang di Teluk Jakarta tidak hanya di laut lepas, tetapi juga di wilayah estuari yang menjadi daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan (feeding ground), dan juga tempat memijah (spawning ground) bagi berbagai jenis udang, khususnya udang dari famili Penaidae. Salah satu langkah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya udang di Teluk Jakarta adalah dengan memilih calon kawasan konservasi sumber daya udang. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007, konservasi diharapkan akan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya ikan, termasuk udang. Tujuan dari penelitian ini adalah memilih kawasan asuhan udang yang sesuai untuk dijadikan sebagai calon daerah konservasi agar sumber daya udang yang ada tetap tersedia dan tidak terganggu populasinya. 128 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Metode Penelitian Penelitian dilakukan pada pada bulan April, Juni, Agustus, dan Oktober tahun 2010 di wilayah timur Teluk Jakarta meliputi 7 (tujuh) stasiun penelitian yaitu Muara Gembong (KU1), Tanjung Gembong (KU2), Muara Karawang (KU3), Tanjung Karawang (KU4), Muara Grobak (KU5), Muara Beuting (KU6), dan Muara Bungin (KU7) (Gambar 1 dan Tabel 1). Penentuan wilayah timur Teluk Jakarta sebagai lokasi penelitian karena kawasan ini memiliki kualitas perairan yang lebih baik dibandingkan wilayah barat untuk mendukung pertumbuhan udang dan didukung juga dengan vegetasi mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai lokasi penelitian (Nastiti et al. 2009). Gambar 1. Lokasi penelitian (KU1-KU7) 129 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 1. Posisi geografis lokasi penelitian di Teluk Jakarta No Lokasi Kode 1 2 3 4 5 6 7 KU1 KU2 KU3 KU4 KU5 KU 6 KU 7 Muara Gembong Tanjung Gembong Muara Karawang Tanjung Karawang Muara Grobak Muara Beuting Muara Bungin Posisi Geografis Lintang Selatan Bujur Timur 06o 01.772’ 106o 59’ 237” 06o 00.386’ 106o 59’ 074” 05o 56.655’ 106o 68’ 230” 05o 57.536” 107o 00’ 469” 05o 64.941” 107o 01’ 762” 05o 55.559” 107o 05’ 424” 05o 44’ 939” 107o 02’ 502” Pengumpulan data primer untuk pemilihan kawasan konservasi (Tabel 2) mencakup tiga parameter yaitu bioekologi, sosial, dan ekonomi. Data yang diperoleh dari ketiga parameter tersebut kemudian diolah berdasarkan kriteria pemilihan calon kawasan konservasi (Salm et al. 2000) yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi Teluk Jakarta. Kriteria pemilihan kawasan konservasi ditampilkan pada Tabel 3. Tabel 2. Parameter yang diukur selama pengamatan No 130 Parameter Satuan BIOEKOLOGI A. Fisika: 1 Kedalaman air 2 Kecerahan 3 Suhu air 4 Arus B. Kimia: 5 pH m Cm o C m/dtk 6 7 Mg/L 0 /00 Oksigen Terlarut Salinitas unit Alat/bahan dan metode yang digunakan Depth Meter, in situ Cakram Secchi, insitu Revershing Thermometer , in situ Bola dan tali 10 meter, in situ Titrasi dengan indikator universal pH 4-7/ in situ Water Quality Checker, insitu Refraktometer, insitu Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Tabel 2. Parameter yang diukur selama pengamatan (lanjutan) No Parameter BIOEKOLOGI C. Biologi: 8 Plankton 9 10 D. 11 12 Satuan Alat/bahan dan metode yang digunakan Sel /L Fitoplankton dikumpulkan dengan menggunakan fitoplankton net berbentuk kerucut yang mempunyai diamater mulut 31 cm, panjang 100 cm, dan ukuran mata jaring 0,08 mm (80 um). Ind/L Zooplankton dikumpulkan dengan zooplankton net yang berukuran diameter mulut 45 cm, panjang 180 cm dan mata jaring 0,30 mm Makrozoobentos) Ind/m2 Mini bottom trawl, in situ Vegetasi Kualitatif Sumber Informasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kab. Bekasi Sumber daya udang: Larva Kelimpahan Ind/dm3; Bonggo net, in situ Komposisi %, Mikroskop, Laboratorium Juvenil Kelimpahan Ind/m2; Mini Bottom Trawl, in situ Komposisi % SOSIAL Kualitatif Wawancara dan pengamatan di lapangan (Tabel 3) EKONOMI Kualitatif Wawancara dan pengamatan di lapangan (Tabel 3) 131 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 3. Beberapa parameter sebagai kriteria pemilihan kawasan konservasi (Salm et al. 2000) yang dimodifikasi sesuai kondisi Teluk Jakarta No Parameter 1. Bioekologi Sosial Kelimpahan hayati Peraturan 2. Kealamian 3. Ketergantungan 4. 5. Keterwakilan Produktivitas 6. 7. Ekonomi Kepentingan perikanan Manfaat ekonomi (pariwisata) Dapat digunakan untuk rekreasi masyarakat Budaya (nilai sejarah dari lokasi) Estetika Berpengaruh pada aktivitas masyarakat lokal Aksesibilitas Kelembagaan nelayan Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi adalah: A. Bioekologi yaitu parameter yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara lain: 1. Kelimpahan hayati dapat diartikan keberadaan makhluk hidup yang melimpah dan beranekaragam, seperti plankton, juvenil dan bentos 2. Kealamian dapat diartikan sebuah kondisi lingkungan perairan yang belum tercemar oleh limbah dan biota lautnya masih beraneka ragam serta jarang dijamah oleh manusia 3. Keterwakilan bahwa lingkungan perairan tersebut mewakili jenis biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya 4. Ketergantungan didasarkan pada tingkat ketergantungan spesies pada lokasi atau tingkat di mana ekosistem bergantung pada proses ekologis yg berlangsung di lokasi. 132 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta 5. Produktivitas didasarkan pada tingkat di mana proses-proses produktif di lokasi memberikan manfaat atau keuntungan bagi biota atau manusia (Anonim 2007). B. Sosial, yaitu sebuah parameter yang menelaah ketergantungan dan kepedulian masyarakat terhadap kawasan calon konservasi, di antaranya: 1. Tempat rekreasi dapat diartikan wilayah tersebut sangat cocok sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar atau luar. 2. Budaya dapat diartikan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat yang patut dilestarikan. 4. Estetika dapat diartikan wilayah suaka tersebut memiliki pemandangan yang indah dan mengesankan. 5. Aktivitas masyarakat lokal dapat diartikan ketergantungan masyarakat setempat dan pendatang terhadap kawasan suaka sebagai tempat mencari nafkah. 6. Aksesbilitas dapat diartikan kemudahan bagi para nelayan setempat maupun pendatang untuk memasuki wilayah suaka. 7. Peraturan dapat diartikan sebagai perangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat dijadikan payung hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan. 8. Kelembagaan nelayan dapat diartikan keberadaan kelompok nelayan yang dapat mendukung adanya calon suaka di perairan tersebut. C. Ekonomi 1. Kepentingan perikanan didasarkan pada jumlah nelayan yang bergantung pada lokasi dan ukuran hasil perikanan 2. Pariwisata didasarkan pada nilai keberadaan atau potensi lokasi untuk pengembangan pariwisata Selanjutnya, untuk setiap parameter diberi nilai 1–3, dengan rincian sebagai berikut. 133 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Skor 1 : bila nilai parameter tidak memenuhi persyaratan (Buruk) Skor 2 : bila nilai parameter mendekati persyaratan (Sedang) Skor 3 : bila nilai parameter memenuhi persyaratan (Baik) Setelah skoring, masing-masing parameter diberikan bobot sesuai dengan urutan tingkat kepentingan dengan jumlah 100. Berdasarkan hal tersebut, pemberian bobot pada setiap parameter adalah sebagai berikut: Bioekologi : 75 Sosial : 15 Ekonomi : 10 Skor yang diperoleh dari setiap parameter dikalikan bobot sesuai dengan bagian dari faktor dan hasilnya dijumlahkan, hasil tertinggi dicalonkan sebagai kawasan konservasi sumber daya udang. Klasifikasi konservasi kawasan asuhan udang di Teluk Jakarta berdasarkan bobot total adalah sebagai berikut. Tabel 4. Klasifikasi calon kawasan konservasi asuhan udang Klasifikasi I II III Nilai > 3.000 2.000–3.000 < 2.000 Kategori Baik Sedang Kurang Baik Hasil Dan Pembahasan Lingkungan Perairan Parameter fisika, kimia, biologi perairan serta sumber daya udang ditampilkan pada Tabel 5. Rata-rata kedalaman perairan di lokasi penelitian berkisar 1,85–3,25 meter, di mana lokasi penelitian yang paling dalam perairannya berada di stasiun 3 dan 4, sedangkan terdangkal di stasiun 1. Rata-rata kecerahan perairan berkisar 52,5–97,5 cm, di mana kecerahan di stasiun 5 paling rendah dibandingkan stasiun lainnya. Rendahnya nilai 134 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta kecerahan disebabkan partikel biotik dan abiotik (tanah). Nilai kecerahan akan memengaruhi intensitas cahaya yang masuk dalam perairan sehingga perannya sangat besar untuk kehidupan fitoplankton sebagai produsen primer. Suhu air berkisar 29,65°C–31,35°C, dengan suhu tertinggi berada di stasiun 1 dan terendah di stasiun 4. Menurut Nybakken (1992), suhu normal permukaan air laut berkisar 20°C–30°C. Arus permukaan ratarata berkisar 0,14–6,86 m/detik dengan arus tertinggi di stasiun 6 dan terendah di stasiun 5. Konsentrasi pH di lokasi penelitian berkisar 7,5–8,25, Nilai tersebut masih disukai oleh sebagian besar biota air yaitu antara 7–8,5 (Effendi 2003). Konsentrasi pH tertinggi berada di stasiun 5 dan terendah di stasiun 7. Rata-rata konsentrasi oksigen terlarut berkisar 5,21–6,86 mg/l, di mana konsentrasi oksigen tertinggi berada di stasiun 2 dan terendah di stasiun 1. Salinitas di perairan Teluk Jakarta berkisar 21,2‰–31,33 ‰, di mana nilai salinitas minimum di stasiun 3 dan maksimum di stasiun 6. Nilai ini masih berada dalam kisaran salinitas yang umumnya ditemukan di perairan estuari yaitu sekitar 5‰–30‰ (Effendi 2011; Ohler dan Register 2007). Fitoplankton memiliki peran penting sebagai sumber energi di perairan estuari setelah mangrove. Kelimpahan fitoplankton minimum di stasiun 2 dengan nilai 1.404.105 sel/dm3 dan maksimum di stasiun 5 dengan kelimpahan 6.720.453 ind/dm3. Zooplankton sebagai konsumen pertama di perairan memiliki kisaran kelimpahan antara 2.813–100.694 ind/ dm3, di mana nilai minimum berada di stasiun 3 dan maksimum di stasiun 5. Kelimpahan makrozoobentos berkisar 32–1635 ind/m2 dengan nilai kelimpahan minimum berada di stasiun 6 dan maksimum di stasiun 1. Makrozoobentos sering dijadikan sebagai indikator kualitas air karena habitat hidupnya yang relatif tetap (Sinaga 2009). Kelimpahan larva udang di lokasi penelitian berkisar 61–2035 ind/ dm . Kelimpahan larva udang terbesar ditemui di stasiun 7 (2.035 ind/ dm3) dan terendah di stasiun 1 (61 ind/dm3). Kepadatan juvenil minimum berada di stasiun 2 dengan nilai 0,6 ind/m2 dan kepadatan maksimum berada di stasiun 6 sebesar 336,76 ind/m2. 3 135 136 m/detik unit mg/l ‰ Arus B.KIMIA pH Oksigen terlarut Salinitas C. BIOLOGI Fitoplankton Zooplankton Macrozoobenthos SUMBER DAYA UDANG Kelimpahan Larva Komposisi Larva Kelimpahan Juvenil Komposisi Juvenil °C Suhu air Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata sel/dm³ ind/dm³ ind/m² ind/m² % ind/m² % 61 0,01 1,54 58,9 5.970.276 4.683 1.635 8,13 3,07–4,33 5,21 10–31 22,82 cm Kecerahan Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata 1,5–2,3 1,85 60–100 72,5 30–31,4 31,35 0,39 m Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata KU 1 Unit Parameter/Parameters BIOEKOLOGI A. FISIKA Kedalaman 160 0,03 0,6 47,9 1.404.105 8.396 1.134 8,14 5,01–9,83 6,86 30–31 29,82 1,8–3,3 2,5 90–170 95 30,5–31,3 31,27 0,18 KU 2 KU 4 1,9–2,5 2,6 60–70 52,5 30,4-31,5 30,92 0,14 KU 5 202 0,04 1,13 45,6 2.226.469 2.813 881 731 0.15 49.44 93.4 1.023 0,21 128,29 98,9 2.850.672 6.720.453 5.574 10.694 281 97 7,82 8,07 8,25 5,32–7,28 4,27 –6,04 5,96 –6,77 6,2 5,81 6,15 13–28 28–30 30–32 21,2 22,25 31,3 2,2–2,5 3–3,3 3,25 3,25 50–150 60–220 97,5 95 27,9–30,7 28,5 –31,7 30,27 29,65 5,66 0,40 KU 3 Tabel 5. Nilai parameter perairan di lokasi penelitian Teluk Jakarta 7,5 5,09 –5,9 5,26 10–29 23 1,4 –2,7 2,63 50–60 73,33 28,3–30 30,33 0,23 KU 7 310 0,06 336,76 99,8 2.035 0,42 246,4 94,1 5.668.082 4.925.690 6.151 2.988 32 212 8 5,53 –6,65 6,31 30–35 31,33 2–2,7 2,13 10–90 70 28–30,7 30,26 6,86 KU 6 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya A. Ekologi a) Keanekaragaman Hayati 1. Kelimpahan Larva Udang (ind/dm³) 2. Komposisi Larva udang terhadap biota lain (%) 3. Kepadatan Juvenil Udang (ind/m²) 4. Komposisi Juvenil Udang terhadap biota lain(%) b) Ketergantungan 1. Kelimpahan Fitoplankton(sel/dm³) 2. Kelimpahan Zooplankton (ind/dm³) 3. Kelimpahan Makrozoobentos (ind/m²) 4. Kedalaman (m) 5. Kecerahan (cm) 6. Suhu (°C) 7. Salinitas (‰) 8. DO (mg/l) 9. pH (unit) c) Keterwakilan Parameter >52*105 >8.000 >240 >3 >90 25–32 5–30 >5 >6,5–8,5 ≤13*105 13*105-2*105 ≤2.000 2.000–8.000 ≤60 60–240 <2 2–3 <45 45–90 <25; >32 <5; >30 <3 3–5 <6 6–6,5 3 (Baik) >1.600 >0,2 >200 >60 Kategori Penilaian 2 (Sedang) 400–1.600 0,1–0,2 100–200 30–60 ≤400 ≤0,1 ≤100 ≤30 1 (Buruk) Tabel 6. Pengelompokan parameter dan skor berdasarkan kriteria pemilihan kawasan konservasi (Salm et al. 2000) Parameter-parameter yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria pemilihan kawasan konservasi (Salm et al. 2000) yang telah dimodifikasi dan diberi skor untuk masing-masing parameter (Tabel 6). Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta 137 138 Ekosistem mangrove (jarang, sedang, rapat) d) Kealamian Pemanfaatan perairan (pemukiman, perikanan, jalur transportasi, penambangan pasir, PLTU, pengeboran minyak) e) Produktivitas Produksi juvenil (ton/tahun) B. Sosial 1. Dapat digunakan untuk rekreasi masyarakat 2. Budaya (nilai sejarah dari lokasi) 3. Estetika (keindahan) 4. Berpengaruh pada aktivitas masyarakat lokal 5. Aksesibilitas 6. Peraturan 7. Kelembagaan nelayan C. Ekonomi 1. Kepentingan perikanan 2. Manfaat ekonomi (pariwisata) Parameter Kategori Penilaian 2 (Sedang) Sedang Kurang alami 25–200 Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Cukup Cukup Sedang Sedang 1 (Buruk) Jarang Tidak Alami < 25 Kurang cocok Rendah Kurang Tinggi Mudah Kurang Kurang Kurang Kurang Tinggi Tinggi Cocok Tinggi Indah Rendah Sulit Baik Baik >200 Alami 3 (Baik) Rapat Tabel 6. Pengelompokkan parameter dan skor berdasarkan kriteria pemilihan kawasan konservasi (Salm et al. 2000) (lanjutan) Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta Berdasarkan hasil analisis skoring terhadap beberapa parameter utama (Lampiran 1), yaitu bioekologi, sosial, dan ekonomi menunjukkan bahwa ada beberapa stasiun yang layak dijadikan sebagai calon kawasan asuhan konservasi udang di Teluk Jakarta seperti yang tersaji pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, didapatkan bahwa lokasi penelitian yang sesuai untuk dijadikan sebagai calon kawasan asuhan juvenil udang adalah lokasi dengan kategori baik, di mana nilai skoring yang didapatkan di atas 3.000 (Tabel 4) yaitu Muara Grobak, Muara Beuting, dan Muara Bungin (KU5– KU7). Ketiga lokasi tersebut terletak di luar Teluk Jakarta (Gambar 3), yang pemanfaatan perairannya semakin berkurang. KU7 3.580 KU6 3.355 KU5 3.580 KU4 2.920 KU3 2.830 KU2 2.980 KU1 2.530 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Gambar 2.Evaluasi per stasiun di Teluk Jakarta 139 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Gambar 3.Lokasi yang dijadikan sebagai calon konservasi kawasan asuhan udang Tabel 7. Estimasi luas kawasan asuhan juvenil udang Lokasi Kelimpahan Rataan Rekruitment Total Estimasi Luas Total Juvenil Kelimpahan * (ind/m2) Tangkapan Kawasan (ind/m2) Juvenil Udang ** (ind) Asuhan***(ha) (ind/m2) KU5 509,45 127,36 89,15 11.164.800,00 12,52 KU6 1.34,54 336,89 235,82 11.164.800,00 4,73 KU7 987,30 329,10 230,37 11.164.800,00 4,84 Total 53,92 * Rekruitmen = Kelimpahan rata-rata * SR (Survival Rate) = Kelimpahan rata-rata * 0,7 SR = 70% ** Total Tangkapan udang: Udang Hasil Tangkapan Nelayan, diasumsikan 400 nelayan aktif *** Luas Kawasan Asuhan = (Total tangkapan udang/Rekruitmen)/ 10.000. Tabel 7 menyajikan estimasi luas kawasan asuhan juvenil udang. Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa lokasi dengan nilai rekruitmen juvenil yang tinggi mengindikasikan bahwa habitat tersebut memiliki kualitas yang lebih baik sehingga luas kawasan asuhan yang akan 140 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta dikonservasi menjadi lebih sempit. Nilai rekruitmen di stasiun Muara Grobak (KU 5) untuk juvenil udang sebanyak 89,15 ind/m2 dan estimasi kawasan asuhannya sebesar 12,52 hektare. Nilai ini cukup jauh jika dibandingkan dengan KU 6 (Muara Beuting) dan KU 7 (Muara Bungin) yang estimasi kawasan asuhannya masing-masing hanya 4,73 dan 4,84 hektare, di mana recruitment-nya mencapai 230,37–235,82 ind/m2. HubunganRekruitmenJuvenilTerhadapEstimasi LuasanKonservasiKawasanAsuhanUdang EstimasiLuasanKawasan(ha) 14 12 10 y=Ͳ0.053x+17.30 R²=0.999 8 6 4 2 0 0 50 100 150 200 250 Rekruitment (ind/m2) Gambar 4. Hubungan rekruitment juvenil terhadap estimasi luasan konservasi kawasan asuhan udang. Semakin rendah rekruitment juvenile, luasan kawasan asuhan yang diestimasi akan semakin tinggi (Gambar 4). Hal ini terjadi karena tingginya pemanfaatan perairan yang ada di lokasi tersebut sehingga juvenil yang ada tidak bisa berkembang biak dengan baik, sehingga kawasan yang dikonservasi akan semakin luas. Kesimpulan Kawasan timur Teluk Jakarta yang sesuai untuk konservasi kawasan asuhan udang adalah Muara Grobak (KU 5), Muara Beuting (KU 6), dan Muara Bungin (KU 7) dengan estimasi total luas kawasan asuhan sebesar 53,92 ha. Pemilihan ini didukung oleh berbagai parameter yang menunjang untuk konservasi terutama dari parameter ekologi. 141 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Daftar Pustaka Anonimus. 2009. Buku Statitisk Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta. Effendi. 2011. Fitoplankton. Diunduh dari http://efendikonservasi. blogspot.com/2011/01/fitoplankton.html 6 Mei 2011 Nastiti et al. 2009. Kesesuaian Perairan untuk Upaya Konservasi Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta. Laporan Tahunan. Loka Riset Pemacuan Stok Ikan. Pusat Riset Perikanan Tangkap. BRKP-DKP. Nybakken JW. 1992. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta: PT Gramedia. Ohler RL jr. and KM Register. 2007. Volunteer Estuary Monitoring a Methods Manual 2nd edition. US Environment Protect Agency. PP 60 Tahun 2007. Konservasi Sumber Daya Ikan. Kementerian Kelautan Perikanan. Salm RV, JR Clark, and E Siirila. 2000. Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers. Washington, DC: International Union for The Conservation of Nature and Natural Resources. Washington, DC. 371 pages + prologue. Diunduh dari http://mpa. gov/pdf/helpfulresources/mpalessons.learned.pdf pada tanggal 18 Januari 2010 pukul 14.20 WIB Sinaga T. 2009. Keanekaragaman Makrozoobenthos Sebagai Indikator Kualitas perairan Danau Toba Balige Kabupaten Toba Samosir. Tesis (Tidak dipubilkasikan). Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 142 75 Bobot Skor Bobot Skor 6. Kelimpahan Zooplankton (ind/dm³) Bobot Skor 5.Kelimpahan Fitoplankton(sel/dm³) b)ketergantungan Bobot 2 3 225 2 150 8.396 150 2 4.683 225 3 5.970.276 1.404.105 150 2 150 47,9 75 1 0,6 75 1 0,03 75 1 160 KU2 58,9 75 Bobot 4. Komposisi Juvenil Udang terhadap biota lain(%) 1 Skor 1,54 75 Bobot 3. Kepadatan Juvenil Udang (Ind/m²) 1 Skor 0,01 1 2. Komposisi larva udang terhadap biota lain (%) 61 1. Kelimpahan larva Udang (ind/dm³) KU1 Skor a) Keanekaragaman Hayati A. BIOEKOLOGI Parameter 75 1 202 150 2 2.813 150 2 2.226.469 150 2 45,6 75 1 1,13 75 1 0,04 KU3 Lampiran 1. Hasil skoring parameter bioekologi, sosial, dan ekonomi Stasiun 150 2 5.574 150 2 2.850.672 225 3 93,4 75 1 49,44 150 2 0,15 150 2 731 KU4 225 3 10.694 225 3 6.720.453 225 3 98,9 150 2 128,29 225 3 0,21 150 2 1.023 KU5 75 1 310 150 2 6.151 225 3 5.668.082 225 3 99,8 225 3 336,76 75 1 0,06 KU6 150 2 2.988 150 2 4.925.690 225 3 94,1 225 3 246,4 225 3 0,42 225 3 2.035 KU7 Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta 143 144 Skor 3 2 0,4 1 75 Skor Bobot 150 225 0,18 225 Bobot 14. Arus (m/dtk) 6,86 3 5,21 150 2 29,82 3 Skor 13. DO (mg/l) 75 Bobot 22,82 1 12. Salinitas (‰) Skor 225 3 225 3 Bobot Skor 8,14 8,13 11.pH (unit) 225 3 31,27 225 3 31,35 225 2 150 Bobot Skor 10. Suhu (°C) Bobot 95 150 2 2,5 225 3 1.134 KU2 72,5 75 Bobot 9. Kecerahan (cm) 1 1,85 8.Kedalaman (m) Skor 225 3 1.635 KU1 Bobot Skor 7. Kelimpahan Makrozoobentos (ind/m²) Parameter 225 3 881 225 3 0,09 225 3 6,2 75 1 21,2 225 3 7,82 225 3 30,27 225 3 97,5 225 3 3,25 KU3 75 1 0,4 225 3 5,81 150 2 22,25 225 3 8,07 225 3 29,65 225 3 95 225 3 3,25 225 3 281 KU4 Stasiun Lampiran 1. Hasil skoring parameter bioekologi, sosial, dan ekonomi (lanjutan) 2 97 225 3 0,14 225 3 6,15 225 3 31,3 225 3 8,25 225 3 30,92 225 3 52,5 150 2 2,6 150 KU5 75 1 32 225 3 0,11 225 3 6,31 225 3 31,33 225 3 8 225 3 30,26 225 3 70 150 2 2,13 KU6 150 2 2,63 150 2 212 150 2 0,23 225 3 5,26 225 3 23 225 3 7,5 225 3 20,33 225 3 73,33 KU7 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 2 3 225 0,8 0,6 1 1 15 Skor Bobot 15 1 15 1 75 75 15 1 0,29 288 1 0,66 664 664.146,8 287.667,5 2 1,54 Skor 2. Budaya (nilai sejarah dari lokasi) 2 150 KU2 331.711,7 367.274,7 Bobot 1. Dapat digunakan untuk rekreasi masyarakat B. SOSIAL Bobot Skor Produksi (ton/tahun) Produksi (kg/tahun) Produksi (gr/m²) Kelimpahan Juvenil Udang(ind/m²) Luas (m²) e). Produktivitas 1 75 Skor 150 KU1 Bobot d). Kealamian (Pemanfaatan perairan (Pemukiman, Perikanan, Jalur transportasi, Penambangan pasir, PLTU, Pengeboran Minyak) Bobot skor c). keterwakilan (Ekosistem mangrove)(Jarang, sedang, rapat)) Parameter 2 75 1 150 3 150 2 225 KU5 64,3 49,44 166,8 128,29 323.301 328.072,71 75 1 150 2 Stasiun KU4 3 150 2 225 437,8 336,76 706.762,7 KU6 3 150 2 225 320,3 246,4 709.791,92 KU7 15 1 15 1 75 1 0,48 480 15 1 15 1 75 1 20,78 20.781 15 1 15 1 150 2 54,72 54.716 15 1 15 1 225 3 309,41 309.412 15 1 15 1 225 3 227,36 227.357 479.616,8 20.780.823 54.715.853 309.411.517 227.356.949,2 1,5 1,13 325.878,5 KU3 Lampiran 1. Hasil skoring parameter bioekologi, sosial, dan ekonomi (lanjutan) Kajian Kawasan Konservasi Daerah Asuhan Udang di Teluk Jakarta 145 146 Bobot Bobot 1 3 2.980 2.530 Jumlah Total Bobot 10 1 10 1 30 3 45 3 45 15 1 15 1 15 Bobot KU2 Skor 2. Manfaat ekonomi (pariwisata) 3 30 Skor 1. Kepentingan perikanan C. EKONOMI 3 45 Skor Bobot 7. Kelembagaan nelayan 3 45 Skor 6.Peraturan 1 15 Skor Bobot 5. Aksesibilitas 1 15 Skor Bobot 4. Berpengaruh pada aktivitas masyarakat lokal 1 15 Skor KU1 Bobot 3. Estetika Parameter 1 10 1 30 3 45 3 45 3 15 1 15 1 15 2.830 KU3 1 10 1 30 3 15 1 15 1 15 1 15 1 15 2.920 KU4 Stasiun Lampiran 1. Hasil skoring parameter bioekologi, sosial, dan ekonomi (lanjutan) 2 10 1 30 3 15 1 15 1 45 3 30 2 30 3.580 KU5 2 10 1 30 3 15 1 15 1 45 3 30 2 30 3.355 KU6 2 10 1 30 3 15 1 15 1 45 3 30 2 30 3.580 KU7 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Oleh: Suprapto, Duranta Kembaren1 dan Pratiwi Lestari 1 Abstrak Pemantauan tentang kondisi kualitas perairan Teluk Jakarta telah dilakukan oleh Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) bekerjasama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1996 hingga saat ini. Pengambilan sampel dilakukan di perairan laut dan muara sungai, yang dilaksanakan pada saat musim barat, peralihan barat-timur, musim timur, dan peralihan timur-barat. Parameter yang diukur meliputi kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan yang erat kaitannya dengan penilaian kualitas perairan. Informasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengelolaan perairan di Teluk Jakarta. Hasil analisis terhadap beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi menunjukkan bahwa angin musim memberikan pengaruh yang nyata terhadap pola sebaran parameter dan kualitas massa air di Teluk Jakarta. Karakteristik perairan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh sirkulasi massa air Laut Jawa dan massa air sungai yang berlangsung secara periodik sesuai dengan perubahan musim. Nilai indeks keanekaragaman bentos menunjukkan bahwa perairan Teluk Jakarta termasuk tercemar dalam tingkat ringan sampai berat. Kata Kunci: Kualitas perairan, musim, Teluk Jakarta Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Teluk Jakarta sebagai pintu gerbang masuk ibukota, peranannya sangat penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia. Berbagai sektor industri, pertambangan, perhubungan, perdagangan, kependudukan, perikanan dan pariwisata telah memanfaatkan lingkungan perairan Teluk Jakarta dalam mendukung pembangunan ekonomi. Perkembangan pembangunan di kawasan ini sangat cepat dan masing-masing sektor memiliki berbagai kepentingan pengembangan kawasan, bahkan tampak tidak terintegrasi antara sektor yang satu dengan yang lainnya. Dibalik peran strategis dan prospek yang cerah dari kawasan perairan pesisir dan laut Teluk Jakarta, terdapat kendala yang cenderung mengancam kapasitas berkelanjutan (sustainable capacity) dalam menunjang kesinambungan pembangunan di kawasan Teluk Jakarta, salah satunya adalah masalah pencemaran perairan. Secara ekologis, Teluk Jakarta tergolong perairan yang tercemar tinggi berkaitan dengan tingginya masukan bahan organik (KPPL 1997) dan unsur logam berat (Yatim et al. 1979; Lestari dan Edward 2004). Masalah ini sudah sangat krusial dan belum pernah teratasi hingga saat ini. Berbagai kasus sering terjadi, mulai dari matinya ratusan ribu ikan, udang, rajungan, biota laut dan banyak lagi penghuni ekosistem pantai dan laut, sampai dengan ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian mereka, bahkan hingga masalah buruknya tingkat kesehatan yang diderita nelayan dan warga Jakarta yang mengonsumsi makanan dari laut (Rochyatun dan Rozak 2007; Lestari dan Edward 2004) Pencemaran di perairan Teluk Jakarta dapat terjadi karena berbagai faktor yang sangat kompleks, tidak hanya disebabkan oleh limbah yang dihasilkan kegiatan berbagai sektor industri yang berkembang di sekitar perairan laut, tetapi juga kontribusi bahan pencemar dari darat yang terbawa oleh aliran sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Perairan Teluk Jakarta merupakan tempat pelimpahan terakhir, baik sungai-sungai yang terdapat di kawasan DKI, maupun yang berada di sekitar Bogor, Tangerang, dan bekasi (BOTABEK). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Teluk Jakarta mendapatkan tekanan ekologis yang cukup berat. Hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan ketika beban pencemaran telah melewati daya dukung kawasan Teluk. Tingkat kualitas perairan 148 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta dipastikan menurun dan akan berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai sektor kegiatan, khususnya perikanan maupun pariwisata. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi kualitas perairan Teluk Jakarta, Balai Riset Perikanan Laut bekerja sama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemantauan perairan secara rutin sejak tahun 1996 hingga saat ini. Makalah ini akan menginformasikan hasil pemantauan tersebut, dengan tujuan identifikasi nilai beberapa parameter lingkungan perairan ditinjau dari aspek fisik, kimia, dan biologi perairan serta menganalisis pola sebarannya. Informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan lingkungan perairan Teluk Jakarta. Bahan dan Metode 1. Lokasi Pengamatan Ruang lingkup wilayah perairan Teluk Jakarta yang diamati difokuskan di perairan laut dan beberapa muara-muara sungai di sepanjang pantai Teluk Jakarta. Batas-batas wilayahnya meliputi: di sebelah barat mulai dari wilayah Tanjung Kait, selanjutnya berturut-turut ke arah timur sampai wilayah Tanjung Kerawang. Khusus di laut, pengambilan contoh (sampling) dilakukan pada 23 stasiun dengan posisi tersebar secara acak berlapis di perairan Teluk Jakarta. Agar diperoleh informasi yang representatif dengan gambaran pola sebaran mendatar yang informatif, stasiun pengamatan dibagi menjadi beberapa zona A, B, C dan D. Pengamatan di muara sungai dilakukan pada 9 muara yakni: Muara Kamal (M1), Muara Cengkareng Drain (M2), Muara Angke (M3), Muara Karang (M4), Muara Ancol (M5), Muara Sunter (M6), Muara Cakung (M7), Muara Marunda (M8), dan Muara Gembong (M9). Lokasi daerah penelitian tampak pada Gambar 1, sedangkan posisi geografis tiap stasiun pengamatan ditampilkan pada Lampiran 1. 149 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Gambar 1. Peta lokasi daerah pengamatan kualitas perairan di Teluk Jakarta 2. Waktu Pengamatan dan Analisis Data Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama penelitian antara Balai Penelitian Perikanan Laut (BPPL) dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta. Data dikumpulkan mulai tahun 1996 sampai dengan Agustus 2011, yang telah dilakukan pada saat musim angin (monsoons) yang berbeda, yakni musim barat (Desember, Januari, Februari), musim peralihan barat-timur (Maret, April, Mei), musim timur (Juni, Juli, Agustus) dan musim peralihan timur-barat (September, Oktober, November), selanjutnya data-data mewakili musim yang sama pada tahun yang berbeda dihitung rataannya. Selama musimmusim tersebut, diduga terjadi sirkulasi massa air secara periodik, sehingga memperlihatkan karakteristik lingkungan perairan yang spesifik dan bervariasi baik dari aspek fisik, kimia maupun biologi. 150 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta 3. Parameter Lingkungan yang Diamati 3.1. Fisik dan Kimia Air Parameter fisik air yang diukur meliputi: kedalaman perairan, kecerahan, suhu, salinitas, dan kecerahan air. Kedalaman dan kecerahan air diukur secara manual menggunakan tali sounding dan sechi disk. Nilai suhu air diperoleh secara langsung dengan menggunakan termometer balik (reversing thermometer), sedangkan salinitas dianalisis menggunakan salinometer Bechman terhadap sejumlah volume contoh air yang diambil menggunakan Nansen Bottle Sampler . Parameter kimia air yang diukur meliputi: oksigen terlarut (DO), pH, logam berat (Hg, Cd, CU, Pb, Zn, Ni), organik (KMnO4), amonia (NH3), sulfida (H2S), detergen (MBAS), phenol dan nitrit (NO2). Dua parameter pertama akan dibahas pada makalah ini, sedangkan parameter yang lain telah dianalisis oleh tim peneliti dari BPLHD Provinsi DKI Jakarta dan diinformasikan pada tulisan secara terpisah. Kadar oksigen terlarut dan pH air dianalisis melalui sejumlah volume contoh air yang diambil menggunakan botol Nansen. DO dianalisis dengan metode titrasi iodometri menurut Winkler (Anonimous 1959), sedangkan kadar pH air diperoleh langsung dengan menggunakan pH meter. 3.2. Biologi Perairan Parameter biologi perairan yang diamati terdiri dari kelimpahan bentos, plankton (fito dan zooplankton), dan mikrobiologi (bakteri coli). Khusus analisis bakteri dilakukan oleh tim peneliti BPLHD Provinsi DKI Jakarta, sehingga informasinya tidak dilaporkan pada makalah ini. Sampel fitoplankton dikumpulkan dengan menyaring air secara horizontal di permukaan laut, menggunakan jaring fitoplankton No. 25, berbentuk kerucut, panjang jaring 31 cm, diamater mulut jaring dan diameter mata jaring (mesh zise) 80 µm (setara dengan 0,08 mm). Pengambilan sampel zooplankton menggunakan jaring zooplankton, panjang 180 cm, diameter mulut jaring 45 cm, dan mesh zise 300 µm (0,30 mm). Sampel plankton yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol dan diawetkan dengan larutan formalin 4%. Pencacahan dan penghitungan plankton dilakukan di laboratorium menggunakan mikroskop binokuler dan buku petunjuk identifikasi jenis (Yamaji 1996; Tomas 1997). Hasil perhitungan kemudian 151 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh nilai komposisi, kelimpahan, indeks keragaman dan keseragaman genus (Ludwig dan Reynold 1988; Krebs 1989) dengan persamaan: H’ = - Σ (ni/n) Ln (ni/n) , Di mana H’ = Indeks keanekaragaman Shannon ni = Jumlah individu jenis ke i n = Jumlah individu semua jenis Sampel bentos diperoleh pada substrat dasar perairan yang diambil mengunakan “grab sampler “berukuran 20 x 20 cm. Sampel bentos yang diamati adalah kelompok makrozoobentos yang telah dipisahkan dari substratnya menggunakan ayakan (saringan) berdiameter mata (mesh zise) 1 mm, selanjutnya diawetkan dengan larutan alkohol 70%. Pencacahan dilakukan di laboratorium menggunakan alat bantu mikroskop binokuler. Pengidentifikasian bentos menggunakan referensi Tan dan Peter (1988); Zin dan Ingle (1995); Habe dan Kosuge (1966); Abbot dan Dance (1982). Analisis data struktur komunitas bentos ditujukan untuk memperoleh komposisi jenis, kelimpahan relatif, dan distribusinya secara horizontal di dasar perairan. Indeks keanekaragam jenis diperoleh dengan menggunakan persamaan Shannon-Wiener (Krebs 1989), seperti halnya metode yang diterapkan untuk menganalisis keragaman plankton. Hasil dan Pembahasan 1. Kondisi Fisik Perairan 1.1. Kedalaman dan Kecerahan Perairan Hasil pengukuran kedalaman perairan dan variasi kecerahan air pada setiap stasiun pengamatan seperti tampak pada Lampiran 2. Kedalaman perairan berkisar 5 sampai dengan 25 meter, sedangkan tingkat kecerahan berkisar 2 sampai dengan 7 meter. Daerah pengamatan terdangkal berada di sekitar pantai Tanjung Kait (B1), dan sebagian besar di pantai Ancol dan Marunda (D4, D5). Data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa Teluk Jakarta termasuk perairan dengan kedalaman relatif dangkal, tidak 152 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta ditemukan kedalaman lebih dari 50 meter, perairan terdalam terdalam mencapai 25 meter dengan kecerahan relatif rendah. Bila diperhatikan pola sebaran secara horizontal, zona A (jauh dari pantai) tampak cenderung lebih dalam, kemudian semakin mendekati pantai (zona D) lebih dangkal. Hal tersebut diduga karena pengaruh run off dari sungai yang bermuara di Teluk Jakarta membawa material padat dari daratan. 1.2. Suhu Permukaan Air Laut Hasil pengukuran suhu air permukaan di Teluk Jakarta yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan musim angin (monsoons) diperoleh variasi nilai seperti tampak pada Lampiran 3. Pada musim barat, suhu berkisar 28,50oC sampai dengan 31,04oC, suhu terendah dijumpai pada stasiun B5 dan tertinggi pada stasiun C3. Pada musim peralihan barattimur berkisar 29,96oC–31,12oC, suhu terendah dijumpai pada stasiun B4 dan tertinggi pada stasiun D5 mendekati muara sungai Sunter. Pada musim timur, suhu berkisar 29,12oC–29,97oC, terendah pada stasiun C4 dan tertinggi pada stasiun B1. Sedangkan pada musim peralihan timurbarat, suhu berkisar 29,77oC–31,04oC, suhu terendah teridentifikasi di stasiun B5 dan tertinggi pada stasiun B7. Secara umum, kondisi suhu tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi umum seperti yang dilaporkan Ilahude (1995), yakni pada musim barat berkisar 28,5oC–30,0oC, musim peralihan barat-timur 29,5oC–30,7oC, musim timur 28,5oC–31,0oC, dan musim peralihan timur-barat 28,5oC–31,0oC. Berdasarkan hasil analisis sebaran suhu secara mendatar pada tiap musim, diperoleh gambaran pola sebaran seperti tampak pada Gambar 2. Pada musim barat, suhu rendah cenderung terkonsentrasi antara muara Sunter-muara Marunda yang menyebar hingga pertengahan Teluk bagian timur, selanjutnya kondisi serupa tampak terkonsentrasi di sekitar muara Kamal hingga Tanjung Kait, dan sebaliknya di bagian utara Teluk Jakarta kondisi suhu cenderung tinggi. Pada musim peralihan barat-timur, suhu tinggi cenderung berada di antara muara Sunter-muara Marunda, selanjutnya menyebar hingga pertengahan teluk bagian timur dan sekitar muara Kamal hingga Tanjung Kait, di mana kedua daerah ini pada saat musim barat kondisinya justru relatif rendah, demikian pula di bagian tengah Teluk Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa pada musim ini cenderung rendah. Pada musim timur, terdapat dua massa air yang 153 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya menyebar dengan pola berbeda, yakni suhu relatif rendah terkonsentrasi di sebelah timur, dan sebaliknya suhu tinggi terkosentrasi di bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan pada musim peralihan timur-barat, kondisi suhu malah sebaliknya, yakni suhu tinggi terkonsentrasi di sebelah timur dan suhu rendah terkonsentrasi di sebelah barat Teluk Jakarta. LAUT JAWA TG.KARAWANG TG TG.GEMBONG TG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG ANGKE M.MARUNDA 106.5 106.6 106.7 106.8 SPL - Barat-Timur 106.9 107 107 6.4 106.5 106.6 LAUT JAWA LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.KARAWANG TG.GEMBONG TG.GEMBONG TG.GEMBONG M.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL KAMAL CENGKARENG CENGKARENG ANGKE ANGKE M.KARANG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL M.ANCOL M.ANCOL 106.7 106.8 106.9 107 107 ur Timur 6.4 6.4 106.5 106.5 106.6 106.7 106.6 106.7 Timur BujurTimur Bujur ANGKE 106.8 106.8 106.9 106.9 M.GEMBONG 107 107 107.1 .4 107.1 M.KARANG 154 M.ANCOL SPL - Timur M.MARUNDA M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.ANCOL SPL Timur-Barat M.MAR SPL Timur-Barat TG.GEMBONG TG.GEMBONG M.SUNTER M.CAKUNG 10 M.ANCOL TG.KARAWANG TG.KARAWANG M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 106.5 106.6 M.MARUNDA 106.7 Bujur Timur LAUT JAWA Gambar 2. Pola sebaran mendatar rata-rata suhu permukaan laut (SPL) di perairan Teluk Jakarta pada musim angin yang berbeda pada tahun 1996–2011 LAUT JAWA 106.9 KAMAL CENGKARENG M.SUNTER M.MARUNDA M.SUNTER M.MARUNDA M.CAKUNG M.CAKUNG SPL- Barat-Timur - Timur SPL SPL - Barat 106.8 LAUT JAWA TG.KARAWANG M.GEMBONG M.SUNTER M.CAKUNG 106.7 Bujur Timur Bujur Timur M.KARANG M.MARU M.ANCOL SPL - Barat 6.4 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.ANCOL AUT JAWA KE LAUT JAWA 106.8 106.9 1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG ANGKE M.MARUNDA SPL - Barat 6.4 106.5 106.6 106.7 M.ANCOL SPL - Barat-Timur Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta 106.8 106.9 107 107 6.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106. Bujur Timur Bujur Timur LAUT JAWA LAUT JAWA LAUT JAWA LAUT JAWA M.SUNTER M.CAKU M.KARANG M.ANCOL TG.KARAWANG TG.KARAWANG TG.KARAWANG TG.GEMBONG TG.GEMBONG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG KAMAL ANGKE CENGKARENG ANGKE M.GEMBONG GKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.KARANG M.KARANG 106.8 106.9 6.4 6.4 107 107 106.5 106.5 ujur Timur 106.6 106.7 106.6 106.7 Bujur Timur Bujur Timur 6.6 106.8 106.8 106.9 106.9 SPL Timur-Barat 107.1 .4 107.1 107 107 106.5 106.6 106.7 106.8 Bujur Timur TG.GEMBONG TG.GEMBONG M.GEMBONG M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.MARUNDA M.MARUNDA M.ANCOL SPL Timur-Barat SPL - Timur 106.8 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.ANCOL 106.7 M.ANCOL TG.KARAWANG TG.KARAWANG Bujur Timur M.SUNTER M.CA M.KARANG LAUT JAWA LAUT JAWA NGKE ANGKE SPL - Timur SPL - Barat-Timur SPL - Barat 106.7 KAMAL CENGKARENG M.ANCOL M.ANCOL .6 M.ANCOL M.GEMBONG M.SUNTER M.MARUNDA M.CAKUNG M.SUNTER M.MARUNDA M.CAKUNG 106.9 107 107.1 .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107 Bujur Timur Gambar 2. Pola sebaran mendatar rata-rata suhu permukaan laut (SPL) di perairan Teluk Jakarta pada musim angin yang berbeda pada tahun 1996–2011 (lanjutan) Variasi pola sebaran mendatar suhu menunjukkan bahwa pada musim barat, massa air di Teluk Jakarta didominasi oleh pengaruh massa air Laut Jawa dari utara dengan suhu relatif tinggi (isoterm 30oC) dan massa air sungai suhu rendah (isoterm 28oC) dari Muara Sunter hingga Muara Gembong. Pola serupa juga tampak pada musim peralihan barat-timur. 155 10 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Namun, kondisi kualitas massa airnya memperlihatkan kondisi sebaliknya, yakni massa air suhu tinggi berasal dari muara sungai, sedangkan massa air Laut Jawa relatif rendah. Pada musim timur, kondisi perairan Teluk didominasi oleh pengaruh air sungai bermassa air suhu tinggi dari sebelah barat (Kamal dan Cengkareng) dan dari sebelah timur (Tanjung KarawangGembong) membawa massa air suhu rendah. Sebaran suhu permukaan laut pada musim peralihan timur-barat memperlihatkan pengaruh massa air Laut Jawa sangat kuat dari arah barat. 1.3. Salinitas Hasil pengukuran kadar salinitas permukaan laut yang telah dikelompokkan ke dalam empat musim berbeda tercantum pada Lampiran 4. Pada musim barat, salinitas berkisar 27‰–32‰, terendah pada stasiun C5 dan tertinggi pada stasiun D4. Pada musim peralihan barattimur, salinitas berkisar 22,0‰–30,5‰, salinitas minimum terdeteksi pada stasiun A7, dan maksimum pada stasiun B5. Pada musim timur, salinitas berkisar 30,9‰–32,8‰, terendah pada stasiun C2 dan tertinggi pada stasiun C4. Sedangkan pada musim peralihan timur-barat, salinitas berkisar 25,0‰–30,7‰, terendah pada stasiun C2 dan tertinggi pada stasiun B2. Sebaran salinitas permukaan pada empat musim angin yang berbeda memperlihatkan pola yang bervariasi seperti tampak pada Gambar 3. Pada musim barat, salinitas relatif tinggi cenderung berada di sebelah barat, sebaliknya di sebelah timur relatif rendah. Pada musim peralihan barat-timur, kondisi hampir serupa terjadi pada musim peralihan barattimur. Pada musim timur kondisi sebaran salinitas tampak sebaliknya dibanding dua musim sebelumnya, yakni salinitas rendah terkonsentrasi di sebelah barat terutama sekitar muara Kamal dan Cengkareng dengan salinitas tertinggi berada di sebelah timur. Kondisi serupa juga terjadi pada musim peralihan timur-barat. Pada musim timur kondisi salinitas tampak lebih tinggi, berkisar 30,9‰–32,8‰ (rata-rata 32,3‰), sebaliknya pada saat musim peralihan, kondisinya relatif rendah (barat-timur, rata-rata 28,5‰; timur-barat 29,1‰). Hal tersebut menunjukkan bahwa musim angin berhubungan erat dengan kondisi massa air di Teluk Jakarta. 156 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL SALIN - Barat .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL SALIN - Barat-Timur 6.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107. Bujur Timur Gambar 3. Pola sebaran mendatar salinitas permukaan laut di perairan Teluk Jakarta pada musim yang berbeda. 157 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL SALIN - Timur 6.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107 Bujur Timur LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL SALIN - Timur-Barat .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107. Bujur Timur Gambar 3. Pola sebaran mendatar salinitas permukaan laut di perairan Teluk Jakarta pada musim yang berbeda (lanjutan) 158 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Massa air laut Teluk Jakarta secara umum merupakan massa air Laut Jawa yang pada dasarnya memiliki kadar salinitas relatif tinggi (Ilahude 1995). Kondisi biofisik pantai—banyak sungai-sungai yang bermuara— serta pengaruh kondisi iklim yang terjadi secara periodik akan memengaruhi kualitas perairan Teluk Jakarta. Pada musim barat, pengaruh air tawar sangat kuat berasal dari sungai-sungai di sebelah timur (Tg. KarawangGembong), pengaruh sungai ini masih tampak kuat hingga musim peralihan barat-timur. Pada musim timur justru sebaliknya, pengaruh sungai sangat kuat berasal dari sungai-sungai di sebelah barat (KamalCengkareng), selanjutnya pada musim peralihan timur-barat banyak dipengaruhi sungai-sungai sebelah timurnya (Angke-Muara Karang). 2.1.Oksigen Terlarut (DO) Kadar oksigen terlarut permukaan laut tiap musim angin memperlihatkan nilai yang tidak barvariasi (Lampiran 5). Pada musim barat, oksigen terlarut berkisar 5,44–9,54 ppm, terendah pada stasiun B1 dan tertinggi pada stasiun C6. Pada musim peralihan barat-timur, DO berkisar 6,34–8,06 ppm, oksigen terendah dijumpai pada stasiun A3 dan tertinggi pada stasiun C5. Pada musim timur, kadar oksigen terlarut relatif lebih rendah, berkisar 5,44–7,62 ppm, oksigen terendah dijumpai pada stasiun A3 dan tertinggi pada stasiun B1. Pada musim peralihan timur-barat, kadar oksigen relatif sama dibandingkan pada musim timur, berkisar 5,41–7,48 ppm. Pola sebaran mendatar kandungan oksigen terlarut di Teluk Jakarta disajikan pada Gambar 4. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada musim barat, kadar oksigen tertinggi terkonsentrasi di sebelah timur Teluk Jakarta, terutama di sekitar muara Gembong, sebaliknya di sebelah barat (sekitar muara Kamal dan Cengkareng) cenderung rendah. Pada musim peralihan barat-timur, sebagian besar oksigen terlarut terkonsentrasi di dekat muara-muara sungai yang berada di pantai sebelah selatan, sebaliknya di sebelah utara hingga perairan tengah Teluk Jakarta oksigen terlarut cenderung rendah. Pada musim timur, sebagian besar perairan Teluk Jakarta memiliki kadar oksigen terlarut relatif rendah, sebaliknya pada beberapa lokasi muara Kamal dan Cengkareng tampak tinggi. Pada musim peralihan timur-barat, kondisi menunjukkan sebaliknya. 159 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL DO Barat-Tmur 6.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL DO - Barat .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur Gambar 4. Pola sebaran mendatar rata-rata oksigen terlarut di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011 160 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL DO Tmur .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL DO Timur-Barat 4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur Gambar 4. Pola sebaran mendatar rata-rata oksigen terlarut di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011 (lanjutan) 161 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Gambaran pola sebaran oksigen terlarut pada setiap musim menunjukkan adanya pengaruh massa air Laut Jawa sangat kuat. Pada musim barat, massa air Laut Jawa dengan kadar oksigen relatif rendah tampak memasuki perairan Teluk Jakarta dari arah barat menuju tenggara. Sementara itu, pada saat yang sama pula massa air sungai beroksigen tinggi yang berasal dari sebelah tenggara (Marunda-Gembong) juga memasuki Teluk Jakarta, meskipun tidak tampak dominan. Pola sebaran berikutnya tampak berkembang ketika musim peralihan barat-timur berlangsung, yakni massa air dari muara dengan kadar oksigen relatif tinggi telah mendorong sangat kuat ke sebagian besar perairan Teluk Jakarta. Pada saat memasuki musim timur, massa air Laut Jawa dengan kadar oksigen rendah kembali memasuki perairan Teluk sangat dominan hingga menekan sampai pantai sebelah selatan. Pada musim peralihan timurbarat, pola sebaran tampak mirip dengan musim timur dengan kualitas sangat berbeda, yakni didominasi massa air Laut Jawa berkadar oksigen relatif tinggi. Sementara itu, pengaruh air sungai berkadar oksigen rendah pada musim ini juga memasuki perairan Teluk Jakarta walaupun tidak begitu dominan 2.2. Kadar pH air Nilai pH air permukaan laut pada masing-masing stasiun relatif stabil tidak banyak bervariasi, nilainya berada pada kisaran lebih dari 7 sampai 8 (Lampiran 6). Pada musim barat pH berkisar 7,11–8,19, terendah dijumpai pada stasiun B2 dan tertinggi pada stasiun C5. Pada musim peralihan barat-timur, pH berkisar 7,30–8,28, nilai terendah pada stasiun C6 dan tertinggi pada stasiun C5. Pada musim timur, pH air berkisar 7,80–8,20, pH terendah pada stasiun C2 dan tertinggi pada stasiun zona B. Pada musim peralihan, kondisinya tidak berbeda dengan kondisi pada musim timur, pH berkisar 7,86–8,35. pH terendah pada stasiun B1 dan tertinggi pada stasiun A1. Berdasarkan pada variasi nilai pH di permukaan, menunjukkan pola sebaran yang bervariasi pada setiap musim yang berbeda (Gambar 5). Pada musim barat, pH relatif tinggi cenderung berasal dari muara sungai yang berada di sebelah timur (Tg. Karawang-GembongMarunda) yang memasuki Teluk sampai dengan wilayah tengah. Pada saat musim peralihan barat-timur, kondisinya berubah, massa air sungai dengan pH tinggi yang sebagian berasal dari sungai di sepanjang pantai 162 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta selatan Teluk memasuki sebagian besar Teluk Jakarta hingga tengah laut. Pada musim timur, tampak bahwa massa air dengan pH tinggi dari muaramuara sungai sebelah timur (Tg. Karawang-Gembong) kembali memasuki wilayah perairan dan bergerak menuju barat Teluk. Pada musim peralihan timur-barat, massa air di sebagian besar teluk terdiri dari dua massa air yang berbeda (muara sungai dan Laut Jawa), yang masing-masing tidak mendominasi sehingga tampak terpusat pada tempat-tempat tertentu. LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL pH - Barat 6.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL pH - Barat-Timur 6.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur Gambar 5. Pola sebaran mendatar rata-rata pH air di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011 163 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL pH - Timur .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107. Bujur Timur LAUT JAWA TG.KARAWANG TG.GEMBONG M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG M.MARUNDA M.ANCOL pH Timur-Barat .4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107. Bujur Timur Gambar 5. Pola sebaran mendatar rata-rata pH air di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011 (lanjutan) 164 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta 3. Kondisi Biologi Perairan 3.1. Bentos Analisis kelimpahan bentos difokuskan pada nilai keanekaragaman jenis makrozoobentos yang merupakan salah satu indikator biologi untuk menilai status tingkat pencemaran di perairan. Hasil analisis menunjukkan nilai indeks keanekaragaman jenis yang bervariasi seperti tampak pada Lampiran 7. Pada musim barat, indeks keragaman tertinggi 2,97 ditemukan pada stasiun B6, sebaliknya terendah bernilai nol, dijumpai pada stasiun muara Kamal (M1) dan muara Angke (M3). Pada musim peralihan barattimur, indeks keragaman serupa seperti pada musim barat, berkisar nol sampai 2,99 dengan indeks terendah dijumpai pada muara Angke (M3) dan relatif tinggi pada stasiun B6. Pada musim timur, kondisinya tampak lebih rendah, berkisar nol sampai dengan 2,43, terendah umumnya di muara-muara sungai Kamal dan Cengkareng, sedangkan relatif tinggi di stasiun A4. Kondisi agak lebih baik tampak terjadi pada musim peralihan timur-barat, yakni berkisar 0,21–3,0, indeks tertinggi pada stasiun B6 dan terendah pada stasiun D5. LAUT JAWA -5.8 Indeks div. Barat TG.KARAWANG -5.9 -6 TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.MARUNDA M.ANCOL -6.2 0 1 2 3 -6.3 -6.4 106.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 106.3 to to to to 1 2 3 4 106.4 tercemar berat tercemar ringan tercemar sedang tidak tercemar 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur Gambar 6. Variasi rata-rata indeks keanekaragam jenis bentos tiap stasiun penelitian di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011 165 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya LAUT JAWA -5.8 Indeks div. Barat-Timur TG.KARAWANG -5.9 -6 TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.MARUNDA M.ANCOL -6.2 0 1 2 3 -6.3 -6.4 106.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 106.3 to to to to 1 2 3 4 106.4 tercemar berat tercemar ringan tercemar sedang tidak tercemar 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107. Bujur Timur LAUT JAWA -5.8 Indeks div. Timur TG.KARAWANG -5.9 -6 g TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.MARUNDA M.ANCOL -6.2 0 1 2 3 -6.3 -6.4 106.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 106.3 to to to to 1 2 3 4 106.4 tercemar berat tercemar ringan tercemar sedang tidak tercemar 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur LAUT JAWA -5.8 Indeks div. Timur-Barat TG.KARAWANG -5.9 -6 TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE M.MARUNDA M.ANCOL -6.2 0 1 2 3 -6.3 -6.4 106.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 106.3 to to to to 1 2 3 4 106.4 tercemar berat tercemar ringan tercemar sedang tidak tercemar 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur Gambar 6. Variasi rata-rata indeks keanekaragam jenis bentos tiap stasiun penelitian di Teluk Jakarta pada musim yang berbeda tahun 1996–2011 (lanjutan) 166 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Berdasarkan sebaran nilai indeks keragamannya, diperoleh gambaran pola sebaran seperti tampak pada Gambar 6. Nilai indeks keanekaragaman tampak sangat rendah di sebagian besar perairan muara. Bahkan pada musim timur, kondisi tersebut hampir merata pada semua perairan Teluk. Variasi nilai indeks keanekaragaman bentos pada masing-masing stasiun pengamatan berkisar nol sampai dengan 3, rata-ratanya antara 1,02 sampai dengan 1,71. Hal tersebut menunjukkan nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan nilai baku mutu perairan, sehingga dapat dikatakan sebagian besar perairan Teluk Jakarta sudah tercemar dengan tingkat ringan sampai berat. Kondisi tampak lebih buruk khususnya di sekitar muara-muara sungai, terutama pantai sebelah selatan Teluk Jakarta, yang diduga berkaitan erat dengan tingginya bahan pencemar di daerah tersebut. 3.2. Kelimpahan Plankton Analisis terhadap plankton pada penelitian ini difokuskan pada nilai kelimpahan fitoplankton yang dianggap sebagai indikator kesuburan perairan. Hasil analisis kelimpahan fitoplankton pada musim barat, peralihan barat-timur dan peralihan timur barat tercantum pada Lampiran 8, sedangkan pada musim timur tidak ditampilkan karena data tidak mencukupi. Pada musim barat, kelimpahan relatif tinggi, berkisar 816x105 sel/ m3 sampai dengan 25.372(x105 ) sel/m3, tertinggi pada stasiun D5 dan terendah pada stasiun B2. Pada musim peralihan barat-timur, berkisar 3x105 sel/m3 sampai dengan 909.634 x105 sel/m3. Kelimpahan fitoplankton paling rndah ditemukan pada saat musim peralihan barat timur, berkisar 21 sampai 2.350 x105 sel/m3. Berdasarkan sebaran nilai kelimpahan fitoplankton, diperoleh gambaran pola sebaran secara mendatar seperti pada Gambar 7. Pada musim barat, kelimpahan tertinggi terkonsentrasi di dekat muara-muara, terutama di sekitar pantai sebelah timur dan selatan Teluk Jakarta. Pada musim peralihan barat-timur, perairan yang padat fitoplankton terkonsentrasi dekat muara pada pantai sebelah selatan, sedangkan pada musim peralihan timur-barat, konsentrasi terpadat berada di pantai 167 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya sebelah barat dan selatan Teluk Jakarta. Bila dilihat dari sebaran variasi nilai kelimpahan fitoplankton, tampak bahwa pola sebarannya tidak memberikan pola yang nyata pada musim yang berbeda. Pada musimmusim peralihan barat-timur maupun timur-barat polanya hampir sama yakni kelimpahan terpadat cenderung pada muara-muara sungai Sunter ke arah timur hingga muara Gembong. LAUT JAWA -5.8 Fitoplankton. Barat TG.KARAWANG -5.9 -6 TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE -6.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 8160003.5 to 39576840 M.MARUNDA M.ANCOL 39576840 to 53224280 -6.3 53224280 to 80779658 80779658 to 107523733.5 107523733.5 to 253800000 -6.4 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107.1 Bujur Timur LAUT JAWA -5.8 Fitoplankton. Barat-Timur TG.KARAWANG -5.9 -6 TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE -6.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 8160003.5 to 39576840 M.MARUNDA M.ANCOL 39576840 to 53224280 -6.3 53224280 to 80779658 80779658 to 107523733.5 107523733.5 to 253800000 -6.4 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107. Bujur Timur Gambar 7. Variasi sebaran rata-rata kelimpahan fitoplankton di perairan Teluk Jakarta pada tiga musim yang berbeda pada tahun 1996–2011 168 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta LAUT JAWA -5.8 Fitoplankton. Timur-Barat TG.KARAWANG -5.9 -6 TG.GEMBONG -6.1 M.GEMBONG KAMAL CENGKARENG ANGKE -6.2 M.SUNTER M.CAKUNG M.KARANG 8160003.5 to 39576840 M.MARUNDA M.ANCOL 39576840 to 53224280 -6.3 53224280 to 80779658 80779658 to 107523733.5 107523733.5 to 253800000 -6.4 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8 106.9 107 107 Bujur Timur Gambar 7. Variasi sebaran rata-rata kelimpahan fitoplankton di perairan Teluk Jakarta pada tiga musim yang berbeda pada tahun 1996–2011 (lanjutan) Kesimpulan 1. Perairan Teluk Jakarta termasuk perairan dangkal dengan kecerahan relatif rendah. 2. Variasi musim angin sangat nyata pengaruhnya terhadap pola sebaran suhu, salinitas, DO maupun pH yang erat kaitannya dengan sirkulasi massa air Laut Jawa maupun massa air sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. 3. Berdasarkan nilai indeks keanekaragaman bentos, disimpulkan bahwa perairan Teluk Jakarta terindikasi tercemar ringan sampai sangat berat. Daftar Pustaka Anonimous. 1959. U.S.Navy Hydrographic Office, Instruction Manual for Oceanographic of Observation , H.O.Publ.No. 607, Washingto DC, p. 1-210. Abbort RT and Dance SP. 1982. Compendium of Sea Shells, A Full Colour Guide to More Than 4200 of The World Marine Shells, E.P.Duta Inc., New York, 410 pp. 169 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Habe T and Kosuge S. 1966. Shells of The World in Colour, Vol. II”The Tropical Pacific”, Hoikhusha, Tokyo, 193 pp Ilahude AG. 1995. Sebaran suhu, Salinitas, Sigma-T, Oksigen Terlarut dan Zat Hara di Perairan Teluk Jakarta dalam Suyarso (ed). Atlas oseanologi Teluk Jakarta. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia-P3O,.Krebs CJ. 1989. Ecological methodology. Harper and Collins, New York: xii+654 hlm KPPL. 1997. Studi potensi kawasan perairan Teluk Jakarta, Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) DKI Jakarta. Interim Report 1997. Ludwig JA and JF Reynold. 1988. Statictic Ecology. A. Primer on Methods and Computing. New York: John Wiley & Sons, 337 pp. Lestari dan Edward, 2004. Dampak Pencemaran Logam Berat terhadap Kualitas Air Laut dan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus Kematian Massal Ikan-Ikan) di Teluk Jakarta. Makara Sains, Vol.8, No.2: 52–58 Rochyatun E dan A Rozak. 2007. Pemantauan Kadar Logam Berat dalam Sedimen di Perairan Teluk Jakarta. Makara Sains,Vol.11, No.1: 2836 Thomas CR. 1997. Identifying Marine Phytoplankton. San Diego: Academic Press. Tan LWH and Peter KL. 1988. A Guide to Seashore Science Centre, Singapore, 159pp. Yatim S, Surtipanti S, Suwirma dan E Lubis. 1979. Distribusi logam berat dalam air permukaan Teluk Jakarta. Majalah Batan, No.12: 1–19 Yamaji I. 1996. Illustrations of The Marine Plankton of Japan. Osaka: Hoikhusha Publi. Co.Ltd. Zim HS and Ingle L. 1955. A Golden Guide: Seashores, A Guide to Animals and Plants a Long The Beaches. New York: Golden Press, 160 pp. 170 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Lampiran 1. Posisi geografis lokasi penelitian kualitas perairan Teluk Jakarta Nomor stasion A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C6 D3 D4 D5 D6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Posisi (o) Lintang Selatan 5,985 5,976 5,964 5,958 5,942 5,926 5,910 6,060 6,048 6,039 6,027 6,010 5,988 5,976 6,117 6,102 6,083 6,072 6,050 6,152 6,135 6,113 6,105 6,100 6,140 6,151 6,162 6,177 6,140 6,137 6,136 6,099 Bujur Timur 106,545 106,626 106,697 106,774 106,845 106,920 106,983 106,588 106,651 106,720 106,794 106,867 106,938 106,997 106,639 106,736 106,808 106,882 106,952 106,751 106,792 106,901 106,969 106,544 106,570 106,638 106,659 106,749 106,863 106,918 106,940 107,024 171 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Lampiran 2. Variasi kedalaman perairan dan tingkat kecerahan air di Teluk Jakarta 172 Stasiun Kedalaman (m) Kecerahan (m) A1 11 3 A2 20 4 A3 25 5 A4 25 7 A5 25 6 A6 23 5 A7 19 3 B1 5 2 B2 14 3 B3 19 4 B4 22 5 B5 21 5 B6 21 4 B7 15 3 C2 11 3 C3 15 4 C4 15 4 C5 16 3 C6 15 3 D3 7 4 D4 6 3 D5 8 3 D6 10 3 Minimum 5 2 Maksimum 25 7 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Lampiran 3. Suhu air permukaan laut Teluk Jakarta pada musim yang berbeda pada periode tahun 1996–2011 Stasiun A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C6 D3 D4 D5 D6 Min Max Musim Barat 29.22 30.86 30.12 29.20 29.01 29.38 29.18 29.67 29.06 30.53 29.18 28.50 28.87 29.86 29.09 31.04 29.10 28.94 29.13 29.75 28.70 28.80 28.87 28.50 31.04 Peralihan Barat-Timur Musim Timur Peralihan Timur-Barat 30.45 29.62 30.07 30.54 29.50 30.45 30.45 29.55 30.34 30.24 29.54 29.96 30.24 29.33 30.10 30.08 29.35 30.25 30.33 29.50 30.48 31.02 29.97 30.43 30.37 29.50 30.14 30.43 29.44 30.11 29.96 29.42 29.98 30.16 29.23 29.77 30.62 29.30 29.94 30.24 29.20 31.04 30.35 29.90 30.32 30.54 29.40 30.34 30.47 29.12 30.32 30.46 29.12 30.33 30.62 29.40 30.59 30.65 29.50 30.54 30.75 29.40 30.71 31.12 29.48 30.72 30.67 29.38 30.85 29.96 29.12 29.77 31.12 29.97 31.04 173 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Lampiran 4. Kadar salinitas permukaan laut (‰) Teluk Jakarta pada musim yang berbeda pada periode tahun 1996– 2011 Stasiun A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C6 D3 D4 D5 D6 Min Max 174 Musim Barat Peralihan Barat-Timur Musim Timur Peralihan Timur-Barat 31.4 28.90 31.5 29.6 31.3 29.96 32 29.5 30.6 30.12 32.5 30.3 31.3 30.30 32.8 29.9 30.3 28.70 32.7 29.1 30.2 28.82 32.7 28.1 27.8 22.04 32.2 28.2 31.1 28.40 31 30.4 31.6 29.53 31.5 30.7 30.7 29.53 32.6 29.6 31.4 29.39 32.4 29.5 31.6 30.47 32.6 29.4 28.2 28.21 32.6 29.1 28.7 28.07 32.7 27.0 31.3 27.84 30.9 25.0 31.6 29.44 32.7 29.3 31.6 29.43 32.8 29.3 27.0 28.73 32.6 29.3 30.0 25.01 32.5 28.9 31.4 29.88 32.7 28.7 32.0 29.89 32.6 29.4 31.3 27.76 32.6 29.4 31.0 25.50 32.3 29.4 27.0 22.0 30.9 25.0 32.0 30.5 32.8 30.7 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Lampiran 5. Kadar oksigen terlarut permukaan laut (ppm) Teluk Jakarta pada musim yang berbeda, pada periode tahun 1996–2011 Stasiun A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C6 D3 D4 D5 D6 Min Max Musim Barat 6.65 6.49 6.49 6.89 7.39 6.96 7.20 5.44 6.57 6.81 6.57 8.13 7.36 7.28 6.34 6.42 7.12 7.55 9.54 6.42 7.82 9.07 9.33 5.44 9.54 Peralihan Barat-Timur 7.34 7.77 6.34 6.51 6.74 6.58 6.71 7.92 7.68 7.40 6.96 7.08 7.19 6.96 7.65 7.09 7.40 8.06 7.31 7.18 7.28 8.01 7.77 6.34 8.06 Musim Timur 6.48 5.70 5.44 5.56 5.66 5.60 5.69 7.62 6.81 5.87 5.82 5.72 6.02 6.37 6.28 5.70 5.45 5.62 6.29 6.52 5.74 6.43 6.71 5.44 7.62 Peralihan Timur-Barat 6.13 7.42 6.90 6.59 6.96 6.94 7.10 5.41 7.25 7.48 6.57 7.22 7.35 6.82 6.86 7.01 7.11 7.02 7.37 6.29 6.91 6.55 6.02 5.41 7.48 175 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Lampiran 6. Kadar pH air laut di permukaan Teluk Jakarta pada musim yang berbeda pada periode tahun 1996– 2011. Stasiun A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C6 D3 D4 D5 D6 Min Max 176 Musim Barat 7.22 7.41 7.18 7.21 7.98 8.12 8.05 7.20 7.11 7.20 7.96 8.00 8.04 7.91 7.67 7.36 8.13 8.19 8.13 7.48 8.07 8.12 8.16 7.11 8.19 Peralihan Barat-Timur 7.63 7.75 7.64 7.56 7.53 7.45 7.79 7.68 7.64 7.62 7.55 7.73 7.72 7.65 8.03 8.15 8.07 8.28 7.30 7.87 8.17 7.88 7.55 7.30 8.28 Musim Timur Peralihan Timur-Barat 7.9 8.35 8 8.09 8 8.00 8 8.21 8.1 8.01 8.1 7.94 8.1 8.00 8.2 7.86 8.2 7.92 8.2 8.03 8.2 8.00 8.1 8.01 8.2 7.94 8.2 7.99 7.8 8.01 7.9 8.08 7.9 8.21 7.9 8.11 8 7.92 8 8.00 8 8.08 8.1 8.01 8 8.03 7.80 7.86 8.20 8.35 Kondisi Lingkungan Perairan Teluk Jakarta Lampiran 7. Nilai indeks keanekaragaman jenis makrozoobentos di perairan Teluk Jakarta pada musim yang berbeda, pada periode tahun 1996–2011 Stasi un Musi m Barat Peral i han Barat-Ti mur Musi m Ti mur A1 2.88 2.50 1.27 Peral i han Ti mur-Barat 2.55 A2 2.16 2.31 1.45 1.81 A3 2.34 2.04 1.85 2.13 A4 2.22 1.56 2.43 2.01 A5 1.88 2.00 0.73 1.90 A6 1.92 2.28 1.76 1.82 A7 2.66 2.52 0.97 1.99 B1 1.90 1.50 0.84 1.45 B2 2.66 2.76 0.44 2.44 B3 2.69 2.08 1.26 2.45 B4 1.93 2.51 2.22 1.67 B5 2.87 2.84 1.86 2.58 B6 2.97 2.99 0.58 3.00 B7 1.59 2.43 1.95 1.48 C2 1.28 0.84 1.78 1.02 C3 2.24 2.34 0.81 2.52 C4 2.88 2.76 1.65 2.85 C5 1.29 2.86 0.30 1.39 C6 1.45 1.73 0.48 1.29 D3 1.00 0.75 0.39 0.81 D4 0.73 0.89 0.24 0.81 D5 0.08 0.24 0.21 0.21 0.47 D6 0.70 0.46 2.14 M1 0.00 0.66 0.00 0.93 M2 0.59 1.12 0.00 1.31 M3 0.00 0.00 1.36 0.60 M4 1.27 0.98 0.11 0.72 M5 1.43 1.23 1.35 1.05 M6 0.92 0.33 0.11 0.92 M7 1.99 1.81 1.18 1.10 M8 1.77 1.34 0.83 0.94 M9 0.44 2.24 0.07 1.41 Mi n 0.00 0.00 0.00 0.21 Max 2.97 2.99 2.43 3.00 177 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Lampiran 8. Kelimpahan fitoplankton (x105 sel/m3) pada lokasi stasiun penelitian di Teluk Jakarta pada tiga musim berbeda, pada periode tahun 1996–2011. Stasiun A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C6 D3 D4 D5 D6 Min Max 178 Musim Barat Peralihan Barat-Timur Peralihan Timur-Barat 3958 10075 212 5322 34249 2350 7657 26 236 8165 13768 56 8078 46 65 9424 2251 21 10752 8 78 3576 223 302 816 123194 98 10123 388 194 6846 13200 118 6108 1082 146 5081 874 109 3566 3 146 12105 593506 243 13002 471 34 3648 384859 129 4129 239969 260 10574 2707 771 7677 92 242 4159 259240 826 25372 909634 517 16532 299567 215 816 3 21 25372 909634 2350 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh Muhammad Taufik , Tuti Hariati1 dan Mohamad Fauzi1 1 Abstrak Sumber daya ikan pelagis kecil sebagai salah satu sumber daya ikan di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu merupakan sumber daya yang penting. Selain sebagai sumber pemenuhan gizi dan protein yang murah, sumber daya tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Sumber daya ikan pelagis kecil sudah sejak lama dimanfaatkan di Teluk Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama tahun 2006–2008 dapat diketahui jenis-jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu antara lain adalah ikan kembung (Rastrelliger brachysoma), banyar (Rastrelliger kanagurta), selar (Selar crumenophthalmus), selar kuning (Selaroides leptolepis), selar hijau (Atule mate), tetengkek (Megalaspis cordyla), tembang (Sardinella gibbosa), siro (Amblygaster sirm), dan teri (Stolephorus sp.). Alat tangkap yang dioperasikan nelayan untuk menangkap ikan pelagis kecil adalah payang, jaring rampus kembung, dan bagan. Alat tangkap bagan merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena hasil tangkapannya didominasi trash fish, merupakan ikan-ikan kecil yang bila dibiarkan tumbuh besar akan bernilai ekonomis tinggi. Hasil penelitian mengenai biologi ikan kembung (Rastrelliger brachysoma) pada tahun 2010 di perairan Teluk Jakarta menunjukkan bahwa nilai L∞=19,9 cm; L50=16,1 cm dan Lm=16,37 cm. Kata kunci: pelagis kecil, Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu, alat tangkap. 1 Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Sumber daya ikan laut yang tertangkap di kawasan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta terdiri dari ikan pelagis kecil dan demersal. Kelompok jenis ikan pelagis kecil antara lain jenis ikan kembung, selar, tembang, dan layang, sedangkan kelompok ikan demersal ikan petek dan ikan manyung. Sifat sumber daya ikan laut yang penting adalah mampu memperbarui dirinya (renewable) namun bukan tanpa batas, sehingga dapat luruh (perishable) dengan tekanan eksploitasi yang berlebihan (over exploitated). Sebagai sumber daya yang pemanfaatannya bersifat terbuka (open access) dengan pemilikan yang bersifat umum (common property) diperlukan usaha pengelolaan yang akan mengatur pemanfaatan, pelestarian, dan (jika diperlukan) juga rehabilitasinya. Peranan sumber daya ikan pelagis kecil sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sumber daya tersebut berperan dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan protein masyarakat di dalam negeri, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan serta penduduk di wilayah pesisir. Selain itu, sumber daya ikan pelagis kecil memberikan lapangan kerja, mendukung agribisnis, dan agroindustri serta pengembangan wilayah (Widodo et al. 1994). Sumber daya ikan pelagis kecil mempunyai sifat-sifat berikut: 1) bentuk badan seperti cerutu, 2) kulit dan tekstur tubuh yang mudah rusak serta daging yang berkadar lemak tinggi sehingga mudah mengalami kerusakan mutu, 3) membentuk gerombolan-gerombolan yang terpencar (patchness), 4) melakukan ruaya (migrasi) secara reguler baik temporal maupun spatial mengikuti pola perubahan musiman dari kondisi lingkungan, dan 5) mempunyai variasi rekrutmen yang tinggi dan erat kaitannya dengan kondisi lingkungan yang labil (Widodo et al. 1994). Pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di perairan Kawasan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta sudah berlangsung sejak tahun 1960an menggunakan alat tangkap bagan. Saat ini jenis-jenis alat tangkap lainnya yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil terutama jaring insang/rampus, sero, dan payang. Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan perikanan, informasi sumber daya perikanan terkini sangat penting bagi para perencana 180 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu pembangunan perikanan di suatu daerah. Tulisan ini menyajikan hasil riset tahun 2006–2007 serta 2010. Data dan informasi perikanan pelagis kecil di perairan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta yang dihasilkan, diharapkan bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pelaksanan pengelolaan di wilayah tersebut. Metodologi € Gambar 1. Peta lokasi penelitian Pengumpulan data perikanan pelagis kecil dilakukan oleh Tim Peneliti dari Balai Penelitian Perikanan Laut pada tahun 2006–2008. Adapun jenis data yang dikumpulkan meliputi data alat tangkap, daerah penangkapan, jenis ikan yang tertangkap, dan beberapa aspek biologi ikan pelagis kecil. Lokasi-lokasi penelitian pada tahun 2006 dipusatkan di perairan Teluk Jakarta (Pulau Bidadari, Pulau Onrust dan sekitarnya) (Gambar 1), pada tahun 2007 di perairan Kepulauan Seribu (Pulau Tidung, Pulau Kelapa, 181 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pulau Lancang) dan pada tahun 2008 dipusatkan di gugusan Pulau Pari dan sekitarnya. Penelitian aspek biologi hanya dilakukan terhadap jenis ikan kembung perempuan (Rastrelliger brachysoma) yang dilaksanakan pada tahun 2010. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengikuti aktivitas penangkapan setiap jenis alat tangkap sampel di perairan. Pengambilan sampel untuk pengamatan aspek biologi ikan kembung dengan melakukan pengukuran terhadap karakter individu dari setiap individu ikan seperti panjang (FL dan TL, cm), berat tubuh (gram), sex, tingkat kematangan gonad (visual), berat gonad segar (gram). Sex dan tingkat kematangan gonad (TKG) ditentukan secara visual melalui pembedahan bagian perut (abdomen) terlebih dahulu. Gonad (testis dan ovary) ditimbang dalam keadaan segar. Beberapa ovary, terutama TKG III/maturing dan IV/mature diambil dan diawetkan dengan larutan Gilson untuk validasi TKG dan eksaminasi telur/ova secara mikroskopik. Ekstra sampling juga dilakukan terhadap ikan-ikan betina matang (dengan hydrated oocyte) yang biasanya berukuran lebih besar. Posisi (Lintang dan Bujur) pengoperasian setiap jenis alat tangkap yang diikuti, dicatat dengan alat GPS. Hasil dan pembahasan 1. Jenis Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil Jenis-jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap di kawasan perairan Kepulauan Seribu—yang mencakup perairan Teluk Jakarta—umumnya sama dengan yang biasa tertangkap di perairan lainnya di wilayah Indonesia, seperti ikan kembung, banyar, selar, tembang, alu-alu, tetengkek dan teri. Jenis-jenis ikan pelagis kecil tersebut juga ditemui di perairan pantai lainnya, misalnya di perairan Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Malaka, dan di perairan barat Sumatera (Hariati 2005). Salah satu jenis ikan yang kehadirannya temporer adalah ikan cekong (Sardinella sp.). Ikan tersebut muncul ketika kadar garam perairan meningkat yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Jenis ikan pelagis kecil yang bernilai ekonomis di antaranya adalah ikan kembung, ikan banyar, dan ikan selar kuning (Indarsyah dan Hartati 2008). 182 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Selama pengamatan terhadap hasil tangkapan dari beberapa jenis alat tangkap yang beroperasi di kawasan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta, dapat diketahui terdapat 6 Famili ikan pelagis kecil yang terdiri dari 13 spesies yaitu Carangidae (5 spesies), Clupeidae (3 spesies), Scombridae (2 spesies), Engraulidae (1 spesies), Sphyraenidae (1 spesies), dan Chirocentridae (1 spesies). Nama jenis-jenis ikan pelagis kecil tersebut beserta nama lokalnya dapat dilihat dalam Tabel 1. Tabel 1. Sumber daya ikan pelagis kecil utama yang tertangkap di perairan Kepulauan Seribu tahun 2006-2008 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Famili Carangidae Clupeidae Scombridae Engraulidae Spyraenidae Chirocentridae Spesies Selaroides leptolepis Alepes spp. Atule mate Selar crumenophthalmus Selar boops Sardinella gibbosa Sardinella sp. Amblygaster sirm Rastrelliger kanagurta Rastrelliger brachysoma Stolephorus spp. Sphyraena spp. Chirocentrus dorab Nama lokal Selar kuning Selar como Selar hijau Selar bentong Selar bentong Tembang Cekong/Krismon Siro/Lemuru Jawa Banyar Kembung Teri Alu-alu Parang-parang 2. Jenis Alat Tangkap untuk Menangkap Ikan Pelagis Kecil Jenis-jenis alat tangkap yang dioperasikan nelayan di perairan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta adalah payang, bagan tancap, muroami, sero, pancing dan jaring (gillnet) rampus. Pengamatan ini khusus mengamati alat tangkap ikan pelagis kecil yaitu bagan, payang, jaring rampus atau jaring kembung. Daerah penangkapan ikan pelagis kecil hampir terdapat di seluruh perairan Kepulauan Seribu. Untuk bagan terdapat di perairan Teluk Jakarta terutama di sepanjang pantai bagian barat (Pulau Bidadari, Onrust, dan sekitarnya), Pulau Lancang dan di gugusan Pulau Pari; untuk payang di perairan Teluk Jakarta misalnya 183 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pulau Damar, Muara Angke dan sekitarnya pada kedalaman perairan 20– 30 meter, di Kepulauan Seribu sekitar Pulau Kelapa. 2.1 Bagan Tancap Daerah Penangkapan Berdasarkan hasil penentuan posisi geografis alat tangkap bagan tancap di Teluk Jakarta pada tahun 2006, diperoleh daerah penangkapan bagan seperti dalam Gambar 2 yang meliputi seluruh bagian dari Teluk Jakarta dengan bagian terpadat di sebelah barat. Sedangkan 7 unit bagan tancap sampel yang terletak di bagian barat Teluk sekitar Pulau Kayangan, Bidadari dan Onrust posisinya dapat dilihat pada gambar 3. Lokasi penelitian pada tahun 2007 dapat dilihat pada Gambar 4 di mana lokasi bagan sampel ada di perairan sebelah barat Pulau Lancang, berjarak kurang lebih 1 km dari pantainya. Menurut informasi nelayan, jumlah bagan di perairan Teluk Jakarta pada tahun 2005 adalah 498 unit. 5.92 SKALA 1 : 50000 8 15 29 8 6.00 16 24 19 9 10 15 17 7 2 6 12 10 178 6.08 30 11 30 2420 6 10 42 16 9 13 9 5 8 1 9 12 1925 3 Lokasi aktivitas tangkap Bagan 6.17 106.67 106.75 106.83 106.92 107.00 Gambar 2. Peta lokasi pengamatan aktivitas bagan tancap di seluruh perairan Teluk Jakarta 184 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu 6.1 2 6.05 . Kamal 1 3 4 6 5 7 6 Pluit 5.95 Priok 106.7 106.75 106.8 106.85 106.9 106.95 107 107.05 Gambar 3. Peta lokasi pengamatan aktivitas bagan tancap sampel di perairan barat Teluk Jakarta, bulan Mei 2006 (1–7 = Posisi bagan tancap yang diamati) Komposisi jenis ikan hasil tangkapan bagan Komposisi jenis ikan hasil tangkapan bagan pada tahun 2006 didominasi oleh ikan campuran (Trash Fish) sebanyak (60%), kemudian diikuti oleh kelompok ikan pelagis kecil (36%) yaitu ikan banyar (Scombridae) 21%, tembang (Clupeidae) 9%, dan teri (Engraulidae) 6%. Sisanya (4%) terdiri dari jenis-jenis nonikan seperti sotong (Sepiidae), rebon (Hemirhampidae), dan jenis-jenis ikan demersal kapas-kapas (Gerreidae), seperti kuwe (Carangidae) dan sokang (Triacanthidae). Pada tahun 2007, hasil tangkapan bagan didominasi oleh teri (49%), di mana secara keseluruhan hasil tangkapan didominasi oleh kelompok ikan pelagis kecil (71 %) yang terdiri dari ikan teri, belo, tembang, dan selar kuning. Komposisi hasil tangkapan ikan pelagis kecil dari bagan pada bulan Mei 2006 diperkirakan sebanyak 80%, yang terdiri dari ikan tembang (36%), banyar (38%), dan ikan teri (6%). Pada bulan Oktober dan Desember 2006, persentase hasil tangkapan ikan pelagis kecil dari hasil tangkapan total bagan tancap menurun dari bulan Mei 2006 (80%) menjadi masing-masing 20% dan 27%. 185 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Gambar 4. Daerah penangkapan ikan dengan bagan tancap di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu pada tahun 2007 Jika dibandingkan dengan hasil tangkapan bagan pada tahun 1996– 1998, telah terjadi gejala penurunan hasil tangkapan bagan pada tahun 2007. Pada tahun 1996–1998 hasil tangkapan bagan tancap mencapai 500 kg/bagan. Demikian juga dengan ukuran hasil tangkapan yang semakin mengecil. Selain perubahan faktor lingkungan, bertambahnya jumlah bagan tancap dan sero dari tahun ke tahun (adanya lebih tangkap) diduga sebagai penyebabnya. Ikan campuran (Trash fish) terdiri dari jenis-jenis ikan berukuran kecil (nonekonomis) yang hampir selalu mendominasi hasil tangkapan bagan di perairan Teluk Jakarta (Prihatiningsih dan Hartati 2008). Pada bulan Mei 2006, dari pengamatan terhadap komposisi trash fish hasil tangkapan 4 unit bagan sampel telah teridentifikasi 41 jenis ikan, 17 jenis di antaranya adalah ikan pelagis kecil (44%) yang didominasi oleh ikan tembang (Sardinellabrachysoma) 27% dan banyar (Rastreliger kanagurta) 17%. Kemudian kelompok ikan demersal (20 jenis) yang didominasi oleh ikan petek (Leiognathus bindus) dari famili Leiognathidaedan, ikan beseng (Ambassis spp.) dari famili Apogonidae, serta dari kelompok nonikan (4 186 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu jenis) didominasi oleh udang kipas (Chloridopsis scorpio) sekitar 16%. Untuk mempertahankan kelestarian sumber daya ikan, diharapkan ikan campuran (Trash fish) tidak tertangkap. Jika tidak tertangkap, trash fish dapat tumbuh menjadi ikan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Laju tangkap ikan pelagis kecil Hasil observasi dari 6 bagan pada bulan Mei 2006, hasil tangkapan berkisar 10–132 kg dengan laju tangkap 50 kg/bagan/hari. Berdasarkan pengamatan pada bulan Oktober 2006, hasil tangkapan total dari 2 bagan masing-masing 150 kg dan 1.082 kg/dengan rata-rata 616 kg/bagan/ hari. Pada bulan Desember, hasil tangkapan dari 7 unit bagan berkisar 37–172 kg dengan laju tangkap 74 kg/bagan/hari. Diduga laju tangkap ikan pelagis kecil pada bulan Mei, Oktober dan Desember masing-masing 40 kg/bagan/hari, 123,2 kg/bagan/hari, dan 20 kg/bagan/hari. Hasil tangkapan ikan dari alat tangkap bagan tancap yang didaratkan di Pulau Lancang pada bulan Juli 2007 berkisar 2–190 kg dengan laju tangkap 25 kg/bagan/trip/hari. Selama pengamatan pada tahun 2006–2007, laju tangkap total jenisjenis ikan yang tertangkap bagan 38–170 kg/bagan/hari, sedangkan laju tangkap ikan pelagis kecil berkisar 17–40 kg/bagan/hari. Mengingat komposisi jenis-jenis ikan campuran (Trash fish) yang tertangkap oleh alat tangkap bagan terdiri dari yuwana dan ikan-ikan ekonomis, diperlukan pengaturan agar jumlah (%) tangkapan trash fish sekecil mungkin sehingga ikan-ikan tersebut mendapat kesempatan tumbuh yang kemudian tertangkap pada ukuran dewasa. Ukuran jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ikan banyar dan tembang yang tertangkap di perairan Kepulauan Seribu terutama oleh alat tangkap bagan pada umumnya relatif kecil karena terdiri dari ikan muda, seperti yang telah dikemukakan oleh Prihatiningsih dan Hartati (2008). Prihatiningsih dan Hartati (2008) menyarankan agar areal penangkapan bagan sebaiknya tidak dibangun di lokasi-lokasi yang merupakan daerah asuhan yang diduga berada di perairan Teluk Jakarta, tetapi di perairan Kepulauan Seribu di mana tertangkap jenis-jenis ikan teri seperti di sekitar Pulau Lancang. 187 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 2.2 Payang Daerah penangkapan Daerah penangkapan payang yang diamati pada tahun 2006 meliputi perairan di sekitar Pulau Damar, Pulau Bendera, Pulau Onrust, Pulau Putri dan di perairan sekitar Kronjo Muara Pecah, Muara Angke. Daerah penangkapan yang diamati pada tahun 2007 adalah di sekitar perairan Pulau Pabelokan sampai ke perairan Pulau Gosong pada kedalaman 20– 30 m. Lama trip payang adalah satu hari (one day fishing), yaitu dari jam 6 sore hari sampai jam 4–6 pagi keesokan harinya. Daerah penangkapan kegiatan penangkapan jaring payang ada juga yang dilakukan hanya pada siang hari, yaitu dari jam 07.00 sampai jam 14.00 siang. Daerah penangkapan siang hari hanya di perairan sebelah barat Pulau Genteng. Kapal yang digunakan berukuran panjang 10–12 m, lebar 2,0–2,5 m, dan dalam 1,5 m dengan tenaga penggerak mesin 300 PK. Awak kapal jaring payang berjumlah 6–8 orang. Dari 15 pelele atau pengumpul ikan yang berada di Pulau Kelapa, rata-rata memiliki 7–8 armada. Komposisi jenis ikan hasil tangkapan payang Hasil tangkapan payang terdiri dari jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ikan cekong (Sardinella sp.), kembung (Rastrelliger sp.), tembang (Sardinella brachyosoma), alu-alu (Sphyraena sp.), dan jenis-jenis ikan demersal. Dalam tahun 2006 hasil tangkapan didominasi ikan pelagis kecil (83%), sedangkan ikan demersal 17% dari total tangkapan payang (Tabel 2). Pada bulan Agustus dan Oktober 2006, kelompok ikan pelagis kecil mendominasi hasil tangkapan payang, masing-masing 70% dan 90% (gambar 4), bahkan pada bulan Oktober, hasil tangkapan ikan pelagis kecil mencapai 19 kali lebih besar daripada ikan demersal. Sebaliknya, pada bulan Desember 2006, kelompok ikan demersal tertangkap tiga kali lebih besar dari ikan pelagis kecil yang berjumlah 25%. Pada bulan Maret 2007, hasil tangkapan dari 3 unit payang didominasi oleh 2 jenis ikan pelagis kecil (100%) yaitu ikan selar kuning (Selaroides leptolepis) 99% dan sisanya 1% adalah ikan kembung (Tabel 5). Hasil tangkapan ikan pelagis kecil yang tinggi pada bulan Agustus dan Oktober 2006 disebabkan tertangkapnya ikan cekong/ikan krismon 188 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu (Sardinella sp.) dalam jumlah besar. Ikan cekong pernah muncul pada tahun 1997, saat salinitas air laut tinggi karena musim kemarau yang panjang. Pada bulan Desember ikan cekong sulit dicari sehingga nelayan menangkap ikan demersal (ikan yang menetap di perairan Teluk Jakarta). Tabel 2. Komposisi gabungan hasil tangkapan payang sampel (Agustus, Oktober, dan Desember 2006) dari perairan Teluk Jakarta Famili Carangidae Chirocentridae Clupeidae Engraulidae Scombridae Sphyraenidae Trychyuridae Nonikan Kelompok/Jenis Ikan I. Ikan Demersal II. Ikan Pelagis kecil : 1. Como/Alepes djedaba 2. Selar kuning/Selaroides leptolepis 3. Parang parang (Chirocentrus dorab) 4. Cekong (Sardinella sp.) 5. Tembang (Dussumieria elopsoides) 6. Tembang (Escaulosa thoracata) 7. Tembang (Hilsa sp.) 8. Tembang (Sardinella brachysoma) 9. Tembang (Sardinella sp.) 10. Tembang (Thryssa mystax) 11. Teri (Stolephorus devisi) 12. Teri (Stolephorus waitei) 13. Teri (Anadontostoma chacunda) 14. Teri (Stoleporus indicus) 15. Banyar (Rastrelliger kanagurta) 16. Alu-alu (Sphyraena sp.) 17. Alu-alu (Sphyraena barracuda) 18. Layur (Trychiurus sp.) 19. Layur (Trychiurus savala) udang dan cumi-cumi Jumlah Berat (gram) 5.860,4 28.631,7 15,5 91,6 5,3 10.248 80 290 800 6.682,4 7.245,6 312,6 228,5 98,4 1.500 76,2 15,1 90 174 370 16,3 76,5 34.276,6 % 17,11 82,67 0,05 0,27 0,02 29,90 0,23 0,85 2,33 19,50 21,14 0,91 0,67 0,29 4,38 0,22 0,04 0,26 0,51 1,08 0,05 0,22 100 189 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 3. Laju tangkap ikan pelagis kecil dari payang pada tahun 2006 Bulan Agustus Oktober Desember Laju tangkap (kg/hari/kapal) Total Ikan pelagis kecil 137 98,6 (70%) 5.000 4.500,0 (95%) 42 10,5 (25%) Jenis ikan pelagis kecil dominan tembang cekong tembang 100 % berat 80 60 40 20 0 Agustus 2006 Oktober 2006 ikan demersal ikan pelagis Desember 2006 non ikan Gambar 5. Komposisi ikan demersal, ikan pelagis, dan non ikan yang tertangkap payang bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2006 di perairan Teluk Jakarta Laju tangkap payang Hasil tangkapan payang pada bulan Agustus 2006 berkisar 85–190 kg dengan laju tangkap 137 kg/trip/hari. Jenis yang mendominasi adalah ikan campuran (Trash fish) mencapai 50%. Pada bulan Oktober 2006, hasil tangkapan mencapai 2.083–7.045 kg/trip yang didominasi oleh ikan cekong (Sardinella sp.). Berdasarkan data dan hasil wawancara pemilik kapal payang, ikan cekong atau krismon muncul kembali ke perairan Teluk Jakarta setelah 10 tahun yang lalu yaitu antara tahun 1996–1997 dengan hasil tangkapan mencapai 5 ton/payang. Hasil tangkapan payang pada bulan Desember relatif rendah, yaitu pada kisaran 28–56 kg/trip, dengan laju tangkap 42 kg/trip/hari. Berdasarkan persentase ikan pelagis kecil dan hasil tangkapan payang pada 3 bulan pengamatan, laju tangkap ikan pelagis kecil dapat dilihat pada Tabel 3. 190 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Pada bulan Maret 2007, hasil tangkapan payang berkisar 60–600 kg dengan laju tangkap 216 kg/trip/hari/kapal. Pada bulan Juli 2007, laju tangkap payang adalah 60 kg/hari/kapal didominasi oleh ikan selar kuning dengan laju tangkap 9,4 kg/hari/kapal. Berdasarkan informasi dari nelayan, hasil tangkapan yang melimpah biasanya terjadi pada bulan Januari–Februari. Tabel 4. Komposisi jenis ikan hasil tangkapan payang yang didaratkan di Pulau Kelapa pada bulan Maret 2007 No Jenis Ikan Hasil tangkapan (kg) % 1 Selar kuning (Selaroides leptolepis) 860 99 2 Kembung (Rastrelliger brachysoma) 5 1 865 100 Total 2.3 Jaring Rampus/Insang Daerah Penangkapan Daerah penangkapan jaring insang/rampus pada bulan Desember 2006 hanya di sekitar Pulau Damar, sedangkan pada tahun 2007 adalah di sekitar perairan Pulau Lancang, Pulau Damar, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka. Pengoperasian jaring rampus umumnya dilakukan pada malam hari, berangkat melaut pada pukul 17.00 sore dan kembali pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 pagi. Perahu yang digunakan nelayan jaring rampus berukuran panjang 6–7 m, lebar 2,5–3 m dan dalam 1 m dengan menggunakan mesin 16 PK. Jumlah ABK antara 3–4 orang. Kegiatan penangkapan ikan dengan gillnet kembung dilakukan secara harian, dimulai dari pukul pukul 17.00 sampai dengan 06.00 WIB. Dalam satu trip penangkapan biasanya dilakukan tawur sebanyak 2 kali. Komposisi jenis ikan hasil tangkapan jaring insang Komposisi hasil tangkapan jaring insang kembung pada bulan Desember 2006 adalah kembung, banyar tembang, alu-alu, tenggiri, kuro, kakap dan ikan campuran (Trash fish), sedangkan pada tahun 2007 didominasi oleh ikan kembung (Rastrelliger brachysoma) dan ikan banyar (Rastrelliger kanagurta). Hasil identifikasi terhadap ikan campuran dari jaring kembung sampel terdiri atas 17 jenis ikan dan 1 jenis nonikan (rajungan). 191 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Laju tangkap jaring insang Hasil tangkapan pada bulan Desember 2006 berkisar 18–64 kg, dengan laju tangkap 45 kg/trip/hari. Berdasarkan berat masing-masing jenis ikan, komposisi ikan campuran terdiri atas ikan pelagis kecil (78%), ikan demersal (18,7%), ikan karang (2,3%), dan rajungan (1%) (Tabel 5). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap ikan pelagis kecil yang tertangkap jaring insang diketahui bahwa ukuran yang tertangkap berkisar 10,0 cm dan 17,9 cm di mana ukuran rata-rata ikan kembung (Rastrelliger brachysoma) dan tembang (Sardinella gibbosa) adalah 16,4 cm dan 11 cm (Tabel 6). Tabel 5. Komposisi ikan campuran tertangkap jaring rampus pada bulan Desember 2006 No Famili No I II Clupeidae Scombridae Carangidae 1 2 3 4 5 6 7 8 III IV Carangidae 9 10 Ikan demersal Ikan pelagis Berat (gram) 1.849,7 7.713,6 18,7 78,0 Belo (Hilsa kelee) Tembang (Sardinella gibbosa) Cekong (Sardinella sp.) Tembang (Sardinella fimbriata) 4.116,2 642,9 45,9 307,1 41,6 6,5 0,5 3,1 Banyar (Rastrelliger kanagurta) Kembung (Rastrelliger brachysoma) 68,8 2.433 0,7 24,6 Selar kuning (Selaroides leptolepis) Selar hijau (Atule mate) Ikan karang 20,4 79,3 223,5 0,2 0,8 2,3 155,6 67,9 101,3 9.888,1 1,6 0,7 1,0 100,0 Jenis Ikan Kuwe (Alepes vati) Kuwe (Alectis sp.) Nonikan Jumlah % Laju tangkap ikan pelagis kecil pada bulan Desember diperkirakan sebesar 35,1 kg/hari/trip. Pada tahun 2007, hasil tangkapan berkisar 26– 192 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu 210 kg/hari/kapal, dengan laju tangkap 115 kg/kapal/trip/hari. Komposisi hasil tangkapan dari 4 unit jaring kembung di perairan Kepulauan Seribu pada bulan Mei 2007 didominasi kelompok ikan pelagis kecil yang terdiri dari 5 jenis, yaitu ikan banyar (dominan), tembang, layur, tetengkek dan alu-alu (Tabel 7). Tabel 6. Ukuran ikan yang dominan di dalam hasil tangkapan jaring rampus di perairan Teluk Jakarta pada bulan Desember 2006 Jenis ikan dan spesies Jumlah Belo, Hilsa kelee Kembung, Rastrelliger brachysoma Tembang, Sardinellagibbosa 65 28 31 Panjang cagak (FL) Kisaran Rerata 13,5–16,5 11,9–17,9 10–12,3 14,8 16,4 11,0 Tabel 7. Komposisi hasil tangkapan 4 kapal jaring kembung sampel di perairan Kepulauan Seribu bulan Mei 2007 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jenis Ikan dan non ikan Banyar (Rastrelliger kanagurta) Tembang ( Sardinella brachysoma) Layur ( Trichius lepturs) Tetengkek (Megalaspis cordyla) Alu-alu ( Sphyraena forsteri) Tongkol ( Scomberomorus sp.) Tenggiri (Scomberomorus commerson) Cumi-cumi (Loligo sp.) Kuro ( Polydactylus plebeius) Total hasil tangkapan Hasil Tangkapan (kg) 350 25 2 3 3 18 46 3 4 460 % 76,1 5,4 0,4 0,7 0,6 3,91 10,00 0,65 0,86 100,00 Dari pengamatan dengan mengikuti kegiatan nelayan jaring kembung pada bulan Juli 2007, rata-rata hasil tangkapan adalah 33 kg/kapal/ hari terdiri atas ikan pelagis kecil yang didominasi oleh ikan kembung (30 kg), banyar (2 kg), dan tetengkek (1 kg). 3. Biologi Reproduksi Ikan Kembung Ikan kembung (R. brachysoma) di pantai utara Jawa termasuk spesies neritic yang mengalami eksploitasi penuh (heavy exploitation) oleh 193 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya perikanan artisanal (pukat cincin mini) (Suwarso et al. 2010). Ukuran ikan yang tertangkap semakin besar ke arah barat (Teluk Jakarta), di mana di perairan Teluk Jakarta sex ratio lebih seimbang (F:M=1,0:1,2). Lebih jauh lagi Suwarso et al. (2010) menyatakan bahwa pemijahan ikan kembung diduga lebih terkonsentrasi di perairan sebelah barat (Teluk Jakarta) walaupun di Blanakan juga terindikasi ada pemijahan. Pemijahan diduga berlangsung setelah bulan Oktober. Berat rata-rata ikan betina matang sekitar 91 gram; batch fecundity 244 butir/gram atau 5.930 butir telur matang. Data length-frekuensi menunjukkan kecenderungan munculnya satu kelompok ukuran (modus), baik menurut waktu maupun lokasi, kecuali di Teluk Jakarta (dua kelompok ukuran). Ukuran asymptotic (L∞) berdasarkan ukuran maksimum yang tertangkap sekitar 19,9 cm. Ukuran recruit (10 cm) terlihat di Teluk Jakarta. Rata-rata ukuran ikan yang tertangkap (L50) sebesar 16,1 cm lebih rendah dari nilai ukuran pertama kali matang gonad (Lm=16,37 cm). Ukuran ikan pertama kali tertangkap (Lc) jauh lebih rendah dari kedua nilai tersebut sebesar 12,8 cm. Kesimpulan dan saran 1. Jenis-jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap di kawasan perairan Kepulauan Seribu yang mencakup perairan Teluk Jakarta umumnya sama dengan yang biasa tertangkap di perairan lainnya di wilayah Indonesia terutama dari Laut Jawa. Sebagian besar dari hasil tangkapan berukuran relatif kecil. 2. Alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap ikan pelagis kecil di wilayah perairan Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta adalah bagan, payang, dan jaring (gillnet) kembung. 3. Selama pengamatan pada tahun 2006–2008, laju tangkap jenis-jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap bervariasi. Dari jenis alat bagan, laju tangkap 38–170 kg/bagan/hari, dengan laju tangkap ikan pelagis kecil berkisar 17–40 kg/bagan/hari, sedangkan dari jaring (gillnet) kembung 33–100 kg/trip/payang/hari. 4. Ukuran jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ikan banyar dan tembang yang tertangkap di perairan Kepulauan Seribu terutama oleh alat tangkap bagan pada umumnya relatif kecil karena terdiri dari ikan muda. 194 Keragaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Perlu pengaturan agar jumlah (%) trash fish menjadi sekecil mungkin, untuk mendapat kesempatan tumbuh sampai ukuran dewasa sebelum tertangkap. 2. Daerah penangkapan bagan sebaiknya tidak dibangun di lokasi-lokasi yang merupakan daerah asuhan jenis-jenis ikan (yang diduga berada di perairan Teluk Jakarta,) tetapi di perairan Kepulauan Seribu, yang tertangkap hanya jenis-jenis ikan teri seperti di sekitar Pulau Lancang. Daftar Pustaka Hariati T. 2005. Perkembangan Pemanfaatan Ikan Pelagis Kecil Menggunakan Pukat Cincin di Perairan Barat Sumatera pada Tahun 2003. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol. 11 No. 2: 57–67. Indarsyah IJ dan ST Hartati. 2008. Kajian Aspek Biologi Selar Kuning (Selaroides leptolepis) Hasil Tangkapan Jaring Payang yang Didaratkan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ikan V. Masyarakat Iktiologi Indonesia bekerjasama dengan PRPT, BRKP-DPK, FPIK IPB, PPB- LIPI & PPO-LIPI: hal. 47–54. Prihatiningsih dan ST Hartati. 2008. Perkembangan Perikanan dan Aspek Biologi Beberapa Jenis Ikan Hasil Tangkapan Bagan Tancap di Perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ikan V. Masyarakat iktiologi Indonesia bekerjasama dengan PRPT, BRKP-DPK, FPIK IPB, PPB- LIPI & PPO-LIPI: hal. 175–186. Widodo J, et al. 1994. Pedoman Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil dan Perikanannya. Departemen Pertanian. Badan Litbang Pertanian Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan: 109 hal. Suwarso, Hariati T dan Ernawati T. 2011. Biologi Reproduksi dan Dugaan Pemijahan Ikan Kembung (Rastrelliger brachysoma, FAM. SCOMBRIDAE) Di Pantai Utara Jawa. In press. 195 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya Hufiadi*), Tri Wahyu Budiarti*), Baihaqi*), dan Mahiswara*) *) Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta Abstrak Kajian perkembangan perikanan tangkap dilakukan berdasarkan periodesasi. Trawl, jaring arad, bondet, jaring insang dasar yang merupakan tipe alat tangkap yang beraktivitas di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu mengalami perkembangan, perubahan, dan pergeseran orientasi. Pelarangan pengoperasian trawl tahun 1980 menyebabkan perkembangan modifikasi alat tangkap jaring dogol, cantrang dan pukat pantai berupa rancang bangun, konstruksi dan cara operasinya. Pada periode setelah 1991, perkembangan teknologi pada pukat cincin ditandai dengan penggunaan lampu sorot (fluorosence lamp) dan GPS, kemudian tahun 2000-an memanfaatkan teknologi fish finder. Hal yang sama terjadi pada perikanan bagan, pada akhir periode tahun 1990-an menggunakan generator set sebagai sumber cahaya dan memasang fluorosence lamp, sebagai upaya mengefektifkan upaya menarik ikan ke area penangkapan. Berdasarkan kajian kapasitas penangkapan dikaitkan dengan pengukuran efisiensi perikanan menunjukkan bahwa kapasitas penangkapan di perairan Jakarta dan sekitarnya (payang, pancing, bubu dan muroami) menunjukkan telah terjadi kelebihan kapasitas. Kondisi ini diindikasikan oleh tidak optimalnya pemanfaatan kapasitas selama periode antara tahun 2001–2010. Kata kunci: perkembangan, pemanfaatan, kapasitas penangkapan, Teluk Jakarta, Pulau Seribu Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Aktivitas perikanan tangkap di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu terus berkembang, mengikuti kondisi sumber daya perikanan yang ada. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun, terdapat beberapa jenis alat tangkap yang tetap dioperasikan sepanjang periode waktu antara 1970 sampai dengan sekarang, antara lain bagan, bubu,sero, jaring insang. Jenis alat tangkap muroami dengan target penangkapan ikan ekor koning (Caesio spp.) yang pada tahun 70-an cukup dominan, sempat mengalami penurunan, sebelum muncul kembali pada periode tahun 2000-an. Produksi ekor kuning pada tahun 1969 -1977 mencapai kisaran 800 – 1400 ton/tahun, namun pada tahun 2001 - 2007, hasil tangkapan hanya pada kisaran 1 - 34 ton per tahun (Anonim, 2007). Semenjak keluarnya Kepres No. 39 Tahun 1980, alat tangkap trawl, tidak lagi beroperasi di perairan Teluk Jakarta dan sekitarnya. Dalam perjalanannya, pengoperasian alat tangkap yang masih ada saat ini telah mengalami penyesuaian dari segi teknologi baik menyangkut alat tangkap, alat bantu penangkapan, wahana maupun cara pengoperasian. Pergeseran dominansi aktivitas jenis alat tangkap yang dioperasikan di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu menyebabkan terjadinya pergeseran dominansi produksi jenis ikan yang didaratkan. Pada periode 70-an, ikan hias merupakan salah satu komoditas yang dihasilkan dari perairan Kepulauan Seribu. Namun, seiring dengan praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab, saat ini dari wilayah perairan Kepulauan Seribu tidak lagi dihasilkan jenis ikan hias bernilai ekonomis tinggi. Di samping jenis ikan, perubahan juga terjadi pada ukuran ikan yang tertangkap, yang cenderung semakin kecil seperti pada jenis ikan ekor kuning (Caesio spp.) yang kembali muncul pada periode tahun 2000-an. Pada tahun 2002 produksi penangkapan mengalami penurunan sebesar 17,29%, demikian juga nilainya menurun sebesar 39,10% (Fauzy dan Anna 2005). Patut diduga bahwa penurunan ini disebabkan karena tangkap lebih (over fishing) sebagai akibat meningkatnya input/effort, tercemarnya perairan serta kerusakan terumbu karang. Penangkapan yang berlebih ini diindikasikan dari angka CPUE (catch per unit effort) yang mengalami penurunan pada tahun 2000–2010. 198 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya Salah satu masalah yang dihadapi perikanan tangkap adalah adanya tangkap lebih dan kapasitas lebih. Pada intinya, pengertian kapasitas penangkapan mengacu pada komponen input dan output yang digunakan dalam perikanan. Substitusi terhadap input berupa teknologi yang lebih canggih menyebabkan upaya efektif terus meningkat. Kombinasi peningkatan jumlah kapal, perbaikan dalam teknologi penangkapan, dan ekspansi upaya penangkapan menyebabkan terjadinya fenomena kapasitas lebih, baik dalam jangka pendek (excess capacity) maupun jangka panjang (over capacity). Konsep kapasitas dalam perikanan tangkap dapat didefinisikan dan diukur, baik dengan pendekatan ekonomi, teknologi maupun dinyatakan secara eksplisit dalam optimisasi berdasarkan teori mikroekonomi (Morrison 1985, 1993). Tulisan ini menyajikan kajian perkembangan penangkapan ikan dan kondisi pemanfaatan kapasitas yang terjadi di perairan Jakarta dan sekitarnya berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun. Bahan dan Metode Data dan informasi kegiatan perikanan tangkap di perairan Jakarta dan sekitarnya berupa data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber serta data hasil penelitian. Data untuk keperluan kajian kapasitas perikanan tangkap berupa data statistik perikanan yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintan Provinsi DKI Jakarta. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan perikanan tangkap. Untuk mengetahui kapasitas penangkapannya, data dianalisis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan BCC (Cooper et al. 2004) dan PeakTo-Peak (PTP). Menurut Ballard dan Roberts (1997) dalam Zheng and Zhou (2005), metode PTP adalah pengukuran sederhana terhadap respons lembaga atau pengamat oleh industri untuk mengubah permintaan. Pengukuran itu didasarkan pada tren melalui pendekatan puncak yang dianggap mencerminkan output maksimum yang dicapai pada stok modal dan ikan. Model analisis yang digunakan dalam analisis efisiensi bersifat variable return to scale (VRS). 199 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Hasil Dan Bahasan 1. Perkembangan Teknologi Penangkapan Pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu telah berlangsung sejak lama. Kepulauan Seribu dengan bagian terbesar merupakan habitat perairan karang, hingga saat ini masih dikenal sebagai salah satu daerah penangkapan ikan-ikan karang, baik untuk kelompok ikan konsumsi maupun ikan hias. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan karang sampai saat ini antara lain adalah muroami dan bubu. Untuk sumber daya ikan pelagis kecil antara lain menggunakan alat tangkap bagan dan jaring insang. Alat tangkap pancing tonda dan jaring insang hanyut merupakan jenis alat tangkap yang dioperasikan untuk menangkap ikan pelagis besar. Kelompok ikan demersal dan sumber daya udang penaeid juga merupakan komoditas yang dihasilkan dari perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Jenis alat tangkap seperti trawl, jaring arad, bondet, jaring insang dasar merupakan beberapa contoh tipe alat tangkap tidak mengusahakan sumber daya ini. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu mengalami perkembangan, perubahan, dan pergeseran orientasi. Perubahan dalam pemanfaatan sumber daya ikan, merupakan bentuk penyesuaian pemanfaatan terhadap berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap kondisi sumber daya ikan dan lingkungan. Menurunnya kuantitas dan kualitas ikan hias dari Kepulauan Seribu misalnya, merupakan akibat dari cara penangkapan yang tidak mengindahkan kelestarian. Kondisi ini menyebabkan nelayan menyesuaikan target penangkapannya dengan komoditas yang tersedia dan melakukan pergantian alat tangkap, bahkan tekniknya. Pergeseran aktivitas perikanan tangkap yang terjadi di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu terjadi sebagai dampak adanya perubahan peran dan fungsi wilayah dalam rangka pengembangan ekonomi. Wilayah perairan Kepulauan Seribu yang berada di ibukota terus didorong untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Dampak positif kegiatan ini 200 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya adalah terjadinya pergeseran sebagian peran perikanan tangkap menjadi bukan saja sekadar commersial fishing namun juga leisure fishing. Pemanfaatan teknologi penangkapan dengan trawl (pukat tarik udang tunggal) di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu mengalami perkembangan dalam dua periode, sebelum 1970 dan antara tahun 1971–1980. Sejak tahun 1981, alat tangkap trawl mengalami penurunan yang drastis setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap trawl di seluruh perairan Indonesia. Pelarangan pengoperasian trawl menyebabkan nelayan melakukan pengembangan alat tangkap jaring dogol, cantrang dan pukat pantai dengan melakukan modifikasi baik rancang bangun, konstruksi maupun cara operasinya. Pada perikanan pelagis, awal tahun 1990-an penangkapan ikan dengan pukat cincin mulai memanfaatkan perkembangan teknologi berupa penggunaan lampu mercuri dan GPS. Pada tahun 2000-an, penangkapan perikanan pelagis memanfaatkan teknologi fish finder untuk melacak keberadaan ikan. Hal sama terjadi pada perikanan bagan, di mana pada akhir periode tahun 1990-an, mulai menggunakan generator set sebagai sumber cahaya dan memasang fluorosence lamp untik menarik ikan ke area penangkapan. Dalam satu dekade terakhir, jenis alat tangkap seperti pancing, bubu, jaring insang, garpu, jala, tombak dan muroami masih dioperasikan nelayan. Pengoperasian jenis alat tangkap ini sangat mungkin dikembangkan, sekaligus untuk menunjang program pariwisata yang tengah dilakukan di Kepulauan Seribu. Dengan memberikan sedikit sentuhan untuk mendukung aspek keselamatan, unit-unit penangkapan tersebut sangat potensial meningkatkan kesejahteran nelayan. Orientasi pengoperasian alat tangkap yang selama ini hanya tertuju untuk memproduksi ikan diharapkan dapat ditambah menjadi sebagai sarana perikanan rekreasi (leisure fishing). 2. Kapasitas Penangkapan Untuk mengetahui perkembangan perikanan tangkap di wilayah Jakarta, telah dilakukan analisis kapasitas penangkapan terhadap 4 jenis unit penangkapan yaitu payang, pancing, bubu, dan muroami. Data runtun waktu yang digunakan adalah data perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 201 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2001–2010. Analisis digunakan untuk mengetahui pola efisiensi dari keempat unit penangkapan. 2.1 Perikanan Payang Hasil dari analisis kapasitas penangkapan menunjukkan bahwa payang menghasilkan skor efisiensi paling tinggi yaitu rata-rata 0,8. Sementara itu, untuk tiga alat tangkap yang lain yaitu pancing rata-rata 0,6; bubu 0,7; dan muroami rata-rata 0,6. Gambar 1 memperlihatkan trajektori paling efisien perikanan payang yang terjadi pada tahun 2001, 2002, 2006 dan 2008. Sementara itu, trajektori paling tidak efisien terjadi pada tahun 2009 dan 2010. Perikanan payang pada tahun 2001, 2002, 2006 dan tahun 2008 dapat dijadikan tahun acuan, sedangkan tahun lainnya dibandingkan secara relatif terhadap tahun tersebut. Gambar 1. Trajektori efisiensi payang di perairan Teluk Jakarta Peningkatan efisiensi yang tajam terjadi setelah tahun 2004 yang dibarengi dengan ekspansi input (trip penangkapan) mencapai 170%. Dengan peningkatan jumlah trip operasi secara agregat, terjadi juga peningkatan output. Pada kondisi ekspansi seperti digambarkan mulai tahun 2004 dan mencapai puncak pada 2006, akan terjadi kontraksi dari sumber daya perikanan yang mengakibatkan stok sumber daya menurun. Hal ini diperlihatkan dengan menurunnya tingkat efisiensi setelah tahun 2006. Ketika ekspansi kembali terjadi, efisiensi kembali meningkat, namun pola yang sama terjadi kembali menurun setelah tahun 2008. Pola seperti ini (double bump) akan terjadi berulang-ulang secara alami 202 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya pada perikanan yang dikelola secara quasi open access (Fauzi A dan Anna 2005). Perbedaan produksi aktual dengan produksi potensial perikanan payang selama periode 2001–2010 dapat dilihat pada Gambar 2. Dari gambar tersebut tampak bahwa jika kapasitas perikanan dikendalikan, produksi perikanan sebenarnya mampu ditingkatkan mengikuti grafik produksi potensial, misalnya pada tahun 2009 dan 2010, kapasitas perikanan payang masing-masing adalah 265% dan 477% lebih besar dari produksi aktual. Dengan mengurangi kapasitas sebesar 73% dan 83% pada tahun 2009 dan 2010 akan memungkinkan output diproduksi secara optimal. 3000 Actualcatch(ton) Produksi(ton) 2500 Potentialcatch(ton) 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 2009 2010 Gambar 2. Produksi aktual dan produksi potensial perikanan payang DKI Jakarta periode tahun 2001–2002 Pada tahun 2010, khusus untuk payang hanya mampu mendukung sekitar 17% dari sumber dayanya untuk mencapai kapasitas optimum. Artinya, tingkat input yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya (optimal). 2.2 Perikanan pancing Gambar 3 memperlihatkan bahwa trajektori paling efisien perikanan pancing terjadi pada tahun 2002, 2003, 2008 dan 2010. Sedangkan trajektori paling tidak efisien terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Pada tahun 2007 dan 2009, masing-masing hanya mampu men-support sekitar 19% dan 18% dari input yang ada untuk mencapai kapasitas optimum. Penurunan efisiensi yang tajam terjadi setelah tahun 2003 dan 2008. 203 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Hal ini lebih disebabkan oleh produksi aktual yang menurun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah upaya (effort) yang ada tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. 1.20 Efisiensi 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun Produksi(ton) Gambar 3. Trajektori efisiensi pancing di perairan Teluk Jakarta 3000 Potentialcatch(ton) 2500 Actualcatch(ton) 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 2009 2010 Gambar 4. Produksi aktual dan produksi potensial perikanan pancing DKI Jakarta periode tahun 2001–2002 Kombinasi peningkatan jumlah kapal, perbaikan teknologi penangkapan, dan ekspansi upaya penangkapan menyebabkan terjadinya fenomena kapasitas lebih, baik dalam jangka pendek (excess capacity) maupun jangka panjang (over capacity). Le Floc’h et al. (1998) dalam Muldoon (2009) menyebutkan bahwa teknologi adalah penyebab utama perubahan excess fishing capacity yang berdampak pada perikanan skala tradisional maupun industri. Kapasitas lebih (excess capacity) perikanan pancing divisualisasikan pada Gambar 4, yaitu sebagai selisih kapasitas produksi potensial dengan 204 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya produksi aktual. Indikasi telah terjadi excess capacity pada perikanan pancing terutama ditunjukkan pada tahun 2005, 2007, dan 2009. Pada tahun 2005, 2007, dan 2009 kapasitas perikanan pancing masing-masing adalah 265%, 415% dan 471%, lebih besar dari produksi aktual. Untuk meningkatkan produksi perikanan pancing mengikuti grafik produksi potensial pada tahun 2005, 2007 dan 2009 adalah dengan mengurangi kapasitas masing-masing sebesar 73%, 81% dan 83%. 2.3 Perikanan Bubu Berdasarkan perhitungan DEA, nilai kapasitas penangkapan perikanan bubu yang beroperasi di perairan DKI Jakarta dan sekitarnya selama periode 2001–2010 diperoleh rata-rata sebesar 0,69. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut perikanan bubu beroperasi 69% dari kapasitas optimal. Artinya, perikanan tersebut semestinya mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi seperti ditunjukkan oleh produksi potensial dari yang ada saat ini. Secara teknis, perikanan mengalami excess capacity sebesar 31%. Gambar 5 memperlihatkan trajektori paling efisien pada perikanan bubu terjadi pada tahun 2002 dan 2009. Sementara itu, trajektori paling tidak efisien terjadi pada tahun 2010 yang hanya mampu men-support sekitar 24% dari input yang ada untuk mencapai kapasitas optimum. 1.20 Efisiensi 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 2009 2010 Gambar 5. Trajektori efisiensi bubu di perairan Teluk Jakarta Perbedaan produksi aktual dengan produksi potensial perikanan bubu selama periode 2001–2010 dapat dilihat pada Gambar 6. Pada tahun 2010, produksi aktual diperoleh sebesar sebesar 0,297 ton. Pada tahun 2010, nilai pemanfaatan kapasitas yang diperoleh paling kecil 205 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya (0,24) jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnyanya. Seharusnya kapasitas perikanan bubu pada tahun 2010 adalah 318% lebih besar dari produksi aktual. Dengan demikian, dengan mengurangi kapasitas sebesar 76% tahun 2010 akan memungkinkan output diproduksi soptimal secara ekonomi. Produksi(ton) Potentialcatch(ton) Actualcatch(ton) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 2009 2010 Gambar 6. Produksi aktual dan produsi potensial perikanan bubu DKI Jakarta periode tahun 2001–2010 2.4 Perikanan Muroami Berdasarkan hasil perhitungan, kapasitas penangkapan pada perikanan muroami yang beroperasi di perairan DKI Jakarta dan sekitarnya, diperoleh 3 periode waktu yang mempunyai nilai efisiensi penuh (100%) yaitu tahun 2001, 2002 dan 2007 (Gambar 7). Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut tingkat kapasitas pemanfaatan optimal dengan asumsi tahun-tahun tersebut perikanan karang/demersal mencapai kondisi output maksimum jangka pendek dalam kondisi teknologi penangkapan dan stok yang ada. Sementara pada beberapa tahun lainnya, tingkat kapasitas pemanfaatannya menunjukkan tingkat yang paling rendah (tidak optimal). Nilai terendah tingkat pemanfaatan kapasitas pada periode waktu tersebut adalah 0,43 terjadi pada tahun 2008 dan 0,13 pada tahun 2010. Artinya, input potensial yang dimanfaatkan sekitar 43% dan 13% dari input aktual selama kapal beroperasi. Dengan kata lain, pada tahun 2008 dan 2010 masing-masing hanya mampu men-support sekitar 43% dan 13% dari input yang ada untuk mencapai kapasitas optimum. 206 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya 1.20 Efisiensi 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun Gambar 7. Trajektori efisiensi muroami di perairan Teluk Jakarta Hasil tangkapan (actual catch) yang diperoleh pada kurun waktu 2001– 2010 mempunyai tren yang hampir sama jika dibandingkan dengan nilai kemampuan tangkap (potential catch) (Gambar 8). Pada tahun 2009 dan 2010, kapasitas penangkapan payang yang sesuai adalah 265% dan 477% lebih besar dari produksi aktual. Dengan mengurangi kapasitas sebesar 73% dan 83% pada tahun 2009 dan 2010, akan memungkinkan output diproduksi secara optimal. Hal ini mengindikasikan pemanfaatan sumber daya ikan perairan DKI Jakarta dan sekitarnya sudah mengalami kapasitas berlebih (excces capacity). Excess capacity merupakan perbandingan relatif antara tingkat tangkapan potensial (maksimal) terhadap hasil tangkapan aktual berdasarkan pengamatan dalam jangka pendek. Secara umum, perbedaan produksi aktual dengan produksi potensial menunjukkan jika kapasitas perikanan dikendalikan, produksi perikanan sebenarnya mampu ditingkatkan mengikuti grafik produksi potensial. Dalam rangka mengatasi kapasitas berlebih, penerapan kebijakan pembatasan intensitas berupa kebijakan pengurangan kapasitas harus dilakukan oleh penentu kebijakan agar dihasilkan perikanan yang efisien. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan efisiensi harus dikendalikan. Di samping pengendalian upaya penangkapan (effort), faktor-faktor seperti pengendalian kondisi pencemaran di perairan Jakarta dan sekitarnya mungkin akan membantu meningkatkan efisiensi perikanan ke pengelolaan yang lestari. 207 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Produksi(ton) Potentialcatch(ton) Actualcatch(ton) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 2009 2010 Gambar 8. Produksi aktual dan produksi potensial perikanan muroami DKI Jakarta periode tahun 2001–2010. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Perikanan tangkap yang beroperasi di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu cenderung terus mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi penangkapan yang berkembang. Sentuhan teknologi ini juga merambah pada unit-unit penangkapan yang mengoperasikan alat tangkap konvensional seperti bagan, pancing, bubu, arad dan lain-lain, seperti pada penggunaan fluorosence lamp, GPS, fish finder. 2. Secara umum kapasitas penangkapan payang, pancing, bubu dan muroami menunjukkan adanya kelebihan kapasitas yang diindikasikan oleh tidak optimalnya pemanfaatan kapasitas (CU) selama periode antara 2001–2010. Hal ini mengakibatkan penangkapan sumber daya ikan di Teluk Jakarta menjadi tidak efisien. Untuk mengefisienkan penangkapan sumber daya ikan di Teluk Jakarta, harus dilakukan pengurangan input yang berlebih di samping pengendalian faktorfaktor pencemaran perairan. 208 Perkembangan Kapasitas Penangkapan di Perairan Jakarta dan Sekitarnya Saran 1. Pengendalian upaya penangkapan dan faktor-faktor pencemaran lingkungan perairan harus terus dilakukan di perairan Teluk Jakarta untuk meningkatkan efisiensi perikanan tangkap yang berkelanjutan. 2. Pada saat ini, dengan meningkatkan aspek keselamatan armada penangkapan, perikanan tangkap dapat lebih menyokong program wisata Kepulauan Seribu melalui perikanan tangkap rekreasi (leisure fishing), seperti yang sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Daftar Pustaka Anonim. 2007. Identifikasi Kondisi Sumber Daya dan Lingkungan pada Lokasi Pemanfaatan Lahan Perikanan di Perairan Teluk Jakarta. Laporan Akhir. 2007. Cooper WC, LM Seiford , Tone, Kaoru. 2004. Data Envelopment Analysis. Massachusets: Kluwer Academic Publisher. Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. 2011. Buku Tahunan Statistik Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. Jakarta . Fauzi A dan S Anna. 2005. Data Envelopment Analysis (DEA) Kapasitas Perikanan di Periaran Pesisir DKI Jakarta. Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan: untuk Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Moorrison CJ. 1985. Primal and Dual capacity utilization: An Aplication to Productivity Measurenment in the U.S. Automobile Industry. Journal of Business and Economic Statistics Vol.3. pp.312–324. Moorrison CJ. 1993. A Microeconomic Aprooachto the Measurenment of Economic Performance: Productyvity Growth, Capacity Utilization, and Performance Indicators. Berlin: Springer-Verlag. Muldoon GJ. 2009. Innovation and Capacity in Fisheries: Value-Adding and The Emergence of The Live Reef Fish Trade as Part of The Great Barrier Reef Reef-Line Fishery. Phd thesis, James Cook University, http:// eprints.jcu.edu.au. 209 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Subani W. 1978. Alat dan Cara Penangkapan Ikan di Indonesia, jilid I. : LPPL. Zheng Yi and Qi Zhou Ying. 2005. Measures of the Fishing Capacity of Chinese Marine Fleets and Discussion of the Methods, www.terrapub. co.jp diakses tanggal 10 Mei 2011 210 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Oleh: Suherman Banon Atmaja1) Abstrak Sejumlah artikel ilmiah dan populer menunjukkan krisis habitat dan kegagalan pengelolaan perikanan yang telah menyebabkan krisis ini. Dengan tingkat pencemaran Teluk Jakarta sudah sangat berat, sulit merestorasi terumbu karang. Nasib nelayan di pesisir teluk tidak pernah akan berubah, justru sebaliknya kehidupan mereka kian sulit akibat dampak langsung dari krisis habitat. Upaya pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Jakarta .melalui intervensi lingkungan yang meliputi: membangun terumbu karang buatan, rehabilitasi mangrove, dan marikultur. Proses menuju pengelolaan perikanan berkelanjutan masih berhadapan dengan permasalahan dasar yaitu human dimension. Selain itu, bentuk kebijakan perikanan yang akan ditetapkan juga beragam sesuai dengan hierarki perikanannya. Pendahuluan Secara umum diakui bahwa sumber utama krisis perikanan global adalah buruknya pengelolaan perikanan yang dapat dilihat dari fenomena, yakni over capcity dan kerusakan habitat. Dari kedua fenomena itu kemudian muncul berbagai penyebab lain, misalnya subsidi yang massif, kemiskinan, 1 Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya over fishing dan berbagai turunan lainnya (Fauzi 2005). Permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumber daya hayati laut sebagai masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan antara lain: (1) pemanfaatan berlebih (over exploitation) terhadap sumber daya hayati, (2) penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, (3) perubahan dan degradasi fisik habitat, (4) pencemaran, (5) introduksi spesies asing, (6) konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan (7) perubahan iklim global serta bencana alam (Dermawan et al. 2008). Teluk Jakarta terdiri dari dua ekosistem pantai (coastal ecosystems), yaitu Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu atau Pulau Seribu Complex (Williams et al. 2000 dalam Arifin 2004). Keseluruhan ekosistem, yang disebut Greater Jakarta Bay Ecosystem terbentang dari garis bujur timur 106o 20’– 107o 03’, dari garis lintang selatan 5o 10’–6o 10’, terletak di bagian barat Tanjung Pasir dan bagian timur Tanjung Karawang. Kawasan Kepulauan Seribu memiliki karakteristik rantaian dari 110 gugusan pulau-pulau kecil dengan rataan pantai yang dangkal dan terlindung (protected shallow sea) memiliki ciri khas karang penghalang (barrier reef) dengan rataan pantai memiliki reef flet dan goba (lagoon), secara ekologis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kawasan Metropolitan Jakarta (Gambar 1). Situasi perikanan tangkap di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu saat ini yang meliputi: ekologis, ekonomi, sosial, kelembagaan dan permasalahan terkait dengan kebijakan memperlihatkan kompleksitas krisis pengelolaan. Perubahan signifikan yang telah terjadi adalah perubahan wilayah pantai yang mencakup daerah tutupan hutan mangrove. Dalam kurun 42 tahun, tutupan mangrove di kawasan teluk ini telah berkurang dari semula 1.334 ha menjadi 232 ha, atau telah kehilangan sekitar 80%. Perairan teluk ini kini telah menjadi hiper-eutrofik atau subur berlebihan sampai sejauh 3–5 km dari pantai (Ongkosongo et al. 2008). Suharsono (Media Indonesia; 27-4-2009) mengatakan bahwa pencemaran berat yang melanda Teluk Jakarta membuat terumbu karang di perairan ini hanya tersisa 2. Penyusutan habitat alami (50%) mengakibatkan penyusutan keanekaragaman spesies (10%). Selain itu, juga mengakibatkan penyusutan keanekaragaman spesies mencapai 50% (Keanekaragaman Hayati KelautanKeanekaragaman Hayati Laut. web.ipb.ac.id/ ~mujizat/). Sementara itu, 212 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu sebagian besar pulaumya berada di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKPS), sebagai Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai fungsi: (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Gambar 1. Ekosistem Teluk Jakarta terdiri dari dua ekosistem pantai (coastal ecosystems), yaitu Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu atau Pulau Seribu Complex (sumber: Williams et al. 2000 dalam Arifin 2004) Berdasarkan aspek hukum dan kelembagaan, adanya disharmonisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan terbatasnya kapasitas pengelolaan, serta kurang koordinasi antarinstansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya ikan menyebabkan penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. Dari faktor sosial ekonomi diperoleh informasi bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan nelayan sangat rendah, sumber daya manusia rendah, serta belum ada budaya konservasi. 213 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi kondisi Teluk Jakarta dalam dua dekade terakhir, untuk menilai perubahanperubahan ekologi yang terjadi di perairan ini. Selain itu, juga meninjau ulang sistem pengelolaan perikanan di DKI Jakarta, sejauhmana pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Bahan dan Metode Bahan tulisan ini merupakan hasil penelusuran studi pustaka. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara memetakan fenomena perikanan yang sedang berlangsung didukung oleh diskusi terbatas dengan berbagai pemangku usaha perikanan pada saat melakukan observasi lapang, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil Dan Pembahasan 1. Penurunan Kualitas Ekosistem Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu serta Kondisi Perikanan Tangkap Kondisi ekologis air laut dan kondisi ekosistem pantai memengaruhi langsung kehidupan masyarakat. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan berlokasi di Teluk Jakarta dan dekat daratan Metropolitan Jakarta, harus berhubungan dengan permasalahan kota besar. Permasalahan utama yang datang dari Jakarta dan bagian pinggir kota adalah ledakan populasi dan residu limbah rumah tangga serta industri. Menurut UNESCO (2000), rata-rata 1.400 m3 sampah dibuang ke sungai sehari-hari. Diperkirakan dalam sehari lebih dari 7.000 m3 limbah cair termasuk di antaranya yang mengandung logam berat dibuang melalui empat sungai yang melintasi wilayah Tanggerang dan bermuara di Teluk Jakarta, yaitu: Sungai Cisadane, Cimanceri, Cirarab dan Kali Sambi (Lestari dan Edward 2004). Firman dan Dharmapatni (1994) melaporkan polusi air telah berdampak terhadap kesehatan manusia dan kehidupan akuatik. Polusi organik juga telah berkontribusi terhadap kemunduran terumbu karang di Teluk Jakarta. Kandungan air raksa di dalam spesies ikan komersil di esturin Angke melebihi ambang batas petunjuk WHO dunia untuk konsumsi manusia. Arifin (2004) menyatakan bahwa selama 20 tahun, rata-rata konsentrasi Pb dan Cu dalam sedimen Teluk Jakarta meningkat masing-masing 5 dan 214 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu 9 kali. Distribusi spasial Pb dan Cu tertinggi di bagian barat dan tengah Teluk Jakarta, di mana aktivitas manusia terkonsentarsi di kawasan ini. Permasalahan pencemaran tersebut juga berpengaruh langsung, terutama di sekitar kampung Pulau Untung Jawa dan Pari. Hanya di kampung Pulau Tidung yang berlokasi lebih ke utara, kondisi air laut masih relatif baik dibandingan kedua pulau sebelumnya. Survei terumbu karang pada periode 1969–1995 sudah menunjukkan suatu kemunduran kesehatan terumbu karang yang dramatis, dan beberapa pulau sudah menghilang dalam dekade terakhir. Berdasarkan data jarak pulau dari daratan Pulau Jawa dan persentase tutupan karang hidup memperlihatkan semakin jauh dari daratan Pulau Jawa, kondisi terumbu karang semakin baik (Tabel 1 dan Gambar 2). Jarak kurang dari 15 km dari pantai, terumbu karangnya hanya tersisa kurang dari 5%, sedangkan untuk jarak 15–20 km dari pantai tinggal 5%–10%, dan pada jarak 20 km tinggal 20%–30%. Tabel. 1. Persentase penutupan terumbu karang untuk 2 pulau di Kepulauan Seribu Lokasi 1969–1970 1985 1995 Pulau Pari 80% 22% 15% Pulau Air 70% 25% 30% Sumber: (UNESCO 2000) Secara umum terumbu karang di Kepulauan Seribu dalam kondisi baik pada 1920an, walaupun beberapa pengaruh manusia telah nyata pada turumbu karang dekat pantai (Umbgrove 1928, 1929, 1939 dan Verwey 1931 dalam Cesar 1996). Dengan perluasan ibukota yang begitu cepat, meningkatkan penggunaan sumber daya terumbu karang dan pulau-pulau di Laut Jawa (Harger 1986 dalam Cesar 1996; Tomascik et al. 1994 dalam Cesar 1996). Suatu kemunduran kesehatan terumbu karang yang dramatis di Kepulauan Seribu direkam antara tahun 1985 dan 1995 (Vantier et al. 1998 dalam Cesar 1996). Kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu pada umumnya dapat dikategorikan dalam kondisi rusak hingga sedang. Persentase penutupan karang hidup hanya berkisar 0%–24,9 % dan 25%–49,9%. Hal ini menunjukkan dominasi tutupan unsur-unsur abiotik seperti pasir, pecahan 215 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya karang, serta karang mati telah melampaui 50%. Kerusakan terumbu karang sebagian besar diakibatkan oleh penambangan karang batu untuk bahan bangunan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia. Pada tahun 2000, terumbu karang di Kepulauan Seribu mengalami pemulihan dengan tutupan karang hidup sekitar 20%–30% (Burke et al. 2002). Pengamatan yang dilakukan pada bulan September 2005 menunjukkan persentase tutupan karang hidup tiap zona berkisar 24,6%–34,4% (Terangi 2007). Suharsono (Media Indonesia, 27-4-2009) mengatakan bahwa tingkat pencemaran Teluk Jakarta sudah sangat berat, sehingga terumbu karang yang tersisa tidak bisa lagi ditingkatkan dan penanaman terumbu karang baru juga tidak bisa dilakukan. Satu-satunya jalan untuk menumbuhkan kembali terumbu karang adalah dengan memperbaiki kualitas perairan di Teluk Jakarta, dan ini pun sangat sulit dilakukan. Gambar 2. Hubungan antara tutupan karang hidup dan jarak dari daratan (pengamatan 28 pulau di Kepulauan Seribu) (Sumber: Hutomo 1987 dalam Cesar 1996) Kawasan mangrove di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1939 tercatat 1.210 ha (Backer 1952 dalam Waryono 2006), saat sekarang tercatat tinggal 310,50 ha (Distanhut 2000 dalam Waryono 2006). Dari potensi luasan tersebut, 168 ha di antaranya berada di pantai Jakarta, meliputi: 216 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu (a) kawasan hutan lindung (44,0 ha), suaka alam (25,0 ha), dan hutan wisata mangrove (99,0 ha). Hutan mangrove di pantai utara Jakarta dalam kondisi kritis hanya tersisa 10% (3 km dari 32 km garis pantai Jakarta) yang masih ditumbuhi mangrove (Kompas, 31-7-2009). Tekanan berat terhadap kawasan mangrove di DKI Jakarta, antara lain meliputi: (a) pengembangan permukiman, seperti kawasan Pantai Indah kapuk, (b) pembangunan fasilitas rekreasi, dan (c) pemanfaatan lahan pasang surut untuk kepentingan budi daya pertambakan. Secara ekologis, degradasi fisik habitat hayati (yaitu: degradasi mangrove, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran, yaitu: sedimentasi, eutrofikasi, kekurangan oksigen) berimplikasi langsung terhadap penurunan produktivitas primer perairan dan spesies ikan memiliki tingkah laku antarkoneksi habitat (inter habitat connectivity), seperti krustasea, moluska dan ikan yang memiliki keteraturan migrasinya terganggu. Gambar 3. Diagram illustrasi pergerakan ikan antara habitat mangrove, padang lamun, dan terumbu karang pada perbedaan tingkat daur hidup (adaptasi dari Mumby et al. 2003 dalam Unsworth 2007) Khusus bagi ikan pelagis kecil yang bersifat neritik dan oseanik, hilangnya perlindungan secara alami (daerah pemijahan dan asuhan) yang berkaitan dengan estuarine dan perairan karang, akan menyebabkan perubahan tingkah laku dan siklus hidup, mereka hanya didukung oleh kondisi kawasan estuarine di sekitar Kepulauan Seribu dan adanya kolomkolom massa air yang berkualitas baik. Pada akhirnya berdampak terhadap proses pemulihan (renewable) biota laut termasuk ikan, secara langsung akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas stok ikan. Namun demikian, penentuan krisis spesies dan varietas merupakan bagian tersulit karena pelaporan kejadian banyak tidak didokumentasikan. Dari beberapa 217 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya indikator yang mendukung terjadinya krisis habitat, ditandai oleh sektor produksi perikanan tangkap yang menurun selama kurun waktu tahun 1999–2002. Produksi ikan secara terus menerus mengalami penurunan, semula 35.008,0 ton pada 1999 menjadi 28.525,6 ton pada tahun 2000 dan terakhir menjadi 17.828,7 ton pada tahun 2002 (DP2K-DKI 2003 dalam Arifin 2004). Bahkan sejak tahun 2002 lalu, produksi ikan nelayan di kawasan ini menurun hingga 38%. Indikator lainnya adalah persepsi pemimpin sosial lokal. Kebanyakan dari masyarakat Kepulauan Seribu menyatakan bahwa kondisi sumber alam, yaitu terumbu karang dan hutan mangrove menurun dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, dan kondisi ini juga berperan terhadap penurunan jumlah hasil tangkapan (Napitupulu et al. 2005). Ribuan nelayan tradisional di perairan pantai Kabubaten Indramayu juga merasakan kelangkaan ikan yang tidak ada kaitannya dengan musim paceklik. Mereka menyatakan pada periode 70an merupakan masa jaya penangkapan. Pada periode 1985–1990-an mulai terasa kemerosotan potensi sumber daya perikanan. Pada umumnya, masyarakat nelayan di desa-desa pantai Utara Jawa menghadapi persoalan yang sama dengan nelayan Indramayu, kecuali nelayan bermodal besar yang beroperasi hingga lepas pantai (off shore). Secara sosial ekonomi, tingkat kehidupan nelayan tradisional tidak banyak berubah. Justru tingkat kesejahteraan mereka semakin merosot jika dibandingkan masa-masa tahun 1970-an, bahkan para nelayan buruh lebih parah (Kusnadi 2002). Kematian massal ikan dan biota air di perairan sekitar Ancol dan Dadap pada tahun 2004 merupakan sinyal bahwa perairan Teluk Jakarta telah mengalami tingkat pencemaran yang sangat berat. Untuk menghindari kematian (cangkang kerang keropos) pada budi daya kerang hijau yang banyak terdapat di perairan Kamal dan Dadap dari ancaman pencemaran, mereka harus memindahkan rakit semakin ke Tengah. Pada Tambak percobaan Instalansi Kamal Balai Riset Perikanan Laut, hampir dipastikan spesies udang sudah tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, begitu juga hasil tangkapan udang di saluran tambak menurun drastis sejak tahun 1990-an. Dengan demikian, nasib nelayan di pesisir teluk tidak pernah akan berubah, justru sebaliknya kehidupan mereka kian sulit akibat dampak langsung krisis habitat. 218 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu 2. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Gambar. 4. Dualistik kegiatan yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya pesisir, yang tidak terbatas pada peraturan perikanan (kiri), tetapi juga termasuk intervensi aktif bertujuan untuk rehabilitasi habitat atau perangkat tambahan yang sebenarnya (kanan) Tantangan untuk memelihara sumber daya ikan yang sehat menjadi isu yang cukup kompleks dalam pembangunan perikanan. Keberlanjutan perikanan merupakan isu yang bersifat multidemensional. Dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan, terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara empiris adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut (Satria 2004). Kusumastanto (*) menyatakan bahwa perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (as fish) atau keuntungan ekonomi semata (as rents), tetapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan (sustainable community) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (institutional sustainability) yang mencakup kualitas 219 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan, dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan komunitas perikanan. Sementara itu, Pitcher dan Pauly (1998) menyatakan bahwa lebih penting untuk memulihkan ekosistem dibandingkan terjaminnya keberlanjutan, dan hal ini harus menjadi tujuan dalam pengelolaan perikanan. Keberlanjutan adalah memberdayakan tujuan terkait dengan pemanenan ikan oleh manusia yang mengarah pada penyederhanaan terhadap pentingnya ekosistem, tingginya keuntungan, dan semakin rendahnya “trophic level” jenis ikan yang dapat bertahan dari perusakan maupun penurunan kualitas habitat. Menurut Pauly dan Eng (1988) ada dua tingkat pengelolaan perikanan, yakni pengelolaan melalui regulasi perikanan dan melalui intervensi lingkungan. Regulasi perikanan meliputi aturan-aturan penutupan daerah dan musim, peningkatan ukuran mata jaring, kontrol terhadap upaya penangkapan, pembatasan jumlah izin masuk, pengunaan hak wilayah (territorial uses right fisheries). Sementara pengelolaan melalui intervensi lingkungan meliputi: membangun terumbu karang buatan, penanaman kembali lamun, penanaman kembali mangrove, pengembalaan ikan di laut, marikultur, dan kontrol yang ketat terhadap pencemaran (Gambar 4). Dari beberapa penelitian menunjukkan ada beberapa indikator yang diperkirakan sensitif terhadap pembangunan yang berkelanjutan di pesisir Jakarta. Dari aspek ekonomi adalah pengaturan hasil tangkapan, sistem bagi hasil, dan lapangan pekerjaan di luar sektor perikanan, serta peningkatan taraf hidup. Aspek teknologi penangkapan diarahkan untuk memperbaiki selektivitas alat tangkap. Perikanan di dalam teluk secara ekonomi cenderung memiliki sustainability rendah. Hal tersebut terjadi mungkin karena teluk telah tercemar, sehingga menghasilkan nilai ekonomi rendah dan biaya sosial cukup tinggi (Fauzi dan Anna 2005). Status keber1anjutan perikanan tangkap di DKI Jakarta berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pendapatan alternatif di luar perikanan tangkap (Susilo 2003). Beberapa strategi yang penting mendukung keberlanjutan pengelolaan tersebut adalah pemberdayaan SDM, peningkatan pengawasan melekat, penyuluhan kepada nelayan, manajemen terpadu untuk mempertahankan fungsi ekosistem perairan, standarisasi terhadap perikanan skala kecil, dan pengaturan hari operasi dengan penerapan closedopen season (Radarwati et al. 2010). Dengan demikian, tidak ada solusi 220 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu sederhana yang dapat berfungsi sebagai model untuk mengelola sumber daya milik bersama (common property resources), proses menuju pengelolaan perikanan berkelanjutan atau masih berhadapan dengan permasalahan dasar “human dimension“. 3. Restorasi Habitat dan Pemberdayaan Masyarakat Beragam program untuk mengatasi krisis habitat dan penurunan stok sumber daya ikan Kepulauan Seribu telah dilakukan. UNESCO-CSI (1999), dalam rangka proyek “Environmental governance and wise practices for tropical coastal mega-cities: Sustainable human development of the Jakarta Metropolitan Area”, merumuskan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan Jakarta, secara garis besar sebagai berikut: (1) Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong partisipasi masyarakat dan LSM dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan; (2) Mengintegrasikan kegiatan peningkatan kualitas kawasan pesisir sebagai salah satu bagian dari program pembangunan pemerintah (pusat dan daerah), merumuskan kebijaksanaan lingkungan hidup dan sistem pemantauan, analisis and desiminasi hasil lapangan; dan (3) Meningkatkan kesadaran sektor swasta (para pengelola kawasan pariwisata dan kawasan industri) akan pentingnya arti dari pelestarian lingkungan hidup. Restorasi ekologi merupakan upaya untuk memulihkannya seperti sediakala sebelum terdegradasi, sehingga menjamin kembali pulihnya habitat bagi kehidupan satwa liar dan mengembalikan fungsinya sebagai produsen primer dalam ekosistem dengan melihat dari berbagai sudut pandang ilmiah. Restorasi habitat mangrove dan terumbu karang melalui pemberdayaan masyarakat yang dituangkan terhadap arah kebijakan perikanan bertujuan mempercepat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas utama budi daya perikanan dan industri pariwisata bahari. Dua sektor ini diharapkan menjadi primemover pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Beberapa prioritas utama program yang dilakukan bertujuan untuk: 1) memperbaiki produktivitas subsistem, 2) promosi keikutsertaan dan community based management, 3) pengembangan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat 221 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya dan nelayan, 4) regenerasi lingkungan, dan 5) efektivitas pengaturan sumber daya alam (Tabel 2). Tabel 2. Beberapa program intervensi/manipulasi lingkungan dari Suku Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Jenis Budi daya Lokasi Ikan kerapu Pulau Lancang, Pari, Tidung dan Kongsi (1). Pulau Panggang, Hara-pan, Kelapa dan Kelapa dua (2) Rumput laut Pulau Pari, Kongsi, Tikus dan Burung (1), Panggang (2) Transplantasi karang Tujuan Sasaran Pulau Gosong, Pulau Pramuka Semak daun (2) Pemulihan kembali kondisi terumbu karang Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang arti penting terumbu karang bagi biota laut Gugusan Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Tidung (1), Mengamankan kawasan DPL dari eksploitasi yang berlebihan dan mempertahankan ekosistem terumbu karang Sarana peningkatan produksi Perikanan, meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat dan nelayan, lokasi pemancingan, ekowisata (diving) Rumah Singgah ikan Pulau panggang dan Harapan (2) Program Sea Farming Semak daun (2) Di luar kawasan MPA, (2) Dalam kawasan MPA * (Sumber Suku Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta) Salah satu aktivitas penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan baik oleh pemerintah (Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu bersama dengan Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta) maupun oleh NGO, untuk mencari alternatif mata pencaharian selain menangkap ikan Pelatihan teknis budi daya terumbu karang dan ikan, serta NGO di Pulau Panggang memperkenalkan ekowisata, dimulai organisasi akar rumput “Elang Ekowisata”. UNEP (2006) menyatakan 222 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu organisasi ini tidak akan mampu berkembang jika ketiadaan pengalaman dan dukungan dalam mengembangkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ekowisata. Fauziah (1994) menyimpulkan keadaan sosial ekonomi nelayan yang mendapat kesempatan kerja di bidang Kepariwisataan sebagai pemandu wisatawan bahari lebih baik daripada keadaan sosial ekonomi nelayan biasa. Hal ini disebabkan nelayan pemandu wisatawan bahari mempunyai 2 sumber mata pencarian, ketika pada saat tidak melaut mereka bekerja tambahan di bidang kepariwisataan. Selain itu, Suku Dinas Perikanan dan Kelautan, dalam penguatan kelembagaan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan juga dilakukan pada kelembagaan pengawasan di tingkat akar rumput melalui pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di beberapa Pulau di Kepulauan Seribu (Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Sebira, Pulau Sepa). Pembentukan Pokmaswas adalah suatu proses membentuk kelompok atau organisasi masyarakat yang akan mempunyai peran dan fungsi bidang tertentu (konservasi, produksi, peningkatan peran, dan kemampuan perempuan). Pokmaswas mempunyai tugas dan tanggung jawab utama, yaitu (1) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang arti dan nilai penting ekosistem terumbu karang, adanya ancaman terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. (2) Berperan aktif dalam penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang terpadu (RPTK Terpadu) yang mencakup program pengelolaan terumbu karang, pengembangan mata pencaharian alternatif, pengembangan prasarana dasar, dan peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat. (3) Mengimplementasikan RPTK terpadu sesuai dengan bidang Pokmaswas yang bersangkutan, misalnya Pokmaswas konservasi melaksanakan program-program pengelolaan terumbu karang. (4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan masing-masing Pokmaswas. Selain itu, di Kepulauan Seribu juga sudah dikembangkan 5 (lima) lokasi DPL berbasis masyarakat (DPL BM) yang dikukuhkan melalui SK Bupati Kepulauan Seribu nomor 375/2004, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (Pulau Tidung, Pulau Pari), Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (Pulau Harapan, Pulau Panggang dan Gosong Pramuka). 223 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya 4. Peranan Perikanan Tangkap Perikanan tangkap di Teluk Jakarta telah mengalami tekanan pencemaran, sedangkan di bagian Utara (Kepulauan Seribu) dibatasi oleh Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, Prioritas pengembangan perikanan tangkap adalah dengan melakukan ekspansi daerah penangkapan ke luar teluk dan Kepulauan Seribu. Hierarki perikanan tangkap di DKI Jakarta dapat dibedakan berdasarkan kemampuan jangkauan daerah penangkapan, dengan mengacu pada klasifikasi Yamamoto (1983), yaitu: (i) perikanan pesisir atau coastal fishery, (ii) perikanan lepas pantai atau offshore fishery, dan (iii) perikanan laut lepas atau distant-water fishery. Pada perikanan pesisir, sebagian besar nelayan artisanal menggunakan jenis alat tangkap relatif sederhana dan perahu relatif kecil, biasanya mereka kurang dari 10 gross ton (GT), serta daerah penangkapan masih terkonsentrasi di dalam Teluk dan Kepulauan Seribu. Terdapat tiga kelompok nelayan, yaitu nelayan yang tinggal pesisir Pulau Jawa, nelayan di sekitar Kepulauan Seribu yang sangat bergantung pada keberadaan terumbu karang dan nelayan pendatang atau dikenal dengan “andon” yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, umumnya mereka menggunakan pukat cincin dan cantrang. Setelah keberhasilan motorisasi, kini daerah penangkapan beberapa alat tangkap seperti muroami, bouke ami, gillnet, bubu, dan pancing, meliputi Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa dan Pulau Bawean, Pulau Bangka dan Belitung, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Di Jakarta Utara, jumlah nelayan yang terdaftar mencapai 18.996, nelayan yang menetap sebanyak 11.525 dan nelayan pendatang sebanyak 7.471, yang hidupnya masih berada di dalam lingkaran kemiskinan. Dari enam kecamatan, kawasan Cilincing menjadi salah satu tempat domisili terbesar masyarakat nelayan di Jakarta Utara dengan jumlah nelayan mencapai kurang lebih 8.000 nelayan dengan kehidupan yang umumnya masih di bawah garis kemskinan (http/utara.jakarta.go.id). Hasil tangkapan ratusan nelayan di sepanjang pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten terus berkurang karena kerusakan habitat yang diakibatkan hilangnya hutan mangrove di sepanjang pantai dan adanya pengerukan pasir pantai. Dalam dua tahun terakhir, ikan, udang, dan rajungan yang biasa mereka tangkap sehari-hari, jumlahnya menurun drastis (indonesia.com). Selain 224 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu itu, dengan terbentuknya seluruh wilayah Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Kepulauan Seribu, ternyata berimbas ke kalangan nelayan Tangerang karena mereka akan melanggar batas wilayah Jakarta. Sebagian besar nelayan yang melaut hingga perairan Kepulauan seribu tidak memiliki izin resmi (Suara Karya 22/5/2011). Sementara itu, ribuan nelayan tradisional di pesisir utara Bekasi kini terancam bangkrut. Mereka kekurangan modal untuk melaut dan mengembangkan usaha karena penghasilan dari usaha perikanan tangkap terus merosot, sedangkan untuk mengembalikan biaya operasional susah (Koran Tempo 2/8/2004) Perikanan lepas pantai yang beroperasi di luar Teluk dengan kapal lebih besar (biasanya lebih dari 10 GT) umumnya memiliki karakteristik dimensi ekonomi menjadi dominan, karena pelaku perikanan terus mengusung konsep efisiensi dan produktivitas, sehingga masalah ekologi kerapkali diabaikan. Pada kenyataannnya, untuk alat tangkap tertentu kerapkali daerah penangkapan antara perikanan pesisir dengan perikanan lepas pantai tidak dapat dipisahkan secara tegas dan tumpang tindih daerah penangkapan akan terjadi, terutama pada perikanan cantrang, cumi-cumi, dan pukat cincin. Sementara itu, perikanan laut lepas yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai di luar ZEEI (Samudera Hindia) digerakkan oleh pelaku yang berciri industrial. Mereka padat modal dan berteknologi tinggi, terutama pada perikanan tuna, cumi-cumi, dan pukat cincin pelagis besar. Pada Tabel 3 disajikan jenis alat tangkap berdasarkan klasifikasi perikanan yang berada di DKI Jakarta. Perkembangan yang sangat pesat pada perikanan lepas pantai dan laut lepas, terutama perikanan tuna (rawai tuna), pukat cincin dan jaring cumi. Namun, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja nelayan di pesisr Teluk Jakarta masih relatif kecil, karena pada umumnya nahkoda lebih mementingkan ABK dari keluarganya sendiri atau ABK yang berasal satu desa dengannya, untuk lebih mudah diatur dan dipercaya. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan nelayan pesisir ke ABK nelayan kapal yang beroperasi relatif lama 225 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 3. Jenis alat tangkap berdasarkan hierarki perikanan Perikanan pesisir Sero/Jermal Cantrang/Dogol Jr. rampus Jr. Kritik Jr. Insang lingkar Tramell net Jr. Insang lingkar Jr. Insang hanyut Jr. Insang tetap Payang Bagan Tancap Bagan Perahu Pukat Pantai Pancing Lainnya Perikanan pesisir Kepulauan Seribu Bubu Pancing muroami Pukat Bagan jaring ikan hias Arad, Payang panah, pengkoan Perikanan lepas pantai Pukat cincin Jr. Cumi-cumi Cantrang Jr. Insang hanyut Pancing Rawai dasar Perikanan laut lepas Rawai Tuna Pukat cincin Jr. Insang hanyut Kesimpulan 1. Kesulitan pengelolaan di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu diakibatkan segenap faktor eksternal bekerja secara sinergis dan bersama, sehingga menyebabkan efek akut terhadap ikan dan biota air. 2. Upaya pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Jakarta melalui intervensi lingkungan yang meliputi pembangunan terumbu karang buatan, rehabilitasi mangrove, dan marikultur. 3. Dengan tingkat pencemaran Teluk Jakarta yang sudah sangat berat, sulit merestorasi terumbu karang. Satu-satunya jalan untuk menumbuhkan kembali terumbu karang adalah dengan memperbaiki kualitas perairan di Teluk Jakarta, dan ini pun sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, nasib nelayan di pesisir teluk tidak pernah akan berubah, justru sebaliknya kian mempersulit kehidupan mereka akibat dampak langsung krisis habitat. 4. Upaya pemerintah dalam melaksanakan undang-undang telah menyerahkan sebagian tanggung jawab untuk mengelola sumber daya ikan kepada masyarakat lokal dalam bentuk kawasan konservasi. 226 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Namun, masih ada beberapa hambatan darlam mentransf pengelolaan penuh kepada organisasi berbasis masyarakat, karena kontrol penuh untuk pengelolaan bersama oleh masyarakat dan pemerintah masih relatif baru dan belum teruji. Selain itu, keberhasilan pengelolaan tersebut sangat bergantung pada ukuran kelompok, heterogenitas peserta, ketergantungan mereka pada manfaat informasi yang tersedia bagi peserta, dan latar belakang peserta Daftar Pustaka Arifin Z. 2004. Local Millenium Ecosystem Assessment: Condition and Trend of the Greater Jakarta Bay Ecosystem. The Ministry of Environment, Republic of Indonesia. 30 pp Burke L, Selig E and M. Spanding. 2002. Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara. Publikasi World Resources Institut, United Nations Environment Program-World,Conservation Monitoring Centre, World Fish Center, dan International Coral Reef Action Network.44pp Cesar,H. 1996. Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. International Coral Reef Initiative. Evironment Department. Work in Progress. 103 pp. http://csc.noaa. gov/ mpas/ Dermawan A, A.Rusandi, D Sutono dan Suraji. 2008. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Mendukung Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional VI di Manado, 27 September 2008. surajis.multiply.com/ journal/item/20 - 93k Fauzi A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sistesis, dan Gagasan. Jakarta: PT Gramedia, 187p. Fauzi A dan Anna S. 2005. Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia, 335p. Fauziah H. 1994. Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Nelavan di Kepulauan Seribu. Ecotourism.:http:// digilib.ui.ac.id/opac/Firman T and IA Dharmapatni. The Challenges to Sustainable Development in Jakarta Metropolitan Region, Habitat International, Vol. 18, No. 3 (1994), p. 88 227 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya http/ utara.jakarta.go.id.redaktur. Kehidupan Nelayan Jakarta Utara Masih Memrihatinkan. Diakses tanggal 6 April 2011. Kompas. 31/7/2009. Pantai Utara Kritis. http://koran.kompas.com/read/ xml/2009/07/31/03393673/pantai.utara.jakarta.kritis Koran Tempo. 2/8/2004. Ribuan Nelayan Bekasi Terancam Bangkrut. www.infoanda.com Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKIS. Jogyakarta. 190p Kusumastanto (*). Kusumastanto T (*). .Revitalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. tridoyo.blogspot.com Lestari dan Edward. 2004. Dampak Pencemaran Logam Berat terhadap Kualitas Air Laut dan Sumber daya Perikanan (Studi Kasus Kematian Massal Ikan –Ikan di Teluk Jakarta). Makara Sains. Vol.8. No.2: 56–62 Media Indonesia. Rumah Ikan di Teluk Jakarta Tersisa 2%. Senin, 27 April 2009 Napitupulu, D Lydia, SN Hodijah and AC Nugroho, 2005. Sosio-Economic Assessment: In The Use of Reef Resources by Local Community and Other Direct Stakeholder (Angraini, editor): A research Report Submmiied to: NOAA. The Indonesian Coral Reef Foundation (Yayasan Terangi). 128 pp. Radarwati S, MS Baskoro, DR Monintja, A Purbayanto. 2010. Analisis Faktor Internal – Eksternal dan Status Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Teluk Jakarta. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol. 1, No. 1 Pauly D and CT Eng. 1988. The Overfishing of Marine Resources: Sosioeconomi Background in Southeast Asia. Ambio, a Journal of The Human Environment. Vol 17 (3): 200-206 Pitcher TJ and D Pauly. 1998. Rebuilding Ecosystems, Not sustainability, as The Proper Goal of Fishery Management. in Reinventing Fisheries Management ed T. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series. Pages 311–325 (Chapter 24 ). 228 Upaya Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Fragmentasi Habitat Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Ongkosongo OSR, Helfinalis, Pramudji, Hadikusumah, M Muchtar, T Sidabutar, A Djamali, A Aziz, Ruyitno, Z Arifin. 2008. Kajian Perubahan Ekologis Perairan Teluk Jakarta. LIPI Press. 228 pp Satria A. 2004. Paradigma Perikanan Berkelanjutan REPUBLIKA. Jumat, 16 Juli 2004 Suara Karya 22 Mei 2011. Perikanan Nelayan Tangerang Mengaku Diperas Oknum Polair Jakarta. Suara karya online Susilo SB. 2003. Keberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Kelurahan Pulau Panggang Dan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Disertasi. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Terangi 2007. Terumbu Karang di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Warta Terangi Vol 2 No 1, Januari–Juli 2007. Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Tridoyo KT. (*) Revitalisasi Sektor Kelanjutan dan Perikanan Secara Berkelanjutan. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. tridoyo.blogspot.com.UNEP 2006. Raising Awareness and Capacity of Grassroots Organisations on Coral Reef Ecology and Coral Reef Monitoring in Panggang Island in Case-Studies of Coral Reef Monitoring and Management Projects (2004–2005). Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA):13–17. UNESCO-CSI. 1999. Environmental Governance and Wise Practices for Tropical Coastal Mega-Cities: Sustainable Human Development of The Jakarta Metropolitan Area. Workshop on Wise Coastal Practices for Sustainable Human Development. www.unesco.org/csi/ act/other/indonesi.htm. UNESCO 2000. Reducing Megacity Impacts on The Coastal Environment-Alternative Livelihoods and Waste Management in Jakarta and The Seribu Islands. Coastal Region and Small Island Papers 6, UNESCO, Paris, 59 pp. Unsworth RKF. 2007. Aspects of The Ecology of Indo-Pacific Seagrass Systems. A thesis submitted for the degree of doctor of philosophy Department of Biological Science University of Essex. 229 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Yamamoto T. 1983. Fishery Regulations Adopted for Coastal and Offshore fisheries in Japan with particular reference to the Fishing Right System. Papers presented at the Expert Consultation on the Regulation of Fishing Effort (Fishing Mortality), Rome, 17–26 January 1983. Waryono T. 2006. Konsepsi Manajemen Pemulihan Kerusakan Mangrove di DKI Jakarta. Seminar Perencanaan Pemulihan Mangrove. Yayasan Mangrove Indonesia. Jakarta 12 Desember 2006. http://www.indonesia.com/. tangerang. 230 hasil-tangkapan-nelayan-pantai-utara- Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta Ali Suman *) Abstrak Perairan Teluk Jakarta dan sekitarnya sudah lama dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Semakin meningkatnya angkatan kerja di sektor perikanan dan meningkatnya permintaan akan komoditas perikanan mengakibatkan tekanan penangkapan semakin intensif. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya penangkapan yang berlebih (over fishing) dan dalam jangka panjang akan mengarah kepada terancamnya kelestarian sumber daya ikan. Untuk mencegah hal tersebut, sumber daya ikan harus dikelola secara rasional. Saat ini terlihat pengelolaan yang ada di Teluk Jakarta belum memenuhi kaedah-kaedah tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan pembaruan opsi-opsi pengelolaan untuk mencari alternatif pengelolaan yang dapat memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan di Teluk Jakarta. Alternatif pengelolaan yang dianjurkan adalah dengan menerapkan opsi penutupan daerah penangkapan terutama pada daerah asuhan, pembatasan upaya, penerapan kuota, dan mendorong budi daya perikanan. *) Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pendahuluan Produksi ikan di perairan Teluk Jakarta mengalami penurunan secara terus menerus yaitu dari 35.008 ton pada 1999 menjadi 28.526 ton pada tahun 2000 dan pada tahun 2002 menjadi 17.828,7 ton (DP2K-DKI, 2003 dalam Arifin 2005). Sejak tahun 2002 lalu, produksi ikan nelayan di kawasan ini menurun hingga 38 persen. Indikator lainnya adalah persepsi pemimpin lokal dan masyarakat Kepulauan Seribu yang menyatakan bahwa kondisi sumber alam seperti terumbu karang dan hutan mangrove menurun dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, dan kondisi ini turut berperan terhadap penurunan jumlah hasil tangkapan (Napitupulu et al. 2005). Dengan demikian pengelolaan sumber daya ikan di Teluk Jakarta saat ini belum mampu menjamin kelestarian sumber dayanya dan apabila dibiarkan dalam jangka panjang akan dapat menyebabkan kepunahan sumber daya di perairan tersebut. Dalam kaitan tersebut, evaluasi pengelolaan terhadap sumber daya ikan di perairan Teluk Jakarta mutlak diperlukan, mengingat penangkapan yang dilakukan sangat intensif yang melibatkan berbagai bentuk armada penangkapan. Hal ini menyebabkan intensitas pemanfaatan sumber daya ikan telah berada pada tingkat yang tinggi dan kondisi pemanfaatan sumber daya ikan saat ini sudah mengarah kepada pemanfaatan yang berlebih dan cenderung sudah over-exploited. Apabila keadaan ini dibiarkan terus dalam jangka panjang maka akan mengarah kapada terancamnya kelestarian sumber daya dan bahkan dapat mengalami kepunahan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian alternatif pengelolaan terhadap sumber daya ikan di Teluk Jakarta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tersebut. Dengan demikian tujuan pengelolaan sebagaimana tertera dalam UU Perikanan No.45 tahun 2009 dapat tercapai serta dapat mengakomodir implementasi undang-undang mengenai otonomi daerah. Bahan dan Metode Bahan makalah ini merupakan hasil penelusuran studi pustaka dari berbagai sumber terutama dari hasil-hasil penelitian Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara memetakan fenomena perikanan yang sedang berlangsung didukung oleh 232 Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta diskusi terbatas dengan berbagai sumber pada saat melakukan observasi lapang. Status Pemanfaatan Kepadatan ikan demersal dan karang di perairan Kepulauan Seribu pada tahun 2007 42 ekor/250 m2–536 ekor/250 m2, didominasi oleh Caesionidae, Nemipteridae, Pomacentridae, Labridae, dan Lethrinidae. Kepadatan ikan dalam kriteria sangat jarang, yaitu pada kisaran 1–5 ekor/m2. Pada umumnya hasil tangkapan menunjukkan kecenderungan menurun dan relatif rendah. Pada perikanan muroami menunjukkan gejala kolaps pada awal tahun 2000. Secara ekonomi usaha penangkapan ikan demersal masih cukup menguntungkan dan layak untuk diusahakan, dengan tingkat kelayakan usaha bervariasi antara 1,31–9,95. Hal inilah yang menyebabkan nelayan masih terus memanfaatkan sumber daya ikan demersal ini, walaupun dari sisi lain stok sumber daya ikan sudah mengalami penurunan (Hartati et al. 2011). Perairan Teluk Jakarta juga merupakan salah satu daerah penangkapan sumber daya rajungan penting di pantai utara Jawa. Alat tangkap utama untuk menangkap rajungan adalah jaring rajungan (lokal: kejer) dan bubu lipat, sedangkan pada sero dan bagan merupakan hasil tangkapan ikutan. Produksi rajungan cenderung menurun sejak tahun 2006. Pada bulan April-Mei 2007, laju tangkap rajungan tertinggi (23 kg/unit/hari) terdapat pada bubu lipat, diikuti oleh jaring rajungan, sedangkan terkecil (3,25 kg/unit/hari) terdapat pada bagan tancap. Rata-rata ukuran rajungan yang tertangkap dengan jaring insang relatif lebih besar. Hubungan lebar karapas-berat individu bersifat isometrik yang berarti pertambahan panjang sebanding dengan pertambahan beratnya (Sumiono et al. 2011). Komposisi jenis kekerangan di Teluk Jakarta sekitar 103 jenis dan yang mendominasi adalah S. cornea dan A. nodifera.Pemanfaatannya sudah menunjukkan kecenderungan berlebih yang terindikasi dari menurunnya jumlah jenis kerang sekitar 103 jenis pada tahun tahun 1977 menjadi 40 jenis pada tahun 1995. Jenis kerang dara dan bulu (Anadara spp.) sudah tidak ditemukan pada stasiun pengamatan tahun 2006. Selain itu CPUE kekerangan juga telah mengalami penurunan yaitu dari 2 ton per trip tahun 1980 menurun menjadi 255 kg per trip pada saat ini. Daerah 233 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya penangkapan saat ini semakin menyempit hanya di perairan Tanjung Kait. Pada awal 1980 daerah penangkapan kekerangan meliputi semua perairan Teluk Jakarta, mulai dari perairan pesisir Tanjung Karawang, Marunda, Cilincing, Kali Adem M. Angke dan Kamal sampai Tanjung Kait. Berkurangnya daerah penangkapan tersebut diduga ikarena dampak pencemaran dan adanya konflik interest dengan nelayan lokal terutama nelayan jaring rajungan (Nuraini et al.,2011). Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Selain jenis ikan demersal, tertangkap juga ikan pelagis kecil di perairan Teluk Jakarta. Jenis-jenis ikan pelagis kecil yang tertangkap umumnya sama dengan yang biasa tertangkap di perairan lainnya di wilayah Indonesia terutama dari Laut Jawa. Alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap ikan pelagis kecil ini adalah bagan, payang dan jaring (gillnet) kembung. Ukuran jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ikan banyar dan tembang yang tertangkap di perairan Kepulauan Seribu terutama oleh alat tangkap bagan pada umumnya relatif kecil karena terdiri dari ikan muda. Status pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di perairan Teluk Jakarta sudah berada dalam tahapan yang jenuh seperti umumnya yang terjadi di Laut Jawa (Hariati et al. 2011). Opsi-Opsi Pengelolaan Menyadari keseriusan permasalahan pemanfaatan sumber daya perikanan dunia, maka Komisi Perikanan Dunia (The Committe on Fisheries) pada sidang yang kesembilan belas pada bulan Maret 1991 melakukan pengembangan konsep baru menuju perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya pada Konferensi Internasional tentang penangkapan ikan yang bertanggung jawab yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Cancun, Mexico telah menunjuk FAO untuk mempersiapkan suatu konsep petunjuk pelaksanaan (code of conduct) untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab (responsible) dan memperhatikan prinsipprinsip berkelanjutan (sustainability). Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (sustainable mangement) dalam perikanan timbul karena adanya isu global tentang terbatasnya sumber daya perikanan di satu pihak dan kebutuhan akan sumber daya perikanan yang terus meningkat akibat meningkatnya penduduk di lain pihak. Dengan menerapkan konsep 234 Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan maka akan dapat menyelamatkan sumber daya ikan tersebut dari kepunahan dan sekaligus menyelamatkan kepentingan kehidupan semua orang yang bergantung kepada sumber daya perikanan ini. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam yang terbarui untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarikan sumber daya tersebut. Menurut Dahuri (2000), pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tidak rusak. Selanjutnya Monintja (2000) menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan mempunyai beberapa kriteria yaitu: (1) hasil tangkapan tidak melebihi jumlah yang boleh dimanfaatkan, (2) menggunakan bahan bakar lebih sedikit, (3) secara hukum alat tangkap legal, (4) investasi yang dibutuhkan rendah dan (5) produk mempunyai pasar yang baik. Agar pemanfaatan sumber daya ikan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka sumber daya ini harus dikelola secara rasional. Oleh karena itu maka sumber daya harus dikelola mulai dari tingkat awal pemanfaatannya sehingga diperoleh keseimbangan antara pengembangan dan keuntungan yang optimal. Dalam konteks ini kita dianjurkan untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan pengelolaan dan selanjutnya menentukan metode yang paling sesuai untuk itu. Dalam menentukan langkah-langkah pengelolaan maka harus didasarkan pada bukti ilmiah yang akurat. Berbagai macam peraturan dan undang-undang telah dikeluarkan untuk pengelolaan dan pemanfaatan ikan yang berkelanjutan untuk melindungi sumber daya tersebut dari kelebihan tangkap dan kepunahannya. Pada prinsipnya metode-metode pengelolaan tersebut digolongkan menjadi dua bagian yaitu pengontrolan ukuran udang yang tertangkap dan pengontrolan jumlah penangkapan (amount of fishing). 1. Penutupan daerah dan musim penangkapan Tindakan ini terutama dimaksudkan untuk memelihara siklus pertumbuhan, agar tidak terjadi pemutusan terhadap siklus yang dapat 235 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya mengakibatkan penurunan populasi dan kepunahan satu atau beberapa jenis udang. Tindakan ini terutama ditujukan untuk membatasi efisiensi penangkapan, dan hanya akan efektif bila dilakukan secara simultan dengan pembatasan terhadap ukuran, jumlah serta kekuatan mesin kapal. Penutupan musim penangkapan tidak boleh berjalan terlalu lama, sebab akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan bagi nelayan yang mata pencahariannya tergantung sepenuhnya pada kegiatan penangkapan. Penutupan daerah penangkapan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh relatif terbatas terhadap pembatasan upaya penangkapan. Penerapan tindakan ini pada umumnya dapat berupa penutupan terhadap berlakunya suatu jenis alat tangkap tertentu, misalnya trawl pada kedalaman atau jarak tertentu dari pantai. Dalam prakteknya, pelaksanaan peraturan penutupan daerah penangkapan kadang-kadang akan merupakan problema yang sulit diatasi tanpa adanya patroli/pengawasan yang efisien. 2 Pembatasan Ukuran Ikan Terkecil Pengontrolan ukuran ikan pada saat pertama kali ditangkap dengan menentukan ukuran minimum yang boleh didaratkan ternyata kurang efektif dan telah merangsang praktek-praktek memusnahkan dan membuang kembali ke laut ikan-ikan yang ukurannya di bawah ukuran yang telah ditentukan. Walaupun demikian, peraturan tersebut dapat membantu dalam menegakkan peraturan lain seperti penutupan daerah penangkapan. Peraturan ini mungkin akan lebih efektif jika pemasaran ikan yang berukuran di bawah minimum yang telah ditetapkan juga dilarang. 3 Pengaturan Ukuran Mata Jaring Pengaturan ukuran mata jaring dimaksudkan untuk meloloskan individu-individu ikan yang berukuran kecil (muda) dari suatu stok. Jika pengaturan ukuran mata jaring telah menjadi pilihan, beberapa faktor berikut perlu dicoba. Termasuk diantaranya selektivitas (pengaruh tipe jaring dan benang yang berbeda dan ukuran hasil tangkap serta waktu penarikan), pendugaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dan penentuan efektivitas penegakan peraturan. 236 Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta 4 Pembatasan Jumlah Penangkapan Berbagai metode telah dicoba untuk mengurangi kematian karena penangkapan, tetapi tingkat keberhasilannya cukup bervariasi. Termasuk ke dalam cara pembatasan jumlah penangkapan ini adalah mempersingkat musim penangkapan, mengurangi daerah penangkapan yang dibuka, menggunakan alat dan metode yang kurang efisien, penentuan kuota hasil tangkapan, pembatasan jumlah kapal atau izin penangkapan dan pembatasan modal. Karena kelimpahan stok sangat bervariasi (yang tergantung faktor lingkungan), manajer harus diberi informasi peramalan terakhir jika ia harus mengontrol tekanan penangkapan dan mencegah kelebihan tangkap penambahan baru (recruitment over-harvest). Manajer juga harus cepat menyadari setiap perubahan dari upaya penangkapan atau praktek-praktek lain yang mungkin mempengaruhi total hasil tangkapan. Manajer harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi karena pengurangan efisiensi nelayan terutama selama periode meningkatnya biaya operasional dan pengolahan. 5 Pembatasan Alat Penangkapan Hasil tangkapan dapat dikurangi dengan membatasi efisiensi unit penangkapan yang ada dengan syarat nelayan tidak meningkatkan upaya penangkapannya. Metode yang biasa digunakan adalah pembatasan ukuran trawl atau melarang penggunaan trawl di daerah tertentu. Thailand telah melarang penggunaan trawl bermesin pada perairan sejauh 3000 m dari pantai. Di seluruh perairan Indonesia penggunaan trawl telah dilarang untuk melindungi nelayan tradisional. Tindakan tersebut sudah tentu memberikan dampak sosial ekonomi yang besar. 6 Kuota Penangkapan Walau kuota terhadap total hasil tangkapan tahunan sering dilakukan untuk hewan air yang umurnya panjang (ikan paus, halibut, cod, udang Pandalid), tetapi kuota terhadap hasil tangkapan tidak begitu cocok. Karena umurnya pendek, kuota tahunan tidak akan mengontrol kematian penangkapan, bahkan mungkin akan merangsang nelayan untuk menangkap secara intensif pada waktu musim penangkapan karena khawatir jangka waktu kuota sangat singkat. 237 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Pembatasan hasil per kapal per hari atau per trip dapat mengurangi mortalitas. Cara ini dilakukan pada beberapa perairan pantai di teluk Meksiko-Amerika Serikat untuk membatasi penangkapan yuwana udang. Hal ini memerlukan tingkat pemantauan yang tinggi agar penegakan hukum dapat efektif. 7 Pembatasan Upaya Penangkapan Walau metode pengelolaan lain seperti kuota penangkapan dapat mencapai maksud-maksud biologi, tapi kontrol langsung terhadap upaya penangkapan (atau kapasitas armada penangkapan) kelihatannya masih perlu untuk merealisasikan keuntungan ekonomi yang nyata yang dapat diperoleh dari pengelolaan yang efektif. Metode ini kelihatannya juga dapat memberikan cara pengalokasian sumber daya diantara kelompok pemakai yang berbeda-beda. Implikasi Kebijakan Sumber daya ikan dipandang sebagai sumber daya yang dapat pulih kembali (renewable resources), maka pemanfaatan yang berkelanjutan harus diartikan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya yang laju ekstrasinya tidak boleh melampaui laju kemampuan daya pulihnya. Oleh karena itu rezim pemanfaatan secara terbuka, sebagaimana yang umumnya dianut di Indonesia saat ini, sudah seharusnya tidak digunakan untuk mengusahakan sumber daya ini. Dari tujuh macam cara pengelolaan untuk menuju pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan seperti yang telah dikemukakan, terlihat tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya ikan di Teluk Jakarta. Pembatasan atau penentuan ukuran ikan terkecil yang boleh didaratkan tidak dapat dilaksanakan, karena juvenil ikan yang harus dilindungi dan ikan dewasa lainnya terdapat pada daerah yang sama (bercampur). Kesukaran lain ialah jika sebagian hasil tangkap nelayan terdiri dari ikan-ikan dengan ukuran dibawah ukuran ikan terkecil yang telah ditetapkan, akan membuat nelayan membuang kembali hasil tangkapannya ke laut dan akan terbuang percuma karena akan mati sendiri. 238 Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta Dengan demikian dari beberapa metoda pengelolaan yang dikemukan untuk menuju pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan di perairan Teluk Jakarta, ternyata metode yang layak dilaksanakan adalah penutupan musim dan daerah penangkapan, pembatasan upaya penangkapan dan kuota penangkapan. Penutupan daerah dan musim penangkapan bertujuan untuk melindungi ikan muda serta meningkatkan ukuran ikan pertama kali matang kelamin dan akhirnya meningkatkan produksi. Dengan metode ini maka waktu yang krusial yang dibutuhkan oleh ikan dalam siklus hidupnya, yaitu mulai memijah, menjadi larva dan menuju daerah asuhan dalam bentuk post larva, dapat terlindungi dan dengan demikian akan terjamin kelestarian sumber daya. Penerapan metode pengelolaan berupa pembatasan upaya penangkapan ikan didasarkan pada hasil riset kapasitas penangkapan. Kajian kapasitas penangkapan perikanan tangkap kaitannya dengan pengukuran efisiensi perikanan menunjukkan bahwa kapasitas perikanan Jakarta dan sekitarnya (payang, pancing, bubu dan muroami) menunjukkan telah terjadi kelebihan kapasitas diindikasikan sebagian besar berada pada tingkat pemanfaatan yang tidak optimal (Hufiadi et al. 2011). Selanjutnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dapat diaplikasikan adalah kuota penangkapan. Kuota penangkapan yang dilakukan adalah dengan membagi potensi penangkapan yang ada berdasarkan kemampuan wilayah dalam menangkap ikan. Prinsip kuota ini sangat sejalan juga dengan prinsip otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 1999. Berdasarkan kemampuan penangkapan ikan per wilayah tersebut maka alokasi penangkapan dan alokasi produksi masing-masing wilayah di sekitar daerah penangkapan di perairan Teluk Jakarta. Selanjutnya untuk mendasari pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan ke depannya, maka masukan data dan informasi penelitian yang dibutuhkan disajikan pada Tabel 1. 239 Sumber Daya Ikan di Perairan Teluk Jakarta dan Alternatif Pengelolaannya Tabel 1. Kebutuhan data dan informasi bagi pemanfaatan secara berkelanjutan Informasi Kebutuhan metode pemanfaatan - Rata-rata ukuran matang kelamin Penentuan ukuran ikanl yang boleh ditangkap - Musim pemijahan Penutupan daerah/musim - Laju Pertumbuhan Pengendalian jumlah upaya - Laju Kematian Pengendalian jumlah upaya - Laju Pengusahaan Pengendalian jumlah upaya - Pola penambahan baru Penutupan daerah/musim - Indeks Kelimpahan Stok Pengendalian jumlah upaya - Potensi Lestari Pengendalian jumlah upaya - Ukuran Ikan Penutupan daerah/musim - Migrasi - Daerah Pemijahan - Selektivitas - Kemampuan tangkap Penutupan daerah/musim Penutupan daerah/musim Pembatasan alat tangkap Pembatasan alat tangkap Kesimpulan Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan maka harus dimulai dari awal pemanfaatannya, dengan mulai mengidentifikasi skenario pengelolaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam kaitan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Teluk Jakarta maka harus dilakukan pengendalian jumlah upaya seperti pada tahun 2008. Selain itu, pada waktu-waktu tertentu harus dilakukan penutupan daerah dan musim penangkapan serta penetapan kuota penangkapan, disamping itu harus dilakukan MCS dengan baik. 240 Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Teluk Jakarta Daftar Pustaka Dahuri R. 2002. Regenerasi dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. Harian Kompas Jakarta, edisi 21 Februari 2002, hal: 28. Hartati ST, IN Edrus, A Nurfiarini dan I Juanita. 2011. Status Perikanan Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Seribu. Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta. Hariati T, M Taufik dan M Fauzi. 2011. Status pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di Perairan Kepulauan Seribu. Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta. Hufiadi TW, Budiarti, Baihaqi dan Mahiswara. 2011. Perkembangan Perikanan Tangkap di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya. Monintja DR. 2000. Prosiding Pelatihan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. IPB Bogor, hal: 45–57. Napitupulu, D Lydia, SN Hodijah and AC Nugroho. 2005. SosioEconomic Assessment: in The Use of Reef Resources by Local Community and Other Direct Stakeholder (Anngraini, editor): A research Report Submmiied to: NOAA. The Indonesian Coral Reef Foundation (Yayasan Terangi). 128 pp. Nuraini S, Wahyuningsih, Prihatiningsih dan Wejatmiko. 2011. Status Pemanfaatan Kekerangan di Perairan Teluk Jakarta dan Sekitarnya. Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta. Sumiono B, K Wagiyo, D Kembaren dan Prihatiningsih. Aspek Penangkapan dan Biologi Rajungan (Portunus pelagicus Linn) di Perairan Teluk Jakarta. Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta 241