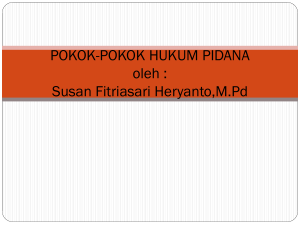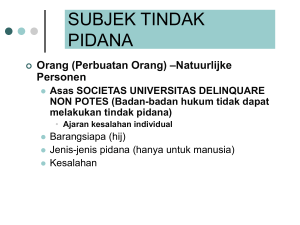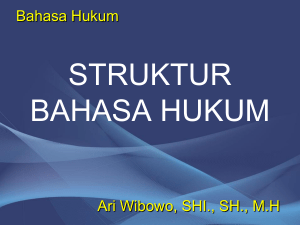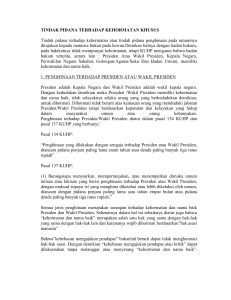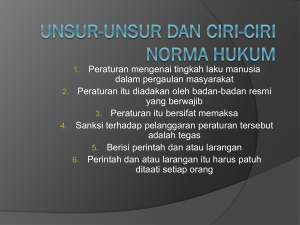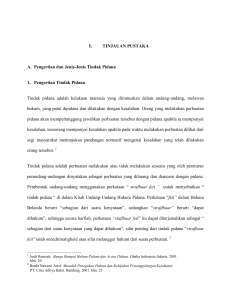Haatzaai Artikelen: Pedang DamoclesPembunuh Demokrasi
advertisement

Occasional Paper Series #4 Haatzaai Artikelen: Pedang Damocles Pembunuh Demokrasi, Reformasi dan HAM Oleh Togi Simanjuntak ELSAM Jakarta 2004 Haatzaai Artikelen:Pedang Damocles Pembunuh Demokrasi, Reformasi dan HAM oleh Togi Simanjuntak Editor Erasmus Cahyadi T. Desain Sampul: Layout: Cetakan Pertama, Oktober 2004 Hak terbitan dalam bahasa Indonesia ada pada ELSAM Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penerbit ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510 Tlp.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519 E-mail: [email protected], [email protected]; Web-site: www.elsam.or.id Daftar Isi 1. Latar Belakang 2. Ancaman bagi Demokrasi, Reformasi, dan Hak Asasi Manusia 3. Karakter Penggunaan dan Korbannya di Masa Reformasi 4. Harus Ditiadakan Profil Elsam Haatzaai Artikelen:1 Pedang Damocles2 Pembunuh Demokrasi, Reformasi dan HAM Togi Simanjuntak Latar Belakang Belum lagi genap satu tahun masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (selanjutnya disebut Rezim Megawati), ruang tahanan mulai diisi kembali oleh tahanan-tahanan politik.3 Situasi ini sangat kontras dengan putusan pengadilan yang membebaskan para koruptor penjarah uang negara, atau putusan pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc yang menghukum ringan (bahkan membebaskan) para perwira militer yang diindikasikan melanggar HAM. Sebagian dari para tahanan politik itu merupakan para mahasiswa dan pemuda yang melakukan unjuk-rasa menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik (BBM/TDL) awal Januari 2003, juga para aktivis organisasi non-pemerintah, atau tokoh masyarakat di wilayah konflik yang menyampaikan pendapat dan pikirannya atas situasi yang berkembang di wilayahnya. Memang sebagian dari antara mereka belum diadili. Tetapi beberapa yang diadili, seperti misalnya tokoh Front Pembela Islam (FPI) Jafar Umar Thalib, tokoh Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alexander Hermanus Manuputty, serta aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Muhammad Nazar sudah divonis. Yang mengejutkan, mereka dikenakan pasal-pasal karet tentang apa yang dimaksudkan dengan penyebaran rasa kebencian atau Haatzaai Artikelen. Haatzaai Artikelen, yang di masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid mulai dikuburkan itu, kini dibangkitkan kembali. Tampaknya pendulum kebebasan politik, kebebasan berekspresi, dan menyatakan pendapat cepat bergeser. Saat ini, jerat untuk kasus-kasus politik kembali dipasang. Di berbagai daerah – dari Aceh, Jakarta, hingga Papua – bisa ditemui kasus-kasus politik yang berakhir dengan pemenjaraan. Kasusnya pun sangat beragam, dari aksi teatrikal yang mencoret dan menginjak-injak gambar presiden/wakil presiden, membakar boneka wayang berwajah presiden, menggelar aksi demonstrasi tanpa izin, melanggar ketertiban umum, menghasut, melawan petugas, sampai “hanya” mengibarkan bendera. 1 Dalam seluruh artikel ini, penyebutan haatzaai artikelen (misalnya seperti yang dipakai penulis untuk tabel 4 artikel ini) tidak hanya dimaksudkan dengan pasal-pasal penyebar kebencian yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tapi juga menyangkut semua produk hukum yang terkait dengan kejahatan keamanan negara (misalnya Undang-undang dan sebagainya) maupun pidana politik lainnya. 2 Pedang Damocles diambil dari kisah Damocles, penduduk Syracuse, Yunani, pada abad ke-4 Masehi saat diperintah oleh tiran Dionysus. Pada suatu kesempatan Damocles diundang sang tiran untuk menghadiri sebuah pesta yang diadakannya, kemudian Damocles memenggal kepala Dionysius. Sedemikian tajamnya pedang tersebut, sehingga dikisahkan mampu memotong setipis apapun rambut seorang manusia. Lihat Thomas E. Guinn, “The Sword of Damocles”, di dalam http://www.csanews.net/ 3 Saat tulisan ini digarap, Presiden Megawati Soekarnoputri belum genap satu tahun memerintah. Oleh karena itu data yang digunakan didalam artikel ini berasal dari periode tersebut. Pada periode itu banyak terjadi unjuk rasa menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak, dan juga kerusuhan di daerah-daerah konflik. Hal ini bisa dimengerti, mengapa pasal-pasal penyebar kebencian banyak digunakan penyidik kepolisian bagi para terdakwa demonstrasi dan “penyulut” kerusuhan di daerah konflik. Semakin berkurangnya intensitas demonstrasi pada tahun kedua dan tahun ketiga pemerintahan Megawati, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah semakin berkurang pula penggunaan pasal-pasal penyebar kebencian oleh aparat penyidik kepolisian. 1 Mengapa pasal-pasal karet tersebut kembali dipergunakan rezim Megawati? Apa yang melatarbelakangi penggunaan Haatzaai Artikelen untuk membungkam suara-suara kritis di masyarakat? Apakah ini berarti kita telah kembali ke zaman otoriter sebelum bergulirnya reformasi yang dipelopori para mahasiswa? Apakah akibatnya bagi kelanjutan reformasi, pertumbuhan demokrasi, serta penegakan HAM di Indonesia?4 Menjelaskan motif yang melatarbelakangi penggunaan kembali Haatzaai Artikelen oleh rezim Megawati untuk menjerat para aktivis politik bisa didekati dari beberapa perspektif teori. Pertama, mereka yang mencoba menjelaskannya dari pendekatan paradigmatik ideologi politik yang dianut Megawati dan partainya, yakni ideologi nasionalisme yang diusung dalam varian nasionalisme organik.5 Dalam varian nasionalisme ini, maka negara ditempatkan secara lebih superior vis a vis rakyatnya. Negara dengan otoritas yang dimilikinya dapat mengabaikan hak-hak sipil dan politik warga-masyarakatnya. Penggunaan yang sistematis dari model nasionalisme ini bisa mengarah kepada otoritarianisme, dan -dalam bentuk ekstremnya- adalah fasisme negara. Kondisi ini kemudian bisa diparalelkan dengan penerapan nasionalismenya rezim Soeharto di masa lalu. Kedua, adalah mereka yang mencoba menjelaskannya dari pendekatan pembangunan kembali sistem hukum yang mendukung atau mem-back up praktik-praktik paradigma ideologi politik nasionalisme rezim Megawati. Atau – meminjam istilah MM Billah – pembangunan kembali sistem hukum ini sebagai bagian dari upaya rekonsilidasi otoritarianisme.6 Kecenderungan upaya penguatan sistem atau produk hukum untuk rekonsilidasi otoritarianisme ini sudah tampak dari beberapa proses legislasi di DPR. Sementara kebutuhan atas produk hukum yang bisa melindungi penguatan proses demokratisasi dan penegakan HAM terabaikan, di lain sisi, proses legislasi yang mendukung rekonsilidasi otoritarianisme menjadi porsi perhatian DPR maupun pemerintah untuk segera disetujui. Untuk sekedar menyebut beberapa contoh, misalnya RUU Anti-terorisme, RUU Intelijen, RUU Kebebasan Informasi, dan RUU TNI. Dalam konteks sosio-politik seperti inilah, menjadi jelas logika penerapan Haatzaai Artikelen oleh rezim Megawati. Artinya, sebelum suatu produk undang-undang yang sahih 4 Demokrasi, reformasi, dan HAM yang dimaksudkan dalam artikel ini merupakan suatu kosa kata yang lahir dari hasil pengalaman historis dan sosiologis masyarakat di negara-negara liberal-kapitalis Barat. Oleh sebab itu, untuk mengukur pelanggaran hak-hak sipil dan politik, yang diakibatkan oleh penggunaan pasal-pasal penyebar kebencian, dalam kaitannya dengan proses demokratisasi, reformasi, dan penegakan HAM di Indonesia, penulis menggunakan referensi para teoritisi liberal-universalis, dan libertarian-individualis (sebagaimana tabel 2, dan 3 pada artikel ini), darimana pengertian HAM itu dilahirkan. Kedua, penggunaan referensi para teoritisi liberal-universalis, dan libertarian-individualis dalam artikel ini sesungguhnya ingin menunjukkan, bahwa konsepsi demokrasi dan perjuangan HAM telah diletakkan dalam kerangka prosedur baku pentahapan politik (yang ilutif): “non-demokrasi—transisi-demokrasi penuh”. Sementara itu, dalam pandangan kaum sosialis, praksis pembebasan dan emansipasi kemanusiaan yang sejati dengan sendirinya akan mereduksi kebutuhan-kebutuhan atas dasar kategorikategori HAM sebagaimana dipraktikkan di negara-negara kapitalis pusat maupun pinggiran. Kategorikategori HAM adalah agenda terselubung (hidden agenda) kaum pemilik modal untuk mempertahankan sistem dan struktur sosial yang tidak adil, di negara-negara kapitalis pusat maupun pinggiran. 5 Nasionalisme organik ini bertolak-belakang dengan nasionalisme-kerakyatan yang diusung para foundingfathers Indonesia – Soekarno dan kawan-kawan – yaitu yaitu suatu bentuk nasionalisme pembebasan dan pemerdekaan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperi-kemanusiaan. Sedangkan nasionalisme-organik adalah suatu bentuk nasionalisme yang sudah termanipulasikan untuk kepentingan kekuasaan elite politik dan ekonomi saja. Semboyannya yang terkenal adalah, “right or wrong is my country”. 6 Lihat epilog M.M. Billah di dalam Stagnasi Hak Asasi Manusia, KontraS, 2002, hal. 92ff. 2 untuk berlangsungnya kembali praktik otoritarianisme memperoleh legitimasinya oleh negara, maka sebagai suatu “transisi” adalah relevan untuk menggunakan pasal-pasal karet Haatzaai Artikelen dalam kaitan menangkapi, dan memenjarakan para anggota masyarakat yang kritis. Bahkan lebih jauh lagi, jika di masa rezim Soeharto, penerapan Haatzaai Artikelen itu masih memiliki bobot politik, karena disesuaikan dengan esensi atau substansi delik politik terhadap para pelakunya. Maka, di masa rezim Megawati ini, seseorang bisa dikenakakan Haatzaai Artikelen atas tuduhan penghinaan yang sebenarnya belum menyentuh esensi atau substansi seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal delik politik pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti misalnya, membalikkan foto Presiden Dan Wakil Presiden, membawa wayang yang disimbolikkan sebagai figur Presiden Megawati, atau juga membakar patung yang mirip wajah presiden. Ancaman bagi Demokrasi, Reformasi, dan Hak Asasi Manusia Penerapan Haatzaai Artikelen ini, bisa berimplikasi negatif bagi keberlangsungan reformasi, proses demokratisasi, dan penegakan HAM di Indonesia. Lebih spesifik, bahwa praksis penerapannya, secara substansial, bisa melanggar hak-hak sipil dan politik warganegara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Polirtical Rights/ICCPR). Bahkan, dalam hubungannya atau kaitannya dengan penghargaan dan penghormatan atas HAM sebagaimana tercantum pada konstitusi negara, yaitu Amandemen Kedua UUD 1945 Bab XA Pasal 28A hingga 28J. Bagaimanakah bisa dijelaskan karakter-karakter ancaman itu pada ketiga aspek: kehidupan demokrasi di suatu negara, keberlangsungan reformasi dan penegakan HAM khususnya? Seperti diketahui Haatzaai Artikelen ini memiliki beberapa sifat atau watak “karet”. Berbeda dengan azas yang dianut pada hukum pidana yang limitatif, maka Haatzaai Artikelen ini menganut azas non-limitatif. Hukum Pidana mempersyaratkan batasanbatasan yang jelas secara formal-material atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan seseorang, yang justru tidak dipenuhi oleh pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Yang lainnya lagi, bahwa Haatzaai Artikelen ini berangkat dari presumtion of guilty, bukan presumtion of innocence sebagaimana dikenal pada proses hukum acara pidana. Dua aspek ini – presumtion of guilty dan azas non-limitatif – jelas menjadi celah atau ruang untuk membuka peluang terjadinya praktik pelanggaran HAM, terutama atas pengakuan hak-hak sipil dan politik warganegara. Secara umum, para human rights scholar dan human rights defender/activist mengelompokkan atau mengklasifikasikan hak-hak sipil dan politik tersebut atas tiga kebebasan dasar, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul. Dan, hukum hak asasi manusia internasional (termasuk ICCPR) memperbolehkan pembatasan atas kebebasan-kebebasan dasar hanya pada “saat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan yang keberadaannya dinyatakan secara resmi.” Pembatasan ini hanya diberlakukan, “sejauh hal itu dibutuhkan sekali oleh urgensi situasi.”7 7 Lihat kata pengantar Sydney R. Jones, “Tiga Kebebasan Dasar Di Asia: Suatu Tinjauan Umum”, di dalam Membelenggu Kebebasan Dasar: Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia, Elsam, 1999, hal.xxiii. 3 Lagi pula tentang pembatasan ini, sebagaimana dicermati pada berbagai pertemuan Komite Hak Asasi Manusia PBB8, maka kebebasan berpendapat dapat dilakukan pembatasan, “tetetetapi hanya sebatas sebagaimana ditentukan undang-undang, dan sejauh untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban publik, kesehatan, atau moral masyarakat.” Sementara itu, untuk kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dibatasi atas semua aspek di atas, maupun demi kepentingan melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain. Tetetapi, pembatasan itu harus dicantumkan dalam undang-undang, dan hanya “sejauh diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis.” Walaupun demikian kovenan memiliki suatu pembedaan yang jelas, dan tegas antara kebebasan berpendapat dengan kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi penting untuk diungkapkan, karena argumentasi yang dihasilkannya akan berimplikasi, mengapa Haatzaai Artikelen itu dapat membuka celah dan ruang bagi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Jika hak atas kebebasan berpendapat merupakan hal yang bersifat pribadi dan absolut, tanpa membuka celah untuk paksaan apa pun, sementara kebebasan berekspresi, merupakan hal yang bersifat umum dalam tingkat kepentingan sosial, serta memiliki batasan-batasan yang alami. Pokoknya, ekspresi tersebut dapat menjadi subjek dari larangan-larangan, tetetetapi hanya dalam kerangka prinsip legalitas, yaitu larangan atas kebebasan berekspresi harus diatur dengan undang-undang, memiliki kadar urgensi, juga karena disebabkan untuk tujuan-tujuan umum tertentu dan spesifik.9 Jadi, kebebasan berekspresi ini sebagaimana Paragraf 3 dari Pasal 19 ICCPR mengandung klausul pembatasan, bahwa penerapan dari hak-hak yang diatur dalam paragraf 2 Pasal 19 juga disertai tugas dan tanggung-jawab khusus. Selengkapnya bunyi paragraf 3 Kovenan sebagai berikut: “Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung-jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan tertentu, tetetetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a. menghormati hak dan nama baik orang lain; b. melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum” 8 Komite atau komisi ini dibentuk pada tahun 1946, dengan tugas melakukan pengkajian-pengkajian, mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi dan rancangan instrumen-instrumen internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Komite juga menjalankan tugas-tugas khusus dari Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial, termasuk dugaan-dugaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Komisi ini bekerjasama dengan semua badan PBB yang berwenang di bidang hak asasi manusia. Juga membantu Dewan Ekonomi dan Sosial dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dalam sistem PBB. Komite yang semula terdiri dari 18 anggota, sekarang terdiri dari perwakilan 43 Negara Anggota yang dipilih untuk masa tiga tahun. Beberapa tahun terakhir, Komite Hak Asasi Manusia telah membentuk organ-organ untuk menyelidiki masalah-masalah hak asasi manusia di negara-negara dan wilayah-wilayah, serta untuk tema-tema pelanggaran tertentu. Diantaranya termasuk pencarian fakta oleh para ahli yang terdiri dari pelapor-pelapor khusus (special rapporteurs), perwakilan atau orang-orang yang ditunjuk oleh komite untuk mempelajari situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu. Lihat Pusat Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Centre for Human Rights), Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia: Lembar Fakta (Terjemahan), Komnas HAM dan British Council, 1999, hal. 3-4. 9 Lihat Karl Josef Partsch, “Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik”, di dalam Ifdal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Elsam, Juli 2001, hal. 256ff. 4 Persoalan yang kemudian mengemuka adalah – sebagaimana pengalaman Komite Hak Asasi Manusia PBB – terjadinya perdebatan mengenai tafsir dan interpretasi terhadap poin b ayat 2 Pasal 19 tersebut, karena ini menyangkut hubungan antara negara dengan warganegaranya, serta antara suatu negara dengan negara lainnya. Pada umumnya, kesepakatan yang diambil –sebagai suatu kompromi dan jalan tengah – adalah akses atas rahasia militer, hubungan diplomatik, atau urusan pemerintahan lainnya. Juga menyangkut pelarangan atas material-material pornografi. Jika dikaitkan dengan penerapan Haatzaai Artikelen, maka kontroversi atas pembatasan menjadi relevan untuk dibahas, karena siapakah yang memutuskan apakah sebuah pembatasan dapat dibenarkan? Bukankah ini akan terkait dengan pandangan subjektif siapa yang berkuasa di suatu negara, dalam sistem demokrasi apa pun? Misalkan tentang keamanan nasional, maka Michael HH Low, menyatakan, bahwa pengertian tentang keamanan nasional sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan fisik (intervensi militer) dari luar. Kadar dari keamanan adalah relatif, karena tergantung kepada persepsi elite politik suatu pemerintahan, dan juga harus didasarkan pada pertimbangan objektif dari pandangan dan kemampuan pihak luar. Juga subjektif tergantung kepada karakter elite politik, serta moralitas yang berkembang di masyarakat.10 Dalam konteks Indonesia misalnya, maka terdapat penafsiran terhadap definisi “politik”, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi, human rights defender, juga lembaga yudikatif negara (Mahkamah Agung) sekalipun. Pada berbagai kasus delik politik yang menggunakan pasal-pasal Haatzaai Artikelen sering terjadi perdebatan antara jaksa, pembela, dan hakim apakah seseorang itu dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang menyerang pemerintah, padahal di pihak lain, perbuatannya itu masih dianggap sebagai hak warganegara untuk mengeluarkan pendapatnya yang dijamin oleh konstitusi negara. Permasalahannya adalah sejauh mana seseorang dianggap telah menyebarkan rasa benci, bermusuhan, atau menghina pemerintah. Kapankah seseorang dianggap membenci, bermusuhan atau menghina pemerintah, dan sejauh mana pendapat itu masih dianggap sebagai suatu kritik.11 Meskipun ditandai dengan adanya pembatasan, tetetapi pada prinsipnya tiga kebebasan dasar tersebut, termasuk hak-hak yang terhimpun di dalamnya, dikategorikan sebagai hak-hak negatif (negative rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat minus. Ini jelas bertolakbelakang dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dikategorikan sebagai hak-hak positif (positive rights). Dengan menguraikan tentang pembatasan, serta kategori jenis kebebasan dasar kovenan sipil-politik itu, dimaksudkan untuk meletakkan dan menempatlan posisi Haatzaai Artikelen, sebagai suatu instrumen hukum yang berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Mengacu kepada pasal-pasal ICCPR, maka hak-hak negatif dapat dibagi atas dua klasifikasi.12 Pertama, hak-hak dalam jenis non-derogable, yaitu hak yang bersifat absolut, dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam jenis ini adalah: (1) hak atas hidup (rights to life); (2) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (3) hak 10 Lihat Michael HH Low, Introduction to the National Security Concept, Institute for Strategic Studies University of Pretoria, ISSUP, South Africa, 1977, hal.10-11. 11 Lihat Lobby Loeqman, Delik Politik di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia, Jakarta, IND-HILL-CO, 1993, hal. 7 dan 80. 12 Lihat Ifdhal Kasim, “Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar” di dalam Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan, Jakarta, Juli 2001, xi-xiii. 5 bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (6) hak sebagai subjek hukum; dan (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Kelompok kedua, adalah hak-hak dalam jenis derogable, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini antara lain: (1) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (2) hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; (3) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan dan tulisan). Dari dua jenis klasifikasi tersebut, maka Haatzaai Artikelen itu potensial berbenturan, menegasi, dan mengeliminasi, baik pada jenis non-derogable terutama hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama, maupun pada jenis derogable, yakni pada keseluruhan hak seperti hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi. Jika dikaitkan kepada kedua jenis hak tersebut, pada beberapa kasus penggunaan Haatzaai Artikelen di masa pemerintahan Megawati, maka sudah tampak akibatnya bagi upaya penegakan HAM. Pengadilan atas Ja’far Umar Thalib, Alexander Manuputty, Muhammad Nazar, atau juga dua pemuda aktivis (Nanang Mamija dan Muzakkir), melanggar pasal-pasal ICCPR, baik pada jenis non-derogable (Pasal 18 kovenan), dan jenis derogable (Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 kovenan). Tabel 1 Penggunaan Haatzaai Artikelen Rezim Megawati Soekarnoputri dan Jenis Pelanggaran HAM Menurut ICCPR Nama Tokoh/Aktivis Dakwaan/Pasal Politik Ja’far Umar Thalib (i)Menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia; (ii)Melakukan provokasi, menghasut, dan menghina Presiden/Wakil Presiden; (iii)Menghasut orang supaya melakukan perbuatan pidana (Pasal 134 KUHP; Pasal 134 jo Pasal 136, dan Pasal 160) Melakukan tindak pidana makar (Pasal 106 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Mengkampanyekan separatisme di Aceh (Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, dan Pasal 161 KUHP) Menghina Kepala Negara (Pasal 134 dan 137 KUHP) Alexander Manuputty Muhammad Nazar Nanang Mamija dan Muzakkir Delik Jenis Pelanggaran HAM Menurut Pasal ICCPR Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 Pasal 19 dan Pasal 22 Pasal 19 dan Pasal 22 Sumber: diolah dari berbagai media-massa Dengan menganalisis instrumen-instrumen Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang dikomparasikan kepada pasal-pasal Haatzaai Artikelen menjadi jelas, bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkannya terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia. Tak hanya 6 itu, secara politis, penerapan Haatzaai Artikelen juga berimplikasi kepada proses demokratisasi dan reformasi yang kini menjadi agenda pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Mengapa Haatzaai Artikelen ini menjadi semacam “api dalam sekam” bagi kehidupan demokrasi di suatu negara (termasuk Indonesia), karena hal ini menyangkut filosofi dasar tentang konsepsi keamanan negara dan kejahatan negara. Sementara itu, Haatzaai Artikelen sendiri merupakan jenis pidana atau delik politik dan/atau delik kejahatan keamanan negara. Di sinilah letak persoalannya, jika – dalam definisinya yang paling sederhana sekalipun – demokrasi hendak meletakkan atau menempatkan rakyat dalam posisi sentral pada setiap pengambilan keputusan politik di suatu negara, maka – sebaliknya/bertolak belakang – filosofi dasar delik politik atau keamanan negara yang menjadi landasan berpijak Haatzaai Artikelen adalah rakyat sebagai subordinasi dari kekuasaan negara di mana keamanan negara harus didahulukan ketimbang kepentingan individu. Dengan logika demikian, maka demokrasi menjadi bermakna sejauh mendukung kepentingan-kepentingan ideologi-politik yang diusung suatu negara. Atau juga, HAM menjadi sesuatu yang bisa dinomor-duakan, sementara keamanan negara menjadi sesuatu yang mesti didahulukan. Di sini juga letak seriusnya ancaman Haatzaai Artikelen bagi demokrasi, karena dengan sifat “karet”-nya, dan azas “presumtion of guilty” yang dianutnya, maka pengadilan akan menghukum seorang warganegara yang secara kritis menggugat, mempertanyakan, dan bahkan menolak suatu kebijaksanaan pemerintah yang dinilai tidak demokratis. Dari berbagai pendekatan yang ada, maka untuk menilai ciri hakiki suatu negara demokratis biasanya para ahli ilmu politik menggunakan dua pendekatan, yaitu demokrasi sebagai tujuan, dan kedua, cara penyelenggaraan negara yang memungkinkan terwujudnya negara yang demokratis. Untuk melihat dari perspektif cara penyelenggaraan negara, maka mazhab Schumpeterian – yakni suatu mazhab dari para teoritisi ilmu politik yang melihat pendekatan prosedur dalam demokrasi – bisa menjelaskan tentang posisi sentral rakyat di dalam suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai demokratis. Mazhab ini melihat, bahwa esensi dari karakteristik demokrasi adalah melalui prosedur kelembagaan untuk melakukan perubahan kepemimpinan dengan kompetisi yang bebas (free competition) melalui pilihan rakyat (popular vote).13 Robert A Dahl14 misalnya, yang menggunakan istilah “poliarki” (polyarchy) untuk demokrasi, menyebutkan ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Hal ini bisa dilihat, pertama, seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; kedua, seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Maka, untuk menjamin pemerintah berperilaku demokratis, harus ada kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk: (1) merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan (3) mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. 13 J Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, George Allen and Unwin, London, 1970, p. 269273. 14 Robert A Dahl, Demokrasi dan Para Pengeritiknya (Democracy and Its Critics), diterjemahkan oleh A Rahman Zainuddin, Cet.1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992. 7 Selain dari mazhab Schumpeterian, maka Diamond, Linz, dan Lipset15 memprasyaratkan demokrasi yang dijalankan di suatu negara yang demokratis atas tiga syarat berikut: (1) adanya kompetisi yang meluas antara individu-individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk meraih kekuasaan berdasarkan jangka waktu yang reguler, dan tanpa paksaan; (2) adanya partisipasi politik yang melibatkan partisipasi sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan umum; (3) adanya kebebasan sipil dan politik yang dimanifestasikan melalui kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besarkah bahayanya penggunaan Haatzaai Artikelen tersebut bagi demokrasi di suatu negara, jika menggunakan parameter negara demokratis para pemikir Schumpeterian itu? Jika dimatrikskan, maka akan terlihat penegasian pasal-pasal dari Haatzaai Artikelen sebagai ancaman hukuman terhadap warga negara yang mempergunakan hak-hak sipil dan politiknya sebagai berikut. Tabel 2 Ciri Hakiki Negara Demokratis Schumpetarian vs. Ancaman Delik Politik Haatzaai Artikelen Teoritisi Schumpeterian Prasyarat Demokrasi Penegasian Prasyarat (Hak Politik Rakyat) Demokrasi Melalui Haatzaai Artikelen Robert A Dahl (1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; (2) kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; (3) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif (1) menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154); (2) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 155 ayat 1); (3) menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia (Pasal 156); (4) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia (Pasal 157 ayat 1); (5) penghinaan dengan lisan dan tulisan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207); (6) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum 15 L Diamond, J Linz, and S Lipset (eds), Democracy in Developing Countries, Vol. 3: Asia, Adamantine Press, London, 1989, p. 51ff 8 J. Madison16 (1) hak-hak warganegara yang “equal” , termasuk hak secara langsung untuk mengawasi jalannya pemerintahan; (2) sistem politik yang harus memberi jaminan kepada kaum minoritas untuk memperoleh kesejahteraan, kekuasaan, dan status (Pasal 208 ayat 1); (7) tanpa izin polisi mengadakan keramaian (Pasal 510) Sama dengan di atas, yakni Pasal 154, Pasal 155 ayat 1, Pasal 156, Pasal 157 ayat 1, Pasal 207, Pasal 208 ayat1, Pasal 510 Tabel 3 Ciri Hakiki Negara Demokratis mazhab Demokrasi Liberal vs. Ancaman Delik Politik Haatzaai Artikelen Teoritisi Liberal Demokrasi Prasyarat Demokrasi Penegasian Prasyarat (Hak Politik Rakyat) Demokrasi Melalui Haatzaai Artikelen Diamond, Linz, dan Lipset 1) Kebebasan berbicara, (2) kebebasan pers, (3) kebebasan untuk berorganisasi (1) menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154); (2) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 155 ayat 1); (3) menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia (Pasal 156); (4) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan yang mengandung perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia (Pasal 157 ayat 1); (5) penghinaan dengan lisan dan tulisan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207); (6) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 208 ayat 1); (7) tanpa izin polisi mengadakan keramaian (Pasal 510) 16 Lihat Paul Cammack, Capitalism and Democracy in the Third World: The Doctrine for Political Development, Leicester University Press, London and Washington, 1997, p.20. 9 Dari matriks seperti diperlihatkan oleh tabel tersebut, maka terlihat jelas bahwa prasyarat demokrasi seperti yang diajukan baik oleh para teoritisi Schumpetarian, para teoritisi demokrasi liberal dan/atau demokrasi pluralis lainnya akan menjadi tidak memenuhi syarat, jika produk hukum formal yang eksis di Indonesia masih tetap mengakomodir pasal-pasal karet tersebut. Sebabnya adalah karena pasal-pasal karet itu merupakan manifestasi suatu kondisi dari pemberlakuan konsepsi keamanan negara yang memasukkan konsep “internal subversion”, yakni suatu konsep pengelolaan negara yang menempatkan rakyat dan/atau warga negaranya sebagai musuh negara, karena adanya kecurigaan dari negara bahwa tindakan subversi lebih banyak datang dari dalam negeri. Apakah ia “murni merupakan aspirasi lokal”, ataukah ia merupakan “infiltrasi dari unsur-unsur asing ke dalam negeri”. Menurut sifatnya, kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara dapat dibedakan dalam dua jenis.17 Pertama, pengkhianatan intern (hoogverraad), yaitu kejahatan terhadap bentuk pemerintahan dan bentuk negara. Misalnya pembunuhan terhadap kepala negara, pemberontakan dan sebagainya. Dalam hal ini yang dilanggar adalah keamanan intern negara (inwindige velligheid) atau “internal security”. Kedua, pengkhianatan ekstern (landverraad), yaitu kejahatan keamanan negara dari luar, atau kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi negara sehubungan dengan negara-negara asing. Misalnya perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri (uitwindige veiligheid) atau “external security”, karena berhubungan dengan aspek-aspek yang berada di luar wilayah negara. Karakter Penggunaan dan Korbannya di Masa Reformasi Penerapan Haatzaai Artikelen jelas berimplikasi secara signifikan bagi kehidupan demokrasi, arah reformasi, dan – khususnya – penegakan HAM di Indonesia. Setelah terjadinya semacam jeda di masa pemerintahan Gus Dur, tampaknya pasal-pasal karet tersebut kembali dipergunakan oleh aparat kepolisian di masa pemerintahan Megawati untuk menangkapi dan menjerat mereka yang menyampaikan aspirasi politiknya, melalui aksi-aksi unjuk rasa. Spektrum (luas jangkauan) dan gradasi (tingkatan) orang-orang maupun jenis, bentuk atau ruang lingkup aktivitas yang bisa dimasukkan dan/atau dikategorikan sebagai pantas untuk dijerat dengan pasal-pasal karet itu begitu luas dan beragam. Dari sisi latar belakang ideologi-politik, mereka yang terjerat bisa merupakan aktivis politik beraliran sosialisme (marxis, atau trostkys), juga mereka yang menganut faham fundamentalisme agama, atau bahkan seorang nasionalis kerakyatan. Dari sisi ruang lingkup aktivitas, mereka yang terjerat bisa merupakan akibat dari suatu pemogokan buruh, menulis artikel di media-massa, unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, hingga menyebarkan atau menempelkan pamflet di tempat-tempat keramaian. Dari sisi profesi, status sosial, dan posisi kelas, maka mereka yang dijerat pasalpasal karet tersebut, mulai dari seorang akademisi hingga buruh pabrik, dari seorang wartawan hingga pengamen jalanan, dari seorang human rights defender hingga buruh percetakan, dari seorang politisi partai hingga petani tak bertanah, dan dari seorang mahasiswa hingga office boy sebuah organisasi non-pemerintah. 17 Lihat Oemar Seno Adji, “Delik Politik”, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 1986. 10 Fakta bahwa semenjak Megawati berkuasa telah terjadi sejumlah penangkapan dengan mempergunakan Haatzaai Artikelen sebagai pidana penjeratnya, memang tidak bisa diperbandingkan dengan tindakan serupa yang dilakukan oleh rezim-rezim pemerintahan sebelumnya, baik di masa Soekarno, maupun Soeharto. Sulit, jika mengukur tingkat ancamannya bagi demokrasi dan penegakan HAM atas dasar kuantifikasi rekapitulasi angka-angka korban Haatzaai Artikelen. Soeharto misalnya, mempraktikkan tindakan anti-demokrasi dan HAM itu selama lebih 32 tahun, sementara Megawati baru memerintah belum lagi genap satu tahun. Yang lebih penting adalah, jika melihat implikasi penerapan Haatzaai Artikelen secara esensial dan substansial bagi kehidupan demokrasi, reformasi, dan HAM. Artinya, seberapa besar tingkat kualitatif yang ditimbulkannya bagi nilai-nilai kemanusiaan, jika Haatzaai Artikelen itu tetap dipertahankan oleh suatu rezim yang berkuasa. Meskipun demikian, kuantifikasi rekapitulasi angka-angka pun bisa berbicara jujur tentang penggunaan Haatzaai Artikelen ini di masa rezim Megawati. Tabel 4 Perbandingan Rekapitulasi Angka Korban Haatzaai Artikelen dan/atau Pidana Politik Rezim Soeharto dan Rezim Megawati Soekarnoputri Nama Rezim Jumlah Korban Haatzaai Keterangan Persebaran Artikelen18 Korban (Wilayah, Golongan, dan lain-lain) Rezim Soeharto 378 orang19 Rezim Megawati Soekarnoputri 244 orang20 (1)Aceh dan Lampung 78 orang; (2)Irian Jaya/Papua 44 orang; (3)Jakarta, NTB, Jabar, dan Wilayah lain 71 orang; (4)Mahasiswa/Pemuda: -Peristiwa Malari (1974) 37 orang; -ITB (1989) 6 orang; -Golput Semarang (1992) 2 orang; -Front Aksi Mahasiswa Indonesia (1989) 21 orang; -Buku Pramoedya (UGM, 1989) 3 orang; -Kasus Partai Rakyat Demokratik (1996) 14 orang; -Kasus striker SDSB 1 orang (5)Tanjung Priok (1984) 45 orang; (6)Timor Timur 18 orang; (7)Buruh (Medan dan Pematang Siantar, 1994) 38 orang (1)Maluku (Front Kedaulatan Maluku dan Front Pembela 18 Baik yang sudah divonis, disidangkan, atau dijerat Haatzaai Artikelen, tapi kemudian tuntutannya dibatalkan. 19 Jika bukan sebagai dakwaan primair, maka sebagai dakwaan subsidair, biasanya pasal-pasal Haatzaai Artikelen disandingkan dengan UU Subversi. 20 Biasanya disandingkan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Belum termasuk 84 orang mahasiswa anti-Golkar, yang ditahan karena dituduh masuk ke pekarangan kantor partai tanpa izin. 11 Islam) 8 orang; (2)Mahasiswa dan Pemuda: -Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi 49 orang; -Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 20 orang; -Berbagai elemen 47 orang; -Universitas Muslim Indonesia Makassar 15 orang; -Mahasiswa IKIP PGRI Jember 27 orang; -Gerakan Pemuda Kerakyatan 4 orang; -IISIP 15 orang; -PRD 1 orang; -Komunike Bersama 1 orang; (3)Aceh 4 orang; (4)Buruh (FNPBI dan lainnya) 52 orang; (5)FPI (Habib Rizieq Shihab) 1 orang Sumber: diolah dari berbagai media-massa Sebagai suatu angka statistik, maka banyaknya jumlah orang yang menjadi korban di masa rezim Megawati ini, yang dijerat dengan pasal-pasal pidana politik dan Haatzaai Artikelen khususnya, dan produk hukum yang terkait dengan keamanan negara umumnya bisa melahirkan sejumlah pertanyaan tentang kecenderungan arah pemerintahan yang semakin otoritarian. Jadi, jika setahun dihitung 365 hari – meskipun saat tulisan ini dikerjakan Megawati belum lagi genap setahun berkuasa – maka setiap 1,5 hari terjadi penangkapan terhadap seorang warganegara yang dijerat dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen atau pun dengan undang-undang yang terkait lainnya. Jumlah orang yang dijerat Haatzaai Artikelen, pasal-pasal pidana politik, dan produk hukum tentang keamanan negara dengan pendekatan kuantifikasinya, memang bisa menjadi penilaian (assesment) tersendiri terhadap arah kecenderungan pemerintahan Megawati dalam mengelola negara ini. Tetetapi, di lain pihak, kita pun menyaksikan kembali dipergunakannya pola-pola atau metode penangkapan terhadap warganegara yang disangkakan melakukan pelanggaran pidana politik, yang mengingatkan kita pada masa otoritarianisme rezim Soeharto dahulu. Meskipun sebagian ditangkap pada saat berdemonstrasi, tetetapi sebagian lainnya ditangkap setelah demonstrasi selesai. Bisa malam harinya, keesokan hari, atau beberapa hari kemudian. Iqbal Siregar, aktivis Gerakan Pemuda Islam (GPI), yang melakukan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, disatroni aparat, ditangkap menjelang tengah malam di rumahnya. Ia ditangkap dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap presiden karena kedapatan meMegawating potret wajah Megawati yang diberi tanda silang dengan lakban warna hitam.21 Pola penangkapan sejenis juga dialami Nanang Mamija dan Muzakkir, dua aktivis Gerakan Pemuda Kerakyatan. Empat hari setelah berdemonstrasi, Muzakkir, yang juga seorang pengamen itu disergap aparat polisi di perempatan jalan di kawasan Galur, Jakarta Pusat ketika sedang menjalankan profesinya tersebut. Sehari kemudian, Nanang diciduk saat sedang tidur di rumah orang tuanya di kawasan Cileduk, Tangerang. Keduanya 21 P Bambang Wisudo dan Windoro AT, “Penjara Buat Para Aktivis Politik”, Kompas, 1 Maret 2003. 12 divonis satu tahun penjara olen Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena terbukti melakukan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Memang dalam aksi 14 Juni 2002, kedua pemuda itu melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan foto Megawati-Hamzah sebagai lakon. Pada akhir lakon, foto itu dinjak-injak lantas ditaburi nasi dan lauk basi. Aksi ini berakhir dengan tertib dan tanpa insiden. Ternyata hal ini berbuntut panjang. Persoalannya menjadi mencuat ketika Jacob Nuwa Wea, kader PDI Perjuangan yang juga Menteri Tenaga Kerja itu bereaksi keras atas cara kedua pemuda itu menyampaikan aspirasinya. Bahkan Megawati yang marah mengancam akan mencabut ke-WNI-an para demonstran.22 Tampaknya aksi menyobek, menginjak, dan membakar potret atau boneka kepala negara sudah menjadi ritual yang selama ini biasa dilakukan demonstran dan disaksikan masyarakat di layar televisi. Jika pada masa Habibie, dan Gus Dur, situasi ini berlalu begitu saja23, maka situasi yang berbeda terjadi pada masa Megawati. Tiba-tiba foto Presiden menjadi demikian penting, dan bisa membenarkan aparat untuk mencabut kebebasan seseorang atas dasar pasal-pasal penyebaran kebencian. Sakralisasi gambar wajah Megawati ini segera memakan banyak korban terutama kalangan mahasiswa di berbagai daerah. Selain Muzakkir, dan Nanang, maka terjadi hal serupa di berbagai kota, Jakarta, Surabaya, dan Banda Aceh, dimana para mahasiswa itu dijerat dengan delik penghinaan/penyebaran kebencian. Tetetapi bukan hanya penghinaan terhadap kepala negara saja yang dipakai aparat untuk menjerat aktivis. Polisi juga menggunakan pasal-pasal dalam UU Nomor 9 Tahun 1999 berkaitan dengan penyelenggaraan aksi unjuk rasa tanpa izin, pelanggaran ketertiban umum Pasal 156 KUHP, Pasal 154 dan 160 KUHP tentang penghasutan, atau Pasal 214 dan 218 soal tindakan menyerang petugas. Gelombang demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), telepon, dan tarif dasar listrik (TDL) pada awal tahun 2003 juga membawa korban dengan dijeratnya para aktivis mahasiswa-pemuda dengan pasal-pasal haatzaai artikelen. Ign Mahendra, dan Yoyok didakwa telah melakukan penghinaan terhadap kepala negara, yakni presiden dan wakil presiden saat melakukan aksi demo menuntut penurunan BBM, TDL, dan telepon di Bunderan UGM, Jl. Cik Di Tiro pada tanggal 17 Januari 2003. Mereka didakwa telah melakukan pembakaran foto presiden dan wakil presiden. Perbuatan ini oleh jaksa diartikan telah menyerang kehormatan dan nama baik seorang kepala negara. Keduanya diancam dengan Pasal 134 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.24 Selain terhadap mahasiswa dan pemuda, maka rezim Megawati juga menggunakan pasal-pasal karet ini untuk meredam unjuk rasa kaum buruh. Pada 24 September 2002, sebanyak 2000 buruh berdemonstrasi di Cimahi, Jawa Barat menuntut kenaikan upah buruh 100 persen, menolak pemutusan hubungan kerja, menolak Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) beserta revisinya, dan juga UU No. 25/1997. Buntut dari demonstrasi itu, sebanyak 32 buruh ditangkap, serta dinyatakan bersalah melanggar Pasal 510 KUHP, yakni berdemonstrasi tanpa meminta izin kepada aparat keamanan.25 Di Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung, aksi unjuk rasa yang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian terjadi pada 13-14 Juni 2002, yang mengakibatkan sebanyak 20 22 Lihat “Menghina Mega, Memenjarakan Tapol,” Kompas, 31 Agustus 2002. Pernah terjadi, ratusan foto Gus Dur dikubur oleh para mahasiswa Makassar. Gus Dur tenang-tenang saja, jangankan memerintahkan menangkap pelakunya, untuk memberangus aksi-aksi itu pun ia tak tergoda. Ibid. 24 “Dihadiri Massa PDIP, Pembakar Foto Mega Disidang”, detik.com, 26 Pebruari 2003. 25 “Ribuan Buruh Berdemonstrasi: 32 Orang Ditangkap di Cimahi”, Kompas, 25 September 2002. 23 13 buruh anggota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) ditahan dengan tuduhan menghasut, karena menghimpun buruh dan menyebarkan pamflet mengajak buruh bergerak menentang tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang akan mempermudah pemecatan buruh oleh pihak pemilik perusahaan.26 Mahasiswa, pemuda, buruh, dan aktivis organisasi non-pemerintah menjadi target utama untuk dijerat dengan Haatzaai Artikelen, sebagai konsekuensi yang akan dihadapi mereka yang menggunakan hak-hak sipil dan politiknya. Lalu bagaimana pemerintah dalam hal ini aparat keamanan- mempersepsikan pasal-pasal karet tersebut pada daerahdaerah konflik? Tidak bisa dipungkiri, bahwa angin kebebasan yang dihembuskan oleh euforia reformasi menghantarkan semangat “perlawanan” daerah-daerah yang selama ini merasa dimarginalkan secara ekonomi dan politik oleh pemerintah pusat. Setelah lebih 32 tahun sepertinya tak memiliki ruang gerak untuk mengartikulasikan diri, sekonyong-konyong banyak elite politik daerah yang menyuarakan hak-hak daerah mereka, bahkan jika perlu dengan tuntutan maksimal melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).27 Ternyata persoalan daerah seperti magma tersumbat sebuah gunung berapi, dimana selama puluhan tahun kebijakan pembangunan yang tidak adil itu tidak dicari jalan ke luarnya atau akar masalahnya dengan melihat persoalan secara menyeluruh (holistik dan multidimensional), tetetapi justru dengan pendekatan represif (militeristik dan bersandar pada hukum positif semata), yaitu melalui penerapan UU Subversi No.11/PNPS/1963, serta –last but not least – pasal-pasal haatzaai artikelen. Dalam kasus kerusuhan sosial di Maluku sejak tahun 1999 yang telah memakan korban lebih 3000 jiwa itu, pemerintah pusat seolah-olah mencari jalan pintas dan “mencari kambing hitam” dengan memidana tokoh-tokoh yang dianggap memperkeruh atau memanas-manasi situasi. Panglima Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib meskipun akhirnya dinyatakan tak besalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi sempat mendekam di penjara, karena didakwa menyatakan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, dan juga melakukan provokasi, menghasut, dan menghina Presiden dan Wakil Presiden, serta menghasut orang supaya melakukan perbuatan pidana. Ia dituduh melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP pada dakwaan pertama; Pasal 134 jo Pasal 136 pada dakwaan kedua; dan Pasal 160 KUHP pada dakwaan ketiga, karena pidatonya di Masjid Al Fatah, Ambon, Maluku pada 26 April 2002.28 Sementara itu, Pimpinan Eksekutif Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alexander Hermanus Manuputty dan Pimpinan Yudikatif FKM Samuel Waeleruny divonis 3 tahun penjara oleh hakim PN Jakarta Utara, karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kedua orang itu dipersalahkan karena mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di markas RMS di Ambon.29 Alex sendiri menolak hukuman dan tuduhan yang ditujukan terhadap dirinya. Ia menilai, pengadilan hanya menyoroti peristiwa 26 Kompas, 15 Juni 2002. Selain di Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, dan Papua, maka wacana tentang selfdetermination juga muncul di Provinsi Riau yang kaya sumber daya alam mineral. Di Riau, salah seorang pelopornya adalah Letjen (Purn) Syarwan Hamid, seorang militer loyalis Soeharto yang diduga tersangkut pada beberapa kasus pelanggaran HAM seperti misalnya Peristiwa 27 Juli 1996. 28 “Ja’far Umar Thalib Divonis Bebas”, Kompas, 31 Januari 2003. 29 “Manuputty Divonis 3 Tahun”, Kompas, 29 Januari 2003. 27 14 kelahiran RMS di masa lalu, dan mengenai aktivitasnya, ia melakukan penelitian yang tak membahayakan keselamatan orang lain.30 Di Papua, menyusul kerusuhan di Wamena yang menewaskan 11 penduduk setempat akibat tembakan aparat keamanan, serta 19 orang pendatang pada 9 Oktober 2000, sebanyak lima orang aktivis politik, serta 16 orang anggota milisi pro-kemerdekaan, Satgas Papua ditahan dan dikenai tuduhan pasal-pasal haatzaai artikelen, serta Pasal 2 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1963 tentang Keadaan Darurat.31 Kelima aktivis tersebut adalah Pendeta (Pdt) Obed Komba, Pdt Yudas Meage, Yafet Yelemagen, Murjono Murib, dan Amelia Yigibalom. Meskipun para saksi mata menyebutkan, kelimanya sama sekali tidak terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi, dan bahkan melakukan upaya-upaya untuk meredam massa yang beringas, tetapi aparat keamanan tetap menjatuhkan dakwaan atas pasal-pasal 106 KUHP tentang perbuatan yang mendukung separatisme; pasal 110 KUHP tentang turut serta dalam perbuatan yang mendukung separatisme; pasal 154 KUHP tentang menyebarkan rasa permusuhan; kebencian, dan penghinaan kepada pemerintah yang sah; pasal 155 KUHP tentang menyebarkan rasa kebencian di antara masyarakat melalui media; pasal 160 KUHP tentang mempengaruhi masyarakat untuk membangkang pemerintah atau melawan hukum; serta pasal 169 KUHP tentang ikut serta dalam organisasi yang menganjurkan perbuatan melawan hukum.32 Sementara itu, dari 16 anggota Satgas Papua, 15 orang di antaranya dikenai dakwaan atas UU Keadaan Darurat, serta Pasal 214 KUHP, yakni memiliki senjata api secara gelap. Seorang lainnya, Sudirman Pagawak didakwa atas Pasal 160 KUHP, dan Pasal 192 KUHP tentang merusak fasilitas publik.33 Tak hanya para aktivis di Papua yang dikenai pasal-pasal karet, di Jakarta pun, sebanyak 4 aktivis Papua ditahan dan dikenai Pasal 106, 110, dan 154 KUHP sebagai buntut dari demonstrasi 300 orang Papua, yang menuntut kemerdekaan di Kedutaan Besar Belanda pada 1 Desember 2000. Keadaan yang serupa terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dimana pemerintah pusat dalam upaya meredam pikiran-pikiran kritis dan tuntutan politik masyarakat Aceh atas hak-hak mereka, menangkap serta menjatuhkan dakwaan pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Muhammad Nazar, Ketua Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) salah satu korbannya. Karena mengorganisir rencana Unjuk Rasa Untuk Perdamaian (“Mass Rally for Peace”) yang diprediksi akan diikuti ribuan rakyat NAD pada 11 November 2000, Nazar ditangkap polisi atas tuduhan sebagai orang yang selalu mengkampanyekan separatisme di Aceh. Nazar pun didakwa atas pasal-pasal 154, 155, 160, dan 161 KUHP. Ia diadili pada Pebruari 2001.34 Selain Nazar, pasal ini juga menjerat Reihana Diani, aktivis Organisasi Perempuan Demokratik Aceh, yang ditangkap bersama enam aktivis lainnya dalam aksi menuntut Megawati-Hamzah mundur, serta menyerukan kemerdekaan untuk Aceh. Ia diajukan ke pengadilan dengan dakwaan menghina kepala negara dan divonis enam bulan penjara, hanya beberapa saat setelah pemerintah RI dan GAM menandatangani kesepakatan penghentian permusuhan di Geneva (Swiss) 9 Desember 2002. 30 Lihat “Dituntut Lima Tahun Penjara”, di dalam http://www.TokohIndonesia.com Lihat Amnesty International, Briefing on the Current Human Rights Situation in Indonesia, 31 Januari 2001, hal. 2 dan 7. 32 Ibid, hal.8 33 Ibid, hal.7 34 Ibid, hal.6. 31 15 Dari berbagai contoh kasus penerapan Haatzaai Artikelen di masa reformasi ini, tampak jelas belum berubahnya sifat, watak, dan karakter aparat keamanan di dalam mempersepsikan aktivitas warganegara untuk mengaktualisasikan hak-hak sipil dan politiknya. Pendekatan yang dipergunakan masih belum beranjak dari model pendekatan represif dan militeristik seperti yang diterapkan pada masa rezim otoriter Soeharto. Pemerintahan Megawati bersikap ambigu terhadap persoalan ini. Di satu sisi, aparat keamanan sepertinya bersikap “reformis” dengan memberi ruang berekspresi bagi warga negara untuk berunjuk-rasa pada berbagai kasus yang tidak menyentuh atau menghujam ke masalah posisi dan kedudukan kekuasan elite politik seperti aksi unjuk rasa menentang invasi AS ke Irak. Tetetapi di sisi lain, aparat keamanan sepertinya cepat bereaksi ketika aksi unjuk rasa tersebut, sudah menyentuh atau menghujam ke wilayah yang terkait dengan persoalan suksesi kepemimpinan nasional ataupun memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Harus Ditiadakan Jika Haatzaai Artikelen ini sesungguhnya sangat berbahaya untuk kehidupan demokrasi, keberlangsungan reformasi, dan penegakan HAM, ini artinya keberadaannya tidak memiliki legitimasi untuk dipertahankan. Baik secara historis-filosofis, historis-juridis, maupun historis-politis. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan oleh segenap komponen bangsa untuk memutuskan mata-rantai dengan produk hukum yang potensial bagi terjadinya praktek-praktek pelanggaran HAM tersebut? Untuk menjawabnya, maka ada baiknya terlebih dahulu kita membedah untuk kemudian mematahkan dalil-dalil serta argumen yang sebelumnya menjadi dasar legitimasi dicantumkan, dan digunakannya pasal-pasal karet tersebut di dalam KUHP. Pasal-pasal penyebar kebencian itu hingga kini belum dicabut, bahkan tetap diakomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)35 yang kini masih diagendakan di DPR. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengkritisi keberadaan pasal-pasal itu di dalam sistem hukum nasional kita. Secara historis, maka sudah jelas bahwa motif mengapa haatzaai artikelen ini tetap dipertahankan keberadaannya, adalah sebagai upaya rezim pada suatu masa pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaannya. Rezim yang berkuasa, baik pada masa kolonial maupun pasca kolonial, selalu berusaha meredam dan mencoba untuk menyelesaikan suatu konflik politik melalui penggunaan delik politik yang diakomodasi pada sistem hukum nasional. Sesungguhnya haatzaai artikelen ini tidak memiliki legitimasi sama sekali untuk dipertahankan. Baik secara historis-filosofis, historis-juridis, maupun historis-politis. Dari aspek historis-filosofis36 misalnya, haatzaai artikelen ini dicangkokkan kepada KUHP pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905, dari British Indian Penal Code yakni ketentuan pidana yang berlaku di India sewaktu dijajah Inggris. Padahal upaya untuk memasukkan materi tersebut kepada KUHP Belanda sendiri ditolak oleh partaipartai politik, dan Parlemen Negeri Belanda karena dianggap melanggar hak-hak asasi warga negara Belanda. Landasan filosofisnya mengapa pasal-pasal itu tetap diberlakukan, karena dinilai pantas untuk diterapkan hanya bagi penduduk negeri jajahan. Bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, sifat delik haatzaai artikelen ini diubah dari yang asli menjadi sangat mematikan. Pada materi aslinya, haatzaai artikelen 35 Periksa kembali Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor…Tahun…Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundangundangan 1999-2000. 36 Lihat RH Siregar,”Indonesia Masih Dijajah Belanda”, Suara Pembaruan, 27 Juni 2002. 16 membebankan kepada penyidik untuk membuktikan terlebih dahulu telah terjadi perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah, menjadi sebaliknya, yakni tak ada keharusan bagi penyidik untuk membuktikan perasaan tersebut. Dari aspek historis-juridis dan historis-politis, maka haatzaai artikelen ini tidak layak untuk diterapkan, karena sulit untuk merumuskan delik politik akibat sulitnya mencari definisi yang universal tentang politik. Delik politik merupakan istilah sosiologis, bukan istilah juridis. Akibatnya dalam sejarah hukum, pada sistem hukum yang berlaku pada suatu masa, di suatu negara manapun, tidak pernah diketemukan suatu kesatuan pendapat tentang substansi delik politik. Padahal asas dalam hukum pidana menghendaki kejelasan yang mempunyai sifat limitatif, untuk mencegah terjadinya multi-tafsir. Mengutip Remmelink, Lobby Loeqman37 menjelaskan, perlunya dibedakan antara perbuatan politik dengan kejahatan politik. Perbandingan antara keduanya, akan memperlihatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk menimbulkan kekacauan dengan suatu tujuan mengacaukan negara, akan tetetetapi melakukan suatu perbuatan kritik yang melanggar undang-undang dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat dengan medium ekspresinya seperti demonstrasi, petisi, aksi protes, dan sebagainya. Pelaku delik politik dengan penuh kesadaran berkeyakinan, bahwa dirinya beritikad baik telah melakukan suatu perbuatan yang menurutnya tidak bertentangan dengan tertib masyarakat. Bahkan perbuatannya adalah demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja –sebagai konsekuensinya – akan diikuti dengan suatu peristiwa kekerasan. Bagi seseorang yang ingin melakukan kritik terhadap suatu kebijakan pemerintah, tidaklah secara otomatis dianggap sebagai ingin melakukan kekacauan di bidang ketatanegaraan, akan tetetetapi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah. Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa38, maka untuk memahami sikap beberapa negara atas pemberlakukan delik politik dibedakan atas empat teori. Dalam konteks Indonesia, maka haatzaai artikelen melihat kepada pengaturannya yang ada di dalam KUHP, termasuk dalam teori objektif, atau teori absolut, yaitu delik politik yang ditujukan terhadap negara dan lembaga-lembaga negara. Sedangkan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang subversi (UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi), termasuk dalam klasifikasi teori subjektif, yaitu pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan dengan berlatar-belakang atau bertujuan politik adalah suatu delik politik. Rumusan tentang delik politik memang sangat beragam, dan berbeda-beda. Biasanya, karena sistem otoriter dan represif dari negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, seseorang yang bisa dipidana politik selalu dikaitkan dengan aktivitasnya sebagai aktivis politik, atau oposan pemerintah. Padahal beberapa teori hukum juga menegaskan, bahwa seseorang, kelompok, atau golongan yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana politik39 bukan hanya tehadap warga negara, tetetapi juga 37 Lihat Lobby Loeqman, “Penyelesaian Konflik Politik: Tinjauan Historis-Filosofis dan Praktis Pemanfaatan Peradilan Sebagai Wahana”, di dalam http://www.geocities.com/RainForest/vines/3367/lukman.html 38 Ibid , seperti dikutip Lobby Loeqman dari Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht, Tjeenk Willink Alphen a/d Rijn, 1984 39 Sue Titus Reid memberi rumusan demikian untuk tindak pidana politik: “…Political crimes are those that challenge the authority of the state and, particularly, its monopoly on the use of force. “Lebih jauh Reid menambahkan, bahwa seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial, dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana politik, dan mungkin diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mempertahankan struktur atau hukum tertentu yang diberlakukan karena alasan politis. Lihat Sue Titus Reid, Crime and Criminology, 9th edition, McGraw and Hill Companies, 2000, hal. 256ff. 17 terhadap pejabat pemerintah yang dinilai melakukan –dalam istilah Hugh Barlow40 – korupsi politik (political corruption) dalam bentuk, pertama, kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan uang; kedua, kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan politik kelompok tertentu. Jadi, dalam konteks Indonesia, jika dipergunakan definisi Barlow, seseorang atau mereka yang dapat dikenakan delik atau pidana politik, semestinya bukan hanya diberlakukan terhadap mereka yang berpikir kritis untuk mengeritik pemerintah, tetetapi juga terhadap pejabat publik atau pegawai negeri yang dapat dikategorikan melakukan korupsi dan kolusi, serta juga terhadap politisi yang –misalnya – melakukan suatu caracara untuk memperoleh dana-dana pemilihan umum secara tidak sah. Argumentasinya, bahwa korupsi dan kolusi yang dilakukan birokrat maupun politisi itu jelas dampaknya merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, definisi kejahatan politik tidak semata “suatu perbuatan yang menjurus kriminal akibat adanya ancaman terhadap negara dan stabilitas politik pada khususnya” (an action considered criminal because it represent a threat to the state or its political stability), tetetapi lebih luas lagi menyangkut “tingkah laku para birokrat dan pejabat publik” (behaviour of the office holders), termasuk di dalamnya “para penegak hukum” (law enforcement agents). Oleh sebab itu, definisi kejahatan politik yang terdapat dalam KUHP sekarang ini menafsirkan pelakunya hanya anggota masyarakat saja, padahal sesungguhnya si peMegawating kekuasaan, yaitu mereka yang mempunyai jabatan tertentu, dapat pula dituduh melakukan kejahatan politik, karena berusaha mempertahankan suatu orde pemerintahan tertentu, dan kemudian melanggar hukum yang telah diputuskan sebelumnya. Contohnya adalah kekerasan yang dilakukan polisi (police brutality), pengabaian terhadap kebebasan berbicara (denial of free speech), pencegahan kemerdekaan berserikat (restriction of free assembly), dan seterusnya.41 Jika definisi Barlow yang disepakati, maka tindak pidana politik patut pula dikenakan kepada para elite politik dan elite ekonomi yang tidak mengindahkan asas kedaulatan rakyat. Dengan mengutip Barlow dan Reid, terlihat adanya upaya peng-antitesa-an terhadap cara pandang selama ini, yang melihat delik politik atau delik keamanan negara dari perspektif kekuasaan menjadi ke perspektif rakyat sebagai peMegawating tertinggi kedaulatan pada suatu negara demokrasi. Semangat yang bisa dianalisis dari perspektif Barlow dan Reid, bahwa keselamatan dan keamanan negara justru terancam oleh praktekpraktek penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan para birokrat maupun elite ekonomi. Persoalannya sekarang, bahwa tetap dipertahankannya pasal-pasal karet di dalam KUHP, dan bahkan masih “muncul” di dalam RUU KUHP di era reformasi yang “konon” sebagai representasi suatu pemerintahan sipil-demokratis, seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak –akademisi, human rights defender, aktivis pro-demokrasi, politisi parpol, hingga birokrat dan teknokrat pemerintah yang kritis – untuk bersama-sama memperjuangkan hapusnya Haatzaai Artikelen dari hukum positif di negara ini. 40 Demikian rumusan Hugh Barlow: “…We speak of political corruption when officer-holder in government and politics violate the laws regulating their official conduct so as to benefit themselves or specific others, or use the power and influence associated with their office to induce others to commite crimes…We may encounter political corruption at city, county, state, and federal levels of the political process…Lihat Hugh D Barlow and David Kauzlarich, Introduction to Criminology, 8th edition, Upper Saddle River, Prentice-Hall, New Jersey, 2002, hal. 258ff 41 Lihat Irawan Saptono dan Togi Simanjuntak, Politik Pembebasan Tapol, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 26-27. 18 Sebagai suatu pasal yang dicangkokkan ke dalam KUHP kolonial dari British Indian Penal Code, semestinya haatzaai artikelen itu menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena lima sebab berikut ini. Pertama, dasar argumentasi yang dipakai untuk mempergunakannya adalah untuk kepentingan penjajahan negara-negara kolonial terhadap negara-negara terjajah. Dengan sistem monarki yang dianut pada sebagian negara Eropa pada abad ke-18/19, yang menuntut kepatuhan mutlak dan absolut kepada Raja/Ratu-nya. Kedua, karena sifat karet dan subjektif yang melekat pada pasal-pasal tersebut secara filosofis bertolak-belakang dengan azas yang dianut pada hukum pidana pada abad ke-20 ini, yaitu mempunyai kejelasan yang bersifat limitatif. Ketiga, pasal-pasal ini pun tidak sesuai lagi dengan semangat yang berkembang di antara bangsa-bangsa di dunia, terutama menyangkut atau yang berhubungan dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi, yang tercantum pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,42 sebagai suatu hak dasar yang ‘menjiwai’ hakhak sipil-politik lainnya. Keempat, jika tetap dipertahankan, maka pasal-pasal karet ini bisa mereduksi dan bahkan mengeliminasi (dalam prakteknya) penghargaan dan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana tercantum pada konstitusi negara RI, yaitu Amandemen kedua UUD 1945 Bab XA Pasal 28A hingga 28 J. Kelima, jika pun “terpaksa” untuk tetap diberlakukan, sebagai suatu alternatif, maka pasal-pasal delik kejahatan politik atau delik keamanan negara itu dicantumkan atau dimasukkan ke dalam KUHP, tetetetapi dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, demi untuk mendukung penegakan HAM, keberlangsungan reformasi, dan proses demokratisasi maka pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang masih terdapat pada KUHP harus dicabut. Sebagai suatu jurisprudensi, hal ini pernah dilakukan pada tahun 1946, pada saat republik masih berusia muda, dimana pemerintah kala itu mencabut pasal 153 bis dan 161 bis dari KUHP.43 Saat itu, pemerintah melakukan perubahan secara parsial, seperti juga yang dilakukan terhadap Pasal 171 KUHP dengan menggantinya melalui Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946. Berdasarkan pengalaman itu, maka sebaiknya elite politik di legislatif dan eksekutif tidak perlu berpikir muluk-muluk untuk membuat RUU KUHP secara seutuhnya, melainkan mengingat situasi dan kondisi serta urgensinya, maka penyempurnaan sebaiknya dilakukan parsial. Yaitu beberapa pasal yang dinilai sangat mendesak untuk diubah, dijadikan prioritas untuk ditangani. Sebaiknya cara seperti itulah yang ditempuh, apabila penciptaan KUHP nasional seutuhnya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. (*) 42 Pasal 19 DUHAM berbunyi, “Setiap orang memiliki hak bagi kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran; hak tersebut termasuk kebebasan untuk memiliki pandangan tertentu tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan meneruskan informasi dan gagasan melalui sarana apapun dan tanpa batas.” 43 Pasal 153 bis dan 161 bis merupakan pasal-pasal yang paling sering dipergunakan pemerintah kolonial untuk menjerat para tokoh pergerakan nasional. Pasal-pasal ini dipergunakan bagi mereka yang disebut sebagai penghasut atau pemberontak, dengan disertai exorbitante rechten atau hak-hak luar biasa dari gubernur jenderal untuk menggunakannya. Soekarno pada saat disidang pada 18 Agustus hingga 22 Desember 1930 di Bandung juga dikenakan pasal-pasal tersebut. Lihat Ir. Sukarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung, 1930, Haji Masagung, Jakarta, 1989. 19