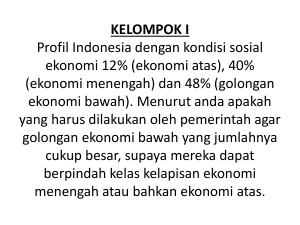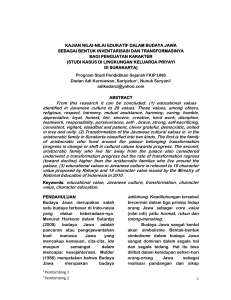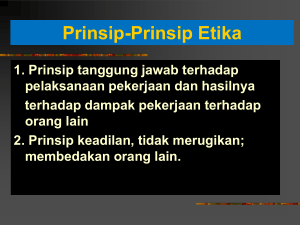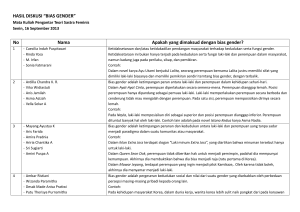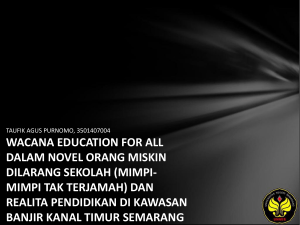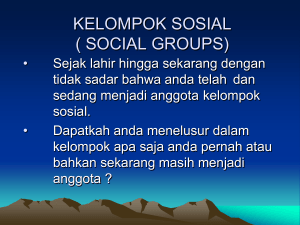teori interaksi simmel dalam novel para priyayi
advertisement

TEORI INTERAKSI SIMMEL DALAM NOVEL PARA PRIYAYI KARYA UMAR KAYAM DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Oleh Agnis Afriani NIM. 109013000099 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 ABSTRAK Agnis Afriani NIM. 109013000099. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi, “Teori Interaksi Simmel dalam Novel Para Priyayi karya Umar Kayam dan Implikasinya pada Pembelajaran Sastra di Sekolah.” Pembimbing: Novi Diah Haryanti, M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori interaksi dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam dan implikasinya pada pembelajaran sastra di sekolah. Hasil penelitian mendeskripsikan nilai-nilai sosial melalui interaksi sosial antara individu, keluarga, masyarakat, dan Negara. Nilai-nilai sosial, seperti nilai kepedulian, nilai kerukunan, nilai pengayoman, nilai ketuhanan, nilai keikhlasan, nilai kasih sayang, nilai kesopanan, nilai kebersamaan, nilai keakraban, nilai kebiasaan, dan nilai pengabdian terdapat pada kalimat-kalimat dalam dialog atau cerita para tokoh melalui interaksi sosial antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam relasi-relasi yang terbagi menjadi enam kategori, yaitu 1) relasi individu dengan dirinya, 2) relasi individu dengan keluarga, 3) relasi individu dengan lembaga, 4) relasi individu dengan komunitas, 5) relasi individu dengan masyarakat, dan 6) relasi individu dengan nasion. Pembahasan dan analisis penelitian novel Para Priyayi dapat diimplikasikan pada pembelajaran sastra di sekolah untuk materi menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia agar peserta didik dapat membangun karakter kritis, kreatif, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, melalui pemahaman tentang tokoh dan penokohan serta latar sosial. Peserta didik juga dapat belajar mengenai bagaimana harus bersikap, memilih jalan hidup, dan semangat mencapai cita-cita. Semuanya terdapat dalam kehidupan melalui interaksi sosial dengan menjalin relasi melalui sosialisasi antara individu dengan individu, keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat, dan Negara. Kata Kunci: Nilai-nilai, Novel Para Priyayi, Relasi, Interaksi. i ABSTRACT Agnis Afriani NIM. 109013000099. Department of Language and Literature Education of Indonesia. Faculty of Tarbiyah and Teaching. State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta. Thesis title, “Simmel’s Theory of Interaction in the Novel Para Priyayi by Umar Kayam and Implications on Literature Learning in Schools.” The advisor: Diah Novi Haryanti, M.Hum. This study aimed to describe the social values in the novel Para Priyayi by Umar Kayam and implications on teaching literature in Schools. The results of the study describes the social values through social interaction between individuals, families, communities, and country. Social values, such asconcern value, the value of harmony, the value of security, the value of the deity, the value of sincerity, the value of compassion, modesty value, the value of togetherness, closeness values, customs value, and the value of devotion found in the sentences in the dialogue or story figures through social interaction between individuals, families, and communities in relationships that are divided into six categories, namely 1) the relation of individual with himself, 2) the relation of individual with family, 3) the relation of individuals with institutions, 4) the relation of individuals with the community, 5) the relation of individuals with the community, and 6) the relation of individuals with the nation. Discussion and research analysis can be implied novel Para Priyayi literature on learning in school to analyze the material elements of intrinsic and extrinsic Indonesian novel so that learners can build a critical character, creative, whether cognitive, affective, and psychomotor, through an understanding of the character and characterization as well as the background social. Learners can also learn about how to behave, choose a way of life, and the spirit of achieving goals. Everything is there in life through social interaction by building relationships through socialization among individuals with individuals, families, institutions, communities, society, and country. Keywords: Values, Novel Para Priyayi, Relation, Interaction. ii KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Teori Interaksi Simmel dalam Novel Para Priyayi Karya Umar Kayam dan Implikasinya pada Pembelajaran Sastra di Sekolah”. Rasa syukur kepada Allah dan Nabi Muhammad yang tak terhingga. Penulis bersyukur karena akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sungguh sebuah kerja keras yang luar biasa ditengah berbagai macam kendala yang penulis hadapi. Akan tetapi, berkat rahmat Allah dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya karya ilmiah yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan ini dapat diselesaikan. Maka sudah seharusnya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Nurlena Rifa’i, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2. Dra. Mahmudah Fitriyah Z.A., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus Penasihat Akademik Kelas C yang baik hati, bersahaja, dan selalu ringan tangan terhadap mahasiswa. 3. Novi Diah Haryanti, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat mengayomi, sabar, dan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu Dosen yang luar biasa baiknya. 5. Keluarga tercinta (Bapak Achmad Yani, Mama Yuyun, Adik-adikku, Ilmiah Hilwani, Sulton Rizky Muzayyin, dan Abdul Ghani Muhammad) dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya. 6. Ferry Abdullah yang selalu memberi semangat dan doa terbaik untuk penulis. 7. M. Sahrul Munir, S.S., yang baik hati telah meminjamkan beberapa buku referensi dan memberi semangat kepada penulis. iii 8. Siti Hasanah, S.Pd yang selalu menyemangati dan mendoakan saya. 9. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada; Nada, Nuriel, Kiky, Fuah, dan Khozanah. 10. Dayat, Cecep, Agung, dan Dia, teman-teman 5 CM yang selalu mendukung penulis. Semoga selalu kompak, kawan. 11. Lenjee; Reny, Suci, Sasya, dan Dinda yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat berkumpul berlima lagi. 12. TKost Annisa (Ibu Arab); Intan, Nia, Anita, Yeyen, Elsa, Dian, Wardah, Nisa, Trisni, dan Kiky. 13. Yonita, Wahyu, dan adik-adik Bimbel; Rini, Nabila, Opin, Dita, Ilham, Mayla, Deska, Nasya, Fajar, Sri, Refi, dan Rifqi. Terima kasih, Semestaku atas doa kalian. 14. Teman-teman PBSI angkatan 2009, khususnya kelas C yang memberikan semangat, suka duka, canda tawa, persahabatan dan kenangan indah selama ini. 15. Teman-teman PPKT SMP Fatahillah, Pondok Pinang. 16. Uda Is, Bang Tyo, Riski, dan Uda Ade yang setia melayani foto kopi dan juga memberikan motivasi kepada penulis. Maju Jaya! 17. Rekan-rekan kerja di PT Christalenta Pratama dan PT Citra Gemilang Apik yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga Allah membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk yang memerlukannya. Jakarta, 5 Juli 2014 Penulis iv DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH LEMBAR UJIAN MUNAQASAH ABSTRAK ………………………………………………………………….. i ABSTRACT ………………………………………………………………... ii KATA PENGANTAR ……………………………………………………... iii DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 B. Identifikasi Masalah ......................................................................... 6 C. Batasan Masalah ............................................................................... 7 D. Rumusan Masalah ............................................................................ 7 E. Tujuan Penelitian............................................................................... 7 F. Manfaat Penelitian ............................................................................ 8 G. Metodologi Penelitian ...................................................................... 8 BAB II KAJIAN TEORI A. Sosiologi Sastra .............................................................................. 11 1. Pengertian Sosiologi Sastra ....................................................... 11 B. Novel ............................................................................................... 14 1. Pengertian Novel ....................................................................... 14 2. Unsur Novel ............................................................................... 16 C. Nilai Sosial ....................................................................................... v 21 1. Pengertian Nilai Sosial ………………………………………… 22 D. Teori Interaksi Simmel ………………………................................ 23 E. Pembelajaran Sastra ......................................................................... 28 F. Penelitian yang Relevan ................................................................... 31 BAB III TINJAUAN NOVEL DAN BIOGRAFI PENGARANG A. Tinjauan Internal .............................................................................. 33 1. Sinopsis Novel Para Priyayi........................................................ 33 2. Gambaran Umum Novel Para Pyiyayi.......................................... 36 B. Tinjauan Eksternal ............................................................................ 38 1. Biografi Umar Kayam ................................................................. 38 2. Karya-karya Umar Kayam .......................................................... 42 3. Pandangan Hidup Umar Kayam ................................................... 44 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS NILAI SOSIAL A. Unsur-unsur Intrinsik dalam Novel Para Priyayi............................ 49 B. Analisis Nilai Sosial dalam Novel Para Priyayi.............................. 113 C. Implikasi pada Pembelajaran Sastra di Sekolah .............................. 129 BAB V PENUTUP A. Simpulan ......................................................................................... 138 B. Saran ............................................................................................... 138 DAFTAR PUSTAKA LEMBAR UJI REFERENSI BIOGRAFI PENULIS vi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini pasti memiliki nilai. Nilai merupakan hal yang penting bagi kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tidak pernah lepas dari kehidupan dan aktivitas manusia, terutama nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia, baik itu nilai sosial, moral, agama, maupun pendidikan. Nilai-nilai tersebut penting untuk generasi penerus bangsa dalam membentuk kepribadian yang cerdas, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Arus modernisasi telah banyak memberi perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya mengarah pada krisis moral. Krisis moral tersebut umumnya terjadi karena masalah pendidikan. Pendidikan seharusnya mampu membentuk generasi penerus bangsa yang dapat melanjutkan tonggak perjuangan di masa yang akan datang dan mampu mengubah suatu masyarakat menjadi lebih baik, sehingga pendidikan menjadi sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Dunia pendidikan bukan satu-satunya yang patut dihakimi. Namun, mau tidak mau melalui pendidikanlah peradaban suatu masyarakat dapat terbentuk, bahkan disebut-sebut sebagai agent of change. Lembaga pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia-manusia yang berjiwa luhur, berperikemanusiaan, tidak merampas hak orang lain, jujur, dan mandiri. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan jiwa-jiwa kebaikan pada setiap manusia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang berkualitas 1 2 mampu menghasilkan perubahan kepribadian dan peradaban setiap manusia bahkan bangsa yang lebih baik. Guru adalah pengajar dan pendidik. Oleh karena itu, peran apa pun yang diberikan masyarakat kepada guru selalu memiliki kaitan dengan posisi pengajaran dan pendidikan dalam masyarakat itu. Kurangnya peran guru dapat menjadi salah satu penyebab perubahan nilai yang mengarah pada krisis moral. Guru seharusnya memberikan perhatian lebih kepada siswa dalam menggali nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui pelajaran yang diajarkan, khususnya pada pembelajaran sastra Indonesia. Selain itu, guru dapat mengarahkan siswa pada hal-hal positif agar nantinya mereka menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa hal dapat dilakukan untuk mencegah, bahkan mengatasi perubahan nilai yang mengarah pada krisis moral, yaitu dengan mengenalkan sastra, pendidikan sastra usia dini, dan memperbanyak porsi pengajaran sastra. Sastra yang diperkenalkan tentunya yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Mengenalkan sastra kepada anak berarti mendekatkan nilai-nilai yang berguna untuk memahami kehidupan. Harus diakui tradisi mendongeng orang tua kepada anak yang sudah turun-temurun dimiliki negeri ini, kini sudah semakin terkikis. Selain itu, sedikitnya pendidikan usia dini yang berbasis sastra membuat semakin kurangnya pengetahuan anak mengenai sastra, bahkan sampai saat ini, porsi pengajaran sastra hanya mendapat bagian kecil dari pengajaran bahasa. Ketersediaan guru sastra yang kompeten di sekolahsekolah juga sangat terbatas. Demikian pula dengan pemanfaatan bahan ajar sastra yang belum optimal. Sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi manusia tidak akan pernah lepas dari bahasa yang merupakan media utama dalam karya sastra. Sastra dan manusia erat kaitannya karena pada dasarnya keberadaan sastra sering bermula dari persoalan dan permasalahan yang ada pada manusia dan 3 lingkungannya. Kemudian dengan adanya imajinasi yang tinggi seorang pengarang menuangkan masalah-masalah yang ada disekitarnya menjadi sebuah karya sastra. Oleh karena itu, sastra merupakan suatu bentuk seni dan budaya yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung nilai-nilai yang penting bagi kehidupan bermasyarakat. Karya sastra adalah hasil pemikiran mengenai kehidupan. Karya sastra adalah sebuah karya fiksi yang berisi imajinasi seorang pengarang dalam menceritakan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Karya sastra bersifat imajinatif dan fiktif, yaitu suatu cerita rekaan yang berasal dari daya khayal seorang pengarang. Pengarang menyampaikan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian ia kemukan melalui karyanya. Cerita yang ditampilkan pengarang mengandung permasalahan yang sesuai dengan permasalahan masyarakat pada masa atau peristiwa tertentu. Maka, pengarang menyampaikan bagaimana keadaan atau situasi di mana ia berada melalui cerita pada karyanya. Salah satu hasil karya sastra adalah novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang berjenis prosa. Novel juga merupakan bagian dari karya fiksi yang memuat khayalan dan kenyataan yang dialami oleh seorang pengarang. Dapat dikatakan bahwa novel adalah suatu gambaran dari kehidupan dan diwujudkan melalui bahasa yang indah. Sebagai karya fiksi hasil kreativitas seorang pengarang, novel mempunyai beberapa unsur pembangun di dalamnya, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Novel menjadi cerminan dari persoalan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, novel juga dapat berupa rekaman dari peristiwa sejarah yang telah dialami dan dirasakan oleh seorang pengarang. Melalui karya sastra, seperti novel, pengarang berusaha mengungkapkan peristiwa yang berisi persoalan sosial, baik suka maupun duka di dalam kehidupan 4 masyarakat. Pada umumnya, novel menceritakan tentang kehidupan manusia dan lingkungannya dengan berbagai macam konflik yang ada di dalamnya. Horatius menyatakan bahwa fungsi sastra hendaknya memuat dulce (indah) dan utile (berguna). Ungkapan ini menunjukkan fungsi karya sastra tidak hanya sekedar untuk menghibur, tetapi juga mengajarkan sesuatu atau hal yang berguna. Karya sastra yang baik adalah karya yang dapat bermanfaat bagi pembaca, dengan kata lain pembaca mampu mengambil pelajaran dan mampu memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya. Fungsi karya sastra (fiksi) merupakan sebuah cerita, dan karenanya terkandung juga di dalamnya tujuan memberikan hiburan kepada pembaca disamping adanya tujuan estetik. Membaca sebuah karya fiksi berarti menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin. Daya tarik cerita inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang-orang yang membacanya. Hal itu dikarenakan pada dasarnya setiap orang senang cerita, apalagi yang sensasional, baik yang diperoleh dengan cara melihat maupun mendengarkan. Melalui cerita itulah pembaca secara tak langsung dapat belajar, merasakan, dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang sengaja ditawarkan pengarang. Hal itu disebabkan, cerita fiksi tersebut akan mendorong pembaca untuk ikut merenungkan masalah hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, cerita fiksi atau kesastraan pada umumnya sering dianggap dapat membuat manusia lebih arif, atau dapat dikatakan sebagai “memanusiakan manusia”.1 Novel merupakan sebuah cerminan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Novel Para Priyayi merupakan novel yang mengandung nilai-nilai sosial yang berhasil menggambarkan keadaan sosial pada masa itu. Novel ini menceritakan perkembangan tiga generasi (tiga zaman). Berawal dari seorang petani kecil yang tinggal di Wanagalih bernama 1 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajan Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 3-4. 5 Soedarsono yang pada akhirnya berhasil menjadi seorang priyayi. Kemudian permasalah-permasalahan sosial muncul pada generasi-generasi penerusnya (keluarga Soedarsono), yaitu Hardojo dan Harimurti. Peristiwa yang dikisahkan dalam novel ini adalah masa prakemerdekaan sampai pascakemerdekaan yang di dalamnya terdapat masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Novel Para Priyayi yang ditulis oleh Umar Kayam di New Haven pada tahun 1991. Melalui novel ini Umar Kayam sebagai penulis ingin menyampaikan idealismenya mengenai kepriyayian, karena selama ini stereotip priyayi selalu erat dengan orang-orang birokrat yang menggunakan statusnya untuk menguasai orang lain, berjiwa anti-sosial dan arogan. Kemampuan Umar Kayam dalam mendeskripsikan kehidupan priyayi di dalam novel tersebut memang tampaknya tidak lepas dari pengalaman yang didapatnya semasa kecil sebagai anak priyayi. Dalam novel ini, Umar Kayam menggambarkan perjuangan seorang petani kecil yang ingin menaikkan status sosialnya menjadi seorang priyayi melalui pendidikan. Hampir seluruh cerita dikisahkan menjadi citraan sosial pada masa itu. Oleh karena itu, hampir setiap bagian dalam novel mengungkapkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat.2 Melalui sastra, terutama novel kita dapat mengerti lebih banyak mengenai kehidupan manusia. Suatu karya sastra dapat memperkaya wawasan pembaca dengan berbagai sudut pandang, seperti psikologi, sejarah, sosial, politik, dan antropologi. Ketika membaca novel Para Priyayi karya Umar Kayam, pembaca akan merasakan bahwa novel ini sarat dengan unsur-unsur sosiologi karena latar sosial masyarakat Jawa yang sangat ditonjolkan. Selain itu, Para Priyayi sangat mendidik dan bagus untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa, karena 2 Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan Terjemahan dari Theory of Literature oleh Melani Budianta, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 110. 6 dapat dijadikan sebagai sarana pendukung untuk memperkaya bacaan para siswa. Pembelajaran sastra di sekolah dapat memberikan keseimbangan pada pengembangan kepribadian dan kecerdasan peserta didik. Pembelajaran sastra akan memberikan keseimbangan antara spiritual, emosional, etika, logika, estetika, dan kinestetika. Oleh karena itu, pembelajaran sastra tidak hanya berkaitan dengan estetika dan etika. Pembelajaran sastra sangat strategis digunakan untuk mengembangkan kompetensi atau kecerdasan spiritual, emosional; bahasa, atau untuk mengembangkan intelektual, dan kinestetika. Sehubungan dengan pernyataan di atas, peneliti tertarik mengkaji “Nilai Sosial dalam Novel Para Priyayi Karya Umar Kayam dan Implikasinya pada Pembelajaran Sastra di Sekolah”. Suatu hal yang menarik untuk mampu memahami peranan priyayi dalam kehidupan masyarakat Jawa yang dijabarkan dalam novel Para Priyayi. Menarik untuk diteliti karena di dalamnya menceritakan realita kehidupan tokoh-tokohnya mengenai kehidupan keluarga besar priyayi Jawa dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Perjuangan hidup untuk membangun satu generasi priyayi yang berasal dari seorang petani kecil di Wanagalih. Tentunya perjuangan hidup yang sangat baik untuk diteladani. Hal ini akan dicapai melalui analisis sosiologi karya sastra. Kemudian dari isi cerita novel akan dicari dan dianalasis makna nilai sosial yang terkandung di dalamnya yang nantinya dapat dijadikan materi pembelajaran sastra Indonesia di sekolah. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya mengarah pada krisis moral. Krisis moral tersebut umumnya terjadi karena masalah pendidikan. 7 2. Kurangnya peran orang tua dan guru sebagai agen perubahan dalam menggali nilai-nilai kehidupan, terutama guru dalam menggali nilai sosial dalam pembelajaran sastra di sekolah. 3. Kurangnya porsi pengajaran sastra dan terbatasnya ketersediaan guru-guru sastra yang memiliki kompetensi, serta pemanfaatan bahan ajar sastra yang belum optimal di sekolah. C. Batasan Masalah Untuk membatasi terlalu luasnya pembahasan, maka permasalahan pada penelitian ini akan difokuskan pada teori interaksi Simmel untuk menganalisis nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam melalui tinjauan sosiologi sastra dan implikasinya pada pembelajaran sastra di sekolah. D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana teori interaksi Simmel dalam menganalisis nilai sosial yang terkandung dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam? 2. Bagaimana implikasi nilai sosial dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam pada pembelajaran sastra di sekolah? E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan teori interaksi Simmel untuk menganalisis nilai sosial yang terkandung dalam novel Para Priyayi karya Umar kayam. 2. Mendeskripsikan implikasi nilai sosial dalam novel Para Priyayi pada pembelajaran sastra di sekolah. 8 F. Manfaat Penelitian Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai studi sastra Indonesia, khususnya dalam pembelajaran sastra di sekolah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan dalam kajian sosiologi sastra dalam mengungkap novel Para Priyayi karya Umar Kayam, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami isi cerita dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam, terutama menguraikan cara pandang pengarang yang direpresentasikan dalam karyanya dengan pemanfaatan lintas disiplin ilmu yaitu sosiologi dan sastra. G. Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data ilmiah. Data berhubungan dengan konteks keberadaan melibatkan sejumlah besar gejala sosial yang relevan.3 Lebih tepatnya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode content analysis atau analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan teks yang telah dicari berupa masalah atau temuan, kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Strategi yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan mengkaji isi berdasarkan data yang didapatkan. Metode content analysis atau analisis isi dari suatu novel. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Pengkajian deskriptif menyarankan pada pengkajian yang dilakukan sematamata hanya berdasarkan pada fakta atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya (sastrawan). Artinya, yang dicatat dan dianalisis adalah 3 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 47. 9 unsur-unsur dalam karya sastra seperti apa adanya. Maka, jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian dasar yang memfokuskan pada deskripsi mengenai nilai sosial yang terdapat dalam novel. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan tujuan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah teori interaksi Simmel untuk menganalisis nilai sosial yang terdapat dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam dan bagaimana implikasinya pada pembelajaran sastra di sekolah. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat serta ungkapan yang ada dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam, sedangkan sumber data penelitian ini adalah novel Para Priyayi (data primer), dan buku literatur, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian dan karya-karya Umar Kayam (data sekunder). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang membahas tentang hubungan antarindividu, individu dengan keluarga, masyarakat, komunitas, lembaga, dan negara, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba menguraikan berbagai nilai sosial yang terkandung dalam novel. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Membaca secara cermat novel Para Priyayi karya Umar Kayam; 2. Mencatat kalimat yang berkaitan dengan struktur novel, dan kalimat yang menggambarkan nilai sosial dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam; 3. Hasil mencatat kalimat dijadikan sebagai data untuk menganalisis nilai sosial dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam; 4. Setelah melalui analisis yang mendalam, hasilnya digunakan sebagai data untuk mengimplikasikan nilai sosial dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam pada pembelajaran sastra di sekolah. 10 Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data adalah: 1. Menganalisis novel Para Priyayi karya Umar Kayam dengan menggunakan analisis struktural. Analisis struktural dilakukan dengan membaca dan memahami kembali data yang sudah diperoleh. Selanjutnya, mengelompokkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam yang mengandung unsur tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat; 2. Analisis dengan tinjauan sosiologi sastra dilakukan dengan membaca dan memahami kembali data yang diperoleh. Selanjutnya, mengelompokkan kutipan-kutipan yang diperoleh sesuai teori interaksi Simmel mengenai nilai sosial dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam; 3. Mengimplikasikan nilai sosial yang terdapat dalam novel Para Priyayi pada pembelajaran sastra di sekolah. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkan materi pelajaran sastra di sekolah. BAB II KAJIAN TEORI A. Sosiologi Sastra 1. Pengertian Sosiologi Sastra Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat reflektif. Penelitian ini melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak lahir dalam kekosongan sosial. Kehidupan sosial menjadi pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra yang berhasil atau sukses, yaitu yang mampu merefleksikan zamannya. Ilmu sosiologi berkembang menjadi ilmu yang benar-benar otonom, meninggalkan kesusastraan yang dianggap sebagai bidang rumit dengan definisi yang sangat tidak pasti, dan yang dilindungi oleh semacam rasa hormat manusiawi.1 Dalam bukunya yang berjudul The Sociology of Literature, Swingewood (1972) dalam Faruk (1994) mendefinisikan sosiologi sebagai studi ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup,2 sedangkan sastra adalah ekspresi kehidupan manusia yang tak lepas dari akar kemasyarakatannya.3 1 Robert Escarpit, Sosiologi Sastra Penerjemah Ida Sundari Husen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 8-9. 2 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 1. 3 Suwardi Endaswara, Metodologi Penelitian Sastra, Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 78. 11 12 Seperti halnya sosiologi, sastra berurusan dengan manusia dan masyarakat: usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Dalam hal isi, sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama.4 Perbedaan antara keduanya adalah sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedangkan novel menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya.5 Dengan demikian, Objek studi sastra adalah ekspresi kehidupan manusia yang tidak terlepas dari akar masyarakat di sekitarnya, sedangkan objek studi sosiologi adalah manusia. Penelitian sosiologi sastra banyak membahas tentang kaitan pengarang dengan kehidupan sosialnya. Keduanya dapat saling melengkapi dalam kaitan cabang ilmu sosiologi sastra. Meskipun sosiologi dan sastra adalah dua cabang ilmu yang mempunyai perbedaan tertentu dan dianggap rumit, namun sosiologi dan sastra memperjuangkan masalah yang sama. Keduanya berurusan dengan masalah manusia dan masyarakat dalam proses-proses sosialnya dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian harus diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai berikut. a. Karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut adalah anggota masyarakat. 4 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), h. 10. 5 Ibid., h. 11. 13 b. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. c. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah mengandung masalah-masalah kemasyarakatan. d. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat istiadat, dan tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika, bahkan juga logika. Masyarakat jelas sangat berkepentingan terhadap tiga aspek tersebut. e. Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya.6 Di antara genre utama karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama, genre prosalah, khususnya novel, yang dianggap paling dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial. Alasan yang dapat dikemukakan di antaranya: a) novel menampilkan unsur-unsur cerita paling lengkap, memiliki media yang paling luas, menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan yang juga paling luas, b) bahasa novel cenderung merupakan bahasa sehari-hari, bahasa yang paling umum digunakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa novel merupakan genre yang paling sosiologis dan responsif, karena sangat peka terhadap fluktuasi sosiohistoris.7 Dengan demikian, dipilihlah novel Para Priyayi karya Umar Kayam sebagai objek penelitian. Novel Para Priyayi dipilih karena mampu mewakili perjuangan hidup manusia dalam mobilitas sosial sebuah keluarga di lingkungan masyarakat pada waktu itu. Selain itu, Para Priyayi memiliki 6 Nyoman Kuta Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 332-333. 7 Ibid., h. 335-336. 14 unsur-unsur cerita yang lengkap, menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan yang luas dengan bahasa sehari-hari yang sederhana dan yang paling umum digunakan dalam masyarakat Jawa. Gaya penulisannya sederhana, bernarasi Jawa yang akrab, mudah dicerna dengan kritik-kritik yang segera mengajak pembaca membuat perenungan yang sebenarnya memiliki kandungan makna dan filosofi kehidupan. Selain budaya pewayangan yang banyak diekspos dalam novel Para Priyayi, Umar Kayam juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan sosial para tokoh yang sangat mencerminkan masyarakat sosial pada umumnya. B. Novel 1. Pengertian Novel Karya sastra merupakan sarana pendidikan yang memiliki bermacam- macam bentuk, seperti puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada salah satu karya sastra, yaitu novel. Kata novel berasal dari kata Latin novellus yang diturunkan pula dari kata novies yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain.8 Kata “novel” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.9 Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh.10 8 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar sastra, (Bandung: Angkasa, 2001), h. 167. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 969. 10 E. Kosasih, Dasar-dasar Keterampilan Bersastra, (Bandung: Yrama Widya, 2012), Cet. I, h. 60. 9 15 Novel merupakan suatu karya fiksi, yaitu karya dalam bentuk kisah atau cerita yang melukiskan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa rekaan. Sebuah novel bisa saja memuat tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa nyata, tetapi pemuatan tersebut biasanya hanya berfungsi sebagai bumbu belaka dan mereka dimasukkan dalam rangkaian cerita yang bersifat rekaan atau dengan detail rekaan. Walaupun peristiwa dan tokoh-tokohnya bersifat rekaan, mereka memiliki kemiripan dengan kehidupan sebenarnya. Mereka merupakan “cerminan kehidupan nyata”.11 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa novel merupakan karya fiksi yang berbentuk karangan prosa, tetapi tidak terlalu panjang yang mengisahkan atau menceritakan para tokoh dengan masing-masing watak dan masalah atau peristiwa yang merupakan cerminan nyata dalam kehidupan. Menurut Sumarjo, novel adalah produk masyarakat. Novel berada di masyarakat karena novel dibentuk oleh anggota masyarakat berdasarkan desakan-desakan emosional dan rasional dalam masyarakat. Menurut Faruk, novel adalah cerita tentang suatu pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai yang otentik yang dilakukan oleh seorang hero problematik dalam suatu dunia yang juga terdegradasi. Jadi, jelas bahwa kesusastraan dapat dipelajari dari disiplin ilmu sosial juga.12 Menurut Selden, novel menurut pandangannya adalah cerminan realitas, tidak hanya melukiskan wajah wajah yang tampak pada permukaan, tetapi memberikan kepada kita “sebuah pencerminan realitas yang lebih benar, lebih lengkap, lebih hidup, lebih dinamik”. Sebuah novel mungkin membawa pembaca “ke arah suatu pandangan yang lebih konkret kepada realitas.13 11 Furqonul Aziez dan Abdul Hasim, Menganalisis Fiksi Sebuah Pengantar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. I, h. 2. 12 Wijaya Heru Santosa dan Sri Wahyuningtyas, Pengantar Apresiasi prosa, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h. 47. 13 Nani Tuloli, Kajian Sastra, (Gorontalo: BMT “Nurul jannah”, 2000), h. 62. 16 Maka dapat disimpulkan pula bahwa novel adalah cerita rekaan yang menyajikan aspek kehidupan itu sendiri yang sebagian besar merupakan kenyataan sosial dan ada yang meniru atau subjektivitas manusia. 2. Unsur Novel Pada umumnya, para ahli membagi unsur novel menjadi unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk mengkaji novel atau karya sastra pada umumnya. a. Unsur Ekstrinsik Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun di luar karya sastra. Unsur ini mempengaruhi cara penyusunan cerita dalam sebuah karya satra. Selain itu, juga membantu dalam penafsiran suatu karya, sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Unsur ekstrinsik terdiri dari unsur-unsur di luar karya. Unsur yang dimaksud antara lain biografi pengarang, buah pemikiran pengarang, serta latar sosial-budaya yang menunjang kehadiran teks sastra. Pemahaman unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa karya sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Misalnya, faktor sosioekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosio-politik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. Unsur ekstrinsik tidak dibahas dalam penelitian ini. Akan tetapi, dapat dilihat pada BAB III. b. Unsur Intrinsik Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) turut serta dalam 17 membangun cerita. Kepaduan antarberbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel terwujud.14 Unsur pembangun dari dalam karya ini terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang dimaksud adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Unsur ini akan dianalisis dalam novel saat kita membacanya. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik yang akan dianalisis lebih mendalam dalam novel Para Priyayi. Pembahasan dan analisis tersebut terdapat pada BAB IV. 1) Tema Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita.15 Tema sebuah cerita bersifat individual sekaligus universal. Tema memberi kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang sedang diceritakan sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Apa pun nilai yang terkandung di dalamnya, keberadaan tema menjadi salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dengan kenyataan cerita.16 Menurut Hartoko dan Rahmanto dalam Nurgiyantoro, tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan.17 Dengan demikian, tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Dalam menentukan sebuah tema harus membaca secara mendalam dan menelusuri seluruh isi cerita, sehingga menghasilkan “benang merah” yang menjadi gagasan terbangunnya sebuah cerita. 14 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajan Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 23. 15 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 161. 16 Robert Stanton, Teori Fiksi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I, h. 7. 17 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajan Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 68. 18 2) Tokoh dan Penokohan Menurut Sukada dan Aminuddin dalam Siswanto, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam prosa rekaan, sehingga peristiwa tersebut menjalin suatu cerita, sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan.18 Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang paling berkaitan dalam unsur intrinsik pada sebuah prosa rekaan. Keduanya menjadi saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pembahasan. Ditinjau dari peranan dan keterlibatan dalam cerita, tokoh dapat dibedakan atas tokoh primer (utama), tokoh sekunder (tokoh bawahan), dan tokoh komplementer (tambahan).19 Dari tiga jenis tokoh tersebut menunjukkan bahwa dalam sebuah cerita tidak hanya ada satu jenis tokoh. Ada berbagai macam tokoh yang sastrawan tampilkan dalam sebuah novel. 3) Alur Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita.20 Menurut Abrams dalam Siswanto, alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjalin sebuah cerita yang yang dihadirkan oleh pelaku dalam suatu cerita.21 Tahap-tahap tersebut mengandung unsur urutan waktu, baik secara tersirat maupun tersurat. Tahap awal cerita pun tidak hanya dimulai dari waktu yang paling awal, sehingga dalam sebuah cerita urutan waktu bisa diatur sesuai keinginan sastrawan. Dengan demikian, alur merupakan elemen yang penting karena sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya 18 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 142. Ibid., h. 143. 20 Robert Stanton, Teori Fiksi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I, h. 26. 21 Siswanto, Op. Cit., h. 159. 19 19 pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh terhadap jalan cerita. 4) Latar “The overall setting of a narrative or dramatic work is general locale, historical time, and social circumstance in which its action occurs; the setting of a single episode or scene within such a work is the particular physical location in which it takes place.”22 Abrams mengemukakan bahwa latar cerita adalah tempat umum, waktu kesejarahan, dan kebiasaan masyaratkat dalam setiap episode atau bagian-bagian tempat. Menurutnya, latar atau setting disebut juga sebagai landasan tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.23 Akan tetapi, tidak semua novel menonjolkan ketiga latar tempat, waktu, maupun sosial. Mungkin dalam sebuah cerita yang paling menonjol adalah latar waktu maupun tempat dan ada kalanya yang menonjol adalah latar sosial. 5) Sudut Pandang Sudut pandang merupakan strategi, teknik, atau siasat yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya.24 Dari sinilah pengarang menampilkan tokoh dalam cerita yang dipaparkannya. Dengan demikian, segala sesuatu yang dikemukakan oleh pengarang disalurkan melalui sudut pandang tokoh. Ada banyak jenis sudut pandang, tetapi semuanya tergantung dari mana sudut pandang tersebut dilakukan. Jenis sudut pandang yang peneliti gunakan berdasarkan pemaparan Nurgiyantoro. Berikut ini adalah jenis-jenis sudut pandang. 22 M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, (Boston: Heinle & Heinle, 1999), h. 284. Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajan Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h. 216. 24 Ibid., h. 248. 23 20 a) Sudut pandang persona ketiga: “Dia” Pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang ini terletak pada seorang narator yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata ganti orang. Dalam sudut pandang persona ketiga “Dia” dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu “Dia” mahatahu (narator mengetahui segalanya dan serba tahu) dan “Dia” terbatas atau hanya sebagai pengamat (narator mengetahui segalanya, namun terbatas hanya pada seorang tokoh). b) Sudut pandang persona pertama: “Aku” Pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang ini terletak pada seorang narator yang ikut terlibat dalam cerita. Dalam sudut pandang persona pertama “Aku” dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu “Aku” (tokoh utama) dan “Aku” (tokoh tambahan). c) Sudut pandang campuran Penggunaan sudut pandang ini lebih dari satu teknik. Pengarang dapat berganti-ganti dari teknik yang satu ke teknik yang lain. Semua itu tergantung pada kemauan pengarang untuk menciptakan sebuah kreativitas dalam karyanya. 6) Gaya Bahasa “Figurative language is a conspicuous departure from what the users of a language apprehend as the standard meaning of words, or else the standard order of words, in order to achive some special meaning or effect.”25 Abrams mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa agar kata-kata yang standar dapat mencapai makna khusus. Gaya bahasa pada suatu karya 25 Abrams, Op. Cit., h. 96. 21 sastra biasanya menggunakan pilihan kata yang mengandung makna padat, relektif, asosiatif, bersifat konotatif, dan dipadu dengan kiasan dan majas, sehingga terwujudlah kalimat yang menunjukkan adanya variasi dan harmoni. 7) Amanat Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra; pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar.26 Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu.27 Amanat merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya dan tertuang secara tersirat dalam cerita. Melalui amanat dalam cerita, biasanya pengarang menuangkan pandangan hidupnya. C. Nilai Sosial 1. Pengertian Nilai Sosial Kehidupan bersama manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial selalu dilandasi aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu, manusia tidak bisa berbuat dan bertindak semaunya. Aturan-aturan ini diciptakan dan disepakati bersama untuk mencapai ketentraman dan kenyamanan hidup bersama dengan orang lain. Aturan-aturan itu dipakai sebagai ukuran, patokan, anggapan, serta keyakinan tentang sesuatu itu baik, buruk, pantas, janggal, asing, dan seterusnya. Aturan-aturan ini yang biasa kita sebut dengan istilah nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik. Menurut perkataan bagus filsuf JermanAmerika, Hans Jonas, nilai adalah the address of a yes, “sesuatu yang 26 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 162. E. Kosasih, Dasar-dasar Keterampilan Bersastra, (Bandung: Yrama Widya, 2012), h. 71. 27 22 ditujukan dengan „ya‟ „kita”. Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iyakan atau aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri—seperti penderitaan, penyakit, atau kematian—adalah lawan dari nilai, adalah “nonnilai” atau disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan di sini istilah “nilai negatif”, sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut “nilai positif”.28 Kluckhohn, seorang antropolog yang banyak membahas mengenai nilai-nilai, menyatakan bahwa suatu nilai merupakan (C. Kluckhohn 1951: 395) “A conception, explicit or implicit, distinctive of individual or characteristic of a group, of the desirable, which influences the section from available modes, means and ens action.”29 Kata “nilai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya; berhubungan erat dengan etika. Kata “nilai” diartikan sebagai harga, kadar, mutu atau kualitas.30 Maka, sesuatu harus memiliki sifat-sifat yang penting dan bermutu atau berguna bagi kemanusiaan dan menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Kata “sosial” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berkenaan dengan masyarakat.31 Maka, segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, seperti suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, dan menderma dapat disebut sebagai sosial. 28 K. Bertens, ETIKA, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1993), h. 149. Soerjono Soekanto, Pribadi dan Masyarakat (Suatu Tinjauan Sosiologis), (Bandung: Alumni, 1983), h. 160. 30 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 963. 29 31 Ibid., h. 1331. 23 Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Dengan ukuran itu, suatu masyarakat akan tahu mana yang baik atau buruk, benar atau salah, dan boleh atau dilarang. Nilai sosial yang terbukti langgeng dan tahan zaman akan membaku menjadi sistem nilai budaya. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan tata nilai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial merupakan hal-hal yang bersifat penting dan berguna bagi kemanusiaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat sebagai sebuah kehidupan bersama tentulah memiliki berbagai aturan atau kesepakatan yang luhur untuk mengatur berlangsungnya kehidupan bersama. Kehidupan bersama tentu juga memiliki sesuatu yang dijunjung tinggi, dihormati, serta ditaati oleh seluruh anggota masyarakatnya. Di sisi lain ada juga sesuatu yang dilarang untuk dilakukan dan harus dijauhi oleh anggota masyarakat. Sesuatu tersebut secara umum disebut sebagai nilai sosial. D. Teori Interaksi Simmel Manusia tercipta sebagai makhluk pribadi sekaligus juga makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk mencapai tujuannya. Itulah sebabnya manusia berinteraksi dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Para ahli, seperti Maclver, J.L. Gillin, dan J.P.Gillin sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai, norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup 24 manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.32 Teori Interaksi Simmel adalah teori yang mengkaji masalah hubungan antarpribadi (interpersonal). Penjelasan Simmel tentang interaksi adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat terbentuk dari jaringan relasi-relasi antarorang, sehingga mereka merupakan satu kesatuan. Dalam jaringan relasi tersebut terjadi aksi dan reaksi yang tak terbilang banyaknya, sehingga masyarakat merupakan proses dinamis yang ditentukan oleh perilaku anggotanya, (2) Jaringan relasi-relasi itu tidak sama sifatnya. Artinya dari jaringan relasi tersebut, dapat terbentuk komunitas asosiasi, bahkan ada tendensi, ada pergeseran dari pola relasi afektif dan personal menjadi fungsional dan rasional, (3) Dalam jaringan relasi tidak selamanya terbentuk integrasi dan harmonis, tetapi dapat pula terjadi kritik, oposisi, konflik, dan lain-lain. Bagi strukturasi sosial yang sehat, maka kritik, oposisi, persaingan sama-sama diperlukan, sebagaimana halnya kesesuaian paham, persahabatan, dan partisipasi. Keduanya, baik hal negatif maupun positif menurut pandangan sepintas sebenarnya mempunyai efek positif dalam proses interaksi. Tindakan yang dianggap negatif menurut individuindividu, sebenarnya mempunyai akibat positif bagi keseluruhan relasi yang ada dalam masyarakat atau organisasi, (4) Frekuensi interaksi dan kadar interaksi bervariasi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Semakin penting hal yang mempertemukan orang dalam relasi timbal balik, semakin cepat relasi-relasi itu dilembagakan. Pada intinya Simmel memandang masyarakat sebagai produk dari proses interaksi individu-individu. Terjadinya interaksi akibat dorongan-dorongan dan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga akibatnya ada kesatuan sosial yang sifatnya dapat lama atau sementara. Tujuan dan dorongan itu sendiri bukan sosial tetapi sebagai isi 32 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), Cet. IV, h. 122. 25 sosialisasi. Proses sosialisasi itu sendiri terdapat dalam bentuk-bentuk yang berupa interaksi.33 Individu barulah individu apabila pola perilakunya yang khas di dirinya itu diproyeksikan pada suatu lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Kekhasan atau penyimpangan dari pola perilaku kolektif menjadikannya individu, menurut relasi dengan lingkungan sosialnya yang bersifat majemuk serta simultan. Dari individu dituntut kemampuan untuk membawa dirinya secara konsisten, tanpa kehilangan identitas nilai etisnya. Relevan dengan relasi-relasi sesaat antara dirinya dengan berbagai perubahan lingkungan sosialnya. Satuan-satuan lingkungan sosial yang melingkari individu terdiri dari keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat, dan nasion. Individu mempunyai “karakteristik” yang setiap kali berbeda fungsinya, struktur, peranan, dan proses-proses yang berlangsung di dalam dirinya. Posisi, peranan, dan tingkah lakunya diharapkan sesuai dengan tuntutan setiap satuan lingkungan sosial dalam situasi tertentu. Relasinya bersifat kompleks dan menjadi sasaran berbagai disiplin ilmu, tetapi diperoleh gambaran mengenai relasi individu dengan lingkungan sosialnya sebagai berikut. 1. Relasi Individu dengan Dirinya Merupakan masalah khas psikologi. Di sini muncul istilah-istilah Ego, Id, dan Superego serta dipersonalisasikan (apabila relasi individu dengan dirinya adalah seperti dengan orang asing saja), dan sebagainya. Dalam diri seseorang terdapat tiga sistem kepribadian yang disebut Id atau “es” (jiwa ibarat gunung es di tengah laut), Ego atau “aku”, dan Superego atau uber ich. Id adalah wadah dalam jiwa seseorang, berisi dorongan primitif dengan sifat temporer yang selalu menghendaki agar segera dipenuhi atau dilaksanakan demi kepuasan. Contohnya, seksual dan libido. Ego bertugas melaksanakan dorongan-dorongan Id, tidak bertentangan dengan kenyataan dan tuntutan dari Superego. Ego dalam tugasnya berprinsip pada kenyataan relative principle. 33 Ibid., h. 56. 26 Superego berisi kata hati atau conscience, berhubungan dengan lingkungan sosial, dan punya nilai-nilai moral sehingga merupakan control terhadap dorongan yang datang dari Id. Karena itu ada semacam pertentangan antara Id dan Superego. Bila Ego gagal menjaga keseimbangan antara dorongan dari Id dan larangan dari Superego, maka individu akan mengalami konflik batin yang terus menerus. Untuk itu perlu kanalisasi melalui mekanisme pertahanan. Demikian psikoanalisa sebagai teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud (1856-1939), sarjana berkebangsaan Jerman. 2. Relasi Individu dengan Keluarga Individu memiliki relasi mutlak dengan keluarga. Ia dilahirkan dari keluarga tumbuh, dan berkembang untuk kemudian membentuk sendiri keluarga batinnya. Terjadi hubungan dengan ibu, ayah, dan kakak-adik. Dengan orang tua, dengan saudara-saudara sekandung, terjalin relasi biologis yang disusul oleh relasi psikologis dan sosial pada umumnya. Peranan-peranan dari setiap anggota keluarga merupakan resultan dari relasi biologis, psikologis, dan sosial. Relasi khusus oleh kebudayaan lingkungan keluarga dinyatakan melalui bahasa (adat-istiadat, kebiasaan, norma-norma, bahkan nilai-nilai agama sekalipun). 3. Relasi Individu dengan Lembaga Lembaga diartikan sebagai norma-norma yang berintegrasi di sekitar suatu fungsi masyarakat yang penting. Oleh karena itu, ada segi kultural berupa norma-norma dan nilai-nilai, dan ada segi strukturalnya berupa berbagai peranan sosial. Berfungsi dalam integrasi dan stabilitas karena lembaga sosial merupakan keutuhan tatanan perilaku manusia dalam kebersamaan hidup. Tumbuhnya individu ke dalam lembaga-lembaga sosial berlangsung melalui proses sosialisasi karena lembaga disadari dan mempunyai arti sebagai realitas-realitas objektif. Posisi dan peranan individu dalam lembaga 27 sosial sudah dibakukan berdasarkan moral, adat, atau hokum yang berlaku. Individualitasnya ditanggung didalam struktur, yaitu hubungan kelembagaan. Individu bertingkah laku spesifik, berbeda dengan yang lainnya. Individu merupakan ketua, direktur, pemimpin, tokoh, dan lainlainnya. Terjadi kompleksitas interaksi sosial, merupakan struktur baku dalam pola relasi yang terungkap dalam pranata sosial. 4. Relasi Individu dengan Komunitas Dalam sosiologi, komunitas diartikan sebagai satuan kebersamanaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciri-ciri: (1) teritorialitas yang terbatas, (2) keorganisasian tata kehidupan bersama, dan (3) berlakunya nilainilai dan orientasi nilai yang kolektif (Poplin, 1960). Ketentuan batas wilayah bersifat objektif dan subjektif, sehingga batas-batas administratif dan batas kultural tidak tumpang tindih dalam kehidupan komunitas. Komunitas mencakup individu-individu, keluarga-keluarga, dan juga lembaga yang saling berhubungan secara interdependen. Bersifat kompleks, dari makna kehidupannya ditentukan oleh orientasi nilai yang berlaku, artinya oleh kebudayaannya, yang menumbuhkan pranata-pranata sosial struktur kekerabatan keluarga dan perilaku individu maupun kolektif. Posisi dan peranan individu didalam komunitas tidak lagi bersifat langsung, sebab perilakunya sudah tertampung atau direndam oleh keluarga dan kebudayaan yang mencakup dirinya. Sebaliknya pengaruh komunitas terhadap individu tersalur melalui keluarganya dengan melalui lembaga yang ada. 5. Relasi Individu dengan Masyarakat Masyarakat merupakan suatu lingkungan sosial yang bersifat makro. Aspek teritorium kurang ditekankan, namun aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif memperoleh bobot yang lebih besar. Kedua aspek itu menunjuk kepada derajat integrasi masyarakat karena keteraturan esensial dan hidup kolektif ditentukan oleh kemantapan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari pranata, status, dan peranan individu. Variable-variabel tersebut 28 dipakai dalam mengkaji dan menjelaskan fenomena masyarakat menurut persepsi makro. Sifat makro diperoleh dari kenyataan, bahwa masyarakat pada hakikatnya terdiri dari sekian banyak komunikasi yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga, dan individu-individu. 6. Relasi Individu dengan Nasion Menurut Ernest Renan (1823-1892), nasion adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Persetujuan keinginan dinyatakan dengan jelas untuk melanjutkan kehidupan bersama. Relasi individu dengan nasionnya dinyatakan pula dengan posisi serta peranan-peranan yang ada pada dirinya. Semuanya tertampung oleh atau tersalurkan melalui unit-unit lingkungan sosial yang lebih makro. Hubungan langsung individu dengan nasion diekspresikan melalui posisinya sebagai warga Negara.34 E. Pembelajaran Sastra Istilah pengajaran yang mempunyai makna proses, cara, perbuatan mengajar atau mengajarkan; perihal mengajar; sedangkan pembelajaran biasa diucapkan sejalan dengan semangat dan perubahan yang terjadi. Pembelajaran lebih dipilih dan dipergunakan secara formal, karena didalam kata ini aktivitas yang terjadi adalah seimbang antara pihak guru dan anak didiknya; mereka sama-sama aktif dan diharapkan juga sama-sama kreatif.35 Istilah sastra berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tulisan atau karangan. Sastra biasanya diartikan sebagai karangan dengan bahasa yang indah dan 34 Ibid., h. 123-127. Rohinah M. Noor, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi Pendidikan Moral yang Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), h. 137. 35 29 isi yang baik. Bahasa yang indah artinya dapat menimbulkan kesan dan menghibur pemabacanya. Isi yang baik artinya berguna dan mengandung nilai pendidikan. Indah dan baik yang ini menjadi fungsi sastra yang terkenal dengan istilah dulce et utile. Bentuk fisik dari sastra disebut karya sastra. Penulis karya sastra disebut sastrawan.36 Pembelajaran sastra penting bagi siswa karena berhubungan erat dengan kepribadian. Sastra dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir orang mengenai hidup, baik dan buruk, benar dan salah serta cara hidup. Oleh karena itu, selain memberikan kenikmatan dan keindahan, pembelajaran sastra juga mampu memberikan nilai-nilai sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Pembelajaran sastra di sekolah merupakan sesuatu yang penting dan patut diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Dari usia dini, yaitu tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Jika sastra diajarkan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat membantu bidang pendidikan. Ketepatan dalam pengajaran sastra tersebut dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi empat manfaat, yaitu: membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang pembentukan watak.37 Manfaat tersebut juga berguna untuk menafsirkan dan memahami masalah-masalah dunia nyata, walaupun sastra sendiri merupakan karya fiktif. Oleh karena itu, pengajaran sastra dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang penting dan patut menempati tempat yang selayaknya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah Kelompok Mata Pelajaran Wajib. Kelompok Mata Pelajaran Wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan menengah dalam kurikulum 2013 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa, pengenalan lingkungan fisik dan alam, kebugaran jasmani serta seni budaya daerah 36 Ibid., h. 17. B. Rahmanto, Metode Pengajaran Sastra, ( Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 16. 37 30 dan nasional, sedangkan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia termasuk dalam Kelompok Mata Pelajaran Peminatan. Kelompok Mata Pelajaran Peminatan bertujuan (1) untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) untuk mengembangkan minat terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Dalam struktur kurikulum SMA/MA terdapat penambahan jam belajar per minggu sebanyak 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar, sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk mengamati, bertanya, mengasosiasi, dan berkomunikasi. Proses pembelajaran yang dikembangkan guru menghendaki kesabaran dan menunggu respons peserta didik karena mereka belum terbiasa. Selain itu, bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Mengikutsertakan pengajaran sastra dalam kurikulum berarti akan membantu siswa berlatih keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis yang masing-masing erat kaitannya. Dalam pengajaran sastra, siswa dapat melatih keterampilan menyimak dengan mendengarkan suatu karya yang dibacakan oleh guru, teman atau lewat pita rekaman. Siswa dapat melatih keterampilan berbicara dengan ikut berperan dalam suatu drama. Siswa dapat pula meningkatkan keterampilan membaca dengan membacakan puisi atau prosa cerita. Mengapresiasi sastra itu menarik, siswa dapat mendiskusikannya dan kemudian menuliskan hasil diskusinya sebagai latihan keterampilan menulis. 31 Pembelajaran sastra dapat ditingkatkan lagi dengan pendidikan melalui sastra. Melalui sastra, kita dapat mengembangkan peserta didik dalam hal keseimbangan antara spiritual, emosional, etika, logika, estetika, dan kinestetika; pengembangan kecakapan hidup; belajar sepanjang hayat; serta pendidikan keseluruhan dan kemitraan. Selain itu, dengan pendidikan sastra, peserta didik tidak hanya diajak untuk memahami dan menganalisis berdasarkan bukti nyata yang ada dalam karya sastra dan kenyataan yang ada di luar karya sastra, tetapi juga diajak untuk megembangkan sikap positif terhadap karya sastra. Pendidikan semacam ini akan mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sastra bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, menyeimbangkan pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan kinestetika peserta didik. F. Penelitian yang Relevan Pada penelitian ini penulis menggunakan novel Para Priyayi sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra dalam mengkaji objek penelitian. Sebelumnya ada beberapa penelitian lain yang dapat dijadikan perbandingan dan penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Skripsi Atik Hendriyati (2009) dengan judul penelitian “Kajian Intertekstual dan Nilai Pendidikan dalam Novel Canting Karya Arswendo Atwomiloto dengan Para Priyayi Karya Umar Kayam”. Berdasarkan analisis Atik Hendriyati, hubungan intertekstual antara Canting dan Para Priyayi merupakan karya hipogram, yaitu karya yang melatarbelakangi penciptaan karya selanjutnya, sedangkan Para Priyayi disebut karya transformasi karena mentransformasikan teks-teks yang menjadi hipogramnya. Persamaan kedua novel ini terdapat dalam beberapa aspek, yaitu tema, alur, penokohan dan perwatakan, dan latar, baik tempat, waktu maupun sosial. Perbedaannya terdapat pada nilai yang dianalisis. Penelitian ini meneliti mengenai nilai pendidikan, yaitu nilai pendidikan dalam sikap atau tindakan, yaitu nilai-nilai 32 yang diperoleh dan dapat dicontoh dari sikap atau tindakan para tokoh dalam cerita. Selain itu, nilai pendidikan disampaikan melalui ungkapan atau pepatah dari para tokohnya yang mengandung ajaran moral yang tinggi. 38 Kedua, skripsi Permadi Hendra Lesmana (2013) “Perubahan Ideologi Kepriyayian Jawa: dari Tradisi ke Modern dalam Novel Para Priyayi dan Jalan Menikung Karya Umar Kayam serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMA”. Berdasarkan hasil analisis Permadi Hendra Lesmana, perubahan ideologi yang terdapat dalam Para Priyayi dan Jalan Menikung Karya Umar Kayam dikelompokkan menjadi enam, yaitu 1) Perubahan Ideologi Kayam terkait pernikahan, 2) Perubahan ideologi Kayam terkait sudut pandang agama lain dalam menilai Islam, 3) Perubahan ideologi Kayam terkait sikap kepada penguasa, 4) Perubahan ideologi terkait sikap orang tua ditunjukan oleh tokoh utama yang sebelumnya tidak memberikan restu pernikahan beda agama menjadi sebaliknya, 5) Perubahan ideologi terkait menyikapi kebudayaan Jawa, sebelumnya Kayam menjadikan budaya Jawa sebagai panduan kehidupan dan kemudian hanya menjadi seni hiburan saja, 6) Perubahan ideologi terkait konsep perselingkuhan, sebelumnya perselingkuhan hanya dianggap sebagai hiburan dan perselingkuhan itu sendiri tidak pernah terjadi pada tokoh utama tetapi kemudian menjadi sebaliknya, perselingkuhan menjadi kebutuhan dan benar-benar terjadi.39 Persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian relevan di atas adalah samasama meneliti mengenai beberapa aspek, yaitu tema, alur, penokohan dan perwatakan, dan latar, baik tempat, waktu, maupun sosial. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis nilai sosial, sedangkan kedua penelitian relevan di atas meneliti mengenai nilai pendidikan dan perubahan ideologi. 38 Atik Hendriyati, “Kajian Intertekstual dan Nilai Pendidikan Novel Canting Karya Arswendo Atmowiloto dengan Para Priyayi Karya Umar Kayam”, Skripsi pada Strata 1 Universitas Sebelas Maret, Purwakarta, Purwakarta, 2009, tidak dipublikasikan. 39 Permadi Hendra Lesmana, “Perubahan Ideologi Kepriyayian Jawa: dari Tradisi ke Modern dalam Novel Para Priyayi dan Jalan Menikung Karya Umar Kayam serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMA”, Skripsi pada Strata 1 Universitas Islam Negeri, Jakarta, Jakarta, 2013, tidak dipublikasikan. BAB III TINJAUAN NOVEL DAN BIOGRAFI PENGARANG A. Tinjauan Internal 1. Sinopsis Novel Para Priyayi Lantip, nama aslinya adalah Wage karena lahir pada hari Sabtu Wage. Nama Lantip itu adalah sebuah nama pemberian dari keluarga Sastrodarsono saat Lantip tinggal di keluarga itu, yaitu di jalan Satenan di kota Wanagalih. Sebelumnya Lantip tinggal bersama Emboknya Desa Wanalawas yang hanya beberapa kilometer dari kota Wanagalih. Hubungan Embok Lantip dengan keluarga Sastrodarsono itu dimulai dari penjualan tempe. Rupanya tempe buatan Embok Lantip itu berkenan di hati keluarga Sastrodarsono. Buktinya kemudian tempe Embok itu jadi langganan keluarga tersebut. Lantip selalu ikut membantu menyiapkan dagangan tempe, dan ikut menjajakan nya berjalan di samping atau di belakang Mboknya menyelusuri jalan dan lorong kota. Lantip ingat bahwa dalam perjalan itu sengatan terik matahari Wanagalih. Wanagalih memang terkenal sangat panas dan rasa haus yang benar-benar mengeringkan tenggorokan. Sekali waktu Lantip pernah merengek kepada Emboknya untuk dibelikan jajanan. Dengan ketus Emboknya menjawab dengan ―Hesy! Ora usah‖, dan Lantip pun terdiam. Lantip tahu Emboknya, meskipun murah hati juga sangat hemat dan tegas. Dia akan lebih senang bila kami melepas haus di sumur pojok alun-alun atau bila beruntung dapat sekedar air teh di rumah langganan Emboknya. Salah satu langganan Emboknya yang murah hati itu adalah keluarga Sastrodarsono. Mereka dipanggil oleh keluarga Sastrodarsono. Mereka menyebutnya dengan ―Ndoro Guru‖ dan ―Ndoro Guru Putri‖. Waktu mereka melihat Embok datang 33 34 membawa Lantip, Ndoro Guru menanyakan dengan nada suara sangatlah ulem-nya dan penuh wibawa. Sejak itu rumah keluarga Sastrodarsono menjadi tempat persinggahan mereka, hubungan mereka dengan keluarga itu menjadi akrab, bahkan lamalama rumah itu menjadi semacam rumah kedua bagi mereka. Tetapi sangatlah tidak pantas rumah gebyok itu terlalu besar dan bagus untuk dikatakan rumah kedua mereka bila disejajarkan dengan rumah mereka yang terbuat dari gedek atau anyaman bambu di desa Wanalawas. Juga bila diingat bahwa rumah itu adalah rumah milik seorang priyayi, seorang mantri guru sekolah desa, yang pada zaman itu mempunyai kedudukan cukup tinggi di mata masyarakat seperti Wanagalih. Mantri guru sudah jelas didudukan masyarakat dan pemerintah sebagai priyayi, ia punya jabatan dan juga punya gaji. Suatu ketika Soedarsono yang telah berganti nama menjadi Sastrodarsono, mengutus Soenandar untuk mengurus sekolah yang didirikannya di Wanalawas, diharapkan agar Soenandar lebih mandiri dan dapat bertanggung jawab, tapi Soenandar justru menghamili anak penjual tempe dan kabur. Lahirlah Wage yang kemudian diboyong ke wanagalih, dirawat dan disekolahkan, kemudian diganti namanya menjadi Lantip. Wanagalih adalah sebuah ibukota kabupaten. Kota itu lahir sejak pertengahan abad ke-19. Di kota itu Lantip sering teringat akan Mbah guru Sastrodarsono yang selalu memberikan nasihat pada seisi rumah setiap kali ia pulang dari pertemuan pagi. Semenjak Lantip mengetahui perihal ayahnya, ia merasa kecewa dan malu karena ia hanya anak jadah dan haram meskipun jelas bapaknya tetapi tidak mau menikah dengan Emboknya. Ternyata bapaknya adalah gerombolan perampok. Selain itu juga sekarang Lantip mengerti mengapa keluarga Sastrodarsono sangat memperhatikan kehidupannya dan Ngadiyem Emboknya, karena Soenandar, yang ayahnya Lantip itu, adalah masih tergolong keluarga dari Sastrodarsono. 35 Keluarga Sastrodarsono perlahan berhasil membangun keluarga priyayi mereka sendiri. Kelahiran tiga anak mereka, yaitu Noegroho, Hardojo dan Soemini menambah lengkap keluarga priyayi mereka. Semua anak mereka pun sukses mengikuti jejak Sastrodarsono menjadi seorang priyayi. Noegroho yang menjadi Guru HIS kemudian banting setir ikut PETA pada zaman pendudukan Jepang, dan kemudian pindah menjadi perwira TNI pada zaman kemerdekaan. Hardojo, menjadi seorang abdi Mangkunegaran dan menantunya Harjono (suami Soemini) seorang Asisten Wedana. Sastrodarsono, adalah anak tunggal Mas Atmokasan seorang anak petani desa Kedung Simo. Sebelumya ia hanya bekerja sebagai guru bantu di Ploso. Dengan jabatan guru bantu itu, berarti Sastrodarsono adalah orang pertama dalam keluarganya yang berhasil menjadi priyayi. Sastrodarsono dijodohkan dengan Ngaisah yang nama aslinya Aisah putri tunggalnya seorang mantri candu di Jogorogo. Dik Ngaisah, begitu ia memanggil istrinya, ia seorang istri yang mumpunyai lengkap akan kecakapan dan keprigelannya bukan hanya pandai mamasak ia juga memimpin para pembantu di dapur, karena memang sejak lahir ia sudah menjadi anak priyayi dibandingkan dengan Sastrodarsono yang baru akan menjadi priyayi. Sepeninggalannya Mbah putrid, kesehatan Eyang kakung semakin memburuk yang sampai akhirnya ia meninggal dunia. Dalam upacara sambutan selamat tinggal untuk Sastrodarsono, semua anggota keluarga Sastrodarsono tidak ada yang berani memberikan pidato kata-kata terakhir. Akhirnya Lantip yang dijadikan wakil dari keluarga besar Sastrodarsono yang menyampaikan pidato selamat jalan itu. Lantip, meskipunia adalah anak haram hasil hubungan Soenandar dan ibu kandungnya, Ngadiyem, tetapi sesungguhnya dialah yang telah berhasil menjadi seorang priyayi yang sebenarnya. Terlihat dari ketulusan dan kesediaannya membantu para anggota keluarga Sastrodarsono. Namun, ia tak bangga dengan semua itu. Cerita pun 36 ditutup dengan peristiwa Lantip mengajak calon istrinya yang bernama Halimah ke makam Embok dan Embahnya dengan perasaan yang bahagia. 2. Gambaran Umum Novel Para Priyayi Novel Para Priyayi karya Umar Kayam dengan 308 halaman yang diterbitkan pada tahun 1992 ini menggambarkan warna-warni kehidupan tokoh-tokohnya yang berlatar kehidupan Jawa. Novel ini menceritakan realita kehidupan tokoh-tokohnya mengenai kehidupan keluarga besar priyayi Jawa dan masalah-masalah yang ada didalamnya. Keluarga ini adalah keluarga Sastrodarsono. Sastrodarsono adalah seorang anak petani desa yang berjuang hidup untuk membangun keluarga besar priyayi. Berkat kesetiaan ayahnya menggarap sawah Ndoro Seten, seorang priyayi Kedungsimo, ia disekolahkan dan berhasil mengantongi beslit guru bantu. Melalui dunia pendidikan itulah ia masuk golongan para priyayi. Pandangan hidup yang dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu sebagai guru bantu ternyata membuahkan hasil yang tak terduga. Mimpinya membangun keluarga priyayi, disertai dengan keuletan, taat pada orang tua dengan sikap orang jawa yang ikut, nurut, dan manut ternyata dapat terwujud. Ia merupakan gambaran pria jawa yang selalu patuh, mulai dari perjodohannya dengan seorang gadis sampai pada kesabaran dan ketelatenannya menjalani karir dan juga berumah tangga. Perjuangan menaiki tangga priyayi yang dibangun oleh Satrodarsono tidak selamanya berjalan sesuai keinginannya. Perjuangannya mulai luntur pada generasi anak cucunya. Mereka sudah mulai tergilas arus modernisasi. Akan tetapi, di sisi yang lain, keluarga Sastrodarsono berhasil menemukan priyayi yang sesungguhnya, yaitu Lantip. Ia adalah seorang lelaki yang tidak berdarah priyayi, namun memiliki jiwa priyayi yang sebenarnya. Dalam konteks kebudayaan Jawa, kata priyayi digunakan untuk menyebut orang-orang yang terhormat atau disegani dalam masyarakat. Dalam konteks ini, semua guru, pejabat atau pemerintah bisa juga disebut 37 priyayi. Namun, novel Para Priyayi menyajikan ceritayang berbeda mengenai priyayi yang sebenarnya, bahwa priyayi itu bukan dari darah birunya, bukan dari posisi dan jabatannya, melainkan dari sikap kesungguhannya untuk melayani dan mengayomi rakyat. Hal ini disampaikan pada bagian terakhir saat tokoh Lantip ketika ia berpidato di pemakaman Eyangnya. Lantip memaparkan dengan jelas tentang keberadaan Eyangnya selama masih hidup dalam mengayomi rakyat banyak terutama di bidang pendidikan. Novel ini menggambarkan kebudayaan lokal dengan penciptaan suasana, tempat, budaya, gaya bahasa, alur dan banyak hal lainnya dengan sangat mendetail. Budaya Jawa menjadi salah satu tolok ukur dan juga masalah yang diangkat dalam novel ini. Adanya kelas dalam masyarakat Jawa, membuat Sastrodarsono ingin membangun keluarga priyayi yang priyayi agung. Perjalanan Sastrodarsono diwarnai dengan berbagai tradisi lokal tentang perjodohan, gaya hidup priyayi yang meliputi cara hidupnya, berpakaian, makan, dan bagaimana posisi seorang istri priyayi harus bersikap intelek, baik secara pemikiran atau sikap. Para tokoh dalam novel ini pun dilahirkan dari latar tempat, sosial, dan waktu yang memang benar-benar menggambarkan kebudayaan Jawa pada saat itu. Terlihat jelas karena novel ini diwarnai dengan beberapa penggal tembang kinanti yang merupakan perwujudan kesenian Jawa di bagian tengah dan akhir novel. Tokoh-tokoh dalam novel terlahir dari latar budaya Jawa yang sangat kental, terutama dari dialog dan cara mengatasi berbagai konflik. Dalam novel ini terdapat kesenjangan sosial atau perbedaan kelas antara golongan priyayi dan masyarakat biasa, dimana seolah priyayi adalah cerminan tokoh putih dalam suatu cerita yang sangat dihormati dan dipercayai secara berlebihan. Status priyayi merupakan status yang banyak terlahir dalam suasana kehidupan orang Jawa. Priyayi sangat konsekuen dalam menjaga berlakunya sistem nilai dan rakyat kecil mengacu serta menganggap sistem nilai tersebut sempurna dan yang terbaik untuk dihormati bahkan diikuti. 38 Bahasa Jawa yang disajikan dalam novel ada tiga bahasa; Kromo Inggil (sangat halus), Kromo (halus), dan Ngoko (kasar). Misalnya, pada saat Lantip berbicara pada Sastrodarsono, Lantip menggunakan bahasa yang terkesan begitu halus dan berbeda pada saat Lantip berbicara dengan orang yang statusnya sama atau sebaya dengannya. Biasanya bahasa seperti Kromo Inggil tersebut dipakai oleh orang yang muda kepada orang yang tua apapun strata sosialnya, sedangkan kalau orang yang muda berbicara kepada orang yang muda juga atau yang setara umurnya, biasanya memakai yang halus (Kromo) atau bahasa yang kasar (Ngoko). Selain itu, disisipi pula istilah atau ungkapan Jawa disertai artinya. Bahasa yang digunakan mampu menghidupkan suasana, sehingga mampu membawa pembaca serasa larut dalam cerita. Terutama bahasa Jawa (logat Jawa) yang digunakan tokoh untuk berdialog. Selain itu, terdapat bahasa lain seperti bahasa Belanda dan Bahasa Jepang untuk menunjukkan masa pemerintahan pada saat itu. Melalui novel Para Priyayi, pembaca Indonesia yang berlatar belakang bukan Jawa akan dapat mengenal dan memahami sebagian kehidupan sosial budaya Jawa. Tingkah laku tokoh-tokoh dalam novel tersebut sarat akan nilai sosial. Mereka mengikatkan diri dengan penuh kesadaran terhadap aturan kelembagaan masyarakat Jawa. B. Tinjauan Eksternal 1. Biografi Umar Kayam Umar Kayam lahir di Ngawi, Jawa Timur, pada tanggal 30 April 1932.Ia memperoleh gelar Ph. D di Cornell University dengan tesis mengenai problem koordinasi pembangunan masyarakat Indonesia. Sejak menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada ia telah aktif dalam berbagai kegiatan kesenian. Namun baru mulai menulis karya-karya sastra pada tahun 1960‘an ketika berada di New York. Pada tahun 1968, cerita pendeknya ―Seribu 39 Kunang-kunang di Manhattan‖ dinilai sebagai cerpen terbaik yang dimuat dalam majalah Horison.1 Dalam dialog santai dengan A.S. Laksana dkk, dua bulan sebelum meninggal, Umar Kayam sempat mengisahkan masa kecilnya, kegemaran membaca yang terkondisi sejak kecilnya, dan awal kepengarangannya. Umar Kayam berasal dari keluarga guru. Ayahnya seorang guru Hollands Inlands School (HIS; sekolah dasar untuk anak-anak priyayi yang menyiapkan priyayi-priyayi gubernemen pada saat pemerintahan kolonial Belanda) di Mangkunegoro, Surakarta. Di sekolah dasar itu, ia sekelas dengan Wiratmo Soekito—Budayawan yang kelak terkenal sebagai konseptor Manifes Kebudayaan—yang dipanggilnya sebagai Kliwir. Keragaman membaca buku secara dini diperolehnya dari ayahnya yang mempunyai perpustakaan pribadi. Waktu di MULO (sekarang SMP), secara sembunyisembunyi karenatakut dimarahi ibunya – ia telah banyak membaca romanroman yang seharusnya baru boleh dibaca setelah ia dewasa, seperti novel Margaret Mitchel Gone with the Wind yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Belanda pada saat itu. Ia bisa menikmati novel yang mengisahkan perang saudara di Amerika Serikat itu. walaupun secara jujur ia mengatakan bahwa banyak yang tidak dipahaminya ketika itu.2 Kayam memulai dunia kesenian sejak SMP dengan giat di bidang drama, sastra, dan koran dinding. Saat ia di sekolah dasar ada keharusan untuk membaca dongeng-dongeng, dan ada pelajaran bercerita di depan kelas dalam bahasa Belanda. Diakuinya pendidikan Belanda itu memang baik, teratur, dan disiplin. Di kelas lima HIS, ia sudah menguasai bahasa Belanda. Sehariharinya, bersama orang tuanya ia berbicara dalam bahasa Jawa halus (kromo) campur Belanda. Bahasa Melayu dalam waktu itu bukan bahasa sehari-hari.Ia 1 DBB,Umar Kayam Memenangkan SEA Write Award 1987, HarianBerita Buana, Jakarta, 14 Juli1987, h. 4. 2 B. Rahmanto, Umar Kayam: Karya dan Dunianya, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 1-2. 40 les bahasa Melayu sore hari. Baru pada masa pendudukan tentara Jepanglah bahasa Indonesia diwajibkan secara intensif sebagai bahasa pengantar. Ia mulai belajar mengarang saat duduk di SMA bagian A (Bahasa) di Yogyakarta. Awalnya, karena memenuhi tugas pelajaran dengan tema-tema yang diberikan oleh gurunya. Bersama teman-teman sekelasnya, seperti Nugroho Notosusanto dan Daoed Joesoef (dua-duanya pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI), Umar Kayam mendapat tugas mengelola majalah dinding sekolah. Di majalah dinding itulah Umar Kayan dan tema-temannya mengekspresikan tulisannya dalam bentuk puisi (katanya yang paling banyak), cerpen, esai, dan pembicaraan karya-karya pengarang, seperti Tagore, S. Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Chairil Anwar.3 Umar Kayam Universitas Gadjah melanjutkan pendidikan di Mada, Yogyakarta. Ia Fakultas ruang Pedagogi kemahasiswaan ―Universitaria‖ di RRI Nusantara II Yogyakarta yang berisi berita dan kegiatan mahasiswa dan mendirikan majalah mingguan bertajuk Minggu. Minatnya terhadap dunia pers ini kelak akan tersalurkan lewat kolom rutinnya di halaman depan yang diterbitkan di harian Kedaulatan Rakyat setiap hari Selasa sejak 12 Mei 1987 sampai dengan pertengahan tahun 2000. Kolom Kedaulatan Rakyatmenarik minat banyak pembaca kerena dituturkan dengan singkat, penuh humor cerdas, canda, tidak ngotot, kadang secara tidak langsung menyampaikan sendirian, protes, usul, nasihat, dan sebagainya. Kolom ini akhirnya dikumpulkan dan diterbitkan kembali menjadi 4 buah buku. Tahun 1955 Umar Kayam menyelesaikan sarjana muda-nya, lalu bekerja di Jakarta beberapa tahun. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Amerika Serikat, memperoleh gelar Master of Educationdari Newyork University School of Education (1963), dan akhirnya memperoleh gelar 3 Ibid., h. 2-3. 41 Doctor of Philosophydi Cornell University dengan disertasi berjudul ―Aspect of Interdepartmental Coordination Problems in Indonesian Community Development‖ (1965). Sepulangnya dari Amerika Serikat, oleh Presiden Soeharto ia ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Departemen Penerangan RI (1966-1969); kemudian ia terpilih untuk menggantikan Trisno Sumardjo (1969-1972) sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan selama itu pula ia merangkap sebagai Rektor Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ; sekarang Institut Kesenian Jakarta, IKJ) di Jakarta, di samping sebagai anggota Board of Trustee International Broadcast Institute yang berpusat di Roma, Italia selama dua tahun. Jabatan lainnya yang pernah diemban adalah Direktur Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin, Ujungpandang (1975-1976), Direktur Pusat Penelitian Kebudayaan di UGM (1977-1997), dosen pascasarjana UGM, dan dosen kontrak di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (19982001). Ia dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Sastra UGM dengan pidato bertajuk ―Transformasi Budaya Kita‖ yang diucapkannya di depan rapat senat terbuka Universitas Gadjah Mada, 19 Mei 1989, dan pamit pensiun dalam seminar untuk Umar Kayam sehubungan dengan purnabakti sebagai guru besar Fakultas Sastra UGM, 11-12 Juli 1997.4 Umar Kayam juga pernah bermain film dan sinetron, antara lain dalam film Karmilayang disutradarai oleh Ami Priyono, memerankan Bung Karno dalam film Pengkhianatan G-30-S/PKI dengan sutradara arifin C. Noer, dan berperan sabagai Pak Bei dalam sinetron yang diangkat dari novel Arswendo Atmowiloto yang berjudul Canting. 4 Ibid., h. 4-5 42 Umar Kayam, disamping seorang sastrawan, adalah seorang budayawan. Sebagai sastrawan ia telah menulis beberapa karya sastra, antara lain, Seribu Kunang-Kunang di Manhattan (Kumpulan Cerpen), Sri Sumarah dan Bawuk, (dua novel pendek dalam satu buku), Parta Krama (Kumpulan Cerpen), Para Priyayi, dan Jalan Menikung. Sementara itu, sebagai seorang budayawan ia telah menghasilkan beberapa kumpulan tulisan mengenai seni dan budaya yang antara lain terkumpul dalam Mangan Ora Mangan Kumpul, Sugih Tanpa Banda, Madhep Ngalor Sugih, Madhep Ngidul Sugih, Perubahan Nilai dalam Islam, dan Seni dan Tradisi dalam Masyarakat.5 Umar Kayam menikah dengan Roosliana Hanum, 1 Maret 1959, dikaruniai dua orang putri, yang sulung bernama Sita Aripurnami dan si Bungsu Wulan Anggraeni. Ia meninggal dunia di Jakarta menjelang usianya yang genap 70 tahun, Sabtu, 16 Maret 2002, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet, Jakarta. 2. Karya-karya Umar Kayam Dalam karya-karyanya yang berlatar Amerika, Umar Kayam bertutur sebagai pengamat. Umar Kayam mulai menulis cerpen dengan agak teratur ketika ia tugas belajar di Amerika Serikat. Begitu tugas belajar selesai dan pulang ke tanah air, muncullah cerpen pertamanya di majalah Horison, No. 4 Tahun I, 1966 berjudul ―Seribu Kunang-kunang di Manhattan‖. Cerpen ini terpilih sebagai cerpen terbaik majalah Horison1966/1967. Cerpen ini sangat populer sehingga oleh Yayasan Obor Indonesia (1999) diterbitkan dalam terjemahan 13 bahasa daerah yang masih hidup di Indonesia dalam rangka Program Pemetaan Bahasa Nusantara 1999. Setelah kumpulan cerpennya ―Seribu Kunang-kunang di Manhattan‖, Umar Kayam menerbitkan kumpulan cerita panjang ―Bawuk dan Sri Sumarah‖. Cerpen-cerpennya ini menceritakan tentang kejiwaan dan 5 Acep Iwan Saidi, Matinya Dunia Sastra Biografi Pemikiran & Tatapan Terberai Karya Sastra Indonesia, (Jakarta: Pilar Media, 2006), h. 112. 43 pergolakan batin wanita-wanita Jawa, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Harry Aveling. Dua cerpennya yang terakhir ini diterbitkan kembali pada tahun 1986, dengan ditambah beberapa cerpen lainnya yang terbaru seperti ―Kimono Biru untuk Istriku‖, bukunya yang terakhir inilah yang mengantarkan Umar Kayam menjadi pemenang SEA Write Award 1987.6 Umar Kayam pernah menulis buku kanak-kanak Totok dan Toni (1975).Dua noveletnya yang berjudul ―Sri Sumarah‖ dan ―Bawuk‖ pernah diterbitkan menjadi satu buku dengan judul Sri Sumarah dan Bawuk(1975). Akan tetapi, akhirnya disatukan dengan kumpulan cerpennya Seribu Kunangkunang di Manhattan (1972) ke dalam judul Sri Sumarah dan Cerita Pendek lainnya (1986). Tiga cerpennya, yaitu ―Seribu Kunang-kunang di Manhattan‖.―Bawuk‖, ―Musim Gugur Kembali di Connecticut‖, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dimuat dalam antologi Harry Aveling (ed.) From Surabaya to Armagedon (1976). Cerpen-cerpennya yang lain juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Harry Aveling dan diterbitkan di Singapura dengan judul Sri Sumarah and other stories (1976). Kumpulan cerpennya yang lain adalah Parta Krama (1997) yang diterbitkan dalam rangka ulang tahunnya yang ke-65, dan Lebaran di Karet, di Karet ... (2002) yang diterbitkan setelah Umar Kayam meninggal. Ia juga menulis dua buah novel yang berjudul Para Priyayi (1992), dan Jalan Menikung Para Priyayi 2 (1999). Para Priyayi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Sebagai sastrawan, tahun 1987 ia memperoleh Hadiah Sastra ASEAN.7 6 DBB, Umar Kayam Memenangkan SEA Write Award 1987, Harian Berita Buana, Jakarta, 14 Juli 198, h. 4. 7 B. Rahmanto, Umar Kayam: Karya dan Dunianya, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 5-6. 44 Umar kayam dalam peta kesusastraan Indonesia mencuat namanya karena cerpen panjangnya ―Sri Sumarah‖ dan ―Bawuk‖ serta beberapa cerpen lainnya yang dimuat di majalah Horison. Melalui cerpen-cerpennya ia berhasil mengangkat kultur Jawa dengan sangat meyakinkan. Begitu pula dengan novelnya, yaitu Para Priyayi. Novel Para Priyayi menghadirkan kebudayaan Jawa melalui tokoh-tokohnya yang sangat kental dengan citra priyayinya. Karya Umar Kayam yang berbentuk buku nonfiksi, antara lain Seni, Tradisi, Masyarakat (1981) dan The Soul of Indonesian, A Culture Journey yang diterbitkan oleh Louisiana University Press yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Semangat Indonesia: Suatu Perjalanan Budaya (1985). Selain menjadi kolumnis di beberapa surat kabar dan majalah, kolom-kolomnya yang sangat digemari pembaca di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Kolom-kolomnya yang secara rutin hadir setiap hari Selasa, akhirnya diterbitkan secara berseri dengan judul Mangan Ora Mangan Kumpul (1990), Sugih Tanpa Banda (1994), Madhep Ngalor sugih, Madhep Ngidul Sugih (1998), dan Satrio Piningit ing Kampung Pingit (2000). Sebelum wafatnya, Umar Kayam masih sempat menerbitkan hasil penelitiannya pada tahun 1993-1995 tentang wayang kulit dan dibukukan dengan2 judul Kelir Tanpa Batas (2001).8 3. Pandangan Hidup Umar Kayam Umar Kayam, disamping seorang sastrawan, adalah seorang budayawan. Dua predikat yang disandang Kayam tersebut tidak bertolak belakang, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Melalui karya sastra, ia menuangkan pemikiran-pemikirannya mengenai kebudayaan dan sebaliknya, gagasan-gagasan besarnya mengenai kebudayaan dapat dilihat dalam nilai-nilai yang terdapat dalam tulisannya. 8 Ibid., h. 6. 45 Ia berpandangan terhadap para penulis bahwa seorang penulis mempunyai tugas sosialnya sendiri. tugas ini bukan memimpin, bukan mewejang karena dia bukan seorang pendeta atau kyai, bukan ‗menyelamatkan dunia‘ karena dia bukan seorang nabi. Menurutnya, tugas seorang penulis adalah sederhana: bercerita dengan jujur, pada tempatnya dan indah‖. Ia tidak alergi terhadap kebudayaan asing. Kebudayaan Indonesia adalah ―… kemajemukan budaya dan kreativitas kita ‗memainkan‘ kemajemukan kita itu. Ini berarti bahwa kita mesti bersedia memiliki ‗bidang bahu yang selebar-lebarnya‘ dalam menyediakan ruang gerak yang bebas untuk mengembangkan ‗kepribadian bangsa‘ yang akan muncul bersama kultur kita yang majemuk dinamis itu‖.9 Kayam dengan semangat sosialnya selalu mengikhtiarkan seni tradisi yang kini baur dengan timbulnya seni kontemporer yang elitis hingga kesenian rakyat makin terpencil dan kesenian klasik ―kraton‖ menjadi kesenian salon, maka ia menghimbau: ―Sudah waktunya kreativitas dipahami dalam konteks perkembangan masyarakat. ―Sudah waktunya ‗strategi pengembangan kesenian‘ mengacu kepada kaitan kreativitas seni dengan perkembangan masyarakat‖. Salah satu pandangannya mengenai kebudayaan adalah masalah transformasi. Kayam berpandangan bahwa nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat terbentuk melalui proses transformasi. Melalui tulisannya, Transformasi Budaya Kita, Kayam mengandaikan transformasi sebagai suatu proses pengalihan total dari suatu bentuk baru yang akan mapan. Transformasi dapat pula dibayangkan sebagai suatu proses yang lama 9 Diro Aritonang, Doktor Umar Kayam Budayawan yang Tangguh, Harian Pikiran Rakyat, Bandung, 30 Oktober 1982, h. 7. 46 bertahap-tahap, tetapi dapat pula dibayangkan sebagai suatu titik balik yang cepat, bahkan abrupt.10 Masyarakat Jawa adalah salah satu komunitas budaya yang mengalami proses transformasi. Gambaran budaya Jawa tersebut, selain dapat dilihat dari perilaku, adat istiadat, gaya hidup, dan pola pikir masyarakat, juga tercermin dalam berbagai karya sastra. Transfrormasi nilai budaya Jawa dalam novel Para Priyayi tercermin melalui peristiwa-peristiwa yang dialami keluarga Sastrodarsono (sebagai generasi pertama) dan keluarga Hardojo dan Harimurti (generasi kedua dan ketiga). Umar Kayam terkenal dengan teorinya mengenai manusia Indonesia sebagai ―Pejalan Budaya‖ (Cultural Commuter), yaitu sebagai orang-orang yang bergerak secara bolak-balik dari budaya tradisional ke budaya modern, dari desa ke kota, dan sebagainya. Berbagai ilustrasi mengenai sudut pandang serta teori perubahan dan transformasi menunjukkan bahwa masyarakat Negara dibayangkan, pada suatu masa, berubah, bahkan menghendaki perubahan yang terakhir (sementara) dengan status transformasi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa cepat atau lambat serat-serat suatu budaya yang menyangga, anyaman teguh suatu kebudayaan masyarakat, pada suatu saat akan meruyak dan membusuk untuk kemudian tidak berfungsi lagi sebagai pengikat suatu kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan Jawa secara khusus dan Indonesia pada umumnya, Kayam menguraikan secara historis terjadinya transformasi tersebut. Menurutnya, transformasi itu mulai terjadi ketika agama Hindu dan Budha dianut masyarakat. Ketika itu terjadi transformasi budaya India ke dalam kebudayaan Indonesia. Berikutnya transformasi budaya terjadi lagi ketika pada abad ke-13 Islam datang. Terjadilah pertemuan antara HinduBudha dan Islam yang kemudian di Jawa dikenal juga dengan Islam-Jawa. 10 Acep Iwan Saidi, Matinya Dunia Sastra Biografi Pemikiran & Tatapan Terberai Karya Sastra Indonesia, (Jakarta: Pilar Media, 2006), h.114. 47 Selanjutnya bangsa Barat, antara lain Inggris, Portugis, dan Belanda pun menyusul berdatangan ke Indonesia. Maka sekali lagi transformasi budaya terjadi, yakni menyebarnya budaya Barat yang secara otomatis dibawa oleh bangsa-bangsa tersebut. Kayam menawarkan beberapa kriteria perilaku, yakni terbuka (kompromis dan dialogis), luwes, dan kreatif. Kayam mengatakan bahwa sikap ini adalah ―perintah historis‖. Ia telah lama dimiliki oleh nenek moyang kita. Ketika Hindu dan Budha datang dengan budaya Indiannya, yang terjadi bukan Indianisasi, melainkan Indonesianisasi atau Jawanisasi dalam konteks kebudayaan Jawa. Yang menarik dari transformasi itu, menurut Kayam, adalah nampaknya bahasa ―perintah historis‖ yang agaknya selalu mengingatkan pada nenek moyang kita untuk pandai-pandai memperhitungkan serta memanfaatkan kondisi geografis, geoekonomis, serta geopolitik dari kepulauan kita. Bahasa tersebut mengisyaratkan idiom luwes, lentur, adaptable, dan kreatif dalam menghadapi berbagai budaya luar. Dari sikap tersebut terciptalah suatu hasil yang mengagumkan sebagaimana ungkapan berikut ini. Kebudayaan yang terbentuk di Sriwijaya, Mataram I, Singasari, Majapahit, Aceh, Makasar, Bone, Kemudian Mataram II, dan sebelumnya Demak dan Pajang adalah contoh-contoh dari hasil dialog budaya dengan agama-agama Budha, Hindu, dan Islam. Dialog budaya tersebut manghasilkan, baik arsitektur ―dalam‖ seperti seni memerintah, pertunjukan, tari, kesusastraan, dan berbagai macam seni ritual yang kaya dan canggih. Karena sikap terbuka, luwes, dan kreatif tersebut, konflik-konflik budaya dapat dihindarkan meskipun budaya yang datang mengikis habis hegemoni politik dan kekuasaan pada saat transformasi terjadi di Demak. Untuk hal ini Kayam memberi contoh transformasi Islam yang terjadi di Demak. Menurutnya, meskipun Demak muncul untuk menggantikan hegemoni Majapahit dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, ia 48 memberikan satu indikator adanya transformasi yang tidak menimbulkan konflik-konflik sosial, transformasi itu berjalan melalui penyebaran gagasan dan ide.11 Cara pandang tersebut ternyata bukan sebatas retorika, melainkan juga melekat dalam perilakunya. Ia adalah seorang Islam abangan, Islam yang unsur Jawanya sangat kental, Islam yang merupakan hasil dialog terbuka dengan budaya Jawa. Dengan perkataan lain, Islam abangan adalah Islam hasil transformasi budaya yang kompromis. Jika sebuah cara pandang terhadap sesuatu telah menjadi jalan hidup, sebagai seorang sastrawan, terbuka peluang besar bagi kawan untuk mengemukakan gagasan-gagasannya tersebut melalui karya-karyanya.12 Demikianlah inti dari gagasan Kayam mengenai transformasi budaya.Dari gagasannya tersebut dapat ditemukan bagaimana sikap Kayam dalam ―memandang dunia‖. Cara pandangnya yang terbuka dalam arti kompromis dan dialogis dengan diimbangi oleh kreativitas adalah sikap mendasar Kayam dalam menyikapi transformasi budaya yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini terutama budaya Jawa tempat ia dilahirkan, hidup, dan bergaul secara intens, baik melalui media literer maupun interaksi langsung sebagai manusia Jawa. 11 Ibid., h. 115. Ibid., h. 117. 12 BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS NILAI SOSIAL A. Unsur-unsur Intrinsik dalam Novel Para Priyayi 1. Tema Setiap novel mengandung gagasan pokok atau sering disebut dengan tema. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah cerita. Sebuah karya sastra, seperti novel tentulah tidak terlepas dengan adanya tema. Selain karena tema adalah sebuah topik dalam cerita, tema juga merupakan gagasan dasar yang menunjang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks, sehingga tema sering menjadi kiblat untuk menentukan konflik dalam rangkaian peristiwa. Tema yang diangkat dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam mengenai perubahan status sosial. Bagaimana perjuangan hidup untuk mengubah status sosial demi membangun satu generasi priyayi yang berusaha diwujudkan oleh seorang anak petani yang sebagai pemula telah berhasil menjadi priyayi. Tema ini menonjol pada kutipan di bawah ini. “Hari itu saya, Soedarsono, anak tunggal Mas Atmokasan, petani Desa Kedungsimo, pulang dari Madiun dengan berhasil mengantongi beslit guru bantu di Ploso. Guru bantu. Itu berarti sayalah orang pertama dalam keluarga besar kami yang berhasil menjadi priyayi, meskipun priyayi yang paling rendah tingkatnya. Itu tidak mengapa. Yang penting kaki saya sudah melangkah masuk jenjang priyayi.”1 Sastrodarsono, nama aslinya Soedarsono adalah anak Atmokasan seorang petani desa Kedungsimo yang berhasil menempuh pendidikan dengan baik sehingga diangkat menjadi guru bantu di Ploso. Itulah awal kepriyayiannya, meski priyayi yang paling rendah tingkatannya. Dia 1 Umar Kayam, Para Priyayi Sebuah Novel, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2011), Cet. XIII, h. 32. 49 50 mengawali karir priyayinya dengan menjadi guru bantu hingga akhirnya naik pangkat dan menjadi priyayi sungguhan. Ia membangun keluarga besar priyayi. Para Priyayi karya Umar Kayam menampilkan kehidupan sosok priyayi dari berbagai perspektif kepriyayian. Priyayi merupakan sebuah takdir, karena terlahir dari rahim perempuan priyayi. Akan tetapi, priyayi juga dapat diperoleh dari sebuah proses pendidikan dan pemerolehan jabatan pemerintahan. Novel Para Priyayi menunjukkan hal ini. Status kepriyayian diungkapnya. Seperti apa sebenarnya kehidupan priyayi, bagaimana seorang priyayi seharusnya berperilaku di masyarakat, dan bagaimana jika priyayi tidak memiliki etika idealnya seorang priyayi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “… Beberapa tahun lagi, kalau saya rajin dan setia kepada gupermen, saya akan menjadi guru penuh sekolah desa. Itu akan lebih memantapkan kedudukan saya sebagai priyayi, sebagai abdi gupermen. Dan kalau saya sudah menjadi mantri guru, wah, itu sudah boleh dikatakan menjadi priyayi yang terpandang.”2 Masalah pendidikan pun ikut menentukan status sosial dan mengangkat martabat seseorang dalam masyarakat. Pendidikan ikut menentukan kepriyayian seseorang, dan kesanggupannya mengejawantahkan status kepriyayian itu dalam kehidupan ini, terutama pertanggungjawabannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “... semangat kerukunan dan persaudaraan itu yang terpenting ...semangat pengabdian kepada masyarakat wong cilik. ... perjalanan mengabdi pada masyarakat banyak, terutama wong cilik, tidak akan ada habisnya.”3 Priyayi adalah sebuah status sosial yang dianggap terhormat di masyarakat, yang tidak semua orang dapat menyandang status tersebut. 2 Ibid., Ibid., h. 333-335. 3 51 Keluarga priyayi harus bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang priyayi agar keturunannya tidak keluar dari konsep “kepriyayian”, namun faktanya banyak keluarga priyayi yang tidak mampu menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang priyayi. Justru orang yang berasal dari keturunan wong cilik, dengan usahanya dapat mencapai status priyayi dan mampu menjaga sikap dan perilakunya layaknya seorang priyayi. Perjuangan priyayi sejati demi mengayomi keluarga dan rakyat kecil ini ditunjukkan oleh Lantip. Lantip yang merupakan anak hasil hubungan di luar nikah antara Ngadiyem dan Soenandar, keponakan Sastrodarsono, tampil sebagai pahlawan. Lantip mampu menyelesaikan permasalahan anak-cucu Sastrodarsono dan menjadi priyayi yang sebenarnya. Bukan sekedar priyayi yang terhormat, tetapi bagaimana sesungguhnya menjadi seorang priyayi yang mriyayeni atau mengayomi rakyat kecil. Dengan demikian, dalam novel Para Priyayi digambarkan bahwa status priyayi tidak mutlak milik darah biru saja, melainkan lebih merupakan sebuah proses pencapaian. Lantip dan Sastrodarsono merupakan tokoh yang mengemban proses menjadi priyayi. Keduanya bukan berasal dari keluarga priyayi, melainkan hanya wong cilik yang hidup di desa. Hanya saja dengan usaha, ketrampilan, kecakapan, dan keberuntungan keduanya mencapai tingkatan priyayi. Setelah menganalisis tema yang merupakan unsur yang paling penting dan dominan dalam unsur intrinsik, selanjutnya peneliti akan menganalisis tokoh dan penokohan. 2. Tokoh dan Penokohan Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang paling berkaitan dalam unsur intrinsik pada sebuah cerita rekaan. Keduanya menjadi saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pembahasan. Tokoh adalah pelaku yang memegang peran sebuah peristiwa dalam cerita rekaan sehingga terjalin 52 suatu cerita, sedangkan cara sastrawan menampilkan citra tokoh dalam cerita disebut penokohan. Ditinjau dari peranan dan keterlibatan dalam cerita, tokoh dapat dibedakan atas tokoh primer, tokoh sekunder (bawahan), dan tokoh komplementer (tambahan). a. Lantip Lantip, nama aslinya adalah Wage karena lahir pada hari Sabtu Wage. Nama Lantip itu adalah sebuah nama pemberian dari keluarga Sastrodarsono saat Lantip tinggal di keluarga itu, yaitu di jalan Satenan di Wanagalih. Dalam bahasa Jawa, nama ini punya makna yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Nama anakmu akan kami ganti. Nama Wage rasanya kok kurang pantes buat anak sekolah. Saya usul namanya diganti Lantip. Lantip artinya cerdas, tajam otaknya. Bagaimana?”4 “Bentuk penokohan yang paling sederhana adalah pemberian nama. Setiap sebutan adalah sejenis cara memberi kepribadian, menghidupkan.”5 Dalam novel Para Priyayi, Umar Kayam menciptakan tokoh dengan nama yang indah sesuai dengan karakternya. Seperti “Lantip”, maka ia betul-betul seperti itu dalam ceritanya. Benar-benar tajam otaknya, cerdas. Dia selalu menjadi juru selamat tatkala anak-anak dan cucu-cucu Sastrodarsono terkena musibah. Karena kepintarannya juga, dia dengan mudah lulus dari UGM, dan menjadi dosen. Dia juga dengan luwes dan berhasil menyesuaikan diri dalam etika kepriyayian. Lantip direpresentasikan sebagai priyayi ideal. Dalam ceritanya pun, Lantip nyaris tidak mengalami konflik. 4 Ibid., h. 20. Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan Terjemahan dari Theory of Literature oleh Melani Budianta, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 287. 5 53 Sebelumnya Lantip tinggal bersama Emboknya di desa Wanalawas yang hanya beberapa kilometer dari kota Wanagalih. Hubungan Embok Lantip dengan keluarga Sastrodarsono itu dimulai dari penjualan tempe keliling. Rupanya tempe buatan Embok Lantip itu berkenan di hati keluarga Sastrodarsono. Hingga akhirnya keluarga Sastrodarsono menjadi pelanggan tetap tempe Emboknya Lantip. Selain itu, Lantip diminta tinggal di Setenan dan disekolahkan oleh Sastrodarsono dan Ngaisah. Lantip sangat bersyukur atas kesempatan yang ia peroleh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Saya tidak membayangkan apa-apa. Saya sudah merasa bersyukur mendapat kesempatan bersekolah, diongkosi, mendapat tempat berteduh lagi di Setenan.”6 Lantip merupakan tokoh primer. Tokoh primer merupakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Ia menjadi tokoh penting, karena semua cerita terfokus dan tertuju kepadanya (sentral). Dalam novel Para Priyayi, Lantip menjadi tokoh yang cukup banyak mengambil bagian dalam cerita. Ia juga berfungsi sebagai pengantar cerita dari tokoh satu kepada tokoh yang lain. Dalam novel diceritakan bahwa Lantip menjadi tokoh yang paling dominan, karena tahapan kehidupan Lantip diceritakan secara tuntas dari awal cerita hingga akhir cerita. Selain karena tahapan kehidupan Lantip yang diceritakan secara tuntas, ia juga menjadi sentral dari penyampaian tema cerita yang tergambar dalam setiap tahapan yang dilaluinya. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada kutipan-kutipan di bawah sebagai berikut. Tahap pertama kehidupan Lantip digambarkan telah menjadi priyayi agung Jakarta. Kemudian, diceritakan keadaan Lantip pada 6 Kayam, Op. Cit., h. 28. 54 masa kanak-kanak dengan ibunya yang berjualan tempe. Lantip diceritakan belum mengetahui ayah kandungnya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Ayah saya... wah, saya tidak pernah mengenalnya. Embok selalu mengatakan ayah saya pergi jauh untuk mencari duit.”7 Setelah ibunya meninggal, Lantip diberi tahu oleh Pak Soeto, Dukuh Wanalawas, mengenai ayah kandungnya. Lantip akhirnya tahu bahwa ia adalah anak jadah (haram) antara ngadiyem dan Soenandar, yang tidak lain adalah keponakan Sastrodarsono. Mulai saat itu ia tahu bahwa ibunya mengenal keluarga Sastrodarsono bukan suatu kebetulan, karena jiwa besar dan baktinya kepada keluarga Sastrodarsono yang ternyata adalah Embah Kakungnya, ia pun telah mengerti dan berjanji tidak akan sakit hati ketika Sastrodarsono marah, kemudian memaki Lantip dengan sebutan anak gento ataupun anak maling. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Dan Embah Guru yang penuh humor itu akan seketika berubah menjadi makhluk yang lain sekali. Menakutkan. “Guoblok! Disuruh minta uang saja tidak bisa. Dasar anak gento, anak maling cecrekan….” Begitulah umpat serapah itu.”8 “Dan panjenengan Ndoro Guru Kakung miwah putri. Apa yang dapat saya katakan selain rasa terima kasih saya yang tulus dan utang budi yang tidak akan mungkin lunas hingga akhir hayat saya. Saya akan kembali ke Wanagalih, ke dalem Setenan, ke bawah perlindunganmu, berbakti kepada seluruh keluargamu. Umpatanmu yang sekali-sekali kau lontarkan, “anak maling, perampok, gerombolan kecu”, tidak akan mungkin menyakiti saya lagi. Bahkan sebaliknya akan memperkokoh semangat saya untuk menjunjung keluarga Sastrodarsono.”9 7 Ibid., h. 11. Ibid., 9 Ibid., h. 134. 8 55 Tokoh Lantip digambarkan sebagai tokoh yang sabar, rajin, taat, dan ulet. Selain itu, ia juga cekatan dalam mengerjakan tugastugas dalam rumah tangga priyayi. Ketika itu, Lantip masih kecil dan baru saja ikut keluarga Sastrodarsono, tetapi Lantip sudah dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Wah, wong anak desa sekecil kamu, kok ya cepet belajar mengatur rumah priyayi, lho,” kata Lik Paerah.10 Lantip digambarkan sebagai tokoh yang sabar. Ketika masuk sekolah pertama kali, Lantip diganggu teman-temannya. Temantemannya berusaha membuat Lantip marah, tetapi ia selalu ingat pesan emboknya bahwa jangan mudah tersinggung dengan omongan bahkan ejekan teman. Pesan emboknya itu begitu kuat sehingga menjadi rem yang sangat manjur dalam tubuh Lantip. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Berapa kali sudah saya kena coba kawan-kawan yang seperti biasanya selalu ingin menjajaki kekuatan anak-anak baru. Tidak pernah saya ladeni.”11 …. “Anak ini selalu dapat kami diandalkan. Dalam usianya yang mendekati tiga puluh tahun itu belum juga sempat berumah tangga. Padahal dia sudah menjadi sarjana Gadjah Mada, sudah menjadi dosen, dan kabarnya ada kemungkinan akan ditarik ke Jakarta untuk satu jabatan yang lebih penting. Meski sudah sarjana dan pangkat sudah tinggi, dia masih saja tinggal bersama Hardojo dan menjadi anak yang setia di rumah itu. Semua tugas, mulai dari membantu mengurus rumah tangga hingga menjadi pendamping Hari, dilaksanakan dengan rasa enteng, gembira, dan beres.”12 Lantip adalah tokoh yang dapat diandalkan oleh seluruh keluarga besar Sastrodarsono dan suka menolong. Sikap Lantip ini 10 Ibid., h. 21. Ibid., h. 24. 12 Ibid., h. 253-254. 11 56 digambarkan secara dramatik. Ngaisah memberikan pandangannya mengenai Lantip yang selalu dapat diandalkan keluarganya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Setiap kali saya ingat anak ini tidak habisnya saya mengucap syukur. Gusti Allah Maha Adil. Anak jadah ini tumbuh sebagai anak yang sungguh baik dan amat berbakti kepada semua keluarga kami.”13 Lantip kuliah bersama dengan Harimurti. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Gus Hari, seperti telah saya katakan, adalah anak yang cerdas. Kuliah-kuliah di fakultas tidak ada yang Nampak sulit baginya. Saya mengambil jurusan fakultas yang sama, yaitu ilmu sosial dan ilmu politik, membutuhkan waktu sedikitnya dua kali lipat lebih lama daripada waktu Gus Hari untuk belajar.”14 Ketika Harimurti berpacaran dengan Retno Dumilah, seorang penyair yang juga merupakan teman organisasinya di Lekra, Lantip masih belum menemukan pasangan. Akan tetapi, ia tertarik pada seorang perempuan bernama Halimah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Akan saya sendiri, yang usianya sudah merayap mendekati tiga puluh satu tahun, masih juga belum bertemu dengan pacar yang pas. Tetapi, Halimah, rekan asisten asal Pariaman, Sumatra Barat, itu semakin tampil menarik saja. Mungkinkah ….”15 Ternyata Lantip dan Halimah berjodoh. Akhirnya ia bertunangan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Kang Lantip bertunangan dengan Halimah akhirnya. Saya ikut senang. Kakak saya itu sudah terlalu terlambat untuk bertunangan pada usia setua itu.”16 Setelah Ngaisah meninggal dunia, tidak lama setelah itu Sastrodarsono pun mengalami kemunduran pada kesehatannya, hingga 13 Ibid., h. 255. Ibid., h. 281. 15 Ibid., h. 284. 16 Ibid., h. 300. 14 57 akhirnya ia meninggal dunia. Pada saat jenazah Sastrodarsono dibawa menuju makam, keluarga bermusyawarah mengenai siapa yang akan berpidato selamat jalan sebagai perwakilan dari keluarga. Pada akhirnya, Lantiplah yang dipilih karena ia dianggap paling berjasa besar. Lantiplah priyayi sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Calon yang lebih pantas dan paling besar jasanya buat keluarga besar kita. Dialah orang yag paling ikhlas, tulus, dan tanpa pamrih berbakti kepada kita semua. Dialah priyayi yang sesungguhnya lebih daripada kita semua. Dia adalah Kakang Lantip.”17 Tahapan terakhir tokoh Lantip adalah ketika ia ikhlas menerima keputusan keluarga besar Sastrodarsono sebagai perwakilan keluarga dalam menyampaikan pidato selamat jalan. Kemudian ia sedikit merenung mengenai siapa dirinya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Saya menundukkan kepala. Saya anak pungut, anak haram jadah dari seorang bajingan, perusak nama baik keluarga, penghancur remuk nasib Embah Wedok dan embok saya, diusulkan untuk mewakili keluarga besar Satrodarsono.”18 Pada akhirnya, Lantip menyampaikan pidato selamat jalan kepada Sastrodarsono sebagai baktinya kepada keluarga yang sangat dicintainya itu. Jika merujuk pada pendapatnya P.J. Suwarno, dapat disimpulkan bahwa Lantip ialah “misioner” Umar Kayam, sebagai bentuk kritiknya terhadap penelitian Geertz.19 Di samping karena menikah di usia tua, ada usaha Umar Kayam untuk membuktikan “ucapannya”. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “... Kata itu 17 Ibid., h. 332. Ibid., 19 P.J. Suwarno, Novel Multidimensional, Majalah Basis, Yogyakarta, No.10/XL1/Oktober 1992, h. 386-389. 18 58 (priyayi maksudnya) tidak terlalu penting lagi bagi saya.”20 Lantip adalah orang yang ikhlas, sabar, tulus, dan tanpa pamrih. Dia adalah sosok priyayi yang sebenarnya. b. Sastrodarsono Sastodarsono adalah anak tunggal seorang petani yang bernama Atmokasan, petani Desa Kedungsimo. Sebelumya ia hanya bekerja sebagai guru bantu di Ploso. Dengan jabatan guru bantu itu, berarti Sastrodarsono adalah orang pertama dalam keluarganya yang berhasil menjadi priyayi. Ia berhasil menjadi guru bantu pertama dalam keluarga besarnya. Hal itu menandakan bahwa dialah orang pertama yang menjadi priyayi dikeluarga besarnya yang semuanya adalah petani desa. Dalam novel Para Priyayi, Sastrodarsono merupakan tokoh sekunder. Setelah tokoh primer, tokoh sekunder juga dianggap penting dalam sebuah cerita. Ia juga berfungsi sebagai pengantar dari cerita. Hal ini jelas digambarkan pada bagian ia pulang ke kampungnya setelah mendapat pangkat guru bantu. Sastrodarsono digambarkan sebagai tokoh yang patuh atau menurut saran dari orang tua. Sifat ini dapat dilihat ketika ia diberi nama tua. Selain itu, ketika orang tua Sastrodarsono memilihkan jodoh untuknya, ia pun menerimanya dengan kepatuhan. “Karena itu sudah sepantasnya kamu menyandang nama tua, Le. Nama Soedarsono, meskipun bagus, nama anak-anak. Kurang pantas untuk nama tua. Namamu sekarang Sastrodarsono. Itu nama yang kami anggap pantas buat seorang guru karena guru akan banyak menulis di samping mengajar. Sastro rak artinya tulis to, Le?” Saya mengangguk, menerima dan menyetujui, karena pada saat seperti itu hanya itulah yang dapat saya lakukan. “Inggih, Pak.”21 20 Kayam, Op. Cit., h. 307. 59 Nama Sastrodarsono diambil dari kata Sastro yang artinya tulis. Sastro, jika dikaitkan dengan “sastra”, bermakna bahasa yang tinggi, punya makna, dan berharga. Bahasa sastra mengacu pada bahasa kitab suci. Nama Satrodarsono dianggap pantas untuknya karena ia seorang guru yang pasti menulis ketika sedang mengajar. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “… Namamu sekarang Sastrodarsono. Itu nama yang kami anggap pantas buat seorang guru karena guru akan banyak menulis di samping mengajar. Sastro rak artinya tulis to, Le?”22 Awalnya nama Soedarsono (nama awal Sastrodarsono), diberikan oleh priyayi yang bernama Ndoro Seten, sedangkan kedua orangtua Soedarsono, jelas petani. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “....Dan karena hubungan itu pula saya mendapat nama Soedarsono, nama yang menurut bayangan kami hanya pantas dimiliki anak-anak priyayi saja. Dan Ndoro Seten, menurut Bapak, begitu saja menghadiahi nama kepada Embok saya waktu diketahuinya Embok hamil tua. ...”23 Dari peristiwa itu jelas sekali bahwa anak yang dikandung oleh istri Atmokasan, kelak akan menjadi priyayi. Ternyata benar, dia menjadi priyayi pertama dalam keluarganya. Dalam masyarakat Jawa terdapat tradisi mendapat nama tua ketika seseorang akan membangun rumah tangga. Inilah yang terjadi kepada Soedarsono yang kemudian berubah nama menjadi Sastrodarsono. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. 21 Ibid., h. 39. Ibid., 23 Ibid., h. 31. 22 60 “Saya duduk termangu, tidak mengira kalau saya akan mendapat nama tua pada hari itu. Tentu saya berharap juga pada suatu ketika mendapat nama tua itu karena memang sudah menjadi kebiasaan orang Jawa untuk mengubah nama anaknya menjadi nama tua pada waktu anak itu sudah mulai siap untuk membangun keluarga…”24 Sastrodarsono, sesuai dengan namanya, pintar membaca dan menulis, sampai akhirnya sekolah dan setamatnya langsung menjadi guru bantu, kemudian menjadi mantri guru atau kepala sekolah. Ini jelas suatu prestasi, bahkan diakui juga bahwa kedudukannya sebagai priyayi menjadi mapan. .... “Le, begini yo, Le. Bapak dan embokmu sudah mendapatkan jodoh buat kamu. Ini juga sudah kami rundingkan dengan pakde dan paman-pamanmu. Sudah kami pertimbangkan masak-masak. Sudah kami perhitungkan pula kedudukanmu sebagai priyayi. Sudah, to, calonmu ini akan cocok betuk dengan kamu.”25 Kutipan di atas menjelaskan bahwa setelah memasuki jenjang priyayi, Sastrodarsono mendapatkan beberapa kehormatan dari keluarganya. Sastrodarsono diberi nama tua dan dijodohkan oleh orang tuanya. Selain itu, kelihatan bagaimana Umar Kayam berusaha memformulasikan karakter seorang ayah di kalangan priyayi dan bagaimana peran seorang ayah dalam sebuah keluarga priyayi ketika menangani sebuah perjodohan anaknya. Di situ tercermin adanya karakter khas kehidupan priyayi Jawa yang bersifat patriarki tanpa harus didefinisikan dengan kalimat-kalimat kaku dan mati. Sastrodarsono dijodohkan dengan Ngaisah yang nama aslinya Aisah putri tunggalnya seorang mantri candu di Jogorogo. Dik Ngaisah, begitu ia memanggil istrinya, ia seorang istri yang 24 Ibid., h. 40. Ibid., 25 61 mumpunyai lengkap akan kecakapan dan keprigelannya bukan hanya pandai mamasak ia juga memimpin para pembantu di dapur, karena memang sejak lahir ia sudah menjadi anak priyayi dibandingkan dengan Sastrodarsono yang baru akan menjadi priyayi. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama saya tidak merasa terlalu kikuk menjadi kepala rumah tangga seperti yang dibentuk oleh istri saya itu. Dan ploso, desa yang lebih kecil dari Kedungsimo, jelas tidak susah menerima rumah tangga kami sebagai rumah tangga priyayi. Kami, karena penampilan Dik Ngaisah, dipandang oleh para guru di sekolah Desa Ploso sebagai lebih priyayi dari mereka.”26 Sastrodarsono menikah dengan Ngaisah. Ia tinggal di Ploso dan membangun rumah tangga priyayi bersama Ngaisah yang berasal dari keluarga priyayi. Maka akhirnya menjadi tidak sulit bagi keduanya untuk menciptakan rumah tangga priyayi. Akan tetapi, mereka hanya setahun tinggal di Ploso. Berkat usul atasannya, Ndoro Seten, Sastrodarsono dinaikkan pangkatnya menjadi guru di Karangdompol. Kemudian ia pindah dari Ploso ke Wanagalih. Itu pun atas usul Ndoro Seten dan mertuanya, Romo Mukaram. Alasannya karena jika tinggal di Karangdompol, rumah tangga Sastrodarsono tidak akan berkembang menjadi rumah tangga priyayi seperti yang diharapkan Sastrodarsono. Soedarsono memiliki tiga orang anak, Noegroho (Opsir Peta), Hardojo (Guru), dan Soemini (istri Asisten Wedana). Anak-anak mereka lahir dalam jarak dua tahun antara seorang dengan yang lain. Noegroho anak yang paling tua, kemudian menyusul kelahiran adikadik Noegroho, Hardojo dan Soemini. Anak-anaknya mereka masukan ke sekolah HIS, sekolah dasar untuk anak-anak priyayi, kemudian meneruskan pelajaran ke sekolah menengah atas priyayi, seperti 26 Ibid., h. 50. 62 MULO, AMS atau sekolah-sekolah guru menengah, seperti Sekolah Normal, Kweek Sekul dan sebagainya. Sastrodarsono hidup berkecukupan. Oleh karena itu, ia merasa wajib membantu sanak saudaranya yang tidak mampu, dibawalah tiga keponakannya (Sri, Soedarmin, dan Soenandar) untuk ikut tinggal dan di sekolahkan di Wanagalih. Salah satu keponakannya Soenandar memiliki perangai yang berbeda dari yang lain, jahil, nakal, dan selalu gagal dalam belajar. Suatu ketika Soedarsono yang telah berganti nama menjadi Sastrodarsono, mengutus Soenandar untuk mengurus sekolah yang didirikannya di Wanalawas, diharapkan agar Soenandar lebih mandiri dan dapat bertanggung jawab, tetapi Soenandar justru menghamili anak penjual tempe dan kabur. Lahirlah Wage yang kemudian diboyong ke wanagalih, dirawat dan disekolahkan, kemudian diganti namanya menjadi Lantip. Sastrodarsono memiliki sifat yang mudah menaruh belas kasih kepada orang lain. Hal ini dapat dilihat ketika Sastrodarsono melihat Ngadiyem membawa Lantip, yang masih kecil, berjalan berkilo-kilo meter untuk menjual tempe. Begitu melihat Lantip, Sastrodarsono meresa kasihan dan langsung bertanya kepada Ngadiyem yang membawa anaknya berjualan. Waktu mereka melihat Embok datang membawa saya, Ndoro Guru langsung menanyakan dengan nada suara, setidaknya bagi saya waktu itu, sangatlah ulem-nya dan sangat penuh wibawa. Percakapan itu kira-kira berbunyi seperti ini. “Lho, Yu, anakmu kok kamu bawa?” “Inggih, Ndoro. Di rumah tidak ada orang ynag menjaga, tole.” “Lha, kasian begitu. Anak sekecil itu kamu eteng-eteng ke mana-mana.”27 27 Ibid., h. 15. 63 Sastrodarsono juga memiliki sifat yang mudah terharu akan perilaku orang lain. Sifat ini dapat terlihat ketika Sastrodarsono melepas kepergian Martoadmodjo yang dipindahtugaskan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Pada satu sore menjelang pesta selamatan perpisahan dengan Mas Martoadmodjo di sekolah, beliau dengan anak dan istri mampir ke rumah. Kami nerima mereka dengan penuh keakraban dan keharuan.”28 Sastrosardono, meskipun orangnya baik dan adil, juga keras dan bila marah suka membentak sembari misuh, mengumpat. Hal ini ia lakukan pada Lantip. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “ Nah, pada waktu kadang-kadang saya mendapat hadiah umpatan itulah saya diberitahu secara tidak langsung siapa ayah saya itu. Umpatan itu berbunyi “bedes, monyet, goblok anak kecu, gerombolan anak maling……” umpatan itu biasanya keluar bila saya sudah dianggap keterlaluan bodoh dalam menjalankan tugas.”29 Sastrodarsono sangat mencintai istrinya, Ngaisah. Ketika Ngaisah meninggal ia begitu terpukul. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “….Mungkin pada saat Embah Kakung menyadari bahwa istri yang sangat dikasihinya itu pergi untuk selama-lamanya, beliau juga semakin menyadari akan arti kehadiran istrinya, Dik Ngaisah itu di sampingnya. Istri yang sudah membagi susah dan senang selama ini bersama Embah Kakung. Hal itu nampak benar pada waktu Embah Kakung menabur bunga di atas pusara Embah Putri. Ditaburkannya berkali-kali dengan irama gerak tangan yang sangat pelan dari arah utara, tempat kepala Embah Putri diletakkan, kea rah selatan, tempat kaki Embah Putri diletakkan.”30 28 Ibid., h. 71. Ibid., h.11. 30 Ibid., h. 267. 29 64 Setelah Ngaisah meninggal dunia, Sastrodarsono semakin mundur kesehatan dan pikirannya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Tiba-tiba kami mendapat surat kilat khusus dari Pakde Ngadiman bahwa Embah Kakung semakin mundur kesehatannya. Juga semakin pikun dan mulai sering menceracau juga. Bapak dan Ibu segera memerintahkan saya dan Gus Hari untuk pergi ke Wanagalih membantu Pakde Ngadiman dan anak-anaknya menjaga dan merawat Embah Kakung. Tahun 1967 ini Embah Kakung sudah berumur kirakira delapan puluh tiga tahun. Untuk orang Jawa itu sudah merupakan usia yang sangat lanjut. Kami seluruh keluarga besar mulai mengkhawatirkan bahkan sesungguhnya juga sudah bersiap untuk menghadapi keadaan yang paling buruk dengan kesehatan Embah Kakung.”31 Benar saja pada akhirnya Sastrodarsono meninggal dunia setelah ia begitu bersemangat ketika pemotongan pohon nangka yang ia anggap sebagai perlambangan keluarga besarnya, ia terjatuh tak sadarkan diri. Ia meninggal ketika seluruh keluarga besarnya berkumpul. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. “Kami semua para cucu pada ikut tertawa dan merasa gembira melihat Embah Kakung kembali bersemangat. Pada waktu kemudian pemotongan kayu itu selesai dan orang-orang pada kembali ke rumah mereka masing-masing dengan bagian mereka, Embah Kakung memberi isyarat untuk digandeng masuk ke ruang dalam. Saya dan Gus Hari segera menggandeng beliau masuk. Jalannya pelan sekali. Srek, srek, srek, srek. Tiba-tiba Embah Kakung menggelantungkan tubuhnya. Masya Allah Embah Kakung pingsan ….” “Kelurga demi keluarga pada berdatangan pada hari-hari berikutnya. Bahkan Halimah ikut datang bersama Bapak dan Ibu. Tepat pada waktu keluarga terakhir datang, yaitu Mbak 31 Ibid., h. 329. 65 Marie dan Mas Maridjan, Embah Kakung meninggal, seda …. ”32 Sastrodarsono sangat sadar akan status sosialnya. Sebagai seorang priyayi yang hidup berkecukupan, ia mengajak keponakankeponakannya yang tidak mampu untuk tinggal dan disekolahkan. Ia adalah orang yang pennuh belas kasihan dan mudah terharu. Ia orangnya baik dan adil, juga keras dan bila marah suka membentak sembari misuh, mengumpat. Akan tetapi, ia begitu mencintai istrinya, Ngaisah. c. Siti Aisah/Dik Ngaisah Dalam novel Para Priyayi, Siti Aisah atau Ngaisah merupakan tokoh komplementer. Tokoh komplementer merupakan tokoh tambahan sebagai pelengkap cerita. Namun, tokoh komplementer juga dapat menjadi penjelas dari tema yang dibahas dalam sebuah cerita. Pada hakikatnya tokoh komplementer merupakan tokoh selain tokoh primer dan sekunder. Siti Aisah atau Ngaisah adalah istri Sastrodarsono. Mereka menikah karena dijodohkan. Perjodohan yang direncanakan karena keduanya adalah seorang priyayi. Ngaisah merupakan anak perempuan dari paman jauhnya, Mukaram, mantri penjual candu. Seperti dalam kutipan berikut, “Calonmu itu, Le, masih sanak jauh. Itu lho, Ngaisah, putrinya pamanmu jauh, Mukaram, mantri penjual candu di Jogorogo. Masih ingat kamu, Le?”33 Ternyata perjodohan dan pernikahan berjalan lancar sesuai harapan. Ngaisah adalah sosok istri yang diharapkan Sastrodarsono. Ia perempuan yang mumpuni dalam mengurus rumah tangga dan 32 Ibid., h. 330-331. Ibid., h. 41. 33 66 berwibawa. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Dik Ngaisah, alhamdulillah adalah istri seperti yang saya harapkan semula. Ia adalah perempuan yang agaknya, memang sudah disiapkan orang tuanya untuk menjadi istri priyayi yang mumpuni, lengkap akan kecakapan dan keperigelannya. Di dapur ia tidak hanya tahu memasak, tetapi juga memimpin para pembantu di dapur. Wibawa kepemimpinannya dalam pekerjaan mengatur rumah tangga langsung terasa. Dalam mengatur meja makan serta kamar tidur dan mengatur kursi dan meja di ruang depan dan ruang dalam jelas Dik Ngaisah lebih berpengalaman dari saya. Segera saja terlihat bagaimana bekas tangan rumah tangga priyayi melekat pada semua yang disentuhnya.”34 Sebagai putri dan juga istri seorang priyayi, Ngaisah dapat dikatakan telah berhasil menciptakan suasana rumah tangga priyayi. Selain itu, ia juga perempuan yang halus dalam bersikap dan berbicara, murah senyum serta mampu mengendalikan perasaan. Seperti dalam kutipan berikut, “Dik Ngaisah jelas hasil dari halus yang sudah berakar lebih lama dari saya. Sikap dan bahasanya halus. Meskipun ia perempuan yang sumeh, murah senyum, ia adalah perempuan yang tahu mengendalikan perasaan.”35 Meskipun demikian, Ngaisah tetaplah seorang perempuan dan istri yang memiliki rasa takut dan rasa khawatir yang berlebihan, karena dia sangat tahu bagaimana watak suaminya, Sastrodarsono. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Dik Ngaisah ternyata gugup dan takut sesudah saya ceritakan tentang percakapan saya dengan Opziener dan Mas Martoatmodjo. Apalagi sesudah melihat-lihat surat kabar Medan Priyayi. 34 Ibid., h. 49. Ibid., h. 50. 35 67 “Wah, mbok Kamas jangan ikut-ikutan Mas Marto. Kok terus mau cari molo, cari sakit saja lho, Kamas ini. Kalau ada apaapa bagaimana dengan saya dan anak-anak.”36 .... “Belum. Saya gelisah dan takut memikirkan hari depan kita sesudah Kamas bercerita tentang percakapanmu dengan Romo Opziener dan Mas Martoatmodjo.” .... “Lha, bagaimana bisa memikirkan membesarkan anak, kalau hari depan kita jadi menakutkan begitu?” .... “Soalnya Kamas kalau sudah punya kehendak ....” .... “Dengan itu percakapan larut malam saya tutup. Saya lihat dari sudut mata saya Dik Ngaisah kelihatan tegang dan matanya mulai mengeluarkan airmata. Perempuan.”37 Akan tetapi, sekali lagi Ngaisah memang perempuan sekaligus istri yang kuat. Selain cerdas, ia juga menjadi tumpuan keluarganya ketika berbagai macam masalah menimpa keluarganya. Bahkan ketika ayahnya tersandung masalah yang cukup berat hingga akhirnya meninggal. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya tertawa. Dik Ngaisah, (ah, sudah berapa lama nama itu tidak pernah saya sebut lagi) memang istri yang cerdas. Dia selalu bekerja keras, jarang sekali mengeluh, dan selalu menjadi tumpuan kami serumah setiap kali kami tertumbuk pada macam-macam persoalan. Dan selalu saja dia bisa mengatasi dengan baik. Bahkan waktu ayahnya, Romo Mukaram, kena musibah diberhentikan oleh gupermen karena dituduh kong-kalikong dengan cina-cina penyelundup candu, istri saya menerima itu dengan tabah. Begitu juga pada waktu tidak terlalu lama kemudian mertua saya itu jatuh sakit, mengenas, dan malu karena pemberhentian itu, dan akhirnya meninggal, istri saya, sekali lagi menghadapi itu dengan hati yang tabah.”38 36 Ibid., h. 63. Ibid., h. 65-66. 38 Ibid., h. 91-92. 37 68 Ngaisah adalah istri yang selalu setia kepada suaminya. Ngaisah sering digoda anak dan menantunya tentang kebaktiannya yang dianggap terlalu berlebihan kepada suami. Akan tetapi, ia tidak pernah mengubah sikap terhadap suaminya. Hal ini terdapat pada kutipan berikut, “Orang jawa mengatakan istri adalah garwa, sigarane nyawa, yang berarti belahan jiwa. Maka sebagai belahan jiwa bukankah saya mesti tidak boleh berpisah dari belahan yang satu lagi?”39 Ngaisah adalah pribadi yang riang dan ikhlas. Lantip begitu mengagumi Embah Putrinya ini dengan mengatakan bahwa beliau adalah wanita cantik, meskipun usianya sudah tujuh puluh tahun. Menurut dia, cantiknya bukan hanya karena kebiasaan minum jamu Jawa, tetapi karena sikapnya yang gembira dan ikhlas dalam menjalani hidup. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya selalu heran dengan bagaimana seorang ibu rumah tangga yang bekerja begitu keras, mendampingi seorang suami seperti Embah Kakung Sastrodarsono yang begitu aktif di masyarakat serta mengelola tegalan dan sawah ladah hujan dan mengurus begitu banyak orang di rumah, bisa menjaga tubuh yang sehat serta wajah yang tetap segar dan cantik pada usia yang tujuh puluh tahun. Pastilah itu hanya bukan karena beliau teratur minum jamu Jawa saja. Pastilah kegembiraan serta kelenturan dan keikhlasan sikap beliau dalam menjalankan semua pekerjaan itu yang membuat Embah Putri awet muda.”40 Akan tetapi, setelah beberapa masalah yang dihadapi oleh anak-mantunya selesai, rupanya itu cukup menguras pikiran hingga memengaruhi kesehatannya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. 39 Ibid., h. 227. Ibid., h. 256. 40 69 “Dalam kunjungan teraturnya yang terakhir, Dokter Waluyo menasihatkan kepada saya agar saya lebih berhati-hati menjaga badan. Dari pemeriksaannya terlihat bahwa tekanan darah saya tinggi. Dia menganjurkan agar saya banyak istirahat dan mengurangi garam. Rupanya kunjungan Soemini dan Sus dalam dua bulan terakhir ini berpengaruh juga bagi tubuh saya.” “…. Saya selalu pasrah terhadap kemauan tubuh saya. Saya sadar bahwa tujuh puluh tahun adalah umur yang cukup panjang yang dianugerahkan Gusti Allah kepada saya. Saya hanya bisa bersyukur dibolehkan mengeyamhidup hingga sejauh ini.41 Terlebih lagi ternyata ia mengidap penyakit yang dirahasiakannya dari Sastrodarsono. Hingga pada akhirnya ia meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. “…. Tetapi, Allah Maha Besar. Bel pintu berdering keras sekali. Seorang pembawa telegram menyerahkan telegram. Embah Putri Sastrodarsono meninggal di Wanagalih.”42 “Embah Putri, menurut Gus Hari yang mendengar itu dari Bapak ternyata telah lama mengidap penyakit lever. Dokter Waluyo bahkan wanti-wanti pesan kepada Bapak dan Pakde Noeg dan lainnya agar tidak membocorkan kepada Embah Kakung.”43 Dapat disimpulkan bahwa Ngaisah adalah seorang perempuan yang cakap dan prigel dalam mengurus keluarga priyayinya. Ia paham betul bagaimana menjadi seorang istri, ibu, dan nenek. Ia begitu lihai dalam segala pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, memimpin pembantu di dapur, mengatur meja makan, merapikan rumah. Selain itu, ia adalah perempuan yang berpendidikan halus. Sikap dan 41 Ibid., h. 254. Ibid., h. 265. 43 Ibid., h. 266. 42 70 bahasanya halus, sumeh, murah senyum, dan pandai mengendalikan perasaan. d. Noegroho Kedekatan kaum priyayi dengan wong cilik mengalami kelunturan pada masa generasi anak-anak dan cucu Sastrodarsono. Tidak ada hubungan erat antar tokoh yang berbeda status seperti Ngadiyem dan Sastrodarsono, bahkan dapat dikatakan anak-anak Sastrodarsono cenderung bersikap acuh tak acuh pada wong cilik. Misalnya, Noegroho, hidup dalam kemewahan ala Belanda. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “di meja makan kami biefstuk daging has yang lengkap dengan segala kentang dan jus dan slada hussar adalah hidangan yang tidak asing.”44 Mereka enggan „mencicipi‟ kesederhanaan yang tercermin melalui penganan tempe. Kutipan di atas menunjukkan bagaimana priyayi menjauhkan diri dari wong cilik, berlawanan dengan sifat Sastrodarsono yang masih merasakan kedekatan dengan wong cilik. Tidak tampak lagi relasi antara kaum wong cilik dan priyayi pada masa generasi anakanak dan cucu Sastrodarsono. Kesan yang terjadi justru berkebalikan, para priyayi semakin menjauhkan diri dari wong cilik. Dalam novel Para Priyayi, Noegroho merupakan tokoh komplementer. Tokoh komplementer merupakan tokoh tambahan sebagai pelengkap cerita. Namun, tokoh komplementer juga bisa menjadi penjelas dari tema yang dibahas dalam sebuah cerita. Pada hakikatnya tokoh komplementer merupakan tokoh selain tokoh primer dan sekunder. Noegroho merupakan anak pertama Sastrodarsono dan Ngaisah. Akan tetapi, Noegroho sangat berbeda dengan ayahnya. 44 Ibid., h. 179. 71 Salah satu perbedaannya adalah sifat pemberani yang tidak dimiliki oleh Noegroho. Misalnya, disaat Sastrodarsono berani membangkang terhadap perintah Jepang, Noegroho malah sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Saya ternyata tidak seberani Bapak yang menolak untuk menjalani upacara saikere kita ni muke, membungkuk dalam-dalam ke arah utara….”45 Noegroho terpilih menjadi tentara Peta (Pembela Tanah Air). Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Kemudian, tanpa saya duga sama sekali, datanglah panggilan itu. Saya terpilih atau terpanggil untuk ikut tentara Peta atau Pembela Tanah Air ….”46 Noegroho memiliki sikap pasrah, tabah, dan ikhlas. Sikap ini ditunjukkan ketika anaknya yang pertama meninggal dunia karena tertembak tentara Belanda yang sedang patroli. Selain itu, sikap pasrah Noegroho ditunjukkan pula ketika ia mengetahui bahwa Lantip diangkat anak oleh Hardojo. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan berikut, “Iya, iya, Bu. Sing sabar ya, Bu. Ikhlas, Bu, kita ikhlaskan anak kita pergi ya, Bu. Kalian juga ya, Marie dan Tommi, ikhlaskan kamas-mu pergi.”47, dan “Sudah, sudah, Bu. Ingat. Sing tawakal, Bu. Kita manusia hanya dititipi Gusti Allah anak-anak kita. Kalau Dia mau mengambil kembali, Dia akan mengambil kembali. Dan pasti itu untuk alasan yang baik. Pasti itu untuk kebaikan Toni juga.“, serta “… kemudian begitu saja keluar dari mulut saya: Bapak ikhlas, Le.”48 Meskipun terlihat mengikhlaskan kematian Toni, Noegroho ternyata berubah. Ia menjadi lemah, tidak segagah dulu. Karena setelah peristiwa itu, ia memanjakan anak-anaknya yang pada akhirnya 45 Ibid., h. 194. Ibid., h. 196. 47 Ibid., h. 223. 48 Ibid., h. 224. 46 72 malah mencoreng nama besar keluarga Sastrodarsono. Menurut Sastrodarsono, Noegroho telah dilenakan oleh kekayaan dan kedudukan. Begitu yang ia katakan kepada Ngaisah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Yang saya sesalkan itu, Noegroho yang dulugagah begitu, kok sekarang lemah, mlempem, tidak menguasai rumah tangganya. Apa kekayaan dan kedudukan dia yang membuatnya dia begitu ya, Bune.”49 Noegroho adalah anak pertama Sastrodarsono yang menjadi tentara. Gaya hidupnya tinggi. Ia memiliki sikap pasrah, tabah, dan ikhlas. Sikap ini ditunjukkan ketika anaknya yang pertama meninggal dunia. Akan tetapi, ia berubah menjadi lemah. Ia terlena dengan kekayaan dan kedudukan sehingga tidak dapat menjaga keluarganya dengan baik. e. Hardojo Hardojo adalah anak kedua dalam keluarga Sastrodarsono. Hardojo adalah orang yang cerdas. Keberhasilannya dalam meniti karier tidak terlepas dari modal kualitas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “HARDOJO, anak saya yang kedua, mungkin adalah anak saya yang paling cerdas dan mungkin yang paling disenangi orang. Soemini sangat sayang kepadanya. Noegroho, yang cenderung paling serius dari semua anak-anak saya, juga sangat dekat dengan adiknya itu, dan kami orang tuanya selalu bisa dibikin menuruti kemauannya”.50 Selain Noegroho, Hardojo pun menjauhkan diri dari wong cilik. Tidak tampak lagi relasi antara kaum wong cilik dan priyayi pada masa generasi anak-anak dan cucu Sastrodarsono. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Anak-anak kampung itu lain betul dengan Hari, 49 Ibid., h. 252. Ibid., h. 102. 50 73 lho, Sum. Mereka suka omong jorok dan suka misuh. Kita ini orang Mangkunegaran, lho, Sum.”51 Dari kutipan tersebut kita dapat mengerti bahwa seiring dengan meningkatnya status priyayi pada diri Hardojo ia semakin mengambil jarak dengan wong cilik. Tanpa disadarinya ia telah menggunjing kaum wong cilik dan ayahnya sendiri, karena Sastrodarsono dahulunya adalah anak petani desa. Priyayi adalah keluarga terhormat sehingga harus menghimpun keluarga terhormat dengan mencari besan dari kalangan terhormat pula. Dengan demikian pada keluarga priyayi muncul tradisi mencarikan jodoh bagi anak. Orang tua memiliki hak khusus dalam memilihkan jodoh dari keluarga tertentu yang cocok dengan kriteria keluarga mereka. Si anak yang akan dengan senang hati menerima pilihan orang tuanya karena pilihan priyayi adalah priyayi dengan berbagai kriteria pula. Ngaisah adalah pilihan Ndoro Seten untuk Sastrodarsono. Begitu pula Noegroho dan Soemini mendapat pasangan hidup hasil pilihan orang tuanya. Lain halnya dengan Hardojo yang memiliki pilihan sendiri. Ia memilih perempuan priyayi kristen yang tidak sesuai dengan dengan agama keluarganya. Maka tidak diterimalah kehendak Hardojo oleh keluarganya. Ia harus merelakannya. Dalam novel Para Priyayi, Hardojo merupakan tokoh komplementer. Tokoh komplementer merupakan tokoh tambahan sebagai pelengkap cerita. Hardojo adalah anak yang cerdas. Ia berhasil menjadi priyayi dengan menjadi orang Mangkunegaran. Ia menikah dengan Sumarti dan dikaruniai seorang anak bernama Harimurti. f. 51 Ibid., h. 167. Soemini 74 Soemini adalah anak bungsu Sastrodarsono dan Ngaisah. Ia digambarkan memiliki sifat bandel, keras kepala, dan selalu ingin dituruti kemauannya. Akan tetapi, ketika dewasa ia menjadi perempuan yang penurut dan sangat mementingkan pendidikan. Emansipasi wanita ditunjukkan dengan perlawanan wanita untuk keluar dari kekangan patriarkal. Seorang wanita biasanya dijodohkan sejak masih muda, seperti yang dialami tokoh Ngaisah. Soemini di lain pihak, mengikuti pemikiran R.A. Kartini menolak untuk menikah pada usia dini dan memilih untuk melanjutkan sekolah di Van Deventer School. Hal ini terdapat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Bukankah kita termasuk keluarga priyayi maju pengikut pikiran Raden Ajeng Kartini yang tidak setuju perempuan kawin terlalu muda.”52 “Saya mau sekolah dulu di Van Deventer School. Selesai itu baru saya bersedia jadi istri Kamas Harjono.”53 Seorang priyayi harus memiliki pribadi khas karena terpelajarnya. Sehingga tindaknya harus sesuai dengan norma yang mulia. Sastrodarsono dan ketiga anaknya berusaha mencontohkan perilaku priyayi ini, namun keturunan mereka yang mendapat status priyayi karena pemberian, justru menunjukkan perilaku bukan priyayi. Perilaku mereka jelek, tidak dapat menjaga diri dan perilakunya. Soemini menikah dengan Harjono dan dikaruniai beberapa orang anak. Masalah pun datang dalam rumah tangganya. Ia mengetahui suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Soemini aktif dalam organisasi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. 52 Ibid., h. 79. Ibid., h. 86. 53 75 “…. Mas Harjono ternyata punya selir gelap yang disimpan di Rawamangun. Hal itu saya ketahui secara kebetulan dari rekan di organisasi.”54 “…. Saya memang kurang waspada karena karena saya sendiri juga banyak terlibat dengan organisasi.”55 Soemini adalah aktivis wanita. Ia merupakan pengurus anggota Perwari. Organisasi ini anti madu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Dan bagaimana malu kami kepada tantemu Mini yang anggota pengurus Perwari itu kalau mendengar ini. Juga tantemu mini sendiri akan malu juga. Pengurus Perwari yang anti madu kok membiarkan kemenakan sendiri dimadu orang.”56 Soemini merupakan tokoh komplementer. Tokoh komplementer merupakan tokoh tambahan sebagai pelengkap cerita. Soemini adalah perempuan yang sangat mengutamakan pendidikan. Ia memiliki sifat bandel, keras kepala, dan selalu ingin dituruti kemauannya. Soemini adalah contoh perempuan modern yang sangat aktif. g. Sus Sus merupakan tokoh komplementer. Ia adalah istri Noegroho. Menurut Ngaisah, sus adalah perempuan yang cantik dan lemah. Hal ini terdapat pada kutipan berikut, “Ah, saya kira tidak, Pakne. Sus lain dengan Soemini. Sus cantik dan lemah. Tidak seperti anakmu, atos, keras. Tapi justru karena gabungan cantik dan lemah itu membuat Noegroho akan terus lengket dengan istrinya.?”57 Akan tetapi, sikap memanjakan anak-anaknya menjadi bumerang baginya. Hal itu ia lakukan karena trauma akan peristiwa 54 Ibid., h. 233. Ibid., h. 234. 56 Ibid., h. 277. 57 Ibid., h. 244. 55 76 meninggalnya Toni. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya masih belum bisa melupakan keterkejutan serta kepedihan saya waktu ditinggal mati Toni. Sungguh sangat sedih dan kosong rasanya sehabis Toni pergi itu. Maka saya bertekad tidak mau kehilangan anak-anak saya lagi. mereka kami jaga baik-baik. Kami turuti semua kemauan mereka asal mereka senang dan berbahagia.”58 Sus merasa bersalah kerena sikapnya itu pada akhirnya menimbulkan masalah yang besar bagi kehormatan keluarga Sastrodarsono. “Bapak, Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menjaga cucu Bapak dan Ibu. Saya yang salah, kurang waspada dan terlalu jauh memanjakan dia. Bagaimana nanti kalau Mas Noeg mendengar ini. Pasti saya akan kena marah habis-habisan.”59 Kutipan di atas menjelaskan betapa Sus merasa bersalah. Ia merasa gagal mendidik anak-anaknya, karena Marie hamil di luar nikah dan Tommi menjadi anak yang tidak peduli, tidak dapat diandalkan. Sus merupakan tokoh komplementer. Tokoh komplementer merupakan tokoh tambahan sebagai pelengkap cerita. Sebagai istri Noegroho dan ibu dari Marie dan Tommi, Sus merasa gagal dalam menjaga rumah tangganya. Ia cantik, tetapi lemah. Ia begitu manjakan anak-anaknya yang lain semenjak ia kehilangan anaknya yang meninggal karena tertembak. h. Marie Marie adalah anak perempuan Noegroho dan Sus. Ia anak tertua dan memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Tommi dan Toni. 58 Ibid., h. 245. Ibid., h. 251 59 77 Setelah Toni meninggal dunia, Sus, ibu Marie memanjakan Marie dan Tommi karena takut kehilangan anaknya lagi. Akan tetapi, karena sikap itulah Marie tumbuh menjadi anak yang sangat bebas dalam pergaulan, bahkan kuliahnya berhenti di tengah jalan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. …. “Setiap kami menduga ada seorang laki-laki agak akrab dengandia adalah calon suaminya, segera pula kami dibuatnya kecele. Kuliah Marie, seperti Bapak dan Ibu tahu, berhenti di tengah jalan. Alasan bosan. Dan kami tidak kuasa membujuknya apalagi memaksanya agar dia mau terus kuliah. Memang harus kami akui bahwa kami cenderung lemah, bahkan agak kami manjakan anak-anak kami. Sejak Toni gugur dulu, kami, terutama saya, selalu diliputi perasaan takut satu ketika akan kehilangan anak lagi.”60 Marie bekerja di kantor ayahnya. Ia bekerja semau hatinya. Hal itu tentu membuat ibunya khawatir. Akan tetapi, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan Sus dibandingkan dengan sikap semena-mena Marie, yaitu hubungannya dengan Maridjan. Benar saja kekhawatiran ibunya itu. Marie memberi pengakuan kepada Sus. Marie hamil di luar nikah. Lelaki itu adalah Maridjan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan percakapan di bawah sebagai berikut. “Ma!” “Huh!” Untuk beberapa saat diam lagi. Marie tidak meneruskan kalimatnya. “Ma, saya mau bilang.” “Ngomonglah.” Marie kemudian membalikan tubuhnya, mukanya menghadap muka saya yang menatap langit-langit. Saya terkejut. Muka Marie kelihatan kusut, bawah matanya kelihatan hitam kelelahan. Kemudian airmatanya mulai menitik. Marie yang badung menangis? “Ma, saya sedang susah, nih.” 60 Ibid., h. 245. 78 Saya diam memperhatikan muka anak saya itu. “Ma, saya … mungkin hamil.” “Hah?”61 Marie memiliki sifat manja dan acuh tak acuh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Sedang Marie, anak manja dan sering bersikap acuh tak acuh, hari itu Nampak agak gugup.”Marie merupakan tokoh komplementer. Sebagai pelengkap cerita, ia merupakan salah satu tokoh yang membuat konflik dalam keluarga besar Sastrodarsono. Marie merupakan tokoh komplementer. Ia adalah anak perempuan satu-satunya Noegroho dan Sus. Marie memiliki sifat manja dan tak acuh. Gaya hidupnya tinggi dan bebas. i. Harimurti Harimurti merupakan anak tunggal Hardojo dan Sumarti. Harimurti merupakan tokoh komplementer. Tokoh komplementer merupakan tokoh tambahan sebagai pelengkap cerita. Keberadaannya mendukung tokoh utaadan sekunder dalam cerita. Harimurti atau Hari adalah tokoh yang namanya memiliki makna yang indah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “... Anak kami, laki-laki, Harimurti, tahu-tahu juga sudah lima tahun umurnya. Kami namakan dia Harimurti karena waktu baru lahir merah sekali warna kulitnya. Kata orang bayi yang kulitnya merah mangar-mangar akan menjadi hitam bila sudah tumbuh dewasa. Maka kami namakan dia Harimurti, dengan harapan ia akan sehitam Batara Kresna, titisan Wisnu itu. Tentulah kami tahu benar bahwa dia bukan titisan Wisnu. Tetapi, setidaknya kami berharap semoga anak itu akan menjadi orang yang bijaksana seperti Prabu Kresna dari 61 Ibid., h. 250. 79 Dwarawati itu. Juga orang yang peka serta tajam perasaannya, sanggup membaca perubahan zaman. ...”62 Hari tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap peduli dan solidaritas yang tinggi, apalagi terhadap keluarganya ketika Embah putrinya, Ngaisah meninggal dunia. Ia bersedia menemani Embah Kakung Sastrodarsono di Wanagalih bersama dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini terlihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Kesediaan Gus Hari untuk ikut tinggal bersama ibu dan buliknya mengharukan pakde dan paklik-nya dan sudah tentu juga bulik, bude, dan ibunya. Saya sendiri sesungguhnya tidak terkejut. Dan mestinya juga Bapak dan Ibu. Kami tahu betul sifat Gus Hari, momongan saya itu. Orangnya penuh belas dan gampang merasa trenyuhkepada penderitaan orang lain, apalagi ini adalah Embah Putrinya yang disayanginya. Rasa solidaritasnya juga kuat betul dengan mereka yang menderita.”63 Harimurti memang pemuda yang peka, mudah trenyuh, cerdas, dan sangat menyukai kesenian. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Gus Hari seperti selalu saya amati dan duga sejak kecil, tumbuh sebagai seorang pemuda yang peka, gampang menaruh belas kepada penderitaan orang. Dia juga anak yang sangat cerdas dan menaruh perhatian yang besar pada kesenian.”64 Hari yang cerdas itu ikut bergabung dalam organisasi Lekra dan CGMI. Hal ini ia akui dan tanyakan pada Lantip. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Tip, saya beri tahu, ya? Aku sekarang bergabung dengan Lekra dan CGMI. bagaimana kau setuju, „kan?”65 62 Ibid., h. 161. Ibid., h. 269. 64 Ibid., h. 280. 65 Ibid., h. 282. 63 80 Sejak mengenal dan bersahabat dengan Sunaryo yang berpandangan Marxis, pandangan Harimurti pada kesenian yang sebelumnya ia nikmati sebagai keindahan sekarang bergeser menjadi menjadi alat politik. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Kesenian bagi Gus Hari bergeser menjadi bagian dari politik dan berubah menjadi alat politik. Saya baru mulai sadar bahwa Sunaryo adalah seorang yang berpandangan Marxis berkat pergaulannya dan pendidikannya dengan kawan-kawannya Marxis, baik yang ada di Lekra, CGMI maupun kemudian yang di HIS.”66 Hari semakin bergairah dengan Lekra. Ia semakin meyukai seni. Akan tetapi, kesenian yang ia tekuni sekarang adalah seni pinggiran. Baginya seni adalah alat perjuangan kelas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Perkembangan kemudian adalah perkembangan Gus Hari yang semakin bergairah dengan Lekra. Wayang orang, wayang kulit serta klenengan gamelan tidak lagi diminati karena, katanya, itu semua adalah klenengan adiluhung, indah tinggi, dari kaum feodal. Yang dia tekuni adalah ketoprak dan ludruk serta gamelan pinggiran. Itulah, katanya, seni oleh rakyat dan untuk rakyat. Seni sebagai alat perjuangan kelas wong cilikmelawan kelas feodal, katanya lagi.”67 Harimurti sangat sayang kepada kedua orang tuanya walaupun kadang berbeda pandangan, ia tetap menghormati kedua orang tuanya. Ia juga memiliki sifat yang jujur dan tulus. Baginya kejujuran dan ketulusan lebih penting daripada gaya penampilan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya diam tidak berusaha meneruskan perdebatan dengan orang tua saya. Jelas kami sudah berbeda pandangan. Dan perbedaan itu memang menandakan perbedaan pandangan antara angkatan yang lain. Bagi mereka mungkin yang 66 Ibid., Ibid., h. 284. 67 81 terpenting adalah gaya penampilan karena itu dipandang sebagai pancaran jiwa dalam. Bagi saya tidak. Bagi saya kejujuran dan ketulusan lebih penting. Gaya penampilan dapat dikembangkan sambil berjalan.”68 Hari memiliki kekasih yang ternyata juga satu organisasi dengannya. Namanya Retno Dumilah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Saya juga mengamati Gus Hari mulai pacaran. Ah, itu perkembangan yang menyenangkan. Pacarnya adalah seorang penyair, Lekra tentu, bernama Retno Dumilah, tetapi lebih suka dipanggil dengan nama samaran sebagai penyair, Gadis Pari.”69 Ketika terjadi penangkapan besar-besaran terhadap organisasiorganisasi yang diduga pemberontak atau anggota PKI, Hari dan Gadis berpisah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “…. Sesudah pawai, kami diberi tahu bahwa Angkatan Bersenjata telah mengambil alih semuanya dan mulai mengadakan pembersihan terhadap semua anggota PKI dan ormas—ormasnya. Kami dianjurkan bersembunyi dan menunggu keadaan. Saya pulang dan Gadis pulang ke Wates.”70 Hari dipenjara karena aktif di Lekra yang dicurigai sebagai sayap organisasi PKI. Keturunan priyayi justru rusak moralnya. Seolah kepriyayiannya hilang tanpa bekas. Hari begitu liberal dan tidak dapat menjaga diri. Ia berperilaku amoral. Tidak mengindahkan nilai. Hari meminta maaf kepada orang tuanya karena ada hal lain yang telah terjadi dalam hubungan dengan Gadis waktu Lantip memberi kabar bahwa Gadis di tahan dalam keadaan hamil tujuh bulan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. …. 68 Ibid., h. 293. Ibid., h. 284. 70 Ibid., h. 306. 69 82 “Menurut informan saya, tahanan Gerwani bernama Retno Dumilah sekarang ini sedang hamil tujuh bulan. Bagaimana itu mungkin?” …. “Perempuan itu hampir bisa saya pastikan Gadis.” “Bagaimana kamu bisa pasti, Le.” “Bapak, Ibu, dan kang Lantip. Saya minta maaf. Saya akan menceritakan bagian lain dari hubungan saya dengan Gadis yang belum sempat saya laporkan kepada Bapak, Ibu, dan Kang Lantip. Hubungan saya dengan Gadis sesungguhnya sudah amat jauh dan mendalam. Menjelang kemelut itu, Gadis sudah bercerita kepada saya bahwa dia sudah satu bulan tidak mendapat haid. Kalau kata Kang Lantip, Gerwani itu hamil tujuh bulan, dan namanya Retno Dumilah, pastilah dia itu Gadis. Yang ada dalam kandungannya adalah anak saya.”71 Harimurti sangat sedih ketika ia tahu ternyata Gadis meninggal dunia karena melahirkan anaknya terlalu cepat. Karena begitu sedih, ia sampai tidak bisa menangis dan diam membatu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Oh, Allah, Lee. Sudah nasibmu, Nggeer. Istrimu, Naak, istrimu sudah tidak ada …..” Saya jadi berdiri membatu. Tidak bisa menangis lagi, tidak bisa apa-apa. “Saya hanya mendengar cerita ibu dan bapak saya. Gadis meninggal beberapa hari lalu sebelum mereka datang. Gadis meninggal melahirkan terlalu cepat sepasang anak kembar laki dan perempuan.”72 Harimurti memang pemuda yang peka, mudah trenyuh, cerdas, dan sangat menyukai kesenian. Harimurti ikut dalam pemberontakan dengan masuk ke dalam Lekra, sebuah organisasi kesenian beraliran komunis. Setelah berkenalan dan berhubungan dengan Gadis pengaruh komunis semakin meresap, namun sebenarnya dalam dirinya ia mempertanyakan esensi dari gerakan itu. Sampai pada akhirnya ia dan 71 Ibid., h. 319. Ibid., h. 326. 72 83 Gadis dipenjarakan. Hari merasa bersalah kepada Gadis dan anaknya yang lahir terlalu cepat itu. akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak dapat lagi menjalani hidup bersama Gadis. j. Retno Dumilah (Gadis Pari) Retno Dumilah adalah kekasih Harimurti. ia adalah seorang penyair. Ia juga ikut dalam organisasi Lekra dan tidak menyukai feodalisme, hingga ia lebih suka dipanggil Gadis Pari. Ketika terjadi penangkapan besar-besaran terhadap organisasiorganisasi yang diduga pemberontak atau anggota PKI, Hari dan Gadis berpisah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “…. Sesudah pawai, kami diberi tahu bahwa Angkatan Bersenjata telah mengambil alih semuanya dan mulai mengadakan pembersihan terhadap semua anggota PKI dan ormas—ormasnya. Kami dianjurkan bersembunyi dan menunggu keadaan. Saya pulang dan Gadis pulang ke Wates.”73 Di mata Hari, Gadis adalah perempuan yang beda dengan yang lain. Hal itu yang membuat Hari langsung tertarik kepada Gadis. Hubungan Hari dan Gadis melebihi seorang kekasih, hingga akhirnya Gadis hamil. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Dan Gadis? Bagaimana saya bisa terpikat dan akhirnya saya tetapkan dialah calon istri saya? Gadis adalah potret keterombang-ambingan juga seperti saya. Makanya saya langsung saja jatuh cinta kepadanya. Beda Gadis dengan saya adalah Gadis anak Priyayi yang lebih merasakan kepahitan hidup, sedang saya, seperti dikatakan oleh Gadis, adalah anak priyayi yang mujur. Ah, kekasihku. Gadisku, di mana kau sekarang? Betulkah kau mengandung bibitku, anak kita ….?”74 73 Ibid., h. 306. Ibid., h. 310. 74 84 Gadis memang anak priyayi. Akan tetapi, nasibnya pahit. Kebalikan dari Harimurti. Gadis adalah anak dari seorang pensiunan. Ia mempunyai saudara laki-laki yang cacat bernama Kentus. Kentus cacat otak sejak lahir. Gadis menganggap Kentus sebagai anak yang cacat karena penindasan kapitalisme dan bukan karena bawaan lahir. Gadis dan keluarganya perna mengalami secara langsung penderitaan kelas yang tertindas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Ah, kau priyayi yang selalu beruntung dan sukses. Orang tua saya, meski juga priyayi, priyayi kecil yang hanya hidup dari gaji. Kentus itu anak sepupu ibu saya yang priyayi lebih kecil lagi dan mengalami nasib yang sial. Suaminya guru desa yang pernah punya sebidang sawah yang kecil. Sawah yang kecil itu digadaikan kepada seorang haji tuan tanah untuk mengongkosi pengobatan Kentus ke sejumlah dukun, dan akhirnya juga dokter. Sampai habis uang gadai itu, Kentus ya tetap begitu saja keadaannya. Uang gadai tidak dapat dikembalikan dan tentu saja swah yang kecil itu kemudian jatuh ke tangan haji tuan tanah itu. Akhirnya mereka merana, sakit tbc dan seorang demi seorang meninggal. Jadilah Kentus kami ambil menjadi adik saya. Kalau bukan kelas yang tertindas, apalagi nama keluarga saya itu?”75 Gadis sendiri walaupun mengakui statusnya sebagai priyayi kecil tetap menganggap dirinya seperjuangan dengan rakyat tertindas. Menurutnya, komunisme telah menguras pemikiran mereka untuk mengabdi pada wong cilik dengan cara yang bersih, dengan “sistem yang tidak percaya lagi pada pendapat bahwa untuk mengangkat nasib rakyat harus dibunuhi beratus atau beribu orang.”76 Kutipan di atas menjelaskan bahwa gadis begitu membenci priyayi yang kaya raya dan feodalisme. Beberapa nilai buruk dari feodalisme di antaranya adalah mentalitas berorientasi kepada atasan, 75 Ibid., h. 299. Ibid., h. 291. 76 85 hanya menunggu perintah atasan, patuh dan loyal secara berlebihan sampai merendahan diri, dan mengutamakan kesenangan atasan. Feodalistik, artinya setia pada atasan, bertindak dengan maksud memelihara hubungan baik dengan atasan, menerima segalanya dari atasan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Tole semua. Dengarkan baik-baik perintahku ini... Begitulah perintah dari sesepuh keluarga Sastrodarsono dijatuhkan. Kami semua tidak bisa lain daripada manaatinya dan melaksanakannya.”77 Orang jawa cenderung fatalistik, yaitu menganggap baik buruknya nasib sudah diatur oleh takdir. Namun, dalam menanggung semuanya ini ada juga sikap menggerutu diam-diam, atau hanya berkata “Ya” di bibir, tetapi “tidak” di hati, bahkan jika mencoba mencermati maka akan nampak bahwa feodalistik ini tidak hanya erat hubunganya dengan wong cilik, tetapi ternyata golongan priyayi juga sangat feodalistik. Feodalistik digambarkan Umar kayam dalam novelnya saat masuk penjajahan Jepang segalanya harus berbau dan mengikuti pola yang dipergunakan Jepang termasuk juga sekolah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Setiap pagi kami, baik guru, mesti membungkukkan badan dalam-dalam memberi hormat kepada Tenno Heika, yaitu kaisar Jepang yang katanya adalah keturunan dewa. Habis itu kami semua diwajibkan taiso, yaitu olahraga, baru kemudian mulai dengan pelajaran. Setiap hari mesti ada pelajaran bahasa Nippong buat guru-guru yang terpilih. Ndoro putri diam mendengar gerutu Ndoro Kakung yang panjang itu.”78 Seluruh gaya hidup di lingkungan priyayi dipolakan menurut ethos (feodalistik), baik yang privat maupun publik, baik yang formal 77 Ibid., h. 302. Ibid., h. 138. 78 86 maupun yang informal, seluruh hubungan sosial, sikap pribadi, baik pada tingkat etis maupun pada tingkat estetis ataupun etiket, semuanya dijiwai oleh prinsip feodalistik. Gadis ditahan di Plantungan. Ia dituduh termasuk dalam Gerwani yang galak. Lantip berusaha menemuinya dan menguatkannya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Retno Dumilah, Gerwani yang ditahan di Plantungan itu, memang ternyata Gadis. Waktu kang Lantip dipertemukan Gadis di kantor kepala tahanan, keduanya saling memandang dengan terheran-heran. Gadis sama sekali tidak menyangka kalau akan kedatangan tamu Kang Lantip. Sedang Kang Lantip, meski sudah tahu, terheran-heran juga waktu melihat Gadis tampil dengan perut yang sudah besar karena hamil tua.” …. “Sabarlah, Gadis. Kami sekeluarga sedang mencari upaya untuk mengeluarkan kau.” “Huh, bagaimana bisa, Kang. Aku di sini sudah dinilai sebagai Gerwani galak. Padahal anggota Gerwanisaja tidak lho, saya. Saya memang penyair Lekra, anggota Lestra. Tetapi apa mau dikata. Buat mereka kami ini semuanya Gerwani. Dan memang dalam Tanya-jawab, interogasi. Saya sering dianggap galak karena saya suka mengundang polemik dengan mereka.” 79 Ketika keluarga Harimurti hendak menjemput Gadis di Plantungan, ternyata Gadis sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu karena melahirkan terlalu cepat. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Saya hanya mendengar cerita ibu dan bapak saya. Gadis meninggal beberapa hari lalu sebelum mereka datang. Gadis meninggal melahirkan terlalu cepat sepasang anak kembar laki dan perempuan.”80 79 Ibid., h. 321-322. Ibid., h. 326. 80 87 Dapat disimpulkan bahwa tokoh Gadis adalah perempuan yang tertindas, tetapi berjiwa kuat. Gadis tidak menyukai feodalistik manusia Jawa. k. Ngadiyem Ngadiyem adalah ibu kandung Lantip, anak Embah Wedok seorang penjual tempe yang tinggal di desa Wanawalas, tempat sekolah bantu yang didirikan oleh Sastrodarsono. Ngadiyem digambarkan sebagai tokoh yang, murah hati, hemat, dan tegas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Dengan ketus Embok menjawab dengan “Hesy! Ora usah”, dan saya pun jadi terdiam. Saya tahu Embok, meskipun murah hati, juga sangat hemat dan tegas.”81 Semasa hidupnya, Ngadiyem selalu menderita. Ngadiyem anak Mbok Soemo warga Dukuh Wanalawas. Adanya Lantip dimulai dengan berdirinya sekolah di Wanalawas dengan guru Den Bagus Soenandar yang tinggal di rumah Mbok Soemo. Soenandar menjadi seorang guru karena turut membantu Sastrodarsono. Ia akrab dengan Ngadiyem anak Mbok Soemo. Seiring kedekatan itu membuahkan Lantip di rahim Ngadiyem. Kebahagiaan Mbok Soemo anaknya kecipratan bibit priyayi kandas ketika menemui Den Bagus Soenandar minggat dan membawa seluruh tabungan keluarga itu. Ia bekerja keras berjualan membantu ibunya dan membahagiakan Lantip, anaknya. Ngadiyem adalah perempuan hebat yang selalu tabah menjalani takdir hidupnya. Lantip, anaknya memuji kehebatan Ngadiyem sebagai perempuan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Dan di tengah himpitan kesedihan itu, dia selalu tersenyum bahkan tertawa berderai setiap kali dia reriungan bersama saya. 81 Ibid., h. 14. 88 Perempuan yang istimewa. Perempuan yang hebat. Dan begitu saya menyimpulkan sosok embok saya, saya jadi ikhlas melepasnya ke dunia sana. Bahkan saya mengucap syukur kepada jamur yang membunuhnya dengan cepat. Sebab alangkah sudah besar dan banyak penderitaannya.”82 Ngadiyem adalah sosok perempuan yang hebat. Meskipun begitu banyak hal yang berat dalam hidupnya yang harus ia lalui. Ia tetap kuat dan ikhlas. Ia juga pekerja keras. l. Soenandar Soenandar adalah keponakan Sastrodarsono dan juga merupakan ayah kandung Lantip. Soenandar diserahkan orang tuanya agar dididik oleh keluarga Sastrodarsono. Akan tetapi, Soenandar malah membuat malu keluarga Satrodarsono karena ulahnya yang selalu membuat onar. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah sebagai berikut. “Belum lagi keponakan saya seperti Soenandar yang nakalnya bukan main, yang kerjanya selain membikin onar di rumah tidak ada lagi. Bila Sri sedang bersembahyang Isya pada malam hari, Soenandar kadang-kadang dengan berkerudung sarung akan menggodanya dari balik jendela yang menghadap ke kebun. Bila Sri menjerit-jerit karena kaget dan ketakutan, Soenandar akan tertawa terkekeh-kekeh. Dan di waktu yang lain saya dapati Sri dan Darmin menangis karena kena dibohongi Soenandar untuk makan saren, darah ayam goreng. Enak enggak makan saren haram, enak enggak, ganggu Soenandar.”83 Soenandar merupakan tokoh komplementer. Ia digambarkan sebagai tokoh yang nakal, cerdas, licik, pemalas dan kurang jujur. Hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya tidak habis mengerti bagaimana keponakan yang satu ini bisa begitu jahat kepada sepupu-sepupunya yang lain. Seakan82 Ibid., h. 134. Ibid., h. 78. 83 89 akan mengganggu sepupu-sepupu, atau mungkin orang mana saja, merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa baginya. Dari guru-gurunya di sekolah kami sering mendapat laporan akan kenakalan Soenandar. Sesungguhnya Soenandar adalah anak yang cukup cerdas, kata gurunya. Hanya saja dia malas, sering tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya, jelas gurunya lebih lanjut. Kesenangannya mengganggu anak-anak perempuan dan mengajak berkelahi anak-anak laki-laki.”84 Hal lain yang membuat keluarga Sastrodarsono malu bukan main adalah saat guru Soenandar, Menir Soerojo, mengantar pulang Soenandar karena ia kedapatan mencuri di sekolah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Ini, Kamasdan Mbakyu. Wah, nuwun sewu betul, lho, Kamas dan Mbakyu. Kali ini kenakalan Soenandar agak terlalu jauh. Dia kedapatan mencuri sangu, uang jajan temannya sekelas dan kami mendapat laporan dari embok kebon sekolah yang membuka warung di sekolah kalau Soenandar suka jajan tapi tidak mau bayar.”85 Dalam mendidik keponakan-keponakannya, Sastrodarsono merasa ia telah gagal. Terutama mendidik Soenandar. Ulahnya makin menjadi-jadi. Bahkan Paerah, pembantu di rumah keluarga Sastrodarsono pun dikerjai olehnya sampai seperti orang kesurupan. Selain gagalnya Soenandar menamatkan sekolahnya, ia juga tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah di percayakan padanya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kutipan dibawah sebagai berikut. “Yang repot adalah Soenandar. Saya tidak tahu setan apa yang masuk dalam kepalanya. Sifatnya jahat, jahil, suka menipu, dan rupanya juga suka perempuan. Paerah yang tempo hari digodanya hingga jadi seperti kesetanan rupanya mengalami beberapa kali godaannya sehingga hampir saja Paerah mau minta pulang ke desanya.”86 84 Ibid., h. 79-80. Ibid., h. 80. 86 Ibid., h. 109. 85 90 “Setelah kegagalannya menamatkan pelajaran di HIS tempo hari, dia kami beri tanggung jawab untuk menjadi mandor yang mengawasi buruh-buruh yang pada mengerjakan tegalan dan sawah kami di belakan rumah. Gagal juga. Hubungan dengan para buruh tidak baik, suka membentak-bentak dan uang hasil penjualan palawija dan kelebihan padi sering tidak beres pertanggungjawabannya.”87 Hal lain yang menjadi puncak dari kenakalan Soenandar adalah perbuatannya terhadap Ngadiyem. Soenandar menjalin kasih dengannya hingga akhirnya ia hamil di luar nikah. Akan tetapi, setelah mengetahui kehamilan Ngadiyem, Soenandar malah meninggalkannya dengan membawa tabungan Mbok Soemo dan Ngadiyem. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. “Rupanya Soenandar, sesudah beberapa waktu tinggal di rumah Mbok Soemo, dapat merebut hati Ngadiyem ....”88 .... “Sampai pada suatu ketika Ngadiyem merasa haidnya sudah mulai tidak teratur lagi datangnya ....” .... “Tetapi, waktu hal ini diceritakan kepada Soenandar, Soenandar diam saja.” .... “.... Kemudian pada suatu malam Soenandar minggat. Mbok Soemo dan Ngadiyem baru tahu keesokan harinya, waktu ditemuinya kamarnya kosong, pakaian yang bergantungan di kamar tidak ada dan, lebih celaka dari itu, semua uang tabungan keluarga yang ditabung dalam celengan ayamayaman dari tanah, yang ditaruh di atas rak bambu di ruang tengah, juga hilang ....” Akhirnya keluarga Sastrodarsono mencarinya dang ternyata dia menjadi anggota perampok. Malang nasibnya ketika ditangkap polisi 87 Ibid., h. 109-110. Ibid., h. 121. 88 91 dan ia hangus terbakar di dalam rumah rumah kosong yang sengaja dibakar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kutipan di berikut, .... “.... kemudian saya melihat Soenandar diantara gerombolan itu. Masya Allah, Soenandar keponakan saya, anak sepupu saya yang dititipkan kepada saya untuk menjadi priyayi, ikut gerombolan kelompok Samin Genjik?” .... Nuwun sewu, Dimas. Gambar ini diambil beberapa minggu yang lalu, waktu mereka tertangkap sehabis merampok di daerah Gorang-gareng. Sehabis digambar waktu mereka mau dibawa ke Madiun, di jalan mereka entah bagaimana, bisa lepas dan melawan polisi. Mereka lari masuk ke sebuah rumah kosong di sebuah kampung. Mereka dikepung. Kemudian atas nasihat dukun yang mengetahui kesaktian Samin Genjik, rumah itu mesti dibakar. Dan rumah itu dibakar habis oleh polisi dan orang-orang kampung.89 Tokoh Soenandar merupakan simbol keretakan relasi yang terjadi dalam keluarga besar Sastrodarsono. Meskipun Soenandar hanya keponakan Sastrodarsono. Ia tetap telah mencoreng nama baik keluarga dengan menghamili Ngadiyem kemudian lari membawa harta Ngadiyem dan ibunya. Soenandar memiliki sifat yang buruk. Ia digambarkan sebagai tokoh yang nakal, cerdas, licik, pemalas dan kurang jujur. m. Martoatmodjo Ia adalah senior Sastrodarsono sekaligus kepala sekolah di Karangdompol. Ia senangi dan dihormati, kerena sifatnya yang baik dan mau mengayomi juniornya, seperti Sastrodarsono. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut, “Saya selalu senang dan hormat kepada kepala sekolah saya. Dia adalah seorang atasan yang baik, penuh 89 Ibid., h. 122. 92 pengertian, cerdas, dan selalu mau membimbing rekan-rekannya yang masih muda dan kurang berpengalaman seperti saya.”90 Martoatmodjo diduga melakukan pergerakan dan mempunyai gundik seorang penari tayub oleh School Opziener. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Ada dua perkara. Pertama, hubungannya dengan pergerakan. Kedua, hubungannya dengan penari tayub di Desa Karangjambu.”91 “Dimas Sastro tertarik dengan Medan Priyayi? Bawalah kalau tertarik untuk membacanya. Tetapi, mingguan ini sudah tidak boleh terbit lagi. Pemimpinnya sudah dihukum dan dibuang.” “Lantas apa salah Mas Marto dengan menyimpan mingguanmingguan yang sudah berhenti terbit ini?” “Ya, karena menyimpan dan membaca mingguan-mingguan ini.” “Cuma itu?” “Nyaris cuma itu. Tetapi koran ini dianggap koran pergerakan, Dimas. Mingguan ini yang dianggap oleh gupermen menghasut masyarakat. Dan juga orang-orang Serikat Dagang di Lawean Solo itu hampir semua membaca mingguan-mingguan ini.”92 Kutipan di atas menjelaskan bahwa membaca dan menyimpan koran Medan Priyayi itu dianggap sebagai kegiatan pergerakan melawan gupermen pada waktu Pemerintah Hindia menguasai negeri kita. Medan Priyayi, mingguan yang memuat artikel-artikel perlawanan terhadap kolonialisme, seperti Multatuli, dan kritikan bagi pejabat yang korup. Banyak priyayi yang tidak berani mengikuti jejak Martoatmodjo karena takut kehilangan status dan kemapanan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Mereka takut dengan bacaan seperti ini. Mereka takut kehilangan pekerjaan mereka.”93 90 Ibid., h. 59. Ibid., 92 Ibid., h. 62. 93 Ibid., h. 57. 91 93 Kemunculan pemikiran ini adalah suatu bentuk reformasi idealisme priyayi yang terkesan pasif dan individualitis menjadi dinamis. Oleh karena itu, Martoatmodjo dituduh menghasut masyarakat. Pergerakan yang dilakukan Martoatmodjo dikhawatirkan oleh Opziener dapat mengancam keberadaan gupermen dan pada akhirnya barisan priyayi maju. Martoadmodjo adalah tokoh yang memiliki sifat berani. Selain itu, ia juga seorang atasan yang baik, penuh pengertian, cerdas, dan selalu mau membimbing rekan-rekannya yang masih muda dan kurang berpengalaman, seperti Sastrodarsono. Akan tetapi, pemerintah Belanda tidak menyingkirkannya karena dianggap sebagai pemberontak yang dapat mengancam pemerintahan Belanda. Setelah menganalisis tokoh dan penokohan, peneliti akan menganalisis alur Para Priyayi. 3. Alur Novel Para Priyayi terdiri atas beberapa episode, di antaranya yaitu, Wanagalih, Lantip, Sastrodarsono, Lantip, Hardojo, Noegroho, Para Istri, Lantip, Harimurti, dan Lantip. Masing-masing episode ini membentuk alurnya sendiri-sendiri. Akan tetapi, antara episode yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat. Hubungan ini ditandai dengan episode Lantip. Lantip merupakan penghubung antara episode yang satu dengan yang lain. Dengan adanya pembagian episode ini, para tokoh diberi kesempatan untuk menuturkan dirinya sendiri bahkan menilai tokoh lain. Secara umum, alur novel Para Priyayi adalah alur campuran, menggunakan alur maju yang dicampur dengan alur mundur. Oleh karena itu, setiap episode membentuk alurnya sendiri-sendiri, tahapan alur tidak dapat digambarkan secara jelas. Berikut ini adalah tahapan alur novel Para Priyayi secara keseluruhan dilihat dari sisi tokoh utama. a. Tahap Awal (Perkenalan) 94 Tahap ini melukiskan latar tempat yang menjadi pusat cerita dalam novel ini, yaitu Wanagalih. Pada bagian yang berjudul “Wanagalih” (hlm. 1—8). Tahap perkenalan ini diceritakan oleh tokoh Lantip. Ketika itu, Lantip digambarkan telah menjadi priagung Jakarta.Bagian berikutnya, “Lantip” (9—28), yang bercerita masih tokoh Lantip mengenai keadaan Lantip pada masa kanak-kanak dengan ibunya Sastrodarsono. yang berjualan Lantip tempe diceritakan hingga belum ikut keluarga mengetahui ayah kandungnya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Ayah saya.... wah, saya tidak pernah mengenalnya. Embok selalu mengatakan ayah saya pergi jauh untuk mencari duit.”94Baru setelah ibunya meninggal, Lantip diberi tahu oleh Pak Dukuh Wanalawas mengenai ayah kandungnya. Lantip tahu bahwa ia adalah anak jadah dari Ngadiyem dan Soenandar, yang tidak lain adalah keponakan Sastrodarsono. Mulai saat itu ia tahu bahwa ibunya mengenal keluarga Sastrodarsono bukan suatu kebetulan. Ia pun telah mengerti dan tidak akan sakit hati ketika Sastrodarsono marah, kemudian memaki Lantip dengan sebutan anak gento ataupun anak maling.“Dan Embah Guru yang penuh humor itu akan seketika berubah menjadi makhluk yang lain sekali. Menakutkan. “Guoblok! Disuruh minta uang saja tidak bisa. Dasar anak gento, anak maling cecrekan….” Begitulah umpat serapah itu.”95 b. Tahap Pemunculan Konflik Pemunculan konflik ini dapat dilihat ketika Sastrodarsono mengalami konflik intern tentang penentuan sikap kepriyayiannya. Ketika ia bersimpati pada tokoh Martoatmodjo, seorang tokoh pergerakan. Ia harus melakukan sesuatu. Atas nasihat Martoatmodjolah, ia mendirikan sekolah di Wanalawas yang pada 94 Ibid., h. 11. Ibid., 95 95 akhirnya ditutup setelah mendapat teguran School Opziener karena dianggap menghidupkan sistem ”sekolah liar”. Padahal mendirikan sekolah itu ia sebut sebagai ideologi keluarga. Tetapi yang lebih memalukan adalah karena ulah Soenandar, Kemenakannya yang ia beri tanggung jawab. Soenandar menghamili Ngadiyem, seorang anak gadis Desa Wanalawas—tempat didirikanya “sekolah liar”. Selain mencoreng nama keluarga besarnya, hal ini juga menghancurkan seluruh reputasi kepriyayian Sastrodarsono. “Pada suatu siang, waktu itu saya baru pulang dari mengatur koordinasi dengan para lurah desa untuk pengaturan makan dan perlengkapan lain bagi pasukan, datang berita itu. Seorang kurir datang dari kota membawa berita itu. Toni meninggal ditembak Belanda waktu sedang mencoba pulang untuk menengok ibu dan adik-adiknya. Masya Allah! Inna lillahi wa inna illaihi rojiun.... Anakku sulung, anakku lanang mati! Dan alangkah mudanya dia! Tanpa bisa saya bendung air mata saya berlelehan.”96 Peristiwa tersebut membuat Noegroho dan Sus terlalu memanjakan anak mereka yang lain. Mereka berdua takut apabila sesuatu terjadi pada Marie dan Tommi seperti yang dialami Toni. Akan tetapi, sikap mereka yang memanjakan anak mengakibatkan anak-anaknya menjadi salah pergaulan dan menimbulkan banyak permasalahan. c. Tahap Klimaks (Penanjakan Konflik) Sastrodarsono pemerintahan ditempeleng daerah. Tuan keputusannya Sato pensiun dan dari tidak kantor mau membungkukkan badan menghadap ke utara setiap pagi untuk menyembah menghormati 96 Ibid., h. 222. dewa matahari, Jepang. Padahal Sastrodarsono bukan itu dianggap tidak permasalahannya, 96 Sastrodarsono merasa tidak sanggup membungkuk karena usianya yang telah senja. Dengan susah payah dan kaku Ndoro Guru Kakung mencoba membungkukkan badannya. Tuan Sato kelihatan tidak puas dengan bungkuk Ndoro Guru Kakung. Tiba-tiba, dengan secepat kilat, tanpa kita nyana, tangan Tuan Sato melayang menempeleng kepala Ndoro Kakung. Plak! Plak! Ndoro Kakung geloyoran tubuhnya. Dengan cepat saya tangkap bersama Menir Soetardjo terus kami dudukkan di kursi goyang. ”Darusono, jerek, busuk. Genjimin bogero!” Sehabis mengumpat begitu Tuan Sato pergi dengan diiringi yang lain-lainnya. Sesudah sepi ruang depan itu barulah ketegangan itu terasa mereda. Tetapi, justru waktu itu saya lihat muka Ndoro Guru Kakung pucat pasi, nglokro, lesu. Air matanya berlelehan keluar. Beliau menangis. Selain itu, penanjakan konflik dapat dilihat ketika diketahui bahwa Marie hamil di luar nikah dengan Maridjan. Kejadian ini sangat mengagetkan kedua orang tuanya dan Sastrodarsono. Terlebih lagi, ternyata Maridjan telah menikah, mempunyai istri dan anak. Kejadian ini semakin membuat seluruh keluarga Noegroho terkejut, terutama Marie yang juga belum mengetahui permasalahan ini. “Heeh?! Maridjan sudah punya istri dan anak? Asu, bajingan tengik Maridjan!” Bude Sus hampir pingsan mendengar laporan saya. Pakde Noegroho merah padam mukanya. Sedang Marie mukanya jadi pucat pasi, tegang, matanya memandang entah ke mana. Tommi, yang biasa acuh tak acuh, kali itu ikut gelisah tidak menentu.” Konflik semakin meningkat ketika Ngaisah meninggal dunia. Kepergian Ngaisah begitu mendadak bagi Sastrodarsono. Sebelum meninggal, Ngaisah masih sempat menasihati putrinya, Soemini, dalam membina rumah tangga dan menasihati menantunya, Sus, dalam 97 mendidik anak-anaknya. Sebenarnya Ngaisah telah lama mengidap penyakit liver, namun Sastrodarsono tidak mengetahuinya. Kepergian Ngaisah begitu berat dirasakan oleh Sastrodarsono. d. Tahap Peleraian Setelah peristiwa penempelengan itu, Ngaisah mengirimkan surat kepada ketiga anaknya untuk pulang ke Wanagalih. Kedatangan mereka adalah obat yang mujarab bagi Sastrodarsono. Ia merasa lebih baik.Ketika usia Sastrodarsono delapan puluh tahun, Ngaisah meninggal dunia. Sastrodarsono pun sakit karena usianya sudah lanjut yakni 83tahun. Harimurti menunggu dengan harap-harap cemas keluarganya menjemput Gadis, calon istrinya yang sedang hamil tua, dari penjara. Ternyata Gadis meninggal dunia karena terlalu cepat melahirkan. Kabar tersebut sangat mengejutkan Hari bagaikan petir di siang bolong. Gadis melahirkan terlalu cepat sepasang anak kembar laki dan perempuan. e. Tahap Penyelesaian Sastrodarsono mengalami kemunduran pada kesehatannya. Ketika ia ikut menyaksikan pohon nangka yang merupakan saksi perjalanan hidup keluarga besarnya, ia pingsan hingga akhirnya meninggal dunia setelah semua keluarganya berkumpul. “Tiba-tiba kami mendapat surat kilat khusus dari Pakde Ngadiman bahwa Embah Kakung semakin mundur kesehatannya. Juga semakin pikun dan mulai sering menceracau juga. Bapak dan Ibu segera memerintahkan saya dan Gus Hari untuk pergi ke Wanagalih membantu Pakde Ngadiman dan anak-anaknya menjaga dan merawat Embah Kakung.”97 97 Ibid., h. 329. 98 Di akhir cerita, Lantip berpidato sebagai perwakilan dari keluarga besar Sastrodarsono. Berdasarkan kepadatan cerita, novel Para Priyayi beralur longgar. Tergolong alur longgar disebabkan peristiwa-peristiwa dalam cerita seolah-olah berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan terdirinya sepuluh episode dalam cerita ini. Selain itu, hubungan antara tokoh yang satu dan yang lain longgar karena cerita ini memiliki banyak tokoh. Dalam Para Priyayi dikisahkan seorang anak petani desa, Sastrodarsono, yang berjuang untuk meningkatkan golongannya dan berhasil masuk jenjang priyayi. Cerita tersebut memiliki kemungkinan terjadi di masyarakat dan masuk akal. Akan tetapi, mungkin hanya orang sedikit yang melakukan usaha seperti Sastrodarsono yang membangun keluarganya dari golongan petani desa menjadi keluarga priyayi yang mumpuni. Tegangan (suspense) dalam novel ini terjadi ketika Harimurti menunggu dengan harap-harap cemas keluarganya menjemput Gadis dari penjara. Sementara itu, kejutan (surprise) dalam novel ini, yaitu ternyata Gadis meninggal dunia karena terlalu cepat melahirkan. Kabar tersebut sangat mengejutkan Harimurti dan seluruh keluarganya. Sementara itu, akhir cerita novel Para Priyayi ini dapat dikatakan berakhir bahagia. Hal ini disebabkan setiap tokohnya telah mendapatkan kebahagiaan, Marie telah hidup bahagia dengan Maridjan dan Harimurti telah mendapat kebebasannya. Setelah menganalisi alur, peneliti akan menganalisis latar Para Priyayi. 4. Latar a. Latar tempat Latar tempat merupakan lokasi kejadian dalam novel. Melalui latar tempat, pembaca dapat membayangkan kondisi suasana tempat 99 yang sedang terjadi, sedangkan suasana yang dimaksud di atas terkait dengan alur cerita yang sudah dipaparkan di atas. Latar tempat dalam novel Para Priyayi berada di beberapa tempat berikut ini. 1) Wanagalih Wanagalih adalah sebuah ibukota Kabupaten di Jawa. Kota itu lahir sejak pertengahan abad ke-19. Wanagalih merupakan tempat tinggal Sastrodarsono dan Ngaisah. Tempat ini merupakan pusat berkumpulnya seluruh anggota keluarga Sastrodarsono. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. “Keputusan kami untuk bertempat tinggal di Wanagalih dan tidak di desa saya bekerja, yaitu di Karangdompol, adalah juga atas nasihat Ndoro eh, Romo Seten Kedungsimo yang didukung oleh mertua saya Romo Mukaram.”98 “Seperti biasa, bila kami semua berkumpul di Wanagalih, kami akan mereguk semua kenikmatan yang ditawarkan oleh rumah induk keluarga kami di Jalan Setenan, ….”99 2) Wanalawas Wanalawas merupakan tempat Sastrodarsono mendirikan sekolah bantu untuk warga Wanalawas agar mereka dapat membaca dan menulis.Hal ini dapat dilihat pada kutipan,“Akhirnya semua persiapan untuk sekolah itu selesai juga. Semua perlengkapan, meski sangat sederhana, tersedia. Bangku dan meja secara gotong royong dibuat oleh orang-orang Wanalawas dengan alat-alat sederhana dan dari kayu-kayu yang didapat di sekitar Wanagalih.” 3) Karangdompol Desa Karangdompol merupakan tempat di mana Sastrodarsono mendirikan sekolah bantu atas usulan dari seniornya, Martidiatmojo. 98 Ibid., h. 52. Ibid., h. 198-199. 99 100 Inilah salah satu kutipannya, “Desa Karangdompol, tempat sekolah saya berada itu, ada di seberang Kali Madiun.”100 4) Wonogiri Wonogiri sendiri merupakan tempat mengajar Hardojo. Hardojo berada di Wonogiri selama dua tahun. Beliau juga mendapatkan istri yang berasal dari daerah Wonogiri. Inilah salah satu kutipannya, “Tempat saya mengajar di HIS Wonogiri, yang berjarak lebih kurang tiga puluh kilometer dari kota solo….”101 5) Solo Solo merupakan tempat bekerja Hardojo setelah mendapat tawaran menjadi abdi dalem Mangkunegaran. Hardojo mengurusi bidang pendidikan orang dewasa dan gerakan pemuda. Oleh karena itu, seluruh daerah yang berada di bawah kerajaan Mangkunegaran ia datangi. Berikut kutipannya. “… untuk akhirnya waktu menjelang masuk stasiun Sangkrah di Solo hanya wajah Sumantri saja yang terbayang.”102 6) Yogyakarta Yogyakarta merupakan tempat tinggal keluarga Noegroho sebelum pindah ke Jakarta. Pada masa penjajahan Belanda, ia bekerja sebagai guru HIS di Jetis Yogyakarta. Selain itu, Hardojo juga tinggal di Yogyakarta setelah ia kecewa dengan sikap Mangkunegaran yang memihak Belanda.Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini.“Kami pun lantas untuk sementara pindah lagi ke Yogya ke rumah ibu Sus, yang menetap di Yogya sejak pensiunnya di Semarang. Rumah itu 100 Ibid., h. 23. Ibid., h. 151. 102 Ibid., h. 171. 101 101 tidak berapa besar, di bilangan Jetis, tidak jauh dari bekas sekolah dasar, tempat saya mengajar dulu.”103 7) Jakarta Jakarta merupakan tempat tinggal keluarga Noegroho. Ketika keluarga Noegroho terkena musibah, Marie hamil di luar nikah, Lantip ditugasi oleh Sastrodarsono dan Ngaisah untuk ikut Sus ke Jakarta dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, keluarga Soemini, anak Sastrodarsono yang ketiga, juga tinggal di Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut,“Di Jakarta, di rumah Pakde Noegroho, saya langsung bertemu dengan Marie dan Tommi. Saya langsung pula berhadapan dengan sepupu-sepupu yang angkuh dan manja.”104 dan “Bagi mereka berdua yang terpenting akad nikah itu akhirnya sudah berlalu dengan selamat dan direstui oleh hadirnya semua anggota keluarga besar yang pada datang berkumpul di Jakarta.”105 b. Latar Waktu Latar waktu novel ini diawali pada masa penjajahan Belanda kemudian pendudukan Jepang, awal kemerdekaan hingga pemberontakan PKI. Tahun 1910 cerita ini dimulai, Sastrodarsono mulai menapakkan kakinya ke jenjang priyayi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Waktu itu, sekitar tahun 1910 Masehi, daerah di sekitar desa-desa tersebut boleh dikata masih lebat hutannya....”106 Pada masa penjajahan Belanda, priyayi tidak hanya mengacu pada keluarga keraton dan sejenisnya. Kebutuhan akan pegawai pribumi yang berpendidikan telah membuka pintu bagi seluruh lapisan 103 Ibid., h. 207. Ibid., h. 257. 105 Ibid., h. 278. 106 Ibid., h. 36. 104 102 masyarakat untuk maju menjadi priyayi. Pendidikan menjadi modal awal bagi kaum wong cilik untuk mendobrak keterbatasan statusnya. Bagi priyayi yang telah berhasil adalah suatu kewajiban untuk membantu wong cilik untuk mencapai status priyayi, hal ini dilakukan dengan jalan pendidikan. Selain itu perubahan juga dapat terlihat pada perkembangan seni budaya, emansipasi wanita, dan idealisme pengabdian. Pentingnya intelektualitas semakin disadari oleh kaum wong cilik karena dengannya mereka mendapat kesempatan untuk menjadi priyayi, dengan bantuan kaum priyayi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Jangan hanya puas jadi petani, Le. Kalian harus menjadi priyayi.”107 Status priyayi berarti kehormatan, pangkat dan kemapanan hidup secara ekonomi. Menjadi priyayi adalah impian hidup keluarga Atmokasan, namun untuk mencapai tujuan itu pendidikan menjadi modal dasar, seperti kutipan berikut, “Kalian harus sekolah.”108 Dengan memiliki pendidikan mereka akan diperhatikan oleh pemerintah dan dapat menduduki suatu jabatan. Ndoro Seten berperan dalam proses ini sebagai pembuka jalan, Sastrodarsono. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. “… dicarikan jalan lewat Ndoro Wedono dan para Priyagung di Madiun untuk dapat diterima magang menjadi guru bantu.”109 Sastrodarsono melakukan proses yang sama dengan mengangkat Lantip untuk menjadi priyayi. Tiga puluh tahun kemudian adalah masa pendudukan Jepang dan revolusi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Seperti di tempat-tempat lain di Jawa, tentara Jepang masuk dan menguasai 107 Ibid., h. 30. Ibid., 109 Ibid., h. 31. 108 103 Wanagalih dengan mudah.”110 Tokoh yang muncul pada waktu itu adalah anak-anak Sastrodarsono. Noegroho menjadi anggota tentara, Hardojo menjadi abdi dalem di Mangkunegaran, dan Soemini menjadi istri asisten wedana. Cita-cita Sastrodarsono untuk membangun keluarga priyayi dapat dikatakan berhasil. Zaman Jepang, yang walaupun sebentar, menjadi masa paling memprihatinkan bagi Sastrodarsono. Pada masa ini, berdasarkan fakta sejarah, terjadi tahun 1942-1945. Tidak secara eksplisit disebutkan angka tahun ini dalam novel Para Priyayi, tetapi peristiwa-peristiwa yang menampilkan keberadaan Jepang di Indonesia sangat kentara. Misalnya, saat Sastrodarsono disuruh saikere ke arah utara, hal ini terdapat pada kutipan berikut, “Bayangkan, Bune, orang setua saya disuruh membungkuk-bungkuk menghadap ke utara setiap pagi untuk menyembah dewa. ...”111. Awal kemerdekaan, ditandai dengan kalahnya Jepang pada 1945. Angka ini tidak muncul secara nyata dalam novel, tetapi digambarkan pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Tahu-tahu Jepang kalah perang dan kami, Peta, dibubarkan dan dilucuti senjata kami. Begitu saja. Kami pun lantas untuk sementara pindah lagi ke Yogya ke rumah ibu Sus, yang menetap di Yogya sejak pensiunnya di Semarang….” …. “…. Untunglah juga segera sesudah kita memproklamasikan kemerdekaan, kita mulai memikirkan akan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Saya segera bergabung dengan kawan-kawan bekas Peta, Heiho dan Polisi dan para pemuda untuk menyusun Badan Keamanan Rakyat di Yogya. Kemudian kami harus memperlengkapi diri dengan senjata yang harus kami rebut dari Jepang.”112 110 Ibid., h. 135. Ibid., h. 126. 112 Ibid., h. 207. 111 104 Tak lama setelah itu, zaman revolusi masuk. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Zaman revolusi ternyata adalah kepanjangan penderitaan zaman Jepang. Bedanya tentu zaman Jepang adalah penderitaan orang yang dijajah dengan sangat kejam oleh negeri yang sedang perang, sedang penderitaan zaman revolusi adalah penderitaan yang memang diniati oleh bangsa yang ingin punya negara merdeka.”113 Secara spesifik tahun 1947 tidak ada, akan tetapi peristiwa yang mewakili tahun itu terlihat jelas dalam Para Priyayi. Hal ini terdapat pada kutipan berikut, “Akhirnya Belanda menyerbu Yogyakarta juga. ...”, Dalam sejarah Indonesia, tahun ini merujuk pada Agresi Militer Belanda I, dan salah satu kota sasaran Belanda ialah Yogyakarta. Dalam agresi ini, anak Noegroho (Toni) meninggal ditembak tentara Belanda.114 Pada masa-masa ini, terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan karena itu pasukan Siliwangi ditugaskan untuk menggempur kekuatan PKI di daerah Madiun, Solo, dan Pati, tetapi kemudian usaha ini tidak cukup berhasil, karena revolusi tidak dipimpin dan dilaksanakan oleh rakyat. Situasi makin tidak terkendali tatkala Muso datang dari Rusia dan mengambil alih kepemimpinan PKI. PKI melakukan pemberontakan dan beberapa teman Sastrodarsono seperti Pak Haji Mansur, ikut menjadi korban pembantaian PKI. Sampai pada gilirannya, pasukan Siliwangi datang dan mengambil alih keadaan sehingga orang PKI dan antek-anteknya, termasuk Pak Martokebo, digiring ke alun-alun yang kemudian mereka meregang nyawa di ujung regu penembak Siliwangi. 113 Ibid., h. 209. Ibid., h. 202. 114 105 Penyerahan kedaulatan terjadi pada tahun 1950. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Pada waktu sebagian besar pegawai republik ikut pindah ke Jakarta sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950. Bapak memilih pindah ke Yogya dan bekerja pada pemerintahan DIY. Rupanya Bapak yang pernah dikecewakan oleh Mangkunegaraan yang tidak tegas memilih republik dan kemudian malah membantu Belanda, tetap senang bekerja dalam lingkungan kerajaan. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipandangnya sesuai benar baginya. Dia merasa sekaligus dipuaskan keinginannya untuk mengabdi kepada republik dan suatu lingkungan budaya tradisi Jawa yang dipimpin oleh seorang sultan yang berjiwa modern dan republiken.”115 Pada 8 Mei 1964, Soekarno mengumumkan pelarangan Manifes Kebudayaan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Gadis mau mentraktir saya malam itu. Hari itu, saya ingat benar, adalah tanggal 8 Mei 1964, hari Pemimpin Besar revolusi mengumumkan pelarangan Manifes Kebudayaan. Gadis ingin merayakan kekalahan Manikebu, kekalahankekalahan penulis-penulis lawan Lekra, bersama saya. Saya ingin merayakan kemenangan ini hanya dengan kamu, katanya.”116 Setahun setelah itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengambil alih semuanya (termasuk Dewan Revolusi) dan mulai mengadakan pembersihan terhadap semua anggota PKI dan ormasormasnya. Pada peristiwa ini, Gadis masuk penjara sementara Harimurti, atas saran Lantip, menyerahkan diri. Cerita dalam novel berakhir padaperiode awal Orde Baru. Hal ini dapat dilihat pada 115 Ibid., h. 281. Ibid., h. 285. 116 106 kutipan berikut, “Tahun 1967 ini Embah Kakung sudah berumur kirakira delapan puluh tiga tahun.”117 Dengan waktu cerita yang begitu panjang itu, Para Priyayi seolah-olah menjadi semacam sintesis dari waktu cerita yang pernah digunakan dalam sejumlah novel Indonesia modern yang mengangkat latar sejarah sejak zaman awal pergerakan hingga masa Orde Baru. c. Latar Sosial Latar sosial yang menonjol dalam Para Priyayi adalah latar status sosial tokoh Sastrodarsono yang turut menentukan kelas sosialnya dalam masyarakat Jawa. Kenaikan status sosialnya dalam masyarakat begitu mengagumkan bagi keluarga besarnya. Ia mendapat beslit guru bantu dan berhasil menjadi seorang priyayi, meskipun hanya menjadi priyayi tingkat rendah. Akan tetapi, di mata masyarakat kedudukan priyayi sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Pada zaman itu kedudukan seorang mantri guru sekolah desa adalah kedudukan yang cukup tinggi di mata masyarakat, seperti masyarakat Wanagalih. Mantri guru jelas didudukan masyarakat dan pemerintah sebagai priyayi. Ia punya jabatan, ia punya gaji tetap.”118 Pengertian kelas adalah kesetaraan kemampuan ekonomi orang-orang dalam suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dan statusnya. Semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu kelas untuk memiliki jasa, benda dan lain-lain berarti semakin tinggi kelasnya dalam masyarakat. Kelas menengah ke bawah memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas untuk mendapatkan kemewahan selayaknya kelas atas. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat terbagi dalam tingkatan-tingkatan sosial. 117 Ibid., h. 301. Ibid., h. 16. 118 107 Menurut Geertz pembagian kelas dalam masyarakat Jawa tidak terpaku pada hierarki kemampuan ekonomi tiap orang, namun lebih kearah jenis pekerjaan, pendidikan, dan spiritual. Kaum priyayi dianggap sebagai kaum tingkat menengah ke atas karena mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pekerjaaan dalam pemerintahan dan memimpin upacara adat. Kelompok sosial yang terpisah satu sama lain nampaknya tidak memungkinkan untuk menjalin hubungan yang erat antar status. Para priyayi di satu sisi selalu dianggap sebagai penguasa, sedangkan abangan/wong cilik hanya menjadi pekerja kasar. Hal tersebut memperlebar jarak dan juga memberikan batas antara kedua kaum tersebut. Akan tetapi, Umar Kayam dalam novel Para Priyayi justru memutarbalikkan situasi tersebut menjadi suatu hubungan timbal balik antara kaum priyayi dan wong cilik dan mendobrak pembatas antar mereka. Priyayi tidak lagi digambarkan sebagai kaum yang individualistis tetapi bersimpati pada wong cilik. Hubungan sosial antar kaum terjalin lewat peranan priyayi dalam menjembatani kaum abangan/wong cilik yang ingin menjadi priyayi. Sebagai contoh, budaya ngenger membuka peluang bagi semua kaum untuk menjadi priyayi. Sehingga dengan kata lain orang dengan kelas yang lebih rendah dapat berelasi dengan kaum priyayi. Anak yang dingegerkan oleh kerabatnya atau masyarakat dari pedesaan, Anak-anak tersebut secara ekonomis merupakan beban rumah tangga priyayi. Akan tetapi, dengan adanya anak pungut dan anak ngengeran itu terjalin hubungan antara keluarga priyayi dengan kerabat si anak di pedesaaan atau kerabat priyayi yang lebih rendah. Paling tidak kerabat dari anak pungut atau anak ngengeran akan menjunjung nama baik keluarga priyayi bersangkutan di daerahnya. Anak pungut dan anak ngenger ini dapat pula memperkuat kedudukan 108 orang tua angkatnya (keluarga priyayi) dan nantinya anak pungut dan anak ngenger akan menjadi priyayi pada derajat yang lebih rendah. Hal inilah yang melatarbelakangi Sastrodarsono mengangkat Wage menjadi anak asuhnya dan mengganti namanya dengan Lantip. Ada dua alasan menurut asumsi penulis, mengenai “Lantip” ini. Pertama, Umar Kayam setuju terhadap pendapat Geertz yang menyatakan bahwa unsur “bangsawan” ini sekarang kurang penting.119 Kedua, sebagai bentuk kompromi (negosiasi) terhadap karya Geertz. Kita tahu bahwa Geertz menyatakan, priyayi itu sebagai sesuatu yang fix, bahwa ia merupakan sesuatu yang diperoleh secara keturunan, terutama dari Raja-raja Jawa klasik; bahwa priyayi akarnya ialah Hindu-Jawa. Terhadap kedua pandangan tersebut, Umar Kayam berlaku resistens, buktinya ialah ketika menceritakan Hardojo, putera kedua Sastrodarsono. Priyayi baru itu jatuh cinta kepada Nunuk, gadis Katolik dari Solo. Ketika Hardojo meminta ayahnya melamar, ayahnya menolak karena alasan agama. Dengan demikian priyayi abangan menurut Umar Kayam sebenarnya masih berakar pada Islam juga, bagaimanapun bentuknya. Begitu juga mengenai asal usulnya Sastrodarsono, atau Lantip, keduanya bukan keturunan raja. Yang satu petani desa, yang satu lagi hasil dari hubungan gelap: anak jadah. Akan tetapi untuk satu masalah yang lain, yaitu perihal kepriyayian sekarang tidak penting lagi, Umar Kayam bersepakat dengan Geertz. Setelah mengalisis latar, peneliti akan menganalisis sudut pandang Para Priyayi. 5. Sudut Pandang Sudut pandang pengarang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini terlihat pada setiap episode cerita. 119 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terjemahan Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 308. 109 Pengarang bertindak sebagai orang pertama yang sedang menuturkan pengalamannya. Sudut pandang ini menempatkan pengarang sebagai “saya” atau “aku” dalam cerita. Pada bagian Lantip, pengarang menjadi Lantip, pada bagian Sastrodarsono, pengarang menjadi Sastrodarsono, begitupula seterusnya. Ini suatu cara bercerita yang menarik karena pengarang menjadi beberapa tokoh sekaligus dalam satu rangkaian cerita. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kutipan sebagai berikut. “Saya ingat bagaimana kemudian suami-istri sastrodarsono memandang kami lama-lama. Tentulah saya hanya dapat melihat sekilas dari sudut mata saya karena saya hanya berani menundukkan kepala selama percakapan itu berlangsung. Untuk seorang anak desa yang baru berumur enam tahun, anak bakul tempe lagi, keberanian apa yang bisa saya kerahkan untuk mendongak melihat ke atas menatap muka priyayi-priyayi itu. Tidak mungkin ada keberanian itu. Mungkin terpikirkan pun tidak. Mungkin wajar saja, begitu saja, saya menundukkan kepala di hadapan seorang priyayi.”120 (Lantip) Tokoh-tokoh dalam Para Priyayi yang bertindak sebagai pencerita, terus berlanjut ganti-berganti secara konsisten. Oleh karena yang digunakannya bentuk pencerita akuan (saya), maka secara efektif terasa lebih dekat pada model catatan biografis—atau autobiografis—dari masing-masing tokohnya. Umar Kayam menceritakan setiap tokoh melalui sudut pandang orang pertama sehingga pembaca lebih merasakan peran tokoh dibandingkan peran penulis dalam cerita. Setelah menganalisis sudut pandang, peneliti akan menganalisis gaya bahasa Para Priyayi. 6. Gaya Bahasa Gaya bahasa merupakan cara pengungkapan khas pengarang dalam karya. Hal ini dapat di lihat dari cara pengarang menyampaikan idenya dengan kalimat-kalimat yang indah. 120 Ibid., h. 15. 110 Gaya bahasa mengandung pengertian tiga hal yang terkait gaya bahasa; pertama, berupa media, berupa kata, dan kalimat. Kedua, berupa hubungan gaya dengan makna dan keindahannya. Ketiga, berupa ekspresi pengarang yang akan berhubungan erat dengan masalah individual kepengarangan dan latar belakang masyarakat sekitar pengarang. Gaya penceritaan adalah tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa yang menjadikan sastra hadir. Pada dasarnya karya sastra merupakan salah satu kegiatan pengarang yang membahas atau menuturkan sesuatu kepada orang lain. Gaya bahasa yang digunakan Umar Kayam dalam novel Para Priyayi antara lain menggunakan majas hiperbola. Majas hiperbola yang digunakan Umar Kayam dalam novel Para Priyayi terdapat pada kutipan berikut, “Tanah Wanagalih yang ganas itu akan segera menghancurkannya.”121 Gaya penulisan Umar Kayam memiliki ciri khasnya. Cara penyampaian yang apa adanya dan sederhana membuat pembaca akan dengan mudah mengerti apa yang ingin disampaikannya. Ia menulis dengan rinci dan jelas. Sebagai seorang sejarawan tulisan-tulisan yang dia buat menyangkut kehidupan yang nyata. Bahasa yang digunakan Kayam dalam menyampaikan cerita sehingga mampu menuansakan makna, menyentuh daya intelektual, dan mampu menggugah emosi pembaca. Oleh karena itu, ia mampu menarik pembaca untuk masuk ke dalam cerita sehingga pembaca pun seolah-olah mengetahui secara pasti situasi dan kondisi dari cerita yang dibacanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa merupakan cara pengarang menggunakan diksi yang cocok ketika memadukan cerita dengan unsur intrinsik yang membuat cerita tersebut menjadi lebih hidup. Karakteristik 121 Ibid., h. 2. 111 sebuah karya dan pengarangnya pun dapat terlihat melalui gaya bahasa yang digunakan. Kecerdasan Umar Kayam dalam bercerita seolah-olah seperti kenyataan, juga turut mempengaruhi pembaca untuk masuk ke dalam cerita. Setelah menganalisis gaya bahasa, peneliti akan menganalisis amanat Para Priyayi. Amanat 7. Amanat yang dapat kita petik dalam novel Para Priyayi ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang priyayi yang mempunyai kedudukan dan pendidikan terhadap keluarganya yang lain. Tidak boleh menikmati rezeki dan pangkatnya untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Rezeki dan pangkat itu jangan dimakan dan dikangkangi sendiri, begitulah saya dengar Ndoro Guru berkali-kali menasihati anakanaknya dan siapa saja. Tidak pantas, saru, bila ada seseorang anggota keluarga besar priyayi yang kleleran, terbengkalai, jadi gelandangan tidak ada yang mengurus, tidak menikmati pendidikan, begitu nasihatnya yang lain. Priyayi yang tidak urus begitu adalah priyayi yang jelek bahkan bukan priyayi, tekan Ndoro Guru lebih jauh.”122 Pesan yang dapat diteladani pula adalah kita tidak boleh lupa asal usul kita, dan berterima kasih serta bersyukur dengan pencapaian yang kita dapat. Selain itu, menjaga nama baik sebagai orang yang terpandang karena berpendidikan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Le, kamu, meski sudah jadi priyayi, jangan lupa aka asal usulmu. Kacang masa akan lupa dengan lanjaran-nya. Rumah tanggamu, meski rumah tangga priyayi, tidak boleh tergantung dari gajimu, Le. Jadi priyayi itu jadi orang terpandang di masyarakat, bukan jadi orang kaya. Priyayi itu terpandang kedudukannya, karena kepinterannya….”123 122 Ibid., h. 17. Ibid., h. 53. 123 112 Selain itu, bagaimana sebenarnya seorang yang dikatakan "priyayi" yaitu seorang yang dapat mengayomi keluarga dan rakyat miskin, memiliki pendirian yang kokoh, dan berjuang keras tanpa pamrih. Selalu menjaga nama baik keluarga, "Mikul duwur mendhem jero, menjunjung tinggi-tinggi keharuman nama keluarga, menanam dalam-dalam aib keluarga ....”124 Cerita dalam novel ini memberikan pelajaran hidup kepada kita bahwa hidup ini adalah perjuangan yang keras. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Embah Kakung ingin melihat keluarga besar ini tumbuh kukuh, kuat, dan berisi galih, bagian kayu yang paling keras. Adapun galih, bagian kayu yang paling keras yang ingin beliau kembangkan dan tumbuhkan itu adalah semangat, nilai mengabdi dari priyayi kepada orang banyak, kepada masyarakat luas. Sebagai keturunan petani desa, beliau ingin memulai usaha untuk ikut mengisi dan memberi bentuk sosok semangat priyayi itu suatu kerja raksasa yang selama ini hanya boleh dikerjakan oleh mereka yang dianggap darah biru.”125 Berdasarkan kutipan di atas, terlihat pernyataan bahwa priyayi adalah tentang kerja keras dan semangat mengabdi kepada masyarakat luas. Hal ini tampak dari kehidupan Sastrodarsono yang memulai kepriyayiannya dari bawah. Sastrodarsono merupakan pemula dari keseluruhan priyayi dalam cerita. Ia adalah asal mula pendiri kepriyayian di keluarganya. Orang tuanya hanya seorang petani yang mengabdi dengan tekun dan jujur kepada majikannya. Pengabdian itu pula yang membawa Lantip menjadi sosok priyayi yang sesungguhnya. Umar Kayam ingin menyampaikan pesan bahwa priyayi yang sesungguhnya tidak memandang asal mula ia berada. Seperti yang digambarkan dalam dua sosok, yakni Sastrodarsono dan Lantip. Sastrodarsono anak seorang petani bahkan Lantip justru anak haram yang 124 Ibid., h. 132-133. Ibid., h. 305. 125 113 lahir dari dari Soenandar yang diketahui menjadi perampok. Akan tetapi, kedua orang inilah yang mampu menggambarkan sosok priyayi ideal. Setelah menganalisis unsur-unsur intrinsik, selanjutnya peneliti akan menganalisis nilai sosial dalam novel Para Priyayi. B. Analisis Nilai Sosial dalam Novel Para Priyayi Novel Para Priyayi karya Umar Kayam terbit pada tahun 1992 dengan ketebalan 337 halaman ini mengandung nilai sosial yang sangat beragam. Nilai-nilai sosial tersebut nampak dari penggambaran kesepakatan masyarakat dan pandangan hidup para tokoh dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Hal ini terlihat dalan percakapan atau narasi yang disampaikan oleh para tokoh dalam novel yang telah penulis teliti. Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan nilai-nilai sosial tersebut melalui interaksi sosial antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam relasi-relasi yang terbagi menjadi enam kategori Simmel sebagai berikut. 1. Relasi Individu dengan Dirinya, 2. Relasi Individu dengan Keluarga, 3. Relasi Individu dengan Lembaga, 4. Relasi Individu dengan Komunitas, 5. Relasi Individu dengan Masyarakat, dan 6. Relasi Individu dengan Nasion. Adanya aspek sosial—kebersamaan yang melekat pada individu menyebabkan kodratnya hidup bersama individu lain. Individu yang mewujudkan pola perilakunya yang khas pada suatu lingkungan sosial disebut bagian dari masyarakat. Satuan-satuan lingkungan sosial yang melingkari individu terdiri dari keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat, dan nasion. Berikut nilai sosial dalam enam kategori relasi sosial yang terdapat dalam novel Para Priyayi karya Umar Kayam. 114 1. Relasi Individu dengan Dirinya. Hubungan ini berkaitan erat dengan masalah kejiwaan seseorang. Masalah ini dialami oleh Sastrodarsono ketika ia harus mengalami konflik intern tentang penentuan sikap kepriyayiannya. Ia bersimpati pada tokoh Martoatmodjo, seorang tokoh pergerakan yang merupakan seniornya di Sekolah. Akan tetapi, ia juga memikirkan nasib keluarga kecilnya yang baru mulai menapaki kehidupan rumah tangga priyayi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan dalam Novel Para Priyayi di bawah sebagai berikut. “Waktu tiba di Wanagalih sesudah berlibur demikian lama di Jogorogo dan Kedungsimo, saya mendapat surat beslit itu. saya diangkat menjadi kepala sekolah menggantikan Mas Martoadmodjo yang dipindah ke sekolah desa Gesing. Gesing! Itu adalah satu daerah yang cengkar, tandus, tanahnya keras, pecah-pecah, berbongkahbongkah, terpencil di kaki Pegunungan Kendeng. Kasihan Mas Martoadmodjo disingkirkan ke neraka yang begitu mengenaskan.”126 Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, nilai sosial digambarkan melalui nilai kepedulian Sastrodarsono yang merasa iba terhadap nasib Martoadmodjo. Martoadmodjo adalah senior sekaligus kepala sekolah tempat ia mengajar. Hal ini menunjukan bahwa ia seorang ia orang yang mudah menaruh belas kasihan dan mudah terharu terhadap perilaku orang lain. Martoadmodjo dituduh melakukan pergerakan karena membaca harian Medan Priyayi. Pada waktu itu membaca harian tersebut dianggap melakukan pergerakan dan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Sastrodarsono datang menemui Martoatmodjo setelah diberitahu oleh Nippon mengenai tuduhan pergerakan yang dilakukan Martoatmodjo. Ia ingin memastikan kebenarannya. Medan Priyayi, mingguan yang memuat artikel-artikel perlawanan terhadap kolonialisme, seperti Multatuli, dan kritikan bagi pejabat yang korup. Banyak priyayi yang tidak berani mengikuti jejak Martoatmodjo karena takut 126 Ibid., h. 71. 115 kehilangan status dan kemapanan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Mereka takut dengan bacaan seperti ini. Mereka takut kehilangan pekerjaan mereka.”127 Sastrodarsono mengalami konflik batin yang cukup hebat, karena ia sangat menghormati Martoatmodjo sebagai senior sekaligus kepala sekolah di Karangdompol. Selain itu, sebagai kepala rumah tangga, ia pun gelisah dengan istri dan anak-anaknya. Jika ia membantu Martoadmodjo, maka ia akan bernasib sama dengannya, yaitu disingkirkan dari Karangdompol bahkan diasingkan, sedangkan ia baru saja mendapatkan status priyayi. Pada akhirnya dengan berat hati ia menuruti nasihat keluarga dan saran Martoatmodjo untuk tidak mengikuti jejak Martoadmodjo. Meskipun hatinya tidak sejalan. Kemunculan pemikiran ini adalah suatu bentuk reformasi idealisme priyayi yang terkesan pasif dan individualitis menjadi dinamis. Oleh karena itu, Martoatmodjo dituduh menghasut masyarakat. Pergerakan yang dilakukan Martoatmodjo dikhawatirkan oleh Opziener dapat mengancam keberadaan gupermen dan pada akhirnya barisan priyayi maju. Selain Sastrodarsono, Harimurti juga mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Ia merasa menjadi pribadi yang terombang-ambing dalam ketidakjelasannya untuk menentukan sikap sebagai keturunan priyayi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya adalah orang yang terombang-ambing antara berbagai perasaan simpati dan solider. Simpati dan solider kepada wong cilik yang tidak kunjung beruntung nasibnya menjadi bulan-bulanan mereka yang berkuasa. Simpati dan solider kepada para priyayi yang muncul dari lumpur-lumpur sawah dan ingin menyeret seluruh kerabatnya ke permukaan untuk ikut mengecap dan menikmati dan akhirnya ikut menentukan sosok budaya besar, apapun itu artinya. Dan keterombang-ambingan saya ini aneh sekali saya lihat hanya dapat ditampung oleh Lekra.”128 127 128 Ibid., h. 57. Ibid., h. 310. 116 Harimurti ikut dalam pemberontakan dengan masuk ke dalam Lekra, sebuah organisasi kesenian beraliran komunis. Setelah berkenalan dan berhubungan dengan Gadis pengaruh komunis semakin meresap, namun sebenarnya dalam dirinya ia mempertanyakan esensi dari gerakan itu. Ia terombang ambing antara perasaan simpati dan solider. Hal ini menunjukkan ia adalah orang memiliki sifat simpati sekaligus solider terhadap orang lain. Seni yang dipelihara oleh priyayi sebagai bentuk estetika justru dieksploitasi sebagai alat politik. Hal ini terjadi ketika Hari bergabung dalam Lekra, sebuah kelompok pencinta seni yang diprakarsai oleh kaum komunis. Seni tradisional dihubungkan dengan feodalisme yang ditujukan untuk kekuasaan, dengan kata lain cerita rakyat Jawa adalah “… cerita kekuasaan.”129 Beberapa tokoh seperti Bung Naryo beranggapan bahwa “cinta memang bisa indah, tetapi dalam kisah cinta itu embel-embel dari strategi kekuasaan yang sangat kejam.”130 Dari sini tampak bahwa kaum priyayi mencemari seni dengan idealisme sosialis demi kepentingan politis. Hal inilah yang awalnya menjerumuskan Hari ke dalam Lekra. 2. Relasi Individu dengan Keluarga Hubungan ini merupakan relasi yang mutlak. Relasi ini membentuk kedekatan biologis, psikologis, dan sosial. Dalam kekerabatan, nilai kerukunan sangat diperlukan dalam membangun relasi yang harmonis antara priyayi dan wong cilik. Relasi yang awalnya antar status antara priyayi dan wong cilik bertransformasi menjadi hubungan yang lebih bersifat kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Dan karena hubungan itu pula saya mendapat nama saya yang Soedarsono, …. nama yang menurut bayangan kami hanya pantas dimiliki anak-anak priyayi saja.”131 Soedarsono adalah nama asli Sastrodarsono. 129 Ibid., h. 270. Ibid., 131 Ibid., h. 31. 130 117 Dari situlah kedekatan yang sudah seperti keluarga sendiri terjalin, bahkan Ndoro Seten sampai memberikan nama priyayi untuk anak yang sedang dikandung oleh istri Atmokasan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan ini terjadi melalui sosialisasi karena interaksi yang sering antara keduanya. Pada masa Sastrodarsono masih tinggal di Kedungsimo, Atmokasan menjaga hubungannya dengan Ndoro Seten sehingga kerukunan tercipta. Hubungan kemudian bersifat timbal balik, Atmokasan mengerjakan kewajibannya sebagai petani dengan selalu jujur dalam bekerja. Di lain pihak Ndoro Seten menghargai kerja kerasnya dengan membantu Sastrodarsono menjadi seorang priyayi. Ia menghormati Ndoro Seten dengan berbuat jujur dan tidak mengecewakannya. Kerukunan pun terjaga dengan baik karena kedua pihak saling mengerti. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Bukan main besar, sesungguhnya, utang budi orang tua saya kepada Ndoro Seten. Waktu orang tua saya menyatakan hal itu kepada Ndoro Seten, dengan tersenyum mereka mengatakan bahwa itu adalah hadiah mereka buat kejujuran dan ketulusan orang tua kami menggarap sawah Ndoro Seten. Orang tua kami dinyatakan oleh Ndoro Seten sebagai petani yang tahu menepati kewajiban, menyetor hasil panen kepada mereka tak pernah mencoba mengurangi atau mencuri bawonan atau ikatan panenan padi waktu habis menuai.”132 Relasi kekeluargaan terlihat ketika Ndoro Seten telah menganggap Atmokasan sebagai saudara tua dengan memanggil „kamas‟, sedangkan Sastrodarsono kini memanggilnya dengan „romo‟. Tradisi kekerabatan diturunkan pada Sastrodarsono. Ia mengangkat sepupunya Soenandar untuk masuk dalam keluarganya supaya mendapat pendidikan yang memadai dan mampu menjadi priyayi seperti dirinya. Sastrodarsono juga banyak berhubungan dengan warga desa Wanalawas dan membantu dengan 132 Ibid., h. 35. 118 mendirikan sekolah bagi wong cilik, yang diserahkan pada Soenandar. Hal ini menunjukkan sifat kepriyayian Sastrodarsono yang bak hati dan suka membantu. Hal ini juga merupakan keharusan sebagai seorang priyayi. Keluarga besar Sastrodarsono merupakan relasi yang terjalin dengan kuat antara individu yang satu dengan yang lainnya. Saling membantu dan menjaga kerukunan adalah pembagian kerja dalam keluarga menjadi hal yang biasa dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga besar Sastrodarsono. Hal ini terbukti ketika masalah demi masalah menimpa keluarga besarnya, semua anggota keluarga ikut merasakan dan membantu menyelesaikan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya memenuhi janji saya untuk sowan ke Wanagalih sesudah menjalani latihan di Bogor. Saya datang dengan seluruh keluarga saya. Demikian juga dengan adik-adik saya yang juga datang bersama keluarga mereka. Alangkah rukun dan guyub keluarga besar kami sesungguhnya. Pada saat-saat yang kami anggap penting, apalagi yang kami nilai peka, kami selalu berkumpul di Wanagalih.”133 Berdasarkan kutipan di atas, nilai sosial yang yang terdapat di dalamnya adalah nilai kerukunan. Keluarga Sastrodarsono selalu berkumpul di Wanagalih dalam setiap keadaan yang penting. Hal itu sudah menjadi kebiasaan. Nilai sosial yang berupa nilai kerukunan antarindividu dalam keluarga juga diwujudkan melalui pembagian kerja seorang istri dan suami agar seimbang dan selalu tercipta kerukunan dalam keluarga. Ngaisah meyakini hal ini dalam kehidupan rumah tangganya. Ngaisah adalah istri yang sangat setia dan berbakti kepada suaminya. Meskipun anak-mantunya suka menggodanya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Anak-anak mantu saya sering mengganggu saya dengan mengatakan bahwa saya terlalu memanjakan dan terlalu berbakti kepada bapak mereka. Saya heran dengan jalan pikiran anak sekarang. Masa begitu dikatakan memanjakan dan terlalu berbakti. Bukankah itu pembagian 133 Ibid., h. 198. 119 kerja saja antara saya dan bapak mereka? Bapak sudah membanting tulang mencari nafkah, saya yang ada di garis belakang mengurus semuanya agar dalam keadaan beres. Kalau sampai tidak beres, bapake tole bingung dan marah-marah, bisa kacau dia bekerja.”134 Nilai kerukunan juga ditunjukkan oleh seluruh keluarga yang hadir dalam acara pertunangan Lantip dan Halimah. Harimurti terharu dengan ikatan keluarga besar Sastrodarsono yang masih kuat. Meskipun Ngaisah sudah tidak ada dan Sastrodarsono tidak dapat hadir, ternyata kerukunan keluarganya masih dapat dibanggakan.Hal ini terdapat pada kutipan berikut, “…. Kemudian saya terharu karena melihat ikatan keluarga besar Sastrodarsono yang ternyata masih kukuh. Kerukunan keluarga kami ternyata masih dapat dibanggakan dan diandalkan.”135 Selain nilai kerukunan antarindividu dalam keluarga, hubungan individu dengan keluarga juga terdapat nilai pengayoman yang biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua, seperti orang tua ke anakanaknya. Hal inilah yang dilakukan Ngaisah dan Sastrodarsono dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga anak dan menantunya. “Begini saja, Pak. Saya coba dulu ngobrol dengan dia, ya? Nanti pelan-pelan kita luruskan hatinya. Kalau Bapak yang bicara sekarang, saya khawatir anakmu malah jadi mau manja.” “Yo, wis. Terserah kamu, Bune. Cuma hati-hati-hati, lho, Bune. Kita usahakan agar ikan bisa kita tangkap tanpa harus membuat airnya keruh. Kecekel iwake, ojo nganti butek banyune, Bune.” “Begitulah kami putuskan. Saya mendapat tugas untuk melumerkan hati Soemini yang keras itu.”136 Dari beberapa kutipan di atas, nilai sosial yang terdapat di dalamnya adalah nilai pengayoman. Masih melalui pembagian kerja, nilai pengayoman ditunjukan oleh Ngaisah dan Sastrodarsono sebagai orang tua untuk menyelesaikan konflik yang sedang dialami anak perempuannya, Soemini. 134 Ibid., h. 230. Ibid., h. 301. 136 Ibid., h. 238. 135 120 Soemini terkenal dengan sifat keras kepalanya. Oleh karena itu, Ngaisah dan berusaha dengan hati-hati bicara dan menasihati untuk meluluhkan hatinya agar masalah dengan suaminya cepat selesai. “Asal kau sabar dan pintar. Kau jangan terus larut dalam kemarahan. Saya perhitungkan suamimu hari-hari ini mungkin akan datang menyusulmu. Setidaknya akan berkirim surat. Kalau surat atau suamimu itu datang, jangan kau menghadapi dia dengan hati yang keras atau angkuh. Kau terima dia dengan baik.” “Lho, ini buat lekernya semua to, Nduk. Nah, kalau sudah sampai di Jakarta, kau kurangi dulu pergi ke luar rumah buat organisasi. Kau urusi suami dan anak-anakmu dengan baik, meskipun tidak diurusi pun mereka juga tidak apa-apa sesungguhnya. Tapi tunjukkan kalau kau bisa memegang mereka semua. Nah, nanti pelan-pelan kau bisa desak suamimu supaya mundur dari sangres itu. Mungkin tanpa kau desak pun dia akan mundur sendiri. Wis to, percayalah sama ibumu.”137 Setelah berbicara dengan hati-hati terhadap anak perempuannya itu, ia mulai memberi nasihat. Nilai pengayoman ditunjukkan oleh Ngaisah melalui nasihat-nasihatnya. Sebagai orang tua terhadap anak dalam sebuah keluarga. Setelah masalah Soemini selasai, giliran Noegroho dan keluarga yang mengalami musibah. Anak perempuannya, Marie hamil diluar nikah. Sebagai ibu, Sus sangat frustasi hingga ia pergi ke Wanagalih, mencurahkan isi hatinya kepada Sastrodarsono dan Ngaisah. Awalnya mereka pun kaget dan menyesalkan apa yang menimpa cucunya. Akan tetapi, pada akhirnya mereka menerima dan memberikan nasihat kepada Sus agar pulang saja ke Jakarta dengan Lantip karena Noegroho masih bertugas di luar. Lantip diberi amanat untuk menyelesaikan masalah Marie dengan Maridjan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Hari berikutnya kami melanjutkan perbincangan kami dengan Sus. Kami menganjurkan agar Sus pulang kembali ke Jakarta dengan diantar Lantip. Maksudnya di samping Lantip dapat ikut menjaga Sus sementara suaminya belum datang, juga untuk segera menghubungi 137 Ibid., h. 241. 121 Maridjan dan mengatur segala sesuatunya. Sus menurut dan kami segera memanggil Lantip dari Yogya.”138 Sastrodarsono mengangkat Lantip, anak Ngadiyem, sebagai bagian dari keluarganya dan memberikan pendidikan yang layak untuk merekatkan kembali relasi tersebut. Di lain pihak, Lantip merasa berterima kasih atas kebaikan Sastrodarsono yang telah mengangkatnya sebagai bagian dari keluarga priyayi. Lantip bersumpah pada dirinya sendiri untuk mengabdi pada keluarga Sastrodarsono. Pengabdiannya pada keluarga Sastrodarsono dibuktikan dengan sikap „kepahlawanan‟ dalam membantu menyelesaikan konflik dalam keluarga. Nilai sosial yang ditunjukkan oleh Noegroho adalah nilai religiositas. Bagaimana ia tidak berkeberatan melakukan saikere waktu pendudukan Jepang. Baginya itu soal keyakinan dalam hati. Karena ia sekeluarga tetap sholat dan Tuhan yang ia yakini dalam hati adalah Allah, bukan matahari. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Dan soal keberatan harus membungkuk kepada dewa matahari, bukankah kalau itu tidak kita masukkan dalam hati kita tidak berarti apa-apa? Dan kami serumah tetap sholat seperti biasa. Buat kami Tuhan itu tetap Allah dan Muhammad tetap Rasulullah. Jadi, membungkuk ya membungkuk, salat ya salat.”139 Setelah satu per satu masalah anak mantunya selesai, kesehatan Ngaisah mengalami kemunduran. Akan tetapi, ia bersyukur masih diberi kesempatan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Hal ini terdapat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Saya sadar bahwa umur tujuh puluh tahun adalah umur yang cukup panjang yang dianugerahkan Gusti Allah kepada saya. Saya hanya bisa bersyukur dibolehkan mengenyam hingga sejauh ini. Juga lebih-lebih ikut bersyukur melihat kesehatan dan kegesitan tubuh bapake tole.” 138 Ibid., h. 253. Ibid., h. 195. 139 122 “Saya harus lebih rendah hati. Peringatan dokter untuk orang yang setua saya, saya artikan bahwa hari sungguhlah amat senja. Saya ikhlas. Saya malah merasa bersyukur masih mendapat kesempatan untuk ikut memecahkan persoalan berat anak-anak saya.”140 Nilai sosial yang terdapat dalam kutipan di atas adalah nilai keikhlasan. Sebagai orang tua sekaligus nenek, Ngaisah sangat ikhlas dengan kemunduran kesehatan yang ia alami karena masalah-masalah dalam keluarganya. Ia malah bersyukur masih diberi kesempatan membantu keluarganya di usianya yang sudah tua. Hal ini menunjukkan bahwa Ngaisah adalah perempuan yang ikhlas dan pandai bersyukur. Nilai keikhlasan pun ditunjukkan oleh tokoh Lantip. Ia begitu rendah hati dengan tidak memikirkan perlakuan kedua sepupunya (Marie dan Tommi). Ia menerima kenyataan sejak keluarga Hardojo mengambilnya sebagai anak. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “…. Bagi mereka mungkin masih saja sulit untuk menerima saya sebagai sepupu mereka. Saya tidak terlalu memikirkan itu dalam-dalam. Saya terima itu sebagai suatu kenyataan yang sejak semula saya diambil oleh Bapak Hardojo.”141 Sekali lagi Lantip menunjukkan nilai keikhlasannya dalam membantu dan menjalankan amanah Embah yang sangat ia kasihi. Itulah nilai sosial berwujud nilai keikhlasan dalam hubungan individu dengan keluarga. Hal ini terdapat pada kutipan berikut, “Saya mengangguk. Tetapi, di dalam hati kecewa juga melihat sikap Pakde itu. Kok hanya sampai begitu jauh rasa sembodo yang dimilikinya. Tetapi, saya ikhlas melaksanakan tugas ke Wonosari itu. Demi amanah Embah Putri dan Embah Kakung.”142 “Saya bertekad untuk kembali lagi ke Wanagalih begitu tugas saya untuk membantu membereskan urusan Marie dan Maridjan selesai. Saya ingin dekat-dekat beliau dan ikut menjaga beliau. Sokur-sokur 140 Ibid., h. 255. Ibid., h. 257. 142 Ibid., h. 272. 141 123 kalau kehadiran saya itu dapat mengembalikan kegembiraan dan kegairahan beliau.”143 Nilai sosial yang terdapat pada kutipan di atas adalah nilai kasih sayang. Lantip yang sangat sayang kepada Embah Putrinya, Ngaisah, merasa ada yang berbeda dengan Embah Putrinya setelah menyelesaikan masalah yang menimpa anak mantunya. Ngaisah terlihat mengalami kemunduran dalamkesehatannya. Ia tidak terlihat gembira seperti biasanya. Maka dari itu, Lantip yang diutus Embah Putri dan Embah Kakung untuk membantu keluarga Paklik Noegroho berniat akan menjaga Ngaisah setelah urusannya selesai. Hal itu adalah wujud kasih sayang seorang cucu kepada neneknya sebagai bagian dari keluarga. Selain Lantip, Harimurti juga merupakan cucu yang sangat sayang kepada kedua Embahnya. Hal ini terlihat pada kutipan di atas. Terdapat nilai sosial yang ditunjukkan oleh Hari sebagai seorang cucu, yaitu nilai kasih sayang. Ketika Ngaisah meninggal dunia, ia dengan kesediaannya mau tetap tinggal di Wanagalih menemani Sastrodarsono yang begitu terpukul atas kematian istri yang sangat dicintainya itu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah sebagai berikut. “Kesediaan Gus Hari untuk ikut tinggal bersama ibu dan buliknya mengharukan pakde dan paklik-nya dan sudah tentu juga bulik, bude, dan ibunya. Saya sendiri sesungguhnya tidak terkejut. Dan mestinya juga Bapak dan Ibu. Kami tahu betul sifat Gus Hari, momongan saya itu. Orangnya penuh belas dan gampang merasa trenyuh kepada penderitaan orang lain, apalagi ini adalah Embah Putrinya yang disayanginya.”144 3. Relasi Individu dengan Lembaga Hubungan ini menjadi sangat penting bagi keutuhan tatanan perilaku manusia dalam kebersamaan hidup. Interaksi sosial antara individu dengan 143 Ibid., h. 257. Ibid., h. 269. 144 124 lembaga sosial terjadi melalui proses sosialisasi. Lembaga dapat mengintegrasikan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi patokan hidup dalam bermasyarakat. “Saya sungguh tidak mengerti lagi cara berpikir priyayi muda zaman sekarang. Mereka begitu pasti dan berani dengan pikiran-pikiran mereka. Apakah lagi-lagi ini pengaruh sekolah Belanda? Untunglah anak-anak saya itu, meskipun mulai seenaknya mengemukakan pikiran mereka kepada orang tua, masih terpelihara tata kramanya. Mereka tidak kurang ajar kepada kami, masih sopan, dan bahasa Jawanya masih lengkap, itu membesarkan hati saya….”145 Nilai sosial yang ditunjukkan pada kutipan di atas adalah nilai kesopanan. Bagaimana seorang priyayi muda seperti Noegroho, Hardojo, dan Soemini yang berpendidikan tinggi, mengeyam pendidikan di sekolah Belanda masih tetap menjaga nilai-nilai kesopanan terhadap orang tua. Bahkan mereka masih menjaga bahasa yang menjadi ciri khas dalam hidup masyarakatnya, yaitu bahasa Jawa. Jawa adalah sebuah pulau yang berada di wilayah Indonesia. Secara umum pulau jawa dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tetapi dalam masyarakat berkembang perspektif bahwa yang dinamakan “Jawa” adalah wilayah Jawa Tengah (Yogyakarta) dan Jawa Timur, sedangkan Jawa Barat lebih idendik dengan sebutan sunda. Perspektif demikan tidak serta merta muncul begitu saja dalam masyarakat tanpa ada hal-hal yang melatarbelakangi. Bahasa tentu menjadi salah satu faktor utama karena sebagai sarana komunikasi, tetapi lebih jauh lagi bahasa juga merupakan faktor utama pendukung kebudayaan. Setiap daerah pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan merupakan cirri khas dari daerah tersebut. Salah satunya adalah kebudayaan Jawa. Budaya Jawa dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi tata krama dan unggah-ungguh. Jawa kaya akan simbol-simbol yang filosofis 145 Ibid., h. 88-89. 125 sebagai ajaran hidup bermasyarakat. Tata bersosial di masyarakat diatur secara rinci melalui tindak laku manusianya. Begitu pula dalam konsep priyayi, unggah-ungguh sangat kental bahkan tidak boleh tidak ada kehidupan priyayi. Priyayi lahir dan batin menjadi ukuran kualitas seseorang disebut sebagai priyayi. Perubahan kemudian mencangkup masyarakat yang lebih luas. Pembangunan sekolah desa di Wanalawas yang ditujukan untuk mengajari pengetahuan dasar membaca dan menulis bagi warga desa tersebut. Tokoh Mangkunegaran VII diangkat ke dalam novel karena kekaguman penulis akan sikapnya yang modern untuk memajukan masyarakat, “Beliau masih prihatin dengan pendidikan orang dewasa di pedesaan …”146. Dia menghapus keterbelakangan dengan membangun sekolah bagi orang-orang yang buta huruf. Pemikiran untuk membangun kaum wong cilik dalam diri Sastrodarsono didasari oleh tokoh Mas Martoatmodjo yang beranggapan bahwa priyayi seharusnya memajukan masyarakat, “bukan priyayi yang di kemudian hari kepingin jadi raja kecil yang sewenang-wenang terhadap wong cilik.”147 Nilai sosial pada kutipan di atas menunjukkan sifat Sastrodarsono yang sangat peduli terhadap warga desa Wanawalas. Meskipun pada awalnya hal ini merupakan pemikiran Martoadmodjo. 4. Relasi Individu dengan Komunitas Hubungan ini dilatarbelakangi oleh visi dan misi hidup yang sama antarindividu. Komunitas mencakup individu dengan individu, keluarga dengan keluarga, dan juga lembaga yang saling berhubungan secara interdependen. “…. Gus Hari langsung terpikat oleh Sunaryo. Orang yang juga secerdas Gus Hari dan memiliki perhatian yang sama tentang 146 147 Ibid., h. 158. Ibid., h. 63. 126 kesenian, terutama seni tari, teater, dan gamelan. Dalam waktu dekat mereka sudah menjadi sahabat. Mereka semakin sering kelihatan aktif dalam acara-acara kesenian universitas. Waktu itu kami sudah berada pada tahap-tahap terakhir kuliah kami dan dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi sarjana ilmu sosial dan politik.”148 Nilai sosial yang terdapat pada kutipan di atas adalah nilai kebersamaan. Harimurti yang cerdas dan suka dengan seni bertemu dengan Sunaryo, seorang kakak kelas di Universitasnya yang juga sama cerdas dan suka kesenian. Mereka memiliki pandangan yang sama mengenai seni. Mereka bersahabat dan sering menghabiskan waktu bersama dalam berseni. 5. Relasi Individu dengan Masyarakat Hubungan ini sangat bersifat sosial. Karena individu melakukan interaksi sosial melalui proses sosialisasi dengan suatu lingkungan sosial yang bersifat makro. Aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif mempunyai bobot yang besar. Dalam keluarga dan masyarakat, misalnya, orang Jawa harus menjaga kehormatan dan kerukunan dengan berbahasa yang pantas untuk menghindari perselisihan. Rasa rikuh dipertahankan dalam hubungan sosial masyarakat Jawa untuk menjaga sikap dan kelakuan. Selain itu dalam hal etika dan budaya perkawinan, baik sebelum dan sesudah pernikahan mengalami berbagai perubahan, namun inti dari perkawinan yaitu kesetiaan dan penjagaan diri tidak berubah. “…. Karena mendapat kesempatan mengerjakan sawah Ndoro Seten itu pula, maka hubungan NdoroSeten dengan bapak saya jadi akrab. Tentu saja akrabnya hubungan seorang Ndoro Seten yang priyayi dengan Atmokasan yang petani desa. Dan karena hubungan itu pula saya mendapat nama yang Soedarsono ini. Bila tidak karena hubungan itu bagaimana kita orang desa bisa membayangkan mendapat nama Soedarsono, nama yang menurut bayangan kami hanya pantas dimiliki anak-anak priyayi saja. Dan Ndoro Seten, menurut Bapak, begitu saja menghadiahi nama kepada embok saya waktu diketahuinya Embok hamil tua. “Nanti kalau anakmu itu laki-laki, Mbok, namakan Soedarsono,” kata Ndoro Seten. Embok saya terkejut mendengar nama 148 Ibid., h. 282. 127 itu. Menurut Embok sesungguhnya ia ingin memberi nama Islam (meskipun kami tidak sembahyang) seperti Ngali atau Ngusman.149 Berdasarkan kutipan di atas, nilai sosial ditunjukkan melalui nilai keakraban yang terjalin antara Atmokasan dengan Ndoro Seten yang dapat dikatakan sebagai majikan. Atmokasan adalah seorang petani desa yang menggarap sawah milik Ndoro Seten. Atmokasan sebagai seorang petani berstatus wong cilik bekerja di sawah milik Ndoro Seten menjalin hubungan yang bersifat vertikal, antara priyayi dan petani desa. Namun, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan akrab, Ndoro Seten menyerahkan separuh sawahnya untuk diurus oleh Atmokasan. Dalam masyarakat Jawa terdapat tradisi mendapat nama tua ketika seseorang akan membangun rumah tangga. Inilah yang terjadi kepada Soedarsono yang kemudian berubah nama menjadi Sastrodarsono. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Saya duduk termangu, tidak mengira kalau saya akan mendapat nama tua pada hari itu. Tentu saya berharap juga pada suatu ketika mendapat nama tua itu karena memang sudah menjadi kebiasaan orang Jawa untuk mengubah nama anaknya menjadi nama tua pada waktu anak itu sudah mulai siap untuk membangun keluarga…”150 Nilai sosial yang terdapat dalam kutipan di atas adalah nilai kebiasaan atau tradisi yang dijalankan oleh setiap anak dalam masyarakat Jawa, yaitu mengubah nama sebelumnya menjadi nama tua bagi mereka yang akan memasuki kehidupan baru, yaitu berkeluarga. Hal ini jelas menunjukkan relasi antara individu dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Sastrodarsono meninggal, Noegroho sebagai anak tertua menggantikan ayahnya memimpin keluarga Sastrodarsono. Namun pada rembukan malam itu ia menginginkan seorang cucu dari keluarga 149 Ibid., h. 34. Ibid., h. 40. 150 128 Sastrodarsonolah yang sebaiknya memimpin yang menunjukkan bahwa keluarga ini terus mampu menumbuhkan diri. Dalam hal ini Harimurti sebagai cucu menjadi satu-satunya pilihan, namun ia menolak karena merasa tidak pantas, dirinya terlalu banyak menimbulkan masalah dalam keluarga besar Sastrodarsono, namun ia mengajukan sebuah nama. Dia adalah orang yang ikhlas, tulus, dan tanpa pamrih. Dialah Lantip. 6. Relasi Individu dengan Nasion Hubungan ini berkaitan erat dengan posisi dan peranan-peranan yang ada dalam diri setiap individu sebagai warga Negara. Harimurti menceritakan bagaimana ayahnya, Hardojo, setia mengabdi kepada Negara meskipun pernah dikecewakan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kutipan di bawah sebagai berikut. “Noegroho terpilih menjadi tentara dan mengikuti latihan di Bogor. Setelah terpilih, ia memutuskan untuk membela negerinya. Sebagai warga Negara dalam peranannya membela Negara. Nilai sosial yang ditunjukkan oleh Noegroho adalah nilai pengabdian. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut, “Jadi, saya akan berperang untuk negeriku sendiri, putusku. Begitulah saya memasuki latihan di Bogor ….”151 “Pada waktu sebagian besar pegawai republik ikut pindah ke Jakarta sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950. Bapak memilih pindah ke Yogya dan bekerja pada pemerintahan DIY. Rupanya Bapak yang pernah dikecewakan oleh Mangkunegaraan yang tidak tegas memilih republik dan kemudian malah membantu Belanda, tetap senang bekerja dalam lingkungan kerajaan. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipandangnya sesuai benar baginya. Dia merasa sekaligus dipuaskan keinginannya untuk mengabdi kepada republik dan suatu lingkungan budaya tradisi Jawa yang dipimpin oleh seorang sultan yang berjiwa modern dan republiken.”152 Kutipan di atas menjelaskan bahwa nilai sosial yang ditunjukkan oleh tokoh Hardojo adalah nilai pengabdian. Sebagai warga Negara yang baik dan 151 Ibid., h. 197. Ibid., h. 281. 152 129 berbakti pada Negara. Hal ini juga disampaikan oleh Harjono yang dapat dilihat pada kutipan berikut, “Saya setuju dengan Mas Noeg. Kita yang ada di sini adalah semua alat Negara. Cuma ada yang tentara, ada yang sipil. Tapi semuanya alat Negara. Jadi, kalau Negara berperang kita juga harus ikut perang. Ini semua adalah kewajiban.”153 Hal di atas menunjukkan nilai pengabdian sebagai warga Negara, baik secara langsung yang dilakukan oleh Noegroho sebagai tentara, maupun Harjono sebagai rakyat sipil. Menurutnya, kita semua wajib membela Negara. C. Implikasi pada Pembelajaran Sastra di Sekolah Pembelajaran sastra adalah pembelajaran yang mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan proses kreatif sastra. Dengan pembelajaran semacam ini, peserta didik diajak untuk langsung membaca, memahami, menganalisis, dan menikmati karya sastra secara langsung.154 Tujuan pembelajaran sastra terlihat bahwa peserta didik harus mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan. Tujuan ini juga berhubungan dengan pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik yang sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, sebagai upaya pembentukan karakter peserta didik diperlukan adanya campur tangan dari berbagai pihak, khususnya pendidik. Pendidik diharapkan mampu membimbing, memberikan teladan, dan mendukung peserta didik agar memiliki kepribadian yang luhur. Pembentukan kepribadian ini dapat dilakukan dengan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Pembelajaran tersebut cakupannya sangat luas, pendidik dapat memberikan pembelajaran melalui contoh, kisah nyata, aturanaturan,dan sikap. Selain yang telah disebutkan, pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik juga dapat dilakukan melalui pengenalan sastra, baik dongeng, 153 Ibid., h. 205. Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra ( Jakarta: Grasindo, 2008), h. 167. 154 130 cerpen maupun novel. Hal ini dikarenakan dalam karya sastra tertanam nilai-nilai yang sangat baik dan dapat dijadikan teladan oleh peserta didik. Akan tetapi, pendidik harus mampu menimbang, memilih, dan menetapkan karya sastra yang baik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Karena pemilihan karya sangat berpengaruh terhadap kualitas bacaan peserta didik. Dengan demikian, pendidik harus pandai memilih bacaan yang tepat dan mengandung nilai-nilai yang baik untuk dijadikan sumber belajar bagi peserta didik. Jika dikaitkan dengan novel Para Priyayi, peserta didik dapat mengambil nilai-nilai sosial yang sangat kentara dalam cerita melalui peristiwa dan pandangan para tokoh. Guru dapat mengajarkan kepada peserta didik bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dengan menjunjung sikap saling tolong-menolong antarsesama manusia. Dengan begitu, kepekaan yang dimiliki oleh peserta didik terhadap lingkungan sekitar dapat menimbulkan sikap saling toleransi dan terhadap perbedaan yang terjadi. Selain itu, peserta didik dapat mengimplikasikan nilai-nilai sosial yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan kajian terhadap novel Para Priyayi karya Umar Kayam, kompetensi dasar yang dapat diimplikasikan dalam pembelajaran sastra adalah menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Kompetensi tersebut dapat dikembangkan melalui novel Para Priyayi sebagai bahan ajar novel Indonesia. Pembelajaran unsur intrinsik dalam novel Para Priyayi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra untuk mempertajam perasaan, meningkatkan penalaran, daya imajinasi, serta kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengajaran sastra mencakup tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif terkait respons yang diberikan peserta didik dalam bentuk penafsiran setelah membaca sebuah karya sastra. Selanjutnya guru dapat menilai pemahaman siswa dengan cara mengetahui pengetahuan yang diperoleh setelah membaca. Karena terkait dengan pemahaman dari hasil membaca, ranah ini menjadi ranah yang paling awal dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Ranah 131 afektif terkait respons yang diberikan peserta didik terhadap karya sastra yang telah dibacanya, apakah peserta didik tersebut antusias dan merasa terlibat di dalamnya atau tidak sama sekali, sehingga guru dapat mengetahui perubahan yang dialami peserta didik setelah membaca karya sastra, sedangkan ranah psikomotorik terkait respons yang diberikan peserta didik terhadap penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru dituntut agar dapat memposisikan dirinya sebagai guru bahasa Indonesia dalam pengajaran sastra. Guru harus memiliki kompetensi sastra yang memadai. Guru dapat menggunakan kiat khusus dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Dari kiat tersebut, guru dapat membangkitkan minat belajar para peserta didik agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga peserta didik dapat menikmati pelajaran sastra dan nilai-nilai yang terkandung dalam novel, khususnya nilai sosial dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat menumbuhkan perilaku-perilaku yang positif bagi setiap individu. Selain itu, sekolah juga dituntut agar menambah koleksi perpustakaan dengan bukusastra yang variatif, sehingga dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran peserta didik. Pada hakikatnya, pembelajaran sastra melalui pembacaan novel ini diharapkan dapat membantu siswa dalam membentuk kepribadian menjadi manusia yang berkatakter. Oleh karena itu, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menerapkan sikap-sikap positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya turut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan watak dari peserta didik tersebut. Pembelajaran nilai-nilai sosial yang telah didapatkan oleh peserta didik tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bekal dan pegangan dalam perjalanan hidup peserta didik, sehingga peserta didik lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan yang kompleks dan multidimensi seperti sekarang ini. Dengan kata lain, pembelajaran karya sastra, dalam hal ini novel pun turut membantu dalam pembentukan karakter bangsa. 132 Dari pernyataan di atas dapat ditunjukkan bahwa sastra mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia nyata, maka pengajaran sastra harus dipandang sebagai sesuatu yang penting yang patut menduduki tempat yang selayaknya. Jika pengajaran sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat memberikan sumbangan yang besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata di lingkungan masyarakat. Dalam pembelajaran sastra di sekolah, novel Para Priyayi dapat diterapkan di tingkat SMA kelas XI (sebelas) semester satu pada pertemuan yang membahas tentang memahami pembacaan novel melalui kegiatan mendengarkan pembacaan penggalan novel, seperti yang terlampir pada silabus berikut. SILABUS PEMBELAJARAN Sekolah : SMA/MA Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas : XI Semester : 1 Standar Kompetensi : Membaca Memahami berbagai novel Indonesia Kompetensi Materi Kegiatan Indikator Dasar Pembelajaran Pembelajaran Pencapaian Penilaian Alokasi Sumber/ Waktu Kompetensi Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan Novel Indonesia Membaca unsur-unsur intrinsik (alur, Menganalisis Alat Jenis 45 Novel Tagihan: Menit Indonesia novel unsur-unsur Indonesia ekstrinsik dan Tugas Menganalisis ekstrinsik tema, novel penokohan, unsur-unsur (alur, Indonesia sudut pandang, ekstrinsik penokohan, intrinsik Bahan/ individu tema, Tugas kelompok 133 latar, dan Ulangan dan sudut intrinsik pandang, (alur, tema, latar, dalam penokohan, amanat) Instrumen: novelIndonesia sudut novel Uraianbeb (nilai budaya, pandang, Indonesia sosial, moral, amanat) unsur ektrinsik latar, dan amanat) dll) novel Indonesia dan Bentuk as Pilihangan da Jawaban singkat Berikut ini merupakan rencana pembelajaran yang dapat diaplikasikan berdasarkan pembahasan dan silabus di atas. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : SMA Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas/Semester : XI/1 (Satu) Standar Kompetensi : Memahami berbagai hikayat dan novel Indonesia Kompetensi Dasar : Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia Alokasi Waktu : 3 X 45 menit Indikator : 1. Mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia 1. Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) dan unsur ekstrinsik (nilai sosial, budaya, dll) novel Indonesia A. Tujuan Pembelajaran 134 Siswa mampu menjelaskanunsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari pembacaan penggalan novel. B. Materi Pokok o Novel Indonesia o Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel C. Nilai Budaya dan Karakter Bangsa Bersahabat/komunikatif Kreatif Gemar Membaca D. Nilai Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif Kedisiplinan Kepemimpinan E. Metode dan Skenario Pembelajaran Presentasi Diskusi Kelompok Tanya Jawab Penugasan F. Kegiatan Belajar Mengajar 1. Kegiatan Awal a) Guru mengucap salam, kemudian mengajak berdoa bersama b) Guru mengabsen untuk mengecek peserta didik yang tidak hadir dan berkoordinasi dengan siswa agar siap untuk belajar c) Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar d) Guru memberikan apersepsi dengan cara memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang akan dibahas 135 2. Kegiatan Inti a. Eksplorasi Guru meminta peserta didik mencari novel di perpustakaan Guru meminta peserta didik dengan demokratis menentukan bersama salah satu novel yang ingin dicari unsur intrinsik dan ekstrinsik Guru meminta kepada peserta didik untuk membaca dan memahami novel yang dipilih. b. Elaborasi Guru meminta kepada peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi yang terdiri atas 3-4 orang peserta didik. Guru menjelaskn unsur-unsur intrinsik dan ektrinsik yang terdapat dalam novel. Peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. Peserta didik berdiskusi untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) dan ekstrinsik (nilai sosial, budaya, dll) novel Indonsia. Peserta didik berdiskusi untuk membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia. Salah satu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Peserta didik yang lain menanggapi presentasi hasil diskusikelompok yang presentasi. c. Konfirmasi Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan tentang hal-hal yang belum diketahui. 136 Guru menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 2. Kegiatan Akhir Guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memberikan tugas di rumah kepada peserta didik agar mencari novel lain untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Guru menutup kegiatan dan mengucap salam. G. Sumber Belajar NovelPara Priyayi karya Umar Kayam Biografi Umar Kayam Cara menganalisis unsur-unsur intrinssik dan ekstrinsik novel Indonesia Buku Bahasa Indonesia (Pelajaran Bahasa Indonesia: Untuk SMA/MA Kelas XI), Tateng Gunadi, Arya Duta, 2007. H. Penilaian 1. Teknik Tes (PG, isian, dan uraian) Penugasan menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 2. Instrumen soal a. Apa pengertian dari unsur intrinsik dan ekstrinsik? b. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur intrinsik novel Para Priyayi? c. Sebutkan dan jelaskan unsur ekstrinsik dalam novel Para Priyayi 137 Rubrik Penilaian Analisis Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Novel Indonesia Kompetensi Dasar :Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia Nama Siswa : Kelas/No. Absen : Tanggal Penilaian : SKOR 1 2 3 UNSUR YANG DINILAI 1. 2. 3. 4. Analisis Unsur Intrinsik Analisis Unsur Ekstrinsik 1. 2. 3. 4. 5. 4 Ketajaman analisis Kelengkapan unsur yang dianalisis Keruntutan penyajian hasil analisis Manfaat yang bisa diambil dari unsur intrinsik dalam novel Ketajaman analisis Kelengkapan unsur yang dianalisis Keruntutan penyajian hasil analisis Manfaat yang bisa diambil dari unsur ekstrinsik dalam novel Kesimpulan hasil analisis Perolehan Nilai = Total skor x 2 Jakarta,………….. 2014 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (Dwi Astuti) (Agnis Afriani) 5 BAB V PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan novel Para Priyayi Karya Umar Kayam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Hasil penelitian ini mendeskripsikan nilai-nilai sosial melalui interaksi sosial antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam relasi-relasi yang terbagi menjadi enam kategori. Relasi-relasi terdapat dalam teori interaksi Simmel. Dalam novel Para Priyayi ini terdapat nilai-nilai sosial, yaitu nilai kepedulian yang ditunjukkan oleh tokoh Sastrodarsono, nilai kerukunan oleh keluarga besar Sastrodarsono, nilai pengayoman orang tua (Sastrodarsono dan Ngaisah), nilai ketuhanan, nilai keikhlasan, nilai kasih sayang, nilai kesopanan, nilai kebersamaan, nilai keakraban, nilai kebiasaan, dan nilai pengabdian oleh Noegroho dalam membela Negaranya. 2. Implikasi novel Para Priyayi karya Umar Kayam pada pembelajaran sastra di sekolah adalah peserta didik dapat mengambil nilai-nilai sosial yang sangat jelas digambarkan dalam cerita, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, melalui pemahaman tentang tokoh dan penokohan serta latar sosial. Peserta didik juga dapat belajar mengenai bagaimana harus bersikap, memilih jalan hidup, dan semangat mencapai cita-cita seperti yang telah digambarkan oleh tokoh Lantip, Sastrodarsono, dan yang lainnya. B. Saran Berdasarkan hasil dan implikasi penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini. 138 139 1. Orang tua atau guru harus memberitahu kepada anak mengenai tata cara hidup bermasyarakat. Anak diajarkan bagaimana seharusnya dalam bersikap agar tidak melanggar norma dan nilai yang berlaku ketika hidup bersama dalam masyarakat. Guru dan orang tua harus memberi contoh yang baik agar anak mempunyai panutan dalam berperilaku. 2. Guru harus meningkatkan kreativitasnya dalam kegiatan proses belajar mengajar agar peserta didik dapat antusias dan memahami pelajaran sastra. 3. Guru sebaiknya mengajarkan kepada peserta didik agar mengaplikasikan nilai-nilai sosial yang baik yang terkandung di dalam karya sastra dalam kehidupan sehari-hari. 4. Orang tua harus memberi dukungan kepada anak untuk mengembangkan minatnya terhadap sastra, dengan cara memfasilitasi anak dengan menyediakan buku-buku terkait dengan sastra di rumah (minat baca) dan menyemangati anak agar mau belajar membaca bahkan menulis sejak dini. DAFTAR PUSTAKA Abram, M. H. A Glossary of Literary Terms. Boston: Heinle & Heinle, 1999. Hendriyati, Atik. Kajian Intertekstual dan Nilai Pendidikan Novel Canting Karya Arswendo Atmowiloto dengan Para Priyayi Karya Umar Kayam. Purwakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009. Aritonang, Diro. Doktor Umar Kayam Budayawan yang Tangguh. Harian Pikiran Rakyat, 1982. Aziez, Furqonul dan Abdul Hasim. Menganalisis Fiksi Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Bertens, K. ETIKA. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1993. DBB, Umar Kayam Memenangkan SEA Write Award 1987. Harian Berita Buana, 1987. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Damono, Sapardi Djoko. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979. Endaswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra, Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: CAPS, 2013. Escarpit, Robert. Sosiologi Sastra Penerjemah Ida Sundari Husen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994. Tarigan, Henry Guntur. Prinsip-prinsip Dasar sastra. Bandung: Angkasa, 2001. Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terjemahan Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983. Santosa, Wijaya Heru dan Sri Wahyuningtyas. Pengantar Apresiasi prosa. Surakarta: Yuma Pustaka, 2010. Saidi, Acep Iwan. Matinya Dunia Sastra Biografi Pemikiran & Tatapan Terberai Karya Sastra Indonesia. Jakarta: Pilar Media, 2006. Kayam, Umar. Para Priyayi Sebuah Novel. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2011. Cet. XIII. Kosasih, E. Dasar-dasar Keterampilan Bersastra. Bandung: Yrama Widya, 2012. Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Noor, Rohinah M. Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi Pendidikan Moral yang Efektif. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011. Soelaeman, M. Munandar. Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2001. Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajan Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000. Lesmana, Permadi Hendra. Perubahan Ideologi Kepriyayian Jawa: dari Tradisi ke Modern dalam Novel Para Priyayi dan Jalan Menikung Karya Umar Kayam serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMA. Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2013. Rahmanto, B. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta: Kanisius, 1988. __________ . Umar Kayam: Karya dan Dunianya. Jakarta: PT Grasindo, 2004. Semi, Atar. Anatomi Sastra. Padang: Angkasa Raya, 1988 Siswanto, Wahyudi. Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Grasindo, 2008. Soekanto, Soerjono. Pribadi dan Masyarakat (Suatu Tinjauan Sosiologis). Bandung: Alumni, 1983. Sumarno, Jakob. Memahami Kesusastraan. Bandung: Alumni, 1984. Stanton, Robert. Teori Fiksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Suwarno, P. J. Novel Multidimensional, Majalah Basis, No.10/XL1/Oktober 1992. Tuloli, Nani. Kajian Sastra. Gorontalo: BMT “Nurul jannah”, 2000. Wellek, Rene & Austin Warren, Teori Kesusastraan Terjemahan dari Theory of Literature oleh Melani Budianta. Jakarta: Gramedia, 1989. BIOGRAFI PENULIS Agnis Afriani, lahir di Bekasi, 6 Agustus 1990. Menuntaskan pendidikan dasar di MI Attaqwa 16 Wates. Kemudian Ia menuntut ilmu di MTs Al- Falak Kota Bogor. Setelah itu, Ia melanjutkan kejenjang sekolah menengah di MAN 1 Kota Bekasi. Setelah lulus dari MAN 1 Kota Bekasi, Ia meneruskan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Anak dari Achmad Yani dan Yuyun ini bercita-cita ingin menjadi seorang guru sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Baginya, menjadi seorang guru bukan hanya profesi yang ideal bagi perempuan. Akan tetapi, merupakan kegiatan sosial dan pembelajaran sepanjang masa bagi seorang manusia untuk sesama manusia lainnya. Perempuan yang berzodiak Leo ini juga memiliki hobi membaca karya sastra. Ia sangat menyukai puisi dan novel.