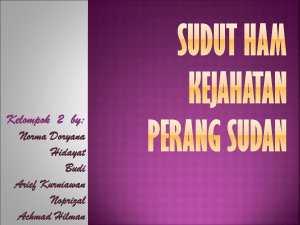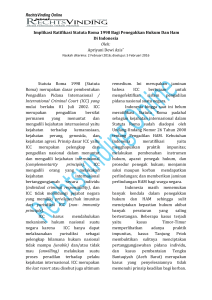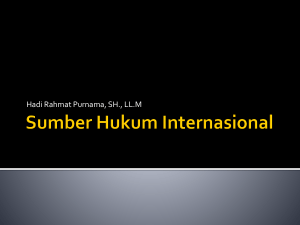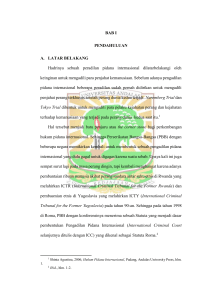Jalan Panjang Menuju Ratifikasi Statuta Roma
advertisement

Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Kata Sambutan Sampai awal Desember 2009, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute on the International Criminal Court – ICC) telah diratifikasi oleh 110 negara. Artinya, sudah lebih dari separuh jumlah negara anggota PBB menjadi negara pihak (state party) dari ICC. Sayangnya, sampai hari ini, Indonesia belum menjadi bagian dari rejim keadilan internasional tersebut. Namun demikian, bisa dipastikan bahwa Indonesia akan segera menjadi negara pihak, karena tidak ada syarat-syarat yang tidak tersedia. Tinggal masalah waktu saja. Setidaknya, begitulah optimisme Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional (Koalisi), yang telah dan sedang melakukan kampanye dan advokasi ratifikasi ICC selama 2 tahun terakhir. iii Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Setelah reformasi, Indonesia sebenarnya telah sudah menunjukkan sikap dan komitmennya untuk masuk dalam rejim keadilan internasional dan memutus rantai impunitas. Partisipasi aktif delegasi Indonesia dalam Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia yang akhirnya mengesahkan Statuta Roma tentang ICC pada tangal 17 Juli 1998 dan Pidato Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa (sekarang Menlu RI) pada sidang Dewan Keamanan PBB bulan Desember 2007 di New York yang menyatakan bahwa impunitas tidak bisa ditolerir, adalah sikap tegas yang selayaknya ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, dalam hal ini dengan meratifikasi ICC. Namun, tetap saja, usaha untuk mewujudkan ratifikasi universal ICC belum menemukan jalan lempang di Indonesia. Walaupun dicanangkan untuk diratifikasi pada tahun 2008, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 – 2009), namun sampai akhir tahun 2009, ICC belum juga diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia. Tidak ada alasan yang sangat jelas mengapa target ratifikasi 2008 tidak tercapai. Namun Koalisi mendapatkan informasi bahwa lembaga pemerintah di sektor pertahanan dan keamanan menyatakan bahwa Indonesia belum siap melakukannya. Beberapa isu seperti kedaulatan nasional dan asas non-retroaktifitas dikatakan masih mengandung kontroversi. Padahal, isu-isu tersebut sebenarnya sangat dijunjung tinggi oleh ICC. Buku ini diterbitkan oleh Koalisi dengan tujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan pemikiran beberapa pakar hukum internasional dan aktifis hak asasi manusia bahwa Indonesia perlu dan siap meratifikasi ICC. Beberapa isu yang dianggap kontroversial oleh beberapa kalangan dikupas dan dipaparkan di sini, dengan harapan agar sikap setuju dan belum setuju meratifikasi ICC tidak didasarkan iv Kata Sambutan pada asumsi-asumsi, tetapi pemahaman yang ilmiah tentang Statuta Roma. Selanjutnya, Koalisi berharap agar pemerintah dan parlemen hasil pemilu 2009 menjadikan rencana ratifikasi ICC ini sebagai prioritas, karena ia mencerminkan ekspresi sikap pemerintah SBY di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam peradaban dunia baru. Jakarta, Desember 2009 Mugiyanto Convenor Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional v Kata Sambutan vii Daftar Isi ix Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia x Daftar Isi xi KATA PENGANTAR Enny Soeprapto PhD Gustav Moynier, yang bersama Henri Dunant membentuk Komite International bagi Pertolongan untuk Orang-orang yang Luka dalam sengketa bersenjata (1863), yang kemudian menjadi Komite International Palang Merah (1876), pada 1872 mengusulkan agar negara-negara yang berperang membentuk pengadilan-pengadilan pidana international, segera setelah pecahnya sengketa bersenjata, yang majelis hakimnya terdiri atas warga negara dari negara-negara yang berperang dan yang netral. 65 tahun kemudian, pada 1937, Liga Bangsa-bangsa berhasil mewujudkan gagasan ini dengan menerima sebuah perjanjian international bagi pembentukan sebuah mahkamah pidana international. Perjanjian international ini tidak sempat berlaku karena kurangnya minat negara-negara untuk mengesahkannya dank arena pecahnya Perang Dunia Kedua (1939). Meskipun demikian, niat komunitas International untuk membentuk sebuah pengadilan pidana international yang bersifat permanen tetap hidup. xiii Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Perhatian komunitas international pada masalah kejahatan international dan, berkaitan dengan ini, berkembangnya hukum pidana international, meningkat setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan ini dapat dilihat, antara lain, dari pembentukan Tribunal Militer International Nuerenberg (45) dan, padanannya untuk Asia Timur, Tribunal Militer International Tokyo (1946), yang keduanya bersifat ad hoc, dan tercantumnya ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948 yang menetapkan bahwa mereka yang dituduh melakukan kejahatan dan perbuatan lain yang berkatian dengan kejahatan ini, akan diadili oleh pengadilan negara tempat terjadinya kejahatan ini atau oleh sebuah “tribunal pidana international” yang mungkin mempunyai yuridikasi terhadap Negara-negara Pihak yang telah menerima yuridikasinya (Pasal VI). Gagasan pembentukan sebuah pengadilan international yang bersifat permanen yang menangani kejahatan international tertentu mulai menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1950. Pada 1950 Majelis Umum (MU) PP meminta Komisi Hukum International (KHI), yang dibentuk oleh MUPBB pada 1947, untuk melakukan empat hal, yakni, pertama, mengodifikasikan prinsip-prinsip Nuerenberg, kedua, menjajaki masalah yurisdikasi pidana international dalam hubungan dengan Konvensi Genosida 1948, ketiga, membahas masalah pendefinisian kejahatan agresi, dan, keempat, menyusun rancangan pengaturan penanganan tindak pidana terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia. Mengenai hal tersebut terakir ini, pada 1951, KHI menyampaikan kepada MUPBB rancangan pengaturan yang bersangkutan beserta usul pembentukan sebuah mahkamah pidana international. Namun, Perang Dingin telah menyebabkan terhalangnya kemajuan KHI dalam melaksanakantugas-tugas yang xiv Daftar Isi diberikan oleh MUPBB tersebut. Baru pada 1989, dengan berakhirnya Perang Dingin, MUPBB meminta KHI, sewaktu membahas Rancangan Pengaturan Tindak Pidana terhadap Perdamaian dan Keamanan umat Manusia, (juga) “membahas masalah pembentukan sebuah mahkamah pidana international atau mekanisme dan pemeriksaan pengadilan kejahatan international yang lain dengan yurisdiksi terhadap orang-orang yang dituduh telahh melakukan kejahatan yang mungkin diliput oleh pengaturan tersebut, termasuk orangorang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika yang melintasi perbatasan nasional”. Pada 1993 KHI menyusun sebuah rancangan statuta Mahkamah Pidana International, yang setelah dibahas oleh MUPBB dan memperoleh masukan dari Negara-negara Anggota PBB, diajukan kepada Konferensi Diplomatik Wakil-wakil Berkuasa Penuh PBB tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang diselenggarakan di Roma pada 16 Juni-17 Juni 1998 yang kemudian diterima pada 17 Juli 1998 dengan suara 120 suara setuju, tujuh menentang, dan 21 abstain. Statuta Mahkamah Pidana International tersebut, yang kemudian terkenal dengan sebutan populernya “Statuta Roma” (karena diterima dalam suatu konferensi international yang diadakan di Roma), mulai berlaku pada 1 Juli 2002, setelah dipenuhinya persyaratan bagi mulai berlakunya instrument tersebut menurut Pasal 126 ayat 1, yakni sesudah disimpankannya piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi yang ke-60 pada Sekretaris Jenderal PBB. Pada saat pemungutan suara pada 17 Juli 1998, Indonesia adalah salah satu dari 120 negara yang memberikan suara setuju bagi penerimaan Statuta Roma dan, kemudian, mencantumkan instrument tersebut dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagai salah satu instrument yang dikategorikan oleh Pemerintah Indonesia, secara implicit, sebagai instrument HAM internasional, yang xv Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia akan disahkan pada 2008. Namun, sampai berakhirnya kala hidup RANHAM 2004-2009 tersebut pada 10 Mei 2009, instrumen tersebut, jangankan disahkan, diproses pengesahannya pun belum. Bahkan, sebaliknya, tampak kecenderungan di sementara di kalangan Pemerintah sekarang untuk justru tidak mengesahkan Statuta Roma. Sudah tentu sikap demikian mencederai citra Pemerintah sendiri, karena mengingkari komitmennya sendiri, sebagai mana dinyatakannya dalam RANHAM 2004-2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) (Keppres 40/2006). Sejak 1999, di kalangan pembuat undangundang dan banyak kalangan lainnya di Indonesia, terjadi kekisruhan konseptual mengenai jenis kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana International (MPI), setidak-tidaknya yang berkenaan dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai “pelanggaran HAM” dengan kualifikasi “berat”, padahal kejahatan-kejahatan tersebut adalah kejahatan internasional (international crimes), bukan “pelanggaran HAM yang berat” . Kekeliruan yang berlanjut ini, pada gilirannya, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum jika tidak secepatnya dikoreksi. Sebagaimana ditetapkan atau dicerminkan dalam instrument konstitutif pengadilan-pengadilan pidana international yang dibentuk secara ad hoc sebelumterbentuknya MPI atau dalam instrument international mengenai penindakan kejahatan international yang bersangkutan, dalam hal ini kejahatan genosida, dapat dicatat pokok-pokok berikut: (a) Kejahatan terhadap kemanusiaan ditetapkan sebagai salah satu dari tiga kejahatan (crimes) yang termasuk yurisdiksi Tribunal Militer International Nuerenberg (Pasal 6 Piagam TMI, 1945); (b) xvi Daftar Isi Genosida dinyatakan sebagai “kejahatan menurut hukum internasional” oleh Konvensi Genosida 1948 (Paragraf preambuler pertama dan Pasal I); (c) Yurisdiksi Tribunal Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia, yang berkewenangan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran hokum humaniter internatsional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 (Pasal 1, Statuta), meliputi genosida (yang dikategorikan sebagai “penerjangan gawat Konvensi-konvensi Jenewa 1949) (Pasal 4 Statuta) dan kejahatan terhadap kemanusiaan apabila terjadi dalam konflik bersenjata (Pasal 5 Statuta); dan (d) Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda, yang berkewenangan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas ‘pelanggaran serius hukum humaniter internasional” (yangterjadi di wilayah Rwanda dan warga negara Rwanda yang bertanggung jawab atas pelanggaran demikian yang terjadi di wilayah negara-negara tetangga, antara 1 January 1994-31 Desember 1994) beryudiksi yang meliputi Genosida (Pasal 2) dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 3). Tidak satupun dari empat instrument internasional yang menyangkut genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dibuat, masing-masing, pada 1945, 1948, 1993, dan 1994 tersebut di atas yang mengaitkan kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan dengan HAM. Selanjutnya, MPI, yang kewenangannya meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Pasal 5 Statuta), mengualifikasikan keempat kejahatan tersebut sebagai “kejahatan paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan” (paragraph preambuler keempat dan kesembilan serta chapeau Pasal xvii Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 5), mengategorikan keempat kejahatan tersebut sebagai “kejahatan internasional” (paragraph preambuler keenam), dan mengklasifikannya sebagai “kejahatan paling serius yang menjadi urusan internasional” (Pasal 1). Statuta MPI, sama halnya dengan instrumen-instrumen internasional yang dibuat sebagaimana disebut dalam paragraph sebelumnya, sama sekali tidak menyebut keempat kejahatan itu sebagai “pelanggaran HAM” ataupun “pelanggaran Ham” yang dikualifikasikan sebagai “serius”, “berat”, atau “gawat”. Statuta Roma adalah instrument hukum pidana internasional (bukan instrument HAM internasional), MPI adalah sebuah pengadilan pidana internasional (bukan pengadilanHAM internasional), sedangkan kejahatan-kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPI (kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi) adalah, pertama, “kejahatan”, kedua, kejahatan itu adalah “kejahatan internasional”, ketiga, kejahatan internasional tersebut merupakan “kejahatan yang paling serius”, dan , keempat, kejahatan yang paling serius itu merupakan “urusan internasional” dan bahkan merupakan ‘urusan komunitas internasional secara keseluruhan”. Meskipun demikian, Statuta Roma memuat tiga hal berikut yang secara eksplisit atau implisit menghormati dan/atau melindungi HAM, yakni, pertama, ketentuan yang menetapkan bahwa penerapan dan penafsiran hukum dalam pelaksanaan Statuta Roma, Unsur-unsur Kejahatan, serta Aturan Acara dan Bukti harus konsisten dengan HAM yang diakui secara internasional serta tanpa pembatasan yang merugikan atas alasan seperti gender, umur, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lain, asal rumpun bangsa, asal etnis, atau asal social, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya (Pasal 21 ayat 3), kedua, penetapan asas-asas hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan penegasan asas-asas HAM HAM xviii Daftar Isi sebagaimana ditetapkan dalam instrument-instrumen HAM internasional, seperti asas legalitas, ketidakberlakusurutan, dan nondiskriminatif (Pasal 22-Pasal 33), dan, ketiga, ketentuan-ketentuan yang secara tidak langsung melindungi HAM tertentu, seperti hak untuk hidup (Pasal 6(a), Pasal 7.1 (a), dan Pasal 8.2 (a(ii), (b) (vi), (xI), dan (xxii), serta e (i)), hak seseorang untuk tidaki dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang (Pasal 7.1(e)), hak untuk tidak disiksa (Pasal 7.1(f) dan Pasal 8.2 (a) (ii) serta (c) (ii)), hak untuk memeluk agama atau kepercayaan (Pasal 8.2(a) (ii) dan (c) (ii), serta hak untuk beribadat menurut agama atau kepercayaan masing-masing (Pasal 8.2(b) (ix)), untuk menyebut beberapa di antaranya. Kekisruhan konseptual yang menyebabkan kekisruhan hukum di Indonesia berawal pada 1999 dengan pemasukan istilah “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” dalam Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) (Pasal 104 ayat (1) beserta penjelasannya). Kekisruhan berlanjut dengan diundangkannya Undang Undang Nomer 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). UU 26/2000 menetapkan pengertian istilah “pelanggaran HAM yang berat” tidak dengan mendefinisikannya melainkan dengan menyebutkan kejahatan apa saja yang terliput oleh istilah ini, in casu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 1 angka 2dan Pasal 7), dengan penjelasan Pasal 7 yang menyatakan bahwa “ Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan’ dalam ketentuan ini sesuai dengan ‘Rome Statute of the International Criminal Court’ (Pasal 6 dan Pasal 7)”. UU 26/2000 makin “meramaikan” kekisruhan konseptual mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan, pertama, mengukuhkan xix Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia istilah umum “pelanggaran HAM yang berat” menjadi istilah yuridis dan mengategorikan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM dengan kualifikasi berat, padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Statuta Roma, kedua kejahatan tersebut, beserta kejahatan perang dan kejahatan agresi, adalah kejahatan internasional dengan dua kualifikasi, yakni, pertama, paling serius dan, kedua, menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan. Dalam konteks keseyogiaan menjadi pihaknya Indonesia pada Statuta Roma, Indonesia harus mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri yang menangani kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPI, sehingga peraturan perundang-undangan nasional Indonesia menjadi instrumen rujukan utama, sedangkan Statuta Roma, sebagaimana ditetapkan sendiri olehnya (paragraph preambuler kesepuluh dan Pasal 1), benar-benar bersifat dan berfungsi sebagai instrument pelengkap belaka. Oleh karena itu, UU 26/2000 harus diganti dengan undang-undang yang baru sama sekal, yang memuat pokok-pokok pengaturan berikut: (a) Bermateri muatan hokum pidana internasional, bukan HAM; (b) Pengadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undangyang baru adalah pengadilan pidana, bukan pengadilan HAM; (c) Yurisdiksi materiil pengadilan pidana yang bersangkutan meliputi, sekurang kurangnya, semua kejahatan yang termasuk yurisdiksi materiil MPI (kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi); (d) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang baru tersebut benarbenar sesuai dengan ketentuan=ketentuan Statuta Roma yang relevan; (e) Ratione personae undang-undang yang baru itu mencakup, pertama, warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan yang termasuk kategori kejahatan yang termasuk yurisdiksi materiil pengadilan pidana yang xx Daftar Isi bersangkutan, di mana pun perbuatan itu di lakukan, di tempat yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia ataupun di luarnya, kedua, orang bukan warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan demikian di tempat yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, dan, ketiga, apabila korban perbuatan demikian, di mana pun terdapatnya, adalah warga negara Indonesia atau milik negara atau warga negara Indonesia; (f) mempunyai hokum acara sendiri yang lengkap; dan (g) dapat diberlakukan secara surut atas dasar kasus demi kasus dengan mekanisme yang menjalin kelancaran pelaksanaannya. Dengan dipunyainya undang-undang pidana yang mengatur penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan atas kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPI dengan ketentuan-ketentuan yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang relevan dari Statuta Roma, maka kekhawatiran ‘intervensi’ MPI ke dalam urusan internal Indonesia dan/atau kecurigaan atan terjadinya ‘pelanggaran kedaulatan” Indonesia oleh MPI menjadi tidak berdasar, sepanjang Indonesia memang benar-benar mau dan mampu melaksanakan undang-undang yang bersangkutan. Ditandai pula terdapatnya kesalahmengertian di sementara kalangan di Indonesia bahwa Statuta Roma dapat diberlakusurutkan, sebagaimana halnya instrument konstitutif pengadilan pidana Internasional yang pernah atau masih ada yang bersifat ad hoc (seperti TMI Nuerenberg, TPI untuk Bekas Yugoslavia, dan TPI untuk Rwanda). Hal ini sudah tentu keliru, karena Pasal 24 ayat 1 Statuta Roma menetatpkan tidak boleh dipertanggungjawabkan secara pidana siapa pun atas tindak yang dilakukannyasebelum mulai berlakunya Statuta Roma. Ketentuan ini berlaku bagi negara-negara xxi Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia yang telah menjadi pihak pada Statuta Roma pada 1 Juli 2002. Untuk negara-negara lain yang menjadi pihak setelah 1 Juli 2002, sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat 2, Statuta Roma baru akan mulai berlaku bagi negara yang bersangan “pada hari pertama dari bulan setelah enam puluh hari sesudah penyimpanan piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi oleh negara yang bersangkutan”, jadi bukan berhitung mulai 1 Juli 2002. Sementara kalangan juga mengertikan secara salah bahwa dengan menjadi pihak Indonesia pada Statuta Roma akan menjadikan warga negara Indonesia “sasaran tembak langsung” Statuta Roma. Pengertian demikian keliru, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut: (a) Sesuai dengan sifat Statuta Roma sebagai instrument pelengkap, Statuta Romahanya dapat diterapkan apabila peraturan perundang-undangan nasional yang menyangkut penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan kejahatan yang termasuk yurisdiksi MPI tidak ada atau, walaupun ada, Negara Pihak yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu melaksanakannya; (b) Karena materi muatan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang bersangkutan adalah kejahatan internasional, maka peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tersebut berlaku tidak saja bagi warga negara Indonesia, di mana pun ia melakukan perbuatannya yang termasuk kejahatan internasioanltersebut ataupun orang asing apabila ia melakukan perbuatan demikiandi wilayah Indonesia (atau di kapal laut atau kapal terbang yang beregistrasi Indonesia), meskipun perbuatan yang bersangkutan dilakukan di luar wilayah Indonesia (atau di luar kapal laut atau pesawat udara yang beregistrasi Indonesia), kecuali jika Indonesia memilih untuk mengekstradisikan orang yang bersangkutan ke negara kewarganegaraannya atau negara tempat dilakukannya perbuatan yang dituduhkan padanya. xxii Daftar Isi Penggesahan dan, kemudian, menjadi pihaknya Indonesia pada Statuta Roma melalui prosedur aksesi, akan merupakan sumbangan bangsa Indonesia sebagai bagian komunitas internasional dalam upaya bersama untuk mengakhiri impunitas pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan sebagai salah satu tujuan Statuta Roma (paragraph preambuler kelima). Pengakhiran impunitas pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan internasional demikian akan menciptakan situasi yang menunjang upaya penciptaan dan pelaksanaan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkanoelh Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945) (alinea keempat). Dengan demikian, pengesahan dan menjadi pihaknya Indonesia pada Statuta Roma tidaklah lain merupakan salah satu langkah yang diambil oleh bangsa Indonesia yang tidak saja merupakan sumbangan pada kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara keseluruhan melainkan juga, tidak lain, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945. Patut dicatat sejak awal bahwa pengesahan dan aksesi Indonesia pada Statuta Roma akan harus dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang bertingkat di bawah undang-undang yang tepat, misalnya peraturan presiden (Perpres), mengenai dua pokok, yaitu, pertama, penerapan Persetujuan tentang Hak Istimewa dan kekebalan MPI (Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court) pada para hakim, penuntut, deputi penuntut, panitera, deputi panitera, penasihat, ahli, saksi, dan orang lain diperlakukan yang mungkin bertugas di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 Statuta Roma dan, kedua, mengenai tata cara kerja sama antara Indonesia dan MPI dalam pelaksanaan Statuta Roma di xxiii Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia bidang-bidang tertentu, sebagai penerapan pasal 86 dan Pasal 88 Statuta Roma. Mengenai hal yang tersebut terakhir ini Indonesia dapat memperhatikan peraturan perundangundangan nasional sejenis yang dibuat oleh negara-negara lain yang telah menjadi pihak pada Statuta Roma xxiv Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia Zaenal Abidin Kata “impunitas” berarti ketidakmungkinan -de jure atau de facto- untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korbankorban mereka.1 Impunitas merupakan problem di banyak negara dan oleh karenanya telah sejak lama dunia internasional memperjuangkan untuk menghentikan praktek-praktek 1 Lihat Serangkaian Prinsip Anti Impunitas yang disusun oleh Louis Joinet. Lihat juga Laporan Diane Orentlicher, Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity. 1 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia impunitas. Sejarah pelanggaran hak asasi manusia diberbagai negara menunjukkan bahwa seringkali tanpa akuntabilitas yakni menghukum para pelakunya dan memberikan hak-hak pemulihan kepada korban. Berbagai mekanisme internasional telah dibangun untuk memastikan penghentian impunitas dengan berbagai bentuk pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban para pelakunya. Setelah serangkaian usaha panjang pengadilan terhadap kejahatan kemanusiaan, pada tahun 1998, dunia internasional sepakat membangun suatu Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. Paragraf kelima dari konsiderans Statuta Roma jelas menyatakan “Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes”. Pernyaataan ini menandakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional salah satu tujuannya adalah untuk menghentikan impunitas para pelaku dan mendorong pencegahan terjadi kejahatah kejahatan semacam kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of aggression).2 Di Indonesia, pada tahun 1998 dengan runtuhnya kekuasaan rejim otoriter orde baru dan masuknya era reformasi menjadikan terjadi tuntutan atas penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa. Terjadi gerakan menuntut adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong adanya penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Pada tahun 2000, salah satu instrumen penting yang lahir yaitu mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi 2 Lihat Pasal 5 Statuta Roma. 2 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia manusia yang berat yaitu kejahatan genosida (the crime of genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) melalui Pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.3 Dua kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan HAM ini merujuk pada Statuta Roma.4 Tahun 2004, muncul UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai suatu mekanisme lain untuk meminta pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu melalui pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi. Karena UU ini mempunyai banyak kelemahan dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak itu, rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum terlaksana sampai terbentuknya UU Baru. Pengadilan HAM yang diharapkan menjadi mekanisme akuntabilitas melalui jalur pengadilan juga akhirnya gagal memenuhi mandatnya. Sejumlah persolan menghadang berjalannya pengadilan HAM, mulai dari kelemahan UU, kapasitas penegak hukum dan dukungan pemerintah terhadap pengadilan HAM. Praktis, sampai tahun 2009 sejumlah kasus yang telah disidangkan gagal menghukum pelaku dan memberikan pemulihan kepada korban. Sementara kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM belum berhasil dilanjutkan ke proses persidangan. 3 Sebelum keluarnya UU No. 26 tahun 2000 Pemerintah Indonesia di bawah Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999. Perpu ini diumumkan presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR. Namun kehadiran Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa. 4 Lihat penjelasan pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000. 3 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Kondisi ini memunculkan kembali persoalan impunitas di Indonesia, kalau tidak bisa dikatakan bahwa impunitas di Indonesia masih terus berlangsung. Merujuk pada pengertian impunitas oleh Louis Joinet, Indonesia telah gagal dalam melakukan penghukuman yang sesuai dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban. Ratifikasi Statuta Roma seharusnya bisa memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dan memajukan pengadilan HAM sebagaimana yang diharapkan. ICC dan Komitmen Indonesia Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court - ICC) yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of aggression).5 Dalam 3 konsiderannya, Statuta Roma tegas menyatakan bahwa penghukuman terhadap kejahatankejahatan yang sangat serius harus dilakukan dan diupayakan untuk mengakhiri impunitas dan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan serius tersebut. konsideran-konsideran tersebut ditujukan untuk menegaskan tujuan-tujuan dari Statuta Roma yang hendak dicapai. Paragraf 4 Statuta Roma menegaskan sebuah tujuan dari politik pemidanaan yaitu “the most serious crimes” … 5 Lihat Pasal 5 Statuta Roma. 4 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia must not go unpunished” dan tugas dari peradilan yang efektif harus dijamin dilaksanakan dengan melakukan tindakan-tindakan pada level nasional dan memperbesar kerja sama internasional untuk mengadili “the most serious crimes” tersebut.6 Paragraf 5 melanjutkan tujuan dari paragraf 4 yaitu “to put an end of impunity for the perpetrators of these crimes”, yang mengisyaratkan bahwa sebuah penegakan hukum secara efektif yang pada saat yang sama mendorong pada pencegahan kejahatan-kejaahatan tersebut dengan membangun kesadaran dan menunjukkan pelaku potensial dari “the most serious crimes” tidak akan lebih lama menikmati impunitas dengan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif.7 Paragraf 6 mengingatkan kepada negara-negara tentang kewajibannya “…state to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes”,8 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Statuta Roma.9 Penegasan tentang tujuan dibentuknya ICC tersebut disetujui oleh Indonesia dengan menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Roma dan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.10 Tahun 1999, Indonesia 6 Lihat paragfat 4 Statuta Roma, “Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation”. 7 Lihat paragfat 5 Statuta Roma, “Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes”. 8 Lihat paragfat 5 Statuta Roma, “Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes”. 9 Otto Triffterer, “Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgessellschaft, 1999, hal. 9-12. 10 Dalam proses pengadopsian Statuta Roma, Indonesia terlibat secara aktif dengan 5 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia menyampaikan pernyataan positif kepada Komite Ke-6 Majelis Umum PBB dalam pandangannya mengenai Statuta Roma. Indonesia menyatakan bahwa “partisipasi universal harus menjadi ujung tombak ICC ” dan bahwa “Pengadilan menjadi bentuk hasil kerjasama seluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya.” Dalam pernyataan yang sama, Indonesia menyatakan bahwa Statuta Roma menambah arti penting pada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi persepakatan, imparsialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan bahwa Mahkamah berusaha untuk melengkapi dan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional.11 Kemandekan Dua Mekanisme Sejak tahun 2000 Indonesia memiliki mekanisme untuk memeriksa dan mengadili kejahatan yang juga menjadi yurisdiksi ICC yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dengan adanya UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000).12 UU ini memberikan mekanisme pertanggungjawaban melalui peradilan baik untuk pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan masa depan. Pada tahun 2000 juga muncul Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V Tahun 2000 tentang mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferansi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998, ketika Statuta Roma itu disahkan. 11 Lihat Kertas Kerja, Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008. 12 Lihat pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Kejahatan genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sesuai dengan Rome Statute 1998. 6 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan ini merekomendasikan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau dan melaksanakan rekonsiliasi. Maksud dan tujuan dari Ketetapan MPR ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, menciptakan kondisi untuk rekonsiliasi dan menetapkan arah kebijakan untuk memantapkan persatuan nasional. Kesadaran dan komitmen untuk memantapkan persatuan ini diwujudkan dengan langkah nyata untuk membentuk KKR Nasional dan merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.13 Setelah dua tahun, yakni pada tahun 2004, terbentuk mekanisme lain untuk akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan adanya UU No. 27 tahun 2004 (UU KKR). Praktis untuk penyelesaian pelanggaran masa lalu Indonesia mempunyai dua mekanisme yaitu melalui pengadilan dan melalui KKR.14 13 Peranan dan fungsi KKR sebagaimana dimandatkan oleh TAP MPR V/2000 dijelaskan dalam Pendahuluan, bagian B, ‘Maksud dan Tujuan,’ yang secara keseluruhan menyatakan bahwa: “Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional”, “Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkahlangkah yang nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.” 14 Sebagai catatan Pada tahun 2001, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menegaskan perlunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.4 KKR Papua mempunyai tugas melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi yang mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. 7 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Sejak itu, tercatat sejumlah kasus telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), namun hanya 2 pengadilan HAM ad hoc dan 1 Pengadilan HAM yang berhasil dibentuk. Hasil dari putusan-putusan pengadilan tersebut ternyata membebaskan semua terdakwa. Banyak kalangan menyatakan bahwa pengadilan ini telah gagal, bahkan selama proses pengadilan berjalan, kritik telah muncul berkaitan dengan kinerja pengadilan yang berada dibawah standar pengadilan internasional,15 dan adanya dugaan bahwa pengadilan ini memang sejak awal sengaja diupayakan untuk mengalami kegagalan.16 Sejalan dengan itu, pengadilan HAM juga gagal dalam memenuhi hak-hak korban yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.17 15 Progress Report ELSAM IV, “Pengadilan HAM dibawah Standar: Preliminary Conclusive Report”, 4 Juli 2002. 16 David Cohen, Intended to Fail , The Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta, ICTJ, July, 2004. 17 Berdasakan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 korban berhak mendapatkan hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 8 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat No 1. Kasus Timor-Timur Putusan/Proses - - - 2. Tanjung Priok - - - Keterangan Mengakui adanya - pelanggaran HAM Tidak ada pelaku yang bersalah Tidak ada - kompensasi kepada korban Tidak mengakui - a d a n y a pelanggaran HAM Tidak ada pelaku yang bersalah - Tidak ada kompensasi kepada korban - 3. Abepura - - - Tidak mengakui - a d a n y a pelanggaran HAM Tidak ada pelaku yang bersalah Tidak ada - kompensasi kepada korban Putusan pertama, banding dan kasasi saling bertolak belakang Pandangan hakim sangat berbeda dalam mengimplementasikan UU No. 26/2000 Putusan pertama, banding dan kasasi saling bertolak belakang Pada tingkat pertama ada yang dinyatakan bersalah dan ada kompensasi untuk korban, yang dianulir di tingkat banding dan kasasi. Pandangan hakim sangat berbeda dalam mengimplementasikan UU No. 26/2000 Pada tingkat pertama pengadilan gagal menghukum pelaku dan kompensasi untuk korban Kelanjutan tingkat banding dan kasasi tidak jelas. Kegagalan pengadilan untuk melakukan proses pengkuman yang efektif dan memberikan remedies kepada korban membuka kenyataan bahwa pengadilan ini ternyata memiliki sejumlah kelemahan dan hambatan. Studi dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan 9 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia bahwa kelemahanan proses peradilan HAM terjadi dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Persoalan ketidakcukupan regulasi disebutsebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kegagalan pengadilan. Faktor lainnya yang juga diduga sebagai faktor yang memperlemah pengadilan HAM adalah kapasitas para penegak hukumnya baik mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini.18 Sejalan dengan kegagalan di level pengadilan, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU KKR karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan lebih khusus bertentangan dengan hukum ham dan hukum humaniter internasional. Mahkamah kemudian memandatkan untuk membentuk UU KKR yang baru yang lebih sesuai dengan hukum HAM internasional dan Konstitusi.19 Keputusan ini menggagalkan upaya untuk membuka serangkaian pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme pencarian kebenaran.20 Padahal, pada tahun 2006 juga terbentuk UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memandatkan pembentukan KKR Aceh dan pengadilan HAM di Aceh. Pembentukan KKR Aceh dimaksudkan untuk menyelesaian pelanggaran 18 Lebih jauh tentang berbagai aspek kegagalan ini dapat dilihat dalam tulisan “Pengadilan Yang Melupakan Korban”, Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau, Pengadilan Hak Asasi Manusia , ELSAM – KONTRAS – PBHI, 24 Agustus 2006 19 Lihat putusan terhadap perkara 006/PUU-IV/2006,. Putusan ini muncul sebagai akibat dari adanya judicial review yang dilakukan sejumlah organisasi (LSM) dan korban atas sejumlah pasal dalam UUKKR dan bukan untuk membatalkan keseluruhan UU KKR. Analisis selengkapnya lihat dalam tulisan “Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi Konstitusionlias Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu : Pandangan kritis atas putusan MK dan implikasinya bagi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu”, ELSAM, 19 Desember 2006. 20 Pada Tahun 2006, setelah tertunda hamppir 2 Tahun, proses seleksi anggota KKR ini telah berjalan namun belum diajukan presiden untuk dilakukan seleksi oleh DPR. 10 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia HAM masa lalu di Aceh yang merupakan bagian dari KKR Indonesia.21 Pembatalan UU KKR dan kegagalan pengadilan HAM semakin memperbesar problem impunitas di Indonesia. Terdapat pandangan bahwa pembuatan upaya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR tampaknya lebih banyak digunakan oleh pemerintah untuk kebutuhan politik diplomatisnya, ketimbang untuk menyelesaikan problem di masa lalu, membela para korban apalagi untuk mencari keadilan dan kebenaran. Terkesan prakteknya akan melegalisir praktek impunitas, dimana para pelaku kejahatan HAM tidak akan pernah di hukum, tapi justru mendapatkan pengampunan. Pola-pola impunitas itu adalah; pertama, pelaku sama sekali tidak disentuh oleh proses hukum. Kedua, pelaku dibebaskan oleh hakim dalam proses pengadilan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Ketiga, kasus dipeti-eskan atau dibiarkan mengambang dengan alasan-alasan teknis yuridis-prosedural.22 21 Lihat pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 22 Ikohi, Resolusi Konggres II Ikohi, “Stop Impunitas dan Kekerasan Negara, Tegakkan Hak-Hak Korban Sekarang Juga”, 7-10 Maret 2006. 11 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Hasil Tiga Pengadilan HAM No 1. Kasus Pelangaran HAM di TimorTimur Perkembangan Kasus Terdakwa 1. Adam Damiri 2.Tono Suratman 3. M. Noermuis 4. Endar Prianto 5. Asep Kuswani 6. Soejarwo 7. Yayat Sudrajat 8.Liliek Koeshadiyanto 9.Achmad Syamsudin 10. Sugito 11. Timbul Silaen 12. Adios Salova 13. Hulman Gultom 14. Gatot Subyaktoro 15. Abilio Jose Osorio Soares Tingkat I 3 Tahun Bebas 5 Tahun Bebas Bebas 5 Tahun Bebas Bebas Banding Kasasi Bebas Bebas Bebas bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas 3 Tahun Bebas Bebas Bebas Bebas - Bebas 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun (PK Bebas) Bebas 16. Leonito Mar- Bebas tens 17. Herman Bebas Bebas Sedyono 18. Eurico Gu10 Tahun 5 Tahun 10 tahun terres 12 Kompensasi Tidak ada satupun putusan tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Kepada Korban Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia 2. 3. Pelanggaran HAM di Tanjung Priok 1.Rudolf Adolf 10 tahun Bebas Butar-butar 2. Pranowo Bebas Bebas 3. Sriyanto Bebas Bebas 4. Sutrisno Mascung 5. Asrori 6. Siswoyo 7. Abdul Halim 8. Zulfata 9. Sumitro 10. Sofyan Hadi 11. Prayogi 12. Winarko 13. Idrus 14. Muhson 3 Tahun Bebas Bebas 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Bebas Pelangga- Jhoni Wainal ran HAM Usman di Papua Daud Sihombing Bebas (Abepura). 13 Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut. Tidak ada kompensasi Tidak ada kompensasi Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut. Tidak ada kompensasi Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Pola impunitas pertama dan kedua sudah terbukti dan pola yang ketika inilah yang terjadi pada kasus tragedi Mei 1998 dan kasus Trisakti-Semanggi I dan II, dan lainnya. Sampai dengan tahun 2008, nasib hasil penyelidikan Komnas HAM juga tidak jelas kelanjutanya. Sejumlah problem masih mengganjal soal pembentukan pengadilan HAM karena Kejaksaan Agung tidak mau melakukan penyidikan dari hasil laporan Komnas HAM. Setidaknya terdapat 5 hasil penyelidikan Komnas HAM kasus yang saat ini mandeg di Kejaksaan. Pokok persoalan dari tahun ke tahun masih sama, yaitu ketidakmauan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dengan berbagai alasan misalnya untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 belum ada rekomendasi dari DPR dan untuk pelanggaran HAM yang terjadi setelah tahun 2000 masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi oleh Komnas HAM. Kasus-kasus Yang Mandeg No Kasus Posisi 1. Trisakti, Semanggi I Di Kejaksaan Agung dan Semanggi II 2. Wasior dan Wamena Di kejaksaan Agung 3. Penghilangan Paksa Di kejaksaan Agung 1997-1998 4. Talangsari Di kejaksaan Agung Keterangan Tidak ada rekomendasi DPR Kejaksaan Agung meminta Komnas HAM melengkapi penyelidikan Belum ada rekomendasi DPR. Baru pada akhir September 2009 muncul rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Belum ada rekomendasi DPR Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak mempengaruhi atau bahkan dipatuhi oleh Kejaksaan 14 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia Agung untuk melakukan penyisikan. MK dalam putusannya berpendapat bahwa untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, yaitu Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.23 Keputusan ini harusnya menjadi jalan pembuka baru bagi tersendatnya proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Perkembangan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sedikit ada perkembangan ketika pada akhir tahun Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang yang dibentuk oleh DPR untuk menyelesaikan kasus orang hilang pada tahun 1997-1998. Pasus ini dianggap bersifat politis karena berencana memanggil sejumlah petinggi militer pada masa lalu yang terkait dengan kasus ini diantaranya Wiranto dan Prabowo yang dianggap akan menjegal mereka dalam pemilu tahun 2009. Pansus ini sebetulnya sudah dibentuk sejak Februari 2008.24 Tidak jelas arah pansus ini karena dalam perkembangannya, pansus sepertinya tidak hanya melaksanakan tugasnya untuk membantu DPR memberikan rekomendasi tentang pembentukan pengadilan HAM ad 23 Putusan MK No 18/PUU-V/2007 tanggal 21/2/2008. 24 Kompas.com, 14 November 2008. ”IKOHI : Pansus Orang Hilang Bermuatan Politik” http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/14/15233213/ikohi..pansus. orang.hilang.bermuatan.politik 15 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia hoc namun juga melakukan penyelidikan ulang terkait kasus ini. Sampai dengan awal tahun 2009 hasil pansus belum terlihat.25 Akhirnya, pada 28 September 2009, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad Hoc untuk kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.26 Namun, hasil rekomendasi ini perlu terus dipantau agar jelas implementasinya. Mandegnya dua mekanisme tersebut menjadikan proses akuntabilitas pelanggaran HAM yang berat di Indonesia kian tidak jelas. Tidak ada perkembangan khusus terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu dan akuntabilitas untuk sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi paska Tahun 2000. Semua proses yang berjalan mandeg ditengah jalan. Padahal. berdasarkan pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), peningkatan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat adalah salah satu rencana yang dicanangkan pada periode 2004-2009. Selain itu adalah peningkatan pengembangan standar operasional pembuktian (SOP) untuk pelanggaran HAM yang berat dan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi sebagai sarana penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.27 Hingga kini, upaya-upaya perbaikan pengadilan HAM juga belum terlaksana, demikian juga pembentukan UU KKR baru yang masih jauh dari kenyataan. Sampai titik ini pula, impunitas masih terus berlangsung, sementara para korban menunggu keadilan tanpa ada kepastian. 25 Lihat Laporan Hukum dan HAM, “2008 : Perjuangan Melawan Lupa”, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Januari 2009. 26 Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk menangani kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa. 27 Lihat Lampiran Keppres RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009. 16 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia Ratifikasi Statuta Roma sebagai Pendorong Penghentian Praktek Impunitas di Indonesia Kemandekan mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia saat ini menunjukkan adanya impunitas terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Sampai dengan tahun 2009, meski terdapat berbagai pengadilan, tidak ada satu pelaku pelanggaran HAM yang berat dijatuhi pidana dan adanya pemenuhan hak-hak kepada para korban. Problem impunitas ini sudah sejak lama diidentifikasi oleh berbagai kalangan. Pada tahun 2000 persoalan impunitas ini mengemuka karena berbagai pelanggaran HAM yang tengah terjadi di Aceh dan Papua, tidak mendapatkan prioritas bahwa cenderung untuk diabaikan dan negara cenderung melakukan pembiaran terus menerus.28 Kegagalan pengadilan ini sebetulnya tidak menurunkan semangat untuk memperbaiki sistem peradilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 2004 Presiden Megawati Sukarnoputeri mengesahkan Rencana Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 -2009. Rancangan tersebut menyatakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008. Demikian pula dengan Parlemen Indonesia yang pada Agustus 2006, perwakilan parlemen Indonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentang Mahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakan ratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat. Tahun 2007 telah didirikan 28 Lihat Kontras, Siaran Pers No 61/Kontras/SP/XII/2000 Tentang Tahun 2000, Tahun Impunitas : Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia : Menyambut Peringatan Hari HAM Se-dunia, 10 Desember 2000. http://www.kontras.org/ index.php?hal=siaran_pers&tahun=2002 17 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia pula Parliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapters, dimana sekretariat internasional PGA selama ini sangat aktif mendukung universalitas Mahkamah Pidana Internasional.29 Niat baik pemerintah untuk meratifikasi itu ternyata tidak sejalan dengan kemajuan dan perbaikan penegakan HAM, termasuk perbaikan akuntabilitas melalui pengadilan HAM. Selama tahun 2007, berbagai masalah HAM yang terjadi ternyata tidak diselesaikan oleh aparatus negara. Fakta ini bertentangan dengan komitmen dan janji Pemerintah Indonesia terhadap Dewan HAM dan komunitas Internasional. Kasus-kasus tersebut antara lain, penculikan aktivis 97-98, Tragedi Mei, Trisakti Semanggi I dan II dan Timor Leste.30 Selain kemandekan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, penyelesaian kasus Munir juga menunjukkan masih kuatnya impunitas di Indonesia. Bebasnya Muchdi PR dalam dugaan pembunuhan terhadap pejuang HAM Munir adalah menambah daftar panjang kasus-kasus impunitas yang selalu dipertanyakan dunia Internasional kepada Pemerintahan Indonesia. Sampai saat ini problem impunitas (kekebalan) hukum masih menjadi penghalang penegakkan HAM di Indonesia.31 Melihat berbagai kegagalan dalam proses pengadilan dan khususnya pengadilan HAM, maka bisa dikatakan 29 Lihat Kertas Kerja, Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008. 30 Lihat Press Release, Mempertegas Komitmen Internasional Untok kondisi HAM di Indonesia, Imparsial, 15 Maret 2007. http://www.imparsial.org/pers_release/ index.php?year=2007&month=3&action=READ&lang=id-8859&id=pers_ release45f915a9669ef 31 Detiknews, “Muchdi Pr Bebas, Potret Buruk Penegakan HAM, Catatan Buat SBY”, 31 Desember 2008. http://www.detiknews.com/read/2008/12/31/154941/ 1061539/10/potret-buruk-penegakan-ham-catatan-buat-sby 18 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia mekanisme yang dibuat justru menjadi tempat berlindungan yang aman bagi para pelaku. Contoh 3 pengadilan HAM yang digelar menunjukkan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia yang berakhir dengan kegagalan Pengadilan untuk menemukan dan menghukum para pelakunya. Sementara kemandekan kasus-kasus lainnya menunjukkan kompleksitas prosedural yang dihadapi dan kemauan pemerintah secara serius untuk menyelesaikannya. Pada sisi lain, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk menghentikan dan mencegah praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional yang serius yang diatur oleh Statuta Roma serta membuat perubahan signifikan atas perilaku aktor negara-bangsa. Terdapat dua faktor penting keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai pencegah terjadinya kejahatan serius internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Pertama, para penguasa tidak dapat lagi melakukan praktik dengan alasan apapun termasuk melakukan impunitas dengan maksud melindungi menggunakan mekanisme hukum nasional baik dengan jalan menggelar pengadilan yang bertujuan melindungi pelaku yang ataupun pengampunan (amnesty). Kedua, para pelaku selain tidak dapat berlindung melalui mekanisme perundangan nasional negaranya juga tidak dapat berlindung pada negara lain sekalipun negara itu bukan menjadi pihak dari statuta. Dalam praktiknya, negara-negara yang telah menjadi pihak telah melakukan transformasi terhadap Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional sehingga ketentuan-ketentuan statuta menjadi bagian dari hukum nasional secara penuh. Berdasarkan kenyataan praktek impunitas dan kegagalan pengadilan HAM dikaitkan dengan peranan dan tujuan ICC untuk menghentikan praktek impunitas, 19 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia meratifikasi atau mengaksesi Statuta Roma menjadi pilihan yang penting. Hal ini mengingat peranan ICC dan juga kewajiban dan hak negara pihak yang meratifikasi. Dengan meratifikasi atau aksesi berbagai perubahan positif diharapkan terjadi misalnya mempercpat proses reformasi hukum di Indonesia, efektifitas hukum nasional, dan peningkatan upaya perlindungan HAM. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia punya kewajiban untuk memperbaiki mekanisme pengadilan HAM sesuai dengan standar-standar ICC. Artinya, berbagai kelemahan pengadilan HAM yang menghambat penghukuman yang efektif dan hambatan untuk memberikan keadilan kepada korban harus segera diperbaiki dengan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi regulasi maupun berbagai sisi yang lainnya. perbaikan-perbaikan ini akan menjadikan perbaikan sistem pengadilan HAM untuk mampu menjerat secara efektif pelaku pelanggaran HAM yang berat dan memberikan keadilan kepada para korban. Penutup ICC merupakan mekanisme akuntabilitas terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius yang menjadi concern masyarakat seluruh dunia. Mekanisme ini salah satu tujuannya adalah menghentikan praktek impunitas dan pencegah terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut terjadi dan ICC memberikan kesempatan pertama (kepada hukum nasional suatu negara untuk melakukan proses penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang paling serius tersebut. Indonesia saat ini bisa dikatakan terus menerus melanggengkan praktek impunitas dengan serangkaian 20 Ratifikasi Statuta Roma dan Upaya Menghentikan Impunitas di Indonesia kegagalan proses akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Pengadilan HAM yang diharapkan menjadi mekanisme yang efektif justru penuh dengan personalan baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Dengan meratifikasi Statuta Roma untuk ICC, Indonesia berkesempatan memperbaiki mekanisme akuntabilitas terhadap kejahatan-kejahatan yang sanga serius dan menjadi bagian dari negara-negara yang berjuang untuk menghentikan impunitas. 21 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC Galuh Wandita Selama tanggal 30 s/d 13 September 1999 Ana ditangan TNI, Polisi, dan milisi Darah Merah dan diperlakukan sesuai dengan kehendak mereka. Pada tanggal 11 September Ana minta kepada mereka untuk diantar kerumah untuk menengok kedua anaknya. Setelah sampai di rumah dan dihadapan saya Ana ditarik dan ditelanjangi dan diperkosa secara bergiliran di halaman rumah. Yang lain berjaga-jaga dan saya juga diancam akan dibunuh. Saya tahu persis ditubuh Ana ada bekas luka bakar mulai dari kemaluan sampai di payudara, juga bekas siraman air panas. Dan mereka masih sempat keluarkan uang dari saku celana Ana sebanyak Rp 200.000. Tanggal 12 September Ana dibonceng oleh seorang anggota Kodim berkeliling di pelosok kota Gleno untuk di pamerkan. [Keesokan 23 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia harinya] seorang komandan Darah Merah [memanggil Ana untuk ikut dalam mobilnya.] … mulai pagi itu saya menunggu hingga sore tidak ada yang muncul. Tiba-tiba ada seorang tentara yang memberitahukan, “Mama jangan menunggu terus karena [Ana] sudah dibunuh.” 1 Kejahatan terhadap kemanusiaan mempunyai akar dalam sejarah manusia yang cukup jauh kebelakang, tetapi biasanya dianggap bahwa secara formal ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ digunakan untuk pertama kalinya dalam pengadilan militer Nuremberg dan Tokyo sesudah Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu sudah ada beberapa kesepakatan internasional untuk kejahatan perang, misalnya Konvensi den Haag (1907), Konvensi Jenewa (1949) yang mengatur peraturan perang antar negara.2 Tetapi belum ada kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga-negara sendiri. Dalam konteks rejim Nazi di Jerman pemusnahan warga-negara Jerman yang beragama Yahudi, musuh-musuh politik, dan orang-orang pinggiran seperti kaum homoseksual –ada diluar jurisdiksi kejahatan perang. Sehingga pada saat itu, perlu ada sebuah konstruksi kejahatan internasional yang baru yang mencakup kejahatan terhadap warganegaranya sendiri. Pengadilan militer ini diselenggarakan oleh para pemenang Perang Dunia Kedua dan sering dikritik sebagai ‘keadilan pemenang’ atau victor’s justice. Tetapi pengamat dan praktisi pengadilan internasional memandang bahwa Pengadilan Nuremberg dan Tokyo menaruh fondasi yang 1 Kesaksian Ines Lemos pada Audiensia Publik Perempuan dan Konflik, yang diadakan CAVR, di Dili, April 2003. Ia menceritakan penculikan, perkosaan dan pembunuhan anaknya, Ana Lemos, seorang guru dan aktivis prokemerdekaan di Ermera. 2 Perkosaan disebut dalam kedua konvensi ini walaupun dikategorikan sebagai pelanggaran martabat keluarga, penyerangan martabat, dan tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang berat. 24 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC kuat untuk proses peradilan internasional, karena: • Menjamin hak-hak terdakwa • Hak untuk mendapat pembelaan hukum • Hak untuk mendapatkan surat dakwaan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh terdakwa • Putusan yang berdasarkan hukum • Proses peradilan mencegah eksekusi seketika Dibawah Pasal 6 Piagam Mahkamah Militer Internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai “…pembunuhan, pembasmian (extermination), perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, sebelum atau sesudah perang; atau persecution berdasarkan politik, ras, agama yang dilakukan berkaitan dengan kejahatan yang berada dibawah jurisdiksi mahkamah tidak tergantung apakah kejahatan tersebut meruppakan pelanggaran dalam undang-undang domestik dimana kejahatan itu terjadi.”3 Definisi ini berkontribusi pada 2 prinsip modern kejahatan terhadap kemanusiaan –bahwa kejahatan tersebut dapat terjadi dalam maupun diluar konteks perang, dan bahwa kejahatan ini mempunyai jurisdiksi universal –tidak terbatas pada undang-undang domestik. Walaupun kekerasan seksual terjadi dalam Perang Dunia II terjadi secara meluas dan sistematik, kedua mahkamah militer ini tidak mengadili kekerasan seksual secara optimal. Perkosaan tidak disebut dalam piagam yang menjadi landasan hukum kedua pengadilan, walupun 3 Kritz, Neil J., Transitional Justice: How emerging democracies reckon with former regimes, Vol. III, (Washington, USA: USIP Press, 1995) p. 459-460. 25 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dalam salah-satu peraturan yang dibuat Sekutu, Allied Local Council Law no 10, perkosaan disebut dalam daftar kejahatahan terhadap kemanusiaan. Namun perkosaan tidak disebutkan baik dalam dakwaan-dakwaan maupun putusan pengadilan Nuremberg. Dalam pengadilan Tokyo perkosaan disebutkan dalam bukti-bukti yang dipaparkan didepan pengadilan dan menjadi bagian dari putusan pertanggung-jawaban komando terhadap Jendral Toyoda dan Matsui, serta beberapa orang lainnya.4 Ada dua perangkat hukum lainnya yang muncul paska-Perang Dunia Kedua, yaitu Konvensi Genosida (1948) dan Konvensi-konvensi Jenewa (1949).5 Namun walaupun ada ‘persenjataan hukum’ ini Perang Dingin membuat dunia internasional tidak berdaya, khususnya mekanisme PBB lumpuh dihadapan berbagai pelanggaran HAM berat— pembantaian di Indonesia, Timor-Leste, Kamboja beberapa contoh dari Asia. Sebagai respon dari ‘pembantaian etnis’ di Balkan, Dewan Keamanan PBB yang sudah terbebaskan dari belenggu Perang Dingin menggunakan kekuasaannya untuk menentukan sebuah ancaman terhadap perdamaian internasional dan tindakan untuk memulihkan perdamaian. Sebuah terobosan radikal dilakukan oleh Dewan Keamanan yang membuat keputusan untuk mendirikan sebuah Pengadilan Adhoc untuk Yugolsavia (ICTY) pada tahun 1993. Lebih dari satu tahun kemudian, pengadilan yang serupa didirikan untuk genosida di Rwanda (ICTR). 4 Asian Legal Resource Center, Specific Context of Sexual Torture. http://www. alrc.net/mainfile.php/torture/151 (retrieved February 20, 2003.) 5 Perkosaan dan kekerasan seksual tidak disebut secara khusus dalam Konvensi Genosida, walaupun dapat diinterpretasi sebagai salah satu unsur kejahatan genosida, yaitu ‘menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius pada anggota kelompok.’ Demikian pula Konvnesi Jenewa hanya dianggap pelanggaran terhadap martabat dan bukan pelanggaran berat (grave breaches). 26 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC Dalam waktu singkat, dibentuk dua pengadilan untuk mengadili kejahatan internasional yang maju dengan pesat, sesudah lebih dari empat dasawarsa adanya impunitas de-facto bagi pelaku kejahatan internasional. Ada beberapa pencapaian ICTY dan ICTR, termasuk jurisdiksi universal untuk perang saudara, penangkapan terdakwa secara lintasnegara, dan penuntutan yang berhasil untuk perkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional. Kedua pengadilan internasional ini menjadi batu-landasan untuk dikembangkannya Statuta Roma untuk didirikannya mahkamah pidana internasional (ICC), dan turut mendesak pengadilan-pengadilan domestik dibeberapa negara untuk melaksanakan jurisdiksi universal atas kejahatan internasional. Putusan-putusan ICTY dan ICTR tentang kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional:6 Perkosaan sebagai penyiksaan 6 Dalam kasus Celibici (1998), pengadilan ICTY memutuskan bahwa perkosaan terhadap perempuan dalam kamp penjara Celebici adalah tindakan penyiksaan. Hazim Delic, seorang wakil pimpinan camp, bersalah atas pelanggaran berat Konvensi Jenewa (penyiksaan) dan kejahatan perang (penyiksaan) karena perkosaan-perkosaan yang dilakukannya. Zdravko Mucic diputuskan mempunyai pertanggungjawaban komando atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam kamp tersebut, termasuk penyerangan seksual. Putusan bersejarah ini menyatakan bahwa perkosaan menyebabkan penderitaan berat secara fisik dan psikologis yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. Dalam putusannya, hakim menulis bahwa kekerasan seksual, “menyerang inti dari martabat manusia dan integritas fisik.” Putusan ini juga menekankan bahwa terjadi dua bentuk pelanggaran –perempuan diperkosa karena ia perempuan, dan perempuan diperkosa karena etnisitasnya—sehingga diskriminasi jender menjadi unsur dari kejahatan penyiksaan. Tabel ini diterjemahkan dan dikembangkan dari sebuah penelitian Human Rights Watch, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/kos0510.htm 27 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan Perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan Perkosaan sebagai genosida Perkosaan sebagai pelanggaran hukum kebiasaan perang Pertanggungjawaban komando untuk perkosaan Dalam putusan Akayesu (1998), ICTR menemukan terdakwa bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena ia menyaksikan dan mendorong terjadinya perkosaan perempuan Tutsi sebagai pimpinan komunitasnya. Pengadilan menyatakan bahwa perkosaan terjadi secara sistematis dan meluas. Dalam kasus Tadic, ICTY mendengar kesaksian tentang perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi di kamp penahanan Omarska dan Trnoploce. Tadic bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas pemukulan yang ia lakukan terhadap perempuan Muslim di kamp tersebut. Dalam kasus Foca (1996), ICTY membuat keputusan bersejarah tentang perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus ini, sembilan orang disekap dalam sebuah apartemen oleh paramiliter elit Serbia, mengalami perkosaan beruntun, dan dipaksa bekerja didalam dan diluar rumah. Empat orang perempuan akhirnya ‘dijual’ pada tentara lain, walaupun dalam putusan pengadilan ini, penjualan bukan pra-syarat pembuktian perbudakan seksual. Dalam kasus Akayesu (1998), terdakwa dinyatakan bersalah atas kejahatan genosida. Bukti-bukti yang didengar oleh pengadilan ICTR termasuk karena ia menyaksikan dan mendorong terjadinya perkosaan dan mutilasi seksual terhadap perempuan Tutsi sebagai bagian dari kampanye genosida, pada saat ia menjadi pimpinan komunitasnya Dalam kasus Furundzija (1998), pengadilan ICTY memutuskan bahwa Anto Furundzija, seorang pimpinan militer Croat Bosnia, bersalah dalam membantu (aiding and abetting) perkosaan seorang perempuan Muslim Bosnia. Ia dinyatakan memberi “dukungan, bantuan, dukungan moral” dalam perkosaan seorang perempuan oleh bawahannya yang sedang diinterogasi oleh Furundzija. Dalam putusan Celebici (1998), ICTY memutuskan bahwa Zdravko Mucic diputuskan mempunyai pertanggungjawaban komando atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh bawahannya dalam kamp tersebut. Hakim menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut begitu sering terjadi dan begitu terkenal sehingga tidak mungkin ia tidak mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan tersebut terjadi, termasuk perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak buahnya. Dalam dakwaan terhadap pimpinan Serbia Bosnia yang bernama Karadzic dan Mladic termasuk juga pertanggung-jawaban komando atas perkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 28 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC Perkosaan sebagai kejahatan perang dalam perang internal Kehamilan yang dipaksakan sebagai genosida Akayesu juga dituntut melakukan kejahatan perang perkosaan dalam perang saudara ini. Namun tuntutan ini ditarik kembali karena tidak ditemukan cukup bukti bahwa ia menjadi anggota militer, atau mempunyai tugas-tugas militer. Dalam putusan Akayesu, disebut bahwa apabila ada perkosaan yang terjadi dengan maksud ‘mencemarkan’ garis keturunan etnis ini dapat menjadi unsur dari kejahatan genosida. Putusan-putusan pengadilan ICTY dan ICTR memutuskan mata-rantai impunitas untuk kejahatan berbasis jender yang sudah sekian lama bertahan. Walaupun terobosan ini terjadi karena adanya sebuah ruang khusus ditingkatan internasional tidak menutup kemungkinan bahwa terobosan-terobosan ini bisa, lambat laun, juga mempengaruhi bagaimana pengadilan domestik dapat menghadirkan keadilan untuk korban-korban kejahatan berbasis jender di tingkat nasional. Terobosan Statuta Roma untuk Kejahatan berbasis Jender 7 Berdasarkan jurisprudensi diatas, Statuta Roma membangun terobosan untuk mengintegrasikan kejahatan seksual dalam kerja-kerja pokok ICC. Terobossan ini dapat dilihat dalam 3 ruang: substansi, prosedur, dan struktur. Substansi Kejahatan Berbasis Jender dalam Statuta Roma • 7 Statuta Roma secara eksplisit telah menyatakan Ulasan dibawah ini disadur dari “GENDER IN PRACTICE: Guidelines & Methods to address Jender Based Crime in Armed Conflict” oleh Women’s Initiatives for Jender Justice] 29 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia bahwa tindakan-tindakan sbb: pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang, baik di dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional dan juga sebagai kejahatan kemanusiaan. ( Lihat Pasal 8(2)(b)(xxii), 8(2)(e)(vi) dan 7(1)(g).) • Statuta Roma mengadopsi definisi genosida melalui Konvensi Genosida, dimana dinyatakan, antara lain, bahwa tindakan mencegah kehamilan bisa menjadi salah-satu tindakan genosida. (Lihat Pasal 6.) • Statuta Roma juga menyatakan secara spesifik bahwa aplikasi dan interpretasi dari hukum harus dijalankan tanpa perbedaan yang mendiskriminasi, termasuk dari perspektif jender. (Lihat Pasal 21(3).) Perlindungan saksi dan partisipasi korban, yang bersahabat dengan perempuan • Partisipasi dan Perlindungan Saksi: ICC diberi tanggung jawab besar untuk melindungi keamanan, keadaan fisik dan psikologis, martabat dan privasi dari korban dan saksi, termasuk berkaitan dengan faktor usia, jender, kesehatan dan bentuk kejahatan. Mahkamah dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan di dalam persidangan, termasuk melakukan sidang tertutup (in camera) dan pengadaan bukti-bukti dengan menggunakan bantuan elektronik. Bahkan, Penuntut Umum 30 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC harus mempertimbangkan perlindungan saksi dan korban ini didalam tahap penyelidikan dan persidangan. (Lihat Pasal 68.) • Unit Saksi Korban: Statuta Roma juga membentuk sebuah Unit Saksi dan Korban (Victim and Witness Unit – VWU) di dalam tubuh panitera ICC. VWU bertugas menyediakan perlindungan, keamanan, konseling dan bentuk bantuan lainnya bagi korban dan saksi yang muncul sebelum Persidangan, dan orang – orang lainnya yang berisiko. (Lihat Pasal 43.) • Partisipasi: Statuta Roma mengakui hak korban secara eksplisit untuk berpartisipasi di dalam proses peradilan, baik secara langsung maupun melalui representasi hukum mereka, dengan diberikannya kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka dalam proses persidangan. (Lihat Pasal 68(3).) • Reparasi: Statuta Roma memberi kekuatan kepada Mahkamah untuk membuat prinsipprinsip kerja, dan dalam situasi khusus, memberikan reparasi kepada korban, termasuk dengan cara memberikan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. (Lihat Pasal 75.) Keterlibatan Perempuan dalam ICC • Personil perempuan di dalam tubuh Mahkamah: Statuta Roma mensyaratkan “representasi yang adil dari hakim perempuan dan laki-laki” dalam proses seleksi hakim. Ketentuan yang sama juga diaplikasikan kepada pemilihan staf Penuntut 31 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Umum dan Panitera. (Lihat Pasal 36 (8)(a)(iii); Pasal 44(2).) • Pakar Trauma: Panitera diwajibkan mempunyai staf yang memiliki keahlian dalam bidang trauma, termasuk trauma yang berkaitan dengan kekerasan seksual. (Pasal 43(6).) • Keahlian tentang Kekerasan terhadap Perempuan: Statuta Roma mensyaratkan adanya keahlian dalam persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam memilih hakim, penuntut dan staf lainnya, untuk memastikan adanya penyelidikan dan penuntutan kejahatan jender. (Lihat Pasal 42 (9), 44(2) dan 36(8).) • Dana Abadi bagi Korban: Statuta Roma mensyaratkan didirikannya Penyandang Dana Abadi untuk kepentingan korban dari kejahatan yang tersebut di dalam jurisdiksi Mahkamah, dan untuk keluarga mereka. (Pasal 79) Sebagai langkah yang lebih konkrit, Statuta Roma juga menyodorkan sebuah lampiran tentang unsur-unsur kejahatan yang juga telah disetujui oleh negara-negara penanda-tangan Statuta Roma. Unsur-unsur kejahatan ini mencerminkan kesepakatan antara negara-negara beradab, sehingga mempunyai nilai yang telah mendekati hukum kebiasaan internasional. Namun, unsur-unsur ini tidak mengikat secara hukum melainkan menjadi panduan bagi para hakim ICC nantinya. Apabila nantinya hakimhakim ICC menggunakan unsur-unsur ini, maka unsurunsur ini menjadi bagian dari jurisprudensi hukum pidana internasional. Contoh dari salah-satu penjabaran unsurunsur kejahatan adalah definisi unsur-unsur “Perkosaan 32 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan,” sbb: Pelaku menginvasi tubuh seseorang dengan tindakan yang mengakibatkan penetrasi, sedikit apapun, dari bagian manapun dari tubuh korban atau pelaku dengan organ seksualnya, atau lubang anus atau kelamin korban dengan benda apapun atau dengan bagian tubuh manapun. 1. Invasi dilakukan dengan paksa, atau dengan ancaman paksa atau pemaksaan, seperti yang mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, penekanan psikologis atau penyalah-gunaan kekuasaan, terhadap orang tersebut atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau invasi dilakukan atas seseorang yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya. 2. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyerangan sistematik atau luas terhadap masyarakat sipil. 3. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya adalah bagian dari atau berniat bahwa tindakannya adalah bagian dari penyerangan luas atau sistematik terhadap masyarakat sipil.8 Sampai dengan sekarang ICC masih dalam proses investigasi dan persiapan dakwaan. Penuntut Umum MorenoOcampo telah menyiapkan beberapa dakwaan penting untuk kasus-kasus di Afrika, namun sangat disayangkan dengan perangkat hukum yang begini lengkap, masih belum 8 Lampiran ICC ini menguraikan unsur-unsur kejahatan untuk semua kejahatan yang ada dalam jurisdiksi Statuta Roma. Untuk melihat penjabaran unsurunsur kejahatan berbasis jender bisa dilihat di “Perempuan dan Hukum Pidana Internasional,” Volume II, Komnas Perempuan, 2007. 33 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia ada dakwaan yang mengikut-sertakan kejahatan kekerasan seksual.9 Di lain pihak, standar yang telah dikembangkan di ICC sepatutnya menjadi contoh bagaimana mengupayakan keadilan jender dalam proses pengadilan di tingkat nasional. Penutup Jurisprudensi kekerasan seksual dalam pengadilan ICTY dan ICTR, maupun dalam Statuta Roma, tidak muncul dengan sendirinya. Kekerasan seksual juga terjadi dalam skala yang luas dan sistematis pada Perang Dunia Kedua, namun sampai sekarang masih terselubung kabut impunitas. Dalam pengadilan ICTY, ICTR, ada penekanan dan dorongan dari kelompok perempuan dan hak asasi manusia untuk mengangkat kekerasan seksual yang terjadi ke meja pengadilan. Sebelumnya, kelompok perempuan telah aktif mengangkat persoalan kekerasan seksual dalam konflik pada forum internasional seperti Konferensi Dunia Hak Asasi di Wina (1993) dan Konferensi Perempuan di Beijing (1995). Menurut Rhonda Capelon, surat dakwaan untuk kasus Akayesu pada awalnya tidak menyebut perkosaan. Ada pandangan dari pihak kejaksaan di ICTR bahwa perkosaan bukan kejahatan yang serius dan para perempuan yang hanya diperkosa cukup beruntung tidak dibunuh, walaupun sudah cukup banyak laporan NGO yang mengungkapkan kejahatan ini dalam konteks genosida di Rwanda. Satu-satunya hakim perempuan di ICTR, Hakim Navanethem Pillay, yang malahan mengungkapkan kekerasan seksual yang terjadi pada saat Hakim tersebut bertanya kepada saksi yang dihadirkan jaksa untuk memberi 9 Lihat “Outcry Over ICC’s Scrapping of Rape Charges: Victims of sexual violence in DRC angered by court’s controversial move” di http://www.peacewomen.org/ news/Africa/GreatLakes/June08/DRCChargesDroped.html 34 Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Terobosan Jurisprudensi Internasional dan ICC kesaksian tentang kejahatan yang lain. Saksi J menceritakan bahwa anaknya yang berumur 6 tahun diperkosa oleh milisi Interahamwe sebelum membunuh suaminya. Saksi lain juga menceritakan bahwa ia diperkosa dan ia menyaksikan perkosaan perempuan-perempuan lainnya pada sat itu. Menurut Capelon, pihak jaksa tetap enggan memperbaiki dakwaan tetapi akhirnya, sesudah banyak surat dilayangkan kepada Chief Prosecutor Louise Arbour (mantan Komisaris Tinggi HAM PBB) oleh kelompok perempuan dan sebuah amicus brief dimasukkan ke pengadilan, akhirnyan jaksa merubah dakwaannya.10 Demikian pula sebuah proses pengadilan untuk kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tidak akan muncul dengan sendirinya di Indonesia. Harus ada upaya yang konsisten dan jangka-panjang untuk menjawab impunitas untuk kejahatan terhadap kemanusiaan secara umumnya, dan impunitas untuk kekerasan seksual sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa upaya misalnya: • 10 Perhatian dan tekanan yang konsisten terhadap proses pengadilan HAM berat yang telah atau akan berjalan di Indonesia. Termasuk melakukan dokumentasi dan advokasi untuk proses pengadilan pelanggaran HAM berat untuk kasuskasus pelanggaran berbasis jender di Aceh, Papua, berkaitan dengan peristiwa 1965, dan juga yang terjadi di Timor-Timur pada tahun 1999 dan sebelumnya. Rhonda Capelon, “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law”, (2000) 46 McGill L.J. 217. Dalam makalah ini ia juga menceritakan peran kelompok perempuan menulis amicus brief untuk kasus-kasus lain di ICTY/R. 35 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia • Perhatian dan tekanan terhadap mekanismemekanisme non-judisial yang adalah bagian dari proses melawan impunitas, seperti memastikan adanya kepekaan jender dalam draft RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. • Pendekatan hukum tidak cukup, tanpa penguatan korban dan komunitasnya, perubahan budaya yang mengorbankan korban, khususnya korban perempuan. Termasuk disini perhatian pada upaya treansformasi budaya dalam institusi-institusi penegak hukum. • Proses pembelajaran dalam rangka ratifikasi ICC, khususnya perubahan apa yang masih harus diperjuangkan untuk memastikan perangkat hukum domestik di Indonesia bisa mengadili kejahatan seksual sebagai pelanggaran HAM berat. Pada akhirnya, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tanggung-jawab kita semua, tanpa batas, sebagai bagian dari umat manusia. Impunitas yang berkelanjutan melanggar martabat manusia dan inti dari kemanusiaan. Perempuan Indonesia dan Timor-Leste korban kekerasan seksual dan keluarganya, seperti Ines Lemos, masih menunggu keadilan. 36 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional Reny Rawasita Pasaribu Pengesahan perjanjian internasional dikenal melalui beberapa cara. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam Pasal 1 mengatur bahwa Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). Meski demikian yang paling umum digunakan dan juga seringkali membingungkan diantara keduanya adalah penggunaan istilah ratifikasi dan aksesi. Ratifikasi yaitu apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. Sedangkan aksesi (accession) yaitu apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangi naskah perjanjian. Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan “ratifikasi” sebagai 37 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia tindakan internasional dari suatu negara dengan mana dinyatakan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian.1 Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary ratifikasi adalah: Confirmation and acceptance of a previous act, thereby making the act valid from the moment it was done.2 Dalam hukum ketatanegaraan, ratifikasi selalu diartikan sebagai tindakan persetujuan oleh suatu organ Negara terhadap perbuatan pemerintah untuk membuat perjanjian atau konfirmasi organ tersebut terhadap penandatangan suatu perjanjian oleh pemerintahnya.3 Dari sisi hukum perjanjian maka Ratifikasi pada esensinya adalah konfirmasi. Konfirmasi ini dibutuhkan karena pada era permulaan berkembangnya perjanjian internasional masalah komunikasi serta jarak geografis antar Negara merupakan faktor yang mengharuskan adanya ruang bagi setiap Negara untuk mengkonfirmasi setiap perjanjian yang telah ditandatangani oleh pejabatnya4. Meski istilah yang tepat adalah aksesi dalam konteks 1 Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Binacipta, 1986, hlm.6. Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional: “ ‘ratification’, ‘acceptance’, ‘approval’ and ‘accession’ mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”. 2 Black’s Law Dictionary. 7th Edition (c) 1999. 3 Damos Dumoli Agusman, Apa Arti Pengesahan? Ratifikasi perjanjian Internasional. http://www.scribd.com/doc/16710619/Apa-Arti-PengesahanRatifikasiPerjanjian-Internasional, diakses tanggal 27 September 2009. 4 Ibid. 38 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional Statuta Roma karena Indonesia tidak ikut menandatangani Statuta Roma namun karena lebih dikenalnya istilah ratifikasi di kalangan masyarakat dan juga pengambil kebijakan maka demi kepentingan advokasi, koalisi menggunakan istilah ratifikasi ketimbang aksesi. Karena materi Statuta Roma masuk kedalam beberapa kategori dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka pengesahan Statuta Roma harus dilakukan dengan bentuk Undang-Undang.5 Undang-Undang sebagai Bentuk Pengesahan Meski UU Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan baik dengan undang-undang atau keputusan presiden (Pasal 9 ayat 2) namun karena materi muatan Statuta Roma setidaknya berkaitan dengan: i) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. ii) kedaulatan atau hak berdaulat negara; ii) hak asasi manusia serta iv) pembentukan kaidah hukum baru maka pengesahan Statuta Roma harus dilakukan dengan undang-undang. Terkait bentuk pengesahan ini maka setidaknya ada tiga peraturan yang menjadi dasar hukum pengesahan Statuta Roma dengan Undang-undang yaitu: UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang5 Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang- undang apabila berkenaan dengan : i) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; ii)perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; iii) kedaulatan atau hak berdaulat negara; iv) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; v) pembentukan kaidah hukum baru; vi) pinjaman dan/atau hibah luar negeri. 39 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang_ Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden. Meski sudah ada ketiga peraturan tersebut namun masih ada banyak ketidakjelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. UU 10 tahun 2004 hanya mengatur soal teknis pembuatan UU saja, misal bentuk baku UU pengesahan dan cara penulisannya. Perpres 68 tahun 2005 hanya sebatas mengatur pelaksanaan persiapan RUU di tingkat pemerintah sedangkan UU Perjanjian Internasional masih sangat umum mengatur prinsip-prinsip dasar perjanjian internasional. Beberapa pertanyaan mendasar yang sama sekali tidak ditemukan dalam peraturan tersebut yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan akademisi adalah: a. Sejauh apa kewenangan inisiatif DPR sebagai pemegang kewenangan pembentukan undangundang dalam proses ratifikasi? b. Bagaimana harmonisasi hukum seharusnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari ratifikasi? DPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan utama dalam pembentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 memegang peran dominan dalam proses pembuatan undang-undang pada umumnya hanya saja dalam proses ratifikasi kewenangan tersebut tidak seluas sebiasanya karenanya proses ratifikasi perjanjian internasional merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang unik karena ada peralihan titik berat kewenangan legislasi dari legislatif ke eksekutif. 40 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional Terkait kewenangan inisiatif DPR, dalam prakteknya ketidakjelasan kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses legislasi. Masyarakat yang ingin mendorong ratifikasi sebuah perjanjian internasional pasti akan kesulitan dalam melakukan advokasi karena tidak jelasnya pihakpihak yang harus didekati karena ketidakjelasan pemegang kewenangan sebagaimana yang sempat dialami oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Ratifikasi Statuta Roma. Disisi lain, ketidakjelasan ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk berkelit dan menyalahkan DPR yang lambat bekerja ketika proses ratifikasi tidak juga dilakukan. Padahal, dalam banyak kasus ratifikasi keterlambatan proses berada pada pihak pemerintah yang lambat menyerahkan RUU ratifikasi kepada DPR. Lambatnya pemerintah bekerja dalam proses ratifikasi dapat terlihat dari daftar UU ratifikasi yang dihasilkan DPR dimana sebagian besar UU ratifikasi tersebut adalah untuk perjanjian yang sudah jauh hari ditandatangani oleh pemerintah. Misalnya saja UU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and The Republic of Korea) yang sudah ditandatangani sejak tahun 2000 oleh pemerintah namun baru diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk diratifikasi pada 2005. Proses ratifikasi suatu perjanjian internasional sesungguhnya sangat ringkas jika dibandingkan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pembahasan antara DPR dan Pemerintah biasanya berlangsung lebih kurang satu sampai tiga minggu saja. Bandingkan dengan pembahasan RUU pada umumnya yang bahkan bisa sampai satu tahun atau bahkan lebih. Kesulitan terbesar dalam proses pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional sesungguhnya adalah pada kajian implikasi 41 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia perjanjian tersebut terhadap hukum nasional. Idealnya ketika pemerintah sudah memutuskan menandatangani suatu perjanjian internasional maka sebelumnya sudah dilakukan kajian implikasi tersebut sehingga proses ketika ratifikasi diajukan kepada DPR, perdebatan soal implikasi sudah selesai atau sangat minim. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah baru mengusulkan ratifikasi perjanjian yang sudah ditandatangani tersebut empat atau delapan tahun kemudian6. Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai tujuh ratifikasi saja. Tahun 2008 jumlah RUU ratifikasi sebanyak tiga RUU, jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2007 DPR melakukan ratifikasi lima perjanjian internasional sedangkan pada 2006 dan 2005 masing-masing ada tujuh ratifikasi perjanjian internasional7. Sebagai konsekuensi diberi bentuk undang-undang, maka seharusnya segala tata cara membentuk undang-undang berlaku pada peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional. Keenam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 10 tahun 2004 juga berlaku untuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang terdiri dari: 6 Aria Suyudi et.al., Catatan Awal TahunKinerja Legislasi DPR Tahun 2008; Mengais Harapan Diujung Pengabdian, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 2008. 7 Ibid. 42 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional a. Perencanaan; Seharusnya semua undang-undang yang akan dihasilkan oleh pemerintah dan DPR masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) yang dihasilkan untuk lima tahun dan daftar prioritas tahunan yang dihasilkan setiap tahunnya, termasuk pula RUU ratifikasi8. Daftar ini dimaksudkan agar arah kebijakan legislasi nasional dapat dengan maksimal mendukung arah kebijakan pembagunan nasional. Perencanaan ini juga diperlukan untuk kepentingan penghitungan sumberdaya manusia dan rencana anggaran berjalan. Namun dalam prakteknya, utamanya untuk daftar prioritas legislasi tahunan, terkait RUU pengesahan perjanjian internasional, daftar perencanaan tersebut tidak menyebutkan secara rinci jumlah dan judul perjanjian internasional yang akan disahkan. Daftar tahunan tersebut hanya mencantumkan kalimat “Daftar Rancangan UndangUndang Kumulatif terbuka tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional”. Ketidakjelasan jumlah dan judul RUU yang menjadi prioritas ini menyulitkan pihak yang ingin terlibat dalam proses. Perpres 68 Tahun 2005 mengatur bahwa RUU tentang pengesahan perjanjian internasional sebagai salah satu RUU yang dapat dipersiapkan diluar Prolegnas. Pengaturan ini membuat daftar prioritas RUU pengesahan perjanjian internasional semakin tidak transparan dan sulit diakses publik. 8 Prolegnas adalah program pembuatan undang-undang yang berbentuk daftar judul RUU yang disusun dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk masa kerja lima tahun. Prolegnas 2004-2009 mencantumkan 284 judul RUU yang menjadi prioritas. Sedangkan daftar prioritas tahunan adalah daftar judul undangundang yang disepakati bersama oleh presiden dan pemerintah untuk diselesaikan dalam periode satu tahun. Daftar prioritas tahunan ini diambil dari RUU yang dicantumkan dalam Prolegnas dan beberapa RUU lainnya yang masuk dalam kategori keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Perpres 68 Tahun 2005. 43 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia b. Persiapan; Tahap persiapan ini pada prinsipnya adalah tahap pembuatan naskah akademis dan draf RUU oleh pemerintah untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR untuk dibahas. Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah pada saat penyusunan Prolegnas 2004-2009 maka setiap RUU harus disertai dengan naskah akademis yang menjelaskan urgensi dari pembuatan undang-undang tersebut. Setelah naskah akademis selesai maka draf RUU dapat segera dibuat. BPHN adalah pihak yang biasanya bertanggungjawab dalam pembuatan naskah akademis sedangkan dephukham bertanggungjawab dalam merumuskan draf RUU. Meski demikian ada banyak kasus dimana naskah akademis digarap langsung oleh departemen pemrakarsa. Dalam menyusun draf RUU, departemen pemrakarsa harus ikut menyertakan dephukham sebagai lembaga yang mengkoordinir segala proses terkait pembuatan peraturan perundang-undangan. RUU pengesahan perjanjian internasional Batang tubuhnya pada dasarnya hanya terdiri atas 2 (dua) pasal yaitu: i. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. ii. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. Sederhananya format RUU pengesahan perjanjian internasional ini seharusnya mendorong segeranya proses 44 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional ratifikasi dilakukan apabila pemerintah sudah mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. UU 10 Tahun 2004 mengatur bahwa RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya (Pasal 18). Karena RUU pengesahan perjanjian internasional merupakan RUU dari Presiden maka proses penyiapannya berada dibawah kewenangan pemerintah. Masalah dalam prakteknya adalah seringkali terjadi lempar tanggungjawab atau malah tarik menarik antar lembaga pemerintah untuk memprakarsai sebuah RUU yang pada akhirnya membuat proses persiapan menjadi kontraproduktif. Perjanjian internasional sangat varian isinya, mulai dari isu sosial budaya, hak asasi manusia sampai soal tapal batas negara. Karena isunya yang menyentuh banyak lini inilah sering terjadi irisan antar departemen terkait soal siapa yang seharusnya memprakarsai RUU pengesahan tersebut. Konflik kewenangan terbesar adalah antara kewenangan Departemen Luar Negeri yang mengurusi segala bentuk pengikatan perjanjian dengan negara lain dengan kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) yang bertanggungjawab dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di pemerintah. Selama koalisi melakukan advokasi mendorong pengesahan Statuta Roma, konflik serupa muncul dimana baik Deplu dan Dephukham mengulur-ulur waktu dalam memutuskan siapa yang akan menjadi Departemen Pemrakarsa yang berakibat semakin tertundanya proses persiapan RUU pengesahan Statuta Roma. 45 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Dalam tahapan ini pula departemen Pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen sebagai forum komunikasi antardepartemen terkait RUU yang dibuat. Forum ini dimaksudkan pula sebagai forum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi RUU yang sedang dibahas tersebut. Jika RUU pengesahan perjanjian internasional sudah disepakati di pemerintah maka Presiden akan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang pada intinya menyerahkan RUU tersebut kepada Pimpinan DPR untuk segera melakukan pembahasan antar kedua belah pihak. Dalam surat tersebut Presiden menunjuk menteri/pejabat yang akan melakukan pembahasan dengan DPR terkait RUU yang dimaksud. Dengan diserahkannya RUU tersebut oleh Presiden kepada DPR maka RUU pengesahan perjanjian internasional tersebut resmi menjadi RUU usul pemerintah. c. Pembahasan; Dalam tahapan ini pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terhadap RUU pengesahan perjanjian internasional yang diajukan oleh pemerintah. Biasanya pembahasannya cukup singkat hanya dalam beberapa minggu saja. Sebagaimana dengan UU pada umumnya, tahapan pembahasan ini ada dua yaitu: i. Tahap I: pembahasan antara Pansus/Komisi dengan pemerintah dalam forum Rapat Pansus/Komisi atau turunannya (Panitia Kerja,Tim Sinkronisasi, Tim Perumus) ii. Tahap II: Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dimana baik DPR dan pemerintah 46 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional menyatakan persetujuan bersama atas RUU yang sedang dibahas d. Pengesahan; Jika RUU sudah disetujui bersama anatara pemerintah dan DPR dalam forum Rapat Paripurna maka pimpinan DPR akan mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden untuk dimintakan pengesahannya. Pengesahan dilakukan dengan Presiden membubuhkan tanda tangannya pada RUU yang disetujui bersama tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undangundang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden (Pasal 38 UU 10 Tahun 2004) e. Pengundangan; Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional baik dalam bentuk UU maupun Perpres harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan penjelasan UU ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. (Pasal 45 dan Pasal 46 UU 10 Tahun 2004) f. Penyebarluasan. Pemerintah merupakan pihak yang wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 51 UU 10 tahun 2004) termasuk pula UU pengesahan perjanjian internasional. Keenam tahapan proses legislasi tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan 47 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia pengesahan perjanjian internasional. Meski segala tata cara membentuk undang-undang berlaku pula pada peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional menurut Bagir Manan untuk Perjanjian internasional terdapat dua pengecualian. Pertama, hak inisiatif membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional semata-mata ada pada Presiden. DPR tidak mempunyai hak inisiatif membuat atau memasuki suatu Perjanjian Internasional karena berdasarkan sistem pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan, hubungan luar negeri masuk ke dalam lingkungan kekuasaan eksekutif bahkan sebagai kekuasaan eksklusif (exclusive power) esksekutif9. Jadi, kalau pernah ada pengesahan suatu Perjanjian Internasional atas inisiatif DPR merupakan suatu penyimpangan atas Asas Pembagian Kekuasaan sebagai kekuasaan eksklusif Presiden (Pemerintah) -Prof. DR. Bagir MananKedua, DPR tidak mempunyai hak amandemen dalam pengesahan Perjanjian internasional. DPR hanya berwenang menyetujui atau tidak menyetujui, menerima atau menolak mengesahkan suatu perjanjian internasional. RUU suatu Perjanjian Internasional adalah hasil kesepakatan yang sudah diparaf oleh masing-masing pemerintah. Dalam hal memasuki perjanjian internasional, DPR hanya setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang sudah ada.10 DPR tentu saja dapat 9 Bagir Manan, Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara). Focus Group Discussion tentang Status Perjanjian INternasional dalam Sistem Hukum Nasional . Departemen Luar Negeri-Universitas Padjajaran, 29 November 2008. http://www.scribd.com/ doc/17599259/Status-Perjanjian-Internasional-Dalam-Tata-PerundangUndanganNasional, diakses tanggal 28 September 2009. 10 Ibid. 48 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional mendorong proses ratifikasi. Idealnya keterlibatan DPR hanya sebatas mendorong dan menekan pemerintah untuk segera mengajukan usul inisitif RUU ratifikasi dalam koridor pengawasan yang dimilikinya. Sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya, jika memang DPR merasa ada perjanjian internasional yang perlu segera diratifikasi karena alasan tertentu, DPR dalam koridor fungsi pengawasannya dapat mendorong pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional tersebut apalagi jika misalnya perjanjian tersebut sudah disebut sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah yang dijanjikan ke publik. Misalnya saja ratifikasi terhadap Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang masuk Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dimana disebutkan bahwa Pemerintah akan meratifikasi statuta tersebut pada tahun 2008, namun nyatanya sampai akhir 2008, pemerintah bahkan belum menyerahkan RUU ratifikasi statuta tersebut ke DPR11. Berdasarkan alasan inilah koalisi masyarakat sipil untuk ratifikasi Statuta Roma melakukan advokasi. Pemerintah merupakan pihak sentral dalam ratifikasi karenanya menjadi sasaran utama dalam proses advokasi. Meski demikian pendekatan kepada DPR tetap dilakukan agar DPR dapat ikut mendorong pemerintah untuk segera menghasilkan RUU ratifikasi. Harmonisasi: Pilihan antara Monisme atau Dualisme Setelah sebuah RUU pengesahan perjanjian internasional sudah disahkan menjadi UU maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana relasi antara hukum internasional yang sudah disahkan tersebut dengan hukum 11 Aria Suyudi, op.cit. 49 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia nasional? apakah perjanjian internasional tersebut dapat langsung diimplementasikan? Pertanyaan ini yang sampai sekarang masih belum diselesaikan dalam peraturan Indonesia yang saat ini berlaku yang mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal implikasi dari ketidakjelasan inilah yang menjadi sumber mandulnya perjanjian internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia. Sumber perdebatan soal ini berputar pada apakah Indonesia menganut monisme atau dualisme.. Monisme menempatkan hukum nasional dan hukum internasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum pada umumnya, keduanya saling berhubungan. Monisme dibagi lagi menjadi dua yaitu monism primat hukum nasional dan monism primat hukum internasional. Yang dimaksud primat hukum nasional adalah ketika Hukum nasional dianggap lebih tinggi dari hukum internasional sedangkan primat hukum internasional adalah ketika hukum internasional dianggap lebih tinggi dari hukum nasional. Dualisme menempatkan hukum nasional dan hukum internasional sebagai sistem hukum yang terpisah, masingmasing berdiri sendiri dan tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Meski menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia menganut aliran monisme dengan primat Hukum Internasional12 namun dalam prakteknya masih terjadi ketidakkonsistenan soal ini. 12 Praktek Indonesia dalam masalah implementasi perjanjian internasional dalam hukum nasional RI tidak terlalu jelas mencerminkan apakah Indonesia menganut monisme, dualisme atau kombinasi Prof. Dr. Ibrahim R. Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional (permasalahan teoritik dan praktek). 50 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional keduanya. Dalam prakteknya, sekalipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan UU, masih dibutuhkan adanya UU lain untuk mengimplementasikannya ada domain hukum nasional,. Di lain pihak, terdapat pula perjanjian internasional yang diratifikasi namun dijadikan dasar hukum untuk implementasi seperti konvensi wina 1961/1963 tentang hubungan diplomatik/ konsuler yang diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1982 13 Pilihan terhadap konsep dasar ini menentukan sejauh apa harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan terhadap suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Apakah perlu dibuat undang-undang khusus yang mengadopsi ulang perjanjian tersebut seperti UNCLOS 1982 yang diratifikasi oleh UU No. 17 Tahun 1985 tetap membutuhkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan atau cukup membuat aturan pelaksana saja (jika dirasa perlu) yang merupakan turunan langsung dari perjanjian internasional tersebut? Apapun pilihannya harmonisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ratifikasi perjanjian internasional. Kesesuaian materi perjanjian internasional yang ditandatangani pemerintah dengan hukum positif Indonesia menjadi kendala utama dalam penerapan perjanjian internasional tersebut dengan kata lain perlu dilakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Jika belum sesuai dengan hukum positif berarti perlu dilakukan 13 Damos Dumoli Agusman, Perjanjian internasional dalam teori dan praktek di indonesia: kompilasi permasalahan/. Direktorat Perjanjian Ekonomi sosial dan Budaya, Direktorat jenderal hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, 2008, http://www.scribd.com/doc/18623572/Perjanjian-InternasionalDalam-Teori-Dan-Praktek-Di-Indonesia-Kompilasi-Permasalahan?from_ email_04_friend_send=1, diakses tanggal 27 September 2009. 51 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia penyesuaian dengan hukum Indonesia lewat ketentuan pelaksananya. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat atau mengubah hukum positif yang berlaku. Pekerjaan harmonisasi dan sinkronisasi bukan pekerjaan gampang. Butuh kajian mendalam dan komprehensif karena memiliki akibat hukum yang luar biasa jika harmonisasi dan sinkronisasi tidak maksimal. Kekosongan hukum, tabrakan nilai dan silang kewenangan akan menimbulkan chaos di masyarakat. Mirisnya, harmonisasi dan sinkronisasi terkait ratifikasi perjanjian internasional sangat lambat akibatnya ratifikasi hanya sebatas formalitas saja tanpa makna dan dampak langsung ke masyarakat. Jika harmonisasi dan sinkronisasi sudah dilakukan maka dapat terlihat apakah perlu dibuat aturan pelaksana baru atau perubahan terhadap peraturan yang sudah ada. Badan Pembinaan Hukum Nasional pernah mengeluarkan sebuah buku mengenai metode harmonisasi dan sinkronisasi yang menjadi panduan bagi BPHN dalam melakukan setiap kajian harmonisasi dan sinkronisasi. Menurut panduan tersebut harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan. Panduan ini sudah memasukan ratifikasi perjanjian internasional sebagai salah satu kemungkinan terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan karenanya perlu dilakukan harmonisasi. 52 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional Harmonisasi adalah suatu proses upaya menuju harmoni. Tujuan yang disebut harmoni ini merupakan pengertian abstrak yang sulit untuk dirumuskan. Akan tetapi mudah jika kita berpangkal tolak dari pengertian disharmoni, yaitu alasan mengapa diperlukan dan diupayakan harmonisasi. Disharmonisasi dibidang hukum dapat terjadi karena: a. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau perundangundangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif. b. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjianperjanjian atau konvensi internasional c. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat dan atau hukum agama d. Adanya perbedaan pengaturan antara undangundnag dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undnagan dengan kebijakan pemerintah lainnya. Deasa ini dikenal berbagai juklak (petunjuk pelaksanaan) atau juknis (petunjuk teknis) yang sifatnya kebijaksanaan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan 53 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dilaksanakan e. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung f. Kebijaksanaan-kebijaksanaan antar instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan, serta adanya perbedaan antara kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Daerah g. Adanya rumusan ketentuan yang kurang tegas dan mengundang perbedaan tafsiran h. Adanya benturan antara wewenang instansiinstansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Pertama yang harus dikerjakan adalah identifikasi masalah dengan melihat bagian yang berbenturan atau berhimpitan yang memerlukan harmonisasi, sebab dan akibat benturan tersebut, siapa atau instansi mana yang terlibat serta apa maksud dan tujuan, demikian pula pangkal tolak serta dasar hukum masing-masing. Jika hal-hal ini sudah jelas baru diambil langkah-langkah harmonisasi. Dasar dan orientasi setiap langkah harmonisasi adalah tujuan harmonisasi, nilai-niai, dan asas hukum serta tujuan hukum itu sendiri yaitu harmoni antara keadilan, kepastian hukum dan atau sesuai tujuan. Secara umum, langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan harmonisasi hukum adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji secara mendalam rancangan peraturan perundang-undangan (baik RUU maupun RPP) yang telah disusun oleh departemen/LPND teknis, 54 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional baik dari segi materi muatan maupun dari aspek teknis perundang-undangan 2. Inventarisasi permasalahan-permasalahan pokok yang tertuang dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 3. Pembahasan terhadap materi-materi tidak sematamata dilandasi oleh analisis hukum, tetapi harus dilakukan analisis interdisipliner termasuk analisis ekonomi 4. Inventarisasi keterkaitan materi muatan yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan atau konvensi-konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan yang telah berlaku efektif atau telah diimplementasikan dalam perundang-undangan nasional 5. Memberikan pandangan-pandangan umum menyangkut materi muatan yang tertuang dalam rancangan suatu peraturan perundang-undangan yang dikaji 6. Mengambil kesimpulan dan/atau rekomendasi guna penyempurnaan rancangan peraturan perundangundangan yang diharmonis14. Di tingkat nasional Departemen Hukum dan HAM adalah pihak yang memiliki peran paling signifikan dalam menjalankan fungsi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 14 Moh. Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 1996/1997. 55 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia perundang-undangan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan berbagai ketentuan dalam UU 10 Tahun 2004 dan Perpres 61 Tahun 2005. Belum ada kejelasan soal harmonisasi yang dilakukan ketika suatu peraturan sudah berjalan (sudah diimplementasikan). Selama ini kegiatan harmonisasi baru dilakukan ketika ada pembuatan peraturan baru. Padahal untuk mendapatkan pengaturan yang komprehensif perlu dilakukan monitoring yang berkelanjutan atas implementasi peraturan-peraturan terkait sektor tertentu secara spesifik. Secara spesifik memang target kegiatan harmonisasi hukum dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan khususnya yang berbentuk Naskah Akademis RUU/RPP dan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah. Dari pengaturan ini ada pembagian peran antara BPHN dan Dirjen PP dephukham, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap produk legislasi pemerintah. BPHN di desain untuk melakukan kajian harmonisasi di tingkat penyusunan RUU/RPP/RPerpres. Sedangkan Dirjen PP Dephukham memiliki lebih banyak peran untuk melakukan harmonisasi selama pembahasan RUU/RPP/RPerpres sedang dilakukan dan ketika sudah diimplementasikan. Pentingnya harmonisasi peraturan perundangundangan paska pengesahan perjanjian internasional untuk dapat bekerja secara maksimal maka seharusnya perlu dibuat mekanisme dimana menjamin segera dibuatnya ketentuan pelaksana sebagai turunan dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional tersebut. Sebagaimana yang saat ini sudah diatur dalam UU 10 Tahun 2004 soal harus 56 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional diaturnya secara jelas batas waktu pembentukan PP, Perpres atau Perda sebagai turunan dari UU, maka dikemudian hari seharusnya UU pengesahan perjanjian internasional dapat mengakomodir hal yang sama dengan mencantumkan pasal yang mengatur mengenai aturan pelaksana apa saja yang perlu dibuat atau diubah agar selaras dan memenuhi standar perjanjian yang diratifikasi tersebut beserta batas waktu pembuatannya. Batas waktu ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan pelaksana tersebut sungguh dibuat dan tidak ditunda-tunda sehingga UU pengesahan perjanjian internasional tersebut segera efektif berlaku. Pencantuman pasal soal ketentuan pelaksana ini bukan hal yang mustahil dilakukan saat ini. Meski belum pernah dilakukan dalam UU pengesahan perjanjian internasional namun jika merujuk pada UU 10 Tahun 2004 yang menggunakan kata pada dasarnya dalam pasal yang mengatur soal jumlah pasal dalam UU pengesahan perjanjian internasional maka jika memang perlu penambahan pasal selain dua pasal yang secara tegas disebutkan dalam UU 10 tahun 2004 tersebut maka sangat mungkin dilakukan. 15 Pentingnya harmonisasi hukum untuk memastikan bekerjanya UU pengesahan perjanjian internasional dipahami betul oleh koalisi masyarakat sipil sehingga dalam naskah akademis, RUU dan berbagai kertas kerja dan materi advokasi koalisi daftar harmonisasi peraturan perundangundangan yang diperlukan terkait rencana ratifikasi Statuta Roma juga disertakan. Sinkronisasi dilakukan secara 15 Lampiran UU 10 Tahun 2004 (huruf F) menyebutkan bahwa: Batang tubuh Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas dua pasal yaitu: Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. ii) Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. 57 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia vertikal dan horisontal. Secara vertikal dilakukan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal dengan nilai-nilai hak asasi manusia lokal (nasional). Sedangkan secara horisontal dilakukan terhadap perundang-undangan yang mempunyai derajat yang sama.16 Pembandingan ini dilakukan melalui interpretasi hukum (penafsiran hukum). Interpretasi bertujuan untuk mempelajari arti yang sebenarnya dan isi dari peraturanperaturan hukum yang berlaku. Dalam hukum Indonesia, dikenal beberapa bentuk interpretasi, diantaranya:17 1. Interpretasi tata bahasa (taalkundige atau gramatikale interpretetie) yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang – undang, dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang – undang; yang dianit adalah arti perkataan menurut tatabahasa sehari-hari. 2. Interpretasi sahih atau autentik atau resmi, yaitu penafsiran sebagaimana maksud pembuat undang – undang itu sendiri dengan maksud agar mengikat seperti ketentuan atau pasal lainnya. 3. Interpretasi historis atau sejarah (rechthistorische – interpretatie), yaitu sejarah terjadinya hukum dan undang – undang atau ketentuan hukum tertulis. 16 Hassan Suryono, Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asaasi Manusia Internasional dan Nasional, dalam Muladi (ed), Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Reflika Aditama, 2005, hlm.88. 17 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 99-111, CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.66- 69. 58 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional 4. Interpretasi sistematis atau dogmatis, yaitu penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan yang sedang ditafsir. 5. Interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran yang mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang melatarbelakangi pembuatan suatu undang-undang 6. Interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang mengemukakan maksud dan tujuan dari si pembuat undang-undang. 7. Interpretasi ekstentif, yaitu memperluas arti kata dalam suatu peraturan sehingga suatu peristiwa atau perbuatan dapat dimasukan ke dalamnya. 8. Interpreatasi restriktif, yaitu penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti kata-kata dalam suatu peraturan. 9. Interpretasi analogis, yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan menggunakan perumpamaan (pengibaratan) terhadap katakata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya. 10. Interpretasi argumentum a contrario atau pengingkaran, yaitu cara menafsirkan suatu undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu perundang-undangan. Sehinga diperoleh kesimpulan bahwa soal yang 59 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dihadapi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Interpretasi terhadap aturan internasional 18 (konvensi) yang menggunakan bahasa yang berbeda digunakan interpretasi secara gramatikal dan sistematis agar tidak terjadi perbedaan makna. Selain terhadap substansi, sinkronisasi dan interpretasi dilakukan juga terhadap komponen kultur, yaitu gagasan-gagasan, harapan-harapan dari semua peraturan hak asasi manusia.19 Berikut secara rinci inventarisir disharmonisasi dan kebutuhan harmonisasi yang berhasil ditemukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk ratifikasi Statuta Roma. I. Disharmoni hukum positif Indonesia dengan Statuta Roma 1. Aturan mengenai kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Aturan mengenai kejahatan dalam yurisdiksi ICC memang belum memadai dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM hanya mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (pasal 8 untuk kejahatan genosida, dan pasal 9 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan), sedangkan kejahatan perang belum terakomodir dalam aturan hukum di Indonesia. Namun jika merujuk dalam Rancangan KUHP Indonesia ketiga kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC 18 Dalam hal ini Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional / International Criminal Court(ICC). 19 Hassan Suryono, op. cit., hlm. 89. 60 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional ini sudah diatur20, sayangnya hingga saat ini rancangan tersebut belum disahkan sehingga belum bisa dijadikan dasar hukum. Saat ini di Indonesia memang masih terjadi perdebatan panjang mengenai aturan kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Sejauh ini, ada tiga usulan: 1. Mengamandemen Undang-Undang 26/2000 tentang pengadilan HAM, dan memasukkan kejahatan perang ke dalamnya; 2. Memasukkan ketiga jenis kejahatan itu menjadi tindak pidana dalam KUHP yang baru. Seperti yang sudah diatur dalam Rancangan KUHP 2004; 3. Membuat undang-undang baru yang mengakomodir ketiga jenis kejahatan tersebut Lemahnya aturan dalam Undang-Undang di Indonesia tidak hanya dalam soal ketiga jenis kejahatan dalam yurisdiksi ICC namun juga dalam hal aturan beracara serta unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdksi ICC. Sehingga seiring dengan dibenahinya aturan perundangan yang mengatur kejahatan dalam yurisdiksi ICC, maka aturan beracaranya pun harus segera dibenahi. Dan agar terdapat satu visi yang sama antara aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketiga kejahatan tersebut sebagai suatu delik pidana maka seharusnya ada aturan yang jelas mengenai unsur-unsur kejahatannya, baik dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang maupun dalam buku pedoman 20 Kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC diatur dalam BAB IX Rancangan KUHP (2004) tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia, yakni dalam Pasal 390 tentang tindak pidana genosida, Pasal 391 tentang tindak pidana kemanusiaan dan Pasal 392 mengenai tindak pidana perang dan konflik bersenjata. 61 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia tersendiri seperti element of crimes dalam Statuta Roma.21 2. Aturan mengenai kadaluarsa Aturan kadaluarsa tidak berlaku bagi kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Aturan tidak berlakunya kadaluarsa bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang juga telah lama diatur dalam Konvensi tentang Tindak Berlakunya Kadaluarsa Bagi Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tahun 1968.22 Sementara dalam KUHP di Indonesia, aturan kadaluarsa masih berlaku sebagai salah satu faktor gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, hal yang sama juga masih tetap diatur dalam Rancangan KUHP 200423. Namun dalam Undang-Undang 26/2000, secara eksplisit dinyatakan bahwa aturan kadaluarsa tidak berlaku bagi pelanggaran berat HAM24. Agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menerapkan aturan kadaluarsa tersebut, aturan implementasi Statuta Roma di Indonesia nantinya harus secara eksplisit 21 The Asia Foundation bekerjasama dengan ELSAM telah merampungkan pembuatan Hukum Acara dan Pembuktian bagi Undang-Undang 26/2000 serta Unsur-Unsur Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan serta UnsurUnsur Pertanggungjawaban Komando. Saat ini draft yang sudah final tersebut telah diteruskan ke Mahkamah Agung untuk lebih lanjut disahkan sebagai PERMA. 22 Pasal 1(b) 1968 Convention on Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity menyatakan statuta ini berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan baik yang terjadi pada saat damai maupun konflik bersenjata seperti yang diatur dalam Piagam Nuremberg serta kejahatan genosida seperti yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948 23 Kadaluarsa dalam hal penuntutan dan pelaksanaan pidana diatur dalam : Pasal 76, 78-82, 84,85 KUHP, Pasal 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153 Rancangan KUHP 2004. 24 Pasal 46 Undang-Undang 26/2000 menyatakan bahwa : “Untuk pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. 62 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional menyatakan bahwa aturan kadaluarsa tidak berlaku bagi kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. 3. Aturan mengenai Ne bis in Idem Ne bis in idem berarti seseorang tidak boleh diadili dua kali atas suatu perbuatan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Ne bis in idem adalah merupakan prinsip-prinsip umum hukum pidana (general principle of criminal law), dan prinsip ini diatur dalam Statuta Roma (Pasal 21) juga dalam KUHP Indonesia (Pasal 76) seperti halnya prinsip-prinsip umum hukum pidana lainnya (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, non-retroaktif, dll) . Namun, prinsip ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 yang justru merupakan satu-satunya Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang berat. Sebagai prinsip umum hukum pidana, maka sudah seharusnya prinsip-prinsip umum ini selalu dicantumkan di setiap konvensi atau Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum pidana, demikian pula dalam aturan implementasi Statuta Roma Indonesia nantinya, jangan sampai prinsipprinsip umum ini tidak dicantumkan seperti dalam UndangUndang 26 Tahun 2000. 4. Aturan mengenai pidana mati Statuta Roma menjelaskan bahwa pidana mati tidak berlaku bagi kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah. Pidana maksimum yang berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang adalah pidana penjara seumur hidup. 63 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Indonesia adalah termasuk Negara yang masih menerapkan pidana mati. Aturan pidana mati diatur baik dalam KUHP dan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM25. Sementara dalam Rancangan KUHP baru (2004), dijelaskan bahwa pidana mati tidak berlaku bagi tindak pidana hak asasi manusia.26 Jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma, tentu saja aturan pidana mati ini akan bertentangan dengan Statuta, kecuali jika pada akhirnya Rancangan KUHP sudah disahkan. 5. Aturan mengenai amnesti Dalam berbagai konvensi internasional aturan hukum amnesti sudah dianggap sebagai aturan hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya aturan yang mengatur bahwa semua pelaku kejahatan internasional harus dihukum.27 Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak selamanya amnesty bertentangan dengan hukum internasional, karena amnesty bisa dibenarkan sebagai bentuk derogation (pengurangan) yang dibenarkan dalam hukum internasional.28 Jose Zalaquett, mantan pengacara HAM Amnesti International, berkewarganegaraan Chille, menyatakan 25 Pidana mati diatur dalam Pasal 10 dan 11 KUHP dan Pasal 36-37 Undang-Undang 26/2000. 26 Rancangan KUHP 2004 menjelaskan pidana maksimum untuk genosida adalah 15 tahun (Pasa390), tindak pidana kemanusiaan maksimum 15 tahun (Pasal 391), dan tindak pidana perang dan konflik bersenjata maksimum 15 tahun (Pasal 392). 27 Misalnya, Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan semua Negara pihak untuk menuntut dan menghukum orang-orang yang diduga melakukan kejahatan yang diatur dalam perjanjian tersebut (genosida dan kejahatan perang). Sehingga, memberlakukan hukum amnesti terhadap para pelaku kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Konvensi tersebut. 28 Ifdhal Kasim,…Op.Cit,p. 6 64 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional bahwa negara yang sedang menghadapi masa transisi, dapat masuk ke dalam konteks ”public emergency” yang diatur dalam pasal 4 Persetujuan Internasional hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga diperbolehkan mengurangi (derogation) sebagian kewajiban internasionalnya.29 Namun, masih menurut Pepe (panggilan akrab Zalaquett) terdapat syaratsyarat yang harus dipenuhi untuk pemberian amnesty yaitu30: a. Kebenaran terlebih dahulu harus ditegakkan; b. Amnesty tidak diberikan untuk pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida; c. Amnesty harus sesuai dengan ”keinginan” rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesty bagi kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC adalah tetap merupakan hal yang bertentangan dengan hukum internasional. Harmonisasi yang Harus Dilakukan Paska Ratifikasi a. KUHP, RKUHP dan KUHAP Pelanggaran HAM yang berat tidak diatur dalam KUHP sehingga pengaturan secara khusus di luar KUHP dibenarkan menurut sistem hukum Indonesia karena 29 Argumen penggunaan azas derogation itu dikemukakan oleh Naomi RothArriaza, “Special Problems of a Duty to Prosecute Derogation, Amnesties, Statute of Limitation, and Superior Orders”, dalam Impunity and Human Rights in International Law and Practice, New York :Oxford University Press, 1995,p. 5770, dikutip dari Ifdhal Kasim,…ibid,p. 9. 30 Ibid. 65 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia sifatnya yang khusus. Beberapa pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ICC sama dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Kesamaan tersebut diantaranya dalam beberapa prinsip yang dianut oleh ICC yang juga telah diatur dalam KUHP Indonesia, yakni prinsip legalitas (non retroactive principle), pertanggungjawaban individual, hal tentang penyertaan, percobaan dan pembantuan serta pemufakatan. Namun pengaturan secara teknis memang tidak sepenuhnya sama, karena dalam KUHP tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.31 Secara substansi, tidak ada masalah antara KUHP dan Statuta Roma diantaranya prinsip legalitas (nonretroaktif), pengaturan mengenai penghukuman terhadap pelaku pembunuhan. Meskipun banyak hal yang belum sesuai32 diantaranya KUHP yang masih menganut ancaman hukuman mati pada terpidana, hal ini tidak dikenal dalam ICC. Disamping itu masalah mengenai kadaluwarsa yang masih dianut dalam KUHP, sedangkan dalam kejahatan berat terhadap HAM yang diatur dalam ICC, tidak dikenal adanya kadaluwarsa. Perbedaan yang cukup besar terdapat dalam hukum acara. Dalam Statuta Roma semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan ICC bersifat independen, berdiri sendiri tanpa pengaruh pihak manapun, begitu juga dengan proses beracaranya yang berbeda dengan perkara pidana biasa. Sistem yang digunakan ICC merupakan gabungan hasil kesepakatan negara-negara bersistem AngloSaxon dan Eropa Kontinental. Sedangkan dalam Pengadilan HAM kita yang diatur oleh Undang-Undang No.26 Tahun 31 op cit, hlm.38. 32 lihat selanjutnya dalam Bab 3, Implementasi Efektif Statuta Roma. 66 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional 2000, hukum acara yang digunakan adalah sama dengan acara yang terdapat dalam KUHAP dengan sistem kita yang menganut Eropa Kontinental. b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang ini merupakan awal tonggak pengaturan HAM secara khusus, dan juga merupakan Undang-Undang yang menunjuk KOMNAS HAM sebagai badan penyelidik dan penyidik kasus pelanggaran HAM yang berat, bersifat independen sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam pelanggaran HAM yang berat. Lembaga independen ini diantaranya memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan meditasi tentang hak asasi manusia.33 Pengakuan terhadap nilai-nilai HAM diatur lebih spesifik. Meskipun demikian undang-undang ini belum menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam jurisdiksi ICC sehingga perlu penyelarasan dengan substansi dari statute roma c. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang – undang ini dibuat atas dasar kesadaran dan kepentingan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pertimbangan yang dilakukan tentunya didasari prinsip dasar pembentukan suatu peraturan perundangan di Indonesia, diantaranya landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Sebagi landasan filosofis, Undang-Undang ini dibuat sebagai penerapan cita-cita bangsa yang dipelopori oleh para pendiri bangsa ini dalam rangka pencapaian tujuan bangsa diantaranya mensejahterakan rakyat Indonesia 33 Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 67 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia melalui perlindungan HAM. Pertimbangan yuridis yang menjadi landasan Undang-Undang ini yaitu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan KUHP Indonesia tidak mengatur pelanggaran berat terhadap HAM yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Dalam sistem hukum Indonesia, suatu hal yang belum diatur dalam KUHP dapat diatur dalam peraturan tersendiri sehingga Undang-Undang 26 Tahun 2000 banyak melakukan terobosan-terobosan aturan hukum yang tidak diatur sebelumnya dalam KUHAP (seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I). Landasan sosiologis dalam Undang-Undang ini yaitu sebagai upaya menjaga dan meningkatkan upaya perlindungan HAM, dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Sedangkan alasan politik dalam Undang-Undang ini yaitu bahwa pelanggaran HAM yang berat bersifat politis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memegang kekuasaan. Adanya Undang-Undang No.26 Tahun 2000 yang isinya banyak mengadopsi dari Statuta Roma ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menunjukan bahwa Indonesia mampu melaksanakan peradilan sendiri yang sesuai dengan standar internasional (Statuta Roma) dan untuk menguatkan prinsip komplementaritas yang dianut oleh ICC. Undang-Undang ini menunjukan niat dan itikad baik pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat di negaranya. d. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sejak tahun 2006, Indonesia telah mempunyai UU khusus tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini 68 Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional mengatur tentang hak-hak korban dan saksi, termasuk dalam saksi dan korban kejahatan-kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat. Beberapa hak saksi yang diatur diantaranya hak-hak saksi untuk diberikan perlindungan pergantian identitas dan relokasi saksi (pasal 5). Selain itu juga mengadopsi berbagai ketentuan dalam Statuta Roma tentang perlindungan saksi diantaranya pemeriksaan saksi in camera, atau pemberian kesaksian melalui media elektronik lainnnya (pasal 9). Meski demikian masih banyak standar perlindungan yang perlu disesuaikan dengan standar yang diatur dalam Statuta Roma. Dalam rangka melindungi saksi dan korban secara lebih baik, UU ini juga memandatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dengan anggota yang mewakili lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat dan dengan sistem kerja yang berkoordinasi dengan lembagalembaga penegak hukum lainnya. Meskipun berbeda konsepnya dengan unit perlindungan saksi dan korban di ICC, namun dalam beberapa hal lembaga ini mempunyai kesamaan tujuan dan fungsi. Adanya UU Perlindungan saksi dan korban ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam menuntut kejahatan-kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat dengan adanya sistem perlindungan bagi saksi dan korban. Demikian juga komitmen untuk memberikan hak-hak reparasi (pemulihan) kepada para korban, yang sesuai dengan hukum internasional dan Statuta Roma. Harmonisasi yang dilakukan oleh koalisi masyarakt sipil untuk ratifikasi Statuta Roma ini lebih kepada membuat aturan turunan/pelaksana dari Statute Roma ketimbang 69 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia mentransformasikannya kedalam hukum nasional dengan membuat undang-undang baru yang membahasakan ulang pasal-pasal dari Statuta Roma. 70 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia Bhatara Ibnu Reza Pendahuluan Komitmen Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM). Akan tetapi komitmen tersebut yang seharusnya dilaksanakan pada 2008 ternyata masih harus tertunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Ratifikasi Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya di sebut Koalisi) telah memprediksi beberapa kendala yang akan dihadapi dalam upaya mendesak Pemerintah Republik 71 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Indonesia (RI) untuk mewujudkan bergabung Indonesia bersama-sama dengan negara-negara di dunia yang telah menjadi pihak dalam kampanye menegakan keadilan internasional. Adapun diantara kendala-kendala tersebut adalah lambannya kejelasan proses yang dilakukan negara dalam menentukan focal point dalam proses peratifikasian yang kemudian oleh belakangan negera menetapkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal lain yang tak kalah penting adalah tantangan yang kuat dari tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara jelas mengungkapkan keberatan-keberatan mereka jika Indonesia menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Berbagai alasan mereka ungkapkan salah satunya berkait dengan belum siapnya perangkat hukum nasional yang compatible dengan Statuta Roma. Namun dibalik alasan itu adalah kekhawatiran TNI terhadap kemungkinankemungkinan mereka untuk menjadi target dari Mahkamah Pidana Internasional jika terdapat dugaan pelanggaranpelanggaran serius yang diakui dalam hukum internasional (serious violations recognized by international law) sebagaimana termaktub dalam Statuta Roma. Kekhawatiran ini jelaslah sangat berlebihan mengingat personil TNI tidak selalu menjadi target tetapi juga dapat menjadi korban. Perspektif salah kaprah ini dapat saja diartikan bahwa TNI dalam setiap operasi militernya selalu menggunakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM sehingga dengan Indonesia menjadi pihak dalam Statuta Roma, TNI tidak dapat lagi leluasa menggunakan kekerasan terutama terhadap penduduk sipil. Bila ditelisik lebih jauh sudah sepantasnya pemahaman yang benar mengenai Statuta Roma dilakukan oleh Indonesia mengingat keikutsertaan aktifnya dalam 72 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia pembahasan dan pengadopsian Statuta Roma pada 17 Juli 1998 dalam Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia. Konferensi yang digelar selama tiga hari (15-17 Juli 1998) ini dihadiri oleh wakil dari 160 negara dan ratusan peserta mewakili LSM internasional. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana reformasi sektor keamanan Indonesia dalam kaitannya dengan reformasi peradilan militer serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang justeru merupakan upaya militer untuk memperkuat posisi dan kedudukannya dalam hukum di Indonesia. Selain itu perubahan tersebut akan memperlihatkan bagaimana upaya militer untuk memperluas yurisdiksi formalnya dengan menarik orang sipil sebagai pelaku kejahatan militer serta yurisdiksi material yaitu memasukan kejahatan perang dalam Kitan Undang-ndang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Reformasi Sektor Keamanan Indonesia Indonesia yang masih berada dalam masa transisi masih terus dibayangi dengan kemungkinan-kemungkinan kembalinya peran besar yang dimiliki militer dalam perpolitikan nasional dengan cara yang lebih halus dan legal. Akan tetapi, reformasi politik menuntut posisi militer dalam supremasi sipil serta mengembalikannya sebagai institusi pertahanan dan profesional. Tidak hanya militer, lembaga kepolisian, lembaga intelijen serta seluruh lembaga pelaksana sektor keamanan juga mengalami reformasi yang terus berlanjut hingga saat ini yaitu menempatkan fungsifungsi sebagai aktor keamanan dalam negeri sekaligus aktor yang menjunjung tinggi HAM. Untuk memperbesar otoritas sipil diperlukan dua 73 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia pendekatan, pertama, militer haruslah tidak terlibat dalam arena politik dan kedua, otoritas sipil harus terlibat dalam permasalahan-permasalahan militer sebagaimana fungsinya dalam pertahanan nasional negara dibawah pengawasan dan kontrol sipil.1 Keterlibatan sipil dalam hal ini tidak hanya diwakili oleh para elit politik namun oleh elemen warga negara seperti kelompok masyarakat sipil yang concern dengan perubahan dalam reformasi sektor keamanan dilakukan dengan keterlibatannya melalui penanataan ulang institusi keamanan dan pertahanan melalui regulasi politik atau reformasi legislasi. Dengan melakukan perubahan pada regulasi politik tersebut diharapkan terjadinya perubahan terhadap para aktor keamanan untuk menjadi lebih profesional dibawah kontrol sipil. Hal ini juga dimungkinkan karena perubahan politik pascajatuhnya Soeharto yang turut serta mengubah konfigurasi politik menjadi lebih demokratis yang membuka kesempatan atau peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum sehingga yang dihasilkan adalah sebuah produk hukum yang berkarakter yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.2 Adapun tolok ukur dalam melihat suksesnya reformasi sektor keamanan ditentukan oleh tujuh komponen:3 1 Lihat Terence Lee, “The Nature and Future of Civil-Military Relations in Indonesia”, Asian Survey at 703-704, Vol. 40, No. 4 (Jul.-Aug., 2000). 2 Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, Cet.2, 2001), hal. 24-25. 3 Lihat Nicolle Ball, Tsjeard Bouta dan Luc van de Goor, Enhancing Democratic Governance of the Security Sector, An Institutional Assessment Framework, (Clingendael: The Netherlands Ministry of Foreign Affairs/TheNetherlands Institute of International Relations, 2003) 74 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 1. Tertatanya ketentuan perundang-undangan berdasarkan the rule of law. 2. Terbangunnya kemampuan pengembangan kebijakan, menyusun perencanaan pertahanan dan keamanan (defense and security planning). 3. Terlaksanannya pelaksanaan (Implementasi kebijakan). dari kebijakan 4. Terwujudnya profesionalisme aktor pelaksana. 5. Kemampuan dan efektifitas pengawasan. 6. Penggelolaan proporsional. anggaran yang logis dan 7. Terselesaikannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Tolok ukur tersebut bukanlah merupakan pilihanpilihan yang harus dilakukan oleh otoritas politik akan tetapi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Indonesia saat ini masih belum mampu untuk menyelesaikan reformasi sektor keamanan disebabkan ketidakpahaman politisi sipil akan posisi militer pada Negara demokrasi. Yang terjadi kemudian adalah politisi sipil masih berpikir bahwa keterlibatan militer adalah suatu keharusan tidak hanya dalam ranah politik tetapi dalam semua aspek kehidupan bernegara. Di Indonesia, militerisasi terhadap semua aspek kehidupan telah dimulai jauh sebelumnya hingga Soeharto 75 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia berkuasa pada 1966 posisi militer semakin kuat.4 Salah satu aspek penting adalah melakukannya dengan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan legitimasi bagi militer secara sah terlibat dalam kehidupan politik negara. Terdapat enam karakter masyarakat yang telah termiliterisasi, pertama, secara nyata kehadiran militer dalam pemerintahan baik diwujudkan sebagai rejim militer atau sebuah kekuatan yang dipaksa (force established) kedalam ruang politik langsung dibawah kekuatan eksekutif (executive power).5 Kedua, kehadiran militer dalam kehidupan ekonomi masyarakat dari pusat hingga ke daerah hinga tingkat desa sehingga mendekati negara korporasi yang mendukung perekonomian militer.6 Ketiga, terjadi proses pembelokan nilai-nilai tradisional dan normanorma atau sedang dalam proses pembelokan dengan nilainilai dan norma-norma militer dengan militerisasi terhadap institusi-insitusi sosial.7 Keempat, administrasi dengan cara melakukan pelanggaran HAM merupakan bagian yang tidak 4 Literatur-literatur sejarah dan politik militer Indonesia yang diangkat dengan berbagai tema oleh penulis-penulis dalam dan luar negeri seperti Ulf Sundhaussen Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945 -1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI, [The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967], [Dirterjemahkan oleh Hasan Basari], (Jakarta: LP3ES, 1986); Nugroho Notosusanto, Ed., Pejuang dan Prajurit: konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991); Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter, (Bandung: Rosda Karya, 1998); Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Kedua, 2002); Dwi Pratomo Yulianto, Militer dan Kekuasaan: Puncakpuncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, (Yogyakarta: Narasi, 2005); Salim Said, Legitimizing Military Rule: Indonesian Armed Forces Ideology 19582000, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006); Leonard C. Sebastian, Realpolitik Ideology: Indonesia’s Use of Military Forces, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies-ISEAS, 2006). 5 Mathews George Chunakara, The Militarisation of Politics and Society: Southeast Asian Experiences, (Hongkong: DagaPress, 1994), hal. 21. 6 Ibid. hal. 21. 7 Ibid. hal. 21. 76 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia terpisahkan dari kehidupan negara. Kelima, operasi terhadap pemberontak (counterinsurgency operation) yang tidak lain sebagai sebuah ekspresi militer dengan sikap represifnya.8 Dan terakhir adalah negara memiliki kebijakan perluasan program transfer persenjataan militer serta produksi senjata domestik yang menjadi bagian dari sumber budget militer.9 Sejumlah karakteristik masih dapat terlihat terutama karakter pertama yaitu insitusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih berada dibawah Presiden. Alhasil, militerisasi mengakibatkan intervensi kehidupan warga sipil dan tentunya mengancam HAM dan kekebasan-kebebasan dasar (fundamental freedoms) yang telah dijamin oleh konstitusi. Perlu kiranya juga untuk mengingat kembali tolok ukur suksesnya reformasi sektor keamanan yaitu tertatanya ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rule of law dan terwujudnya profesionalisme aktor pelaksana.10 Maksud dari rule of law adalah semangat hukum yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan keadilan sehingga legislasi yang dihasilkan tidak sekedar dasar dari kekuasaan belaka. Prinsip demokrasi dalam legislasi sektor keamanan haruslah diiringi dengan semangat ketertundukan militer atas kontrol otoritas sipil yang sah. Sedangkan dalam kaitannya dengan profesionalisme, tentunya legislasi yang dihasilkan menjadikan serta mendukung terwujudnya kemampuan aktor pelaksana untuk menjadi profesional dan tidak menjadikan mereka terlibat dalam politik. 8 Ibid. hal. 21. 9 Ibid. hal. 21. 10 77 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Upaya Menghalangi Mahkamah Pidana Internasional: Reformasi Peradilan Militer dan Perluasan Yurisdiksi Formal dan Material Peradilan Militer Upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat internasional memutus rantai impunitas dengan meratifikasi Statuta Roma justeru mendapatkan rintangan dari berbagai pihak khususnya militer Indonesia. Sebagaimana telah diulas dimuka bahwa kekhawatiran utama dari militer Indonesia adalah mereka akan menjadi target utama dari pemberlakukan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Alasan lain yang sering diungkapkan Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang mengadopsi Statuta Roma sehingga dipandang tidak siapa untuk meratifikasinya. Padahal Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan yang memang diadopsi dari Statuta Roma yaitu UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meski dalam praktiknya justeru tidak mengindahkan standar internasional. Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran berlebihan yang tidak didasarkan pada kenyataan dan pemahaman terhadap hukum internasional secara benar. Selain itu, alasan tersebut muncul dari “trauma” saat Indonesia menghadapi tekanan masyarakat internasional untuk bertanggungjawab dalam pelanggaran berat HAM (gross violations of human rights) pascajajak pendapat di Timor Timur pada 1999. Karena itulah reformasi sektor keamanan yang salah satu tujuannya untuk melakukan penataan terhadap hukum justeru digunakan untuk menambah kekebalan 78 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia militer dari yurisdiksi pengadilan yang mengadili kejahatankejahatan serius yang dikenal dalam hukum internasional (serious violations recognized by international law) sebagaimana diatur dalam Statuta Roma yaitu kejahatan perang. Dengan kata lain upaya pertama yang dilakukan oleh adalah militer mencoba mempertahankan eksistensi peradilan militer tetap berada dalam pengaturannya meski fakta-fakta telah menunjukannya sebagai sarana impunitas. Kedua, adalah dengan melakukan perluasan yurisdiksi peradilan militer dengan dua sasaran yaitu orang sipil dan memasukan kejahatan-kejahatan serius yang diakui dalam hukum internasional sebagai bagian dari kejahatan militer. 1. Perluasan Yurisdiksi Formal Peradilan Militer: Superioritas Peradilan Militer Sepanjang 2004-2009, pemerintah melalui Departemen Pertahanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas RUU Perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pemerintah melalui Departemen Pertahanan sejak Oktober 2005 saat pertama kali pembahasan telah dengan sengaja menarik ulur persoalan-persoalan yang krusial dalam rangka menempatkan peradilan militer dalam sistem kekuasaan kehakiman yang benar. Dalam upayanya yang pertama, terdapat tiga hal penting yang menjadi fokus utama dalam pembahasan RUU ini yaitu soal yurisdiksi; pengadilan dengan acara koneksitas dan keterlibatan perangkat penegak hukum militer seperti Polisi Militer (PM) dalam penyelidikan kasus di peradilan umum serta pelaksanaan putusan. Ketiga hal ini tidak hanya menempatkan kedudukan peradilan militer menjadi superior tetapi juga merupakan contoh konkrit penggambaran dari upaya menempatkan militer sebagai kelas superior dalam masyarakat Indonesia. 79 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Perihal yurisdiksi dimana RUU tersebut menyatakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum dan jika melakukan kejahatan militer akan diadili di Peradilan Militer sebagaimana amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dan UU No. 34 Tahun tentang TNI.11 Namun dalam hal ini akhirnya Persoalan yurisdiksi ini sempat menjadikan pembahasan RUU ini menjadi berlarut-larut karena Departemen Pertahanan bersikukuh untuk tidak menerima yurisdiksi peradilan umum terhadap prajurit TNI. Akan tetapi pada akhir November 2006, ketika masih berada di Tokyo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin bahwa Pemerintah setuju prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum. Dengan pernyataan tersebut, maka kebuntuan yang selama ini terjadi antara DPR dengan Pemerintah sudah menemui jalan keluar dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan.12 Kedua, tentang pengadilan dengan acara koneksitas yaitu jika suatu tindak pidana dilakukan secara bersamasama antara anggota militer dengan warga sipil dan untuk tidak menimbulkan konflik yurisdiksi maka penentuannya dilakukan dengan melihat apakah tindak pidana yang dilakukan mereka merugikan kepentingan militer atau kepentingan publik secara umum. Dalam pembahasannya, Panitia Kerja RUU Perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer akhirnya menerima pendapat pemerintah mengenai perlunya mempertahankan peradilan koneksitas dalam peradilan militer yang kali ini mencoba 11 Ibid. hal. 229. 12 Ibid. hal. 229. 80 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia menjaring warga sipil yang melakukan tindak pidana militer yang pada praktik sebelumnya apakah sebuh tindak pidana merugikan kepentingan pada salah satu pihak apakah militer atau sipil. Argumen pemerintah yang terdengar absurd ini mengandaikan keterlibatan warga sipil bersamasama dengan militer dalam tindak pidana militer. Dalam praktiknya koneksitas merupakan cara yang dilakukan militer untuk melindungi anggotannya mengingat sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menitikberatkan pada status pelaku kejahatan dan bukan jenis kejahatan. Walhasil tindak kejahatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kejahatan yang memang khas militer menjadi yurisdiksi peradilan militer. Bahkan acara koneksitas telah terbukti sebagai bagian dari superioritas militer terhadap berbagai kasus yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana militer. Aturan tentang kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil pertama kali diatur dalam UU No. 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan. Akan tetapi penggunaan istilah koneksitas baru diperkenalkan di masa Orde Baru ketika ditabalkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman dan kemudian diatur juga oleh Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk pelaksanaan penanganan perkara koneksitas itu kemudian dikeluarkan sebuah Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung (MA) RI yang dituangkan dalam No. KEP/B/61/XII/1971 tentang Kebijaksanaan dalam Pemeriksaan yang Dilakukan Bersama-sama oleh Orang 81 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia yang Termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata dan Orang yang Termasuk dalam Yurisdiksi di Lingkungan Peradilan Umum yang diterbitkan pada 7 Desember 1971. Dari segi hukum, surat ini jelas bermasalah mengingat tidak terdapat batas antara MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dengan sebagian pihak yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan legislatif. Hal ini terjadi karena pengaruh luar biasa ABRI saat itu dalam sistem peradilan Indonesia di mana lembaga peradilan dan penuntutan telah mengalami kooptasi dan militerisasi. Selain itu keputusan ini lebih mencerminkan politik hukum Pemerintahan Soeharto daripada sebuah peraturan perundang-undangan. Terbitnya KUHAP bagi ABRI saat itu dianggap tidak cukup memadai sehingga kemudian dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman KEP.10/M/XII/1983 dan KEP.57. PR.09.03 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Tindak Pidana Koneksitas. Setelah diterbitkannya Keputusan Bersama tersebut di atas, selanjutnya Mabes ABRI menerbitkan sebuah surat keputusan yaitu Skep Pangab No. 809/IX/1988 tangggal 2 November 1988 tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Kegiatan Tim Tetap untuk Penyidikan Tindak Surat Keputusan itu kemudian direspon oleh Oditur Jendral (Orjen) ABRI dengan menerbitkan Surat Edaran Orjen ABRI No. SE/B/95/VII/1991 tanggal 29 Agustus 1991 tentang Penunjuk Sementara Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas dan Petunjuk Pelaksana Orjen 82 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia ABRI No. Juklak/01/IV/1993 tanggal 7 Juni 1993 tentang Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Adalah fakta sejarah yang tak dapat dipungkiri dimana terdapar warga sipil yang diadili oleh peradilan militer khususnya oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Mahmilub yang memiki kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkaraperkara khusus yang ditentukan oleh Presiden dalam bentuk keputusan presiden sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Pnps Tahun 1963 tentang PembentukanMahkamah Militer Luar Biasa. Sederetan kasus yang telah diadili melalui mekanisme melalui Mahmilub berdasarkan keputusan presiden tersebut diantaranya pengadilan terhadap tokoh RMS, Dr. Soumokil dengan Keppres No. 6 Tahun 1964, perkara H. Bachrum Effendi auctor intellectualis peristiwa Idhul Adha dengan Keppres No. 156 Tahun 1964, perkara Ibnu Hajar dalam kasus pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dengan Keppres No. 157/1964 serta pengadilan terhadap sejumlah perwira dan tokoh PKI di tahun 1965 dengan Keppres No. 370 Tahun 1965. Namun bila kita ditelisik lebih dalam, pengadilan dengan menggunakan mekanisme Mahmilub merupakan pelaksanaan politik hukum Demokrasi Terpimpin yang memberikan ruang kekuasaan intervensi terhadap independensi peradilan kepada Presiden Soekarno. Saat itu kekuasaan kehakiman dalam hal ini pengadilan merupakan alat revolusi sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undangundang ini kemudian memberikan kewenangan penuih bagi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi untuk campur tangan dalam pengadilan demi kepentingan revolusi, kehormatan 83 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat. Hakikatnya setiap peristiwa yang melibatkan warga sipil dan kelompok militer bersenjata dalam tindak pidana menggulingkan pemerintah atau makar adalah merupakan yurisdiksi peradilan umum. Di berbagai belahan dunia praktik peradilan terhadap kejahatan makar atau yang disebut sebagai high treason ini merupakan wilayah kewenangan peradilan umum meski terdapat keterlibatan militer didalamnya. Selain itu pengertian high treason tidak hanya menyangkut upaya untuk meenggulingkan pemerintah yang sah tetapi juga termasuk tindak pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Untuk yang terakhir ini kembali sejarah peradilan Indonesia pada masa keemasannya pernah melakukannya sekali dan belum pernah terulang kembali adalah kasus Sultan Hamid II. Dalam kasus ini, Sultan Hamid II terlibat berkolaborasi dengan Kapten Raymond Westerling dalam usaha percobaan pembunuhan terhadap sejumlah menteri diantaranya Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kemudian memunculkan Peristiwa APRA di Bandung yang menewaskan sejumlah perwira APRIS. Persidangan kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat saat itu digelar MA dan dipimpin langsung ketuanya yaitu Prof. Mr. Wirjono Projodikoro selaku ketua majelis hakim serta Jaksa Agung Soeprapto selaku penuntut umum. 13 Dengan melihat berbagai kasus tersebut dapat dikatakan peradilan koneksitas tidak dapat lagi menjadi jawaban dalam menangani kasus-kasus pidana militer. Jika praktik mekanisme Mahmilub yang menjadi dasar argumen 13 Lihat Iip D. Yahya, Mengadili Menteri Memeriksa Perwira: Jaksa Agung Suprapto dan Penegakan Hukum di Indonesesia Periode 1950-1959, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004). 84 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia bagi pemerintah sebagai dasar pembenar untuk menyeret warga sipil masuk ke dalam yurisdiksi peradilan militer adalah kesalahan besar. Preseden yang digunakan justeru menafikan independensi dan imparsialitas peradilan yang telah menjadi prinsip yang diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Ditambah lagi, praktik tersebut muncul dari sejarah kelam hukum Indonesia yang imbasnya masih kita rasakan sehingga tidak tepat juga untuk dijadikan contoh ditengahtengah upaya mereformasi dunia peradilan Indonesia. Ketiga, persoalan ketelibatan Polisi Militer dalam penyelidikan dalam kasus-kasus tindak pidana umum. Usulan ini datang dari pemerintah dengan alasan bahwa meski anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada yurisdiksi peradilan umum akan tetapi prosesnya tetap dilakukan dalam yurisdiksi peradilan militer dan kasusnya akan dilimpahkan oleh Oditur Militer. Konsep ini jelas memosisikan superioritas peradilan militer terhadap peradilan umum. Upaya ini dilakukan persoalan kedudukan polisi militer dijadikan pemerintah untuk mengganjal yurisdiksi peradilan umum berkait dengan tindak pidana umum. Selain itu, upaya pemerintah untuk memasukan hal ini dalam pembahasan merupakan upaya menarik ulur pembahasan rancangan legislasi ini.14 DPR sebagai pembuat undang-undang harus secara tegas melihat bahwa persoalan kendala psikologis tidak dapat dijadikan alasan dalam upaya penegakan hukum. Bagaimanapun juga Kepolisian Negara RI merupakan aktor utama sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) dalam penyelidikan tindak pidana umum dan 14 Lihat Pernyataan Bersama, “Pansus Peradilan Militer jangan Terjebak Permainan Pemerintah” (Konferensi Persi Ruang Wartawan Nusantara III DPR, 19 Desember 2008). Lihat www. vivanews.com, “Pemerintah Dinilai Sengaja Tarik Ulur”, http://politik.vivanews.com/news/read/16763-pemerintah_dinilai_sengaja_tarik_ ulu, (Diakses pada 17April 2009). 85 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia bukan polisi militer. Sehingga menempatkan polisi militer kedalam sistem peradilan pidana umum menjadikan mereka seakan-akan memiliki yurisdiksi dalam peradilan umum dan berujung pada kekacauan penerapan hukum acara pidana. Tidak hanya itu, superioritas peradilan militer kedepan akan berpengaruh pada proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh lembaga lain seperti Komnas HAM selaku penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan keterlibatan PM serta Oditur selau jaksa penuntut umum dilingkup peradilan militer artinya sama saja bahwa prinsip yurisdiksi peradilan umum terhadap pelaku militer sama sekali diabaikan dan malah yang terjsdi adalah penguatan kedudukan peradilan militer terhadap peradilan umum. Superioritas peradilan militer juga semakin Nampak jika kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) serta mekanisme Perwira Penyerah Perkara (Papera) tidak mengalami perubahan dalam rancangan legislasi ini dan turut serta berperan dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Ankum memiliki kewenangan sebagai penyelidik sekaligus penyidik perkara dalam lingkup peradilan militer sehingga jikalau mekanisme ini dipakai maka jalannya perkara akan ditentukan oleh tiga aktor yaitu PM, Oditur Milter serta Ankum. Sedangkan Papera adalah perwira yang memiliki kewenangan khusus untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI yang berada dibawah komandonya diserahkan kepada atau diselesaiakan diluar pengadilan militer. Jikalau peran Papera juga masuk dalam 86 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia penanganan tindak pidana umum kemungkinan akan terjadi impunitas mengingat Papera untuk tidak menyerahkan anak buahnya terutama dengan alasan-alasan bahwa prajurit tersebut memiliki keahlian yang dibutuhkah dalam operasi militer. Dengan kata lain, Papera memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk menutup sebuah perkara tidak hanya di peradilan militer tetapi juga dilingkup peradilan umum Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah masih tetap bersikukuh atas pendapatnya yang menjadikan pembahasan melalui Panitia Sinkronisasi antara DPR dengan Pemerintah mengalami deadlock. Hal ini seharusnya dapat dihindari apabila DPR tetap pada pendiriannya untuk melakukan reformasi total terhadap peradilan militer. Adalah benar dalam proses pembuatan undang-undang, DPR melakukannya bersama-sama dengan pemerintah. Namun dalam hal ini DPR lebih memiliki peranan mengingat kedudukan dan kewenangannya selaku pembuat undangundang yang telah dikuatkan dalam konstitusi. Dengan kata lain, DPR seharusnya dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk tidak berkompromi dikarenakan DPR telah membaca gelagat niat tidak baik pemerintah selama proses pembahasan berlangsung. Padahal jikalau menilik lebih jauh terhada substansi RUU ini, yang tak kalah penting juga adalah perihal jaminan hak terhadap prajurit. Meski prajurit adalah bagian dari negara akan tetaoi mereka masih memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang terbatas termasuk dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang termasuk dalam rumpun hak-hak yang tidak dapat dkurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights). Dalam kaitan itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penerapan hak-hak tersebut antara UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 87 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Undang-undang Hukum Pidana dengan RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pembatasan-pembatasan ini jelas menjadikan peradilan militer secara tidak langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap hak-hak non-derogable rights para prajurit. Bagaimanapun hak-hak ini dapat menimbulkan efek ketidakadilan terutama bagi prajurit sendiri serta keluarganya jika hendak melakukan keluhan atau langkah hukum jika dikemudian hari peradilan militer melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Seharusya dalam pembahasan rancangan legislasi ini, DPR hendaknya dapat mendasarkan diri pada sejumlah prinsip-prinsip guna mewujudkan TNI yang profesional, dalam konteks Peradilan Militer berdasarkan pengalaman sejarah, amanat reformasi serta perkembangan dan perbandingan internasional, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dan mendasari UU Peradilan Militer yang baru, yaitu15, prinsip pertama, peradilan militer harus menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, sesuai dengan amanat konstitusi. Prinsip kedua, Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Oleh karena itu di dalam peradilan militer juga harus dijamin asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Prinsip ketiga, reformasi peradilan militer harus mengarah pada penguatan wibawa peradilan militer untuk memperkuat disiplin anggota militer, dengan tetap mengacu 15 Lihat Bhatara Ibnu Reza, et,al, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, (Jakarta: Imparsial, 2007). hal. 65-66. 88 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip keempat, posisi dan komposisi peradilan militer harus diatur sedemikian rupa sehingga meskipun merupakan bagian dari TNI, namun peradilan militer dapat bekerja independen tanpa terpengaruh oleh rantai komando yang berlaku di TNI. Prinsip kelima, peradilan militer harus menjamin keadilan bagi semua prajurit TNI dan melindungi hak asasi prajurit TNI. Tidak boleh ada diskriminasi dalam sistem peradilan militer, artinya baik prajurit maupun perwira harus diposisikan sama di muka hukum. Dalam hal prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, maka hak untuk didampingi pengacara, hak untuk menghubungi keluarga, hak untuk tidak disiksa, hak untuk segera diadili, dan lainlain harus dijamin dengan Undang-undang. Prinsip keenam, peradilan militer harus memiliki yurisdiksi yang jelas. Dalam hal ini yurisdiksi peradilan militer harus didasarkan terutama oleh tindak pidana yang disangkakan, dan bukan semata-mata pada subyek pelaku, waktu, atau lokasi terjadinya kejahatan. Dengan demikian, yurisdiksi peradilan militer terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer. Yurisdiksi berdasarkan tindak pidana yang disangkakan tersebut (ratione materiae) dapat diperluas jika dan hanya jika Indonesia sedang mengalami situasi perang. Dari aspek subyek pelaku tindak pidana (ratione personae), yurisdiksi peradilan militer terbatas pada mereka yang menjadi anggota militer serta yang dipersamakan. Sedangkan dari segi lokasi kejadian perkara (ratione loci), yurisdiksi peradilan militer hanya terbatas pada medan pertempuran ketika Indonesia sedang dalam situasi perang. Dalam situasi perang, aspek-aspek ratione 89 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia materiae, personae dan loci di atas dapat diperluas dengan berdasarkan keputusan/persetujuan DPR. Maka dari itu, dengan prinsip ini praktek peradilan koneksitas menjadi tidak relevan dan harus dihapuskan dari sistem peradilan militer. Prinsip ketujuh, peradilan militer harus bersifat terbuka sehingga bisa dikontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Segala bentuk pelanggaran serta tindakan terhadap pelanggaran hukum pidana dan disiplin militer, harus dilaporkan dan dapat di-review oleh eksekutif melalui Menteri Pertahanan. Dengan demikian diharapkan dapat dicegah terjadinya pemidanaan militer dan mekanisme disiplin militer terhadap tindakan yang semestinya masuk yurisdiksi peradilan umum. Prinsip kedelapan, menyangkut akuntabilitas peradilan militer, harus ada aturan yang jelas dan terukur mengenai mekanisme hukum dan disiplin militer yang berlaku di lingkungan internal militer. Oleh karena itu mekanisme-mekanisme ekstra-yudisial seperti Dewan Kehormatan Militer atau Dewan Kehormatan Perwira harus dihapus. Kalaupun diperlukan mekanisme ekstra-yudisial semacam itu, tidak boleh bersifat subtitutif terhadap sistem hukum yang berlaku. Mekanisme-mekanisme ekstra-yudisial tersebut harus ditempatkan sebagai komplemen/suplemen dari sistem hukum yang berlaku. Prinsip kesembilan, sebagai bagian dari unifikasi hukum dan menghindari dualisme rezim hukum tata usaha di Indonesia, maka Undang-undang Peradilan Militer tidak semestinya mengatur tata usaha militer. Perluasan Yurisdiksi Material Peradilan Militer: Perebutan 90 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia Setelah sebelumnya melakukan perluasan yurisdiksi formal dengan memasukan orang sipil dalam yurisdiksi Pengadilan militer. Kali ini fokus utamanya adalah perluasan yurisdiksi material berkait dengan upaya militer untuk memasukan salah satu kejahatan serius dalam hukum internasional. Dalam draft RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (2005), dimana dimasukan kejahatan seperti kejahatan perang. Sedangkan Komnas HAM dalam Draft RUU Amandemen UU No. 26 Tahun 2000 telah memasukan pula kejahatan perang sebagai yurisdiksinya. Dengan kata lain militer “berlomba” dengan Komnas HAM untuk memperebutkan yurisdiksi kejahatan perang bagi Pengadilan militer dan Pengadilan HAM. Padahal bila ditelisik dengan seksama dari praktikpraktik pengadilan internasional seperti International Military Tribunal (IMT) atau Nuremberg Tribunal 1945; International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) atau dikenal sebagai Tokyo Tribunal 1945; International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) 1994 serta International Criminal Tribunal for Rwanda (1996), menunjuklan bahwa tidak hanya anggota militer yang dapat didakwa melakukan kejahatan perang melainkan juga orang sipil. Salah satu contoh kasus adalah ketika bekas Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic akhirnya diadili oleh ICTY dalam dengan salah satu dakwaannya adalah kejahatan perang. Preseden ini juga bukan menjustifikasi kejahatan perang berada dalam yurisdiksi material Pengadilan Militer dengan fokus keterlibatan orang sipil. Sama sekali tidak karena justeru Pengadilan Militer harus dan hanya mengadili kasus-kasus kejahatan yang memang khas militer serta mengeluarkan kejahatan perang didalamnya. 91 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Jika menelisik KUHPM dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP, namun berlaku khusus untuk militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan militer.16 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain tunduk pada KUHPM mereka juga masih tunduk pada ketentuan-ketentuan KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya.17 Alasanalasan di mana keberadaan KUHPM merupakan tambahan dari KUHP antara lain bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan tertentu di mana perbuatan itu jika dilakukan oleh seorang militer di dalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat. Misalnya adalah kejahatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan Pasal 140 KUHPM. Selain itu beberapa perbuatan yang terdapat dalam KUHPM hanya dapat dilakukan oleh militer. Misalnya sengaja tidak menaati perintah kedinasan (Pasal 103 KUHPM) atau menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 118 KUHPM).18 Pada Buku II KUHPM mengatur perihal kejahatan dan membaginya atas tujuh bab yaitu: 1. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. 2. Kejahatan-kejahatan terhadap kewajibankewajiban militer tidak dengan maksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh. 16 Marjoto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1965), hal. 8. 17 Ibid. hal. 8. Lihat juga Pasal 1 dan 2 KUHPM. 18 Ibid. hal 8-9. 92 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 3. Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksaan kewajiban dinas. 4. Kejahatan-kejahatan pengabdian. 5. Kejahatan-kejahatan tentang pelbagai keharusan dinas. 6. Pencurian dan penadahan. 7. Merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang. Sebagian besar kejahatan itu sebenarnya diatur juga dalam KUHP. Salah satu kejahatan yang sama-sama diatur oleh KUHPM dan KUHP adalah kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam KUHPM kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 72 sedangkan pada KUHP diatur dalam Pasal 104 hingga 129. Berangkat dari berbagai macam kejahatan itu serta hubungannya dengan KUHP, tindak pidana militer sebagaimana yang diatur dalam KUHPM dibagi dalam dua bagian yaitu:19 1. Tindak pidana militer murni yaitu tindakantindakan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Adapun contohnya: a. Seorang militer yang dalam keadaan 19 S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hal. 19. 93 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia perang dengan sengaja menyerahkan seluruh atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM). b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM) c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM) 2. Tindak Pidana Militer Campuran yaitu tindakantindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain namun diatur kembali dalam KUHPM atau undang-undang hukum pidana militer lainnya karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu yang sifatnya lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana semula sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 KUHP. Contoh dari tindak pidana tersebut adalah seorang militer yang ikut serta melakukan pemberontakan diatur dalam Pasal 65 KUHPM yang pada intinya juga diatur dalam Pasal 108 KUHP. Perbedaan dari kedua Pasal tersebut adalah subyek dan ancaman pidananya. Dalam melihat tindak militer campuran, sebagaimana telah dijelaskan dalam kaitannya dengan kejahatan makar kita haruslah jeli melihat bahwa yurisdiksi yang berlaku adalah peradilan umum. Kekosongan pengaturan kejahatan perang dalam hukum nasional kita juga dapat menjadi permasalahan. Selain itu kita dapat melihat contoh berkait dengan praktik pasukan 94 Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia perdamaian PBB dimana Indonesia sangat aktif dalam peran sertanya menjaga perdamaian dunia.20 Asas Komplementer tetap berlaku namun permasalahannya Indonesia tidak memiliki mekanisme hukum nasional untuk mengadili para pelaku khususnya berkait dengan kejahatan perang. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengatur kejahatan perang dalam yurisdiksinya. Sehingga dapat dimungkinkan kemungkinan dikategorikan tidak mampu (unable) untuk mengadili para pelaku kejahatan. Namun sepertinya militer mengmabil kesempatan ini untuk mereka dapat mengadili sendiri kasus-kasus kejahatan perang baik dalam penugasan nasional maupun internasional. Simpulan Berangkat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi sektor keamanan Indonesia lebih banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan militer yang sebenarnya tidak beranjak dari persoalan-persoalan yang seharusnya direformasi. Reformasi peradilan militer yang menjadi bagian didalamnya telah membuktikan kegagalan Indonesia untuk memutus rantai impunitas yang selama ini dipraktikan oleh peradilan Militer. Perubahan-perubahan seperti perluasan yurisdiksi formal dan terutama sekali yurisdiksi material merupakan bukti lain dimana militer mencoba menjadi sangat superior dalam dunia peradilan. Statuta Roma, preseden-perseden serta keputusan-keputusan pengadilan internasional berkait dengan kejahatan perang tidak menjadi tolok ukur bahwa pengadilan militer tidak memiliki yurisdiksi dalam mengadili kejahatan tersebut. 20 Secara khusus dapat dibaca dalam pembahasan perihal Perlindungan Pasukan Perdamaian dan Buruh Migran 95 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Sungguhpun demikian, jalan keluar dari persoalan ini adalah Indonesia secepatnya meratifikasi Statuta Roma. Ratifikasi Statuta Roma justeru menjadi pemicu dari upaya Indonesia untuk perbaikan serta penguatan atas mekanisme hukum nasionalnya. Dengan demikian adalah tepat memasukan kejahatan perang dalam Amandemen UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sekaligus sebagai bentuk implementasi Statuta Roma dalam hukum nasional Indonesia. 96 Tentang Complementarity dan Retroactivity Agung Yudhawiranata Asas Komplementer Terdapat kekhawatiran di beberapa kalangan bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berarti menyetujui dan mengikatkan diri terhadap semua aturan dalam Statuta Roma.1 Hal ini menurut beberapa kalangan sangat beresiko khususnya bagi negara berkembang, dikarenakan pandangan bahwa ICC akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan ICC terhadap pengadilan / sistem hukum suatu negara. 1 Merupakan reaksi terhadap prinsip non-reservasi yang dianut oleh Statuta Roma 1998 dalam Pasal 120 yang menyatakan bahwa “No reservation may be made to this statute.” Artinya bila suatu Negara meratifikasi dan menjadi pihak dalam Statuta ini maka Negara harus menerima dan melaksanakan semua ketentuan dalam Statuta Roma tanpa kecuali. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dan tidak sampainya tujuan yang dimaksud dalam pembuatan Statuta. Lihat William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001, hlm.159-160., Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, BadenBaden : Nomos Verl Ges., 1999, hlm. 1251-1263. 97 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Kekhawatiran sebagian masyarakat akan adanya intervensi internasional oleh ICC ke dalam hukum nasional Indonesia sebenarnya terjawab dengan uraian mengenai prinsip komplementer (complementarity principle) yang merupakan prinsip fundamental dari keberlakuan ICC dalam suatu Negara. Prinsip ini tertuang dalam paragraf 10 Mukadimah2 yang berarti bahwa ICC hanya merupakan pelengkap bilamana pengadilan nasional tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) mengadili suatu pelanggaran berat terhadap kemanusiaan menjadi alasan dasar yang menepis kekhawatiran Negara akan intervensi internasional dalam kedaulatan negaranya bilamana menjadi negara pihak Statuta Roma. Pasal 1 Statuta Roma juga menyatakan bahwa tujuan pembentukan Mahkamah adalah untuk menerapkan jurisdiksi atas pelaku tindak pidana internasional sebagaimana terdapat dalam Statuta dan memiliki fungsi untuk melengkapi (complementarity) sistem peradilan nasional Negara.3 Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah adalah sebuah hasil proses perundingan demokratis yang ingin menciptakan “international justice” dan lebih mengedepankan nilai-niliai hukum sesuai dengan tujuan utama PBB (Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB)4 diantaranya untuk mencegah berkembangnya 2 Paragraf 10 Preamble Statuta Roma: “Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”. 3 Hans-Peter Kaul, Breakthrough in Rome Statute of the International Criminal Court; Law and State, vol.59/60, Supp.10 (a/49/10) 4 Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB: “Tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian” 98 Tentang Complementarity dan Retroactivity kejahatan-kejahatan internasional.5 Singkatnya, Mahkamah Pidana Internasional dilarang melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan ketika pengadilan nasional sedang mengadili kejahatan yang sama dan (i) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, (ii) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan; (iii) kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah (Pasal 17 Statuta Roma). Dan sebagai tambahan, (iv) orang yang bersangkutan telah dihukum atau dibebaskan atas kejahatan yang sama, melalui pengadilan dan layak dan adil (Pasal 17(c) dan 20 Statuta Roma).6 Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan mekanisme hukum nasional suatu Negara kecuali jika Negara tersebut “tidak mau” (unwilling) atau “tidak mampu” (unable) untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku sehingga kejahatan tersebut menjadi yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17 Statuta Roma). Selain itu, prinsip komplementer ini tidak hanya berlaku terhadap Negara pihak Statuta saja tetapi juga terhadap negara yang bukan merupakan pihak Statuta Roma (Pasal 18 (1)) tetapi memberikan pernyataan sebagai pengakuannya atas jurisdiksi ICC. Misalnya, seorang warga 5 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003, hlm.544. 6 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 342. 99 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia negara bukan pihak Statuta yaitu negara A telah melakukan kejahatan internasional dalam wilayah teritori negara B yang merupakan pihak dari Statuta Roma, kemudian ia kabur ke negara C yang bukan merupakan pihak Statuta Roma. Negara C melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara A tersebut dengan dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dalam perjanjian internasional dan tersangka berada dalam wilayah teritorinya (the forum deprehensionis principle) atau juga karena didasarkan pada prinsip universalitas. Dan Mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila terbukti bahwa Negara C memiliki kemauan dan mampu untuk melaksanakan pengadilan yang layak dan adil.7 Paparan di atas secara jelas menggambarkan bahwa ICC tidak berfungsi untuk menggantikan pengadilan nasional suatu Negara melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi ICC. Bahwa tanggungjawab utama untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC adalah Negara, bukan ICC. Karena itu mekanisme penegakkan hukum di Negara tersebut harus benar-benar efektif, misalnya dengan memasukkan kejahatan dalam yurisdiksi ICC sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasionalnya. Pengalaman Indonesia dalam menegakkan hukum khususnya hukum HAM dengan disertai berbagai hambatan dalam instrumen hukum, aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, menjadikan peratifikasian Statuta Roma terasa begitu penting untuk mendorong Indonesia segera membenahi berbagai kekurangan dan kelemahannya tersebut. Peratifikasian Statuta Roma merupakan bentuk komitmen nyata dalam rangka upaya perlindungan HAM dan penegakan hukumnya 7 ibid 100 Tentang Complementarity dan Retroactivity yang dapat memberi banyak keuntungan baik secara hukum maupun politis. ICC merupakan the last resort atau disebut juga ultimum remedium. Pasal 17 ayat (1) huruf a, b dan c menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan Negara tidak dapat dikontrol oleh ICC, jadi bila Negara mampu melakukan penuntutan maka ICC tidak akan mencampuri jurisdiksi nasional Negara tersebut. Ini merupakan jaminan bahwa ICC bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu Negara. Asas Non-retroaktif Selain prinsip complementarity, Statuta Roma juga menganut prinsip non-retroktif. Artinya, kejahatankejahatan yang masuk dalam yurisdiksi Statuta Roma namun terjadi sebelum disahkannya Statuta Roma, tidak akan dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dengan demikian, Indonesia tidak perlu khawatir bahwa para pejabat negaranya akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional dengan tuduhan bertanggung jawab atas kejahatan HAM yang terjadi di masa lalu. Khususnya mengenai prinsip non-retroaktif ini, terjadi pemahaman yang keliru mengenai penerapannya dalam sistem dan mekanisme hukum Indonesia. Sebagian kalangan mengkhawatirkan, jika Statuta Roma diratifikasi maka mekanisme pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk oleh UU No.26 Tahun 2000 untuk mengadili kejahatan serius HAM di masa lalu terpaksa dihapuskan atas nama mentaati prinsip non-retroaktif yang dijunjung tinggi dalam Statuta Roma, dan oleh karenanya akan menghilangkan harapan 101 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia korban pelanggaran HAM masa lalu akan keadilan.8 Berdasarkan praktek hukum internasional, kewenangan untuk mengadili pelanggaran masa lalu yang dimungkinkan melalui mekanisme pengadilan HAM ad hoc berdasarkan UU No.26/2000 bukanlah merupakan pelanggaran terhadap asas non-retroaktif, karena yang ada adalah kewenangan pelaksanaan yurisdisksi retrospektif (exercising retrospective jurisdiction) dan bukan pengakuan atas asas retroaktif. Dalam hukum internasional tidak dikenal adanya asas retroaktif, yang dikenal adalah asas nonretroaktif yang menjadi prinsip dasar (cardinal principle) dari hukum internasional. Menurut prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang menjadi sumber hukum internasional, pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi dari UU No.26 Tahun 2000 yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan kejahatan genosida (crimes of genocide) merupakan kejahatan internasional paling serius (most serious international crimes) yang tunduk pada yurisdiksi hukum internasional sebagai ius cogens dimana pelakunya dianggap musuh semua umat manusia (hostis humane generis) dan merupakan kewajiban semua bangsa (obligatio erga omnes) untuk mengadili pelakunya. Sejak diselenggarakannya pengadilan Nuremberg 1946 dan Pengadilan Tokyo 1946 maka pengadilan atas kejahatan internasional paling serius tersebut tidak lagi dianggap pelanggaran terhadap asas non-retroaktif. 8 Pendapat ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk oleh UU No.26 Tahun 2000 adalah penerapan asas retroaktif. Pemahaman ini keliru, karena dalam hukum pidana internasional tidak dikenal adanya asas retroaktif, yang ada hanya asas non-retroaktif sebagai pengejawantahan dari asas kardinal nulla poena sine lege primae. 102 Tentang Complementarity dan Retroactivity Selain itu, perlu kembali diingat bahwa Statuta Roma menjunjung tinggi asas complementarity yang mengutamakan proses pidana domestik sebelum dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Ini merupakan pengakuan eksplisit bahwa kepentingan nasional Negara Pihak menjadi hal yang diutamakan. Maka, mekanisme pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran berat HAM masa lalu sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 dapat diletakkan dengan tepat dalam konteks argumen “demi kepentingan nasional” karena memang ada kebutuhan obyektif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia agar dapat menatap masa depan Indonesia yang lebih baik, dan karenanya mekanisme internasional tidak dapat mengganggu gugat kondisi ini. Kepentingan Nasional Tujuan Statuta Roma untuk memberikan jaminan penghukuman bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida, menghapuskan rantai impunity dan mengefektifkan mekanisme hukum nasional, dapat menjadi sarana pendorong bagi Indonesia untuk segera membenahi kekurangannya tersebut dan mewujudkan komitmennya sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakkan HAM. Diharapkan, dengan diratifikasinya Statuta Roma disertai dengan penyerbarluasan informasi yang terstruktur dan sistematis, maka pemahaman tentang aturan hukum HAM dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum HAM internasional dapat lebih baik lagi. Dan tentu saja, untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik serta peran aktif berbagai pihak baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan, legislatif sebagai sarana legitimasi, para penegak hukum, akademisi dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. 103 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Implikasi ratifikasi sendiri tidak hanya keluar, tapi juga ke dalam. Selama ini ratifikasi instrumen internasional / absorbsi nilai-nilai universal dianggap melemahkan integritas nasional bukan menguatkan, sehingga dalam penerapannya ada resistensi-resistensi. Harus dibangun wacana/argumen bahwa meratifikasi ini justru adalah upaya untuk memperkuat ikatan-ikatan kebangsaan, NKRI, dsb (termasuk bahwa nilai-nilai yg diperjuangkan ICC khususnya dan gerakan HAM pada umumnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yg adil dan beradab) perlu dielaborasi. Misalnya tentang jaminan keadilan, jaminan pencegahan kekejaman di masa depan, dan sebagainya. ini diletakkan dalam prinsip-prinsip ratifikasi yang tidak menyerang nasionalisme. Sebaliknya, proses ratifikasi ini justru diharapkan dapat melakukan purifikasi terhadap pemahaman yang salah atas nasionalisme selama ini. Mengingat pentingnya arti Statuta Roma dalam upaya perlindungan HAM internasional, dan menyadari kelemahan Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan HAM bagi warganegaranya ditandai dengan masih terjadinya praktek impunity, ketidakmemadaian instrumen hukum HAM, aparat penegak hukum serta sarana prasarana perlindungan saksi dan korban di Indonesia menjadikan peratifikasian Statuta Roma sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Dalam konteks ini, perlu dibangun pemahaman bersama bahwa national interest Indonesia bukan hanya menjaga sovereignty of the State, tapi bahwa menghormati HAM juga bagian dari national interest yang diakui dalam konstitusi seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta secara aktif dalam memelihara perdamaian, ketertiban dan keamanan dunia. 104 REKAM PROSES PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM UPAYA MENDORONG RATIFIKASI STATUTA ROMA DI INDONESIA Pengantar Ratifikasi Statuta Roma (ICC – International Criminal Court) merupakan agenda penting bagi kemajuan hukum dan keadilan di Indonesia. Ratifikasi Statuta Roma akan memberikan kontribusi yang sangat positif dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, ditingkat regional dan internasional. Kegagalan mekanisme hukum nasional untuk memenuhi keadilan bagi korban dan semakin berkembangnya fenomena impunitas menjadi dasar kebutuhan Indonesia akan mekanisme hukum internasional 105 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia yang dapat memberikan keadilan bagi korban dan melindungi masyarakat dari tindak pelanggaran HAM. Pentingnya posisi Statuta Roma ICC sebagai salah satu mekanisme internasional yang dapat menjamin penegakan dan perlindungan HAM menjadikan ratifikasi ICC sebagai agenda bersama bagi komunitas korban pelanggaran HAM dan organisasi HAM di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan upaya Indonesia dalam meratifikasi ICC menunjukkan perkembangan positif dengan adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi pada tahun 2008 seperti tertuang dalam Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009. Di sisi lain, perkembangan positif ini juga menghadirkan beberapa tantangan untuk memenuhi komitmen ratifikasi ICC pada tahun 2008. Tantangan ini bisa dideskripsikan sebagai: pertama, bagaimana publik dapat memastikan Pemerintah melaksanakan komitmen untuk meratifikasi ICC dan, kedua, pada waktu yang beriringan juga untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai ICC dalam insitusi pemerintahan dan anggota DPR yang berada dalam level pemerintahan. Selain itu, ketiga, peningkatan pemahaman publik mengenai apa itu ICC dan alasan mengapa masyarakat membutuhkan ICC harus dilakukan secara lebih massif dengan mengumpulkan berbagai perspektif dan pendapat masyarakat mengenai ICC. Dalam perspektif tersebut, IKOHI dengan dukungan dari Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF), menjalankan program “Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma ICC” sebagai sebuah upaya untuk mendorong ratifikasi ICC di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut 106 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia diatas. Tantangan ini memang bukan tantangan yang mudah dan sederhana karena mencakup dua ranah kerja yang kadang sangat sulit berhubungan: masyarakat dan pemerintah. Namun dengan pendekatan dan strategi yang tepat dan didukung berbagai aktivitas, diyakini mampu menjawab tantangan tersebut. Setelah melalui pergulatan dan kerja keras selama lebih dari satu tahun, berbagai perkembangan positif telah dicapai. Menguatnya wacana ratifikasi Statuta Roma ICC dalam masyarakat dan konsolidasi masyarakat sipil dalam mendorong proses ratifikasi adalah sebagian perkembangan positif yang telah dicapai. Tulisan ini mencoba merekam proses dan upaya yang telah dilakukan sebagai sebuah bahan refleksi dari upaya masyarakat sipil dalam mendorong ratifikasi ICC di Indonesia. Membangun dan Mengelola Dukungan Masyarakat Sipil Dalam rangka merancang dan melaksanakan strategi kerja yang komprehensif dalam proses ratifikasi Statuta Roma ICC di Indonesia, pada tanggal 10 Juni 2008 di Jakarta diadakan sebuah pertemuan untuk membentuk tim ahli dan sekaligus motor kerja untuk membuat draft naskah akademis dan mempersiapkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan rancangan strategi tersebut. Tim ini beranggotakan lima orang berdasarkan latar belakang kemampuan dan bidang kerja yang ditekuni. Mereka adalah Mugiyanto dari IKOHI yang berkecimpung dalam perjuangan keadilan dan hak-hak korban pelanggaran HAM, Agung Yudhawiranata (ELSAM) yang selama ini mengeluti riset dan kajian mengenai HAM, Bhatara Ibnu Reza (IMPARSIAL) yang menekuni isu HAM dan security sector reform, Reny Rawasita Pasaribu (PSHK) yang intens 107 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dalam kajian dan penguatan instrumen hukum, serta Zainal Abidin (YLBHI) yang berpengalaman dalam riset dan pembelaan kepada masyarakat. Pada bulan April 2009, posisi Reni Rawasita Pasaribu digantikan oleh Herni Sri Nurbayanti (PSHK) karena Reny harus pindah ke Perancis. Untuk memastikan implementasi dan penerapan strategi serta menjadi jembatan komunikasi bagi anggota tim, dibentuklah tim kesekretariatan yang berlokasi di IKOHI. Keberadaan tim ahli inilah, beserta dengan lembaga masingmasing, yang menjadi pencetus sekaligus tulang punggung berdirinya Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Untuk memberikan penguatan dan masukan terhadap berbagai draft yang diproduksi, Koalisi meminta beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai isu seputar ICC sebagai Dewan Pengarah dalam Koalisi. Dewan Pengarah ini terdiri dari: Enny Soeprapto, Ph.D, Fadillah Agus, S.H., M.H, Galuh Wandita, B.A., LL.M, Ifdhal Kasim, S.H, Kemala Tjandrakirana, M.A dan Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. Dalam memperkuat dukungan publik untuk proses ratifikasi di Indonesia, dalam workshop Statuta Roma yang diadakan di Jakarta pada bulan Juni 2008, seluruh partisipan sepakat untuk membuat koalisi yang lebih luas untuk mensupport ratifikasi. Koalisi sendiri dinamakan “Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional” yang diluncurkan pada tanggal 25 Juni 2008. Anggota koalisi terdiri dari banyak sector dari akademisi, media, kelompok perempuan, komunitas korban dan NGO. Koalisi juga terdiri dari person individu yang memiliki kepedulian tentang reformasi hukum, keadilan, dan HAM di Indonesia. 108 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Koalisi Indonesia juga menjadi anggota koalisi internasional untuk ICC (CICC), sebuah koalisi internasional dengan lebih dari 2,500 organisasi di seluruh dunia, koalisi ini dibangun untuk mendukung kampanye dalam proses ratifikasi. Menggelar Konsultasi Publik untuk Isu ICC Sebagai elemen penting dalam upaya mendorong ratifikasi ICC, konsultasi publik adalah sebuah proses yang sangat penting. Konsultasi publik merupakan sebuah wadah untuk menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai isu ICC. Untuk mengoptimalkan prose’s konsultasi publik ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional menyusun serangkaian proses konsultasi publik dalam format focused group discussion (FGD) di enam daerah yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Aceh dan Papua. 109 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Masing-masing FGD mendiskusikan dan memuat masukan strategis dari 15 orang stakeholder utama dan ahli-ahli ditingkat daerah. Partisipan yang terlibat termasuk pejabat pemerintah, akademisi, pengacara dan pemuka masyarakat dalam bidang yang relevan. Secara lebih spesifik, rangkaian FGD ini memiliki tujuan untuk: (1) mendapatkan pemahaman mengenai tujuan ratifikasi Statuta Roma dalam konteks hukum, politik dan ekonomi serta mendiskusikan strategi kampenye dan penyebaran informasi mengenai pentingnya ratifikasi Statuta Roma kepada publik, (2) berbagi pengetahuan dan sumber daya antara pemerintah, parlemen, akademisi dan masyarakat sipil untuk mengatur dan mempercepat proses ratifikasi dan (3) pembagian peran dan kerja diantara stakeholder dan peserta dalam rangka mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma. Rangkaian proses dan hasil dari konsultasi publik atau FGD dapat dipaparkan sebagai berikut: Jakarta 110 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Sebagai pembuka proses konsultasi publik tentang ICC digelar FGD di Jakarta selama dua hari pada tanggal 24-25 Juni 2008 di Hotel Harris, Jakarta. Proses ini dihadiri lebih dari 20 orang yang berasal dari institusi pemerintah dan masyarakat sipil. Pada sesi hari pertama difokuskan pada topik urgensi Indonesia meratifikasi Statuta Roma, konsekuensi-konsekuensi ratifikasi, dan isuisu penting seperti non-surrender agreement, kedaulatan negara, dan pelanggaran HAM masa lalu dengan narasumber Bhatara Ibnu Reza (Tim Ahli - Imparsial) dan Evelyn Balais Serrano (Coalition for The International Criminal Court CICC). Pada hari kedua, proses dilanjutkan dengan menfokuskan pada perkembangan terakhir dalam proses persiapan ratifikasi, kendala yang dihadapi dan upaya mencari kesepakatan jalan keluar, kebutuhan penyusunan peraturan pelaksanaan yang terpadu dengan narasumber Nursyahbani Katjasungkana (DPR RI) dan Prof Hakristuti Hakrisnowo, SH, MA, Ph.D (Dirjen HAM-Depkumham RI) Dari proses selama dua hari ini, terpaparkan kendala-kendala yang dapat menjadi ganjalan upaya ratifikasi ICC bagi Indonesia. Kendala-kendala tersebut adalah: • Ratifikasi ICC tidak masuk dalam PROLEGNAS 2005-2009 • Hubungan antara ICC dan sistem hukum nasional, khususnya dalam implementasi peraturan dibutuhkan untuk meratifikasi Statuta Roma 111 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia • Ratifikasi Statuta Roma tergantung pada kebijakan dan sikap politik pemerintah • Ada keengganan dari beberapa aktor politik di Indonesia Menghadapi kendala-kendala ini disusun beberapa rekomendasi penting yang meliputi: • Media memiliki peran penting untuk mendorong proses ratifikasi Statuta Roma, dan adalah hal yang penting untuk melibatkan media dalam kerja-kerja koalisi • Pentingya publik. menyebarkan materi ICC kepada • Materi ICC akan sangat menarik dalam kuliah di universitas. Forum Dekan direkomendasikan sebagai salah satu kelompok sasaran untuk diajak 112 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia bekerjasama dalam konteks menggelar kuliah di tingkat universitas. • Di setiap propinsi, Forum RANHAM direkomendasikan sebagai kelompok sasaran untuk diajak bekerjasama untuk mendorong proses ratifikasi Statuta Roma • Pentingnya untuk bekerjasama dengan kelompok atau institusi yang menangani isu-isu perempuan Pada acara ini juga, secara resmi diluncurkan keberadaan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional sebagai langkah konkrit dari masyarakat sipil untuk mendorong ratifikasi ICC di Indonesia. Selain oleh Koalisi ini, dorongan agar Indonesia meratifikasi ICC juga dilakukan oleh Koalisi Internasional untuk ICC (CICC), sebuah koalisi internasional yang beranggotakan 2.500 organisasi. CICC meluncurkan program Kampanye Ratifikasi Universal bulan Juni 2008 dengan target Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye tersebut, CICC telah mengirimkan surat ke Presiden SBY, Menkumham dan Menlu tanggal 11 Juni 2008. Surabaya P r o s e s konsultasi publik dilanjutkan dengan FGD di Surabaya yang dilakukan pada 29 - 30 Juli 2008 dengan peserta 113 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 33 orang yang berasal dari lembaga pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil seperti: Komisi A DPRD Jatim, SBMIJatim, KPPD – Surabaya, ALHA-RAKA Syarikat-Jember, LPKP 65-Surabaya, MBH-Surabaya, BEM UWK-Surabaya, BEM FISIP Unair- Surabaya, IKOHI-Malang, Forsam – Unair, LBH-Surabaya, Repdem – Jatim, Tim Advokasi TNI/ Polri, Lakpesdam NU – Sumenep, AGRA – Jatim, Walhi – Jatim, CRCS, AJI Surabaya, Staff Pengajar HI FISIP Unair, Korban Alas Tlogo – Pasuruan. Fokus utama proses FGD adalah mengenai bagaimana mekanisme ICC dapat diimplementasikan dalam kasuskasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah lokal. Meskipun pelanggaran HAM masa lalu tidak termasuk dalam jurisdiksi ICC, meratifikasi Statuta Roma merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai affirmative action untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi lagi dimasa yang akan datang. Adapaun untuk mengawal proses diskusi dihadirkan narasumber Agung Yudhawiranata (Tim ahli – ELSAM), Riawan Adi (Ahli Hukum Pidana) dan R. Herlambang Perdana (Dosen Hukum dan HAM, Universitas Airlangga). Dalam proses ini dihasilkan kesepakatan umum bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Artinya selain segera meratifikasi Statuta Roma, pemerintah juga harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terutama kasus-kasus yang terjadi di Jawa Timur. Organisasi lokal juga memiliki 114 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia komitmen untuk mendesak pemerintah daerah untuk mendeklarasikan bahwa mereka mendukung pemerintah pusat di Jakarta untuk meratifikasi Statuta Roma. Hal senada juga terjadi dalam proses konsultasi publik yang dilakukan di Makassar pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2008, di Aceh pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2008 dan di Medan pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2008. Papua Proses konsultasi publik yang dilakukan oleh koalisi di Papua dilaksanakan pada 29-30 Agustus 2008 dalam bentuk diskusi publik dan workshop. Banyaknya kasuskasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua juga karena alasan sebaran representasi geografis menjadikan Papua salah satu daerah yang wajib masuk dalam daftar daerah yang perlu dikunjungi dalam proses mendorong ratifikasi. Sebagaimana pula konsultasi yang dilakukan di daerah 115 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia lain, di Papua peserta berasal dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, pemerintahan daerah, akademisi dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berjumlah kurang lebih enam puluhan. Selain perwakilan dari sekretariat koalisi masyarakat sipil untuk ratifikasi Statuta Roma, hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi publik tersebut Bruder Budi Hermawan dari Serikat Keadilan Perdamaian dan Harry Martubong dari Kontras Papua. Kegagalan menghadirkan Dirjen HAM Dephukham dan Ketua Komnas HAM dalam diskusi ini menyebabkan banyak peserta diskusi kecewa karena tidak bisa mendapatkan kepastian resmi sejauh apa proses ratifikasi di pemerintah sudah berjalan dan bagaimana komitmen sesungguhnya dari pemerintah baik terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun paska ratifikasi. Banyaknya kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terungkap menyeret arah diskusi kepada manfaat ratifikasi ICC terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu tersebut. Fakta bahwa ICC hanya memiliki yurisdiksi paska ratifikasi, jelas menimbulkan kekecewaan dari sebagian besar peserta utamanya dari keluarga korban yang semula sangat berharap akan mendapat manfaat langsung terhadap ratifikasi ICC. Dalam diskusi bahkan sempat muncul pernyataan bahwa ratifikasi sama sekali tidak perlu dilakukan jika memang tidak ada korelasi langsung dengan penyelesaian kasus-kasus HAM yang selama ini terjadi di Papua. Karena banyaknya perbedaan opini selama diskusi, dan sulitnya mengontrol berkembangnya isu selama diskusi berlangsung, sekretariat mengambil pendekatan yang berbeda dengan tidak menyimpulkan hasil diskusi 116 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia tapi memetakan kekhawatiran dan harapan peserta dari ratifikasi Statuta Roma. Kekhawatiran dan harapan tersebutlah yang kemudian dikemas menjadi pernyataan bersama peserta diskusi untuk mendorong ratifikasi. Harapan dan kekhawatiran yang berhasil direkam selama proses berlangsung tersebut adalah sebagai berikut: Harapan Kekhawatiran 1. Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma 2. Keuntungan Indonesia apabila ratifikasi Statuta Roma tercapai 3. Jaringan masyarakat sipil di setiap propinsi di Indonesia segera bekerja 4. Peraturan yang lebih baik untuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk korban pelanggaran HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM 5. Perlindungan yang lebih baik agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang 1. 2. 3. 4. Konsistensi pemerintah dalam proses ratifikasi Pemerintah sering mengulurulur waktu dalam proses ratifikasi ICC memiliki prinsip tidak berlaku surut sehubungan dengan pelanggaran HAM masa lalu Masalah dalam implementasi ICC dalam prosedur hukum nasional Harapan yang muncul dan paling banyak diungkapkan adalah bahwa ratifikasi Statuta Roma agar segera dilakukan. Dari ratifikasi inilah nantinya keuntungankeuntungan lainnya bisa didapatkan yang dapat mendorong perbaikan proses peradilan di Indonesia yang kemudian berujung pada berkurangnya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Perbaikan yang dimaksud termasuk pula perbaikan terhadap sistem kompensasi, 117 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia restitusi dan rehabilitasi yang masih sangat tidak berpihak pada korban. Dalam proses mendorong ratifikasi tersebut, peserta juga berharap agar jaringan kerjasama masyarakat sipil antardaerah dapat segera terwujud untuk memperkuat dorongan pada pemerintah agar segera melakukan ratifikasi. Disisi lain ada banyak kekhawatiran yang muncul dari peserta terkait proses ratifikasi yang paling menonjol adalah bahwa proses ratifikasi sendiri tidak dilakukan dengan serius oleh pemerintah. Dalam proses tersebut pemerintah terlihat mengulur-ngulur waktu untuk melakukan ratifikasi dan tidak konsisten terhadap kebijakan pemerintah sendiri yang sudah mencanangkan proses ratifikasi di Tahun 2008 tapi belum juga dilakukan bahkan belum ada persiapan sama sekali. Kekhawatiran lainnya adalah terkait relasi ratifikasi dengan kasus-kasus HAM berat masa lalu yang tidak memiliki kaitan langsung. Seolah-olah kasus-kasus HAM yang selama ini belum terselesaikan tersebut sudah terlupakan dan tidak lagi penting. Selain itu dikhawatirkan implementasi UU ratifikasi tidak ada sebagaimana praktek yang banyak muncul dari ratifikasi konvensi-konvensi internasional lainnya. Karenanya, salah satu poin penting yang dimunculkan dalam pernyataan bersama adalah terus diusutnya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. 118 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Kampanye publik Selain melakukan proses konsultasi publik, aktivitas kampanye diyakini akan memberikan kontribusi besar dalam menggalang dukungan masyarakat untuk mendorong proses ratifikasi ICC di Indonesia. Berbagai seminar dan diskusi publik dilakukan dalam kerangka tersebut. Dan untuk semakin meluaskan kampanye, dilakukan berbagai talk-show radio jaringan nasional dengan harapan dapat menjangkau publik yang lebih luas. Gambaran proses kampanye publik disajikan sebagai bahan refleksi atas upaya yang dilakukan untuk menggalang dukungan publik. Untuk mendukung kerja kampanye ratifikasi, Koalisi juga memproduksi kampanye material, 119 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia diantaranya adalah penerbitan buku saku ICC yang berisi informasi dasar mengenai apa dan bagaimana mekanisme ICC. Buku saku ini dibuat dalam format pertanyaan dan jawaban dengan cara penulisan yang populer. Buku saku berisi informasi dasar mengenai ICC disebarakan kepada publik dan institusi pemerintah. Selain itu, Koalisi juga memproduksi pin, tas dan block-note yang dibagiakan pada seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Koalisi. Seminar Nasional Seminar nasional sebelumnya direncanakan akan digelar di Jakarta. Dengan beberapa pertimbangan diantaranya untuk mengumpulkan lebih banyak lagi dukungan untuk ratifikasi Statuta Roma dari lebih banyak stakeholder diluar Jakarta, koalisi memutuskan untuk menggelar seminar nasional di Yogyakarta. 120 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (PusHAM UII), seminar dilaksanakan pada 6 April di Plaza Hotel Jogyakarta dengan topik “Tantangan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia pasca Pemilu 2009”. Pembicara dalam seminar nasional ini adalah Ifdhal Kasim dari Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab dari ELSAM, Bhatara Ibnu Reza salah satu tim ahli dari koalisi dan Abdul Haris Semendawai dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). T Kurang lebih 100 orang partisipan dari beberapa aparat pemerintah, penegak hukum, NGO, akademisi, mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam seminar nasional ini. Pada bagian akhir seminar, partisipan bersepakat bahwa siapapun yang terpilih pada Pemilu 2009 seharusnya lebih memperhatikan penegakan HAM dalam rangka meningkatkan demokrasi sejati di Indonesia. Salah satu kerja untuk membuat hal tersebut tercapai adalah dengan 121 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia meratifikasi perjanjian internasional atau mekanisme internasional, dimana salah satunya adalah Statuta Roma ICC. Talk-show Radio Talk show radio dikemas sebagai media menyebarkan informasi mengenai pentingnya ratifikasi Statuta Roma dan isu-isu terkait kepada publik. Koalisi mengadakan aktivitas ini dengan bekerjasama dengan KBR 68H dan VHRmedia (Voice of Human Rights). Beberapa proses dan hasil talkshow akan dideskripsikan dibawah ini. Diskusi radio dengan tema “Pentingnya Ratifikasi ICC di Indonesia” ini bekerjasama dengan KBR 68H. Diskusi radio ini diadakan di Olive Tree Restaurant, Hotel Nikko dengan menghadirkan pembicara Mugiyanto (IKOHI), 122 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Djoko Susilo (Komisi I DPR RI), dan Riyawan Pramudjo (Direktur HAM, Ditjen HAM-Depkumham RI). Kegiatan ini mengundang beberapa wartawan dan masyarakat umum. Selain itu memang diharapkan ada respon dari pendengar KBR 68H yang menanggapi materimateri yang dibawakan dari pembicara. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum dapat mengenal lebih jauh mengenai ICC dan merasa penting untuk mendukung ratifikasi ICC, karena jelas mekanisme mahkamah pidana internasional ini akan berpengaruh besar pada kehidupan demokrasi di Indonesia dan akan mencegah kasus-kasus pelanggaran HAM di kemudian hari. Kegiatan diskusi radio ini, selain dipublikasikan oleh KBR 68H, juga dipublikasikan oleh Koran TEMPO pada tanggal 26 Juni 2008. Dari diskusi radio ini memang diketahui bahwa ada komitmen pemerintah, khususnya Depkumham, untuk segera meratifikasi ICC. Proses ratifikasi ICC yang dilakukan 123 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia oleh Depkumham sedang dalam tahap pengkajian oleh tim Litbang Depkumham. Namun sesungguhnya pengajuan draft ratifikasi ICC ini sudah harus diserahkan kepada DPR pada tahun 2008. Karena hal ini tertuang dalam RANHAM 2004-2009 yang menyatakan Indonesia akan meratifikasi ICC pada tahun 2008. Namun kelemahannya adalah tidak semua pejabat Negara yang berwenang dalam ratifikasi ICC ini memahami secara jelas mengenai mekanisme ICC. Bahkan menurut Djoko Susilo, di Komisi III, komisi yang berhubungan langsung dengan Depkumham, belum tentu memahami mengenai mekanisme ICC. Maka dari itu, harus segera dibuat sebuah kegiatan untuk mensosialisasikan mekanisme ICC ini kepada anggota parlemen, khususnya anggota Komisi III. Karena tentunya pemahaman yang tidak jelas terhadap mekanisme ICC akan menghambat berjalannya proses ratifikasi ICC di tingkat parlemen. 124 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Masyarakat umum yang mendengarkan diskusi ini melalui radio juga mendesak agar pemerintah dan parlemen bekerja secara serius dalam meratifikasi ICC ini. Karena dari tanggapan masyarakat, mereka merasa bahwa proses ratifikasi ICC ini akan dapat mencegah terjadinya kasuskasus pelanggaran HAM dan menjadi sebuah pembelajaran demokrasi di Indonesia. Selain rangkaian diskusi radio reguler, Koalisi juga menyelenggarakan diskusi radio pada momen-momen yang berhubungan dengan ICC. Sebagai contoh adalah pada momen peringatan Hari Keadilan Sedunia. Pada momen peringatan ini Koalisi juga menyelenggarakan diskusi Radio dengan tema “ World Day of International Justice dan Ratifikasi ICC di Indonesia” diadakan di Kedai Tempo pada tanggal 10 Juli 2008. Diskusi kali ini menghadirkan pembicara Agung Yudhawiranata (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional), Hakristuti Hakrisnowo (Dirjen HAM Depkumham) dan Ifdal Kasim (Komnas HAM). Pembahasan dalam diskusi kali ini adalah tentang World Day of International Justice yang diperingati sebagai hari ditetapkannya Statuta Roma pada tanggal 17 Juli. Diskusi tersebut membahas mengenai mengapa hari tersebut begitu bersejarah bagi keberlanjutan keadilan di dunia dan pentingnya Statuta Roma tersebut bagi kehidupan berkeadilan. Karena Statuta Roma tersebut adalah cikal bakal dari terbentuknya sebuah mekanisme permanen untuk mengadili para pelaku. 125 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Penyusunan Kertas Posisi dan Naskah Akademis Sesuai dengan alur dan pembagian kerja, tim ahli bertanggungjawab penuh untuk membuat draft dan menyelesaikan material pendukung ICC, seperti: kertas posisi, naskah akademik dan draft RUU ratifikasi yang nantinya akan didistribusikan dan dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, tim ahli menggelar beberapa pertemuan untuk mengatur pembagian kerja. Pada pertemuan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2008 disepakati mengenai pembagian dan penanggungjawab kerja dalam rangka mengumpulkan referensi untuk kertas posisi dan naskah akademis. Selanjutnya tim mulai bekerja dan melakukan berbagai pertemuan koordinasi. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 2009, tim berhasil menyelesaikan kertas posisi dan mempublikasikannya untuk mendukung kampanye pentingnya ratifikasi Statuta Roma di Indonesia. Kertas posisi ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa inggis untuk kepentingan kampanye internasional. Materi kampanye ini telah didistribusikan ke beberapa institusi dan publik, contohnya: dalam seminar dan diplomatic briefing yang diadakan oleh Kedutaan Besar Swiss pada 28 Agustus 2008 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Beberapa partisipan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Kedutaan Jerman, Kedutaan Belanda, Kedutaan Kanada, Kedutaan Australia, Kedutaan Afrika Selatan, Kedutaan Swiss, Kedutaan Inggris, Uni Eropa, IALDF, AusAID, United Nation, dan ICRC. Sementara itu, proses pembuatan naskah akademik dan draft RUU Ratifikasi Statuta Roma dimulai pada pertemuan tim ahli sehari penuh yang dilaksanakan pada 126 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia bulan Agustus 2008 di Imparsial dan dilanjutkan dengan pertemuan sehari penuh di Elsam pada bulan November 2008. Dalam pertemuan-pertemuan ini, tim ahli membuat draft naskah akademik dan draft RUU Statuta Roma dan mendistribusikan naskah tersebut kepada tim ahli adhoc seperti: Enny Suprapto, Fadillah Agus, Ifdhal Kasim, Kemala Chandrakirana dan Rudi Rizky untuk mendapatkan komentar dan masukan. Dengan saran yang diberikan oleh tim ahli ad-hoc: Enny Suprapto dan Fadillah Agus, serta pembaca: Ifdhal Kasih – Komnas HAM yang menyarankan kepada koalisi untuk mengembalikan isu ICC ke area hukum kriminal dan tidak terlalu mengedepankan pelanggaran HAM masa lalu, dan revisi untuk naskah akademik final selesai pada 7 februari 2009 dalam pertemuan lain tim ahli di Aston Residence Jakarta. Dalam naskah akademis final, koalisi memberi penjelasan lebih lanjut mengenai keuntungan ratifikasi Statuta Roma untuk Indonesia, misalnya seperti perlindungan buruh migran dan misi menjaga perdamaian. Workshop Bersama Parlemen 127 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Workshop bersama dengan anggota DPR dilaksanakan di gedung DPR pada 17 Februari 2009 dengan bekerjasama dengan Parliament for Global Action (PGA) dengan tema “ICC: Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma”. Workshop ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman anggota DPR mengenai ICC dan mendorong DPR untuk bekerja bersama koalisi dalam proses ratifikasi ICC di Indonesia. Workshop ini dilaksanakan bersamaan dengan kedatangan delegasi internasional yang dipimpin oleh Senator Kanada Ms. A. Raynell Anreychuk (ketua, Komite HAM) dan Australia MP Ms. Melissa Parke (Ketua, Komisi Australia untuk integritas Penegakan Hukum). Workshop tersebut dibuka oleh ketua PGA Indonesia Dr. Theo Sambuaga dan dilanjutkan dengan pembicara kunci Mr. John Holmes, Duta Besa Kanada untuk Indonesia, yang menyatakan bahwa jurisdiksi ICC adalah tidak berlaku surut, bersifat komplemener terhadap hukum nasional dan ICC didesign untuk memperkuat sistem hukum nasional, dimana di dalamnya terdapat tanggungjawab utama untuk menyeret pelaku kejahatan serius untuk dihukum secara adil. 128 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Pembicara selanjutnya adalah, Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen HAM DepkumHAM) yang menjelaskan bahwa pemerintah telah terikat secara inklusif dengan proses konsultasi dan legal drafting ratifikasi ICC,. Pemerintah juga sangat memahami bahwa batas waktu tahun 2008 untuk meratifikasi Statuta Roma telah lewat dan sekarang naskah akademis harus menjadi prioritas. Pembicara dari pihak koalisi, Reny Rawasita Pasaribu, menekankan mengenai dukungan dari masyarakat sipil kepada pihak pemerintah dan DPR untuk meratifikasi ICC. Sementara Marzuki Darusman menyatakan bahwa ratifikasi Statuta Roma harus disepakati di DPR antara bulan Mei dan Juni 2009. Pernyataan Marzuki Darusman dipertegas oleh Partrice Morin dengan pernyataan: “DPR harus membuat perubahan dalam legislatif, dan ICC hanyalah masalah waktu saja” Pada momentum ini juga, sebagai tanggapan atas percepatan yang terjadi di DPR, koalisi membuat pernyataan pers yang menekankan pada: • Pemerintah berkomitmen untuk meratifikasi ICC sebelum pemilihan DPR baru 2009-2014. Dari perspektif pemerintah, ratifikasi Statuta Roma akan memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia • Pertanyaan-pertanyaan mengenai kerahasiaan tidak lagi menjadi hal yang penting, mengingat ICC memberikan jaminan hukum yang berlaku secara universal bagi semua orang. 129 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Lobby dan Audiensi Audiensi dengan DPR Audiensi dengan DPR, khususnya dengan Komisi I dan Komisi III yang berhubungan dengan isu ICC adalah kegiatan penting dalam mendukung percepatan ratifikasi Statuta Roma. Sehubungan dengan tujuan ini, koalisi menghadiri pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III pada 26 Mei 2009 dan dengan Komisi I pada 10 Juni 2009. Dalam pertemuan dengan Komisi III yang difasilitasi oleh Suripto, Nasir Djamil (keduanya dari Partai Keadilan Sejahtera) dan Yudho Paripurno (PPP), Komisi III memberikan komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma dan berencana untuk menggunakan Hak Inisiatif antar seluruh anggota Komisi III. Pada 10 Juni 2009, koalisi mengadakan pertemuan dengan Komisi I yang difasilitasi oleh Theo Sambuaga (Ketua Komisi I), Marzuki Darusman dan Sidharto Danusubroto (PDIP). Komisi I juga memberikan komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma dan memajukan beberapa isu “sensitif” yang berhubungan dengan ICC seperti: • Prosedur legislatif: naskah akademis dan draft RUU ratifikasi ICC • Salah satu kemungkinan yang dihadapi oleh pemerintah yang belum selesai adalah naskah akademis dan RUU. Di beberapa kesempatan, Dirjen HAM menyatakan telah membuat tim dan mencoba untuk menyelesaikan dua dokumen tersebut. Namun kenyataannya sampai April 2009 perkembangannya masih belum jelas. 130 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia • Fakta bahwa naskah akademis dan RUU, sebagai satu kondisi untuk mempercepat ratifikasi, belum selesai dan harapan untuk ratifikasi pada tahun 2009 masih sangat jauh dari kenyataan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, pertama, adalah hal yang penting untuk menyebarkan naskah akademik dan draft RUU kebeberapa departemen dan kepada publik untuk mendapatkan masukan; kedua, membuat sinkronisasi dengan kebijakan lain yang akan dibuat oleh Dirjen Perundang-undangan Depkumham untuk kemudian ditandatangani oleh Mentri Hukum dan HAM. • Isu kedaulatan dan harmonisasi hukum • Ada dua isu besar yang muncul dalam ratifikasi di Indonesia. Mengenai jurisdiksi ICC dan harmonisasi dengan peraturan nasional yang telah ada. ICC memiliki prinsip tidak berlaku surut, hal tersebut yang tidak banyak diketahui, sehingga hal tersebut menciptakan ketakutan bahwa dengan ratifikasi akan mengarah pada penghukuman perwira TNI yang telah melakukan pelanggaran HAM dimasa lalu. Meskipun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono telah memiliki perspektif yang jelas mengenai posisi dan implikasi ICC, namun tetap saja ada ketakutan mengenai hubungan ICC dengan pengadilan nasional (mekanisme domestik). Prinsip ini jelas penting sebagai antisipasi isu kedaulatan nasional yang sering dimunculkan oleh beberapa ahli hukum. • Isu harmonisasi ICC dengan sistem hukum nasional, sebagai contoh, seperti yang tampak pada kehadiran UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 131 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Beberapa pihak melihat bahwa Indonesia telah mengakomodir dua kejahatan intenasional dalam UU tersebut, kejahatan melawan kemanusiaan dan genosida. Seperti hukum perang, hal tersebut bisa dibawa ke pengadilan internasional. • Isu “tidak mau dan tidak mampu” • Isu “tidak mau dan tidak mampu” dalam konteks mekanisme pengadilan nasional dimunculkan oleh pihak militer dalam hubungannya dengan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang telah diadili di pengadilan HAM adhoc seperti kasus Timor Leste, Tanjung Priok dan Penghilangan Paksa Aktivis 1998. Penjelasan atas intervensi ICC dalam mekanisme nasional dibutuhkan untuk mempengaruhi pihak militer dan DPR bahwa terminology “tidak mau dan tidak mampu” sangat mudah untuk dilaksanakan oleh prosecutor ICC dan telah memiliki mekanisme yang sangat jelas untuk dijalankan. Selain pertemuan-pertemuan formal yang digelar, koalisi juga secara rutin menghubungi para anggota DPR terutama anggota PGA Indonesia seperti: Nursyabani Katjasungkana, Marzuki Darusman, Theo Sambuaga, untuk mendiskusikan dan berbagi infomasi tentang perkembangan isu ICC. Pertemuan dengan Depkumham Koalisi Masyarakat SIpil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional mengadakan audiensi dengan Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen HAM) pada tanggal 27 Maret 2009. Dalam pertemuan tersebut, 132 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia ibu Harkristuti Harkrisnowo menyoroti perlunya para akademisi bicara mengenai sinkronisasi Statuta Roma ICC dengan mekanisme hukum nasional. Dirjen HAM juga menjelaskan keuntungan apabila akademisi mendukung untuk proses ratifikasi, khususnya untuk meyakinkan pihak militer dan pemerintah dalam isu ratifikasi. Selain itu, pertemuan juga menghasilkan beberapa poin: 1. Dalam perkembangan di Depkumham, terjadi koordinasi antara Dirjen HAM dengan BPHN untuk mendiskusikan naskah akademik dan draft RUU ratifikasi Statuta Roma 2. Ada masalah yang timbul sehubungan dengan sikap Departemen Luar Negeri yang menyatakan bahwa ratifikasi harus menunggu sinkronisasi dengan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ICC 3. Koalisi telah menyerahkan naskah akademis dan draft RUU Ratifikasi Statuta Roma kepada Dirjen HAM dan akan terus mendukung proses dalam Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan proses ratifikasi ICC. Pertemuan dengan Komnas HAM Untuk mendukung proses ratifikasi, pertemuan dengan Komnas HAM diperlukan karena Komnas HAM adalah salah satu stakeholder dalam isu ini. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan dukungan dari Komnas HAM sebagai salah satu lembaga pemerintah dalam proses ratifikasi. 133 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Pertemuan pertama dengan Komnas HAM dilaksanakan pada 23 Juni 2008 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Ifdal Kasim (Komnas HAM), Evelyn (CICC), Mugiyanto, Agung Yudha, Bhatara Ibnu Reza, Reny Rawasita Pasaribu, Zainal Abidin, Ari Yurino dan Veronica Iswinahyu dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional. Sebagai kesimpulan pertemuan, Komnas HAM sepakat untuk mendukung secara aktif kerja-kerja yang dilakukan untuk meratifikasi Statuta Roma ICC di Indonesia. Pertemuan kedua dengan Komnas HAM dilaksanakan pada 18 Februari 2009 di kantor Komnas HAM. Pertemuan dihadiri oleh Ifdal Kasim (Komnas HAM), Fadillah Agus (tim ahli Ad-hoc), Enny Soeprapto (tim ahli Ad-hoc), Zaenal Abidin, Simon dan Agung Yudhawiranata (Koalisi). Beberapa hasil pertemuan adalah: 1. Komnas HAM dalam waktu singkat akan mengeluarkan kertas posisi mengenai Statuta Roma yang akan sangat berguna sebagai materi lobby kepada Deplu dan Depkumham 2. Komnas HAM akan mengadakan seminar publik dengan Menteri Hukum dan HAM dalam upaya mendorong proses ratifikasi Statuta Roma 3. Sehubungan dengan kerja Komnas HAM dalam revisi UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM, ratifikasi Statuta Roma masih dapat berjalan, mengingat perdebatan mengenai prinsip komplimenter dapat melindungi prinsip retroaktif dalam hukum pengadilan HAM 134 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Roundtable discussion bersama Mr. Song Sang-hyun (President ICC) Presiden ICC Song Sang-hyun mengunjungi Indonesia pada 28 April 2008. Koalisi mendapatkan kesempatan untuk mengadakan diskusi komprehensif dengan Song Sang-hyun. Pertemuan diadakan di Hotel Millenium Sirih – Jakarta dimulai pukul 14.00 – 15.30. Prof. Dr. Komariah Emong (Mahkamah Agung) dan Enny Suprapto juga terlibat dalam diskusi ini. Setelah koalisi mempresentasikan perkembangan proses ratifikasi di Indonesia, Mr. Song mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia sangat penting karena ICC mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh di dunia, Indonesia harus menjadi bagian ICC. Kedatangan presiden Song juga untuk mendorong Indonesia, yang di sebut 135 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia sebagai negara yang “penting” dan “berpengaruh” untuk menyelesaikan proses ratifikasi, dimana Mr. Song telah diberitahu bahwa hal tersebut akan diselesaikan tahun lalu. Media juga diundang dalam aktivitas ini, diantaranya adalah: Jakarta Post, Vivanews dan Voice of Human Rights. Selama kedatangan presiden, banyak sekali peliputan media dan mereka sangat berguna bagi perkembangan proses ratifikasi di Indonesia. Pertemuan dengan Mr. Rod Rastan dari kantor Prosecutor – ICC Pada 9 juni 2008 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Depkumham menggelar FGD bersama Mr. Rod Rastan dari Kantor Prosecutor Jurisdiction – ICC sebagai salah satu pembicara kunci dalam diskusi mengenai Statuta Roma yang memfokuskan pada pengalaman empiris ICC dalam mendorong jurisdiksi tersebut selama 7 tahun belakangan. Tujuan dari pertemuan ini juga untuk mendapat masukan atas draft naskah akademik ratifikasi Statuta Roma yang sedang disusun oleh Departemen Hukum dan HAM. Untuk merespon kedatangan Rod Rastan ini, Koalisi menggelar pertemuan untuk memberikan masukan dan penjelasan kepada Mr. Rastan sehubungan dengan perkembangan terakhir dari proses ratifikasi dan persoalan yang dihadapi. Pertemuan ini digelar sebagai input dari masyarakat sipil untuk Mr. Rastan. 136 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia Catatan Akhir Program Indonesia Menuju Ratifikasi ICC merupakan inisiatif masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam reformasi hukum dan mempromosikan perlindungan HAM di Indonesia. Dari persepsi masyarakat sipil, ratifikasi Statuta Roma ICC diyakini akan meningkatkan mekanisme hukum di Indonesia, khususnya untuk mekanisme pidana, juga untuk menangani pelanggaran berat HAM di Indonesia. Sejalan dengan tujuan fundamental dari Statuta Roma ICC, masyarakat sipil percaya bahwa ratifikasi dan implementasi ICC akan mengakhiri praktek impunitas di Indonesia Sehubungan dengan tujuan ini, pemerintah Indonesia telah memiliki tekad untuk meratifikasi ICC Statuta Roma sejak 2004 dengan memasukkan Statuta Roma dalam RANHAM 2008. Lembaga negara atau institusi negara yang berhubungan dengan menyoroti komitmen ini dengan pernyataan yang sering disampaikan oleh lembagalembaga pemerintahan. Namun sangat disayangkan, sampai pada akhir kabinet SBY-JK pada 2009, tidak ada realisasi atas komitmen mengenai ratifikasi. Secara umum, strategi dan implementasi aktivitas koalisi menghasilkan beberapa perkembangan untuk memajukan proses ratifikasi Statuta Roma ICC khususnya dalam hal kampanye publik dan pembukaan jalur komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan pengamatan dalam proses program, hambatan dan dan posisi para stakeholder dapat dideskripsikan sebagai berikut: 137 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Masalah Naskah Akademis dan Draft RUU ratifikasi Statuta Roma Dukungan dari DPR Resistensi dari institusi militer Pendapat dari Akademisi Posisi Menteri Luar Negeri Posisi Politik Presiden Deskripsi Naskah Akademis dan Draft RUU Ratifikasi Statuta Roma yang diterima oleh pemerintah seharusnya diproduksi oleh Kementrian untuk diberikan kepada presiden dan diajukan kepada DPR DPR, Komisi I dan Komisi III, memberikan komitmen yang besar untuk ratifikasi Insitusi militer masih memiliki keengganan dalam ratifikasi Statuta Roma. Pendapat dari akademisi merupakan salah satu elemen kunci dalam proses ratifikasi. pada harihari terakhir, beberapa akademisi memiliki keberatan dengan ratifikasi Statuta Roma dengan berbagai mancam argumentasi Menteri Luar negeri merupakan salah satu focal point dalam proses ratifikasi Statuta Roma, namun bersikap pasif. Posisi politik presiden sehubungan dengan Ratifikasi Statuta Roma masih belum jelas. Stakeholders/ Aktor Mentri Hukum dan HAM Komisi I dan Komisi III Anggota PGA di Indonesia seperti: - - - - - - Marzuki Darusman Theo Sambuaga Nursyahbani K Djoko Susilo Menteri Pertahanan MABES TNI Akademisi hukum terkemuka di Indonesia Menteri Luar Negeri Presiden Berdasarkan pemetaan hambatan dan pemetaan aktor serta pencapaian program dan perkembangan terakhir, 138 Rekam Proses Peran Masyarakat Sipil dalam Upaya Mendorong Ratifikasi Statuta Roma Di Indonesia upaya untuk meneruskan dan mengembangkan inisiatif masyarakat sipil untuk mendorong ratifikasi Statuta roma di Indonesia masih diperlukan. Upaya kedepan ini minimal meliputi beberapa area kerja, diantaranya: • Penyebaran isu ratifikasi Statuta Roma ditingkatan publik untuk semakin menggalang dukungan yang kuat untuk meyakinkan pemerintah RI. • Mendukung dan memfasilitasi proses dan membuat Naskah Akademis dan Draft RUU ratifikasi pada Menteri Hukum dan HAM serta DPR • Menginisiasi dan menjaga dukungan dari akademisi untuk mendukung ratifikasi Statuta Roma • Melakukan pendekatan dan memfasilitasi penyebaran prinsip-prinsip Statuta Roma kepada institusi militer untuk mengatasi keengganan mengenai Statuta Roma ***** 139 Beberapa Pelajaran yang Bisa Dipetik Mugiyanto Segera setelah Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional disahkan dalam sebuah Konferensi Diplomatik di Roma, Italia pada tanggal 17 Juli 1998, beberapa NGO hak asasi manusia, lembaga akademik dan pemerintah di Indonesia telah melakukan kerja-kerja pengkajian dan advokasi agar Indonesia menjadi negara pihak (state party) dari ICC. Pekerjaan tersebut terus berlangsung, dan semakin intens ketika ICC enter into force pada tahun 2002, ketika 60 negara telah meratifikasinya. Tidak hanya di tingkat nasional, kerja-kerja pengkajian dan advokasi juga dilakukan dengan terlibat dan melibatkan komunitas internasional, baik itu pihak ICC sendiri yang berkedudukan di Den Haag negeri Belanda, maupun dengan koalisi internasional untuk ratifikasi dan implementasi ICC, International Coalition on International Criminal Court (CICC) yang juga berkedudukan di Den Haag dan New York, Amerika Serikat. Beberapa seminar, workshop dan konferensi digelar di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Beberapa pakar hukum internasional dan 141 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia aktifis HAM juga terlibat secara aktif dalam beberapa forum internasional, termasuk dalam menghadiri sidang Majelis Negara Pihak (Assembly of States Party – ASP) baik di Den Haag maupun di New York. Berawal dari pekerjaan-pekerjaan dan aktifitas inilah, dalam sebuah workshop di Jakarta pada bulan Juni 2008 didirikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. Beberapa lembaga yang menjadi inisiator pembentukan Koalisi ini adalah Elsam, Imparsial, YLBHI, PSHK dan IKOHI, yang kemudian meluas dan melibatkan ratusan lembaga dan individu yang menaruh perhatian pada reformasi sistem hukum, penegakan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Pembentukan Koalisi ini didasari kebutuhan untuk mensinergikan langkah dan gerak lembaga-lembaga dan individu-individu yang berada di dalamnya agar usaha untuk memastikan Indonesia meratifikasi ICC menjadi lebih kuat dan efektif. Terbukti, tak lama setelah Koalisi berdiri, proses pengkajian, diseminasi informasi, kampanye dan advokasi tentang ICC berjalan di hampir seluruh propinsi di Indonesia, dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik elemen masyarakat sipil maupun pemerintah dan parlemen. Dalam proses ini, Koalisi bahkan bisa berjalan beriringan dengan focal point pemerintah untuk persiapan ratifikasi ICC, yaitu Depkumham dan Deplu dengan cukup baik. Dalam masa kerja yang belum genap 2 tahun, Koalisi telah menerbitkan buku saku tentang ICC, kertas kerja (lobby paper), serta Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Ratifikasi ICC yang kesemuanya sudah diserahkan ke focal point pemerintah untuk menjadi sandingan dokumen yang akan dibuat pemerintah, sebelum nantinya diajukan ke DPR untuk disahkan. 142 Beberapa Pelajaran yang Bisa Dipetik Sebagai anggota CICC, Koalisi setidaknya telah 3 kali menghadiri Sidang Majelis Negara Pihak (ASP) di Den Haag dan New York, dimana laporan perkembangan ICC, penanganan-penanganan kasus (situasi) dan perdebatanperdebatan mengenai partisipasi korban, keadilan jender, kejahatan agresi dan lain-lain terjadi. Secara paralel, lobilobi untuk mendapatkan dukungan internasional juga dilakukan oleh delegasi Koalisi dalam forum tersebut. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2007 CICC menggelar Strategy Meeting di Jakarta, yang pada saat yang sama melakukan lobi kepada pemerintah dan DPR. Bahkan pada bulan Juni 2009, Indonesia dijadikan sasaran Universal Ratification Campaign (URC) CICC. Universal Ratification Campaign adalah strategi kampanye CICC yang diluncurkan tiap bulan dengan menyasar satu negara untuk menjadi sasaran lobi dan kampanye ratifikasi. Untuk tujuan tersebut, ratusan surat dari CICC dan lembaga-lembaga HAM internasional terkemuka dikirimkan ke President. Tidak hanya itu, secara informal, Jaksa Penuntut (Chief Prosecutor) ICC, Luis Moreno Ocampo dan Hakim Ketua (Chief Judge), Judge Song Sang-hyun juga berkunjung ke Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 untuk bertemu dengan pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk dengan Koalisi. Di tingkat parlemen, pada tahun 2008 juga terbentuk Parliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapter, yang salah satu fokus utamanya adalah mempersiapkan proses ratifikasi ICC. Sayangnya, anggota PGA yang sudah sangat terbuka dan mendukung ratifikasi ICC ini tidak bias melakukan banyak hal, karena prosesnya tengah dijalankan oleh pemerintah. 143 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Dalam kegiatan sosialisasi, kampanye dan advokasi ICC di Indonesia, Koalisi mendapatkan banyak sekali masukan dan dukungan dari dari masyarakat sipil, terutama dari kalangan aktifis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM. Akan tetapi, tantangan masih sangat besar, karena ICC masih merupakan hal baru dalam dunia penegakan HAM, sehinga masih sering disalahartikan dengan Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ), termasuk minimnya pemahaman mengenai jurisdiksi dan kewenangannya. Hal lain yang juga ditemukan dalam proses ini adalah masih belum nyaringnya suara-suara kalangan akademisi dan ahli hukum internasional yang sejalan dengan semangat perlunya Indonesia bergabung dalam rejim keadilan global ini. Suara yang kerap muncul justru dari kalangan ahli hukum konservatif, yang melihat ICC sebagai ancaman, dan bukan sebagai peluang bagi perbaikan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai penutup, rencana ratifikasi tahun 2008 memang sudah terlewati. Tetapi proses tetap berjalan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai focal point masih terus menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, untuk kemudian diajukan ke DPR untuk persetujuan. Namun nampaknya proses ini tidak berjalan terlalu mulus. Ada indikasi, beberapa pihak terutama di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI masih belum nyaman dengan ICC. Isu kedaulatan nasional dan potensi intervensi asing, serta jurisdiksi ICC atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu nampaknya dijadikan sebagai argumen bahwa Indonesia belum siap menjadi negara pihak. Namun, ada argumen lain yang nampaknya juga dijadikan alasan penundaan ratifikasi yang mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi ICC karena sudah ada 144 Beberapa Pelajaran yang Bisa Dipetik UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebuah argumen gegabah dan menyesatkan. Presiden SBY yang tengah mengemban mandat kedua diharapkan belajar dari kekurangan dan kegagalan di masa pemerintahan sebelumnya. Terlebih lagi, penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia kini semakin menjadi buah bincang pemerintah. Ratifikasi ICC tidak hanya perlu dimasukkan kembali dalam RANHAM 2010 – 2015, tetapi harus dijadikan sebagai prioritas Program Legislasi Nasional 2010. Hanya dengan begitu, Indonesia akan benar-benar membuktikan dirinya sejajar dengan negara-negara beradab lain yang telah menjadi bagian dari sistem keadilan internasional. Dan Koalisi, bersama kelompok masyarakat sipil lainnya akan terus mengawal dan mendampingi proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah. 145 Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Disusun Oleh: Elsam-Imparsial-IKOHI-PSHK-YLBHI BAB I Latar Belakang Masalah A. Latar Belakang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (MPI) Empat Pengadilan Pidana Ad Hoc Internasional telah dibentuk selama abad ke-20 yakni; International Military at Nuremberg, Tokyo Tribunal, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan International Crimminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kelebihan dan kekurangan dari keempat Mahkamah ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendirian dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court yang selanjutnya disebut sebagai MPI). Khususnya dalam Draf International Law Commission (ILC) tahun 1994 tentang MPI, mendapat pengaruh yang sangat besar dari Statuta ICTY.1 Di bawah 1 Report of the ILC on the Work of Its 46th Sess, UN GAOR, 49th Sess, Supp No. 10(A/49/10). Diambil dari Kriangsak Kittichaisaree, International Criminal Law, Oxford University Press, January, 2001, p. 27. 149 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia ini akan diuraikan secara singkat mengenai Mahkamahmahkamah Pidana Ad hoc tersebut dan berbagai kritikankritikan masyarakat internasional yang mewarnai kinerja keempat mahkamah ad hoc tersebut yang pada akhirnya bermuara pada pendirian MPI. Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg adalah sebuah pengadilan yang dibentuk oleh empat Negara pemenang perang setelah Perang Dunia II untuk mengadili warganegara Jerman. Empat Negara tersebut adalah Inggris, Perancis, Uni Soviet dan AS yang bertindak atas nama “semua negara”. Mahkamah ini telah mengadili 24 terdakwa penjahat perang Nazi di mana 3 terdakwa dibebaskan, 12 dihukum mati, 3 dipenjara seumur hidup dan 4 dihukum penjara.2 Namun, tidak semua pelaku kejahatan yang merupakan pemimpin Nazi tersebut dihadapkan ke pengadilan, bahkan kebebasan dari penghukuman yang mereka terima nampak sebagai suatu balas jasa atas apa yang telah mereka lakukan dan mereka mendapat pengampunan atas kejahatan mereka tersebut.3 Mahkamah, yang dibentuk berdasarkan perjanjian London tanggal 8 Agustus 1945 ini, juga dikritik sebagai Mahkamah bagi pemenang perang (victor’s justice) karena semua jaksa dan hakim berasal dari kekuatan sekutu, bukan dari Negara yang netral. Semua terdakwa dan pembelanya berasal dari Jerman, dan mereka mendapat fasilitas yang sangat terbatas dalam mempersiapkan kasus-kasus mereka serta mendapatkan pemberitahuan mengenai bukti-bukti penuntutan.4 Sehingga jelas Mahkamah ini bukanlah Mahkamah yang imparsial. 2 3 4 Kriangsak…ibid, p.18 Geoffrey Robertson QC, Kejahatan terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia2002, p. 252. Ibid, p.271 150 Lampiran Terlepas dari segala kekurangan dan kegagalannya, Mahkamah Nuremberg sangat berarti bagi penegakkan hak asasi manusia internasional karena telah meletakan prinsipprinsip dasar pertanggungjawaban pidana secara individu (yang tertuang dalam Nuremberg Principle). Selain itu, definsi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 6(c) Piagam Nuremberg, belum pernah ditemukan dalam Konvensi-konvensi sebelumnya. Mahkamah ini juga secara tegas menolak prinsip ‘impunitas kedaulatan negara’ seperti yang tertuang dalam pasal 7 Piagam Nuremberg. Mahkamah Internasional Timur Jauh, atau dikenal dengan Mahkamah Tokyo, juga merupakan mahkamah yang didirikan sekutu (berdasarkan deklarasi Mc Arthur) untuk mengadili penjahat perang. Julukan Victors Justice juga melekat dalam Mahkamah ini karena: Jepang tidak diijinkan untuk membawa AS ke hadapan Mahkamah Tokyo atas tindakan pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan AS, dan Jepang juga tidak diijinkan untuk mengadili Uni Soviet atas pelanggarannya terhadap perjanjian kenetralan tanggal 13 April 1941.5 Selain itu praktek impunitas juga sangat jelas terjadi dalam Mahkamah ini ketika Amerika Serikat memutuskan untuk tidak membawa Kaisar Hirohito ke meja pengadilan, tapi justru melanggengkan kedudukannya dalam Kekaisaran Jepang. 6 Hal ini sangat bertolak belakang mengingat sumbangan yang paling besar dari Pengadilan ini adalah konsep “pertanggungjawaban komando” ketika mengadili Jenderal Tomoyuki Yamashita (teori ini kemudian menjadi dasar penuntutan di ICTY atas kasus Mladic dan Karadzic). Impunitas lain yang dipraktekan dalam pengadilan ini adalah 5 6 Lihat. Y Onuma, “The Tokyo Trial : Between Law and Politics, in C.Hosoya.N.Ando, Y.Onuma and R Minear (eds), The Tokyo War Crimes Trial : An Internasional Symposium (Kodansha, 1986), p.45. Diambil dari Kriangsak…Op.cit,p. 19 Geoffrey Robertson…Op.Cit, p. 252 151 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia tidak diadilinya para industrialis Jepang yang menjajakan perang serta pemimpin-pemimpin nasionalis yang senang kekerasan. Hampir setengah abad setelah Perang Dunia berakhir, masyarakat internasional kembali dikejutkan dengan praktek pembersihan etnis yang lagi-lagi terjadi di Eropa yakni di Negara bekas Yugoslavia. Konflik di Bosnia-Herzegovina, sejak April 1992 dan berakhir bulan November 1995, merupakan praktek pembersihan etnis yang kekejamannya sudah mencapai tingkat yang tidak pernah dialami Eropa sejak Perang Dunia II. Kamp-kamp konsentrasi, perkosaan yang sistematis, pembunuhan besar-besaran, penyiksaan, dan pemindahan penduduk sipil secara massal adalah bukti-bukti yang tidak dapat diingkari yang akhirnya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY) berdasarkan Resolusi 808 tanggal 22 February 1993, dengan pertimbangan bahwa sudah meluasnya tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter termasuk praktek pembersihan etnis sehingga sangat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.7 Berbagai kritikan kembali muncul seiring terbentuknya ICTY ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa mahkamah ini hanyalah kebetulan belaka mengingat berbagai kegagalan diplomasi dan sanksi serta penolakan PBB untuk mengorbankan tentara keamanannya melalui intervensi bersenjata membuat mahkamah terhadap penjahat perang sebagai alat satu-satunya untuk menyelamatkan muka PBB.8 7 8 Florence Hartman, Bosnia, diambil dari Roy Gutman and David Rieff, Crimes of War : What Public Shuld Know, W.W Norton Company, New York-London, 1999, p. 53. Geoffrey Robertson, …Op.Cit, p. 352-353. 152 Lampiran Walaupun mahkamah ini bukan lagi merupakan keadilan pemenang perang namun justru dikenal sebagai keadilan yang selektif (selective justice) karena hanya mendirikan Mahkamah untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di Negara-negara tertentu, serta Mahkamah ini juga jelas berdasarkan pada anti-Serbian bias.9 Selain itu, Mahkamah ini juga tidak mengadili angkatan bersenjata NATO yang ikut melakukan pemboman di Negara bekas Yugoslavia. Padahal, sangatlah jelas serangan udara yang dilakukan NATO terhadap Kosovo seharusnya menuntut pertanggungjawaban para pemimpin NATO atas pilihan target pemboman yang mereka lakukan karena jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum perang.10 Kritikan yang sama mengenai “selective justice” juga ditujukan kepada PBB ketika Dewan Keamanannya mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 955 tanggal 8 November 1994 di kota Arusha, Tanzania. Pengadilan ini didirikan untuk merespon terjadinya praktek genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang sudah meluas yang terjadi di Rwanda.11 Banyak kalangan menilai, ICTY dan ICTR ini hanyalah Mahkamah Internasional yang didirikan dengan alasan yang sangat politis, dan berdasarkan prinsip yang abstrak dan tidak jelas. Bagaimana dengan penyiksaan yang terjadi di Beijing terhadap anggota Falun Gong hingga meninggal dan menjual organ-organ vital mereka? 9 10 11 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 337. Professor Jeremy Rabkin, The UN Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda : International Justice or Show of Justice?, diambil dari William Driscoll, Joseph Zompetti and Suzette W. Zompetti, The International Criminal Court: Global Politcs and The Quest for Justice, The International Debate Education Association, New York, 2004, p. 131. Kriangsak Kittichaisaree, Op.Cit,p. 24. 153 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Bagaimana dengan pembunuhan besar-besaran di Shabra dan Shatila terhadap wanita dan anak-anak Palestina? Akankah pelaku kejahatan-kejahatan tersebut juga dibawa ke Mahkamah seperti halnya Mahkamah untuk Yugoslavia dan Rwanda? Akankah PBB memiliki keberanian untuk itu? Selective Justice adalah keadilan yang ditunda dan itu sama saja dengan victors justice.12 Berbagai kekurangan dan kegagalan dari mahkamah-mahkamah internasional di atas akhirnya menggerakkan PBB untuk melaksanakan konferensi pada tahun 1998 untuk mendirikan suatu Mahkamah Pidana yang permanen yang diharapkan dapat menyempurnakan berbagai kelemahan dari Mahkamah Internasional sebelumnya. Aspirasi untuk mendirikan MPI telah muncul di era 1980-an melalui proposal yang diajukan Negara-negara Amerika Latin (yang diketuai oleh Trinidad dan Tobago) kepada Majelis Umum PBB.13 Selanjutnya, setelah pendirian ICTY dan ICTR, Majelis Umum PBB mendirikan Komite yang bernama Komite Persiapan untuk pendirian MPI (Preparatory Committee for The Establishment of an International Criminal Court), yang telah bertemu enam kali sejak 19961998 untuk mempersiapkan teks Konvensi sebagai dasar MPI.14 Puncak dari proses yang panjang tersebut adalah disahkannya Statuta MPI dalam Konferensi di Roma tanggal 17 Juli 1998 sehingga Statuta tersebut akhirnya 12 13 14 Taki, Unpopular Truht: Selective Justice, from “Slobodamnation”, New York Press, Volume 14, issued 28. This Article was found at http : // www.issuesviews.com. Surat tanggal 21 Agustus 1989 dari Perwakilan Permanen Trinidad dan Tobago kepada Sekretaris Jenderal PBB, UNGAOR, 47th Sess, Annex 44, Agenda item 152, Un.Doc.A/44/195 (1989), diambil dari Kriangsak Kittichasairee, … Op.Cit,p. 27. Kriangsak Kittichasairee, ibid,p. 28. 154 Lampiran dikenal dengan nama Statuta Roma. Seperti yang tertuang dalam Mukadimah dari Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, bahwa Mahkamah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang global (Global Justice), memutuskan rantai kekebalan hukum (impunity) bagi para pelaku kejahatan, serta mengefektifkan kinerja mekanisme hukum nasional dalam menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. B. Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) MPI didirikan berdasarkan Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998, ketika 120 negara berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court” telah mesahkan Statuta Roma tersebut.15 Dalam pengesahan Statuta Roma tersebut, 21 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel, dan India16. Kurang dari empat tahun sejak Konferensi diselenggarakan, Statuta yang merupakan dasar pendirian Mahkamah bagi kejahatan yang paling serius yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi ini, sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 60 negara meratifikasinya. Ini adalah waktu yang sangat cepat jika dibandingkan dengan perjanjian multilateral lain dan jauh lebih cepat dari waktu yang diharapkan oleh masyaratakat internasional. Hingga saat ini telah ada 108 negara peratifikasi Statuta Roma17. 15 16 William Driscoll, Joseph Zompetti and Suzette W. Zompetti, The International Criminal Court: Global Politcs and The Quest for Justice, The International Debate Education Association, New York, 2004,p.30 17 Berdasarkan data tanggal 28 Juli 2008 dari www.iccnow.org. ibid, p. 131. 155 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Mahkamah Pidana Internasional (MPI) sendiri secara resmi dibuka di Den Haag tanggal 11 Maret 1998 dalam sebuah upacara khusus yang dihadiri oleh Ratu Beatrix dari Belanda serta Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan.18 Berbeda dengan mahkamah internasional sebelumnya yang sifatnya ad hoc, Mahkamah ini merupakan pengadilan yang permanen (Pasal 3(1) Statuta Roma). Mahkamah ini hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku (Pasal 24 Statuta Roma). Mahkamah ini merupakan mahkamah yang independent dan bukan merupakan organ dari PBB, karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral. Namun antara Mahkamah dengan PBB tetap memiliki hubungan formal (Pasal 2 Statuta Roma). Pasal 13b serta Pasal 16 Statuta Roma juga menjelaskan mengenai tugas yang cukup signifikan dari Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah yakni Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk memulai atau menunda dilakukannya investigasi berdasarkan bab VII Piagam PBB. Mahkamah ini juga hanya boleh mengadili para pelaku di atas usia 18 tahun. Yurisdiksi MPI terbagi empat : a. territorial jurisdiction (rationae loci): bahwa yurisdiksi MPI hanya berlaku dalam wilayah negara pihak, yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara pihak, dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi MPI berdasarkan deklarasi ad hoc. (Pasal 12 Statuta Roma) 18 Hans Peter Kaul, Developments at The International Criminal Court : Construction Site for More Justice: The ICC After Two Years, April 2005, p. 170. 156 Lampiran b. material jurisdiction (rationae materiae): bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi MPI terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan agresi (Pasal 5-8 Statuta Roma) c. temporal jurisdiction (rationae temporis): bahwa MPI baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku yakni 1 Juli 2002. (Pasal 11 Statuta Roma) d. personal jurisdiction (rationae personae): bahwa MPI memiliki yurisdiksi atas orang (natural person), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi MPI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual criminal responsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil. (Pasal 25 Statuta Roma). Selanjutnya, dalam hal penerapan dari keempat yurisdiksi MPI diatas pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental yakni MPI “harus merupakan komplementer (pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu Negara” (complementarity principle). Hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam paragraph 10 Mukadimah Statuta Roma serta dalam Pasal 1 Statuta Roma. Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip ini akan diuraikan secara lengkap dalam Bab II. Namun pada intinya prinsip komplementer (complementarity principle) ini menegaskan bahwa fungsi MPI bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu Negara, namun MPI merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika Negara tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI. 157 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional. Sehingga pada akhirnya kejahatan-kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak akan terulang di kemudian hari. Karena pada hakikatnya, keadilan yang tertunda akan meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed can be justice denied)19. C. Indonesia dan Mahkamah Pidana Internasional Pengalaman penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu harus menjadi pelajaran berharga bagaimana Indonesia di masa depan seharusnya bersikap. MPI sebagai sebuah pengadilan yang diakui secara internasional yang bekerja dengan menggunakan standar, rasa keadilan dan hukum internasional pastinya menjadi jaminan penyelesaian kasus serupa di masa yang akan datang, meniadakan praktek impunitas. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia menunjukan lemahnya upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Praktek Pengadilan HAM baik yang Ad Hoc (untuk kasus Tanjung Priok) maupun permanen (untuk kasus Abepura yang diadili melalui Pengadilan HAM Makassar) terbukti sulit untuk menjangkau dan menghukum orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Tidak terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara memadai menunjukan bahwa ada masalah dalam mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang saat 19 Geoffrey Robertson, …Op.Cit,p. 254. 158 Lampiran ini dimiliki oleh Indonesia baik itu terkait sistem hukum maupun kapasitas aparat penegak hukumnya. Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain bebasnya para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hakhak korban pelanggaran HAM yang berat. Hak-hak korban yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sampai saat ini tidak satupun yang diterima oleh korban. Padahal para korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Studi dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kelemahan proses peradilan HAM terjadi dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Persoalan ketidakcukupan regulasi menjadi salah satu faktor yang mendorong kegagalan pengadilan. Faktor lainnya yang memperlemah pengadilan HAM adalah kapasitas para penegak hukumnya baik mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini. Kebutuhan terhadap mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan pelbagai kejahatan hak asasi manusia berat juga menjadi isu di dunia internasional yang kemudian berujung pada lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) pada 17 Juli 1998. Dengan demikian Indonesia memiliki kesamaan dengan masyarakat internasional dalam hal kebutuhan akan mekanisme yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan paling serius dan memberikan keadilan pada korban. 159 Lampiran BAB II Kebutuhan Indonesia untuk Meratifikasi Statuta Roma Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma walaupun “sebagian” kejahatan yang merupakan yurisdiksi dari Statuta ini sudah diadopsi oleh UndangUndang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hanya saja ada banyak kritik terhadap bagaimana UU tersebut telah salah mengadopsi dan bahkan tidak mengambil beberapa ketentuan dalam Statuta Roma. Hal-hal penting yang tidak terambil seperti misalnya tidak masuknya kejahatan perang, perlindungan saksi yang tidak maksimal, dan hukum acaranya yang masih menggunakan hukum acara KUHP. Ketidaklengkapan aturan ini sangat berkontribusi terhadao bolong besar dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia masih banyak menemukan kendala dalam hal penegakkan hukum khususnya Hukum HAM, uraian di bawah ini akan menjelaskan betapa ternyata Indonesia sangat memerlukan 161 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia ratifikasi Statuta Roma ini sebagai sarana pendorong untuk membenahi berbagai kelemahan dan kekurangan dari segi instrumen hukum, aparat penegak hukum, serta prosedur penegakkan hukumnya sehingga Indonesia dapat benarbenar mampu memberikan jaminan perlindungan HAM bagi warganegaranya. a. Menghapus Berbagai Praktek Impunity Salah satu tujuan didirikannya MPI adalah untuk menghapuskan praktek impunitas (impunity). Pasal 28 Statuta Roma secara rinci mengatur bahwa seorang atasan baik militer maupun sipil, harus bertanggungjawab secara pidana ketika terjadi kejahatan dalam yurisdiksi MPI yang dilakukan oleh anak buahnya. Aturan yang telah ada sejak Piagam Nuremberg, Tokyo, Konvensi Jenewa 1949, ICTY, ICTR dan kemudian disempurnakan dalam Pasal 28 Statuta Roma, memiliki tujuan untuk dapat menghukum “the most responsible person” walaupun orang tersebut memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan yang seringkali sulit terjangkau hukum. Pasal 28 Statuta Roma telah diadopsi dalam pasal 42 Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun terdapat banyak kesalahan penterjemahan yang justru menjadi celah bebasnya para atasan/komandan tersebut.20 Secara umum impunitas dipahami sebagai “tindakan yang mengabaikan tindakan hukum terhadap pelanggaran (hak asasi manusia)” atau dalam kepustakaan umum diartikan sebagai “absence of punishment”. Dalam perkembangannya istilah impunity digunakan hampir secara ekslusif dalam konteks hukum, untuk menandakan suatu 20 Uraian rinci tentang kesalahan penterjemahan pasal 42 tersebut dapat dilihat dalam Bab I Sub Bab ii. Mengatasi kelemahan sistem hukum di Indonesia tentang Undang-undang 26/2000, p.13-14. 162 Lampiran proses di mana sejumlah individu luput dari berbagai bentuk penghukuman terhadap berbagai tindakan illegal maupun kriminal yang pernah mereka lakukan.21 Praktek impunitas ini telah terjadi sejak berabad yang lalu diantaranya adalah gagalnya Negara-negara Eropa untuk mengadili Raja Wilhelm II sebagaimana yang direkomendasikan oleh Perjanjian Versailles, tidak diadilinya Kaisar Hirohito oleh Mahkamah Tokyo atas keputusan AS, berbagai pengadilan pura-pura yang mengadili serdadu-serdadu rendah dengan hukuman yang ringan dan melawan hari nurani keadilan masyarakat.22 Praktek ini menunjukan bahwa setiap Negara selalu memiliki kecenderungan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya sendiri apalagi apabila pelaku tersebut merupakan orang yang memegang kekuasaan di Negara tersebut. Fenomena ini menunjukan betapa kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek masih dominan ketimbang penegakkan HAM dan keadilan. Bagaimana impunity dalam konteks Indonesia, terutama setelah jatuhnya rezim Soeharto? Peralihan kekuasaan Soeharto ke Habibie menyisakan sejumlah catatan penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun Peradilan Militer dibentuk di masa Habibie untuk mengadili sejumlah petinggi dan anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan penculikan orang secara paksa, tetapi tidak pernah ada penjelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas korban-korban penghilangan paksa yang belum kembali hingga saat ini. Peradilan ini lebih kepada kompromi politik elit-elit politik dan militer, untuk tidak menjatuhkan 21 Genevieve Jacques, Beyond Impunity: An Ecumenical Approach to Truth, Justice and Reconciliation, Geneva: WWC Publication, 2000, p.1 . 22 Abdul Hakim G Nusantara, Sebuah Upaya Memutus Impunitas : Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat HAM, Jurnal HAM Komisi Nasional HAM Vol.2 No.2, November 2004, p.v 163 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia hukuman yang dinilai mampu mengakibatkan keguncangan dalam tubuh militer. Sekaligus mencoba untuk berkompromi dengan korban-korban yang sudah dilepaskan. Yang pasti peradilam militer kasus penculikan tersebut gagal untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan.23 b. Mengatasi Kelemahan Sistem Hukum Indonesia Meratifikasi Statuta Roma serta memasukkan kejahatan internasional serta prinsip-prinsip umum hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum pidana nasional, akan meningkatkan kemampuan negara untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang. Bahkan negara secara efektif akan menghalangi dan mencegah terjadinya kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional tersebut. Dengan melaksanakan kewajibannya untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius tersebut, negara secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap keamanan, stabilitas, kedamaian nasional, regional, bahkan internasional.24 Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang juga ingin berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta menyadari begitu banyaknya kelemahan dalam sistem hukumnya seringkali membuat Indonesia sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam menghukum pelaku kejahatan internasional. Indonesia harus melakukan begitu 23 Daniel Hutagalung, Negara dan Pelanggaran Masa Lalu : Tuntutan Pertanggungjawaban Versus Impunitas diambil dari Dignitas : Jurnal HAM ELSAM, Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri, Volume No.1, 2005, p. 230231. 24 Michael Cottier, The Ratification of the Rome Statute and the Adoption of Legislation Providing Domestic Jurisdiction over International Crimes, makalah disampaikan dalam acara : accra conference on “domestic implementation of the rome statute of the international criminal court”, 21 - 23 February 2001. 164 Lampiran banyak pembenahan khususnya dalam hal instrumen hukum serta sumber daya manusianya. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terlalu banyaknya Undang-Undang yang antara satu dan lainnya saling bertentangan sehingga dalam hal kepastian hukum seringkali membingungkan. Tidak hanya di tingkat Undang-Undang, namun juga di tingkat aturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Daerah). Selain itu, sistem hukum Indonesia khususnya dalam mengasorbsi hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia masih sangat tidak jelas. Praktek di Indonesia menunjukan bahwa setelah meratifikasi suatu konvensi Internasional (baik dalam bentuk Undang-undang maupun Keppres) maka harus segera disertai dengan aturan pelaksanaan (implementing legislation) yang memuat lembaga pelaksana dan sanksi pidana efektif suatu kejahatan tertentu sehingga konvensi itu bisa benar-benar berlaku efektif terhadap warga negaranya.25 Padahal berdasarkan Pasal 7(2) Undang-Undang 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional”. Sementara itu, banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami aturan hukum internasional dan berbagai praktek internasional yang terjadi, bahkan banyak diantara mereka cenderung tidak memiliki keberanian untuk melakukan terobosan dengan mendasarkan suatu kejahatan yang terjadi dengan praktek internasional. Sehingga, sangat jarang ditemukan suatu putusan pengadilan di Indonesia 25 Misalnya dalam hal kejahatan perang. Sejak tahun 1958 melalui Undang-Undang No.59 tahun 1958, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Namun hingga saat ini Konvensi tersebut tidak dapat berlaku efektif karena tidak adanya aturan pelaksanaan yang memuat sanksi pidana efektif dari kejahatan perang tersebut. 165 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia yang mendasarkan pada kasus-kasus internasional atau hukum kebiasaan internasional. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kelemahan sistem hukum Indonesia sehingga ratifikasi Statuta Roma sangat dibutuhkan untuk membenahinya, yaitu : a. Instrumen hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Banyak aturan dalam KUHP yang sudah tidak lagi relevan dan memadai untuk mengakomodir jenis-jenis kejahatan yang sudah semakin berkembang. Khususnya dalam hal penegakan hukum HAM, beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampasan kemerdakaan, perkosaan, penganiayaan adalah jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP. Namun jenis kejahatan tersebut adalah jenis kejahatan yang biasa (ordinary crimes) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat atau kejahatankejahatan dalam yurisdiksi MPI harus memenuhi unsur atau karateristik tertentu. Perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif pelaku pelanggaran HAM yang berat. 26 2. Hukum Acara: Dalam pasal 10 Undang-Undang 26/2000 dijelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat maka hukum acara yang digunakan adalah Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tentu saja hal ini 26 Agung Yudhawiranata, Pengadilan HAM di Indonesia : Prosedur dan Praktek, p. 1. 166 Lampiran tidak lah memadai mengingat jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam undang-undang ini adalah extra ordinary crimes sehingga banyak hal yang baru yang tidak diatur dalam KUHAP. Sebagian dari hal-hal baru tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 26/2000 yakni mengenai 27: a) Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc b) Penyelidik hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM sedangkan penyidik tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP c) Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. d) Ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi 27 Namun terdapat aturan khusus lain yang tidak diatur baik dalam KUHAP maupun UndangUndang 26/2000 sehingga sangat diperlukan hukum acara dan pembuktian yang khusus (seperti bentuk rules of procedure and evident dari Statuta Roma) sebagai dasar hukumnya. Hal-hal yang tidak diatur baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang 26/2000 diantaranya adalah dasar hukum sub poena power yang dimiliki penyelidik dalam hal ini KOMNAS HAM. ibid, p. 7. 167 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 3. Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM: Undang-undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat. Yurisdiksi Pengadilan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Walaupun undang-undang ini dikatakan sebagai pengadopsian dari Statuta Roma namun terdapat banyak kelemahan (entah disengaja atau tidak) yang akhirnya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Misalnya Undang-Undang 26/2000 hanya mencantumkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagai yurisdiksinya sementara kejahatan perang yang juga merupakan yurisdiksi Statuta Roma tidak dicantumkan dalam Undang-Undang ini. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan perang di Indonesia maka belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana yang efektif bagi kejahatan ini. 28 Berbagai kesalahan penterjemahan juga banyak ditemukan dalam pasal-pasal di undang-undang ini. Misalnya dalam pasal 9 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan28, terdapat kata-kata “serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil” sementara dalam teks asli Statuta Roma “directed against civilian population” yang artinya “ditujukan kepada penduduk sipil”. Penambahan kata “secara langsung” di sini dapat berakibat sulitnya menjangkau para pelaku yang bukan pelaku lapangan. Para pelaku di tingkat Pasal 9 UU 26/2000 : “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :…” 168 Lampiran pemberi kebijakan sulit terjangkau berdasarkan pasal ini. 29 Dalam Pasal 42 (1) mengenai pertanggungjawaban komando bagi komandan militer29 terdapat katakata “dapat bertanggungjawab”. Sementara dalam teks asli Statuta Roma kata yang digunakan adalah “shall be criminally responsible” (lihat Pasal 28 Statuta Roma) yang berarti “harus bertanggung jawab secara pidana”. Penggantian kata “harus” dengan “dapat” diartikan bahwa komandan tidak selalu harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Dan penghilangan kata “pidana” diartikan bahwa komandan tidak harus bertanggung jawab secara pidana tetapi tanggungjawab administratif saja sudah cukup. Sehingga tidak lah mengherankan jika banyak para komandan militer terbebas dari jeratan hukum dalam Pengadilan HAM baik Ad Hoc maupun permanen di Indonesia. Anehnya lagi, kata-kata “dapat bertanggungjawab” tidak ditemukan dalam ayat (2) yang berlaku bagi atasan sipil. Hal ini menunujukan adanya inkonsistensi penerjemahan dalam Undang-Undang ini. Dalam Statuta Roma terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur kejahatan yang menjadi yurisdiksinya Pasal 42 UU 26/2000: (1) komandan militer atau seseorang yg secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam jurisdiksi ... (2) seseorang atasan, baik polisi maupun sipil, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : ...” 169 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia yaitu unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang, serta unsur dari pertanggungjawaban komando. Penjelasan mengenai unsur-unsur ini dapat memudahkan aparat penegak hukum ketika menafsirkan kejahatan ini dalam proses pembuktian, penuntutan maupun sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Undang-undang 26/2000 tidak ada penjelasan mengenai unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida, baik dalam penjelasan undang-undang maupun terpisah dalam bentuk buku pedoman lain. Hal ini tentu saja seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam berproses di Pengadilan. Ketidakjelasan uraian yang menunjukan delik kejahatan yang diatur dalam Undang-undang 26/2000 khususnya unsur kejahatan terhadap kemanusiaan mengakibatkan hakim seringkali memberikan penafsiran yang berbeda dalam putusannya karena rujukan yang digunakan pun berbeda-beda. Terlepas dari begitu banyaknya kelemahan dalam Undang-Undang 26/2000 namun Undangundang ini juga banyak melakukan terobosan misalnya dalam hal alat bukti, praktek Pengadilan HAM Ad Hoc untu Timor-Timur membuktikan dimungkinkannya digunakan alat bukti lain diluar yang diatur dalam KUHAP30 seperti rekaman baik dalam bentuk film atau kaset, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian, kliping, Koran, artikel lepas, dll.31 30 Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 31 Progress report pemantauan pengadilan HAM Ad Hoc ELSAM ke X tanggal 28 170 Lampiran b. Sumber Daya Manusia Dengan meratifikasi Statuta Roma, akan banyak sekali manfaat bagi Indonesia sebagai Negara Pihak, khususnya dalam hal meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan menjadi Negara Pihak MPI maka secara otomatis Indonesia menjadi anggota dari Majelis Negara Pihak (Assembly of States Parties) yang memiliki fungsi sangat penting dalam MPI32. Majelis Negara Pihak ini kurang lebih sama dengan fungsi dari Majelis Umum dalam Badan PBB. Fungsi penting dari Majelis Negara Pihak diantaranya adalah dapat ikut serta melakukan pemilihan terhadap semua posisi hukum di MPI. Posisi tersebut diantaranya adalah posisi hakim dan penuntut umum.33 Tujuh bulan setelah Statuta Roma berlaku, yakni tanggal 7 Februari 2003, tujuh wanita dan sebelas laki-laki dari lima kawasan berbeda di dunia telah dipilih oleh Majelis Negara Pihak sebagai delapan belas hakim MPI pertama34. Selain itu, pada bulan Maret, Luis Moreno-Ocampo (Argentina) juga telah dipilh oleh Majelis Negara Pihak untuk Januari 2003, diambil dari makalah Agung Yudhawiranata, Pengadilan HAM di Indonesia : Prosedur dan Praktek. 32 Berbagai keuntungan menjadi anggota dari Assembly of State Parties diantaranya adalah setiap Negara pihak memiliki perwakilan di Assembly, mereka memiliki suara dan setiap masalah susbstansi di ICC harus disetujui oleh 2/3 suara anggota yang hadir. (lebih lengkap mengenai Assembly of State Parties dapat dilihat dalam Pasal 112 Statuta Roma). 33 International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR), Update on the International Criminal Court, Vancouver, Canada, 2002,p.5 34 Hans Peter Kaul, Developments at The International Criminal Court : Construction Site for More Justice: The ICC After Two Years, April 2005,p. 370. 171 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia menjadi Ketua Penuntut Umum35. Jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma sebelum 30 November 2002, maka Indonesia berhak mengajukan salah satu warganegaranya untuk dinominasikan sebagai salah satu calon hakim. Namun, walaupun para hakim telah terpilih sebagai hakim pertama di MPI, namun kesempatan bagi Indonesia masih tetap terbuka seiring dengan pergantian hakim yang telah habis baktinya.36 Karena itu, semakin cepat Indonesia meratifikasi Statuta Roma, maka akan semakin terbuka pula kesempatan sumber daya manusia Indonesia untuk menempati posisi sebagai salah satu hakim internasional di MPI. Dengan demikian, menjadi Negara Pihak dalam Statuta Roma, berarti Indonesia turut berperan aktif dalam memajukan fungsi efektif dari MPI. Itu juga berarti sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam sistem international, sehingga hal itu akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, setelah meratifikasi Statuta Roma maka para aparat penegak hukum mau tidak mau harus membuka diri mereka untuk lebih terbiasa dan terlatih dalam melihat perkembangan kasuskasus internasional yang terjadi dan menjadikannya bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia. Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah 35 ICC Press Release, Election of the Prosecutor-Statement by the President of the Assembly of State Parties Prince Zeid Ra’ad Zeid Al Husein, 25 March,2003. 36 Mengenai persyaratan, pencalonan dan pemilihan hakim ICC dapat dilihat dalam Pasal 36 Statuta Roma. 172 Lampiran banyak aparat penegak hukum yang tidak siap khususnya ketika harus mengadili kasus-kasus yang merupakan extra ordinary crimes di mana pengaturannya sangat tidak memadai jika hanya mendasarkan pada KUHP dan KUHAP. Sedangkan sebagian besar dari mereka hanya terlatih untuk selalu mendasarkan setiap kasus pidana dengan KUHAP dan KUHP. Misalnya, praktek Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur mencatat berbagai kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Kekurangan tersebut diantaranya adalah37: i. Dalam hal pemilihan hakim oleh Mahkamah Agung, seleksi dilakukan secara subjektif dan tidak sesuai dengan track record para calon hakim ii. Tidak ada publikasi mengenai proses persidangan (prosiding) serta sangat sulit untuk mendapatkan hasil keputusan dalam bentuk tertulis. iii. Banyaknya laporan yang dikeluarkan oleh para aktivis HAM di Indonesia mengenai praktek korupsi yang sudah meluas dalam sistem pengadilan HAM. iv. Kurangnya independensi, impartiality, dan profesionalisme dari para aparat penegak hukum v. Kurangnya kepercayaaan terhadap pengadilan. 37 masyakarakat Report to the Secretary General of The Commission of experts to Review the Prosecution of Serious Violations of Human Rights in Timor Leste 1999, 26 May 2005, p. 55. 173 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Di samping itu, pelapor khusus mengai kenetralan hakim dan pengacara (Special Rapporteur on the independence of judges and lawyer) Dato’ Param Cumaraswamy menyatakan bahwa ada sejumlah hakim yang hanya mendapatkan sedikit sekali pelatihan mengenai standar dan praktek internasional dalam hal mengadili kejahatan serius seperti kejahatan terhadap kemanusiaandan genosida.38 Kualitas para hakim tentu saja sangat mempengaruhi hasil dari suatu kasus. Misalnya,ada pendapat yang dikemukakan oleh seorang pengamat Pengadilan Ad Hoc Timor Timur yang mengatakan bahwa kelompok hakim terbagi tiga ; (1) hakim konservatif yang bekerja menurut buku dan kaku pada hukum acara pidana, (2) hakim karir dan ad hoc yang dikenal akan pengetahuannya tentang hukum humaniter internasional dan berpandangan progresif, kelompok ini bertanggungjawab atas munculnya sejumlah keputusan bersalah, dan (3) kelompok tengah yang dapat pergi ke mana saja tergantung panel di mana mereka duduk. Menurut para pengamat kelompok yang ke-3 ini “ingin terlihat menguasai hukum humaniter internasional tapi motivatisnya lebih hanya untuk karir”. 39 Para hakim karir di pengadilan HAM Ad Hoc Timur-Timur juga tetap harus menangani kasuskasus yang lain sehingga sulit bagi mereka untuk fokus pada proses pengadilan HAM. Mereka juga 38 ibid. 39 Professor David Cohen, Intended to Fail : The Trials Before The Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta, International Center for Transitional Justice, July, 2004, p. 55-56. 174 Lampiran sangat kurang mendapatkan bantuan fasilitasfasilitas yang mendukung perkara yang mereka tangani misalnya perpustakaan, komputer, dan akses internet. c. Perlindungan Saksi dan Korban Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk menjamin korban dan saksi mendapatkan perlindungan. Perlindungan saksi dan korban diatur baik dalam Statuta Roma maupun dalam Rules of Procedure and Evidence-nya (RPE). Aturan ini didasarkan pada norma yang sama yang telah diatur dalam dua pengadilan ad hoc internasional sebelumnya yakni ICTY dan ICTR. Partisipasi saksi dan korban mendapatkan jaminan dalam setiap tingkat proses persidangan di MPI. Perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 68 Statuta Roma, yaitu: i. Proses persidangan in camera (sidang tertutup untuk umum), dan memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana khusus atau sarana elektronika lain (Pasal 68(2) Statuta Roma). Secara khusus, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. ii. Unit Saksi dan Korban (Pasal 68(4) Statuta Roma): dalam Mahkamah Pidana Internasional, unit ini dibentuk oleh Panitera di dalam Kepaniteraan. Setelah berkonsultasi dengan Kantor Penuntut Umum, unit ini berfungsi untuk menyediakan 175 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasihat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Unit ini juga mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual (Pasal 43(6) Statuta Roma). Bahkan dalam RPE, unit ini wajib untuk menjamin perlindungan dan kemanan saksi agar semua saksi dan korban dapat hadir di persidangan. Untuk itu unit ini wajib untuk membuat rencana perlindungan korban dan saksi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, setelah berkonsultasi dengan Kantor Kejaksaan, unit ini harus menyusun tata cara mengenai keamanan dan kerahasiaan professional untuk para penyelidik, pembela dan organisasiorganisasi (pemerintah dan non-pemerintah) yang bertindak atas nama Mahkamah. Disamping itu unit ini juga diberi kewenangan untuk membuat perjanjian dengan Negaranegara untuk kepentingan pemukiman (resettlement) korban dan saksi yang mengalami trauma atau ancaman. 40 Di Indonesia, perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Pasal 34 UndangUndang 26/2000 dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 sebagai aturan pelaksanaannya. Namun berbagai aturan perlindungan saksi dan korban serta reparasi bagi korban yang diatur dalam Statuta Roma di atas banyak yang tidak diatur dalam Pasal 34 serta Peraturan Pemerintah tersebut. Akibatnya, praktek pengadilan HAM Ad Hoc 40 Rudi Rizki at al, Pelaksanaan Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003, p. 28 176 Lampiran Timor Timur dan Tanjung Priok membuktikan bahwa banyak korban serta saksi yang tidak mau hadir ketika dipanggil ke pengadilan. Alasan-alasan mereka diantaranya adalah ketidakpercayaan adanya jaminan keamanan karena tidak adanya perahasiaan korban, tidak ada safe house, perlakuan terhadap korban dan saksi dari aparat, kurangnya persiapan dan pengalaman aparat, dan alasan biaya. Akibat dari ketidakhadiran saksi maka kebenaran tidak terungkap dengan baik sehingga keputusan tidak memenuhi rasa keadilan. Disamping itu asas peradilan yang cepat dan hemat pun tidak tecapai karena seringnya pengunduran / perobahan jadwal persidangan akibat ketidakhadiran saksi. Selain mendapatkan perlindungan, para saksi dan korban juga berhak mendapatkan reparasi moral dan material. Pasal 75 Statuta Roma mengatur mengenai berbagai bentuk reparasi terhadap korban (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi). Selain itu Pasal 79 Statuta Roma berdasarkan Majelis Negara-Negara Pihak berhak menetapkan adanya Trust Fund untuk kepentingan para korban dan keluarganya. Mahkamah dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer, atas perintah Mahkamah, kepada Trust Fund. Pengelolaan Trust Fund adalah berdasarkan kriteria yang diatur Majelis Negara-Negara Pihak. Aturan lebih jelas mengenai hal diatas diatur dalam Aturan 94 dari MPI Rules of Procedure and Evidence (RPE). Proses untuk menentukan reparasi bisa atas permohonan korban sendiri (Aturan 94 (1) RPE) atau atas mosi Mahkamah sendiri berdasarkan pasal 75 (1) 177 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Statuta Roma (Aturan 95 (1) RPE). Korban dan terdakwa boleh mengambil bagian dalam proses penetuan reparasi. Mahkamah juga dimungkinkan untuk mengundang ahli untuk membantu proses reparasi tersebut dalam hal menetapkan kerugian, kerusakkan atau luka dan memberikan saran dalam hal “tipe-tipe dan cara reparasi yang layak untuk dilakukan”. Menariknya, berdasarkan Aturan 97(2) “Mahkamah harus mengundang secara layak para korban dan penasihat hukumnya, terdakwa, orang-orang serta negara yang berkepentingan lainnya untuk memberikan penilaian terhadap laporan dari ahli tersebut”. 41 Selain melaksanakan penghukuman bagi pelaku, pemberian kompensasi kepada korban adalah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Negara (state responsibility) ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat di wilayahnya. Karena itu, idealnya pemberian kompensasi ini tidak harus menunggu pelaku atau pihak ketiga tidak mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya, namun merupakan kewajiban yang sudah melekat bagi Negara. Definisi ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 (6) Undang-Undang KKR No.3 tahun 2004, dan seharusnya definisi inilah yang diterapkan dalam praktek Pengadilan HAM kita sehingga dibebaskan atau dihukumnya terdakwa tidak akan mempengaruhi kewajiban Negara untuk memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. d. Mahkamah Pidana Internasional dan Kejahatan Terorisme Statuta Roma secara khusus tidak memiliki yurisdiksi khusus terhadap kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme sendiri menjadi perhatian dunia pasca 9/11 yang 41 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 430. 178 Lampiran kemudian oleh Amerika Serikat (AS) dipergunakan sebagai bagian politik globalnya untuk memulai kampanye perang terhadap terorisme (war against terrorism). Kampanye ini tidak didasarkan pada penegakan hukum internasional yang justru berdampak pada munculnya sejumlah pelanggaran HAM dalam penanganan kasus-kasus terorisme dan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Padahal dalam mengadili pelaku terorisme walaupun melalui mekanisme yurisdiksi nasional haruslah sesuai dengan standar hukum internasional khususnya dalam perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini penting mengingat munculnya produk perundangundangan anti terorisme yang bersifat draconian di berbagai negara di dunia pasca 9/11. Bagaimanapun, kejahatan terorisme telah diakui sebagai ancaman secara global dan MPI adalah satu-satunya institusi yang tepat untuk mengadili para pelaku kejahatan terorisme. Bila ditelisik dari segi yuridiksi rationae personae, Statuta Roma mengatur bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap orang atau individu sehingga dalam mengadili para pelaku, Mahkamah akan tetap fokus pada pertanggungjawaban pidana secara individu (individual criminal responsibility). Selain itu yang tak kalah penting adalah bila mengacu pada prinsip komplementer dimana mekanisme yurisdiksi nasional diberlakukan terlebih dahulu untuk mengadili para pelaku. Dengan demikian penanganan terorisme melalui mekanisme MPI dapat menekan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dan menghindarkan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Karenanya menjadi agenda penting untuk Indonesia memasukan kejahatan terorisme dalam yurisdiksi 179 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia MPI. Jalan satu-satunya adalah dengan mengusulkannya dalam review conference pada 2010 mendatang sehingga akan tercapai standardisasi internasional dan perubahan perspektif terhadap penanganan kejahatan terorisme yang saat ini penuh dengan nuansa politik global AS dan terbukti menimbulkan permasalahan penghormatan dan penegakan hukum internasional. Indonesia akan dapat melakukannya jika telah meratifikasi Statuta Roma. e. Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerangka Piagam ASEAN Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN pada Oktober 2008 sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat dan berkontribusi bagi organisasi regional ini. Meski ada banyak kritik terhadap substansi piagam akan tetapi tetap berkait erat dengan upaya untuk mempromosikan penghormatan HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Hal inilah yang dapat memperkuat Indonesia dalam perannya di ASEAN bila ratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional segera direalisasikan. Pada Prinsip-prinsip Piagam ASEAN dalam Pasal 2(2)(j) Piagam ASEAN ditegaskan bahwa negara-negara anggota akan menjunjung tinggi Piagam PBB dan Hukum Internasional termasuk Hukum Humaniter Internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasional dari negaranegara anggota ASEAN. Terdapat dua hal penting yang tercermin dari pasal ini, pertama, ini merupakan bentuk penegasan ASEAN bahwa negara-negara ASEAN hanya menerima dan mengakui hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasionalnya atau dengan kata lain hukum internasional yang telah diratifikasi. Artinya ASEAN melakukan penerimaan secara parsial terhadap hukum internasional tertentu dan menolak hukum 180 Lampiran internasional lainnya seperti hukum HAM internasional yang sebagian besar telah menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law). Kedua, di satu sisi ASEAN secara khusus memfokuskan diri pada penghormatan hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional termasuk didalamnya soal pengungsi dan kejahatan perang. Namun pertanyaannya kemudian apakah mungkin hukum humaniter internasional dapat berlaku dengan baik jika hukum HAM internasional tidak menjadi bagian penting bagi perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata? Bila kita gunakan instrumen HAM internasional sebagai ukuran akan peneriman negara-negara ASEAN terhadap HAM universal maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh semua negara ASEAN yaitu Convention on Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Selain itu semua negara ASEAN juga telah menjadi pihak dalam satu instrumen hukum humaniter internasional yaitu Geneva Conventions 1949. Sedangkan Indonesia telah meratifikasi 24 Instrumen HAM termasuk di dalamnya 8 instrumen pokok HAM internasional serta 52 peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang berkait dengan perlindungan dan penegakan HAM serta termasuk negara yang paling dahulu meratifikasi Geneva Conventions 1949. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil peran lebih dalam kawasan Asia Tenggara dalam kaitannya dengan penghormatan dan promosi keadilan internasional. 181 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Bila ditelisik negara-negara anggota ASEAN khususnya Cambodia. Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV) serta negara-negara semi otoriter seperti Malaysia dan Singapura dan negara monarki absolut seperti Brunei memiliki permasalahan dalam kaitannya dengan penegakan Hukum Humaniter Internasional dan HAM. Sedangkan Indonesia dan Filipina merupakan negara yang secara progresif melakukan ratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional. Indonesia juga dapat mengambil peran dalam rangka penghapusan rantai impunitas di ASEAN melalui ratifikasi Statuta Roma. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia akan melengkapi ketentuan yang telah diatur oleh Piagam ASEAN yang telah pula menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Kedua instrumen tersebut juga akan memperkuat kebijakan Indonesia di dalam negeri khususnya dalam memutus rantai impunitas dan mempromosikan pelaksanaan keadilan internasional di kawasan Asia Tenggara. 182 Lampiran BAB III Menimbang Untung Rugi Implementasi Statuta Roma Ratifikasi merupakan bentuk kepedulian dan keseriusan suatu negara terhadap suatu hal yang diatur dalam konvensi internasional. Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan “ratifikasi” sebagai tindakan internasional dari suatu negara dengan mana dinyatakan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian.42 Ratifikasi merupakan bentuk penundukan suatu negara terhadap suatu ketentuan hukum (konvensi) internasional, artinya bilamana suatu negara meratifikasi suatu konvensi maka ia terikat dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam konvensi tersebut. Selain ratifikasi, pengesahan perjanjian internasional dapat pula dalam bentuk aksesi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 42 Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: Binacipta, 1986, hlm.6. Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional: “ ‘ratification’, ‘acceptance’, ‘approval’ and ‘accession’ mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”. 183 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia tentang Perjanjian Internasional. Jika ratifikasi dilakukan apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian maka aksesi dilakukan apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Namun secara umum istilah ratifikasi lebih banyak digunakan dalam praktek pengesahan peraturan perjanjian internasional. Ratifikasi berarti konfirmasi dari suatu negara bahwa suatu perjanjian yang diratifikasinya tidak bertentangan dengan kepentingan negaranya Dalam kerangka Hukum Tata Negara ratifikasi merupakan pernyataan untuk menegaskan bahwa perjanjan internasional yang telah disepakati tidak bertentangan dengan hukum nasional.43 Dalam konteks urgensi ratifikasi Statuta Roma, hal ini berarti semua negara peserta konvensi terikat dengan segala hak dan kewajiban dalam Statuta Roma, diantaranya kewajiban untuk mengadili para pelaku kejahatan sesuai dengan jurisdiksi Mahkamah. Negara peratifikasi berkewajiban untuk bekerjasama dalam investigasi dan penuntutan (pasal 86) dalam bentuk penerapan dalam hukum nasional.44 Sehingga sebelumnya Negara tersebut harus menjamin bahwa peraturan perundangan di negaranya sudah memadai (sebagai bentuk efektifitas prinsip komplementer). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009 berdasarkan Keppres No.40 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004 diantaranya mencakup rencana ratifikasi terhadap Statuta Roma pada tahun 2008. 43 R.C. Hingorani, “Commencement of Treaty” dalam S.K. Agrawala, ed. “Essays on the Law of Treaties”, Madras, 1972, hlm.19 diambil dari Budiono, op.cit., hlm. 7. 44 Amnesty International, The International Criminal Court – The case for Ratification, diambil dari http://iccnow.org/pressroom/factsheets.FS-Al-CaseforRatification. pdf. 184 Lampiran Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste juga secara eksplisit menekankan perlunya upaya untuk menciptakan budaya hukum dan hak asasi manusia dikalangan masyarakat luas, diantaranya dengan memasukan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Inisiatif yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah sosialisasi dan implementasi hak-hak yang tercantum dalam instrmeninstrumen hak asasi manusia dan hukum internasional terutama Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Rekomendasi ini sejalan dengan pelaksanaan RANHAM 2004-2009 seperti yang tersebut di atas. Sekali lagi hal ini dapat menunjukan dan menegaskan itikad baik serta komitmen Indonesia dalam rangka perlindungan HAM internasional yang selaras dengan hukum nasional. Urgensi ratifikasi Statuta Roma dirasa semakin mendesak, seiring dengan kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum HAM. Bukan karena tren dunia internasional yang tengah mempromosikan MPI, namun hal ini memang diperlukan agar dapat mendorong kemajuan perlindungan HAM dan penegakan hukumnya terutama dalam perbaikan sistem peradilan Indonesia. Tujuan penerapan MPI ke dalam hukum nasional: 1. untuk menempatkan Negara Pihak dalam kewajibannya untuk bekerjasama penuh dengan MPI 185 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 2. agar jurisdiksi MPI dapat menjadi pelengkap terhadap sistem pengadilan nasional negara pihak (prinsip komplementer) Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional mempunyai kewajiban untuk menghukum para pelaku kejahatan yang termasuk dalam kejahatan internasional yang dianggap dapat mengancam dan mengganggu perdamaian, keamanan dan ketertiban dunia sesuai dengan isi Piagam PBB. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3074 (XXVIII) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 1973 yang menyatakan bahwa penerapan jurisdiksi internasional mengikat semua Negara anggota PBB, “setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama satu sama lain secara bilateral atau multilateral untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggungjawab melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.” Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjadi negara pihak dalam Statuta Roma tentang MPI, mengingat salah satu tujuan pendirian MPI yaitu menjamin penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Sehingga dengan menjadi Negara Pihak Statuta Roma mau tidak mau suatu negara akan termotivasi untuk melaksanakan penegakan hukum melalui pengefektifan praktek dan sistem peradilan nasionalnya yang dilatarbelakangi salah satu prinsip fundamental MPI yaitu prinsip komplementer. Proses ratifikasi Statuta Roma merupakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan akibat yang lebih besar di kemudian hari, juga memberikan perlindungan dan reparasi bagi korban. Beranjak dari pengalaman pengadilan-pengadilan ad hoc yang pernah ada, dimana pertanggungjawaban dirasa kurang mencukupi karena 186 Lampiran selalu dipengaruhi unsur politik, MPI menekankan pertanggungjawaban individu45 atas kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresi. A. Keuntungan Meratifikasi Statuta Roma Konsekuensi logis dari proses ratifikasi suatu instrumen internasional yaitu bahwa negara yang melakukan ratifikasi terikat dengan aturan dalam konvensi tersebut. Berbagai pertimbangan tentu diperlukan oleh suatu negara yang hendak meratifikasi suatu perjanjian internasional dalam hal ini Statuta Roma. Selain bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam suatu konvensi dan dasar kepentingan suatu negara, dampak yang dapat timbul akibat peratifikasian pun harus menjadi salah satu pertimbangan, jangan sampai dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya. Diantaranya dampak terhadap legislasi nasional maupun kelembagaan hukum di Indonesia serta hubungan keterkaitan dan keterpengaruhan peran Indonesia dalam percaturan dunia internasional.46 a. Hak preferensi secara aktif dan langsung dalam segala kegiatan MPI. Keuntungan nyata yang diperoleh yaitu bilamana ada suatu musyawarah yang melibatkan negara peserta, maka kita akan dapat memberikan suara dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi Statuta maupun hal-hal lain yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan MPI, termasuk masalah administratif, dimana kita 45 Necessity of Ratifying the Statute of the International Criminal Court, Zagerb April 10, 2000, Translation of Press Release. www.beehive.govt.nz 46 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II, Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama, 2004, hlm.48. 187 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia menjadi anggota Majelis Negara Pihak (Assembly of States Parties).47 Bagi negara pihak Statuta Roma, hal ini berarti memberikan hak preferensi secara aktif dan langsung untuk memberikan peranannya secara aktif dalam segala kegiatan MPI, termasuk diantaranya melindungi warga negaranya yang menjadi subjek MPI. b. Kesempatan untuk menjadi bagian dari organ MPI. Dengan menjadi negara pihak dalam Statuta Roma, maka kesempatan untuk menjadi bagian dari organ MPI pun terbuka lebar, karena setiap negara pihak berhak mencalonkan salah satu warganegaranya untuk menjadi hakim, penuntut umum ataupun panitera. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum Indonesia dalam berpraktek di pengadilan internasional dan dapat menguatkan posisi tawar negara dalam pergaulan internasional. Sementara negara bukan pihak tidak dapat mencalonkan wakilnya untuk menjadi organ inti MPI. c. Membantu percepatan pembaharuan hukum (legal reform) di Indonesia. 47 Dengan meratifikasi Statuta Roma, maka Indonesia akan segera terdorong untuk membenahi instrumen hukumnya yang belum memadai agar selaras dengan aturan dalam Statuta Roma. Hal Lihat William A. Schabas, op.cit., hlm.157, lihat pasal 112 Statuta Roma 1998. Majelis Negara Pihak merupakan organ yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memberikan keputusan berkenaan dengan masalah administratif dan isi Statuta, diantaranya dalam memilih, mengangkat dan memberhentikan hakim serta penuntut umum juga menentukan anggaran serta amandemen terhadap Statuta. 188 Lampiran ini dikarenakan prinsip non-reservasi dalam proses ratifikasi Statuta Roma, yang berarti bahwa negara pihak tunduk pada semua aturan dalam Statuta Roma. Salah satu hal yang patut dicontoh oleh Indonesia dalam rangka pembaharuan sistem hukum, khususnya dalam Pengadilan HAM yaitu mekanisme pre-trial48 di MPI yang sangat berbeda dengan pra-peradilan dalam sistem KUHAP. Dalam sistem KUHAP, pra-peradilan merupakan pemeriksaan awal berkaitan dengan proses beracara yang diantaranya berkenaan dengan49: i. Sah tidaknya penangkapan atau penahanan tersangka, diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; ii. sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penyidikan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; iii. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain dengan kuasa dari tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 48 Istilah pre-trial tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena belum ditemukan padanan kata yang tepat dan bahwa mekanisme ini adalah praktek yang berbeda dengan hukum acara pidana di Indonesia, untuk menghindari ambiguitas dan perbedaan penafsiran maka istilah pr-trial dibiarkan sebagaimana istilah aslinya. 49 Pasal 1 angka 10 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 189 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Sementara itu, ada tiga cara di mana MPI dapat memulai proses penyelidikkan (trigger mechanism) yakni (i) Negara pihak boleh melaporkan suatu “situasi” kepada Penuntut Umum di mana telah terjadi satu atau lebih kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI (Pasal 13 (a) dan pasal 14 Statuta Roma) , (ii) atas inisiatif Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan proprio motu50, karena adanya informasi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI, dan Penuntut Umum telah diberikan kewenangan oleh Pre-Trial Chamber untuk melaksanakan penyelidikan pidana (Pasal 13(c) dan Pasal 15 Statuta Roma), () atas dasar laporan dari Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di mana telah terjadi satu atau lebih kejahatan (yang berada dalam yurisdiksi MPI) berdasarkan Bab VII Piagam PBB (Pasal 13(b) dan 52(c) Statuta Roma)51. Trigger mechanism yang didasarkan atas inisiatif Penuntut Umum berdasarkan penyelidikan proprio motu karena ada informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya harus melewati mekanisme PreTrial Chamber terlebih dahulu. Penuntut Umum harus menganalisis keseriusan informasi tersebut dengan mencari keterangan tambahan dari badanbadan PBB, organisasi antar pemerintah, LSM, dan sumber lain yang dapat dipercaya. Ketika Penuntut Umum menyimpulkan bahwa terdapat dasar yang masuk akal untuk melaksanakan 50 Bahasa latin yang berarti tindakan berdasarkan insiatif sendiri 51 A Joint Project of Rights and Democracy and The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, International Criminal Court : Manual for the Ratification of the Rome Statute, Vancouver, 2002, p. 4 190 Lampiran penyelidikkan, Penuntut Umum dapat meneruskan permohonan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikkan kepada Sidang Pre-Trial yang terdiri dari tiga orang hakim disertai dengan keterangan pendukungnya52. Korban secara khusus dapat mengirimkan wakilnya dalam Sidang Pre-Trial, khususnya untuk mendukung Sidang agar memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan. Jika Sidang Pre-Trial, setelah memeriksa permohonan dan bahan pendukung, menyatakan adanya ‘dasar yang masuk akal’ untuk memulai pennyelidikan yang merupakan yurisdiksi dari Mahkamah, maka Sidang harus segera memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melaksaksanakan penyelidikan (pasal 15(4) Statuta Roma). Namun jika Sidang Pre-Trial menolak untuk memberikan wewenang, hal ini tidak menutup kemungkinan Penuntut Umum untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan fakta-fakta atau bukti baru (Pasal 15(5) Statuta Roma).53 Mekanisme pre-trial memang tidak dikenal dalam KUHAP Indonesia karena berasal dari sistem hukum Anglo Saxon yang dipraktekan dalam proses persidangan. Namun dalam prinsip-prinsip dalam mekanisme ini telah digunakan dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan istilah dismissal process 52 Rules of Procedure and Evidence, UN Doc.PCNICC/2000/INF/3/Add.3, Rule 50 53 William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001,p. 98 191 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dan juga digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan istilah pemeriksaan persiapan.54 Belajar dari pengalaman Pengadilan HAM dalam kasus di Indonesia, mekanisme ini akan memberikan banyak manfaat jika dipraktekan dalam penegakan hukum HAM di Indonesia, diantaranya: i. Pre-trial ini dapat mencegah terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyelidik (KOMNAS HAM) dengan penyidik (Kejaksaan Agung) yang biasanya disebabkan karena ketidaklengkapan hasil penyelidikan atau karena hal teknis lain misalnya tidak disumpahnya penyelidik. ii. Kelengkapan bukti-bukti, perlindungan saksi dan korban, jumlah saksi yang akan dibawa ke persidangan,dll, dapat dipersiapkan semaksimal mungkin dalam Sidang Pre-Trial sehingga terhindar dari pengadilan yang dinilai seolah tidak serius.55 iii. Hal-Hal yang telah diperiksa dan diputuskan 54 Diskusi dengan A.H Semendawai, ELSAM, 20 Desember 2005 dan wawancara dengan Rudi M. Rizki, pakar HAM, 29 Desember 2005. 55 Pengalaman pada persidangan kasus Timor-Timur dimana diantaranya terdapat ketidakseimbangan antara saksi yang meringankan dan memberatkan, tidak ada perlindungan saksi dan korban sebagaimana layaknya pengadilan HAM internasional, para saksi yang ternyata tidak dapat hadir dalam persidangan karena alasan biaya dan transportasi, kurangnya fasilitas penerjemah bagi saksi yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dakwaan tunggal dan ’kurang memanfaatkan’ perangkat hukum lain yang terkait sehingga dapat mengakibatkan terdakwa dapat dengan mudah lepas dari dakwaan/tuntutan, dan hal-hal teknis maupun nonteknis lainnya. Pernyataan Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, hakim ad hoc Pengadilan HAM Indonesia, Rudi M. Rizki, pakar HAM Internasional, hakim ad hoc Pengadilan HAM Indonesia. 192 Lampiran oleh Pre-Trial tidak perlu lagi diperiksa dalam Pengadilan sehingga akan tercapai tujuan pengadilan yang murah, cepat dan efisien. Sebenarnya mekanisme ini pernah digunakan dalam kasus Trisakti Semanggi Satu (TSS I) di mana pada akhirnya DPR memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM yang berat pada kasus tersebut. Namun tidak dilakukan dengan tepat karena mekanisme pre-trial dilakukan oleh DPR yang notabene adalah institusi politik, dimana seharusnya diberikan pada institusi yudikatif. Disini terlihat jelas pengaruh politik masih sangat besar dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Inilah salah satu hal yang harus diperbaiki dalam sistem hukum kita. Dengan kata lain, dengan meratifikasi Statuta Roma ini sangat mendukung dan dapat mempercepat upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya berkenaan dengan mekanisme penegakkan hukum Indonesia. d. Mengefektifkan sistem hukum nasional. 56 Indonesia tidak perlu khawatir untuk meratifikasi Statuta Roma ini, karena dalam Statuta Roma itu sendiri ditegaskan secara nyata bahwa penyelesaian suatu perkara tetap mengutamakan upaya hukum nasional baik secara formal maupun material dengan prinsip dan asas-asas yang sesuai dengan hukum internasional. Artinya MPI justru membuka kesempatan yang besar untuk mengefektifkan sistem hukum nasional dan pengadilan domestik56 Ini juga yang menjadi alasan sebagian besar Negara-negara Uni Eropa dalam meratifikasi Statuta Roma. Lihat www.npwj.org 193 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dalam menuntut para pelaku kejahatan. Ini yang disebut pendekatan komplementer melalui pola yang strategis dan lebih terfokus.57 Kita telah memiliki instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM yang cukup memadai, seperti dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang N0.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan KUHP, sehingga kekhawatiran akan adanya intervensi dari forum internasional dapat dieliminir melalui implementasi yang tegas atas instrumen-instrumen tersebut. Artinya hal ini dapat mendorong para penegak hukum dan pemerintah serta semua pihak untuk turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. e. Sebagai motivator dalam peningkatan upaya perlindungan HAM. 57 Adanya MPI ini dapat menjadi motivator untuk terus menggiatkan dan meningkatkan peran Indonesia dalam upaya perlindungan HAM internasional, seperti tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu turut aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Serta menunjukan komitmen Indonesia bahwa Indonesia dapat melaksanakan perlindungan HAM melalui pengadilan HAM secara efektif dan efisien dengan menjamin prinsip pertanggungjawaban individu, penuntutan dan penghukuman bagi pelaku kejahatan. Secara politis hal ini dapat mengangkat status Indonesia di mata pergaulan internasional. www.hrw.org, www.untreaty.un.org 194 Lampiran f. Menjadi preseden positif bagi khususnya di Asia Tenggara. negara lain, Indonesia sebagai Negara besar di Asia Tenggara seharusnya dapat menjadi contoh dan dapat mempengaruhi negara-negara lain di sekitarnya. Namun, dalam hal menjadi pihak dalam Statuta Roma, justru negara-negara di Asia Tenggara yang biasanya dianggap tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh telah melakukan penandatanganan dan meratifikasi Statuta Roma, seperti Kamboja dan Timor Leste58. Sebaliknya, negara-negara berpengaruh justru belum bertindak apapun, hanya Filipina dan Thailand yang telah menandatangani Statuta Roma meskipun belum meratifikasinya hingga sekarang. Demikian pula dengan negara-negara besar lainnya di dunia.59 Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia Tenggara dapat menjadi contoh (trendsetter) yang baik dalam upaya perlindungan HAM dan penegakan hukum internasional khususnya bagi negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. B. Kerugian Tidak Meratifikasi Statuta Roma Kerugian secara umum tentunya adalah kebalikan dari keuntungan-keuntungan seperti yang telah diuraikan di atas. Namun terdapat beberapa hal lain disamping hal tersebut 58 Kamboja melakukan penandatanganan pada 23 Oktober 2000 dan meratifikasi pada 11 april 2002. lihat www.amnesty.org. 59 lihat selengkapnya dalam www.amnesty.org dan www.iccnow.org. 195 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia diatas yang menjadi perhatian khusus, diantaranya: a. Tidak memiliki posisi tawar yang signifikan Kerugian suatu negara tidak meratifikasi Statuta Roma diantaranya adalah negara tidak dapat memberikan suara berkaitan dengan isi maupun pelaksanaan Statuta. Kesempatan untuk mengajukan warga negaranya sebagai hakim dan jaksa di MPI juga tidak dimungkinkan. Namun berbeda bila negara tersebut mendukung dan meratifikasi Statuta Roma. b. Reformasi hukum nasional akan berjalan lambat apabila tidak termotivasi dengan tidak adanya keinginan untuk memperbaiki sistem yang berlaku. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma yang berisi aturan mengenai bentuk-bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang bersifat dinamis tetapi tidak diatur dalam KUHP dapat memotivasi negara untuk memperbaiki hukum nasional terutama sistem peradilannya, termasuk dalam hal hukum acara karena setelah meratifikasi Statuta, negara pihak harus menyesuaikan hukum domestiknya agar berjalan sesuai aturan pelaksanaan dan isi Statuta. c. Praktek impunitas Belajar dari pengalaman penegakkan hukum di Indonesia seperti yang telah diuraikan dalam Bab I di mana masih banyak terjadi praktek impunitas. Para penguasa atau para komandan/atasan masih bisa berlindung dari jeratan hukum karena alasan 196 Lampiran tugas negara atau karena tidak memadainya instrumen hukum Indonesia yang memberikan celah untuk membebaskan mereka. Dalam konteks ini diakibatkan oleh unsur politis masih sangat kental dalam penegakkan hukum di Indonesia. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi ketika Indonesia meratifikasi Statuta Roma karena Indonesia tidak ingin dinilai tidak mau (unwilling) untuk menghukum pelaku (yang merupakan komandan/ atasan tersebut) ketika terbukti Pengadilan tidak independen atau tidak serius dalam menghukum pelaku. d. Resiko intervensi asing dalam kedaulatan negara semakin besar. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dengan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 tidak berarti bahwa Indonesia terlepas dari ancaman intervensi pihak asing terhadap kedaulatan hukum negaranya. Resiko intervensi pihak asing justru semakin besar jika tidak meratifikasi, karena prinsip komplementer hanya berlaku bagi negara pihak Statuta Roma. Dengan menerapkan yurisdiksi universal, suatu negara dapat mengadili warga negara lain yang melakukan kejahatan internasional dengan menggunakan mekanisme hukum domestiknya. Jika bukan merupakan Negara pihak dari Statuta Roma, maka Negara tersebut tidak dapat membela warga negaranya yang diadili melalui penerapan yurisdiksi universal, karena tidak dapat mengajukan penerapan prinsip komplementer yang ada dalam statuta roma. e. Tekanan dari dunia internasional. 197 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Dari sisi pergaulan internasional, jika tidak segera meratifikasi statuta roma, Indonesia dapat dianggap tidak mendukung upaya pencapaian tujuan perdamaian dunia, yang salah satunya adalah penghormatan dan perlindungan HAM dengan cara penegakan hukum. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dapat dianggap hanya sebagai retorika politis karena dalam prakteknya Indonesia tidak mendukung upaya-upaya yang mengarah pada kemajuan perlindungan HAM. f. Kesiapan Infrastruktur dan Instrumen Hukum Indonesia Statuta Roma sebagai pembentuk MPI merupakan angin segar dan bentuk solidaritas sekaligus bentuk pertanggungjawaban masyarakat internasional terutama dalam upaya penegakan hukum pidana internasional dengan salah satu tujuannya yaitu menghentikan impunitas para pelaku kejahatan internasional. Seperti dikemukakan di atas, bahwa untuk mengadopsi ketentuan hukum internasional ke dalam ketentuan hukum nasional melaui kebijakan legislatifnya (diantaranya kebijakan meratifikasi konvensi internasional), perlu dipertimbangkan berbagai aspek untuk mengantisipasi adanya perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Dalam implementasinya di tingkatan hukum nasional diperlukan pertimbangan dari berbagai aspek yang berkembang, diantaranya sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi. Hanya dengan meratifikasi Statuta Roma, kita dapat memahami dengan baik melalui implementasinya di tingkat nasional. 198 Lampiran C. Pro Kontra Ratifikasi Mahkamah Pidana Internasional Silang Pendapat mewarnai rencana ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Kekhawatiran terbesar muncul karena pendapat yang mengatakan bahwa ketika Indonesia meratifikasi Statuta Roma berarti menyetujui dan mengikatkan diri terhadap semua aturan dalam Statuta Roma.60 Hal ini menurut beberapa kalangan sangat beresiko khususnya bagi negara berkembang, dikarenakan pandangan bahwa MPI akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan Mahkamah terhadap pengadilan/sistem hukum suatu negara. Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah adalah sebuah hasil proses perundingan demokratis yang ingin menciptakan “international justice” dan lebih mengedepankan nilainiliai hukum sesuai dengan tujuan utama PBB (Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB)61 diantaranya untuk mencegah berkembangnya kejahatan-kejahatan internasional62. 60 Merupakan reaksi terhadap prinsip non-reservasi yang dianut oleh Statuta Roma 1998 dalam Pasal 120 yang menyatakan bahwa “No reservation may be made to this statute.” Artinya bila suatu Negara meratifikasi dan menjadi pihak dalam Statuta ini maka Negara harus menerima dan melaksanakan semua ketentuan dalam Statuta Roma tanpa kecuali. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dan tidak sampainya tujuan yang dimaksud dalam pembuatan Statuta. Lihat William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001, hlm.159-160., Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, BadenBaden : Nomos Verl Ges., 1999, hlm. 1251-1263. 61 Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB: “Tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian” 62 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003, hlm.544. 199 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Kekhawatiran di atas sebenarnya tidak akan terjadi jika kita memahami benar mengenai prinsip komplementer (complementary principle) seperti yang telah disinggung dalam Bab I. Prinsip ini tertuang dalam paragraf 10 Mukadimah63 dimana Mahkamah hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya sebagai pelengkap bilamana hukum nasional tidak mampu (unable) dan atau tidak mau (unwilling) melakukan suatu proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah. Pasal 1 Statuta Roma juga menyatakan bahwa tujuan pembentukan Mahkamah adalah untuk menerapkan jurisdiksi atas pelaku tindak pidana internasional sebagaimana terdapat dalam Statuta dan memiliki fungsi untuk melengkapi (complementarity) sistem peradilan nasional Negara.64 Singkatnya, Mahkamah Pidana Internasional dilarang melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan ketika pengadilan nasional sedang mengadili kejahatan yang sama dan (i) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, (ii) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan; () kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah (Pasal 17 Statuta Roma). Dan sebagai tambahan, (iv) orang yang bersangkutan telah dihukum atau dibebaskan atas kejahatan yang sama, melalui pengadilan 63 Paragraf 10 Preamble Statuta Roma: “Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”. 64 Hans-Peter Kaul, Breakthrough in Rome Statute of the International Criminal Court; Law and State, vol.59/60, Supp.10 (a/49/10) 200 Lampiran dan layak dan adil (Pasal 17(c) dan 20 Statuta Roma).65 Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan mekanisme hukum nasional suatu Negara kecuali jika Negara tersebut “tidak mau” (unwilling) atau “tidak mampu” (unable) untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku sehingga kejahatan tersebut menjadi yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17 Statuta Roma). Selain itu, prinsip komplementer ini tidak hanya berlaku terhadap Negara pihak Statuta saja tetapi juga terhadap negara yang bukan merupakan pihak Statuta Roma (Pasal 18 (1)) tetapi memberikan pernyataan sebagai pengakuannya atas jurisdiksi MPI. Misalnya, seorang warga negara bukan pihak Statuta yaitu negara A telah melakukan kejahatan internasional dalam wilayah teritori negara B yang merupakan pihak dari Statuta Roma, kemudian ia kabur ke negara C yang bukan merupakan pihak Statuta Roma. Negara C melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara A tersebut dengan dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dalam perjanjian internasional dan tersangka berada dalam wilayah teritorinya (the forum deprehensionis principle) atau juga karena didasarkan pada prinsip universalitas. Dan Mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila terbukti bahwa Negara C memiliki kemauan dan mampu untuk melaksanakan pengadilan yang layak dan adil.66 Dengan demikian, Mahkamah merupakan the last resort atau disebut juga ultimum remedium. Ini merupakan jaminan bahwa Mahkamah bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu Negara. Mahkamah 65 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 342. 66 ibid 201 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dapat menerapkan jurisdiksinya diantaranya67 pada negara yang menjadi pihak yakni negara peratifikasi Statuta Roma. 67 Jurisdiksi MPI berlaku pada Negara pihak atau Negara bukan pihak tapi mengakui jurisdiksi MPI melalui pernyataan/deklarasi tertulis. 202 Lampiran BAB IV Implikasi Ratifikasi Statuta Roma terhadap Sistem Hukum Indonesia Negara yang sudah menjadi Pihak dalam Statuta Roma berarti negara tersebut mengakui bahwa MPI memiliki yurisdiksi di negaranya terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta68, serta terhadap warganegara atau orang lain yang berada dalam wilayah teritori negara pihak tersebut untuk diadili di MPI dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dalam Statuta. Dengan demikian, negara pihak harus menjamin bahwa tidak ada halangan dalam hal kerjasama dengan MPI tersebut. Negara yang telah menjadi pihak Statuta berarti memiliki dua kewajiban fundamental dalam hal:69 68 Kejahatan-kejahatan tersebut adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. 69 Amnesti International, International Criminal Court : Checklist for Effective Implementation, July 2000,p. 2 203 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 1. Complementarity : Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 17 Statuta Roma, Negara pihak mengakui bahwa negara, bukan MPI, memiliki tanggungjawab utama dalam mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tidak hanya Negara yang memiliki kewajiban untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, namun MPI juga dapat mengadilinya hanya apabila Negara tersebut tidak mampu dan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Jika MPI menjadi pelengkap efektif suatu Negara dalam sistem pengadilan internasional, maka Negara tersebut harus melaksanakan tanggungjawabnya. Negara harus membuat dan menegakkan hukum nasionalnya yang mengatur bahwa kejahatan terhadap hukum internasional adalah berarti kejahatan terhadap hukum nasionalnya. Negara yang gagal melaksanakan kewajibannya tersebut akan beresiko untuk dianggap sebagai Negara yang tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI. Membuat peraturan implementasi yang efektif akan menunjukan bahwa Negara peduli terhadap kewajiuban utamanya berdasarkan hukum internasional untuk menjamin ditegakkannya hukum bagi kejahatan tersebut dan akan mengadilinya melalui pengadilan nasionalnya. 2. Kerjasama yang penuh (fully cooperation): Ketika MPI telah menetapkan bahwa MPI memiliki kewajiban untuk melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan prinsip komplementer, Negara pihak setuju untuk berkerjasama penuh dengan MPI dalam hal penyelidikkan dan penuntutan terhadap 204 Lampiran kejahatan yang menjadi yurisdiksi MPI. Kewajiban ini berarti bahwa Negara harus memberikan perlakuan khusus dan kekebalan tertentu kepada aparat penegak hukum dan personil MPI70. Tanpa perlakuan khusus dan kekebalan seperti ini, akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin, bagi MPI untuk berfungsi efektif71. MPI memiliki perjanjian terpisah yang mengatur mengenai perlakuan khusus dan kekebalan bagi staf MPI (Agreement on Privilege and Immunities of the MPI)72 dan Pasal 48 Statuta Roma menjelaskan keharusan Negara pihak untuk meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian ini. Beberapa aturan yang penting dalam perjanjian ini diantaranya adalah Penuntut Umum dan Pembela MPI dapat melaksanakan penyelidikan yang efektif dalam yurisdiksinya, dan pengadilan nasional serta aparat penegak hukumnya harus bekerjasama penuh dalam memberikan dokumen, penempatan serta perampasan asetaset dari tersangka, melaksanakan pencarian dan perampasan barang bukti, melindungi saksi serta menahan dan menyerahkan tersangka kepada MPI. Negara juga harus bekerjasama dengan MPI dalam menegakkan hukuman dengan membuat fasilitas penahanan bagi pelaku yang telah dihukum. Untuk lebih mengefektifkan kerjasama dengan MPI, Negara harus memberikan pendidikan dan 70 Coalition for the International Criminal Court, Question and Answer : The Privileges and Immunities Agreement of the ICC, Last updated 13 February 2003, diambil dari www.iccnow.org. 71 ibid. 72 Agreement on Privilege and Immunities of the ICC dirancang oleh Komisi Persiapan ICC dan diadopsi oleh Assembly of State Parties (ASP) tanggal 9 September 2002. Perjanjian ini akan berlaku setelah diratfikasi oleh 10 negara. Hingga saat ini ada 31 negara yang sudah meratifikasinya. 205 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia pelatihan kepada aparat penegak hukum (jaksa, hakim, pengacara) serta publik mengenai kewajiban Negara berdasarkan Statuta Roma. Untuk menjamin bahwa sistem hukum internasional terintegrasi dengan penuh, dimana pengadilan nasional dan internasional saling menguatkan satu sama lain, Negara tidak hanya harus melaksanakan kerjasama dengan MPI namun juga dengan ICTY dan ICTR. Negara juga harus mengakui yuirsdiksi universal terhadap kejahatan internasional dan memperkuat sistem kerjasama antar Negara melalui ekstradisi dan bantuan hukum yang saling menguntungkan. Uraian diatas adalah gambaran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban suatu Negara apabila memutuskan untuk menjadi pihak dalam MPI. Namun, mengingat Indonesia belum meratifikasi MPI, maka muncul pertanyaan manakah yang harus didahulukan antara ratifikasi Statuta Roma ataukah membuat peraturan implementasi Statuta Roma? Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, bahwa setelah Negara meratifikasi Statuta Roma maka Negara tersebut berhak mengirimkan satu orang perwakilannya dalam Majelis Negara Pihak dan memiliki satu suara di Majelis. Berdasarkan Pasal 112 Statuta Roma, Majelis Negara Pihak memiliki tugas yang sangat penting antara lain memilih hakim dan jaksa dan menentukan anggaran Mahkamah.73 Sehingga, Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan fungsi MPI. Berbeda jika suatu Negara hanya merupakan penandatangan tapi bukan peratifikasi Statuta Roma. 73 A Joint Project of Rights and Democracy and The International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, International Criminal Court : Manual for the Ratification of the Rome Statute, Vancouver, 2002, p.10 206 Lampiran Negara tersebut hanya diberikan status sebagai peninjau dan tidak memiliki suara dalam Majelis Negara Pihak. Beberapa Negara di Eropa dan Afrika berdasarkan konstitusinya, biasanya harus mempersiapkan undangundang implementasi dahulu sebelum meratifikasi sebuah perjanjian internasional. Namun demikian, mereka akhirnya memutuskan untuk meratifikasi Statuta Roma terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan waktu antara ratifikasi dan berlakunya Statuta Roma (entry into force) untuk membuat rancangan undang-undang implementasi mereka74. Jadi dapat disimpulkan, bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma terlebih dahulu akan memberikan lebih banyak manfaat bagi negara khususnya Indonesia, jika dibandingkan dengan membuat dan mengesahkan terlebih dahulu undang-undang implementasinya. Namun hal itu bukan berarti persiapan pembuatan peraturan implementasi tidak penting, karena kesiapan Indonesia dalam membuat peraturan implementasi Statuta Roma akan dapat meminimalkan intervensi internasional (karena Indonesia tidak akan dianggap tidak mau dan tidak mampu) dan mengefektifkan mekanisme penegakkan hukum nasionalnya. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah dari 100 negara peratifikasi Statuta Roma, hanya 36 negara yang sudah mengesahkan undang-undang yang mengimplementasikan berbagai kewajiban yang tertuang dalam Statuta Roma dan berbagai aturan hukum internasional kedalam hukum nasionalnya75. Dari 36 negara tersebut hanya 74 Ibid ,p.11. Proses ratifikasi Negara-negara ini dilakukan sebelum Statuta Roma berlaku yakni sebelum 1 Juli 2002. 75 Beberapa diantara 64 Negara Pihak lainnya telah memiliki rancangan undangundang implementasi, dan masih dalam proses untuk pengesahannya. Proses 207 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 19 negara yang mencantumkan kewajiban komplementer (complementarity obligations) dan kewajiban kerjasama (cooperation obligations) dalam Undang-Undangnya76. Dan, hanya 31 negara yang meratifikasi Agreement on Privileges and Immunities of the MPI77 dan tidak ada satu Negara pun yang sudah mengimplementasikannya.78 A. Peraturan Perundangan yang Perlu Disinkronisasikan Setelah melihat uraian hal-hal apa saja yang harus diakomodir dalam peraturan implementasi Statuta Roma, maka kita juga harus melihat aturan-aturan dalam instrumen hukum nasional Indonesia. Apakah telah selaras dengan aturan-aturan Statuta Roma, atau justru malah banyak yang bertentangan sehingga perlu disinkronisasikan? Dibawah ini akan dijelaskan beberapa aturan yang kurang memadai, beberapa diantaranya ada yang bertentangan, dengan aturan-aturan dalam Statuta Roma. Sehingga Indonesia perlu segera melakukan pembenahan baik dengan melakukan amandemen dari instrumen hukum yang telah ada, atau membuat undang-undang baru untuk mengakomodir aturan-aturan tersebut. Juga disertai dengan praktek beberapa Negara yang telah merafikasi Statuta pembuatan rancangannya sebagian dilakaukan dalam bentuk diskusi tertutup tanpa melibatkan masyarakat umum, walaupun ada beberapa Negara yang juga turut melibatkan masyarakat umum dalam pembuatan rancangannya (Peru, Democratic Republic of Congo, UK). Data diperoleh dari Amnesti International, International Criminal Court : The Failure of States to Enact Effective Implementing Legislation, September 2004, p. 1 76 Negara-negara tersebut diantaranya adalah : Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Iceland, Lithuania, Malta, The Netherlands, New Zealand, Slovakia, South Africa, Spain dan UK. Data diperoleh dari Amnesti Internasional…ibid, p.2 77 www.iccnow.org 78 Amnesty International, Op Cit, p. 42 208 Lampiran Roma dan membuat undang-undang implementasinya. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah: 1. Aturan mengenai kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI Aturan mengenai kejahatan dalam yurisdiksi MPI memang belum memadai dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM hanya mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (Pasal 8 untuk kejahatan genosida, dan Pasal 9 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan), sedangkan kejahatan perang belum terakomodir dalam aturan hukum di Indonesia. Namun jika merujuk dalam Rancangan KUHP Indonesia ketiga kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI ini sudah diatur79, sayangnya hingga saat ini rancangan tersebut belum disahkan sehingga belum bisa dijadikan dasar hukum. Saat ini di Indonesia memang masih terjadi perdebatan panjang mengenai aturan kejahatan dalam yurisdiksi MPI. Sejauh ini, ada tiga usulan: a. Mengamandemen Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan memasukkan kejahatan perang ke dalamnya; b. Memasukkan ketiga jenis kejahatan itu menjadi tindak pidana dalam KUHP yang baru. Seperti yang sudah diatur dalam Rancangan KUHP 2004; 79 Kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC diatur dalam BAB IX Rancangan KUHP (2004) tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia, yakni dalam Pasal 390 tentang tindak pidana genosida, Pasal 391 tentang tindak pidana kemanusiaan dan Pasal 392 mengenai tindak pidana perang dan konflik bersenjata. 209 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia c. Membuat undang-undang baru yang mengakomodir ketiga jenis kejahatan tersebut 80 Sebagai perbandingan, Negara Swiss yang sudah meratifikasi Statuta Roma sejak tanggal 12 Oktober 2001 juga mengalami kendala yang sama ketika harus mengakomodir kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI ke dalam hukum nasionalnya. Setelah Hukum Federal (Federal Law) Swiss tentang kerjasama dengan MPI dan amandemen Hukum Pidana Swiss tentang pelanggaran terhadap tata pelaksanaan peradilan disahkan bersamaan dengan berlakunya MPI (July 2002), selanjutnya masalah yang masih dibahas dalam interdepartmental working group adalah mengenai substansi hukum pidana tentang kejahatan yang diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma. Apakah akan dimasukkan dalam Hukum Pidana yang sudah ada atau dibuat undangundang baru? Akhirnya, walaupun belum final, ada kecenderungan untuk memasukkan kejahatan tersebut ke dalam Hukum Pidana serta ke dalam Hukum Pidana Militer Swiss.80 Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab I mengenai kelemahan sistem hukum di Indonesia, ketidakmemadaian aturan dalam Undang-Undang di Indonesia tidak hanya dalam hal aturan yang memuat ketiga jenis kejahatan dalam yurisdiksi MPI namun juga dalam hal aturan beracara serta Jurg Lidenmann, The Ratification and Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in Switzerland, diambil dari International Academy of Comparative Law, International Criminal Courts, International Congress of Comparative Law, Brisbane 14-20 July 2002. Hingga saat ini, Swiss belum mengesahkan peraturannya mengenai kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC tersebut. 210 Lampiran unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdksi MPI. Sehingga seiring dengan dibenahinya aturan perundangan yang mengatur kejahatan dalam yurisdiksi MPI, maka aturan beracaranya pun harus segera dibenahi. Dan agar terdapat satu visi yang sama antara aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketiga kejahatan tersebut sebagai suatu delik pidana maka seharusnya ada aturan yang jelas mengenai unsur-unsur kejahatannya, baik dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang maupun dalam buku pedoman tersendiri seperti element of crimes dalam Statuta Roma.81 2. Aturan mengenai kadaluarsa Bagian (1) di atas menjelaskan bahwa semua aturan kadaluarsa tidak berlaku bagi kejahatan dalam yurisdiksi MPI. Aturan tidak berlakunya kadaluarsa bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang juga telah lama diatur dalam Konvensi tentang Tindak Berlakunya Kadaluarsa Bagi Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tahun 1968.82 Sementara dalam KUHP di Indonesia, aturan kadaluarsa masih berlaku sebagai salah satu faktor gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, hal yang 81 The Asia Foundation bekerjasama dengan ELSAM telah merampungkan pembuatan Hukum Acara dan Pembuktian bagi Undang-Undang 26/2000 serta Unsur-Unsur Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan serta UnsurUnsur Pertanggungjawaban Komando. Saat ini draft yang sudah final tersebut telah diteruskan ke Mahkamah Agung untuk lebih lanjut disahkan sebagai PERMA. 82 Pasal 1(b) 1968 Convention on Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity menyatakan statuta ini berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan baik yang terjadi pada saat damai maupun konflik bersenjata seperti yang diatur dalam Piagam Nuremberg serta kejahatan genosida seperti yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948 211 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia sama juga masih tetap diatur dalam Rancangan KUHP 200483. Namun dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000, secara eksplisit dinyatakan bahwa aturan kadaluarsa tidak berlaku bagi pelanggaran berat HAM84. Agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menerapkan aturan kadaluarsa tersebut, aturan implementasi Statuta Roma di Indonesia nantinya harus secara eksplisit menyatakan bahwa aturan kadaluarsa tidak berlaku bagi kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. 3. Aturan mengenai Ne bis in Idem Ne bis in idem berarti seseorang tidak boleh diadili dua kali atas suatu perbuatan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Ne bis in idem adalah merupakan prinsipprinsip umum hukum pidana (general principle of criminal law), dan prinsip ini diatur dalam Statuta Roma (Pasal 21) juga dalam KUHP Indonesia (Pasal 76) seperti halnya prinsip-prinsip umum hukum pidana lainnya (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, non-retroaktif, dll) . Namun, prinsip ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang justru merupakan satu-satunya Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang berat. Sebagai prinsip umum hukum pidana, maka 83 Kadaluarsa dalam hal penuntutan dan pelaksanaan pidana diatur dalam : Pasal 76, 78-82, 84,85 KUHP, Pasal 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153 Rancangan KUHP 2004. 84 Pasal 46 Undang-Undang 26/2000 menyatakan bahwa : “Untuk pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. 212 Lampiran sudah seharusnya prinsip-prinsip umum ini selalu dicantumkan di setiap konvensi atau UndangUndang yang berkaitan dengan hukum pidana, demikian pula dalam aturan implementasi Statuta Roma Indonesia nantinya, jangan sampai prinsipprinsip umum ini tidak dicantumkan seperti dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. 4. Aturan mengenai pidana mati Statuta Roma menjelaskan bahwa pidana mati tidak berlaku bagi kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah. Pidana maksimum yang berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang adalah pidana penjara seumur hidup. Dewan Keamanan PBB jug telah mengecualikan aturan pidana mati dalam Statuta ICTY dan ICTR untuk kejahatan yang sama dengan yuridiksi MPI. Penerapan pidana mati juga bertentangan dengan hak untuk hidup seperti yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hampir setengah jumlah Negaranegara di dunia (118 negara) sudah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya85. Namun yang menjadi perhatian serius sekarang ini adalah beberapa Negara pihak Statuta Roma seperti Democratic Republic of Congo (Pasal 17), Mali (Pasal 32), Republic of Congo (Pasal 2,3,5,7,8,9,dan 10), Uganda (bagian 7(3)(a) dan Pasal 9(3)(a)), telah mencantumkan aturan hukuman mati dalam rancangan undang-undang implementasinya86. Hal 85 Amnesti International, Abolitionist and Retentionist Countries (diambil dari www.amnesti.org/pages/deathpenalty-countries-eng) 86 Amnesti International, International Criminal Court : The Failure of States to Enact Effective Implementing Legislation, September 2004, p.27 213 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia ini jelas bertentangan dengan Statuta Roma karena Statuta Roma menyatakan bahwa Negara pihak harus mengecualikan aturan pidana mati terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang dalam hukum nasionalnya. Indonesia adalah termasuk Negara yang masih menerapkan pidana mati. Aturan pidana mati diatur baik dalam KUHP dan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM87. Sementara dalam Rancangan KUHP baru (2004), dijelaskan bahwa pidana mati tidak berlaku bagi tindak pidana hak asasi manusia.88 Jika Indonesia meratifikasi Statuta Roma, tentu saja aturan pidana mati ini akan bertentangan dengan Statuta, kecuali jika pada akhirnya Rancangan KUHP sudah disahkan. 5. Aturan mengenai amnesti Dengan memberlakukan amnesti terhadap pelaku tindak pidana maka sebagai konsekwensinya adalah: (1) penuntut akan kehilangan hak atau kewenangannya untuk melaksaksanakan penyidikkan, (2) semua hukuman yang diberlakukan bagi tindak pidana tersebut dihapuskan. Alasan pemberian amnesti adalah karena amnesti dianggap cara yang paling baik untuk menyembuhkan sakit masyarakat atas tejadinya konflik bersenjata, huru-hara, dengan cara melupakan kesalahankesalahan masa lalu dan menghapuskan semua 87 Pidana mati diatur dalam : Pasal 10 dan 11 KUHP dan Pasal 36-37 UndangUndang 26/2000. 88 Rancangan KUHP 2004 menjelaskan pidana maksimum untuk genosida adalah 15 tahun (Pasa390), tindak pidana kemanusiaan maksimum 15 tahun (Pasal 391), dan tindak pidana perang dan konflik bersenjata maksimum 15 tahun (Pasal 392). 214 Lampiran pelaku kejahatan dari semua pihak peserta konflik. Cara ini dipercaya merupakan cara yang paling tepat dan efisien untuk menghentikan kebencian dan mencapai rekonsiliasi nasional. Namun, dalam beberapa kasus, para pejabat militer serta pimpinan polisi banyak yang mendapatkan amnesti dengan alasan untuk memberikan perubahan yang diharapakan dalam pemerintahan dan agar terbebas dari penuntutan di masa mendatang89. Misalnya setelah Perang Dunia II, Perancis dan Itali memberikan amnesti kepada warganegaranya yang telah berperang melawan Jerman. Chile dan Argentina memberikan amnesti kepada semua kejahatan yang terjadi selama periode pasca Allende. Sementara Peru dan Uruguay juga memberikan amnesti kepada semua pelanggaran berat Hukum HAM termasuk penganiayaan.90 89 90 Dihadapkan oleh kenyataan untuk menyelamatkan demokrasi terlebih dahulu, masyarakat-masyarakat transisi banyak yang memilih kebijakan amnesty ketimbang pengajuan ke Pengadilan. Jalan inilah yang ditempuh untuk menyelesaikan masa lalu mereka, untuk menarik garis pembeda yang tajam dari rezim terdahulu: bahwa rezim ini bukanlah kelanjutan dari rezim lama. Kebijakan amnesty merupakan necessary evil yang harus diambil oleh pemerintah baru untuk mencapai tujuan yang lebih besar yakni menjaga stabilitas demokrasi yang masih rapuh yang sewaktu-waktu dapat berbalik ke arah sistem politik semula yang otoriter. Pemberian Antonio Casesse, International Criminal law, Oxford University Press, New York, 2003, p. 312. Ibid. 215 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia amnesty dengan demikian dapat dipandang sebagai tindakan khusus dalam konteks menyelesaikan masalah transisi.91 91 92 93 94 Namun, dalam berbagai konvensi internasional aturan hukum amnesti sudah dianggap sebagai aturan hukum yang bertentangan dengan aturanaturan hukum mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya aturan yang mengatur bahwa semua pelaku kejahatan internasional harus dihukum.92 Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak selamanya amnesty bertentangan dengan hukum internasional, karena amnesty bisa dibenarkan sebagai bentuk derogation (pengurangan) yang dibenarkan dalam hukum internasional.93 Jose Zalaquett, mantan pengacara HAM Amnesti International, berkewarganegaraan Chille, menyatakan bahwa negara yang sedang menghadapi masa transisi, dapat masuk ke dalam konteks ”public emergency” yang diatur dalam Pasal 4 Persetujuan Internasional hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga diperbolehkan mengurangi (derogation) sebagian kewajiban internasionalnya.94 Ifdhal Kasim, Menghadapi Masa Lalu : Mengapa Amnesty?, Briefing paper Series tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi No.2 tanggal 1 Agustus 2000, ELSAM, p. 6 Misalnya, Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan semua Negara pihak untuk menuntut dan menghukum orang-orang yang diduga melakukan kejahatan yang diatur dalam perjanjian tersebut (genosida dan kejahatan perang). Sehingga, memberlakukan hukum amnesti terhadap para pelaku kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Konvensi tersebut. Ifdhal Kasim,…Op.Cit,p. 6 Argumen penggunaan azas derogation itu dikemukakan oleh Naomi RothArriaza, “Special Problems of a Duty to Prosecute Derogation, Amnesties, Statute of Limitation, and Superior Orders”, dalam Impunity and Human Rights in International Law and Practice, New York :Oxford University Press, 216 Lampiran Namun, masih menurut Pepe (panggilan akrab Zalaquett) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemberian amnesty yaitu95 : a) Kebenaran terlebih dahulu harus ditegakkan; b) Amnesty tidak diberikan untuk pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida; c) Amnesty harus sesuai dengan ”keinginan” rakyat. 95 96 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian amnesty bagi kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI adalah tetap merupakan hal yang bertentangan dengan hukum internasional. Tahun 2000, Perancis merevisi Konstitusinya sebagai langkah pengimplementasian Statuta Roma. Dalam Constitutionality of the MPI Statute, Perancis berkewajiban untuk menahan dan menyerahkan kepada MPI orang yang memiliki potensi untuk diberi amnesti oleh Perancis untuk diadili. Sementara aturan ini bertentangan dengan Konstitusi Perancis (Pasal 34) yang menyatakan bahwa pemberian amnesti adalah hak prerogatif dari Parlemen Perancis. Namun kemudian, untuk kejahatan yang merupakan yurisdiksi MPI, Perancis tunduk pada aturan bahwa hukum amnesti tidak berlaku untuk kejahatan demikian.96 Kewenangan untuk memberikan amnesti dimiliki 1995,p. 57-70, dikutip dari Ifdhal Kasim,…ibid,p. 9. Ibid. Antonio Casesse, ...Op.Cit, p. 315 217 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia oleh Presiden setelah meminta pertimbangan dari DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Namun sampai saat ini belum ada aturan yang memperinci mekanisme dan kategori penilaian pemberian amnesti karenanya mekanisme ini sangat rentan terhadap terjadinya praktek impunity yang dilegalkan oleh Negara. Meski kontroversial, sebelumnya mekanisme amnesti diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam UU KKR ini, ada subkomisi yang khusus untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden tentang permohonan amnesti. Keputusan MK No. 006/ PUU-IV/2006 yang membatalkan Undang-Undang KKR ini kembali memberikan ketidakpastian soal pemberian amnesti. Aturan-aturan di atas hanyalah beberapa contoh aturan-aturan di Indonesia yang perlu disinkronisasikan dengan aturan-aturan dalam Statuta Roma. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma maka Indonesia berkewajiban untuk menerapkan aturanaturan Statuta Roma dalam hukum nasionalnya, dan agar tidak terjadi pertentangan agar UndangUndang yang telah ada dengan aturan Statuta Roma, maka sinkronisasi ini menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. B. Kebutuhan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Nasional Paska Ratifikasi Dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah melakukan berbagai upaya bahkan sebelum adanya Statuta Roma 1998 maupun 218 Lampiran Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Para pendiri bangsa kita telah memikirkan dan menerapkannya dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Seiring perkembangan jaman maka pengaturan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia semakin berkembang dan khusus, dimulai dari UUD 1945 sampai yang terakhir adalah UU No.26 Tahun 2000. Berbagai pengaturan baik dari tingkat lokal maupun yang berasal dari konvensi – konvensi internasional telah diratifikasi dan berlaku menjadi hukum positif. Hal ini menunjukan kepedulian dan eksistensi Indonesia terhadap perlindungan HAM. Indonesia telah selangkah lebih maju diantara negara ASEAN lainnya dalam upaya ini.97 Sinkronisasi dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal dilakukan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal dengan nilai-nilai hak asasi manusia lokal (nasional). Sedangkan secara horisontal dilakukan terhadap perundang-undangan yang mempunyai derajat yang sama.98 Pembandingan ini dapat dilakukan melalui interpretasi hukum (penafsiran hukum). Interpretasi bertujuan untuk mempelajari arti yang sebenarnya dan isi dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam hukum Indonesia, dikenal beberapa bentuk interpretasi, diantaranya:99 97 98 99 Romli Atmasasmita, Op cit, hlm.61. Hassan Suryono, Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asaasi Manusia Internasional dan Nasional, dalam Muladi (ed), Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Reflika Aditama, 2005, hlm.88. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 99-111, CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.66- 69. 219 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 1. Interpretasi tata bahasa (taalkundige atau gramatikale interpretetie) yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang – undang, dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang – undang; yang dianit adalah arti perkataan menurut tatabahasa sehari-hari. 2. Interpretasi sahih atau autentik atau resmi, yaitu penafsiran sebagaimana maksud pembuat undang – undang itu sendiri dengan maksud agar mengikat seperti ketentuan atau pasal lainnya. 3. Interpretasi historis atau sejarah (rechthistorische – interpretatie), yaitu sejarah terjadinya hukum dan undang – undang atau ketentuan hukum tertulis. 4. Interpretasi sistematis atau dogmatis, yaitu penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan yang sedang ditafsir. 5. Interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran yang mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang melatarbelakangi pembuatan suatu undang-undang 6. Interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang mengemukakan maksud dan tujuan dari si pembuat undang-undang. 7. interpretasi ekstentif, yaitu memperluas arti kata dalam suatu peraturan sehingga suatu peristiwa atau perbuatan dapat dimasukan ke dalamnya. 220 Lampiran 8. Interpreatasi restriktif, yaitu penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti kata-kata dalam suatu peraturan. 9. Interpretasi analogis, yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan menggunakan perumpamaan (pengibaratan) terhadap katakata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya. 10. Interpretasi argumentum a contrario atau pengingkaran, yaitu cara menafsirkan suatu undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu perundang-undangan. Sehinga diperoleh kesimpulan bahwa soal yang dihadapi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Interpretasi terhadap aturan internasional (konvensi)100 yang menggunakan bahasa yang berbeda digunakan interpretasi secara gramatikal dan sistematis agar tidak terjadi perbedaan makna. Selain terhadap substansi, sinkronisasi dan interpretasi dilakukan juga terhadap komponen kultur, yaitu gagasan-gagasan, harapan-harapan dari semua peraturan hak asasi manusia.101 Di sisi lain, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UndangUndang No. 39 Tahun 1999 102 maka seharusnya setelah Undang-Undang peratifikasian Statuta Roma disahkan oleh 100 101 102 Dalam hal ini Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional / International Criminal Court(ICC). Hassan Suryono, op. cit., hlm. 89. Pasal 7 ayat (2): Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. 221 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Presiden, maka Statuta Roma otomatis menjadi hukum nasional (positif) kita, begitu juga dengan ratifikasi konvensikonvensi lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan masalah kesiapan perangkat hukum kita yang kini dirasa belum memadai, karena perangkat hukum berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia telah terakomodir dengan berbagai konvensi internasional yang telah kita ratifikasi dan sudah otomatis menjadi hukum nasional. Berikut paparan secara rinci kebutuhan harmonisasi yang dibutuhkan paska ratifikasi Statuta Roma: a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Seperti telah dikemukakan di atas, para pendiri Indonesia telah merumuskan pengaturan perlindungan HAM dalam UUD 1945 baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh. Dalam Pembukaan, secara eksplisit dan implisit Indonesia mengemukakan pernyataan dan komitmennya dalam upaya perlindungan HAM. Dimana salah satunya dilakukan melalui peran aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang juga merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia.103 Dalam perjalanannya, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yang diantaranya sangat berkaitan dengan perlindungan HAM baik dari sisi hak-hak sipil dan politik maupun yang termasuk dalam hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. i. Amandemen Pertama UUD 1945 103 lihat paragraph 4 Pembukaan UUD 1945 222 Lampiran Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999, pada garis besarnya amandemen ini dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan Presiden, pengangkatan, janji serta hak untuk mengajukan Rancangan Undang Undang. ii. Amandemen Kedua UUD 1945 Amandemen kedua yang disahkan pada tahun 2000 pada intinya dilakukan terhadap pasalpasal yang bekenaan dengan hak dan kewajiban DPR, serta pengaturan mengenai Pemerintah Daerah. Selain itu amandemen ini mendapat perhatian besar dari kalangan aktivis HAM karena dalam amandemen ini dibuat aturan yang lebih rinci berkenaan dengan pengaturan perlindungan HAM khususnya di bidang hak-hak sipil dan politik, yaitu dalam BAB X A Pasal 28 A – Pasal 28 J yang merupakan aturan baru yang mengatur lebih rinci tentang perlindungan HAM dan penegakan hukumnya dalam UUD 1945. Sebelumnya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM secara rinci hanya diatur dalam Undang Undang dan perangkat hukum lainnya di bawah UUD. iii. Amandemen Ketiga UUD 1945 Amandemen ini disahkan pada tahun 2001 yang diantaranya mengatur masalah kekuasaan kehakiman, hak uji materil dan mekanisme pemilihan umum. Selain itu diatur juga masalah kerjasama antara presiden dan DPR. 223 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia iv. Amandemen Keempat UUD 1945 Amandemen keempat yang disahkan pada tahun 2002 ini lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya. b. KUHP, RKUHP dan KUHAP Pelanggaran HAM yang berat tidak diatur dalam KUHP sehingga pengaturan secara khusus di luar KUHP dibenarkan menurut sistem hukum Indonesia karena sifatnya yang khusus. Beberapa pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam MPI sama dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Kesamaan tersebut diantaranya dalam beberapa prinsip yang dianut oleh MPI yang juga telah diatur dalam KUHP Indonesia, yakni prinsip legalitas (non retroactive principle), pertanggungjawaban individual, hal tentang penyertaan, percobaan dan pembantuan serta pemufakatan. Namun pengaturan secara teknis memang tidak sepenuhnya sama, karena dalam KUHP tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.104 Secara substansi, tidak ada masalah antara KUHP dan Statuta Roma diantaranya prinsip legalitas (nonretroaktif), pengaturan mengenai penghukuman terhadap pelaku pembunuhan. Meskipun banyak hal yang belum sesuai105 diantaranya KUHP yang masih menganut ancaman hukuman mati pada terpidana, hal ini tidak dikenal 104 105 op cit, hlm.38. lihat selanjutnya dalam Bab 3, Implementasi Efektif Statuta Roma. 224 Lampiran dalam MPI. Disamping itu masalah mengenai kadaluwarsa yang masih dianut dalam KUHP, sedangkan dalam kejahatan berat terhadap HAM yang diatur dalam MPI, tidak dikenal adanya kadaluwarsa. Perbedaan yang cukup besar terdapat dalam hukum acara. Dalam Statuta Roma semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan MPI bersifat independen, berdiri sendiri tanpa pengaruh pihak manapun, begitu juga dengan proses beracaranya yang berbeda dengan perkara pidana biasa. Sistem yang digunakan MPI merupakan gabungan hasil kesepakatan negara-negara bersistem AngloSaxon dan Eropa Kontinental. Sedangkan dalam Pengadilan HAM kita yang diatur oleh UndangUndang No.26 Tahun 2000, hukum acara yang digunakan adalah sama dengan acara yang terdapat dalam KUHAP dengan sistem kita yang menganut Eropa Kontinental. Angin segar dibawa oleh RKUHP Tahun 2004 yang memasukkan jurisdiksi MPI (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang) menjadi bagian RKUHP. Pengaturan ini diantaranya terdapat dalam Buku Kedua tentang ‘Tindak Pidana’; Bab I tentang ‘Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara’ paragarf 4 tentang ‘Tindak Pidana Waktu Perang’ (pasal 233-237) serta Bab IX tentang ‘Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia’ (pasal 390 – 399). Di dalamnya berisi pengaturan dari segi materi tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana tersebut. Memang terdapat perbedaan berat hukuman dengan yang 225 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia telah ditentukan oleh Undang Undang No.26 Tahun 2000, tetapi hal ini dapat dipertimbangkan kembali. Namun yang menjadi hal penting dalam RKUHP ini bahwa bila RKHUP ini disahkan dengan segera artinya kita tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan buruk yang dapat timbul106 dari peratifikasian Statuta Roma berkenaan dengan pengaturan jurisdiksi yang berbeda dengan Undang Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang hanya memasukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam jurisdiksinya. RKUHP ini menunjukan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam upaya perlindungan HAM yang sejalan dengan standar aturan hukum internasional. c. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 106 Undang-Undang ini merupakan awal tonggak pengaturan HAM secara khusus, dan juga merupakan Undang-Undang yang menunjuk KOMNAS HAM sebagai badan penyelidik dan penyidik kasus pelanggaran HAM yang berat, bersifat independen sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam pelanggaran HAM yang berat. Lembaga independen ini diantaranya memiliki fungsi pengkajian, penelitian, kekhawatirkan diantaranya akan adanya intervensi internasional bilamana Indonesia meratifikasi ICC karena kejahatan perang tidak termasuk dalam jurisdiksi Undang Undang N0.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sedangkan konflik yang terjadi di Aceh tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran terhadap common article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang juga diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c. 226 Lampiran penyuluhan, pemantuan dan meditasi tentang hak asasi manusia.107 Pengakuan terhadap nilai- nilai HAM diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam jurisdiksi MPI, tetapi Undang Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan diantaranya yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berkaitan dengan forum internasional, Undang Undang ini pun tidak menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka perlindungan HAM bilamana upaya yang dilakukan di forum nasional tidak mendapat tanggapan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 39 Tahun 1999: 107 108 “Setiap orang berhak untuk mengajukan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.” Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakan HAM dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum Indonesia108 Pasal 76 ayat (1) Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. misalnya oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan termasuk upaya banding ke Pengadilan Tinggi ataupun mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke 227 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional.109 Hal ini seiring dengan prinsip komplementer yang dianut MPI. d. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 109 Undang – undang ini dibuat atas dasar kesadaran dan kepentingan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pertimbangan yang dilakukan tentunya didasari prinsip dasar pembentukan suatu peraturan perundangan di Indonesia, diantaranya landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Sebagi landasan filosofis, UndangUndang ini dibuat sebagai penerapan cita-cita bangsa yang dipelopori oleh para pendiri bangsa ini dalam rangka pencapaian tujuan bangsa diantaranya mensejahterakan rakyat Indonesia melalui perlindungan HAM. Pertimbangan yuridis yang menjadi landasan Undang-Undang ini yaitu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan KUHP Indonesia tidak mengatur pelanggaran berat terhadap HAM yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Dalam sistem hukum Indonesia, suatu hal yang belum diatur dalam KUHP dapat diatur dalam peraturan tersendiri sehingga Undang-Undang 26/2000 banyak melakukan terobosan-terobosan aturan hukum yang tidak diatur sebelumnya dalam Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Penjelasan Pasal 7 Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 228 Lampiran KUHAP (seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I). Landasan sosiologis dalam Undang-Undang ini yaitu sebagai upaya menjaga dan meningkatkan upaya perlindungan HAM, dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Sedangkan alasan politik dalam Undang-Undang ini yaitu bahwa pelanggaran HAM yang berat bersifat politis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memegang kekuasaan. Adanya Undang-Undang No.26 Tahun 2000 yang isinya banyak mengadopsi dari Statuta Roma ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menunjukan bahwa Indonesia mampu melaksanakan peradilan sendiri yang sesuai dengan standar internasional (Statuta Roma) dan untuk menguatkan prinsip komplementaritas yang dianut oleh MPI. Undang-Undang ini menunjukan niat dan itikad baik pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat di negaranya. Perangkat hukum yang telah dimiliki Indonesia merupakan kelebihan dan ‘modal’ yang dimiliki Indonesia yang menunjukan kesiapan sistem hukum kita dalam penegakan HAM, jika dibanding negara lain seperti Norwegia dan Kamboja ataupun negaranegara yang tergabung dalam Uni Eropa110 yang telah meratifikasi Statuta Roma tapi belum memiliki aturan pelaksanaan maupun perangkat hukum yang mendukung implementasi Statuta Roma. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi penghalang itikad 110 Lihat selengkapnya dalam www.npwj.org. 229 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia baik mereka dalam mewujudkan komitmen yang kuat dalam upaya perlindungan HAM dan penegakan hukumnya. Hal ini terlihat dari komitmen yang dibuat oleh Norwegia yang akan melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai perangkat hukumnya yang disesuaikan dengan pengaturan dalam Statuta Roma111 seperti KUHP, KUHPerdata dan aturan kemiliterannya.112 Begitu pula yang terjadi dengan Kamboja yang melakukan ratifikasi terlebih dahulu lalu kemudian selanjutnya dibuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, didukung dengan uraian sejumlah peraturan perundangan (khususnya peraturan mengenai HAM) yang dimiliki Indonesia di atas, menunjukan kesiapan Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma. Kekhawatiran akan dibayang-bayanginya proses penegakkan hukum HAM di Indonesia oleh MPI bila Indonesia menjadi negara pihak Statuta Roma, menjadi tidak beralasan dengan uraian mengenai prinsip komplementer di atas. Sehingga, sudah saatnyalah Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut serta secara aktif dalam memelihara perdamaian, ketertiban dan keamanan dunia. 111 112 sebagian besar Negara yang tergabung dalam Uni Eropa melakukan hal ini bahkan jika diperlukan dilakukan amandemen terhadap konstitusinya. Herta Daubler-Gmelin, International Law and the International Criminal Court. 230 Lampiran BAB V KESIMPULAN Upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM internasional telah diakui sebagai hal yang sangat penting dan mendesak. Empat Mahkamah Internasional ad hoc telah dilaksanakan untuk menghukum para pelaku kejahatan internasional khususnya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kritik yang muncul yang mewarnai kinerja mahkamah-mahkamah tersebut diantaranya adalah victors justice, selective justice, dan praktek-praktek impunity yang sulit dihapuskan. Berangkat dari tujuan ingin menyempurnakan kekurangan-kekurangan mahkamah-mahkamah terdahulu serta menjamin penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang paling serius yang meresahkan masyarakat internasional agar tidak terulang di kemudian hari, maka didirikanlah 231 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia suatu Mahkamah Pidana Internasional permanen (MPI) berdasarkan Statuta Roma 1998 yang telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2002. Hingga saat ini sudah 100 negara yang menjadi pihak Statuta Roma. MPI ,dalam menerapkan yurisdiksinya, memiliki prinsip yang fundamental yakni prinsip komplementer (complementary principle). Prinsip ini menegaskan bahwa MPI hanyalah mekanisme pelengkap bilamana suatu negara tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) untuk mengadili para pelaku kejahatan dalam jurisdiksinya yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan agresi. Prinsip ini jelas membuktikan bahwa fungsi MPI bukan untuk melaksanakan intervensi internasional dengan mengambil alih fungsi pengadilan nasional suatu negara, namun justru menjunjung tinggi kedaulatan nasional suatu negara dengan mengutamakan keefektifan mekanisme hukum nasionalnya untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya. Indonesia yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma, seringkali menemukan kesulitan dalam menegakkan hukum HAM dikarenakan instrumen hukum HAM tidak memadai serta ketidaksiapan aparat penegak hukumnya dalam menghadapi isu HAM yang relatif baru bagi mereka. Hal ini seringkali menyebabkan Indonesia sulit memenuhi kewajiban untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat seperti yang misalnya terjadi dalam kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Ratifikasi Statuta Roma diharapkan dapat menjadi sarana pendorong bagi Indonesia untuk segera membenahi kekurangannya tersebut sehingga Indonesia bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan perlindungan HAM terhadap warganegaranya. 232 Lampiran Jika dibandingkan negara ASEAN lain, Indonesia dapat berbangga dengan kesiapan instrumen hukum yang memberikan perlindungan HAM bagi warganegaranya seperti misalnya yang tercantum dalam UUD 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang 39/1999, dan Undang-Undang 26/2000. Walaupun banyak kekurangan seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, instrumen hukum yang dimiliki Indonesia sudah cukup menunjukan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dinilai sudah cukup siap untuk meratifikasi Statuta Roma. Keuntungan yang akan didapatkan Indonesia ketika menjadi pihak dalam Statuta Roma selain mendorong pembenahan sistem hukum nasional Indonesia (khususnya hukum HAM) juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dengan terbukanya kesempatan khususnya bagi aparat penegak hukum untuk berpartisipasi dalam mahkamah internasional dengan menjadi hakim, jaksa atau panitera di MPI. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam MPI dapat menjadi contoh yang baik bagi negaranegara tetangganya khususnya negara-negara besar di ASEAN yang hingga saat ini belum satupun yang menjadi negara pihak Statuta Roma. Berdasarkan berbagai alasan inilah maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus segera meratifikasi Statuta Roma tentang MPI. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang maka RUU tentang Pengesahan Perjanjian internasional sekurangkurangnya terdiri atas dua pasal yaitu pasal pertama memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah aslinya atau naskah asli bersama dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 233 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia dan Pasal kedua memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya undang-undang pengesahan tersebut. Ratifikasi Statuta Roma saja tidak cukup jika akhirnya aturan Statuta Roma tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif hanya karena aturan-aturan tersebut belum menjadi hukum nasional di Indonesia, seperti nasib dari banyak konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia namun hanya menjadi dekorasi hukum semata, misalnya Konvensi Jenewa 1949. Belajar dari hal tersebut, maka segera setelah Indonesia meratifikasi Statuta Roma, maka aturan implementasinya pun harus segera disahkan pula. Hal ini penting untuk meminimalkan intervensi internasional karena Indonesia tidak akan dikategorikan sebagai negara yang unwilling/unable. Penyusunan aturan implementasi Statuta Roma bisa dimulai dari penjabaran aturan-aturan Statuta Roma yang belum terakomodir di Indonesia sehingga aturan tersebut bisa terabsorpsi dalam hukum nasional kita. Selanjutnya melakukan pembaharuan terhadap aturan-aturan yang sudah ada yang bertentangan dengan aturan dalam Statuta Roma, seperti misalnya aturan pidana mati, aturan kadaluarsa, dan aturan amnesty bagi pelanggaran HAM yang berat. Sehingga pada akhirnya, aturan Statuta Roma tersebut dapat berjalan selaras dengan hukum nasional dan implementasinya akan berjalan efektif sehingga tujuan peratifikasian Statuta Roma akan tercapai. Selain melaksanakan sinkronisasi, penyebarluasan informasi mengenai aturan Statuta Roma juga tidak kalah pentingnya, khususnya ke kalangan aparat penegak hukum, unit-unit angkatan bersenjata, serta para akademisi dan praktisi hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang 26/2000 mengenai Pengadilan HAM yang merupakan 234 Lampiran pengadopsian “sebagian” aturan dalam Statuta Roma, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengenalkan aturan ini khususnya kepada aparat penegak hukum. Misalnya, berbagai pelatihan, seminar dan studi banding ke negara lain telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan para hakim dan jaksa Pengadilan HAM Indonesia mengenai mekanisme penegakkan hukum HAM internasional. Selain itu kesadaran akan pentingnya hukum HAM juga sudah semakin meningkat di kalangan angkatan bersenjata seiring dengan banyaknya para petinggi militer yang diadili di Pengadilan HAM. Namun, di kalangan akademisi, materi MPI masih sangat jarang ditemukan dalam kurikulum perkuliahan. Diharapkan, dengan diratifikasinya Statuta Roma disertai dengan penyerbarluasan informasi yang terstruktur dan sistematis, maka pemahaman tentang aturan hukum HAM dan kewajiban negara dalam menegakkan hukum HAM internasional dapat lebih baik lagi. Dan tentu saja, untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik serta peran aktif berbagai pihak baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan, legislatif sebagai sarana legitimasi, para penegak hukum, akademisi dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. 235 Lampiran BAB VI PENUTUP Pentingnya arti Statuta Roma dalam upaya perlindungan HAM internasional, dan menyadari kelemahan Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan HAM bagi warganegaranya ditandai dengan masih terjadinya praktek impunity, ketidakmemadaian instrumen hukum HAM, aparat penegak hukum serta sarana prasarana perlindungan saksi dan korban di Indonesia menjadikan peratifikasian Statuta Roma sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Karena, tujuan Statuta Roma untuk memberikan jaminan penghukuman bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida, menghapuskan rantai impunity dan mengefektifkan mekanisme hukum nasional, dapat menjadi sarana pendorong bagi Indonesia untuk segera membenahi kekurangannya tersebut dan mewujudkan komitmennya sebagai negara yang menjunjung tinggi penegakkan HAM. 237 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Agar tujuan peratifikasian Statuta Roma bagi penegakkan Hukum HAM di Indonesia tercapai, maka ratifikasi tersebut harus segera diikuti dengan pengesahan aturan implementasi dari Statuta Roma tersebut. Hal ini penting agar aturan-aturan dalam Statuta Roma bisa segera berlaku efektif menjadi bagian dari hukum nasional di Indonesia. Karena, walaupun proses ratifikasi suatu konvensi internasional merupakan wujud terikatnya suatu negara terhadap aturan dalam konvensi internasional tersebut, namun seringkali aturan-aturanya tidak dapat diterapkan langsung ke dalam lingkup teritorial suatu negara. Artinya harus ada proses transformasi atau penjabaran aturan dalam konvensi internasional dalam hal ini Statuta Roma ke dalam hukum (pidana) nasional Indonesia dengan cara membuat aturan implementasinya. Proses pembuatan aturan implementasi dilakukan dengan melakukan sinkronisasi aturan dalam Statuta Roma dengan hukum (pidana) nasional Indonesia. Aturan-aturan yang penting dalam Statuta Roma harus segera diakomodir dalam hukum nasional Indonesia, dan memperbaharui aturan-aturan yang bertentangan dengan Statuta Roma. Mekanisme sinkronisasi bisa dengan jalan mengamandemen Undang-Undang yang sudah dimiliki Indonesia misalnya Undangt-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM, atau mengesahkan Undang-Undang baru yang merupakan undang-undang khusus pengeimplementasian aturan dalam Statuta Roma seperti yang dilakukan beberapa negara peratifikasi Statuta Roma atau mengesahkan Rancangan KUHP Indonesia yang baru dengan terlebih dahulu mensinkronisasikan aturan dalam RKUHP tersebut dengan aturan dalam Statuta Roma. Mengingat pentingnya aturan implementasi Statuta Roma ini maka pengesahannya harus dilaksanakan segera 238 Lampiran setelah Indonesia meratifikasi Statuta Roma agar Indonesia tidak dikatakan sebagai negara yang unwilling/unable untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Artinya persiapan pembuatan aturan implementasi Statuta Roma harus sudah dilaksanakan dari sekarang mengingat begitu banyaknya aturan dalam hukum nasional Indonesia yang harus disinkronisasi dengan aturan dalam Statuta Roma. Untuk mewujudkannya, maka dalam salah satu pasal UndangUndang Ratifikasi Statuta Roma Indonesia hendaknya juga diatur mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi Indonesia untuk segera mengesahkan aturan implementasi Statuta Roma tersebut. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi suatu kepastian hukum bagi pembuat Undang-Undang untuk segera melaksanakan kewajibannya sehingga peratifikasian Statuta Roma tidak menjadi dekorasi hukum semata. 239 Lampiran DRAFT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN ….. TENTANG PENGESAHAN ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 1998 (STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL 1998) Disusun Oleh: Elsam-Imparsial-IKOHI-PSHK-YLBHI 241 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN ….. TENTANG PENGESAHAN ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 1998 (STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL 1998) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; b. bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional yang juga ingin berperan aktif dalam perdamaian dunia, bangsa Indonesia mendukung segala bentuk penindakan terhadap kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan tindakan agresi serta menolak segala bentuk impunitas; c. bahwa dengan melaksanakan kewajibannya untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius tersebut, Indonesia secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap keamanan, stabilitas, kedamaian nasional, regional, bahkan internasional; 243 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia d. bahwa sistem hukum Indonesia akan semakin kuat jika didukung oleh perangkat sistem hukum internasional yang sudah lebih mapan dalam menangani isu kejahatan internasional dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan internasional; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Rome statute of International Criminal Court, 1998 (Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, 1998). Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012). 244 Lampiran Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 1998 (STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL 1998) Pasal 1 (1) Mengesahkan Rome statute of International criminal court, 1998 (Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional) yang salinan naskah asli Rome statute of International criminal court, 1998 (Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal ….. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …. NOMOR ….. 245 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN …… TENTANG PENGESAHAN ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 1998 (STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL 1998) I. UMUM A. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI Empat Mahkamah Pidana Ad Hoc Internasional telah dibentuk selama abad ke-20 yakni; International Military at Nuremberg, Tokyo Tribunal, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan International Crimminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kelebihan dan kekurangan dari keempat Mahkamah ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendirian dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court yang selanjutnya disebut sebagai ICC). Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg adalah sebuah pengadilan yang dibentuk oleh empat negara pemenang perang setelah Perang Dunia II untuk mengadili warganegara Jerman. Empat Negara tersebut adalah Inggris, Perancis, Uni Soviet dan AS yang bertindak atas nama “semua negara”. Mahkamah ini telah mengadili 24 terdakwa penjahat perang Nazi di mana 3 terdakwa dibebaskan, 12 dihukum mati, 3 dipenjara seumur hidup dan 4 dihukum penjara. Namun, tidak semua pelaku kejahatan yang merupakan pemimpin Nazi tersebut dihadapkan ke pengadilan, bahkan kebebasan dari penghukuman yang mereka terima nampak sebagai suatu balas jasa atas apa yang telah mereka lakukan dan mereka mendapat pengampunan atas kejahatan mereka tersebut. 246 Lampiran Mahkamah, yang dibentuk berdasarkan perjanjian London tanggal 8 Agustus 1945 ini, juga dikritik sebagai Mahkamah bagi pemenang perang (victor’s justice) karena semua jaksa dan hakim berasal dari kekuatan sekutu, bukan dari Negara yang netral. Semua terdakwa dan pembelanya berasal dari Jerman, dan mereka mendapat fasilitas yang sangat terbatas dalam mempersiapkan kasus-kasus mereka serta mendapatkan pemberitahuan mengenai bukti-bukti penuntutan. Sehingga jelas Mahkamah ini bukanlah Mahkamah yang imparsial. Terlepas dari segala kekurangan dan kegagalannya, Mahkamah Nuremberg sangat berarti bagi penegakkan hak asasi manusia internasional karena telah meletakan prinsipprinsip dasar pertanggungjawaban pidana secara individu (yang tertuang dalam Nuremberg Principle). Selain itu, definsi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 6(c) Piagam Nuremberg, belum pernah ditemukan dalam Konvensi-Konvensi sebelumnya. Mahkamah ini juga secara tegas menolak prinsip ‘impunitas kedaulatan negara’ seperti yang tertuang dalam pasal 7 Piagam Nuremberg. Mahkamah Internasional Timur Jauh, atau dikenal dengan Mahkamah Tokyo, juga merupakan mahkamah yang didirikan sekutu (berdasarkan deklarasi Mc Arthur) untuk mengadili penjahat perang. Julukan Victors Justice juga melekat dalam Mahkamah ini karena: Jepang tidak diijinkan untuk membawa AS ke hadapan Mahkamah Tokyo atas tindakan pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan AS, dan Jepang juga tidak diijinkan untuk mengadili Uni Soviet atas pelanggarannya terhadap perjanjian kenetralan tanggal 13 April 1941. Selain itu praktek impunitas juga sangat jelas terjadi dalam Mahkamah ini ketika Amerika Serikat memutuskan untuk tidak membawa Kaisar Hirohito ke meja pengadilan, tapi justru melanggengkan kedudukannya dalam Kekaisaran Jepang. Impunitas lain yang dipraktekan dalam pengadilan ini adalah tidak diadilinya para industrialis Jepang yang menjajakan perang serta pemimpin-pemimpin nasionalis yang senang kekerasan. Hampir setengah abad setelah Perang Dunia berakhir, masyarakat internasional kembali dikejutkan dengan praktek 247 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia pembersihan etnis yang lagi-lagi terjadi di Eropa yakni di Negara bekas Yugoslavia. Konflik di Bosnia-Herzegovina, sejak April 1992 dan berakhir bulan November 1995, merupakan praktek pembersihan etnis yang kekejamannya sudah mencapai tingkat yang tidak pernah dialami Eropa sejak Perang Dunia II. Kamp-kamp konsentrasi, perkosaan yang sistematis, pembunuhan besar-besaran, penyiksaan, dan pemindahan penduduk sipil secara masal adalah buktibukti yang tidak dapat diingkari yang akhirnya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY) berdasarkan Resolusi 808 tanggal 22 Februari 1993, dengan pertimbangan bahwa sudah meluasnya tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter termasuk praktek pembersihan etnis sehingga sangat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Berbagai kritikan kembali muncul seiring terbentuknya ICTY ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa mahkamah ini hanyalah kebetulan belaka mengingat berbagai kegagalan diplomasi dan sanksi serta penolakan PBB untuk mengorbankan tentara keamanannya melalui intervensi bersenjata membuat mahkamah terhadap penjahat perang sebagai alat satu-satunya untuk menyelamatkan muka PBB. Walaupun mahkamah ini bukan lagi merupakan keadilan pemenang perang namun justru dikenal sebagai keadilan yang selektif (selective justice) karena hanya mendirikan Mahkamah untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di Negara-negara tertentu, serta Mahkamah ini juga jelas berdasarkan pada antiSerbian bias. Selain itu, Mahkamah ini juga tidak mengadili angkatan bersenjata NATO yang ikut melakukan pemboman di Negara bekas Yugoslavia. Padahal, sangatlah jelas serangan udara yang dilakukan NATO terhadap Kosovo seharusnya menuntut pertanggungjawaban para pemimpin NATO atas pilihan target pemboman yang mereka lakukan karena jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum perang. Kritikan yang sama mengenai “selective justice” juga ditujukan kepada PBB ketika Dewan Keamanannya mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 955 tanggal 248 Lampiran 8 November 1994 di kota Arusha, Tanzania. Pengadilan ini didirikan untuk merespon terjadinya praktek genosida, serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang sudah meluas yang terjadi di Rwanda. Banyak kalangan menilai, ICTY dan ICTR ini hanyalah Mahkamah Internasional yang didirikan dengan alasan yang sangat politis, dan berdasarkan prinsip yang abstrak dan tidak jelas. Berbagai kekurangan dan kegagalan dari mahkamahmahkamah internasional di atas akhirnya menggerakkan PBB untuk melaksanakan konferensi pada tahun 1998 untuk mendirikan suatu mahkamah pidana yang permanen yang diharapkan dapat menyempurnakan berbagai kelemahan dari mahkamah internasional sebelumnya. Aspirasi untuk mendirikan ICC telah muncul di era 1980-an melalui proposal yang diajukan Negara-negara Amerika Latin (yang diketuai oleh Trinidad dan Tobago) kepada Majelis Umum PBB. Selanjutnya, setelah pendirian ICTY dan ICTR, Majelis Umum PBB mendirikan Komite yang bernama Komite Persiapan untuk pendirian ICC (Preparatory Committee for The Establishment of an International Criminal Court), yang telah bertemu enam kali sejak 1996-1998 untuk mempersiapkan teks Konvensi sebagai dasar ICC. Puncak dari proses yang panjang tersebut adalah disahkannya Statuta ICC dalam Konferensi di Roma tanggal 17 Juli 1998 sehingga Statuta tersebut akhirnya dikenal dengan nama Statuta Roma. Seperti yang tertuang dalam Mukadimah dari Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, bahwa Mahkamah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang global (Global Justice), memutuskan rantai kekebalan hukum (impunity) bagi para pelaku kejahatan, serta mengefektifkan kinerja mekanisme hukum nasional dalam menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998, ketika 120 negara berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court” telah 249 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia mensahkan Statuta Roma tersebut. Dalam pengesahan Statuta Roma tersebut, 21 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel, dan India. Kurang dari empat tahun sejak Konferensi diselenggarakan, Statuta yang merupakan dasar pendirian Mahkamah bagi kejahatan yang paling serius yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi ini, sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2002 yakni setelah 60 negara meratifikasinya. B. ARTI PENTING KONVENSI BAGI INDONESIA Indonesia masih banyak menemukan kendala dalam hal penegakan hukum khususnya hukum hak asasi manusia (HAM), uraian di bawah ini akan menjelaskan betapa ternyata Indonesia sangat memerlukan ratifikasi Statuta Roma ini sebagai sarana pendorong untuk membenahi berbagai kelemahan dan kekurangan dari segi instrumen hukum, aparat penegak hukum, serta prosedur penegakkan hukumnya sehingga Indonesia dapat benar-benar mampu memberikan jaminan perlindungan HAM bagi warganegaranya. 1. Menghapuskan Berbagai Praktek Impunitas Salah satu tujuan didirikannya ICC adalah untuk menghapuskan praktek impunitas (impunity). Pasal 28 Statuta Roma secara rinci mengatur bahwa seorang atasan baik militer maupun sipil, harus bertanggungjawab secara pidana ketika terjadi kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan oleh anak buahnya. Aturan yang telah ada sejak Piagam Nuremberg, Tokyo, Konvensi Jenewa 1949, ICTY, ICTR dan kemudian disempurnakan dalam Pasal 28 Statuta Roma, memiliki tujuan untuk dapat menghukum “the most responsible person” walaupun orang tersebut memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan yang seringkali sulit terjangkau hukum. Pasal 28 Statuta Roma telah diadopsi dalam pasal 42 UndangUndang 26/2000 tentang Pengadilan HAM, namun terdapat banyak kesalahan penterjemahan yang justru menjadi celah bebasnya para atasan/komandan tersebut. Secara umum impunitas dipahami sebagai “tindakan yang 250 Lampiran mengabaikan tindakan hukum terhadap pelanggaran (hak asasi manusia)” atau dalam kepustakaan umum diartikan sebagai “absence of punishment”. Dalam perkembangannya istilah impunity digunakan hampir secara ekslusif dalam konteks hukum, untuk menandakan suatu proses di mana sejumlah individu luput dari berbagai bentuk penghukuman terhadap berbagai tindakan illegal maupun pidana yang pernah mereka lakukan. Praktek impunitas ini telah terjadi sejak berabad yang lalu diantaranya adalah gagalnya Negara-negara Eropa untuk mengadili Raja Wilhelm II sebagaimana yang direkomendasikan oleh Perjanjian Versailles, tidak diadilinya Kaisar Hirohito oleh Mahkamah Tokyo atas keputusan AS, berbagai pengadilan pura-pura yang mengadili serdadu-serdadu rendah dengan hukuman yang ringan dan melawan hari nurani keadilan masyarakat. Praktek ini menunjukan bahwa setiap negara selalu memiliki kecenderungan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya sendiri apalagi apabila pelaku tersebut merupakan orang yang memegang kekuasaan di Negara tersebut. Fenomena ini menunjukan betapa kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek masih dominan ketimbang penegakkan HAM dan keadilan. Bagaimana impunity dalam konteks Indonesia, terutama setelah orde baru? Peralihan kekuasaan Soeharto ke Habibie menyisakan sejumlah catatan penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun Peradilan Militer dibentuk di masa Habibie untuk mengadili sejumlah petinggi dan anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan penculikan orang secara paksa, tetapi tidak pernah ada penjelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas korban-korban penghilangan paksa yang belum kembali hingga saat ini. Peradilan ini lebih kepada kompromi politik elit-elit politik dan militer, untuk tidak menjatuhkan hukuman yang dinilai mampu mengakibatkan keguncangan dalam tubuh militer. Sekaligus mencoba untuk berkompromi dengan korban-korban yang sudah dilepaskan. Yang pasti 251 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia peradilam militer kasus penculikan tersebut gagal untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Praktek Pengadilan HAM baik yang Ad Hoc (untuk kasus Tanjung Priok) maupun permanen (untuk kasus Abepura yang diadili melalui Pengadilan HAM Makassar) juga terbukti sulit untuk menjangkau dan menghukum orang yang paling bertanggung jawab. Penyebab kegagalan tersebut diantaranya adalah perangkat hukum HAM di Indonesia khususnya hukum acaranya yang tidak memadai serta aparat penegak hukum yang dinilai kurang siap untuk menghadapi kasus yang relatif baru bagi mereka. Inilah tantangan bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk dapat menemukan celah-celah keadilan yang selama ini sulit untuk ditembus oleh hukum. Dengan menjadi pihak dalam Statuta Roma menjadikan Indonesia mau tidak mau harus membenahi aturan hukumnya khususnya dalam hal menghapuskan rantai impunitas di negaranya sebagai komitmen keseriusan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan serta penegakkan HAM terhadap warga negaranya. 2. Melengkapi Kekurangan Sistem Hukum Indonesia Meratifikasi Statuta Roma serta memasukkan kejahatan internasional serta prinsip-prinsip umum hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum pidana nasional, akan meningkatkan kemampuan negara untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang. Bahkan negara secara efektif akan menghalangi dan mencegah terjadinya kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional tersebut. Dengan melaksanakan kewajibannya untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius tersebut, negara secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap keamanan, stabilitas, kedamaian nasional, regional, bahkan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang juga ingin berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta 252 Lampiran menyadari begitu banyaknya kelemahan dalam sistem hukumnya seringkali membuat Indonesia sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam menghukum pelaku kejahatan internasional. Indonesia harus melakukan begitu banyak pembenahan khususnya dalam hal instrumen hukum serta sumber daya manusianya. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terlalu banyaknya undang-undang yang antara satu dan lainnya saling bertentangan sehingga dalam hal kepastian hukum seringkali membingungkan. Tidak hanya di tingkat Undang-Undang, namun juga di tingkat aturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Daerah). Selain itu, sistem hukum Indonesia khususnya dalam mengasorbsi hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia masih sangat tidak jelas. Praktek di Indonesia menunjukan bahwa setelah meratifikasi suatu konvensi internasional (baik dalam bentuk Undang-undang maupun Keppres) maka harus segera disertai dengan aturan pelaksanaan (implementing legislation) yang memuat pengaturan mengenai lembaga pelaksana dan jika perlu sanksi pidana efektif suatu kejahatan tertentu sehingga konvensi itu bisa benarbenar berlaku efektif terhadap warga negaranya. Padahal berdasarkan Pasal 7(2) Undang-Undang 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional”. Sementara itu, banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami aturan hukum internasional dan berbagai praktek internasional yang terjadi, bahkan banyak diantara mereka cenderung tidak memiliki keberanian untuk melakukan terobosan dengan mendasarkan suatu kejahatan yang terjadi dengan praktek internasional. Sehingga, sangat jarang ditemukan suatu putusan pengadilan di Indonesia yang mendasarkan pada kasuskasus internasional atau hukum kebiasaan internasional. 253 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Di bawah ini akan diuraikan beberapa kelemahan sistem hukum Indonesia sehingga ratifikasi Statuta Roma sangat dibutuhkan untuk membenahinya, yaitu : a. Instrumen hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Banyak aturan dalam KUHP yang sudah tidak lagi relevan dan memadai untuk mengakomodir jenis-jenis kejahatan yang sudah semakin berkembang. Khususnya dalam hal penegakan hukum HAM, beberapa jenis kejahatan seperti pembunuhan, perampasan kemerdakaan, perkosaan, penganiayaan adalah jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP. Namun jenis kejahatan tersebut adalah jenis kejahatan yang biasa (ordinary crimes) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat atau kejahatankejahatan dalam yurisdiksi ICC harus memenuhi unsur atau karateristik tertentu. Perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif pelaku pelanggaran HAM yang berat. 2. Hukum Acara: Dalam pasal 10 UndangUndang 26/2000 dijelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat maka hukum acara yang digunakan adalah Kitab-Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tentu saja hal ini tidak lah memadai mengingat jenisjenis kejahatan yang diatur dalam undangundang ini adalah extra ordinary crimes sehingga banyak hal yang baru yang tidak diatur dalam KUHAP. Sebagian dari hal-hal baru tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 26/2000 yakni mengenai: a) Diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc b) Penyelidik hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM sedangkan penyidik 254 Lampiran tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP c) Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. d) Ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi Namun terdapat aturan khusus lain yang tidak diatur baik dalam KUHAP maupun UndangUndang 26/2000 sehingga sangat diperlukan hukum acara dan pembuktian yang khusus (seperti bentuk rules of procedure and evident dari Statuta Roma) sebagai dasar hukumnya. Hal-hal yang tidak diatur baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang 26/2000 diantaranya adalah dasar hukum sub poena power yang dimiliki penyelidik dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). 3. Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM: Undang-undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat. Yurisdiksi Pengadilan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Walaupun undangundang ini dikatakan sebagai pengadopsian dari Statuta Roma namun terdapat banyak kelemahan yang akhirnya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Misalnya Undang-Undang 26/2000 hanya mencantumkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagai yurisdiksinya sementara kejahatan perang yang juga merupakan yurisdiksi Statuta Roma tidak dicantumkan dalam Undang-Undang ini. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan perang di Indonesia maka belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana yang efektif bagi kejahatan ini. 255 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia Berbagai kesalahan penterjemahan juga banyak ditemukan dalam pasal-pasal di undangundang ini. Misalnya dalam pasal 9 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat kata-kata “serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil” sementara dalam teks asli Statuta Roma “directed against civilian population” yang artinya “ditujukan kepada penduduk sipil”. Penambahan kata “secara langsung” di sini dapat berakibat sulitnya menjangkau para pelaku yang bukan pelaku lapangan. Para pelaku di tingkat pemberi kebijakan sulit terjangkau berdasarkan pasal ini. Dalam Statuta Roma terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur kejahatan yang menjadi yurisdiksinya yaitu unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang, serta unsur dari pertanggungjawaban komando. Penjelasan mengenai unsur-unsur ini dapat memudahkan aparat penegak hukum ketika menafsirkan kejahatan ini dalam proses pembuktian, penuntutan maupun sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Sedang Undang-Undang 26/2000 tidak memberikan penjelasan mengenai unsurunsur kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida, baik dalam penjelasan undang-undang maupun terpisah dalam bentuk buku pedoman lain. Hal ini seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam berproses di Pengadilan. Ketidakjelasan uraian yang menunjukan delik kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang 26/2000 khususnya unsur kejahatan terhadap kemanusiaan mengakibatkan hakim seringkali memberikan penafsiran yang berbeda dalam putusannya karena rujukan yang digunakan pun berbeda-beda. 256 Lampiran b. Sumber Daya Manusia Dengan meratifikasi Statuta Roma, akan banyak sekali manfaat bagi Indonesia sebagai Negara Pihak, khususnya dalam hal meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dengan menjadi Negara Pihak ICC maka secara otomatis Indonesia menjadi anggota dari Majelis Negara Pihak (Assembly of States Parties) yang memiliki fungsi sangat penting dalam ICC. Majelis Negara Pihak ini kurang lebih sama dengan fungsi dari Majelis Umum dalam Badan PBB. Fungsi penting dari Majelis Negara Pihak diantaranya adalah dapat ikut serta melakukan pemilihan terhadap semua posisi hukum di ICC. Posisi tersebut diantaranya adalah posisi hakim dan penuntut umum. Semakin cepat Indonesia meratifikasi Statuta Roma, maka akan semakin terbuka pula kesempatan sumber daya manusia Indonesia untuk menempati posisi sebagai salah satu hakim internasional di ICC. Dengan demikian, menjadi Negara Pihak dalam Statuta Roma, berarti Indonesia turut berperan aktif dalam memajukan fungsi efektif dari ICC. Itu juga berarti sumber daya manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam sistem internasional, sehingga hal itu akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, setelah meratifikasi Statuta Roma maka para aparat penegak hukum mau tidak mau harus membuka diri mereka untuk lebih terbiasa dan terlatih dalam melihat perkembangan kasus-kasus internasional yang terjadi dan menjadikannya bahan referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia. Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah banyak aparat penegak hukum yang tidak 257 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia siap khususnya ketika harus mengadili kasuskasus yang merupakan extra ordinary crimes di mana pengaturannya sangat tidak memadai jika hanya mendasarkan pada KUHP dan KUHAP. Sedangkan sebagian besar dari mereka hanya terlatih untuk selalu mendasarkan setiap kasus pidana dengan KUHAP dan KUHP. Misalnya, praktek Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur mencatat berbagai kekurangan dalam hal sumber daya manusia. Kekurangan tersebut diantaranya adalah: i. Dalam hal pemilihan hakim oleh Mahkamah Agung, seleksi dilakukan secara subjektif dan tidak sesuai dengan track record para calon hakim ii. Tidak ada publikasi mengenai proses persidangan (prosiding) serta sangat sulit untuk mendapatkan hasil keputusan dalam bentuk tertulis. iii. Banyaknya laporan yang dikeluarkan oleh para aktivis HAM di Indonesia mengenai praktek korupsi yang sudah meluas dalam sistem pengadilan HAM. iv. Kurangnya independensi, impartiality, dan profesionalisme dari para aparat penegak hukum v. Kurangnya kepercayaaan masyakarakat terhadap pengadilan. Di samping itu, pelapor khusus mengai kenetralan hakim dan pengacara (Special Rapporteur on the independence of judges and lawyer) Dato’ Param Cumaraswamy menyatakan bahwa ada sejumlah hakim yang hanya mendapatkan sedikit sekali pelatihan mengenai standar dan praktek internasional dalam hal mengadili kejahatan serius seperti kejahatan terhadap kemanusiaandan genosida. Kualitas para hakim tentu saja sangat mempengaruhi hasil dari suatu kasus. Misalnya, 258 Lampiran ada pendapat yang dikemukakan oleh seorang pengamat Pengadilan Ad Hoc Timor Timur yang mengatakan bahwa kelompok hakim terbagi tiga ; (1) hakim konservatif yang bekerja menurut buku dan kaku pada hukum acara pidana, (2) hakim karir dan ad hoc yang dikenal akan pengetahuannya tentang hukum humaniter internasional dan berpandangan progresif, kelompok ini bertanggungjawab atas munculnya sejumlah keputusan bersalah, dan (3) kelompok tengah yang dapat pergi ke mana saja tergantung panel di mana mereka duduk. Menurut para pengamat, kelompok yang ke-3 ini “ingin terlihat menguasai hukum humaniter internasional tapi motivatisnya lebih hanya untuk karir”. Para hakim karir di pengadilan HAM Ad Hoc Timur-Timur juga tetap harus menangani kasus-kasus yang lain sehingga sulit bagi mereka untuk fokus pada proses pengadilan HAM. Mereka juga sangat kurang mendapatkan bantuan fasilitas-fasilitas yang mendukung perkara yang mereka tangani misalnya perpustakaan, komputer, dan akses internet. 3. Perlindungan saksi atau korban Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk menjamin korban dan saksi mendapatkan perlindungan. Perlindungan saksi dan korban diatur baik dalam Statuta Roma maupun dalam Rules of Procedure and Evidence-nya (RPE). Aturan ini didasarkan pada norma yang sama yang telah diatur dalam dua pengadilan ad hoc internasional sebelumnya yakni ICTY dan ICTR. Perlindungan korban dan saksi pada hakikatnya terbagi dua: a. Perlindungan korban dan saksi Partisipasi korban dan saksi mendapatkan jaminan dalam setiap tingkat proses persidangan di ICC. Perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 68 Statuta Roma, yakni: 259 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia i. Proses persidangan in camera (sidang tertutup untuk umum), dan memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana khusus atau sarana elektronika lain (Pasal 68(2) Statuta Roma). ii. Unit Saksi dan Korban (Pasal 68(4) Statuta Roma): dalam Mahkamah Pidana Internasional, unit ini dibentuk oleh Panitera di dalam Kepaniteraan. Setelah berkonsultasi dengan Kantor Penuntut Umum, unit ini berfungsi untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasihat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Unit itu juga mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual (Pasal 43(6) Statuta Roma). Bahkan, dalam RPE, unit ini wajib untuk menjamin perlindungan dan kemanan saksi agar semua saksi dan korban dapat hadir di persidangan. Untuk itu unit ini wajib untuk membuat rencana perlindungan korban dan saksi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Disamping itu unit ini juga diberi kewenangan untuk membuat perjanjian dengan Negara-negara untuk kepentingan pemukiman (resettlement) korban dan saksi yang mengalami trauma atau ancaman. Di Indonesia, perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang 26/2000 dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 sebagai aturan pelaksanaannya. Namun berbagai aturan perlindungan saksi dan korban serta reparasi bagi korban yang diatur dalam Statuta Roma di atas banyak yang tidak diatur dalam Pasal 34 serta Peraturan Pemerintah tersebut. Akibatnya, praktek pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Tanjung Priok membuktikan bahwa banyak korban serta saksi yang tidak mau hadir ketika dipanggil 260 Lampiran ke pengadilan. Alasan-alasan mereka diantaranya adalah ketidakpercayaan adanya jaminan keamanan karena tidak adanya perahasiaan korban, tidak ada safe house, perlakuan terhadap korban dan saksi dari aparat, kurangnya persiapan dan pengalaman aparat, dan alasan biaya. Akibat dari ketidakhadiran saksi maka kebenaran tidak terungkap dengan baik sehingga keputusan tidak memenuhi rasa keadilan. Disamping itu asas peradilan yang cepat dan hemat pun tidak tecapai karena seringnya pengunduran / perobahan jadwal persidangan akibat ketidakhadiran saksi. b. Selain mendapatkan perlindungan, para saksi dan korban juga berhak mendapatkan reparasi moral dan material. Pasal 75 Statuta Roma mengatur mengenai berbagai bentuk reparasi terhadap korban (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi). Selain itu Pasal 79 Statuta Roma berdasarkan Majelis Negara-Negara Pihak berhak menetapkan adanya Trust Fund untuk kepentingan para korban dan keluarganya. Mahkamah dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer, atas perintah Mahkamah, kepada Trust Fund. Pengelolaan Trust Fund adalah berdasarkan kriteria yang diatur Majelis Negara-Negara Pihak. Secara rinci aturan ini diatur dalam Aturan 94 dari ICC Rules of Procedure and Evidence (RPE). 4. POKOK-POKOK ISI KONVENSI Secara garis besar isi konvensi adalah: BAB 1 Pembentukan Mahkamah. Mahkamah ini merupakan mahkamah yang permanen, mandiri dan bukan merupakan organ dari PBB, karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral. Namun antara Mahkamah dengan PBB tetap memiliki hubungan formal. Mahkamah berkedudukan di Den Haag, Belanda. 261 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia BAB 2 Jurisdiksi, Hukum yang dapat diterima dan diterapkan. Yurisdiksi ICC terbagi empat : a. territorial jurisdiction (rationae loci) : bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak, yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara pihak, dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi ad hoc. (Pasal 12 Statuta Roma) b. material jurisdiction (rationae materiae) : bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan agresi (Pasal 5-8 Statuta Roma) c. temporal jurisdiction (rationae temporis) : bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku yakni 1 Juli 2002. (Pasal 11 Statuta Roma) d. personal jurisdiction (rationae personae) : bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (natural person), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual criminal responsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil. (Pasal 25 Statuta Roma). BAB 3 Prinsip-prinsip Umum Hukum Pidana . Bagian ini mengatur mengenai beberapa prinsip umum hukum pidana yang digunakan oleh ICC yaitu bahwa ICC tidak berwenangan mengadili kejahatan yang dilakukan sebelum pendirian ICC. ICC hanya berwenang mengadili kejahatan yang masuk dalam jurisdiksinya, dan penghukuman yang dilakukan ICC harus selalu berdasar pada ketentuan yang ada pada Statuta Roma. Selain itu diatur bahwa ICC mengadili tanggung Jawab Pidana Perorangan dan bahwa kejahatan yang dilakukan anak dibawah usia 18 tahun tidak dapat diadili. 262 Lampiran BAB 4 Komposisi dan Administrasi Mahkamah. Mahkamah terdiri dari badan-badan berikut ini: (a) Kepresidenan; (b) Divisi Banding, Divisi Pengadilan dan Divisi Pra-Peradilan; (c) Kantor Penuntut Umum; (d) Kepaniteraan. BAB 5 Penyelidikan dan Penuntutan. Bagian ini berisi pengaturan mengenai: (a) Dimulainya Penyelidikan; (b) Tugas dan Kekuasaan Penuntut Umum Berkenaan dengan Penyelidikan; (c) Hak Orang-Orang Selama Penyelidikan; (d) Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pra-Peradilan. BAB 6 Persidangan. Bagian ini menjelaskan mengenai (a) Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pengadilan; (b) Hak-Hak Tertuduh; (c) Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dan Keikut-sertaan Mereka dalam Proses Pengadilan; (d) Bukti; (e) Perlindungan terhadap Informasi Keamanan Nasional; (f) Ganti Rugi kepada Korban BAB 7 Hukuman. Hukuman yang Bisa Diterapkan dan pengaturan mengenai Trust Fund BAB 8 Permohonan Banding dan Peninjauan Kembali. Pengaturan mengenai mekanisme perohonan banding dan pengaturan mengenai kompensasi kepada seorang yang ditahan atau dihukum BAB 9 Kerjasama Internasional dan Bantuan Yudisial. Salah satu yang paling menarik dibagian ini adalah adanya kewajiban dari Negara-Negara Pihak untuk memastikan bahwa ada prosedur yang tersedia dalam hukum nasional mereka bagi semua bentuk kerjasama yang ditetapkan di bawah bagian ini. 263 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia BAB 10 Pemberlakuan. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme pemberlakuan penghukuman. Kerjasama Negara-negara pihak dalam pemberlakuan penghukuman dan mekanisme pengawasannya. BAB 11 Majelis negara-negara Pihak. Pengaturan mengenai berbagai kewajiban dan kewenangan dari Negara-negara pihak. BAB 12 Pendanaan. Pengeluaran Mahkamah dan Majelis Negara-Negara Pihak, akan disediakan oleh sumber-sumber berikut ini: (a) Kontribusi yang diperkirakan oleh Negara-Negara Pihak; (b) Dana yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tunduk pada pengesahan Majelis Umum, terutama dalam kaitan dengan pembiayaan yang timbul yang disebabkan oleh penyerahan dari Dewan Keamanan. BAB 13 Klausal Penutup. Setiap perselisihan akan diatur dengan keputusan agama. Bagian terakhir ini mengatur pula larangan reservasi dan mekanisme amandemen bagi Statuta Roma. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan aslinya dalam bahasa Inggris. Pasal 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR….. 264 KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL IKOHI – ELSAM – PSHK – YLBHI – IMPARSIAL Sekretariat: Kalasan Dalam No. 5 Menteng – Jakarta Telp/fax: +6221 3157915, email: [email protected] PROFIL KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Tentang Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil yang mengkampanyekan ratifikasi dan implementasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Dalam pandangan Koalisi, kampanye dan penggalangan dukungan bagi Indonesia untuk ratifikasi Statuta Roma sangat penting. Selain karena sudah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, ratifikasi Statuta Roma ini akan menjadi ukuran keseriusan Indonesia dalam rejim keadilan internasional dan menghentikan impunitas. Mahkamah Pidana Internasional yang merupakan mekanisme sistem keadilan internasional menjadi satu kebutuhan untuk menghentikan impunitas bagi berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat yang tidak tuntas dan mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM yang berat di kemudian hari. Sampai hari ini, 108 negara telah meratifikasi Statuta Roma dan hanya 7 265 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia diantaranya dari Asia yaitu Afghanistan, Tajikistan, Mongolia, Kamboja, Timor Leste, Jepang dan Korea Selatan. Ratifikasi oleh Indonesia akan memberi contoh dan dorongan bagi negara-negara lain di wilayah Asia. Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Koalisi yang sudah terbentuk sejak tahun 2006 terutama difokuskan pada pembuatan dan penyempurnaan Naskah Akademis dan RUU Ratifikasi Statuta Roma; sosialisasi mengenai pentingnya ratifikasi Statuta Roma bagi pemenuhan keadilan untuk korban dan perbaikan system hukum di Indonesia; melakukan advokasi dalam proses legislasi RUU Ratifikasi Statuta Roma di DPR RI; serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah untuk merealisasikan ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Struktur Koalisi Convenor: Mugiyanto Tim ahli: - Agung Yudhawiranata, S.IP, LL.M - Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si, LL.M. - Reny Rawasita Pasaribu, S.H., LL.M - Zainal Abidin, S.H. Penasehat: - Enny Soeprapto, Ph.D - Fadillah Agus, S.H., M.H. - Galuh Wandita - Ifdhal Kasim, S.H. - Kamala Tjandrakirana, M.A - Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M Sekretariat: - Simon, S.H. - Dhyta Caturani, - Veronica Iswinahyu Anggota: Koalisi ini beranggotakan lembaga-lembaga dan individu yang menaruh perhatian pada reformasi sistem hukum, penegakan keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain Elsam, IKOHI, Imparsial, PSHK, YLBHI, Demos, KontraS, PAHAM FH Unpad, FRR, terAs Trisakti, Komunitas Korban 65, Komunitas 266 Lampiran Korban Tanjung Priok, Federasi LBH APIK Indonesia, Gema Prodem, DPP.SSSV, Kontras Medan, SBMI-SU, FH USU, PBHI Wil. USU, Univ.D Agung, Bakuaa SU, LBH Medan, SMM Medan, KKP HAM, Senat FH UNCEN, Kontras Papua, Komunitas Supervisor Papua, PMKRI Jayapura, Komunitas Supervisor Abepura, UKM Dehaling, LBH Papua, IKOHI K2N, ElshamPB, HMI Cab. Jayapura, LP3A-P, 6 MKI JPR, KPK GKI, KPKC HKBP-Medan, STH Uel Mandiri, Dewan adat papua, STIH, AMTPI, Aji papua, UKM Dehaling UNCEN, BEM STIH, Fosis UMI, LBH Makasar, Walhi Sul-Sel, EPW Sul – Sel, PUSHAM – UH, Gardan, PKHUN-UH, Aji Makasar, Kontras Sulawesi, FIK ORNOP, LPR KROB, LAPAR, Sedrap, LBH Apik Makasar, SPAM, SKP-HAM, Pusham Univ’45, Walhi Sulsel, LBH-Makassar, LPKP, BEM- UNM, SKP- HAM Sul – Sel, Komisi A DPRD Jatim, SBMI-Jatim, KPPD – Surabaya, ALHA-RAKA, SyarikatJember, LBH-Surabaya, IKOHI-Malang, LPKP 65-Surabaya, MBH-Surabaya, SMKR-Surabya, BEM UWK-Surabaya, LHKISurabaya, BEM FISIP Unair- Surabaya, Repdem – Jatim, Forsam – Unair, Marules – Banyuwangi, CRCS – Surabaya, Lakpesdam NU – Sumenep, LSAPS – Lamongan, AGRA – Jatim, Walhi – Jatim, FKTS – Pasuruan, Korban Alas Tlogo – Pasuruan, Jerit, WE SBY, KBS, CRCS, CRCS, Aji Surabaya, AIMSA – Surabaya, BM – PAN – Jatim, Staff Pengajar HI FISIP Unair, LPKP 65, ICRC, FRR Law Office, LESPERSSI, IKOHI-Jakarta, Voice Human Rights, dan lainnya. Alamat Sekretariat: Jl. Kalasan Dalam No.5 Menteng Jakarta Pusat Telepon/Fax: (021) 3157915 e-mail: [email protected] 267 Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia 268 ICC atau Mahkamah Pidana Internasional digagas sebagai jawaban atas kebutuhan akan keadilan dan sekaligus refleksi dari berbagai tribunal yang pernah digelar yang lebih merupakan pengadilan bagi pemenang. Institusi permanen yang disahkan pada tahun 2002 menjadi pilihan terbaik saat ini bagi negara-negara dan masyarakat dunia dalam upaya memenuhi dahaga akan keadilan yang independen, berwibawa dan partisipatif. Tak kurang hingga saat ini 108 negara mengikatkan diri pada mekanisme ICC. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi niali-nilai kemanusiaan universal dan keadilan menunjukkan keinginan kuat untuk bergabung dengan negara-negara lain dalam mekanisme ICC. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya ICC dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2008. Berlandaskan pada tekad ini, pemerintah telah memerintahkan jajaran terkait untuk mewujudkannya. Sambutan positif juga diberikan masyarakat sipil atas niat pemerintah untuk segera meratifikasi ICC. Terbentuknya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Ratifikasi ICC di Indonesia yang beranggotakan hampir 100 lembaga dan individu yang peduli menjadi bukti sekaligus bagian dari upaya mendorong niat ratifikasi menjadi kenyataan. Upaya mendorong pemerintah untuk menepati jadwal ratifikasi ICC sesuai dengan RANHAM bukannya pekerjaan yang mudah dan lapang. Sebaliknya, upaya ini merupakan jalan berliku dan membutuhkan proses panjang. Mengenalkan ICC dan seluk-beluknya pada para pihak, meyakinkan bahwa ICC adalah mekanisme yang dihadirkan bukan untuk menyudutkan siapapun dan menjaring aspirasi dan harapan publik akan kehadiran ICC menjadi bagian keseharian dari kerja koalisi. Meyakini bahwa setiap proses dan perjalanan adalah landasan terbaik bagi refleksi dan pembelajaran, maka pencatatan atas proses, liku dan pengalaman dalam kerja koalisi adalah mutlak. Penulisan buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. ld f INDONESIA • AUSTRALIA LEGAL DEVELOPMENT FACILITY Jalan Panjang menuju Ratifikasi ICC di Indonesia K eadilan selalu menjadi harapan dalam sejarah kehidupan manusia yang penuh dengan kontradiksi dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya. Perbenturan kepentingan melahirkan ketidakadilan yang menuntun moral dan pemahaman manusia akan kebutuhan akan mekanisme dan perangkat kehidupan yang bertujuan mewujudkan keadilan. Diantaranya dalah mekanisme pengadilan.