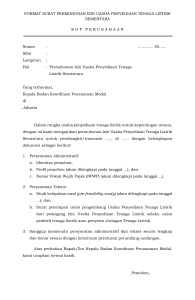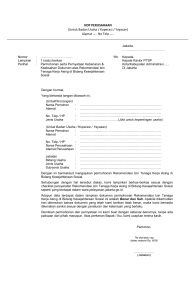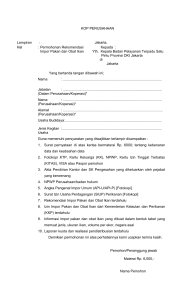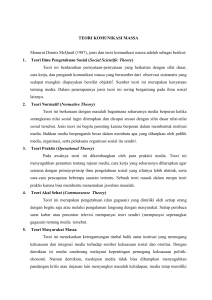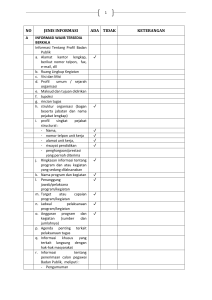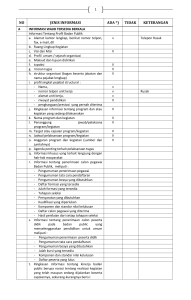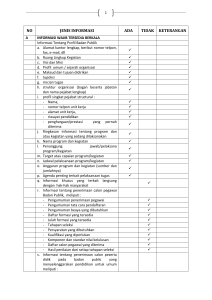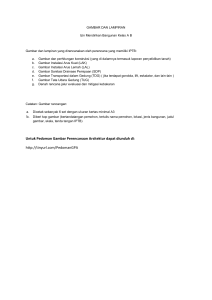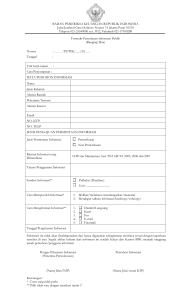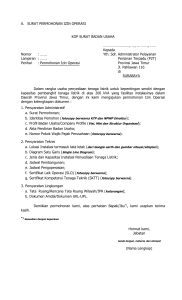Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH
advertisement

Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Perihal: Kesimpulan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6; Pasal 57 ayat (2) dan (3); serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, c dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat, Perkenankanlah kami: Wahyudi Djafar, S.H., Al Araf, S.H., M.T., Indriaswati D. Saptaningrum, S.H., LL.M., Kristina Viri, S.H. Zainal Abidin, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Ardimanto Putra, S.H., Emerson Junto, S.H., Donal Fariz, S.H., Lola E. Kaban, S.H., Abraham Utama, S.H., Erwin Natosmal Oemar, S.H., Refki Saputra, S.H., Dina Ardiyanti, S.H., M.A., M. Fandrian Hadistianto, S.H., Ari Lazuardi, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Eddy H. Gurning, S.H., Adiani Viviana, S.H. Kesemuanya adalah advokat/pengacara publik/asisten advokat/asisten pengacara publik, yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kebebasan Berserikat, memilih domisili hukum di Jalan Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telp. 021-7972662 Fax. 02179192519, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2013 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama: 1. Yayasan FITRA Sumatera Utara, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, Gg. Sukmawati No. 1A Medan 20217, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan FITRA Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Irvan Hamdani HSB, S.Kom., warga negara Indonesia, lahir di Gunung Tua, 25 Oktober 1978, agama Islam, selaku Sekretaris Dewan Pengurus. Selanjutnya disebut sebagai _______________________________________ Pemohon I 2. Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), beralamat di Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Akta Pendirian Perkumpulan ICW, dalam hal ini diwakili oleh Danang Widoyoko, S.T., lahir di Rembang, 8 Maret 1973, agama Katholik, warga negara Indonesia, selaku Koordinator Badan Pekerja. Selanjutnya disebut sebagai ______________________________________ Pemohon II 3. Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), beralamat di Jl. Pedati Raya No. 20, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian YAPPIKA, dalam hal ini diwakili oleh Abdi Suryaningati, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, 7 Februari 1964, agama Islam, selaku Sekretaris Pengurus. Selanjutnya disebut sebagai _____________________________________ Pemohon III 4. Ir. H. Said Iqbal, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 5 Juli 1968, pekerjaan karyawan swasta sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), agama Islam, bertempat tinggal di jalan Lestari RT/RW 009/003, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai _____________________________________ Pemohon IV 5. M. Choirul Anam, S.H., warga negara Indonesia, lahir di Malang, 25 April 1977, pekerjaan Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG), agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mahoni Blok CO No. 02 BDB. 2 RT/RW 006/015, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai ______________________________________ Pemohon V 6. Poengky Indarti, S.H., LL.M., warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, 18 Februari 1970, pekerjaan Direktur Eksekutif Imparsial, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sentosa Blok D8 No. 10, RT/RW 007/009, Kel. Nanggewer Mekar, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai _____________________________________ Pemohon VI Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai PARA PEMOHON. Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajukan kesimpulan dalam perkara No. 03/PUUXII/2014 perihal pengujian Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6; Pasal 57 ayat (2) dan (3); serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, c dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada kesempatan yang baik ini, untuk dan atas nama Para Pemohon, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas dilangsungkannya persidangan dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dalam suatu ruang pembuktian yang baik dan adil. Dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing-masing, atas permasalahan yang mengemuka dalam pengujian undang-undang a quo. Proses persidangan ini telah berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dengan argumentasi konstitusional dan hukum, serta aspek-aspek lain yang melingkupinya, termasuk politis dan sosiologis. Perdebatan-perdebatan seputar jaminan konstitusional dan hukum terhadap hak atas kebebasan berserikat, diperbincangkan dengan begitu terbuka selama berlangsungnya persidangan. Banyak perspektif dan sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli yang dihadirkan, sehingga melengkapi setiap celah persoalan dalam perlindungan hak Page 1 of 19 atas kebebasan berserikat, sehingga kami berharap itu semua bisa membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, di dalam mengakhiri perdebatan seputar ruang lingkup dan batasan perlindungan hak atas kebebasan berserikat yang diatur dalam UUD 1945. Dari persidangan ini, seluruh masyarakat Indonesia, bisa mengikuti betapa luasnya perdebatan seputar hak atas kebebasan berserikat, termasuk sejauhmana negara bisa terlibat untuk mengaturnya. Selain itu, khusus bagi para pembentuk undang-undang, juga pemerintah selaku pelaksana undang-undang, yang dalam praktiknya langsung bersinggungan dengan masyarakat, kami harap dapat menarik pelajaran yang berharga dalam menegakkan prinsipprinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia, dalam koridor negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Lebih jauh, untuk keperluan menyempurnakan seluruh proses persidangan yang telah dilangsungkan, maka melalui uraian ini, kami Para Pemohon hendak membabarkan Kesimpulan dari permohonan atas proses pemeriksaan di persidangan yang telah berjalan. Kesimpulan ini sebagai penutup agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar dapat mengambil putusan yang berdasarkan konstitusi dan aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan cita hukum lainnya, kepastian dan kemanfaatan tentunya. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Pemohon dalam uraian permohonannya, bahwa melalui permohonan ini Para Pemohon hendak mengujikan Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6; Pasal 57 ayat (2) dan (3); serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, c dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945. Menurut Para Pemohon ketentuan a quo telah melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of constitution. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi ialah satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Hal ini seperti dituangkan di dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 maupun secara detail telah diatur di dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bersandar pada ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi jelas memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. B. Kedudukan hukum Para Pemohon Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing). Sementara Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar, akibat berlakunya UU a quo. Pemohon I s.d Pemohon III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan Page 2 of 19 sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam pemberantarasan korupsi, serta menumbuhkembangkan partisipasi dan insiatif masyarakat dalam pembangunan. Dasar dan kepentingan hukum Pemohon I s.d Pemohon III dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 1 angka 6; Pasal 57 ayat (2) dan (3); serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, c dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya, seperti telah dijelaskan dalam permohonan a quo. Upaya-upaya dan serangkain kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon III adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Selain jaminan perlindungan konstitusional, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang bersih. Ketentuan serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari UU a quo merupakan persoalan setiap warga negara karena sifat universalnya, yang bukan hanya urusan Pemohon I s.d Pemohon III, terutama menyangkut keberlanjutan serta kepastian ruang partisipisasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo, merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I s.d Pemohon III untuk terus mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, maupun penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemohon I khususnya, telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan aktual akibat berlakunya UU a quo. Kerugian ini terjadi saat Pemohon I mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kab. Karo, Sumatera Utara. Permohonan informasi ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan, juga merupakan pelaksanaan dari hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Page 3 of 19 Menanggapi permintaan tersebut, Dinas Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kab. Karo menolak untuk memberikan informasi sebagaimana diajukan oleh Pemohon I dengan alasan bahwa Pemohon I belum terdaftar di Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Karo. Merujuk pada UU a quo, Dinas Informasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Karo menyatakan bahwa Pemohon I belum absah, sehingga SKPD di Kabupaten Karo tidak dapat memenuhi permintaan informasinya. Kejadian yang dialami oleh Pemohon I jelas memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dari UU a quo, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional Pemohon I. Mengapa menimbulkan ketidakpastian hukum? Bahwa Pemohon I berdasarkan pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, nyata-nyata telah terdaftar sebagai badan hukum Yayasan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor: AHU-8315.AH.01.04 Tahun 2012, tertanggal 26 Desember 2012. Oleh karena Pemohon 1 telah terdaftar sebagaimana diatur oleh UU Yayasan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo, maka Pemohon I tidak perlu melakukan pendaftaran kembali pada organisasi mana pun, termasuk Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Karo. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo menyebutkan, “Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar”. Terjadinya peristiwa tersebut, terlihat sangat nyata dan aktual kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I akibat dari berlakunya UU a quo, yang menciptakan situasi ketidakpastian hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), sehingga menghambat partisipasi Pemohon I dalam pembangunan (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945), serta dalam menjalankan hak asasinya (Pasal 28F UUD 1945). Oleh karena itu, Pemohon I mempunyai hubungan causal-verband dengan berlakunya UU a quo, dan memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan publik, khususnya badan hukum serupa, untuk mengajukan permohonan uji materiil UU a quo. Sedangkan terhadap Pemohon II, berlakunya UU a quo juga telah menghambat upaya menguatkan posisi tawar rakyat yang teroganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan jender. Jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 28 Tahun 1999) bagi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemohon II dalam rangka mencapai tujuannya maupun maksud yang hendak dicapai oleh UU No. 28 Tahun 1999, potensial digagalkan oleh lahirnya UU a quo, yang menciptakan situasi ketidakpastian hukum. Sementara terhadap Pemohon III, pembatasan dan rezim pengaturan tunggal terhadap organisasi masyarakat sipil yang diatur oleh UU a quo, dengan berbagai kerumitannya, telah berakibat pada dirugikannya hak-hak konstitusional Pemohon III. Kerugian ini khususnya terjadi dikarenakan lahirnya UU a quo sangat potensial menggagalkan upaya-upaya Pemohon III di dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum. Dalam rangka upaya tersebut, Pemohon III berupaya untuk menumbuhkembangkan berbagai macam organisasi masyarakat sipil, dengan beragam bentuk dan aktivitasnya. Sebaliknya, berlakunya UU a quo, malah berupaya untuk membatasi upaya itu semua, yang diakibatkan oleh berbagai kerumitan aturan pendirian organisasi. Page 4 of 19 Secara umum berlakunya UU a quo juga nyata-nyata atau setidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon III untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maupun sejumlah peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi sebagai akibat: (i) UU a quo didesain untuk menghambat pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat; dan (ii) UU a quo menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil. Pemohon IV merupakan individu warga negara Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang aktif memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan buruh di Indonesia, melalui wadah serikat/organisasi buruh. Bahwa keberadaan serikat buruh, selain dilindungi oleh UUD 1945, juga dijamin oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan Indonesia dalam undang-undang nasionalnya. Lahirnya UU a quo nyata-nyata atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon IV, dalam rangka memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan buruh melalui wadah organisasi buruh, dikarenakan munculnya UU a quo baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat hidup dan berkembangnya organisasi buruh sebagai ruang perjuangan buruh. Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Wakil Direktur dari Human Rights Working Group (HRWG), sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang aktif mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi. Bahwa Pemohon V juga aktif melakukan penyadaran publik dan terlibat secara terus-menerus dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik, melalui beragam aktifitas. Berlakunya UU a quo, nyata-nyata atau setidak-tidaknya potensial menghambat atau bahkan menggagalkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemohon V. Pemohon VI merupakan individu warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Direktur Eksekutif Imparsial, sebuah organisasi hak asasi manusia di Indonesia yang aktif melakukan pemantuan pelaksanaan HAM di Indonesia dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemohon VI juga aktif melakukan penyadaran publik dan terlibat secara terusmenerus dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik, melalui beragam aktifitas di tempat bekerjanya. Sebagaimana Pemohon V, berlakunya UU a quo, juga nyata-nyata atau setidaknya berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon VI. Dari uraian tersebut secara jelas terlihat bahwa Pemohon IV s.d. Pemohon Pemohon VI adalah individu-individu warga negara yang concern dengan kepentingan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan buruh yang diperjuangan melalui serikat buruh, serta upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berserikat. Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan adanya rumusan pasal, ayat dan frasa dari UU a quo, karena tidak sejalan dengan jaminan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, serta berseberangan dengan jaminan hak atas kebebasan berserikat, yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Pemohon IV s.d. Pemohon VI juga merupakan pembayar pajak (tax payer) aktif, yang menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya UU a quo, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak berpartisipasi dalam pembangunan dan hak atas kebebasan berserikat. Page 5 of 19 Berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu pula, keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU a quo terhadap UUD 1945. C. UU a quo mengkhianati amanat reformasi, pengesahannya dipaksakan dan minim dukungan serta legitimasi publik Reformasi konstitusi menjadi pijakan penting dalam menghidupkan kembali wibawa hukum, yang bersandar pada prinsip-prinsip the rule of law, setelah berakhirnya pemerintahan rezim otoritarian birokratik Soeharto. Selama pemerintahan militer Orde Baru berkuasa, meski senantiasa mengatasnamakan hukum dalam bekerjanya, namun tegas harus dikatakan, hukum sebatas menjadi alat legitimasi kekuasaan, propaganda dan teror. 1 Produk-produk hukum yang diciptakan tidak berpegang pada prinsip the rule of law, tetapi sebaliknya, justru mengedepankan pendekatan the rule by law. Suatu cara pikir yang menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan belaka, dengan menitikberatkan pada model legalistik. 2 Merujuk pendapat Moh. Mahfud MD (1998), dalam situasi ini, politik cenderung mendeterminasi hukum, akibatnya hukum berkarakter menindas dan tunduk pada politik kekuasaan. 3 Oleh karena itu, amandemen konstitusi berupaya untuk melakukan pembongkaran terhadap rumusan-rumusan UUD 1945 yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, dengan mengatasnamakan hukum, melalui penciptaan aturan yang lebih detil. Sistem cheks and balances juga diperkuat, sebagai sarana saling mengawasi antar-cabang-cabang kekuasaan negara. Amandemen konstitusi juga memberikan penegasan perihal jaminan ruang yang besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dengan beragam saluran yang disediakan, termasuk mendirikan serikat/organisasi, sebagaimana ditegaskan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru mencengkramkan kekuasaan politiknya, dalam rangka pembentukan ‘negara kuat’ salah satunya dengan pembentukan sejumlah undang-undang bidang politik, diantaranya adalah UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Undang-undang ini dibentuk sebagai sarana kontrol negara terhadap kehidupan organisasi masyarakat sipil, dalam bingkai asas tunggal, termasuk juga penciptaan wadah tunggal untuk organisasi-organisasi yang sejenis. Sayangnya, seiring dengan berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru, undang-undang yang materinya bertentangan dengan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat, sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ini, justru tidak segera dilakukan pencabutan. Kondisi ini seperti dikemukakan oleh Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Hamdan Zoelva, pada saat proses amandemen UUD 1945, yang terkait dengan materi hak asasi manusia. Pada kesempatan tersebut Hamdan Zoelva mengatakan: 4 Lihat Julie Southwood dan Patrick Flanagan, Indonesia: Law, Propaganda and Terror, (London: Zed Press, 1983). Lihat Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 3 Lihat Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998). 4 Lihat Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 288. 1 2 Page 6 of 19 Seperti halnya yang lalu di Pasal 28 diamanahkan hak berserikat kemudian diatur di dalam Undang-Undang Keormasan, maka hak berserikat itu dibatasi sedemikian rupa dalam undang-undang sehingga membelenggu hak-hak asasi manusia yang sudah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar itu. Pernyataan tersebut seperti memberi penegasan bahwa UU Ormas sebagai produk dari pemerintahan Orde Baru, meski dikatakan sebagai pengejawantahan dari Pasal 28 UUD 1945, namun materinya justru kontradiktif dengan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat yang ditegaskan konstitusi. Oleh karenanya, sudah selayaknya pula undang-undang ini dihapuskan keberadaannya dalam era demokrasi konstitusional hari ini, yang menjunjung tinggi negara hukum dan hak asasi manusia. Namun demikian, setelah satu dekade masa reformasi, justru pemerintah dan DPR berencana untuk melakukan ‘revitalisasi’ terhadap eksistensi UU Ormas, dengan memasukkan agenda pembentukan UU Ormas, sebagai salah satu prioritas legislasi nasional (Prolegnas) 2009-2014. Sejumlah isu jangka pendek, khususnya tindak kekerasan yang kerap dilakukan oleh Ormas tertentu, menjadi argumentasi resmi pemerintah dan DPR, untuk memberikan legitimasi bagi upaya menghidupkan kembali salah satu undang-undang warisan otoritarian ini. Padahal problem utamanya terletak pada ketidaktegasan aparat penegak hukum, untuk menindak secara pidana, oknum-oknum Ormas yang melakukan tindak kekerasan. Hal ini sebagaimana juga diakui oleh pemerintah dan DPR, dalam rapat gabungan antara Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mendagri, Menkumham, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pada 30 Agustus 2010. Persoalan utamanya bukan pada ketiadaan aturan untuk menindak. Kendati begitu, pada kenyataannya pemerintah dan DPR tetap merekomendasikan pentingnya revisi UU Ormas. Bukan untuk menjamin hak atas kebebasan berserikat, namun semangatnya agar dapat mengawasi dan menindak secara hukum serikat/organisasi. Klimaksnya, pada 2 Juli 2013, DPR dan Pemerintah menyepakati pengesahan RUU Ormas menjadi undang-undang. 5 Pengesahan ini terkesan dipaksakan, mengingat besarnya penolakan publik terhadap pengesahan RUU ini, termasuk dari organisasi-organisasi besar, yang memiliki pengaruh sangat kuat di Indonesia. Publik justru menghendaki UU Ormas dicabut, bukan ‘direvitalisasi’. Dalam pernyataannya, Muhammadiyah menilai RUU Ormas memiliki paradigma totaliter dan menganut paham kekuasaan yang absolut. Muhammadiyah menolak dan menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun RUU Perkumpulan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 28 UUD 1945. Sementara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan enam pokok pandangan kritis dan meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Ormas, guna menghindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pengesahan RUU ini. Berbagai organisasi keagamaan lainnya juga secara tegas menolak kehadiran UU Ormas, seperti dinyatakan antara lain oleh: Majelis Taklim Alqur'an (MTA), Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Media Umat Kristen Indonesia (MUKI), Walubi, Forum Komunikasi Kristen Jakarta (FKKJ), Nasyiatul Aisyiah, Dewan Dakwah Islamiah, PGI Wilayah, Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) DKI Jakarta, dan Parmusi. Kelompok buruh juga menyatakan penolakan serupa, seperti diungkapkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPSI, FSPMI, FSPNI, FSP, Ini merupakan rapat paripurna ketiga yang digelar dengan agenda pengesahan RUU Ormas. Dua rapat paripurna sebelumnya gagal mengesahkan, akibat kuatnya penolakan dari dalam DPR sendiri. 5 Page 7 of 19 KEP, PPMI, dan FSP. Beberapa kali unjuk rasa besar dilakukan oleh kelompok buruh di gedung DPR, untuk menolak RUU Ormas. Pernyataan menolak RUU Ormas, secara resmi dikemukakan pula oleh sejumlah lembaga negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Komnas HAM, RUU Ormas dinilai bertentangan dengan nilai-nilai HAM, serta menjadi ancaman terhadap kebebasan berserikat. Lebih jauh Komnas HAM merekomendasikan agar segera dibentuk dan disahkan UU Perkumpulan, sebagai pendamping UU Yayasan. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan, tindakan pengesahan RUU Ormas menjadi undangundang, oleh DPR dan pemerintah, adalah salah satu bentuk ‘pengkhianatan’ nyata terhadap mandat reformasi, yang menghendaki adanya jaminan atas kebebasan berserikat. Sedangkan UU Ormas adalah bentuk nyata pengekangan terhadap kebebasan berserikat, yang jauh dari mandat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan, pemaksaan pengesahan RUU Ormas oleh DPR dan pemerintah, di tengah fakta-fakta masifnya penolakan terhadap RUU tersebut, juga memperlihatkan bahwa pembentukan UU Ormas tidak memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. D. UU a quo berwatak otoritarian, tidak relevan dan bertolak belakang dengan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat Membaca secara keseluruhan materi muatan UU a quo, jelas kita tidak akan menemukan perbedaan yang diametral dengan UU Ormas terdahulu, UU No. 8 Tahun 1985. Oleh karena itu, secara lugas bisa disimpulkan, bahwa UU a quo berwatak otoritarian, meski lahir dalam sebuah era yang demokratis. Kesimpulan ini setidaknya tergambar dari keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan ini. Ahli Drs. Amir Effendi Siregar, M.A., misalnya mengatakan, materi UU a quo tak bisa dilepaskan dengan Permendagri 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang dikeluarkan pada 23 April 2012. Permendagri yang isinya penuh dengan semangat anti demokrasi dan bersifat sangat otoriter itu justru materi muatannya diadopsi dan dinaikkan statusnya oleh UU a quo. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa semua organisasi wajib mendaftarkan diri dan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini bisa dicabut apabila organisasi menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 6 Lebih jauh, ahli Amir Effendi Siregar menyatakan, secara substansi, materi UU a quo tidak jauh berbeda dengan Permendagri No. 33 Tahun 2012 dan UU No. 8 Tahun 1985, yang lahir pada masa otoriter. UU a quo berambisi mengatur seluruh organisasi masyarakat sipil, termasuk yayasan dan perkumpulan. Bahkan tidak hanya itu, UU a quo juga menghambat kebebasan berkomunikasi dan kemerdekaan pers. Dalam UU a quo termuat larangan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila (atheisme, komunisme/marxisme, leninisme). Akibatnya, organisasi pers dapat diklasifikasikan sebagai organisasi bermasalah, yang dianggap melanggar UU a quo, karena pemberitaan, artikel, informasi yang diberitakannya seringkali menyebarkan ideologi lain, 6 Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 11 Februari 2014, hal. 17. Page 8 of 19 yang kadangkala memang tidak sesuai Pancasila. Padahal, tugas media dan wartawan adalah menyajikan informasi yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pandangan dan ajaran yang dapat saja bertentangan dengan Pancasila. 7 Sekali lagi, pembentukan UU a quo, jelas telah menantang semangat jaman, yang menghendaki adanya jaminan penuh terhadap hak atas kebebasan berserikat, yang juga memiliki korelasi kuat dengan perlindungan terhadap kebebasan pers. Dalam proses amandemen UUD 1945, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili Didik Supriyanto, pada saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR mengatakan: 8 Oleh karena itu, selayaknya dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Bahkan perlu dinyatakan pula bahwa tidak boleh ada satupun undangundang ataupun peraturan lainnya yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Tidak hanya AJI, organisasi-organisasi pers lainnya, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia (MPPI), juga memberikan usulan senada. PWI yang diwakili Tarman Azam, pada saat itu meminta kepada MPR, untuk menegaskan adanya jaminan kebebasan pers, sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari ketentuan Pasal 28 UUD 1945. 9 Usulan-usulan tersebut ditegaskan kembali oleh anggota PAH I BP MPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul Kholiq, yang mengatakan: 10 Pada Pasal 28, meskipun ini tidak terbahas di dalam Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja dan menjadi kesepakatan bulat. Tetapi saya kira kita juga harus mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang masuk dari kalangan masyarakat pers kita. Karena di situ mengesankan bahwa Pasal 28 ini bentuk pengekangan yang diabadikan. Oleh karena itu maka kami usulkan bahwa Pasal 28 ini disempurnakan menjadi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dijamin oleh negara”. Jadi kata yang ditetapkan dengan undang-undang itu disempurnakan menjadi, dijamin oleh negara. Saya kira ini lebih logis dan kemudian bisa memberikan satu pemahaman bahwa, demokrasi kita memang berjalan dengan baik. Bersandar dari penafsiran historis (original intent) atas pembahasan terhadap Pasal 28, dalam proses amandemen UUD 1945, nampak sekali bahwa jaminan terhadap hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran serta pendapat, merupakan material penting yang akan menjadi alat ukur sejauhmana berjalannya demokrasi kita. Oleh karena itu, segala bentuk pengekangan harus dijauhkan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Sementara ahli Sri Budi Eko Wardhani, M.Si., menyebutkan, untuk pertama kalinya, kelahiran UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas, adalah dimaksudkan untuk menjauhkan aktivitas masyarakat sipil di tingkat bawah dari kegiatan politik. Pada masa ini ormas dihimpun dalam satu wadah pembinaan, yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Menurut UU Ormas, pemerintah dapat membekukan atau membubarkan pengurus atau organisasi apabila mereka Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 11 Februari 2014, Hal. 18-19. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 257. 9 Ibid., hal. 255. 10 Ibid., hal. 202. 7 8 Page 9 of 19 melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum atau menerima bantuan dana asing tanpa persetujuan pemerintah. Situasi berbeda terjadi setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Pada era demokrasi, masyarakat sipil tidak dapat lagi diabaikan dalam proses perubahan politik ke arah yang lebih demokratis, sebab merekalah yang sesungguhnya yang memberikan legitimasi politik bagi kekuasaan pemerintahan. 11 Namun demikian, dikatakan oleh Sri Budi Eko Wardhani, ketegangan antara masyarakat sipil dan negara kembali terjadi, khususnya paska-Pemilu 2009, yang berujung dengan lahirnya UU a quo. Mengapa demikian? Sebab Organisasi Masyarakat Sipil kemudian berkembang dengan memerankan berbagai fungsi, termasuk yang didorong adalah kontrol terhadap otoritas politik. Sayangnya, negara membaca peranan tersebut sebagai ancaman. Lebih jauh dikemukakannya, salah satu persoalan krusial dari UU a quo, adalah rumusan norma dari UU a quo yang telah menyempitkan makna masyarakat sipil menjadi Ormas. Hal ini memperlihatkan, bahwa pembentuk undang-undang sesungguhnya tidak memahami keragaman masyarakat sipil, yang sebetulnya bisa tumbuh dari komunitas yang kecil. Pada kenyataanya di lapangan, organisasi masyarakat sipil tidak selalu terlembaga dan memiliki AD/ART. Keunikan organisasi masyarakat sipil disesuaikan dengan kebutuhan untuk berkumpul agar kepentingannya dapat tersampaikan. Organisasi Masyarakat Sipil juga memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Esensi keberadaan masyarakat sipil adalah pengawasan dan kontrol terhadap proses politik negara, karena dia berada di luar arena politik. Oleh karenanya, keberadaan UU a quo secara evolutif dan sistematis jelas akan melemahkan fungsi kontrol dari masyarakat sipil. Kondisi ini dinamakan semi otoriter, yaitu secara prosedural demokratis namun secara substansial nondemokratik dan ini sangat berbahaya, tegas Sri Budi Eko Wardhani. 12 Pandangan senada juga dikemukakan oleh ahli Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Menurutnya paradigma yang melatarbelakangi cara pandang penerbitan UU a quo sangat keliru, karena cenderung melihat masyarakat sipil sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan bahkan sumber disintegrasi bangsa. Padahal, masyarakat sesungguhnya adalah sumber legitimasi bagi keabsahan negara dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu demokratis. Oleh karenanya, menjadi sangat aneh, ketika masyarakat yang tidak lain adalah himpunan warga negara, yang telah memberi mandat politik melalui pemilu, dicurigai sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan bahkan sumber disintegrasi bangsa. 13 Kerangka pikir semacam itu, dikatakan oleh Syamsuddin Haris, hanya pantas dimiliki oleh rezim-rezim otoriter seperti Orde Baru, yang menjadikan masyarakat sebagai musuh negara, sehingga semua aktivitas masyarakat dicurigai dan diawasi oleh negara. Hal itu wajar saja, mengingat dalam sistem otoriter, negara hanya percaya pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sangat mengherankan jika di dalam sistem demokrasi konstitusional, paradigma dan kerangka pikir yang keliru dan sesat itu dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang, dengan mengesahkan UU a quo. Ironisnya lagi, paradigma dan kerangka pikir yang keliru dan sesat tersebut, dihidupkan atas nama Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan bangsa. 14 Dilihat dari urgensinya dalam sistem demokrasi konstitusional sekarang ini, ditegaskan Syamsuddin Haris, UU a quo tidak diperlukan dan tidak relevan, karena semua kekhawatiran Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 27 Februari 2014, hal. 10-11. Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 27 Februari 2014, hal. 12, 13 dan 34. 13 Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 17 Maret 2014, hal. 4. 14 Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 17 Maret 2014, hal. 5. 11 12 Page 10 of 19 terkait, misalnya tindak kekerasan oleh ormas tertentu, penyimpangan terhadap ideologi negara, dan juga pemberian sumbangan dari atau kepada pihak asing, telah ada solusi dan sanksi hukumnya di dalam berbagai produk perundang-undangan lainnya. Meningkatnya tindak kekerasan oleh berbagai elemen masyarakat selama lebih dari 10 tahun ini, tentunya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menerbitkan UU a quo. Tindak kekerasan massa lebih terkait dengan kegagalan negara mengelola kebebasan berekspresi di satu pihak, dan ketidakmampuan aparat negara dalam penegakan supremasi hukum di lain pihak. 15 Ahli yang dihadirkan Para Pemohon, Prof. Dr. Syamsuddin Haris bahkan menyatakan, UU a quo justru lebih buruk dari UU No. 8 Tahun 1985 yang diterbitkan oleh rezim otoriter. Mengapa lebih buruk? Jawabannya sangat jelas, karena paradigma dan kerangka pikir yang keliru dan sesat itu, justru dihidupkan kembali dalam era demokrasi konstitusional. Seperti diketahui, tiga keberatan kita atas UU No. 8 Tahun 1985, ternyata juga kembali diadopsi oleh UU a quo, yang meliputi: (i) adanya kewajiban bagi setiap ormas berideologikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dalam UU a quo, kemudian bahasanya dihaluskan menjadi tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; (ii) kewenangan pembinaan juga sama, hanya bahasanya diganti menjadi pemberdayaan, otoritasnya pun masih berada di instansi yang sama—Kementerian Dalam Negeri; dan (iii) kewenangan pemerintah untuk membekukan kepengurusan dan bahkan membubarkan Ormas jika dinilai tidak berasaskan Pancasila. 16 Dari paparan sejumlah ahli yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon, maupun juga penafsiran terhadap materi rumusan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dengan memperhatikan perdebatan pembahasannya, nampak terang benderang, bahwa UU a quo, telah melenceng jauh dari jaminan konstitusional hak atas kebebasan berserikat. Bahkan dari perdebatan yang mengemuka, terlihat betul adanya kecenderungan untuk mengembalikan kontrol negara terhadap masyarakat, yang diidentifikasi sebagai ancaman. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya sebuah paradoks dari UU a quo, dalam periode demokrasi konstitusional dewasa ini, karena UU a quo justru memberikan gambaran tentang bekerjanya sistem otoriter. E. UU a quo menciptakan kekacauan hukum, yang menimbulkan situasi ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak atas kebebasan berserikat Salah satu permasalahan krusial dalam UU Ormas (UU No. 8 Tahun 1985), seperti juga diakui di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ormas (NA RUU Ormas), yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR, tahun 2011, adalah terkait dengan konsepsi Organisasi Masyarakat. Dalam NA RUU Ormas disebutkan, persoalan mendasar dari UU No. 8 Tahun 1985 adalah kerancuan pengertian ormas. Definisi ormas dalam UU tersebut mencakup semua organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, baik berdasarkan keanggotaan atau pun tanpa anggota. Akan tetapi karena tidak diikuti kejelasan norma, maka seringkali ditafsirkan hanya mengatur organisasi berdasarkan keanggotaan. 17 Kejanggalan muncul, ketika kerancuan konstruksi ormas dalam UU No. 8 Tahun 1985, justru kembali digunakan dalam rumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU a quo, padahal sebelumnya dikatakan, kerancuan tersebut ialah problem utama UU Ormas. Kekacauan hukum yang ditimbulkan oleh UU a quo, disinggung oleh ahli Para Pemohon, Surya Tjandra, S.H., LL.M., yang mengatakan, pengertian Ormas dalam UU a quo sangat rancu dan politis. Hal itu terjadi karena semenjak awal kelahirannya, Ormas dipandang bukanlah Ibid. Ibid., hal. 7. 17 Lihat Naskah Akademik RUU Organisasi Kemasyarakatan (2011), hal. 16. 15 16 Page 11 of 19 melulu sebagai suatu badan hukum melainkan lebih bersifat politis. Parahnya, Ormas ditempatkan secara superior di dalam posisi di atas, yang meliputi organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU a quo. 18 Pandangan ahli Surya Tjandra ini diperkuat dengan pendapat ahli dari Para Pemohon yang lain, Dr. Zainal Arifin Mochtar, yang mengatakan bahwa UU a quo, telah mencampuradukkan pengaturan organisasi yang berbasis anggota (perkumpulan), dengan organisasi yang tidak berbasis anggota (yayasan). Menurutnya, percampuran pengaturan ini sangatlah tidak tepat, karena keduanya memiliki tipe yang sangat berbeda, sehingga tidak dapat dipaksakan dalam satu undang-undang yang sama, yakni UU a quo. Pengaturan UU a quo jutru tidak memberi jaminan atas pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat berkumpul, karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang UUD 1945. 19 Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat penormaan dalam UU a quo, juga diperlihatkan oleh ahli Para Pemohon, Prof. Dr. Saldi Isra. Dalam keterangan tertulisnya, ahli Saldi Isra menyebutkan, pada satu sisi UU a quo membuat pemisahan/melakukan pembedaan antara Ormas berbadan hukum dengan Ormas tidak berbadan hukum, namun pada sisi yang lain juga mencampur keduanya, seperti yang termaktub dalam Bab VII UU a quo, yang mengatur tentang struktur dan kepengurusan ormas. Dengan demikian, seluruh ketentuan Bab VII UU a quo, berlaku untuk semua Ormas tanpa membeda-bedakan bentuknya. Persoalannya kemudian, apabila ormas berbadan hukum yayasan, bagaimana mungkin ormas tersebut diharuskan pula memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah propinsi di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Ormas? Dijelaskan Saldi Isra, bukankah yayasan tunduk pada ketentuan UU Yayasan? Di mana, dalam UU Yayasan tegas didefinisikan, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2004). Pertanyaan lanjutan dikemukakan oleh ahli Saldi Isra, apabila norma-norma yang terdapat dalam Bab VII UU a quo dikatakan tidak berlaku untuk Ormas yang berbadan hukum yayasan, pada ketentuan mana pengecualian tersebut diatur? Sebab, pengecualian terhadap yayasan hanya ditemukan dalam ketentuan Pasal 9 UU a quo, yang mengatur persyaratan pendirian ormas. Oleh karena itu, dapat dipastikan ketentuan terkait organisasi dan kepengurusan ormas yang diatur dalam Bab VII juga berlaku untuk Ormas berbadan hukum yayasan. Dalam konteks inilah akan muncul ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dan mengancam jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat. Persoalan lain yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan UU a quo, adalah terkait dengan pengaturan mengenai pendaftaran. Melihat logika struktur yang dibangun dalam UU a quo, pembentuk undang-undang menggunakan logika pendaftaran partai politik. Akan tetapi, ketika mengatur tentang lingkup organisasi dan wilayah kerja, justru pembentuk undang-undang menggunakan logika pendaftaran yayasan, perkumpulan dan lingkup kerja profesi (seperti advokat). Hal ini menunjukkan UU a quo dibuat dengan logika tambal-sulam, sehingga menyebabkan norma yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Termasuk hal yang menyangkut teknis pendaftaran pun nampak adanya ketidakpastian hukum, ketika dua kementerian sekaligus memiliki wewenang melakukan pendaftaran. Kementerian 18 19 Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 11 Februari 2014, hal. 16. Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 17 Maret 2014, hal. 11. Page 12 of 19 Hukum dan HAM untuk Ormas yang berbadan hukum, Kementerian Dalam Negeri untuk yang tidak berbadan hukum. Sementara itu, pada saat yang bersamaan sistem informasi Ormas dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski UU a quo mengatakan Ormas yang sudah berbadan hukum otomatis terdaftar, tapi dalam praktiknya untuk membangun sistem informasi tersebut, mereka harus mendaftarkan diri kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Situasi demikian tentu dapat dimanfaatkan untuk menekan dan mengebiri hak-hak organisasi/serikat, tambah Saldi Isra. F. UU a quo tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia Para pemohon dalam argumentasi permohonannya telah membabarkan perihal ketidaksinkronan pembatasan hak atas kebebasan berserikat, yang dilakukan oleh UU a quo, baik merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, UU No. 39 tentang Hak Asas Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, maupun instrumen hukum internasional hak asasi manusia lainnya. Pendapat serupa juga ditegaskan oleh ahli dari Para Pemohon, Roichatul Aswidah, M.A., yang menyatakan bahwa UU a quo telah mengenyampingkan prinsip-prinsip tentang pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Prinsipprinsip Siracusa dan Prinsip-prinsip Johanesburg. Mengapa demikian? Sebab UU a quo bersifat ambigu serta dibuat tidak secara hati-hati dan teliti. Ahli Roichatul Aswidah bahkan menyebutkan, UU a quo telah menjadi batu sandungan bagi bekerjanya sistem demokrasi, karena pengaturannya yang sewenang-wenang, sehingga sebenarnya pengaturan tentang pembatasan tersebut tidak dibutuhkan. Merujuk pada sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia, Roichatul Aswidah menegaskan, bahwa pembatasan hak tidak boleh dilakukan dan diterapkan untuk melemahkan inti dari suatu hak yang diakui oleh Kovenan. Oleh karena itu pembatasan hak harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kovenan. Dijelaskannya, terkait dengan hak atas kebebasan berserikat, pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh negara harus tetap menjamin dan tidak membahayakan aspek-aspek penting dari kebebasan berserikat tersebut, yakni: (i) harus menjamin kebebasan tujuan organisasi; (ii) harus menjamin kebebasan bentuk organisasi; (iii) harus menjamin dari tiadanya kontrol terhadap kegiatan; (iv) harus menjaminan bahwa proses pendaftaran tidak dilakukan secara sewenang-wenang; (v) harus menjamin tiadanya pembatasan dan pembubaran organisasi yang sewenang-wenang. Sedangkan UU a quo, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, telah mengatur rincian tujuan sebuah organisasi, sehingga pada hakikatnya telah membuat tujuan sebuah organisasi menjadi terbatas dan justru membahayakan aspek penting dari kebebasan berserikat. Begitu pula mengenai bentuk, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU a quo, yang menggabungkan organisasi berbasis anggota dengan yang tidak berbasis anggota. Ketentuan ini telah menafikan pengaturan yang lebih khusus yang secara spesifik mengatur tentang perkumpulan atau perserikatan tersebut. Kontrol terhadap kegiatan organisasi juga sangat potensial terjadi, berdasarkan pada UU a quo. Potensi ini mengemuka antara lain dengan adanya rumusan Pasal 16 UU a quo, yang mensyaratkan adanya surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan. Selain itu, rumusan Pasal 59 ayat (2) tentang larangan-larangan, dapat pula menjadi instrumen negara untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan organisasi, karena rumusannya yang luas dan Page 13 of 19 kabur. Ketidaksesuaian pengaturan UU a quo dengan prinsip pembatasan hak atas kebebasan berserikat juga nampak dalam pengaturan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 UU a quo, yang mengatur tentang kewajiban Ormas untuk mendaftar secara aktif dan memenuhi seluruh persyaratan administratif. Menguatkan keterangan dari ahli Roichatul Aswidah, ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar dengan menggunaan penafsiran sistematis terhadap Pasal 28E UUD 1945 menyebutkan, bahwa hak berserikat dan berkumpul dalam Pasal 28E ayat (3) merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani yang dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani diekspresikan dalam bentuk, diantaranya berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Selain itu, jika merujuk pada jaminan Pasal 28E ayat (1) yang melindungi hak untuk memeluk agama, termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Oleh karena itu, hak berserikat dan berkumpul sebagai salah satu ekspresi dari hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani pengaturannya tidak boleh ditujukan untuk mengurangi, menghalangi, atau menghilangkan hak-hak tersebut. Pengaturan dalam bentuk pembatasan hanya bisa dilakukan semata-mata, sebagai jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, sebagaimana penegasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 20 G. UU a quo mencengkram semua bentuk organisasi, akibatnya kebebasan berserikat dikekang, dan menghambat pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Konstruksi Ormas yang dibangun oleh UU a quo telah menyentuh hampir semua bentuk dan aspek organisasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, UU a quo memiliki dampak ancaman yang luar biasa besar bagi hidupnya hak atas kebebasan berserikat. Ahli dari Para Pemohon, Surya Tjandra mengungkapkan, dengan memperhatikan bahasa dan susunannya, UU a quo dibuat amat detil—sampai pada hal-hal kecil dan preskriptif, dengan tujuan untuk sejauh mungkin memberikan definisi dan meliputi setiap unsur dari pembentukan dan berfungsinya organisasi. Akan tetapi, karena terlalu preskriptif, sebagaimana terumuskan dalam pengaturan tujuan, fungsi, dan cakupan Ormas, pada saat yang sama UU a quo menjadi tidak jelas dan melebar. Akibat pengaturan yang demikian, menurut Surya Tjandra, UU a quo akan memiliki implikasi yang membahayakan terhadap penjaminan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat di Indonesia. Sebuah organisasi masyarakat sipil dengan segala aktivitasnya akan dengan mudah dinyatakan ilegal karena dianggap keluar dari definisi-definisi yang tercantum secara eksplisit dalam UU a quo. Selain itu, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat pengaturan UU a quo, sehingga memungkinkan kelenturan dalam penafsiran mengenai cakupan definisi dan ruang lingkup, telah berdampak pada pemaknaan yang sewenang-wenang dari aparat pemerintahan. Hal ini seperti halnya yang Serikat Buruh di Kabupaten Singkil, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam cakupan UU a quo, untuk dikualifikasi sebagai Ormas, namun dalam praktiknya pemerintah daerah melalui Dinas Kesbangpol, tetap memaksakan serikat-serikat buruh setempat, untuk mendaftarkan diri, dengan persyaratan sebagaimana layaknya pengaturan dalam UU a quo. 20 Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 17 Maret 2014, hal. 8. Page 14 of 19 Padahal, merujuk keterangan ahli Dr. Meuthia Ganie Rochman, pada faktanya di lapangan, sebagian besar Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), memiliki kapasitas pelayanan skala kecil dengan perubahan yang terbatas, karena memang pengetahuan inovatif dan sumberdayanya pun terbatas. Oleh karena itu, hadirnya UU a quo akan sangat membebani secara psikologis maupun sumberdaya atas keharusan administratif misalnya ADRT, rencana kerja, bagi organisasi skala kecil tersebut. Situasi demikian tentu akan berimplikasi sangat serius bagi pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya yang dilakukan secara kolektif, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dr. Meuthia Ganie Rochman dalam keterangan ahlinya kemudian menekankan bahwa “Organisasi Masyarakat Sipil tidaklah sama dengan Ormas”. Organisasi Masyarakat Sipil mencakup pengertian organisasi yang sangat luas dan memiliki peran yang sangat penting bagi demokrasi. Sementara, Ormas memiliki pengertian sempit secara sejarah dan politis dengan supervisi dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri. Dengan berlakunya UU a quo, ada potensi disempitkannya pengertian Organisasi Masyarakat Sipil ke dalam Ormas. Hal ini tercermin dalam definisi luas yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) UU a quo dan dalam praktik yang dijalankan Dirjen Kesbangpol, yang kerap mencampuradukkan antara Ormas, Organisasi Nirlaba, dan LSM. Cengkraman terhadap organisasi masyarakat sipil, yang merupakan pengejawantahan dari kebebasan berserikat, menjadi kian nyata, dengan diberikannya ruang bagi pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, meski dengan dalih pemberdayaan. Hal itu seperti ditegaskan ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar. Lebih jauh dikemukakannya, paradigma kontrol terhadap aktifitas berserikat dan berkumpul tersebut, akan lebih rentan lagi jika dilakukan oleh dinas-dinas Kesbangpol di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan memiliki kuasa sangat besar terhadap masyarakat dengan mengatasnamakan pemberdayaan Ormas. Bukan tidak mungkin demokrasi di tingkat lokal terancam jika kepala daerah, melalui dinas Kesbangpol, memiliki kewenangan pengendalian terhadap ormas di daerah. Potensi lain yang bakal terjadi, ialah perilaku kepala daerah, yang bertindak demi kepentingan politiknya, dengan mematikan Ormas tertentu yang berseberangan dengannya, dan memberikan fasilitas kepada ormas tertentu lainnya yang sejalan. Hak atas kebebasan berserikat nyata-nyata berada dalam ancaman, karena kemudian akan ada ormas plat merah dan ormas yang bukan plat merah, tegas Zainal Arifin Mochtar. 21 H. Kerugian konstitusional yang sifatnya faktual, telah banyak terjadi akibat berlakunya UU a quo Salah satu kerugian konstitusional yang nyata, akibat berlakunya UU a quo, adalah yang dialami oleh Pemohon I, Yayasan FITRA Sumatera Utara. Hanya 1,5 bulan setelah pengesahan UU a quo, tepatnya pada 19 Agustus 2013, Yayasan FITRA Sumut telah merasakan dampak nyata dari ketidakpastian hukum dari rumusan UU a quo. Organisasi yang berbadan hukum yayasan ini mengalami penolakan permohonan informasi publik dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Pusat Data Elektronik, Kabupaten Karo, dengan alasan tidak terdaftar di Kesbangpolinmas setempat. Dengan alasan merujuk pada berlakunya UU a quo. Padahal, berdasarkan pada ketentuan UU a quo, ditegaskan pula Ormas berbadan hukum yang telah mendapatkan status badan hukum, secara otomatis dinyatakan terdaftar, dan tidak perlu melakukan pendaftaran diri kembali. 21 Risalah sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 17 Maret 2014, hal. 9-10. Page 15 of 19 Tidak lama berselang, pada 23 Agustus 2013, KONSORSIUM Lombok Tengah menjadi salah satu organisasi yang dikelompokkan ke dalam kategori ilegal oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah. KONSORSIUM Lombok Tengah adalah koalisi yang beranggotakan sekitar 20 organisasi masyarakat sipil Lombok Tengah. 22 Dibentuk pada 2006, KONSORSIUM Lombok Tengah merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pembangunan dan penyusunan peraturan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin. Pemkab Lombok Tengah menempatkan KONSORSIUM Lombok Tengah sebagai anggota TKPKD (Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah), yang dikuatkan melalui SK Bupati Lombok Tengah. Sebagai pengaturan internal, KONSORSIUM Lombok Tengah memiliki statuta yang mengikat seluruh anggotanya. Berlakunya UU a quo, telah mengakibatkan legalitas KONSORSIUM Lombok Tengah terganggu, termasuk partisipasinya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dijamin UUD 1945. Dalam pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Kesbangpol Lombok Tengah, menyatakan mayoritas LSM di Lombok Tengah tidak memiliki kantor resmi dan tidak memiliki izin. Temuan lain mendapatkan rata-rata LSM memanfaatkan kediaman koordinatornya sebagai kantor dan tidak memasang plang lembaga. Walaupun LSM tersebut memiliki akte pendirian, AD/ART, dan struktur kepengurusan, keberadaan kantor dianggap menjadi salah satu pengakuan secara hukum di mata Kesbangpolinmas, sehingga LSM yang tidak memiliki kantor dan izin dianggap ilegal. Dinas Kesbangpolinmas Lombok Tengah bahkan telah bertindak lebih jauh daripada Kementerian Dalam Negeri. Meski Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pendaftaran Ormas berdasar pada ketentuan UU a quo belum diundangkan, Kesbangpolinmas setempat telah mengeluarkan edaran mengenai syaratsyarat untuk melakukan pendaftaran Ormas. Kedua fakta di atas, sekali lagi menegaskan betapa masifnya kerancuan hukum yang ditimbulkan akibat berlakunya UU a quo. Selain itu, kelahiran UU a quo juga telah secara langsung dan faktual mengancam pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, termasuk juga menjadi penghalang dalam pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sebagaimana dijamin UUD 1945. Pemerintah juga ternyata gagal menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Februari 2014. Pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Pihak Pemerintah adalah, “apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah jika ada organisasi yang tidak mendaftar?”. Ternyata Pemerintah tidak mampu menjawab pada saat sidang tersebut dan berjanji akan menyerahkan jawaban tertulis. Sampai saat ini, Pemerintah tidak juga mampu menyediakan jawaban lisan maupun tertulis atas pertanyaan tersebut. I. Membatalkan UU a quo pilihan terbaik bagi tegaknya hak atas kebebasan berserikat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Dalam keterangannya, ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar menyebutkan, bahwa UU a quo telah memberikan ruang besar kepada pemerintah atas nama negara memasuki wilayah negara, untuk mengontrol masyarakat sipil, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengancam inisiatif warga yang kritis. Misalnya, dalam bidang antikorupsi, pelanggaran HAM, dan perusakan lingkungan. Dengan situasi yang demikian, pengaturan UU a quo, meski disandarkan pada ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang dimaksudkan 22 Risalah Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XII/2014, 27 Februari 2014, hal. 4-8. Page 16 of 19 guna mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, akan tetapi justru mematikan inti dari hak atas kebebasan berserikat itu sendiri. Sebagaimana telah berulangkali disinggung dalam paparan di atas, model pengaturan yang dianut oleh UU a quo, jelas bertentangan dengan esensi hak atas kebebasan berserikat yang diatur dalam Pasal 28 dan secara tegas dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Bahkan jika merujuk pada perdebatan selama proses pembahasan amandemen UUD 1945, mencuplik pendapat Anggota PAH I BP MPR, Hamdan Zoelva, munculnya UU a quo adalah belenggu terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD 1945 sendiri. Apabila terus dibiarkan hidup, UU a quo juga akan kian mempersempit dan mempersulit ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang merupakan mandat dari Pasal 28C ayat (2). Dibatalkannya UU a quo tidak akan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum), karena peraturan perundang undangan terkait organisasi yang bergerak di bidang sosial telah ada. Ada UU Yayasan yang mengatur organisasi sosial yang berbentuk badan hukum yang tidak mempunyai anggota (non membership organization), dan ada Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen) yang mengatur bentuk Perkumpulan (membership based organization). Ormas bukanlah suatu badan hukum, melainkan hanya suatu status politik yang menyatakan bahwa suatu organisasi tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol). Jika UU Ormas dibatalkan maka rezim status politik tersebut akan hapus. Tidak akan terjadi kekosongan hukum, justru hal tersebut akan mengembalikan pendekatan hukum yang benar kepada organisasi masyarakat sipil dan pada akhirnya akan menjaga kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia. UU a quo seharusnya dicabut, bukan direvisi. Indonesia perlu mengembalikan pengaturan kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum Yayasan (untuk organisasi sosial tanpa anggota) dan badan hukum Perkumpulan (untuk organisasi sosial dengan anggota). RUU Perkumpulan telah masuk dalam Prolegnas 2010-2014, dan mendapatkan nomor 228, sebagai prioritas, namun sampai hari ini belum juga dibahas oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, sangat cukup alasan dan argumentasi bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk membatalkan UU a quo, sebagai jalan terbaik bagi tegaknya hak atas kebebasan berserikat dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembatalan terhadap UU a quo, juga merupakan langkah besar dalam penyelamatan agenda demokratisasi di Indonesia, yang sistemnya sudah kita bangun sedikitnya dalam 15 tahun terakhir. Pembaruan UU Yayasan dan pembahasan RUU Perkumpulan sebagai pengganti dari Staatsblad Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, menjadi pilihan paling tepat dalam pengaturan mengenai jaminan hak atas kebebasan berserikat di Indonesia, tanpa harus khawatir dengan terjadinya kekosongan hukum akibat dibatalkannya UU a quo. Proses ini, akan menjadi ikhtiar bagi kita semua untuk terus merawat supremasi konstitusi. J. Penutup Dari seluruh paparan argumentasi yang kami susun dalam permohonan, serta dikuatkan oleh para ahli yang kami hadirkan selama proses persidangan, dan ditutup dengan uraian kesimpulan di atas, pada akhirnya, dengan kerendahan hati, kami Para Pemohon, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon untuk: Page 17 of 19 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 57 ayat (2) dan (3); Pasal 59 ayat (2) huruf b, c dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 1 angka 1; Pasal 8; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 23; Pasal 29 ayat (1); Pasal 57 ayat (2) dan (3); Pasal 59 ayat (2) huruf b, c dan e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dibaca “Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia”; 7. Menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia”; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aeque et bono). Page 18 of 19