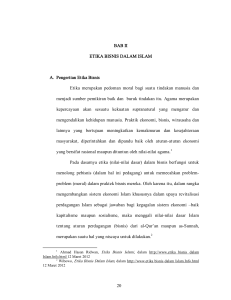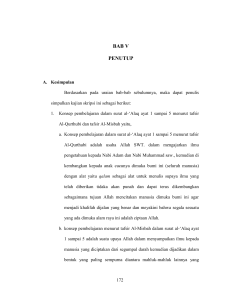METODOLOGI DAN IDEOLOGI AL-MÂWARDIY DALAM AL
advertisement

METODOLOGI DAN IDEOLOGI AL-MÂWARDIY
DALAM AL-’AHKÂM AL-SHULTHÂNIYYAH
Tesis
Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora
(M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
NIM : 036322013
Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008
ii
iii
iv
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul “Metodologi dan Ideologi AlMâwardiy dalam Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah” merupakan hasil karya dan
penelitian saya sendiri. Di dalam bagian tesis ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
Peminjaman karya-karya sarjana lain di dalam tesis ini adalah semata-mata untuk
keperluan ilmiah sebagaimana diacu secara tertulis dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, 03 November 2008
Abdurrosyid
v
MOTTO
4 +, +
- . (*
!"# $
%&' ("#
)*
* /-) -!*
01- 2 3'
786 5
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui." Q.S. al-Nisâ’ (4): 58.
9/:9
; < - =!
"Dan sesungguhnya kamu [Muhammad] benar-benar berbudi pekerti yang
agung." Q.S. Nun/al-Qalam (68): 4
vi
PERSEMBAHAN
!
"
#
$
!
#
%
$
!
!
&
'(()
%
*
%
'((+
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setiap manusia hidup dengan pemahaman terhadap masa lalu yang
diceritakan, yang memungkinkannya mengkondisikan diri dalam kekinian, bahkan
menyusun angan-angan masa depan. Dengan demikian, masa lalu adalah lokus
pencarian makna "jatidiri" setiap orang. Imajinasi, impian, tak lain kecuali
serangkaian preskripsi tentang bagaimana menempatkan hasil pemahaman: – iman
/ideologi – dalam orbit kehidupan, dan menghadapi kekuatan-kekuatan yang
meremehkan '
jatidiri'
.
Penulis terlahir di lingkungan budaya yang sangat menghargai masa lalu
Islam: pesantren salafiy,1 di sebuah desa pinggiran sebelah timur kota besar,
Semarang. Namun, seperti ciri pesantren salafiy pada umumnya, Pondok Pesantren
Tafsir dan Sunnah: Al-Itqon, tempat kelahiran penulis, merupakan wahana bagi
warga pesantren untuk menemukan jalinan intensif masa lalu-masa kini-masa depan,
melalui prinsip fikih: Al-muhâfazhatu ‘ala al-qadîmi al-shâlihi wa al-akhdzu bi aljadîdi al-’ashlahi ("menjaga nilai-nilai masa lalu yang baik dan mengambil nilai-nilai
baru – kekinian – yang lebih baik"), sebuah prinsip melihat sejarah secara dinamis.
Melalui prinsip hidup yang dijunjung tinggi di lingkungan pesantren semacam AlItqan ini, warga sangat menyadari dan menghargai arti "relatifitas nilai".
Suatu hari, ketika penulis masih duduk di bangku kelas enam Madrasah
Diniah Ibtidaiah, masuk seorang santri baru yang berasal dari desa tetangga. Ia
berusia kira-kira 5-7 tahun lebih tua dari usia rata-rata santri di kelas kami. Meski
teman santri baru ini berumur relatif lebih dewasa daripada santri-santri lain, ia
tampak mengalami kesulitan menangkap pemahaman dari pelajaran-pelajaran yang
ada, terutama pelajaran pokok ilmu "nahwu" dan "sharaf". Apalagi, ia tidak sebagai
1
Istilah "pesantren salafi" diartikan sebagai pesantren yang masih mengajarkan kitab-kitab
warisan intelektual Islam klasik (turâts) sebagai kurikulum utama, dan perbandingannya adalah
"pesantren hadîtsiy/khalafiy" seperti pesantren-pesantren yang menamakan diri "pesantren
modern". Pada pesantren jenis yang kedua tersebut, kitab-kitab turâts tidak dikaji sebagai
kurikulum utama.
viii
santri mukim melainkan sebagai santri kalong,2 sehingga tidak banyak kesempatan
baginya untuk mendiskusikan kesulitan-kesulitan pelajaran yang dihadapinya
bersama teman-teman santri maupun guru-guru pembimbing. Hal yang paling
menonjol darinya adalah keaktifannya dalam organisasi santri, baik di tingkat kelas
maupun di tingkat madrasah.
Kurang-lebih dua tahun berikutnya, Sang teman mulai jarang-jarang masuk
kelas, hingga akhirnya tidak masuk sama sekali. Belakangan penulis ketahui, ia aktif
mengadakan dan mengikuti kajian agama di mana-mana, yang jelas di luar pesantren.
Suatu hari ia datang ke pesantren/madrasah dengan penampilan fisik dan sikap yang
di luar kebiasaan. Ia tidak lagi memakai sarung dan pecis, ciri khas pakaian santri
laki-laki, tetapi baju koko dan celana '
congklang'
, dan berkopiah. Ia menampakkan
semangat yang gigih dan besar sebagai pemuda gerakan yang menginginkan
"kehormatan Islam" dengan mendirikan "Negara Islam" (khilâfah/’imâmah). Bahkan,
ia menilai bahwa kajian agama model pesantren/madrasah seperti yang pernah ia ikuti
tidak efektif dalam menjawab tuntutan '
kehormatan Islam'yang ia cita-citakan itu. Ia
pun memperkenalkan kepada teman-teman santri buku-buku (terjemahan) dan
majalah-majalah, sebagai bahan bacaan barunya. Penulis dan teman-teman santri lain,
kami warga pesantren umumnya, sebenarnya telah memiliki "standar" penilaian
tersendiri terhadap buku-buku dan majalah-majalah seperti yang diperkenalkannya
itu.
Setelah itu, ia tak pernah lagi berkunjung ke pesantren dan kami tak tahu
bagaimana kabarnya. Sampai akhirnya, setelah kurang-lebih 20-an tahun penulis
tidak pernah berjumpa dengannya, ketika penulis menyimak siaran '
Kabar Petang'
dari sebuah stasiun televisi swasta, diberitakan bahwa seorang laki-laki yang diduga
sebagai anggota teroris tewas ditembak petugas "Polisi Detasemen Lapan-Lapan", di
Sleman Yogyakarta. Menurut berita itu, laki-laki itu memiliki banyak nama dan salah
satunya berinisial "Em-En" yang berasal dari salah satu desa tetanggaku. Penulis
penasaran, jangan-jangan laki-laki yang diberitakan itu adalah Sang teman yang
2
Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, santri mukim adalah
murid-murid yang tinggal di pesantren, sebaliknya santri kalong adalah murid-murid yang tidak
menetap di dalamnya dan disebut juga santri lajon, yaitu mereka yang biasanya berasal dari desadesa di sekeliling pesantren yang bolak-balik dari rumahnya sendiri untuk mengikuti pelajaran di
pesantren. Bandingkan Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup
Kyai, LP3ES, Jakarta, 1982, h. 51-52.
ix
penulis ceritakan. Seminggu kemudian ketika penulis pulang ke Semarang, ternyata
dugaan itu benar.
Tentu,
ini
hanyalah
salah
satu
kisah
yang
terkait
dengan
isu
khilâfah/’imâmah. Sebuah isu tentang problem "Islam" yang sampai hari ini masih
sangat nyaring terdengar. Isu yang telah meminta banyak keringat, air mata, dan
darah "syuhada". Menurut penulis, jarang sekali isu khilâfah/’imâmah itu didekati
secara ilmiah melalui kajian sejarah. Bahkan, isu itu telah menjelma sebagai gelora
ideologi gerakan yang mendakwahkan diri sebagai kelompok "Islam militan".
Bagaimanakah asal-usul dan mekanisme ide khilâfah/’imâmah itu terbangun, dan
bagaimana
pula
ideologi
melingkupinya?
Kajian
terhadap
Al-’Ahkâm
al-
Shulthâniyyah karya al-Mâwardiy adalah sebuah cara untuk memahami salah satu
fenomena sejarah Islam itu yang masih sangat aktual hingga kini.
Pertama-tama, Penulis harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada para petugas di Perpustakaan Kolsani dan Perpustakaan Pusat Universitas
Sanata Dharma atas pelayanan dan dedikasi mereka, terutama mas Slamet (Kolsani)
yang tak pernah jera melayani peminjaman buku oleh penulis dan yang sangat santun
dalam memberi teguran kepada penulis karena selalu terlambat dalam pengembalian,
bahkan selalu me-ngendon buku-buku dalam waktu yang lama. Yang kedua, terima
kasih penulis ucapkan kepada Pak Nardi (Dr. S(i)t(i). Sunardi) atas segala
bimbingannya; Romo Baskara, Romo Banar, Pak Budiawan, dan Mbak Devi; mereka
yang selalu berempati tehadap penulis, bahkan penulis merasa telah diperlakukan
lebih dari sekedar sebagai mahasiswa. Ketiga, terima kasih pula kepada Mas Tri
bersama istri yang banyak membantu dan memberi motivasi, tak lupa kepada Entis,
I'
im dan suami yang memberi banyak waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian untuk
selesainya tesis ini, serta Izzah, Mas Totok (juragané "Joglo Semar"), Icul, Pak Teo,
Yus, dan semua "adik-adik" di IRB: Hasan, Anziem, Dona, Olvi, dan terutama Kang
Wahyudin yang sempat menjadi "dosen penguji" dalam simulasi ujian. Spesial,
terima kasih buat Mbak Hengky dan Mbak Yayas, serta Mas Mulyadi yang rajin
x
selalu, dan terakhir terima kasih kepada Prof. Dr. Mujahirin Tohir (Guru Besar
Antropologi di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang) atas keramahan,
keakraban, dan terutama keutuhan dedikasinya dalam membaca laporan penelitian ini
secara teliti dan kritis.
Akhirnya, penulis berharap dan berdoa, semoga kajian ini bermanfaat dan
semua orang yang berjasa pada hidup penulis dan dalam kajian ini mendapatkan ganti
kebaikan dari Allah Subhânahû wa Ta‘âlâ, amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Abdurrosyid
Yogyakarta, Desember 2008
xi
DAFTAR ISI
...............................................................................................
HALAMAN JUDUL ...................................................................................
HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................
HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................
MOTTO .......................................................................................................
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................
KATA PENGANTAR ................................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................................
PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................
ABSTRAK ...................................................................................................
Hal
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
xi
xiv
xvii
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................
A. Latar Belakang ...................................................................
B. Rumusan Masalah..............................................................
C. Tujuan Penelitian ..............................................................
D. Relevansi Penelitian...........................................................
E. Survei Hasil-hasil Penelitian..............................................
F. Orientasi dan sistematika Penulisan...................................
1
1
11
11
13
21
33
BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN METODE PENELITIAN
A. Kerangka Teoretis dan Pengertian Konsep-Konsep ....
1. Situasi Sosial Historis dan Peranannya dalam
Pembentukan Pengetahuan ..........................................
2. Mekanisme Pembentukan Pengetahuan.......................
3. Fungsi Pengetahuan .....................................................
4. Kritik Pengetahuan......................................................
5. Ideologi ........................................................................
6. Kritik Ideologi..............................................................
B. Metode Penelitian ............................................................
1. Sumber data .................................................................
2. Teknik Pengumpulan data...........................................
3. Teknik analisa Data......................................................
37
37
BAB III
EKSPLORASI TERHADAP AL-MÂWARDIY
DAN AL-’AHKÂM AL-SHULTHÂNIYYAH
A. Substansi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah...........................
1. Asal-usul Imamah dan Fungsinya................................
2. Landasan Normatif Legalitas Imamah.........................
3. Ketentuan Yuridis Pengangkatan Imam/Khalifah.........
38
41
45
51
53
56
60
60
60
61
63
64
64
68
70
xii
4. Kualifikasi "Dewan Pemilih" dan Calon Imam ..........
a. Kualifikasi "Dewan Pemilih".................................
b. Kualifikasi Calon Imam.........................................
5. Mekanisme Pengangkatan Imam .................................
a. Sistem Pemilihan ...................................................
b. Sistem Permandatan...............................................
6. Tugas-tugas Pokok Imam ............................................
7. Pemakzulan Imam, Kudeta, dan Pemberontakan .. .....
8. Sistem Birokrasi Negara ..............................................
B. Konteks Historis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah .............
1. Riwayat Hidup Al-Mâwardiy ......................................
2. Kondisi Sosial dan Politik di Bagdad abad IV H/10 M
3. Sejarah Wacana Politik Islam .....................................
C. Metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah........................
1. Asal-usul Pembentukan Fikih (Hukum Islam) ...........
2. Metodologi Pembentukan Fikih .................................
3. Metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.....................
D. Wacana-wacana Ideologis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
BAB IV
71
71
72
73
74
75
77
80
82
84
85
89
99
115
116
120
124
124
ANALISA HISTORIS, METODOLOGIS, DAN MITOS AL131
’AHKÂM AL-SHULTHÂNIYYAH ........................................
A. Analisa Historis:
Sosiologi-Genealogi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah..........
134
1. Konteks Sosial-Budaya yang Melahirkan
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah ........................................
135
2. Konteks Politik yang Melahirkan
137
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah ........................................
3. Konteks Budaya Intelektual [Wacana Politik] yang
Melahirkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah .....................
140
4. Posisi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dalam Konteks
Sosial, Politik, dan Budaya Islam Abad IV H/X M .....
141
5. Efek Konteks Historis terhadap al-’Ahkâm al-ShulthâNiyyah .........................................................................
143
a. Historisitas Konsep Imamah ....................................
144
b. Implikasi Ideologis Konsep Imamah .......................
155
1. Nuansa Ideologis Kewajiban Pengangkatan Imam 167
2. Nuansa Ideologis Mekanisme Pengangkatan Imam 169
3. Nuansa Ideologis Tugas-tugas Imam...................
186
4. Nuansa Ideologis Mekanisme Pemakzulan Imam
188
5. Nuansa Ideologis Pengabsahan Kudeta
dan Pemberontakan..............................................
190
6. Nuansa Ideologis Pembatasan Hak Wanita
dalam Kepemimpinan ..........................................
192
Catatan Penutup Analisa Historis ..................................
196
xiii
BAB V
B. Analisa Metodologis.........................................................
1. Sistem Metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.........
2. Batas-batas Metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
dan Implikasinya ..........................................................
a. Batas-batas secara Metodis-Epitemis dan
Implikasinya.............................................................
b. Batas-batas secara Ideologis dan Implikasinya........
Catatan Penutup Analisa Metodologis...........................
197
199
C. Analisa Mitis ....................................................................
1. Konsep Inti al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan
Sistem Mitisnya ...........................................................
2. Sistem Pemikiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan
Sistem Mitisnya ...........................................................
3. Fungsi Mitis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah ...................
212
202
202
209
212
216
231
234
KESIMPULAN .......................................................................
A. Konteks Historis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan
Implikasinya.......................................................................
B. Syarat-syarat Ilmiah (Metodologi) al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan Implikasinya ...................................................
238
BAB VI
PENUTUP ...............................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN : 1. Tabel Operasionalisasi Metodologi al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah
2. Daftar Isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
248
255
242
245
261
275
xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi dimaksudkan untuk menuliskan kata-kata atau istilah-istilah Arab ke
dalam tulisan bahasa Indonesia (Latin). Semua kata atau istilah Arab, kecuali
nama, yang belum menjadi bahasa baku bahasa Indonesia, ketika ditulis dengan
bahasa Indonesia, ditransliterasi dan dicetak miring (italik), seperti
ditransliterasi dengan khilâfah. Kata-kata atau istilah yang sudah baku tidak perlu
ditransliterasi, seperti salat, Zakat, dan Ramadan. Pedoman transliterasi itu
sebagai berikut:
A. Konsonan
Arab Latin
’ (apostrof)
b
t
ts (t dan s)
j
h (h garis bawah)
kh (k dan h)
d
dz (d dan z)
r
z
s
sy (s dan y)
sh (s dan h)
dh (d dan h)
th (t dan h)
zh (z dan h)
xv
‘
!
gh (g dan h)
"
f
#
q
$
k
%
l
&
m
'
n
(
w
)
h
*
y
B. Vokal
1. Vokal tunggal:
a
i
u
2. Vokal rangkap
*
: ai (tanda baca "a" yang bersambungan dengan yâ’ sukûn)
(
: au (tanda baca "a" yang bersambungan dengan waw sukûn)
3. Vokal panjang (madd)
: â (tanda baca "a" yang bersambungan dengan alif)
*
+
: î (tanda baca "i" yang bersambungan dengan yâ’ sukûn)
(
+
: û (tanda baca "u" yang bersambungan dengan waw sukûn)
xvi
C. Tâ’ Marbûthah ( ):
1. Ditulis dengan "h", apabila tidak berhubungan atau tidak dibaca sambung
dengan kata lain, seperti ,
./ ditransliterasi dengan al-madînah
2. Ditulis dengan "t" dan disesuaikan dengan tanda baca "a", "u", atau "i",
apabila dibaca sambung dengan kata lain sesudahnya, seperti 01,
/ ,
./
ditransliterasi dengan Al-Madînatu al-Munawwarah, Al-Madînata alMunawwarah, atau Al-Madînati al-Munawwarah, sesuai dengan kaidah
’i‘rab-nya.
D. Penulisan kata yang menggunakan "al-" (% )
1. "Al-" yang terletak di awal kalimat, "a"-nya ditulis dengan huruf kapital
dan sesudah "l" diberi garis datar "-", seperti 01,
/ ,
./ ditransliterasi
dengan Al-Madînatu al-Munawwarah. Khusus kata 2 "a"-nya ditulis
dengan huruf kapital: "Allah", dan tidak dicetak miring jika tidak dalam
satu rangkaian dengan kata yang lain. Jika terangkai dengan kata lain
menjadi satu kata seperti 2 .
3
4, ditulis menjadi: ‘abdullâh, atau ‘abdillâh,
‘abdallâh.
2. "Al-" yang terletak di tengah kalimat, "a"-nya ditulis dengan huruf kecil.
3. "Al" yang dimiliki suatu kata yang terletak di tengah kalimat tetap ditulis
"al-", seperti 01,
/
,
./ ditransliterasi dengan Al-Madînatu al-
Munawwarah
4. "Al-" yang berhubungan dengan huruf-huruf Syamsiyyah tetap ditulis
dengan "al-", seperti 5/6 ditransliterasi dengan al-syams.
5. Huruf konsonan setelah "al-" ditulis dengan huruf kapital jika merupakan
nama benda atau merupakan judul.
F. Semua nama surat al-Qur'
an ditransliterasi, tetapi tidak ditulis miring.
xvii
ABSTRAK
Penelitian ini membahas metodologi dan ideologi al-Mâwardiy dalam al’Ahkâm al-Shulthâniyyah, sebuah karya monumental dari seorang cendekiawan
Muslim klasik, dalam upaya mencari akar-akar sejarah pemikiran etika politik
Islam dan kaitannya dengan ideologi. Dalam konteks kajian pemikiran Islam yang
lebih luas, penelitian ini merupakan upaya kritik sejarah dan kritik ideolgi, suatu
upaya yang dihindari kebanyakan orang karena khawatir dapat merong-rong
kemapanan iman.
Walaupun al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah ditulis al-Mâwardiy pada abad IV
H/X M, kitab ini masih dijadikan rujukan utama dalam diskursus mengenai model
kekuasaan dan pemerintahan Islam hingga sekarang. Kajian kritis terhadap al’Ahkâm al-Shulthâniyyah mensyaratkan penelusuran sejarah kelahirannya, metode
pembentukannya, serta jangkauan-jangkauan ideologisnya.
Dalam konteks teoretis dan praktis politik Islam, kehadiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah menjadi wacana "penanda" yang penting bagi pembakuan model
"negara Islam": khilâfah, yang merujuk pada pengalaman "negara Madinah".
Namun sejarah menunjukkan, bahwa "negara Madinah" sebagai sumber imajinasi
politik Islam telah berkembang sedemikian rupa menjadi "negara ‘Umâwiyyah",
"negara ‘Abbâsiyyah", "negara Fâthimiyyah", dan "negara ‘Utsmâniyyah" yang
semuanya mengklaim sebagai pewaris sah tahta kekuasaan Islam. Al-‘Ahkâm alShulthâniyyah menampilkan dirinya sebagai pemikiran politik Islam yang ideal
dan mengatasi perbedaan-perbedaan sejarahnya yang nyata dan penuh konflik.
Penelitian ini menyimpulkan, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dilahirkan dan
dibentuk oleh sejarah yang melingkupinya, sistem berpikir yang mengarahkannya,
serta mengandung fungsi dan bias-bias yang bersifat ideologis.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bagi kehidupan setiap kelompok orang atau masyarakat, kekuasaan
memiliki arti penting karena mereka hidup dan bergerak dengan kekuasaan itu
sendiri.3 Dalam konteks Islam, kekuasaan juga selalu menjadi perhatian kaum
muslimin. Bahkan, masalah itu telah mengarahkan seluruh sejarah mereka sejak
masa pendirian Islam hingga sekarang. Sejak awal pertumbuhan di Arab,
fenomena keterkaitan Islam dengan kekuasaan dapat dibuktikan melalui
pengalaman Muhammad. Selain sebagai Nabi utusan Allah (Rasulullah), dia juga
memiliki “senjata” dengan mendirikan komunitas (’ummah) di bawah
kepemimpinannya. Justru karena dia muncul sebagai yang berwenang dalam
agama maka dia menjadi pemimpin Umatnya.4 Kenyataannya, Nabi Muhammad
memang tampil sebagai pendiri sebuah negara yang sepeninggalnya mampu
menguasai tata dunia global selama berabad-abad.
Maka wajar, ketika Nabi Muhammad wafat dan jasadnya pun belum
dimakamkan, di kalangan Sahabat5 muncul persoalan pertama yang berdimensi
3
Dalam ilmu sosial dan politik, kekuasaan adalah konsep yang penting meskipun hingga sekarang
hakikatnya masih sangat sulit untuk dipahami. Namun, menurut April Carter kekuasaan
mempunyai dua ciri: pertama kemampuannya untuk menghasilkan kesetiaan yang bersifat suka
rela, dan kedua kemampuannya untuk memerintah dan memaksakan kepatuhan. Lihat April
Carter, Otoritas dan Demokrasi, Jakarta: Rajawali, 1985, h. 25-28.
4
Lihat Mohammed Arkoun “Agama dan Kekuasaan”, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.),
Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Jakarta: INIS, 1994, h.
210.
5
Kata "Sahabat" dengan huruf kapital "S" berarti orang yang hidup semasa dengan Nabi
Muhammad atau orang yang terlahir ketika Nabi masih hidup, dan ia beriman kepadanya.
2
politik: siapa yang akan menjadi pengganti (khalîfah)6 tugas-tugasnya. Persoalan
pertama ini segera menjadi polemik, pertentangan dan bahkan di kemudian hari
berkembang menjadi krisis politik yang menentukan sejarah Islam ke masa depan.
Krisis politik yang terjadi di seputar masalah suksesi kepemimpinan
setelah Nabi wafat dan munculnya berbagai peristiwa tragis yang berlipat ganda,
adalah bukti lain yang menunjukkan bahwa Islam sebagaimana teraktualisasikan
dalam proses sejarah tidak terlepas dari masalah kekuasaan.
Meskipun kekuasaan memiliki arti penting dalam artikulasi Islam dan
merupakan pengalaman sejarah umat Islam yang otentik, tetapi secara teoretis
ternyata Alquran maupun sunah (hadis) tidak memberikan panduan yang spesifik
bagaimana seharusnya sistem kekuasaan dapat ditegakkan dan diorganisasikan
dalam Islam. Tepatnya, di dalam dasar-dasar ajaran Islam tidak ada ketentuan
yang pasti mengenai bentuk kekuasaan tertentu dan sistem pemerintahannya.7
Oleh sebab itu, dapat dimaklumi adanya perbedaan pendapat di kalangan Sahabat
sepeninggal Nabi tentang siapa yang akan menjadi penggantinya. Demikian juga
6
Istilah khalîfah secara harfiah berarti "pengganti", dan dalam wacana politik Islam istilah tersebut
berarti "pemimpin pengganti Rasulullah", yaitu setiap orang yang memegang jabatan kekuasaan
Islam yang tertinggi setelah Rasulullah wafat (dalam urusan negara dan agama) yang
melaksanakan syariat (hukum) Islam di kehidupan negara. Selanjutnya, istilah tersebut ditulis
"Khalifah" dengan huruf kapital "K" jika berfungsi sebagai sebutan, dan ditulis "khalifah" jika
berarti sebagai jabatan. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 563.
Dalam konteks Suni (Ahlu Sunah[Waljamaah]), istilah "khalifah" sama artinya dengan "Imam"
(’imâm). Istilah "khalifah" dalam laporan peneletian ini juga diartikan sama dengan istilah
"Imam", yaitu "pemimpin/penguasa tertinggi Islam". Dalam arti itu, kata "Imam" ditulis dengan
huruf kapital "I" yang membedakannya dengan kata "imam" yang berarti "pemimpin" di luar
bidang negara atau politik, seperti imam salat, imam mazhab, dll.. "Khalifah/Imam" menunjuk
kepada "orang/pejabat" dan "kekuasaan-lembaga-negara" disebut "khilafah" (khilâfah) atau
"imamah" (’imâmah). Tetapi tidak demikian halnya dalam konteks Syî‘ah. Mazhab Islam yang
satu ini hanya memiliki konsep "Imam-imamah" dalam arti spesifik, yaitu pemimpin/penguasa
Islam yang kekuasaannya bersifat suci (ma‘shûm) dan merupakan hak mutlak Nabi Muhammad
dan keturunannya (’âlu baiti al-Naby). Syî‘ah tidak menerima konsep "khalifah-khilafah"
sebagaimana dipahami Suni.
7
Lihat Qamaruddin Khan, Al-Mawardi’s Theory of The State, Lahore: Islamic Book Foundation,
1983, h. 39.
3
polemik dan pertentangan politik di antara mereka menjadi tidak mudah
diselesaikan.
Ironisnya, siapapun yang bermaksud menjelaskan karakter tertentu
kekuasaan politik yang Islami, memastikan struktur dan mekanismenya, dan
menyusun sistemnya, justru tidak akan dapat terhindar dari perangkap-perangkap
kepentingan dan ideologi. Karena tidak dapat disangkal bahwa polemik berupa
klaim-klaim politik, pertentangan, dan pertumpahan darah yang terjadi adalah
bermotivasi kekuasaan dan perbedaan kepentingan antar pribadi atau antar
kelompok yang pada taraf tertentu diatasnamakan bermotivasi menegakkan
kebenaran agama. Klaim kalangan Quraisy atas hak kekuasaan terhadap selain
mereka, klaim elit Quraisy yang pro-’Abû Bakr terhadap kalangan yang pro-‘Aly
bin ’Abî Thâlib misalnya, atau sebaliknya, adalah contoh-contoh yang nyata
operasi kepentingan politik kekuasaan dan ideologinya.
Tidak dapat disangkal pula bahwa faksi-faksi politik yang saling bersaing
untuk meraih kekuasaan telah memanfaatkan berbagai sarana seperti kekuatan
sosial, kekuatan ekonomi, dan kekuatan ideologi. Khusus mengenai kekuatan
ideologi, strategi operasinya dapat dirunut dari munculnya klaim-klaim kelompok
sebagai yang paling berhak atas kekuasaan. Wacana yang berkembang adalah
bagaimana mekanisme suksesi kepemimpinan harus ditempuh serta siapa aktor
dan dari kelompok mana yang berhak dan pantas menduduki jabatan khalifah.
Pernyataan ’Abû Bakr misalnya, bahwa tidak ada landasan teoretis yang pasti
4
yang dapat dijadikan pedoman bagi mekanisme suksesi kepemimpinan,8 jelas
berhadapan dengan klaim kalangan pro-‘Aly yang memastikan kepemimpinan
sebagai hak istimewa keluarga keturunan Nabi (’âlu baiti al-Naby).9 Wacana
permulaan yang tidak dapat terlepas dari muatan “penumpang gelap” ideologi ini
terus berkembang seiring dengan perkembangan realitas politik di mana otoritas
kekhalifahan berhasil ditegakkan di atas segala macam bentuk dominasi sekaligus
tandingannya.10
Apalagi dalam prakteknya, masing-masing faksi selain menciptakan
komunitas-komunitas yang dibentuk atas dasar keterikatan area geografis, suku,
budaya, dan kepentingan tertentu, juga mengembangkan konsep dasar dan
karakteristik gerakannya. Konsekuensinya, pertentangan antar faksi untuk meraih
kekuasaan berkembang menjadi perbedaan paham (aliran) dalam sistem teologi
(dasar-dasar kepercayaan, hukum, dan struktur sosial yang lain). Kebutuhan yang
8
Dalam lingkaran para elit Sahabat di Saqîfah Banî Sâ‘idah, ’Abû Bakr menyatakan: “Seharusnya
saya menanyakan, siapa yang akan menggantikan dia (Nabi Muhammad) dalam kekuasaan politik.
Jika dia mengangkat seseorang, maka siapapun tidak bisa menolak calonnya dalam masalah ini.
Dan seharusnya saya menanyakan juga kepada Nabi, apakah kaum Ansar berhak dalam kekuasaan
politik.” Lihat ’Abû Muhammad ‘Abdullâh bin Muslim bin Qutaibah al-Dainuriy (’Ibn Qutaibah),
Al-’Imâmatu wa al-Siyâsah: Târîkhu al-Khulafâ’, Mesir: Muassasat al-Halabiy wa al-Syarîkah,
t.t., jilid I, h. 19. Namun, di tengah-tengah perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan
kelompok Ansar, ’Abû Bakr mengemukakan sebuah hadis Nabi bahwa: “Para Imam adalah tetap
dari Quraisy”. Lihat al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, Bairut: Dâru al-Fikr, 1416/1996, h.
6
9
Kelompok Sahabat yang pro-‘Aly berpendirian bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk dan
memproklamirkan ‘Aly, menantunya, sebagai penggantinya. Pendirian demikian utamanya
didasarkan pada peristiwa Ghâdir Khûm yang terjadi pada bulan Zulhijah tahun ke-10 hijriah
ketika Nabi menyampaikan pidato dalam haji wadak. Lihat Usman Abu Bakar dkk., “Negara dan
Pemerintah: Studi Komparatif Pemikiran Al-Mâwardiy dan ’Ibn al-Farrâ’”, Semarang: Balai
Penelitian IAIN Walisongo, 1994/5, h. 2, tidak diterbitkan.
10
Faksi politik mayoritas yang pada akhirnya menamakan diri golongan Ahlu Sunah Waljamaah
(Suni) mengembangkan wacana kekuasaan yang mengkristal pada konsep ‘Wewenang Dewan
Permusyawaratan’ (’ahlu al-syûra/’ahlu al-halli wa al-‘aqd). Sementara itu wacana kekuasaan
’âlu al-bait yang diusung oleh kelompok pro-‘Aly yang kemudian menamakan diri Syî‘ah terus
dimatangkan menjadi konsep ’imâmah dengan segala keistimewaannya. Demikian juga faksi
Khawârij, yang anti pada kedua faksi utama, mengusung wacana "kebebasan" yang berujung pada
ekstrimitas dan keabsahan memberontak terhadap penguasa.
5
riil untuk menyusun ajaran-ajaran Islam yang komprehensif dan sistematis oleh
masing-masing
komunitas
bertumpang-tindih
dengan
kepentingan-
kepentingannya sebagai faksi politik. Maka, perkembangan suatu paham atau
aliran di dalam Islam sangat terkait dengan kepentingannya sebagai faksi politik
dan sangat dipengaruhi oleh dominasi paham atau aliran yang dianut oleh rezim
yang berkuasa. Dengan demikian, wacana kekuasaan dengan ideologinya telah
menyebar ke segala arah sehingga mampu menembus batas-batas kesadaran
massa
karena
mengambil
bentuk-bentuk
wacana
baru
(dogma-dogma
keagamaan).
Karena latar belakang konflik politik yang berkepanjangan dan tidak
adanya pedoman teoretis yang dapat dijadikan pijakan untuk mengorganisasikan
sistem kekuasaan dalam Islam, kaum intelektual Muslim (ulama) merasa
terpanggil untuk menyusun teori hukum konstitusional Islam
seiring dengan
semangat untuk mensistematisasi seluruh ajaran Islam. Di dalam golongan Suni
misalnya, para imam mazhab fikih seperti: ’Abû Hanîfah [al-Nu‘mân] (80-150 H
/699-767 M), Mâlik bin ’Anas (93-179 H /w.795 M), Muhammad bin ’Idrîs alSyâfi‘iy (150-204 H/w. 819 M), Ahmad bin Hanbal (164-241 H), dan al-’Auza‘iy
(w. 773 M) telah merintis kajian politik (al-fiqh al-siyâsiy) dan memasukkannya
ke dalam kitab-kitab fikih (hukum Islam) karangan mereka, meskipun masih
bersifat terbatas dan parsial. Barulah di tangan para murid mereka yang terkemuka
kajian politik kenegaraan dibahas secara tersendiri (terpisah dari tema-tema kajian
fikih yang lain), mendalam, meluas, detail dan sistematis. Sederet nama besar di
antara mereka adalah ’Abû Yûsuf Ya‘qûb al-Kûfiy (w. 182 H, murid ’Abû
6
Hanîfah), ’Ibn Qutaibah (w. 300 H/913 M), al-Jâhizh (w. 305 H/917 M), alBâqillâniy (w. 403 H), ’Abû Hasan ‘Aly bin Muhammad bin Habîb [alMâwardiy] (364-450 H /974-1058 M), al- Baghdâdiy (w. 463 H), dan ’Abû Ya‘lâ
al-Farrâ’ (380-458 H /963-1011 M). 11
Secara umum dapat dikatakan bahwa sebaik apapun kualitas moral
individu para cendekiawan tersebut, sekuat apapun dedikasi mereka terhadap
tanggung jawab keilmuan, dan seteguh apapun upaya independensi mereka dari
pengaruh kekuasaan, di balik karya teoretis mereka terdapat endapan-endapan
kepentingan untuk memanfaatkan agama secara ideologis dalam konteks
persaingan bersama lawan-lawan mereka di dalam ruang politik yang ada.
Secara khusus dalam kasus ’Abû Hasan ‘Aly bin Muhammad bin Habîb
al-Mâwardiy (terkenal dengan sebutan al-Mâwardiy), ia telah menulis kitab al’Ahkâm al-Sulthâniyyah. Secara substansial, isi kitab ini telah memenuhi tuntutan
kebutuhan
teoretis
atas
landasan
hukum
konstitusional
bagi
praktek
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam kerangka etika politik Islam. Bukan
saja cakupan materi kitab tersebut yang komprehensif, tetapi juga disusun secara
sistematis, dan menggunakan metode ilmiah yang sulit diragukan.
Maka tidak mengherankan jika kitab tersebut dinilai sebagai karya
monumental, literatur penting tentang prinsip-prinsip kekuasaan dalam Islam, dan
memiliki pengaruh yang dominan terhadap pemikiran politik Islam.12 ’Al-Ahkâm
al-Sulthâniyyah merupakan masterpiece karya al-Mâwardiy yang menjadi rujukan
11
Catatan tahun wafat para cendekiawan Muslim tersebut mengacu kepada ‘Umar Ridhâ Kihâlah,
Mu‘jamu al-Mu’allifîn, Beirut, Dâru ’Ihyâ’i al-Turâtsi al-‘Arabiy, tt.
12
Lihat Ann K. S. Lambton, State and Government in Medieval Islam, Oxford: Oxford University
Press, 1981, h. 83.
7
terpenting pemikiran politik Suni pada abad-abad setelahnya hingga sekarang. Di
Indonesia, pengaruh al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah tampak seperti dalam tradisi
intelektual yang berlaku di dunia pesantren, di mana kitab ini dianggap sebagai
literatur yang paling muktabar mengenai pemikiran politik Islam. Selain itu,
pengaruh al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah juga tampak di dalam pemikiran
organisasi/gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), seperti tertuang di dalam edisiedisi buletinnya: "Al-Islam", yang fokus pada perjuangan menegakkan
"khilafah".13
Namun dari sudut pandang sejarah terlihat, bahwa al-’Ahkâm alSulthâniyyah ditulis oleh al-Mâwardiy dalam konteks ketegangan pertentangan
politik antar dinasti dan golongan yang terus bersaing untuk meraih kekuasaan
dan menanamkan pengaruhnya. Sejak pertengahan abad ke-9 M, kekuasaan
khalifah dari dinasti ‘Abbâsiyyah yang berkedudukan di Bagdad mulai melemah.
Khalifah dinasti ‘Abbâsiyyah tidak lagi memiliki kekuasaan yang eksklusif dan
penuh. Otoritas khalifah mulai terganggu dengan munculnya penguasa-penguasa
lokal yang tidak selalu menaruh respek terhadap eksistensi pemerintahan pusat.
Kekuasaan dinasti Thâhir di Persia, dinasti Thûlûn di Mesir, dan berbagai
pemberontakan telah ikut serta memperlemah posisi khalifah. Apa yang dapat
dipertahankan khalifah pada saat itu adalah sebatas otoritas simbolik sebagai
13
Hizbut Tahrir memang tidak pernah menyebutkan bahwa gagasan "khilafah"-nya merujuk
secara spesifik kepada al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah karya al-Mâwardiy. Tetapi bagi siapapun yang
mengusung gagasan itu dalam konteks politik sekarang, atau siapapun yang ingin mendalami teori
politik Islam, ia tidak dapat mengabaikan posisi al-Mâwardiy dengan teorinya di dalam al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah.
8
penguasa tunggal dunia Islam.14 Kemudian, pada tahun 944 M, dinasti Buwaihiy
yang merupakan para petinggi militer yang memiliki kecenderungan Syî’ah yang
kuat berhasil masuk dan menguasai pusat kekuasaan Khalifah ‘Abbâsiyyah di
Bagdad. Faksi Syî’ah yang semula lebih merupakan gerakan bawah tanah, dengan
kehadiran dinasti Buwaihiy di pusat kekuasaan, menjadi lebih leluasa berkembang
dan membangun jaringan komunitasnya. Sehingga, dalam waktu yang relatif
singkat Bagdad, Ray, Isfahan, Qazwin, Syiraz, dan Thabaristan telah berkembang
menjadi pusat-pusat dinamika Syî’ah. Di bawah pengaruh perlindungan para
’amîr dan sultan15 dari dinasti Buwaihiy berbagai perayaan keagamaan yang
bersandar pada doktrin Syî’ah berlangsung secara semarak. Gerakan intelektual
juga berkembang dengan pesat. Beberapa ilmuwan terkenal seperti ’Ibn
Bâbawaih, al-Mufîd, ‘Allâm al-Hudâ, dan al-Thûsiy hidup pada masa tersebut dan
berhasil mengembangkan doktrin-doktrin Syî’ah lebih jauh.16
Perkembangan situasi sosial dan politik tersebut jelas mengundang reaksi
dari kelompok lawan untuk mengadakan gerakan tandingan. Suni (Ahli Sunah)
sebagai faksi politik yang terbesar, terutama melalui sayap mazhab Hambali
merespon perkembangan situasi tersebut secara fundamental, yakni mengadakan
14
M. Nafis, dkk., “Konfigurasi Keagamaan dalam Islam: Studi tentang Sekte dan Mazhab Abad
XI di Daerah Bagdad dan Khurasan”, Semarang: Balai Penelitian IAIN Walisongo, 1996, h. 18,
tidak diterbitkan.
15
Pada masa kepemimpinan ’Abû Bakr hingga ’Aly, pemimpin Islam disebut ’amîru al-mu’minîn.
Perkembangan kemudian, umat Islam juga mengenal sebutan "khalifah", "Imam", "malik", "amir",
dan "sultan" bagi penguasa-penguasa mereka. Dalam tataran praktis maupun teoretis politik Islam
yang terus berkembang seiring dinamika politik dan perluasan wilayah kekuasaan Islam ,
penguasa tertinggi Islam (penguasa pusat) disebut "khalifah", atau "Imam", atau ’amîru almu’minîn yang menyimbolkan kesatuan kekuasaan Islam; sedangkan "malik", "amir", dan "sultan"
adalah penguasa-penguasa daerah otonom. Fenomena ini terus berlangsung hingga dihapuskannya
lembaga khilafah terakhir yang berpusat di Turki oleh Mustafa Kamal pada pertengahan abad ke19 M.
16
M. Nafis, Ibid., h. 20.
9
polemik serta perlawanan terhadap gerakan Syî’ah. Pertengkaran antara dua
kelompok inipun seringkali terjadi.
Pada sisi lain, semangat faksi Suni dalam melakukan gerakan tandingan
dimanfaatkan Khalifah al-Qâdir Billâh (berkuasa: 991-1031 M) untuk
memperkuat posisinya dan mengembalikan otoritas kekuasaan kekhalifahan yang
selama hampir dua abad dipegang oleh para "amir" dan sultan yang
membangkang. Untuk tujuan tersebut, Khalifah al-Qâdir Billâh menetapkan
kebijakan politik berupa “Dekrit Qadiriah”, yaitu pemberlakuan sistem teologi
Suni sebagai mazhab resmi negara sekaligus penguatan otoritas institusi khalifah
sebagai penguasa tunggal negara Islam (al-Dawlat al-Islâmiyyah). Koalisi antara
pihak khalifah dengan faksi Suni ini di kalangan sarjana Barat dikenal sebagai
“the Suni Revival and Restoration”.17 Khalifah yang menggantikan al-Qâdir
Billâh, yaitu al-Qâ’im Billâh (berkuasa: 1031-1075 M), melanjutkan kebijakan
tersebut dengan membentuk panitia khusus yang bertugas mempersiapkan segala
sesuatu yang berhubungan dengan pengembalian otoritas khalifah. Usaha restorasi
ini tidak hanya ditujukan kepada kekuasaan dinasti Buwaihiy, tetapi juga
ditujukan kepada seluruh dinasti yang berkuasa di beberapa daerah Islam, seperti
dinasti Hamdâniy, dinasti Saljûq, dan dinasti Fâthimiyyah.18
Koalisi antara pihak Khalifah ‘Abbâsiyyah dengan kekuatan faksi Suni
yang mayoritas memiliki makna yang strategis bagi kedua belah pihak, terbukti
dengan semakin menguatnya posisi dan otoritas khalifah atas dinasti-dinasti
pesaingnya dan diberlakukannya mazhab Suni sebagai mazhab resmi negara, serta
17
Lihat G. Makdisi, “The Suni Revival”, dalam D. S. Richard (ed.), Islamic Civilization 950-1150,
Oxford: Bruno Cassier, 1973, h. 68-155.
18
Usman Abu Bakar, Op. Cit., h. 20-21.
10
diangkatnya ulama Suni menjadi pejabat-pejabat penting negara, antara lain
sebagai penasehat khalifah atau hakim. Hal-hal inilah yang mempengaruhi kondisi
struktur politik dan formasi keagamaan.19
Gambaran umum situasi dan kondisi sosial dan politik seperti tersebut di
atas menjadi pengalaman hidup al-Mâwardiy, bahkan sebagai salah satu tokoh
terkemuka dari mazhab Suni dia terlibat langsung dalam struktur pemerintahan
dengan menjadi hakim agung (’aqdh al-qudhât).
Terkait dengan kehadiran al-Mâwardiy sebagai salah satu pemikir
terkemuka mazhab Suni, dan bahkan dia terlibat langsung dalam praktek politik
pemerintahan dengan menjadi hakim agung, patut diduga bahwa seluruh situasi
yang menjadi konteks dan melingkupi kehidupannya itu memiliki pengaruh yang
kuat terhadap karya pemikirannya, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Diasumsikan bahwa al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah bukanlah datang secara
sekonyong-konyong: hampa sejarah (a-historis), atau tidak terkait dengan
kerangka epistemik (metodologis dan ideologis) yang berkembang pada masa itu.
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai hasil pemikiran merupakan sebagian simbol
dari realitas: pergulatan antar-kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan budaya
pada zamannya. Atau dengan perkataan lain, tentu ada kekuatan-kekuatan sosial,
politik, dan budaya (khususnya ilmu pengetahuan dan ideologi) yang mendorong
dan atau melahirkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, mengoperasikannya pada
zamannya, bahkan mengkanonkannya pada zaman sesudahnya sehingga sekarang.
19
M. Nafis, Op. Cit., h. 4.
11
Dengan demikian ada gejala-gejala sejarah, epistemologi, dan ideologi
yang perlu diungkap terkait dengan kelahiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, dan
gejala-gejala itu sulit didekati dengan perspektif teologis-substansialis. Oleh
karena itu, gejala-gejala yang terkait dengan kelahiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah perlu dilihat dari sudut pandang teori kritis dan menempatkannya
dalam wilayah kajian budaya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil tema “fenomena
historis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah karya al-Mâwardiy”. Tema penelitian ini
dimaksudkan untuk menjawab masalah utama: kekuatan-kekuatan sejarah yang
melahirkan dan membentuk gagasan etika politik Islam al-Mâwardiy dalam al’Ahkâm al-Shulthâniyyah”. Garis besar masalah ini dapat diuraikan menjadi tiga
persoalan spesifik sebagai berikut:
1. Kondisi sosial, politik, dan budaya macam apa yang menentukan kelahiran
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah karya al-Mâwardiy?
2. Apa metodologi yang dipakai al-Mâwardiy untuk menyusun al-’Ahkâm alShulthâniyyah?
3. Bagaimana implikasi dari keduanya secara ideologis?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan persoalan tersebut di atas,
penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu:
12
1. Mengungkap dan menggambarkan kondisi-kondisi sosial-historis yang
menentukan kelahiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah karya al-Mâwardiy.
Pengungkapan kondisi sosial-historis ini penting untuk menunjukkan
bahwa al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai sebuah gagasan bukan
merupakan kreasi mental al-Mâwardiy yang transenden dan terlepas dari
aspek-aspek kesejarahan. Sebaliknya, pengungkapan kondisi sosialhistoris itu akan memperlihatkan kelahiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
sebagai fenomena yang bersifat budaya dan manusiawi, dan dengan
demikian ia sangat terikat dengan aspek-aspek kesejarahan.
2. Mengungkap dan menggambarkan metodologi atau sistem pemikiran yang
diapakai untuk merumuskan pandangan-pandangannya tentang etika
politik Islam dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Penjelasan mengenai
sistem
pemikiran
al-Mâwardiy
ini
penting,
karena
pandangan-
pandangannya tentang etika politik Islam pastilah berada di dalam sistem
budaya pemikiran tertentu dan dirumuskannya melalui teknik-teknik
pemikiran yang ada di dalam sistem itu. Pengungkapan aspek metodologi
ini merupakan salah satu konsekuensi teoretis dari perspektif penelitian
yang menempatkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai fenomena
budaya.
3. Menganalisis implikasi-implikasi ideologis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
baik yang terkait dengan aspek historis, metodologis, maupun substansi.
Karena penelitian ini menempatkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai
fenomena budaya, maka ideologi merupakan sebagian aspek lain yang
13
juga perlu diperhitungkan. Bahkan, jika aspek ini diabaikan dalam
mengkaji al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, selain akan berakibat mengurangi
arti bobot kajian dengan perspektif kritik sejarah, lebih-lebih hal itu juga
akan mengakibatkan perolehan pemahaman mengenai al-’Ahkâm alShulthâniyyah yang lebih kuat nuansa teologisnya. Padahal pemahaman
yang lebih berorientasi teologis sangat kecil kemungkinannya dapat
menghindar dari "perangkap" ideologi yang ada pada dirinya sendiri,
maupun kemungkinan untuk dapat menangkap keberadaan ideologi dalam
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai sebuah wacana keagamaan yang
otoritatif.
D. Relevansi Penelitian
Islam memiliki makna yang historis, tetapi, pada saat yang sama, fenomena ini
sering diabaikan dalam pemahaman dan kajian terhadap Islam, atau pemahaman
yang ada tentang fenomena ini sangat kurang memadai.
Menurut Mohammed Arkoun, telah lama wacana Islam dimonopoli oleh
kalangan yang disebut sebagai revivalis (salafiy: secara literal berarti pengikut
kaum terdahulu yang saleh) dan terkungkung oleh postulat-postulat modernisme.
Sejak permulaan Nahdhah (kebangkitan Islam) pada abad ke-19 M hingga saat
ini, wacana Islam terjebak dalam konfrontasi antara dua sikap dogmatis: klaimklaim teologis dari kaum reformis salafiy yang menempuh jalan pemikiran
14
’ishlâhiy,20 dan postulat-postulat ideologis dari rasionalisme positivis kaum
modernis.21 Wacana Islam konfrontatif ini terangkum dalam semua diskusi
skolastik tentang Orientalisme. Islam, dalam diskusi-diskusi ini, diasumsikan
sebagai sebuah kesatuan sistem pemikiran, kepercayaan, non-kepercayaan yang
spesifik, esensial, dan tak dapat diubah, yang superior atau inferior (menurut umat
Islam atau non-Islam) terhadap sistem Barat (Kristen). Pendekatan historis
terhadap Islam dalam kedua tradisi tersebut tidak lebih dari sebagai sandaran
ideologis dan perhitungan naratif terhadap fakta-fakta. Sejarah hanya dilihat
secara antikuarian, di mana masa lampau terlalu diagung-agungkan dan diangkat
sebagai hakim dan menjadi legitimasi atas masa kini.22 Menurut Arkoun, "inilah
saatnya menghentikan konfrontasi tidak relevan antara dua sikap dogmatis ini."23
Ada fenomena lain sebagai akibat dari wacana konfrontatif di atas. Semua
polemik yang belakangan ini ditujukan terhadap Orientalisme memperlihatkan
20
Sikap reformis (’ishlâhiy), menurut Mohammed Arkoun, merupakan ciri utama pemikiran Islam
sejak Nabi Muhammad wafat (632 M). Dalam pandangan model pemikiran ini, nilai perilaku
manusia dan, secara lebih umum, nilai perkembangan suatu masyarakat sejak saat itu, dianggap
semata-mata bergantung pada keselarasan dengan teks-sumber-model atau dengan contoh-contoh
dan warisan-warisan dari figur-figur yang diidealkan, yaitu Nabi, para Sahabat dan Imam (’imâm).
Setiap langkah penyimpangan dari model-model ini dirasa dan dipikir sebagai degenarsi pribadi
dan dekadensi komunal. Akibatnya ulama dari setiap mazhab, hingga saat ini, mendakwahkan
kembali kepada pola yang benar dari eksistensi manusia yang serba asli. Diskusi yang lengkap
mengenai hal ini lihat, Mohammed Arkoun, Pemikiran Arab, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996,
h. 21. Di tempat lain Arkoun mendefinisikan pemikiran ’ishlâhiy sebagai pemikiran pembaruan
yang muncul sejak abad ke-19 oleh mazhab salaf [kaum revivalis]. Lihat Mohammed Arkoun,
"Rethinking Islam", dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam
Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta, Paramadina, 2001, h. 336.
21
Suasana intelektual Barat abad ke-19 M menekankan manusia sebagai makhluk yang dikenal
sangat rasional dan menaruh harapan besar dalam pemikiran (akal) sebagai satu-satunya sarana
untuk mengerti dan menyelesaikan setiap masalah sosial. Paham ini merasuk dalam lingkungan
intelektual Muslim, salah satu nama yang memiliki pengaruh besar hingga saat ini adalah
Muhammad ‘Abduh (Mesir: 1849-1905 M). Di Indonesia hingga sekarang, pemikiran-pemikiran
pembaruan ‘Abduh masih berpengaruh sangat dominan di lingkungan intelektual Muslim yang
mengklaim sebagai kelompok "pembaru" [modernis].
22
Ungkapan “sejarah antikuarian” meminjam istilah yang dipakai St. Sunardi, lihat tulisannya,
“Kajian Budaya: Pada Mulanya Adalah Perlawanan ….”, dalam RETORIK, Vol. 2, No. 4, Oktober
2003, h. 12.
23
Mohammed Arkoun, “Rethinking Islam”, h. 337.
15
dengan jelas bahwa apa yang dikenal sebagai kelompok Islam "fundamentalis"
bersikeras menegakkan simbol-simbol ajaran Islam sebagai sebuah institusi
formal (seperti konsep "khilafah" [khilâfah] atau "imamah" [’imâmah]), yang tak
lebih hanya sebagai sebuah alat ideologis untuk mencapai kepentingankepentingan politiknya. Pada tataran praktis, Islam diposisikan dalam kerangka
strategi yang tidak menyentuh realitas sosial, bahkan seringkali menimbulkan
kekerasan.
Demikian juga, karena terperangkap dalam wacana Orientalisme,
kesarjanaan modern tetap jauh dari proyek epistemologis apapun yang dapat
membebaskan Islam dari postulat-postulat esensialis dan substansialis tentang
metafisika klasik.24 Studi Islam, khususnya, dihambat oleh warisan definisi dan
metode yang kaku dari teologi dan metafisika klasik.25 Kelemahan ini, bahkan
tampak lebih jelas tergambar melalui literatur-literatur pemikiran Islam modern
yang miskin, konformis, dan seringkali polemis. Kebanyakan literatur justru
menunjukkan kecenderungan ke arah jalan pemikiran ’ishlâhiy yang membabibuta.26 Selain itu, karena dikuasai oleh postulat-postulat rasionalisme positivistik,
24
Mohammed Arkoun, Loc. Cit.
Contoh yang paling nyata adalah postulat mengenai Alquran. Sejak kekalahan doktrin
Muktazilah tentang kemakhlukan Alquran, "Islam resmi" sampai sekarang berpegang pada
keyakinan yang baku bahwa Alquran bukan makhluk dan bersifat azali. Oleh karena itu, hingga
saat ini masih tidak mungkin, umpamanya, menggunakan ekspresi "problem Tuhan" dalam studi
Islam, menggabungkan Tuhan dan musykil (problem); Tuhan tidak dapat dianggap sebagai
problematik. Ia diketahui dengan baik, ditampilkan dengan baik dalam Alquran; manusia hanya
diharuskan untuk merenungkan, meresapi, dan memuja apa yang Tuhan wahyukan tentang DiriNya dalam Kata-kata-Nya sendiri. Contoh lainnya adalah definisi yang dibakukan mengenai
kelompok sosial mu’minûn di satu sisi, dan kâfirûn, munâfiqûn, serta musyrikûn di sisi yang lain.
Definisi-definisi tersebut beserta konsep-konsep turunannya terpelihara secara masif dalam
literatur Islam dan nyaris tertutup untuk didiskusikan.
26
Corak pemikiran ’ishlâhiy dalam literatur-literatur pemikiran Islam modern, antara lain
tergambar melalui pemikiran-pemikiran Jamâl al-Dîn al-’Afghâniy (18381897) dan Muhammad
‘Abduh yang diadopsi dengan yakin oleh program International Institute of Islamic Thougth
(didirikan pada tahun 1981 di Washington, D. C., "untuk pembaruan dan kemajuan pemikiran
25
16
pemikiran Islam modern hanya cenderung menitikberatkan esensi dan substansi
sebuah ajaran, dengan mengabaikan tata aturan teoretis-metodologis. Pendekatan
rasional terhadap esensi dan substansi ajaran Islam lebih dikedepankan ketimbang
detail-detail aturan metodologis yang memang rumit dan memusingkan.
Akibatnya, literatur-literatur itu tidak hanya miskin nuansa melainkan juga
simplistik secara metodologis. Ungkapan-ungkapan seperti: Islam sesuai dengan
semangat kemodernan, kemajuan, kebebasan, demokrasi dan egalitarianisme,
sebenarnya hanyalah jargon-jargon imitatif yang mengais isu-isu dari Barat.
Dalam hal kebebasan berpikir misalnya, kaum intelektual Islam "modernis" dan
"liberal" selalu mengedepankan isu kebebasan berijtihad sembari menuduh
(seperti perilaku guru-guru Orientalis mereka) kelompok tertentu sebagai yang
terbelakang, yang beku, yang anti kemajuan, dan yang menyebabkan kemunduran
Islam. Tetapi sampai dengan sekarang, isu-isu mereka tak lebih hanyalah omongkosong. Melalui penelitian ini, penulis tidak mau terlibat dalam semua diskusi
yang membicarakan relevansi intelektual dan ilmiah Islam dari sikap mental
inferior
tersebut,
sikap
yang
tidak
memperhatikan
problem-problem
epistemologis, sikap yang juga memiliki motivasi ideologis.
Tugas yang jauh lebih mendesak dan bermakna dibanding semua diskusi
skolastik tentang Orientalisme adalah studi kritis-radikal yang mengevaluasi
Islam"). Salah satu proyek lembaga ini adalah "Islamisasi Pengetahuan". Di Indonesia, pengaruh
keduanya dapat ditemukan dalam pemikiran dan slogan kaum intelektual Muslim "modernis" yang
mendengung-dengungkan kebutuhan pembaruan pemikiran Islam (propaganda kebutuhan
pemikiran rasional) di satu sisi, dan di sisi lain mempropagandakan kebutuhan umat Islam untuk
kembali kepada sebuah "kerangka Islam" yang selalu valid, transenden, otentik, dan universal,
yang dengannya seluruh aktivitas dan inisiatif manusia harus dikontrol dan diintegrasikan dengan
benar, dan oleh karena itu mereka berusaha keras memberantas "bidah". Salah satu slogan yang
sangat terkenal di era 1990-an adalah "otak Jerman-hati Mekah". Slogan ini cukup
menggambarkan "imajinasi sosial" kaum intelektual Muslim "modernis" tentang kualitas umat
Islam yang "modern".
17
dengan perspektif epistemologi baru terhadap karakteristik-karakteristik sistemsistem pengetahuan Islam. Perspektif ini dapat dirumuskan sebagai sikap yang
“regresif-progresif”: perspektif yang mendorong penggunaan nalar (penelitian)
secara bebas menuju elaborasi pandangan baru dan koheren, dengan memasukkan
situasi-situasi baru yang dihadapi masyarakat-masyarakat dan unsur-unsur hidup
tradisi umat Islam.27 Pendekatan historis, arkeologis, sosiologis, antropologis,
linguistik, semiotik, kritik ideologi, dan dekonstruksi, yang menjadi perspektif
baru ilmu-ilmu sosial kemanusiaan kontemporer, tampaknya lebih memungkinkan
sebagai alat bedah untuk membeberkan, menggeledah, membongkar, dan
memilah antara dimensi historis, dimensi mitis, dan fungsi-fungsi ideologis
pengetahuan yang terbentuk dalam fakta Islam. Dalam model studi demikian,
nalar harus dibebaskan dari ontologi, transendentalisme, dan substansialisme yang
telah membuatnya terpenjara, khususnya melalui berbagai postulat teologis yang
diterima tanpa diskusi. Pendekatan-pendekatan teoretis tersebut memiliki peran
yang lebih penting dalam memikirkan kembali status kognitif wacana Islam. Ia
bukan hanya menyediakan cara untuk dapat melihat, menilai, dan menempatkan
masa lalu Islam, melainkan pada saat yang sama ia juga mengajak siapapun untuk
kritis terhadap apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam Islam. Hal
ini adalah sekaligus sebuah metodologi, sebuah epistemologi, dan sebuah teori
sejarah.28
Penelitian ini didedikasikan untuk memenuhi tugas mendesak dan penting
tersebut, yaitu studi kritis dalam kerangka rethinking Islam. Tentu usaha
27
28
Mohammed Arkoun, "Rethinking Islam", h. 336.
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 344
18
memikirkan kembali (rethinking) Islam adalah proyek laten yang tidak akan
pernah berhenti dengan hasil yang final. Dalam gagasan Arkoun, proyek
memikirkan kembali Islam berarti inisiatif intelektual yang terus-menerus, yang
berusaha menemukan suara yang berwenang atau teori yang diakui yang dapat
memberikan gambaran tentang sebuah Islam yang menyerap ke dalam mentalitas
modern yang saintifik, dan pada saat yang sama ke dalam pengalaman keagamaan
umat Islam. Sebagai ilustratif Arkoun mempertanyakan:
… mungkinkah mengartikulasi sebuah visi modern Islam dapat
mempunyai pengaruh yang sama, terhadap masyarakat, dengan pengaruh
Risâlah [’Abû ‘Abdillâh Muhammad] al-Syâfi‘iy (767-820 M.) atau ’Ihy
‘Ulûmu al-Dîn [’Abû Hâmid Muhammad] al-Ghazâliy (1058-1111 M.)?
Saya mengacu kepada kedua karya besar itu, karena keduanya
menggambarkan inisiatif intelektual yang sama dengan yang saya tuju,
yaitu untuk memasukkan, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Syâfi’iy
dan al-Ghazâliy, disiplin-displin baru, pengetahuan baru, dan pemahamanpemahaman historis yang baru ke dalam Islam sebagai sebuah pandangan
spiritual dan historis tentang keberadaan manusia.29
Dengan mengapresiasi semangat dan langkah ilmiah Arkoun, telah cukup
jelas perbedaan posisi penelitian ini dibanding posisi revivalisme dalam konteks
diskusi tentang Orientalisme. Tetapi orang masih dapat mengajukan pertanyaan:
di mana letak perbedaan penelitian ini dengan kajian Orientalis? Bukankah
melakukan studi secara kritis dengan menggunakan seperangkat metode ilmu
sosial kemanusiaan kontemporer (yang notabene berkembang dalam sejarah
tradisi pemikiran Barat) terhadap karakteristik-karakteristik pengetahuan Islam,
sama saja dengan apa yang dilakukan oleh para sarjana Orientalis dan para sarjana
pengikut mereka?
29
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 338.
19
Budaya Barat seperti juga budaya Timur atau Islam bukanlah budaya yang
tunggal dan monolog. Dalam aspek pemikiran misalnya, pengetahuan dan
keilmuan Barat merupakan ragam dialog antar gagasan dan bahkan kontradiktif.
Rasionalisme positivistik dalam ilmu sosial yang dominan di Barat sejak abad ke19, menjelang berakhirnya abad ke-20 telah banyak digugat paradigma dan status
epistemologinya. Postulat-postulat epistemik yang mendasari ilmu sosial
kemanusiaan (humaniora) dibongkar. Maka lahirlah teori-teori ilmu humaniora
yang membongkar dan emansipasif, seperti banyak digunakan dalam studi
kebudayaan kontemporer (cultural studies). Teori-teori ini lahir di Barat dan
sebagai kritik atas tradisi keilmuan Barat.
Ketika kebanyakan reaksi sarjana-sarjana non-Barat mengambil bentuk
yang secara kultural benar-benar defensif terhadap wacana Orientalisme,
sementara itu Edward W. Said secara sengaja berpijak pada keilmuan Eropa yang
emansipasif membongkar epistemologi Orientalisme. Orientalisme yang rasionalpositivistik mengklaim bahwa kultur Barat Eropa yang modern dan humanis
adalah model bagi masyarakat-masyarakat di luar Eropa, dan bahwa ekspansi
Eropa ke seluruh penjuru dunia adalah sebagai proses peradaban global. Klaimklaim seperti ini terasa mengabsahkan bagaimana penjajah-penjajah Eropa
membangun dominasi dan kekerasan, dan Orientalisme dengan konsep
antropologi dan sosiologinya berperan penting dalam menjamin kelangsungan
proses-proses itu. Tetapi dalam pandangan Said, “Timur dulu diciptakan – atau,
dalam ungkapan yang lebih saya sukai – , ditimurkan…. Hubungan antara Timur
20
dan Barat didasarkan pada kekuasaan, atau dominasi dan berbagai tingkat
hegemoni yang kompleks.”30
Studi Said tentang Orientalisme hanya salah satu dari banyak contoh studi
kritik atas tradisi nalar Barat dengan memakai konsep-konsep metodologis yang
orisinal milik Barat. Said, yang berpijak pada teori-teori ilmu sosial kemanusiaan
kontemporer milik Michel Foucault, Antonio Gramsci, dan lain-lain, tampak
memiliki keistimewaan dalam cara memandang Barat. Sekurang-kurangnya, Said
telah menunjukkan bahwa jawaban bagi Orientalisme tidak bisa Oksidentalisme.31
Walaupun penulis sangat simpati dan sependapat dengan kritik Said atas
Orientalisme, tetapi pada taraf tertentu penulis melihat kritik Said dapat menjadi
senjata atau cara baru bagi Oksidentalisme untuk melawan Orientalisme. Penulis
merasa tidak perlu menjadi epigon semangat Said terhadap Orientalisme, tetapi
mencoba bertindak seperti Foucault, atau Gramsci, atau ‘pendekar-pendekar’
mazhab Frankfurt yang merumuskan teori kritis untuk mengkritik budayanya
sendiri. Jadi, penelitian ini adalah semacam otokritik, tanpa harus menolak atau
apalagi mengamini Orientalisme.
Terkait dengan pengaruh "wibawa" yang dimiliki
al-Ahkâm al-
Sulthâniyyah, penelitian ini penting untuk menghindari "perangkap-perangkap"
ideologis yang diyakini ada di dalamnya, maupun untuk mengkritisi klaim dari
kelompok-kelompok Islam yang mencoba memanfaatkannya – baik langsung atau
tidak langsung – secara ideologis sebagai "resep ampuh" atas problem politik
Islam sekarang.
30
31
Edward W. Said, Orientalism, New York: Random House, 1979, h. 5.
Edward W. Said, Ibid., h. 328.
21
E. Survei Hasil-Hasil Penelitian
Di kalangan para ahli studi politik Islam, reputasi al-Mâwardiy dengan karyanya:
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, telah sangat dikenal. Meskipun al-Mâwardiy
bukanlah perintis pemikiran politik Islam, tetapi pemikiran politik yang
dituangkannya di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dinilai paling komprehensif
dan sistematis. Oleh karena itu, al-Mâwardiy dianggap sebagai tokoh pemikir
yang berperan penting dalam mengembangkan teori politik Islam yang melebihi
para pemikir pendahulunya, mulai dari al-Baghdâdiy, al-Bâqillâniy, ’Ibn
Qutaibah, al-Jâhizh, ’Ibn al-Muqaffâ, hingga ’Abû Yûsuf.32
Maxmillian Enger adalah orang pertama yang berjasa memperkenalkan
karya al-Mâwardiy tersebut kepada publik ilmiah Eropa. Pada tahun 1853, Enger
menterjemahkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah ke dalam bahasa Inggris dengan
judul yang sama.33
Tulisan yang lebih bersifat kajian dibuat oleh H.A.R. Gibb, (1937), dalam
bentuk artikel dengan judul “Al-Mâwardi’s Theory of the Caliphate”.34 Penelitianpenelitian kecil yang lain dilakukan oleh Khâlid M. ’Ishaque dengan judul “AlAhkâm al-Sulthâniyya: Law of Government in Islam”35, dan Muhammad ’Abû
Zahrah dengan judul “’Abû al-Hasan al-Mâwardiy”.36
32
Lihat komentar Qamaruddin Khan, Al-Mawardi'
s Theory of The State, h. 20-21.
Maxmillian Enger (ed.), Al-’Ahkâm al-Sultâniyya, Bonn: Adolphus Marcus, 1853. Di sini, perlu
disampaikan koreksi atas informasi Nur Mufid yang melaporkan bahwa al-’Ahkâm alShulthâniyyah dalam edisi bahasa Inggris baru terbit pada tahun 1996 yang ditulis oleh Asadullah
Yate dengan judul: the Laws of Islamic Governance, di London oleh penerbit Ta-Ha Publishers.
Lihat Nur Mufid, “Lembaga-lembaga Politik Islam Menurut Al-Mâwardiy dalam Kitabnya al’Ahkâm al-Shulthâniyyah ah”, Surabaya: Balai Penelitian IAIN Sunan Ampel, 1998.
34
H.A.R. Gibb, “Al-Mâwardi’s Theory of the Caliphate”, Islamic Culture 11, No. 3, Juli 1937.
35
Khâlid M. Ishaque, “Al-Ahkâm al-Sulthâniyya: Law of Government in Islam”, Islamic Studies
4, No. 3, September 1965.
36
Dimuat dalam Majallat al-‘Arabi 76, Maret 1965.
33
22
Ann K. S. Lambton, melalui perspektif ilmu hukum, menulis buku State
and Government in Medieval Islam, 1981. Sesuai judul buku, isinya merupakan
pengantar bagi pembaca untuk mengenal konsep negara dan pemerintahan dalam
Islam Abad Pertengahan. Di dalam buku tersebut, Lambton mengemukakan
ikhtisar pemikiran beberapa tokoh yang dianggap mewakili atas pemikiran
beberapa tokoh yang lain, dan di antara tokoh yang dibahas pemikirannya adalah
al-Mâwardiy. Lambton mencoba menganalisa al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah untuk
menemukan corak pemikiran politik al-Mâwardiy. Menurut Lambton, teori politik
al-Mâwardiy bersifat yuridis dan bukan teori politik yang bercorak pemikiran
spekulatif (filosofis).37 Lambton juga mengemukakan bahwa teori politik alMâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah yang bersifat yuridis tidak hanya
didasarkan pada kaidah-kaidah ijtihad hukum tertentu, melainkan lebih banyak
didasarkan pada fakta-fakta historis yang disimpulkan sebagai ijmak. Oleh karena
itu, menurut Lambton, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah sebuah dokumen kunci
untuk mengetahui prinsip-prinsip kekuasaan dalam praktek Islam yang terdapat
pada abad ke-6 M. sampai dengan masa hidup al-Mâwardiy, yang diterima (secara
ijmak) oleh para ahli (ulama) hukum Islam.38 Tetapi, Lambton tidak sampai
menemukan dan mengulas metodologi penyimpulan hukum (al-manhaj li
’istinbâth al-hukm) yang dipakai al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Penulis mempunyai kesan, bahwa Lambton hanya melihat teks pemikiran alMâwardiy yang eksplisit dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, sementara aspek
historis yang menjadi latar belakang teks dan metodologi yang menjadi kaedah37
Ann K. S. Lambton, State and Government in Medieval Islam, Oxford: Oxford University Press,
1981, h. 83.
38
Ann K. S. Lambton, Loc. Cit.
23
kaedah pengarah bagi teks, yang kedua-duanya implisit diabaikannya. Selain itu,
Lambton hanya berkutat pada aspek hasil pemikiran (product of thought) alMâwardiy dengan memindah isi teks al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah secara ringkas
dan menjelaskan beberapa maknanya. Dengan demikian, Lambton lebih bertindak
sebagai promotor atau quality control atas ‘produk’ al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
daripada bertindak sebagai seorang teknisi ahli. Karena itu, Lambton masih
berpijak pada posisi tradisi Orientalis klasik yang memiliki kecenderungan
esensialis dan substansialis terhadap teks-teks yang menjadi obyek studinya.
Sebuah kajian yang eksklusif mengenai al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
ditulis dalam bentuk buku oleh Qamaruddin Khan berjudul Al-Mâwardi’s Theory
of the State, (1983). Buku Qamaruddin tersebut, meskipun tipis tetapi koheren, di
mana ia menganalisa teori politik al-Mâwardiy secara kritis-refleksif. Ia mencoba
membandingkan pemikiran al-Mâwardiy dengan pendirian para ahli hukum
sebelumnya di satu sisi, dan mendialogkannya dengan kondisi politik
kontemporer pada sisi yang lain. Qamaruddin berhasil menunjukkan poin-poin
kelebihan pemikiran al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah atas
pemikiran-pemikiran para ahli yang lain, seperti diungkapkannya: bahwa al’Ahkâm al-Shulthâniyyah lebih komprehensif, detil, dan sistematis,39 sehingga
“…. al-’Ahkâm al-Sultânia became a standard work of reference on political and
administrative practice,”40 dan bahwa “al-Mâwardi was the founder of the science
of politics in the political world.”41 Sekaligus, Qamaruddin menggaris-bawahi
39
Qamaruddin Khan, Al-Mâwardi’s Theory of the State, Lahore: Islamic Book Foundation, 1403
H/1983 M, h. 23.
40
Qamaruddin Khan, Ibid., h. 53.
41
Qamaruddin Khan, Ibid., h. 52.
24
beberapa hal di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah yang menurutnya perlu
dikritisi.
Di antara kritik-kritik Qamaruddin terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
adalah: pertama, seperti gambaran yang ditangkap oleh Lambton, Qamaruddin
juga melihat bahwa al-Mâwardiy bukanlah seorang pemikir (thinker) politik, dan
oleh karena itu dia tidak mengemukakan konsepnya tentang negara secara
filosofis. Al-Mâwardiy, menurut Qamaruddin, tidak mendiskusikan hakikat
(meaning) negara, tujuan-tujuannya, struktur hukumnya (jurisdiction), mekanisme
kebijakan-kebijakan (obligations) dan pertanggungan-jawabnya (responsibilities),
dan konsep kedaulatannya (sovereignty), sehingga tidak dapat diketahui secara
lengkap gagasannya tentang konstitusi. Kehati-hatian al-Mâwardiy, atau dalam
ungkapan Qamaruddin dikatakan: “did not indulge in empty speculation”,
sehingga memiskinkan teorinya tentang konstitusi negara, menurut Qamaruddin
membawa dampak: “….has not only very much reduced the value of alMawardi’s work but has its deadening effect on the later development of Islamic
political thought.”42
Kedua, terkait dengan konsep demokrasi, Qamaruddin melihat bahwa
kesetujuan al-Mâwardiy terhadap praktek pemilihan khalifah hanya melalui
penunjukan oleh khalifah yang menjabat sebelumnya adalah tidak demokratis.
Lebih dari itu, menurut Qamaruddin, al-Mâwardiy sangat mengkhususkan hakhak dan prerogatif khalifah, tetapi tidak memberikan atensi pada hak-hak dan
tuntutan-tuntutan (claims) rakyat. Akhirnya, kata Qamaruddin: “lack of the idea of
42
Qamaruddin Khan, Ibid., h. 54.
25
fundamental rights of men has been one of the principal sores in Muslim polity for
ages, and has been mainly responsible for almost complete absence of the growth
of democratic life in Muslim lands”.43
Buku Qamaruddin tersebut telah cukup adil dalam menilai al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Qamaruddin mengkritik pemikiran al-Mâwardiy itu secara
seimbang: mengakui kelebihan-kelebihannya dan sekaligus menunjukkan
kekurangan-kekurangannya. Tetapi, Qamaruddin agak berlebihan (kurang
proporsional) di dalam kritiknya. Ia tidak fair, karena mengkritik pemikiran alMâwardiy tidak berdasarkan tuntutan konteks situasi politik saat itu (epistème
Islam Abad Pertengahan), melainkan berdasarkan wacana-wacana politik dan
tuntutan budaya masyarakat kontemporer. Penulis menganggap, Qamaruddin
telah meletakkan “beban” yang terlalu berat di atas “pundak” al-Mâwardiy.
Di kalangan intelektual Muslim Indonesia, nama al-Mâwardiy dan al’Ahkâm al-Shulthâniyyah juga sangat dikenal. Di lingkungan akademik, kajian
terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dapat ditemukan, antara lain, di dalam buku
Syafii Maarif yang berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang
Percaturan dalam Konstituante.44 Buku Syafii Maarif ini semula merupakan
disertasinya di Universitas Chicago. Ketika Syafii Maarif membangun kerangka
teoretis untuk disertasi tersebut, khususnya konsep ’imâmah, ia menyinggung
pemikiran al-Mâwardiy. Dengan mengacu kepada al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
Syafii Maarif mengulas teori al-Mâwardiy tentang ’imâmah. Tetapi, mungkin
karena alasan tempat yang sempit atau tema ini bukan merupakan obyek langsung
43
Qamaruddin Khan, Loc. Cit.
Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante,
Jakarta: LP3ES, 1985.
44
26
penelitiannya, Syafii Maarif hanya mengutip komentar-komentar orang lain
tentang al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, tanpa menunjukkan pendapat atau
analisanya sendiri.
Penulis juga menemukan buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali
berjudul Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.45 Seperti
tampak dari judul buku tersebut, isinya merupakan ringkasan sejarah hidup dan
teori politik tokoh-tokoh Muslim Abad Klasik dan Abad Pertengahan. Apa yang
dikerjakan Munawir itu hampir sama dengan yang dikerjakan Lambton dalam
State and Government in Medieval Islam. Perbedaannya, di antara banyak
perbedaan yang lain, Lambton mengkaji al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah melalui
pendekatan ilmu hukum, sedangkan Munawir mengkajinya melalui pendekatan
ilmu politik. Sesuatu hal yang baru dalam tulisan Munawir adalah ulasan
perbandingan antara konsep bai‘ah (baiat) al-Mâwardiy dengan teori "kontrak
sosial" dari pemikiran para filsuf Barat seperti: Hubert Languet (Perancis: 15191581 M), Thomas Hobbes (Inggris: 1588-1679 M), John Locke (Inggris: 16321704 M), dan Jean Jaques Rousseu (Perancis: 1712-1778 M).
Usman Abu Bakar bersama dosen-dosen lain sejawatnya di IAIN
Walisongo Semarang, melakukan tugas penelitian pada tahun 1994 dengan obyek
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Penelitian yang mereka lakukan diarahkan untuk
menjawab masalah yang kontroversial di kalangan pemerhati teori politik Islam
sehubungan pada tahun 1938 ditemukan kitab tulisan ’Abû Ya’lâ al-Farrâ’ (w.
1066 M) – pengikut ’Ahmad bin Hanbal – yang berjudul sama dengan kitab al45
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1990.
27
Mâwardiy: al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Masalah-masalah yang dipolemikkan
seperti: apa perbedaan kedua al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah itu? siapa yang lebih
dulu menulis, al-Mâwardiy atau al-Farrâ’? mungkinkah seseorang telah menjiplak
karya yang lain? Usman dkk. berhasil menemukan jawaban bagi masalah-masalah
tersebut.46
Ada sebuah artikel, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku tipis,
ditulis oleh Marzuki Wahid dengan judul Latar Historis Narasi Ketatanegaraan
al-Mâwardiy dan Ibn al-Farr : Bacaan “Seorang Rakyat” atas Dua Kitab alAhkâm al-Sulthâniyyah.47 Seumpama tubuh, buku Marzuki tersebut berdiri di atas
dua kaki. Kaki yang satu adalah Al-Mâwardi’s Theory of the State karya
Qamaruddin Khan, dan kaki yang lain adalah hasil penelitian Usman Abu Bakar
dkk.. Penulis menganggap, Marzuki banyak berhutang kepada Qamaruddin dan
Usman dkk..
Marzuki, sesuai dengan judul bukunya, mengemukakan kembali latar
belakang sosial dan politik al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah karya al-Mâwardiy dan
al-Farrâ’. Ia memang menyarankan, bahwa konteks sosial, politik, dan budaya
harus diperhatikan ketika membaca kitab al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Tetapi,
pemaparan Marzuki tentang latar belakang historis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah di
dalam buku tersebut, sepertinya sia-sia saja. Karena, Marzuki justru menganalisa
isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah berdasarkan latar belakang sosial dan politik
kekinian (di luar konteks al-Mâwardiy dan al-Farrâ’). Akibatnya, Marzuki mudah
46
Lihat laporan penelitian Usman Abu Bakar, "Negara dan Pemerintah: Studi Komparatif
Pemikiran al-Mâwardiy dan al-Farrâ’", Semarang: Balai Penelitian IAIN Walisongo, 1994/5.
47
Marzuki Wahid, Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mâwardiy-’Ibn al-Farrâ’: Bacaan
“Seorang Rakyat” atas Dua Kitab al-Ahkam al-Sulthâniyyah, Cirebon: Jaringan Informasi &
Lektur Islam (JILLI), 1997.
28
menyimpulkan bahwa ada problem yang besar jika kitab al-’Ahkâm alShulthâniyyah harus diterapkan secara apa adanya dalam konteks sekarang, di
mana masyarakat telah menjadi plural-mondial: agama hanyalah menjadi satu sub
dari sejumlah sub dalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena
itu Marzuki menyarankan: butuh pemikiran yang mendalam jika kitab al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah harus dibenturkan dengan konsep negara-bangsa (nation-state)
yang telah menjadi “anutan suci” masyarakat dunia.48
Pada tahun 1997, Sri Mulyati menulis sebuah artikel berjudul “The Theory
of State of al-Mâwardi”. Artikel Sri Mulyati ini bersama artikel-artikel penulis
yang lain terkumpul di dalam buku Islam & Development: A Politico-Religious
Response.49 Salah satu masalah yang ingin diketahui kejelasannya oleh Sri
Mulyati adalah perbedaan antara konsep khilâfah dan konsep ’imâmah dalam teori
al-Mâwardiy, mengingat penggunaan dalam kajian politik Islam, kedua konsep itu
sering diartikan berbeda: khilâfah adalah konsep kenegaraan mazhab Suni, dan
imâmah adalah konsep kenegaraan mazhab Syî‘ah50. Sri Mulyati menemukan
kenyataan bahwa di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, al-Mâwardiy tidak
membedakan kedua konsep tersebut, bahkan justru al-Mâwardiy yang dikenal
sebagai salah satu pembesar ulama Suni lebih banyak menggunakan istilah
’imâmah atau ’imâm daripada khilâfah atau khalîfah. Dengan mengutip Munawir
Sjadzali, Sri Mulyati menyatakan: “al-Mâwardi’s understanding of the role the
48
Marzuki Wahid, Ibid., h. 32-33.
Sri Mulyati, “The Theory of State of al-Mâwardi”, dalam Sri Mulyati dkk., Islam &
Development: A Politico-Religious Response, Montreal: Permika Montreal & LPMI, 1997.
50
Lihat Sri mulyati, Ibid., h. 4.
49
29
imâm is simply that it is equivalent to that of the ’khalîfah, king, sultan or head of
state.”51
Terdapat juga laporan penelitian dari Nur Mufid (1998) dengan judul
“Lembaga-Lembaga Politik Islam menurut al-Mâwardiy dalam Bukunya al’Ahkâm al-Shulthâniyyah”, di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang sedang
dikerjakan Nur Mufid sesungguhnya adalah menterjemahkan al-’Ahkâm alShulthâniyyah, kemudian memasukkan unsur-unsurnya yang sesuai dengan judul
ke dalam sistematika penelitiannya.
Selain ditemukan karya-karya hasil kajian tersebut, juga berhasil didapat
sebuah karya terjemahan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah yang ditulis oleh Abdul
Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin52.
Sepanjang pembacaan terhadap karya-karya tersebut di atas, diperoleh
beberapa kesan. Pertama, karya-karya hasil kajian terhadap al-’Ahkâm alShulthâniyyah tersebut cenderung linier, esensialis, substantif, dan reproduktif,
terutama karya-karya yang menggunakan pendekatan sejarah-kisah gagasan.
Kebanyakan hanya melihat pemikiran jadi (product of thought) al-Mâwardiy
dengan memindah isi teks al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan menjelaskan
maksudnya. Hal ini menyebabkan kesan pemikiran al-Mâwardiy yang kering,
miskin nuansa, dan a-historis. Khusus mengenai tulisan Lambton dan Munawir
Sjadzali, keduanya lebih menempatkan teks al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai
dokumen berbagai himpunan gagasan al-Mâwardiy yang berdiri sendiri dan
51
Sri Mulyati, Ibid., h. 22. Lihat juga Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah,
dan Pemikiran, h. 63.
52
Al-Mâwardiy, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Abdul Hayyie alKattani & Kamaluddin Nurdi (pent.), Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
30
berkembang hanya karena interaksi dengan gagasan lain. Padahal, suatu teks
(gagasan) adalah produk sebuah budaya. Sebuah gagasan adalah makhluk mental
yang tidak stabil. Meminjam ungkapan Mohammed Arkoun, “gagasan tergantung
pada kendala bahasa, masyarakat, politik, dan ekonomi.”53
Dengan demikian, penelitian terhadap faktor-faktor historis suatu teks
menjadi penting dilakukan untuk menemukan makna teks itu dalam konteks
sejarahnya. Walaupun semua karya tulis di atas telah mengemukakan latar historis
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, tetapi satu karyapun belum menjelaskan bagaimana
faktor-faktor kesejarahan berpengaruh terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Dengan kata lain, latar kesejarahan pada masa hidup al-Mâwardiy belum
dimanfaatkan oleh para penulis tersebut untuk menempatkan al-’Ahkâm alShulthâniyyah fenomena budaya pada masanya. Dalam karya-karya mereka, latar
belakang historis ditulis sebatas sebagai ilustrasi konteks bagi al-Mâwardiy dan
karyanya, dan hanya demi memenuhi kepatutan (formalitas) sebuah studi
mengenai gagasan seorang tokoh.
Kedua, karena para penulis di atas lebih condong kepada pemikiran jadi
al-Mâwardiy, akibat dari sikap itu, maka mereka mengabaikan
proses dan
prosedur berpikir yang ditempuh al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Tentu, gagasan Al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah tidaklah datang
sekonyong-konyong, tanpa metode. Metode yang dipilih atau digunakan alMâwardiy pun, tentu mengakar pada keyakinan dan konsepsi-konsepsi awal yang
tertanam dalam dirinya, dan situasi epistemik tertentu. Semestinya dalam hal ini,
53
Mohammed Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru,
Jakarta: INIS, 1994, h. 43.
31
tulisan Lambton lebih dapat membuka kemungkinan untuk memasuki aspek
metodologi yang digunakan al-Mâwardiy, karena dia mendekati pemikiran alMâwardiy melalui perspektif ilmu hukum sedangkan teori politik al-Mâwardiy
adalah produk dari ilmu hukum Islam. Sayangnya, hal terakhir ini tidak juga
dibahas oleh Lambton. Seandainya hal itu benar-benar dikerjakan oleh Lambton,
pembaca (khususnya publik ilmiah di Eropa atau non-Muslim) akan mendapatkan
gambaran teori politik al-Mâwardiy yang lebih “unik” dan “mengigit”. Karena,
persoalan metodologilah yang sesungguhnya menyebabkan ada “jarak” antara
tradisi pemikiran hukum Islam dengan tradisi pemikiran hukum yang lain.
Ketiga, terkait dengan despotisme Barat, penulis menangkap kesan bahwa
ada semacam rasa kekecewaan dan rendah diri yang mengendap dalam batin
kebanyakan intelektual Muslim masa kini, baik yang mengaku diri sebagai
tradisionalis, moderat, atau liberal sekalipun, meskipun kadar intensitasnya dan
cara mereka menyikapinya masing-masing berbeda. Dalam wilayah kasus
penelitian ini misalnya, fenomena tersebut terlihat dalam tulisan Qamaruddin
Khan, Sri Mulyati, Marzuki Wahid, dan Munawir Sjadzali. Ketika mereka
membaca teks pemikiran al-Mâwardiy, perkembangan situasi dan beban problem
politik yang dihadapi umat Islam sekarang juga melingkupi benak mereka. Maka,
Qamaruddin dan Sri Mulyati menilai bahwa teori ’imâmah al-Mâwardiy tidak
demokratis (undemocratic),54 dan Marzuki pun menyatakan bahwa ada problem
besar jika teori al-Mâwardiy tersebut harus diterapkan dalam kondisi sekarang.55
Jika ungkapan “undemocratic” direfleksi secara mendalam, hal itu merupakan
54
Lihat Qamaruddin Khan, Al-Mâwardi'
s Theory of The State, h. 54, dan Sri Mulyati (ed.), Islam
and Development: A Politico-Religious Respons, h. 37.
55
Marzuki Wahid, Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mâwardiy-’Ibn al-Farrâ’, h. 32.
32
ekspresi kekecewaan.56 Mereka kecewa, karena problem politik yang bersifat etisfilosofis yang sedang mereka hadapi bersama Umat tidak ditemukan
pemecahannya dari membaca al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Mereka kecewa,
ternyata al-Mâwardiy tidak memiliki penawarnya. Dan mengenai tulisan Munawir
Sjadzali, itu adalah contoh dari fenomena yang lain. Munawir dengan penuh
semangat menunjukkan keterdahuluan teori "kontrak sosial" (bai‘ah) yang
digagas oleh Al-Mâwardiy (abad X M), atas teori yang sama yang digagas oleh
para pemikir di Eropa (abad XVI M) yang termasyhur.57 Munawir seperti
mengatakan: “Ternyata, al-Mâwardiy (yang adalah bagian dari Saya-MuslimTerjajah) lebih "senior" daripada mereka: Barat-Kristen-Penjajah.” Jika
direfleksi secara mendalam, semangat Munawir itu sebenarnya berangkat dari rasa
"rendah diri".
Terkait dengan ketiga kesan tersebut, maka penelitian lebih memilih posisi
sebagaimana ditunjukkan oleh Arkoun dalam kata-katanya:
Kita menengok ke belakang bukan untuk melemparkan ke dalam teks-teks
fundamental tersebut tuntutan-tuntutan dan kebutuhan masyarakat Muslim
jaman sekarang – sebagaimana dilakukan oleh ‘ulamâ’ ’ishlâhiy –
melainkan untuk mengungkap mekanisme historis serta faktor-faktor yang
menghasilkan teks-teks tersebut dan fungsi-fungsinya. Pada waktu yang
bersamaan kita harus ingat bahwa teks-teks ini masih hidup, aktif sebagai
sistem ideologis dari kepercayaan dan pengetahuan yang ikut menentukan
dalam membentuk masa depan. Oleh karena itu kita harus memeriksa
proses perubahan yang terjadi pada teks-teks tersebut, yaitu dari
kandungan dan fungsi perdana ke kandungan dan fungsi yang baru.58
56
Tentu penulis menyadari bahwa ungkapan tersebut bisa memiliki banyak makna yang lain.
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h. 67.
58
Dikutip melalui St. Sunardi, “Islam dan Kekuasaan: Telaah Tentang Pemikiran Arkoun”,
makalah yang terkumpul dalam kertas kerja, Islam dalam Lintasan Sejarah, belum diterbitkan.
57
33
Dari
kutipan
di
atas
dapat
dipahami
bahwa
Arkoun
hendak
menggabungkan aspek diakronis dan sinkronis dalam kajian terhadap teks-teks
fundamental Islam. Artinya, teks-teks itu dilihat Arkoun sebagai sistem
kepercayaan dan pengetahuan yang dipakai kelompok-kelompok Islam dalam
situasi historis tertentu untuk memahami dan membentuk tatanan kehidupan yang
diinginkan,
dan
karenanya
bersifat
historis.
Kajian-kajian
Arkoun
dimaksudkannya untuk mengungkap mekanisme historis pemikiran Islam dan
faktor-faktor yang menghasilkannya. Pada waktu bersamaan, Arkoun memeriksa
fungsi-fungsi pemikiran-pemikiran itu sebagai sistem mitis/ideologis yang
hidup/dihidupkan yang ikut menentukan dalam membentuk masa depan. Dengan
demikian, studi Islam Arkoun dapat juga diartikan sebagai usaha intelektual yang
memperhadapkan pemikiran-pemikiran Islam klasik yang otoritatif dengan
mencari syarat-syarat kemungkinannya yang baru pada masa sekarang dan masa
yang akan datang. Metode inilah yang sesungguhnya telah mengarahkan seluruh
studi Arkoun tentang (masyarakat) Islam yang ia sebut sebagai proyek “thinking
Islam”.
Dengan mengapresiasi sebagian posisi ilmiah Arkoun, telah cukup jelas
perbedaan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu mengenai
al-Mâwardiy dan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
F. Orientasi dan Sistematika Penulisan
Tesis ini disusun menjadi empat bagian. Bagian I merupakan pendahuluan, yang
pertama-tama menguraikan pengalaman politik Islam secara umum sejak masa
34
pendirian hingga perkembangannya, sebagai latar belakang masalah penelitian.
Titik tolak permasalahan berangkat dari fenomena kemiskinan teori politik Islam
yang
berguna
bagi
generasi
Sahabat
untuk
melanjutkan
tugas-tugas
kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat, sehingga memunculkan berbagai
klaim dari kelompok-kelompok yang bersaing. Klaim-klaim tersebut terus
dikembangkan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan ranah kepentingan
dan budayanya sehingga, dalam kasus kelompok Suni, muncul teori-teori politik
yang digagas oleh kaum intelektualnya (ulama), antara lain teori yang digagas
oleh al-Mâwardiy dalam kitab al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Akhirnya, uraian
tentang latar belakang masalah mengerucut pada penegasan inti persoalan
penelitian. Setelah itu, dalam bagian ini pula ditunjukkan tujuan penelitian dan
relevansinya dalam konteks kajian Islam kontemporer. Hasil studi kepustakaan
dilaporkan dalam akhir bagian ini, sehingga dapat dibedakan posisi penelitian ini
dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang pernah ada.
Bagian II dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama membahas kerangka
teori penelitian, dan bagian kedua membahas metode penelitian. Berkenaan
dengan kerangka teoretis, akan dibahas beberapa konsep yang penting untuk
langkah pendekatan, pengolahan data dan analisanya. Konsep-konsep itu meliputi
sosiologi pengetahuan, sejarah pengetahuan, epistème, diskursus, ideologi, dan
kritik ideologi. Kemudian, bertolak dari kerangka teoretis tersebut akan ditetapkan
metode penelitian.
35
Bagian III merupakan inti pertama penelitian, merupakan bab yang berisi
data-data penelitian. Pembahasan bagian III akan dibagi menjadi tiga sub bab
sebagai berikut:
Sub bab pertama berisi substansi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Pada bagian
ini, tidak semua isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah akan dipaparkan melainkan hanya
teori dasar al-Mâwardiy tentang ’imâmah. Sub bab kedua berisi latar belakang
historis al-Mâwardiy dan karyanya al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Pembahasannya
meliputi: riwayat hidup al-Mâwardiy, kondisi sosial dan politik masyarakat
Muslim abad IV H/ X M, dan sejarah wacana politik Islam. Pemaparan data-data
historis tersebut bermanfaat untuk mengungkapkan konteks al-’Ahkâm alShulthâniyyah, epistème yang membentuknya, dan implikasi-implikasinya yang
bersifat metodologis dan ideologis.
Pada sub bab ketiga dikemukakan metodologi yang dipakai al-Mâwardiy
dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Sebelum pembahasan masuk ke dalam
metodologi al-Mâwardiy, pada bagian ini akan disinggung terlebih dahulu selintas
pandang sejarah pembentukan fikih (hukum Islam) dan metodologi yang dipakai
untuk merumuskannya.
Sebagai penutup bagian ini, akan dipaparkan wacana-wacana ideologis al’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Bagian IV merupakan inti kedua penelitian, bab yang paling penting, yaitu
analisa data. Dalam bab ini, analisa penelitian dibagi menjadi tiga sub bab. Sub
bab pertama berisi uraian analisa historis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
menunjukkan konteks sosial-historis yang melahirkannya, historisitasnya, dan
36
implikasinya. Sub bab kedua berisi ulasan metodologi al-’Ahkâm alShulthâniyyah dan batas-batasnya. Pada sub bab ketiga diisi paparan mitos-mitos
dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan analisanya yang disebut analisa mitis.
Analisa juga akan diarahkan kepada sistem pemikiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah untuk mengetahui sistem mitis dari sistem pemikiran itu dan
fungsinya.
Bagian V merupakan kesimpulan penilitian. Bab ini berisi narasi sejarah
pembentukan teori politik Islam secara umum, dan secara khusus akan
ditunjukkan nuansa kesejarahan (historisitas) al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah: faktorfaktor sejarah (syarat-syarat historis) yang melahirkannya, cara-cara pembentukan
(syarat-syarat ilmiah) gagasan-gagasannya, serta implikasi dari keduanya yang
bersifat ideologis.
Bagian VI adalah penutup yang merupakan ikhtisar penelitian secara
umum.
37
BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN METODE PENELITIAN
Perlu dinyatakan kembali di sini bahwa penelitian ini dilakukan dalam rangka
menyambut proklamasi Arkoun untuk menghentikan konfrontasi tidak relevan
antara dua sikap dogmatis: klaim-klaim teologis dari kaum reformis salafi dan
postulat-postulat ideologis dari rasionalisme positivis kaum modernis, dan
sekaligus untuk memenuhi tugas, yang menurutnya, mendesak dan penting: yaitu
studi kritis dalam kerangka rethinking Islam. Pada bab terdahulu juga telah
disinggung metode yang dipakai Arkoun untuk memulai proyek pemikirannya itu,
yaitu penggabungan aspek-aspek diakronis dan sinkronis dalam setiap kajian
terhadap teks pemikiran Islam.
Sejalan dengan maksud dan langkah utama Arkoun tersebut, serta
mengingat tiga rumusan persoalan di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan
memanfaatkan konsep-konsep metodologis Arkoun dan konsep-konsep dari
ilmuwan sosial lain yang sejalan, yaitu teori ilmu sosial kontemporer semisal
sosiologi pengetahuan, sejarah pengetahuan, dan kritik ideologi, sebagai kerangka
teoretis penelitian. Kemudian, berdasarkan kerangka teoretis inilah akan
ditetapkan metode penelitian.
A. Kerangka Teoretis dan Pengertian Konsep-Konsep
Kerangka teoretis yang penting untuk menjawab dan menganalisa tiga persoalan
penilitian ini adalah: (1) situasi sosial historis dan peranannya terhadap
38
pembentukan pengetahuan, (2) mekanisme pembentukan pengetahun, dan (3)
fungsi-fungsi pengetahuan. Secara berurutan, kerangka teoretis tersebut beserta
konsep-konsep kunci yang terkait dijelaskan sebagai berikut:
1. Situasi Sosial Historis dan Peranannya dalam Pembentukan Pengetahuan
Mengenai pengetahuan manusia, Arkoun mengatakan: "saya betul-betul meyakini
bahwa segala macam dan tingkat pengetahuan diproduksi oleh hidup, aksi, dan
pemikiran manusia dalam sebuah situasi-sosial historis yang ada sedemikian
rupa",59 dan dengan demikian, "segala upaya untuk memikirkan obyek
pengetahuan tergantung pada postulat-postulat epistemik",60 maka: individu,
pemikir, dan "penulis (harus) tunduk kepada semua faktor kebahasaan, budaya,
politis, dan sosiologis pada semua lingkungan (environment) yang beraneka
macam dan pada seluruh periode kesejarahan yang kesemuanya mewarnai
pandangan-pandangannya."61
Tesis Arkoun tersebut jika ditempatkan dalam konteks teori ilmu sosialhumaniora kontemporer, berhubungan erat dengan pandangan para ilmuwan
sosiologi, antropologi, sejarah, dan psikoanalisa yang memandang individu
sebagai produk bahasa dari bahasa-bahasa yang ada dan hasil dari sistem
kemasyarakatan dari sistem-sistem kemasyarakatan yang beraneka macam, serta
hasil dari tradisi, kepercayaan, orientasi-orientasi imperatif yang diharuskan oleh
sejarah tertentu pada setiap (kelompok) masyarakat.
59
Mohammed Arkoun, "Rethinking Islam”, dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal:
Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 344
60
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 345
61
Mohammed Arkoun, Membongkar wacana Hegemonik, Surabaya: Al Fikr, 1999, h. 9
39
Para pencetus dan pendukung teori sosiologi pengetahuan misalnya,
mereka dengan sengaja memahami gagasan tidak mulai dari seorang individu dan
pemikirannya secara abstrak melainkan lebih-lebih berusaha memahami
pemikiran dalam latar belakang konkret dari situasi sosial-historis tertentu yang
memunculkan pikiran individual yang berbeda-beda secara sangat bertahap-tahap.
Dalam pandangan ilmuwan sosiologi pengetahuan, bukanlah manusia pada
umumnya yang berpikir, melainkan manusia dalam kelompok-kelompok tertentu
yang telah mengembangkan suatu gaya pemikiran tertentu dalam rangkaian
tanggapan terus-menerus terhadap situasi-situasi khusus tertentu yang mencirikan
posisi umum mereka.62 Oleh sebab itu sosiologi pengetahuan menyatakan, seperti
diungkapkan Karl Mannheim, terdapat cara-cara berpikir yang tak dapat dipahami
secara memadai selama asal usul sosialnya tidak jelas.63
Teori sosiologi pengetahuan juga menegaskan, tidaklah tepat mengatakan
bahwa seorang individu berpikir, lebih tepatlah menyatakan bahwa ia mengambil
bagian dalam pemikiran lebih lanjut yang telah dipikirkan orang lain sebelumnya.
Ia berada dalam suatu situasi yang diwariskan dengan pola-pola pemikiran yang
sesuai untuk suatu situasi dan berusaha menjelaskan lebih lanjut cara-cara
menanggapi yang telah ada atau menggantinya dengan cara-cara lain supaya dapat
menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dari peralihan-peralihan dan
perubahan-perubahan
situasinya
secara
memadai.64
Perspektif
sosiologi
pengetahuan ini berbanding lurus dengan tesis dasar '
Teori Kritik' Jurgen
62
Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Kanisius,
Yogyakarta, 1991, h. 3
63
Karl Mannheim, Ibid., h. 2
64
Karl Mannheim, Loc. Cit.
40
Habermas (mazhab Frankfurt) yang menyatakan bahwa kemampuan-kemampuan
subyek transendental mempunyai landasannya dalam sejarah alam dari species
manusia, bahwa mengetahui adalah alat manusia untuk mempertahankan diri.65
Sevisi dengan perspektif sosiologi pengetahuan Karl Mannheim dan Teori
Kritik J. Habermas, Michel Foucault dengan arkeologi pengetahuannya menaruh
perhatian terhadap kondisi-kondisi historis yang membentuk dan menentukan
pengetahuan yang disebutnya epistèmè. Epistèmè adalah sebuah kata Yunani yang
berarti "pengetahuan", tetapi oleh Michel Foucault digunakan dalam arti a priori
historis: pengandaian-pengandaian tertentu, prinsip-prinsip tertentu, syarat-syarat
kemungkinan tertentu, dan cara-cara pendekatan tertentu yang menjadi landasan
epistemologis
yang
dimiliki
setiap
zaman.66
Keseluruhan
pengandaian-
pengandaian itu membentuk suatu sistem (pemikiran) yang teguh yang tidak
diinsafi dengan jelas oleh orang-orang yang bersangkutan, tetapi secara
tersembunyi menentukan pemikiran, pengamatan, dan pembicaraan mereka (the
general system of the formation and transformation of statements).67
Foucault menganggap bahwa bahasa merupakan fenomena penting dalam
studi ilmu sosial-kemanusiaan. Bahasa, menurut Foucault, membangun dan
menghasilkan makna di bawah kondisi-kondisi historis dan material yang spesifik.
Dia
menyelidiki
bagian-bagian
menentukan/memainkan
65
peranan
dan
atas
kondisi-kondisi
historis
pernyataan-pernyataan
yang
yang
Jurgen Habermas, Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi, LP3ES, Jakarta, 1990, h. 172
K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer: Prancis, Gramedia, Jakarta, 2001, h. 215, lihat juga; h.
314-5. Tentang a priori historis lihat, Michel Foucault, Pengetahuan dan Metode: Karya-karya
Penting Foucault, Paul Rabinow (ed.), Jalasutra, Yogyakarta, 2002, h. 402
67
K. Bertens, Op. Cit., h. 316. Lihat juga, Michel Foucault, Archaeology of Knowledge, Great
Britain, London: Tavistock Publications, 1972, h. 126-131
66
41
dikombinasikan dan diregulasikan (regulated) menjadi bentuk (form) yang
membatasi
perbedaan
lapangan
pengetahuan/obyek,
yang
menghendaki
seperangkat konsep-konsep dan menentukan batas-batas tertentu “rezim
kebenaran” (regime of truth; misalnya apa yang dihitung sebagai kebenaran).
Foucault berusaha mendefinisikan kondisi-kondisi historis dan aturan-aturan yang
menentukan pembentukan (rules of formation) dan meregulasikan sebagai cara
untuk mengatakan sesuatu tentang obyek.68
2. Mekanisme Pembentukan Pengetahuan
Setelah tesis-tesis dasar mengenai pengetahuan manusia yang historis tersebut
berhasil dijelaskan sebagai kerangka teoretis penelitian yang pertama, selanjutnya
perlu dijelaskan pula kerangka teoretis yang kedua tentang bagaimana proses
(mekanisme) pembentukan pengetahuan yang historis itu terjadi.
Dalam penglihatan Arkoun, umat manusia muncul sedemikian rupa dalam
masyarakat melalui berbagai fungsi yang terus berubah. Setiap fungsi dalam
masyarakat, kata Arkoun, dikonversi ke dalam suatu tanda dari fungsi itu, yang
berarti bahwa realitas-realitas digambarkan melalui bahasa-bahasa sebagai sistem
tanda. Tanda-tanda, kata Arkoun, adalah persoalan radikal bagi suatu pengetahuan
yang kritis, terkontrol. Persoalan ini muncul terutama pada setiap usaha untuk
menafsirkan wahyu. Kitab suci sendiri disampaikan melalui bahasa-bahasa natural
yang digunakan sebagai sistem tanda, dan masing-masing tanda adalah tempat
yang tepat (locus) bagi operasi-operasi penghampiran (convergent operations)
68
Melalui Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice, London, Thousand Oaks, New
Delhi: Sage Publications, 1999, h. 78
42
(persepsi, ekspresi, interpretasi, terjemah, komunikasi), yang melibatkan seluruh
hubungan antara bahasa dan pemikiran. Oleh karena itu, Arkoun menyatakan:
"inti pemikiran Islam harus ditampilkan sebagai isu linguistik dan semantik".69
Arkoun mengatakan, bahasa sebagai sistem tanda atas realitas beserta
semua produksi semiotik manusia, dalam proses kemunculan sosial dan
kulturalnya tunduk pada perubahan historis (historisitas). Kebenaran pun dibentuk
dengan alat-alat, konsep-konsep, definisi-definisi, dan postulat-postulat yang terus
berubah. Ini berarti bahwa tidak ada akses menuju yang absolut di luar dunia
fenomenal dataran kehidupan manusia yang historis.70
Hampir senada dengan Arkoun, J. Habermas menggambarkan secara lebih
luas kategori-kategori yang memungkinkan pengetahuan. Dengan perspektif
sosiologi pengetahuan, Habermas mengatakan: "Sudut-sudut pandang, yang
darinya kita secara transendental harus memahami realitas, menetapkan tiga
kategori pengetahuan yang mungkin: informasi-informasi yang memperluas
kemampuan penguasaan teknis kita; tafsiran-tafsiran yang memungkinkan suatu
pengarahan tindakan di dalam tradisi bersama; dan analisis-analisis yang
membebaskan kesadaran dari ketergantungan kepada kekuatan-kekuatan yang
dihipotesiskan. Sudut-sudut pandang itu lahir dari jalinan hubungan kepentingan
manusia, yang sudah sejak semula terikat kepada medium-medium sosialisasi
tertentu: kepada kerja, bahasa dan kekuasaan.”71
69
Mohammed Arkoun, "Rethinking Islam”, dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal:
Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 345
70
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 346
71
Jurgen Habermas, Op. Cit., h. 173
43
Dalam konteks sejarah pengetahuan, Foucault mengatakan: "pengetahuan
bukanlah ilmu dalam penempatan yang terus-menerus dari struktur internalnya;
pengetahuan merupakan lapangan sejarah aktualnya."72
Menurut Foucault, makna-makna secara temporer distabilisasikan atau
diregulasikan ke dalam sebuah diskursus (wacana) melalui operasi kekuasaan (the
operation of power).73 Dengan demikian, setiap bentuk '
kebenaran'(makna) dapat
dilacak secara genealogis (historis) pada institusi dan wacana dominan yang
melahirkannya. Terkait dengan kepentingan pengetahuan, kehendak untuk tahu
adalah nama lain bagi kehendak untuk berkuasa.74
Diskursus “mempersatukan” antara bahasa dan praktek bahasa, serta
menunjukkan produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberikan arti
terhadap obyek-obyek material dan praktek-praktek sosial. Walaupun obyek
material dan praktek sosial berdiri di luar bahasa, akan tetapi keberartiannya
secara diskurisif dibentuk oleh bahasa. Diskursus menyusun, mendefinisikan, dan
menghasilkan obyek-obyek pengetahuan dalam cara yang dapat difahami
(intelligible) sambil mengasingkan bentuk-bentuk nalar lain yang dianggap sebagi
hal yang tidak mungkin dipahami (unintelligible).75 Selain itu, Foucault juga
menyatakan bahwa diskursus tidak hanya meregulasikan apa yang dapat
dikatakan di bawah determinasi kondisi-kondisi sosial dan kultural, tetapi juga
72
Michel Foucault, "Arkeologi Pengetahuan: Tanggapan atas Lingkaran Epistemologi", dalam
Paul Rabinow (ed.), Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault, Jalasutra,
Yogyakarta, 2002, h. 166
73
Melalui Chris Barker, Op. Cit., h. 78
74
Melalui Paul Rabinow (ed.), Op. Cit., h. 333
75
Melalui Chris Barker, Loc. Cit., h. 78
44
siapa yang dapat berbicara, kapan, dan di mana.76 Bagaimana sesuatu fenomena
dikategorisasikan, didefinisikan, dan ditindaklanjuti tergantung pada komponenkomponen diskursif: institusi-institusi, teknik-teknik, kelompok sosial, persepsi
organisasi-organisasi, dan hubungan di antara bermacam-macam wacana.77 Dari
sinilah awal kerja Foucault menginvestigasi sejarah kekuasaan.
Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengetahuan
manusia diekspresikan melalui sistem penandaan; '
kebenaran'(makna) dibentuk
dengan alat-alat, konsep-konsep, definisi-definisi, dan postulat-postulat yang
memungkinkan pengarahan tindakan kepada nilai yang dikehendaki dalam
konteks sosial tertentu, dan yang mengakibatkan konfigurasi sosial tertentu pula.
Tanda dan makna bukan suatu yang ajeg dan kodrati, ia dibentuk dan selalu
berubah bentuk. Semuanya tak lebih dari bentukan sosial. Setiap ilmu
memperoleh suatu jenis kemerdekaan dengan adanya hukum-hukum, dasar-dasar,
metode-metode, dan postulat-postulat yang sangat penting bagi pijakan akal untuk
menerapkan ilmu-ilmu tersebut.78 Arkoun menyatakan: "Apa yang dapat
dipertanyakan adalah bagaimana mendasarkan semua pemikiran pada postulat
keberadaannya.79 Keyakinan dibentuk, diekspresikan, dan diwujudkan dalam dan
melalui wacana. Secara berturut-turut, keyakinan, setelah mengambil bentuk dan
akar-akar melalui wacana keagamaan, politik, dan keilmuan, selanjutnya
76
Melalui Chris Barker, Ibid., h. 79
Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, Great Britain: Tavistock Publications
Limited, 1972, h. 72
78
Mohammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik, Al Fikr, Surabaya, 1992, h. 21
79
Mohammed Arkoun, "Rethinking Islam”, dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal:
Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 348
77
45
mengemukakan sasaran dan postulat-postulatnya terhadap wacana-wacana dan
perilaku-perilaku (individual dan kolektif)."80
3. Fungsi Pengetahuan
Mohammed Arkoun juga menaruh perhatian kepada
fungsi/kepentingan
pengetahuan. Menurut dia, manusia tidak semata-mata digerakkan oleh material
dan ekonomi tetapi juga digerakkan oleh gambaran fantasi (image) dan mimpimimpi
indah.
Dalam
konteks
masyarakat-masyarakat
al-Kitab,
Arkoun
menyatakan: "Terdapat fantasi gabungan (kolektif) pada setiap masyarakat yang
terbentuk, diturunkan, dan ditanamkan selama sejarah yang panjang melalui
kelahiran kitab yang diwahyukan."81 "Sesungguhnya aspek fungsional yang
menguasai fantasi ......... itulah yang seharusnya menjadi bahan pertama untuk
analisa, pemahaman, dan penafsiran."82
Dalam hal ini, Arkoun mengajak orang untuk kritis terhadap faktor-faktor
non-teoretis yang ikut menentukan pengetahuan. Faktor-faktor non-teoretis itu
bisa saja berupa "ideologi" maupun berupa dorongan-dorongan, kehendak
kolektif, halusinasi individual, dan fantasi kolektif masyarakat (kelompok).
Jika dilihat secara cermat, metode Arkoun tersebut bertolak-belakang
dengan metode sejarah intelektual yang berorientasi pada konsep a priori yang
meyakini bahwa perubahan-perubahan gagasan dapat dipahami pada taraf
gagasan-gagasan (sejarah intelektual imanen). Sebaliknya, metode Arkoun
tampak bersesuaian dengan sosiologi pengetahuan yang menganggap bahwa
80
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 347
Mohammed Arkoun, Op. Cit., h. 211
82
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 210
81
46
kekuatan-kekuatan yang hidup dan sikap-sikap aktual yang mendasari sikap-sikap
teoretis sama sekali bukan merupakan sesuatu yang individual belaka. Kekuatankekuatan dan sikap-sikap itu lebih-lebih muncul dari tujuan-tujuan kolektif suatu
kelompok yang mendasari pemikiran individu. Individu hanyalah berpartisipasi di
dalam pandangan yang telah digariskan sebelumnya.
Dengan demikian, semakin jelaslah tesis bahwa pengetahuan tidak bisa
dimengerti secara betul selama kaitannya dengan kehidupan atau dengan
implikasi-implikasi sosial kehidupan manusia tidak diperhitungkan.83 Karl
Mannheim mengatakan:
Dunia diketahui lewat banyak orientasi yang berbeda-beda karena ada
banyak kecenderungan pemikiran yang bersamaan dan saling bertentangan
(tidak sama sekali nilai yang sama) yang bersaing satu sama lain dengan
berbagai penafsiran mereka tentang pengalaman '
bersama'
. Dengan
demikian, petunjuk untuk konflik ini tidak dapat ditemukan pada '
objek
pada dirinya sendiri'(jika demikian, mustahillah memahami mengapa
objek dapat tampak dalam sedemikian banyak pembiasan), melainkan di
dalam harapan-harapan, tujuan-tujuan, dorongan-dorongan yang sangat
berbeda-beda yang muncul keluar dari pengalaman.84
Atas
dasar
prinsip
tersebut,
Mannheim
menghendaki
sosiologi
pengetahuan sebagai sebuah metode tidak memisahkan cara-cara pemikiran yang
konkret ada dari konteks tindakan kolektif. Dalam pandangan sosiologi
pengetahuan, manusia dilihat sebagai kelompok-kelompok yang menghadapi
objek-objek dunia ini dari taraf abstrak pikiran dan bertindak dengan dan terhadap
kelompok-kelompok yang lain yang tertata secara berbeda-beda, dan sambil
melakukan semua itu, mereka berpikir dengan dan terhadap yang lain. Orang83
Lihat Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Kanisius,
Yogyakarta, 1991, h. 292
84
Karl Mannheim, Ibid., h. 292-3
47
orang ini yang terikat bersama ke dalam kelompok-kelompok, berjuang keras
menurut ciri dan posisi kelompok-kelompok mereka untuk mengubah dunia dan
masyarakat atau berusaha memeliharanya tetap pada kondisi yang telah ada. Arah
dari kegiatan kolektif inilah yang menghasilkan kompleks pemikiran yang
memberi petunjuk bagi munculnya permasalahan, konsep-konsep dan bentukbentuk pemikiran mereka.85
Mannheim menganggap bahwa pertentangan antar kelompok tersebut
sebagai kompetisi yang pada dirinya merupakan sebuah kasus yang mewakili
tempat proses-proses ekstra-teoretis mempengaruhi kemunculan dan arah
perkembangan pengetahuan. Kata Mannheim:
Kompetisi tidak hanya mengontrol ekonomi, tidak sekedar arus peristiwaperistiwa sosial dan politis, melainkan juga memberi daya penggerak di
balik berbagai penafsiran tentang dunia yang bila latar belakng sosial
penafsiran-penafsiran itu disingkapkan, menyatakan diri sebagai ekspresiekspresi intelektual dari kelompok-kelompok yang bertentangan yang
memperebutkan kekuasaan.86
"Kompetisi" yang disebut Karl Mannheim sebagai tempat terjadinya
proses-proses ekstra-teoretis yang mempengaruhi kemunculan dan arah
perkembangan pengetahuan, dapat dibandingkan dengan konsep Foucault tentang
"rasionalitas diskursif", yaitu otoritas yang menentukan pilihan teoretis yang
dikarakterisasi oleh posisi-posisi kenikmatan (desire) dalam hubungan yang
memungkinkan wacana.87 Foucault mengatakan:
Tak ada buku yang eksis dengan sendirinya; ia bisa eksis karena adanya
relasi dengan dan bergantung pada kesatuan buku yang lain; inilah inti
85
Karl Mannheim, Ibid., h. 4
Karl Mannheim, Ibid., h. 292
87
Lihat Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, Great Britain: Tavistock Publications
Limited, 1972, h. 64-70.
86
48
jaringannya, yang isinya suatu sistem indikasi yang memberikan tekanan
baik eksplisit maupun implisit terhadap buku, teks, kalimat, dan lainlain.88
Lebih jauh, "kompetisi" yang dimaksudkan Mannheim sebagai tempat
proses-proses ekstra-teoretis juga dapat dipahami dengan istilah Foucault "ruang
kebebasan konkret", yaitu kemungkinan transformasi bagi cara kerja intelektual,
apa yang dibutuhkan akal sebagai kebutuhan, atau apa yang ditawarkan sebagai
bentuk-bentuk rasionalitas yang disadari sebagai keharusan mengada. Tapi
Foucault mengingatkan bahwa semua bentuk rasionalitas ini – ditempatkan dalam
proses kerja dominasi – melarikan analisis di dalam dirinya sendiri.89 Singkatnya,
menurut Foucault, dalam pengetahuan (connaissance) atau teknik, di sana
terdapat pertukaran: transmisi, perpindahan, dan campur tangan. Pada saat yang
sama, terdapat beragam perjanjian yang saling berhubungan.90
Dari sinilah lahirnya konsep Foucault tentang "kekuasaan" dalam
hubungannya dengan "rasionalitas diskursif" yang ditempatkan pada posisi kerja
dominasi. Meskipun terdapat ragam perjanjian yang saling berhubungan dalam
tiga '
kerajaan'pertukaran yang saling berkaitan, itu bukanlah isomorfisme. Oleh
karena itu, Foucault mengingatkan:
Ketika saya membahas hubungan kekuasaan dari bentuk rasionalitas, yang
dapat mengatur dan meregulasikan mereka, saya tidak merujuk pada
Kekuasaan – dengan huruf K kapital – yang dominan dan mengesankan
rasionalitasnya di atas totalitas struktur sosial. Nyatanya memang ada
88
Michel Foucault, "Arkeologi Pengetahuan: Tanggapan atas Lingkaran Epistemologi", dalam
Paul Rabinow (ed.), Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Foucault, Jalasutra,
Yogyakarta, 2002, h. 128
89
Michel Foucault, "Strukturalisme dan Post-Strukturalisme", dalam Paul Rabinow (ed.), Ibid., h.
338-9
90
Michel Foucault, “Strukturalisme dan Post-Strukturalisme”, dalam Paul Rabinow (ed.), Ibid., h.
340
49
hubungan kekuasaan. Hubungan yang beragam; hubungan itu mempunyai
bentuk yang berbeda-beda, mereka dapat berperan dalam hubungan
keluarga, atau dalam suatu institusi atau suatu administrasi, atau antara
satu kelas yang mendominasi dan kelas yang didominasi. Hubunganhubungan kekuasaan memiliki bentuk rasionalitas yang spesifik, bentukbentuk yang serupa dengan mereka, dan sebagainya. Ini adalah suatu
medan analisis, bukan suatu referensi bagi segala kesementaraan yang
unik.91
Foucault memberi ilustrasi yang bagus tentang akibat dari praktek
kekuasaan terhadap posisi yang didominasi: ketika psikiatri mendefinisikan
konsep modern tentang alienasi mental, kemudian konsep ini mengubah praktek
penanganan orang gila. Konsepsi itu lalu diterjemahkan melalui praktek-praktek
baru seperti didirikannya rumah sakit yang tertutup atau tempat pengasingan
untuk penderita penyakit tersebut. “Orang gila” merupakan hasil pendefinisian
pengetahuan-kekuasaan, atau akibat posisi yang didominasi.92
Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai yang melekat pada
kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana (diskursus), kehendak untuk
mengetahui
terumus
dalam
pengetahuan.
Bahasa
menjadi
alat
untuk
mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk
pengetahuan, karena ilmu-ilmu terumus dalam bentuk pernyataan-pernyataan.
Kekuasaan-pengetahuan terkonsentrasi di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah.
Oleh karena itu, semua masyarakat berusaha menyalurkan, mengontrol, dan
mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah. Wacana macam ini
dianggap mempunyai otoritas, karena kriteria keilmiahan seakan-akan mandiri
91
Michel Foucault, "Strukturalisme dan Post-Strukturalisme", dalam Paul Rabinow (ed.), Ibid., h.
341
92
Melalui Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 220.
50
terhadap subyek: wacana ilmiah memiliki kekuasaan yang bisa mengklaim dirinya
benar. Padahal, klaim ini merupakan bagian dari strategi kekuasaan.93
Di antara tujuan penting kekuasaan adalah memberi struktur-struktur
kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Orang hanya bisa ambil bagian atau
menderita kekuasaan melalui jaringan-jaringan atau gugusan-gugusan kekuasaan
lokal yang tersebar (micro-pouvoirs) seperti keluarga, sekolah, barak militer,
pabrik, penjara, asrama. Dari situ kelihatan bahwa kekuasaan memberi struktur
kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat dan selalu rentan terhadap
perubahan. Struktur-struktur kegiatan itu disebut institusionalisasi kekuasaan,
yaitu keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan-aturan sosial yang
melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Tentu saja
pengetahuan yang menyatakan diri obyektif berperan dalam pelanggengan itu.94
Dan salah satu lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat
adalah agama. Lembaga ini tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik
kekuasaan normatif dan disipliner. Agama mengatur individu dan masyarakat
melalui teknik penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian, maupun ritus.
Dengan teknik itu akan dihasilkan identitas, yang akan memudahkan
mendapatkan kepatuhan dari pemeluknya. Teknik penyeragaman juga berfungsi
untuk menafikan mereka yang bukan pengikut.95
Hubungan pengetahuan-kekuasaan itu, dalam konteks pemikiran agama,
ditegaskan oleh Arkoun sebagai berikut:
93
Melalui Haryatmoko, Ibid., h. 225-226.
Melalui Haryatmoko, Ibid., h. 224.
95
Melalui Haryatmoko, Ibid., h. 230.
94
51
Bahwa pemikiran berdasarkan kitab/tulisanlah yang menetapkan
pandangan-pandangan, batasan-batasan, pembagian-pembagian, dan
sistem realisasinya terhadap masyarakat dengan medium domain
fungsional yang bekerja dan sangat efektif di antara empat kekuatan yang
ada. Dan dengan kekuatan-kekuatan tersebut akan berakhir kepada
hegemoni terhadap seluruh bidang kemasyarakatan (yaitu kepada seluruh
anggota masyarakat) Kekuatan-kekuatan ini adalah: Negara,
Tulisan/Kitab, Peradaban elit (yaitu peradaban baku/resmi bagi orang yang
mengerti baca-tulis), dan ortodoksi keagamaan.96
Kesimpulannya, jika pengetahuan adalah implikasi kekuasaan dan akibat
dari kekuasaan adalah adanya posisi yang didominasi, sementara pengetahuan
memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan, maka pengetahuan
adalah teknologi/strategi kekuasaan untuk menjalankan operasi dominasinya.
Operasi dominasi itu menjadi “tersembunyi” secara “teknologis” atau “strategis”,
karena pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada
subyek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subyek tertentu. Kriteria
pengetahuan “yang ilmiah” seakan-akan mandiri terhadap subyek. Pendek kata,
pengetahuan adalah ideologis: bukan hanya yang berhubungan dengan akibat
dominasi golongan/kelas, bahkan lebih menjadi sumber dan pembenaran dominasi
dalam masyarakat.
4. Kritik Pengetahuan
Proyek Arkoun "rethinking Islam" menyerupai proyek Horkheimer yang ingin
sekali membuka selubung ‘ideologis’ dari teori-teori positivistis yang membeku
dalam Teori Tradisional. Horkheimer menunjukkan adanya tiga asumsi dasar
yang membuat Teori Tradisional menjadi ideologi dalam arti yang ketat. Pertama,
96
Mohammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik, Al Fikr, Surabaya, 1992, h. 123
52
Teori Tradisional mengandaikan bahwa pengetahuan manusia tidak menyejarah
(a-historis) dan karenanya teori-teori yang dihasilkan juga a-historis dan a-sosial.
Apa yang telah lama dicita-citakan dan seolah-olah telah dicapai di dalam Teori
Tradisional
adalah
bentuk
pengetahuan
yang
bebas
dari
kepentingan
(disinterested). Kedua, Teori Tradisional beranggapan bahwa pengetahuan
bersifat netral, maka teori-teori yang dihasilkannya pun bersifat netral. Teori
adalah deskripsi murni tentang fakta, yang merupakan ‘pengetahuan demi
pengetahuan’. Ketiga, bahwa teori dapat dipisahkan dari praxis, proses penelitian
dari tindakan-tindakan etis, dan pengetahuan dari kepentingan.97
Di tangan Habermas, proyek Horkheimer menjadi Teori Kritik yang
dimanfaatkan untuk memeriksa syarat-syarat kemungkinan bagi pengetahuan dan
praxis manusia, yaitu kepentingan-kepentingan yang mengarahkan pengetahuan.
Pertama, manusia sebagai spesies memiliki kepentingan teknis untuk mengontrol
ligkungan eksternalnya melalui perantaraan kerja
dan kepentingan ini
mewujudkan dirinya di dalam pengetahuan informatif yang secara metodis
disistematisasikan menjadi ilmu-ilmu empiris-analitis. Kedua, manusia sebagai
spesies memiliki kepentingan praktis untuk menjalin saling pemahaman timbalbalik melalui perantaraan bahasa dan kepentingan ini mewujudkan dirinya di
dalam pengetahuan interpretatif yang disistematisasikan secara metodis menjadi
ilmu-ilmu
historis-hermeneutis.
Ketiga,
manusia
memiliki
kepentingan
emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan-hambatan ideologis melalui
perantaraan kekuasaan dan kepentingan ini mewujudkan dirinya dalam
97
Melalui Francisco Budi Hardiman, Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan,
Yogyakarta, Kanisius, 1990, h. 56
53
pengetahuan analitis yang disistematisasikan secara metodis menjadi ilmu-ilmu
sosial yang kritis atau kritik-ideologi.98
5. Ideologi
Ideologi adalah satu dari sekian banyak konsep yang paling ekuivokal
(meragukan) dan elusif (sukar ditangkap), yang terdapat dalam ilmu-ilmu
pengetahuan sosial; tidak hanya karena beragamnya pendekatan teoretis yang
menunjukkan arti dan fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi karena ideologi
adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik dan digunakan secara luas
dalam kehidupan sehari-hari dengan makna yang beragam.99
Istilah ideologi mula-mula digunakan oleh Destertt de Tracy pada akhir
abad ke-18, dan dikembangkan penuh sebagai konsep selama abad ke-19. Tetapi
perenungan yang lebih dalam (preokupasi) dengan beberapa persoalan yang
dimunculkan oleh pengertian ideologi telah dimulai jauh lebih awal. Ada
fenomena yang mengaitkan antara legitimasi intelektual dari dominasi sosial
dengan berbagai sumber penyimpangan mental dalam pengetahuan realita selama
ada masyarakat-masyarakat golongan. Dalam pengertian ini ideologi bukan
fenomena baru dalam sejarah umat manusia. Meskipun demikian analisa yang
menarik dan studi yang sistematis berkaitan dengan fenomena ini baru muncul
dalam zaman modern setelah disintegrasi masyarakat Barat pada Abad
Pertengahan. Dalam konteks zaman modern, persoalan yang timbul, yang
selanjutnya berasosiasi dengan konsep ideologi, erat hubungannya dengan
98
99
Melalui Francisco Budi Hardiman, Ibid., h. 192-193
Jorge Larrain, Konsep Ideologi, Yogyakarta: LKPSM, 1996, h. 1
54
perjuangan pembebasan kaum borjuis dari belenggu aristokrasi kaum feodal dan
dengan sikap pikiran modern baru yang kritis untuk menjalankan kekuasaan. 100
Ada beberapa pertanyaan yang menjadi sentral perdebatan mengenai
konsep ideologi. Pertama, apakah ideologi mempunyai arti negatif atau positif. Di
satu pihak, ideologi dapat dimengerti dalam istilah-istilah yang sungguh negatif,
sebagai konsep kritis yang berarti bentuk kesadaran palsu atau kebutuhan untuk
melakukan penipuan (desepsi), maksudnya bagaimana memutar-balikkan
pemahaman orang mengenai realitas sosial. Nilai kognitif dari ide-ide yang
dipengaruhi oleh ideologi, selanjutnya, dipertanyakan. Di pihak lain, konsep
ideologi dapat dimengerti sebagai istilah yang positif, sebagai ekspresi dari sudut
pandang mengenai kelas. Sampai tingkat ini orang dapat berbicara mengenai
“ideologi”, yang secara umum adalah beberapa pendapat, teori dan sikap yang
dibentuk dalam kelas (golongan) untuk membela dan memajukan kepentingankepentingannya.
Kemudian,
nilai
kognitif
dari
ide-ide
ideologis
itu
dikesampingkan sebagai suatu persoalan yang berbeda.101
Kedua, apakah ideologi mempunyai sifat yang benar-benar subyektif dan
memiliki watak psikologis atau sebaliknya, seluruhnya tergantung pada faktorfaktor obyektif. Jika subyektif, ideologi dipahami sebagai perubahan bentuk
kesadaran, yang entah bagaimana tidak dapat mengerti realita seperti adanya. Jika
obyektif, ideologi muncul sebagai penipuan yang disebabkan oleh realita itu
sendiri, bukan subyek itu yang memutar-balikkan realita, tetapi realita itu sendiri
yang menipu subyek. Selagi pandangan subyektif menekankan peranan individu,
100
101
Jorge Larrain, Ibid, h. 7-8
Jorge Larrain, Ibid., h. 2
55
golongan, atau partai dalam produksi ideologi, maka pandangan obyektif
menganggap ideologi sebagai pengisian struktur dasar masyarakat.102
Ketiga, apakah ideologi harus dianggap sebagai suatu bentuk fenomena
tertentu di dalam deret luas fenomena struktural, atau apakah ideologi itu sesuai
dan ko-ekstensif dengan seluruh lingkungan kultural yang biasa disebut dengan
“super struktur ideologi”. Yang pertama mengandalkan pada konsep ideologi
yang restriktif (mengekang) karena tidak semua obyek kultural itu akan menjadi
ideologis. Sebaliknya, yang kedua menyamakan ideologi dengan tingkat
masyarakat yang obyektif yang mencakup semua bentuk kesadaran sosial.103
Keempat, bagaimana orang harus melihat berbagai hubungan antara
ideologi dan ilmu pengetahuan. Ideologi dapat dimengerti sebagai antitesis ilmu
pengetahuan yaitu, dapat dipersamakan dengan pre konsepsi atau elemen-elemen
tidak rasional yang mengganggu dan mencegah upaya mencapai kebenaran. Maka
bila mana metode ilmiah diterapkan dengan betul, ideologi diduga menghilang. Di
sisi lain, mungkin sekali ideologi lebih menekankan hal-hal penting dari ilmu
pengetahuan dan ideologi daripada perbedaan-perbedaannya, dengan begitu
ideologi dan ilmu pengetahuan akan mempunyai basis bersama dalam sudut
pandang mengenai golongan yang menciptakannya. Dalam hal ini, ideologi tidak
dapat diatasi oleh ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sendiri dapat menjadi
102
103
Jorge Larrain, Loc. Cit.
Jorge Larrain, Ibid., h. 3
56
ideologis.104 Jika penulis mengingat Foucault, pada sisi terakhir inilah dia
memandang relasi pengetahuan dan ideologi.105
6. Kritik Ideologi
Ada banyak teori yang dimaksudkan sebagai kritik ideologi, hampir sama
banyaknya dengan teori ideologi itu sendiri. Teori-teori yang ada tidak perlu
diulas semuanya di sini. Tetapi, yang penting, harus dipilih teori mana yang dapat
dugunakan untuk melihat dan menganalisa data yang terkait dengan pokok-pokok
persoalan penelitian ini.
Menurut Haryatmoko, “pemikiran Foucault membawa sikap kritis
terhadap para pembacanya, mengajak berpikir secara lain terhadap aktualitas yang
ada. Dia menolong mengurai pencampuradukan antara yang seharusnya dan yang
sesungguhnya terjadi. Dia mempertanyakan norma. Norma bukan sesuatu yang
universal dan bukan tanpa sejarah. Norma atau hukum adalah produk kekuasaan.
Selain itu, Foucault juga mengajak bicara benar, jujur terhadap diri sendiri dan
orang lain. Dengan prosedur menalar yang kritis dan berpikir dengan
menempatkan diri pada posisi orang lain orang belajar bicara benar. Dengan
pengambilan jarak orang menyadari konsekuensinya, membongkar kepentingan,
motivasi atau ilusinya”.106
Seperangkat konsep yang dikemukakan Foucault memang dapat
dimanfaatkan untuk melakukan kritik ideologi terhadap wacana dengan
104
Jorge Larrain, Loc. Cit..
Lihat Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, Great Britain: Tavistock Publications
Limited, 1972, h. 184-6
106
Haryatmoko, Op. Cit., h. 238.
105
57
pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah Foucauldian bermanfaat sebagai kritik
ideologi sejauh untuk mengungkap persoalan-persoalan ideologis yang implisit di
balik wacana seperti; apa motivasi seseorang mewacanakan sesuatu? dan
bagimana hubungan suatu wacana dengan kekuasaan? Selebihnya, pendekatan
Foucauldian tidak memiliki cukup konsep untuk melihat unsur-unsur ideologis
yang eksplisit di dalam teks suatu wacana dan menjelaskannya secara kritis.
Untuk kepentingan yang terakhir itu dibutuhkan model pendekatan sebagaimana
yang dirintis oleh Roland Barthes, yaitu semiotika sebagai kritik ideologi.107
Apalagi – dan ini bukan suatu kebetulan – ada kesamaan pandangan antara
Foucault dan Barthes tentang bahasa, seperti dikemukakan St. Sunardi berikut ini:
Menurut Foucault, yang di kemudian hari diikuti oleh Barthes, masalah
berbicara bukan hanya menyangkut masalah bahasa yang tidak lebih
hanyalah sistem tanda. Masalah berbicara (wacana), katanya, adalah soal
hubungan kekuasaan. Ada kondisi-kondisi sosio-politis (istilahnya:
hubungan kekuasaan) yang membuat orang harus berbicara atau tidak
berbicara, mengucapkan atau tidak mengucapkan bahasa tertentu. Dengan
kata lain narasi kehidupan seseorang bukan hanya soal tanda melainkan
kekuasaan.108
Memang,
bahasa
dan
persoalan
esensial
kehidupan
manusia
(kemanusiaan) adalah tema sentral proyek pemikiran Barthes. Setelah ia
menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan hidupnya untuk melahirkan dan
mengembangkan semiotika, ia ingin membawa semiotika sebagai kekuatan
eksentrik bagi kehidupan manusia sekarang (modern). Katanya: “……saya ingin
107
Foucault dan Roland Barthes memiliki hubungan “persahabatan istimewa”. St. Sunardi dalam
awal bukunya, Semiotika Negativa, menulis kisah singkat yang menarik tentang persahabatan
mereka itu. Lihat St. Sunardi, Semiotika Negativa, Yogyakarta: Kanal, 2002, h. 3-7.
108
St. Sunardi, Ibid., h. 98.
58
sekali menggeser definisi semiotika […] dan menggunakannya sebagai kekuatan
eksentrik bagi modernisme.”109
Semiotika pada intinya adalah teori tentang bahasa, tentang tanda. Supaya
semiotika bermanfaat bagi kehidupan manusia modern, ia harus digunakan secara
kreatif: semiotika harus dapat membuat orang kreatif dalam menggunakan bahasa,
atau paling tidak, dapat membuatnya tidak terikat pada bahasa yang diciptakannya
sendiri.110 Pendek kata, Barthes ingin menjadikan “semiotika plus”, “pasca
semiotika”, atau apapun istilahnya sebagai medium pembebasan manusia dari
“belenggu” bahasa yang diciptakannya sendiri. Terkait dengan pengetahuan dan
wacana sebagai fenomena bahasa, Barthes berharap: “…semiotika akan menjadi
semacam kursi roda, kartu As dalam pengetahuan kontemporer, sebagaimana
tanda merupakan kartu As dalam wacana”.111 Bagaimana caranya?
Mitos sebagai kritik ideologi adalah konsep yang ditawarkan Barthes
untuk proyek tersebut. Barthes berkata: “Mitologi menjadi bagian dari semiotika
sejauh mitologi menjadi ilmu formal, dan menjadi bagian ideologi sejauh mitologi
menyangkut ilmu sejarah, yaitu mempelajari ide-ide-dalam-bentuk (ideas-inform).”112 Dengan definisi ini, mitologi merupakan bidang yang bisa dipelajari
baik oleh semiotika atau ideologi. Dengan definisi ini pula Barthes menunjukkan
bahwa semiotika memang sebuah pendekatan formal (cenderung sinkronis); akan
tetapi ketika semiotika digabungkan dengan ideologi, bisa didapatkan sebuah
pendekatan sinkronis-diakronis tentang ideologi, karena ideologi selalu terkait
109
Melalui St. Sunardi, Ibid., h. 3.
Lihat St. Sunardi, Ibid.. h. 98.
111
Melalui St. Sunardi, Ibid., h. 4.
112
Melalui St. Sunardi, Ibid., h. 100.
110
59
dengan masyarakat tertentu. Barthes memilih budaya media sebagai bidang
penelitian. Ini berarti bahwa kajian Barthes merupakan sebuah kritik atas ideologi
budaya media dengan menggunakan semiotika sebagai pendekatannya. Inti
kerjanya memeriksa bentuk-bentuk mitos yang ditemukan dalam media massa dan
muatan ideologis di dalamnya.113
Akhirnya, harus dinyatakan di sini bahwa untuk melakukan kritik ideologi
terhadap al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, penelitian ini akan memanfaatkan teori kritik
sejarah Foucauldian serta teori mitos Barthesian. Model pendekatan pertama akan
dimanfaatkan untuk menganalisis motivasi di balik al-Ahkâm al-Sulthâniyyah
sebagai sebuah wacana serta bagaimana hubungannya dengan kekuasaan, dan
pendekatan kedua akan dimanfaatkan untuk menganalisis mitos-mitos (wacanawacana mitis) yang eksplisit dalam al-Ahkâm al-Sulthâniyyah.
Model pendekatan yang terakhir ini masih sangat langka dipakai dalam
wilayah studi agama. Karena, seperti dikatakan Arkoun, sesungguhnya agamaagama wahyu, sampai sekarang, menolak untuk mengakui keberadaan
pengetahuan mitos pada teks-teks dasarnya. Demikian juga, positivisme
historisisme dan sekularisme telah melemparkan pengetahuan mitos ke keranjang
sampah atau memasukkannya ke bidang berita dongeng, khurafat (mitologi),
keyakinan-keyakinan magis dan sihir.114
113
114
St. Sunardi, Loc. Cit..
Mohammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik, Al Fikr, Surabaya, 1992, h. 101
60
B. Metode Penelitian
Penelitian ini mengambil obyek ide-ide atau pemikiran al-Mâwardiy, khususnya
yang terdapat dalam buku al-Ahkâm al-Sulthâniyyah. Jadi, penelitian ini
merupakan studi kepustakaan. Sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang akan
dicari jawabannya dalam penelitian ini, data-data akan dikumpulkan dari sumber
kepustakaan yang bersifat primer dan sumber yang bersifat sekunder.
1. Sumber Data
Sumber kepustakaan primer sebagai obyek penggalian data adalah kitab
al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, edisi berbahasa Arab yang diterbitkan oleh Dâr alFikr, Beirut, Lebanon (t.t). Sedangkan data-data dari sumber sekunder diambil
dari literatur-literatur: etika politik Islam, historiografi Islam, ushûl al-fiqh, filsafat
ilmu sosial, dan kritik ideologi.
2. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan tiga persoalan yang telah dirumuskan dan kerangka teoretis yang
terbangun, data-data penelitian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: datadata yang bersifat historis (berupa kondisi sosial, politis, dan budaya yang
menentukan kelahiran al-Ahkâm al-Sulthâniyyah), data-data yang bersifat
metodologis (metodologi yang dipakai al-Mâwardiy untuk merumuskan ideidenya dalam al-Ahkâm al-Sulthâniyyah), dan data-data yang bersifat ideologis.
Khusus mengenai data-data yang bersifat ideologis akan diuangkap sejauh yang
61
berkaitan dengan aspek-aspek historis, metodologis, dan substansi al-Ahkâm alSulthâniyyah.
Untuk menemukan data-data yang bersifat historis, pendekatan teoretis
yang digunakan adalah sosiologi pengetahuan dan arkeologi Foucauldian. Teori
sosiologi pengetahuan dan arkeologi pengetahuan digunakan untuk menemukan
kondisi-kondisi sosiol-historis yang menentukan kelahiran al-Ahkâm alSulthâniyyah, khususnya, wacana etika politik yang berkembang pada saat itu,
dan hubungan antara wacana itu dengan kekuasaan. Kemudian, data-data
metodologis al-Ahkâm al-Sulthâniyyah dicari dengan pendekatan ushûli; yaitu
sistem metodologis yang dipakai oleh para ahli hukum Islam (fuqah ) untuk
merumuskan hukum. Lebih jelasnya, metodologi al-Mâwardiy dalam al-Ahkâm
al-Sulthâniyyah akan dilihat dalam kerangka ‘ilm al-ushûl, khususnya ushûl alfiqh. Terakhir, data-data yang bersifat ideologis akan diungkap melalui
pendekatan konsep ideologi Foucauldian (praktek diskursif: hubungan antar
wacana-pengetahuan dan kekuasaan), dan teori mitos Barthesian.
3. Teknik Analisa Data
Data yang terkumpul akan diolah secara analitis; yaitu penelaahan, penafsiran,
pengelompokan, dan pengorganisasian secara logis-sistematis. Secara umum,
langkah penting yang dilakukan pada tahap ini adalah mencari dan menjelaskan
arti, sebab-akibat, pola-pola konfigurasi, dan proposisi-proposisi,115 berdasarkan
kerangka teoretis yang relevan. Prinsip-prinsip sosiologi pengetahuan dan
115
Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001,
h. 194
62
arkeologi pengetahuan dimanfaatkan untuk menganalisa data-data yang bersifat
historis, prinsip-prinsip ‘ilm al-ushûl dimanfaatkan untuk menganalisa data-data
yang bersifat metodologis, dan prinsip-prinsip kritik ideologi dimanfaatkan untuk
menganalisa data-data yang bersifat ideologis.
Selama analisa berlangsung, dilakukan proses seleksi untuk memilih datadata yang perlu dikembangkan narasinya, menajamkannya, menggolongkannya,
dan mengorganisasikannya sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulankesimpulan finalnya. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan
informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk (gestalt) yang disederhanakan
atau konfigurasi yang mudah dipahami116.
Klimaks dari kegiatan analisis adalah menarik kesimpulan, yang
sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari satu konfigurasi yang utuh.
Kesimpulan akhir ditarik dari proposisi-proposisi awal dan konfigurasikonfigurasi yang telah ditemukan selama proses seleksi, melalui metode berpikir
induksi.
116
Imam Suprayogo, Ibid., h. 195.
63
BAB III
EKSPLORASI TERHADAP AL-MÂWARDIY
DAN AL-’AHKÂM AL-SULTHÂNIYYAH
Pada bab ini, akan dikemukakan data yang terkait dengan masalah penelitian.
Permasalahan utama yang menjadi topik penelitian ini adalah: (1) kondisi sosial,
politik, dan budaya yang menentukan kelahiran al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, (2)
metodologi yang dipakai al-Mâwardiy untuk merumuskan pemikirannya dalam
al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, dan (3) implikasi-implikasi dari kondisi sejarah dan
metodologi tersebut terhadap al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah secara ideologis.
Pada tahap pertama, akan dikemukakan data literer al-’Ahkâm alSulthâniyyah terlebih dahulu, baru kemudian secara berurutan, data-data yang
bersifat historis, metodologis, dan ideologis.
Pada bagian mengenai kandungan isi al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, akan
disajikan rangkuman bab pertama (‘aqd al-’imâmah) saja, yang sebenarnya ditulis
al-Mâwardiy dalam 20 bab. Rangkuman bab pertama ini penting sebagai bahan
refleksi dan sebagai data yang akan dianalisa.
Pada tahap berikutnya, akan dipaparkan data-data historis yang
menentukan kelahiran al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, data-data metodologinya, serta
wacana-wacananya yang bersifat ideologis. Wacana ideologis dipahami sebagai
mitos-mitos yang ada di dalam al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, maupun wacanawacana
yang
dapat
menunjukkan
fungsi
dan
diperhadapkan dengan wacana lain sebagai tandingannya.
kepentingannya
ketika
64
A. Substansi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
"Berkatalah selagi kau mampu, dan berusahalah berkata benar.
Sesungguhnya perkataanmu akan selalu hidup dan diam adalah beku. Jika
kau tak mampu menemukan perkataan benar yang akan kau ucapkan,
maka diammu karena tanpa kebenaran adalah benar."117
Al-Mâwardiy
Al-Mâwardiy adalah fakih (ahli fikih: ilmu hukum Islam), bahkan ia seorang
hakim agung yang menjadi guru besar fikih mazhab Syafii (Muhammad bin ’Idrîs
al-Syâfi‘iy) pada masanya.118 Ia menulis kitab: al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, yang
sesuai namanya, adalah kitab yang berisi hukum tatanegara. Sebagai kitab hukum,
al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah disusun oleh al-Mâwardiy dengan bahasa yang sangat
lugas dan cenderung legal-formalis. Meskipun al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah berisi
hukum tatanegara yang lengkap, tetapi al-Mâwardiy tidak menyebutkan secara
eksplisit definisi-definisi dan konsep-konsep, serta tidak mendiskusikan
pemikiran-pemikiran hukumnya secara filosofis. Rupanya, kecenderungan ini
memang disengaja oleh al-Mâwardiy, karena al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah tidak
dimaksudkannya
sebatas
sebagai
wacana
untuk
memperkaya
hazanah
pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai tatanegara, melainkan
justru sebagai pedoman yuridis-praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan Islam
pada masa itu. Kesan ini didasarkan pada perkataan al-Mâwardiy sendiri dalam
Kata Pengantar al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, sebagai berikut:
Keberadaan hukum tatanegara sangat penting bagi para penguasa
pemerintahan (wullât al-’umûr), sementara selama ini masih bercampur
dengan hukum-hukum yang lain sehingga mereka kesulitan membukanya,
117
Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M, h. 206
Keterangan ini merujuk pada bagian Kata Pengantar yang ditulis oleh Penerbit Dâr al-Fikr
untuk buku al-Mâwardiy, Ibid., h. 4
118
65
apalagi mereka disibukkan dengan masalah-masalah politik dan
pemerintahan. Maka, saya sengaja menyusun hukum tatanegara dalam
kitab tersendiri, karena melaksanakan perintah seseorang yang wajib
dipatuhi, agar ia mengetahui pendapat-pendapat para ahli fikih dalam halhal yang menjadi haknya hingga ia berusaha memperolehnya, serta dalam
hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya hingga ia menunaikannya,
berbuat adil dalam menjaga hak dan menunaikan kewajiban, serta berhatihati dalam mengambil haknya dan memberikan hak yang dimiliki orang
lain.119
Al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah ditulis al-Mâwardiy menjadi 20 bab. Pada bab
pertama dibicarakan masalah kepemimpinan Islam (al-’imâmah), merupakan bab
yang paling pokok (dasar). Al-Mâwardiy mengatakan:
Imamah adalah dasar; karena di atasnyalah, peraturan Agama (qawâ’id almillah) dan kemaslahatan Umat (mashâlih al-’ummah) didirikan;
dengannyalah, urusan [kepentingan] umum (al-’umûr al-‘âmmah)
diselenggarakan; serta darinyalah, dimunculkan kekuasaan-kekuasaan
khusus. Maka, pembahasan hukum mengenai masalah itu harus
didahulukan dan mengakhirkan pembahasan hukum-hukum tatanegara
yang lain.120
Dengan demikian, bab kedua dan seterusnya adalah bab-bab turunan dan
sekaligus rincian dari bab pertama tersebut. Karena keterbatasan tempat di sini,
seluruh bab itu tidak akan disebutkan dengan penjelasan secara rinci. Yang
penting dikemukakan adalah rangkuman bab-bab sebagai data yang diperlukan
untuk ’bahan baku’ analisis pada Bab IV nanti. Selebihnya, untuk memberikan
gambaran umum mengenai isi al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, akan disebutkan
seluruh daftar isinya dalam daftar lampiran laporan penelitian ini.
119
120
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, Beirut: Dâr al-Fikr, tt. h. 3
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
66
1. Asal-usul Imamah dan Fungsinya
Bagi orang beriman, lebih-lebih fakih seperti al-Mâwardiy, Allah adalah sumber
dari segala sesuatu. Allah adalah sumber pengetahuan, ajaran, hukum, kebenaran,
wewenang, kekuasaan, dan seterusnya, Yang mengutus Nabi Muhammad untuk
menunaikan semua kualitas-kualitas itu dalam sejarah hidup manusia, demi
kebaikan hidup mereka. Al-Mâwardiy berkata:
Segala puji bagi Allah Yang telah menampakkan petunjuk-petunjuk
Agama bagi kita, Yang menganugerahi Kitab yang menjelaskan, Yang
memberlakukan hukum halal dan haram untuk kemaslahatan makhluk
semesta, hukum yang menetapkan kaidah-kaidah kebenaran; Dia yang
memandatkan semua itu kepada para pemimpin/penguasa sebagai
pengaturan hidup yang sebaik-baiknya dan peraturan dalam menjalankan
pemerintahannya. Hanya bagi-Nya segala pujian atas semua apa yang
telah Dia tetapkan dan Dia atur. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang
membawa ajaran-Nya dan menunaikannya dengan benar, Nabi
Muhammad, keluarga, serta sahabatnya.121
Kemahabijaksanaan Allah yang transenden mengejawantah dalam sejarah
hidup manusia di muka bumi melalui Kalam dan Tindakan-Nya, yang memantul
dari sosok Muhammad sebagai seorang nabi. Dengan demikian Nabi adalah wakil
utama Allah yang memanifestasikan Kebijaksanaan-Nya bagi manusia, sehingga
dia adalah manusia yang paling berwenang dan berkuasa menentukan jalan
keselamatan (syarî‘ah) bagi mereka.
Nabi adalah manusia, dan dia pasti wafat. Dalam doktrin keimanan Islam,
Muhammad adalah Rasul yang terakhir sampai hari kiamat datang. Wafatnya
Rasul bukanlah akhir dari dunia. Masyarakat Islam (al-’ummah: Umat) yang telah
terbentuk masih harus meniti jalan sejarahnya yang panjang. Lalu, siapakah yang
dapat mengganti wewenang dan kekuasaan Nabi dalam mengatur hidup Umat?
121
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
67
Inilah satu pertanyaan yang ternyata tidak mudah dijawab. Seperti perkataan alSyahrastâni di atas, satu pertanyaan itu merupakan masalah besar yang dihadapi
umat Islam dan memunculkan perselisihan yang paling dahsyat.
Menurut al-Mâwardiy, dalam tubuh Umat harus ditegakkan kepemimpinan
(’imâmah) sebagai ganti (khilâfah) dari fungsi kenabian dalam menjaga
kelangsungan agama dan mengatur (siyâsah) dunia.122 Sehingga dengan demikian,
Imam (al-’imâm) adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk
mengatur urusan agama dan urusan dunia dalam kehidupan Umat pasca Nabi
wafat. Kata ’imâmah atau ’imâm yang sering digunakan al-Mâwardiy sama
artinya dengan kata khilâfah atau khalîfah.123
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan atas manusia
adalah hak Allah dan berasal dari-Nya. Kepemimpinan Allah atas manusia
terjelmakan melalui kenabian Muhammad, dan setelah ia wafat kepemimpinannya
dilanjutkan/diganti oleh institusi yang disebut ’imâmah/khilâfah. Orang yang
memegang jabatan tertinggi dalam institusi itu disebut ’imâm/khalîfah. Fungsi
utama institusi itu adalah melanjutkan fungsi kenabian, yaitu menjaga agama dan
mengatur dunia. Berdasarkan fungsi ini al-Mâwardiy kemudian memerinci tugastugas pokok ’imâm/khalîfah, seperti akan disebutkan di bawah nanti.124
Di tempat lain al-Mâwardiy menyatakan bahwa urusan agama dan urusan
dunia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama, menurut al-
122
Al-Mâwardiy, Ibid, h. 5
Al-Mâwardiy menggunakan semua empat istilah itu di dalam al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah.
’Imâmah sama artinya dengan khilâfah dan ’imâm sama artinya dengan khalîfah.
124
Selanjutnya, penulisan kata-kata: ’imâmah, khilâfah,’imâm, khalîfah digunakan ejaan sesuai
kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu imamah, khilafah, Imam, dan khalifah dengan kandungan
arti tersebut di atas serta arti yang telah dijelaskan pada catatan kaki ke-4/Pendahuluan.
123
68
Mâwardiy, merupakan dasar yang paling kuat untuk membangun kebaikan dunia,
dan ia merupakan satu-satunya landasan untuk mencapai kebaikan akhirat. Oleh
karena itu, lanjut al-Mâwardiy, etika ada dua macam: etika syariat (’adab
syarî‘ah) dan etika politik (’adab siyâsah). Etika syariat adalah kebijakan yang
mengatur bagaimana kewajiban (fardu) dari Allah dapat dilaksanakan, sedangkan
etika politik adalah kebijakan yang mengatur kemakmuran dunia. Kedua-duanya
berpulang pada keadilan pemimpin/penguasa. Keadilan merupakan prasyarat
kejayaan penguasa dan kemakmuran negara. Orang yang meninggalkan
kewajiban dari Allah, maka ia telah menganiaya (zhalama) dirinya sendiri.
Sedangkan orang yang merusak dunia, maka ia telah menganiaya orang lain.125
Dari uraian al-Mâwardiy tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan alMâwardiy negara atau penguasa harus merepresentasikan keadilan, dan untuk itu
negara harus dipimpin oleh penguasa dengan memakai etika syariat dan etika
politik. Al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah dan ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn adalah
sebagian karya Al-Mâwardiy yang berisi dua macam etika yang dikatakannya itu.
2. Landasan Normatif Legalitas Imamah
Karena kekuasaan imamah dipandang bersumber dari Allah, yang berfungsi
sebagai pengganti kenabian dengan tugas pokok menjamin diselenggarakannya
kewajiban-kewajiban agama dan mengatur ketertiban dunia, maka Al-Mâwardiy
mendasarkan kewajiban pengangkatan Imam pada ketentuan syariat, bukan pada
125
Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, h. 96
69
akal.126 Dengan kata lain, landasan normatif bagi legalitas wewenang dan
kekuasaan Imam adalah syariat. Karena itulah, maka semua hal yang terkait
dengan imamah yang meliputi pengangkatan Imam, syarat-syarat kompetensinya,
mekanismenya, sistem pemerintahannya, dan lain-lain harus didasarkan pada
ketentuan-ketentuan syariat. Singkatnya, bahwa imamah adalah kepemimpinan
atas manusia dari syariat, oleh syraiat, dan untuk syariat. Demikianlah, maka
seluruh isi al-’Ahkâm al-Sultâniyyah harus dibaca dengan kerangka sistem
kekuasaan syariat ini.
Tetapi dalam kitab ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn yang lebih memiliki kadar
renungan filosofis, al-Mâwardiy mengemukakan secara panjang lebar mengenai
eksistensi manusia sebagai makhluk Allah yang bersifat lemah secara individu,
yang memiliki perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta
kemampuan, sehingga semua itu mendorong manusia untuk bersatu dalam
kesatuan sosial dan saling membantu.127 Di sisi lain, manusia juga memiliki
keinginan atau aspirasi yang berbeda-beda, kecenderungan untuk menang sendiri
dan egois, mengalahkan lawan-lawannya, dan sebagainya. Dilihat dari dua sisi
eksistensi manusia itu, kebutuhan manusia untuk hidup bersama dan saling
membantu dan dorongan keinginan untuk selalu menang sendiri, maka untuk
menjamin kebaikan kehidupan dunia mutlak diperlukan penguasa yang
berwibawa (sulthân qâhir).128 Dengan perkataan lain, sebab lahirnya wewenang
dan kekuasaan kepemimpinan adalah hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan
bersama, dan akal mereka yang mengajari tentang bagaimana mengadakan ikatan
126
Lihat al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, h. 5
Lihat Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, h. 92-5
128
Lihat Al-Mâwardiy, Ibid, h. 96
127
70
satu sama lain. Lantas, kepemimpinan macam bagaimana yang memiliki
wewenang dan kekuasaan mengatur hajat hidup manusia? Menurut al-Mâwardiy,
jawabannya adalah ; “al-sulthânu fî nafsihî ’imâmun matbû‘un wa fî sîratihî dînun
masyrû‘un”, yaitu penguasa (negara) yang di dalam dirinya terdapat otoritas
kepemimpinan yang diikuti (dipatuhi) dan di dalam penyelenggaraannya terdapat
ketentuan-ketentuan agama yang dijalankan; penguasa yang mampu melindungi
agama dan yang mau menjalankan kekuasaannya sesuai tradisi (sunan) agama dan
hukum-hukumnya. 129
Kesimpulannya, bahwa meskipun al-Mâwardiy juga memperhatikan
aspek-aspek fisik, psikologis, dan sosiologis manusia, dia tetap lebih condong
mendasarkan legalitas wewenang dan kekuasaan negara pada agama. Atau agama
benar-benar dijadikan oleh al-Mâwardiy sebagai landasan normatif legalitas
wewenang dan kekuasaan imamah.
3. Ketentuan Yuridis Pengangkatan Imam/Khalifah
Setelah al-Mâwardiy menetapkan bahwa landasan legalitas kekuasaan imamah
adalah syariat (agama), selanjutnya ia berbicara mengenai ketentuan-ketentuan
yuridis yang terkait dengan pengangkatan Imam.
Menurut Al-Mâwardiy, karena imamah harus (wâjib) ada, maka demikian
juga harus ada seseorang yang berdiri sebagai Imam. Mengenai status kewajiban
pengangkatan seseorang dijadikan Imam, al-Mâwardiy mengatakan statusnya
adalah wâjib kifâyah (fardu kifayah). Artinya, jika ada seorang yang tampil
129
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 97
71
memangku jabatan itu dari kalangan orang-orang yang berkompeten maka
kewajiban itu gugur atas orang lain, seperti berjihad dan mencari ilmu
pengetahuan.130 Tetapi jika tidak ada seorang pun yang tampil menjabatnya, maka
kewajiban ini menjadi tanggung jawab dua kelompok kualifikasi secara hukum,
yaitu: (1) orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai "dewan memilih" (’ahlu
al-’ikhtiyâr), dan (2) orang-orang yang memiliki kualifikasi menjadi Imam (’ahlu
al-’imâmah). Keseluruhan Umat, selain dua kelompok kualifikasi itu, dianggap
tidak bersalah dan tidak berdosa jika terjadi situasi vakum kepemimpinan.131
4. Kualifikasi "Dewan Pemilih" dan Calon Imam
Dalam rangka menciptakan imamah, menurut al-Mâwardiy harus ada "dewan
pemilih" dan calon Imam yang akan dipilih. Kedua-duanya harus memenuhi
kualifikasi yang berbeda:
a. Kualifikasi "Dewan Pemilih"
Keberadaan "dewan pemilih" (dalam teori al-Mâwardiy disebut dengan istilah:
’ahlu al-halli wa al-‘aqdi, atau ’ahlu al-’ikhtiyâr) merupakan konsekuensi dari
penetapan al-Mâwardiy bahwa pemilihan atau pengangkatan Imam hukumnya
fardu kifayah, yaitu kewajiban dari syariat (agama) yang melekat kepada umat
Islam secara kolektif.
Meski kewajiban itu bersifat kolektif, pada prakteknya kewajiban itu
terutama "dibebankan" kepada orang-orang yang memenuhi tiga persyaratan
130
131
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, h. 5
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 5-6
72
kualifikasi yang terakui (muktabar), sebagai berikut: (1) memiliki kredibilitaskeadilan (al-‘adâlah),132 (2) memiliki pengetahuan yang memungkinkan mereka
mengetahui orang yang berhak dan pantas untuk dijadikan Imam dengan syaratsyaratnya, (3) memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan
mereka memilih orang yang paling tepat, mampu dan pandai membuat kebijakan
yang dapat mewujudkan kemaslahatan Umat.133
b. Kualifikasi Calon Imam
Penetapan al-Mâwardiy mengenai kualifikasi calon Imam adalah konsekuensi
yang kedua dari penetapannya bahwa hukum pemilihan atau pengangkatannya
adalah fardu kifayah.
Menurut al-Mâwardiy, seseorang berhak dicalonkan atau mencalonkan
dirinya menjadi Imam, jika dia memenuhi tujuh syarat kualifikasi berikut ini: (1)
memiliki kredibilitas-keadilan, (2) memiliki pengetahuan yang memungkinkannya
melakukan ijtihad dalam menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan
membuat kebijakan hukum, (3) sehat pendengaran, penglihatan, dan pendengaran
sehingga ia dapat menangkap dengan benar apa yang dicercap oleh indranya itu,
(4) sehat anggota-anggota tubuhnya atau tidak ada kekurangan yang
132
Al-Mâwardiy menyatakan persyaratan yang pertama ini dengan ungkapan al-‘adâlatu aljâmi‘atu lisyurûtihâ: "keadilan yang meliputi seluruh aspeknya". Dia tidak menjelaskan pengertian
konsep al-‘adâlah dalam al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah. Dalam kerangka etis-teologis, pengertian
keadilan mencakup kualitas pribadi yang memiliki kejujuran (al-shidq) dan keseimbangan (altawassuth) dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, dalam hubungan dengan Allah maupun
makhluk-Nya. Secara teknis, intensitas keadilan yang ada pada diri seseorang diketahui dari
tingkatan kredibilitasnya. Citra manusia-manusia yang memiliki kualifikasi keadilan dalam
Alquran adalah para nabi dan pengikut-pengikutnya yang setia. Definisi yang lebih kongkrit
tentang al-‘adâlah dikemukakan oleh ’Ibn al-’Azraq, ia mengatakan: "Pokok-pokok keutamaan
ada tiga; bijaksana, berani, dan menjaga harga diri/kepribadian. Ketiga pokok tersebut tersimpul
dalam istilah al-‘adâlah." ’Ibn al-’Azraq, Badâ’i‘u al-Sulk fî Thabâ’i‘i al-Mulk, Vol. 1, h. 102.
133
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 6
73
menghalanginya untuk cepat bergerak, (5) memiliki visi pemikiran yang dapat
menghasilkan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan kemaslahatan mereka, (6)
mempunyai keberanian dan wibawa sehingga mampu menjaga keutuhan wilayah
dan melawan serangan musuh, (7) keturunan (nasab) dari suku Quraisy. Khusus
mengenai kualifikasi yang ketujuh al-Mâwardiy mengemukakan alasan karena
adanya nas tentang hal itu dan telah terwujud ijmak tentang masalah itu.134
5. Mekanisme Pengangkatan Imam
Dalam "negara agama" sebagaimana dikonsepsikan al-Mâwardiy, kedaulatan
adalah milik Tuhan. Maka, wewenang dan kekuasaan pun harus dijalankan sesuai
dengan Kehendak Tuhan. Pengesahan seseorang untuk menjadi Imam juga harus
menggunakan mekanisme yang dipahami dan diyakini sebagai bagian dari ajaran
Tuhan (syariat). Bagi kalangan ortodoks seperti al-Mâwardiy, ketentuan
mekanisme itu tidak cukup deserahkan kepada akal bebas manusia, meskipun
tidak ada nas dalam Alquran maupun sunah mengenai hal itu.135 Jalan yang
kemudian ditempuh al-Mâwardiy untuk memperoleh ketentuan mekanisme
pemilihan dan pengangkatan Imam adalah meneliti praktek-praktek dan
kesepakatan-kesepakatan (ijmak) yang dilakukan oleh generasi sebelumnya,
terutama generasi Sahabat.
134
Maksud ijmak dalam ketentuan ini adalah kesepakatan para Sahabat dalam pertemuan di
Saqîfah Banî Sâ’idah untuk memilih khalîfah (pengganti) kepemimpinan Rasul, pada hari setelah
ia wafat. Pada saat itu terjadi pertentangan sengit antara kelompok Sahabat Muhajirin dan Ansar
untuk memperebutkan posisi itu, yang pada akhirnya mereka sepakat (’ajma‘a) bahwa yang
berhak menjadi imâm/khalîfah adalah dari kalangan Muhajirin suku Quraisy. Lihat Al-Mâwardiy,
Loc. Cit., dan tesis ini pada halaman 3, catatan kaki ke-6.
135
Dalam masalah ini tentu harus dikecualikan pendapat golongan Syî‘ah yang meyakini bahwa
’imâm adalah hak Nabi yang diwariskan kepada ‘Aly bin ’Abî Thâlib dan keturunannya.
74
Menurut al-Mâwardiy, mekanisme pengangkatan Imam ada dua: (a)
Melalui pemilihan "dewan pemilih", dan (b) melalui permandatan (al-‘ahd) oleh
Imam sebelumnya.
a. Sistem Pemilihan
Mekanisme yang dianggap al-Mâwardiy paling legal untuk mengangkat Imam
adalah melalui prosedur pemilihan oleh "dewan pemilih". Ia mengatakan: "Imam
dipilih dan diangkat oleh '
orang-orang yang mempunyai wewenang (kekuasaan)
mengurai dan mengikat masalah'(’ahlu al-halli wa al-‘aqdi)."136 Di banyak
tempat al-Mâwardiy juga orang-orang itu dengan istilah ’ahlu al-’ikhtiyâr
("dewan pemilih") dan ’ahlu al-syûrâ ("dewan permusyawaratan/legislatif").137
Al-Mâwardiy tidak mendiskusikan secara rinci mengenai mekanisme atau
prosedur pembentukan institusi "dewan pemilih" ini, kecuali dia menyebutkan
adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah anggota "dewan
pemilih" sebagai standar legalitas keputusannya. Pertama, kelompok pendapat
yang menyatakan bahwa Imam dipilih oleh "dewan pemilih" dari setiap daerah
"kabupaten" (balad), sehingga keputusan mengenai orang yang dipilih
memperoleh persetujuan secara luas (‘âmm) dan kepemimpinannya diterima oleh
mayoritas. Kedua, kelompok pendapat yang menyatakan bahwa jumlah minimal
"dewan pemilih" adalah lima orang, yang mana salah seorang dari mereka akan
dipilih menjadi Imam dengan kesepakatan empat orang selainnya. Ketiga,
136
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 6-7
Secara teknis ketiga istilah yang dipakai Al-Mâwardiy itu dapat diartikan sebagai orang-orang
yang memiliki kompetensi: orang-orang yang memiliki kewenangan (kekuasaan) untuk
menentukan (memutuskan sesuatu). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2002, h. 584.
137
75
kelompok yang berpendapat bahwa jumlah "dewan pemilih" minimal enam orang
dengan ketentuan yang sama dengan pendapat kedua. Keempat, kelompok yang
berpendapat bahwa jumlah "dewan pemilih" minimal tiga orang dengan ketentuan
sama dengan pendapat kedua dan ketiga. Bahkan kelima, kelompok yang
menyatakan bahwa pemilihan Imam legal oleh hanya satu orang pemilih.138
Dari kelima prosedur tersebut, prosedur yang pertama justru ditolak oleh
Al-Mâwardiy. Menurutnya, Imam tidak harus dipilih oleh "dewan pemilih" dari
setiap daerah "kabupaten" karena baiat terhadap ’Abû Bakr untuk memegang
khilafah dilakukan oleh hanya orang-orang yang hadir di forum Saqîfah, dan hal
itu legal. Pemilihan Imam dengan prosedur yang kedua sampai dengan yang
kelima dianggap legal oleh Al-Mâwardiy, karena hal itu telah dipraktekkan pada
masa al-khulafâ’u al-râsyidûn.139
Jika Imam tidak dipilih melalui prosedur pemilihan oleh "dewan pemilih"
tersebut, maka pengangkatannya dapat dilakukan melalui baiat-mandat oleh Imam
sebelumnya (prosedur permandatan). Cara permandatan merupakan prosedur yang
kedua untuk mengangkat Imam yang dikatakan "legal" oleh Al-Mâwardiy.
b. Sistem Permandatan
Dalam sistem permandatan, Imam diangkat melalui mandat dari Imam
sebelumnya. Al-Mâwardiy mengatakan bahwa sistem permandatan ini boleh
dilakukan sejak sebelumnya dan telah disepakati legalitasnya secara ijmak.140
138
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
140
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 10
139
76
Menurut al-Mâwardiy, legalitas prosedur ini didasarkan pada praktek yang
telah dilakukan oleh kaum Muslimin generasi Sahabat dan mereka tidak
mengingkarinya. Praktek pertama, ’Abû Bakr telah menyerahkan mandat jabatan
Imam kepada ‘Umar bin Khaththâb, kemudian kaum Muslimin mengakui legalitas
jabatan ‘Umar itu. Praktek kedua, ‘Umar bin Khaththâb menyerahkan mandat
jabatan itu kepada "dewan permusyawaratan". Mereka adalah para Sahabat senior
yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang diakui pada masa itu (’a‘yânu al‘ushr) yang berjumlah enam orang, sementara para Sahabat senior yang lain
berada di luar dewan itu. Menurut al-Mâwardiy, kedua praktek tersebut telah
diterima oleh kaum Muslimin secara ijmak (diakui legalitasnya oleh mayoritas
besar kaum Muslimin) sehingga menunjukkan bahwa prosedur permandatan
wewenang/kekuasaan Imam itu legal.141
Dengan demikian, al-Mâwardiy tidak mau berspekulasi sedikitpun
mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain dari apa yang telah dipraktekkan
oleh generasi Sahabat mengenai prosedur pemilihan/pengangkatan Imam.
Kemudian, ada hal penting yang perlu dikemukakan di sini. Al-Mâwardiy
menyebutkan secara rinci terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama
mengenai otoritas "dewan pemilih" ketika berhadapan dengan otoritas Imam
untuk menjatuhkan mandat kepada hanya satu orang (alias orang itu langsung
dibaiat menjadi Imam pelanjut). Menurut sebagian ulama Basra, bahwa
persetujuan "dewan pemilih" terhadap baiat yang dilakukan Imam kepada hanya
satu orang untuk menggantikannya, adalah syarat keabsahan baiat itu sehingga
141
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
77
imamahnya mengikat Umat. Mereka beralasan bahwa baiat imamah adalah hak
Umat, dan baiat Imam terhadap hanya satu orang tidak dapat mengikat Umat
kecuali dengan persetujuan "dewan pemilih" dari mereka.142 Mengenai pendapat
dan argumentasi yang dinyatakan oleh sebagian ulama Basra tersebut alMâwardiy menanggapinya sebagai berikut:
Yang sahih, bahwa baiat Imam terhadap satu orang [untuk
menggantikannya] adalah '
sah' (mun'
aqadah) dan persetujuan '
dewan
pemilih'terhadap hal itu tidak dipandang perlu (ghairu mu‘tabar), karena
baiat imamah [yang diterima] '
Umar [bin Khaththâb dari ’Abû Bakr] tidak
bergantung kepada persetujuan Sahabat, dan kerena Imam lebih berhak
dengan baiat imamah itu sehingga keputusan pilihannya lebih berfungsi
(’amdhâ) dan perkataan baiatnya lebih memiliki kekuatan (’anfadz).143
6. Tugas-Tugas Pokok Imam
Wewenang/kekuasaan imamah diimplementasikan al-Mâwardiy ke dalam tugastugas umum yang menjadi tanggung jawab Imam, yang menurutnya ada sepuluh
hal sebagai berikut:
a. Menjaga ajaran agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan
dan sesuai pemahaman yang telah disepakati oleh generasi terdahulu umat
Islam. Jika muncul orang yang membawakan paham baru (mubtadi’) atau
pembuat kesesatan, Imam berkewajiban untuk menjelaskan argumen (hujah)
kebenaran baginya dan menjelaskan pemahaman yang benar kepadanya.
Imam juga harus menuntutnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang
142
143
Lihat Al-Mâwardiy, Ibid., h. 10.
Lihat Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
78
ada, sehingga ajaran agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang
salah.144
b. Menegakkan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan
permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan
oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat aniaya dan tidak
ada orang yang dizalimi yang tidak mampu membela dirinya.
c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga mereka dapat hidup tenang dan
bepergian dengan aman tanpa rasa takut mengalami penipuan dan ancaman
atas diri dan hartanya.
d. Menjalankan hukum pidana (hadd) sehingga larangan-larangan Allah tidak
ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang
dan binasa.
e. Menjaga perbatasan negara dengan peralatan dan kekuatan yang memadai
untuk mempertahankan negara dari serangan kekuatan asing sehingga
menjamin keamanan warga Muslimin dan kalangan kâfir mu‘ahhad ("non
Muslim yang terikat perjanjian damai").
f. Melaksanakan perang agama (jihâd) melawan pihak yang menentang Islam
setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga mereka masuk Islam atau
masuk dalam jaminan Islam (dzimmah). Dengan demikian, usaha untuk
144
Tidak diragukan, ini adalah kewajiban Imam yang paling utama dan signifikansi negara di
bawah syariat.
79
menjunjung tinggi agama Allah di atas agama-agama seluruhnya dapat
diwujudkan.145
g. Menarik fai’146 dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh syariat berupa nas ataupun hasil-hasil ijtihad, tanpa rasa takut
dan usaha-usaha untuk memeras dan menindas.
h. Menentukan gaji pegawai negeri dan besarnya subsidi (‘athâ’) kepada rakyat
dan pihak-pihak yang mempunyai bagian dari kas perbendaharaan negara
(bait al-mâl), tanpa melebihi atau mengurangi, dan memberikannya pada
waktunya.
i. Mengangkat pejabat-pejabat yang kredibel dan kompeten untuk membantunya
dalam menunaikan amanat (wewenang dan kekuasaan) yang ia pegang,
sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dalam pengaturan
orang-orang yang terpercaya.
j. Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti
jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik negara dengan
baik dan menjaga Agama. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang
lain, sementara ia sendiri menikmati kelezatan hidup duniawi atau
menenggelamkan diri dalam kehidupan rohani, karena orang yang terpercaya
145
Dengan demikian, seorang Imam terikat dengan perjanjian Allah untuk membangun supremasi
Islam lebih dari semua agama dan kepercayaan yang lain. Lihat komentar Qamaruddin Khan, AlMawardi’s Theory of the State, h. 37
146
Fai’ adalah harta yang didapatkan dari kaum non Muslim tanpa melalui perang. Harta ini
berbeda sifat dan hukumnya dengan zakat. Lihat Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h.
128. Ada banyak macam sifat harta dan status hukumnya yang diperoleh negara dari orang-orang
non Muslim. Keterangan rinci mengenai hal ini dapat dibaca bab XII dan seterusnya buku AlMâwardiy tersebut atau umumnya buku-buku fikih dalam Pasal Jihâd.
80
dapat saja menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah
menjadi penipu.147
Dalam keterangan akhir, al-Mâwardiy memperingatkan bahwa meskipun
Imam memiliki wewenang/kekuasaan dan hak memerintah sesuai jabatannya
berdasarkan legitimasi hukum agama, ia harus sadar bahwa wewenang dan
kekuasaannya itu merupakan bagian dari hak-hak politik setiap rakyat (kulli
mustar‘in). Untuk itu al-Mâwardiy mengutip sabda Nabi: “Setiap kamu adalah
penguasa dan kamu dimintai pertanggungjawaban dari kekuasaanmu itu”.148
Tetapi, al-Mâwardiy tidak menjelaskan bagaimana mekanisme hak politik itu
dapat dijalankan oleh rakyat secara terlembaga untuk melakukan kontrol terhadap
wewenang dan kekuasaan Imam, dan sampai batas mana hak politik itu dapat
dimanfaatkan rakyat untuk melakukan bargaining politik terhadap kekuasaan
Imam.
Kesepuluh fungsi Imam tersebut selain menjelaskan cakupan wewenang
dan kekuasaannya, adalah juga kerangka dasar yang kemudian dipakai alMâwardiy untuk menyusun sistem birokrasi dan administrasi negara.
7. Pemakzulan Imam, Kudeta, dan Pemberontakan
Setelah al-Mâwardiy mendiskusikan kewajiban-kewajiban seorang Imam, ia
memperluas teori imamahnya dengan menunjukkan batas-batas wewenang dan
kekuasaannya.
147
148
Lihat Al-Mâwardiy, Ibid., h. 15-16
Lihat Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
81
Menurut al-Mâwardiy, jika Imam menjalankan fungsinya untuk memenuhi
hak-hak Umat seperti telah disebutkan, maka sungguh dia telah menunaikan hakhak Allah baik yang berkenaan dengan hak-hak Umat maupun kewajibankewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Selama itu, Imam mempunyai
dua hak atas Umat, yaitu: pemerintahannya dipatuhi dan dibantu.149
Namun, masih menurut al-Mâwardiy, Imam dapat saja diberhentikan dari
jabatannya (makzul), jika ia mengalami kecacatan sebagai berikut:
a. Jika terjadi cacat moral yang secara teknis disebut hilangnya ‘adâlah
(kredibilitas-keadilan). Cacat moral yang dimaksud adalah kefasikan (fusq).
Cacat moral ini berkaitan dengan dua bidang: (1) berkaitan dengan perbuatan
anggota tubuh (fisik), yaitu jika Imam melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang Agama, melakukan kemungkaran, mengumbar syahwat, dan
menuruti hawa nafsunya, sehingga menghalangi seseorang dapat diangkat
sebagai Imam atau melanjutkan jabatan itu, dan (2) berkaitan dengan prinsipprinsip keyakinan (’i‘tiqâd), yaitu jika Imam berpegang pada ’i‘itiqâd yang
mentakwil suatu masalah yang kontroversial (syubhât) dengan mengada-ada
sehingga
dia
menghasilkan
pemahaman
yang
menyalahi
kebenaran
(berpegang pada pendapat yang bertentangan dengan prinsip Agama yang
mapan sehingga melakukan bidah).
b. Jika terjadi cacat tubuh atau mengalami keterbatasan-keterbatasan politik yang
menghalangi fungsi kekuasaannya. Mengenai cacat tubuh, dua macam
kecacatan Imam yang dianggap paling fatal adalah karena ia kehilangan akal
149
Al-Mâwardiy, Ibid, h. 17
82
(menjadi gila) dan kehilangan indra penglihat (menjadi buta). Adapun maksud
keterbatasan-keterbatasan
politik
yang
dianggap
menghalangi
fungsi
kekuasaan Imam adalah jika ia dikuasai secara paksa (mahjûr) oleh para
bawahannya atau ia ditawan oleh musuh (kekuatan asing maupun kekuatan
pemberontak).150
Terkait dengan perkataan al-Mâwardiy sendiri bahwa rakyat memiliki hak
politik yang berkenaan dengan imamah, dan ia tidak menjelaskan bagaimana hak
politik rakyat itu dapat difungsikan secara legal dan formal sebagaimana telah
disinggung di atas, teori pemakzulan Imam yang dikemukakan barusan pun tidak
dapat dimanfaatkan sebagai penjelasan yang representatif mengenai pemungsian
hak politik itu. Artinya, teori pemakzulan itu tidak cukup merepresentasikan cara
bagaimana hak politik rakyat itu dapat direalisasikan secara legal dan formal
untuk melakukan kontrol politik bahkan menurunkan Imam dari jabatannya.
Karena meskipun pemakzulan Imam diteorisasikan al-Mâwardiy sebagai tindakan
yang legal dengan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan, ia juga tidak
menyatakan dengan jelas bagaimana mekanisme yang legal dan formal seorang
Imam dapat dimakzul dari jabatannya. Satu-satunya cara yang justru tampak
"disediakan" oleh al-Mâwardiy adalah melalui kudeta dan pemberontakan. AlMâwardiy benar-benar telah "menyelundupkan" teori legalitas kudeta dan
pemberontakan di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, dan dengan demikian teori
itu sekaligus merupakan "prosedur" alternatif untuk mengangkat Imam.
150
Lihat Al-Mâwardiy, Ibid, h. 17-20.
83
8. Sistem Birokrasi Pemerintahan
Teori al-Mâwardiy tentang lingkup wewenang dan kekuasaan Imam adalah
landasan bagi teorinya kemudian tentang sistem birokrasi pemerintahan. Poin
pertama yang mesti dinyatakan di sini adalah bahwa Imam memiliki otoritas
penuh untuk menyusun dan mengawasi sistem birokrasi pemerintahannya dan
memilih para pejabat pembantunya.
Menurut al-Mawardi, sistem birokrasi adalah alat yang dimiliki Imam
untuk menjalankan pemerintahannya. Sistem ini meliputi empat kewenangan yang
masing-masing berbeda dalam sifat dan bidangnya, yaitu:151
1. Pejabat yang kewenangannya umum dalam mengatur masyarakat secara
umum (mencakup seluruh wilayah teritorial negara dan seluruh bidang
kehidupan). Pejabat ini diangkat oleh Imam sebagai wakil atau pembantunya
dalam mengatur urusan-urusan negara tanpa pembatasan. Mereka adalah
perdana menteri (wazîr tafwîdh) dan para menteri eksekutif (wazîr tanfîdz).
2. Pejabat yang kewenangannya umum, namun dalam lingkup teritorial tertentu.
Meraka adalah ’amîr al-’aqâlim (gubernur) dan ’amîr al-bilâd (bupati).
3. Pejabat yang kewenangannya khusus, namun dalam lingkup teritorial umum.
Mereka adalah ’aqdh al-qudhât (hakim agung), naqîb al-juyûsy (panglima
angkatan bersenjata), hâmi al-tsughûr (penjaga perbatasan negara), mustawfi
al-kharâj (pemungut pajak), jalbi al-shadaqât (pengumpul zakat).
4. Pejabat yang kewenangannya terbatas pada bidang tertentu dan dalam lingkup
teritorial tertentu pula. Mereka adalah para qâdhi ’iqlîm (hakim propinsi),
151
Lihat Al-Mâwardiy, Ibid., h. 21
84
qâdhi balâd (hakim kabupaten), penarik pajak dan pemungut zakat di tingkat
provinsi dan kabupaten, panglima daerah, dan sebagainya.
Setiap pejabat dalam sistem birokrasi itu, kata al-Mâwardiy, harus dipilih
dengan memenuhi syarat-syarat kualifikasi dan diangkat dengan prosedurprosedur tertentu yang menentukan validitas pengangkatannya sehingga ia dapat
menduduki jabatannya.152
Bab II sampai dengan bab XX buku al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah berisi
pembahasan yang rinci mengenai sistem birokrasi tersebut dan aturan-aturan
administrasinya. Menurut Qamaruddin Khan, sumbangan al-Mâwardiy yang
paling besar adalah bahwa dia telah memberi paparan yang rinci tentang
bagaimana menggerakkan berokrasi dan menata administrasi pemerintahan.153
Memang, al-Mâwardiy tidak hanya menggambarkan apa yang ada, namun juga
apa yang seharusnya ada. Sesungguhnya, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah memiliki
informasi yang kaya mengenai praktek birokrasi dan administrasi dalam Islam,
yang meliputi bidang ritual agama, politik, sosial, maupun ekonomi. Perpaduan
antara aspek-aspek yang ideal dan yang real di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
menjadikan karya al-Mâwardiy ini populer bagi setiap rezim penguasa Islam dan
generasi yang datang kemudian hingga sekarang.
B. Konteks Historis Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Apa yang dimaksud dengan istilah "konteks historis" adalah kondisi sosial,
politik, dan budaya Islam pada abad X-XI masehi, serta wacana politik Islam yang
152
153
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
Qamaruddin Khan, Al-Mawardi'
s Theory of The State, h. 53.
85
berkembang hingga kurun itu. Kondisi-kondisi tersebut diasumsikan sebagai,
sesuai perspektif teoretis yang telah dibahas di depan, fenomena epistemik yang
menentukan kelahiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Sebelum hal ini dipaparkan, terlebih dahulu akan dikemukakan biografi alMâwardiy secara singkat. Meskipun singkat, diharapkan biografi ini dapat
membantu dalam melakukan analisa nanti, terutama untuk menentukan posisi alMâwardiy dalam struktur sosialnya, dan posisi pemikirannya di antara pemikiranpemikiran yang lain.
1. Riwayat Hidup Al-Mâwardiy
Al-Mâwardiy memiliki nama lengkap ’Abû Hasan ‘Aly bin Habîb Al-Mâwardiy
al-Bashriy al-Baghdâdiy. Ia lahir di Basra, pada tahun 364 H/974 M, ketika kota
ini menjadi salah satu pusat pengajaran dan pendidikan di dunia Muslim.154 Di
154
Kota Bashrah (Basra) dibangun pada tahun 16 H (636 M) pada masa pemerintahan Khalifah
‘Umar bin Khaththâb, setelah wilayah Irak dikuasai oleh tentara Islam di bawah pimpinan Sa‘d bin
’Abî Waqqâs tahun 635. Lokasi pembangunan kota Basra ditetapkan sendiri oleh Khalifah ‘Umar
di daerah Kharîbah yang berdekatan dengan kota pelabuhan Ubullah di teluk Persia. Selama
pemerintahan ‘Umar, Basra menjadi markas tentara Islam. Dalam perkembangannya, setelah
didatangi para pedagang, Basra menjadi pusat perdagangan, baik pada masa al-khulafâ’u alrâsyidûn berikutnya, maupun pada masa dinasti ‘Umâwiyyah dan ‘Abbâsiyyah.
Untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Basra, Khalifah ‘Umar mengirimkan ulama
dari Madinah ke kota itu, antara lain ’Abû Mûsâ al-Asy‘ariy. Sejak itu sampai di masa
pemerintahan ‘Umâwiyyah dan ‘Abbâsiyyah, Basra menjadi salah satu pusat pendidikan di dunia
Islam. Para siswa berdatangan ke kota itu untuk mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan.
Kota itu menjadi tempat bertemunya kebudayaan Persia dan Arab. Ketika ilmu pengetahuan dan
peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dengan berpusat di Bagdad, Basra menjadi pusat
kajian bahasa Arab, sastra dan sains yang penting, serta menjadi tempat berkumpulnya para
pujangga Arab, sehingga kota itu disebut Khazânatu al-‘Arab. Kemajuan Basra di bidang
perdagangan, bahasa, sastra dan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam disebut dalam buku
cerita terkenal Seribu Satu Malam (Alfu Lailatin wa Lailah).
Sebagai kota ilmu pengetahuan, bahasa dan sastra, kota Basra telah melahirkan sejumlah
ulama, tokoh pemikir dan penyair. Ulama yang terkenal antara lain ‘Amr bin al-‘Ulâ, Yûnus bin
Habîb, ‘Isâ bin ‘Amr, al-Khalîl bin Ahmad bin ‘Amr, dan al-’Asma‘iy, serta Sîbawayh. Tokoh
pemikirnya antara lain [’Abû] al-Hasan al-Bashriy dan Wâshil bin ‘Athâ'
. Sedangkan penyairnya
antara lain Farazdaq, Bisyâr bin Bard, Muslim bin Wahîd, dan ’Abû Nuwwâs. Sampai dengan
sekarang, Basra merupakan kota propinsi terbesar kedua setelah Bagdad. Seluruh keterangan ini
86
kota inilah ’Abû Hasan ‘Aly, putra desa yang menjadi tempat sentra penyulingan
air mawar (mâ’u al-ward), memperoleh pendidikan dasarnya. Karena berasal dari
desa tersebut, ’Abû Hasan ‘Aly kemudian dikenal dengan sebutan al-Mâwardiy.
Ia belajar hadis pada al-Hasan bin ‘Aly bin Muhammad al-Jabaly, Muhammad bin
‘Adiy bin Zuhri al-Muqri´iy, Muhammad bin al-Ma'
lâ al-’Uzdiy, dan Muhammad
bin al-Fadhal al-Baghdâdiy. Ia juga belajar fikih pada ’Abi al-Qâsim ‘Abd alWâhid bin Muhammad al-Shaimariy, seorang hakim di Basra saat itu. Kemudian
ia melanjutkan studinya ke kota Bagdad di “kampus” al-Za‘farâniy [Al-Hasan bin
Muhammad bin al-Shabâh Abû ‘Aly al-Za‘farâniy, w. 260 H]. Di kota pusat
peradaban Islam dan pusat pemerintahan dinasti ‘Abbâsiyyah ini, al-Mâwardiy
menajamkan disiplin ilmunya di bidang hadis dan fikih pada seorang guru
bernama ’Abû Hâmid ’Ahmad bin ’Abî Thâhir al-’Isfirâyîniy (w. 406 H).155 AlMâwardiy secara khusus mempersiapkan diri untuk menjadi pejabat negara
sebagai hakim,156 dan kenyataannya kemudian, ia memang diangkat oleh Khalifah
al-Qâ’imbillâh menjadi hakim tingkat wilayah dan bertugas di beberapa daerah.
Selain sebagai hakim, al-Mâwardiy juga diberi jabatan istimewa, yaitu sebagai
duta khusus keliling bagi khalifah dari tahun 381 H. sampai dengan tahun 422
merupakan catatan ensiklopedis, lihat Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994,
hlm. 243-244
155
Lihat pengantar penerbit Dâr al-Fikr untuk, Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, Beirut:
Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M, h. 4. Lihat juga Nur Mufid, “Lembaga-lembaga Politik Islam
Menurut Al-Mâwardiy dalam Bukunya al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah”, Surabaya: Balai Penelitian
IAIN Sunan Ampel, 1998, h. 12.
156
Qamaruddin Khan, Al-Mawardi'
s Theory of the Satate, Lahore: Islamic Faoudation, 1983, h.
20-21
87
H.157 Hingga pada tahun 429 H. Khalifah al-Qâ’imbillâh mengangkatnya menjadi
hakim agung (’aqdh al-qudhât) yang berkedudukan di Naisabur.158
Setelah sekian lama al-Mâwardiy menekuni karirnya sebagai hakim
agung, akhirnya, ia memilih menetap di Bagdad dan menekuni kesibukan baru
sebagai pengajar. Di kota ini pula al-Mâwardiy menghabiskan waktunya untuk
menulis banyak buku, yang mencakup bermacam-macam disiplin seperti: fikih,
hadis, tafsir, bahasa Arab, sastra, administrasi, politik, dan etika.
Namun, sampai sekarang hanya 12 karangan al-Mâwardiy yang telah
diterbitkan dalam bentuk buku, yaitu: 159
1) Al-Hâwy al-Kabîr [Kandungan Besar]; kitab kumpulan hukum fikih Syafiiah
yang terdiri dari 20 jilid
2) Al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah [Hukum-hukum Ketatanegaraan]
3) Nasîhat al-Mulûk [Nasehat untuk Raja-raja]
157
Nur Mufid, Op. Cit., h. 13
Pada tahun 429 H, Khalifah al-Qâ’im bin al-Qâdir Billâh mengumpulkan empat orang ahli
hukum, yang masing-masing mewakili empat mazhab fikih, untuk menyusun sebuah ringkasan
mengenai fatwa hukum. Al-Mâwardiy dipilih mewakili mazhab Syafii dan menulis kitab yang
diberi judul al-’Iqnâ‘, al-Ghuduriy mewakili mazhab Hanafi menulis kitab al-Mukhtashar, sedang
dua kitab lainnya dianggap tidak begitu penting. Khalifah mengakui karya al-Mâwardiy sebagai
yang terbaik, dan untuk menghargai jasanya itu, al-Mâwardiy diangkat sebagai hakim agung
(’aqdh al-Qudhât). Gelar dan jabatan tersebut adalah yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan
pengangkatan terhadap al-Mâwardiy untuk memegang jabatan dengan gelar tersebut
memunculkan keberatan beberapa ahli hukum terkemuka lainnya, seperti ’Abu al-Thayyib alThabariy (seorang hakim waktu itu, w. 460 H, lihat Kihâlah, Mu‘jam al-Mu’allifîn, vol. 8, h. 264)
yang menyatakan bahwa tidak seorang pun berhak menyandang gelar itu kecuali Allah. Namun alMâwardiy mengabaikan berbagai keberatan ini dengan tetap menerima pengangkatannya, dan
menjalankan jabatan dengan gelarnya itu sampai akhir masa hidupnya. Alasan al-Mâwardiy
mempertahankan gelar itu, karena para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar
Mâlik al-Mulûk al-’A‘zham (Rajadiraja yang paling mulia) bagi Sultan Rukn al-Dawlah. Lihat
keterangan ini pada Qamaruddin Khan, Al-Mawardi’s Theory of the State, h. 21. Terdapat
keterangan yang kontradiktif mengenai alasan al-Mâwardiy tersebut, karena dalam kasus gelar
Mâlik al-Mulûk al-’A‘zham, menurut Muhammad bin Kan‘an, al-Mâwardiy tidak
memperbolehkannya. Lihat keterangan di bawah nanti.
159
Lihat pengantar penerbit Dâr al-Fikr untuk, Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, Beirut:
Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M, h. 4-5
158
88
4) Qawânînu al-Wizârâh wa Siyâsatu al-Mulk [Undang-undang Kementerian dan
Politik Kekuasaan]
5) Al-Nukatu wa al-‘Uyûn fî Tafsîri al-Qur’âni al-Karîm. [Masalah-masalah
Pelik dan Pilihan: Tafsir Alquran]
6) Al-’Iqnâ‘ [Kerelaan]; ringkasan al-Hâwy al-Kabîr
7) ’Adab al-Qâdhi [Etika Hakim]
8) ’A’lâm al-Nubuwwah [Tanda-Tanda Kenabian]
9) Tashîl al-Nazhar wa Ta’jîl al-Zhafr [Mempermudah Pandangan dan
Mempercepat Hasil Tujuan]
10) Al-Nahw [Tata Bahasa Arab]
11) Al-’Amtsâl wa al-Hukm [Contoh-contoh (Kasus) dan Hukumnya]
12) ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn [Etika Agama dan Dunia]
Selain 12 buku tersebut, karya-karya al-Mâwardiy, sampai dengan
sekarang, masih dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di sejumlah
perpustakaan atau museum di berbagai negara, terutama di Eropa.160 Di antara
banyak karangan al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah adalah yang
memasyhurkan namanya sejak masa hidupnya hingga sekarang. Dalam sejarah
Islam, karya itu merupakan naskah ilmiah yang pertama tentang ilmu politik dan
administrasi negara.161
160
Komentar singkat tentang keistimewaan buku-buku karya al-Mâwardiy tersebut dan informasi
tempat penyimpanan manuskrip-manuskripnya dapat ditemukan dalam Nur Mufid, Op. Cit., h. 1217
161
Qamaruddin Khan, Al-Mawardi'
s Theory of The State, h. 22
89
Al-Mâwardiy adalah seorang ahli fikih yang sangat terkenal, tokoh
terkemuka paham Suni dan pendukung utama mazhab Syafii,162 serta pejabat
tinggi istana yang besar pengaruhnya pada masa menjelang akhir kekuasaan
dinasti ‘Abbâsiyyah. Di Bagdad pula, akhirnya, al-Mâwardiy wafat pada tahun
450 H/1058 M.163
Kesimpulannya, al-Mâwardiy terlahir di daerah yang menjadi pusat
pemerintahan dan peradaban Islam abad IV H/X M, ia mempelajari berbagai
bidang/disiplin ilmu dan terutama mendalami ilmu fikih, karena ilmu ini memang
dianggap paling penting dan merupakan standar baku untuk melihat kredibilitas
intelektual Muslim di dunia Islam. Karena kemampuan keilmuannya, alMâwardiy dipercaya sebagai salah seorang pejabat tinggi istana yang sangat
berpengaruh. Akhirnya, al-Mâwardiy bukan saja tampil sebagai seorang pejabat
tinggi negara, melainkan juga seorang intelektual yang produktif menulis karyakarya ilmiah yang penting. Sebuah karya yang memiliki pengaruh besar hingga
masa sekarang adalah al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah.
2. Kondisi Sosial dan Politik di Bagdad Abad IV H / X M
162
Lihat, ’Abû Bakr al-Baghdâdiy, Târîkhu al-Baghdâd, Beirut: Dâru al-Turâtsi al-‘Arabiy, 1942,
XIII, h. 102. A. Hasjmy memasukkan al-Mâwardiy ke dalam daftar 30 jajaran ulama pendukung
utama mazhab Syafii pada urutan ke-16, setelah ’Abû Thayyib Thâhir ‘Abdullâh al-Thabariy (w.
460 H). Lihat, A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1393 H/1973 M, h.
330
163
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1990, hlm. 58
90
Sejarah Bagdad sesudah Islam dibagi atas dua periode besar: (1) periode
kekuasaan dinasti ‘Abbâsiyyah selama kurang lebih 500 tahun dan (2) periode
sejak jatuhnya kekuasaan dinasti ‘Abbâsiyyah hingga sekarang.164
Periode pertama dimulai sejak ’Abû Ja‘far al-Manshûr, khalifah kedua
dinasti ‘Abbâsiyyah. Dialah pendiri kota Bagdad yang sebelumnya hanya sebuah
perkampungan kecil. Ia meletakkan batu fondasi pembangunan kota baru itu
sebagai ibu kota pemerintahan Khilafah Islam pada tahun 145 H (762 M).
Pemilihan Bagdad sebagai ibu kota dinasti ‘Abbâsiyyah yang masih muda itu,
utamanya didasarkan pada pertimbangan politis selain geografis. Al-Manshûr
tidak memilih Damaskus, ibu kota kekuasaan dinasti ‘Umâwiyyyah, karena di
kota itu masih banyak pendukung dinasti ‘Umâwiyyah yang baru saja
digulingkannya itu. Demikian pula ia tidak memilih kota Basra dan atau kota
Kufa, karena di dua kota itu banyak pengikut ‘Aly bin ’Abî Thâlib yang menjadi
musuhnya, lagi pula letaknya jauh dari Persia, padahal inti kekuatan yang
mendukung berdirinya dinasti ‘Abbâsiyyah adalah rakyat Persia.165
Semula, para Khalifah ‘Abbâsiyyah memiliki kekuasaan yang kuat dan
penuh. Namun setelah kekuasaan mereka dapat mencapai puncak kejayaan,
berangsur-angsur otoritasnya mulai melemah. Kenyataan terpenting yang
menjadikan kekuasaan khalifah semakin menurun adalah ketika terjadi
penyerbuan oleh tiga amir bersaudara Banî Buwaihiy dari Dailam: ’Ahmad ’Abû
al-Hasan (Mu‘izz al-Dawlah), ’Abû al-Hasan (’Imâd al-Dawlah), dan ’Abû ‘Aly
(Rukn al-Dawlah), atas Bagdad dengan
164
165
membawa pasukan tentara yang
Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 215
Loc. Cit.
91
berjumlah besar, pada tahun 334 H./947 M. Khalifah ‘Abdullâh bin al-Muktafi
Billâh (al-Mustakfi Billâh) yang berkuasa ketika itu tidak mampu berbuat banyak
untuk menghadang kekuatan para pemberontak itu. Akhirnya, Khalifah alMustakfi diturunkan secara paksa dari kursi singgasananya dan dimasukkan ke
dalam penjara hingga akhir hidupnya.166
Banî Buwaihiy bersaudara kemudian berhasil memegang kendali
kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan Islam, termasuk menentukan
orang untuk menduduki posisi sebagai khalifah, yang ketika itu diberikan kepada
Abû al-Qâsim al-Fadhl ibn al-Muqtadir Billâh (bergelar Khalifah al-Muthî‘
Lillâh), sebagai khalifah ke-23 Banî ‘Abbâsiyyah. Mulai saat itu kekuasaan
khalifah sangat lemah, hingga dia sama sekali tidak memiliki kewenangan
mengatur jalannya pemerintahan ataupun mengangkat para menteri. Khalifah
hanya memiliki seorang sekretaris yang bertugas mengurusi kebutuhankebutuhannya. Sebaliknya, kekuasaan sepenuhnya atas kendali pemerintahan
berada di tangan Mu‘izz al-Dawlah ibn Buwaihiy yang memproklamirkan diri
sebagai ’amîr al-’umarâ’ ("amir tertinggi").167 Khalifah al-Muthî‘ menduduki
jabatannya selama 29 tahun 5 bulan. Dia memperoleh kesempatan memegang
jabatan khalifah sedemikian lamanya karena dia rela menerima posisinya itu
sebagai lambang kekuasaan Khilafah Islam belaka. Mu‘izz al-Dawlah sendiri
berhasil mempertahankan jabatannya sebagai ’amîr al-’umarâ’ selama 22 tahun
(334-356 H/945-966 M).168
166
Muhammad bin Ahmad Kan‘an, Târîkhu al-Dawlati al-‘Abbâsiyyah: Khulâshatu Târîkhi ’Ibni
Katsîr, Beirut: Mu’assasatu al-Ma‘ârif, 1419 H/1998 M, h. 270
167
Muhammad bin Ahmad Kan‘an, Ibid., h. 271
168
Joesoef Sou‘yb, Sejarah Daulat Abbasiah, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, h. 172
92
Suatu kenyataan lain yang sangat menonjol pada masa itu adalah: jikalau
Khalifah al-Muthî‘ itu seorang Suni, maka kekuasaan Banî Buwaihiy ditegakkan
di atas supremasi doktrin-doktrin Syî‘ah aliran ’Itsnâ-‘Asyarah. Oleh karena
kekuasaan Banî Buwaihiy, maka perayaan-perayaan Syî‘ah dijadikan perayaan
resmi. Misalnya Perayaan 10 Muharram untuk memperingati peristiwa
terbunuhnya Imam Syî‘ah: Husain bin ‘Aly bin ’Abî Thâlib di Karbela, oleh
tentara Mu‘âwiyah bin ’Abî Sufyân;169 dan perayaan 1 Zulhijah yang disebut
dengan yaum al-ghâdir atau "Hari Raya Ghâdir", yang menurut kepercayaan
dalam lingkungan Syî‘ah, bahwa pada tanggal itulah di suatu tempat bernama
Ghâdir Khum, Nabi Muhammad menjatuhkan wasiat kepada ‘Aly sebagai warismutlak kekuasaan duniawi maupun kekuasaan agama atas kaum Muslimin,
sepeninggalnya kelak.170
Perayaan-perayaan itu dianggap oleh golongan Suni sebagai tindakantindakan berlebihan, aneh, dan bahkan bidah. Namun demikian, mereka tidak
mampu berbuat banyak untuk mencegahnya karena kondisi pendukung Syî‘ah
yang terlampau banyak dan semakin kuat, apalagi posisi mereka didukung penuh
oleh kekuasaan Sultan Mu‘izz al-Dawlah bin Buwaihiy sebagai ’amîr al’umarâ’.171 Kekuasaan Banî Buwaihiy di Bagdad juga mentolerir gerakan Syî‘ah
garis keras, yaitu sayap Râfidhah. Karena merasa mendapat dukungan dan
perlindungan dari Sultan, kelompok Râfidhah banyak menulis pamflet yang berisi
cacian, celaan, dan penghinaan terhadap tokoh-tokoh terdahulu yang dianggap
169
Muhammad bin Ahmad Kan‘an, Op. Cit., h. 285.
Joesoef Soe‘yb, Op. Cit., h. 175. Sejak saat itu, perayaan-perayaan serupa dilaksanakan di
kalangan Syî‘ah dan menjadi tradisi tahunan yang tetap berlangsung hingga sekarang. Lihat
Muhammad bin Kan‘an, Op. Cit., h. 285.
171
Muhammad bin Kan‘an, Loc. Cit.
170
93
musuh besar mereka seperti: Mu‘âwiyah bin ’Abî Sufyân, ’Abû Bakr, ‘Umar bin
Khaththâb, ‘Utsmân bin ‘Affân, dan Marwân bin Hakam, yang ditempelkan di
masjid-masjid. Tokoh-tokoh tersebut, menurut kelompok Râfidhah, memiliki
andil yang besar dalam penyingkiran ’âlu al-bait (keluarga dan keturunan Nabi)
dari hak kekuasaan atas kaum Muslimin.172
Musuh terbesar Syî‘ah, menurut kelompok Râfidhah, adalah Mu‘âwiyah.
Tokoh ini disebut tidak saja sebagai penentang kekuasaan Imam ‘Aly, tetapi juga
sebagai penjagal Imam Hasan dan Imam Husain; dua putra ‘Aly. Mu‘âwiyah
adalah tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab atas seluruh penderitaan
yang dialami ’âlu al-bait sejak masa pemerintahannya sebagai khalifah hingga
khalifah-khalifah berikutnya dari Banî ‘Umâwiyyah. Adapun alasan kelompok
Râfidhah melaknat ’Abû Bakr, karena dia dianggap melakukan gasab
(mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri) atas
hak Fâthimah (puteri Nabi): melaknat ‘Umar bin Khaththâb, karena dia dianggap
menjegal masuknya ‘Abbâs (paman Nabi) untuk duduk dalam jajaran syuriah
yang memiliki kewenangan memilih dan mengangkat khalifah; melaknat
‘Utsmân, karena dia dianggap menjegal ’Abû Dzarr untuk duduk dalam jajaran
dewan tersebut; dan melaknat Marwân bin Hakam, karena dia disebut sebagai
orang yang melarang pemakaman jenazah Hasan bin ‘Aly di sisi kakeknya (Nabi)
dan ibunya (Fâthimah).173
Sultan Mu‘izz al-Dawlah, menurut kaum Suni, mendukung propaganda
kelompok Râfidhah tersebut. Bukti yang diajukan adalah bahwa ketika kaum Suni
172
173
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 283
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 284
94
melaporkan pamflet-pamflet dari kelompok Râfidhah tersebut sebagai aksi protes,
Sultan Mu‘izz menganggapnya sebagai bukan tindak kejahatan, dan karena itu,
dia tidak bereaksi apa-apa untuk merespon aksi unjuk-rasa mereka. Sehingga,
kaum
Suni
menyimpulkan
bahwa
Sultan
Mu‘izz
al-Dawlah
memiliki
kecondongan yang kuat kepada gerakan Syî‘ah-Râfidhah.174
Setelah empat tahun kekuasaan Banî Buwaihiy, persengketaan antara
Syî‘ah dan Suni mulai terjadi.175 Seringkali, keduannya melakukan bentrok
setelah sebelumnya saling menghina, dan menyebabkan banyaknya korban yang
tewas dari kedua belah pihak. Misalnya, bentrok antara Suni dengan Syî‘ah dari
penduduk Karkh yang terjadi pada tahun 346 H,176 bentrok antara Suni dengan
Syî’ah dari sayap Râfidhah dua tahun kemudian,177 dan bentrok terbesar terjadi
pada tahun 349 H. di Bagdad,178 dan pada tahun 351 H. bentrok yang besar juga
pecah di Basra.179 Tampaknya, dari beberapa peristiwa bentrokan tersebut, Suni
sudah mulai melancarkan gerakan tandingan atas hegemoni gerakan Syî‘ah.
Perubahan lain tampak dalam penyebutan gelar bagi penguasa. Ketika
’Abû Syujâ‘ ibn Rukn al-Dawlah ’Abû ‘Aly al-Husain ibn Buwaihiy berkuasa, ia
yang pertama kali memakai gelar syahinsyah, atau mâlik al-mulûk, yang artinya
“Rajadiraja“, yang tentu dimaksudkan bahwa pemilik gelar itu posisinya lebih
tinggi dari orang yang berkedudukan sebagai khalifah.180 Dalam pandangan ulama
Suni semisal Al-Mâwardiy dan ’Ibn Katsîr, menurut kutipan Muhammad bin
174
Muhammad bin Kan‘an, Loc. Cit.
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 274
176
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 279
177
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 280
178
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 281
179
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 284
180
Muhammad bin Kan‘an, Ibid., h. 316
175
95
Kan‘an, pemakaian gelar tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan
dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa gelar seperti itu hanya khusus untuk
Allah.181
Selain perubahan situasi sosial, budaya, dan politik tersebut, Banî
Buwaihiy juga menjadikan Syîraz sebagai ibu kota baru dan sebagai pusat
gerakan Syî‘ah yang menggantikan Bagdad.182 Pada masa itu terjadi perubahan
bentuk ketatanegaraan secara kongkrit. Kekuasaan sentral Banî Buwaihiy sudah
tidak mencapai wilayah-wilayah yang berotonomi penuh, sekalipun satu
persatunya masih mengakui khilâfah Banî ‘Abbâsiyyah di Bagdad. Sifat Dawlah
Islâmiyyah sudah lebih mirip dengan bentuk Persemakmuran (Commonwealth) di
bawah naungan khilafah Banî ‘Abbâsiyyah.183 Pada masa Khalifah ’Abû Bakr
‘Abd al-Karîm (al-Thâ’i‘, berkuasa: 363-381 H/973-991 M) misalnya, Mesir
dikuasai oleh Banî Fâthîmiyyah (terutama al-Mu‘izz al-Fâthimiy) dan mulai
mengembangkan pengaruh kekuasaannya ke Damaskus setelah membangun kota
Kairo.184
Di bawah hegemoni kekuasaan sultan-sultan Banî Buwaihiy, Khalifah
Banî ‘Abbâsiyyah setelah al-Thâ’i‘ secara berurutan dipegang oleh al-Qâdir
Billâh (berkuasa: 381-422 H /991-1030 M) dan al-Qâ’im Biamrillâh (berkuasa:
422-467 H /1030-1074 M). Namun, sejak menjelang wafatnya Sultan Rukn alDawlah bin ‘Aly bin Buwaihiy, pamor kekuasaan Banî Buwaihiy mulai menurun
seiring pembagian wilayah kekuasaannya kepada tiga anak-anaknya: ’Adhdu al181
Lihat Muhammad bin Kan‘an, Loc. Cit., lihat juga, Ibid., h. 363.
Joesoef Sou‘yb, Op. Cit., h. 176.
183
Joesoef Sou‘yb, Ibid, h. 204.
184
Muhammad bin Kan‘an, Op. Cit., h. 300
182
96
Dawlah menguasai Persia, Kirman, dan Arjan; Mu’ayyadu al-Dawlah menguasai
Ray dan Asbihan; Fakhru al-Dawlah menguasai Hamadzan dan Dinora.185
Kekuasaan Banî Buwaihiy mulai melemah setelah tidak ada persatuan di antara
mereka, dan masing-masing berseteru untuk menduduki jabatan tertinggi dengan
kekuasaan terbesar.186
Kekuasaan Banî Buwaihiy yang berlangsung 113 tahun lamanya, berakhir
pada tahun 447 H/1055 M. Kemudian de facto puncak kekuasaan Islam di Bagdad
dipegang oleh dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk berasal dari Turki dan beraliran Suni.
Naiknya kekuasaan dinasti Seljuk adalah atas "undangan" Khalifah al-Qâ’im
untuk melumpuhkan kekuatan Banî Buwaihiy di Bagdad. Sampai dengan tahun
467 H/1074 M, jabatan khalifah masih dipegang oleh Khalifah al-Qâ’im, dan pada
tahun ini pula ia wafat. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena
kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai
oleh orang-orang Syî‘ah.187
Jika masa kekuasaan Banî Buwaihiy memunculkan pemikir-pemikir besar
seperti ’Ibn Shinâ (980-1037 M), al-Bîrûniy (973-1048 M), ’Ibn Miskawayh (9301030 M), dan kelompok studi ’Ikhwân al-Shafâ,188 maka pada masa kekuasaan
dinasti Seljuk yang mendampingi kekuasaan Khalifah al-Qâ’im, ilmu
pengetahuan keagamaan yang beraliran Suni mengalami perkembangan pesat.
185
Muhammad bin Kan’an, Ibid., h. 305
Joesof Sou'
yb, Op. Cit., h. 220
187
Joesof Sou'
yb, Loc. Cit.
188
Menurut Bernard Lewis, kebangkitan dinasti Buwayh yang Syî‘ah di abad ke-10 sesungguhnya
menandai titik balik dalam sejarah peradaban Islam Abad Tengah. Syî‘ah selalu merupakan lahan
subur bagi tradisi intelektual filsafat dan mistisisme yang menyambungkan keterputusan mata
rantai intelektual di dunia Islam ketika filsafat dibabat habis oleh kalangan ortodoksi (Suni,
tradisionalis). Lihat Bernard Lewis, Islam in History: Ideas, People, and Events in Middle East,
(Chicago dan La Salle, Illionis: Open Court Publishing Company, 1993), h. 113
186
97
Nizhâm al-Mulk, perdana menteri pada masa itu, mendirikan Madrasah
Nizhâmiyyah (1067 M) dan Madrasah Hanafiah di Bagdad. Cabang-cabang
Madrasah Nizhâmiyyah didirikan hampir di setiap kota. Madrasah ini menjadi
model bagi perguruan tinggi di kemudian hari. Dari madrasah ini telah lahir
banyak cendekiawan Suni dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara para
cendekiawan yang dilahirkan dan berkembang pada periode ini adalah alZamakhsyâriy, penulis dalam bidang tafsir dan ’ushûl al-dîn (teologi), alQusyairiy dalam bidang tafsir, al-Ghazâliy dalam bidang ilmu kalam dan tasawuf,
dan ‘Umar Khayyâm dalam bidang ilmu perbintangan.189
Dari uraian di atas terlihat bahwa al-Mâwardiy hidup di tengah-tengah
ketegangan politik di mana kejayaan Daulat Banî ‘Abbâsiyyah berangsur-angsur
mengalami kemunduran. Pemikiran al-Mâwardiy pun harus dipahami dalam
konteks sejarah ketegangan doktrinal antara Syî‘ah dan Suni khususnya, yang
telah terbentuk sejak jauh sebelum masa-masa hidupnya dan masih terus
berlangsung.
Al-Mâwardiy
hidup
bersamaan
dengan
periode
panjang
perkembangan terpilah antara Islam Arab dan Islam Persia (Islam mawâly190 pada
umumnya); Islam Suni, Islam Syî‘ah, Islam Khawârij dan lain-lain, yang
menimbulkan pemisahan di antara mereka.
Bahkan jika ditelisik secara lebih mendalam, masing-masing faksi tersebut
sebenarnya bukan merupakan kelompok yang tunggal dan utuh. Masing-masing
faksi memiliki variasi mazhab yang banyak dan kompleks. Perkembangan dan
konfigurasi faksi, selain karena latar belakang politis, juga disebabkan oleh faktor
189
190
Ensiklopedi Islam, h. 215
Istilah Islam mawâly merujuk kepada fenomena Islam di daerah taklukan.
98
geografis, tokoh-tokoh pendukung dan institusi pendidikannya, serta metode
pengembangannya. Bagdad, Basra, dan Khurasan adalah tiga wilayah penting
yang menjadi ruang kontestasi persaingan pengaruh politik, ekonomi, agama, dan
budaya; bukan saja antar tiga faksi besar Islam yaitu Suni, Syî‘i, dan Khâriji;
melainkan juga antar mazhab dalam satu aliran faksi.
Pada abad ke-11 M, Bagdad merupakan kota metropolitan dan
masyarakatnya heterogen. Anggota masyarakat terdiri dari keturunan Arab, Turki,
Iran, dan memiliki profesi yang beragam juga. Dengan penduduk kurang-lebih 1,5
juta jiwa, di antara mereka ada yang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang
taat agama seperti kaum ulama dan para pengikut mereka, dan sebagai lawannya
banyak juga yang kurang taat agama seperti pelacur, penjual minuman keras dan
penyanyi. Bagdad merupakan kota yang kaya budaya, kota di mana ragam budaya
yang dibawa oleh penduduk yang datang dari berbagai daerah bertemu. Selain
penduduk yang beragama Islam, ada juga yang beragama Yahudi, Kristen, dan
Zoroaster.191 Dalam suasana demikian, masing-masing kelompok budaya dan
kepentingan saling berlomba memperkuat diri dan berebut pengaruh dalam rangka
menciptakan situasi dan kondisi kehidupan sebagaimana yang diinginkan.
Dalam faksi Suni misalnya, kelompok pengikut mazhab Hambali (Ahmad
bin Hanbal, lahir di Bagdad tahun 164 H / 780 M), tampil sebagai kelompok
fanatik yang membela ajaran agama dari para penentang dan penyeleweng.
Kelompok ini sangat aktif bergerak melawan orang-orang yang melanggar ajaran
agama Islam. Mereka menganggap perlu untuk melakukan reformasi agama untuk
191
M. Nafis dkk., "Konfigurasi Keagamaan dalam Islam: Studi tentang Sekte dan Madzhab Abad
XI di Daerah Baghdad dan Khurasan”, Balai Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 1996, h. 22
99
mengembalikan masyarakat setelah dikotori oleh perbuatan maksiat. Kelompok
mazhab Hambali yang terorganisir juga aktif melawan kelompok Syî‘ah dan para
penguasa yang mendukungnya, beberapa kali mereka bergerak untuk menentang
kaum Muktazilah, dan setelah Muktazilah tidak lagi kokoh mereka terlibat
pertentangan dengan kelompok Asyariah (pengikut Abû al-Hasan al-’Asy‘âriy alBashriy, seorang ahli ilmu kalâm dan diakui sebagai salah satu tokoh besar
pendiri mazhab Suni, w. 307 H) yang didukung oleh pengikut mazhab Syafii.
Demikianlah, tidak perlu lagi disebutkan secara rinci berbagai struktur
sosial dan praktek budaya serta keagamaan yang berkaitan sejak melemahnya
negara khilafah (334 H=945 M) hingga abad XI M yang disaksikan dan dialami
oleh al-Mâwardiy. Selain alurnya akan panjang dan rumit, tidak akan diperoleh
pelajaran lebih banyak mengenai interaksi antara agama, politik, dan masyarakat.
Yang perlu ditambahkan hanyalah bahwa persekutuan terjadi di antara
negara, ortodoksi yang ditetapkan kaum ulama yang menjadi pengelola agama
(termasuk al-Mâwardiy sehingga ia menyusun al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah), dan
angkatan bersenjata yang dikuasai orang-orang ambisius yang berinisiatif besar
dan seringkali memiliki kebijakan politik berbiaya tinggi. Karena setiap petualang
politik dan militer yang mau berhasil mesti membayar serdadu bayaran dan
memenuhi perbendaharaannya, maka beban perpajakan menjadi terlalu berat.
Bersama dengan sebab-sebab yang lain, pajak yang berat ini langsung
melemahkan kelas pedagang dan kaum profesional, dan memiskinkan kehidupan
rakyat pada umumnya.192
192
Fazlur Rahman, Islam, Pustaka, Bandung, 1994, h. 353
100
3. Sejarah Wacana Politik Islam
"Perselisihan paling dahsyat yang terjadi di antara umat Islam adalah
perselisihan dalam masalah imamah. Kelebatan pedang yang terjadi karena
perselisihan dalam masalah kaidah keagamaan, tidak seperti kelebatannya
karena perselisihan dalam masalah imamah di setiap zaman."193
Al-Syahrastâniy
Ini adalah perkataan-kesaksian seorang ahli sejarah politik Islam ternama, yang
menunjukkan masalah di sekitar kepemimpinan sebagai masalah penting dan
besar. Ia juga merupakan sumber informasi yang penting sejarah terbentuknya
aliran-aliran (firkah) Islam dan pertentangan-pertentangannya, yang masih terus
berkembang dan berlangsung hingga masa sekarang.194
Secara historis, keterkaitan Islam dengan politik dapat dirunut jauh ke
belakang sejak masa awal pendiriannya di Mekah oleh Nabi Muhammad, hingga
masa pemantapannya di Madinah. Kata “keterkaitan” bukan serta-merta berarti
bahwa Islam adalah merupakan risâlah agama-politik bagi manusia.
Pada ruang sejarah di mana fakta Islam muncul dan berkembang,
sebenarnya wacana dan praktek yang menempatkan Islam sebagai agama
sekaligus kekuasaan dapat dilihat kembali secara kritis.
Terlepas dari kontroversi teoretis yang masih berlangsung hingga kini
berkenaan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad, apakah hal itu merupakan
model kepemimpinan risâlah, atau kepemimpinan seperti seorang raja; apakah
aspek-aspek kewenangannya adalah aspek-aspek dari sebuah negara politik atau
193
Al-Syahrastâniy, Al-Milalu wa al-Nihal, Kairo: Thab'
at al-Azhar, vol. 1, h. 20
Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, al-Nazhariyyâtu al-Siyâsiyyâtu al-Islâmiyyât, Kairo: Maktabah Dâr alTurâts, 1979, h. 88
194
101
sebuah kepemimpinan keagamaan; apakah Muhammad hanya seorang rasul atau
dia seorang rasul sekaligus sebagai seorang raja; faktanya, misi Muhammad telah
mewujudkan sebuah entitas politik yang paling kuat di seluruh semenanjung
Arabia. Sebuah entitas politik Islam telah berdiri kokoh di bawah kepemimpinan
Muhammad yang berkedudukan di Madinah. Ketika Muhammad wafat, fakta
Islam sebagai sebuah entitas politik inilah yang kemudian menjadi perhatian dan
incaran orang-orang yang berambisi menggantikan kepemimpinannya, maupun
orang-orang yang ingin membebaskan diri dari pengaruh politik Islam.
Di tangan keempat khalifah (pemimpin pengganti Rasulullah) yang
pertama yang disebut ortodoks (11-41 H=632-661 M), wewenang agama dan
kekuasaan negara menyatu dalam istilah ’imâmah/khilâfah. Mereka melanjutkan
bentuk
hubungan
keduanya
dengan
jalan
menerapkan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka di bawah cahaya Alquran195 (yang diterangi oleh Cahaya
Allah196) dan pelajaran yang mereka terima dari Rasul. Mereka menjamin
kontinuitas negara yang didirikan oleh Rasul sejak 622 M itu, dan mengadakan
perluasannya hingga ke Persia dan Afrika.
Namun, berbagai peristiwa politis-tragis dengan cepat terjadi dan semakin
berlipat ganda. ‘Umar bin Khaththâb, ‘Ustmân bin ‘Affân, dan ‘Aly bin ’Abî
Thâlib adalah khalifah-khalifah ortodoks yang mati terbunuh. Tragedi ini
merupakan sisi kecil peristiwa yang dilatarbelakangi motif-motif politik, dan sisi
yang lebih besar adalah peristiwa dua perang sipil antara Khalifah ‘Aly melawan
pemberontakan ‘Â’isyah (janda Rasul), dan antara Khalifah ‘Aly melawan
195
Fazlu Rahman, Op. Cit., h. 51
Mohammed Arkoun, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), Nalar Islami dan Nalar Modern:
Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Jakarta: INIS, 1994., h. 217
196
102
pemberontakan
Mu‘âwiyah.
Peristiwa-peristiwa
itu
menunjukkan
bahwa
pertaruhan utama dari berbagai tragedi adalah perebutan kekuasaan.
Tindakan-tindakan untuk meraih kekuasaan atau mempertahankannya,
tentu tidak hanya membutuhkan dukungan material dan orang-orang (tentara),
tetapi juga selalu membutuhkan alasan-alasan yang membenarkannya. Mengingat
kekuasaan yang diperebutkan itu seara faktual tidak terlepas dari fenomena Islam,
maka tidak ada alasan pembenaran yang lebih kuat daripada pembenaran atas
nama Islam itu sendiri.
Dapat ditemukan contoh dengan mudah bagaimana alasan-alasan dalam
rangka kekuasaan itu harus ada dengan bentuk sebagai isu Islam, seperti klaim
Ansar yang menginginkan kekuasaan dengan alasan bahwa mereka adalah orangorang yang paling berjasa terhadap Islam;197 klaim orang-orang Quraisy bahwa
kekuasaan adalah hak mereka berdasarkan alasan: Nabi pernah mengatakan
bahwa "pemimpin adalah dari orang Quraisy",198 sebab "manusia mengikuti
orang-orang Quraisy: mereka menjadi Muslim karena keislaman orang-orang
Quraisy, dan mereka menjadi kafir karena kekafiran orang-orang Quraisy";199
klaim pendukung ‘Aly bin ’Abî Thâlib yang berhadap-hadapan dengan
pendukung Khalifah ’Abû Bakr; serta klaim ‘Â’isyah dan para pendukungnya
yang memberontak terhadap Khalifah ‘Aly. Pada kasus yang terakhir, polemik
yang terjadi sangat rumit, karena melibatkan seluruh elemen masyarakat Islam.
197
Lihat ’Abû Bakr al-‘Arâbiy, al-‘Awâshimu min al-Qawâshim, Arab Saudi: Kementerian Urusan
Islam, 1419 H, h. 67
198
Adalah hadis Nabi yang dikutip ’Abû Bakr dalam pidatonya di Saqîfah Banî Sâ‘idah, dapat
ditemukan dalam al-Thayâlîsiy, Musnad, hadis ke-926 dan ke-2133.
199
Adalah hadis lain yang dikutip ’Abû Bakr dalam pidatonya di Saqîfah Banî Sâ‘idah, lihat ’Ibnu
Katsîr, al-Bidâyatu wa al-Nihâyah, Mesir: Dâr Ihyâ’i al-Turâtsi al-‘Araby, 1408 H/1988 M, vol.
6, h. 305
103
Apalagi, inilah situasi untuk pertama kalinya sejak Rasulullah wafat, dua
kelompok kaum Muslim berdiri di pihak yang berlawanan dalam keadaan konflik
bersenjata. Inilah situasi yang digambarkan Rasulullah sebagai kemungkinan yang
paling buruk yang akan dihadapi Islam, fitnah: perang saudara; saat senjata kaum
Muslim diarahkan kepada sesama mereka.200
‘Â’isyah harus menjelaskan ihwal pemberontakannya terhadap Khalifah
‘Aly. Untuk itu, ‘Â’isyah bersama dua sekutunya, Thalhah [ibn ‘Ubaidillâh alTaimiy] dan al-Zubair [ibn al-‘Awwâm], terus berkampanye dan membujuk
orang-orang untuk mendukungnya melawan Khalifah ‘Aly yang dituduh "tidak
adil". Ia menyalahkan Khalifah ‘Aly
karena tidak berusaha menghukum
pembunuh ‘Ustmân (khalifah ketiga), padahal sejumlah orang yang ikut
mengepung ‘Ustmân dan identitasnya diketahui, berada dalam barisan tentara
Khalifah ‘Aly sebagai pimpinan pasukan. Akibat kampanye ‘Â’isyah ini, opini
publik terbagi dua. Sebagian pihak berpandangan bahwa bahaya terbesar yang
mengancam umat Islam bukanlah karena diperintahkan oleh "pemimpin yang
tidak adil", melainkan jika jatuh ke dalam perang saudara. Mereka berpandangan
bahwa kata "islam" berarti "kepatuhan". Jika seorang pemimpin yang sah
ditentang, prinsip yang fundamental di dalam tatanan Islam juga berada dalam
bahaya. Sedang pihak yang lain menilai, bahaya yang lebih serius akan
mengancam negara Islam jika pemimpinnya tidak adil, ketimbang perang saudara.
Seorang Muslim tidak harus mematuhi pemimpinnya jika mereka melihat sang
200
Para ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis fitnah dalam setiap kitab mereka dan dikumpulkan
pada bab tersendiri, al-fitan.
104
pemimpin bertindak tidak adil dan munkar.201 Demikian juga alasan-alasan
pembenaran yang digunakan sehingga terjadi perang sipil kedua: Mu‘âwiyah yang
memberontak terhadap Khalifah ‘Aly yang terkenal dengan Perang Shiffîn.202
Kesimpulannya, ’imâmah/khilâfah yang ditegakkan orang-orang Muslim
pasca Nabi, sebenarnya lebih kental berupa isu politik yang menyeret agama,
daripada isu agama yang murni berdiri sendiri. ’Imâmah/khilâfah sebenarnya
menyerah pada permainan kekuatan sosial, intrik politik, dan strategi dominasi.203
Dan meskipun demikian, ciri yang sama dari semua kekuasaan adalah
membutuhkan dan mempertahankan landasan teoretis dari suatu wewenang yang
dapat mengabsahkannya di mana-mana. Maka mudah dipahami ketika segala
kekuasaan dan dinasti yang silih berganti menyatakan selalu merujuk kepada
Alquran, pengalaman Muhammad, dan tokoh-tokoh pendiri yang ideal. Di sisi
lain, pemikiran Islam (dan semua bentuk pemikiran yang lain) memiliki ciri yang
sama. Selain ia membutuhkan postulat-postulat yang bersifat intelektual, ia juga
sangat bergantung kepada kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain yang
bersifat ekstra-teoretis. Pemikiran Islam pun menyatu dengan kepentingankepentingan politik yang mengarahkannya. Maka setiap orang yang ingin
memahami bentuk pemikiran Islam, ia mesti merunut asal kelompok yang
melahirkannya, yaitu faksi politiko-religius sebagai gerakan-gerakan ideologis.
201
Al-‘Asqalâniy, Fathu al-Bâry, Mesir: al-Mathba‘u al-Bahiyyah, 1928, vol. 13, h. 622. Kisah
yang cukup rinci dapat ditemukan juga dalam ’Abû Bakr al-‘Araby, Op. Cit., h. 132-3
202
Peristiwa Perang Shiffin ini dinarasikan oleh ’Ibnu Muzâhim al-Munqiriy, Waq‘atu Shiffîn,
‘Abdu al-Salâm Muhammad Hârûn (ed.), al-Muassasatu al-‘Arabiyyatu al-Hadîtsât, Cet. Ke-2,
1382 H.
203
Mohammed Arkoun, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), Nalar Islami dan Nalar Modern, h.
220
105
Penjelasan di atas akan membantu pemahaman yang lebih baik tentang
fenomena konflik-konflik sosial-politik kemudian, antara kaum Suni, Syî‘i, dan
Khâriji ketimbang pemahaman yang diberikan oleh penjelasan yang biasa melihat
konflik-konflik tersebut dari segi perbedaan-perbedaan teologis. Dengan
demikian,
pemikiran-pemikiran
Islam
yang
lahir
sejak
pendirian
’imâmah/khilâfah hingga "revolusi ‘Abbâsiyyah", lebih dipahami sebagai
gerakan-gerakan sosial-politik dalam pencarian doktrin yang pasti ketimbang
membicarakannya sebagai kelompok-kelompok keagamaan yang murni.
Dari sudut pandang sosial-historis, dua perang sipil besar yang terjadi pada
masa Khalifah ‘Aly adalah pendulum sejarah yang membuahkan polarisasi Islam
menjadi kelompok-kelompok politiko-religius yang saling bersaing untuk
mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Bahkan sampai sekarang, Islam nyaris
tidak mungkin dibicarakan kecuali dalam bentuk-bentuk polarisasi itu. Kelompok
politiko-religius yang pertama kali memunculkan doktrin adalah Khâriji
(jamaknya, Khawârij). Doktrin mereka terkait dengan peristiwa arbitrasi (tahkîm)
yang disetujui oleh Khalifah ‘Aly setelah ia memperoleh kemenangan terhadap
Mu‘âwiyah dalam perang di Shiffîn pada tahun 37 H / 648 M. Dalam perang itu,
kelompok Khâriji semula merupakan bagian dari barisan pendukung Khalifah
‘Aly, dan karena ia menyetujui arbitrasi, mereka kecewa dan menyatakan keluar
(kharaja) dari barisan Khalifah ‘Aly dan membentuk kelompok tersendiri. Sejak
saat itu sebutan Khawârij ("golongan yang keluar") melekat pada kelompok itu.
Alasan yang mendasari tindakan mereka adalah diktum Alquran bahwa "Tuhan
106
adalah satu-satunya hakim dan pemutus hukum",204 dan oleh karena itu arbitrasi
antara Khalifah ‘Aly dan Mu‘âwiyah tidak dapat dibenarkan. Alasan itu akhirnya
berkembang menjadi sebuah kredo yang khas bagi kelompok ini. Atas dasar kredo
ini pula mereka mengirim pasukan teroris yang bertugas mengeksekusi Khalifah
‘Aly pada tahun 40 H/661 M, dan melakukan gerakan-gerakan politik dengan
cara-cara kekerasan sebagai tindakan "amar makruf nahi mungkar" dalam
melawan penguasa-penguasa dari dinasti ‘Umâwiyyah dan ‘Abbâsiyyah.
Pemberontakan dan penggunaan cara-cara kekerasan mereka anggap sah dan
bahkan harus dilakukan untuk menegakkan "keadilan". Sasaran kekerasan mereka
bukan saja setiap pemerintah yang berkuasa, tetapi juga mayoritas umat Islam
yang moderat (anti kekerasan dalam penyelesaian setiap konflik yang terjadi
antara umat Islam). Mayoritas umat Islam telah mengambil sikap politik yang
moderat sejak kerusuhan-kerusuhan pertama pecah di masa pemerintahan
Khalifah ‘Utsmân bin ‘Affân. Khawârij menuduh mayoritas yang moderat itu
sebagai "pengecut-pengecut yang menyesuaikan diri dengan keadaan".205 Dan di
atas semua itu, Khawârij mengklaim diri sebagai orang-orang yang "berangkat ke
medan perang" untuk membela "hak-hak Tuhan".206
Kelompok kedua yang muncul adalah Syî‘ah. Mereka adalah orang-orang
yang mendukung ‘Aly bin Abî Thâlib secara fanatik. Meskipun keberadaan
mereka telah tampak jelas sejak awal setelah wafat Nabi, pembentukannya
semakin mengeras setelah Khalifah ‘Aly terbunuh. Fanatisme Syî‘ah berdasarkan
kepada satu doktrin bahwa kepemimpinan Islam adalah hak ‘Aly bin Abî
204
Q.S. Al-’An‘âm (6):57, Yûsuf (12):67, dan lain-lain.
Lihat Fazlur Rahman, Islam, h. 244-248
206
Mohammed Arkoun, Pemikiran Arab, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 32
205
107
Thâlib/keturunan Nabi. Ini adalah isu yang paling mendasar dari Syî‘ah dan
mereka menganggapnya sebagai salah satu ketentuan pokok dalam Islam. Lebih
daripada itu, orang-orang Syî‘ah memegang dogma bahwa Imam ‘Aly bin Abî
Thâlib dan para keturunannya yang menjadi Imam penerus adalah orang-orang
istimewa yang "terjaga" (ma‘shûm) dari sifat-sifat tercela dan dosa seperti para
nabi.207
Kelompok ketiga adalah mayoritas umat Islam (majma‘u al-’ummah) yang
moderat.208 Prinsip utama dari golongan ini adalah kolektifitas.209 Kepemimpinan
adalah hak umat Islam, bukan perseorangan yang telah ditentukan secara baku dan
pasti atau melalui pewarisan. Dan demi menjaga kebersamaan dan keutuhan umat
Islam, mereka akan menghindari konflik dan kekerasan.210 Maka, doktrin yang
kemudian berkembang luas dalam golongan ini adalah "pemerintah haruslah
dipatuhi walaupun ia tidak adil", karena "penguasa yang tidak adil adalah lebih
baik daripada kekacauan".211 Golongan ini dikenal dengan sebutan Ahli Sunah
Waljamaah ("orang-orang ortodoks yang menempuh jalan tengah dan
persatuan").212
207
Lihat Fazlur Rahman, Islam, h. 224-248.
Fazlur Rahman, Loc. Cit.
209
Muhammad Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, al-Nazhariyyâtu al-Siyâsiyyâtu al-’Islâmiyyât, Dâr alTurâts, Kairo, 1979, h. 82
210
Muhammad Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Ibid., h. 239
211
Muhammad Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Ibid., h. 352-3
212
Al-Rais menjelaskan bahwa golongan ini semula adalah para cendekiawan (ulama) genarasi
penerus Islam (tâbi'
în) yang ahli tafsir Alquran, ahli hadis, dan ahli fikih yang relatif menjaga
jarak dengan perkembangan politik praktis. Perhatian mereka lebih besar tercurahkan untuk
pembangunan keilmuan Islam daripada terlibat dalam situasi fitnah ["krisis politik"] yang
berakibat perpecahan dan pertumpahan darah. Mereka adalah orang-orang yang setuju dengan
pendapat dan sikap yang moderat dari Sahabat-sahabat semisal ’Abû Mûsâ al-'
’Asy‘ariy. Tokohtokoh besar yang mewarisi pendapat dan sikap moderat itu seperti [’Abû] al-Hasan al-Bashriy
[lahir pada masa Khalifah ‘Umar bin Khaththâb], al-Sya‘biy [lahir pada masa Khalifah ‘Umar bin
Khaththâb], Sa‘îd bin Jubair, dan Sa‘îd bin Musayyab yang bersikap "anti konflik" terhadap
fenomena fitnah yang terjadi pada masa Khalifah Mu‘âwiyah. Sikap sosial dan politik mereka juga
208
108
"Islam resmi" terus dibentuk dalam suasana persaingan politik yang tajam
ini dengan masing-masing gerakan berusaha untuk mengedepankan ide-ide Islam
laten yang sangat penting baginya. Ungkapan "Islam resmi" dibenarkan lewat
penindasan terhadap pemberontakan kaum Khawârij dan pemberontakan pro-‘Aly
bin ’Abî Thâlib oleh suatu negara yang mengklaim diri sebagai pewaris dan
pelanjut negara agama yang dibangun oleh Nabi.213
Gerakan sosial-politik yang saling bersaing secara praktis dan teoretis
(doktrinal) pada masa awal Islam ini, masing-masing semakin berkembang luas
seiring dengan imperialisasi Islam ke wilayah bulan sabit dan Persia. Pada tataran
praktis, identitas kelompok politiko-religius itu berkembang menjadi wadah bagi
kekuatan-kekuatan ketidakpuasan sosial dan politis, terutama Khawârij dan
Syî‘ah. Pada tataran teoretis, doktrin-doktrin awal mereka berkembang lebih jauh
setelah bertemu dengan ide-ide Yunani, Kristen, Manikaeisme, dan Budhisme.214
Penerjemahan karya-karya filsuf Yunani telah di mulai sejak masa dinasti
‘Umâwiyyah, yaitu
Sekretaris
Khalifah,
pemerintahan Khalifah Hisyâm (724-743 M/abad 2 H).
Sâlim
bin
’Abu
menerjemahkan risalah-risalah Aristoteles
al-’A‘lâ,
seorang
putera
Persia
hingga Alexander.215 Hal ini
berpengaruh terhadap perubahan diskursus doktrin-doktrin di atas. Karya-karya
penulis besar Persia, ’Ibn al-Muqaffâ, seorang sekretaris negara yang mashur di
dapat diidentifikasi melalui tokoh-tokoh intelektual seperti ’Abû Hanîfah, Mâlik, Syâfi‘i, dan
’Ahmad (empat ulama mazhab fikih) pada masa kekuasaan dinasti ‘Abbâsiyyah. Lihat, Ibid., h.
81-2
213
Mohammed Arkoun, Pemikiran Arab, h. 33. Kaum Khawârij dan kaum Syî‘ah juga bermaksud
membangun negara dan memberikan contoh-contoh tentang "Islam resmi". Lihat, Negara Taher di
Aljazair (777-909 M), orang-orang Fathimi di Afrika dan Mesir (909-1171 M); negara Iran sejak
kaum Safawi.
214
Fazlur Rahman, Islam, h. 252
215
Mohammed Arkoun, Pemikiran Arab, h. 40
109
zaman
kekuasaan
’Abu
Ja‘far
al-Manshûr
(pendiri
kekuasaan
dinasti
‘Abbâsiyyah), yang dihukum mati pada tahun 756 M karena dituduh bidah,
merupakan salah satu contoh dari perubahan horizon-horizon doktrinal itu. Dalam
salah satu karyanya yang paling terkenal, al-Risâlatu fî al-Shahâbah pemikir ini
mengusulkan serangkaian pembenahan administratif dan legislatif yang
mengekspresikan pendekatan positivis terhadap masalah-masalah politik,216
seperti tampak dalam kutipan berikut ini:
Sekarang berkaitan dengan tesis tentang kepatuhan eksklusif kepada
Imam, maka hal ini menyangkut masalah-masalah tentang pendapat,
pertimbangan yang mendalam dan kekuasaan politik yang seluruh
kendalinya ada di tangan Imam, sebuah kekuasaan yang tak seorang pun
dapat memiliki untuk memerintah dan mendapatkan kepatuhan. Masalahmasalah itu adalah: memerintahkan penyerangan dan mundur dari
peperangan; mengumpulkan pajak dan distribusinya; mengangkat dan
memberhentikan (pejabat negara); memberi keputusan pribadi dalam
persoalan yang tidak ada petunjuknya dalam Syariat; menjalankan hukumhukum kriminal dan ketetapan-ketetapan lain yang ada dalam Alquran dan
sunah; melawan musuh dan menyusun strategi untuk melawannya;
membebani pajak kepada umat Islam dan menganugerahi penghargaan
kepada mereka. Persoalan-persoalan ini dan yang lain seperti kepatuhan
kepada Tuhan adalah kewajiban, dan tidak seorang pun mempunyai hak
untuk memerintahkan kepatuhan ini kecuali Imam.217
Peran kaum Muslim non Arab tampak sangat berpengaruh, terutama bagi
Syî‘ah dalam perang melawan kekuasaan yang mapan, seperti halnya orang-orang
yang pemberontakannya dipimpin oleh Mukhtâr di Kûfah (Kufa) pada tahun 685
M.218 Pengaruh yang sama juga tampak pada pengarahan teoretis yang
berjangkauan jauh dalam perumusan esoterisme. Pada umunya, pemeluk-pemeluk
Islam non Arab tetap memegang teguh kepercayaan timur dan gnostik mereka
216
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 34
’Ibn al-Muqaffâ, al-Risâlatu fi al-Shahâbah, Jamharatu al-Rasâ’ili al-‘Arab, vol. 3, h. 31
218
Mohammed Arkoun, Pemikiran Arab, h. 33
217
110
yang lama, bahkan juga praktek-prakteknya, di bawah lapisan tipis rumusanrumusan Islam. Karena itu, di bawah permukaan Islam tersebut tetap terwujud
berbagai macam variasi kepercayaan-kepercayaan agama yang konfrontasinya
dengan Islam menghasilkan fermentasi spiritual yang besar dan kecairan ide-ide
keagamaan. Di antara ide-ide yang ada, terdapat ide-ide Kristen, Manikaeisme,
dan Budhisme. Sebagaimana Syiisme memenuhi tujuan orang-orang yang
terpencil secara politis, maka demikian pula di bawah selubungnya, orang-orang
yang terusir secara spiritual mulai memperkenalkan ide-ide lama mereka ke dalam
Islam. Untuk memperoleh tempat dalam Islam buat ide-ide seperti itu, prinsip
esoterisme di masukkan dari timbunan doktrin-doktrin gnostik yang lama. Prinsip
esoterisme menunjang ide penafsiran ganda, bahkan majemuk, dari teks-teks
Alquran.219
Bagi Syî‘ah, pengemban yang tak mungkin salah dari kebijaksanaan
esoteris ini adalah Imam yang berwibawa yang merupakan poros berputarnya
sistem keagamaan Syî‘ah yang dikelilingi dogma. Namun demikian, sanksi ’imâm
tersebut hanyalah bersifat teoretis semata, karena, Imam yang benar-benar diakui
sebagai figur-figur sejarah kurang lebih hanyalah menjadi tawanan dari gerakan
Syî‘ah yang menciptakan pretensi-pretensi tersebut bagi mereka, sedangkan
setelah "menghilangnya" Imam Muhammad al-Hanîfiyyah yang terakhir, bahkan
tak ada bimbingan teoretis sekalipun; yang ada hanyalah pengharapan akan
"kembali"-nya sebagai al-Mahdiy (yang "terjanji").220
219
220
Fazlur Rahman, Islam, h. 252
Fazlur Rahman, Ibid., h. 253
111
Konsekuensinya, Syî‘ah tidak mengakui kepentingan fundamental dari
ijmak, sebagaimana Islam Suni, dan tempat ijmak tersebut digantikan oleh otoritas
’imâm. Sementara Islam Suni menempatkan otoritas religius yang sebenarnya
dalam ijmak dan mengakui khalifah hanya sebagai kepala eksekutif keagamaan
dan politis, maka Imam Syî‘ah, sebaliknya, adalah tak mungkin berdosa dan
pendapatnya tak tergoyahkan dalam pernyataan-pernyataannya tentang dogma,
dan bahkan tentang semua hal.221
Pada abad ke-9 M, penguasa dinasti ‘Abbâsiyyah, Khalifah al-Ma’mûn (
813-833 M) menggalakkan penerjemahan dengan cara mendirikan lembaga ilmu
pengetahuan: Bait al-Hikmah.222 Pada masa ini, terjemahan pengetahuan Yunani
menjadi lebih akurat dan lebih banyak, apalagi dengan ditemukannya kertas pada
tahun 762 M. Penerjemah-penerjemah terbesar adalah para filsuf Muslim itu
sendiri. Al-Kindiy (w. 870 M) adalah filsuf besar pertama yang karyanya
mencakup berbagai cabang dari apa yang di Zaman Klasik dan Abad Tengah
disebut filsafat (ilmu fisika dan ilmu alam, matematika, kebijaksanaan) yang
mengoreksi intisari tiga Enneades yang terakhir, yang dikenal sebagai Teologi
Aristoteles.223
Sebelum Islam datang, pusat-pusat besar kehidupan intelektual di dalam
bahasa Yunani dan bahasa Syiria pada umumnya dimotori oleh orang-orang
Kristen, di antaranya yaitu: Edessa, Nisibe, Seleucia-Ctesiphon, Jundisapur,
Antioch dan Harran. Pendidikan Kristen di pusat-pusat ini berfungsi untuk
menyebarkan modicum persepsi etis, estetis dan logis serta tingkah laku maupun
221
Fazlur Rahman, Loc. Cit.
Fazlur Rahman, Ibid., h. 37
223
Mohammed Arkoun, Pemikiran Arab, h. 40
222
112
prinsip-prinsip awal spekulasi tentang "kebijakan eternal" kepada masyarakat
secara keseluruhan. Hal ini mengimplikasikan bahwa penetrasi pengetahuan
Yunani ke dalam bahasa Syiria dan kemudian bahasa Arab terjadi di bumi yang
secara tepat telah dipersiapkan untuk menerimanya lewat apa yang dapat disebut
epistemik Yunani-Semit. Ini merupakan suatu kompleks Aristotelianisme,
platonisme,
Stoisisme,
Epikureanisme,
pythagorianisme,
Hermetisme,
Zoroastrianisme, Manichaeanisme, Semitisme kuno dan wahyu YahudiKristen.224
Pada awal abad ke-10 M adalah masa penerjemahan berbagai teks Yunani:
karya-karya Plato baik yang asli maupun yang diragukan keasliannya, dan
komentar atas [karya-karya] Alexander Aphridisias, Porphyrius, Themistisius,
Simplicius, John Philoponus dan lain-lain. Gelombang penerjemahan ini dan
karya-karya orisinal pertama yang diilhaminya ditandai oleh dua ciri khas yang
terbukti menentukan
bagi masa depan pemikiran Islam: (a) Beberapa dari
penerjemah-penerjemah terbaik adalah orang Kristen, yang bekerja untuk patronpatron pengetahuan Muslim yang tercerahkan dan sebagai akibatnya, studi bahasa
Yunani benar-benar tidak pernah berakar dalam tradisi Arab – al-Farâbiy dan
’Ibnu
al-Sinâ
sendiri
bertumpu
pada
terjemahan-terjemahan
untuk
mengembangkan filsafat mereka; (b) cita-cita menuju kehidupan bijak (kebijakan
teoretis yang memungkinkan bagi permenungan harmoni antara alam dan
kebijakan praktis yang mengajarkan bagaimana sebenarnya menjadi bagian dari
kebijakan teoretis itu) tidak menuntut, dan pada kenyataannya menyebabkan tidak
224
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 37
113
semestinya, catatan tentang doktrin-doktrin tertentu secara historis. Doktrindoktrin ini diseleksi atas dasar kemungkinan-kemungkinan konseptual dan logis
yang mereka tawarkan kepada masing-masing "mazhab" Islam-Arab baru dalam
mempertahankan atau mengembangkan keyakinan barunya.225
Mistisisme intelektual Plotinus, sains Alexandrian, teologi Proclus, Gnosis
Alexandrian dan Gnosis Iran, astrologi Sabine, hermetisme, neo-Pythagorisme,
Stoicisme, semuanya menemukan makna penting dan penulisan yang segar
sebagai eksistensi baru di kota Muslim kosmopolitan.226 Sebuah perubahan perlu
dicatat; pada masa lampau penyampaian suatu tradisi kebudayaan lebih
merupakan hasil dari kata yang diujarkan, contoh dan penampilan yang diulangulang tentang suatu tindakan sedemikian rupa ketimbang teks tertulis. Segera
setelah ada suatu teks, sehingga metode-metode, skema-skema dan konsep-konsep
disesuaikan dengan keadaan masing-masing mazhab yang dibentuk. Sebagai
akibatnya, prinsip bahwa filsafat merupakan bagian dari suatu teks dimaksudkan
untuk menyarikan darinya apa saja yang membantu untuk mengembangkan jalur
penalaran formal tertentu.227
Ini merupakan tempat yang tepat untuk membicarakan kelompok politikoreligius keempat; yaitu apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan Muktazilah.
Sebuah kelompok yang pertama-tama muncul di Basra dan kemudian di Bagdad.
Melaui prinsip pembenaran rasional, kelompok ini membedakan diri dengan
mazhab-mazhab lain yang dominan: Syî‘ah, Khawârij, dan Suni. Di Basra
pemikir-pemikir aktif seperti Wâshil bin ‘Athâ’ (w. sekitar 750 M), ’Amr bin
225
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 41
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 42
227
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 38
226
114
‘Ubaid (w. 762 M) serta Dhirâr bin ‘Amr (w. 800/820 M) meletakkan dasar-dasar
apa yang kemudian menjadi lima prinsip doktrin Muktazilah: Tuhan Maha Esa,
Dia Maha Adil, pelaku dosa berada pada posisi antara orang mukmin dan orang
kafir, Tuhan melaksanakan janji dan ancaman-Nya di akhirat, manusia wajib
melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Prinsip-prinsip ini harus
dipahami dalam konteks semangat yang realistik, karena diskusi tentang lima
prinsip ini memiliki dampak praktis yang langsung: pembelaan terhadap keesaan
[Tuhan] sebagai serangan terhadap dualitas Manichean, dan penegasan keadilan
Tuhan merupakan suatu cara untuk menolak ketidakadilan para penguasa, dan hal
ini membangun suatu persekutuan yang berjalan antara kaum Muktazilah di satu
pihak dan kaum Qadariyyah dan bahkan kaum Khawârij di pihak lain.228
Sambutan antusias yang diberikan kepada pemikiran Yunani selama
pertengahan pertama abad ke-9 M memungkinkan kaum Muktazilah Bagdad
dapat memperkuat arah rasionalisme yang telah muncul di Basra. ’Abû Hudzail
al-‘Allâf (w. sekitar 850 M), yang telah diundang ke Bagdad oleh al-Ma’mûn
sekitar tahun 820 M, Bisyr al-Mu’tamir (w. 825 M), al-Nazhzhâm (w. 846 M),
yang adalah kritikus cemerlang terhadap pemikiran Aristoteles, dan muridnya
yang bernama al-Jâhizh (w. 869 M) memberikan andil bagi pengembangan suatu
doktrin Muktazilah yang secara resmi dikemukakan pada tahun 827 M. Lima
prinsip doktrin Muktazilah membentuk dasar-dasar bangunan sistematik yang
dianggap sebagai suatu teologi; atau lebih tepat menyebutnya sebagai ideologi
suatu kelas yang berkuasa yang berhasil dikukuhkan antara 813 M dan 847 M.
228
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 42-3
115
Program mihnah [pembakuan doktrin kemakhlukan Alquran oleh negaraMuktazilah] merupakan puncak dari fenomena perkembangan ini, dan sebagai
episode yang mengawali periode panjang permusuhan antara sikap tradisionalis
dan sikap rasionalis. Di samping itu, episode ini juga menggambarkan dua cara
memahami dan hidup bersama dengan fakta Alquran, yang dikaitkan dengan dua
tipe diskursus yang secara dialektik terkait dengan dua kelompok sosial yang
sangat berbeda.229 Doktrin Muktazilah merupakan ideologi kelas elit yang
berkuasa, sedangkan doktrin tradisionalis-ortodoks merupakan ideologi massa
awam.
Perdebatan teoretis sebagai sistematisasi doktrin terus merambah ke dalam
seluruh bidang pemikiran, termasuk pemikiran mengenai asas-asas wewenang dan
kekuasaan. Akibatnya, apapun doktrin teologis yang dimunculkan dan
dikembangkan oleh kelompok-kelompok Islam, hal itu merupakan ideologi
masing-masing yang sesungguhnya dibuat untuk melayani tujuan sosial-budaya
dan politik yang diinginkan.
C. Metodologi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Dalam literatur Islam, al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dikategorikan sebagai alsiyâstu al-syar‘iyyatu wa al-qadhâ’ [politik-hukum syariat] dan merupakan
bagian dari ilmu fikih. Oleh karena itu, sebelum metodologi yang dipakai alMâwardiy dalam al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dijelaskan, terlebih dahulu akan
229
Mohammed Arkoun, Ibid., h. 44
116
dibahas sejarah pembentukan fikih, metodologinya (’ushûl al-fiqh dan qawâ'
id al
fiqhiyyah) dan membahas konsep-konsepnya.
1. Asal-usul Pembentukan Fikih (Hukum Islam)
Selama Nabi masih hidup, dialah yang menjadi pembimbing agama dan politik
satu-satunya bagi kaum Muslimin, baik melalui wahyu Alquran maupun dengan
ucapan-ucapan dia sendiri di luar Alquran, serta tingkah lakunya. Dengan
kematiannya Alquran tetap utuh, namun bimbingan keagamaannya yang otoritatif
dan pribadi menjadi terputus. Keempat khalifah yang pertama menangani situasisituasi baru yang terus timbul dengan jalan menerapkan kebijaksanaankebijaksanaan mereka di bawah sinaran Alquran dan pelajaran yang mereka
terima dari Nabi.230
Abad berikutnya (dari kira-kira 50-150 H/670-767 M), adalah abad yang
patut dicatat, karena adanya pertumbuhan suatu fenomena yang tepatnya
dijelaskan sebagai fenomena metodologi keagamaan dalam ketiadaan bimbingan
yang hidup dari Nabi dan dari generasi Sahabat yang paling awal.231
Manifestasi pertama dari fenomena tersebut dikenal sebagai hadis atau
tradisi Nabi, yang kemudian dikumpulkan dalam satu seri kumpulan-kumpulan,
enam di antaranya [al-kutub al-sittah], yang ditulis pada abad ke-3 H/9 M,
230
231
Fazlur Rahman, Islam, h. 51
Fazlur Rahman, Loc. Cit.
117
kemudian dianggap sebagai sumber otoritatif kedua tentang Islam sesudah
Alquran.232
Hadis (yang secara harfiah berarti ceritera, penuturan, atau laporan)
sebagaimana yang dikenal sekarang, adalah sebuah narasi, biasanya sangat
singkat dan bertujuan memberikan informasi tentang apa yang dikatakan Nabi,
dilakukan, disetujui atau tidak disetujui olehnya, juga informasi yang sama
mengenai para Sahabat, terutama Sahabat-sahabat senior, dan lebih khusus lagi,
mengenai keempat khalifah yang pertama. Setiap hadis mengandung dua bagian,
teks [matn] dan mata-rantai transmisi atau sanad-nya, yang menyebutkan namanama penuturnya [râwy], yang menjadi dukungan bagi teks hadis tersebut.233
Sementara pada masa Nabi hidup, orang-orang berbicara tentang apa yang
dikatakan atau dilakukan oleh dia sebagaimana mereka berbicara tentang hal-hal
sehari-hari mereka, maka setelah dia wafat pembicaraan tersebut lalu berubah
menjadi suatu fenomena yang disengaja dan penuh kesadaran, karena suatu
generasi baru sedang tumbuh, yang tidak menemui masa hidup Nabi, yang dengan
sewajarnya menanyakan tentang perilaku Nabi.234 Apalagi, seiring dengan
munculnya situasi-kondisi baru yang luas dan kompleks, munculnya kontroversikontroversi dalam sebagian besar masalah, termasuk dalam bidang teologi dan
moral, terutama di mana pengaruh-pengaruh asing telah masuk, maka generasi
baru umat Islam pun membutuhkan norma keagamaan yang praktis. Dalam
kerangka orientasi praktis dan bersifat peneladanan terhadap Nabi atau untuk
memperoleh landasan normatif dari dia inilah, hadis ditransmisikan.
232
Fazlur Rahman, Loc. Cit.
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 68
234
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 69
233
118
Karena itu, untuk memberikan normatifitas kepada pandangan-pandangan
atau praktek-praktek yang aktual, orang-orang mulai melancarkan kampanye
besar-besaran dan massal untuk menstandardisir hadis dan mengkodifikasikannya,
dan menolak penafsiran-penafsiran keagamaan yang ekstrem, baik tentang
dogma-dogma maupun hukum-hukum. Sesungguhnya, untuk menghadapi
ekstremisme dan penafsiran sewenang-wenang yang sudah gawatlah hadis terjun
ke dalam arena dengan skala besar-besaran. Itulah sebabnya mengapa kodifikasi
massal hadis sebagai suatu disiplin, bermula menjelang abad ke-1 H/awal abad
ke-8 M.235 Hal ini menjurus kepada pengenalan dan penyempurnaan mata-rantai
transmisinya, yang mencerminkan suatu kebutuhan dasar yang nyata akan suatu
macam kanonisasi pengalaman-pengalaman interpretatif-asimilatif dari kaum
Muslimin terhadap ajaran-ajaran Nabi yang dianggap otentik.
Akan tetapi, dalam proses kanonisasi ini juga terkandung dua
kemungkinan bahaya. Pertama, dengan merujukkan setiap doktrin teologis,
dogmatis dan hukum kepada otoritas Nabi sebagaimana dituntut oleh logika
fenomena hadis, maka proses interpretasi akan terhenti. Atau kedua, apabila
proses kreatif tersebut terus dilanjutkan, maka produksi hadis dan atau pemalsuan
hadis secara terus-menerus akan terjadi. Dalam kenyataannya, kedua macam
kekhawatiran ini saling berkaitan.236
Namun demikian, sampai kira-kira pertengahan abad ke-3 H/9 M, teologi
dan hukum terus berkembang di bawah perlindungan hadis, demikian pula
235
236
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 76
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 77
119
kegiatan seleksi hadis yang "asli" dari yang "lemah" dan yang "palsu". Masa ini
adalah juga masa pembentukan dan konsolidasi ortodoksi.237
Dalam bidang hukum, pada akar konsepsi hukum Islam terletak ide bahwa
hukum esensinya adalah religius dan berjalan berkelindan secara religius. Itulah
sebabnya mengapa sejak dari awal mula sejarah Islam, hukum sudah dipandang
bersumber dari Syarî‘ah (pola perilaku yang diberikan Tuhan untuk menjadi
tuntunan bagi manusia) atau sebagai bagian darinya.238
Satu-satunya cara yang wajar yang harus dipakai dalam prosedur
penafsiran hukum untuk aplikasi yang sesuai dari Alquran terhadap suatu situasi
yang baru adalah melihat Alquran dalam keadaan sebagaimana ia benar-benar
telah beroperasi dalam masa hidup Nabi, yang merupakan eksponen faktualnya
yang berwenang, dan yang perilakunya memiliki kenormatifan religius yang
tersendiri. Inilah sunah atau hadis Nabi. Oleh karena pada akhir abad ke-1 H/awal
8 M banyak materi yang masif telah dimasukkan ke dalam bidang sunah dari
sumber-sumber yang berbeda, maka kemudian dikenakanlah predikat ‘yang telah
disepakati’ (ijmak) kepada sunah,239 bukan hadis.
Selama masa keempat khalifah yang pertama (sampai kira-kira 40 H/660
M), hukum hampir tak bisa dipisahkan atau bahkan dibedakan dari pemerintahan.
Pada masa ini legislasi, dapat dikatakan, dilakukan oleh khalifah sendiri, karena
dalam prakteknya hal itu dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau oleh
anggota masyarakat yang senior. Akan tetapi pada masa kekuasaan dinasti
‘Umâwiyyah, pemerintahan mengambil bentuk otokrasi yang berkuasa yang
237
Fazlur Rahman, Loc. Cit.
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 91
239
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 94
238
120
menjadi jelas berbeda dari rakyat. Penguasa-penguasa dinasti ‘Umâwiyyah
melaksanakan pemerintahannya dari Damaskus, dengan mengambil pedoman
terutama dari Alquran dan sunah, tetapi dengan penafsiran oleh penasehatpenasehat dan pejabat-pejabat pemerintahan dengan prinsip kepentingan sendiri
dan dalam sinaran praktek-praktek lokal di setiap propinsi yang berbeda-beda.
Menghadapi otorita awam ini, pemuka-pemuka masyarakat keagamaan yang
berpusat di Madinah mulai menyusun kumpulan hukum Islam (fikih). Praktek
lokal daerah Hijaz tak syak lagi merupakan faktor penting dalam kumpulan
hukum mereka. Dengan segera kegiatan legislatif keagamaan juga timbul di Irak,
Basra dan Kufa. Jadi, negara pada waktu itu adalah lembaga eksekutif yang
menerapkan hukum syariat sebagaimana yang dirumuskan oleh otorita hukum
setempat di masing-masing propinsi.240
Khalifah-khalifah ‘Abbâsiyyah memberikan perhatian dan validitas
sepenuhnya
kepada
hukum
syariat
dan
menyempurnakan
mekenisme
penerapannya. Tetapi beberapa perkembangan baru timbul. Tidak hanya para
khalifah mulai memberlakukan hukum-hukum khusus buatan mereka sendiri
untuk menghadapi situasi-situasi yang mendesak, tapi juga muncul kumpulan
hukum yang baru, walupun kecil, yang dibuat oleh otorita-otorita awam untuk
melengkapi hukum syariat. Para ahli hukum (fuqahâ’) yang terkemudian,
termasuk Al-Mâwardiy, mencoba sedikit demi sedikit untuk mengintegrasikan
hukum yang baru ini ke dalam hukum syariat.241
240
241
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 108.
Fazlur Rahman, Ibid., hal. 109
121
2. Metodologi Pembentukan Fikih
Cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa formulasi syariat, sebagaimana
sistem perundang-undangan lainnya, mengikuti tahap-tahap perkembangan
masyarakat. Teknik-teknik penjabaran syariat dari sumber sucinya dan cara-cara
penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk proses
sejarah intelektual, sosial dan politik umat Islam.242
Seperti telah diketahui, tiga abad pertama Islam (abad VII hingga IX M)
adalah periode pembentukan syariat. Sejak masa itu determinan sejarah utama
dalam pembentukan syariat mencakup watak teritorial, geografis, dan konteks
sosial politik umat Islam. Tahap ekspansi Islam dan masuknya berbagai kelompok
etnik dan kultural ke dalam Islam, juga penting. Faktor-faktor teritorial dan
demografis ini mempengaruhi sifat politik dan sosiologis negara Islam dan
memberikan bahan mentah bagi pengembangan institusi dan kebijakan selama
tiga abad pertama yang krusial itu. Kombinasi berbagai faktor itu berpengaruh
pada formulasi syariat.243
Empat sumber syariat adalah Alquran, sunah, ijmak dan kias (qiyâs). Dua
yang pertama telah cukup dijelaskan di muka. Dua yang terakhir biasanya
diterjemahkan dengan "konsensus" dan "penalaran melalui analogi".
Logika syariat sebagai suatu sistem perundang-undangan menempuh
prosedur: pertama, dijabarkan langsung dari Alquran; kedua, dari tradisi atau
242
243
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, LKIS, Yogyakarta, 1994, h. 30
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Loc. Cit.
122
sunah Nabi; dan terakhir dari tindakan individu yang terpercaya dan terbimbing
dan masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu dan tradisi tadi.244
Ijmak sebagai sumber ketiga syariat adalah “tradisi yang hidup” (living
tradition) para Sahabat Nabi, yang menjadi "konsensus" bersama atau "praktekpraktek yang telah disepakati bersama". Disamping berdasarkan alasan logis,
pembenaran sunah juga turut mendukung ijmak sebagai sumber syariat.
Diriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata: “Umatku tidak akan pernah bersepakat
dalam kesalahan”.245
Fazlur Rahman menilai, bahwa karena sifatnya sendiri, ijmak merupakan
faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk dan mengungkapkan kompleks
kepercayaan dan praktek kaum Muslimin, dan pada waktu yang sama juga
merupakan faktor yang paling membingungkan dalam batas-batas formasinya. Ia
adalah suatu proses organis, dan seperti suatu organisme, ia berfungsi dan
sekaligus tumbuh: pada setiap saat ia memiliki kekuatan dan validitas fungsional
yang tinggi, dan dalam artian ini ia bersifat "final"; tetapi pada saat yang sama ia
juga mencipta, mengasimilasi, memodifisir dan menolak unsur-unsur dari luar
dirinya. Itulah sebabnya mengapa pembentukannya tidak bisa dilembagakan
dalam bentuk yang manapun juga. Kelompok ulama dan ahli hukum yang tumbuh
dengan cepat pada abad ke-1 H/7 M dan ke-2 H/8 M dan masa-masa selanjutnya
memang dapat membahas dan merumuskan hasil-hasil pemikiran mereka yang
sangat berpengaruh, terutama bila mereka bersesuaian pendapat [atau lebih
tepatnya, kebetulan bersesuaian – dan ini disebut ijmak ulama], tetapi
244
245
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Ibid., h. 39
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Ibid., h. 47
123
pembentukan ijmak tak dapat dilakukan dalam sebuah ruang diskusi. Ia lebih
condong sebagai opini publik yang cerdas, yang dalam pemikiran-pemikiran yang
dihasilkannya,
perumusan
aliran-aliran
merupakan
faktor
yang
paling
berpengaruh.246
Walaupun prinsip ijmak sebagai sumber syariat sudah diterima sejak dini,
namun pengertian dan ruang lingkupnya masih menjadi bahan perdebatan sampai
sekarang. Apakah yang disebut ijmak? Apakah ia mensyaratkan kebulatan suara
penuh atau dapat dikatakan ijmak meskipun banyak yang tidak sepakat atau
ditolak oleh sebagian kecil orang? Kepada siapa ijmak mengikat? Adakah ia
merupakan konsensus para Sahabat dan pengikutnya di Madinah, ulama dan ahli
hukum Islam secara umum [atau dalam lokalitas yang ada], atau keseluruhan umat
Islam? Adakah ia ijmak satu generasi [ulama atau umat Islam] atau beberapa
generasi? Apakah ijmak generasi lebih awal [atau berbagai generasi] mengikat
seluruh generasi berikutnya? Seluruh pertanyaan ini dan lainnya yang
berhubungan dengan sifat dan ruang lingkup ijmak, terus menjadi perdebatan.247
Di sisi lain, konsep ijtihad (ijtihâd) atau pemikiran rasional (ra‘y) yang
sistematis, yang pada awal penggunaannya begitu terbatas, kemudian berkembang
menjadi sebuah prinsip pemikiran orisinal yang diakui dan digunakan secara luas
pada akhir abad ke-2 H/8 M, dengan mengandalkan kias sebagai metodenya.
Dengan berkembangnya penalaran sistematis, pemakaian ra’y dikutuk keras oleh
ahlu al-Hadîts (pendukung hadis). Setiap kitab kumpulan hadis yang utama dan
sistematis yang mengandung taridisi-tradisi yang dikatakan berasal dari Nabi,
246
247
Fazlur Rahman, Islam, h. 101-102
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Op. Cit., h. 48
124
mengutuk opini pribadi. Meski demikian, kias yang permulaannya sebagai ra’y
dan ungkapan-ungkapan tak resmi lainnya, kemudian ia telah memperoleh
kedudukan yang mantap. Al-Syâfi‘iy (w. 204 H/819 M) – ahli hukum pertama
yang menuliskan dasar-dasar hukum – pada umumnya telah dianggap berjasa
meneguhkan kedudukan kias. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut
memang sudah diterima umum.248
3. Metodologi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Apa yang dinyatakan Al-Mâwardiy sebagai hukum-hukum syariat, kenyataannya
adalah keputusan-keputusan yang disimpulkannya (’istinbâth) dari ayat-ayat
Alquran, hadis, ijmak dan praktek-praktek individu Sahabat, praktek-praktek
pemerintahan Islam masa lalu, mazhab ahli fikih yang menggunakan metode kias,
serta penalaran bebas Al-Mâwardiy sendiri.
Operasionalisasi
metodologi
Al-Mâwardiy
tampak
dalam
daftar
inventarisasi masalah-masalah hukum yang kemudian ia nyatakan status
hukumnya. Operasionalisasi metodologi tersebut terangkum dalam daftar
lampiran.249
D. Wacana-wacana Ideologis Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Tidak dapat dikatakan secara totaliter bahwa seluruh isi al-’Ahkâm alShulthâniyyah merupakan ideologi dan ditulis demi tujuan ideologis. Demikian
248
Fazlur Rahman, Op. Cit., h. 96.
Inventarisasi data-data metodologis ini dibatasi pada 6 bab yang pertama yang mencakup
masalah-masalah mendasar dalam tata pemerintahan dan dekat dengan kepentingan-kepentingan
ideologis. Lihat daftar lampiran.
249
125
juga, tidak dapat dikatakan bahwa al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah bersih dari
ideologi. Berikut ini akan dipaparkan wacana-wacana yang secara kuat
menampakkan diri sebagai mitos (simbol ideologi) atau wacana yang memiliki
implikasi ideologis:
1. Menurut al-Mâwardiy, pemerintah (wullât al-’umûr) adalah lembaga
kekuasaan yang kewenangannya bersumber dari Allah, bertugas (memiliki
kewajiban) melaksanakan dan membuat kebijakan yang dapat menjamin
pelaksanaan hukum-hukum-Nya, dan oleh karena itu, ia bertanggungjawab
kepada-Nya.250 Penegasan al-Mâwardiy ini mengabaikan fakta bahwa
pemerintah adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan mengakses
Kehendak Allah yang absolut dan transenden. Selain itu, gagasan alMâwardiy tersebut juga mengabaikan fakta bahwa baik Alquran maupun
sunah yang disepakati umat Islam sebagai sumber ajaran Islam yang paling
otoritatif tidak menjelaskan secara rinci dan pasti mengenai mekanisme
pengejawantahan mandat Kekuasaan Ilahi kepada kekuasaan manusiawi.
2. Al-Mâwardiy mengemukakan bahwa salah satu alasannya menulis al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah adalah karena melaksanakan perintah seseorang yang wajib
dipatuhi.251 Meski al-Mâwardiy tidak menjelaskan siapa orang yang
dimaksud, tetapi dapat dijelaskan bahwa yang dimaksudkannya adalah
khalifah (al-Qâ’im) karena dialah yang memang wajib dipatuhi sesuai dengan
konsep imamah. Sebagai seorang pejabat negara (hakim agung), sudah
seharusnya jika al-Mâwardiy mematuhi perintah khalifah yang menjadi
250
251
Al-Mâwardiy, Al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 3
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
126
atasannya langsung itu. Terkait dengan relasi jabatan bawahan-atasan, patut
dipertanyakan bagaimana sikap al-Mâwardiy untuk menjaga independensi
pendapat-pendapatnya, terutama mengenai hal-hal atau hukum-hukum yang
bersangkut-paut dengan otoritas khalifah, meskipun al-Mâwardiy mengatakan:
"Saya berdoa kepada Allah subhânahû wa ta‘âlâ sambil meminta
pertolongan-Nya dan saya memohon taufik dan hidayah-Nya, Dialah
sandaranku satu-satunya"?252
3. Al-Mâwardiy mengatakan: "Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa telah
menetapkan adanya pemimpin bagi Umat yang menjadi pengganti fungsi
kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran Agama, memegang kendali politik,
membuat kebijakan pemerintahan yang dilandasi syariat........".253 Pertanyaanpertanyaan yang patut diajukan terkait dengan pernyataan al-Mâwardiy itu
antara lain: di manakah garis ketetapan Allah itu? Seperti apakah bunyi
ketetapan-Nya? Benarkah memang ada ketetapan-ketetapan itu?
4. Al-Mâwardiy mengatakan: "Imamah adalah dasar bagi tegaknya ajaran-ajaran
Agama, bagi terwujudnya kesejahteraan Umat, dan menjadi tumpuan bagi
kepentingan-kepentingan publik, serta menjadi sumber wewenang bagi
kekuasaan-kekuasaan yang khusus."254 Bahwa negara dan kepemimpinannya
harus ada adalah premis yang dapat diterima oleh siapapun yang memiliki
akal sehat, karena hal itu dibutuhkan dalam hidup manusia dan untuk
menjamin kelangsungannya. Manusia, dan bahkan hewan selainnya yang lebih
rendah, tercipta dengan tabiat hidup secara berkelompok, dan di dalam setiap
252
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
254
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
253
127
kelompok itu terdapat "pemimpin" yang memiliki kekuasaan/kemampuan
yang
mengatasi
selainnya.
Lalu,
sejak
kapan
"kepemimpinan"
itu
diagamakan? Sejak kapan '
kepemimpinan'itu menjadi sakral dan suci? Sejak
kapan "kepemimpinan" itu menjadi hak istimewa orang/golongan tertentu
terhadap orang/golongan yang lain? Atas dasar apa bangunan argumentasi
keabsahan model-model "kepemimpinan" itu?
5. Imamah dalam terminologi al-Mâwardiy menunjuk kepada arti "pemerintahan
Islam", dan al-’ummah adalah "umat Islam". Pemaknaan ini, selain didekati
dari segi semantik, secara gramatika bahasa Arab dua istilah itu dipakai alMâwardiy dalam bentuk definitif (’ism al-ma‘rifah). Meskipun al-Mâwardiy
tidak menyertakan kata-kata "Islam" dibelakng dua istilah itu, arti yang
dimaksudkan al-Mâwardiy adalah arti tersebut. Apa implikasi dari
penggunaan istilah-istilah ini?
6. Mengenai salah satu syarat bagi calon Imam, al-Mâwardiy mengatakan: "ia
harus keturunan dari suku Quraisy karena adanya nas tentang hal itu dan telah
terwujudkannya ijmak ulama tentang masalah itu".255
7. Pengangkatan Imam dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemilihan oleh
"dewan pemilih" dan atau melalui permandatan oleh Imam sebelumnya.
Dalam dua mekanisme suksesi itu al-Mâwardiy sama sekali tidak
memperhitungkan hak suara rakyat dengan dalih bahwa keduanya merupakan
mekanisme yang dipraktekkan al-khulafâ’u al-râsyidûn dan telah terwujud
255
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 6
128
ijmak.256 Al-Mâwardiy juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme
pengangkatan anggota "dewan pemilih".
8. Seorang Imam dapat mengangkat siapa saja orang yang cocok sebagai
penggantinya, termasuk mengangkat ayah atau anak laki-lakinya. Persetujuan
"dewan pemilih" tidak diperlukan. Al-Mâwardiy mengatakan: "Imam adalah
orang yang paling berhak atas baiat imamah itu, pilihannya dalam masalah
baiat imamah lebih kuat dan pendapatnya lebih pasti."257
9. Al-Mâwardiy mengatakan: "Imam yang memberikan mandat kepada orang
lain [putra mahkota, pen.] tidak boleh mencabut status mandat yang telah ia
berikan, selama kondisinya belum berubah [sampai terjadi perubahan penting
pada putra mahkota yang secara hukum membatalkannya, pen.]. Dalam
masalah pemberian mandat itu, Imam berlaku sebagai wakil dari kaum
Muslimin sehingga ia tidak berhak untuk mencabutnya kembali, sebagaimana
halnya dewan pemilih tidak dapat memberhentikan orang yang mereka telah
membaiatnya untuk memangku jabatan Imam, selama orang itu belum
berubah sifatnya sehingga tetap mencukupi syarat-syarat kompetensi
jabatannya."258
10. Al-Mâwardiy berkata: "Khalifah boleh memilih dewan pemilih, sebagaimana
ia boleh memilih calon penerima mandat. Hanya pilihan dewan pemilih yang
telah ia tunjuk itulah yang sah, juga hanya pengangkatan orang yang ia
256
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 6-10
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 10
258
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 11
257
129
calonkan sebagai penerima mandatlah yang sah. Ini karena kedua hal itu
merupakan bagian dari hak-hak jabatan kekhalifahannya."259
11. Menurut al-Mâwardiy, khalifah dapat mengangkat dua atau lebih putra
mahkota sebagai penggantinya. Argumentasi ini diambil dari peristiwa
pertempuran di Mu‘tah, di mana Nabi mengangkat Zaid bin Hâritsah sebagai
komandan tentara Islam dan berkata, bahwa jika dia [Zaid] gugur dalam
pertempuran, dia digantikan oleh Ja‘far bin ’Abî Thâlib, kemudian digantikan
oleh ‘Abdullâh bin Rawâhah. Jika Rawâhah juga gugur, maka umat Islam bisa
memilih salah satu di antara mereka sebagai komandannya.260
12. Jika imamah telah dipegang oleh Imam secara resmi, baik dengan penyerahan
mandat maupun pemilihan, seluruh rakyat harus mempercayakan semua
persoalan mereka kepadanya, menyerahkan kepadanya wewenang penetapan
kebijakan umum secara mutlak [tanpa syarat], tanpa meminta penjelasannya
apalagi melawan, sehingga ia dapat menjalankan apa yang diamanahkan
kepadanya, yaitu menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan
kebaikan bagi rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan.261
13. Di antara 10 pokok kewajiban Imam, yang paling utama – al-Mâwardiy
menyebutnya pertama kali – adalah menjaga dan mempertahankan prinsipprinsip Agama yang telah mapan dan telah terwujud konsensus dari otoritasotoritas masa lalu.262
259
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 13
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
261
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 15
262
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
260
130
14. Jika Imam dikudeta oleh salah seorang pembantunya, yang menginginkan
semua kekuasaan ada pada dirinya namun tidak secara terbuka menentang
Imam, maka ia akan tetap menempati posisinya [legalitas jabatannya tidak
gugur].263
15. Menurut al-Mâwardiy, Jabatan menteri termasuk yang dilarang untuk
diduduki wanita. Hal ini berdasarkan hadis: "Suatu bangsa tidak akan
mendapatkan keberuntungan jika mereka menyerahkan urusan negara mereka
kepada wanita". Berlakunya larangan ini, lanjut al-Mâwardiy, karena
menghasilkan pendapat yang tepat serta ketangguhan sikap tidak dimiliki oleh
wanita, serta tidak diperbolehkannya untuk tampil di muka umum.264
263
264
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 19-20
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 27
131
BAB IV
ANALISA HISTORIS, METODOLOGIS, DAN MITOS
AL-’AHKÂM AL-SHULTHÂNIYYAH
Sesuai dengan masalah dan landasan teoretis penelitian, teks al-’Ahkâm alShulthâniyyah akan dianalisis melalui tiga perspektif: historis, metodologis, dan
mitis.
Dengan analisa historis, akan dilihat pengaruh-pengaruh situasi sosial,
politik, dan budaya yang signifikan terhadap kelahiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Melalui analisa historis ini, bukan saja akan diperlihatkan konteks
sosial, politik, dan budaya yang menentukan kelahiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah, serta posisinya di dalam konteks historis itu,265 melainkan juga
akan diperlihatkan arah kehendak, dorongan-dorongan, dan kepentingankepentingan ideologis yang tersembunyi secara rapat dalam forma wacana hukum
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah di dalam konteks sosial dan politiknya. Dalam model
analisa yang terakhir ini, analisa historis diarahkan kepada – meminjam istilah
Mannheim – faktor-faktor temporal dan sosial266 yang memiliki efek pada isi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah di satu sisi, dan di sisi lain faktor-faktor temporal dan
sosial itu menunjukkan fungsi wacana al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah di dalam
265
Analisa terhadap masalah-masalah ini berarti memeriksa faktor-faktor eksisitensial al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah di dalam proses sosial secara periferis. Faktor-faktor tersebut hanya dipandang
semata-mata sebagai sesuatu yang mengkondisikan asal-usul atau perkembangan faktual al’Ahkâm al-Shulthâniyyah, atau sekedar dipandang sebagai faktor-faktor yang memiliki relevansi
genetis dengannya.
266
Lihat Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik,
Yogyakarta: Kanisius, 1991, h. 294
132
konteks historisnya. Model analisa inilah yang dimaksudkan sebagai historisitas
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah yang berkait dengan isi atau wacananya.
Analisa metodologis dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah sebagai wacana etika politik Islam dibentuk berdasarkan cara
pandang dan cara berpikir tertentu (kelompok sosial al-Mâwardiy). Al-Mâwardiy
dalam analisa ini, posisinya dipandang sebagai individu yang berpikir dengan
mengambil bagian dalam pemikiran lebih lanjut yang telah dipikirkan orang lain
sebelumnya. Ia berada dalam suatu situasi yang diwariskan dengan pola-pola
pemikiran yang sesuai untuk situasi ini dan berusaha menjelaskan lebih lanjut
cara-cara menanggapi yang telah ada atau menggantinya dengan cara-cara lain
supaya dapat menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dari peralihanperalihan dan perubahan-perubahan situasinya secara memadai.267 Cara-cara
tertentu yang dipakai al-Mâwardiy untuk menanggapi situasi yang dihadapinya
inilah – penulis mendefinisikannya sebagai metodologi yang membentuk isi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah – yang perlu dikonkretkan rumusannya melalui analisa
yang disebut analisa metodologis. Analisa metodologis bukan hanya dimaksudkan
untuk mendefinisikan rumusan metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, tetapi
juga dimaksudkan sebagai upaya mempertimbangkan jangkauan (batasan)
metodologi itu, implikasi-ipmlikasinya, serta fungsinya secara historis. Pada
momen ini, analisa akan lebih memperkuat fenomena historisitas al-’Ahkâm alShulthâniyyah yang khusus menyangkut aspek metodologinya. Jelasnya, analisa
267
Lihat Karl Mannheim, Ibid., h. 3
133
metodologis juga diupayakan untuk mengungkap historisitas metodolgi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Analisa metodologis pada tahap ini, selain didasarkan pada asumsi teoretis
di atas, juga didasarkan pada asumsi bahwa al-Mâwardiy sebagai individu sangat
terikat dengan kelompoknya. Ia berjuang keras menurut posisi, ciri, dan cara
kelompoknya itu untuk mengubah dunia alam sekitarnya dan masyarakat atau
berusaha memeliharanya tetap pada kondisi yang telah ada. Padahal di dalam
setiap ruang historis, terdapat ragam kelompok dan setiap kelompok memiliki
kepentingan yang sama untuk melakukan tindakan seperti itu dan cenderung
saling menolak atau menghancurkan (terjadi kompetisi). Maka, analisa
metodologis terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah pada tahap ini adalah sebagai
upaya mengungkapkan historisitas metodologinya di dalam ruang kontestasi antar
sistem pemikiran yang saling berkompetisi untuk meraih kekuasaan sosial.
Dengan demikian, tahap ini merupakan momen yang paling penting untuk
mengenali bentuk operasi yang terdalam dari hubungan al-’Ahkâm alShulthâniyyah dengan kekuasaan.
Akhirnya, analisa metodologis bertujuan menyatakan bahwa setiap pilihan
metodologis tertentu dari kelompok tertentu (seperti metodologi al-’Ahkâm alShulthâniyyah) memiliki keterbatasan jangkauan, mengandung implikasiimplikasi, serta fungsi-fungsi ideologis tertentu yang tidak dapat dielakkannya.
Pada taraf tertentu, dalam konteks persaingan sosial, pilihan metodologis itu juga
menunjukkan ideologi subyeknya.
134
Kemudian yang terakhir, analisa mitis lebih diartikan sebagai salah satu
upaya lain untuk melakukan kritik ideologi terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Dalam konteks ini, analisa mitis dioperasikan untuk membedah struktur wacana
mitis
al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah:
mengenali
bentuk-bentuk
mitosnya,
menjabarkan sistem operasinya, dan mendefinisikan fungsinya secara ideologis.
Sehingga, analisa mitis ini juga merupakan salah satu cara untuk melakukan kritik
terhadap ideologi al-Mâwardiy bersama kelompoknya dalam konteks masyarakat
Bagdad abad IV H/10 M. Sebenarnya, langkah analisis yang terakhir ini pun
merupakan strategi yang ketiga untuk menunjukkan historisitas al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Perbedaan strategi ini dengan strategi yang pertama (melalui
analisa historis) terletak pada bobot perspektif sinkronis-diakronis. Pada strategi
pertama, historisitas al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dibedah melalui isi atau
wacananya yang lebih diperlakukan atau dilihat secara sinkronis. Sebaliknya pada
strategi ketiga (melalui analisa mitis), isi atau wacana al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
lebih diperlakukan atau dilihat secara diakronis.
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka bab ini berisi pembahasan
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah melalui: (a) analisa historis, (b) analisa metodologis,
dan (c) analisa mitis.
A. Analisa Historis: Sosiologi-Genealogi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Seperti telah disebutkan di atas bahwa analisa historis ini dimaksudkan sebagai
salah satu usaha untuk melihat kelahiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dalam
hubungannya dengan latar belakang fenomena sosial, politik, dan budaya yang
135
dianggap sangat menentukan. Berdasarkan data-data historis yang telah
dipaparkan di dalam Bab III, secara umum dapat dikatakan bahwa kelahiran al’Ahkâm al-Shulthâniyyah sangat dimungkinkan oleh kondisi sosial, politik, dan
budaya Islam abad IV H/10 M.
1. Konteks Sosial-Budaya yang Melahirkan Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Secara detail, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah terlahir karena kemampuan intelektual
al-Mâwardiy yang mewarisi tradisi intelektual Suni khususnya. Al-Mâwardiy
lahir dan besar di lingkungan kultural Suni yang kuat. Ia mempelajari tradisi Suni
dari tokoh-tokohnya yang merupakan sumber-sumber ilmu pengetahuan ortodoks
yang otoritatif. Secara genealogis, kemampuan intelektual al-Mâwardiy
bersumber dari guru-gurunya yang tidak lain adalah murid-murid al-Syâfi‘iy dan
[’Abû] al-Hasan al-Bashriy: dua guru besar yang dikenal sebagai bagian dari
founding fathers-nya Ahlu Sunah Waljamaah,268 di mana Basra kemudian bagdad
merupakan dua kota basisnya yang terpenting. Basra juga menjadi tempat
kemunculan dan basis gerakan Muktazilah sebelum berkembang ke Bagdad, baik
sebagai gerakan intelektual maupun gerakan sosial. Basra adalah "markas" bagi
Wâshil bin ‘Athâ’ [founding father-nya Muktazilah] untuk melancarkan gagasangagasan dan gerakannya.269
268
Yang pertama adalah guru besar bidang fikih, dan yang kedua adalah guru besar bidang kalâm
Wâshil bin ‘Athâ’, sebelum kemudian dikenal sebagai pendiri kelompok Muktazilah, adalah
salah seorang murid [’Abû] al-Hasan al-Bashriy di "madrasah"-nya. Sang murid memisahkan diri
(i'
tazala) dari Sang guru karena ada banyak perbedaan pendapat di antara keduanya, terutama
masalah "ketentuan Allah" (qadar). Sang murid kemudian mendirikan "madrasah" sendiri dan
menggalang pengikut. Peristiwa ini dikomentari oleh Sang guru dengan kata-kata: "i'
tazalnâ
Wâshil" ["Wâshil memisahkan dirinya dari kita"]. Sejak saat itu Wâshil dan murid-muridnya
disebut sebagai firqah mu'
tazilah ["kelompok yang memisah"]. Sementara itu, mereka tidak mau
diidentifikasi dengan sebutan itu, dan mereka menyebutkan sendiri nama identitas bagi kelompok
269
136
Basra dan Bagdad, yang merupakan dua kota terbesar di wilayah Persia
dengan segala prestasi budaya-intelektualnya yang melimpah dan agung pada
masa itu dan yang paling lama di diami al-Mâwardiy, adalah medan kultural yang
kondusif bagi dia untuk mengembangkan potensi intelektualitasnya. Di dasar
puncak-puncak keagungan kultural-intelektual Muslim di dua kota besar tersebut
khususnya dan di kota-kota besar yang lain pada umumnya, terdapat faktor sosialbudaya yang sangat penting: bahasa Arab. Tanpa bermaksud menampik peran
faktor-faktor sosial-budaya selain bahasa yang juga penting dalam bangunan
kebudayaan Islam abad X M, bahasa – dalam hal ini bahasa Arab – merupakan
"faktor material" sosial-budaya yang paling pokok sehingga bangunan
kebudayaan itu berdiri kokoh. Bahasa Arab pada masa itu merupakan bahasa
"nasional" Islam: alat komunikasi dalam pergaulan sehari-hari (interaksi sosial),
bahasa "resmi" negara, serta sekaligus "lokus" penghampiran dan medium
ekspresi intelektual.270 Dalam lapangan intelektual, penguasaan terhadap ilmu
mereka: al-Qadariyyah atau al-‘Adliyyah. Lihat, Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, al-Nazhariyyâtu alSiyâsiyyâtu al-’Islâmiyyah, Kairo: Maktabah Dâr al-Turâts, 1979, h. 75-6.
270
Khalifah ’Abû Ja‘far al-Manshûr [pendiri al-Daulat al-‘Abbâsiyyah, dibaiat pada tahun 136 H]
merupakan orang yang punya andil besar dalam proses Arabisasi di wilayah bekas kekuasaan
kerajaan Sasanid Persia itu, setelah '
pondasinya'dibangun oleh Khalifah ‘Umar bin Khaththâb jauh
sebelumnya. Pembangunan Basra sebagai kota militer Islam dan perdagangan, pembangunan
Bagdad sebagai Ibu Kota Khilâfah ’Islâmiyyah yang disebut Madînat al-Salâm dengan segala
infrastrukturnya yang lengkap dan megah, serta keberadaan lembaga ilmu pengetahuan Bait alHikmah adalah "artefak" sejarah yang menunjukkan fenomena Arabisasi itu. Puncak dari
fenomena itu adalah mengakarnya bahasa Arab bagi bangsa Persia yang "nyaris" menggusur
bahasa Persia sendiri. Fenomena itu masih bisa disaksikan hingga sekarang. Beberapa edisi
literatur penting yang mengabadikan sejarah Islam Abad Tengah di Bagdad dan kota-kota lain di
Irak antara lain: edisi karya al-Khathîb al-Baghdâdiy, Târîkh Baghdâd, Kairo: Maktabah
Kubrailiy, 1350 H., edisi karya ’Ibnu Khaldûn, Muqaddimah [Târîkh ’Ibnu Khaldûn], Beirut: Dâr
’Ihyâ’i al-Turâtsi al-‘Arabiy, 1978 M., edisi karya Yâqut al-Hamwiy, Târîkhu al-Buldân, Mesir:
Maktabah al-Khanjiy, 1906 M. Khusus mengenai fenomena perkembangan bahasa Arab di
wilayah "taklukan" ini dapat diapresiasi dengan lahirnya tokoh-tokoh besar ahli ilmu bahasa
Arab/penyair, seperti Sîbawaih [Basra, w. 180 H], al-Kisâ’iy (Basra-Bagdad-Ray, w. 189 H], al’Ashmu‘iy [Bagdad, w. 216 H], ’Ibnu Duraid [Basra, w. 321 H], dan masih banyak lagi yang lain.
Bahkan tokoh-tokoh besar di bidang keilmuan ini kebanyakan berasal dari kota-kota tersebut.
Perkembangan ini mudah dipahami karena masa kekuasaan Banî ‘Abbâsiyyah yang berpusat di
137
bahasa dan sastra Arab merupakan salah satu prasyarat pokok bagi seseorang
dapat diakui otoritas keilmuannya dalam bidang lain yang spesifik, seperti dalam
bidang tafsir, hadis, dan fikih. Karena tanpa penguasaan bahasa Arab secara
sempurna, bidang-bidang keilmuan yang spesifik itu tidak dapat dimasuki. AlMâwardiy
misalnya,
kepakarannya
di
bidang
fikih
dilandasi
dengan
kredibilitasnya dalam hal ilmu bahasa Arab. Dalam hal ini pun, al-Mâwardiy
bukan sekedar sebagai konsumen, melainkan ia adalah salah satu "produsen"
bahasa Arab. Terbukti, ia menulis sebuah buku: al-Nahw [Gramatika Bahasa
Arab, pen.], serta khazanah syair Arab banyak bertebaran di dalam buku-bukunya
yang lain, salah satunya adalah ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn.
Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa, secara sosiologis-genealogis,
konteks sosial-kultural yang melahirkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah
lingkungan tradisi sosial-intelektual ortodoksi Suni di Basra dan di Bagdad
khususnya, yang secara kultural kelahirannya ditopang dengan modalitas bahasa
Arab sebagai "lokus" penghampiran dan "medium ekspresi" intelektual Muslim
pada abad IV H/X M, seperti al-Mâwardiy.
2. Konteks Politik yang Melahirkan Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Pada Bab III telah diuraikan secara panjang-lebar dan rinci bagaimana situsi
politik Islam pada umumnya, dan secara khusus pertarungan politik antar elit
bersama massa di pusat kekuasaan Islam di Bagdad pada abad IV H/X M. Situasi
politik tersebut benar-benar disaksikan dan dialami oleh al-Mâwardiy. Ia bukan
Bagdad adalah masa puncak keemasan peradaban Islam. Untuk survei para ahli bahasa Arab dan
penyair ternama dapat melalui karya ’Abû al-Mahâsin [al-Tanûkhiy], Târîkhu al-'
Ulamâ’i alNahwiyyîn [410 H].
138
sekedar saksi pasif dari situasi carut-marut politik Islam yang telah berlangsung
selama kurang-lebih empat abad sebelumnya yang tidak mudah diselesaikan.
Bahkan ia menyaksikan situasi politik yang paling krusial di sepanjang sejarah
Khilafah Islam: hilangnya kekuatan (power) dan otoritas (authority) khalifah.
Terlepas dari segala kekurangan setiap khalifah, kekuatan dan otoritasnya
merupakan prasyarat penting untuk menjamin keberlangsungan khilafah dalam
menjaga ketertiban dan keamanan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan
sosial. Apalagi, al-Mâwardiy menyaksikan bahwa hilangnya kekuatan dan otoritas
institusi kekhalifahan bukan saja disebabkan oleh sikap hidup para khalifah yang
secara umum lebih cenderung mengabaikan kualitas moral kepemimpinan, atau
disebabkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan para pejabat negara yang semestinya
harus membantunya [kebetulan, mereka adalah para petinggi militer bersaudara:
Banî Buwaihiy, yang berafiliasi dengan faksi politik Syî‘ah], tetapi juga
disebabkan oleh ketiadaan sistem perundang-undangan politik dan peraturanperaturan pemerintahan.
Situasi-situasi krisis politik tersebut, baik yang bersifat praktis maupun
teoretis benar-benar disaksikan, dialami, dan diinsafi oleh al-Mâwardiy. Sebagai
warga negara yang relatif telah mengalami pencerahan, al-Mâwardiy berusaha
melibatkan dirinya secara aktif dalam kancah krisis. Dengan modalitas sosial dan
intelektual yang dimiliki, al-Mâwardiy dapat masuk ke dalam lingkungan
"birokrasi" [lingkungan yang memiliki wewenang membuat kebijakan dan
menetapkan keputusan]. Tidak tanggung-tanggung, al-Mâwardiy berhasil menjadi
pejabat negara dengan posisi yang sangat strategis: sebagai hakim hingga hakim
139
agung. Dialah orang pertama yang menjadi hakim agung dalam sejarah dunia
hukum dan pemerintahan Islam. Dalam konteks kebudayaan Islam secara umum
pada masa itu, jabatan hakim bukan saja bernilai strategis tetapi juga bersifat
prestisius dan sekaligus "sakral", apalagi hakim agung. Melalui jalur jabatan
"birokratis"
tersebut,
al-Mâwardiy
memegang
peranan
penting
dalam
menyelesaikan konflik-konflik politik, baik yang terjadi di tingkat elit (konflik
politik tingkat tinggi) maupun yang terjadi di tingkat massa.
Al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah ditulis al-Mâwardiy bukan dari "menara
gading" dunia intelektual yang jauh dari wilayah realitas politik praktis, bahkan ia
justru lahir di dalam kancah persaingan politik yang panas. Al-’Ahkâm alShulthâniyyah lahir di dalam pusat kekuasaan: sebuah ruang yang selalu menjadi
dambaan dan incaran oleh hampir semua orang, ruang yang telah meminta ratusan
ribu atau mungkin
jutaan nyawa kaum Muslimin terkorbankan, ruang yang
berkubang darah dan air mata.
Singkatnya, fenomena carut-marut dunia politik Islam pada abad IV H/X
M, yang berpangkal sejak peristiwa-peristiwa politis-tragis awal yang
menyebabkan pecahnya perang sipil yang pertama [perang antara pasukan
Khalifah ‘Aly melawan pemberontakan yang dipimpin ‘Â’isyah dan para
sekutunya] adalah "medan sejarah yang aktual" bagi kelahiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Persaingan politik yang keras di tingkat elit dan massa yang selalu
terjadi, berupa rebutan kekuasaan yang selalu mengaitkan kepentingan politik dan
agama, adalah salah satu faktor "ekstra-teoretis" yang pasti turut andil dalam
melahirkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Semula, ia lahir tampak sebagai upaya
140
intelektual agamis untuk "menata" fenomena itu menjadi "lebih baik", tetapi
fenomena itulah yang justru melahirkannya, membentuknya, dan mengarahkan
fungsinya seperti akan digambarkan lebih jelas berikut ini.
3. Konteks Budaya Intelektual [Wacana Politik] yang Melahirkan Al’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Berkaitan dengan data historis mengenai sejarah wacana politik Islam seperti telah
dipaparkan pada Bab III, diketahui bahwa budaya intelektual Islam hingga abad
IV H/X M tidak hanya bertumpu kepada bahasa dan budaya Arab. Fenomena itu
juga dihidupi oleh "angan-angan [imajinasi]" kaum Muslimin tentang tatanan
kehidupan yang ideal. Angan-angan, imajinasi, atau fantasi kolektif kaum
Muslimin itu merujuk kepada masa dan pengalaman sejarah tertentu, yaitu
kehidupan kaum Muslimin pada masa puncak keemasannya dalam kepemimpinan
Nabi Muhammad. Fantasi kolektif tersebut, yang tersimpul dalam konsep wihdatu
al-’ummati al-’Islâmiyyah ["kesatuan umat Islam"], merupakan sebagian faktor
yang mendorong dan mengarahkan tujuan-tujuan dari pikiran dan tindakan kaum
Muslimin.
Kenyataannya, meskipun kaum Muslimin memiliki fantasi kolektif dan
menambatkan angan-angan dalam lokus sejarah yang sama, tetapi terwujudnya
suatu kesamaan atau kolektifitas yang utuh dan sempurna dalam setiap operasi
penghampiran, persepsi, dan interpretasi terhadap lokus sejarah yang sama itu
sangat sulit terjadi. Karena proses ini sangat dipengaruhi oleh kepentingankepentingan, dorongan-dorongan, dan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan
141
kekuasaan sosial. Persepsi yang justru muncul adalah "kesatuan umat Islam tidak
akan terwujud kecuali dengan kesatuan kepemimpinan".271 Dan persis dalam
persepsi ini, terkait dengan dorongan-dorongan dan kepentingan-kepentingan
kekuasaan, umat Islam menjadi kelompok-kelompok yang saling mengajukan
klaim sebagai yang paling berhak atas kekuasaan. Dan dengan dalih persepsi
tersebut,
masing-masing
membangun
wacana
intelektual
yang
saling
mengasingkan. Setiap kelompok berjuang agar wacana intelektualnya yang
dianggap paling benar, dapat menjadi sumber wewenang yang terdalam bagi
kekuasaan, serta menjadi pedoman yang mengarahkan.
Dengan demikian kesimpulannya, imajinasi sosial kaum intelektual
Muslim abad IV H/X M tentang kesatuan kekuasaan Islam, serta persepsi-persepsi
mereka yang saling berkompetisi di dalam "ruang diskursif" kekuasaan adalah
faktor
teoretis-diskurif
yang
memungkinkan
kelahiran
al-’Ahkâm
al-
Shulthâniyyah.
4. Posisi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dalam Konteks Sosial, Politik, dan
Budaya Intelektual Islam Abad IV H/X M
Telah dijelaskan bahwa kelompok sosial yang melahirkan al-’Ahkâm alShulthâniyyah adalah orang-orang Suni, yaitu kelompok masyarakat Muslim yang
mengidentifikasikan dirinya sebagai pengikut dan penerus tradisi Nabi
Muhammad dan "konsensus" [tradisi mayoritas]. Kesimpulan ini dapat dipahami
dengan menelusuri genealoginya: asal-usul substansi pengetahuannya beserta
271
Lihat Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Op. Cit. H. 245-247
142
lingkup sosial yang menghidupinya. Dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah menempati posisi sebagai wacana pewaris-penerus
dari kelangsungan sejarah tradisi-tradisi itu, bahkan yang memperluas
wilayahnya. Ia juga sebagai buku yang mendokumentasikan momen peristiwa
perjumpaan antara tradisi-tradisi itu dengan fenomena historis yang baru, dan
sekaligus yang menampilkan proses dialog antara keduanya.
Dalam konteks sosial yang lebih luas, sebagai salah satu wujud ekspresi
intelektual masyarakat Suni, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah menempati posisi yang
bersinggungan dengan bentuk-bentuk ekspresi intelektual dari kelompok sosial
yang lain: Khawârij, Syî‘ah, Muktazilah, dan Murji‘ah. Maka, posisi al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah bersama bentuk-bentuk ekspresi intelektual yang lain tersebut,
masing-masing adalah sebagai wacana "kontestan" di dalam ruang "kompetisi
sosial" atau "ruang kebebasan diskursif". Di dalam arena kontesatsi sosial dan
wacana, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah pesaing bagi kontestan-kontestan
selainnya, demikian juga sebaliknya. Taruhan utama dari semua peristiwa
kompetisi ini adalah pemerolehan-pemertahanan identitas dan kekuasaan sosial.
Penjelasan posisi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai kontestan dan pesaing di
dalam konteks sosial tersebut berlaku juga di dalam konteks politik dan budaya,
karena kedua konteks yang terakhir ini juga menjadi ruang kontestasi dan
kompetisi bagi masing-masing ekspresi intelektual dari setiap kelompok sosial
yang ada. Perbedaannya: dalam konteks sosial setiap posisi diarahkan untuk
memperoleh dan mempertahankan identitas dan kekuasaan sosial, sedangkan
dalam konteks politik dan budaya setiap posisi bersaing dalam rangka
143
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (power) politik dan pengaruh
wewenang-wibawa (authority).
5. Efek Konteks Historis terhadap Isi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dan
Fungsinya
Sekarang, analisa diarahkan pada isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan fungsinya
dalam hubungannya dengan konteks historis yang melahirkannya untuk melihat
historisitasnya. Maksud utama analisa pada tahap ini adalah mengukur sejauh
mana suatu konteks historis tertentu berpengaruh terhadap pembentukan isi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah berikut pengarahan fungsinya. Atau, analisa ini hendak
menunjukkan bukti-bukti bahwa sebuah wacana tertentu yang terbangun di dalam
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah mengakar secara kuat ke dalam sejarah aktual dan,
pada saat sama, memiliki jangkauan fungsi. Inilah maksud dari historisitas al’Ahkâm al-Shulthâniyyah dalam perspektif sinkronis.
Keseluruhan isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sangat mungkin menjadi
obyek analisa. Namun tidak mungkin isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dituangkan
seluruhnya di sini. Pembahasan sebagai uji historisitas hanya akan diarahkan
terhadap konsep "imamah" guna menetapkan premis-premis khusus untuk
menarik kesimpulan secara umum. Langkah pembatasan ini bukan bermaksud
mereduksi isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah tetapi didasarkan pada tiga alasan:
(1) Karena al-Mâwardiy sendiri menekanan urgensi masalah imamah atas
masalah yang lain, seperti perkataannya berikut ini:
Imamah adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ketentuan-ketentuan
agama dan pangkal bagi terwujudnya kebaikan Umat hingga urusan
144
kepentingan umum. Dari kepemimpinan itulah lahir kekuasaan-kekuasaan
yang menangani wilayah-wilayah dan bidang-bidang urusan khusus. Maka,
pembahasan hukumnya harus didahulukan dari pembahasan hukum-hukum
pemerintahan yang lain............[dst., pen.].272
(2) Karena konsep "imamah" merupakan pokok dari keseluruhan isi al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah, sebagaimana arti yang tersirat dari perkataan al-Mâwardiy
tersebut.
(3) Karena konsep "imamah" dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sering menjadi
referensi utama dalam kajian politik Islam hingga sekarang.
Analisa ini disusun dengan kerangka pembahasan sebagai berikut: (a)
historisitas konsep "imamah", dan (b) implikasi ideologis konsep "imamah".
A. Historisitas Konsep Imamah
“Tidak baik manusia ['
masyarakat'
, pen.] hidup lepas-bebas tanpa
kepemimpinan; dan tidak akan terwujud kepemimpinan [yang baik, pen.]
jika orang-orang bodohnya yang berperan memimpin."273
Al-’Afwah al-’Audiy
"Kekuasaan (al-mulk) dengan agama (al-dîn) akan tegak lestari, dan
agama dengan kekuasaan akan kuat berdiri."274
‘Abdullâh ibn al-Mu‘taz
Al-Ghazâliy menyatakan bahwa keamanan, kerjasama, dan keteraturan adalah
kebutuhan-kebutuhan manusia yang fundamental. Kebutuhan manusia itu akan
272
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah., h. 3
Kalimat ini adalah ungkapan seorang penyair Arab Jâhiliyyah (pra Islam): al-’Afwah al’Audiy, yang dikutip al-Mâwardiy ketika dia memulai pembahasan konsep ’imâmah-nya. Lihat alMâwardiy, Loc. Cit.
274
Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, h. 97
273
145
terpenuhi jika ada hukum-hukum umum tertentu yang dihormati/dipatuhi oleh
semua orang, dan ada organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan
mengatur.275 Organisasi itu lazim dimengerti sebagai organisasi politik atau
negara. Terlepas dari mana pun asal kekuasaan yang dimiliki negara, semua teori
tentang negara menyatakan bahwa kekuasaan itu harus ada dan diperuntukkan
menciptakan kebaikan bagi masyarakat di wilayah kekuasaannya.276
Dalam masalah itu, al-Mâwardiy berpendapat bahwa imamah didirikan
untuk menggantikan fungsi kenabian: menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh
karena itu, pembentukannya adalah wajib. Al-Mâwardiy menyatakan:
Imamah diwujudkan sebagai ganti kenabian dalam menjaga agama dan
mengatur dunia. Mengangkat seseorang sebagai Imam dalam kehidupan
konsensus Sahabat atau ulama'
,
Umat adalah wâjib277 berdasarkan ijmak ['
pen.], walaupun al-’Asham keluar dari konsensus mereka.278
Dari ungkapan tersebut jelas bahwa al-Mâwardiy meletakkan masalah
pendirian negara dan kepemimpinannya di dalam wilayah agama. Inti terdalam
negara dalam konsep al-Mâwardiy adalah fungsinya sebagai pengganti kenabian.
275
Lihat al-Ghazâli, al-’Iqtishâd wa al-’I‘tiqâd, Mesir: al-Mathba‘atu al-Mahmûdiyyah, h. 135
Lihat Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia, Jakarta,
1996, h. 117
277
Istilah wâjib tidak dapat langsung diterjemahkan dengan kata "wajib", "harus", atau "mesti".
Dalam konteks al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, dan umumnya dalam konteks literatur Islam, istilah
tersebut mengandung konotasi religius. Yang dimaksud adalah "kewajiban, keharusan, atau
kemestian yang bersifat agama dan dengan sanksi yang juga bersifat agama: jika dikerjakan akan
memperoleh balasan pahala [’ajr, tsawâb] dari Allah, dan jika ditinggalkan akan memperoleh
balasan siksa ['
iqâb, '
adâzb] dari-Nya. Catatan-catatan linguistis-semantis tersebut penting, bukan
sekedar karena memenuhi tuntutan kaidah penerjemahan teks. Hal itu dilakukan lebih karena
alasan bahwa di dalam istilah-istilah/definisi-definisi yang dikatakan al-Mâwardiy secara '
lepas'
tersebut justru tersimpan fenomena historisitas-diakronis konsep-konsep al-Mâwardiy yang sangat
dalam.
278
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 5
276
146
Secara teologis, acuan konsep bahwa negara berfungsi sebagai pengganti
kenabian berpangkal kepada satu doktrin (nas) Alquran bahwa nabi pembawa
risâlah Allah yang terakhir adalah Muhammad. Alquran menegaskan:
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.279
Pernyataan ayat itu meskipun disebutkan hanya sekali dalam Alquran dan
terkait dengan konteks historis tertentu, merupakan pernyataan yang tegas tentang
posisi Muhammad di antara manusia dan para nabi selainnya. Ini adalah satu
doktrin yang sangat diyakini oleh orang-orang yang beriman sejak ayat itu
diturunkan, hingga munculnya klaim kenabian orang-orang yang murtad pasca
Muhammad wafat. Atas dasar keyakinan tentang kebenaran doktrin tersebut, Abû
Bakr al-Shiddîq selaku penguasa kaum Muslimin kemudian, menumpas habis
gerakan orang-orang murtad itu. Setelah penumpasan itu, tidak pernah muncul
lagi di lingkungan kaum Muslimin, orang-orang yang mengklaim diri sebagai
nabi kecuali klaim dari salah satu aliran Syî‘ah yang menyatakan "kenabian" ‘Aly
bin ’Abî Thâlib serta fenomena "nabi baru" seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ini
artinya, tidak ada orang-orang Muslim yang meragukan atau menolak doktrin
tersebut di atas kecuali orang-orang yang memang sengaja ingin keluar dari Islam
atau ingin membuat fenomena baru di dalam Islam selain mainstream yang ada.280
279
Q.S. Al-’Ahzâb (33):40.
Kecenderungan yang terakhir tersebut telah dimulai sejak ‘Abdullâh bin Saba’ [seorang Yahudi
dari Yaman yang memeluk Islam] menyebarluaskan opini-opini tentang keistimewaan ‘Aly bin
’Abî Thâlib yang melebihi semua orang termasuk Nabi Muhammad, pada masa kekuasaan
Khalifah ‘Utsmân bin ‘Affân. Lihat Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, al-Nazhariyyâtu al-Siyâsiyyât al’Islâmiyyah, Kairo: Maktabah Dâru al-Turâts, 1979, h. 55.
280
147
Demikian juga, di lingkungan kaum Muslimin generasi awal tidak pernah
muncul wacana yang menginginkan agar tidak usah diwujudkan kepemimpinan
Islam pasca Nabi wafat. Karena kenyataannya, Nabi wafat tidak hanya
meninggalkan ajaran-ajaran, melainkan bahkan mewariskan suatu komunitas
Muslim (al-mujtama‘ al-’Islâmiy) dengan identitas sosial dan politik yang jelas.281
Kenyataan ini sangat diinsafi oleh para Sahabat. Mereka sadar bahwa Nabi wafat
serta "ajaran langit" berhenti turun, tetapi bagaimana kelanjutan dari kehidupan
komunitas sosial dan politik mereka yang telah terbentuk dengan kokoh? Harus
ada kepemimpinan yang menggantikan/meneruskan kepemimpinan Nabi, harus
ada pemimpin dalam kehidupan umat Islam yang menggantikannya. Demikianlah
aspirasi yang pasti di kalangan Sahabat, terutama mereka yang senior. Itulah
aspirasi yang dikatakan atau tidak dikatakan, yang mendorong elit-elit Ansar dan
Muhâjirîn berkumpul di Saqîfah Banî Sâ‘idah, bahkan ketika jasad Nabi pun
belum diurus pemakamannya. Itulah juga aspirasi ‘Aly bin ’Abî Thâlib dan
Sahabat-sahabat yang lain, meskipun mereka ingin menunda dalam sementara
waktu untuk membicarakan masalah itu dan tidak hadir di forum Saqîfah. Itulah
juga aspirasi kaum Muslimin dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu di
setiap momen suksesi, hingga sampai ke konteks sejarah al-Mâwardiy.
Lalu, mengapa al-Mâwardiy mesti menyatakan aspirasi itu kembali seperti
pernyataannya di atas? Bukankah soal kepemimpinan Islam yang harus selalu ada,
benar-benar telah menjadi aspirasi umat Islam?Bukankah hal itu merupakan
281
Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Ibid., h. 25.
148
tuntutan realitas sejarah yang jelas? Dalam konteks apakah pernyataan alMâwardiy itu? Serta, apa tujuannya?
Pernyataan al-Mâwardiy bahwa kepemimpinan Islam harus diwujudkan
dan di dalam tubuh umat Islam harus ada pemimpin (za'
îm atau imâm)282
menunjukkan: dia sependapat dengan aspirasi sebagaimana tersebut di atas yang
merupakan mainstream opinion mayoritas besar umat Islam sejak awal hingga
pada masanya. Pernyataan pendapat al-Mâwardiy ini penting mengingat terdapat
sebagian kecil umat Islam yang memiliki aspirasi atau pendapat yang berbeda.
Sebenarnya, sejak kelahiran kelompok Khawârij pada masa Khalifah ‘Aly,
kelompok ini telah memunculkan sebuah gagasan baru tentang "kebebasan" yang,
dalam konteks waktu itu, berarti bebas dari kekuasaan Khalifah ‘Aly maupun
penentangnya: Mu‘âwiyah. Gagasan ini terus dikembangkan oleh salah satu aliran
Khawârij: Najdât [pengikut Najdah bin ‘Athiyyah bin ‘Amir al-Hanafiy], dan
berkembang pula secara luas di lingkungan Muktazilah (al-Qadariyyah). Seperti
telah dipaparkan pada Bab III, dua aliran dan kelompok tersebut menyatakan
bahwa orang-orang Muslim tidak perlu pemimpin dan mengikutinya, mereka
hanya perlu menunaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka
masing-masing dan saling berlaku adil, serta tolong-menolong dalam kebaikan
dan takwa.283 Tokoh-tokoh Muktazilah yang gigih menyebarkan gagasan ini
adalah ’Abû Bakr al-’Asham, Hisyâm bin ‘Amru al-Fûthiy, dan ‘Ubbâd bin
282
Lihat al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 3&5.
Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Op. Cit., h. 144, yang mengutip narasi al-Syahrastâniy dalam Nihâyatu
al-’Iqdâm fî '
Ilm al-Kalâm, h. 481. Survei lebih lanjut tentang masalah ini dapat merujuk kepada
’Abû al-Hasan al-Asy‘ariy, Maqâlât al-’Islâmiyyîn wa ’Ikhtilâf al-Mushallîn, Turki: Thab‘ah
’Istanbul, 1930, vol. 2, h. 460, dan kepada ‘Abd al-Qâhir al-Baghdâdiy, ’Ushûl al-Dîn, Turki:
Thab‘ah ’Istanbul, 1928, h. 271.
283
149
Sulaimân.284 Inilah salah satu opini yang berkembang dan berhadapan langsung
dengan al-Mâwardiy. Maka kesimpulan dari uraian di atas bahwa kepentingan alMâwardiy menyatakan pendapatnya itu sangat terkait dengan konteks historis
yang dihadapinya, yaitu opini "kebebasan" yang diusung sebagian umat Islam.
Kemudian soal bahwa aspirasi tentang kepemimpinan Islam pasca Nabi
merupakan opini yang memiliki akar kuat dalam realitas sosial dan politik umat
Islam, bagi al-Mâwardiy hal itu bukan realitas sejarah yang biasa. Fenomena itu
sangat terkait dengan "nasib" misi kenabian: nasib Islam. Selain itu, aspirasi atau
opini itu juga dihidupi oleh mayoritas besar umat Islam sejak peristiwa Nabi wafat
hingga masa hidup al-Mâwardiy. "Aspirasi mayoritas besar", itu fenomena sejarah
yang luar biasa.
Terkait dengan "nasib" misi kenabian, nasib Islam dengan segala prestasi
sosial dan politik yang telah melekat kepada umat Islam di bawah kepemimpinan
Nabi, merupakan taruhan masa depan yang tidak dapat disepelekan. Demikianlah
kurang-lebih suasana pikiran umat Islam pada umumnya ketika menerima
kenyataan Nabi wafat. Hal itu sebagaimana tergambar dari petikan pidato ’Abû
Bakr berikut ini:
Hai manusia, barang siapa menghamba kepada Muhammad, maka
sesungguhnya Muhammad benar-benar telah mati. Dan barang siapa
menghamba kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan
tidak akan pernah mati. Tidak ada lain Muhammad itu kecuali seorang
284
Khawârij Najdât (pengikut Najdah bin ‘Amir al-Hanfiy dan ‘Athiyyah bin ’Aswad al-Hanafiy),
dan Muktazilah (Qadariyyah) pengikut ’Abû Bakr al-’Asham, Hisyâm bin ‘Amr al-Fûthy, dan
‘Ubbâd bin Sulaimân, orang-orang yang mengembangkan wacana "kebebasan" ini ditengarai
sebagai kelompok filsuf Muslim yang telah menerima pengaruh pemikiran filsafat Plato (Platonis).
Dalam konteks Barat modern pemikiran-pemikiran politik "kebebasan" mereka sama seperti
pemikiran-pemikiran filsafat: H. Spenser [Man Versus the State] dan William Godwin [The
Political Justice]. Lihat, Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Ibid., h. 146-7
150
rasul yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul yang lain. [Syahrastâniy
mengisahkan, sampai ’Abû Bakr berkata:] Sesungguhnya Muhammad
telah menempuh jalan misinya, dan harus ada orang yang berdiri
menggantikannya untuk hal ini. Pikirkan dan ungkapkan pendapat
kalian.285
Orang-orang yang menyaksikan sepakat dengan perkataan ’Abû Bakr, dan
tidak ada seorang pun yang menyatakan pendapat sebaliknya, atau bahwa misi
Muhammad
tidak
harus
dilanjutkan,
meskipun
ada
orang-orang
yang
menginginkan agar masalah itu tidak langsung diputuskan secepatnya karena
butuh pemikiran dalam rangka memilih orang yang tepat.
Kesepakatan tentang urgensi masalah ini berlanjut ke dalam forum Saqîfah
yang berhasil menetapkan ’Abû Bakr sebagai orang yang diberi wewenang
menggantikan misi Nabi. Hal itu berlangsung terus-menerus hingga masa alMâwardiy. Fenomena inilah yang dimaksud sebagai "kesepakatan besar" dari
"mayoritas besar" umat Islam. Dalam pandangan al-Mâwardiy dan ulama Suni
sebelumnya, hal ini merupakan fenomena sejarah yang "luar biasa". Oleh karena
itu dia menyatakan konsep "imamah"-nya seperti tersebut di atas. Fenomena
sejarah itu akhirnya dijustifikasi sebagai sesuatu yang benar-benar "luar biasa"
oleh para ulama ortodoksi Suni: fenomena agama dengan sanksi agama. Mereka
menganggap bahwa imamah, sebagaimana teraktualisasikan dalam sejarah Islam
pasca Nabi, adalah tuntutan agama. Alasan-alasan dasar dari tesis ini adalah: 1)
imamah melaksanakan fungsi kenabian, 2) imamah diinginkan oleh mayoritas
besar umat Islam sejak pendiriannya, dan dihidupi oleh mereka dalam rentang
285
Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Ibid., Kairo: Maktabah Dâru al-Turâts, 1979, h. 132 dari sumber alSyahrastâniy dalam Nihâyatu al-’Iqdâm fî '
Ilm al-Kalâm, h. 479.
151
waktu yang panjang, yang disebut fenomena ijmak.286 Ijmak yang semula
merupakan fenomena yang murni historis kemudian diangkat satusnya oleh
ortodoksi Suni sebagai bagian dari [dasar] agama. Ijmak adalah kaidah yang
paling dasar bagi Ahli Sunah untuk membangun pemikiran tentang imamah yang
telah dirintis oleh al-Syâfi‘iy,287 dan al-Mâwardiy adalah penerusnya.288 Inilah
konteks dan sekaligus alasan, kenapa al-Mâwardiy menyatakan bahwa pendirian
kepemimpinan Islam adalah wajib atas dasar ijmak.
286
Di sini perlu ditambahkan keterangan mengenai konsep "ijmak" (’ijmâ‘) meskipun telah di
paparkan pada Bab III sebagai data metodologis, karena terkait alasan-alasan historis
kemunculannya seperti baru saja dijelaskan, dan konsep metodologis itu berperan penting dalam
pembentukan isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Sekaligus, pembahasan ini merupakan langkah
persiapan untuk analisa metodologis nanti. Al-Syâfi‘iy dianggap orang yang paling berjasa
merintis konsep ijmak sebagai metodologi dalam lapangan fikih, khususnya dalam masalah
’imâmah. Ijmak dalam konsep al-Syâfi'
iy adalah antitesis dari dua kecenderungan metodologis
utama yang saling bertentangan pada waktu itu, yaitu metode pencarian petunjuk pemecahan
masalah dari hadis seperti yang dipegang oleh "pendukung hadis" (’ahl al-hadîts) serta metode
penalaran akal murni yang dipegang oleh "rasionalis" Muktazilah. Dua kecenderungan ini, seperti
telah dipaparkan pada Bab III, memiliki kelemahan. Metode yang pertama memiliki kelemahan
berupa kecondongannya yang membabi-buta terhadap hadis sehingga memunculkan hadis-hadis
palsu yang menguntungkan mazhabnya, sementara metode yang kedua terjerumus kepada
penafsiran akal bebas yang "semena-mena". Al-Syâfi‘iy mengajak kepada mujtahid dari kedua
tradisi itu untuk menyandarkan pencarian petunjuk pemecahan masalahnya dari "fenomena
faktual" [al-wâqi‘] atau dari "kenyataan" [al-haqîqah], yaitu fenomena fakta kehidupan umat
Islam pada masa lalu, khususnya kehidupan umat Islam pada masa keemasannya: masa alkhulafâ’u al-râsyidûn [empat khalifah pembimbing: ’Abû Bakr, ‘Umar bin Khaththâb, ‘Utsmân
bin ‘Affân, dan ‘Aly bin ’Abî Thâlib, pen.], - dalam keyakinan al-Syâfi‘iy, di situlah terletak "ruh
Islam yang benar" – serta hal-hal yang menjadi "konsensus" dari "mayoritas besar" uamt Islam di
setiap masa. Konsep ijmak ini masih dipertajam lagi oleh al-Syâfi‘iy dengan konsep "kias" (qiyâs).
Ijmak dan kias adalah dua konsep al-Syâfi‘iy yang saling terkait sebagai alternatif metodologis
dari "kelemahan" dua kecenderungan metodologis sebelumnya yang saling berhadap-hadapan.
Konsep ijmak al-Syâfi‘iy benar-benar menyiapkan lahirnya konsep "Ahli Sunah Waljamaah"
dalam tataran sosial umat Islam. Lihat Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Ibid., h. 102.
287
Al-Syâfi‘iy, karena jasa-jasanya dalam merintis metodologi ’ushûl al-fiqh [prosedur berpikir
hukum Islam, pen.], terutama jasanya dalam merintis penggunaan konsep ijmak dan kias, dianggap
sebagai "Aristoteles"-nya Islam. Lihat ’Ibn al-Nadîm, al-Fahrasat, Mesir: al-Maktabatu alTijâriyyah, h. 295.
288
Metode ijmak dan kias yang paling banyak dipakai al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm alShulthâniyyah benar-benar menunjukkan bahwa dia merupakan penerus tradisi metodologi alSyâfi‘iy, dan kutipan pendapat al-Mâwardiy seperti telah dikemukakan di atas adalah juga
pendapat Abû al-Hasan al-Asy‘ariy, seorang '
founding father'
-nya Ahlu Sunah Waljamaah di
bidang '
ilm al-kalâm. Lihat, al-’Asy‘ariy, Maqâlât al-’Islâmiyyîn wa ’Ikhtilâf al-Mushallîn,
’Istanbul: Thab‘ah ’Istanbul, 1930, vol. 2, h. 460. Sebelum al-Mâwardiy, pendapat al-’Asy‘ari
telah dijadikan posisi teoretis yang mendasar oleh ‘Abd al-Qâhir [al-Baghdâdiy]. Lihat alBaghdâdiy, ’Ushûl al-Dîn, Istanbul: Thab‘ah ’Istanbul, 1928, h. 271. Setelah al-Mâwardiy, posisi
yang sama diteruskan oleh ’Ibn Hazm, al-Ghazâliy, Fakhru al-Dîn [al-Râziy], al-Nawawiy, alTaftazâniy, kemudian ’Ibn Khaldûn. Lihat Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Op. Cit., h. 103.
152
Di atas telah dinyatakan bahwa imamah dikonsepsikan al-Mâwardiy
sebagai pengganti/pelanjut fungsi kenabian: menjaga agama (Islam) dan mengatur
dunia. Dengan demikian, imamah dikonsepsikan secara teologis dan mengandung
dimensi-dimensi ibadah (suatu hubungan tanggung jawab penghambaan manusia
terhadap Penciptanya). Oleh karena itu mekanisme pendirian imamah harus diatur
dengan ketentuan-ketentuan (qânun atau hukm) agama, bukan aturan-aturan
akal.289
Konsepsi al-Mâwardiy tentang imamah tersebut sebenarnya masih terkait
dengan konteks perbedaan pendapat mayoritas versus pendapat minoritas tentang
masalah ini, seperti telah dibahas tadi. Sebagai tambahan penjelasan, sebenarnya
inti perbedaan dari dua kelompok besar pendapat itu terletak dalam hal "sumber
kebenaran pengetahuan", termasuk sumber pengetahuan tentang imamah:
"agama" versus "akal". Dalam tataran sosial, gagasan yang pertama dihidupi oleh
kelompok ’ahl al-hadîts / ’ahl al-sunnah yang mengerucut, antara lain, menjadi
289
Oleh karena pendirian negara diwajibkan oleh syariat, menurut Al-Mâwardiy, hukum-hukum
yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia adalah ajaran agama (Al-Kitâb) yang
dianugerahkan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Hukum-hukum Allah itu
diberlakukan di dunia untuk menciptakan kebaikan manusia dan menetapkan pokok-pokok
kebenaran. Para penguasa (’uly al-’amr) adalah wakil Allah untuk menetapkan keputusankeputusan dan kebijakan-kebijakan pengaturan. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, pembawa
ajaran-ajaran-Nya, wakil Allah pertama yang menunaikannya dengan benar. Dengan demikian,
’imâmah dimaksudkan al-Mâwardiy sebagai kepemimpinan Islam yang mengatur kehidupan
manusia dengan Alquran sebagaimana kepemimpinan yang telah dilaksanakan oleh Nabi
Muhammad. Nabi Muhammad dan penguasa umat Islam yang diangkat untuk menggantikannya
adalah institusi yang berwenang mengatur/memerintah. Lihat, Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm alShulthâniyyah, h. 4. Di tempat lain Al-Mâwardiy menyatakan: "wajib mengangkat ’imâm sebagai
penguasa dan pemimpin Umat, agar Agama terjaga dengan kekuasaannya dan kekuasaannya
berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan tradisi agama." Dengan demikian, urusan agama dan
urusan dunia tidak dapat dipisahkan: agama dan politik harus menyatu. Karena itu, Al-Mâwardiy
mengutip sebuah syair ’Abdullah bin Mu‘taz: "Kekuasaan (al-mulk) dengan agama (al-dîn) akan
tegak lestari, dan agama dengan kekuasaan akan kuat berdiri." Demikianlah penjelasan lebih lanjut
tentang fungsi kepemimpinan Islam dalam konsep al-Mâwardiy. Lihat, al-Mâwardiy, ’Adab alDunyâ wa al-Dîn, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, h. 97
153
Ahli Sunah Waljamaah, dan gagasan kedua dihidupi oleh ’ahl ra’y yang
mengerucut, antara lain, menjadi kelompok Muktazilah (al-Qadariyyah).290
Dalam hal mekanisme pembentukan imamh, perbedaan pendapat
keduanya digambarkan al-Mâwardiy berikut ini:
Keharusan mendirikan imamah diperselisihkan, apakah berdasarkan
[ditentukan oleh, pen.] akal ataukah syariat. Sebuah kelompok
mewajibkannya berdasarkan akal, karena ada kecenderungan naluri orangorang yang berakal untuk menyerahkan kepada seorang pemimpin agar
bertindak mencegah orang-orang saling berbuat aniaya serta memisah
pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Jika tanpa pemimpin,
mereka akan menjadi liar tak terkendali. Al-’Afwah al-’Audy, penyair
jâhiliy [pra Islam, pen.] mengatakan: '
Tidak baik manusia ['
masyarakat'
,
pen.] hidup lepas-bebas tanpa kepemimpinan; dan tidak akan terwujud
kepemimpinan [yang baik, pen.] jika orang-orang bodohnya yang berperan
memimpin.' Kelompok yang lain mengatakan, kewajiban pendirian
kepemimpinan itu didasarkan [ditentukan oleh, pen.] syariat, bukan akal.
Karena seorang Imam berdiri dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat
syariat, yang terkadang akal memikirkannya sebagai sesuatu yang hanya
'
boleh'(mujawwaz) dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang terkait
dengan pengabdian kepada Tuhan (ta‘abbud).291 Akal hanya
mengharuskan kepada setiap orang berakal agar tidak saling menganiaya
dan memutus hubungan, agar selalu berbuat adil dalam pergaulan, dan
agar bertumpu kepada kemampuan akal sendiri bukan akal orang lain.
Tetapi, syariat telah datang dengan menyerahkan urusan-urusan
[pengaturan, pen.] kepada penguasa yang [telah, pen.] ditentukan di dalam
agama [Islam, pen.]. Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung telah
berfirman: '
Hai orang-orang beriman, patuhilah Allah, patuhilah RasulNya, dan patuhilah '
penguasa urusan'di antara kalian.292
290
Diskusi yang sangat intensif mengenai perbedaan paham di antara dua kelompok Muslim
tersebut dalam konteks pemikiran politik dapat dilihat dalam Dhiyâ’u al-Dîn al-Rais, Op. Cit., h.
127-152, atau ’Ibn Khaldûn, al-Muqaddimah, Kairo: al-Mathba‘atu al-Azhariyyah, 1930, h. 159161.
291
Seperti pendapat ’Abû Bakr al-’Asham, Hisyâm bin ‘Amru al-Fûthiy, dan ‘Ubbâd bin
Sulaimân. Selain orang-orang ini berpendapat bahwa kepemimpinan '
boleh ada-boleh tidak ada'
(jawâz atau mubâh), mereka juga berpendapat bahwa seandainya terdapat suatu kepemimpinan,
keberadaannya dalam kehidupan sosial tidak melebihi konteks "hubungan sosial" saja
(mu‘âmalah), atau kepemimpinan bukan merupakan bagian dari masalah hubungan manusia
dengan Tuhan (‘ibâdah). Dalam bidang fikih atau teologi Islam secara umum, istilah jawâz atau
mubâh berarti status hukum yang bersifat paling "dasar" dan "netral" yang dikenakan kepada
semua perbuatan manusia demi memenuhi kebutuhan kemanusiaannya yang paling mendasar
seperti makan dan minum. Teologi Islam menganggap orang "boleh makan atau minum, boleh
juga tidak", sepanjang tidak ada petunjuk-petunjuk (dalîlât) atau alasan-alasan (qarînât) syariat
yang mewajibkannya atau melarangnya.
292
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 5
154
Lalu, di mana posisi al-Mâwardiy dalam konteks perbedaan pendapat dari
dua kelompok tersebut? Kata-kata al-Mâwardiy berikut ini cukup menjelaskan, ia
berkata: "[Dengan berdasar pada ayat Alquran tersebut, pen.], maka Allah
menetapkan kewajiban (farradha)293 kepada kita patuh kepada penguasa urusan
yang ada di antara kita, mereka adalah para Imam yang [berwenang, pen.]
memerintah atas kita."294
Dari uraian tersebut menjadi jelas sekarang, di mana akar sejarah yang
spesifik, yang telah mendorong al-Mâwardiy menyatakan pemikirannya tentang
dasar-pokok kepemimpinan Islam. Konteks sejarah tersebut benar-benar telah
menunjukkan bahwa konsep "imamah" al-Mâwardiy sangat terkait dengan
kecondongannya terhadap nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang dianut oleh
kelompok sosialnya (Suni), terkait dengan keyakinan-keyakinannya tentang nilai
dan tradisi itu yang dicoba dipertahankannya dengan cara sedemikian rupa, serta
pada saat yang sama terkait dengan nilai atau tradisi yang dianut oleh kelompok
sosial lain (Khawârij Najdât dan Muktazilah pengikut ’Abû Bakr al-’Asham) yang
berbeda yang dicoba ditentangnya dengan cara sedemikian rupa. Konteks sejarah
itu telah menunjukkan betapa teori imamah yang diusung al-Mâwardiy tunduk
kepada historisitasnya. Ia bukan sesuatu yang "mutlak transenden" melainkan
suatu produk budaya yang "ditransendensikan". Analisa ini tidak perlu
diperpanjang kepada teori imamah al-Mâwardiy lebih jauh yang lebih rinci,
karena pokok-pokok isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan fungsinya seperti
293
Sebuah istilah yang spesifik dipakai dalam bidang fikih dengan pengertian yang sama dengan
istilah wâjib adalah fardh.
294
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
155
pembahasan di atas telah cukup menggambarkan keseluruhannya, dan tidak akan
diperoleh kesimpulan yang berbeda dengan perspektif analisis yang sama. Karena
pokok-pokok isi yang telah di bahas itu benar-benar merupakan inti terdalam al’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan dasar bagi al-Mâwardiy untuk menyusun atau
mengembangkan teorinya lebih lanjut.
B. Implikasi Ideologis Konsep Imamah
Analisa di atas telah menunjukkan konteks historis dan wilayah diskursus yang
melingkupi teori al-Mâwardiy tentang imamah, hingga dapat disimpulkan
historisitasnya. Analisa berikut ini akan melihat kemungkinan lebih jauh dari
historisitas konsep "imamah" tersebut, yaitu fungsinya atau implikasi-implikasi
ideologisnya.
Kemungkinan
yang
terakhir
ini
akan
ditempuh
dengan
mempertimbangkan fungsi konsep "imamah" dalam konteks praktik kekuasaan
pada masanya (melalui perspektif kritik sejarah secara sinkronis).
Telah dijelaskan pada Bab III bahwa kelahiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah berada di dalam momentum krisis politik yang paling
"menggelisahkan". Krisis politik itu ditandai dengan semakin hilangnya kekuatan
dan otoritas Khalifah sebagai penguasa tertinggi dalam konsep kepemimpinan
Islam.295 Tidak ada orang/kelompok yang paling gelisah karena menyaksikan
fenomena krisis politik itu, kecuali mereka yang jelas dirugikan atau menerima
akibat jelek dari fenomena tersebut. Mereka adalah Khalifah ‘Abbâsiyyah
bersama patron-patron sosial-politiknya. Mereka menggalang usaha bersama
295
Lihat Bab III, h. 81-82, juga analisa "Konteks Politik yang Melahirkan al-’Ahkâm alShulthâniyyah ", h. 132-134.
156
untuk mengembalikan situasi krisis politik itu pada kondisi yang diinginkan
seperti semula: restorasi.
Dalam konteks di mana Khalifah dinasti ‘Abbâsiyyah yang semakin
kehilangan
kekuatan
dan
pamornya,
dan
di
tengah
upayanya
untuk
mengembalikan kekuasaannya, ia jelas membutuhkan jaminan hukum yang
mempu melegitimasi posisi dan kekuasaannya itu. Tentu, strategi yang paling
ampuh bagi Khalifah adalah jalinan koalisi dengan aliran-aliran Islam, yang
secara kasat mata mereka juga menaruh perhatian dan berkepentingan dengan
politik. Karena aliran-aliran Islam bukanlah sebagi aliran agama yang murni
melainkan juga faksi-faksi politik.
Khalifah dinasti ‘Abbâsiyyah yang sedang mengalami "impoten" tidak
mungkin berkoalisi dengan Syî‘ah, karena meskipun awalnya mazhab ini adalah
pendukung utama dinasti ‘Abbâsiyyah untuk naik tahta dengan menyingkirkan
Khalifah dinasti ‘Umâwiyyah dan ikut menyebarkan propaganda bahwa
kemunculan dinasti ‘Abbâsiyyah adalah sama artinya dengan kebangkitan
kepemimpinan keluarga Nabi, tetapi Syî‘ah jugalah yang telah berperan dalam
menggerogoti kekuasaannya bersama petinggi-petinggi militer dinasti Buwaihiy
dari Dailam, sehingga otoritas khalifah hanya tinggal simbol belaka.
Khalifah dinasti ‘Abbâsiyyah juga tidak mungkin berkoalisi dengan
Muktazilah, meskipun ia pernah berjaya bersama mereka pada masa Khalifah alMa’mûn dan al-Rasyîd. Tetapi, Muktazilah telah menorehkan noda sejarah
dengan melancarkan program mihnah yang membawa korban nyawa yang tidak
157
sedikit dari orang-orang yang menentangnya, sehingga mengakibatkan kemarahan
kelompok mayoritas Suni.
Demikian juga halnya, khalifah tidak mungkin berkoalisi dengan
Khawârij, karena selain mereka hanya kelompok minoritas dan selalu menjadi
"gerakan bawah tanah pengacau keamanan", dengan prinsip-prinsip kebebasan
yang mereka semboyankan seperti telah disebutkan di atas, mereka adalah
kelompok yang tidak mau berkompromi dengan siapapun, mereka adalah para
"ekstremis-anti-damai-langsung-sikat". Citra "anarkis" sangat melekat pada
identitas gerakan mereka, karena mereka memang membolehkan cara-cara anarki
untuk meraih tujuan-tujuan. Faksi ini sangat ditentang, baik oleh faksi Suni
maupun oleh faksi Syî‘ah, dan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mazhab
Muktazilah.
Maka, koalisi paling strategis bagi kepentingan Khalifah ‘Abbâsiyyah
kemudian adalah bersama mazhab Suni, atas dasar berbagai pertimbangan. Suni
adalah mazhab mayoritas; mereka bukan saja rakyat awam, tetapi juga kalangan
terpelajar yang menyebar luas di berbagai bidang keilmuan. Lebih dari itu, Suni
merupakan tandingan yang sepadan dengan Syî‘ah dalam hal ortodoksi; Suni
adalah lawan yang sejajar dengan Muktazilah dalam hal isu "rasionalisasi"; dan,
Suni adalah lambang "supremasi" hukum Islam.
Selanjutnya, khalifah memang bahu-membahu dengan faksi Suni untuk
mengembalikan kekuasaannya, dan salah satunya adalah dengan cara meminta
para kaum intelektualnya, terutama para pejabat pembantunya yang diangkat
158
menjadi hakim agar memikirkan landasan hukum yang dapat dimanfaatkan sebagi
sandaran legitimasi.
Al-Mâwardiy adalah salah seorang elit intelektual Suni pada masa itu. Al’Ahkâm al-Shulthâniyyah, seperti dikatakan Al-Mâwardiy sendiri, ditulis karena
alasan-alasan yang menunjukkan arah kepentingan itu. Al-Mâwardiy berkata:
Hukum tatanegara (al-’ahkâm al-shulthâniyyah) sangat penting bagi para
penguasa (wullât al-’umûr), sementara keberadaannya selama ini masih
berkumpul dengan kajian-kajian hukum yang lain, sehingga menyulitkan
mereka untuk mempelajarinya, apalagi mereka sibuk dengan urusan politik
dan pembangunan negara. [Karena itu, pen.] Saya kemudian menyusun
hukum tatanegara itu secara tersendiri dalam satu kitab, dalam rangka
melaksanakan perintah seorang yang wajib dipatuhi, agar dia dapat
mengetahui pendapat-pendapat para ahli fikih (madzâhib al-fuqah )
mengenai hak-haknya sehingga ia berusaha memperolehnya, dan
mengetahui kewajiban-kewajibannya sehingga ia dapat melaksanakannya
dengan baik; berusaha berbuat adil dalam melaksanakan kebijakan
kepemimpinanya, adil dalam memutuskan hukum, dan adil dalam
mengambil
hak-haknya
dan
dalam
memberikan
kewajiban296
kewajibannya.
Al-Mâwardiy
menunjukkan
dengan
jelas
alasan-alasan
yang
melatarbelakanginya sehingga ia menulis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Alasan
demi alasan tersebut disampaikan oleh al-Mâwardiy dengan bahasa yang ringan
dan lugas. Sepintas pandangan, alasan-alasan al-Mâwardiy itu masuk akal dan
selaras dengan tuntutan situasi dan kondisi historisnya. Setidaknya, ada tiga alasan
utama al-Mâwardiy menulis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan perlu dicermati
dengan lebih seksama.
Pada alasan pertama, al-Mâwardiy menunjukkan situasi wacana hukum
tatanegara pada saat itu yang masih berserakan di mana-mana dan bercampur
296
Lihat Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 3
159
dengan kajian hukum-hukum yang lain, sehingga ia tergerak menulis buku yang
secara spesifik berisi kumpulan hukum tatanegara, yaitu al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Situasi yang ditunjukkan al-Mâwardiy dan yang menjadi salah
satu alasannya untuk menulis buku itu sungguh tepat, karena semula umat Islam
memang tidak mengenal adanya hukum-hukum tatanegara hingga ulama berhasil
mengumpulkan dan membukukan hadis.297 Di dalam buku-buku hadis itu,
masalah tatanegara hanyalah satu bab dari puluhan bab yang membicarakan
masalah-masalah yang lain. Seiring waktu dengan pembukuan dan pembakuan
hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran, teks-teks hadis
merupakan rujukan penting ulama untuk merumuskan pandangan-pandangan
297
Meskipun Islam telah menjadi suatu entitas politik yang besar dan kuat sejak Nabi masih hidup,
tetapi Alquran tidak menyatakan secara eksplisit dan lengkap mengenai mekanisme atau sistem
yang mengatur tegaknya entitas politik Islam itu sebagai sebuah negara. Alquran tidak
mendefinisakan prinsip apapun dengan jelas tentang negara. Pengertian dan ide tentang konstitusi,
konsepsi tentang kedaulatan yang jelas, prinsip pemilihan pemimpin, dan rincian peraturanperaturan tentang organisasi negara, tidak diberikan oleh Alquran di tempat mana pun. Sejauh
menyangkut masalah tatanegara, Alquran hanya memberikan petunjuk-petunjuknya secara umum
bagi Nabi dan komunitas umat Islam yang dipimpinnya. Kenyataan posisi Alquran terhadap
masalah tatanegara yang seperti itu tidak mengalami perubahan/perkembangan hingga Nabi wafat,
yang berarti berakhir pula proses pewahyuan Alquran. Bahkan Abû Bakr pun tidak dapat
menemukan landasan teoretis kekhalifahan, karena semasa akhir hidupnya, dia mengatakan telah
melakukan satu kesalahan bahwa dia tidak bertanya kepada Nabi untuk menjernihkan persoalan
kepemimpinan. Dia berkata: "Seharusnya saya bertanya siapa yang akan menggantikannya dalam
kekuasaan politik setelah kematiannya?" Ibnu Qutaibah, al-’Imâmatu wa al-Siyâsah: Târîkhu alKhulafâ’, Mesir: al-Muassasatu al-Halabiy wa al-Syarîkah, tt., Jilid I, h. 19
Sampai berakhirnya masa khulaf’u al-râsyidûn-pun, negara Islam berjalan dengan tanpa
adanya sistem politik yang baku yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengorganisasikan
kekuasaan, sehingga dinamika politik Islam berlangsung dengan cepat tanpa sisetm kontrol,
berubah-ubah, dan bahkan radikal. Politik kenegaraan berjalan mengikuti alur dinamika sejarahnya
sendiri. Radikalisme praktek politik Islam bahkan telah terjadi sejak masa awal, yang ditandai,
anatara lain, dengan terbunuhnya para khalifah: ‘Umar bin Khaththâb, ‘Ustmân bin ‘Affân, ‘Aly
bin ’Abî Thâlib, Hasan bin ‘Aly bin ’Abî Thâlib, dan Husain bin ‘Aly bin ’Abî Thâlib. Fenomena
politik yang radikal seperti ini terus berlangsung hingga masa kekuasaan dinasti ‘Umâwiyyah dan
dinasti ‘Abbâsiyyah.
Barulah pada masa kekuasaan Mu‘âwiyah (pendiri kekuasaan dinasti ‘Umâwiyyah)
mulai tumbuh pemikiran-pemikiran politik sebagai tanggapan atas peristiwa-peristiwa politik yang
baru dan kasuistik, dan wacananya semakin berkembang luas seiring dengan pertumbuhan
pemikiran-pemikiran di bidang hukum dan lain-lain. Sampai pada masa awal kekuasaan dinasti
‘Abbâsiyyah, pemikiran-pemikiran politik mulai dikembangkan oleh orang-orang yang menaruh
perhatian serius di bidang itu secara skolastik.
160
mereka terhadap masalah-masalah baru yang muncul melalui proses ijtihad.
Selain ulama merujuk kepada Alquran dan hadis dalam proses ijtihad, mereka
juga merujuk kepada ijmak serta memakai metode kias. Hasil ijtihad ulama, yang
kebanyakan menyatakan status hukum masalah-masalah temporer dan kasuistik,
dikumpulkan ke dalam satu bidang wacana yang disebut fikih. Penyusunan bukubuku fikih pun mengikuti sistematika penyusunan buku-buku hadis. Oleh karena
itu, masalah yang berkenaan dengan hukum tatanegara juga ditulis dan
dikumpulkan menjadi satu dengan hukum-hukum yang lain di dalam buku-buku
fikih.298 Maka, usaha yang dilakukan Al-Mâwardiy untuk membahas masalah
hukum tatanegara secara tersendiri dengan menulis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
dalam konteks alasan ini, merupakan upaya perluasan wacana hukum tatanegara
Islam secara umum, dan secara spesifik kitab itu dimaksudkannya sebagai
'
konstitusi kepemimpinan Islam'
.
Dalam konteks krisis politik seperti di atas, yang pada taraf tertentu
sebagian disebabkan oleh tidak adanya peraturan baku yang berfungsi sebagai
hukum konstitusi, kehadiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dapat dimanfaatkan
sebagai landasan dan rujukan utama bagi praktik politik dan pemerintahan.
Pada alasan kedua, al-Mâwardiy menyatakan bahwa penyusunan al’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah dalam rangka memenuhi perintah seorang yang
wajib ditaati. Meskipun al-Mâwardiy tidak menyebutkan dengan jelas siapa orang
298
Telah dilihat jasa rintisan al-Syâfi‘iy dalam proses ini yang kemudian dikembangkan lebih
lanjut oleh murid-muridnya. Metodologi ’ushûl al-fiqh yang disusun al-Syafi‘iy telah memberikan
kemungkinan bagi murid-muridnya untuk mengembangkan teori tata negara menjadi sebuah
sistem konstitusi yang utuh [qânûn dustûriy], yang salah satu sumber materialnya adalah praktik
hukum-politik yang telah dijalankan dan disepakati atau diterima oleh masyarakat Islam pada
masa lalu.
161
yang dimaksudkannya itu, dapat dimengerti bahwa orang itu adalah Khalifah alQâ’im Biamrillâh (berkuasa: 422-467 H), karena ia adalah yang mengangkat alMâwardiy menjadi hakim agung.299
Oleh karena kehadiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah tidak terlepas dari
kepentingan
khalifah mengenai
landasan
hukum
untuk
mengembalikan
otoritasnya yang dirampas oleh dinasti Buwaihiy, keadaan ini sangat
mempengaruhi perspektif yang mesti digunakan al-Mâwardiy dalam menyusun
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, seperti tampak pada alasannya yang terakhir.
Pada alasan yang ketiga terlihat bahwa perspektif yang digunakan alMâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah perspektif seorang
intelektual Islam ortodoks yang memandang realitas kekuasaan, dengan sentuhan
idealitas untuk memperkuat posisi penguasa. Posisi ortodoks dan sentuhan
idealitasnya nampak dari kata-katanya tentang hukum tatanegara yang bersumber
dari pendapat-pendapat para ahli fikih; dan perspektif kepentingan penguasa
tampak sekali, karena Al-Mâwardiy lebih mendahulukan hak-hak penguasa
daripada kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya, perspektif kepentingan penguasa
ini juga tampak dari alasannya yang pertama dan kedua.
Berdasarkan analisa terhadap alasan-alasan yang dikemukan al-Mâwardiy
tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kehadiran al-’Ahkâm alShulthâniyyah berfungsi sebagai perluasan wacana teori hukum tatanegara,
bahkan sebagai sistem konstitusi Islam. Maka dalam konteks ini, kelahiran al’Ahkâm al-Shulthâniyyah dapat dipandang sebagai sumbangan berharga dalam
299
Lihat catatan ke-149 pada halaman 82, lihat juga Yâqût al-Hamwiy, Mu'
jam al-’Adibbâ’, vol. 5,
h. 407
162
dunia politik Islam waktu itu, baik pada tataran wacana maupun praktik. Namun
di sisi lain, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sangat terkait dengan kebutuhan khalifah
untuk mengembalikan kekuasaannya. Dalam konteks ini, al-’Ahkâm alShulthâniyyah juga merupakan semacam “wacana martir” dari al-Mâwardiy yang
mendukung restorasi khalifah vis à vis kekuasaan para amîr dan sultan dinasti
Buwaihiy yang mendominasi.
Secara khusus terkait dengan konsepsi "imamah", nuansa maksud alMâwardiy untuk memperkuat kekuasaan khalifah, semakin terindikasi lebih jelas
ketika ia menerangkan lebih jauh tentang posisi khalifah sebagai "wakil" Allah
untuk menegakkan ajaran-ajaran-Nya di bumi dan mengatur dunia.300 AlMâwardiy mengatakan:
Syariat telah datang dengan menyerahkan urusan dunia dan agama kepada
penguasa, Allah '
Azza wa Jall berfirman: '
Hai orang-orang yang beriman,
patuhilah Allah, patuhilah Rasul-Nya dan para penguasa urusan di antara
kalian'
.301 Allah mewajibkan atas kita patuh terhadap penguasa yang ada di
antara kita. Mereka adalah para pemimpin yang memerintah kita.302
Indikasi lain yang menunjukkan maksud al-Mâwardiy itu juga terlihat jelas
dari pernyataannya mengenai posisi Imam sebagai sentral kekuasaan atau
penguasa tertinggi. Al-Mâwardiy mengatakan:
Allah SWT menggariskan bahwa dalam Umat harus ada pemimpin yang
menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, yang kekuasaannya
meliputi pengaturan agama dan politik, supaya pemerintahannya
bersumber dari syariat agama, dan mengumpulkan aspirasi ke dalam satu
visi kepemimpinan yang diikuti.303
300
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 3
Q.S. An-Nisâ’: 59
302
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 5
303
Al-Mâwardiy, Ibid., hal. 3
301
163
Secara umum, teori tersebut dapat dipahami dan diterima oleh siapapun.
Tetapi, sesungguhnya teori itu dapat dimanfaatkan khalifah sebagai landasan
untuk mengembalikan kekuasaannya yang kian melemah. Karena melalui
ungkapan tersebut, secara tidak langsung, al-Mâwardiy menolak kenyataan
dominasi para amir dan sultan dinasti Buwaihiy atas kekuasaan khalifah, serta
kecenderungan penguasa-penguasa daerah yang ingin melepaskan diri dari
keutuhan imamah. Secara implisit ungkapan al-Mâwardiy tersebut dapat dipahami
bahwa khalifah/Imam adalah orang yang kekuasaannya bersumber dari Allah,
yang harus dipatuhi (bukan malah didominasi atau ditentang), dan yang memiliki
kekuasaan penuh mengatur agama dan dunia (bukan malah diatur-atur atau
peraturannya ditentang). Kesimpulannya, konsep al-Mâwardiy tersebut yang
tampak normatif-teologis, sebenarnya mengandung fungsi historis yang bersifat
temporal dan sosial, yaitu fungsi ideologis: memihak kepentingan khalifah.
Selanjutnya, kecenderungan ideologis konsep "imamah" al-Mâwardiy
dapat dirasakan ketika dia memberikan nilai "sakral" terhadap lembaga imamah
dengan menyebutnya sebagai pengganti fungsi/tugas kenabian, seperti telah
disebutkan di muka. Dia juga memberi nilai yang sama kepada pemegangnya:
yaitu Imam/khalifah. Mereka dikatakan al-Mâwardiy sebagai "wakil" pemegang
"mandat" Allah; mereka diangkat oleh/dengan dan untuk syariat; dan oleh karena
itu, syariat juga menuntut agar mereka dipatuhi.
Dalam konteks historis seperti di atas, labelisasi syar‘iy (bersifat syariat)
dan legitimasi "kesucian" dari pernyataan-pernyataan al-Mâwardiy baik terhadap
lembaga kekuasaan maupun pemegangnya tersebut, pastilah merupakan hal yang
164
menjadi keinginan dan harapan khalifah. Terlepas dari substansi makna ayat yang
dikutip al-Mâwardiy itu, pemunculan dan penekanan ayat tersebut pada saat itu
memiliki
relevansi
dengan
kepentingan
khalifah
untuk
memulihkan
kekuasaannya. Ayat tersebut ditunjukkan al-Mâwardiy kepada khalifah, sebagai
sumber syar‘iy bagi legalitas hak kepatuhan dan legitimasi kekuasaannya.
Implikasinya, al-Mâwardiy dengan sengaja menyembunyikan realitas
sejarah kekuasaan-penguasa pada waktu itu dan dalam rentang masa tiga abad
sebelumnya yang sangat jauh dari apa yang diteorikannya, sehingga teori alMâwardiy tersebut tampak idealis, bahkan seperti utopis. Al-Mâwardiy tidak
melihat secara kritis praktik imamah/khilafah sejak periode itu hingga masa
hidupnya yang jelas ada perbedaan signifikan. Sesungguhnya sejak Nabi wafat,
“jubah khilâfah” (mahkota kekuasaan) menjadi obyek yang diperdebatkan,
diperebutkan, dan bahkan penyebab utama terjadinya “fitnat al-kubrâ”. "Jubah
khilâfah" menjadi taruhan pertentangan antar kaum Muslimin di medan
pertempuran. Apa yang kemudian terjadi sebenarnya adalah kekuasaan
imamah/khilafah ditegakkan di atas kekuatan tentara, modalitas ekonomi, sosial,
dan politik: siapa orang yang menguasai dan mampu mengendalikan semua itu,
dialah yang berkuasa dan mengabsahkan diri sebagai khalifah, seperti tampak
pada proklamasi diri Mu‘âwiyah sebagai khalifah.
Maka, labelisasi "kesucian" dan legitimasi al-Mâwardiy terhadap lembaga
kekuasaan dan penguasa, sesuai dengan konteks historisnya, adalah justru
merupakan salah satu bentuk dari ideologi yang berarti menyembunyikan
kebohongan: kebohongan tentang realitas sejarah khilafah yang "kotor"
165
berlumuran darah dan air mata. Kecenderungan ideologis semacam inilah yang
ikut andil dalam melanggengkan situasi kekuasaan khalifah yang "tertutup"
(mahjûb)304 oleh dinding tebal istana dan keperkasaan tentara/algojo-algojo;
kekuasaan yang jauh dari jangkauan rakyat jelata; sehingga melahirkan penguasapenguasa absolut yang tiranik.
Labelisasi dan legitimasi al-Mâwardiy terhadap kesakralan dan kesucian
lembaga kekuasaan dan penguasa yang tampak sederhana dan dikatakannya
secara normatif itu, ternyata membawa implikasi yang lebih jauh lagi terhadap
pengembangan teorinya kemudian. Teori politik al-Mâwardiy yang sejak semula
menggunakan perspektif kepentingan kekuasaan dan penguasa itu, dalam
perkembangannya telah secara nyata berusaha membuat institusi ini menjadi
sangat kuat, dan sebaliknya, mengebiri hak-hak kerakyatan dan menyingkirkan
rakyat jauh-jauh dari altar istana kekuasaan.
Kemudian, dengan cara yang sangat sistematis dan dengan menggunakan
teknik-teknik yang diklaim sebagai hal yang bersifat syariat, al-Mâwardiy
menteorisasikan mekanisme pengangkatan dan penurunan Imam, tugas-tugasnya,
dan hak-haknya. Masalah-masalah ini akan diperiksa lebih mendalam dengan
mempertimbangkan implikasi-implikasi ideologisnya.
304
Situasi ini dalam peradaban Arab Pertengahan terkenal dengan istilah hijâb al-khilâfah ["tabir
kekuasaan"]. Khalifah ditabiri karena ia merepresentasikan pemusatan kekuasaan yang berbahaya:
kekuasaan untuk membunuh. Tabir-tabir khalifah itu berupa dinding-dinding istana yang tinggi
dan tebal, tentara pengawal dan algojo yang perkasa, aturan-aturan protokoler dan segala bentuk
ritual istana. Sebuah risalah yang banyak memberikan informasi tentang hal ini dan disajikan
dalam bentuk cerita anekdot adalah Risalah al-Jâhizh, "Kitâb al-Hijâb", dalam Rasâ'
il al-Jâhizh,
Kairo: Maktabat al-Khanjiy, 1968, vol. 2, h. 25-86; dan Kitâb al-Tâji fi Akhlâqi al-Mulûk, Beirut:
Al-Syarîkah al-Lubnâniyyah li al-Kitâb, tt. Dalam kitab yang kedua ini, al-Jâhizh menyajikan
pembahasan panjang mengenai penggunaan tabir khalifah, termasuk situasi di mana ia
dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyembunyikan khalifah dari rakyatnya.
166
Jika al-Mâwardiy mengatakan bahwa pendirian lembaga kekuasaan dan
pengangkatan Imam adalah wajib secara syariat, maka kewajiban itu hanya
didasarkan pada ijmak. Kewajiban itu berbentuk fardu kifayah, seperti kewajiban
jihad dan mencari ilmu. Artinya, jika ada orang yang menjalankannya dari orangorang Islam yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur atas orang lain.305
Pendasaran kewajiban kepada ijmak tersebut adalah sebagai konsekuensi
langsung dari kenihilan dasar-dasar argumentasi yang mewajibkan hal itu di
dalam Alquran dan sunah. Ijmak yang dimaksudkan al-Mâwardiy secara khusus
mengacu kepada peristiwa pengangkatan Abû Bakr sebagai khalifah pertama.
Ijmak dalam konteks ini adalah kesepakatan-kesepakatan politik yang terjadi di
kalangan elit Ansar dan Muhajirin dalam hal pemegang tampuk kekuasaan Islam.
Peristiwa itu tidak perlu dipaparkan lagi secara rinci di sini, karena selain telah
sering disinggung di atas, hal itu sudah lazim diketahui dan selalu ditulis dalam
literatur sejarah Islam. Yang paling penting dikatakan di sini adalah bahwa alMâwardiy hanya menerima peristiwa itu apa adanya, dan memanfaatkannya
sebagai dasar yang pasti bagi kewajiban pendirian imamah dan pengangkatan
Imam.
Al-Mâwardiy jelas tidak melihat peristiwa itu secara kritis, misalnya peran
Umat secara keseluruhan dalam penentuan suksesi itu. Kecenderungan yang tidak
kritis mengenai hal ini tidak hanya dilakukan oleh al-Mâwardiy, tetapi juga
dilakukan oleh seluruh yuris Suni yang berusaha menyusun teori politik Islam.
305
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 5
167
Sesungguhnya, kecenderungan demikian telah membawa implikasi
ideologis yang sangat jauh terhadap teori politik Islam. Inti dari implikasi itu
adalah pengebirian hak-hak rakyat (umat secara keseluruhan) untuk ikut serta
dalam proses penentuan hasil suksesi secara khusus, dan pengebirian hak-hak
mereka dalam seluruh wilayah politik pada umumnya. Suksesi kekuasaan dan
keputusan-keputusan politik yang penting yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak, hanya ditentukan oleh segelintir "orang-orang penting" yang ada di
lingkaran pusat kekuasaan, dan rakyat hanya diposisikan pada wilayah kepatuhan
terhadap apapun yang menjadi hasil keputusan politik dari lingkaran elit itu.
Di bawah ini akan ditunjukkan bukti-bukti yang mendukung tesis yang
dikemukakan tadi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) kewajiban
mengangkat Imam, (2) penetapan persyaratan dewan pemilih dan persyaratan
calon Imam, serta mekanisme pengangkatannya, (3) tugas-tugas Imam, (4)
mekanisme penurunan Imam, (5) kudeta dan pemberontakan, dan (6) hak
kepemimpinan wanita.
1. Nuansa Ideologis Kewajiban Pengangkatan Imam
Dalam hal kewajiban mengangkat Imam, Al-Mâwardiy mengatakan:
Jika tidak ada seorang pun yang menegakkan imamah, maka kewajiban
itu dibebankan kepada dua kelompok: pertama adalah orang-orang yang
mempunyai wewenang memilihkan Imam bagi Umat; kedua, adalah
orang-orang yang mempunyai kompetensi menjadi Imam sehingga mereka
menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapun
orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas
penundaan pengangkatan Imam.306
306
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 5-6
168
Teori al-Mâwardiy tersebut patut dipertanyakan: pertama, peristiwa
sejarah yang mana dalam pengalaman umat Islam, ketika tidak ada seorang pun
yang berusaha menegakkan imamah? Meskipun al-Mâwardiy mengatakan kasus
tersebut dengan kalimat pengandaian, pengandaian itu jelas mangada-ada. Karena,
tidak pernah ada dalam sejarah Islam pada setiap momen suksesi, terjadi
kekosongan kepemimpinan yang disebabkan karena tidak ada orang yang
menaruh perhatian pada masalah itu. Justru sebaliknya, setiap orang, terutama
para elit yang paling berkompeten, selalu berkompetisi untuk meraih kekuasaan.
Ingatlah peristiwa suksesi pertama, ketika Nabi wafat dan bahkan jasadnya saja
belum dikebumikan, para elit sudah lebih dulu berkompetisi untuk menentukan
penggantinya sebagai Imam baru Islam.
Kedua, al-Mâwardiy membahasakan kebutuhan kepemimpinan Islam
dengan istilah "kewajiban" (fardu), yang artinya merupakan tanggung jawab yang
terkait dengan hak-hak ketuhanan sehingga hal itu terkait dengan hukum dosa/
siksa bagi orang-orang yang mengabaikannya. Sekaligus, dia menganggap proses
pengangkatan ’imâm seolah sebagai tanggung jawab yang berat dan besar,
sehingga merupakan "kewajiban" yang hanya terkait dengan orang-orang tertentu
saja yang dianggap berkompeten. Untuk arti yang pertama, mungkin saja hal itu
benar, dan hal itu tidak perlu didiskusikan di sini. Tetapi, benarkah proses
pengangkatan Imam hanya soal '
kewajiban'dengan konsekuensinya yang sudah
diketahui? Kenapa al-Mâwardiy tidak mendiskusikan masalah ini dari sisi '
hak'
semua orang, sehingga konsekuensinya; setiap orang atau umat secara
menyeluruh memiliki hak yang sama atas masalah ini? Jika saja al-Mâwardiy mau
169
mendiskusikannya secara demikian, selain ia tidak perlu mengandai-andai, ia akan
menaruh perhatian yang besar terhadap hak-hak umat seluruhnya dalam hal
suksesi, dan hak-hak mereka dalam relasinya dengan kekuasaan secara
menyeluruh. Atau mungkin, al-Mâwardiy justru memaksudkan teori itu sebagai
pembatasan hak-hak politik rakyat, dan sebaliknya menekankan bahwa
suksesi/politik adalah hak eksklusif orang-orang yang dianggap istimewa (mereka
yang berkompetensi saja). Hal terpenting mengenai hak politik rakyat inilah yang
justru hilang dari teori imamah al-Mâwardiy. Ini adalah suatu implikasi ideologis
yang tak terpikirkan.
2. Nuansa Ideologis Mekanisme Pengangkatan Imam
Setelah al-Mâwardiy mengemukakan syarat-syarat kompetensi "dewan pemilih"
dan "orang-orang yang memiliki kompetensi menjadi Imam",307 ia mengatakan
bahwa mekanisme yang sah untuk mengangkat Imam ada dua cara: (1) dengan
cara pemilihan oleh "dewan pemilih", dan atau (2) dengan cara penyerahan
mandat dari Imam sebelumnya.308 Teori al-Mâwardiy ini adalah bagian dari
konsekuensi karena ia mendasarkannya kepada ijmak.
Pada mekanisme yang pertama, al-Mâwardiy hanya mendiskusikan
tentang jumlah minimal anggota "dewan pemilih", yang secara keseluruhan
dikembalikannya kepada arsip-arsip praktek masa lalu. Ia sama sekali tidak
mendiskusikan bagaimana proses pengangkatan "dewan pemilih" di sini, dan
justru mendiskusikannya di saat ia mengelaborasi teorinya untuk mekanisme yang
307
308
lihat al-Mâwardiy, Loc. Cit.
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
170
kedua, yaitu bahwa Imam dapat memandatkan kekuasaannya kepada satu
orang,309 atau dua orang, atau bahkan lebih310 yang ia pilih untuk memegang
jabatan
Imam,
atau
memandatkannya
kepada
"dewan
pemilih"
agar
bermusyawarah untuk menentukan orang yang akan memegang jabatan Imam.311
Jelas
sekali,
al-Mâwardiy
tidak
menyebutkan
mekanisme
pemilihan/pengangkatan "dewan pemilih", kecuali ia dipilih/diangkat oleh Imam.
Bukankah ini sebuah simalakama? Sebuah situasi yang menggambarkan "jeruk
makan jeruk"? Bagaimana ini? Al-Mâwardiy pun mengemukakan dalihnya:
Imam adalah orang yang paling berhak atas jabatan kepemimpinan, maka
[kepada siapa pun ia memandatkannya, pen.] pilihannya itu lebih dapat
dipertanggungjawabkan, dan keputusannya mengenai hal itu lebih kuat
[memiliki kepastian hukum, pen.].312
Apalagi dalam hal jumlah anggota "dewan pemilih", al-Mâwardiy tetap
mengakui keabsahan jabatan Imam seandainya pengankatannya hanya dilakukan
oleh seorang anggota "dewan pemilih" saja. Untuk hal ini, al-Mâwardiy
mengemukakan argumen dengan menceritakan peristiwa pengangkatan ‘Aly bin
’Abî Thâlib sebagai khalifah. Al-Mâwardiy berkata:
‘Abbâs berkata kepada ‘Aly bin ’Abî Thâlib r.a: '
Bentangkanlah
tanganmu, aku membaiatmu'
. Orang-orang yang mengetahui hal itu, lalu
mengatakan: '
Paman Rasulullah s.a.w. telah membaiat anak pamannya,
maka tidak ada orang lain yang dapat menentangmu [‘Aly bin ’Abî Thâlib,
pen.]. Karena baiat ‘Abbâs adalah sebuah hukum, dan hukum [yang
diputuskan, pen.] satu orang adalah sah'
.313
309
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 10
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 13
311
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 10
312
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
313
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 7
310
171
Bagaimana mungkin al-Mâwardiy menteorisasikan hal ini sedemikian
rupa? Teori al-Mâwardiy yang menyangkut mekanisme pengangkatan Imam
tersebut disebabkan oleh barbagai latar belakang, baik latar belakang metodologis
maupun, terutama, latar belakang historis. Dan yang penting, teori itu memiliki
implikasi-implikasi ideologis yang tidak dapat diabaikan. Terkait hal itu, akan
dikemukakan beberapa tesis sebagai berikut:
Pertama, teori-teori Al-Mâwardiy tersebut disebabkan oleh latar belakang
metodologi yang dipakainya untuk menetapkan mekanisme pengangkatan Imam,
yaitu metode ijmak. Metodologi ini benar-benar telah membatasi al-Mâwardiy
untuk mau mengelaborasi teorinya itu. Ia hanya terpaku kepada arsip-arsip masa
lalu, dan arsip-arsip ini diperlakukannya sebagai ketentuan-ketentuan pasti dan
mengikat yang harus dipakai dan mesti diikuti. Ia tidak mengajukan pemikiran
kritis apapun terhadap arsip-arsip itu. Dan, ia juga tidak memikirkan implikasiimplikasi apa pun yang mungkin saja dapat terjadi sebagai akibat langsung dari
teorinya itu. Terkait dengan kepentingan ideologis, patut dikatakan bahwa alMâwardiy memang sengaja mendiamkan semua masalah ini.
Kedua, teori al-Mâwardiy mengenai syarat-syarat kompetensi yang harus
dipenuhi oleh "dewan pemilih" maupun calon Imam, mengindikasikan dengan
jelas bahwa al-Mâwardiy bermaksud untuk membatasi kepentingan imamah
hanya terkait dengan hak para elit tertentu saja. Rakyat secara umum, tidak
memiliki hak dan kompetensi, baik hak memilih Imam, apalagi hak untuk dipilih
menjadi Imam. Apapun argumentasi ijmak yang dibangun al-Mâwardiy mengenai
hal ini, justru semakin membuktikan bahwa ijmak telah diterapkannya sebagai
172
"hakim" yang membatasi ruang gerak intelektual dan hak-hak politik rakyat. Ada
kepentingan apa di balik teori-teori itu? Untuk mengetahui lebih jauh, teori-teori
Al-Mâwardiy itu harus diletakkan ke dalam konteks sejarah politik Islam. Tetapi,
sekarang belum saatnya membahas kepentingan-kepentingan itu di sini,
melainkan nanti pada saat membahas teori kabsahan sistem permandatan.
Masih ada satu hal yang penting yang harus dibahas terlebih dahulu
sekarang, yang terkait dengan teori al-Mâwardiy mengenai persyaratan yang harus
dipenuhi bagi calon Imam. Satu hal penting ini tidak mungkin diabaikan begitu
saja. Al-Mâwardiy mengemukakan bahwa persyaratan yang ke-7 bagi seorang
calon Imam adalah "ia keturunan dari suku Quraisy, karena adanya nas tentang
hal itu dan telah terwujudkannya ijmak ulama tentang masalah itu."314
Terlepas dari klaim al-Mâwardiy mengenai adanya nas dan ijmak tentang
masalah itu, yang sebenarnya merupakan masalah kontroversial,315 teori alMâwardiy tersebut harus dilihat dari sisi kepentingannya dalam konteks sejarah
politik Islam.
Persaingan politik yang telah terjadi sejak Nabi wafat, sebenarnya bukan
hanya mengambil bentuk persaingan antar klan (misalnya, persaingan antara
314
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 6
Masalah kontroversial ini, sedikit telah penulis singgung dalam catatan kaki pada bab
Pendahuluan. Di sana telah dinyatakan bahwa apa yang disebut al-Mâwardiy sebagai nas
mengenai masalah ini adalah pernyataan ’Abû Bakr terhadap kelompok Ansar: "Imam-imam
adalah dari orang-orang Quraisy", yang diklaimnya sebagai perkataan Nabi. Dan yang dimaksud
al-Mâwardiy dengan pernyataannya bahwa telah ada ijmak mengenai maslah itu adalah
penerimaan kelompok Ansar terhadap klaim ’Abû Bakr. Tetapi, ’Ibnu Qutaibah telah
menunjukkan bahwa ’Abû Bakr pun tidak begitu yakin mengenai landasan yang pasti tentang
siapa yang berhak menjadi Imam setelah Nabi. ’Ibnu Qutaibah menceritakan di antara perkataan
Abû Bakr dalam menanggapi aspirasi yang berkembangh di Saqîfah Banî Sâ‘idah: "Seharusnya
saya bertanya siapa yang akan menggantikannya dalam kekuasaan politik setelah kematiannya,
dan seharusnya saya menanyakan kepada Nabi apakah kaum Anshâr berhak berbagi kekuasaan
politik?". Lihat, ’Ibnu Qutaibah, al-’Imâmatu wa al-Siyâsah: Târîkhu al-Khulaf , Mesir: alMuassasatu al-Halabiy wa al-Syarîkah, tt., Jilid I, h. 19
315
173
keturunan Hâsyimiyyah-‘Umâwiyyah), melainkan juga antar suku dan bahkan
lintas kerajaan. Apalagi sejak masuknya daerah-daerah non Arab ke dalam
teritorial kekuasaan [Arab] Islam. Secara sosio-politis, suku Quraisy khususnya
dan bangsa Arab pada umumnya tentu memiliki status tertinggi karena berbagai
alasan, antara lain: mereka lebih dulu memeluk Islam dan yang mengenalkannya
kepada masyarakat lain; meskipun pendatang, tetapi mereka datang sebagai
bangsa “penakluk”.316
Bahkan, eksklusifitas dan hak dominasi bangsa Arab
sengaja dilindungi melalui perangkat hukum, sebagaimana hal itu tampak pada
pendapat ’Abû Hanîfah317 mengenai hukum jizyah, meskipun al-Mâwardiy tidak
sependapat dengannya. ’Abû Hanîfah berkata: “Aku tidak memungut jizyah itu
dari orang Arab, agar mereka tidak menjadi hina karena itu”.318
Pada masa hidup al-Mâwardiy, persaingan politik itu semakin kental dan
mengambil bentuk yang nyata, yaitu dinasti-dinasti penguasa lokal banyak yang
memberontak, baik untuk melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat
maupun untuk menguasai pemerintahannya. Mereka adalah dinasti Thâhir di
Persia, dinasti Thûlûn dan dinasti Fâthimiyyah di Mesir, dinasti Buwaihiy di
Turki, dan lain-lain. Dinasti Buwaihiy-lah yang berhasil menguasai pemerintahan
pusat di Bagdad pertama kali, yang kemudian di susul oleh dinasti Fâthimiyyah.
Jabatan khalifah, meskipun masih dipegang oleh dinasti ‘Abbâsiyyah yang
316
Hadis-hadis yang menerangkan kelebihan Quraisy dan hak istimewa mereka atas jabatan
’imâm, dikumpulkan oleh Muslim dalam kitab Shahîh pada bab "’Imârah".
317
Salah seorang intelektual Suni yang memiliki otoritas yang sangat tinggi dan dikenal
"rasionalis".
318
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 143. Jizyah adalah pajak yang harus dibayar oleh warga non-Muslim
kepada penguasa Islam.
174
notabene adalah keturunan Arab-Quraisy, pada saat itu berubah menjadi sebatas
simbol kekuasan tunggal dunia Islam.
Dalam konteks historis tersebut, terasa sekali nuansa ideologis pendapat
al-Mâwardiy mengenai persyaratan Imam harus seorang Quraisy. Dalam konteks
awal sejarah khilafah/imamah, persyaratan itu berfungsi sebagai pembenaran
dominasi Quraisy terhadap Sahabat Ansar, dan dalam konteks al-Mâwardiy
persyaratan itu pun berfungsi yang kurang lebih sama: penolakan terhadap
legalitas para pemberontak lokal untuk menduduki jabatan khalifah, dan
mempertahankan posisi jabatan itu tetap ada di tangan orang Qurisy (Banî
‘Abbâsiyyah), meskipun sebatas kekuasaan simbolik.
Ketiga, teori al-Mâwardiy tentang legalitas sistem permandatan, ia
membangun argumentasinya berdasarkan arsip-arsip peristiwa pengangkatan
‘Umar bin Khaththâb dan peristiwa pengangkatan ‘Utsmân bin ‘Affân. AlMâwardiy mengemukakan pendiriannya bahwa pengangkatan seseorang menjadi
Imam berdasarkan mandat dari Imam sebelumnya adalah boleh/sah karena hal itu
pernah menjadi keputusan ijmak di kalangan kaum Muslimin dan mereka tidak
mengingkarinya.319 Pendirian al-Mâwardiy itu didasarkan pada argumentasi
seperti di bawah ini:
Sesungguhnya ’Abû Bakr memberikan mandat kepemimpinan itu kepada
‘Umar bin Khaththâb, kemudian kaum Muslimin menetapkan
kepemimpinan ‘Umar atas dasar mandat itu. Selanjutnya, ‘Umar
memberikan mandat kepemimpinannya kepada '
dewan permusyawaratan'
,
mereka adalah tokoh-tokoh terkenal pada masa itu yang mengesahkan
permandatan ‘Umar itu. Bahwa persetujuan '
dewan pemilih'dalam hal
permandatan ini tidak diperlukan dan ketidaksetujuan mereka tidak
mempengaruhi legalitas mandat yang telah diputuskan. Karena
319
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 10
175
pengangkatan ‘Umar oleh ’Abû Bakr tidak tergantung kepada persetujuan
para Sahabat yang lain, dan karena Imam adalah orang yang paling berhak
atas kepemimpinan itu. Maka keputusan pilihannya adalah yang berlaku,
dan keputusannya mengenai hal itu adalah yang paling diakui.320
Pendirian al-Mâwardiy tersebut sepintas tidak ada persoalan, tetapi
kesimpulan-kesimpulan hukum yang ditariknya sangat simplistik dan tendensius,
serta ia banyak membuang fakta-fakta sejarahnya yang lebih lengkap.
’Ibnu Qutaibah melaporkan dalam bukunya, al-’Imâmah wa al-Siyâsah,321
bahwa ketika tanda-tanda kematian mendekati ’Abû Bakr, dia menjadi sangat
cemas tentang siapa yang harus menggantikannya sebagai khalifah. Setelah
mempertimbangkan dengan matang, dia kemudian mengangkat ‘Umar bin
Khaththâb untuk menggantikannya. Dia pun memanggil ‘Ustmân di samping
tempat tidurnya dan memerintahkan kepadanya untuk mengumumkan suksesi.
Ketika kabar itu telah menyebar, rakyat datang berduyun-duyun kepada
’Abû Bakr dan mulai mempersoalkan pilihannya itu. Dengan adanya peristiwa
tersebut, dia berkata: "Jika Tuhan menanyaiku tentang masalah ini, saya akan
mengatakan kepada-Nya bahwa saya telah mengangkat salah satu dari mereka
yang saya anggap paling baik."
Setelah itu, ’Abû Bakr memerintahkan musyawarah kepada majelis umum
rakyat. Ketika mereka telah berkumpul bersama-sama, ia pun mengucap salam
kepada mereka dan berpidato bahwa dia telah memilih dari mereka seorang
dengan kualitas-kualitas yang sepantasnya, serta berkata: "Jika kalian sedemikian
berhasrat, kalian dipersilahkan duduk bersama-sama dan memilih satu orang yang
320
321
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
Seluruh narasi ’Ibnu Qutaibah ini dapat dilihat dalam, ’Ibnu Qutaibah, Op. Cit., h. 19-23.
176
kalian sukai. Namun jika kalian berharap bahwa saya harus menggunakan
kebijaksanaan dalam masalah ini, demi kepentingan kalian, maka saya jamin
kalian terhadap mereka yang tidak percaya kepada Allah, saya akan
mengindahkan tindakan kalian yang terbaik."
Dia lalu berhenti dan menangis, kemudian rakyat pun menangisinya dan
berkata: "Anda adalah yang terbaik dan paling banyak mengetahui di antara kami,
sehingga Anda yang memilihkan bagi kami."
Ketika musyawarah dan kerumunan banyak orang itu membubarkan diri,
dia kemudia memanggil ‘Umar bin Khaththâb dan memberinya pengumuman
suksesi yang berisi mandat kepemimpinan atas dirinya, serta berkata: "Pergilah
pada rakyat dan informasikan kepada mereka bahwa ini adalah pendapat saya, dan
tanyakan kepada mereka apakah mereka mendengarkan dan mematuhinya."‘Umar
menerima dokumen itu dan menyebarluaskan kepada mereka. Mereka semua pun
berkata: "Kami semua mendengarkan dan mematuhinya".
Kesaksian ’Ibnu Qutaibah ini sangat tegas dan menentukan. Kesaksian ini
menolak sama sekali argumentasi al-Mâwardiy. Cukup jelas bahwa Abû Bakr
tidak mencabut hak rakyat atas suksesi untuk memilih pemimpin secara bebas.
Abû Bakr hanya mengungkapkan pendapat pribadinya dan memberikan contoh
kebebasan kepada rakyat. Rakyat boleh menerima atau menolak pandangan dia
itu. Tidak ada hambatan politis dalam peristiwa itu yang membatasi hak rakyat,
177
tidak ada keputusan khalifah yang bersifat prerogratif dan absolut untuk
melestarikan monopoli atas hak-hak rakyat.322
Argumen al-Mâwardiy yang kedua yang digunakan untuk medukung
tesisnya bahwa majelis pemilih terbatas yang dibentuk ‘Umar bin Khaththâb
merupakan prosedur yang sah untuk mengangkat ’imâm, tidak dapat terus
dipertahankan.323 Karena prosedur yang ditempuh ‘Umar itu terbatas demi
menjaga terjadinya pertentangan sipil setelah kematiannya. Dia sepenuhnya tahu
bahwa para calon yang dimungkinkan untuk menjadi khalifah adalah orang yang
paling baik yang pantas diangkat untuk itu. Dia juga sangat yakin bahwa ‘Ustmân
atau ‘Aly adalah orang yang akan dipilih. Karena itu, untuk memfasilitasi
pemilihan khalifah baru ini, dia menetapkan satu prosedur yang paling sedikit
mengundang kejahatan dan menjamin untuk menghindari terjadinya bentrokan
sipil, memilih anggota majelis pemilih terbatas. Karena itu, rencana ‘Umar
tersebut ditentukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan bijaksana.
Bukti atas penegasan ini adalah bahwa secara kategoris ia mengumumkan
kaum Ansar tidak berhak terhadap pembagian apapun mengenai kekuasaan
pemerintahan, meskipun Abû Bakr pada masa hidupnya meragukan hal ini, dan
sekalipun banyak ahli hukum setelahnya tidak menerima putusan ‘Umar tentang
masalah ini.
Sebenarnya, ‘Umar bin Khaththâb melakukan langkah yang tidak biasa ini
untuk mempertahankan keutuhan umat Islam, dan bukan mempertahankan
prosedur prinsip, karena tidak ada prinsip yang jelas mengenai hal ini
322
Qamaruddin Khan, Al-Mâwardiy'
s Theory of The State, Lahore: Islamic Book Foundation,
1403 H/1983 M, h. 31
323
Analisis ini berhutang banyak terhadap Qamaruddin Khan. Liaht, Ibid., h. 32-33
178
sebelumnya. Karena itu bangunan teori politik yang keluar dari putusan ‘Umar itu
tidak bisa diabsahkan begitu saja secara mengikat dan selamanya, atau dihargai
sebagai sebuah prestasi pemikiran politik yang pasti.
Argumentasi al-Mâwardiy tersebut hanyalah sebuah upayanya yang serius
untuk menafsirkan praktek lama demi mengabsahkan fenomena politik historis
yang lebih belakangan. Al-Mâwardiy sama sekali tidak menaruh perhatian
terhadap latar belakang dan tujuan dari keputusan ‘Umar. Sebaliknya, sebagai
seorang ahli hukum Suni yang ternama dari mazhab Syâfi‘iy dan yang dekat
dengan Khalifah ‘Abbâsiyyah; perhatian utamanya adalah membebaskan khalifah
yang Suni dari tirani Buwaihiyah yang Syî‘ah. Karena, teori dan argumentasi alMâwardiy itu adalah stempel yang nyata bagi keabsahan sistem monarki
‘Abbâsiyyah, yang menetapkan sistem itu dengan mengambil preseden
sebelumnya dari dinasti ‘Umâwiyyah.
Para ahli hukum, termasuk al-Mâwardiy, telah mendamaikan diri mereka
sendiri dengan tatanan monarki yang feodalistik saat itu, serta memberinya bentuk
dan sanksi dari otoritas agama. Al-Mâwardiy tidak mengalami kesulitan dalam
menemukan isyarat dari para pendahulunya, dan dari ide-ide yang telah ada
sebelum masa hidupnya.
Dengan pembakuan teori prosedur pengangkatan Imam seperti yang
dilakukan para yuris hingga al-Mâwardiy tersebut, maka tidak mengherankan
ketika Mu’âwiyah (pendiri kekuasaan dinasti ‘Umâwiyyah) maupun ’Abû Ja‘far
al-Manshûr (pendiri kekuasaan dinasti ‘Abbâsiyyah) berusaha melanggengkan
monopoli kekuasaan dengan mewariskan tahtanya kepada para putranya.
179
Khilafah/imamah yang semula menjadi hak bersama umat, kemudian bergeser
menjadi bentuk monarki yang absolut. Khalifah demi khalifah diangkat secara
turun temurun sebagai dinasti. Sistem ini berlangsung terus-menerus, sehingga
sepanjang sejarah khilafah selalu diwarnai pertentangan antar dinasti yang saling
berebut tahta kekuasaan, tanpa mempedulikan apapun suara rakyat.
Kenyataan politik itu justru memperoleh legitimasi "sesuai syariat" dari
kaum ulama melalui teori tersebut. Dengan demikian, mereka jelas ikut
bertanggung jawab dalam proses pelanggengan sistem monarki tersebut dengan
menjamin keabsahan pengangkatan khalifah melalui sistem mandat dari khalifah
sebelumnya.
Dalam kasus mandat kepada putra mahkota, memang ulama berbeda
pendapat, dan masing-masing sebenarnya hanya berdasarkan pada pertimbangan
rasional/spekulatif belaka. Ada tiga mazhab pendapat dalam masalah ini, seperti
disebutkan al-Mâwardiy:
Mazhab pertama, Imam tidak boleh melakukan mandat-baiat kepada anak
atau orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan '
dewan
pemilih'dan mereka setuju atas keputusannya itu. Saat ia mendapatkan
persetujuan mereka, saat itu mandat dan baiat yang ia berikan menjadi sah
karena tindakan yang ia lakukan itu adalah seperti pengukuhan kompetensi
yang berlaku seperti persaksian dan seperti dalam kasus hukum, yaitu
seseorang tidak boleh bersaksi bagi orang tuanya atau anaknya dan tidak
boleh pula memutuskan hukum bagi salah satunya karena adanya praduga
kecenderungan dorongan hati dan keberpihakan.
Mazhab kedua, ia boleh memberikan sendiri mandat itu kepada anak dan
orang tuanya karena ia adalah pemimpin Umat yang perintahnya wajib
dipatuhi, maka hukum kedudukan mengalahkan hukum keturunan dan
praduga keberpihakan dan dorongan hati tidak dinilai sebagai pengurang
sifat amanahnya dan tidak pula menjadi penentangnya. Dalam tindakan
itu, ia seperti memberikan mandat itu kepada selain anak dan orang
tuanya. Apakah persetujuan '
dewan pemilih'setelah adanya mandat itu
mempunyai kekuatan hukum dalam legalitas jabatan itu bagi Umat atau
180
tidak? Jawabannya adalah seperti yang telah saya katakan sebelumnya,
yaitu ada dua bentuk.
Mazhab ketiga, Imam boleh memberikan mandat itu sendiri bagi orang
tuanya, namun ia tidak boleh melakukannya sendirian kepada anaknya
karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anak lebih besar
daripada kecenderungannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, hasil
usaha yang ia dapatkan dalam hidupnya sebagian besar dipersiapkan untuk
anaknya, bukan untuk orang tuanya. Adapun pemberian mandat itu kepada
saudaranya dan kerabatnya yang dekat, adalah seperti pemberian
mandatnya kepada orang jauh yang asing, yaitu boleh melakukannya
sendiri.324
Dalam konteks di mana seseorang memiliki kekuasaan yang absolut
seperti Mu’âwiyah atau ’Abû Ja‘far al-Manshûr, karena keduanya memperoleh
jabatan khalifah setelah sebelumnya memimpin pasukan dan memenangkan
pertempuran dengan mengalahkan lawan-lawan politiknya serta menumpas habis,
dan naluri dasar manusia adalah ingin mempertahankan apa yang pernah
dicapainya
melalui
pewarisan
tahta
kepada
keturunannya,
maka
kecil
kemungkinan mazhab pertama dan ketiga tersebut di atas akan memperoleh
tanggapan dan perhatian dari khalifah yang berkuasa. Mazhab yang justru populer
tentu mazhab yang kedua. Kalaupun toh dalam setiap suksesi khalifah mengajak
bicara ulama, mereka bukan lagi dalam kapasitas sebagai "dewan pemilih" (’ahl
al-halli wa al-‘aqdi), namun sebagai "dewan penasehat" yang rekomendasinya
tidak mengikat. Kalaupun saja mereka tetap dianggap sebagai ’ahl al-halli wa al‘aqdi, posisi politik mereka sangat lemah, karena mereka diangkat oleh khalifah.
Sebenarnya, sejak Khalifah Mu‘âwiyah mengangkat puteranya
menjadi
penggantinya, konsep ’ahl al-halli wa al-‘aqd telah kehilangan maknanya, dan ia
324
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 10.
181
hanyalah lembaga simbolis yang terdiri dari kaum ulama terbatas yang
dimanfaatkan khalifah untuk memperkuat basis legitimasinya.
Sebenarnya, apapun yang mungkin menjadi pertimbangan politik ‘Umar
bin Khaththâb ketika ia memutuskan mengangkat majelis pemilih terbatas yang
tidak diturunkan dari prinsip umum, tentu saja hal ini membawa implikasi yang
sangat berbahaya. Jika hak pengangkatan orang-orang yang berhak memilih dan
calon yang akan dipilih diserahkan kepada Imam, maka teori ini telah membuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi Imam untuk menjadi absolut dan zalim.
Al-Mâwardiy dengan jelas menyatakan tidak sependapat dengan pendapat
mayoritas ulama Basra (ulama dari kampung halamannya sendiri) yang mengakui
bahwa imamah adalah hak kaum Muslimin seluruhnya. Maka, terkait dengan isu
legalitas sistem permandatan tadi, al-Mâwardiy menyatakan:
Imam adalah orang yang paling berhak atas baiat imamah; maka kepada
siapapun imamah itu akan dimandatkannya, ketentuan dan perkataannya
lebih menjamin dan terakui.325
Dengan demikian, al-Mâwardiy benar-benar telah membuka peluang
selebar-lebarnya dan menjamin legalitas mandat kepemimpinan kepada putera
mahkota, dan inilah kenyataan yang terjadi sejak Mu’âwiyah dan terus
dilanggengkan. Bahkan al-Mâwardiy mengesahkan pengangkatan dua atau lebih
putera mahkota. Dalam hal ini al-Mâwardiy mengemukakan argumen:
Rasulullah pernah mengangkat penggantinya untuk memimpin pasukan di
Mu‘tah kepada Zaid bin Harîtsah dan berkata: '
jika terjadi suatu musibah,
maka terus diganti Ja‘far bin ’Abî Thâlib, dan jika ia terkena musibah,
maka dilanjutkan ‘Abdullâh bin Rawâhah, dan jika ia juga terkena
musibah, maka orang-orang Islam dapat merelakan seseorang menjadi
325
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
182
pemimpinnya.'Zaid pun maju ke medan pertempuran, ia gugur. Kemudian
Ja‘far mengambil komando dan maju, ia pun gugur. Dilanjutkan ‘Abdullâh
yang memegang komando, ia juga gugur. Terakhir, orang-orang Islam
sepakat memilih Khâlid bin al-Walîd sebagai komandan. Jika Rasulullah
melakukan hal itu dalam keamiran (al-’imârah), maka diperbolehkan
melakukan hal seperti itu dalam kekhalifahan (al-khlâfah)."326
Penyebutan peristiwa tersebut sebagai acuan untuk mendukung isu
diperbolehkannya dua putera mahkota atau lebih, hal itu adalah alasan yang
dibuat-buat oleh al-Mâwardiy. Kenyataannya, praktek pengangkatan dua atau
lebih putra mahkota ini telah berkembang menjadi kejahatan politik terbesar
dalam sejarah pemerintahan Muslim. Ia sering menimbulkan fitnah dan
menyebabkan perang internal yang merusak, serta sebagai penyebab berbagai
permusuhan dinasti.327
Dan yang lebih penting lagi dikatakan di sini, sebagai konsekuensi dari
teori keabsahan permandatan tadi, al-Mâwardiy sama sekali tidak memikirkan
cara-cara sebagai sarana yang efektif bagi rakyat untuk berperan aktif dalam
politik secara umum, dan khususnya dalam momen setiap suksesi. Padahal, rakyat
sangat membutuhkan itu, tetapi mereka selalu ditinggalkan dalam setiap proses
politik yang menentukan.
Dua ilustrasi berikut ini cukup memberikan gambaran tentang pandangan
yang berbeda antara rakyat biasa dan para elit mengenai dinamika kekuasaan.
Ilustrasi pertama, dalam sebuah perdebatan yang berlangsung di salah satu
masjid Basra, ketika partner ‘Â’isyah yang menggalang dukungan untuk melawan
Khalifah ‘Aly bin ’Abî Thâlib diundang masyarakat untuk menjelaskan motif
326
327
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 13
Qamaruddin Khan, Op. Cit. h. 34-35
183
mereka, seorang pemuda yang tidak tergolong kaum elit, mengucapkan sebuah
pidato yang menyoroti semua persoalan yang tidak jelas mengenai dinamika Islam
yang saat itu dirasakan oleh penduduk awam. Pemuda ini berpidato di masjid
Basra, sebuah tindakan yang bisa menghilangkan nyawanya, di hadapan para
wakil dan sekutu ‘Â’isyah yang mendorong mereka untuk melakukan subversi,
dan mengatakan kepada mereka:
Benar bahwa kalian kaum Muhajirin [kelompok imigran yang berasal dari
Makkah, pen.] adalah orang-orang yang pertama menanggapi panggilan
Rasulullah s.a.w. Kalian memperoleh keistimewaan sebagai seorang
Muslim sebelum orang-orang lain. Tetapi kemudian, setiap orang
mempunyai keistimewaan tersebut dan setiap orang memeluk Islam.
Kemudian setelah Rasulullah wafat, kalian memilih seorang di antara
kalian tanpa bermusyawarah dengan kami [rakyat biasa yang bukan bagian
dari kelompok elit, pen.]. Setelah kematian khalifah, kalian berkumpul lagi
dan mengangkat kembali [khalifah, pen.] yang lain, dan tetap tanpa
meminta pendapat kami…….Kalian memilih ‘Ustmân, dan bersumpah
setia padanya, juga tanpa bermusyawarah dengan kami. Ketika kalian
tidak setuju pada tingkah lakunya, kalian lalu menyatakan perang, juga
tanpa berkonsultasi dengan kami. Kalian memutuskan, juga tanpa
konsultasi pada kami, untuk memilih ‘Aly bin ’Abî Thâlib dan bersumpah
setia padanya. Lalu, apa yang kalian salahkan daripadanya sekarang?
Mengapa kalian memutuskan untuk memeranginya? Apakah ia melakukan
sesuatu yang patut dicela? Jelaskan pada kami apa yang terjadi. Kami
harus yakin jika kami memutuskan untuk terlibat dalam peperangan ini.
Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kalian berperang?328
Jelas bahwa suara pemuda itu menggambarkan suara rakyat pada
umumnya, yang selalu tidak dilibatkan dalam setiap momen suksesi. Meski diam,
mereka menyaksikan bahwa suksesi hanya dimonopoli oleh para elit di pusat
kekuasaan. Sementara itu, para elit mulai sibuk mendekati mereka jika dukungan
328
Komentar-komentar dalam kurung di dalam kutipan ini berasal dari al-Thabariy, Lihat, [’Abû
Ja‘far Muhammad] al-Thabariy, Târîkhu al-’Umami wa al-Mulûk [History of Umams and Kings] ,
Beirut: Dâru al-Fikr, 1979, vol. 5, h. 179
184
mereka sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan
kekuasaannya.
Fenomena seperti ini tidak diperhatikan oleh al-Mâwardiy dalam
menyusun teorinya, sebaliknya teorinya mengenai dua prosedur pengangkatan
Imam jelas-jelas tidak mengakomodasi hak-hak politik rakyat. Pengacuannya
terhadap praktek masa lalu sebagi landasan argumentasi hukumnya, sebenarnya
lebih mengarah kepada kepentingan pembenaran status quo khalifah.
Ilustrasi kedua, seorang sufi, suatu ketika ia ingin bertanya kepada
Khalifah al-Ma’mûn (Khalifah ‘Abbâsiyyah: 198-218/813-833) tentang apa yang
dipikirkannya berkenaan dengan tahtanya. Al-Ma’mûn adalah seorang raja yang
sangat berkuasa pada masanya. Kemegahan kekuasaan dan kemeriahan
perkawinannya dengan Burân mengilhamkan banyak cerita. Namun, di mata sufi
itu, khalifah yang tentaranya menggetarkan dunia itu, hanyalah seorang laki-laki
sebagaimana laki-laki lainnya; laki-laki yang diberi kekuasaan oleh masyarakat
untuk menjadi pemimpin. Al-Mas‘ûdiy menulis sebuah cerita sebagai berikut:
Suatu hari ketika Khalifah sedang mengadakan pertemuan dengan
pengurus rumah tangga istana, ‘Aly bin Shâlih muncul dan berkata
kepadanya: "Amîrul Mu’minîn, seorang laki-laki berpakaian putih dari
bahan yang kasar berada di depan pintu gerbang. Dia minta izin untuk
ambil bagian dalam diskusi ini." Saya paham, lanjut Yahya (pencerita,
salah seorang saksi peristiwa yang ingat pada peristiwa tersebut dan
menceritakannya pada yang lain), laki-laki itu adalah seorang sufi dan
saya mau memberi isyarat kepada Khalifah agar tidak mengizinkannya.
Namun, Khalifah memerintahkan agar ia dibiarkan masuk. Lalu masuklah
seorang laki-laki sambil menyingsingkan jubah dan menenteng sandal. Dia
berhenti di ujung karpet dan berkata: "Salam! Semoga rahmat dan berkat
dilimpahkan pada Anda sekalian!" Al-Ma’mûn membalas salam. Orang
asing itu minta izin mendekat. Khalifah mengizinkan dan mengajak ia
duduk. Setelah duduk ia berkata kepada Khalifah:
"Apakah kau mengizinkan aku menegurmu?"
185
"Berbicaralah tentang apa yang kau ketahui, untuk itu Allah akan
bergembira." Al-Ma’mûn mempersilakannya.
Laki-laki itu lalu bertanya: "Apakah kau lebih berhutang kepada umat
Islam yang telah mengizinkan kau menduduki tahta ini, atau lebih
berhutang kepada kekerasan yang telah kau pergunakan terhadap mereka
melalui kekuatan dan kekuasaanmu?"
Dengan sadar dan cerdas, Al-Ma’mûn menanggapi pertanyaan itu dengan
tepat. Ia menunjukkan hormatnya kepada laki-laki itu yang memiliki
keberanian tulus terhadapnya sebagai khalifah yang sangat berkuasa. AlMa’mûn mengatakan: "Aku tidak berhutang kepada umat Islam (ijtimâ'
)
atau kepada kekerasan (mughâlabah). Tapi berhutang kepada kenyataan
bahwa aku menerima tahta ini dari seorang sultan yang memerintah
sebelumnya dengan persetujuan.329
Ironisnya, rakyat justru dibungkam oleh al-Mâwardiy dengan doktrin
kepatuhan. Untuk doktrin itu, Al-Mâwardiy mengutip ayat: “Hai orang-orang
yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Nya, dan penguasa urusan di
antara kalian….”330 Al-Mâwardiy mengomentari ayat ini dengan mengatakan:
Allah SWT mewajibkan kita untuk patuh kepada pemerintah kita. Mereka
adalah para pemimpin yang memerintah kita.331
Pengutipan ayat beserta komentar al-Mâwardiy tersebut menyiratkan
nuansa ideologis berupa pembelaan dan penguatan terhadap kepentingan
kekuasaan/penguasa. Apalagi, al-Mâwardiy jelas-jelas tidak mau mengutip
(sengaja menyembunyikan?) satu ayat yang telah didahulukan oleh Allah sebelum
ayat kepatuhan itu, yaitu:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
329
Al-Mas‘ûdiy, Murûj al-Dzahab [Meadows of Gold, pen.], Beirut: Dâru al-Ma‘rifah, 1982, vol.
4, h. 20
330
Q.S. Al-Nisâ’: 59
331
Al-Mâwardiy, Op. Cit., hal. 3
186
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.332
Pada ayat ini, dengan sangat jelas Allah menuntut, pertama-tama, kepada
siapa saja yang memegang kebijakan/hukum yang tidak lain adalah para penguasa
agar bertindak adil, baru kemudian memerintahkan orang-orang beriman agar
mematuhi mereka. Allah jelas lebih dahulu menuntut keadilan penguasa sebelum
menuntut agar mereka dipatuhi. Artinya, keadilan penguasa merupakan prasyarat
kepatuhan rakyat terhadap mereka. Dengan demikian, jelas sekali ada upaya alMâwardi untuk menafikan konsep keadilan di dalam teori imamahnya. Padahal, di
dalam konsep keadilan inilah tempat satu-satunya bagi penghormatan dan
perlindungan terhadap hak-hak mereka yang tidak memegang kekuasaan.
3. Nuansa Ideologis Tugas-tugas Imam
Setelah al-Mâwardiy menjelaskan secara panjang lebar teori pengangkatan Imam,
ia menyatakan bahwa ada sepuluh tugas-tugas umum yang harus diembannya.333
Di sini perlu disebutkan lagi satu saja dari kesepuluh tugas-tugas pokok Imam
yang dikatakan al-Mâwardiy, yaitu tugas yang utama dan disebutnya pertama kali:
"Menjaga Agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang telah ditetapkan
dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi umat Islam terdahulu. Jika
muncul pembuat bidah atau pembuat kesesatan, ia berkewajiban menjelaskan
argumentasi kebenaran baginya dan menjelaskan pemahaman yang benar
332
Q.S. Al-Nisâ’: 58
Lihat pokok-pokok tugas yang wajib dilaksanakan seorang Imam dalam bab III, tepatnya dalam
pembahasan mengenai substansi pemikiran al-Mâwardiy.
333
187
kepadanya, serta menuntunnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang
ada, sehingga Agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah."334
Tidak diragukan, ini adalah kewajiban yang paling utama dari seorang
Imam di bawah legitimasi syariat. Sayangnya, para petualang dan mereka yang
mementingkan diri sendiri sering menggunakan dalih ini untuk kepentingankepentingan politiknya. Perang sipil Islam yang melibatkan pertentangan antara
bani ‘Umâwiyyah, bani Hâsyimiyyah dan para pengikut Zubair menggunakan
dalih yang seperti ini.335
Ketika ‘Abbâsiyyah berkuasa, mereka menyebut diri sebagai penjaga
iman, dan menumpas setiap pertikaian politik atas nama agama, dan mengirim
jiwa-jiwa tak berdosa ke tiang gantungan dengan dalih menyelamatkan Islam.
Para pengikut ‘Aly bin ’Abî Thâlib selalu mengklaim bahwa mereka adalah satusatunya tempat menyimpan agama, dan Islam aman jika hanya ada di tangan
Imâm-imâm mereka. Ketika mereka membangun kekuasaan Fâthimiyyah dan
kemudian dinasti Syafawiyyah di Persia, mereka pun memusnahkan lawan-lawan
politiknya dengan kekejaman dan pembunuhan yang tak dapat dipikirkan.
Penyebutan al-Mâwardiy tentang kewajiban ini adalah sangat efektif dan
tepat waktu, karena memberikan peringatan keras kepada dinasti Buwaihiyyah
yang mengambil alih kekuasaan khalifah di Bagdad, dan yang telah
menampakkan bidah keimanan Syî‘ah.
334
335
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 15-16
Lihat Qamaruddin Khan, Op. Cit., h. 36-37
188
4. Nuansa Ideologis Mekanisme Pemakzulan Imam
Al-Mâwardiy menyatakan bahwa Imam dapat diturunkan dari jabatannya, jika ia
keluar dari kompetensinya sebagai Imam.336
Dalam hal ini, al-Mâwardiy hanya menyebutkan dan menguraikan kriteriakriteria khalifah yang dapat diturunkan dari jabatannya, yaitu: pertama, jika
kredibilitasnya rusak, dan dua, jika terjadi ketidaklengkapan pada anggota
tubuhnya. Rusaknya kredibilitas pribadi khalifah dapat terjadi karena ia
melakukan perbuatan yang fasik. Hal itu disebabkan dua macam: ia mengikuti
syahwatnya dan mengikuti perkara yang syubhat. Macam yang pertama berkaitan
dengan perbuatan tubuh, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang agama, melakukan kemungkaran, mengikuti dorongan syahwat, dan
mengikuti hawa nafsunya. Macam yang kedua adalah berhubungan dengan
akidah, yaitu ia melakukan takwil terhadap suatu masalah yang syubhat sehingga
ia menghasilkan takwil yang menyalahi kebenaran. Kekurangan yang terjadi pada
anggota tubuh ada tiga macam: kekurangan pada pancaindra, kekurangan pada
anggota tubuh, dan kekurangan dalam melakukan gerakan.337
Jelas bahwa kriteria
yang disebutkan al-Mâwardiy tersebut hanya
menyangkut cacat fisik dan moral yang bersifat individual. Sedangkan bagi
seorang khalifah, selain hal-hal tersebut seharusnya ada kriteria kecacatan yang
lebih penting untuk dilihat, yaitu cacat sosial dan politik yang terkait dengan
tanggung jawabnya terhadap hak-hak umat. Ini jika al-Mâwardiy mau konsekuen
dengan perkataannya sendiri sebelumnya, ketika ia mengatakan:
336
337
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 17
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
189
Jika Imam telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah saya
sebutkan tadi, yang merupakan hak-hak Umat, maka berarti ia telah
melaksanakan hak-hak Allah, baik yang terkait dengan hak-hak mereka
maupun kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan.338
Kekurangan khalifah yang semestinya dilihat pertama-tama adalah
kekurangan dalam aspek pemenuhannya terhadap hak-hak umat, dan teori alMâwardiy mengenai kecacatan khalifah sehingga ia dapat diturunkan, luput dari
kepentingan ini. Selain itu, memang benar bahwa al-Mâwardiy menekankan aspek
keadilan seorang Imam terhadap Umat. Tetapi ia tidak cukup serius berbicara
tentang hal ini, karena aspek tersebut hanya ditempatkan al-Mâwardiy pada urutan
terakhir dari sepuluh tugas pokok yang harus dilakukan Imam. Lebih daripada itu,
al-Mâwardiy justru terlalu terobsesi dengan kualitas individual seorang Imam
yang harus bersifat amanah seperti nabi,339 sementara itu, ia mengabaikan
kenyataan bahwa Imam hanyalah manusia biasa yang diberi kekuasaan oleh
orang-orang
di
sekelilingnya;
demikian
juga,
ia
mengabaikan
realitas
kepemimpinan mereka yang semakin jauh dari kualitas yang ia dambakan.
Seandainya al-Mâwardiy konsisten dengan perkataannya tadi tentang hakhak umat, dan ia mau serius membicarakan aspek keadilan Imam, ia akan
berupaya
untuk
memikirkan
sistem
kontrol
yang
efektif
yang
dapat
menjamin/memaksa khalifah mau bertindak adil dan bertanggungjawab penuh
terhadap kesejahteraan rakyatnya, daripada ia berbicara mengenai tuntutan
moralitas pemimpin secara personal dan ideal. Bukankah seorang pemimpin yang
memiliki kualitas moral personal yang jelek dapat menjadi baik dengan adanya
338
339
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
Lihat Al-Mâwardiy, Ibid., h. 16
190
sistem kontrol yang baik? Dan bukankah tidak ada yang bisa menjamin bahwa
seorang pemimpin akan selalu baik tanpa adanya sistem kontrol atas
kepemimpinannya?
Kemudian, di antara kriteria yang disebutkan al-Mâwardiy mengenai
seorang Imam yang dapat diturunkan dari jabatannya, atau ia keluar dari
kompetensi untuk memegang jabatan tersebut adalah jika terjadi perubahan dalam
pribadi Imam. Dalam hal ini ada tiga macam: hilangnya perasaan-perasaan psikis,
cacat tubuh, dan hilangnya kemampuan penglihatan.340 Dalam kasus yang
pertama dan kedua sudah jelas dan tidak perlu dikomentari. Tetapi kasus yang
ketiga perlu dikritisi, karena berhubungan erat dengan diskrusus sejarah politik
Islam.
Tradisi melumpuhkan penglihatan dengan besi panas untuk menurunkan
seseorang dari jabatan Imam atau menghambat langkah lawan untuk menduduki
jabatan itu telah menjadi cara yang biasa dilakukan. Kelaziman praktek ini dapat
diukur dari kenyataan bahwa kurang lebih dua lusinan Khalifah ‘Abbâsiyyah telah
dibuat buta demi untuk menurunkan mereka dari kursi kekhalifahan. Tradisi yang
ganjil ini justru mendapatkan sanksi legal dari al-Mâwardiy dengan mengatakan:
Hilangnya penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk memangku
jabatan dan melanjutkan jabatannya. Jika hal itu terjadi pada masa
jabatannya, jabatannya itu batal.341
5. Nuansa Ideologis Pengabsahan Kudeta dan Pemberontakan
340
341
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 18
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
191
Al-Mâwardiy mendiskusikan secara rinci tentang kemungkinan-kemungkinan
kudeta atau pemberontakan terhadap Imam. Menurut al-Mâwardiy, jika seorang
Imam dikudeta oleh salah seorang pembantunya, yang menginginkan semua
kekuasaan ada pada dirinya, namun ia tidak menampakkan kemaksiatan dan tidak
secara terbuka menentang Imam; maka Imam tetap menempati posisinya dan
kekuasaannya tetap sah. Orang yang melakukan kudeta itu harus dilihat
perilakunya; jika ia berbuat sesuai dengan hukum-hukum agama dan memenuhi
keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan Imam. Hal itu dilakukan
agar tindakan kudeta itu tidak mengganggu jalannya pelaksanaan urusan-urusan
agama yang dapat membuat kerusakan umat. Jika tindakan-tindakan yang mereka
perbuat telah keluar dari rel tuntunan agama dan keadilan, ia tidak boleh diakui
dan harus dimintakan pertolongan pihak yang dapat menangkapnya dan
menghapuskan hegemoni kekuasaannya.342
Prinsip ini telah dielaborasi al-Mâwardiy dengan ketelitian dan ketajaman
hukum yang besar. Prinsip yang tidak memiliki sanksi dalam otoritas lama atau
berbagai pendapat para ahli hukum ini, sebenarnya telah didikte oleh jaringan
kekuasaan di mana khalifah ‘Abbâsiyyah telah berkuasa selama dua abad sebelum
al-Mâwardiy.343
Pemberontakan dinasti Buwaihiy di Bagdad dan jatuhnya kekuasaan
khalifah dalam kesia-siaan memerlukan pengembangan formula yang cocok
dengan keadaan darurat waktu itu, dan mengakui secara de facto keberadaan
hubungan antara dinasti Buwaihiyyah dengan dinasti ‘Abbâsiyyah. Prinsip ini
342
343
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 20
Qamaruddin Khan, Op. Cit., h. 42
192
jelas berasal dari prinsip kekhalifahan yang dikemukakan al-Mâwardiy di bagian
awal bukunya. Namun demikian, dia menemukan media untuk mengubah
kontradiksi yang mencolok ini.344
Dalam teori tersebut ada pengakuan yang jelas mengenai situasi yang
terjadi di Bagdad pada satu sisi, dan ada peringatan yang tidak dapat
disembunyikan terhadap dinasti Buwaihiy di sisi yang lain, bahwa jika mereka
melampaui batas, maka mereka dapat dihentikan dengan bantuan kekuatan
Ghasnâwiyyah sebagai sekutu terbuka Khalifah ‘Abbâsiyyah. Pada bagian di
mana al-Mâwardiy mengatakan bahwa jika para pemberontak memperlihatkan
kecurigaan dan sikap memberontak, khalifah dapat meminta bantuan seseorang
yang dapat membebaskannya dari kesulitan. Orang yang dirujuk itu tidak ada lain
adalah Mahmûd al-Ghaznâ. Teori ini telah memberi sumbangan secara langsung
terhadap para petualang dan orang-orang ambisius untuk mengedepankan
kekuatan secara brutal dan keras yang jauh dari kehendak rakyat.345
6. Nuansa Ideologis Pembatasan Hak Wanita dalam Kepemimpinan
Al-Mâwardiy dengan jelas melarang wanita untuk menduduki jabatan-jabatan
kepemimpinan. Dalam teorinya, al-Mâwardiy mengemukakan argumentasi syariat
yang melarang wanita memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan.
Al-Mâwardiy mengatakan:
Jabatan menteri tidak boleh dipegang oleh wanita meskipun beritanya
dapat diterima, karena jabatan itu termasuk jabatan yang dilarang untuk
diduduki wanita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. : '
Suatu
344
345
Qamaruddin Khan, Loc. Cit.
Qamaruddin Khan, Ibid., h. 43
193
bangsa tidak akan mendapatkan keberuntungan jika mereka menyerahkan
urusan negara mereka kepada wanita'
.346
Al-Mâwardiy memberikan komentar hadis ini dengan mengatakan:
Berlakunya larangan ini karena kemampuan menghasilkan pendapat yang
tepat dan ketangguhan sikap tidak dimiliki oleh wanita, serta mereka
memiliki banyak kendala untuk mengurusi kepentingan publik.347
Tampak sekali, al-Mâwardiy melihat dan menganggap wanita memiliki
kelemahan yang adi-kodrati dan permanen. Pandangan al-Mâwardiy tersebut jelas
merupakan bentuk stereotyping, dan memanfaatkan hadis sebagai dasar
pembenarannya.
Hadis itu memang sangat terkenal dan terdapat dalam kitab kumpulan
hadis yang dipandang memiliki otoritas yang tertinggi karya al-Bukhâriy; alJâmi‘ al-Shahîh. Hadis itu diriwayatkan dari Abû Bakrah (w. sekitar 671 M).
Hadis tersebut selalu menjadi argumen andalan yang digunakan oleh mereka yang
ingin mengucilkan kaum perempuan dari kekuasaan.
Hadis yang dikutip al-Mâwardiy tersebut dapat ditemukan juga kutipannya
dalam jilid ketiga kitab karya al-‘Asqalâniy (w. 852 H [1372-1449 M]), Huda alSâri: Muqaddimatu Fathu al-Bâriy [The Travellers Guide, Introduction to "The
Creator'
s Conguest"], yang biasa dikenal dengan Fath al-Bâriy.348 Kitab ini berisi
komentar-komentar al-‘Asqalâniy atas hadis-hadis kumpulan al-Bukhâriy yang
diklasifikasikan sebagai hadis-hadis otentik setelah melalui proses seleksi yang
sangat ketat dan pemeriksaan balik.
346
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 27
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
348
Hadis yang menjadi perhatian penulis di sini, ditemukan pada halaman 46 volume 13 pada edisi
al-Mathba‘atu al-Bahiyyatu al-Mishriyyah (1928), dan pada halaman 166 volume 16 pada edisi
Maktabah Musthafâ al-Bâbi al-Halabiy, Mesir (1963). Referensi berikutnya merujuk pada edisi
tahun 1928.
347
194
Al-‘Asqalâniy
memberikan
komentarnya
terhadap
hadis
itu,
ia
menjelaskan bahwa ’Abû Bakrah adalah seorang Sahabat yang mengenal
Rasulullah s.a.w. semasa hidupnya, dan bergaul cukup lama, sehingga
memungkinkannya untuk bisa meriwayatkan hadis tersebut di atas. Menurutnya,
Rasulullah s.a.w. mengatakan hadis itu setelah mengetahui bahwa bangsa Persia
telah menunjuk seorang perempuan untuk memimpin. "Ketika Kisrâ wafat,
Rasulullah s.a.w., terdorong oleh rasa ingin mengetahui kabar itu, bertanya: '
Dan,
siapa yang telah menggantikannya sebagai pemimpin?' Jawabannya adalah:
'
Mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada puterinya.'
" Saat itulah, kata ’Abû
Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang perempuan.349
Menurut al-‘Asqalâniy, perkataan Rasulullah itu dikemukakan kembali
oleh ’Abû Bakrah pada situasi ketika Khalifah ‘Aly bin ’Abî Thâlib [memerintah
656-661 M] merebut kembali kota Basra, setelah mengalahkan pasukan ‘Â’isyah
(istri Nabi) dalam Perang Unta.350 ’Abû Bakrah meriwayatkan hadis tersebut pada
saat keadaan ‘Â’isyah sangat kritis. Secara politik ia telah kalah: 13.000
pendukungnya gugur di medan pertempuran.351 Ketika ‘Â’isyah berusaha
meminta dukungan dan bantuan kepada ’Abû Bakrah, ia adalah salah satu tokoh
terkemuka yang terhormat di kota Basra, ia menyatakan sikapnya: ia bersikap
menentang fitnah, namun dengan dalih sebagai berikut:
Adalah benar bahwa Anda umm [Ibu, pen.]352 kami; benar bahwa orang
semacam Anda memiliki hak atas kami. Tetapi saya mendengar Rasulullah
349
Al-‘Asqalâniy, Fath al-Bâriy, vol. 13, h. 46
Al-‘Asqalâniy, Loc. Cit.
351
Al-Mas‘ûdiy, Murûj al-Dzahab, Bulaq: Mawqi‘ al-Warrâq, 1866, Vol. 2, h. 380
352
Sesuai Alquran, istri-istri Rasulullah adalah '
Ibu'bagi orang-orang beriman.
350
195
s.a.w. bersabda: '
Barang siapa menyerahkan kekuasaan kepada seorang
353
perempuan, mereka tidak akan pernah sejahtera.'
Pernyataan sikap ’Abû Bakrah terhadap ‘Â’isyah yang dalam posisi kalah
ini, dapat dibandingkan dengan sikap orang lain dalam posisi yang sama-sama
menentang fitnah. Ia adalah ’Abû Mûsâ al-’Asy‘ariy (gubernur Kûfah pada masa
pemerintahan Khalifah ‘Aly bin ’Abî Thâlib). Khalifah ‘Aly, sebelum bertolak ke
Basra yang menjadi basis gerakan ‘Â’isyah, ia meminta ’Abû Mûsâ agar
memobilisasi
penduduk
Kûfah
dan
segera
mengirimkan
pasukan
dan
persenjataan. ’Abû Mûsâ, tidak saja secara pribadi memilih untuk tidak mematuhi
Khalifahnya, bahkan ia merasa berkewajiban untuk "berkonsultasi" dengan
masyarakat yang diperintahnya. Ia memutuskan untuk bermusyawarah dengan
masyarakat yang diundangnya ke masjid untuk diberi informasi dan bertukar
pikiran, seraya menjelaskan kepada mereka tentang pendirian Rasulullah tentang
perang saudara. ’Abû Mûsâ menyampaikan kepada mereka sebuah hadis yang
mengecam fitnah, dan memerintahkan mereka untuk tidak mematuhi Khalifah
‘Aly, dan tidak perlu menjawab panggilannya untuk bergabung. Baginya,
kewajiban seorang Muslim dalam menghadapi fitnah adalah menentang segala
bentuk keikutsertaan. Disampaikannya pula beberapa hadis lain di masjid Kûfah,
kesemuanya menentang fitnah, menentang perang saudara dengan tegas dan jelas.
Ia sama sekali tidak mepermasalahkan jenis kelamin sang pemimpin. Sikap ’Abû
Mûsâ tersebut jelas mengandung resiko yang besar bagi pribadinya, karena
menentang perintah Khalifah ‘Aly, atasannya. Resiko itu terbukti, karena setelah
353
Al-‘Asqalâniy, Op. Cit., vol. 13, h. 46
196
‘Aly berhasil mengalahkan ‘Â’isyah, ia memecat ’Abû Mûsâ dari jabatannya.
Demi mempertahankan sikap itu, ’Abû Mûsâ kehilangan kedudukan dan
kekayaannya.354
Dari analisa itu dapat disimpulkan bahwa pengungkapan hadis tersebut
oleh ’Abû Bakrah terindikasi sekedar sebagai dalih pembenaran atas sikapnya
dalam rangka mengamankan posisinya.
Adapun al-Mâwardiy yang mengemukakan hadis itu dalam al-’Ahkâm alShulthâniyyah, ia sekedar menerima isi hadis itu apa adanya tanpa melakukan
analisa historis.
Sesungguhnya, hadis itu memiliki pengaruh yang besar terhadap nasib
perempuan sejak dikemukakan ’Abû Bakrah sampai dengan sekarang, karena ia
menjadi rujukan utama para yuris untuk menentukan hukum yang terkait dengan
posisi perempuan dalam posisi sosial-politiknya.
Catatan Penutup Analisa Historis
Demikianlah analisa historis yang telah dilakukan serta uraian tentang fenomena
historisitas isi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan fungsinya. Analisa tersebut telah
menjelaskan konteks sosial, politik, serta budaya yang melahirkan al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Uraian historisitas juga cukup menjelaskan bagaimana isi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah yang tampaknya murni teologis, isinya yang
menampilkan ketransendenan Khilafah Islam, ternyata memiliki akar-akar dan
mengandung fungsi-fungsi yang historis, bahkan ideologis.
354
Thabariy, Târîkhu al-’Umami wa al-Mulûk [History of Umams and Kings] , Beirut: Dâr al-Fikr,
1979, vol. 5, h. 188
197
B. AnalisaMetodologis
Pada Bab III telah diperlihatkan cara pandang dan pola-pola pemikiran tertentu
yang dipakai al-Mâwardiy untuk merumuskan teorinya. Cara pandang dan polapola itu dimaksudkan sebagai metodologi al-Mâwardiy yang menjadi syaratsyarat "ilmiah" bagi teorinya.
Berikut ini akan dilakukan analisa terhadap metodologi al-’Ahkâm alShulthâniyyah. Pembahasan sub bab ini dilakukan dengan penyusunan kerangka
sebagai berikut: 1) sistem metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, dan 2) batasbatas metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan implikasinya.
Analisa metodologis dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa al-’Ahkâm
al-Shulthâniyyah sebagai wacana etika politik Islam dibentuk berdasarkan cara
pandang dan cara berpikir tertentu (kelompok sosial al-Mâwardiy). Al-Mâwardiy
dalam analisa ini, posisinya dipandang sebagai individu yang berpikir dengan
mengambil bagian dalam pemikiran lebih lanjut yang telah dipikirkan orang lain
sebelumnya. Ia berada dalam suatu situasi yang diwariskan dengan pola-pola
pemikiran yang sesuai untuk situasi ini dan berusaha menjelaskan lebih lanjut
cara-cara menanggapi yang telah ada atau menggantinya dengan cara-cara lain
supaya dapat menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dari peralihanperalihan dan perubahan-perubahan situasinya secara memadai.355 Cara-cara
tertentu yang dipakai al-Mâwardiy untuk menanggapi situasi yang dihadapinya
inilah – penulis mendefinisikannya sebagai metodologi yang membentuk isi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah – yang perlu dikonkretkan rumusannya melalui analisa
355
Lihat Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, h. 3
198
yang disebut analisa metodologis. Analisa metodologis bukan hanya dimaksudkan
untuk mendefinisikan rumusan metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, tetapi
juga dimaksudkan sebagai upaya mempertimbangkan jangkauan (batasan)
metodologi itu, implikasi-ipmlikasinya, serta fungsinya secara historis. Pada
momen ini, analisa akan lebih memperkuat fenomena historisitas al-’Ahkâm alShulthâniyyah yang khusus menyangkut aspek metodologinya. Jelasnya, analisa
metodologis juga diupayakan untuk mengungkap historisitas metodolgi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
Analisa metodologis pada tahap ini, selain didasarkan pada asumsi teoretis
di atas, juga didasarkan pada asumsi bahwa al-Mâwardiy sebagai individu sangat
terikat dengan kelompoknya. Ia berjuang keras menurut posisi, ciri, dan cara
kelompoknya itu untuk mengubah dunia alam sekitarnya dan masyarakat atau
berusaha memeliharanya tetap pada kondisi yang telah ada. Padahal di dalam
setiap ruang historis, terdapat ragam kelompok dan setiap kelompok memiliki
kepentingan yang sama untuk melakukan tindakan seperti itu dan cenderung
saling menolak atau menghancurkan (terjadi kompetisi). Maka, analisa
metodologis terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah pada tahap ini adalah sebagai
upaya mengungkapkan historisitas metodologinya di dalam ruang kontestasi antar
sistem pemikiran yang saling berkompetisi untuk meraih kekuasaan sosial.
Dengan demikian, tahap ini merupakan momen yang paling penting untuk
mengenali bentuk operasi yang terdalam dari hubungan al-’Ahkâm alShulthâniyyah dengan kekuasaan.
199
Akhirnya, analisa metodologis bertujuan menyatakan bahwa setiap pilihan
metodologis tertentu dari kelompok tertentu (seperti metodologi al-’Ahkâm alShulthâniyyah) memiliki keterbatasan jangkaun, mengandung implikasi-implikasi,
serta fungsi-fungsi ideologis tertentu yang tidak dapat dielakkannya. Pada taraf
tertentu, dalam konteks persaingan sosial, pilihan metodologis itu juga
menunjukkan ideologi subyeknya.
1. Sitem Metodologi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah.
Seperti telah dikemukakan bahwa al-Mâwardiy hidup pada situasi di mana Islam
telah merupakan agama yang menyatu dengan kekuasaan, atau dengan kata lain,
setelah agama dan kekuasaan memiliki hubungan saling mempengaruhi secara
rumit: menjaga Islam adalah tugas kekuasaan, dan kekuasaan adalah kepentingan
dari Islam. Teori yang dibangun al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
tidak lain adalah teori "negara Islam".
Selain gambaran singkat situasi politik tersebut, al-Mâwardiy hidup pada
kondisi sosial-budaya ketika kekuasaan negara Islam telah meliputi wilayahwailayah yang didiami oleh bangsa-bangsa bekas jajahan Kerajaan Byzantium
Romawi dan Kerajaan Sasanid Persia. Lebih jauh, bahwa al-Mâwardiy sebagai
seorang yang terdidik, hidup pada masa kematangan intelektual dan kejayaan
peradaban Islam yang bersumber dari kekuatan wahyu dan akal, yang keduanya
saling mempengaruhi secara rumit dan bahkan bertentangan/bersitegang.
Dari substansi teori al-Mâwardiy di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
khususnya teori ’imâmah, diketahui bahwa fungsi kepemimpinan Islam adalah
200
sebagai pengganti fungsi kepemimpinan Nabi; bahwa ’Iiâm/khalîfah adalah
"wakil"/"mandataris" Allah; bahwa wewenang kekuasaannya adalah bersumber
dari Allah. Maka dasar-dasar pendiriannya, mekanismenya, dan fungsinya harus
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maka tidak ada cara yang musti
ditempuh untuk menegakkan kekusaan dan mengangkat ’imâm, kecuali dengan
membangun dasar-dasar kekuasaan dan sumber-sumber legitimasi penguasa dari
"material" Kehendak Allah. Kehendak Allah adalah sesuatu yang absolut dan
transenden sehingga di luar batas kemampuan akal manusia untuk mengetahuinya.
Kehendak Allah atas kehidupan bumi dapat dimengerti manusia melalui perantara
seorang nabi. Kehendak Allah mengejawantah pada diri seorang nabi melalui
perkataan-perkataan dan tindakan-tindakannya. Dalam konteks Islam, Kehendak
Allah dapat diketahui manusia dari wahyu Alquran dan praktek hidup Nabi
Muhammad. Maka sumber pengetahuan Islam yang utama adalah Alquran serta
perkataan dan praktik hidup Nabi yang disebut sunah/hadis, termasuk
pengetahuan tentang kekuasaan dan mekanismenya. Alquran dan sunah Nabi yang
tertulis adalah material bagi dasar-dasar kekuasaan Islam dan sumber bagi
legitimasi penguasa Islam yang disebut Imam.
Tetapi, telah dinyatakan bahwa Alquran tidak mendefinisikan prinsip apa
pun dengan jelas tentang lembaga kekuasaan Islam, dan apalagi mekanisme
pengorganisasiannya. Para ahli hukum
Islam – termasuk al-Mâwardiy –
menyadari kenyataan ini dan mereka gagal menemukan materi yang cukup dalam
Alquran untuk menyusun teori politik secara rinci. Karena itu, mereka
memperluas upaya pencarian material itu dari sunah. Tetapi, upaya mereka yang
201
kedua ini pun mengalami hal yang sama. Mereka tidak menemukan bukti-bukti
yang cukup dari sunah, baik bukti yang terbuka atau yang tersembunyi, yang
dapat mendukung keinginan mereka untuk menyusun teori kekuasaan Islam.
Demi mewujudkan tujuan itu, kemudian mereka memeriksa arsip-arsip sejarah
awal Islam. Dan, hanya arsip-arsip sejarah inilah merupakan material yang
tersedia untuk penyusunan dasar-dasar kekuasaan Islam, dan hanya pada arsiparsip ini juga letak terdalam sumber legitimasi bagi legalitas mekanisme dan
praktek-praktek kekuasaannya.
Secara umum, demikianlah cara al-Mâwardiy memikirkan hukum tatanegara dan sistem pemerintahan Islam. Sesuai tuntutan yang terkandung dalam
pengertian konsep '
hukum Islam'
, al-Mâwardiy membangun pemikirannya dari
sudut pandang ilmu fiqh dan menggunakan perangkat pemikiran kefikihan
sebagai basis metode keilmiahannya, yaitu ’ushûl al-fiqh yang telah disusun oleh
al-Syâfi‘iy. Metode ini bukan saja menjamin '
keilmiahan'pemikiran-pemikiran alMâwardiy melainkan juga memberi legitimasi bahwa hasil-hasil pemikirannya
merupakan (bagian) hukum syariat. Dalam rangka itu, al-Mâwardiy mendasarkan
pemikirannya kepada ayat-ayat Alquran dan teks-teks hadis – meskipun pada
tahap ini ia telah gagal seperti ulama sebelumnya –, kepada perkataan dan
pengalaman para Sahabat, kepada praktek hukum yang berlaku dalam
pemerintahan dan masyarakat Islam pada masa sebelumnya, dan kepada
pendapat-pendapat hukum dari ulama maupun para hakim yang dianggap
otoritatif, untuk menarik konklusi darinya.
202
2. Batas-batas Metodologi Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dan Implikasinya
Secara umum, metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah memiliki batas-batas, baik
bersifat
metodis,
metodologi
epistemis,
tersebut
beserta
maupun
ideologis.
implikasinya
Penelusuran
dilakukan
melalui
batas-batas
kerangka
pembahasan: (a) batas-batas secara metodis-epistemis, dan (b) batas-batas secara
ideologis.
a. Batas-batas secara Metodis-Epistemis dan Implikasinya
Tanpa harus bersikap a priori terhadap metodologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
seandainya metodologi itu diapresiasi secara penuh pun, ia memiliki keterbatasanketerbatasan, yaitu "keterbatasan metodis-epistemis pada dirinya". Keterbatasanketerbatasan itu meliputi hal-hal seperti dijelaskan di bawah ini.
Pertama, al-Mâwardiy banyak mengutip ayat-ayat Alquran dan teks-teks
hadis sebagai dasar-dasar pemikirannya. Namun, setiap kali ia mengutip ayat
Alquran atau hadis, ia tidak menyertakan kajian secara mendalam. Sehingga, ayatayat Alquran atau hadis yang dikutipnya itu terkesan hanya berfungsi sebagai
"pembingkai", "pembungkus", dan "penyetempel" status konklusi hukum yang
ditetapkannya. Melalui pengutipan ayat-ayat Alquran atau hadis yang mengiringi
keputusan-keputusan hukum yang ingin ditekankan, al-Mâwardiy seperti ingin
menunjukkan bahwa hukum-hukum yang disampaikannya bersifat syariat atau
sesuai dengan Kehendak (Ketentuan) Allah dan Rasul-Nya. Padahal, lebih banyak
ayat Alquran atau hadis yang dia kutip tidak memiliki relevansi (munâsabah)
yang kuat dengan masalah atau kasus yang sedang dibicarakannya, atau ayat
203
Alquran dan hadis itu tidak cukup kuat dijadikan sebagai landasan (dalîl) bagi
bangunan hukumnya. Dalam "bahasa" ’ushûl al-fiqh kecenderungan al-Mâwardiy
itu disebut kelemahan dalam ber-’istidlâl. Sebagai gambaran, akan diperlihatkan
beberapa contoh sebagai berikut:
Contoh 1: al-Mâwardiy mengatakan: "Allah s.w.t. mewajibkan kita patuh
kepada penguasa urusan yang ada pada kita. Mereka adalah para pemimpin yang
memerintah atas kita."356
Dalam konteks perkataan itu, hukum yang ingin ditekankan oleh alMâwardiy adalah kewajiban patuh kepada pemerintah. Dalam rangka maksud itu,
al-Mâwardiy memakai dasar argumentasi ayat Alquran: "Hai orang-orang yang
beriman, patuhilah Allah, Rasul-Nya, dan penguasa urusan di antara
kamu……."357 Bahkan ia juga mengemukakan hadis:
Setelah masaku, kalian akan dikuasai oleh berbagai macam penguasa.
Penguasa yang baik akan memimpin dengan kebaikannya, dan penguasa
yang jahat akan memimpin kalian dengan kejahatannya. Maka
dengarkanlah [perintahnya, pen.] dan patuhilah [mereka, pen.] dalam
segala hal yang mencocoki kebenaran. Jika mereka memimpin dengan
baik, maka manfaatnya bagi kalian dan mereka. Dan jika mereka
memimpin dengan buruk, maka manfaatnya bagi kalian, sedangkan
keburukannya bagi mereka.358
Sebagai orang yang ahli fikih, al-Mâwardiy [tentu] juga ahli Tafsir dan
ahli hadis. Tetapi sama sekali dia tidak mengalaborasi ayat kutipannya itu serta
tidak meneliti status hadisnya.
356
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 5
Q.S. Al-Nisâ’ (4): 59
358
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 5
357
204
Contoh 2: al-Mâwardiy mengatakan bahwa jabatan khalifah dan perdana
menteri, masing-masing tidak boleh diduduki oleh dua orang.359 Perkataannya itu
didasarkan pada ayat: "Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain
Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa….."360
Berdasarkan prinsip ilmu ’ushûl al-fiqh (metodologi fikih), bagaimana
mungkin al-Mâwardiy menganalogikan khalifah-perdana menteri dengan Tuhan?
Adakah "titik temu" (jâmi‘) sebagai "alasan" ('
ilah) sehingga kedua hal yang
esensinya berbeda itu dapat dipersamakan (tasybîh) dalam rangka kias?
Contoh 3: al-Mâwardiy mengatakan: "Seorang panglima perang wajib
mengangkat ketua regu dan perwakilan pasukan."361 Dasar yang digunakannya
berupa ayat: "…..dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal…."362
Apa relevansi tugas panglima mengangkat komandan pasukan dengan
"Kreasi" Allah membuat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Tanpa
pendasaran kepada ayat tersebut, nalar manusia seperti apa yang membenarkan'
seorang panglima memimpin puluhan bahkan ratusan ribu pasukan sendirian?
Contoh 4: al-Mâwardiy menjelaskan salah satu aturan yang harus
dijalankan panglima perang, yaitu: "Tidak memberikan kesempatan dan izin
kepada seorang pun dari tentaranya untuk sibuk berdagang atau bercocok
tanam".363 Aturan ini di dasarkannya kepada sabda Nabi:
359
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 27
Q.S. Al-Anbiyâ’ (21):22, dan al-Mâwardiy, Loc. Cit.
361
Al-Mâwardiy, Ibid., h. 36
362
Q.S. Al-Hujurât (49): 13
363
Al-Mâwardiy, Op. Cit., h. 44
360
205
Aku diutus untuk membawa aturan dan rahmat, bukan untuk menjadi
pedagang atau petani. Golongan yang paling buruk dari Umat ini adalah
para pedagang dan para petani kecuali orang yang amat menjaga tuntunan
agamanya.364
Bahwa seorang tentara sebagai pegawai negara yang telah digaji oleh
pemerintah
dengan uang perbendaharaan negara, sudah seharusnya
ia
bertanggung jawab dengan tugas-tugas negara yang diberikan oleh pemerintah
kepadanya. Tugas seorang tentara adalah selalu menyiapkan dirinya untuk
menjaga keamanan negara, bukan malah berdagang atau bertani, ini jelas. Tetapi,
apa hubungannya hadis yang dikutip al-Mâwardiy tersebut dengan soal tugas
tentara? Juga, apa manfaatnya itu dikemukakan? Terlepas dari masalah mata
rantai (sanad) atau kritik yang dapat diterapkan kepada substansi (matn) hadis
tersebut, ia memiliki konteks (’asbâb al-wurûd) tersendiri yang tidak dapat secara
serta-merta diterapkan kepada suatu kasus dalam konteks yang lain (seperti yang
dilakukan al-Mâwardiy). Dan, obyek stressing (maudhû) hadis di atas bukan pada
jenis pekerjaan: berdagang, bertani, atau yang lain, tetapi kepada bagaimana
(etika) seseorang melakukan pekerjaannya.
Jika masalah kecenderungan metodologi al-Mâwardiy ini dikembalikan ke
dalam konteks riwayat hidupnya dan kemajuan pengetahuan pada waktu itu yang
telah meliputi banyak bidang keilmuan, khususnya ilmu bahasa, filsafat, dan
khususnya ilmu pengetahuan agama; al-Mâwardiy tidak kekurangan modal
intelektual untuk melakukan telaah secara mendalam atas masalah-masalah yang
dipikirkannya jika harus dikaitkan dengan ayat-ayat Alquran dan hadis untuk
364
Al-Mâwardiy, Loc. Cit.
206
menetapkan (konklusi) hukum darinya. Kenapa al-Mâwardiy tidak melakukan hal
itu? Jawabannya, mungkin ia tidak cukup kesempatan atau, mungkin ini alasan
yang agak lebih jelas, ia memaksudkan pemikiran-pemikiran hukumnya dapat
diketahui dengan mudah oleh penguasa/pejabat sebagai jaminan hukum
(legitiamasi) kekuasaannya dan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Karena al-Mâwardiy tidak melakukan elaborasi kajiannya terhadap ayatayat Alquran dan hadis yang dikutipnya, hal ini membawa implikasi terhadap
pemikiran-pemikirannya yang tidak mendalam. Dalam melakukan proses ijtihad,
premis-perimis (muqaddimât) yang diajukannya sangat lemah, sehingga
menghasilkan konklusi (natîjah) yang juga lemah. Kedangkalan itu membawa
implikasi yang lebih jauh, yaitu al-Mâwardiy membicarakan hukum-politik Islam
secara normatif dan simbolis, dan pada saat yang sama ia mengabaikan fenomena
politik Islam/praktek-praktek kekuasaan yang riil. Dengan kata lain, al-Mâwardiy
terlalu memaksakan dirinya berbicara tentang bagaimana “seharusnya” politik
yang “Islami” menurut Alquran dan hadis tanpa mau mengakui bahwa sedikit
sekali (bahkan mungkin nihil) simbol-simbol (dalîl zhâhir) yang dapat diperoleh
dari kedua sumber syariat itu.
Kedua, bahwa dalam rangka menjamin interaksi antara negara dengan
hukum syariat atau menyediakan sistem konstitusional yang lebih lengkap dan
praktis, al-Mâwardiy mengemukakan berbagai produk hukum yang dikatakannya
bersumber dari ijmak. Bahkan, dasar ijmak, yang hakikatnya adalah perkataanperkataan dan praktek-praktek para Sahabat senior (khulafâ’u al-râsyidûn) dan
Sahabat lain di sekitar mereka, adalah yang mendasari seluruh bangunan teori al-
207
Mâwardiy, khususnya tentang sistem kekuasaan Islam (imamah). Pendasaran teori
imamah al-Mâwardiy hanya kepada ijmak, hal ini mengandung dua kemungkinan
alasan; (1) karena terkait erat dengan keinginan al-Mâwardiy untuk menjamin
"otentisitas" praktik politik Islam awal dan menjaga sejarah ‘kemurnian’-nya; dan
(2) karena memang hanya ijmak-lah sumber terdalam yang dapat ditemukan untuk
membangun teorinya.
Seberapa pun nilai penting metodologi/konsep ijmak bagi umat Islam, ia
diaplikasikan al-Mâwardiy tanpa kritik kesejarahan. Al-Mâwardiy dengan jelas
melanggengkan metodologi ijmak dalam wilayah pemikiran politik, tanpa mau
membongkar kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor sejarah yang menjadi latar
belakang sebuah peristiwa [politik] sehingga menjadi produk keputusan yang
disepakati. Setiap al-Mâwardiy mengatakan bahwa suatu hukum berdasar ijmak,
ia selalu tidak menyertakan analisis motif-motif di belakangnya, lebih-lebih ia
tidak melakukan kritik apapun terhadap konsep ijmak melainkan hanya
mengaplikasikannya saja. Sesungguhnya, di bawah ketentuan konsep ijmak serta
timbunan produk-produk hukum yang bersumber dari itulah teori politik Islam
menjadi tidak mampu menyelesaikan problem-problem politik yang dihadapi
sejak semula hingga sekarang.
Konsep ijmak sebenarnya lahir dari faktor-faktor sejarah, dan pada saat
yang sama terikat dengan keterbatasan kesejarahannya. Tetapi, ketika ijmak telah
diperlakukan sebagai bagian dari metodologi syariat dan produk-produk hukum
darinya ditetapkan sebagai hukum syariat, ia dianggap sebagai dogma-dogma
keislaman yang harus berfungsi di segala tempat dan waktu.
208
Ketiga, metodologi lain yang digunakan al-Mâwardiy adalah deskripsi
sejarah praktek hukum dan administrasi dalam Islam sebagai bagian dari aplikasi
konsep ijmak yang sekaligus pintu masuk penerapan konsep kias. Dalam hal ini,
al-Mâwardiy banyak berjasa mengumpulkan pendapat para ahli hukum di
berbagai wilayah kekuasaan Islam dan menyajikan data-data penting mengenai
pengaruh Persia dan Romawi dalam pengembangan sistem administrasi
pemerintahan Islam. Para ahli hukum yang pendapatnya banyak dikutip alMâwardiy adalah empat ulama mujtahid yang memiliki otoritas tertinggi dalam
kelompok Suni: Mâlik bin ’Anas, ’Abû Hanîfah, al-Syâfi‘iy, dan ’Ahmad bin
Hanbal. Al-Mâwardiy sangat toleran terhadap perbedaan pendangan di kalangan
madzhab Suni, tetapi tidak satupun pendapat dari otoritas Syî‘ah atau Khawârij
yang dijadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menarik konklusi.
Keempat, al-Mâwardiy memang banyak mengemukakan pendapatnya
sendiri terhadap kasus-kasus yang dikemukakannya berdasarkan penalaran bebas
sebagai klimaks dari aplikasi konsep kias. Bahkan, metode ini dipergunakannya
lebih banyak daripada metode-metode yang lain. Sampai di sini, dapat diajukan
sebuah pertanyaan: mengapa sejak di awal tulisan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, alMâwardiy menolak secara argumentatif terhadap kecenderungan pemikiran
rasional tentang etika politik/negara? Ketika sebagian orang (kaum Muktazilah)
mencoba melakukan rasionalisasi atas etika politik Islam, al-Mâwardiy
mengatakan bahwa politik Islam harus berdasarkan pada hukum-hukum syariat,
tetapi kenyataannya, apa yang dikatakan al-Mâwardiy tentang etika politik syariat
209
adalah kebanyakan merupakan hasil dari rasionalisasinya sendiri yang dikalim
sebagai sesuatu yang bersifat syariat.
b. Batas-batas secara Ideologis dan Implikasinya
Dengan mengacu sepenuhnya kepada keterbatasan-keterbatasan metodologi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah secara metodis-epistemis, dapat dijelaskan keterbatasanketerbatasannya secara ideologis.
Pertama, keseluruhan sistem metodolgi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
cukup menjelaskan posisi ideologinya, bahwa sistem metodologi itu adalah khas
tradisi pemikiran Suni, di mana al-Mâwardiy "tenggelam" atau "menenggelamkan
dirinya" ke dalam tradisi itu.
Kedua, dalam konteks "kompetisi" antar tradisi, sistem metodologi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah itu juga menjelaskan bahwa secara ideologis ia
"bertanding" dengan metodologi Muktazilah yang lebih cenderung "rasionalis
murni" dan Khawârij yang lebih cenderung "literalis murni". Muktazilah adalah
kelompok yang mengedepankan "rasionalitas bebas" dalam memahami agama dan
negara, dan Khawârij lebih berkecenderungan terpaku kepada "teks lahir" yang
dipadukan dengan "kebebasan bertindak" (free in action).
Khusus mengenai
Muktazilah, pandangan rasionalnya sebenarnya merupakan modal yang baik bagi
Islam
untuk
memikirkan
problem-problem
politik
mengalihkan persoalan-persoalan politik pada
mereka.
Muktazilah
tingkat filosofis. Dengan
memperkenalkan akal ke pentas politik, Muktazilah memaksa umat Islam
membayangkan hubungan-hubungan baru antara penguasa dan yang dikuasai,
210
yang memberi peran kepada semua orang beriman untuk aktif bermain di wilayah
politik. Politik tidak lagi hanya merupakan "duel" antara dua pelaku: Imam dan
pemimpin pemberontak (Khawârij). Tapi harus ada unsur ketiga yakni semua
orang mukmin yang mampu berfikir. Tetapi, sejak Muktazilah menjadi "kuda
tunggangan" kekuasaan dinasti ‘Abbâsiyyah periode awal, ia menjadi bagian dari
kekuasaan yang despotis. Dominasi teologis dan politis Muktazilah pun terdesak
oleh Suni.
Ketiga, setiap sistem metodologi – termasuk sistem metodologi Suni yang
dipakai al-Mâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah – adalah '
inti terdalam'
keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi, ritus-ritus, dan basis paling kuat bagi
bangunan atau jalinan solidaritas sosial. Timbul-tenggelamnya sebuah sistem
metodologi sebagai "inti sistem nilai", ia tidak hanya bergantung kepada
"kekuatan sistem dalamnya/sistem pada dirinya" melainkan lebih bergantung
kepada seberapa kuat kekuasaan [politik] menginginkannya. Demikian juga,
timbul-tenggelamnya sebuah kekuasaan [politik], ia bukan sekedar bergantung
kepada kekuatan ekonomi dan tentara yang ada pada dirinya, melainkan ia juga
sangat ditentukan oleh seberapa besar kekuatan sosial yang terikat dalam satu
solidaritas ada bersamanya. Dalam konteks ini, sistem metodologi merupakan
wilayah "pusaran", tempat berpadunya kepentingan pengetahuan-kekuasaan,
identitas-eksistensi.
Di atas semua analisa keterbatasan metodologis tersebut, keempat, tempat
teori politik Islam al-Mâwardiy berada pada konteks sejarah ketika Islam tampil
sebagai kekuasaan-agama dan agama-kekuasaan. Al-Mâwardiy sama sekali tidak
211
mengelaborasi sejarah Islam secara keseluruhan sejak masa pendiriannya di
Mekkah dan masa pembentukannya di Madinah. Dan dengan demikian, teori
politik al-Mâwardiy tidak lahir dari refleksi kesejarahan Islam melainkan sekedar
idealisasi tentang apa yang disebutnya sebagai politik Islam dan berkutat dalam
lokus "Islam politik".
Maka, al-Mâwardiy sebagai salah seorang ahli hukum syariat memandang
negara sebagai pengejawantahan kekuasaan Allah di bumi, dan karena itu, ia
memandangnya dari "atas", yaitu bertolak dari ajaran-ajaran dasar ideal dan
ketetapan-ketetapan wahyu secara simbolik. Implikasinya, hukum berarti hukum
Allah, Pemberi Hukum Pertama, maupun dari kalangan yang memegang
kekuasaan (penguasa ataupun ulama). Untuk menjamin dan mencukupi keharusan
keyakinan itu, al-Mâwardiy memanfaatkan perangkat intelektual berupa teknikteknik konklusi (’istinbâth) yang telah tersedia pada zamannya dalam upaya
menghasilkan hukum-hukum cabang dari dasar-dasarnya secara teologis, sehingga
hukum-hukum itu terkesan bersifat ketuhanan, yang benar, dan yang sempurna.
Al-Mâwardiy tidak memikirkan dampak-dampak dari sikap pemahaman dan
model ’istinbâth yang ia gunakan terhadap taruhan-taruhan arti politik-negara
bagi rakyat/umat, melainkan justru melancarkan dan melanggengkan dominasi
kekuasaan negara atas rakyat secara hegemonik: kekuasaan berdiri "atas nama
Tuhan", di praktekkan dengan "cara-cara ketuhanan", dan demi Tuhan. Demikian
juga, metodologi itu benar-benar berfungsi sebagai sarana transendensi, serta
sebagai benteng perlindungan paling dasar untuk membangun identitas dan
kekuatan kelompok secara sektarian.
212
Catatan Penutup Analisa Metodologis
Uraian di atas cukup memberi gambaran bagaimana perspektif kritik sejarah
Foucauldian telah berperan menampilkan cara berpikir al-Mâwardiy yang
membentuk al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, yaitu cara berpikir ortodoksi yang
bersifat teologis (fiqhiy), cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan epistèmè Islam
ortodoks. Kajian terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah mesti mempertimbangkan
dua aspek tersebut, karena keduanya merupakan dasar yang membentuk isi al’Ahkâm al-Shulthâniyyah seluruhnya serta mengarahkan fungsinya.
Meskipun merupakan kritik, kritik sejarah ini merupakan salah satu
stretegi untuk memandang al-Mâwardiy dan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah secara
lebih adil dan proporsional. Karena, sesuai dengan perspektif sosiologi-arkeologi
pengetahuan, cara yang lebih memungkinkan melihat keduanya adalah dengan
mempertimbangkan cara-cara berpikir dan epistème yang membentuknya,
sehingga diperoleh pemahaman bahwa apapun yang dipikirkan/dikatkan alMâwardiy memiliki relevansi dengan konteks historis serta cara berpikir yang
diinginkan oleh epistème sosialnya.
C. AnalisaMitis
Analisa mitis yang diterapkan terhadap al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah
semacam upaya "pembebasan" dari wibawanya yang sangat besar sebagai teks
"agung". Kewibawaan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah bukan saja karena ia ditulis
oleh seorang intelektual sekaliber al-Mâwardiy, atas permintaan Khalifah alQâ’im, melainkan juga karena pemikiran-pemikiran al-Mâwardiy di dalamnya
213
dibangun
berdasarkan
kerangka/metode
berpikir
teologis
yang
“suci”,
diungkapkan dengan bahasa hukum “penjaga kesucian” dan difungsikan sebagai
kitab pedoman bagi khalifah/undang-undang yang mengatur kehidupan
masyarakat Islam. Tetapi sebenarnya wibawa inilah yang menjadi tabir tentang
hakikat material teori etika politik Islam al-Mâwardiy, yaitu hakikat
keberadaannya yang dipikirkan/ditulis oleh manusia yang terikat dengan faktorfaktor kesejarahannya. Analisa mitis dapat membantu untuk membuat jarak
dengan "keagungan" dogma-dogma yang diwariskan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah,
yang seolah-olah di luar sejarah atau di luar masa, maupun yang seolah-olah
bersih dari kepentingan ideologis. Dengan demikian, analisa mitis ini berarti
menempatkan "keagungan" dan "wibawa" al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai
sesuatu yang bersifat mitis atau menampilkan bentuk-bentuk mitos. Lalu apa arti
"mitos" dalam kaitannya dengan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah?
Konsep "mitos" dalam hal ini dimengerti bukan sebagai "cerita yang tidak
benar; cerita buatan yang tidak mempunyai kebenaran historis",365 bukan seperti
kata ’usthûrah [jamak: ’asâthîr] yang digunakan Alquran untuk dongeng dan
khayalan palsu yang dihubungkan dengan "fabel-fabel orang-orang dahulu
kala",366 dan ’asâthîr ini berlawanan dengan "kisah-kisah benar" (qashash alhaqq367 atau ahsan al-qashash368) yang diceritakan Alquran. Konsep "mitos"
dalam hal ini, sebagaimana diterapkan pada antropologi kontemporer, justru
365
Mitos (berasal dari bahasa Yunani mutos, berarti cerita) biasanya dipakai untuk menunjuk
cerita yang tidak benar, cerita buatan yang tidak mempunyai kebenaran historis. Lihat St. Sunardi,
Semiotika Negativa, h. 103.
366
Lihat Q.S. Al-’An‘âm (6): 25; al-’Anfâl (8): 31, 84; al-Naml (27): 68; al-Nahl (16): 24; al’Ahqâf (46): 17; dan Nûn/al-Qalam (68): 15.
367
Lihat Q.S. ’Âlu ‘Imrân (3): 62
368
Lihat Q.S. Yûsuf (12): 3
214
dihubungkan dengan qashas daripada ’asâthîr, yaitu cara bagaimana manusia
menyusun suatu strategi, mengatur hubungan daya-daya kekuatannya dan dayadaya kekuatan alam. Konsep "mitos" dimengerti sebagai pola-pola, kaidah-kaidah,
dan modal kemungkinan-kemungkinan manusiawi dalam semua lingkungan
kebudayaan, sekalipun tidak nampak. Dalam setiap lingkungan kebudayaan
perilaku manusia diatur oleh pola-pola semacam itu (bakat atau kemungkinan
untuk merumuskan kaidah-kaidah). Dan perlu digarisbawahi, kebudayaan yang
satu tidak lebih derajatnya daripada kebudayaan yang lain.369
Mengacu kepada batasan pengertian tersebut, maka definisi-definisi,
konsep-konsep, cara-cara berpikir, dan fungsi-fungsi semua itu yang mengatur
pemikiran al-Mâwardiy di dalam
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah adalah mitos.
Mitos-mitos dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah telah cukup dijelaskan bentukbentuk materialnya secara kongkrit pada analisa terdahulu dan pada saat penulis
menafsirkannya secara sinkronis. Tugas berikut ini adalah menganalisa mitosmitos itu melalui analisa mitis, yaitu memahami mitos-mitos itu secara diakronis
yang terkait dengan sejarah dan masyarakat yang melahirkannya. Memahami
mitos-mitos secara diakronis dalam konteks tersebut berarti mengamati macammacam kepentingan yang memberikan bentuk pada cara (mitos) di mana worldview370 ditetapkan dan diadaptasikan oleh al-Mâwardiy dengan kehidupan seharihari. Maka, analisa mitis ini lebih berarti kritik atas kepentingan (ideologi) yang di
bawa oleh mitos-mitos al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, dengan pendekatan semiotis.
369
370
C. A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 36-7.
Dalam batasan pengertian Max Weber
215
Secara semiotik dapat dikatakan bahwa al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah telah
mentransformasikan konsep-konsep dasar tertentu dari Alquran maupun sunah
Nabi. Artinya, al-Mâwardiy telah menghadirkan beberapa konsep di dalam al’Ahkâm al-Shulthâniyyah dengan makna-makna yang baru atau berbeda dengan
makna-makna ketika konsep-konsep itu berlaku pada masa Nabi masih hidup
(masa pendirian Islam). Analisa mitis dimaksudkan untuk melihat perubahan
makna konsep-konsep dasar tertentu dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Maka,
hal ini meniscayakan pengkajian konsep-konsep dasar secara sinkronis (kajian
makna konsep sesuai konteks awal kemunculannya), dan juga secara diakronis,
yaitu kajian terhadap perubahan-perubahan maknanya, terutama sampai pada
masa hidup al-Mâwardiy. Kajian konsep "kepatuhan" dan "kewenangan" secara
sinkronis-diakronis, misalnya, berarti kajian mengenai sejarah perubahan makna
konsep-konsep tersebut.
Ketika berbicara mengenai etika politik Islam, jelas bahwa hal itu
sesungguhnya memaksa untuk kembali ke Jazirah Arab pada Abad ketujuh
masehi sejak turunnya wahyu Alquran: yaitu masa kenabian dan masa pendirian
Islam, sampai masa terbentuknya negara Islam dan teologi Islam yang
mengkristal hingga abad kesepuluh masehi. Secara umum dikatakan bahwa ada
"perbedaan makna" konsep-konsep dasar mengenai Islam dan politik dalam
rentang masa tersebut.
Untuk mendekati permasalahan tersebut perlu ditetapkan obyek analisa
berupa fenomena-fenomena pemitosan yang ada, eksplisit maupun implisit dalam
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Fenomena-fenomena tersebut dapat saja berupa
216
konsep, sistem berpikir yang melahirkan konsep, maupun fungsi-fungsi dari
keduanya. Terkait dengan hal itu, dalam sub bab ini akan dilakukan analisa mitis
dengan kerangka pembahasan: 1) konsep inti al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan
sistem mitisnya; 2) Sistem berpikir al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan sistem
mitisnya; dan 3) fungsi-fungsi mitis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah.
1. Konsep Inti Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dan Sistem Mitisnya
Di antara konsep-konsep inti di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah yang bersifat
mitis, terdapat konsep "kepatuhan" (al-thâ‘at), "penguasa" (’uly al-’amr), dan
"rakyat" (al-’ummat)
Di sini hanya akan dilihat makna konsep "kepatuhan", karena ia
merupakan konsep kunci dalam seluruh bangunan teori al-Mâwardiy dan
pemikiran etika politik Islam yang lain, dan karena dengan membicarakan konsep
"kepatuhan" saja kedua konsep yang lain tercakup di dalamnya.
"Kepatuhan" adalah sebuah kualitas tindakan "kepasrahan" (al-taslîm):
penyerahan hak "kebebasan" oleh siapa dan kepada siapa. Alquran menegaskan:
“Hai orang-orang beriman, patuhilah Allah, Rasul-Nya, dan penguasa urusan di
antara kalian”.371 Dalam konteks khusus, ayat tersebut turun sebagai '
perintah'
Allah kepada orang-orang beriman (para pengikut Muhammad) agar patuh, selain
kepada Allah dan Rasul-Nya, juga patuh kepada seseorang yang diberi mandat
oleh Rasul untuk menjalankan tugas kepemimpinan menggantikannya. Dari
berbagai riwayat, orang yang diberi mandat tugas itu adalah: ‘Abdullâh bin
371
Q.S: Al-Nisâ’, 59
217
Hudzâfah bin Qais al-Sahmiy, atau ‘Ammâr bin Yâsir, atau Khâlid bin Walîd,
untuk memimpin ekspedisi militer. Kenapa Allah memerintah kepada orang-orang
beriman agar mematuhi tiga aktan sebagaimana tersebut pada ayat di atas?
Inti misi kenabian Muhammad [juga nabi-nabi lain] adalah mengajak
manusia kepada ’islâm ("penyerahan"). Orang yang mengaku beriman kepada
misi kenabian Muhammad adalah orang yang "berserah diri" kepada Kehendak
Allah Yang Mengejawantah ke dalam kehendak Muhammad sebagai rasul-Nya,
dan disebut al-muslim [jamak: al-muslimûn]. "Penyerahan diri" itu dinyatakan
secara lisan dalam bentuk "kesaksian" (al-syahâdah): pengakuan bahwa Allah
adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul-Nya, serta diaplikasikan melalui
tindakan "kepatuhan" terhadap perintah dan larangan Allah yang disampaikan
melalui lidah Rasul-Nya. Sejarah telah mencatat bagaimana ragam tanggapan
manusia terhadap misi yang dibawa Muhammad itu, serta bagaimana dia
mengelola misinya.
Muhammad adalah Rasulullah, dan dalam menunaikan misi kerasulannya
ia tidak pernah bertindak sebagai seorang raja karena dia memang bukan seorang
raja. Dia tidak pernah mengaku lebih dari seorang rasul, dan sedikitpun tidak
pernah mengaggap dirinya seorang raja. Tindakannya memimpin manusia yang
mau hidup di bawah kepemimpinannya, bukan semata-mata karena itu merupakan
ambisi pribadinya demi kepentingannya, tetapi semata-mata itu adalah proses misi
kerasulannya. Dia tidak pernah menikmati hidup selayaknya para raja, dia hidup
seperti selayaknya orang biasa. Oleh karena itulah, dia mudah mendapatkan
"kepatuhan" dari orang-orang yang telah menyatakan "penyerahan" kepadanya.
218
Hubungan Muhammad dengan "orang-orang yang berserah diri" (al-muslimûn) itu
adalah hubungan antara Rasul dengan pengikut, hubungan antara pemilik
'
wibawa'(otoritas) dengan orang-orang yang merasa "berhutang makna".
Sementara orang-orang yang belum mau "berserah diri" (al-kâfirûn),
mereka melihat Muhammad hanya sebagai "orang biasa"-nya, kepemimpinannya
terhadap pengikutnya dianggap sebagai kepemimpinan raja terhadap rakyatnya.
Muhammad dilihat sebagai raja dengan segala kekuasaan – power – nya. Ketika
sebagian besar mereka kemudian "menyerahkan diri" karena kesuksesan
Muhammad, "penyerahan" mereka lebih dilatarbelakangi alasan karena mereka
melihat power Muhammad tidak mampu lagi mereka tandingi. Mereka adalah
orang-orang yang
kemudian "menyerahkan diri" karena faktor pertimbangan
politik dan ekonomi. Mereka memang disebut muslimûn, tetapi lebih berarti
sebagai "orang-orang yang takluk".
Sejak bergabungnya orang-orang yang "berserah diri" dengan orang-orang
yang "menyerahkan diri" dalam satu komunitas di bawah kepemimpinan Nabi
Muhammad, mereka adalah satu komunitas yang sangat besar yang meliputi
hampir seluruh penduduk di semenanjung Arab. Dikatakan "hampir" karena,
meskipun power Muhammad telah sedemikian besar, masih ada sebagian kecil
penduduk Arab yang tidak mau "berserah diri" atau "menyerahkan diri". Satu
kenyataan lain, sebagai manusia biasa Muhammad tidak bisa lagi menangani
semua hal sendirian dalam memimpin komunitas yang sangat besar itu. Sejauh dia
bisa menangani suatu urusan/kebutuhan dengan dirinya sendiri, dia akan
menanganinya sendiri dan tidak akan meminta bantuan orang lain. Ia akan
219
meminta bantuan orang lain jika terpaksa harus berbuat begitu, seperti pada kasus
yang di atas telah disebutkan. Dalam konteks demikianlah ayat tersebut turun, dan
secara khusus berkenaan dengan pengiriman pasukan yang tidak dapat dipimpin
oleh Rasulullah sendiri.
Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, terasa sekali "gigitan" ayat
yang telah dinyatakan di atas. Dalam konteks itu, dapat dipahami makna perintah
Allah agar komunitas besar itu patuh kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang yang
"memegang urusan" (’uly al-’amr) atas mandat Rasul. Bagi orang-orang yang
"berserah diri", perintah Allah itu berarti sebagai perintah untuk lebih
meningkatkan
kualitas
"kepatuhan".
Tetapi
kepada
orang-orang
yang
"menyerahkan diri", perintah itu berarti sebagai "perintah" untuk "mematuhi".372
Dengan demikian gabungan al-muslimûn dan al-thâ'
ah, dilihat dari substansinya
saja jelas ada perbedaan kualitas, yaitu: "kepatuhan orang-orang yang berserah
diri" dan "kepatuhan orang-orang yang menyerahkan diri". Demikian juga,
'
kepatuhan mutlak'hakikatnya hanya kepada Aktan Pertama (Allâh), kemudian
menurun kepada aktan kedua (Rasûlullâh), dan lebih menurun lagi kepada aktan
ketiga (’uly al-’amr). Konsep "kepatuhan" ini mudah dimitoskan (mudah jatuh
menjadi mitos "kepatuhan mutlak" untuk semua aktan), apalagi memakai
dukungan perkataan Rasulullah: "Barang siapa mematuhiku, maka dia mematuhi
Allah; barang siapa menentangku, maka dia menentang Allah; dan barang siapa
372
Perang mulut (cekcok) yang terjadi antara ‘Ammâr bin Yâsir dengan Khâlid bin Walîd di
lapangan tugas hingga sekembalinya di hadapan Nabi seperti diriwayatkan ’Ibn Katsîr, semakin
memperkuat pemaknaan di atas. Narasi selengkapnya tentang kasus itu, lihat ’Ibnu Katsîr, Tafsîr
al-Qur'
ân al-‘Azhîm, Beirut: Dâr al-Mufîd, 1403/1983, Vol. 1, h. 459.
220
menentang pemerintahku, maka dia menentangku".373 Tetapi, di sepanjang
kehidupan Muhammad, dia tidak pernah menuntut dipatuhi secara mutlak demi
ke-Muhammad-annya, melainkan semata-mata karena dia adalah Rasulullah.
Maka dia pun memberi batasan kepatuhan kepada aktan ketiga. Dia berkata:
"Orang yang berserah diri (al-muslim) harus mendengarkan dan patuh [kepada
pemerintahku, pen.] dalam hal yang dia senangi atau yang dia benci, selagi dia
tidak diperintahkan melakukan kedurhakaan. Jika dia diperintahkan melakukan
kedurhakaan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh patuh".374
Demikianlah makna "kepatuhan" ketika Rasulullah masih hidup.
Ketika kemudian al-Mâwardiy mengutip ayat tersebut375 (ayat ini juga
sering diulang-ulang dalam kitab-kitab teologi Islam yang lain), makna
"kepatuahan" mengalami perluasan dari maknanya yang semula. Proses yang
kemudian terjadi adalah rasionalisasi "kepatuhan". "Kepatuhan" kepada Allah
mulai dipahami sebagai hak-hak (huqûq) Allah atas manusia, karena Allah adalah
Pencipta, dan tindakan penciptaan tersebut adalah nikmat (karunia). Karena Allah
memberikan nikmat atas manusia dengan menciptakannya pada pusat jagad raya,
dan memberinya tempat yang agung di dalamnya, maka sebagai balasan dari
nikmat-nikmat ini Allah menunggu jawaban yang baik dari manusia, yaitu
kepatuhan dan rasa syukur. Kepatuhan yang dimaksudkan di sini adalah suatu
hubungan yang berdasarkan pengakuan manusia terhadap nikmat-nikmat Allah.
373
Hadis riwayat dari ’A‘masy dari ’Abî Shâlih dari ’Abî Hurairah. Lihat al-Mâwardiy, al-Nukat
wa al-‘Uyûn, tafsir ayat ke-59, surat al-Nisâ’.
374
Hadis riwayat ’Abû Dâwud, Bukhâriy, dan Muslim. Lihat ’Ibnu Katsîr, Op. Cit., h. 458.
375
Lihat pengutipan ayat tersebut oleh al-Mâwardiy, bagaimana komentarnya, dan bagaimana pula
konklusi hukum yang ditariknya dari ayat itu dalam, al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, h. 5, lihat juga
tesis ini pada halaman 182.
221
Berdasar hubungan yang berdiri di atas dasar pengakuan terhadap nikmat-nikmat
inilah ditetapkannya "beberapa kewajiban" (al-wâjibât) atas manusia sebagai
hamba kepada Penciptanya. Kewajiban-kewajiban ini merupakan hak-hak Allah
atas manusia. Secara teologis ditambahkan, bahwa manusia tidak akan cukup dan
tidak akan besar kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali jika Allah masuk ke
dalam dunia dan “tempat” tinggalnya.
Jadi, berdasarkan ayat tersebut al-Mâwardiy menyusun kerangka teologis
hubungan Allah dengan manusia. Dalam hal penciptaan, Allah adalah subyek dan
manusia adalah obyeknya, dan dalam kaitan itu, karena penciptaan adalah '
nikmat'
maka Allah "menuntut" manusia sebagai obyek agar aktif (menjadi subyek)
merespon "nikmat" dengan bersyukur kepada-Nya.
Sampai di sini, sebenarnya "tuntutan" Allah itu masih bersifat "sukarela";
manusia bebas memerankan dirinya: mau bersyukur atau sebaliknya. Jika manusia
merespon "nikmat" dengan bersyukur, maka "kepatuhan" adalah aplikasi syukur
dalam tindakan. Dalam hal ini, manusia adalah subyek dan Allah adalah obyek.
Dengan demikian syukur manusia memiliki tuntutan aplikasi: sikap dan tindakan
kepatuhannya terhadap Kehendak Allah. Tetapi, sedikit pun Allah tidak
"mengambil bagian" dari syukur dan kepatuhan manusia. Karena "kepatuhan
sukarela" berdiri di atas prinsip kebebasan manusia untuk memilih, dan apapun
pilihannya itu, akibat baik atau buruk akan kembali kepada manusia sendiri, cepat
atau lambat.
Kemudian sistem teologi merubah/menetapkan bahwa "kepatuhan" ini
sebagai "kewajiban yang mengikat" (al-wujûb al-taklîfiy) manusia. "Terimakasih"
222
dan "kepatuhan" bukan lagi atas dasar hubungan "sukarela" melainkan "kewajiban
(yang memaksa)". Teologi Islam juga menetapkan bahwa pengawasan
pelaksanaan "kewajiban" merupakan tanggungjawab Nabi dalam menjalankan
risalahnya,
dan
juga
tanggungjawab
utama
negara
(penguasa)
yang
menggantikannya. Kehidupan Nabi bersama para Sahabat pasca hijrah
dipersepsikan
oleh
ulama
teologi
sebagai
lembaga
yang
memerankan
tanggungjawab pelaksanaan dan pengawasan "kewajiban" tersebut.
Demikianlah perubahan makna "kepatuhan", yang semula merupakan
hubungan manusia-Allah atas dasar "kesukarelaan-iman-syukur", berubah
menjadi hubungan terlembaga atas dasar "kewajiban-paksaan". Lembaga yang
berperan merubah pola hubungan ini, tidak ada lain, adalah ulama yang memakai
kerangka berpikir teologi. Sistem berpikir teologis mengasumsikan bahwa Allah,
Nabi, dan negara (penguasa) adalah lembaga-lembaga yang "berwenang" (berhak)
menerima "kepatuhan" manusia, menentukan kewajiban-kewajiban atas mereka
dan mengawasi pelaksanaannya.
Dari sudut pandang antropologi, bahwa apapun bentuk hubungan mansuiaAllah dikonsepsikan, sebenarnya semuanya itu dibangun di atas dasar keimanan.
Artinya, ia merupakan hasil kreasi mental-spiritual dan angan-angan manusia
dalam memahami kehadiran dirinya dan relasinya dengan fenomena penciptaan.
Dengan kata lain, syukur dan patuh, sampaipun ia dipersepsikan sebagai
"kewajiaban (yang memaksa)", ia tak lebih dan tak kurang hanyalah sebuah
produk keyakinan/keimanan. Dengan demikian ia merupakan manifestasi dari
sejarah iman atau iman yang disejarahkan. Tetapi, teologi hubungan manusia-
223
Allah telah dibangun al-Mâwardiy berdasarkan konsepsi yang kedua (paksaan)
yang menghilangkan nuansa kesejarahan iman, atau menutupi kenyataan bahwa
konsepsi tersebut sumber terdalamnya adalah keimanan.
Selanjutnya, secara antropologis, “campur tangan” Allah ke dalam dunia
kemudian terlembagakan melalui sejarah kenabian/pewahyuan, dalam konteks
Islam adalah Nabi Muhammad. Oleh karena Muhammad dan para nabi yang lain
mengaku diri dan diyakini para pengikutnya memiliki akses komunikasi (wahyu)
dengan Allah, dan setiap mereka dianggap menjalankan misi (rasâlah)-Nya, maka
– terkait dengan sejarah kepatuhan – kepatuhan kepada Rasul sesungguhnya
merupakan kepatuhan manusia kepada manusia, dan ini merupakan kepatuhan
level kedua dalam sejarah iman. Artinya, ‘kewenangan’ yang dimiliki Rasul untuk
menerima kepatuhan manusia (pengikut-pengikutnya) adalah terbangun atas dasar
keimanan bahwa ia Utusan Allah yang menjalankan misi-Nya. ‘Kewenangan’
Nabi hanya mengikat kepatuhan orang-orang yang beriman kepadanya, dan
memang pada kenyataannya, Nabi tidak pernah memaksakan keimanan itu kepada
siapapun, menonjolkan kewenangannya, dan apalagi memaksakan kepatuhan
manusia terhadapnya. Sampai di sini, kepatuhan sebenarnya juga masih bersifat
sukarela meskipun Nabi telah menjadi seorang ‘penguasa’ yang memimpin
masyarakat/umat di Madinah.
Seberapa pun wewenang dan kekuasaan yang diberikan Allah kepada
Nabi, wewenang dan kekuasaannya hanya mengharuskan kepatuhan kepada
orang-orang yang mau percaya (beriman) dan tidak memaksakannya kepada
orang-orang yang tidak (belum mau) beriman. Dan bagi orang-orang beriman,
224
kepatuhan mereka kepada Nabi bukan saja dipahami sebagai keharusan yang
diperintahkan Allah sebagaimana bunyi tekas Alquran tersebut di atas, melainkan
juga karena kewibawaan Nabi sehingga mereka memberi kepatuhan secara
sukarela dan merasa bahwa kepatuhan itu sebagai imbalan balas budi karena
mereka "berhutang makna" kepadanya. Mereka meyakini bahwa Nabi adalah
"juru selamat", dan tanpa sosok peran Nabi dalam kehidupan mereka, mereka
merasa hidup tak bermakna dan sia-sia. Dengan demikian, kemunculan Nabi
sebagai "yang berwenang" adalah karena ia diyakini para pengikut sebagai Rasul
Allah, dan karena wibawanya, para pengikut kemudian memberikan '
kepatuhan'
kepadanya secara "sukarela". Kepatuhan mereka bukan karena Muhammad
sebagai seorang "penguasa".
"Kepatuhan" secara "sukarela" ini dapat dibedakan secara jelas dengan
"kepatuhan" kabilah-kabilah Arab terhadap Nabi setelah posisi politiknya sangat
kuat. "Kepatuhan" mereka lebih menunjukkan "ketundukan" secara politik, karena
sebelum itu mereka selalu menolak mengakui kerasulan Muhammad dan bahkan
selalu menggalang kekuatan untuk menentangnya. Setelah mereka menyadari
bahwa kekuasaan Muhammad semakin lama bertambah besar dan tak tertandingi,
mereka merasa tak ada lagi pilihan kecuali harus mengakui "kekuasaan" dan
"kerasulan"-nya. Maka kemudian mereka berbondong-bondong menyatakan
"ketaklukan" dan mengikatkan diri ke dalam kesatuan politik/kekuasaan
Muhammad.
Karena "kepatuhan" kabilah-kabilah Arab tersebut bermotif politik, maka
"kepatuhan" mereka terhadap Islam diharuskan oleh Muhammad sebagai sebuah
225
persyaratan. Dengan kata lain, karena ke-Islam-an mereka karena terpaksa, maka
Muhammad pun kemudian memaksakan wewenangnya dan "mewajibkan
kepatuhan" mereka terhadapnya. Demikian juga yang dilakukan Muhammad
terhadap penduduk Mekkah ketika mereka dapat ditundukkan. Kesimpulannya,
karena mereka memeluk Islam disebabkan faktor-faktor politik dan bermotif
politis, maka sungguh tepat ketika Nabi memperlakukan ke-Islam-an mereka juga
secara politik: menonjolkan kewenangannya dan memaksakan kepatuhan mereka
terhadapnya. Singkatnya, terhadap orang-orang yang masuk Islam secara politik,
Muhammad menekankan dirinya sebagai "Rasul" yang "penguasa". Fenomena
historis inilah yang dilampaui pemikiran teologi Islam yang mengkonsepsikan
"kepatuhan" terhadap Rasul sebagai sesuatu yang mutlak: harus (wâjib) bagi
siapapun. Ia telah melampaui konsep "kepatuhan" sebagaimana dipraktekkan oleh
Rasul sendiri. Ia juga telah menghilangkan dimensi kemanusiaan Rasul yang
dipersepsikan sebagai pengejawantah Kehendak Tuhan yang mengatasi segalanya.
Demikian juga, pemikiran teologi telah melupakan fakta bahwa legitimasi satusatunya kewenangan Rasul memimpin umat adalah keimanan para pengikutnya.
Sekali lagi, keimanan adalah masalah pilihan dan bukan paksaan. Jika hubungan
manusia-Allah saja berada di atas kebebasan iman, maka apalagi hubungan
manusia-Nabi yang notabene juga seorang manusia; hal itu juga berada di atas
landasan kebebasan yang sama.
Terkait dengan al-Mâwardiy, ia benar-benar telah memposisikan
pemikirannya dalam kerangka berpikir teologis tersebut. Seluruh bangunan teori
etika politiknya, terutama mengacu kepada sejarah kepemimpinan Muhammad
226
sebagai seorang Nabi dan sekaligus penguasa, dan tidak membedakan fungsi dari
keduanya dalam pentas sejarah pendirian Islam. Tindakan-tindakan politik Nabi
yang sebenarnya lebih mencerminkan aktualitas manusiawinya, telah dinaikkan
sebagai
tindakannya
yang sakral
dan
ideal:
Kekuasaan Tuhan
Yang
Mengejawantah dalam sejarah manusia, dari mana Islam yang telah terbentuk
harus dilanjutkan juga di atas kekuasaan.376
Ketika kemudian Rasul mendelegasikan beberapa tugas kerasulannya yang
spesifik kepada seorang individu, maka individu tersebut memiliki hak untuk
dipatuhi oleh orang lain. Hal ini merupakan kepatuhan level ketiga dalam sejarah
iman.
Siapapun yang diberi limpahan wewenang dan kekuasaan Rasul untuk
melaksanakan sebuah misi tugas tertentu ketika ia masih hidup, bagi orang-orang
yang beriman relatif mudah mengakui "legalitas" kewenangannya dan
memberikan kepatuhan kepadanya, karena ia memegang mandat dari Rasul.
Tetapi pada taraf ini, sesungguhnya konsep kepatuhan telah mengalami penurunan
kualitas makna. Kepatuhan yang semula merupakan bentuk rasa syukur kepada
karunia Allah dan ungkapan rasa terima kasih atas wibawa Nabi, menurun
menjadi kepatuhan yang "terpaksa" (semata karena seseorang itu sebagai
pemegang mandat Nabi).
Bagaimana kemudian setelah Nabi wafat? Orang-orang beriman yang
telah terlembagakan menjadi kaum Muslimin karena faktor-faktor politik
376
Diskusi yang lebih intensif mengenai hakikat risalah Nabi, lihat: ‘Aly ‘Abd al-Râziq, “Risalah
Bukan Pemerintahan, Negara Bukan Agama”, dalam Charles Kurzman (Editor), Wacana Islam
Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, Jakarta, Paramadina, 2001, hal. 317.
227
sebelumnya, ternyata berselisih pendapat tentang ada atau tidak adanya seseorang
yang diberi mandat untuk menggantikan tugas-tugas kerasulannya. Sejak saat itu,
secara politik terjadi perpecahan aspirasi di kalangan kaum Muslimin yang tidak
mudah dipersatukan karena
masing-masing memiliki
klaim dan dasar
pembenarannya, serta semua mengklaim bersumber dari Nabi. Dalam konteks ini,
bagaimana ayat Alquran di atas tentang keharusan mematuhi orang-orang yang
memiliki kewenangan memerintah (’uly al-’amr) harus dipahami? Siapakah orang
yang memiliki kewenangan itu?
Menurut orang-orang yang mendukung ‘Aly bin ’Abî Thâlib, ’uly al-’amr
adalah dia. Orang-orang ini menyatakan bahwa ‘Aly adalah satu-satunya orang
yang diberi mandat oleh Rasul untuk menggantikannya kelak, semenjak dia masih
hidup. Kelompok lain menyatakan bahwa kewenangan sebagai pengganti Rasul
itu tidak pernah termandatkan kepada siapapun, maka menjadi hak bersama yang
perlu dimusyawarahkan/dinegoisasikan. Karena pada kenyataannya, mereka yang
dianggap memiliki kompetensi hak dan kewenangan, baik untuk melakukan
permusyawaratan maupun memegang pemerintahan hanyalah para elit tertentu
yang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sentimen daripada
pengakuan akan kesamaan hak dan kewajiban di antara kaum Muslimin
seluruhnya; maka, kelompok yang ketiga berpendapat dan menuntut hak
kewenangan itu melekat bagi/kepada semua kaum muslimin secara sama.
Jika legalitas kepatuhan kepada Allah bersumber pada keimanan orangorang yang mau percaya, legalitas kepatuhan kepada Rasul juga bersumber
kepada hal yang sama, legalitas kepatuhan kepada seseorang yang diberi mandat
228
oleh Rasul ketika dia masih hidup adalah bersumber kepada legalitas ke-Rasul-an
itu sendiri, lalu, bagaimana legalitas kewenangan harus bersumber ketika Rasul
telah wafat? Dalam konteks ini, sekali lagi, lembaga mana yang benar-benar dapat
menjamin kepastian bahwa kewenangan itu sah bagi salah satu kelompok, dan
bukan bagi yang lain?
Ketika kemudian al-Mâwardiy mengutip ayat tersebut, siapakah yang
dimaksudkannya sebagai ’uly al-’amr? Berdasarkan teori kepemimpinannya dapat
disimpulkan bahwa yang dia maksudkan dengan istilah tersebut adalah
sebagaimana pendapat kelompok kedua dari ketiga kelompok yang telah disebut
di atas. Dengan demikian, secara langsung/tidak langsung, al-Mâwardiy mengakui
bahwa "kewenangan" dan "'
kepatuhan" merupakan hak bagi orang-orang yang
memerintah dalam versinya itu, yaitu para penguasa setelah Nabi yang disebut
"khalifah" atau ‘amîr al-mu’minîn’. Tetapi juga harus diingat, pada konteks yang
sama, ayat tersebut juga menjadi sandaran dua kelompok yang lain dengan versi
penafsirannya masing-masing.
Maka, sesungguhnya al-Mâwardiy dan hampir seluruh pemikir etika
politik Islam yang selalu mengulang-ulang ayat tersebut, mereka telah berperan
menutupi "kepatuhan" dan "kewenangan" dari arti kesejarahannya : yaitu sejarah
kepatuhan dan kewenangan yang mengalami "penurunan" dan sejarahnya yang
"berubah". Berdasarkan ayat tersebut, pemikiran etika politik Islam menyatakan
bahwa manusia "wajib" mematuhi Allah karena Kekuasaan-Nya, "wajib"
mematuhi Nabi karena ia Rasul-Nya, dan "wajib" mematuhi "para pemerintah"
karena hak kewenangannya. Dengan demikian logika pemikiran etika politik
229
Islam juga menyatakan bahwa konsekuensi keimanan seseorang adalah mematuhi
Allah, mematuhi Rasul-Nya, dan mematuhi para pemerintah Islam. Mematuhi
pemerintah sama dengan mematuhi Rasul dan mematuhi Allah. Maka, lembaga
pemerintahan Islam menjadi sesuatu yang sakral. Sakrealitas lembaga
pemerintahan kemudian menuntut kepatuhan mutlak umat/rakyat untuk
memenuhi hak-hak Allah dan tugas utama negara adalah menjamin hak-hak Allah
tersebut terpenuhi. Hak-hak Allah inilah sebenarnya yang berfungsi sebagai
kontrol moral penguasa atas rakyat, dan bukan sebaliknya. Dalam konsep "negara
kepatuhan", negara benar-benar menjadi sakral dan absolut: penentu "kebenaran",
penentu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan yang paling
tahu tentang apa "yang baik" bagi kehidupan rakyatnya. Karena negara
dilegitimisi dengan hak-hak ketuhanan, maka implikasi terjauh dari konsep
"negara kepatuhan" adalah pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia. Rakyat
dalam relasinya dengan negara ditempatkan dalam konteks manusia dalam
relasinya dengan Tuhan. Rakyat awam dianggap berada dalam domain kegelapan
dan ilusi. Mereka harus mengikuti aturan model Tuhan (yang hakikat materialnya
adalah aturan penguasa/kaum ulama), jika tidak, maka akan dianggap melanggar
Hukum (Kehendak) Tuhan dan biadab.
Pemikiran etika politik Islam menyatakan bahwa lembaga pemerintah
sebagaimana terjelma dalam sejarah Islam dan dalam seluruh angan-angan versi
kelompok-kelompok kaum muslimin adalah esensi pemerintah Islam yang hakiki.
Tetapi,
kenapa
mereka
berpecah-belah,
dan
ironisnya,
masing-masing
mendasarkan legalitasnya kepada Allah dan rasul-Nya, sehingga semua
230
mengklaim bahwa lembaga pemerintah dalam setiap versinya merupakan
pemerintahan Allah dan Rasul-Nya?
Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran al-Mâwardiy
dan pemikiran etika politik Islam yang lain benar-banar telah mengabaikan
realitas sejarah kepatuhan, sejarah kewenangan, dan sejarah pemerintahan dalam
Islam, mengabaikan penurunan makna legalitasnya, bahkan tidak memikirkan
problem legalitas itu sendiri beserta implikasi-implikasinya. Singkatnya, alMâwardiy beserta pemikir-pemikir teologi Islam yang lain telah membaca
Alquran dengan sinaran makna yang berlaku pada zaman mereka dan momenmomen sejarah tertentu yang spesifik, serta bukan memahaminya dengan sinaran
makna
yang
berlaku
pada
masa
turunnya.
Pada
saat
yang
sama,
pembacaan/penafsiran al-Mâwardiy terhadap Alquran yang sungguh mengacu
kepada momen-momen sejarah yang spesifik itu, tertutupi oleh klaim syar‘i-nya
sehingga
seolah-olah
konklusi-konklusi
yang
didapatkannya
merupakan
manifestasi makna Alquran/Hukum-Kehendak-Tuhan. Jika dikaitkan dengan
pembacaan Alquran oleh kelompok-kelompok yang lain, dapat dipertanyakan:
bagaimana mungkin Syariat Tuhan itu saling kontradiktif?
Demikianlah, makna (penafsiran) yang sesungguhnya menurun telah
diangkat tinggi-tinggi; apa yang sesungguhnya bersifat temporal telah dinaikkan
statusnya sebagai sesuatu yang azali-abadi: di luar masa, di luar waktu. Hal yang
sama dapat ditemukan jika diteliti makna-makna dari konsep "iman" dan "islam".
Sebagai contoh hal itu, makna kata "muslim" dalam Alquran atau menurut
Alquran, dengan makna kata "muslim" yang dikaitkan setelah berdirinya negara
231
Islam dan teologi Islam. Maka keduanya berbeda dan tidak sesuai. Realitas
"keberbedaan" dan "ketidaksesuaian" inilah yang secara sengaja atau tidak
sengaja ditutupi di dalam teks-teks pemikiran (teologi) Islam, dan khususnya, alMâwardiy dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Fenomena yang sama juga terjadi
pada konsep ’uly al-amr dan ’ummah.
Telah ditunjukkan bahwa pemikiran al-Mâwardiy sesungguhnya sangat
terikat kepada momen kesejarahan tertentu/terbatas, yaitu periode zaman
pembentukan dan pengokohan teologi dan politik Islam. Sekalipun demikian, dia
berusaha menanggalkan sifat historisnya dan menggantikannya dengan esensi:
yaitu substansi pemikiran yang dianggap azali dan yang sesuai bagi seluruh
zaman dan tempat. Demikianlah, pengacuan al-Mâwardiy terhadap ayat-ayat
Alquran dan hadis Nabi telah difungsikan al-Mâwardiy secara mitis.
2. Sistem Pemikiran Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dan Sistem Mitisnya
Sistem mitis pemikiran al-Mâwardiy dapat dilihat dari seluruh pemikirannya yang
dibangun mengikuti sistem-sistem teologi dengan pembatasan-pembatasan
dualistiknya:
mukmin-kafir,
halal-haram,
suci-najis,
dan
seterusnya.
Sesungguhnya, di dalam pembagian-pembagian dualistis ini terdapat kontradiksi
antara sistem teologi tertentu dengan sistem teologi lainnya, karena sesuatu yang
dipandang haram (tidak boleh) oleh al-Mâwardiy misalnya, ada pada kondisi
kesejarahan tertentu, menjadai halal (boleh) pada kondisi yang lain.
Demikian juga, pemikiran al-Mâwardiy dibangun di atas sistem teologi
yang eksklusif yang mengklaim bahwa dia mewakili kebenaran/realitas yang
232
mutlak tentang kekuasaan. Kontradiksi dualistik dan eksklusifitas ini benar-benar
mengendap dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dan kitab-kitab teologis yang lain,
sehingga yang tampak dari semua itu adalah wajah hukum/etika Islam yang
"agung" dan "suci". Karena anggapan kesucian dan keagungannya, konklusikonklusinya
dianggap
sebagai
kepastian
yang
kokoh
dan
tak
dapat
dirubah/diganti. Kontradiksi dualistik dan eksklusifitas adalah sebagian dari
"forma-forma retorik": bentuk-bentuk "percakapan" yang lazim dijumpai dalam
sistem pemikiran teologis seperti al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Bentuk-bentuk
tersebut dihadirkan sebagai acuan dalam proses pemaknaan terhadap realitas
sosial dan politik secara transenden. Padahal, bentuk-bentuk tersebut sebenarnya
historis: ada periode dalam sejarah ketika kelas tertentu (seperti al-Mâwardiy dan
golongan intelektual yang lain bersama-sama penguasa) mempunyai kesempatan
untuk menciptakannya.
Sistem mitis yang lain, yang yang terkait dengan sistem pemikiran alMâwardiy, dapat ditemukan ketika ia menghadirkan "esensi" pendirian Umat atau
jamâ'
at al-muslimîn pada masa Nabi dan generasi "Sahabat yang tercerahkan" dan
mengubah cerita-cerita tersebut menjadi nilai-nilai agung dan orisinal serta
kepada model-model ideal tertinggi bagi pemikiran dan perilaku kekuasaan, dan
membakukannya sebagai basis pendirian nilai kolektif. Dengan melakukan itu,
sesungguhnya al-Mâwardiy telah melakukan pemitosan dalam pengertian: ia
mengambil dan menghimpun seluruh bentuk perilaku kekuasaan ideal dan
gambaran-gambaran simbolis sebagai medium penyusunan model bagi "ensi
(makna) kekuasaan". Kemudian, bentuk-bentuk tersebut dikemukakannya dengan
233
bentuk yang paling jelas dan pakaian yang paling indah agar diterima dan diulangulang oleh seluruh kaum Muslimin.
Al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah telah menghadirkan bentuk-bentuk perilaku
kekuasaan ideal beserta gambaran-gambaran simbolisnya, dan mewujudkannya
sebagai "hakikat" kekuasaan Islam dan sekaligus memberinya makna/nilai atau
menetapkannya sebagai "skala": pengukuran keabsahan terhadap suatu realitas
atau tindakan politik. Kemudian nilai tersebut menguat dan bertambah kaya
secara terus-menerus dengan jalan penerapan secara kontinyu dan hidup dalam
praktek kekuasaan dan sangat tergantung padanya. Ulama dan penguasa pada
masa al-Mâwardiy adalah kelas yang memiliki "kewenangan" menciptakan
"esensi kekuasaan" dan memegang kendali "ukuran"-nya, serta paling memiliki
"kekuasaan" untuk mempertahan kondisi stabil (status quo) masyarakat Islam.
Konsep "ijmak" yang begitu sentral perananya dalam pembangunan
pemikiran
etika
kekuasaan
al-Mâwardiy
sebagai
medium
penghadiran
esensi/hakikat kekuasaan Islam, sebenarnya ia merupakan bentuk komitmen
kelompok elit Islam yang berfungsi sebagai "alat" penjamin "orisinalitas" nilainilai kekuasaan Islam yang kemudian berkembang menjadi dogma yang
menentramkan. Ketika dogma-dogma ijmak menjadi semakin kuat, maka etika
kekuasaan Islam menjadi menolak terhadap sesuatu yang berbeda darinya.
Sampai di sini, mitos "kekuasaan Islam" yang dihadirkan al-Mâwardiy
berfungsi sebagai
semangat dan cita-cita yang mendorong ke arah realisasi
"kekuasaan Islami" di muka bumi dan ke-"menangan"-nya. Sementara itu, mitos
"kekuasaan Islami" itu justru mengandung fungsi (disadari atau tidak disadari)
234
melemahkan tekad dan menyerukan sikap menyerah terhadap dekapan kekuasaan
otoriter serta tidur di atas sejarah kekuasaan yang tiran dan hegemonik. Fenomena
kedua inilah yang kemudian justru memandu sejarah kekuasaan dalam Islam. Di
sini, mungkin tempat yang tepat untuk mempertanyakan kembali: benarkah
"kekuasaan Islam" adalah [bagian] misi Nabi? Bagaimanakah karakter
sesungguhnya "kekuasaan Islmi" itu? Jawaban yang "benar" atas dua pertanyaan
itu sangat tergantung kepada sejauh mana orang dapat [mau?] menyadari
keberadaan mitos-mitos di dalam "Islam". Tetapi kesadaran tentang mitos, sesuatu
yang sulit ditolerir dalam sistem pemikiran teologi Islam klasik, bukan?
3. Fungsi Mitis Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah
Pemikiran teologis al-Mâwardiy mengenai etika kekuasaan Islam, secara umum
bersumber dari wahyu, tradisi Nabi, dan para "Sahabat yang tercerahkan". Namun
tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat pemikirannya dan sumber-sumber tersebut
merupakan "benda" yang dikuasai/dimanipulasi oleh kekuasaan yang mewujud
pada sistem. Kekuasaan itu berupa kekuasaan politik yang dimiliki oleh para
Imam, bersama-sama dengan kekuasaan agama yang dimiliki oleh kelompok
ulama yang berada pada posisi melayani kekuasaan politik. Pada kenyataannya,
kekuasaan tersebut menjelma pada keduanya ketika sebuah kekuasaan politik
terbentuk dan mengambil bentuk secara kooptatif dengan kekuasaan agama.
Kondisi tersebut bermula sejak dari kekuasaan dinasti ‘Umâwiyyah di Damaskus
pada tahun 661 M, dan terus berlanjut pada masa kekuasaan dinasti ‘Abbâsiyyah
di Bagdad (masa hidup al-Mâwardiy), bahkan seterusnya hingga sekarang.
235
Perluasan kultural terhadap "materi" Alquran dan sunah sebagaimana diperankan
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, berarti peningkatan dalam bidang penulisan dan
bacaan terhadap kedua materi sumber itu. Dan sesungguhnya
al-’Ahkâm al-
Shulthâniyyah sebagai program penulisan dan bacaan dalam konteks perluasan
kultural, adalah medium yang urgen bagi penguasaan pengetahuan dan kekuasaan
sekaligus. Al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah benar-benar telah memerankan perluasan
bidang kultural dengan ciri-ciri itu.
Ditulis dan dibakukannya Alquran dan sunah telah memungkinkan semua
orang memperolehnya dalam bentuk teks yang terbaca, dan memungkinkan juga
bagi kelas terpelajar seperti al-Mâwardiy untuk memperluas dan menjadikannya
sebagai alat kekuatan yang "memaksa", karena kelas terpelajar itulah yang
mengawasi jalannya kekuasaan yang suci, yang dimaksud adalah pelaksanaan
masalah-masalah ibadah, ritus, dan upacara-upacara keagamaan, dan mengenakan
"jubah" kesucian terhadap kekuasaan politis atau mencabutnya dengan kriteria
yang sama. Maka seperti diketahui bahwa kekuasaan kemudian mengklaim
bersumber dari Alquran, sunah, ijmak, dan kitab-kitab lain yang bermacammacam yang ditulis dalam rangka memperluas jangkauannya. Dalam kitab-kitab
tersebut ditetapkan seluruh undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat
Islam dalam segala seginya.
Dengan mengatakan hal-hal di atas, penulis hanya ingin meletakkan
masalah-masalah tersebut di bawah pandangan antropologi terhadap fenomena
pemikiran pengetahuan dan kekuasaan yang disebut Islami. Maka seperti
diketahui bahwa pemikiran dan kekuasaan berdasarkan kitab-kitab tertulis inilah
236
yang menetapkan pandangan-pandangan, batasan-batasan, pembagian-pembagian,
dan sistem realisasinya terhadap masyarakat dengan medium domain fungsional
yang bekerja sangat efektif di antara kekuatan-kekuatan yang ada: negara, tradisi
keilmuan yang berkembang, peradaban elit (yaitu peradaban baku/resmi bagi
orang yang mengerti baca-tulis), dan ortodoksi keagamaan. Kekuatan sejarah
yang melahirkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, yang membentuknya, serta
memfungsikannya, jelas memperlihatkan kerja yang efektif operasi jalinan yang
erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Negara ‘Abbâsiyyah, Alquran dan sunah
yang tertulis, peradaban elit seperti yang dimiliki al-Mâwardiy, dan al-’Ahkâm alShulthâniyyah merupakan salah satu contoh medium domain fungsional operasi
antara pengetahuan dan kekuasaan itu.
Al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebenarnya merupakan salah satu bentuk
pemikiran teologi yang berada di bawah pandangan "teosentris": yaitu suatu
pemikiran yang ditujukan untuk menaikkan, meninggikan, dan mengingkari serta
menjauhkan bentuk kesejarahan dari segala simbol dasar Islam (Alquran, sunah,
dan ijmak). Al-Mâwardiy dan semua pemikir teologi Islam ortodoks telah
mengangkat kodifikasi tekstual dari simbol dasar Islam tersebut kepada martabat
al-Kitâb yang diwahyukan dan disucikan, kepada tahapan al-Kitâb yang tertutup
yang menyerupai jejak yang tidak bisa ditelusuri kembali, dan menjadi tempat
rujukan yang memaksa bagi setiap wacana yang ingin mendalami dan menyelami
firman Allah. Keinginan mereka untuk menaikkan dan meninggikan fenomena alKitâb yang "biasa" menjadi martabat al-Kitâb yang disucikan tersebut telah
sampai pada tingkatan yang keras dan kaku, serta mengalami proses pengingkaran
237
dan penggelapan. Mereka menetapkan bahwa mushaf yang memuat keseluruhan
ayat-ayat Alquran juga memiliki sifat Al-Qur’ân (Kalam Allah) yang bukan
makhluk.
Sesungguhnya proses pengingkaran dan penggelapan terhadap realitas
Alquran, sunah, dan ijmak, yang bersifat lahiriah ini ditujukan kepada maksud
tunggal, yaitu: memberikan model-model ideal yang agung, abadi dan total bagi
imajinasi, serta menanggalkan sifat kesejarahannya yang terbentuk dan
berlangsung di tengah tindakan-tindakan manusia dan kehidupan masyarakat yang
dinamis. Maka teologi kemudian berkembang di bawah proses penggelapan dan
pengingkaran dengan sifatnya yang kuat untuk menakutkan jiwa, membebani
kemampuan intelektual, dan kekuatan untuk membangkitkan kenangan terhadap
kepribadian-kepribadian simbolis yang besar bagi sejarah penyalamatan di
akhirat. Teologi kemudian dihidup-hidupkan dan direnungkan dengan sifatnya
sebagai mahkota atau sebagai sesuatu yang menjadi Kehendak Allah atas sejarah
bumi.
238
BAB V
KESIMPULAN
Pada situasi sejarah ketika Alquran berfungsi sebagai salah satu ikon normatif
yang ingin mengatur manusia melalui pribadi Muhammad sebagai Rasul Allah,
manusia di luar dirinya tidak membutuhkan konsep dan metodologi yang rumit
untuk memahami pesan-pesan dan tindakan-tindakannya. Wacana kenabian itu
hanya membutuhkan satu instrumen agar dia dapat berfungsi : yaitu keimanan.
Wacana kenabian itu, esensinya adalah berupa perkataan (bahasa) dan
perilaku Rasul, yang pada konteks waktu itu, lebih banyak terekam dalam
ingatan/kesaksian langsung para pengikut terdekatnya daripada dalam bentuk
tulisan, karena yang terakhir ini memang belum membudaya atau belum begitu
urgen dibutuhkan, bahkan sampai beberapa tahun setelah Rasul wafat.
Praktek kehidupan kaum Muslimin pada umumnya selama ditinggalkan
Nabi dituntun oleh keimanan dan ingatan mereka kepada perkataan dan contoh
aktual dari Nabi pada masa lalu yang berjalan berkelindan dengan kepentingan
hidup sehari-hari dan bahkan kepentingan kekuasaan, sampai kemudian muncul
tuntutan sejarah untuk mengumpulkan (kodifikasi) Alquran. Pembukuan Alquran
yang pada prakteknya merupakan proyek resmi negara/penguasa, tidak bersih dari
pertentangan dan kontroversi. Negara/kekuasaan benar-benar telah memainkan
peran menentukan (memaksa) terbentuknya satu korpus resmi Alquran, dan
menyingkirkan versi-versi lain pesaingnya.
239
Di sisi lain, contoh aktual Nabi yang menjadi praktek hidup sebagian
Sahabat terus ditransmisikan baik secara verbal di lingkungan terdidik tertentu di
masjid-masjid sebagai pusat pengajaran, maupun berupa praktek-praktek ritus dan
klaim-klaim kesalehan dari orang-orang atau kelompok yang memiliki motif dan
kepentingan-kepentingan
politik
di
berbagai
wilayah
kekuasaan
Islam.
Perkembangan yang tak terhindarkan adalah meluasnya praktek-praktek
kehidupan yang secara bebas mengklaim sebagai yang berdasar pada apa yang
dikatakan/dipraktekkan oleh Nabi. Sejarah (wacana) kenabian kemudian
menjelma menjadi wacana kesalehan berdasarkan klaim-klaim kelompok yang
saling bersaing sebagai yang paling saleh, paling sesuai, paling otentik, dan paling
benar, dan karena itu paling berhak berkuasa.
Sebagian orang yang terpelajar kemudian berupaya mengumpulkan dan
memverifikasi informasi-informasi sejarah (wacana) kenabian dalam rangka
mencari otentisitas dan memenuhi kebutuhan untuk mensistematisasi ajaranajaran Islam. Maka lahirlah korpus-korpus kedua setelah Alquran yang kemudian
disebut hadis atau sunah, enam korpus diantaranya dianggap paling memiliki
otoritas sejak awal pengkodivikasiannya sampai dengan sekarang. Maka Alquran
yang telah ditulis dalam satu mushaf bersama keenam kitab hadis sahih yang
terkumpul, benar-benar difungsikan sebagai kitab-kitab kanonik, dari mana
pemikiran dan praktek Islam harus bersumber.
Sejak wacana kenabian yang telah berhasil dibukukan itulah, ia kemudian
melahirkan jutaan korpus pemikiran Islam hingga sekarang. Maka hakikat
pemikiran Islam adalah merupakan penafsiran-penafsiran orang-orang Islam yang
240
terdidik terhadap wacana kenabian yang telah dibukukan/ditulis secara baku
dalam sejumlah kitab kanonik tersebut. Dan salah satu problem pelik bagi orangorang Islam adalah problem penafsiran dan penakwilan terhadap nas-nas wahyu
serta pengambilan (istinbâth) hukum-hukum syariat (hukum-hukum turunan
wacana kenabian). Kepelikan itu muncul berbarengan dengan terjadinya benturanbenturan sosiologis dan politis yang bermacam-macam serta berhubungan dengan
struktur pengetahuan dan bentuk kemsyarakatan bagi pengetahuan dan perjuangan
ideologis. Akibatnya, karakter pemikiran Islam dimaksudkan oleh masing-masing
kelompok yang saling bersaing sebagai wujud Islam yang benar dan murni yang
sesuai dengan pemahaman agama yang "benar" untuk memerangi bidah-bidah,
menolak orang-orang yang dianggap mengikuti hawa nafsu, membatalkan pahampaham yang dianggap sesat dan menyesatkan, serta mengucilkan dan
menundukkan semua penyelewengan dari jalan yang lurus, kebenaran yang nyata,
dan kelompok yang benar.
Pemikiran Islam sebagai turunan wacana kenabian tersebut membimbing
akal pada fungsinya yang mendasar dan mulia. Hal ini seperti terlihat dalam hadis
yang sering dikutip dalam permulaan kitab-kitab fikih: “Siapapun orang, yang
Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikannya
kepahaman pada (ajaran) agama.”377 Adapun ajaran agama yang dikaji dalam
kitab-kitab pemikiran Islam menyangkut pemahaman yang rumit yang meliputi
makna-makna dan dimensi-dimensi esensial (jauhariyyah) dari Allah atau Maujud
Pertama sampai kepada hakikat realitas, serta hal-hal yang menjadi dambaan
377
Hadis riwayat Muslim dari ’Abî Bakr bin ’Abî Syaibah dalam bab "al-Nahyi ‘ani al-Mas’alah",
hadis ke- 1719 edisi Mawqi‘ al-’Islâm, tt.
241
setiap manusia seperti nasib dan keadilan, juga hal-hal yang menjadi tujuan setiap
pemikiran terhadap konklusi-konklusi yang benar yang tidak mendatangkan
keraguan (metode yang memastikan orang dapat beragama secara benar).
Tetapi, kebenaran (ajaran agama) kemudian menjadi problem yang selalu
diperdebatkan bukan saja mengenai esensinya melainkan juga bagaimana cara
yang benar untuk mendapatkannya. Problematisasi kebenaran tersebut sejak masa
Sahabat (generasi pendiri/pertama) terpusat pada masalah status kebenaran akal
dan kebenaran wahyu serta hubungan antara akal dan wahyu378. Pada generasi
kedua (tabi’în: para pengikut Sahabat) pertentangan tersebut mengkristal antara
kelompok Muktazilah yang mengatakan tentang kemakhlukan Alquran dengan
Ahlu Sunah Waljamaah, terutama pengikut mazhab al-Hanbaliy dan al-’Asy‘ariy
yang mengatakan bahwa Alquran bukan makhluk dan wajib bagi akal untuk
membacanya tanpa mempertanyakan (kebenaran maknanya/bilâ kaifa, karena
memang sudah pasti kebenarannya), dan menerimanya sebagaimana ia
diturunkan. Pertentangan antara dua aliran pemikiran Islam tersebut telah menguat
dan membentuk dua martabat dan paham, dan dua bentuk ontologi yang berbeda
bagi akal, yang bercampur-baur dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan.
Terkakait dengan pertentangan-pertentangan antar aliran pemikiran Islam,
fenomena yang tak terpikirkan sampai sekarang adalah kenyataan bahwa akal
pada hakikatnya merupakan sumber dan subyek bagi semua yang diungkapkan
manusia dan menggunakannya dengan menggunakan bahasa (Arab) tertentu, atau
menggunakan sistem semiologi, oleh karena setiap pemikir/penulis (harus) tunduk
378
Lihat, Syah Wâliyullâh, Hujjatullâh al-Bâlibghah, Dâr al-Ma’rifah, Beirut, vol. 1, hal. 148.
242
kepada semua faktor kebahasaan, budaya, politis, dan sosiologis pada semua
lingkungan (environment) yang beraneka macam dan pada seluruh periode
kesejarahan yang kesemuanya mewarnai pandangan-pandangan, dan bahkan
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari aliran-aliran pemikiran atau
mazhab keagamaan. Kebenaran yang diklaim oleh masing-masing aliran pun
sebenarnya tunduk kepada kesejarahan, karena aspek-aspek dan fungsinya
berubah dengan berubahnya pandangan akal kepadanya. Demikian juga akal
berubah perannya dengan perubahan hasil-hasil dan makna-makna yang menjadi
dasar dan penghubung untuk terus melakukan proses pencarian kebenaran dengan
cara yang benar demi kebenaran tersebut.
Oleh karena itu, apa yang kemudian dibutuhkan terhadap pemikiran Islam
sebagi hasil turunan dari wacana kenabian seperti al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah
adalah melihat faktor-faktor sejarah yang melahirkannya, syarat-syarat ilmiahnya,
dan tujuan-tujuan politisnya. Pemikiran Islam adalah sebagaimana pemikiran
kesejarahan lainnya, seperti pemikiran Marxis misalnya. Pemikiran-pemikiran itu
memperoleh suatu jenis kemampuan karena ada hukum-hukum, dasar-dasar,
metode-metode dan postulat-postulat yang sangat penting bagi pijakan akal untuk
menghasilkan, menetapkan, dan menerapkannya.
A. Konteks Historis Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dan Implikasinya
Meskipun Al-Mâwardiy tidak mengatakan secara jelas bahwa al-’Ahkâm alShulthâniyyah ditulisnya untuk mewakili ortodoksi kelompok Suni dalam konteks
pertentangannya dengan ortodoksi-ortodoksi yang lain, tetapi analisis di atas telah
243
menunjukkan bahwa teori etika politik Al-Mâwardiy itu merupakan manifestasi
dari pola pemikiran ortodoksi Suni yang bersaing dengan ortodoksi-ortodoksi
selainnya: Syî‘ah, Muktazilah, dan Khawârij, terkait dengan isu-isu kekuasaan.
Demikian juga, terori politik Al-Mâwardiy yang merepresentasikan pandangan
ortodoksi Suni itu memiliki jangkauan-jangkauan praktis dan strategis terhadap
kekuasaan.
Program mihnah yang dilancarkan Khalifah al-Ma’mûn dengan dukungan
para elit intelektual Muktazilah, program Syiinisasi yang dilancarkan kaum Syî‘ah
di bawah perlindungan sultan/amir Banî Buwaihiy, serta munculnya "Dekrit
Qâdiriyyah" yang menonjolkan pengaruh Suni dalam praktek pengelolaan
pemerintahan maupun kemasyarakatan; adalah domain kesejarahan yang
membuktikan adanya pertarungan politis dan ideologis yang kuat di antara
kelompok-kelompok tersebut, bahkan peristiwa-peristiwa tersebut merupakan
kristalisasinya.
Proyek intelektual Al-Mâwardiy melalui penulisan al-’Ahkâm alShulthâniyyah tampak sebagai bentuk mental agamis yang suci, menghimpun
semua bentuk ke-Islaman bagi dirinya sehingga membentuk "ortodoksi murni"
yang selamat
dan
menyelamatkan, dengan pengungkapan kepercayaan-
kepercayaan dogmatis yang bersumber kepada kepercayaan dan praktek hidup
manusia-manusia besar, sehingga seperti layak disebut sebagai landasan bagi
bangunan kekuasaan yang Islami, yang kokoh dan benar. Padahal pada
hakikatnya, pemikiran Al-Mâwardiy yang Suni beserta pemikiran-pemikiran
sektarian lainnya merupakan “ortodoksi yang menyeleweng” yang justru menjadi
244
sandaran kekuasaan bagi tujuan-tujuan politiknya, karena agama dan agamawan
(ulama) telah dikuasai oleh kekuasaan politik sejak permulaan kekuasaan dinasti
Mu‘âwiyah, dan penguasaan resmi ini terus berlanjut sampai masa dinasti
‘Abbâsiyyah. Mereka, para elit penguasa telah menguasai dan memonopoli agama
untuk membentuk ideologi yang menyeluruh untuk mendapatkan yustfifikasi
sakralitas kekuasaan.
Dalam kondisi persaingan mental dan intelektual dari masing-masing
kelompok Islam untuk membentuk dan mengokohkan ortodoksinya; fungsi
penampakannya dalam sejarah masyarakat sangat ditentukan oleh kemauan politik
para penguasa. Demikian juga, kekuatan politik para penguasa, selain dia
membutuhkan modal materi yang besar untuk mencukupi kebutuhan politisnya,
dia sangat membutuhkan dasar legitimasi bagi kekuasaannya. Dan, tidak ada dasar
legitimasi yang dianggap lebih kuat dan lebih suci daripada agama. Seperti telah
ditunjukkan di atas, Al-Mâwardiy menulis al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dalam
konteks situasi persaingan antar ortodoksi tersebut, demi mengokohkan versi
ortodoksinya. Pada saat yang sama pembentukannya sangat dipengaruhi oleh
kemauan politik khalifah dinasti ’Abbâsiyyah maupun para amir dinasti Buwaihiy
yang sama-sama menginginkan legitimasi bagi kekuasaannya.
Kelahiran al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dalam konteks sosial-historis
tersebut, jangkauan-jangkauan sosial-politisnya, dan fungsinya dalam struktur
wacana kekuasaan, memiliki implikasi-implikasi ideologis yang mendalam, yaitu:
1. melanggengkan (status quo) sistem kekuasaan monarki dan sumber
legitimasinya;
245
2. merupakan bentuk wacana tandingan terhadap wacana kekuasaan
kelompok Syî‘ah dan khawârij;
3. menyembunyikan fakta-fakta historis politik yang penuh intrik dan
kekerasan melalui penampakan wacana kekuasaan secara normatif dan
ideal;
4. mengandung bias ketidakadilan sosial;
5. mereduksi sejarah kenabian (Islam) sebagai sejarah politik dan
kekuasaan.
Implikasi-implikasi ideologis tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat
sampai masa sekarang, terutama bagi kelompok-kelompok politik yang berjuang
untuk meraih kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaannya; atas nama
menegakkan "Islam".
B. Syarat-syarat Ilmiah (Metodologi) Al-’Ahkâm Al-Shulthâniyyah dan
Implikasinya
Telolog seperti Al-Mâwardiy dan para ahli hukum syariat lainnya, terbiasa untuk
memandang agama, negara, dan dunia dari "atas", yakni bertolak dari ajaranajaran dasar ideal dan ketetapan wahyu, baik dari sisi Allah, Pemberi Hukum
Pertama, maupun dari kalangan yang memegang kekuasaan (penguasa ataupun
ulama). Kemudian dari ajaran-ajaran ideal tersebut mereka menghasilkan hukumhukum cabang yang terkait dengan dasar-dasar keilmuan atau undang-undang
pensyariatan. Maka mereka tidak mempertanyakan tentang dampak-dampak dari
sikap pemahaman dan istinbâth (proses konklusi hukum) ini terhadap
246
pembentukan manusia sebagai individu, warga negara, dan person, tetapi mereka
merasa cukup dengan keharusan akidah (keyakinan) bahwa ajaran-ajaran dasar
tersebut sesuai, benar, sempurna, dan bersifat ketuhanan; dan bahwa istinbâth
tersebut, apapun aspek-aspek kesejarahan dan perangkat-perangkat intelektual
yang digunakan serta pola-pola peradabannya, benar dan sesuai bagi seluruh masa
dan tempat. Demikianlah, metodologi istinbâth yang seolah-olah ilmiah justru
menjadi sarana yang efektif bagi pengoperasian ideologi.
Hukum yang sejatinya merupakan produk pemikiran manusia dengan
segala aspek kesejarahannya telah disucikan; dianggap tanpa kepentingankepentingan individual maupun kelompok, dan tampak seperti hanya bertendensi
akhirat. Tetapi seperti telah ditunjukkan, metodologi istinbâth Al-Mâwardiy dan
hukum yang dihasilkannya sesungguhnya memiliki kepentingan ideologi
kelompok Suni vis à vis kelompok Syî‘ah, Muktazilah, dan Khawârij.
Metodologi istinbâth bukan saja memiliki implikasi ideologis melainkan
juga menimbulkan dampak pembatasan yang serius terhadap dinamika pemikiran
mengenai etika politik Islam. Hak-hak manusia baik sebagai individu maupun
sebagai warga negara menjadi problem yang tak terpikirkan, dan sebaliknya,
metodologi istinbâth sibuk melindungi otoritas dan dominasi negara dengan jubah
kesuciannya. Metodologi istinbâth mengkonsepsikan negara yang terbentuk
secara niscaya sebagai "amanat langit" yang suci dan kokoh; dan bukan sebagai
lembaga wewenang yang kewenangannya merupakan "mandat bumi" dari
individu-individu manusia yang berdaulat yang secara sadar menyerahkan
sebagian hak-hak dan kewenangan mereka kepada penguasa yang mereka
247
kehendaki. Maka, metodologi istinbâth sungguh-sungguh berperan meratakan
jalan bagi dominasi negara terhadap rakyat dan menuntut kepatuhannya, bahkan
menghilangkan hak-hak normatifnya hingga pada tataran wacana. Metodologi
istinbâth benar-benar menempatkan rakyat dalam posisi yang sangat lemah dan
awam, dan oleh karena itu, rakyat harus bungkam dan menurut kepada kehendak
hukum yang dibuat oleh penguasa: umara dan ulama yang berpadu.
248
BAB VI
PENUTUP
"Penyimpangan ideologis terjadi dalam kerangka pemikiran Islam
setiap waktu, bahwa seorang penulis lebih kurang hanya
mengumandangkan sebuah mazhab, sebuah komunitas atau sebuah
tradisi secara tepat, mentransformasi wacana Qurani dari sistem
kognitif yang terbuka kepada sistem kognitif yang tertutup".379
Mohammed Arkoun
Kekuasaan, di manapun, selalu membutuhkan pendasaran legitimasi bagi
eksistensinya, prakteknya, maupun tujuan-tujuannya, bahkan kekuasaan seorang
nabi terhadap umatnya.
Dalam konteks umat Islam, sepeninggal Nabi Muhammad krisis yang
pertama kali dialami adalah krisis politik yang berujung pada krisis legitimasi
bagi kepemimpinan penggantinya. Kedua krisis ini pada taraf tertentu dapat
diatasi dengan konsensus-konsensus politik yang terjadi di lingkungan elit
Sahabat. Namun sejarah membuktikan bahwa tidak adanya petunjuk yang jelas
tentang pemimpin pengganti Nabi dan sistem kepemimpinan yang pasti yang
dapat menjamin legitimasinya adalah sumber utama pertentangan antar kelompok
yang
berkepentingan
terhadap
kekuasaan
dan
perbedaan
klaim-klaim
legitimasinya. Bahkan, konsensus-konsensus politik yang tercipta sejak awal tidak
mampu bertahan dalam waktu yang lama, karena pada akhirnya seluruh dinamika
politik lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tentara dan ekstra konsensus.
379
Mohammed Arkoun, Rethinking Islam Today, Washington, D.C.: Center for Contemporary
Arab Studies, Georgetown University, Ocassional Papers Series, 1987, h. 94
249
Meski demikian, orang atau kelompok manapun yang memegang kendali politik
Islam, selain ia membutuhkan dukungan tentara, ia juga membutuhkan landasan
legitimasi, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat konseptual. Dalam
situasi semacam itu, penyusunan konsep sistem kekuasaan menjadi hal yang
sangat penting dilakukan. Dan dalam setiap konsep mengenai sistem kekuasaan
yang disusun dan dibangun, legitimasi merupakan persoalan inti yang dibahas,
baik pada tataran eksistensi kekuasaan, prakteknya, dan tujuan-tujuannya.
Dengan mengambil al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, penelitian ini
dilakukan berdasarkan asumsi teoretis bahwa usaha penyusunan konsep sistem
kekuasaan Islam yang dilakukan al-Mâwardiy memiliki keterkaitan kuat secara
niscaya dengan sejarah, memakai sistem berpikir tertentu, dan pada saat yang
sama, rentan terhadap kepentingan ideologi. Maka, penelitian diarahkan untuk
menjawab tiga pertanyaan: pertama, soal bagaimana konteks sosial, politik, dan
budaya melahirkan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai konsep sistem kekuasaan
Islam. Kedua, soal bagaimana kaidah dan sistem berpikir tertentu membentuk al’Ahkâm al-Shulthâniyyah? Ketiga, bagaimana kedua aspek masalah itu
mengandung implikasi-implikasi yang bersifat ideologis?
Atas dasar asumsi tersebut, penelitian kepustakaan kemudian
dijalankan, dengan selalu mengingat satu "postulat": bahwa dalam praktek
penyusunan suatu konsep (seperti penyusunan konsep kekuasaan Islam yang
dilakukan oleh Al-Mâwardiy), terjadi fenomena yang bersifat paradoksal. Dalam
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, fenomena paradoksal dipahami sebagai terjadinya
sesuatu yang sebenarnya ingin dihindari al-Mâwardiy dalam menyusun konsep-
250
konsepnya,
berupa
keterbatasan-keterbatasan
historis,
metodologis,
dan
kepentingan-kepentingan ideologis, sehingga konsep-konsepnya itu diharapakan
dapat bersifat ideal dan obyektif. Namun, harapan itu justru tidak akan pernah
tercapai, karena al-Mâwardiy secara pasti dibatasi oleh konteks sejarah,
metodologi dan ideologi. Meskipun keterbatasan-keterbatasan tersebut selalu
ingin dihindari oleh setiap pemikir (seperti al-Mâwardiy) dalam rangka
kesempurnaan pemikirannya, tetapi sesungguhnya keterbatasan-keterbatasan yang
menunjukkan ketidaksempurnaannya adalah hal yang niscaya, dan hal itu sangat
tidak dapat dihindari. Maka dengan asumsi teoretis dan postulat tersebut di atas;
konteks historis, metodologi, dan ideologi al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah kemudian
menjadi tinjauan utama dalam penelitian.
Penelitian
ini
berhasil
menunjukkan
bahwa
al-’Ahkâm
al-
Shulthâniyyah dilahirkan oleh konteks sosial, politik, dan budaya yang
melingkupinya. Secara singkat, konteks historis yang melahirkan al-’Ahkâm alShulthâniyyah yaitu: sistem kepercayaan, pemikiran, dan tradisi-tradisi yang
hidup dan dihidupi oleh kelompok Muslim Suni melalui perantaraan bahasa Arab
di dalam ruang politik dan budaya Islam abad IV H/X M yang penuh intrik dan
gejolak persaingan antar aliran Islam yang sekaligus faksi politik.
Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa al-’Ahkâm alShulthâniyyah yang dilahirkan oleh konteks historis tersebut,
mengandung
keterbatasan-keterbatasan historis (historisitas), baik yang mengenai substansinya,
metodologinya, maupun fungsinya.
251
Konteks historis dan historisitas adalah dua aspek yang tidak pernah
dikatakan oleh al-Mâwardiy di dalam al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, juga secara
umum oleh setiap pemikir-teolog di dalam buku-bukunya. Hal ini merupakan
gejala realitas tersendiri, entah disengaja atau tidak. Dalam kasus al-Mâwardiy
dan al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, fenomena itu dapat diajukan sebagian alasan
pembenarnya, yaitu karena memenuhi tuntutan praktis sebagai buku undangundang pegangan bagi siapa saja, terutama khalifah atau para amirnya; seperti
dikatakan sendiri oleh al-Mâwardiy.
Al-Mâwardiy memang tidak harus menjelaskan konteks historis dan
historisitas karyanya: al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Masalah itu merupakan
sebagian "tantangan" bagi pembaca al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah, dan (mungkin)
justru di dalam masalah itulah terletak desire-nya. Tetapi, alih-alih orang
membaca al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah dengan secara kritis melihat aspek konteks
historis dan bahkan historisitasnya, sekarang kitab ini lebih cenderung dibaca
sebagai pemandu imajinasi sebagian kelompok kaum Muslimin tentang "hakikat"
kekuasaan yang Islami. Kecenderungan demikian ini masih belum seberapa,
karena pencarian identitas adalah hak setiap orang, termasuk pencarian identitas
kekuasaan Islam oleh orang-orang Muslim dengan "mengaca" masa lalu Islam,
sementara al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah memang bagian dari masa lalu Islam dan
telah berperan membentuk identitasnya pada abad IV H/X M. Tetapi, bagaimana
dengan kecenderungan lain, seperti kecenderungan orang-orang yang hanya
mengambil konsep-konsep tertentu yang diwariskan oleh al-’Ahkâm alShulthâniyyah – diakui atau tidak diakui – tanpa pemahaman yang memadai
252
terhadap konsep-konsep itu – disengaja atau tidak disengaja – dan
menampilkannya hanya sebagai simbol-simbol "politik yang Islami"? Bagaimana
dengan orang-orang yang mengusung konsep "khilafah" sebagai jargon "politik
yang Islami", bahkan konsep itu dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi semua
problem umat Islam dewasa ini? Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, penulis
tidak ragu-ragu menyatakan bahwa kecenderungan-kecenderungan tertanda-tanya
itu tidak lebih dari tindakan-tindakan pembenaran mereka terhadap tujuan-tujuan
politik jangka pendek dan sempit, meskipun mereka mengklaim sebagai sesuatu
yang hakiki, yang murni, dan demi ‘izzu al-Islâm wa al-Muslmîn. Omong
kosong!!! Tidak lain, itu semua adalah ideologi "murahan" yang paling nyata.
Kecenderungan-kecenderungan tersebut, seperti yang ditampilkan oleh kelompokkelompok "Islam politis" dewasa ini, adalah suatu realitas tersendiri, suatu (efek?)
yang tak terduga atau bahkan tak disengaja oleh pemikir seperti al-Mâwardiy dari
karyanya: al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah. Dan orang tetap saja boleh mengajukan
pertanyaan: apa salahnya memanfaatkan
al-’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai
ideologi, kalau memang toh ia juga merupakan sebuah bentuk ideologi? Penulis
menyadari, masalah ideologi tidak terkait dengan persoalan "benar-salah" secara
"logis", tetapi lebih merupakan masalah yang terkait persoalan "menang-kalah"
secara politis, dan karena itu ideologi adalah suatu problem etis. Dengan
demikian, persoalan yang mendesak untuk dipikirkan dalam konteks Islam saat
sekarang ini adalah bukan pertanyaan: apakah ideologi Islam itu? Atau,
bagaimana ideologi Islam (seharusnya) agar dapat "menang" dalam arena politis?
Tetapi, bagaimana (seharusnya) Islam terus dipikirkan dan terus diperjuangkan
253
dengan selalu mempertimbangkan peroblem-problem etis kemanusiaan secara
menyeluruh dalam konteks sekarang ini? Karena eksistensi Islam tidak akan
bergantung banyak kepada seberapa luas wilayah politik yang dikuasainya, atau
kepada seberapa banyak sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, melainkan
lebih banyak bergantung kepada seberapa mampu Islam tampil atau ditampilkan
sebagai salah satu kekuatan moral dunia untuk memecahkan problem-problem etis
kemanusiaannya. Eksistensi Islam lebih ditentukan oleh sejauh mana ia bergerak
atau digerakkan untuk "memanusiakan manusia" atau nguwongake wong. Yang
terakhir ini, benar-benar merupakan misi utama dan telah dijalankan oleh
Muhammad sebagai Rasulullah, bukan? Dia, salah seorang yang dengan sikap
penuh rendah hati menyuarakan: "Tidak lain, sesungguhnya aku diutus hanya
untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq",380 bukan? Dan Allah pun telah
memujinya dengan firman: "Dan sungguh engkau [Muhammad, pen.] memiliki
akhlak-akhlak yang agung",381 bukan? Karena, selain pembinaan moralitas
manusia adalah misi utama Muhammad dalam rangka meningkatkan kemuliaan
harkat kemakhlukan mereka, dia melaksanakan misi itu dengan menghormati
martabat kemanusiaan dan dengan moralitas tertinggi, bukan? Dan, karena dia
memulai misinya itu dari "perbaikan" bukannya "membaikkan" terhadap dirinya
sendiri, bukan?
Akhir kata, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai upaya penurunan
derajat kehormatan Al-Mâwardiy sebagai pemikir besar Muslim yang terakui,
demikian juga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melolosi kewibawaan al380
’Ibnu Katsîr, Tafsîr al-Qur'
ân al-‘Azhîm, Dâru Thaibah li al-Nasyri wa al-Tauzî‘, 1420/1999,
vol. 8, h. 190.
381
Q.S. Al-Qalam: 4
254
’Ahkâm al-Shulthâniyyah sebagai salah satu teks Islam yang agung, melainkan
sekedar
menunjukkan
nuansa
kesejarahan
dan
keterbatasan-keterbatasan
jangkauannya yang nyata dan manusiawi. "Kejujuran" melihat al-’Ahkâm alShulthâniyyah secara wajar-manusiawi ini bukan untuk menilainya secara negatif
atau melemparkannya ke dalam "keranjang sampah" peradaban, melainkan justru
untuk "mengelap debu-debu" yang menempelinya selama ini, ketika sejak akhir
abad IV H/X M ia dilahirkan dan hingga kini ia terselip di atas rak buku
perpustakaan-perpustakaan, dan masih akan tetap di sana.
255
DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar, Usman dkk., “Negara dan Pemerintah: Studi Komparatif Pemikiran
Al-Mâwardiy dan ’Ibn al-Farrâ’”, Semarang: Balai Penelitian IAIN
Walisongo, 1994/5
Al-‘Araby, Abû Bakr, Al-‘Awâshim min al-Qawâshim, Arab Saudi: Kementerian
Urusan Islam, 1419 H.
Al-‘Asqalâniy, Fath al-Bâry, Mesir: Maktabah Musthafâ al-Bâbiy al-Halabiy,
1963
Al-’Asy‘ariy, Maqâlât al-’Islâmiyyîn wa ’Ikhtilâf al-Mushallîn, ’Istanbul:
Thab‘ah ’Istanbul, 1930
Al-Baghdâdiy, ‘Abd al-Qâhir,’Ushûl al-Dîn, ’Istanbul: Thab‘ah ’Istanbul, 1928
Al-Baghdâdiy, ’Abû Bakr al-Khathîb, Târîkh al-Baghdâd, Bairut: Dâr al-Turâts
al-‘Arabiy, 1942
Al-Farrâ’, ’Abû Ya‘lâ, Al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, Bairut: Dâr al-Fikr, 1994/1414
Al-Ghazâliy, Al-’Iqtishâd wa al-’I‘tiqâd, Mesir: al-Mathba‘ah al-Mahmûdiyyah,
tt.
Al-Hamwiy, Yâqût, Mu'
jam al-’Adibbâ’, Mauqi‘u al-Warrâq, tt.
Al-Hamwiy, Târîkh al-Buldân, Mesir: Maktabah al-Khanjiy, 1906 M.
Al-Jâhizh, Rasâ'
il al-Jâhizh, Kairo: Maktabat al-Khanji, 1968
Al-Jâhizh, Kitâb al-Tâj fi ’Akhlâq al-Mulûk, Bairut: Al-Syarîkah al-Lubnâniyyah
li al-Kitâb, tt.
Al-Mâwardiy, al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah, Bairut: Dâr al-Fikr, tt
256
Al-Mâwardiy, ’Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, Bairut: Dâr al-Fikr, 1415 H./1995 M
Al-Mâwardiy, Al-Nukat wa al-‘Uyûn, Mauqi‘u al-Tafâsir, tt.
Al-Mâwardiy, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,
Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurdin (ed.), Jakarta: Gema
Insani Press, 2000
Al-Mas‘ûdiy, Murûj al-Dzahab [Meadows of Gold], Bairut: Dâr al-Ma‘rifah, 1982
Al-Munqiry, ’Ibnu Muzâhim, Waq‘at Shiffîn, ’Abdu al-Salâm Muhammad Hârun
(ed.), al-Muassasat al-‘Arabiyyât al-Hadîtsât, 1382 H.
Al-Muqaffâ, ’Ibnu, Risâlah fi al-Shahâbah, Jamharat al-Rasâ’il al-‘Arabiy, tt.
Al-Qur’ân al-Karîm
Al-Syahrastâniy, Nihâyat al-’Iqdâm fî ‘Ilm al-Kalâm, Aksapurd: Thab‘ah A
Juyyûm, 1943
Al-Syahrastâniy, Al-Milal wa al-Nihal, Bairut: Dâr al-Sa‘b, 1986
Al-Rais, Dhiyâ’u al-Dîn, Al-Nadzariyyât al-Siyâsiyyât al-’Islâmiyyâh, Kairo: Dâr
al-Turâts, 1979
Al-Tanûkhiy, ’Abû al-Mahâsin, Târîkh al-‘Ulamâ’i al-Nahwiyyîn, Maiqi‘u alWarrâq, tt.
Al-Thabariy, [’Abû Ja‘far Muhammad], Târîkh al-’Umam wa al-Mulûk [History
of Umams and Kings] , Bairut: Dâr al-Fikr, 1979
An-Na’im, Abdullahi Ahmed, Dekonstruksi Syari’ah, Yogyakarta: LKIS, 1994
Arkoun, Mohammed, Rethinking Islam Today, Washington, D.C.: Center for
Contemporary Arab Studies, Georgetown University: Ocassional
Papers Series, 1987
257
Arkoun, Mohammed, dalam Johan Hendrik Meuleman (ed.), Nalar Islami dan
Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Jakarta: INIS,
1994
Arkoun, Mohammed, Pemikiran Arab, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
Arkoun, Mohammed, Membongkar Wacana Hegemonik, Jauhari dkk. (ed.),
Surabaya: Al Fikr, 1999
Barker, Chris, Cultural Studies: Theory and Practice, London, Thousand Oaks,
New Delhi: Sage Publications, 1999
Bertens, K., Filsafat Barat Kontemporer: Prancis, Jakarta: Gramedia, 2001
Budiman, Arief, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta:
Gramedia, 1996
Carter, April, Otoritas dan Demokrasi, Jakarta: Rajawali, 1985
Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai,
Jakarta: LP3ES, 1982
Achols, John M. dan Shadily, Hassan, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta:
Gramedia, 2000
Esposito, John L. (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World
New York: Oxford University Press, 1995
Foucault, Michel, Archaeology of Knowledge, Great Britain, London: Tavistock
Publications, 1972
Habermas, Jurgen, Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi, Jakarta: LP3ES, 1990
258
Hardiman, Francisco Budi, Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan
Kepentingan, Yogyakarta: Kanisius, 1990
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: gramedia, 2003
Hasjmy, A., Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1393 H/1973
Islamic Culture 11, No. 3, Juli 1937
Islamic Studies 4, No. 3, September 1965
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
Kan‘an, ’Ibnu, Târîkh al-Dawlah al-‘Abbâsiyyah: Khulâshah Târîkh ’Ibn Katsîr,
Bairut: Muassasat al-Ma‘ârif, 1419 H./1998 M.
Katsîr, ’Ibnu, Tafsîr al-Qur‘ân al-‘Azhîm, Bairut: Dâr al-Mufîd, 1403/1983
Katsîr, ’Ibnu, al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Mesir: Dâr ’Ihyâ al-Turâts al-‘Arabiy,
1408 H/1988 M.
Khaldûn, ’Ibn, Al-Muqaddimah, Kairo: al-Mathba‘ah al-’Azhariyyah, 1930
Khaldûn, ’Ibn, Muqaddimah [Târîkh ’Ibnu Khaldûn], Bairut: Dâr ’Ihyâ’i al-Turâts
al-‘Arabiy, 1978
Khan, Qamaruddin, Al-Mawardi'
s Theory of The State, Lahore: Islamic Book
Foundation, 1983
Kihâlah, ‘Umar Ridhâ, Mu‘jam al-Mu’allifîn, Bairut: Dâru ’Ihyâ’i al-Turâts al‘Arabiy, tt.
Kurzman, Charles (ed.), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer
Tentang Isu-isu Global, Jakarta: Paramadina, 2001
Lambton, Ann K. S., State and Government in Medieval Islam, Oxford: Oxford
University Press, 1981
259
Larrain, Jorge, Konsep Ideologi, Yogyakarta: LKPSM, 1996
Lee, Robert D., Overcoming Tradition and Modernity, Boulder, Colorado:
Westview Press, 1997
Lewis, Bernard, Islam in History: Ideas, People, and Events in Middle East,
Chicago & La Salle, Illionis: Open Court Publishing Company, 1993
Maarif, Syafii, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam
Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985
Majallat al-‘Arabiy 76, Maret 1965
Mannheim, Karl, Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik,
Yogyakarta: Kanisius, 1991
Mufid, Nur, "Lembaga-lembaga Politik Islam Menurut Al-Mâwardiy dalam
Kitabnya al-’Ahkâm al-Sulthâniyyah", Surabaya: Balai Penelitian
IAIN Sunan Ampel, 1998
Mulyati, Sri dkk., Islam & Development: A Politico-Religious Response,
Montreal: Permika Montreal & LPMI, 1997
Nafis, M., dkk., “Konfigurasi Keagamaan dalam Islam: Studi Tentang Sekte dan
Madzhab Abad XI di Daerah Baghdad dan Khurasan”, Semarang:
Balai Penelitian IAIN Walisongo, 1996
Peursen, C. A. Van, Strategi Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 1994
Qutaibah, ’Ibnu, Al-’Imâmah wa al-Siyâsah: Tarîkh al-Khulafâ’, Mesir:
Mu’assasat al-Halabiy wa al-Syarîkah, t.t.
Rabinow, Paul (ed.), Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault,
Yogyakarta: Jalasutra, 2002
260
Rahman, Fazlur, Islam, Bandung: Pustaka, 1994
RETORIK, Vol. 2, No. 4, Oktober 2003
Richard, D. S. (ed.), Islamic Civilization 950-1150, Oxford: Bruno Cassier, 1973
Said, Edward W., Orientalism, New York: Random House, 1979
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,
Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990
Sunardi, St., Islam dalam Lintasan Sejarah, kumpulan makalah belum diterbitkan
Sunardi, St., Semiotika Negativa, Yogyakarta: Kanal, 2002
Suprayogo, Imam, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001
Sou'
yb, Joesoef, Sejarah Daulat Abbasiah, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
The Scottish Journal of Religious Studies, Volume 6 (1), Musim Semi, 1985
Wahid, Marzuki, Latar Historis Narasi Ketatanegaraan Al-Mâwardiy-’Ibn AlFarrâ’: Bacaan “Seorang Rakyat” atas Dua Kitab Al-’Ahkâm AlSulthâniyyah, Cirebon: Jaringan Informasi & Lektur Islam (JILLI),
1997
Wâliyullâh, Syah, Hujatullâh al-Bâlighah, Bairut: Dâr al-Ma‘rifah, tt.
261
Lampiran 1 : Operasionalisasi Metodologi Al-Mâwardiy
No.
1
Kasus/masalah
Kewajiban
Imam
Metode Hukum
mengangkat •
didasarkan
logika
Produk Hukum
Kembali kepada Alquran yang menyatakan: “Hai Pengangkatan Imam untuk memimpin umat
orang-orang
yang
beriman patuhilah Allah, Islam
harus
didasarkan
patuhilah Rasul, dan patuhilah penguasa urusan di (agama), bukan logika akal.
akal atau ketentuan syariat?
antara kamu…..” (an-Nisâ’: 59).
•
Kembali kepada sabda Nabi yang menyatakan:
“Setelah masaku, kalian akan dipimpin oleh
berbagai macam pemimpin. Pemimpin yang baik
dan cakap akan memimpin dengan baik dan cakap
pula, sedangkan pemimpin yang buruk dan jahat
akan memimpin dengan buruk dan jahat pula.
Dengarkanlah dan patuhilah mereka selama
kebijakan mereka sejalan dengan kebenaran. Jika
mereka memimpin dengan baik maka kalian
mendapat
ketentaraman
hidup
dan
mereka
kepada syariat
262
mendapatkan pahala, dan jika mereka memimpin
dengan buruk maka kalian mendapatkan pahala
(dengan kesabaran kalian) sementara mereka
mendapatkan dosa.”
•
Kembali ke praktek awal pasca Nabi wafat, umat
Islam
langsung
mengangkat
Imam
sebagai
penggantinya.
•
Argumentasi
rasional
bahwa
rasio
hanya
mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak
melakukan kezaliman dan tidak memutuskan
hubungannya dengan orang lain. Rasio tidak
mendorong/mewajibkan pemimpin negara untuk
menjalankan tugas-tugas agama.
2
Bagaimana status kewajiban Dianalogikan (qiyâs) dengan hukum berjihad dan Status kewajibannya adalah fardu kifayah,
mengangkat
Imam
didasarkan pada syariat?
jika mencari ilmu pengetahuan.
yaitu
jika
ada
orang
yang
telah
melaksanakannya dari kalangan umat Islam,
maka kewajiban itu gugur atas umat Islam
seluruhnya.
263
3
Siapakah yang bertanggung Penalaran bebas dan praktek pemerintahan masa lalu.
Ada dua kelompok:
jawab atas proses suksesi
•
imamah?
Orang-orang yang mempunyai kualifikasi
wewenang untuk memilih Imam. Mereka
lazim disebut "dewan pemilih" atau
"dewan permusyawaratan" (’ahlu al-halli
wa al-‘aqdi, ’ahlu al-’ikhtiyâr, atau ’ahlu
al-syûrâ).
•
Orang-orang yang memiliki kualifikasi
untuk menjadi Imam, disebut ’ahlu al’imâmah).
Orang-orang selain dua kelompok kualifikasi
tersebut tidak berdosa dan tidak bersalah jika
terjadi kekosongan Imam.
4
Apa saja syarat kualifikasi Penalaran bebas.
•
Mempunyai kredibilitas-keadilan
"dewan pemilih" ?
•
Mempunyai pengetahuan
•
Mempunyai pendapat yang kuat dan
kebijaksanaan.
264
5
6
Apa saja syarat kualifikasi Penalaran bebas dan hadis Nabi tentang hak istimewa •
Mempunyai kredibilitas-keadilan
calon Imam?
•
Mempunyai pengetahuan
•
Mempunyai pancaindera yang lengkap
•
Tidak ada kecacatan pada anggota tubuh
•
Mempunyai Visi pemikiran yang baik
•
Berani
•
Dari suku Quraisy.
suku Quraisy.
Bagiamna mekanisme
Kembali kepada praktek-praktek pemerintahan pada •
Melalui prosedur pemilihan oleh "dewan
pengangkatan Imam?
masa empat khalifah yang pertama dan pendapat-
pemilih".
pendapat ahli fikih.
•
Melalui penyerahan mandat dari Imam
sebelumnya
7
8
Apakah
boleh
seseorang Kembali kepada pendapat-pendapat para ahli fikih.
Boleh, dan orang-orang yang berebut untuk
mencalonkan diri sebagai
menjadi Imam tidak kehilangan hak untuk
Imam?
memangku jabatan itu.
Bagaimana
penetapan
mekanisme Kembali kepada pendapat-pendapat para ahli fikih.
Imam
jika
terdapat calon-calon yang
mempunyai kualifikasi yang
•
Imam ditentukan berdasarkan undian
•
Imam deitentukan melalui pemungutan
suara "ewan pemilih".
265
seimbang?
9
Bagaimana
penyelesaian
mekanisme Kembali kepada pendapat para ahli fikih dan •
jika
Pendapat pertama mengatakan bahwa
terjadi penalaran bebas, dan sebagian lagi mengacu (melalui
orang yang berhak menjadi Imam secara
metode kias) kepada hukum pernikahan seorang
legal adalah orang yang dibaiat di
wanita dengan dua laki-laki yang berbeda.
wilayah tempat wafat Imam sebelumnya,
dualisme kepemimpinan?
karena orang yang berada di tempat
kedudukan Imam lebih berhak menjadi
"dewan pemilih" dan lebih berhak untuk
dipilih.
•
Pendapat
kedua
mengatakan
bahwa
keduanya harus melepaskan jabatan itu
dari dirinya dan menyerahkannya kepada
yang
paling
berkompeten
untuk
menciptakan keamanan dan menghindari
terjadinya perang saudara.
•
Pendapat
ketiga
mengatakan
dilakukan undian bagi keduanya.
harus
266
•
Pendapat keempat (mayoritas ahli fikih)
mengatakan bahwa jabatan itu jatuh
kepada orang yang lebih dahulu dibaiat
dan diberikan jabatan itu.
10
Bagaimana
•
legalitas Kembali kepada praktek pada masa Sahabat:
pengangkatan
Imam
1. Khalifah ’Abû Bakr telah menyerahkan
berdasarkan mandat Imam
mandat
jabatannya
sebelumnya?
Khaththâb.
kepada
’Umar
Muslimin
mengakui
legalitas
mengakui
legalitas
jabatan ’Umar.
bin •
2. Khalifah ’Umar menyerahkan mandat jabatan
Kaum
Kaum
Muslimin
sistem penyerahan wewenang itu kepada
"dewan permusyawaratan"
itu kepada “dewan permusyawaratan” yang
terdiri dari enam orang untuk memilih seorang
Imam.
11
Bagaimana jika penerima Mengacu kepada pendapat para ahli fikih.
mandat
(mandataris)
Ada tiga pendapat:
1.
Imam tidak boleh melakukan baiat
merupakan anak Imam atau
terhadap anak atau orang tuanya
orang tuanya sendiri?
sendiri
sebelum
musyawarah
ia
dengan
melakukan
"dewan
pemilih" dan mereka setuju atas
keputusan Imam itu.
267
2.
Imam boleh memberikan sendirian
mandat itu kepada anak atau orang
tuanya karena ia adalah pemimpin
umat
yang
dipatuhi.
perintahnya
Hukum
dengan
yang
kedudukan
mengalahkan
keberpihakan.
wajib
terkait
Imam
praduga
Dorongan
hatiny
tidak dinilai sebagai pengurang sifat
amanahnya dan tidak pula menjadi
penentangnya.
3.
Imam boleh memberikan mandat itu
sendirian terhadap orang tuanya,
namun ia tidak boleh melakukan itu
terhadap anaknya, karena tabiat
manusia cenderung untuk memihak
kepada anak lebih besar daripada
kecenderungannya
tuanya.
kepada
orang
268
12
Bagaimana
menyerahkan
jabatannya
Imam Kembali kepada hadis Nabi yang menceritakan bahwa Maka penyerahan mandat Imam kepada dua
jika
mandat Rasulullah SAW pernah memberi mandat pimpinan orang atau lebih secara bergantian boleh
kepada
dua pasukan dalam Perang Mu’tah kepada Zaid bin dilakukan.
orang atau lebih secara Hâritsah, dan berkata: “jika ia terbunuh, pimpinan
bergantian menjadi Imam?
akan dipegang Ja‘far bin ’Abî Thâlib. Jika ia
terbunuh, pimpinan akan dipegang oleh ’Ábdullâh bin
Ruwâhah. Jika ia juga terbunuh, pasukan Muslimin
dapat memilih sosok yang mereka suakai”.
13
Apa tugas utama Imam?
Penalaran bebas
Tugas-tugas utama Imam ada sepuluh hal:
1. Menjaga ajaran Agama agar tetap di
atas landasan pokok-pokoknya.
2. Memutuskan hukum bagi pihak-pihak
yang bersengketa/bertikai.
3. Menjaga keamanan masyarakat.
4. Menjalankan hukum pidana.
5. Menjaga perbatasan negara.
6. Berjihad
melawan
pihak
yang
menentang Islam.
7. Menarik fai’ dan memungut zakat.
269
8. Menentukan gaji tentara dan pegawai
serta ‘atha’ kepada rakyat.
9. Mengangkat
pejabat-pejabat
yang
terpercaya.
10. Melakukan
inspeksi
pekerjaan
pembantunya.
14
Kapan
Imam
dapat Penalaran bebas
Imam dapat dilengserkan, jika:
dilengserkan?
1. kredibilitas moral pribadinya rusak
2. terjadi
kecacatan
pada
anggota
tubuhnya yang menghalangi geraknya
3. tertawan musuh.
15
Bagaimana
legalitas Kembali kepada Alquran tentang Mûsâ yang ingin Imam boleh mengangkat menteri.
pengangkatan menteri?
mengangkat
Hârun:
“Dan
jadikanlah
untukku
pembantu dari keluargaku, (yaitu) Hârun, saudaraku,
teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah
dia sekutu dalam urusanku.” (Thâhâ: 29-32).
16
Apa
syarat
seorang menteri?
kualifikasi Penalaran bebas dan sebagian menyandarkan diri
pada hadis Nabi.
1. Memiliki kredibilitas
2. Jujur
3. Tidak ambisius
270
4. Memelihara diri dari permusuhan
5. Teliti atas informasi
6. Cerdas
7. Tidak mengikuti hawa nafsu
8. Tidak seorang wanita
17
Bagaimana legalitas jabatan Penalaran bebas
Gubernur
diangkat
dengan
penyerahan
gubernur?
mandat oleh Imam. Kekuasaan gubernur
berasal dari Imam.
18
Apa tugas gubernur?
Penalaran bebas
1. Mengatur penempatan tentara dan
gajinya
2. Mengurus perkara-perkara hukum
3. Memungut kharâj dan zakat
4. Memelihara Agama dari perubahan
dan penggantian (bidah)
5. Melaksanakan hukum pidana
6. Menjadi imam salat Jum‘at
7. Mengatur perjalanan jamaah haji
271
19
legalitas Penalaran bebas
Bagaimana
gubernur
yang
berkuasa
melalui
tekanan
pasukan
Dapat disahkan dengan 3 persyaratan:
1. Menjaga status kedudukan Imam
sebagai pengganti tugas Nabi.
2. Menampilkan kepatuhan beragama
terhadap Imam?
3. Mewujudkan persatuan
Meskipun keluar dari aturan pengangkatan
yang semestinya, baik dari segi syarat-syarat
maupun aturan hukumnya, legalitasnya dapat
diakui
dengan
tujuan
untuk
menjaga
keberlansungan hukum-hukum syariat dan
aturan-aturan agama yang lain, sehingga
tidak membiarkan suatu wilayah negara
berada dalam situasi tanpa aturan dan kacaubalau.
20
Apa tugas panglima tentara? Penalaran bebas dan sebagain kembali kepada
Alquran dan hadis Nabi.
a. Mengatur tentara, meliputi 10 hal:
1.
menjaga tentara dari jebakan
musuh,
2.
memilih
tempat
memerangi musuh,
untuk
272
3.
menyiapkan peralatan dan
perbekalan,
4.
mengikuti
perkembangan
berita,
5.
mengatur tentara dalam regu
dan barisan perang,
6.
memperkuat
jiwa
anggota
pasukan,
7.
merawat
dan
menasihati
kesabaran terhadap tentara
yang terluka,
8.
bermusyawarah dengan para
pakar,
9.
mengingatkan tentara tentang
kewajibannya kepada Allah,
10. menyiagakan pasukan setiap
waktu,
b. Mengatur strategi perang.
273
21
Apa kewajiban para tentara? Kembali kepada Alquran dan hadis Nabi
1. Bersikap teguh dalam menghadapi
musuh.
2. Berperang demi membela agama
Allah
3. Menunaikan amanat ghanîmah (harta
rampasan perang).
4. Tidak
condong
kepada
kaum
musyrikin yang mempunyai ikatan
kekerabatan.
22
Apa syarat jabatan hakim?
Penalaran bebas, mengutip pendapat ahli fikih, dan
1. Laki-laki dewasa
sebagian mengutip ayat Alquran.
2. Mempunyai
pengetahuan
tentang
syariat
yang
hukum-hukum
mencakup ilmu-ilmu pokok (’ushûl)
dan cabang-cabangnya (furû‘)
3. Berstatus merdeka
4. Beragama Islam
5. Mempunyai kredibilitas
6. Penglihatan
sempurna
dan
pendengarannya
274
23
Bagaimana legalitas hakim Mengutip pendapat para ahli fikih
1. Boleh
yang
2. Tidak boleh
berbeda
mazhab
dengan Imam?
24
Bagaimana
hakim
menerima
hadiah
yang Hadis Nabi
Tidak boleh/haram.
dan
mengambil keuntungan dari
jabatannya?
25
Bagaimana pengelolaan dan Mendasarkan pada praktek tradisi/kebiasaan yang
administrasi pertanahan?
1.
diakui (‘urfy)
Bagaimana
pemanfaatan
fasilitas publik?
1. Mendasarkan pada prinsip kemaslahatan (al-
(istihsân)
area
pada
untuk lahan perkebunan
1. mendahulukan siapa yang pantas
didahulukan, atau
mashlahat al-mursalah)
2. Mendasarkan
untuk
perumahan/pemukiman, atau
2.
26
dimanfaatkan
prinsip
kepatutan
2. mendahulukan orang yang memang
lebih dulu mengakses fasilitas publik
itu.
275
2. Daftar Isi Al-Ahkâm Al-Shulthâniyyah
PENDAHULUAN
BAB 1
: PENGANGKATAN KEPALA NEGARA
BAB 2
: PENGANGKATAN MENTERI
BAB 3
: PENGANGKATAN GUBERNUR PROVINSI
BAB 4
: PENGANGKATAN PANGLIMA PERANG
BAB 5
: PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN
BAB 6
: PENGANGKATAN HAKIM
BAB 7
: PENGANGKATAN PEJABAT MAZHÂLIM (KOMISI PELERAI
PERSENGKETAAN)
BAB 8
: PENGANGKATAN PERWAKILAN KELUARGA
TERHORMAT
BAB 9
: PENGANGKATAN IMAM-IMAM SHALAT
BAB 10
: PENGANGKATAN PIMPINAN IBADAH HAJI
BAB 11
: PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT ZAKAT
BAB 12
: PEMBAGIAN FAY’I DAN HARTA RAMPASAN PERANG
BAB 13
: PENENTUAN JIZYAH DAN KHARÂJ
BAB 14
: PENGELOLAAN DAERAH ISTIMEWA
BAB 15
: PENGELOLAAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM
276
BAB 16
: PENGELOLAAN TANAH FASILITAS UMUM
BAB 17
: PENGELOLAAN KEPEMILIKAN TANAH DAN SUBSIDI
BAB 18
: ADMINISTRASI NEGARA
BAB 19
: UNDANG-UNDANG KRIMINAL
BAB 20
: PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM