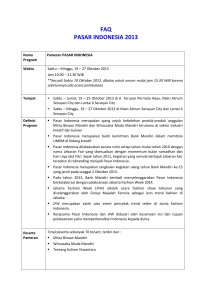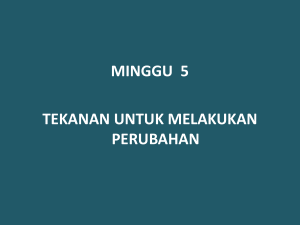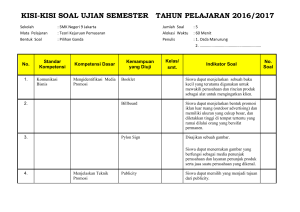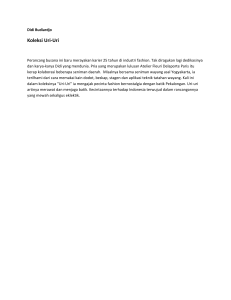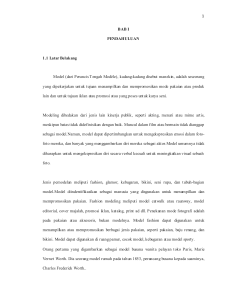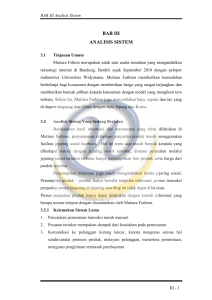FASHION: Fenomena Komunikatif, Kultural, dan Ideologis
advertisement

FASHION: Fenomena Komunikatif, Kultural, dan Ideologis “What [clothing] communicates has mostly to do with the self, chiefly our social identity as this is framed by cultural values bearing on gender, sexuality, social status, age, etc” -Davis, Fred. Fashion, Culture and Identity (1992). Seorang dokter secara sadar mengidentikkan dirinya dengan BlackBerry. Tak pernah merasa canggung memperlihatkan acang (gadget) tersebut di depan pasiennya. Sesungguhnya sang dokter sedang mengomunikasikan identitasnya, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Tak perlu ada bahasa lisan dan tertulis untuk mentransmisikan makna kepada orang lain bahwa sang dokter ingin menegaskan dirinya adalah seorang yang akrab dengan teknologi. Dalam kapasitas profesinya,mungkin sebagai sebuah tanda, ia termasuk dalam golongan dokter berkelas. Seorang pengajar di sebuah pusat kebudayaan asing bercerita tentang beberapa merek terkenal. Ternyata, di habitat alaminya, merek-merek tersebut adalah pakaian sejuta umat. Namun, di Indonesia merek-merek itu melekat kuat pada orang-orang yang datang dari kelas ekonomi menengah-atas. Apa yang terjadi jika mereka mengetahui situasi yang sebenarnya? Begitulah fashion dan pakaian bekerja. Tidak sekadar fungsi dan estetika yang ditonjolkan, tetapi ada transmisi pesan. Fashion dan pakaian adalah bentuk komunikasi nonverbal, karena tidak menggunakan kata-kata lisan atau tertulis, meskipun ada slogan dan merek. Pada level ini, komunikasi nonverbal-lah yang memperkuat makna harfiah slogan atau merek tersebut. Dalam buku “Fashion Sebagai Komunikasi”, Malcolm Barnard secara elegan dan dramatik menguraikan fashion dan pakaian dalam mengomunikasikan identitas sosial, seksual, kelas, dan gender. Barnard menyajikan sebuah sandaran yang luas bagi dasar pemikiran fashion sebagai arsitektur dan seni persuasif. Hal ini akan erat kaitannya dengan komunikasi artifaktual sebagai sebuah bentuk komunikasi nonverbal. Barnard memulai buku ini dengan serangkaian penjelasan mengenai akar kata fashion dan pakaian hingga mengargumentasikan fashion sebagai sebuah entitas yang ambivalen. Tak heran jika penjelasan Barnard kemudian berkembang dalam mengupas fashion dan anti-fashion, fashion dan remeh-temeh, serta fashion dan tipu daya. Pada bab dua dan tiga, Barnard menguraikan fashion dan pakaian terkait dengan komunikasi, budaya, dan fungsinya. Ia mencoba memetakan fashion dan komunikasi dari mazhab proses dan mazhab semiotika atau strukturalis. Aliran semiotika mengidentifikasi fashion menghasilkan komunikasi yang membuat individu menjadi anggota satu komunitas. Pada titik ini fashion merupakan fenomena komunikatif. Ada negosiasi makna di dalamnya. Artinya ada dominasi dan subordinat. Dari sisi budaya, fashion merupakan fenomena kultural yang bekerja melalui praktik penandaan. Artinya, keyakinan, nilai-nilai, ide, dan pengalaman dikomunikasikan melalui praktik-praktik artefak dan institusi. Puncak perhatian buku ini akan telihat jelas di bab empat, lima, dan enam yang menempatkan fashion, pakaian dalam kaitan makna, seks, gender, dan kelas. Jika berbicara komunikasi, maka makna adalah esensi utama. Semiologi menjabarkan dua jenis tingkatan makna, yakni denotasi dan konotasi yang muncul dari perbedaan sintagmatis dan paradigmatik. Selanjutnya, bahwa komunikasi juga melibatkan relasi dan posisi kekuasaan, sehingga fashion merupakan fenomena ideologis yang beimplikasi pada penciptaan dan reproduksi dari relasi dan posisi tersebut. Barnard berhasil membawa pembaca menelusuri fashion dalam fungsi komunikasinya dengan tahapan yang berjenjang. Inilah nilai lebih buku ini. Namun, sekali lagi buku ini dilatarbelakangi oleh konteks barat. Selain itu, buku ini juga mungkin belum menjangkau fashion dalam konteks acang dan media baru seperti internet. Terlepas dari buku aslinya, buku “Fashion Sebagai Komunikasi” dalam versi terjemahan ini, agaknya cukup menciptakan sedikit kerepotan dalam menelusuri barisan kalimatnya. Mungkin inilah pekerjaan rumah bagi buku-buku terjemahan di Tanah Air. Namun, pada dasarnya, kita pun dapat meneropong fenomena komunikasi, kultural, dan ideologi dalam fashion dan pakaian di dalam negeri dengan meminjam premis-premis dalam buku “Fashion Sebagai Komunikasi”, terutama dari sudut pandang kritis. Status fashion yang ambivalen tersibak dalam sisi positif dan negatif. Positif, jika di pandang dari sisi ekonomi dan produksi. Sebaliknya, negatif, bila dikaitkan dengan kapitalis, karena fashion lahir di dunia barat. Bukan sebuah keanehan jika akhirnya Jean Gelman Taylor menyebut fashion adalah sejarah golongan kaya memerintah buruh miskin.