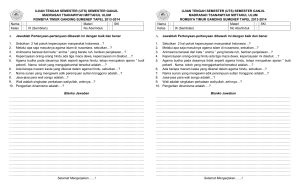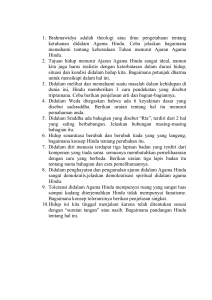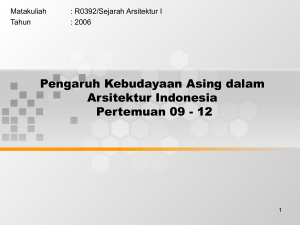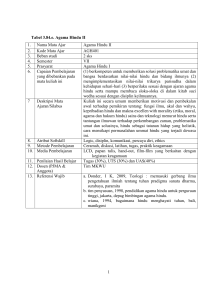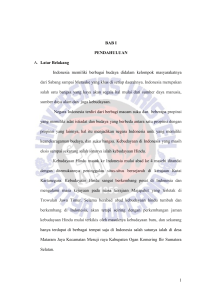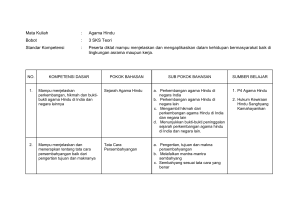Krangka Konseptual Hindu dalam Konteks Pelstarian Lingkungan
advertisement
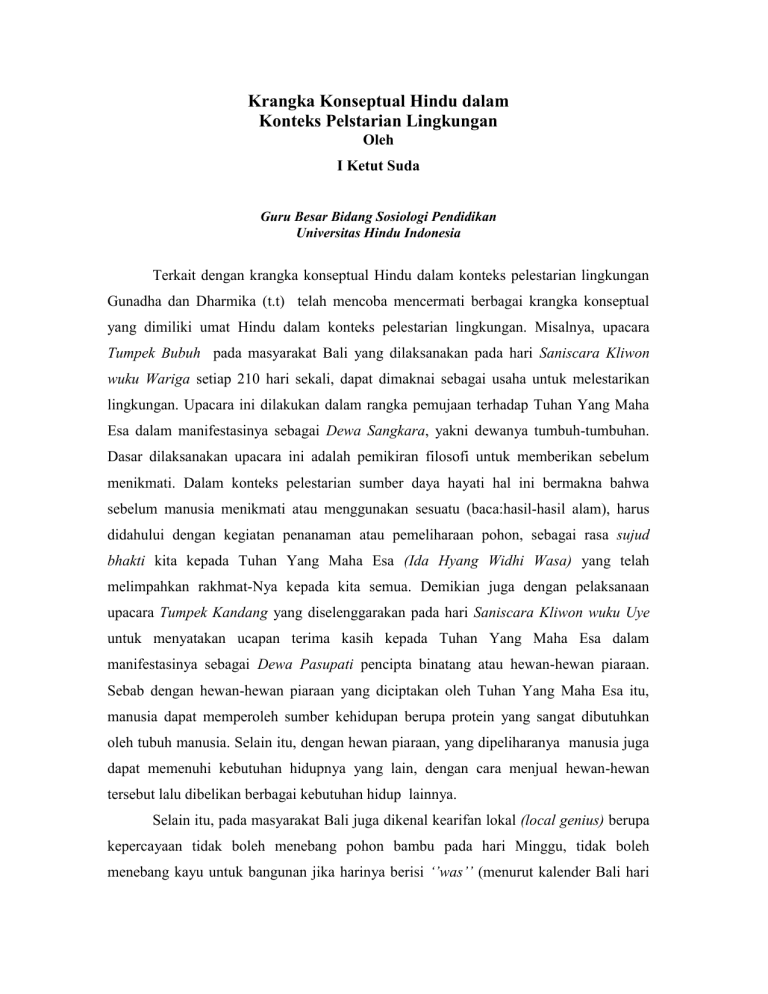
Krangka Konseptual Hindu dalam Konteks Pelstarian Lingkungan Oleh I Ketut Suda Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Terkait dengan krangka konseptual Hindu dalam konteks pelestarian lingkungan Gunadha dan Dharmika (t.t) telah mencoba mencermati berbagai krangka konseptual yang dimiliki umat Hindu dalam konteks pelestarian lingkungan. Misalnya, upacara Tumpek Bubuh pada masyarakat Bali yang dilaksanakan pada hari Saniscara Kliwon wuku Wariga setiap 210 hari sekali, dapat dimaknai sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan. Upacara ini dilakukan dalam rangka pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Sangkara, yakni dewanya tumbuh-tumbuhan. Dasar dilaksanakan upacara ini adalah pemikiran filosofi untuk memberikan sebelum menikmati. Dalam konteks pelestarian sumber daya hayati hal ini bermakna bahwa sebelum manusia menikmati atau menggunakan sesuatu (baca:hasil-hasil alam), harus didahului dengan kegiatan penanaman atau pemeliharaan pohon, sebagai rasa sujud bhakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Hyang Widhi Wasa) yang telah melimpahkan rakhmat-Nya kepada kita semua. Demikian juga dengan pelaksanaan upacara Tumpek Kandang yang diselenggarakan pada hari Saniscara Kliwon wuku Uye untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewa Pasupati pencipta binatang atau hewan-hewan piaraan. Sebab dengan hewan-hewan piaraan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, manusia dapat memperoleh sumber kehidupan berupa protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, dengan hewan piaraan, yang dipeliharanya manusia juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain, dengan cara menjual hewan-hewan tersebut lalu dibelikan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, pada masyarakat Bali juga dikenal kearifan lokal (local genius) berupa kepercayaan tidak boleh menebang pohon bambu pada hari Minggu, tidak boleh menebang kayu untuk bangunan jika harinya berisi ‘’was’’ (menurut kalender Bali hari was datang setiap enam hari sekali) dan banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang terkait dengan konsep pelestarian lingkungan. Masyarakat Hindu di Bali juga menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Kajian ini memperlihatkan bahwa secara konseptual sebenarnya masyarakat Hindu di Bali memiliki banyak nilai kearifan lokal dalam konteks pelestarian lingkungan yang terakumulasi dalam filosofi Tri Hita Karana, yakni harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (unsur Parahyangan); harmonisasi hubungan manusia dengan manusia lainnya (unsur Pawongan); dan harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungannya (unsur Palemahan). Kepemilikan kerangka konseptual seperti itu, ternyata belum banyak memberikan manfaat praksis kepada masyarakat. Sebab dalam kenyataannya filosofi Tri Hita Karana yang dimiliki umat Hindu di Bali hanya berhenti pada tataran konseptual. Artinya, meskipun secara konseptual masyarakat Hindu di Bali sangat kaya dengan konsep-konsep pelestarian lingkungan, seperti larangan menebang pohon pada hari-hari tertentu, melakukan pemeliharaan secara ritual terhadap tumbuhtumbuhan pada hari Tumpek Wariga, dan pemeliharaan secara ritual terhadap binatang pada hari Tumpek Uye, namun dalam kenyataan di lapangan pelestarian lingkungan pada masyarakat Bali masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti di tahun 2002 saja kerusakan hutan di Bali, sebagai refresentasi dari kerusakan lingkungan mencapai 5.789,96 ha yang disebabkan berbagai hal. Pertama, karena kebakaran mencapai luas 544,19 ha, dan kedua, karena pembibrikan mencapai luas 5.245,77 ha, sedangkan kerusakan hutan yang dikarenakan pencurian mencapai 83,17 m3/ph (Dishut Prov Bali, 2002). Berangkat dari fenomena di atas dan jika mangacu pada Kraf (2002) dan Atmadja (2010) dapat dikatakan bahwa etika lingkungan ekosentrisme atau holistik yang dianut oleh manusia Bali kini telah berubah menjadi etika antroposentrisme. Artinya, manusia tidak hanya mengambil jarak dengan lingkungan alam, tetapi juga menganggap dirinya sebagai pusat dari segala-galanya. Atau dengan paparan yang tidak jauh berbeda Chang (2000) mengatakan bahwa modernisasi mengakibatkan sistem pemikiran ekologis berubah menjadi sistem filsafat utilitarianisme dan pragmatisme. Artinya, manusia yang menganut filsafat ini selalu berusaha mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan tanpa memperhatikan dampaknya. Untuk mengatasi semua ini, dapat dilakukan dengan cara menghindari pola hidup materialisme-konsumerisme. Sebab menurut Piliang (2004:307) dalam budaya konsumerisme, konsumsi tidak lagi dimaknai sebagai satu lalulintas kebudayaan benda, akan tetapi sudah menjadi sebuah panggung sosial yang di dalamnya makna-makna sosial saling diperebutkan, dan di dalamnya pula telah terjadi perang posisi diantara anggota masyarakat yang terlibat. Bukan hanya itu, budaya konsumerisme yang berkembang sampai saat ini, juga telah menjadi arena kontestasi, yang di atasnya produk-produk konsumer dijadikan medium untuk pembentukan personalitas, gaya, citra, gaya hidup, dan cara difrensiasi status sosial yang berbeda-berbeda. Ketika kondisi ini telah merasuk ke dalam sukma setiap insan manusia Bali, maka eksploitasi terhadap lingkungan alam untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut sulit dihindari. Guna mengatasi semua itu marilah kita semua melakukan mulat sarira introspeksi diri dan marilah kita hormati lingkungan alam tempat kita berpijak hari ini, sebab semua ini merupakan titipan Tuhan untuk para generasi kita ke depan.