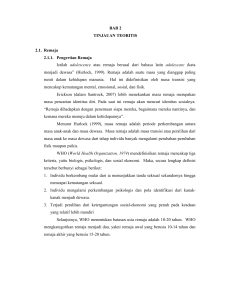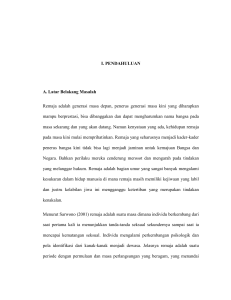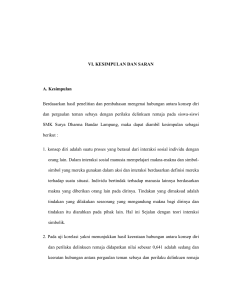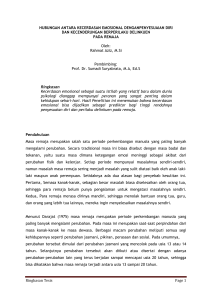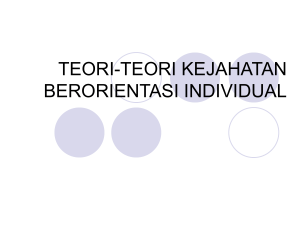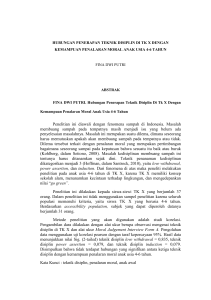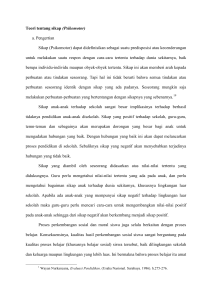BAB 2 TINJAUAN TEORITIS 2.1. Remaja 2.1.1. Pengertian Remaja
advertisement

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS 2.1. Remaja 2.1.1. Pengertian Remaja Istilah adolescence atau remaja berasal dari bahasa latin adolescare (kata menjadi dewasa” (Hurlock, 1999). Remaja adalah suatu masa yang dianggap paling rumit dalam kehidupan manusia. Hal ini didefinisikan oleh masa transisi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Erickson (dalam Santrock, 2007) lebih menekankan masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Pada saat ini remaja akan mencari identitas sosialnya. “Remaja dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya”. Menurut Hurlock (1999), masa remaja adalah periode perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak ke masa dewasa dari tahap individu banyak mengalami perubahan-perubahan fisik maupun psikis. WHO (World Health Organization, 1974) mendefinisikan remaja mencakup tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Maka, secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut: 1. Individu berkembang mulai dari ia menunjukkan tanda seksual sekundernya hingga mencapai kematangan seksual. 2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanakkanak menjadi dewasa. 3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri Selanjutnya, WHO menentukan batasan usia remaja adalah 10-20 tahun. WHO mengkategorikan remaja menjadi dua, yakni remaja awal yang berusia 10-14 tahun dan remaja akhir yang berusia 15-20 tahun. 2.1.2. Tugas-Tugas Perkembangan Remaja Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan masa dewasa yang sehat. Dalam yudrik (2001) mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja itu sebagai berikut: 1. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. 3. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. 4. Menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. 5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. 6. Memperkuat self-control (kemampuan mengendalikan diri) atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. 7. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanakkanakan. Sedangkan menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1999), tugas perkembangan remaja meliputi : a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita b. Mencapai peran sosial pria, dan wanita c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab e. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang dewasa lainnya f. Mempersiapkan karir ekonomi g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilakumengembangkan ideologi. 2.1.3. Ciri-ciri Masa Remaja Sesuai dengan pembagian usia remaja menurut Monks (2002) maka terdapat tiga tahap proses perkembangan yang dilalui remaja dalam proses menuju kedewasaan, disertai dengan karakteristiknya, yaitu : a. Remaja awal (12-15 tahun) Pada tahap ini, remaja mulai beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahanperubahan tersebut. Individu berusaha untuk menghindari ketidaksetujuan sosial atau penolakan dan mulai membentuk kode moral sendiri tentang benar dan salah. Individu menilai baik terhadap apa yang disetujui orang lain dan buruk apa yang ditolak orang lain. Pada tahap ini, sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul, karena ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima saat masih kanak-kanak sudah tidak begitu menarik bagi mereka. b. Remaja madya (15-18 tahun) Pada tahap ini, remaja berda dalam kondisi kebingungan dan terhalang dari pembentukan kode moral karena ketidak konsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keagamaan mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Pada tahap ini, mulai tumbuh semacam kesadaran akan kewajiban untuk mempertahankan aturanaturan yang ada, namun belum dapat mempertanggungjawabkannya. c. Remaja akhir (18-21 tahun) Pada tahap ini, individu dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Individu mau diatur secar ketat oleh hukum-hukum umum yang lebih tinggi. Alasan mematuhi peraturan bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman atau kebutuhan individu, melainkan kepercayaan bahwa hukum adan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan dan fungsi sosial. Remaja sudah memilih prinsip moral untuk hidup. Individu melakukan tingkah laku moral yang dikemudikan oleh tanggung jawab batin sendiri. 2.1.4. Remaja Delinkuen 2.1.4.1 Pengertian Delinkuensi Remaja (Juvenile Delinquency) Delinkuensi remaja atau biasa disebut dengan Juvenile Delinquency berasal dari bahasa latin. Juvenile artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda atau sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan delinquent berasal dari kata “delinquere” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacu, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan sebagainya. Berdasarkan etimologi tersebut, Kartono (2001) mengartikan delinkuensi remaja atau juvenile delinquency sebagai perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, dan merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga remaja tersebut mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Bynum dan Thompson (2001) mendefinisikan delinkuensi remaja sebagai perilaku ilegal serta pelanggaran, yang dapat dinilai oleh masyarakat sebagai suatu penyimpangan. Perilaku menyimpang tersebut dapat diartikan sebagai perilaku yang diterima oleh orang lain sebagai ancaman terhadap harapan orang banyak atau merugikan orang lain serta merugikan diri sendiri. Menurut Dacey dan Kenny (2001), delinkuensi remaja adalah segala perilaku ilegal yang dilakukan oleh remaja. Perilaku delinkuen disini menekankan pada kriminalitas dan aspek illegal dari suatu perilaku. Aktifitas ilegal tersebut tidak semua mengarah kepada pelanggaran yang serius, hal ini dikarenakan frekuensi, keseriusan dan kekronisan remaja melakukan dalam melakukan perilaku tersebut berbeda-beda. Lebih lanjut Newman dan Newman (2006) mengemukakan bahwa perilaku delinkuen merupakan masalah dari eksternalisasi yang berhubungan dengan kesulitan dalam mengontrol dan mengatur dorongan tertentu. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan remaja delinkuen adalah remaja yang melakukan perilaku ilegal serta pelanggaran yang dapat dinilai oleh masyarakat sebagai suatu penyimpangan, yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik itu terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, yang meliputi pencurian, perampokan, penyerangan dengan kekerasan, pemerkosaan, minumminuman keras, penyalahgunaan obat, maupun pembunuhan. 2.1.4.2 Karakteristik Remaja Delinkuen Ada beberapa karakteristik yang terlihat pada remaja yang delinkuen. Diantaranya adalah bahwa remaja yang delinkuen merasakan deprivasi (keterasingan), tidak aman, dan cenderung dengan sengaja berusaha melanggar hukum atau peraturan (Gunarsa, 2004). Penggunaan obat-obatan terlarang dan putus sekolah merupakan beberapa hal yang dapat meningkatkan Munculnya kenakalan remaja. Selain itu remaja delinkuen tidak menyukai sekolah dan karenanya mereka seringkali membolos. Kegagalan akademis sendiri merupakan salah satu kontributor dari delinkuensi (Gunarsa, 2004). Menurut Cole (dalam Gunarsa, 2004) beberapa ciri kepribadian yang tampak menonjol pada remaja delinkuen yaitu : bersikap menolak (resentful), bermusuhan (hostile), penuh curiga, tidak konvensional (unconventional), tertuju pada diri sendiri (self centered), tidak stabil emosinya, mudah dipengaruhi, ekstrovert dan suka bertindak dengan tujuan merusak atau menghancurkan sesuatu. Banyak dari remaja delinkuen juga implusif dan axcitable. Perbedaan mendasar yang mungkin terlihat antara remaja delinkuen dan non delinkuen adalah dalam hal ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan, dan perasaan frustrasi pada remaja delinkuen yang membuat remaja delinkuen tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik dirumah, sekolah, dan masyarakat. 2.2. Penalaran Moral 2.2.1. Pengertian Penalaran Moral Kohlberg (1995), mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Penalaran moral dapat dijadikan prediktor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rest (1979) bahwa penalaran moral adalah konsep dasar yang dimiliki individu untuk menganalisa masalah sosial-moral dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukannya. Menurut Kohlberg (1995) penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka sesuatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. Memperhatikan penalaran mengapa suatu tindakan salah, akan lebih memberi penjelasan dari pada memperhatikan perilaku seseorang atau bahkan mendengar pernyataannya bahwa sesuatu itu salah (Duska dan Whelan, 1975). Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penalaran moral adalah kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosialmoral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. 2.2.2. Tahapan-tahapan Perkembangan Penalaran Moral Kohlberg (1995) menyatakan bahwa proses perkembangan penalaran moral merupakan sebuah proses alih peran, yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih komprehensif, lebih terdiferensiasi dan lebih seimbang dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Melihat pentingnya perkembangan penalaran moral dalam kehidupan manusia, maka berbagai penelitian psikologi di bidang ini dilakukan. Lawrence Kohlberg, memperluas penelitian Piaget tentang penalaran aturan konvensi sosial, menjadi tiga tingkat penalaran moral yang terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Tahap-tahap perkembangan penalaran moral dibagi menjadi 3 tingkat, yang terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional. Tiga tingkat tersebut kemudian dibagi atas enam tahap (Kohlberg, 1995). a. Tingkat Prakonvensional Pada tahap ini si anak mulai mengakui adanya aturan-aturan baik atau buruk mulai mempunyai arti baginya, tapi hal itu semata-mata dihubungkan dengan reaksi orang lain. Penilaian moral terhadap perbuatan hanya didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang dibawakan oleh perilaku si anak : hukuman atau ganjaran, hal yang pahit atau hal yang menyenangkan. Pada tingkat prakonvensional ini dapat dibedakan menjadi dua tahap : Tahap 1) : Orientasi hukuman dan kepatuhan Anak mendasarkan perbuatannya atas otoritas konkret (orangtua,guru) dan atas hukuman yang akan menyusul, bila ia tidak patuh. Anak kecil tidak memukul adiknya, karena hal itu dilarang oleh dan karena melanggar kemauan ibu dan akan membawa hukuman. Ia membatasi diri pada kepentingannya sendiri dan belum memandang kepentingan orang lain. Tahap 2) : Orientasi relativis-instrumental Perbuatan adalah baik, jika ibarat instrumen (alat) dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Anak mulai menyadari kepentingan orang lain juga tapi hubungan antara manusia dianggapnya seperti hubungan orang di pasar: tukar-menukar. Hubungan timbal balik antara manusia adalah soal “jika kamu melakukan sesuatu untuk saya, maka saya akan melakukan sesuatu untuk kamu”(do ut des), bukannya soal loyalitas kesetiaan), rasa terimakasih atau keadilan. b. Tingkat Konvensional Menurut penelitian Kohlberg menunjukan bahwa biasanya (namun tidak selalu) anak mulai beralih ke tingkat ini antara umur 10 dan 13 tahun. Di sini perbuatanperbuatan mulai dinilai atas dasar norma-norma umum dan kewajiban serta otoritas dijunjung tinggi. Tingkat ini oleh Kohlberg disebut “konvensional”, karena di sini anak mulai menyesuaikan penilian dan perilakunya dengan harapan orang lain atau kode yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Memenuhi harapan keluarga, kelompok atau bangsa dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri, terlepas dari konsekuensi atau akibatnya. Dalam sikapnya si anak tidak hanya menyesuaikan diri dengan harapan orangorang tertentu atau dengan ketertiban sosial, melaikan juga menaruh loyalitas kepadanya dan secaraaktif menunjang serta membenarkan ketertiban yang berlaku. Singkatnya, anak mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosialnya beserta norma-normanya. Tingkatan ini juga mencakup dua tahap : Tahap 3) : penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi “anak manis” Anak cenderung mengarahkan diri kepada keinginan serta harapan dari para anggota keluarga atau kelompok lain (sekolah di sini tentu penting). Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Anak mengambil sikap: saya adalah “anak manis”, yang artinya, ia adalah sebagaimana diharapkan oleh orang tua, guru, atau sebagainya. Ia ingin bertingkah laku secara “wajar”, artinya, menurut norma-norma yang berlaku. Jika ia menyimpang dari dari norma-norma kelompoknya, ia merasa malu dan bersalah. Dalam hal ini untuk pertama kali si anak mulai memperhatikan pentingnya maksud perbuatan. Tahap 4) : Orientasi hukum dan ketertiban Pada tahap ini, individu dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Aturan dalam masyarakat merupakan dasar baik atau buruk, melaksanakan kewajiban dan memperlihatkan penghargaan terhadap otoritas adalah hal yang penting. Alasan mematuhi peraturan bukan merupakan ketakutan terhadap hukuman atau kebutuhan individu, melainkan kepercayaan bahwa hukum dan aturan harus dipatuhi untuk mempertahankan tatanan dan fungsi sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri. c. Tingkat Pasca-konvensional Tingkat ini disebut juga moralitas yang berprinsip (principled morality). Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Baik atau buruk didefinisikan pada keadilan yang lebih besar, bukan pada aturan masyarakat yang tertulis atau kewenangan tokoh otoritas. Tahap ini sudah dimulai dari remaja awal sampai seterusnya. Ada dua tahap pada tingkat ini. Tahap 5) : Orientasi kontrak sosial legalistis Pada tingkatan perkembangan moral ini anak mulai memahami nilai moral dan prinsip moral merupakan standar kebenaran yang benar dan dapat terjadi pertentangan dengan apa saja yang diterimanya. (dan bukan membekukan hukum itu sesuai dengan tata tertib gaya tahap 4). Tahap 6) : Orientasi prinsip etika universal Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsipprinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Keenam tingkat penalaran moral yang dikemukakan oleh Kohlberg (1995) tersebut dibedakan satu dengan yang lainnya bukan berdasarkan keputusan yang dibuat, tetapi berdasarkan alasan yang dipakai untuk mengambil keputusan. 2.2.3. Komponen Penalaran Moral Rest (1979) membagi komponen penalaran moral menjadi empat hal. Adapun empat komponen utama penalaran moral yang dikemukakan antara lain : 1. Menginterpretasi situasi dan mengidentifikasi permasalahan moral (mencakup empati, berbicara selaras dengan perannya, memperkirakan bagaimana masingmasing pelaku dalam situasi terpengaruh oleh berbagai tindakan tersebut). 2. Memperkirakan apa yang seharusnya dilakukan seseorang, merumuskan suatu rencana tindakan yang merujuk kepada suatu standar moral atau suatu ide tertentu (mencakup konsep kewajaran & keadilan, penalaran moral, penerapan nilai moral sosial). 3. Mengevaluasi berbagai perangkat tindakan yang berkaitan dengan bagaimana caranya orang memberikan penilaian moral atau bertentangan dengan moral, serta memutuskan apa yang secara aktual akan dilakukan seseorang (mencakup proses pengambilan keputusan, model integrasi nilai, dan perilaku mempertahankan diri). 4. Melaksanakan serta mengimplementasikan rencana tindakan yang berbobot moral (mencakup ego-strength dan proses pengaturan diri). 2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penalaran Moral Menurut Kohlberg (1995), ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral yaitu : a. Kesempatan pengambilan peran Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial seperti situasi dimana seseorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, kewajiban, nilai dan standar orang lain. b. Situasi moral Setiap lingkungan sosial dikarakteristikkan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusiakan dan melibatkan keputusan. Dalam beberapa lingkungan, keputusan diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas (tahap 1). Dalam lingkungan yang lain, keputusan didasarkan pada pertimbangan pada system yang tersedia (tahap 4 atau lebih tinggi). Tahap penalaran moral ditunjukkan oleh situasi yang menstimulasi orang untuk menunjukkan nilai moral dan norma moral. c. Konflik moral kognitif Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi dari pada anak yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Interaksi antara orangtua dan anak dalam berbagai situasi menunjukkan 3 faktor umum di atas. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penalaran moral anak. Menurut muslimin (2004) faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak adalah keluarga, bahwa pengaruh utama dari keluarga adalah pada diskusi antara orangtua dengan anak mengenai nilai-nilai dan norma, dari pada pengalaman anak sendiri akan disiplin, hukuman, dan hadiah dari orangtua. Kohlberg juga menyatakan bahwa penalaran moral dipengaruhi oleh tahap perkembangan kognitif yang tinggi (seperti pendidikan) dan pengalaman sosiomoral. Pendidikan adalah prediktor yang kuat dari perkembangan penalaran moral, karena lingkungan pendidikan yang lebih tinggi menyediakan kesempatan, tantangan dan lingkungan yang lebih luas yang dapat merangsang perkembangan kognitif. Berdasarkan uraian di atas maka ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral seseorang, yaitu kesempatan alih peran, situasi moral, konflik moral kognitif, keluarga, dan pendidikan. 2.3. Kerangka Berpikir Berdasarkan uraian konsep-konsep di atas, maka penulis merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut : Tabel.2.1 Kerangka Berfikir Pemahaman penalaran moral Remaja Pendidikan formal Pendidikan non-formal Perbedaan penalaran moral Gambar 2.1 kerangka berfikir Karakteristik remaja seharusnya dapat bertindak sesuai norma dan harapan masyarakat dan melakukan tingkah laku moral, namu pada kenyataannya banyak remaja yang berprilaku tidak sesuai dengan prisip-prinsip etis. Menururt Kohlberg ini menunjukan tingkat penalaran moral remaja yang rendah. Bahwa di dalam Lapas mereka mendapatkan pemibinaan salah satunya pendidikan formal dan nonformal. Oleh karena itu dapat ditinjau sebagaimana penalaran moral dari perbedaan pendidikan yang mereka dapat. 2.4. Hipotesis Hipotesis menurut Sudjana dalam Ridwan (2005 : 37) adalah asumsi atau pdugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya" Adapun hipotesis pada penelitian ini, adalah : Ha : Terdapat perbedaan penalaran moral pada penghuni Lapas remaja tangerang berdasarkan keikut sertaan pendidikan formal dan non-formal didalam Lapas. H0 : Tidak terdapat perbedaan penalaran moral pada penghuni Lapas remaja tangerang berdasarkan keikut sertaan pendidikan formal dan non-formal didalam Lapas.