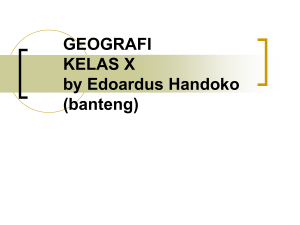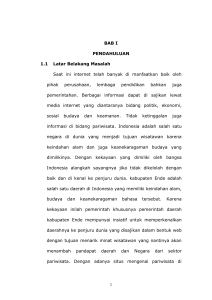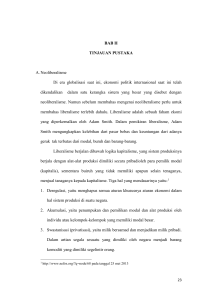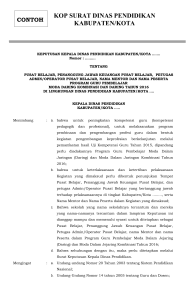Kelompok 6 - WordPress.com
advertisement
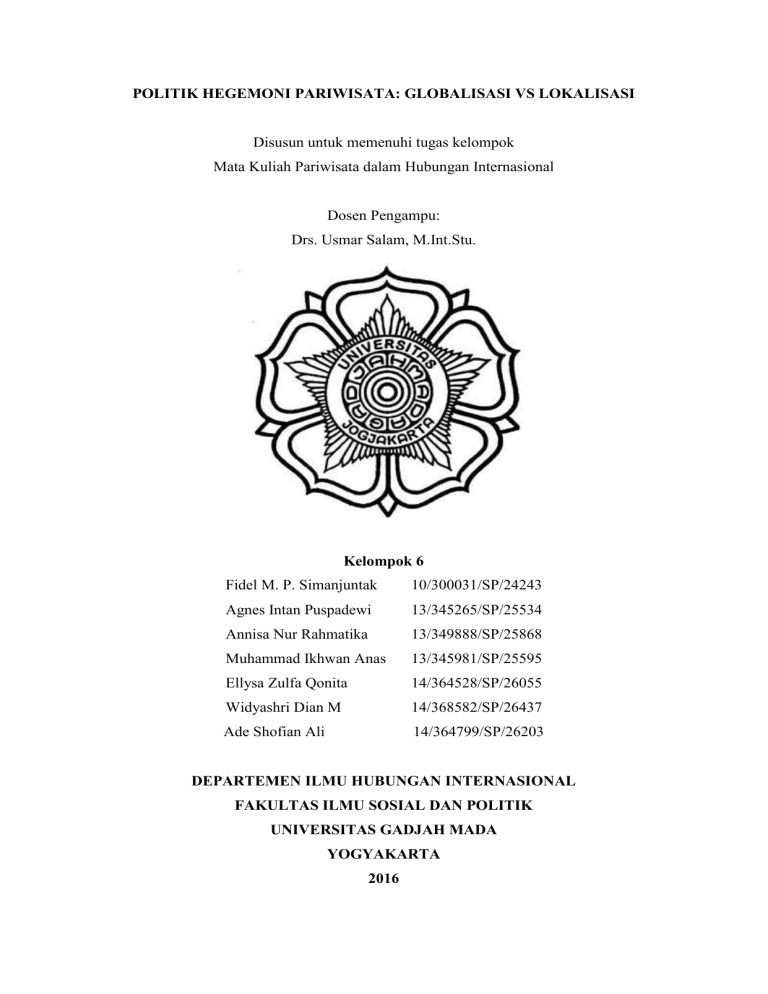
POLITIK HEGEMONI PARIWISATA: GLOBALISASI VS LOKALISASI Disusun untuk memenuhi tugas kelompok Mata Kuliah Pariwisata dalam Hubungan Internasional Dosen Pengampu: Drs. Usmar Salam, M.Int.Stu. Kelompok 6 Fidel M. P. Simanjuntak 10/300031/SP/24243 Agnes Intan Puspadewi 13/345265/SP/25534 Annisa Nur Rahmatika 13/349888/SP/25868 Muhammad Ikhwan Anas 13/345981/SP/25595 Ellysa Zulfa Qonita 14/364528/SP/26055 Widyashri Dian M 14/368582/SP/26437 Ade Shofian Ali 14/364799/SP/26203 DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2016 POLITIK HEGEMONI PARIWISATA: GLOBALISASI VS LOKALISASI Di era kini, kita tidak bisa melepaskan sektor pariwisata dengan perkembangan dunia internasional. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, transportasi, dan perekonomian dunia, sektor pariwisata semakin terbuka terhadap masuknya investasi dan juga turis asing yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Inilah yang kemudian dapat dikategorikan sebagai dampak dari proses globalisasi dunia yang semakin mengikat hubungan simbiosis antara sektor pariwisata di tingkat lokal dengan aktor dan situasi internasional. Hubungan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Jepang untuk semakin mendorong dan mempromosikan sektor pariwisata lokal, yakni berusaha untuk meningkatkan inbound tourism ke dalam negerinya.1 Pada masa ini, Jepang tengah mengalami permasalahan yang cukup sulit kaitannya dengan perekonomian. Hal ini dikarenakan oleh stagnansi ekonomi yang dialami Jepang serta semakin meningkatnya usia non-produktif di Jepang yang diperparah dengan menurunnya angka kelahiran. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini, pemerintah Jepang berusaha untuk meningkatkan kinerja di sektor lain. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Jepang adalah negara yang cukup terkenal untuk menjadi destinasi wisata. Namun pada kenyataannya masih terjadi permasalahan dalam sektor pariwisata di Jepang, khususnya dalam perlakuan untuk para wisatawan mancanegara. Inilah yang menjadi hambatan dalam mempromosikan inbound tourism di Jepang, sekaligus memperlihatkan adanya tubrukan antara globalisasi dengan lokalisasi pariwisata. Antara lain Jepang tidak mengikutsertakan para Gaijin (foreigners) dalam partisipasi di masyarakat, atau dapat dikatakan masyarakat Jepang masih membatasi interaksi dengan orang asing. Selain itu adanya larangan bagi orang asing untuk mengunjungi onsen (hot springs), hotel dan restaurant tradisional di beberapa tempat juga masih menjadi isu dalam sektor pariwisata Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang menjunjung persamaan dan homogenitas dalam masyarakatnya. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pemahaman mengapa cukup sulit bagi masyarakat Jepang untuk menerima orang asing dalam lingkungannya. Adanya target 10 juta wisatawan internasional yang dikeluarkan oleh Japan Tourism Advisory Council’s 1 M. Cooper, R. Jankowska, & J. Eades, ‘The Politics of Exclusion? Japanese Cultural Reactions and the Government’s Desire to Double Inbound Tourism,’ dalam P.M. Burns & M. Novelli (eds.), Tourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities, Elsevier, Oxford, 2007, pp. 71-82. 2 memunculkan dorongan untuk Jepang yang lebih terbuka. Dengan keterbukaan ini diharapkan bahwa inbound tourism Jepang dapat mencapai target pada tahun 2010. Adanya keterbukaan yang dipercepat dengan adanya globalisasi dan sektor pariwisata telah menimbulkan beberapa permasalahan. Khususnya untuk masyarakat yang telah terbiasa terisolasi dari dunia luar. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat tersebut akan lebih sering bertemu dengan orang-orang asing dan dapat mengarah pada rasa tidak nyaman meski berada di lingkungannya sendiri. Situasi tersebut dapat dilihat di Beppu, sebuah kota wisata di bagian selatan Pulau Kyushu. Sebelumnya di kota ini hanya ada segelintir orang asing yang tinggal atau berkunjung. Namun pasca dibukanya Ritsumeikan Asia Pacific University pada tahun 2000, banyak orang asing, yang sebagian besar adalah mahasiswa, berdatangan ke kota ini. Tidak semua warga Beppu senang dengan hal ini, meraka takut akan adanya clash of culture. Namun pada 2006, rasa takut ini berangsur-angsur menghilang karena adanya pengaruh ekonomi yang positif. Pandangan yang kurang baik bagi oleh masyarkat Jepang kepada orang asing juga mendorong adanya xenophobia. Bentuk dari xenophobia antara lain ketakutan terhadap orang asing, serta kekhawatiran akan adanya penyakit baru serta meningkatnya tingkat kriminalitas akibat kedatangan orang asing. Bahkan muncul logika bahwa semakin banyak orang asing maka akan semakin banyak penyakit dan kriminalitas. Pemberitaan media terkait permasalahan yang menyangkut orang asing semakin memperparah situasi ini. Ethnocentrism juga dapat menjadi bagian dari xenophobia. Untuk itu dalam sektor parawisata dimana interaksi dan tindakan menjadi bagian penting, hal-hal yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan harus dihindari. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka wisatawan akan mendapat kenyamanan dan pihak pengelola dapat memperoleh citra yang baik serta publisitas. Permasalahan lain yang dialami orang asing, bahkan untuk para zainchi (penduduk tetap), adalah diskriminasi. Bagi masyarakat Jepang, orang-orang asing ini tidak hanya berasal dari tempat yang jauh namun juga memiliki kultur yang berbeda. Dua faktor utama yang menjadi dasar munculnya ide tentang perbedaan adalah sejarah dan kultur. Hal tersebut terkait dengan hubungan Jepang dan Eropa. Bagi orang Barat, orang-orang Jepang terkesan berjarak dalam berperilaku. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan dalam cara berkomunikasi. Orang Jepang terkesan berbelit-belit (indirect) dalam mengatakan sesuatu. Sedangkan bagi orang Jepang, cara bicara orang Barat yang berterus-terang dianggap tidak sopan. Meski begitu cara berkomunikasi tidak selalu menjadi permasalahan. Permasalahan utama dari adanya perbedaan ini adalah munculnya diskriminasi. Adanya diskriminasi dalam informasi, 3 pelayanan, serta perlakuan sehari-hari tidak dapat diabaikan dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kultur suatu negara. Hal ini harus segera diselesaikan mengingat globalisasi sendiri telah mengaburkan batas-batas antar negara. Isu diskriminasi menjadi sangat penting di Jepang dengan meningkatnya kesempatan pengembangan inbound tourism. Adanya diskriminasi serta xenophobia terhadap wisatawan asing memiliki kaitan dengan Nihonjinron (sebuah teori tentang identitas Jepang). Terdapat dua sisi yang berbeda tentang Nihonjinron, sisi pendukung dan sisi lawan. Pengikut Nihonjinron sering kali dianggap sebagai xenophobic dan nasionalis, sedangkan lawannya sering kali dianggap berusaha untuk memaksakan budaya asing kedalam masyarakat Jepang. Para pendukung mengatakan bahwa Jepang tidak seharusnya berubah untuk menjaga keunikannya. Bagi lawan, Jepang tidak berubah, dan tidak akan mau berubah karena alasan etnosentris mendukung Nihonjinron. Nihonjinron tidak memiliki definisi yang pasti, namun dapat didefinisikan sebagai pembicaraan yang hidup dan popular tentang identitas Jepang, membedakannya dari bangsa lain dan menjadikan Jepang terlihat unik. Tidak adanya definisi yang pasti tentang Nihonjinron dikarenakan Nihonjinron bukanlah suatu teori yang statis namun mengikuti adanya perubahan dan terus mengalami perbaikan yang dapat berdasar pada pengalaman seseorang, literatur, atau situasi yang baru. Terdapat dua tingkatan Nihonjinron yaitu umum dan individual. Kedua tingkatan ini saling memengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini diharapkan bahwa para elite sebagai producer of knowledge mampu memberikan pandangan tentang Nihonjinron kepada masyarakat umum. Dalam kaitannya dalam sektor pariwisata, para elite dapat menggunakannya untuk mengatasi persoalan diskriminasi. Proses ini tergantung pada sejauh mana kepentingan para elite, dan untuk saat ini kepentingan tersebut adalah tentang bagaimana cara agar masyarkat mampu menerima wisatawan mancanegara dengan baik. Nihonjinron sebagai sebuah identitas nasional memiliki popularitas yang besar. Berbeda dengan negara-negara lain yang tidak banyak membicarakan tentang keunikan dan karakteristiknya, Jepang justru dengan bangga selalu menunjukkan bahwa negaranya adalah negara yang memiliki keunikan dan berbeda dengan negara lain. Jepang tidak memiliki kekhawatiran akan anggapan sebagai xenophobic dan terlalu nasionalis. Menurut Ismail (1996), terdapat tiga tujuan utama Nihonjinron.2 Pertama adalah untuk membentuk kembali identitas Jepang melawan ancaman dari luar, khususnya dalam hal budaya. Fungsi kedua 2 F. Ismail, ‘Japanese response to the “world outside,” New Strait Times (online), 19 March 1996. 4 adalah untuk menjelaskan keunikan Jepang dalam kesuksesan membangun ekonomi sepanjang sejarah, terutama dalam periode 1950an dan 1960an. Dalam hal ini dapat dikatakan Jepang ingin menunjukkan signifikansinya dalam pembangunan ekonomi dibanding dengan negara lain pasca perang. Fungsi ketiga adalah untuk mempersatukan berbagai kelompok berbeda yang tinggal di Jepang. Jepang sangat takut dengan keberagaman sehingga mereka mendorong adanya keunikan untuk membuat suatu bangsa sebagai sebuah keseluruhan yang homogen dan sukses. Meski begitu Befu (2001), disisi lan menganggap bahwa Nihonjinron hanyalah sebuah pengganti bagi simbol nasional yang telah kehilangan makna pasca Perang Pasifik.3 Pasca perang, Jepang membutuhkan sebuah simbol baru untuk identitas nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga identitas dan memberikan kekuatan bagi orang-orang untuk membangun kembali negara dan memulai lagi dari awal tanpa bergantung pada nasionalisme dan militerisme. Nihonjinron ini kemudian berpengaruh pada sektor pariwisata di Jepang. Hal ini akan berpengaruh dalam cara berpikir orang Jepang tentang inbound tourism karena Nihonjinron telah membentuk cara interaksi antara orang asing, baik dari domestik maupun luar Jepang. Terdapat beberapa hal yang dapat menganggu internasionalisasi Jepang, khususnya dalam inbound tourism. Pertama adalah perbedaan cara berpikir, berperilaku, serta komunikasi. Tanpa adanya dialog yang baik maka pertukaran informasi akan sulit terjadi antar masyarakat Jepang dan orang asing. Kedua adalah penekanan bahwa Jepang adalah negara yang ‘murni.’ Jika Jepang mampu mengurangi penekanan dalam hal tersebut maka situasi kehidupan orang asing di Jepang akan lebih baik. Oleh karena itu adanya modifikasi Nihonjinron oleh para elite diharapkan juga mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan inbound tourism. Jepang sendiri baru dikatakan serius untuk menggarap inbound tourism pada tahun 1990an. Sebelumnya Jepang sangat outbound-oriented dan domestically oriented. Pada 1996, Jepang meluncurkan program Welcome Plan 21. Lalu pada tahun 2003, diluncurkan Visit Japan Campaign. Adanya program tersebut ternyata belum menunjukkan hasil yang berarti dilihat pada data tahun 2005 bahwa ada sebanyak 17,4 juta orang Jepang yang pergi ke luar negeri, namun hanya 6,8 juta orang asing yang berkunjung Jepang. Akibatnya Jepang mengalami defisit sebesat 15 milyar dollar AS. Selain adanya Nihonjinron, pengembangan inbound tourism di Jepang juga memiliki tantangan lain. Pertama, letak yang jauh serta transportasi yang mahal bagi target utama inbound tourism Jepang yaitu Eropa. Kedua, persepsi akan tingginya harga-harga di Jepang. 3 H. Befu, Hegemony of homogeneity, Trans Pacific Press, Melbourne, 2001. 5 Ketiga, perlunya perhatian pada marketing dan strategi pariwisata. Budget pariwisata Jepang dapat dikatakan sangat kecil yaitu 440 juta yen pada tahun 2002, bandingkan dengan Prancis yang sebesar 5940 juta yen pada tahun 2000 atau Kanada yang mencapai 9870 juta yen pada tahun 2001. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang mendukung pariwisata serta perbedaan kebijakan oleh pemerintah juga menjadi permasalahan. Keempat, pengaruh globalisasi. Masyarakat lokal harus mampu memperluas pandangan untuk mengembangkan inbound tourism. Selain itu mereka juga harus mampu mempresentasikan karakteristik yang unik dan menarik terutama pada wisatawan inbound. Untuk mengatasi permasalahan dalam pariwisata Jepang, pemahaman cross-cultural dan penerimaan sangatlah penting. Nihonjinron merupakan hambatan dalam pariwisata Jepang namun juga mampu menjadi blessing in disguise jika pemerintah mampu memanfaatkannya. Adanya festival dan acara-acara yang merupakan bagian dari pelestarian budaya juga mampu dijadikan daya tarik untuk inbound tourism. Meski begitu, inbound tourism Jepang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi signifikan karena adanya Nihonjinron. Namun dengan adanya upaya untuk mengembangkan pemahaman bersama antara wisatawan asing dan negara secara keseluruhan, diharapkan citra Jepang sebagai negara yang berjarak dan tidak ramah bagi wisatawan asing akan mampu berubah menjadi lebih baik kedepannya. Permasalahan globalisasi dan lokalisasi tak berhenti pada terbuka atau tertutupnya budaya dan sistem masyarakat setempat. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, proses globalisasi turut memberikan ruang dan kesempatan bagi aktor asing untuk terlibat di dalam pembangunan dan pembangunan sektor pariwisata lokal. Hal tersebut dapat berupa investasi untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, hingga sektor jasa di bidang transportasi dan akomodasi turis untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi turis. Keberadaan atraksi internasional pun turut berperan dalam menarik perhatian wisatawan asing untuk mengunjungi sektor pariwisata lokal. Aktor internasional dalam hubungan ini tentunya diharapkan dapat turut serta membangun sektor pariwisata lokal, dalam hal pembukaan lapangan kerja dan pengembangan aktor pariwisata lokal dengan melibatkan masyarakat lokal untuk menyambut kedatangan para turis yang diprediksikan meningkat. Akan tetapi, hal yang terjadi di lapangan pun tak selamanya demikian. Ini terkait dengan hegemoni aktor internasional yang memiliki capital lebih besar dibandingkan dengan aktor lokal dan berujung pada kerugian akibat tidak dilibatkannya aktor lokal dalam pengembangan pariwisata setempat. Salah satu contohnya adalah perayaan MTV Europe Music Award di Edinburg. 6 Pada November 2003 Edinburg menjadi tuan rumah ajang kebudayaan terbesar yang pernah diadakan di Skotlandia: MTV Europe Music Award Edinburg03. Secara sederhana, gelaran ini diharapkan bisa melibatkan banyak penduduk lokal. Apalagi hal itu juga didorong oleh para pemimpin politik dan para pengelola sektor publik di Skotlandia. Bukan tanpa alasan, sebab ajang ini menjadi kesempatan besar bagi sektor pariwisata dan kreatif Skotlandia untuk unjuk diri yang berpotensi menarik audiens global sekira satu miliar orang. MTV memegang posisi sentral di dunia budaya anak muda bercakupan global. Namun sayangnya, Edinburg03 tidak berjalan sesuai dengan harapan penduduk Skotlandia. Alih-alih bisa menarik keterlibatan banyak penduduk lokal, justru ajang ini tetap memakai penyelenggara global yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa dibilang MTV EMA pada 2013 terkesan hanya meminjam tempat dengan pelaksanaannya yang berat sebelah. Dampaknya, di media massa lokal, Edinburg03 mendapatkan sorotan besar berimpresi negatif. Surat kabar Skotlandia membaca kekecewaan penyelenggara lokal dan mengamati hubungan antara pekerja lokal dengan pihak MTV. Konflik antara para elite lokal dengan penduduk terkait pemilihan simbol utama identitas budaya sebagai indikator yang dianggap merepresentasikan dan dianggap atraktif pun menjadi salah satu bukti buruknyaketerbukaan Edinburg03. Namun, tensi yang lebih tinggi memang ditunjukkan lewat ketegangan antara MTV dan penyelenggara lokal. Ketidakseimbangan antara penyelenggara lokal dan penyelenggara global (pemilik event) menunjukkan bahwa inisiator acara ini kadang kala kehilangan kontrol tentang gambaran dasar penyelenggaraan.Pun tidak tercapainya kesepahaman bersama terkait maksud pemilihan lokasi serta definisi program televisi yang baik versi MTV. Di sisi lain, dengan ekonomi global yang pengarah pada penataan ulang struktur serta mendorong terjadinya deindustrialisasi, dan aturan yang diterbitkan guna mengatur kebijakan finansial, kota-kota di seluruh dunia kini berlomba-lomba untuk mendapatkan investasi ke dalam, wisatawan, serta pelayanan yang lebih baik. Apalagi istilah realisme baru (new realism) 4 membuat pemerintah kemudian memperkenalkan kota sebagai sebuah lingkungan yang dinamis untuk tinggal, bekerja, serta mencari hiburan. Kota yang memiliki imej buruk maupun yang memperoleh sedikit sorotan tidak akan dipertimbangkan dalam kompetisi itu. Maka, semakin jelas bahwa awalnya Edinburg03 diharapkan mampu memberikan exposure besar. Tidak hanya secara imej global, namun juga pemberdayaan masyarakat lokal di gelaran internasional. 4 Hughes, G, Urban revitalisation: The use of festive time strategies, Leisure Studies, 1999, pp. 119–135. 7 Edinburg saat ini masih terus berbenah untuk mencapai tujuan ekonomi dan kebangkitan kebudayaan. Di perjalanannya, langkah tersebut dibantu oleh Parlemen Skotlandia, arus dari para profesional muda, investasi swasta dalam bentuk bar serta restoran, ledakan pembangunan, mendorong pasar dengan meletakkan para retailer di sekitar pusat kota, hingga menyematkan reputasi sebagai sebuah kota festival.5 Penelitian ini menganalisis isu kontemporer yang sudah terjadi dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengapresiasi tingkat pentingnya dan kompleksitas dari kondisi kontekstual ajang Edinburg03—terkait hubungan antara event dan organisasi yang terlibat di dalamnya—, Gavin Reid juga mengadopsi beragam metode lain. Penelitian ini dimulai dengan mengikuti literatur yang berhubungan dengan politik lokal, ekonomi lokal, konteks politik, serta MTV. Kenyataannya, memang ada keuntungan ekonomi secara langsung yang diterima oleh Edinburg dari keputusan MTV untuk menyelenggarakan ulang tahun EMA ke-10. Antara lain tingkat okupansi hotel di kota diperkirakan 8000 kamar pada saat pekan event berlangsung—yang disebut menghasilkan £4 juta. Namun itu adalah keuntungan tak langsung yang dirasakan oleh pemerintah. Sedangkan penyelenggara lokal di posisi tidak diuntungkan sebab tidak banyak dilibatkan. Padahal, promosi Edinburg yang sepaket dengan penyelenggaraan EMA jauh lebih efektif untuk menjangkau wisatawan muda potensial dibandingkan melalui pemasaran pariwisata konvensional. Sumber resmi ELTB mempercayai bahwa dengan pemilihan Edinburg, MTV telah mendorong kota tersebut secara instan untuk menjadi tujuan wisata utama bagi generasi muda. Usaha kontemporer itu bahkan dianggap sepadan dengan usaha lima tahun melalui pemasaran cara tradisional. MTV EMA juga berpotensi untuk menyingkirkan label lama Edinburg sebagai “the Athens of the North”. Masalah kembali membesar ketika mulai banyak suara yang beranggapan bahwa MTV EMA seperti layaknya sirkus yang tidak memberikan keuntungan. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang justru tidak mendapatkan tiket untuk acara puncak. Padahal sudah terjadi antrian pembelian tiket—bahkan ada yang sampai 24 jam antrioffline. Ternyata, tiket untuk lokal jumlahnya sangat terbatas pun nomor hotline pemesanan hanya disediakan satu jalur. Sponsor lokal pun tidak mendapat jumlah tiket yang memadai. Sangat bertolak belakang dengan sponsor besar global—American Express, Vodafone Live, Replay Blue Jeans, Footlocker—yang memperoleh alokasi sangat besar. 5 Watson, J. Back to the future. Scotland on Sunday, 30th November 2003. 8 MTV kemudian mencoba mengatasi kekisruhan tersebut dengan menggelar konser “thank you” yang ditujukan bagi penduduk lokal. Tujuannya supaya mereka yang tidak bisa menghadiri puncak acara bisa merasakan pengalaman perayaan yang sama. Namun kenyataannya, hal itu tidak sepadan. Konser “thank you” terkesan setengah hati dan asal ada. MTV kemudian juga mencoba untuk menebus kesalahannya dengan menyediakan slot promosi di salurannya. MTV meneyediakan kesempatan lewat program 30 menit bernama “Come to Scotland” yang diulang-ulang di saluran MTV selama beberapa hari menjelang penyelenggaraan. Tidak mengejutkan, dengan nama yang sudah populer serta tekanan perusahaan, langkah-langkah yang diambil oleh MTV menarik terlalu banyak kritikan. Kebanyakan kritikan yang dilayangkan menyebut bahwa ajang ini hanya menggunakan kerangka global, namun mengabaikan realitas lokal. Seorang sejarawan asal Leith menyebut MTV EMA sebagai “bukan ajang” dan “30 detik kilasan di panci” dengan “penduduk lokal harus membayar untuk ke pesta di mana mereka tidak diundang”. Dia melihat bahwa event ini diselenggarakan hanya untuk MTV. Penyelenggaraan event semacam ini senada dengan pendapat Fredline, dkk tentangpotensi ketidakpuasan ketika tema yang diangkat tidak sesuai dengan sosio-kultural dari komunitas setempat.6 Juru bicara Partai Konservatif bidang kebudayaan menyebut bahwa ajang ini seharusnya diadakan di bulan saja, sejauh perhatian yang diberikan untuk masyarakat Edinburg. Dia melihat bahwa MTV tidak menginginkan masyarakat lokal untuk dekat-dekat. Sedangkan konselor dari Partai Demokrat menyatakan bahwa MTV tidak bisa membawa sebuah event seperti ajang penghargaan ke Edinburg kalau kemudian mengeksklusikan warga lokal. Terlepas dari berbagai kritik yang menjelaskan bahwa MTV Europe Music Awards Edinburg03 semacam pagelaran sirkus, jurnal ini sebenarnya juga melihatnya sebagai salah satu andil dalam membentuk Edinburg sebagai kota paling terkemuka di Eropa utara per 2015. Bukti-bukti yang sudah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara kerangka lokal dan realitas global sangatlah kompleks. Kasus ini menyoroti bagaimana penggunaan subsidi publik dan pengiriman inklusi sosial tidak fokus terhadap sektor lokal. Sebaliknya, dasar pemikiran yang dominan untuk menarik acara yang global, namun tidak memperhitungkan seberapa besar kontribusinya terhadap pariwisata Edinburgh. 6 Fredline, L., Jago, L., & Deery, M, The development of a generic management scale to measure the social impact of events. Event Management, 2002, pp. 23–37. 9 Konflik antara elit lokal dan penduduk mengenai simbol identitas budaya sebagai indikator daya tarik lokal (Hughes, 1999) tampak jelas dalam acara ini. Tetapi, ketegangan terjadi antara MTV dan penyelenggara lokal lebih dari itu. Ketidakseimbangan kekuatan antara panitia lokal dan pemilik acara global dimaksudkan sebelumnya kadang-kadang kehilangan kontrol atas gambaran besar yang diharapkan dari acara tersebut, menghasilkan ketegangan antara tempat niat pemasaran mereka dan definisi MTV sebagai televisi yang baik. Bukti ketegangan antara penyelenggara dan penduduk lokal atas gambar identitas budaya digunakan dalam acara-acara (Hughes, 1999) kemudian memperpanjang ketegangan antara panitia lokal dan pemilik acara global. Terbukti ketika penyelenggara lokal dan representatif MTV tidak mampu menentukan hasil akhir apa yang diharapkan. Penyelenggara lokal jelas melihat gelaran ini untuk memperoleh posisi di dunia internasional sebagai sebuah kota yang patut difavoritkan sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan global, pemberdayaan masyarakat, dan menaikkan pasar investasi. Pemerintah melihat bahwa naiknya popularitas Edinburg sebagai pemimpin destinasi wisata di Eropa turut dipengaruhi oleh jasa MTV dengan cara yang tidak konvensional sehingga menarik wisatawan dari generasi muda—yang condong pada obsesi terhadap para selebritas. Sikap MTV yang hanya melibatkan sedikit masyarakat lokal dalam penyelenggaraan event-nya memang sudah masuk ke kontrol editorialnya. Meskipun, apabila keterlibatan ini bisa diperluas, akan mampu menciptakan momen yang bisa dikenang oleh para anak muda yang terlibat, pun keuntungan jangka panjang membutuhkan inklusif publik lokal yang lebih besar dalam konteks penyelenggaraan di suatu kota. Apabila hal itu timpang, sebuah kerangka event lokal yang berdasarkan strategi pariwisata serta imej pemasaran, digabungkan dengan realitas global dalam televisi milik MTV, selebritas, serta pemasaran itu sendiri, inklusif masyarakat lokal akhirnya termaginalkan. Posisi lainnya yang juga berperan dalam isu global lokal terkait MTV EMA Edinburg03 ini adalah kehadiran media lokal yang secara terus menerus melakukan bombardir bernada kritis. Di sini, kontrol informasi dari MTV diposisikan sebagai antagonis oleh surat kabar lokal yang sudah terlanjur marah karena alokasi tiket bagi perusahaan sponsor global lebih banyak dan diutamakan dibanding buat masyarakat setempat. Laporan bernada negatif dari surat kabar lokal menyebut bahwa terlepas dari kekuatan realitas global MTV EMA, himpunan media massa lokal melihat adanya agenda politik di baliknya. Kritik lain yang berasal dari daerah Leith menganggap bahwa ajang yang telah terselenggara hanya 10 memberi keuntungan bagi MTV, bintang pop global, elite politik lokal, serta pemodal, bukan penduduk lokal. Globalisasi, Hegemoni, dan Interdependensi dalam Pariwisata Kerangka teori yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan fenomena pariwisata di era global adalah dengan memahami bagaimana globalisasi bekerja dengan situasi internasional yang memiliki hubungan hierarkhis antara aktor global yang juga menjadi sebuah hegemon dengan aktor di pihak lokal. Jika dipandang secara umum, teori hegemoni dan globalisasi merupakan dua teori yang berasal dari dua perspektif yang berbeda, dimana teori hegemoni sangat erat kaitannya dengan realisme, begitu pula globalisasi dengan perspektif liberalisme. Peter M. Burns mengatakan bahwa yang disebut dengan hegemoni ialah adanya instrumen yang digunakan oleh aktor yang mendominasi untuk melakukan persuasi terhadap aktor lain dalam praktik sistem politik dan sosio ekonomi. Sedangkan mengenai globalisasi beliau menyatakan bahwa kata globalisasi sendiri mulai terkenal ketika tahun 1980an yang menurut sebagian ahli telah mendorong dunia kedalam sistem neoliberal. 7 Globalisasi seringkali diasosiasikan dengan adanya peningkatan di sektor transportasi, komunikasi dan teknologi informasi dan adanya perubahan dalam manajemen organisasi dan perusahaan. Dalam dunia pariwisata, kita bisa melihat teori hegemoni dengan cara memahami bagaimana sejarah konsep hegemoni itu sendiri. Eksisnya kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang mendorong terciptanya keadaan dimana beberapa negara memiliki kekuatan yang lebih dan negara tersebut senantiasa berusaha untuk menjaga bahkan menambah power yang mereka punya. Hegemoni sendiri pada awalnya dilihat dari sisi keamanan, dimana negara dengan kualitas militer terbaik dan memenangkan perang cenderung memiliki bargaining position yang lebih kuat dari negara lainnya. Namun seiring berjalannya waktu dan berakhirnya perang dunia II, ada aspek-aspek lain yang muncul dan turut mempengaruhi hegemoni negara, antara lain ekonomi, politik dan sosio-kultural. Hadirnya organisasi internasional seperti World Bank dan WTO menurut teori hegemoni merupakan salah satu upaya negara-negara maju untuk mempertahankan powernya, terbukti dengan adanya sistem voting yang ditentukan oleh banyaknya insentif yang diberikan oleh masih-masing negara anggota. Dengan adanya sistem ini, negara-negara maju yang notabene sudah memiliki ekonomi yang stabil dapat memberikan insentif yang lebih 7 P. M. Burns & M. Novelli, Toourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities, Elsevier, Amsterdam, 2007, p. 177. 11 banyak. Selanjutnya, negara-negara maju dapat “menyetir” organisasi internasional tersebut agar kebijakan yang diterapkan sejalan dengan kepentingan negara tersebut. Apabila dihubungkan dengan dunia pariwisata, kita tidak bisa mengabaikan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan untuk menambah pemasukan negara. Sementara di sisi lain, negara berkembang yang sudah engage dengan organisasi internasional seperti WTO dan World Bank memang bisa mengembangkan dunia pariwisatanya dengan menggunakan insentif dari organisasi internasional tersebut, namun demi mendapatkan bantuan tersebut bukan tanpa syarat. Negara berkembang harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dalam organisasi internasional tersebut, yang dalam kalimat lain bisa juga disebut “sudah dibuat oleh negara-negara maju”. Sebagian ahli menyatakan bahwa dunia pariwisata juga bisa dijadikan lahan investasi oleh negara-negara maju. 8 Hal ini menjadi logis jika kita mengingat adanya bisnis transportasi antar negara, travel organizer, dan lain-lain. kebijakan yang dibuat dalam pariwisata global mendorong negara-negara untuk membuka pariwisata seluas-luasnya, dengan pemberlakuan barrier seminimal mungkin. Hegemoni atas negara berkembang dalam hal pariwisata dapat kita lihat melalui 3 kerangka kerja. Pertama yaitu melalui kacamata kultural, bahwasanya hegemoni dari negaranegara maju menyebarkan adanya kultur baru dalam masyarakat yang dikenal dengan nama “Davos Culture Lifestyle”. Kultur Davos ini bisa kita identifikasi dengan adanya perubahan masyarakat yang mulai melihat suatu isu melalui pemikiran-pemikiran/paradigma barat. Kultur ini kemudian mendorong adanya permintaan yang semakin tinggi pada dunia pariwisata.Framework kedua adalah melalui kacamata politik, dimana implementasinya adalah melalui usaha mempeengaruhi kebijakan di organisasi internasional dengan outcome adanya kebijakan yang sesuai dengan keinginan negara maju. Framework yang ketiga yaitu ekonomi, framework ini lebih melihat pariwisata dari perspektif pemilik modal/bisnis, yang kemudian mendorong adanya tourism supply.9 Di sisi lain, globalisasi juga turut andil dalam memberikan dinamika terhadap pariwisata dunia. Pada dasarnya, globalisasi sendiri masih memiliki hubungan dengan teori hegemoni. Menurut Burns dan Novelli, ada hubungan yang linear antara terjadinya hegemoni dan globalisasi. Ketika negara maju telah berhasil membuat hegemoni diatas negara lain, maka ia akan dengan mudah melakukan globalisasi paham yang mereka inginkan, yang 8 P. M. Burns & M. Novelli, Toourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities, Elsevier, Amsterdam, 2007, p. 177 9 P. M. Burns & M. Novelli, p. 182. 12 kemudian sejalan dengan kepentingan nasionalnya.10 Globalisasi ini diiringi dengan adanya perkembangan dalam berbagai sektor seperti transportasi, komunikasi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang memudahkan transfer nilai-nilai dari negara maju ke negara berkembang. Dengan begitu, pada tahan globalisasi, negara maju semakin mudah menguatkan pondasipondasi hegemoninya dengan cara yang lebih halus atau tidak memerlukan penggunaan senjata. Problematika yang terjadi antara globalisasi dalam dunia pariwisata sendiri adalah adanya ketidakcocokan dengan paham “lokalisasi”. Dalam beberapa kasus kita akan menemukan adanya ketidakselarasan antara tuntutan globalisasi dengan realita kultur yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh yaitu Jepang yang memiliki kultur lebih cenderung tertutup dan tidak menyuai adanya kedatangan turis asing tentu mempengaruhi pariwisata Jepang itu sendiri. Dengan sikap masyarakat Jepang tersebut, ada diskriminasi dan pelayanan yang tidak maksimal terhadap turis asing, yang berawal dari adanya perbedaan kultur. Dari sini, kita bisa melihat bahwasanya harus ada adaptasi antara masyarakat dengan globalisasi. Ketika negara memang menginginkan adanya peningkatan dalam sektor pariwisata, pemerintah harus bisa menjamin bahwa masyarakatnya memang sudah siap untuk menerima nilai-nilai yang berbeda dari masyarakat asing. Dalam kasus lain, ketika kita membayangkan bahwa globalisasi dapat meningkatkan sektor pariwisata lokal, dalam beberapa kasus kita justru akan menemukan sebaliknya, bahwasanya globalisasi mematikan sektor pariwisata lokal. Seperti yang telah disebutkan dalam pengadaan acara MTV EMA di Edinburgh, terjadi clash antara adanya nilai globalisasi dengan keinginan untuk memperkenalkan local wisdom. Satu pihak yaitu penyelenggara MTV EMA memanfaatkan organizer lain yang bukan dari wilayah Edinburg itu sendiri, sehingga dalam perspektif masyarakat Edinburg, MTV EMA hanya meminjam tempat tanpa bisa memberikan nilai positif pada pariwisata di Edinburg. Harapan pertama dari masyarakat Edinburg adalah ketika acara tersebut akan diadakan di wilayah mereka, maka mereka akan bisa memperkenalkan budaya-budaya dan keunggulan pariwisata di Edinburg, namun harapan itu harus pupus karena kebijakan dari penyelenggara MTV EMA. Disini kita bisa melihat bagaimana globalisasi dalam hal ini adalah tuntutan masyarakat akan modernisasi dan teknologi yang serba canggih tidak selalu bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat dan ingin diangkat oleh masyarakat setempat tersebut. 10 P. M. Burns & M. Novelli, p. 178. 13 Akan tetapi, kita juga perlu melihat bahwa sesungguhnya hubungan antara globalisasi dengan pembangunan sektor pariwisata lokal tidak lepas dari hubungan ketergantungan atau interependensi antara aktor global seperti turis asing dan juga MNC terhadap sektor dan aktor pariwisata di tingkat lokal dan nasional. Interdepensi ini pula yang kami yakini mampu menjelaskan mengapa hubungan zero-sum yang terjadi dalam kasus Jepang dan Edinburg yang telah dijelaskan sebelumnya juga terjadi di banyak tempat. Teori Interdependensi disini merupakan sebuah teori yang lahir dari perspektif liberalis yang terdapat dalam hubungan internasional. Pertama kali diperkenalkan oleh Harold H. Kelley (1921-2003) dan John W. Thibaut (1917-1986) di dalam buku berjudul The Social Psychology of Groups developed in Interpersonal Relations: A Theory of Interdependence (1978), mulanya teori ini berfokus pada perilaku interaksi sosial antarindividu, namun berkembang lebih luas menjadi hubungan antarnegara. Menurut Mohtar Mas’oed, interdepedensi adalah sebagai kontak atau pertukaran (exchange) diantara bangsa – bangsa yang imbul akibat tindakan suatu pemerintah dan sebagian oleh pemerintah lain. Pengertian interdepedensi ini bersifat positif, karena bisa membuka suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan di era globalisasi.11 Interdependensi menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif dan menguntungkan bagi pihak – pihak yang berinteraksi di dalamnya.12 Aktor transnasional menjadi semakin penting dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Saling ketergantungan mengacu pada situasi yang di karakteristikkan dengan timbal balik antar aktor negara yang berbeda, efek ini merupakan hasil dari transaksi internasional, yaitu aliran arus barang, uang, manusia, dan informasi yang melewati batas – batas negara. Dalam bidang pariwisata dan interdependensi, menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata semestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1)Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya. (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi. (4) Pemerataan kesejahtraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi. (5) Penghasil devisa. (6) Pemicu perdagangan international. (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan R. Lynch, ‘What is Globalization?,’ Global Strategy (daring), 2014, <http://www.globalstrategy.net/what-is-globalization/>, diakses 7 Maret 2016 12 S. Kagan, ‘The Two Dimensions of Positive Interdependence,’ Kagan Online (daring), 2007, <http://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/299/The-Two-Dimensions-of-PositiveInterdependence>, diakses 4 Maret 2016 11 14 profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi. 13 Dengan demikian, di era globalisasi ini akan sangat sulit melepaskan faktor internasional dengan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata lokal. Penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa faktor internal (domestik) memiliki andil dalam melahirkan situasi interdependensi. Pariwisata menjadi sektor yang dikembangkan oleh negara-negara yang berkembang sejak beberapa dekade terakhir, dan ditandai dengan kemunculan negara-negara non-Barat yang berpartisipasi aktif dalam pariwisata internasional. Motivasi utama suatu negara mempromosikan pariwisata adalah peningkatan perekonomian, terutama bagi negara berkembang yang menjadikan industri pariwisata sebagai sarana untuk melakkan pembangunan. Hal ini dikarenakan pariwisata berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang akan didapatkan oleh negara, baik negara tuan rumah ataupun negara asal turis. Besarnya interdependensi pariwisata terlihat dari data World Tourism Organization pada tahun 2000, dimana 698 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US dollar. 14 Gabungan dari pendapatan pariwisata internasional dengan pendapatan transportasi yang menghasilkan lebih dari 575 juta US dollar, dan membuat pariwisata menjadi penghasil ekspor terbesar di dunia diikuti oleh produk otomotif, bahan kimia, minyak bumi, dan makanan. Interdependensi di sektor pariwisata terjadi akibat meningkatnya interaksi antarnegara di era globalisasi. Setiap negara memiliki keunggulan pariwisata masing-masing, baik itu berupa resources, akses, ataupun kecanggihan di bidang teknologi. Keunikan di satu negara yang mungkin tidak ditemui di negara lain, seperti budaya dan kebiasaan masyarakatnya juga akan menarik minat turis dari negara lain untuk datang ke negara tersebut. Interdependensi tersebut akan mengarah pada hubungan kerjasama antarnegara di sektor pariwisata. Kerjasama pariwisata memungkinkan bagi negara-negara untuk menghasilkan barang dan jasa secara langsung dan tidak langsung, menarik mata uang asing, menarik tenaga kerja, dan memberi peluang investasi asing. Hal tersebut penting bagi negara untuk mengembangkan perekonomian. Dampak positif dari interdependensi pariwisata antarnegara bagi negara tuan rumah antara lain adalah membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata dan 13 R. Utama, Pengantar Industri Pariwisata, Deepublish, Yogyakarta, 2014, p.6. P. Keller, Tourism Development After the Crises: Global Imbalances-Poverty Alleviation, Die Deutsche Nationalbibliothek, Berlin, 2011, p.47. 14 15 dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal. Negara penerima turis juga mendapatkan devisa (national balance payment) melalui pertukaran mata uang asing (foreign exchange). Meningkatnya interdependensi yang mendorong turis dari suatu negara datang ke negara lain mendorong masyarakat negara penerima turis untuk berwirausaha di bidang yang berkaitan dengan pelayanan pariwisata, contohnya pedagang kerajinan, penyewaan papan selancar, pemasok bahan makanan dan bunga ke hotel, dan lain-lain. Bidang lain seperti hotel dan resetoran sebagai tempat yang tidak dapat dipisahkan dari turis yang melakukan perjalanan wisata juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka dapat melihat berbagai kemungkinan, misalnya wisatawan yang pergi berwisata bersama keluarganya memerlukan kamar yang besar dan makanan yang lebih banyak dibanding turis yang bepergian seorang diri. Sementara dampak ekonomi tidak langsung dapat dirasakan oleh pedagang-pedagang di pasar karena permintaan terhadap barang (bahan makanan) akan bertambah. Di sisi lain, terdapat dampak negatif interdependensi negara di bidang pariwisata. Pertama, beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu (terror, penyakit, konflik, dan lain sebagainya). Begitu pariwisata mengalami penurunan, langsung atau tidak langsung hal itu akan menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi secara berantai. Kedua, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. permintaan barang konsumsi juga meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Selain itu, dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata akan memicu harga tanah di sekitar lokasi tersebut sampai harga yang tidak masuk akal. Ketiga, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor barang-barang yang di perlukan dalam pariwisatasehingga produksi lokal tidak terserap. Hal ini disebabkan karena wisatawan sebagai konsumen dating dari belahan geografis dengan pola makandan menu yang penuh berbeda dengan masyarakat lokal. Mereka juga memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang sangat berbeda sehingga kebutuhannya pun sangat berbeda. Pariwisata bersifat musiman, tidak dapat di prediksikan dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Pariwisata kelihatan hidup pada bulan-bulan tertentu (musiman) sehingga pendapatan dari ekonomi paiwisata juga mengalami fluktasi. Konsekuensinya, pengembalian modal investasi juga tidak dapat di pastikan waktunya. Akibatnya terjadi ketimpangan daerah dan memburuknya kesenjangan pendapatan 16 antara beberapa kelompok masyarakat. Hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Ditambah lagi negara tujuan wisata juga harus menanggung timbulnya biaya-biaya tersembunyi (hidden cost), khususnya yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam. 15 Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculnya limbah yang besar, polusi, transportasi, dan sebagainya yang memerlukan biaya untuk perbaikannya. Negara juga harus siap menanggung degradasi budaya lokal karena kebudayaan asing masuk ke dalam negaranya. Biaya tambahan juga harus ditanggung negara untuk menunjang pelayanan terhadap turis yang datang, negara meningkatkan impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang digunakan untuk memberikan pelayanan bermutu pada wisatawan dan juga biaya-biaya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada. Permasalahan yang timbul akibat interdependensi antarnegara di sektor pariwisata adalah seringkali keuntungan yang didapatkan negara maju jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang, padahal negara berkembang lebih membutuhkan keuntungan ekonomi yang didapat dari pariwisata untuk melakukan pembangunan, memperoleh pendapatan tambahan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi warganya. Industri pariwisata bertumbuh dalam mekanisme pasar bebas sehingga seringkali destinasi pada negara berkembang hanya menjadi obyek saja, hal lainnya pengembangan pariwisata memang telah dapat meningkatkan kualitas pembangunan pada suatu destinasi namun akibat lainnya seperti peningkatan hargaharga pada sebuah destinasi terkadang kurang mendapat perhatian dan korbannya adalah penduduk lokal. Kerugian akibat interdependensi pariwisata yang harus ditanggung oleh negara berkembang biasanya diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap pariwisata dalam negeri, kesalahan kebijakan. Dengan begitu pemerintah dituntut untuk menerapkan kebijakan pariwisata yang tepat bagi negaranya, apakah akan memilih untuk menerapkan kebijakan inbond tourism, yaitu menarik turis masuk ke negaranya ataukah outbond tourism, yaitu mengirim turis dari negaranya untuk berwisata ke negara lain. Keterkaitan antara interdependensi aktor lokal dan internasional di era globalisasi ini perlu kita kaji secara seksama, terlebih dengan situasi dimana saat ini negara-negara di Asia Tenggara telah memasuki era Asean Economic Community yang baru saja dimulai pada 31 Desember 2015. AEC ini menandakan telah dibukanya gerbang liberalisasi perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Setiap masyarakat nantinya bebas untuk melakukan 15 D. Lusseau, ‘The Hidden Cost of Tourism: Detecting Long-term Effects of Tourism Using Behavioral Information,’ Ecology and Society (daring), 12 Januari 2004, <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art2/>, diakses 5 Maret 2016. 17 kegiatan ekonomi di seluruh negara anggota ASEAN. Dengan adanya Asean Economic Community ini setiap negara kemudian dituntut untuk bisa menggali potensi yang dimilikinya agar dapat bertahan dari derasnya arus liberalisasi. Sektor Pariwisata yang menjadi salah satu poin dalam blueprint ASEAN Economic Community ini, kemudian harus menjadi perhatian serius semua negara di Asia Tenggara. Mengingat Asia Tenggara merupakan salah satu destinasi favorit para wisatawan internasional. Tercatat bahwa jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara-negara Asia Tenggara terus mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 8,3%. 16 Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata yang baik di antara negara-negara anggota Asean yang lain diharapkan dapat memanfaatkan peluang liberalisasi ini. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki pertumbuhan pariwisata yang cukup pesat. Menurut World Economic Forum (WEF) daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat 70 pada tahun 2013. 17 Hal inilah yang menurut Pemerintah Indonesia indonesia harus memanfaatkan kesempatan di dalam MEA ini. Namun terbukanya kesempatan tersebut, sekaligus menimbulkan sebuah dilema bagi indonesia, terutama sektor pariwisata. Salah satu yang dihadapi pariwisata Indonesia adalah kurangnya tenaga kerja yang terdidik serta terampil. Karena dalam MEA ini juga disepakati mekanisme Mutual Recognition Agreement on Tourism Profesional yang disepakati di Bangkok 9 November 2012. Dimana dengan adanya kebijakan ini para tenaga kerja yang tercatat sebagai penduduk negara Asia Tenggara bisa dengan bebas bekerja di negara Asia Tenggara yang lain. 18 Menurut data, Indonesia saat ini memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 122,38 Juta, dan 41% diantaranya adalah tenaga kerja yang hanya memiliki pendidikan setingkat SD.19 Padahal dalam mekanisme MEA ini mobilitas penduduk di negara Asia Tenggara sangat cepat. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan bebas visa bagi para wisatawan ASEAN yang berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN. Hal ini pastinya menuntut peningkatan kapasitas para pekerja di bidang pariwisata Indonesia, dalam rangka menunjang sektor pariwisata di Indonesia. 16 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, ‘Siaran Pers Pelatihan SDM,’ Kemenpar, (daring) 17 Febuari 2016, <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?id=3111 > 17 Hazliansyah, ‘Berpotensi Besar, Pariwisata Indonesia Harus Ambil Peluang Dalam MEA,’ republika, (daring) 19 Agustus 2014, <http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/14/08/19/najmafberpotensi-besar-pariwisata-indonesia-harus-ambil-peluang-pada-mea> diakses 7 Maret 2016. 18 Y. Fukunaga, Assessing the Progress of Asean MRAs On Professional Service, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Maret 2015. 19 N. Fernandez,’ Harus Bersaing di ASEAN, 47% Angkatan Kerja Lulusan SD,’ solopos, (daring), 3 Januari 2016, <http://www.solopos.com/2016/01/03/mea-2016-harus-bersaing-di-asean-47-angkatan-kerjaindonesia-lulusan-sd-676992> diakses 7 Maret 2016. 18 Menurut Menteri Pariwisata Indonesia, saat ini Indonesia masih membutuhkan tenaga kerja terdidik di bidang pariwisata sebesar 4 Juta jiwa tenaga kerja di bidang pariwisata sampai tahun 2019. Karena pada tahun 2019 Indonesia membutuhkan 13 Juta Jiwa tenaga kerja terdidik.20 Tenaga kerja ini dinilai sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata indonesia. Karena jika kita bandingkan pariwisata Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya Indonesia berada di posisi ke-5 dengan nilai 4,0.21 Jika Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia berada dua tingkat di bawahnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa aspek. Dari tingkat sumber daya manusia Indonesia hanya memiliki poin sebesar 5,0. Dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia di bidang pariwisata ini. Pada tahun 2014 Indonesia membangun Gerakan Akselerasi Sertifikasi Tenaga Kerja di bidang pariwisata. Dengan menekankan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Gerakan Sertifikasi ini menargetkan agar pada tahun 2019 mencapai 250.000 tenaga kerja yang memiliki sertifikasi Asean.22 Dari kasus tersebut bias dikatakan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia belum siap menghadapi AEC. Khususnya dari sumber daya masyarakat Indonesia yang secara kualitas masih kalah dengan Negara-negara asia tenggara yang lain. Keterbukaan akses yang mudah untuk masyarakat Asia Tenggara dengan adanya AEC ini tentu akan membuat faktor-faktor lokal dalam negeri berubah jika tidak bisa disikapi dan diserap oleh masyarakat lokal itu sendiri. Terlebih di bidang pariwisata, dengan adanya AEC ini masyarakat lokal mau tidak mau siap tidak siap harus dapat menjaga karakter yang kuat dan berkompetensi, sehingga akan dapat menjaga sustainability-nya. Selain itu, seperti yang diungkapkan pada teori Globalisasi menurut buku Tourism and Politics : Global Frameworks and Local Realities karangan P.M Burns dan M. Novelli bahwa Globalisasi ini diiringi dengan adanya perkembangan dalam berbagai sektor seperti transportasi, komunikasi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang memudahkan transfer nilai-nilai dari negara maju ke negara berkembang, memaksa pemerintah untuk melakukan langkah-langkah agar eksistensi masyarakat lokal tidak luntur akan adanya kemudahaan dalam era global. R. Rinaldi,’ Menteri Arif: Indonesia Kekurangan Tenaga Kerja Pariwisata,’ Tribun News, (daring), 26 November 2014, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/26/menteri-arief-indonesia-kekurangantenaga-kerja-bidang-pariwisata> diakses 7 Maret 2016. 21 S, Latif,’ 10 Keunggulan Wisata Malaysia dari Indonesia: Sebanyak 14 Faktor Dari World Economic Forum,’ viva news, (daring), 4 Juni 2012, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/320516-11-keunggulanwisata-malaysia-dari-indonesia> diakses 7 Maret 2016. 22 Gerakan Akselerasi Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 20 19 Langkah-langkah yang sejauh ini sudah ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan memberikan softskill berupa Gerakan Akselerasi Sertifikasi Tenaga Kerja di bidang pariwisata. Sertifikasi ini mempunyai fungsi ganda, yakni akan memberikan proteksi kepada tenaga kerja pariwisata dalam negeri dari serangan tenaga kerja asing dan sekaligus memberikan dan meningkatkan rekognisi dalam persaingan kompetensi global. Dengan telah ditanda tangani skema sertifikasi ini, agar nantinya pihak-pihak yang bersangkutan segera melaksanakan sertifikasi kompetensi pariwisata dengan kualifikasi ASEAN karena dalam tool box ASEAN telah dilengkapi dengan perangkat asesmen, bagi lembaga pelatihan dan pendidikan dapat segera menerapkan skema ini sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum sehingga akan memastikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Hal ini dimaksutkan untuk peningkatan kualitas SDM masyarakat lokal agar mampu bersaing dengan masyarakat global yang telah dipermudah dengan adanya AEC. Meskipun langkah ini tidak secara instan didapatkan hasilnya, namun dengan adanya program dari pemerintah ini setidaknya pemerintah telah membantu masyarakat lokal untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean. Dalam beberapa kasus kita akan menemukan adanya ketidakselarasan antara tuntutan globalisasi dengan realita kultur yang ada dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut tentu dibutuhkan dukungan dari pemerintah serta partisipasi aktif dalam masyarakat agar tenaga-tenaga kerja masyarakat lokal nantinya tidak tergeser oleh tenaga-tenaga dari luar negeri yang akan bersaing dalam MEA. Dengan demikian, sektor pariwisata lokal Indonesia di era globalisasi ini tidak akan tergerus oleh hegemoni aktor lokal dan terus mampu berkembang menjadi sektor pariwisata yang bertingkat internasional. 20 Daftar Pustaka Buku Befu, H., Hegemony of homogeneity, Trans Pacific Press, Melbourne, 2001. Cooper, M., Jankowska, R., & Eades, J., ‘The Politics of Exclusion? Japanese Cultural Reactions and the Government’s Desire to Double Inbound Tourism,’ dalam Burns, P.M. & Novelli, M. (eds.), Tourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities, Elsevier, Oxford, 2007, pp. 71-82. Fredline, L., Jago, L., & Deery, M, The development of a generic management scale to measure the social impact of events. Event Management, 2002. Fukunaga, Y. Assessing the Progress of Asean MRAs On Professional Service, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Maret 2015. Hughes, G, Urban revitalisation: The use of festive time strategies, Leisure Studies, 1999. Giampiccoli, A. ‘Hegemony, Globalisation and Tourism Policies in Developing Countries’, dalam Burns, P.M. & Novelli, M. (eds.), Tourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities, Elsevier, Oxford, 2007, pp. 175-192. Keller, P. Tourism Development After the Crises: Global Imbalances-Poverty Alleviation, Die Deutsche Nationalbibliothek, Berlin, 2011. Leiper, Neil. Tourism System: An Interdisciplinary Perspective. Department of Management Systems, Business Studies Faculty, Massey University, Palmerston North, New Zealand, 1990. Mathiesen, A. dan Wall, G. Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts. Harlow: Longman. 1982. Reid, G. ‘The MTV Europe Music Awards Edinburgh03: Delivering Local Inclusion?’, dalam Burns, P.M. & Novelli, M. (eds.), Tourism and Politics: Global Frameworks and Local Realities, Elsevier, Oxford, 2007, pp. 263-278. Utama, R. Pengantar Industri Pariwisata, Deepublish, Yogyakarta, 2014. Watson, J. Back to the future. Scotland on Sunday, 30th November 2003. Artikel Daring Fernandez, N.’ Harus Bersaing di ASEAN, 47% Angkatan Kerja Lulusan SD,’ solopos, (daring), 3 Januari 2016, <http://www.solopos.com/2016/01/03/mea-2016-harusbersaing-di-asean-47-angkatan-kerja-indonesia-lulusan-sd-676992> diakses 7 Maret 2016. 21 Hazliansyah, ‘Berpotensi Besar, Pariwisata Indonesia Harus Ambil Peluang Dalam MEA,’ republika (daring), 19 Agustus 2014, <http://www.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/14/08/19/najmaf-berpotensi-besar-pariwisata-indonesia-harus-ambilpeluang-pada-mea> diakses 7 Maret 2016. Kagan, S. ‘The Two Dimensions of Positive Interdependence,’ Kagan Online (daring), 2007, <http://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/299/The-TwoDimensions-of-Positive-Interdependence>, diakses 4 Maret 2016. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, ‘Siaran Pers Pelatihan SDM,’ Kemenpar, (daring) 17 Febuari 2016, <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?id=3111 > Latif, S. ’ 10 Keunggulan Wisata Malaysia dari Indonesia: Sebanyak 14 Faktor Dari World Economic Forum,’ viva news, (daring), 4 Juni 2012, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/320516-11-keunggulan-wisata-malaysia-dariindonesia> diakses 7 Maret 2016. Lusseau, D. ‘The Hidden Cost of Tourism: Detecting Long-term Effects of Tourism Using Behavioral Information,’ Ecology and Society (daring), 12 Januari 2004, <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art2/>, diakses 5 Maret 2016. Lynch, R. ‘What is Globalization?,’ Global Strategy (daring), 2014, <http://www.globalstrategy.net/what-is-globalization/>, diakses 7 Maret 2016. Rinaldi, R.’ Menteri Arif: Indonesia Kekurangan Tenaga Kerja Pariwisata,’ Tribun News, (daring), 26 November 2014, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/26/menteri-arief-indonesia-kekurangantenaga-kerja-bidang-pariwisata> diakses 7 Maret 2016. 22