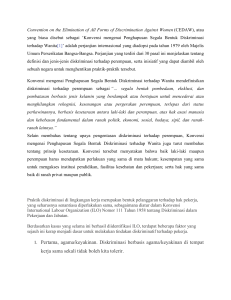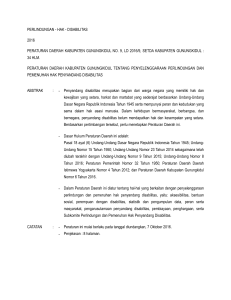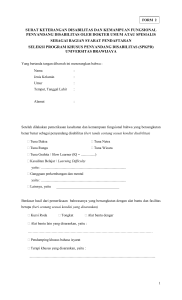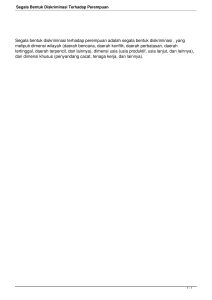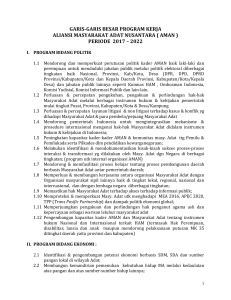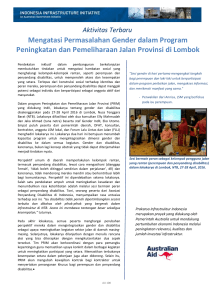BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang menguji ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menimbulkan perdebatan serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Pasal 433 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yang dalam praktiknya merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang dianggap tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, terjadi perubahan mendasar dalam paradigma perlindungan hukum terhadap individu dengan disabilitas mental atau intelektual. Secara historis, pengaturan mengenai pengampuan memiliki akar pada sistem hukum perdata Eropa Kontinental, khususnya Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, yang diadopsi ke dalam KUHPerdata Indonesia sejak zaman kolonial. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan individu yang secara medis atau mental tidak mampu mengurus dirinya sendiri, sekaligus melindungi pihak ketiga dalam hubungan hukum perdata. Namun, pengaturan ini sering kali dipandang diskriminatif karena mengategorikan individu dengan keterbatasan mental sebagai subjek hukum yang tidak cakap tanpa mempertimbangkan kemampuan aktualnya. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo menyatakan bahwa pengampuan terhadap penyandang disabilitas mental harus sejalan dengan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Putusan ini secara substantif menggeser pendekatan dari model "substitusi pengambilan keputusan" (substitute decision-making) menuju model "pendukung pengambilan keputusan" (supported decision-making). Namun, dari sudut pandang akademis, terdapat beberapa kritik yang patut diajukan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Pertama, meskipun perlindungan hak asasi merupakan prinsip fundamental, pendekatan yang diambil MK berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi individu yang benar-benar tidak mampu mengambil keputusan secara sadar. Kedua, putusan tersebut belum secara memadai mengatur mekanisme implementasi model pendukung pengambilan keputusan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Akibatnya, terdapat kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat praktik peradilan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara kritis implikasi putusan MK tersebut terhadap perlindungan hukum bagi orang yang berada di bawah pengampuan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum perdata Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak, termasuk penyandang disabilitas mental.