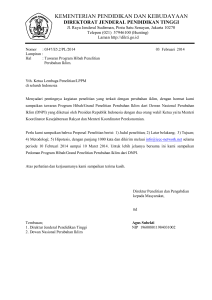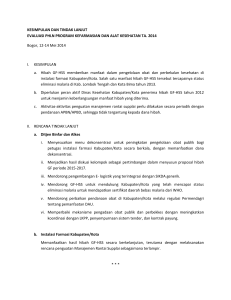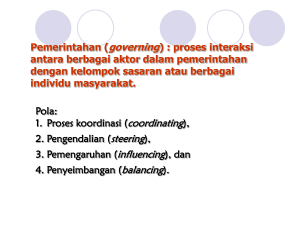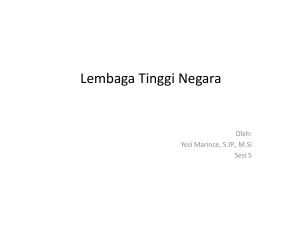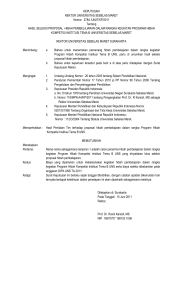rancangan undang-undang tentang perjanjian internasional
advertisement

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL
BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di
era
globalisasi
dimana
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
berkembang dengan pesat, interaksi dan interdependensi antar negara
semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya interaksi tersebut,
meningkat
pula
kerjasama
internasional
di
berbagai
bidang
yang
dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional yang mengikat
para pihak. Ini berarti semua pihak dengan itikad baik harus bersungguhsungguh melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional
yang
telah
disepakati
bersama.
Tidak
dilaksanakannya
perjanjian
internasional oleh suatu pihak dapat berakibat timbulnya gugatan oleh
pihak lain.
Sebagai
melaksanakan
bagian
dari
hubungan
masyarakat
internasional
internasional,
dan
Indonesia
membuat
juga
perjanjian
internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek
hukum internasional lainnya. Agar perjanjian internasional sejalan dengan
kepentingan nasional, memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat
bagi rakyat, maka perlu diatur dalam suatu undang-undang (UU). Sampai
saat ini UU yang mengatur mengenai perjanjian internasional adalah UU
No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mulai berlaku
pada tanggal 23 Oktober 2000.
Pada saat dibentuknya UU No. 24 Tahun 2000, UUD Tahun 1945
baru mengalami dua kali perubahan. Dalam UUD Tahun 1945 Perubahan
Pertama (1999) dan Kedua (2000), Pasal 11 yang menjadi landasan yuridis
pembentukan UU No. 24 Tahun 2000 tidak mengalami perubahan.
Rumusan Pasal 11 tetap seperti semula, yang berbunyi ”Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Sedangkan dalam UUD
Tahun 1945 Perubahan Ketiga (2001) dan Keempat (2002), Pasal 11
mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 ayat, yang rumusan lengkapnya
adalah sebagai berikut:
2
(1) ”Presiden
dengan
persetujuan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian ineternasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur
dengan undang-undang.”
Sebagaimana dikemukakan oleh I Wayan Partiana, ada beberapa
catatan yang dapat dikemukakan dari Pasal 11 UUD Tahun 1945
Perubahan Ketiga dan Keempat tersebut, diantaranya adanya kriteria
perjanjian internasional yang harus membutuhkan persetujuan DPR.1 Pasal
11 UUD Tahun 1945 Perubahan Ketiga dan Keempat seharusnya juga
menjadi landasan yuridis dalam pembentukan UU yang mengatur mengenai
perjanjian internasional.
Permasalahan lain dari perjanjian internasional adalah tidak semua
perjanjian internasional memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Ada beberapa perjanjian internasional yang dianggap oleh sebagian
kalangan masyarakat dapat menyengsarakan rakyat. Misal, berbagai
perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh Pemerintah baik secara
bilateral maupun multilateral seperti ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free
Trade Area, ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area, dan Indonesia-Japan
Partnership.2
Baca: I Wayan Partiana, Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian
Internasional,
Jurnal
Hukum
Internasional,
isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5308460487.pdf –, hal. 473.
2 Baca: Edy Burmansyah (Peneliti Institute for Global Justice), FTA dan UU Perjanjian
Internasional, “Globalisasi”, www.unisosdem.org/article_detail.php?... –.
1
3
Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan
bebas tersebut menyebabkan rakyat dihadapkan kepada perdagangan
bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari luar
negeri di pasar domestik tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Hal
ini tentu akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang sangat
berat bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000,
perjanjian
internasional
di
bidang
ekonomi
dan
perdagangan
tidak
termasuk di dalam kategori yang harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Akibatnya, perjanjian
perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dianggap berada
di dalam ranah eksekutif yang pengesahannya cukup melalui Keputusan
Presiden (Kepres).
Dalam praktiknya, selama ini juga telah terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2000. Pagu pinjaman luar negeri yang
disetujui
oleh
DPR
bersamaan
dengan
disahkannya
UU
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap secara otomatis adanya
persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri. Hal ini tidak
sesuai dengan maksud UU No. 24 Tahun 2000. Persetujuan DPR terhadap
UU
APBN
tidak
identik
dengan
pengesahan/ratifikasi
perjanjian
internasional oleh DPR. UU APBN bukanlah UU mengesahkan/ratifikasi
suatu perjanjian internasional, melainkan UU untuk menyetujui rencana
pemerintah untuk melakukan pinjaman. Sedangkan pengesahan/ratifikasi
adalah lembaga hukum ketatanegaraan tentang pengesahan oleh legislatif
atas perbuatan hukum pemerintah sesuai dengan hukum perjanjian
internasional.3
Beberapa permasalahan tersebut menandakan adanya kelemahan
atau kekurangan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 2000 dalam mengatur
mekanisme pembuatan atau pun pengesahan perjanjian internasional. Hal
ini dikhawatirkan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional
kurang
memberikan
manfaat
yang
maksimal
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Damos Dumoli Agusman, Beberapa Perkembangan Teori dan Praktik di Indonesia tentang
Hukum Perjanjian Internasional, e-library.kemlu.go.id/index.php?...65%3Aapa-perj... –.
3
4
B. Identifikasi Masalah
Penggantian terhadap UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2011. Dalam Lampiran
Keputusan DPR RI No. 02B/DPR/II/2010-2011 tanggal 14 Desember 2010
penggantian Undang-Undang ini terdapat di urutan nomor 37, yang Naskah
Akademik dan draft awal RUU penggantiannya disiapkan oleh DPR RI.
Untuk
itu,
berdasarkan
Surat
Ketua
Badan
Legislasi
Nomor
63/BALEG/DPR RI/V/2010 perihal dukungan teknis administratif dan
keahlian pada Badan Legislasi tanggal 24 Mei 2010 dan sesuai Rapat
Koordinasi Deputi Perundang-Undangan tanggal 22 Desember 2010 dengan
agenda membicarakan tugas pendampingan perancangan undang-undang
dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011, dibentuk Tim Penyusun
Naskah Akademik dan draft awal RUU tentang Penggantian UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan disebutkan bahwa Rancangan UndangUndang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah
Akademik.
Naskah
Akademik
adalah
naskah
hasil
penelitian
atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu
Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.4 Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang akan
dimuat dalam NA RUU Penggantian UU No. 24 Tahun 2000 ini adalah:
1. Bagaimana definisi atau pengertian perjanjian internasional yang tepat
agar tidak ada multitafsir antara perjanjian internasional yang bersifat
publik dan yang bersifat privat?
Lampiran I angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.
4
5
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penggantian
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional?
3. Materi-materi perjanjian internasional apa saja yang pengesahannya
harus memerlukan persetujuan DPR?
4. Bagaimana
mekanisme
pembuatan
dan
pengesahan
perjanjian
internasional agar perjanjian internasional sejalan dengan kepentingan
nasional dan tidak merugikan daerah yang terkena dampak perjanjian
internasional?
5. Bagaimanakah materi muatan RUU tentang Penggantian atas UU No. 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional?
A. Tujuan dan Kegunaan
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka
tujuan penyusunan Naskah Akademik (NA) ini adalah sebagai berikut:
1. menguraikan mengenai pengertian perjanjian internasional.
2. menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan
RUU tentang Penggantian atas UU No. 24 Tahun 2000.
3. menganalisis
materi-materi
perjanjian
internasional
yang
pengesahannya harus dengan persetujuan DPR.
4. menganalisis
mekanisme
pembuatan
dan
pengesahan
perjanjian
internasional yang baik agar sejalan dengan kepentingan nasional dan
tidak merugikan daerah yang terkena dampak perjanjian internasional.
5. merumuskan materi muatan RUU tentang Penggantian atas UU No. 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Adapun kegunaan dari penyusunan NA ini adalah sebagai acuan atau
referensi dalam menyusun dan membahas RUU tentang Penggantian atas
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang tercantum
dalam
daftar
Prolegnas
2011
–
2014
RUU
Prioritas
Tahun
2011.
Penggantian UU tentang Perjanjian Internasional ini akan menjadi landasan
hukum
yang
kuat
dan
menjadi
pedoman
dalam
pembuatan
dan
pengesahan perjanjian internasional sehingga perjanjian internasional
benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
6
C. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis
penelitian
yang
digunakan
dalam
penyusunan
Naskah
Akademik ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis
normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan
dengan meneliti data sekunder.5 Penelitian dilakukan dengan meneliti
ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional yang ada di
dalam
peraturan
perundang-undangan,
konvensi/perjanjian
internasional, dan literatur terkait. Sedangkan sifat penelitian yuridis
normatif ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan
atau gejala-gejala lainnya6.
2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data
Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dan data
primer. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena
dikeluarkan oleh lembaga/pihak yang berwenang, meliputi antara
lain, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan konvensi.
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya membahas bahan
hukum
primer,
seperti:
buku-buku,
artikel,
makalah,
laporan
penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.7 Data sekunder
tersebut diperoleh dari perpustakaan, internet, surat kabar, seminar,
dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang
bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya
dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan8.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
hal. 24.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, 1984, hal. 10.
7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta,1998, hal.103-104.
8
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hal. 103-104.
5
7
Untuk mendukung data sekunder diperlukan data primer yang
diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan berpedoman
pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
Adapun para pihak yang diwawancara adalah para pejabat/pegawai
Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Aceh, anggota DPRD
Kalimantan Barat dan Aceh, dan para akademisi. Disamping itu, data
juga
diperoleh
dengan
mengadakan
diskusi
internal
dengan
pejabat/pegawai Kementerian Luar Negeri, akademisi, dan praktisi.
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2011, sedangkan penelitian ke
daerah dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus 2011.
Adapun daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi
Kalimantan Barat dan
Provinsi Aceh. Pertimbangan pemilihan
Provinsi Kalimantan Barat didasarkan antara lain pada karakteristik
wilayah Provinsi ini sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga Malaysia, yang memiliki kesepakatan Sosek Malindo
atau Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia, dan didasarkan pula pada
adanya kesepakatan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU)
Sister City antara pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah
Yang Mei Taiwan
Sedangkan pertimbangan pemilihan Provinsi Aceh sebagai lokasi
penelitian adalah adanya MoU antara Pemerintah RI dengan Gerakan
Aceh
Merdeka
(GAM)
atau
perjanjian
perdamaian
yang
ditandatangani di Helsinki. Selain itu, terjadinya bencana tsunami
yang menarik perhatian berbagai donor internasional.
8
4. Teknik Penyajian dan Analisis Data
Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif.
Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada,
kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun
teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan
masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas
hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi
meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.9
Sedangkan
rumusan
sifat
regulasi
preskriptif,
yang
bahwa
diharapkan
penelitian
untuk
mengemukakan
menjadi
alternatif
penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturan mengenai
perjanjian internasional di masa yang akan datang.
9
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, cetakan kedua (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), hal. 22.
9
BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. TEORI PERJANJIAN INTERNASIONAL
Dari awal berkembangnya hukum internasional, hukum perjanjian
internasional pada mulanya tumbuh dan berkembang dalam bentuk
hukum
kebiasaan
internasional
(international
customary
law)
yang
kemudian oleh masyarakat internasional diformulasikan dalam bentuk
hukum
tertulis
yang
berupa
konvensi-konvensi
atau
perjanjian
internasional. Hukum kebiasaan internasional pada dasarnya terbentuk
oleh praktik yang sama yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya
subyek hukum internasional yang menentang, dan diikuti oleh banyak
negara. Dengan cara demikian maka hukum kebiasaan internasional
tersebut terbentuk semakin kuat dan berlaku secara universal karena
diikuti oleh banyak negara di dunia.
Konvensi atau perjanjian internasional merupakan salah satu sumber
penting dalam hukum internasional. Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional
menentukan
bahwa
dalam
mengadili
suatu
perkara
Mahkamah sebaiknya menggunakan sumber hukum internasional10:
1. Perjanjian Internasional (International Conventions);
2. Kebiasaan Internasional (International Customs);
3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional (general principles of
international law); dan
4. Keputusan Pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui
kepakarannya (Judicial teachings of the most high qualified publicist).
Konvensi-konvensi tersebut dapat berbentuk bilateral bila yang
menjadi pihak hanya dua negara, dan berbentuk multilateral bila yang
menjadi pihak lebih dari dua negara. Dalam praktiknya terdapat juga
10
Lihat, Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional,
Alumni, Bandung, Edisi Kedua, 2003 hlm 113-116 ; Urutan penyebutan dalam Pasal
38 tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya mana yang paling utama atau
terpenting karena tidak ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 38 tersebut. Pada
praktiknya antara sumber hukum yang satu dengan yang lain saling mengisi. Yang
dapat diklasifikasikan adalah bahwa sumber hukum yang pertama sampai dengan
ketiga adalah sumber hukum utama, sedangkan sumber hukum yang keempat
merupakan sumber hukum tambahan (subsidiary means).
10
konvensi atau perjanjian internasional yang disebut regional bila yang
menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan misalnya ASEAN.
Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh
negara di dunia. Melalui perjanjian internasional tersebut, tiap subyek
hukum internasional menggariskan dasar kerjasama mereka dan mengatur
berbagai kegiatan yang akan disepakati. Dengan demikian perjanjian
internasional merupakan instrumen yuridis bagi masyarakat internasional
untuk menampung kehendak dan persetujuan untuk mencapai tujuan
bersama.
Pembuatan
perjanjian
internasional
merupakan
perbuatan
hukum dari subyek hukum internasional dan mengikat para pihak dalam
perjanjian tersebut.
Berdasarkan praktik-praktik dari hukum kebiasaan internasional,
masyarakat
internasional
berhasil
mengkodifikasikan
kaidah-kaidah
perjanjian internasional ke dalam dua konvensi yaitu :
Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional yang
Mengatur Perjanjian-Perjanjian Internasional Antar Negara dan Negara.
Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional Antara
Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional yang Mengatur
Tentang Perjanjian Internasional, Antara Organisasi Internasional dan
Negara, Ataupun Perjanjian Internasional Antara Sesama Organisasi
Internasional.
Pada dasarnya kedua konvensi tersebut mengatur tentang proses
atau tahap-tahap dalam pembuatan sampai dengan pengakhiran perjanjian
internasional yang secara garis besarnya dimulai dari tahap perundingan
(negotiation) untuk merumuskan naskah perjanjian, penerimaan naskah
perjanjian
(adoption
of
the
text),
pengotentikan
naskah
perjanian
(authentication of the text), persetujuan untuk terikat atau pengikatan diri
pada perjanjian (consent to be bound by treaty) yang dapat disertai dengan
pengajuan pensyaratan (reservation), mulai berlakunya perjanjian (entry into
force of a treaty), dan lain-lain. Indonesia sampai saat ini belum menjadi
negara pihak pada kedua Konvensi Wina tersebut, tetapi ketentuanketentuan yang terdapat di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman
dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain.
11
1. Teori Monisme dan Dualisme
Perjanjian kerjasama internasional
yang dibuat antara negara
dengan negara lainnya atau dengan organisasi internasional merupakan
perjanjian internasional dalam pengertian hukum internasional publik11.
Bagaimana
perjanjian
internasional
sebagai
norma
hukum
internasional diterapkan dalam hukum nasional persoalannya terletak pada
permasalahan bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum
nasional. Dalam hukum internasional, ada dua macam teori yang mencoba
untuk menerangkan hubungan hukum internasional dengan hukum
nasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme12. Menurut aliran
monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua
bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur
kehidupan manusia. Akibat pandangan monisme ini ialah bahwa antara
dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarki.
Karena adanya hubungan hirarki ini, maka timbul aliran monisme dengan
primat hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional.
Menurut monisme dengan primat hukum nasional, berlakunya
hukum internasional karena negara atau hukum negara itu menyetujui
berlakunya hukum internasional, dan karena hukum internasional itu
tidak lain merupakan kelanjutan hukum nasional. Di lain pihak, menurut
monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional mengatur
sesuatu karena diperbolehkan oleh hukum internasional. Menurut aliran
ini
hukum
nasional
membuat
peraturan
pelaksanaan,
dan
pada
hakekatnya tidak terjadi penciptaan hukum tersendiri oleh hukum
nasional. Pembuatan hukum nasional dianggap sebagai penerusan dan
penciptaan hukum internasional.
Sebaliknya, menurut aliran dualisme, hukum internasional dan
hukum nasional itu sama sekali terlepas satu sama lainnya karena masing11
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku-I Bagian Umum,
Bandung: Binacipta, 1977, hal. 42-43.
12
Sri Setianingsi Suwardi, Masalah-masalah Hukum Perjanjian Pinjaman Internasional,
Makalah pada Fakultas Pasca Sarjana Bidang Hukum Internasional UNPAJ, 1990, hal.
5.
12
masingnya mempunyai sifat yang berlainan. Menurut aliran dualisme ini,
daya pengikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara,
maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem
atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Dengan
perkataan lain, dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan
hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena pada
hakekatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak
tergantung satu sama lainnya tapi juga lepas satu dari yang lainnya.
Dengan
demikian,
hukum
internasional
hanya
berlaku
setelah
ditransformasikan dan menjadi hukum nasional13.
Dalam hal perjanjian internasional yang dilakukan antara subyek
hukum internasional publik yakni antara pemerintah Republik Indonesia
dengan negara lainnya, maka hukum yang dipakai adalah hukum
internasional publik, maka asas-asas hukum perjanjian internasional
publik berlaku pada perjanjian ini. Ini berarti bahwa asas-asas hukum
perjanjian internasional baik yang tertuang dalam Konvensi Wina tahun
1986 berlaku untuk perjanjian internasional tersebut.
2. Teori Delegasi
Menurut
teori
delegasi,
aturan-aturan
konstitusional
Hukum
Internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi Negara,
hak untuk menentukan: kapan ketentuan Perjanjian Internasional berlaku
dalam
Hukum
Internasional
Nasional
dan
dijadikan
cara
Hukum
bagaimana
Nasional.
ketentuan
Indonesia
Perjanjian
cenderung
menggunakan teori delegasi. Pengesahan yang dilakukan menurut Hukum
Nasional Indonesia, merupakan bagian prosedur ratifikasi dalam ranah
Hukum Nasional untuk memperoleh instrumen ratifikasi, yang diperlukan
prosedur
ratifikasi
dalam
ranah
Hukum
Internasional.
Ratifikasi
merupakan bagian prosedur pembentukan Hukum Internasional yang
dituangkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Keterikatan Indonesia
pada Perjanjian Internasional yang bersangkutan, dilandaskan pada
13
Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Translated by Anders Wedberg, New
York, Russel & Russel, 1973, hal. 123-124.
13
penyampaian instrumen ratifikasi dalam ranah Hukum Internasional.
Apabila
Indonesia
melaksanakannya
sudah
dengan
menjadi
itikad
Negara
baik
dan
pihak,
Indonesia
melakukan
wajib
penyesuaian
perundang-undangannya dengan Perjanjian Internasional yang sudah
berlaku secara definitif.14
3. Konsep one door policy
Dalam
pelaksanaan
perjanjian
kerjasama
internasional
Negara
merupkan entitas abstrak. Negara terbagi dalam berbagai kekuasaan yang
memiliki tugas dan tanggung jawab yang kesemuanya diatur dalam
konstitusi. Tidak bisa semua institusi negara melakukan hubungan dengan
subyek hukum internasional lainnya. Dalam kebiasaan yang diakui oleh
masyarakat internasional, negara yang memiliki Dalam suatu negara
ditentukan dalam konstitusi lembaga mana yang dapat melakukan
hubungan luar negeri atas nama negara tersebut. Ini penting agar hanya
ada satu pintu (one door policy) dan kebijakan bila pihak lain ingin
berhubungan dengan negara tersebut. Berdasarkan konsep yang dikenal
dalam hukum internasional, pemerintah pusat merupakan pemegang
kedaulatan suatu negara. Subyek hukum internasional lainnya akan
berhubungan dengan pemerintah pusat bila hendak melakukan hubungan
luar negeri. Hukum internasional tidak mengatur lembaga mana yang
dianggap sebagai pemerintah pusat. Ini diserahkan kepada masing-masing
konstitusi dan peraturan perundang-undangan suatu negara.15
Dalam konstitusi Indonesia yakni Pasl 11 ayat (1) UUD 1945
menyatakan:
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara
lain”.
Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan:
14
Mochtar Kusumaatmadja, “Pengantar Hukum Internasional: Buku I- Bagian Umum”, Bina
Cipta, Bandung, 1990, hlm. 65
15
Hikmahanto
Juwana, UU Hbungan Luar Negeri,:Konteks, Konsep pemikiran dan
pelaksanaannya selama ini, artikel Hukum pada Institut for legal and zonstitutional
goverment, 1 Maret 2010.
14
”Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan
satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum
internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban
untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik”. Lebih lanjut
terkait dengan peran pemerintah daerah, pada Pasal 5 ayat (1) UU tentang
Perjanjian Internasional menyebutkan: ”Lembaga negara dan lembaga
pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan
daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional,
terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana
tersebut dengan Menteri”16.
B. PRAKTIK EMPIRIS
1. Tinjauan Terhadap Defenisi Perjanjian Internasional
Mengenai terminologi atau istilah Perjanjian Internasional yang
dipakai oleh masyarakat internasional sampai saat ini dapat berupa
berbagai macam diantaranya traktat (treaties), konvensi (convention),
persetujuan (agreement), piagam (charter), protokol (protocol), nota
kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), dan sebagainya.
Terminologi-terminologi tesebut umumnya tidak mengurangi hak dan
kewajiban
yang
terkandung
di
dalamnya.
Suatu
terminologi
perjanjian internasional digunakan berdasarkan permasalahan yang
diatur dan dengan memperhatikan keinginan para pihak dalam
perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Boer
Mauna sebagai berikut:
“Penggunaan judul tertentu pada suatu perjanjian internasional
juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi perjanjian
tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya
dengan
perjanjian
internasional
lainnya,
atau
untuk
menunjukkan hubungan antara perjanjian internasional tersebut
16
Lihat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional.
15
dengan dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang
telah dibuat sebelumnya.”17
Defenisi
perjanjian
internasional
publik
harus
dibedakan
dengan perjanjian internasional yang bersifat privat atau dengan
kontrak/perjanjian
biasa.
Pemahaman
publik
tentang
apa
itu
perjanjian internasional juga sangat minim dan acapkali melihatnya
dari
segi
popular
yaitu
negara/transnasional.
Pemerintah
RI-GAM
perjanjian
Sebagai
2005
yang
contoh,
akan
bersifat
MOU
dimengerti
lintas
Helsinki
sebagai
batas
antara
Perjanjian
Internasional, MOU RI-Vietnam untuk jual beli beras dan MOU RIMicrosoft 2007 juga dipahami sebagai suatu perjanjian internasional.
Distorsi publik ini pulalah yang mendorong lahirnya klaim bahwa
Production Sharing Contracts (PSC) di bidang minyak dan gas oleh
Pemerintah RI adalah ”perjanjian internasional” sehingga memicu
adanya judicial review terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun
2007. Kasus judicial review ini merupakan kasus yang pertama dalam
jurisprudensi Indonesia yang mengangkat permasalahan teoritis
tentang hukum perjanjian internasional.
Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review
undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
memberikan penegasan dan batasan dan perbedaan yang jelas dalam
pembedaan tersebut. Dalam kasus ini yang menjadi permasalahan
adalah Pasal 11 ayat (2) yang berketentuan : “setiap kontrak
kerjasama yang sudah ditandatangani harus segera diberitahukan
secara tertulis kepada DPR RI” dianggap bertentangan dengan Pasal
11 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan “Presiden dalam membuat
perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan
Negara
dan/atau
mengharuskan
perubahan
atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR”.
17
DR. Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Global, Alumni Bandung, Cetakan ke-4, Bandung, hlm. 89.
16
Di dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan :
“Meskipun bunyi pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menyebut, „perjanjian
internasional lainnya
perjanjian
internasional
lainnya yang
menimbulkan akbiat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau
mengharuskan
perubahan
atau
pembentukan
undang-undang
harus dengan persetujuan DPR”. Kami dapat menyetujui pendapat
pemerintah dan ahli yang diajukan bahwa perjanjian internasionaln
yang dimaksud adalah perjanjian internasional sebagaimana
diartikan dalam pasal 1 dan 2 Konvensi WIna tahun 1969 tentang
Hukum perjanjian (Law of treaties) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a
Konvensi WIna tahun 1986 tentang perjanjian Internasional. Oleh
karenanya Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) undang-undang migas tidak termasuk perjanjian
internasional yang merupakan ruang lingkup pasal 11 UUD
1945…”.
Masalah definisi perjanjian internasional memang salah satu
issue kontroversi dalam literatur hukum perjanjian internasional.
Perdebatan sengit bahkan berlangsung pula dalam perumusan
definisi
ini
pada
Konvensi
Wina
1969
tentang
Perjanjian
Internasional. Menurut Konvensi ini, perjanjian internasional adalah:
“An International Agreement concluded between States and
International Organizations in written form and governed by
International Law, whether embodied in a single instrument or in
two or more related instruments and whatever its particular
designation”
Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang merumuskan
sebagai setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh
hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara,
organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain Dari
pengertian hukum ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang
17
harus dipenuhi oleh suatu dokumen untuk dapat ditetapkan sebagai
suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
yaitu:
an International Agreement;
by Subject of International Law;
in Written Form;
“Governed
by
International
Law”
(diatur
dalam
hukum
internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang
hukum publik);
Whatever Form.
Undang-Undang
Internasional
sendiri
No.
24
telah
Tahun
2000
menekankan
tentang
Perjanjian
bahwa
perjanjian
internasional yang menjadi lingkup Undang-Undang ini adalah hanya
perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang
diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan
kewajiban di bidang hukum publik dan bukan di bidang hukum
perdata. Namun praktik Indonesia tentang pembuatan perjanjian
internasional baik sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang
No. 24 Tahun 2000 tidak luput dari kerancuan ini. Sebelum lahirnya
Undang-Undang ini, semua dokumen sepanjang bersifat lintas
negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah Pemerintah RI,
diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam
”Treaty Room” Departemen Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat
Pemerintah RI dengan NGO juga dianggap sebagai perjanjian
internasional. Agreement yang dibuat oleh Pertamina and PT Caltex,
PT Stanvac and PT Shell juga pernah dianggap sebagai perjanjian
internasional dan bahkan diratifikasi melalui Undang-Undang No. 1
Tahun 1963.
Setelah lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, praktik di Indonesia telah menunjukkan
konsistensi tentang perjanjian namun masih terdapat kesulitan
tentang
pembedaan
yang
berkaitan
dengan
“Governed
by
18
International Law”, sehingga semua dokumen sepanjang dibuat oleh
Pemerintah RI dengan Subjek Hukum Internasional masih dianggap
sebagai perjanjian internasional sekalipun perjanjian itu tunduk pada
hukum nasional seperti “loan agreements”.
Dilihat dari kewenangannya, negara sebagai institusi publik,
dapat menjalankan kewenangannya sebagai institusi perdata dengan
melakukan suatu perdagangan internasional dengan negara lain.
Perjanjian suatu negara dengan subyek hukum lain dikategorikan
sebagai hukum perdata internasional apabila perjanjian tersebut
tunduk pada hukum nasional salah satu pihak dalam perjanjian.
Sebagai contoh, perjanjian pembelian tanah atau pembangunan
gedung atau transaksi lainnya yang dibuat mengacu pada hukum
setempat walaupun dilakukan oleh negara-negara dan organisasiorganisasi internasional bukan merupakan Perjanjian Internasional.18
Pembedaan secara tegas ini sangat penting dan diperlukan apabila
perjanjian yang bersifat ekonomi dan perdagangan dimasukkan ke
dalam
kategori
perjanjian
internasional
yang
memerlukan
pengesahan/ratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Meskipun dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional yang
berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan masuk ke dalam
kategori hukum perdata internasional, namun tidak dapat dipungkiri
bahwa
akibat
yang
dapat
ditimbulkan
dari
suatu
perjanjian
internasional di bidang ekonomi dan perdagangan juga dapat
berpengaruh strategis bagi masyarakat atau kepentingan bangsa,
sehingga pada dasarnya juga perlu dilakukan pengesahan dengan
undang-undang. Contoh, dengan keikutsertaan Indonesia di dalam
ASEAN Free Trade Area (AFTA) maka rakyat dihadapkan kepada
perdagangan bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para pelaku
ekonomi
dari
luar
negeri
di
pasar
domestik
tanpa
adanya
perlindungan dari pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh
dan memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
18
DR. Boer Mauna, Op.Cit, hlm. 88.
19
tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional di bidang
ekonomi dan perdagangan tidak termasuk di dalam kategori yang
harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia. Hal ini berakibat perjanjian perdagangan yang dilakukan
Indonesia dengan negara lain dianggap berada di dalam ranah
eksekutif yang pengesahannya cukup melalui Keputusan Presiden.
Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan terhadap
definisi Perjanjian Internasional dalam revisi Undang-Undang No.24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Terkait dengan definisi
Perjanjian Internasional tersebut, dari hasil pengumpulan data yang
dilakukan
di
Provinsi
Aceh
dan
Provinsi
Kalimantan
Barat
menegaskan, Pengertian PI hendaknya mengacu ke Konvensi Wina,
baik Konvensi Wina yang mengatur PI antar negara maupun Konvensi
Wina yang mengatur PI dengan organisasi internasional. Berpijak
pada Konvensi Wina tersebut maka perjanjian antara RI dengan Aceh
tidak dapat disebut PI. Begitupula perjanjian dengan korporasi
internasional (international corporation) juga bukan dalam lingkup
hukum internasional (bukan PI).
2. Surat Kuasa (Full Powers).
Full Power adalah kuasa penuh atau on behalf merupakan
salah satu kaidah hukum internasional yang menganggap tidak
semua warga negara dapat mewakili suatu Negara dalam pembuatan
hingga pengesahan perjanjian, karena hanya terdapat beberapa orang
dengan jabatan (amtenar) kenegaraanya yang mendapatkan kuasa
yang utuh untuk mewakili negaranya. Full power sebagaimana
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL Surat Kuasa (Full Powers)
adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang
memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili
Pemerintah
Republik
Indonesia
untuk
menandatangani
atau
menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk
20
mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal
lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
Kusa Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konferensi
Wina
1969:
Seseorang dianggap mewakili sesuatu Negara dengan maksud untuk
mengesahkan atau mengotentifikasi naskah dari suatu perjanjian
atau dengan maksud untuk menyatakan kesepakatan dari suatu
Negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian jika: Ia
memberikan surat kuasa penuh.
Selanjutnya Pasal 8 Konfrensi Wina 1969, pada intinya
menyatakan mereka yang mendapatkan kuasa penuh untuk mewakili
Negara adalah :
1) Kepala-kepala Negara, Kepala-kepala pemerintahan dan para
mentri luar negeri, dengan maksud untuk melaksanakan semua
tindakan
yang
berhubungan
dengan
pembuatan
perjanjian
Internasional yakni :
2) Kepala-kepala
perwakilan
diplomatic
dengan
maksud
untuk
mengesahkan naskah suatu perjanjian antara Negara yang
memberikan
akreditasi
dan
Negara
dimana
mereka
diakreditasikan;
3) Wakil-wakil yang diakreditasikan oleh Negara-negara pada suatu
konferensi internasional atau organisasi internasional, atau salah
satu badannya, dengan maksud untuk mengesahkan naskah dari
suatu perjanjian di konfrensi, organisasi atau badan tersebut.
Terkait
dengan
pemberian
surat
kuasa
tersebut,
dalam
Konvensi Wina tidak diatur teknis mengenai jangka waktu Surat
Kuasa, namun dari hasil pengumpulan data yang dilakukan yakni
hasil wawancara dengan Dosen Universitas Udayana dan Universitas
Syech Kuala menyatakan, tidak ada salahnya Indonesia mengatur
dalam RUU. Persoalan jangka waktu sebuah surat kuasa atau surat
kepercayaan, adalah hal teknis. Jangka waktu menyangkut dua hal,
yaitu (1) dalam hubungannya dengan pemerintah daerah yang akan
melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan
negara
21
lain, harus ada ketentuan yang mengikat menteri luar negeri untuk
mengeluarkan suarat kuasa bagi seorang kepala daerah setelah
kepala daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan. (berapa
lama surat kuasa itu dapat digunakan, apakah dapat digunakan
berulang-ulang. Kedua hal ini harus diatur dalam RUU yang baru.
Sebagai catatan bahwa kuasa jabatan sebagaimana dipangku oleh
seorang menteri keuangan misalnya, sangat berbeda pengertiannya
dengan kewenangan yang diterima oleh menteri keuangan melalui
sebuah surat kuasa untuk melakukan suatu perjanjian karena sifat
berlakunya dengan surat kuasa ada tenggang waktunya, yakni
selesainya sebuah perjanjian.
3. Peran Pemerintah Daerah
Terkait dengan peran daerah dalam pelaksanaan perjanjian
internasional khususnya dalam pembuatan perjanjian Internasional,
dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional menyebutkan :
”Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen
maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang
mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional,
ter1ebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai
rencana tersebut dengan Menteri“.
Dengan demikian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5
ayat (1) tersebut, menyimpulkan bahwa daerah yang mempunyai
rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu
melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut
dengan menteri. Dalam pembuatan perjanjian internasional yang
dilakukan oleh pemerintah, kewenangan atau yang menjadi pihak
dalam perundingan rancangan suatu perjanjian tersebut sesuai
dengan bunyi Pasal 5 ayat (4) adalah Menteri atau pejabat lain sesuai
dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.
Selain itu, daei aspek hukum internaional, Subyek Hukum
Internasional adalah Negara, dalam ha1 ini
perjanjian internasional,
22
Pemerintah Daerah meskipun dapat melaksanakan perjanjian atau
kerjasama internasional, tetapi kedudukannya tidak bisa dipandang
sebagaimana layaknya subjek hukum internasional. Tetapi lebih
merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat.
Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban
perjanjian internasional tetap berada di Pemerintah Pusat.
Terkait dengan keinginan daerah untuk dilibatkan dalam
pembuatan PI,
dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di
Universitas .... Provinsi Kalimantan Barat dan Universitas Syech
Kuala Provinsi Aceh, menyatakan, perlu ada kehati-hatian jika
hendak mengakomodir keinginan daerah tersebut dalam UU PI
karena daerah bukan subyek hukum yang memiliki kewenangan
untuk membuat PI (treaty making power). Daerah tidak bisa
dilibatkan secara langsung dalam pembuatan PI.
Namun peran
daerah perlu diatur secara jelas agar tidak terjadi lagi pengalaman
kasus yang telah lalu, misal: rencana Kalbar untuk mendatangkan
mobil bekas yang dituangkan dalam Perda dimentahkan oleh SK
Menteri Perdagangan yang mengakibatkan Perda tidak berlaku.
Kasus yang terbaru adalah mengenai tata gula. Meskipun hal
tersebut tidak dapat dibenarkan dimana produk legislasi (Perda)
dibatalkan oleh eksekutif (SK Menteri Perdagangan), hal tersebut
dapat dimaklumi karena merupakan mekanisme kontrol dari pusat
kepada daerah.
Dalam pembuatan PI, dunia internasional (negara pihak) akan
melihat konstitusi. Berdasarkan konvensi Montivideo yang mengatur
hak dan kewajiban negara, jika negara berbentuk negara kesatuan
maka yang memiliki kewenangan/kemampuan untuk melakukan
hubungan keluar adalah pemerintah pusat. Oleh karena itu, jika
daerah hendak membuat PI maka harus melibatkan pemerintah
pusat. Berbeda halnya dengan negara yang berbentuk federal, dimana
negara bagian ada yang diberi wewenang untuk membuat PI. Untuk
itu, ke depan agar tidak ada permasalahan lagi maka dalam kerangka
NKRI, perlu ada dialog dengan daerah dalam pembuatan PI agar
23
kebutuhan/keinginan
daerah
dapat
terakomodasi.
Sehubungan
dengan hal tersebut, untuk mengantispasi masalah maka perlu ada
”benang merah” antara UU PI dengan UU terkait, diantaranya UU
Hubungan Luar Negeri, UU Perubahan UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagainya. Jika
tidak ada benang merah maka apa pun yang dibuat dalam PI maka
akan timbul masalah di kemudian hari.
4. Pengesahan Perjanjian Internasional
a. Pasal 11 UUD 1945
Dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen dapat
dijumpai
suatu
ketentuan
pokok
yang
berhubungan
dengan
pembuatan perjanjian internasionkekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilanal. Ketentuan yang
dimaksud dituangkan dalam pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi :
“Presiden
dengan
persetujuan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain”.
Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1960 telah dikeluarkan
Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
2826/HK/60 yang isinya berbunyi sebagai berikut :17)
1. “ …………………
2. Menurut pendapat Pemerintah perkataan “perjanjian”
di dalam
pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan
Negara asing, tetapi hanya perjanjian-perjanjian terpenting saja,
yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya
dikehendaki berbentuk traktat (treaty). Jika tidak diartikan
demikian,
maka
Pemerintah
tidak
akan
mempunyai
cukup
keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional
17)
Syahmin AK, Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), Penerbit CV. Armico,
Bandung, Edisi ke-2, Agustus 1988, Lampiran II, Hal.269-271.
24
dengan
sewajarnya,
karena
tiap-tiap
perjanjian
walaupun
mengenai soal-soal yang kecil harus diperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan
internasional
dewasa
ini
demikian
intensifnya,
sehingga
menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang
membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar.
3. Untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama
antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
tertera dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar, Pemerintah akan
menyampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh
persetujuan
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
hanya
perjanjian-
perjanjian yang terpenting saja, (treaties) yang diperincikan
dibawah, sedangkan perjanjian yang lain (agreements) akan
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk
diketahui.
4. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas
Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang harus
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat
persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden ialah perjanjianperjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung
materi sebagai berikut :
a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi
haluan politik luar negeri Negara seperti halnya dengan
perjanjian-perjanjian
persahabatan,
perjanjian-perjanjian
persekutuan (alliansi), perjanjian-perjanjian tentang perobahan
wilayah atau penetapan tapal batas.
b. Ikatan-ikatan
yang
sedemikian
rupa
sifatnya
sehingga
mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara; dapat terjadi
bahwa
ikatan-ikatan
sedemikian
dicantumkan
di
dalam
perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut
sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-
25
undang,
seperti
soal-soal
kewarganegaraan
dan
soal-soal
kehakiman.
Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang
lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh
Presiden.
Dari Surat Presiden tersebut, keikutsertaan DPR seperti
dimaksudkan Pasal 11 UUD 1945, mencakup :
a. Soal-soal politik atau yang akan mempengaruhi politik luar negeri
RI, antara lain :
1) perjanjian persahabatan;
2) perjanjian persekutuan;
3) perjanjian tentang perubahan wilayah;
4) perjanjian kerja sama ekonomi dan teknik;
5) perjanjian pinjaman uang;
b. Soal-soal yang menurut UUD 1945 dan peraturan perundangundangan harus diatur oleh Undang-undang.
c. Soal-soal yang menurut
Undang-undang diatur dalam bentuk
traktat (treaty).18)
Sedangkan perjanjian yang mengandung materi yang lain yang
lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan
hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. Didalam
praktek pembedaan antara traktat dan persetujuan (agreement) dapat
dilihat bahwa traktat memerlukan persetujuan DPR dan bentuk
yuridis persetujuan ini dalam bentuk Undang-undang. Sedang dalam
hal persetujuan DPR hanya diberitahu dan bentuk yuridis ratifikasi
persetujuan dalam bentuk KEPPRES atau kadang-kadang tanpa
ratifikasi.19)
18)
Bagir Manan, Kekuasaan Presiden Untuk Membuat, Memasuki dan Mengesahkan Perjanjian/Persetujuan,
Majalah Universitas Padjajaran No. 3-4, Jilid XVI, 1998. Hal.14.
19)
Sri Setianingsih Suwardi, Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya Dengan Pasal 11 UUD
1945, Makalah Pada Lokakarya “Perjanjian RI dengan Negara Lain serta Ratifikasi oleh DPR RI”, di DPR, 10
Juni 1993. Hal. 15.
26
Ratifikasi sebenarnya adalah suatu metode pengecekan oleh
parlemen mengenai apakah utusan negara yang ditugaskan untuk
berunding dalam suatu perjanjian internasional tidak keluar dari
instruksi. ”Ratifikasi ini dianggap perlu dan penting karena :
Perjanjian itu umunya menyangkut kepentingan dan mengikat
masa depan Negara dalam hal-hal tertentu karena itu harus
disahkan oleh kekuasaan Negara tertinggi.
Untuk
menghindari
kontroversi
antara
utusan-utusan
yang
berunding dengan pemerintah yang mengutus mereka.
Perlu adanya waktu agar intansi-instansi yang bersangkutan
dapat mempelajari naskah yang diterima.
Pengaruh
Parlementer
yang
mempunyai
wewenang
untuk
mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif.”19
Selain
berdasarkan
penandatangan
dan
Ratifikasi,
suatu
perjanjian internasional juga dapat tunduk dan mengikat bagi suatu
negara meskipun bukan sebagai negara peserta dari perjanjian
internasional tersebut melalui cara Aksesi. Yang dimaksudkan
dengan Aksesi disini adalah pernyataan suatu negara yang bukan
peserta
dari
perjanjian
internasional
untuk
tunduk
terhadap
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional
tersebut. Umumnya Aksesi ini dilakukan dengan cara mengirimkan
piagam
Aksesi
ke
negara
penyimpan
untuk
kemudian
memberitahukan kepada negara-negara peserta lainnya.20
Tindakan internasional lain yang lazim dilakukan oleh negaranegara pada saat pembuatan Perjanjian Internasional adalah dengan
mengajukan suatu Pensyaratan (Reservation) terhadap klausul dari
suatu ketentuan dalam perjanjian internasional. Apabila Pensyaratan
tersebut diterima maka negara bersangkutan tidak tunduk terhadap
ketentuan dari pasal yang diajukan Pensyaratan tersebut. Umumnya
19
20
DR. Boer Mauna, Op.Cit, hlm. 118.
Mengenai Aksesi Konvensi Wina 1969 mengaturnya di dalam Pasal 15 yang
menyatakan bahwa Aksesi dapat dilakukan apabila : 1.Perjanjian itu sendiri secara
jelas menyatakan hal tersebut, 2.Bila terbukti Negara-negara yang ikut berunding
menginginkan demikian.
27
Pensyaratan ini diajukan pada waktu penandatanganan, Ratifikasi,
ataupun pada saat Aksesi. Terhadap Pensyaratan ini pada praktiknya
menimbulkan beberapa kesukaran yaitu keseragaman perjanjian
menjadi tidak terjaga karena Pensyaratan suatu negara berbeda-beda
dengan negara lain. Integritas perjanjian internasional juga menjadi
tidak terjamin karena sulit untuk diketahui pasal-pasal mana yang
berlaku atau tidak berlaku bagi suatu negara. Namun meskipun
demikian, praktik Penysaratan ini masih kerap dilakukan dan diakui
oleh masyarakat internasional.21
Mengenai keterikatan atau tunduknya suatu Negara pada
perjanjian
internasional
mengandung
dua
aspek
yaitu
aspek
eksternal dan internal. Aspek eksternalnya adalah negara itu
memikul kewajiban dan menerima hak dari perjanjian internasional
tersebut.
Sedangkan
aspek
internalnya
adalah
perjanjian
internasional itu masuk dan berlaku sebagai bagian dari hukum
nasionalnya. Yang dimaksud dengan aspek internal disini adalah
dampak atau pengaruh dari masuknya perjanjian internasional itu ke
dalam hukum nasional terhadap hukum atau peraturan perundangundangan nasional negara yang bersangkutan yang substansinya ada
hubungannya
dengan
substansi
dari
perjanjian
internasional
tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengharmonisasian atau
penyelarasan substansi dari perjanjian internasional tersebut dengan
substansi dari hukum atau peraturan perundang-undangan terkait.
b. Masalah Ruang Lingkup Pengesahan
Perjanjian tentang Pinjaman/Hibah menurut pasal 10 huruf f
Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
harus mendapat pengesahan/diratifikasi dengan Undang-Undang
dan menurut penjelasan pasal ini akan diatur secara khusus dalam
21
Mengenai Pensyaratan diatur di dalam Konvensi Wina 1969 di dalam Pasal 19 yaitu :
suatu Negara waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, atau aksesi dapat
mengajukan Pensyaratan terhadap suatu Perjanjian kecuali; 1.Pensyaratan dilarang
oleh perjanjian, 2.Pensyaratan tertentu dimana tidak termasuk Pensyaratan yang
dilarang, 3.Pensyaratan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian.
28
Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara menegaskan kembali prinsip perlunya
persetujuan DPR ini sehingga dalam pasal 23 ayat (1) menyatakan
“Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau
menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan
persetujuan DPR. Namun perlu ditekankan bahwa persetujuan DPR
dalam
konteks
Undang-Undang
APBN
tidak
identik
dengan
pengesahan/ratifikasi dengan Undang-Undang (oleh DPR) seperti
yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional.
Undang-Undang APBN bukanlah Undang-
Undang untuk mengesahkan/ratifikasi suatu perjanjian internasional
melainkan Undang-Undang untuk menyetujui rencana pemerintah
untuk melakukan pinjaman. Di lain pihak pengesahan/ratifikasi
adalah lembaga hukum ketatanegaraan tentang pengesahan oleh
legislatif atas perbuatan hukum pemerintah RI sesuai dengan Hukum
Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, perbuatan Pemerintah RI
yang menandatangani suatu perjanjian disahkan dengan UndangUndang
(dengan
demikian
melalui
persetujuan
DPR)
sehingga
Indonesia secara resmi, berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang
Perjanjian Internasional, terikat pada perjanjian itu. Sedangkan
pengertian persetujan DPR pada Undang-Undang APBN bukanlah
mengesahkan perjanjian yang sudah ditandatangani melainkan
menyetujui
rencana
pemerintah
untuk
melakukan
pinjaman.
Persetujuan DPR pada Undang-Undang APBN adalah terhadap
perjanjian yang akan dan belum ditandatangani oleh Pemerintah RI
sedangkan persetujuan dalam konteks pengesahan/ratifikasi adalah
terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani. Dengan demikian,
secara juridis formal, adanya persetujuan DPR dalam APBN tidak
dapat meniadakan persyaratan ratifikasi sebagaimana ditetapkan
oleh pasal 10 huruf f Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, kecuali secara tegas dinyatakan dalam UU
lainnya.
29
Dalam praktiknya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.
2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri yang pada hakekatnya mengatur tentang Naskah Perjanjian
Pinjaman atau Hibah Luar Negeri. Menurut pasal 15 Peraturan
Pemerintah
tersebut,
wewenang
penandatanganan
Perjanjian
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri berada pada Menteri Keuangan.
Pada
Peraturan
Pemerintah
ini
tidak
terdapat
aturan
yang
mengindikasikan bahwa Naskah Perjanjian Pinjaman atau Hibah
harus mendapat persetujuan DPR. Selain itu, Pasal 16 Peraturan
Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri mulai berlaku sejak ditandatangani, kecuali
ditentukan lain dalam naskah/dokumen yang bersangkutan. Pasal
ini
akan
menyulitkan
Departemen
Luar
Negeri
jika
ternyata
perjanjian dimaksud adalah perjanjian internasional publik yang
tunduk pada Konvensi Wina 1969 dan 1986 serta Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Itulah
sebabnya,
dalam
mengamankan
rangka
akuntabilitas
juridis
serta
kepentingan
hukum
khususnya
untuk
kewajiban
pengesahan dengan Undang-Undang, maka posisi Departemen Luar
Negeri
pada
setiap
mengupayakan
perjanjian
klausula
pinjaman
tentang
kategori
dipenuhinya
ini
terlebih
selalu
dahulu
prosedur konstitusional/internal sebelum berlakunya perjanjian.
Dalam
praktik,
notifikasi
“telah
Departemen
terpenuhinya
Luar
Negeri
prosedur
akan
menyampaikan
konstitusional/internal”
setelah mendapatkan konfirmasi tertulis dari Departemen Keuangan
perihal tersebut.
Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia terkait
masalah perjanjian pinjaman ini adalah tidak adanya penegasan
secara juridis baik dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara maupun Peraturan Pemerintah No. 2
Tahun 2006 apakah perjanjian pinjaman ini masuk dalam kategori
perjanjian internasional publik atau perjanjian perdata internasional
30
biasa. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional hanya mengatur tentang perjanjian pinjaman per
definisi
Undang-Undang
ini
yaitu
perjanjian
“Governed
by
International Law”. Untuk perjanjian pinjaman kategori ini, ketentuan
Konvensi Wina 1969 dan 1986 serta Undang-Undang No. 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional diberlakukan. Akibat tidak
adanya penegasan juridis dari Rancangan Undang-Undang ini, akan
terjadi konflik kewenangan antara substansi dan format yaitu Menteri
Keuangan yang memiliki kewenangan atas pinjaman luar negeri
dengan kewenangan Menteri Luar Negeri yang memiliki wewenang
untuk membuat perjanjian internasional itu sendiri. Terlebih lagi,
dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Naskah Perjanjian
Pinjaman
Luar
Negeri
ditandatangani
oleh
Menteri
Keuangan
sedangkan menurut penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.
24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian
Internasional,
“Dalam
hal
pinjaman luar negeri, Menteri (dalam hal ini Menteri Luar Negeri)
mendelegasikan kepada Menteri Keuangan”.
Terkait dengan pemberian hibah dari hasil pengumpulan data
yang dilakukan di Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi
Aceh, menyatakan,
sebaiknya dilaksanakan kebijakan one door
policy, yakni dalam penerimaan hibah Pemerintah Daerah harus
melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena implikasi
dari pemberian hibah berdampak terhadap politik dan ekonomi suatu
daerah. Sebagai contoh pemberian hibah dari suatu Negara terhadap
pemerintah Aceh. Dampak dari pemberian hibah tersebut pemerintah
Aceh harus melakukan kerjasama (dibidang Sumber Daya Alam
misalnya) dengan pihak pemberi hivah tersebut. Oleh karena itu,
dalam revisi UU PI masalah hibah tersebut perlu pengaturan
tersendiri.
31
c. Pengesahan Perjanjian Internasional di Bidang Ekonomi
Indonesia sebagai salah satu Negara yang berkembang dengan
cukup pesat di Asia Tenggara, saat ini terlibat dalam sejumlah
perjanjian
perdagangan
bebas,
yaitu
dengan
World
Trade
Organization (WTO) yang melibatkan 153 negara, ASEAN Free Trade
Agreement (AFTA), dan Indonesia-Jepang Economic Partnership
Agreement. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia juga terlibat FTA
dengan Korea Selatan, India, China, Australia dan Selandia Baru.
Sedangkan dengan Amerika Serikat (AS), diberlakukan sebagai
perjanjian perdagangan antar negara, tetapi hanya perjanjian bisnis
antara sektor-sektor usaha tertentu di Indonesia dan AS.
Dampak
positif
FTA
telah
dipaparkan
oleh
perwakilan
pemerintah. Namun, sejumlah FTA yang melibatkan Indonesia
tersebut tidak dapat dikatakan memberikan dampak yang lebih
positif bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah masalah
sosial yang terjadi, diantaranya: masalah pengangguran, masalah
kemiskinan,
masalah
transformasi
sektor
penanganan
pertanian,
sektor
masalah
informal,
reforma
masalah
agraria,
atau
penanganan terhadap masyarakat adat. Secara statistik, angka
pengangguran di Indonesia memang menurun. Tetapi, lapangan kerja
lebih banyak disumbangkan oleh sektor informal yang selalu
dimarjinalkan. Data BPS menyebutkan pertumbuhan sektor informal
terus meningkat sejak 1997 sebagai akibat berkurangnya lapangan
pekerjaan di sektor formal. Sektor informal ini ibaratnya spons cuci
yang menyerap sisa-sisa kotoran. Ia akan menyerap tenaga kerja yang
terlempar dari piring-piring sektor formal.
Sektor informal di kota-kota besar juga menjadi penyerap bagi
mereka yang terlempar dari sektor pertanian yang sekarang dibanjiri
oleh produk impor. BPS mencatat, selisih ongkos produksi dengan
pendapatan petani dari tahun ke tahun selalu menurun. Akibatnya,
semakin sedikit penduduk yang mau melestarikan pertanian dan
terjadilah
urbanisasi
yang
juga
menimbulkan
masalah
sosial
32
lanjutan. BPS menyebutkan bahwa sampai Februari 2011 sektor
pertanian mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 0,84%
dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan
internasional
di
data
dan
bidang
alasan
ekonomi,
diatas,
maka
khususnya
perjanjian
terkait
dengan
perdagangan bebas harus diratifikasi dalam pengesahannya.
Ada tiga hal utama mengapa perjanjian internasional di bidang
perdagangan
Undang
bebas
harus
Undang,
internasional
pertama
memiliki
penandatanganan
diratifikasi,
;
perjanjian
dampak
perjanjian
atau
penting
disyahkan
melalui
perdagangan
dan
perdagangan
luas.
bebas
bebas
Kedua,
menuntut
konsekuensi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan
lainnya di dalam negeri. Ketiga, perjanjian perdagangan bebas
umumnya mengikat (legally binding), yang pelanggarannya dapat
dikenakan denda atau sangsi secara internasional.
Selama
ini
awam
mengenal
perdagangan
bebas
sebagai
perjanjian perdagangan semata, atau hanya semata-mata urusan jual
beli
antar
Negara.
Perdagangan
bebas
tidaklah
demikian.
Perdagangan bebas adalah suatu rezim yang mengatur tidak hanya
perdagangan barang, akan tetapi investasi dan jasa-jasa. Rezim
perdagangan bebas mengatur seluruh aspek dalam ekonomi.
Melalui WTO yang merupakan suatu organisasi internasional
tentang perdagangan bebas, kita temukan ruang lingkup perjanjian
perdagangan bebas. Perjanjian WTO mencakup perjanjian sektor
pertanian, perdagangan barang, jasa dan kekayaan intelektual. Dasar
seluruh kebijakan WTO adalah prinsip-prinsip liberalisasi, termasuk
komitmen
masing-masing
negara
untuk
menurunkan
dan
menghilangkan tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi pendirian WTO melalui
UU No 7 tahun 1994. Ratifikasi ini berarti bahwa Indonesia
menyetujui dokumen final pendirian WTO dan sekaligus secara resmi
menjadi anggota WTO. Keikutsertaan menjadi anggota WTO telah
menimbulkan
konsekuensi
yang
luas
terhadap
perekonomian
33
nasional. Dalam hal ini semestinya parlemen dapat memanggil
pemerintah/presiden dalam urusan pelaksanaan UU No 7 tahun
1994,
menyangkut
semakin
lemahnya
posisi
Indonesia
dalam
perdagangan internasional.
Selain
WTO
perjanjian
perdgaangan
bebas
lainnya
ditandantangani oleh pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA).
Meski hanya dilakukan antara Negara, antar Negara dengan suatu
kawasan dan antara kawasan yangs atu dengan kawasan lainnya,
namun perjanjian FTA memiliki dampak yang sangat luas. Ruang
lingkup perjanjian FTA lebi komprehensif dibandingak WTO, karena
tidak hanya meliputi pertanian, perdagangan barang, namun juga
liberalisasi dibidang keuangan dan jasa-jasa. Komitmen penurunan
tariff bea masuk dalam perdagangan dan liberalisasi keuangan serta
jasa-jasa dalam FTA lebih tinggi dibandingkan kesepakatan didalam
WTO.
Perjanjian FTA berlangsung sangat cepat. Idonoensia saat ini
telah menandatangani banyak FTA, misalnya perjanjian perdagangan
bebas ASEAN dengan komitmen penuh kea rah ASEAN single market.
Melalui
ASEAN
Indonesia
telah
menandatangani
perjanjian
perdagangan bebas dengan China, Korea, Jepang, Australia , India
dan rencana perjanjian perdagan bebas dengan AS dan EU yang saat
ini dalam proses negosiasi. Dengan ditandantanganinya seluruh
perjanjian FTA tersebut maka berarti Indonesia telah melakukan
liberalisasi penuh terhadap perekonomian nasionalnya baik dalam
bidang investasi, perdagangan dan keuangan.
Berbagai
perjanjian
perdagangan
bebas
tersebut
telah
berdampak penting dan luas. Sebagai contoh perjanjian FTA dengan
China telah menyebabkan Indonesia menjadi sasaran ekspansi
produk manufactur murah asal China. Perdagngan bebas dengan
Australia Newzealand menyebabkan Indonesia menjadi sasaran
ekapansi produk pertanian dan peternakan. Demikian pula halnya
perdagangan bebas dengan Jepang telah menyebabkan Indonesia
menjadi sasaran ekspansi pasar produk Jepang dan sisi lain
34
Indonesia menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam oleh actoraktor ekonomi dari Negara tersebut.
Ringkasnya perjanjian perdagangan bebas memiliki dampak
penting dan luas. Penadatanganan perjanjian ini oleh pemerintah
menyebabkan Negara terikat di dalam rezim internasional yang
seringkali Negara tidak dapat menarik diri keluar dari perundingan
karena
berbagai
konsekusnsi
yang
dapat
diterima
secara
internasional. Sebagai contoh Indonesia gagal melakukan negosiasi
ulang FTA dengan China meski telah jelas merugikan ekonomi
nasional.
Sementara
pemerintah
(eksekutif)
begitu
mudah
menandatangani perjanjian FTA karena menerima insentif seperti
utang, bantuan lainnya, tanpa memikirkan bahwa kesepakatan itu
akan berlaku pada pemerintahan berikutnya dan sulit menarik dari
dari perjanjian yang telah ditandatangani.
Dengan demikian maka satu-satunya cara untuk mengerem
tindakan pemerintah yang “terus menerus” menandatangani FTA
adalah dengan meratifikasi melalui UU. Karena kesepakatan itu
sangat strategis dan harus memperoleh persetujuan dari seluruh
rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR). Selain itu yang
terpenting
adalah
UU
ratifikasi
FTA
nantinya
tidak
boleh
bertentangan dengan semangat proklamasi 1945, Pancasila dan UUD
1945 yang merupakan konstitusi dasar Negara Republic Indonesia.
35
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri
Dalam UU No. 37 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hubungan
luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah,
atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara
Indonesia (Pasal 1 angka 1). Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai
dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan
hukum serta kebiasaan internasional {Pasal 5 ayat (1)}.
Berdasarkan
Pasal
6
ayat
(1),
kewenangan
penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah
Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara
lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut Pasal 6
ayat (2) mengatur bahwa Presiden dapat melimpahkan kewenangan
penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar
Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri. Yang
dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di
bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri (Pasal 1 angka 4).
Masih terkait dengan kewenangan, Pasal 7 ayat (1) mengatur Presiden
dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat
pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar
Negeri di bidang tertentu. Namun sesuai dengan prinsip ”one door policy”,
Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pejabat
negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan Menteri.
36
Sehubungan dengan keinginan Indonesia untuk masuk ke dalam
atau keluar dari keaggotaan organisasi internasional, seperti organisasi
perdagangan
internasional
maka
Pasal
9
dapat
menjadi
pedoman.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), pembukaan dan pemutusan hubungan
diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau
keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden
dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Pembukaan
dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain
atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan
Keputusan Presiden {Pasal 9 ayat (2)}.
Dalam UU No. 37 Tahun 1999, pembuatan dan pengesahan
perjanjian internasional diatur tersendiri dalam Bab III, Pasal 13 sampai
dengan Pasal 15. Sesuai dengan prinsip one door policy, Pasal 13 mengatur
bahwa Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun
non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian
internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana
tersebut dengan Menteri. Pasal 14 mengatur bahwa Pejabat lembaga
pemerintah,
baik
departemen
maupun
nondepartemen,
yang
akan
menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah
Republik
Indonesia
dengan
Pemerintah
negara
lain,
organisasi
internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat
surat kuasa dari Menteri. Sebagai catatan, nomenklatur atau penamaan
lembaga
pemerintah,
baik
departemen
maupun
nondepartemen
sebagaimana yang ada dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tersebut saat ini sudah
tidak sesuai lagi. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara,
istilah
yang
digunakan
adalah
Kementerian
dan
Lembaga
Pemerintah Non Kementerian. Lebih lanjut, Pasal 15 mengamanatkan
untuk
mengatur
ketentuan
mengenai
pembuatan
dan
pengesahan
perjanjian internasional dengan undang-undang tersendiri.
37
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pembuatan perjanjian internasional di bidang pengelolaan sumber
daya alam perlu memperhatikan tujuan penyelenggaraan penananaman
modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007,
yaitu antara lain untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b) menciptakan lapangan kerja; c) meningkatkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan; d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
nasional; e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f)
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g) mengolah ekonomi
potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang
berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h)
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pembuatan perjanjian internasional di bidang pengelolaan
sumber daya alam juga harus memperhatikan kebijakan dasar penanaman
modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1),
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar untuk: a) mendorong terciptanya
iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk
penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b) mempercepat
peningkatan penanaman modal. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) mengatur
bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah: a) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional; b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,
dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan
perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) membuka
kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3),
Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
Tidak seperti Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya, yaitu
UU No. 1 Tahun 1967 yang hanya mengatur penanaman modal asing dan
38
UU No. 6 Tahun 1968 yang hanya mengatur penanaman modal dalam
negeri, UU No. 25 Tahun 2007 memberlakukan prinsip perlakuan sama
(equal treatment) dengan tidak membedakan penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri. Perlakuan sama ini dapat dilihat dari
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, yang menyebutkan: penanaman modal
diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara. Selain itu, perlakuan sama juga dapat dilihat
dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagaimana telah dipaparkan dan
juga Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan: Pemerintah memberikan
perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari
negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut
Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa perlakuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang
memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.
Pemberian perlakuan yang sama (non diskriminasi) kepada penanam
modal baik dalam negeri maupun asing merupakan wujud implementasi
dari prinsip yang diatur dalam WTO, khususnya dalam Agreement on Trade
Related Investment Measure (TRIMs). Beberapa prinsip dalam WTO tersebut
adalah: 1) Prinsip most favoured nations (MFN), yang menuntut perlakuan
yang sama dari negara host country terhadap penanam modal dari negara
asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing lainnya, yaitu
tidak membedakan asal negara penanam modal tersebut; dan 2) Prinsip
national treatment, yang mengharuskan negara penerima modal untuk tidak
membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal
dalam negeri di negara penerima modal tersebut.
Selain perlakuan sama, hal lain yang harus diperhatikan adalah
masalah bidang usaha. Dalam UU No. 25 Tahun 2007, bidang usaha diatur
dalam dalam BAB VII, Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan
penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
39
(2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanam modal asing
adalah:
(3) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan
(4) bidang
usaha
yang
secara
eksplisit
dinyatakan
tertutup
berdasarkan undang-undang.
(5) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang
usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun
dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan,
lingkungan
hidup,
pertahanan
dan
keamanan
nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
(6) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang
tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing
akan diatur dengan Peraturan Presiden.
(7) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi
dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk
Pemerintah.
Untuk melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (4), pemerintah telah
membentuk Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 36 Tahun
2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Terkait
dengan
bidang
usaha,
dalam
rangka
pengembangan
penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, Pasal
13 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha
yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta
bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja
40
sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selanjutnya
Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui
program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi
dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
UU No. 25 Tahun 2007 juga mengatur mengenai hak, kewajiban, dan
tanggung jawab Penanam Modal. Berdasarkan Pasal 14, setiap Penanam
Modal berhak mendapat: a) kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b)
informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c) hak
pelayanan; dan d) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban setiap
Penanam Modal diatur dalam Pasal 15, yaitu berkewajiban: a) menerapkan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan; c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d)
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman
modal;
dan
e)
mematuhi
semua
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Tanggung jawab Penanam Modal diatur dalam Pasal 16, yaitu: a)
menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
b)
menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika
penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; c) menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d)
menjaga kelestarian lingkungan hidup; e) menciptakan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan mematuhi semua
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Selain
tanggung
jawab
tersebut, berdasarkan Pasal 17, Penanam modal yang mengusahakan
sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana
secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan
41
lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
UU No. 25 Tahun 2007 juga mengatur mengenai penyelenggaraan
urusan
penanaman
kewenangan
modal
pemerintah
sehingga
daerah
dan
dapat
diketahui
pemerintah
secara
pusat
di
jelas
bidang
penanaman modal. Penyelenggaraan urusan penanaman modal tersebut
diatur dalam Bab XIII, Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan
keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan
penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal
yang
merupakan
urusan
wajib
pemerintah
daerah
didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas
provinsi menjadi urusan Pemerintah.
(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas
kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada
dalam
satu
kabupaten/kota
menjadi
urusan
pemerintah
kabupaten/kota.
(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang
menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak
terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang
tinggi;
b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan
prioritas tinggi pada skala nasional;
c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan
penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
42
d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi
pertahanan dan keamanan nasional;
e. penanaman
modal
asing
dan
penanam
modal
yang
menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara
lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah
dan pemerintah negara lain; dan
f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah
menurut undang-undang.
(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat
(7),
Pemerintah
menyelenggarakannya
sendiri,
melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau
menugasi pemerintah kabupaten/kota.
(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 30 ayat (9), telah dibentuk
Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. PP ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan yaitu pada tanggal 9 Juli 2007.
Terkait dengan perjanjian internasional di bidang penanaman modal,
dalam Bab XVII (Ketentuan Peralihan), Pasal 35 diatur bahwa Perjanjian
internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang
penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum
Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian tersebut. Lebih lanjut Pasal 36 mengatur bahwa Rancangan
perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral,
dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah
Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang ini. Sebagai catatan UU No. 25 Tahun 2007
mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 26 April 2007
43
C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum
dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dibentuk pemerintahan negara yang
menyelenggarakan
Pembentukan
fungsi
pemerintahan
pemerintahan
negara
dalam
tersebut
berbagai
menimbulkan
bidang.
hak
dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam
suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1
dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan
keuangan negara, hubungan keuangan antara pemerintah dan lembagalembaga
infra/supranasional
meliputi
hubungan
keuangan
antara
pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing,
badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan
perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan
pengelola dana masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
yang mengatur bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah
kepada Pemerintah Daerah/BUMN, dan Pemerintah dapat melakukan
penyertaan modal pada BUMN, pinjaman dan/atau hibah yang diterima
oleh Pemerintah dapat pula diteruskan kepada Pemerintah Daerah dalam
bentuk hibah, atau dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah pada
BUMN. Selain itu pula, pengaturan mengenai hibah/pinjaman luar negeri
diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi:
(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau
menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan
persetujuan DPR.
(2) Pinjaman
dan/atau
hibah
yang
diterima
Pemerintah
Pusat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterus pinjamkan
kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.
44
Pinjaman dan/atau hibah yang berasal dari luar negeri tersebut
dapat diterus pinjamkan atau diterus-hibahkan kepada Pemerintah Daerah,
dan diterus-pinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.
Untuk pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan kemampuan
perekonomian nasional karena dapat menimbulkan beban Anggaran
Pendapatan Belanja Negara/Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup
berat,
sehingga
pengelolaan
diperlukan
pinjaman
luar
kecermatan
negeri.
dan
kehati-hatian
Pengadaan
pinjaman
dalam
dan/atau
penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri
dilakukan dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan
mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan
kesinambungan perekononomian nasional.
Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem
anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin
efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran
pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber
utama
dalam
efektivitasnya.
negeri
yang
Kepentingan
berasal
utama
dari
pajak
pembiayaan
terus
ditingkatkan
pemerintah
adalah
penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan
peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar,
prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan
daya saing ekonomi.
D. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
internasional
sebagaimana
Peraturan Perundang-Undangan
Mengingat
pentingnya
pergaulan
dituangkan pula dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia harus
berperan aktif dalam pergaulan dunia maka tidak dapat dihindari
keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional serta terjalinnya
perjanjian kerjasama dengan negara lain dan tentu saja akan berpengaruh
juga dengan kebijakan nasional karena suatu perjanjian internasional yang
diratifikasi oleh Indonesia atau secara otomatis berlaku bagi negara-negara
anggota perlu dituangkan dalam kebijakan hukum nasional.
45
Terkait perjanjian internasional, Pasal 10 ayat (1) huruf e UndangUndang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur
dengan Undang-Undang berisi salah satunya yaitu pengesahan perjanjian
internasional tertentu. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional
tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian, karena normanorma yang diakibatkan karena pengesahan suatu perjanjian internasional
tertentu harus diterjemahkan dalam norma hukum tertentu yakni undangundang karena hal ini terkait dengan daya mengikat keberlakuannya dan
disesuaikan
dengan
Dikarenakan
kepentingan
negara
dan
bangsa
Indonesia.
akibat hukum yang akan menyertai keberlakuan suatu
pengesahan perjanjian internasional maka menjadi suatu keharusan hal ini
menjadi
salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-
undang.
Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional, menyebutkan bahwa pengesahan
perjanjian
internasional
dilakukan
dengan
undang-undang
apabila
berkenaan dengan:
a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
Indonesia;
c) kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e) pembentukan kaidah hukum baru; dan
f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Sementara itu dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa:
46
(1) Pengesahan
perjanjian
internasional
yang
materinya
tidak
termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan
dengan keputusan presiden.
(2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap
keputusan
presiden
yang
mengesahkan
suatu
perjanjian
internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.
Pengesahan
perjanjian
internasional
melalui
undang-undang
dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk
dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian
dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk
pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.
Pengesahan perjanjian internasional yang dituangkan dalam suatu
undang-undang, terkait juga dengan materi undang-undang yang harus
memuat mengenai tugas dan kewenangan penyelenggara negara. Sehingga
dengan diaturnya ketentuan tersebut sebagai materi muatan suatu undangundang akan memberikan limitasi yang tegas mengenai tugas dan
kewenangan penyelenggara negara dan sebagai upaya preventif dari
detournement de puvoir atau penyalahgunaan wewenang.
Mengacu pada ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) (perubahan ketiga
UUD 1945 yang disahkan pada 10 November 2001) maka perjanjian
internasional yang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang.
Ketentuan
ini
berarti
perjanjian
internasional
yang
tidak
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau tidak mengharuskan
perubahan
atau
pembentukan
undang-undang,
tidak
harus
dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak semua perjanjian
internasional haruslah disahkan dengan undang-undang.
Pengaturan
dengan
undang-undang
merupakan
suatu
bentuk
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapat diartikan
bahwa
semua
pengesahan
perjanjian
internasional
harus
dengan
47
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dengan menggunakan undangundang. Pengesahan perjanjian internasional tidak semuanya harus
diratifikasi dengan Undang-Undang, mengingat perjanjian atau persetujuan
internasional ada yang bersifat teknis dan administratif yang tidak
berpengaruh terhadap hak, kewajiban, dan kehidupan masyarakat luas. Di
samping itu proses pembentukan undang-undang memerlukan waktu yang
panjang, di satu sisi perjanjian internasional harus segera dilaksanakan.
Selain
ketentuan
tersebut
di
atas,
berkaitan
dengan
kondisi
lingkungan global yang semakin menurun dewasa ini, Indonesia sebagai
salah satu negara di dunia dengan kekayaan sumberdaya alam yang sangat
melimpah sudah semestinya mengatur pemanfaatan, pengelolaan serta
perlindungan sumberdaya alam sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga
keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Apalagi Indonesia
merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara sangat rentan dengan
bencana alam, dengan kondisi yang demikian, jika terjadi perubahan
keseimbangan alam di dunia dapat berakibat fatal bagi Indonesia sehingga
sudah seharusnya pemikiran mengenai perlindungan sumber daya alam
memasuki ranah kebijakan yang mesti dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan
di
Indonesia
dan
menjadi
salah
satu
yang
disyaratkan sebagai materi muatan dalam suatu undang-undang.
E. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua
Berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pembuatan
perjanjian inetrnasional, terkait dengan otonomi khusus di provinsi Papua,
dalam
UU
internasional
No.
21
yang
Tahun
berkenaan
2001
mengenai
dengan
pembuatan
kepentingan
perjanjian
provinsi
Papua.
Pembuatan perjanjian inetrnasional di dalam Pasal 4 ayat (6) dinyatakan
bahwa Perjanjian Internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya
terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat
pertimbangan
Gubernur
dan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan. Selanjutnya dalam ayat (7) dinyatakan bahwa Provinsi Papua
dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga
48
atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
Untuk
itu,
dalam
rangka
percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
Provinsi Papua dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan
dengan berbagai lembaga/badan di luar negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hubungan tersebut memungkinkan Provinsi Papua
memiliki lembaga atau badan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi atau
swasta, yang bertujuan memajukan pendidikan, meningkatkan investasi,
dan mengembangkan pariwisata di Provinsi Papua.
Masih berkenaan dengan kekhususan provinsi Papua berkenaan
dengan kerjasama intenasional, dalam Pasal 35 ayat (1) dinyatakan Provinsi
Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya
kepada Pemerintah. Kemudian pemerintah provinsi Papua diberikan
wewenang dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau
luar negeri
untuk membiayai sebagian anggarannya sebagaimana diatur dalam
Pasal 35 ayat (2). Untuk pinjaman dari sumber dalam negeri untuk
Provinsi Papua harus mendapat persetujuan dari DPRP {(Pasal 35 ayat
3)}. Sementara itu, terkait dengan pinjaman yang berasal dari sumber
luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat pertimbangan dan
persetujuan DPRP dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Dalam pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa terkait dengan politik luar
negeri Indonesia, bahwa bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan
penuh mengurus politik luar negeri negara, dan provinsi Papua termasuk
kedalamnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Papua melakukan
kerjasama dan konstultasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan
hal-hal tersebut di Provinsi Papua. Keterlibatan pemerintah pusat tetap
diperlukan
terutama
hal-hal
kesepakatan-kesepakatan
Pelaksanaan
kewenangan
luar
yang
negeri
pembuatan
menyangkut
dan
standarisasi
kerjasama
perjanjian
dan
antarnegara.
internasional
dan
kerjasama internasional baik hibah maupun pinjaman, pemerintah provinsi
Papua harus tetap berkoordinasi dengan pemrintah pusat. Untuk itu
49
pelaksanaan
kewenangan
tersebut
dilakukan
dalam
bingkai
Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya jika isi Pasal 35 di hubungkan
dengan Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, hal ini dikategorikan sebagai suatu bentuk
perjanjian internasional, yang merupakan perjanjian internasional yang
menyangkut pinjaman dan/atau hibah luar negeri disahkan dalam bentuk
Undang-Undang.
Hukum internasional hanya mengenal perjanjian antar negara tanpa
melihat sistem internal negara mengikatkan diri pada perjanjian otonomi,
federal, atau sentralisasi. Pemerintah daerah dalam hal ini bertindak
sebagai elemen negara (lembaga pemrakarsa) yang mengikatkan negara
pada perjanjian inetrnasional. Oleh karena itu, pemrintah daerah bertindak
atas nama negara, bukan atas nama pemerintah daerah.
Undang-Undang
Otonomi
Khusus
hanya
mengatur
mekanisme
daerah mengenai pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme daerah
yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memiliki esensi
yang sama yaitu memberikan ruang partisipasi bagi daerah dalam
pembuatan perjanjian inetrnasional. Mengingat perjanjian internasional
yang di buat oleh pemerintah daerah atas nama negara, perlu di perhatikan
ketentuan nasional yang berlaku termasuk perjanjian internasional dimana
Indonesia menjadi pihak. Oleh karena itu, konsekuensinya diperlukan
koordinasi dan konsultasi berbagai instansi terkait (mekanisme internal).
F. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Pemerintah Daerah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam
melaksanakan kerjasama internasional. Berdasarkan UU No. 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh dapat mengadakan kerjasama
dengan lembaga atau badan di luar negeri serta dapat berpartisipasi secara
langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional. Hal ini
secara jelas disebutkan dalam Pasal 8 mengenai rencana persetujuan
internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang dibuat
oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh.
Selanjutnya dalam Pasal 9 undang-undang tersebut yang menyatakan:
50
(1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga
atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah.
(2) Pemerintah Acemeh dapat berpartisipasi secara langsung dalam
kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
(3) Dalam hal diadakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
dalam
naskah
kerja
sama
tersebut dicantumkan
frasa
Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Aceh
dapat melakukan perjanjian internasional dengan lembaga atau badan luar
negeri secara langsung dalam batasan kewenangannya. Artinya, kerjasama
atau perjanjian internasional hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh di
bidang selain yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang berdasarkan UU
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (3) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
Sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 ayat (4) diatas bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama luar negeri yang dapat
dilakukan oleh Aceh diatur dalam Peraturan Presiden, yaitu Peraturan
Presiden Nomor 11 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh
Dengan Lembaga atau Badan Di Luar Negeri. Dalam perpres ini diatur
secara jelas tentang prinsip kerjsama, tata cara kerjasama, pendanaan
kerjasama, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, serta penyelelesaian
perselisihan.
51
Terkait dengan tugas dan wewenang DPRA, dalam Pasal 23 huruf g
dan huruf h dinyatakan bahwa DPRA mempunyai tugas dan wewenang
untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional
yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan memberikan pertimbangan
terhadap rencana kerjasama internasional yang dibuat oleh Pemerintah
yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh.
Mengenai kewenangan di bidang sumber daya alam di bidang
pertambangan
mineral,
batubara,
panas
bumi,
bidang
kehutanan,
pertanian, perikanan dan kelautan berada pada pemerintah daerah
(Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Sedangkan pengelolaan
sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan di laut di
wilayah kewenangan aceh berada dibawah pengelolaan bersama antara
pemerintah
Pusat
penggunaan
dengan
sumber
Kabupaten/Kota,
Pemerintah
daya
alam
Pemerintah
Aceh
Aceh.
(SDA)
tetap
non
Menyangkut
migas
melakukan
dengan
di
daerah
koordinasi
dan
persetujuan dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pembagian hasil
bagi daerah atas penggunaan sumber daya alam sangat tergantung dari
jenis perjanjian yang dilakukan. Misalnya pertambangan, kehutanan,
perikanan, pembangkit sumber daya listrik yang menjadi kewenangan
masing masing Kabupaten/Kota.
Terkait dengan hal tersebut di atas,
mengenai pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Pasal 156 yang
menyatakan bahwa:
(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota mengelola
sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai
dengan kewenangannya. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan
kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya. (3)
Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang
pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas
bumi,
bidang
kehutanan,
pertanian,
perikanan,
dan
kelautan
yang
dilaksanakan dengan menerap-kan prinsip transparansi dan pembangunan
berkelanjutan. (5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
52
ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing.
Dibuka ruang partisipasi masyarakat bekenaan dengan kerjasama
internasonal,
dalam
hal
ini
penduduk
di
Aceh
dapat
melakukan
perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan {Pasal 165 ayat (1)}. Selanjutnya dalam ayat
(2) dinyatakan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan
izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam
negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional. Hal
tersebut dilakukan untuk pengembangan dan pembangunan provinsi Aceh
dan untuk menyejahterakan masyarakat Aceh.
Pemerintah Daerah dalam pembuatan perjanjian pinjaman luar
negeri, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat
dalam hal ini Menteri Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan
Peencanaan
Pembangunan
Nasonal.
Dalam
pembuatan
perjanjian
internasional tersebut mengacu Pasal 186 Undang-Undang Pemerintahan
Aceh yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh
pinjaman dari Pemerintah yang dananya bersumber dari luar negeri
atau bersumber selain dari pinjaman luar negeri dengan persetujuan
Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri
Dalam Negeri.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh
pinjaman dari dalam negeri yang bukan berasal dari pemerintah
dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pinjaman dari dalam dan/atau
luar negeri dan
bantuan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
53
(4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima
hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada
Pemerintah dan DPRA/DPRK.
(5) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat:
a.tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah, Pemerintah
Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota;
b.tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota;
c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
d. tidak bertentangan dengan ideologi negara.
(6) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mensyaratkan
adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah seperti hibah
yang terkait dengan pinjaman dan yang mensyaratkan adanya dana
pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan
kepada DPRA/DPRK.
Terkait dengan kegatan ekonomi perbankan, dalam Pasal 196 ayat (4)
dinyatakan bahwa Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di
Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu,
bekenaan dengn perjanjian bagi hasi minyak dan gas bumi yang berlokasi
di Aceh antara dengan negara asing atau pihak lain, dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian diatur dalam Pasal 252.
Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan
untuk
melakukan
hubungan
internasional
dan
membuat
perjanjian
internasional ada pada pemerintah pusat yang diwakili oleh Presiden
Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 11
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945
dan Pasal 10 ayat(3) UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 dan Pasal 5
ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000, dan Pemerintah Aceh berdasarkan UU
No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan juga dapat
melakukan hubungan luar negeri dan membuat perjanjian internasional.
Namun untuk pelaksanaannya diperlukan koordinasi dan konsultasi
54
dengan pemerintah pusat. Kepala Daerah merupakan pengemban tugas
dan kewenangan untuk mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan,
termasuk dalam melaksanakan hubungan luar negeri dan membuat
perjanjian internasional namun masih memerlukan adanya surat kuasa
penuh (full powers) dari Menteri Luar Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa
yang memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri dan
untuk membuat serta menandatangani perjanjian internasional adalah
pemerintah pusat yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia.
Kedudukan Kepala Daerah sebagai kepala pemerintah daerah disatu
sisi
dengan
kedudukan
kepala
daerah
sebagai
pejabat
negara
yang
memperoleh surat kuasa penuh (full powers) dari Menteri Luar Negeri untuk
melaksanakan hubungan luar negeri, disisi yang lain adalah saling
berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karenanya obyek hubungan
kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah
segala
urusan
yang
berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan
disebutkan sebagai urusan dari pemerintah daerah. Sedangkan dalam
penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan hubungan
kerjasama luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah
pusat harus terlibat aktif dalam rangka menyelesaikan sengketa yang
terjadi sebab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap
sebagai subyek hukum internasional adalah Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara utuh dan tidak terbagi-bagi. Sehingga oleh karenanya,
walaupun hubungan kerjasama luar negeri di prakarsai dan dilaksanakan
oleh
pemerintah
daerah,
pada
saat
terjadi
sengeketa
internasional
pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja.
Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam
perjanjian sister city melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat
khususnya Kementerian Luar Negeri dan dalam hal kerjasama yang
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA) dan daerah, maka
kami harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA). Dalam hal ini berlaku ketentuan khusus (lex specialis)
bagi Aceh sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ketentuan
55
ini berbeda dengan ketentuan umum (lex generalis) yang berlaku bagi
kebanyakan daerah lainnya di Indonesia.
Mengingat
perkembangan
hukum
yang
mengatur
tentang
Pemerintahan Daerah, baik yang bersifat umum (UU No. 32/2004) maupun
yang bersifat khusus seperti Aceh (UU No. 11/2006) dan Papua (UU No.
21/2001) telah membuka kesempatan bagi daerah-daerah secara khusus
untuk melakukan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, prinsip one door
policy
sebaiknya
diadakan
pembatasan
hanya
terhadap
perjanjian
internasional yang bersifat central power sebagai kewenangan Pemerintah
saja, sedangkan untuk residu power sebagai kewenangan daerah seperti
yang ditentukan di dalam UU No. 11/2006 misalnya tidak dibutuhkan
prinsip kebijakan satu pintu tersebut.
Jika merujuk pada pasal-pasalnya, maka UU tersebut memiliki
beberapa fungsi yaitu, penguat eksistensi NKRI, sebagai instrumen yuridis
untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, instrumen yuridis pelaksanaan
perjanjian
internasional
(Memorandum
of
Understnding)
serta
untuk
penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh.
G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Seiring dengan proses reformasi Indonesia, yang salah satu pilar
utamanya adalah pembentukan sistem otonomi daerah maka tidak dapat
dipungkiri bahwa peran pemerintah daerah sangat penting sebagai salah
satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. Globalisasi yang
secara tidak langsung berimbas kepada kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi saat ini telah menuntut semua lapisan masyarakat mulai dari
pemerintah pusat sampai warga Negara untuk memiliki kapasitas dan
kapabilitas dalam melakukan hubungan luar negeri, tak terkecuali bagi
pemerintah di tingkat daerah. Semakin luas cakupan hubungan luar negeri,
ditambah dengan pemberlakuan otonomi daerah maka secara tidak
langsung akan berdampak pada semakin luasnya aktivitas pemerintah
daerah dalam mengembangkan daerahnya.
56
Dalam melakukan hubungan luar negeri, pemerintah daerah tidak
dapat bertindak diluar aturan mengingat adanya hal-hal yang menjadi
batasan bagi pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, seperti regulasi, wewenang dan kemampuan masingmasing pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri.
Memang kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum
mengetahui tentang batasan-batasan tersebut dan sering kali melangkahi
pemerintah pusat dalam melaksanakan aktivitas hubungan luar negeri,
sehingga dirasakan perlu adanya pemahaman mengenai mekanisme atau
tata cara pelaksanaan hubungan luar negeri yang dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah, serta batasan dan akibat hukum yang muncul akibat
aktivitas tersebut.
Sebenarnya jika dicermati peran pemerintah daerah telah ditegaskan
di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri, yang berbunyi sebagai berikut:22
“hubungan luar negari adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek
regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat
pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan
usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, atau warga negara”.
Sementara pengaturan terkait perjanjian internasional dalam UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tampak pada Pasal 42 ayat (1)
huruf (f), yang berbunyi:23
“DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian
internasional di daerah”.
22
23
Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Lihat Pasal 42 ayat (1) huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
57
Penjelasan: “ yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam
ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar
negeri yang terkait dengan kepentingan daerah.”
Penjelasan yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam
ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri
yang terkait dengan kepentingan daerah, sementara dalam penjelasannya
hanya disebutkan sebagai perjanjian antar pemerintah yang terkait daerah.
Hal
inilah
yang
secara
tidak
langsung
menimbulkan
problematika,
mengingat perumusan pasal ini tidak didukung oleh konsepsi yang jelas
mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam
konteks
pemerintah
daerah
karena
di
dalam
penjelasannya
hanya
disebutkan sebagai perjanjian antar pemerintah yang terkait daerah. Secara
sederhana dapat dirinci permasalahan sebagai berikut:
- Apakah perjanjian yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah
perjanjian internasional seperti yang didefinisikan oleh UU PI?
- Apakah pengertian perjanjian antar pemerintah dimaksudkan untuk
menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud harus perjanjian antar
pemerintah (G to G) atau pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah
pusat sesuai dengan definisi undang-undang ini?
- Apakah
perjanjian
yang
terkait
dengan
kepentingan
daerah
dimaksudkan sebagai perjanjian yang dibuat oleh pemerintah pusat
(Indonesia) namun materinya terkait kepentingan daerah?
Dalam
praktik
internasional,
kekuasaan
membuat
perjanjian
lazimnya berada di tangan pemerintah pusat dan tidak dikenal adanya
perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Memang
jika dicermati dalam praktik Indonesia dikenal juga beberapa jenis
dokumen yang berkaitan dengan pemerintah daerah, seperti:
-
Dokumen yang ditandatangani antar pemerintah daerah, seperti MOU
sister city yang telah dibuat banyak oleh berbagai pemerintah daerah.
-
Dokumen yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan
kepentingan daerah, seperti perjanjian RI – Singapura terkait
kawasan ekonomi khusus Batam, Bintan dan Karimun 2006.
58
Terkait dengan sister city maka perjanjian tersebut bukanlah
merupakan suatu bentuk perjanjian internasional karena dokumen ini
belum diakui memenuhi persyaratan sebagai suatu perjanjian internasional
oleh UU PI mengingat para pihak tidak dimaksudkan bertindak atas nama
Negara melainkan bertindak atas nama lembaganya. Materi yang tertuang
dalam perjanjian ini lebih bersifat administratiF sehingga tidak melahirkan
hak dan kewajiban Negara menurut hukum internasional. Hal ini semakin
diperkuat dimana PBB tidak pernah menerima pendaftaran (depository)
MoU semacam ini berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB.24 Tidak hanya itu,
kenyataan di lapangan
25membuktikan
bahwa sister city lebih didasarkan
pada misi dagang, kerjasama budaya, pariwisata, hubungan etnisitas atau
emosional antara kota tersebut.
Namun sayangnya di lain pihak, seiring dengan pemahaman yang
distortif tentang perjanjian internasional, tidak dipungkiri bahwa di
kalangan pemerintah sendiri masih menganggap MOU seperti ini sebagai
perjanjian internasional dengan perimbangan bahwa karakternya adalah
antar pemerintah (daerah). Dengan demikian, jika bertolak dari definisi
perjanjian internasional maka lebih tepat jika yang dimaksudkan oleh UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini adalah perjanjian yang
dibuat oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Yang perlu untuk diperhatikan lebih jelas apabila konstruksi atau konsep
ini diadopsi maka secara tidak langsung akan memunculkan persoalan
yuridis lain bahwa perjanjian ini harus melalui pendapat dan pertimbangan
dari DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Mekanisme
seperti ini akan memunculkan “double ratification” yang diratifikasi oleh
DPR dan DPRD, mengingat di Indonesia mekanisme seperti ini tidak pernah
dilakukan.
Praktik di Indonesia selama ini masih diarahkan kepada pembuatan
MOU sister city antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah
Negara asing, yang ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
24
Lihat Pasal 102 Piagam PBB.
Pengumpulan data yang dilakukan oleh tim asistensi terkait penyusunan naskah akademik dan draft RUU
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional di Provinsi Kalimantan Barat
(Pontianak).
25
59
Dengan
demikian
maka
praktik
tersebut
bukanlah
dalam
rangka
pembuatan perjanjian internasional seperti yang dimaksud Pasal 42 ayat (1)
huruf (f) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, akan tetapi
semata-mata pelaksanaan dari Pasal 42 ayat (1) huruf (g), yang berbunyi:
“ DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan
terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah
daerah”.
Berdasarkan pengertian pasal tersebut maka MOU sister city lebih
tepat untuk diartikan sebagai kerjasama internasional daripada perjanjian
internasional. Dalam praktiknya, sebelum membuat MOU ini Pemerintah
daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, namun kadang kala
peraturan normative yang seharusnya dilakukan sering terbentur pada
kenyataan atau realita di lapangan, dimana tidak adanya kesepahaman
dalam mekanisme antara Pemerintah daerah dan DPRD itu sendiri.
Jika dicermati untuk membuat perjanjian internasional, seluruh
lembaga
(termasuk
Pemerintah
Daerah)
apabila
ingin
mengadakan
kerjasama dengan pihak dari luar negeri harus melewati proses yang
panjang agar aman dari segi politik, yuridis, security dan teknis. Adapaun
proses pengajuan rencana kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah
adalah sebagai berikut:
Pemerintah daerah mengajukan rencana kerjasama luar negeri kepada
DPRD untuk dipertimbangkan dan disetujui.
1. Pemerintah
daerah
berkonsultasi
dan
berkoordinasi
dengan
Kementeriaan Luar Negeri dan lembaga/departemen terkait tentang
isi perjanjian;
2. Pengajuan full power oleh pimpinan daerah atau pejabat daerah yang
berwenang (jika diperlukan);
Menurut Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional dijelaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional harus
melewati 5 tahapan yaitu:
1. Penjajakan, dalam proses ini dilakukan tukar-menukar draft yang
ingin diajukan melalui jalur diplomatik.
60
2. Perundingan, dalam proses ini kedua belah pihak berunding untuk
menentukan pasal-pasal dalam perjanjian.
3. Perumusan naskah, merupakan hasil kesepakatan perundingan yang
berisi pasal-pasal.
4. Penerimaan, pemberian paraf terhadap naskah perjanjian yang siap
untuk ditandatangani.
5. Penandatanganan, pemberian tanda tangan oleh para pihak yang
melakukan perjanjian melalui presiden, menteri luar negeri, atau
pejabat yang memperoleh full power.
Perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh pimpinan
daerah perlu disahkan agar dapat berlaku di daerahnya. Menurut Pasal 9
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terdapat 2 macam
cara untu mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Pemernitah Daerah,
yaitu:
1. pengesahan dengan undang-undang, jika menyangkut hal-hal yang
tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, mekanismenya adalah sebagai berikut:
- pemerintah daerah menagjukan ijin prakarsa kepada Presiden melalui
menteri luar negeri;
- pemerintah daerah membentuk panitia antar kementeriaan yang
terdiri dari kementeriaan terkait untuk menyiapkan rancangan
undang-undang pengesahan;
- pemerintah daerah menyerahkan berkas-berkas perjanjian kepada
kementeriaan luar negeri;
-
kementeriaan luar negeri mengajukan permohonan amanat presiden;
- Presiden menunjuk menteri atau kepala instansi terkait sebagai
perwakilan pemerintah dalam pembahasan dengan DPR;
- Jika disetujui, rancangan undang-undang berubah menjadi undangundang dan diterbitkan dalam lembar negara;
- Menteri luar negeri menerbitkan instrumen pengesahan.
61
2. Pengesahan dengan peraturan presiden (Perpres), jika menyangkut halhal di luar Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:
- Pemerintah
Daerah
mengkoordinasikan
rapat
interkementeriaan
untuk mempersiapkan pengesahan perjanjian internasional;
- Pemerintah Daerah menyerahkan berkas-berkas perjanjian kepada
kementeriaan luar negeri;
- Menteri luar negeri mengajukan surat permohonan kepada presiden;
- Jika disetujui, rencana peraturan presiden berubah menjadi peraturan
presiden (Perpres);
- Menteri luar negeri menerbitkan instrumen pengesahan.
Selain itu sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan
dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan atau
kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka daerah perlu
mengembangkan potensi daerahnya guna mmpercepat laju pembangunan,
sehingga diperlukan adanya kreatifitas daerah untuk meningkatkan
pendapatan daerahnyab guna membiayai pembangunan yang dimaksud,
salah satunya melalui pinjaman daerah.
Pinjaman luar negeri merupakan salah satu bentuk dari dana luar
negeri. Dana luar negeri itu dapat berbentuk hibah, bantuan program,
bantuan proyek, bantuan teknik dan pinjaman dimana unsur penting
dalam pinjaman ini adalah bahwa pinajman itu harus dibayar kembali
dengan waktu dan persyaratan yang telah disetujui para pihak, yaitu
antara yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Pengertian
pinjaman ini secara tidak langsung membawa kewajiban bagi yang
meminjam
untuk
mengembalikan
uang
yang
dipinjamnya
dengan
memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu tentang
besaranya bunga dan waktu pengembaliannya, dan lain-lain.
Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pinjaman uang
pada umumnya sebagai berikut:
- Ada unsur kepercayaan;
62
- Ada perjanjian pinjam uang;
- Tujuannya
bebas,
artinya
penggunaannya
diserahkan
kepada
keinginan pihak yang meminjam (kreditur);
- Mengandung kewajiban untuk mengembalikan.
Yang dimaksud dengan pinjaman luar negeri menurut Pasal 1a
Keppres No. 59 Tahun 1972 adalah
“Kredit luar negeri adalah pinjaman yang diterima dari luar negeri, yang
pemasukannya ke Indonesia bukan dalam rangka penerimaan kredit dari
badan-badan
internasional
dam
pemerintahan
negara-negara
yang
tergabung dalam Inter-Government Group of Indonesia (IGGI)”.
Sementara peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut yakni SK
Mneteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-261/MK/IV/5/73 Pasal 1
berbunyi:
“yang dimaksud dengan kredit luar negeri adalah‟
a. Semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali
terhadap luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah.
b. Semua pinjaman dalam negeri yang dapat menimbulkan kewajiban
membayar kembali terhadap luar negeri, baik valuta asing maupun
dalam rupiah, baik brdasarkan perjanjian kredit maupun berdasarkan
pengeluaran obligasi, garansi, proses aksep, serta bentuk pinjaman
dan kewajiban pembayaran lainnya yang lazim digunakan termasuk
antara lain charter purchase, elease purchase, deffered payment
purchase arrangement dan sebagainya.
Selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan:
“Terhadap kredit luar negeri yang berasal dari lembaga-lembaga
internasional
seperti
IMF
(International
Bank
for
(International Monetary Funds),
Recontruction
and
Development),
IBRD
IDA
(International Development Agency) dan ADB (Asian Development Bank)
serta negara-negara yang
tergabung dalam
IGGI,
tidak
berlaku
63
ketentuan-ketentuan dalam surat kepeutusan ini sepanjang kredit
tersebut diberikan dalam rangka IGGI”.
Berkaitan dengan pinjaman daerah dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa pinjaman ini
dapat dilakukan dengan perantara pemerintah pusat, diwakili oleh Menteri
Keuangan
(Menkeu)
melalui
perjanjian
penerusan
pinjaman
kepada
pemerintah daerah. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah No. 107
Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah telah diatur bahwa pinjaman daerah
harus terlebih dahulu disetujui oleh Pemerintah Pusat.
Sebenarnya
berdasarkan
peraturan
yang
mengatur
mengenai
perjanjian internasional khususnya terkait dengan pinjaman luar ngeri
untuk pemerintah daerah, maka pemerintah daerah diperbolehkan untuk
meminjam dana dari luar negeri. Ketentuan dapat dilihat melalui UU No. 22
Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah dapat
melakukan pinjaman atas persetujuan presiden atau Dewan Pemerintah
Daerah setingkat lebih diatasnya. Ketentuan ini dapat dilihat juga pada
Pasal 72 UU No. 18 Tahun 1965 dan Pasal 61 UU No. 5 Tahun 1974, yang
menyatakan
Pemeintah
Daerah
dapat
melakukan
pinjaman
dengan
persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah setingkat diatasnya.
Perumusan tentang perjanjian internasional juga dilakukan dalam
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memuat
rumusan sebagai berikut:26
“ perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait
dengan kepentingan provinsi papua dilaksanakan setelah mendapat
pertimbangan
gubernur
dan
sesuai
dengan
pertauran
perundang-
undangan”.
Sementara itu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
juga ikut menyinggung mengenai treaty making power, yang memuat
rumusan sebagai berikut:27
26
27
Lihat Pasal 4 angka 6 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Lihat Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
64
“Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan
Pemerintah
Aceh
yang
dibuat
oleh
pemerintah
dilakukan
dengan
konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh ”.
H. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing
The
World
Trade
Organization
(Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia, yang telah
semakin meningkat jumlahnya dewasa ini, pada hakikatnya bersifat lintas
sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu hukum di Indonesia seperti
Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi dan
bahkan hukum perdata. Dengan demikian maka pada hakekatnya semua
pemangku kebijakan di pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun
yudikatif memiliki keterlibatan yang cukup kental terhadap perjanjian
internasional. Hukum perjanjian internasional dewasa ini dirasakan telah
mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum
internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai
dengan
banyaknya
perubahan-perubahan
mendasar,
antara
lain
munculnya subyek-subyek baru non-negara disertai dengan meningkatnya
interaksi intensif antara subyek-subyek baru tersebut. Indonesia sendiri
juga mengalami fenomena ini, khususnya otonomi daerah dan lembaga non
pemerintah yang interaksinya dengan elemen asing sudah semakin
meningkat.
Globalisasi yang mewarnai sistem internasional saat ini telah pula
menciptakan interaksi yang intensif antara Indonesia dengan masyarakat
internasional bukan hanya antar pemerintah namun juga antar individu.
Interaksi ini akan mengakibatkan meningkatnya persentuhan-persentuhan
hukum antara Indonesia dengan negara-negara lain bahkan dalam tingkat
tertentu akan menimbulkan tumpang tindih antara hukum internasional
termasuk
perjanjian
internasional
dengan
hukum
nasional.
Dengan
fenomena ini, maka cepat atau lambat, publik hukum Indonesia di semua
lini harus bersentuhan dengan perjanjian internasional dan akan semakin
65
menepis anggapan bahwa hukum perjanjian internasional hanya milik
diplomat saja.
Memang
tidak
dapat
dipungkiri
bahwa
globalisasi
di
bidang
perdagangan dan investasi serta lahirnya pasar bebas telah melahirkan pola
hubungan lintas batas yang mengharuskan adanya pemahaman terhadap
hukum
perjanjian
internasional.
Perjanjian-perjanjian
dewasa
ini
khususnya di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan telah banyak
menyentuh bukan hanya kepentingan negara sebagai pihak perjanjian
melainkan juga melahirkan hak dan kewajiban terhadap individu-individu
di negara pihak. Praktik di negara-negara yang telah mengalami pasar
bebas menunjukkan bahwa pemahaman hukum perjanjian internasional
oleh para praktisi hukum termasuk “Law Firm” menjadi mutlak karena
perjanjian internasional telah menjadi kepentingan bagi para pelaku pasar,
investor serta pedagang.
Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia pasca reformasi
pada umumnya mengatur mengenai masalah ekonomi, investasi dan
perdagangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan
bersentuhan dengan kepentingan para warga negara Indonesia. Sejak
tahun 2000, indonesia telah membuat perjanjian internasional rata-rata
100 perjanjian yang didominasi oleh perjanjian ekonomi, investasi dan
perdagangan. Oleh sebab itu, pemahaman tentang perjanjian internasional
telah menjadi kebutuhan mutlak bagi para pelaku ekonomi di Indonesia.
Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis akan menjadi kebutuhan bagi
aparat penegak hukum di Indonesia.
Jika dicermati Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
antara lain menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang
makin mampu menunjang kepentingan nasional dan diarahkan untuk
turut
mewujudkan
tatanan
dunia
baru
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta ditujukan untuk lebih
meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan
meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok. Garis-Garis Besar Haluan
66
Negara juga menggariskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung
peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan
nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendorong ekspor,
khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan penerobosan
serta perluasan pasar luar negeri.
Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, adalah semestinya apabila
segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang
diperkirakan
akan
dapat
mempengaruhi
stabilitas
nasional
serta
pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan seksama sehingga secara
dini
dapat
diambil
langkah-langkah
yang
tepat
dan
cepat
dalam
mengatasinya. Dengan sikap seperti itu, kebijakan pembangunan nasional
yang
bertumpu
pada
pemerataan
pembangunan
dan
hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, dapat tetap dipelihara.
Dalam
rangka
menghadapi
perkembangan
dan
perubahan,
serta
memanfaatkan peluang yang ada tersebut, Indonesia terus berusaha ikut
serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara, terutama untuk
mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka,
adil, dan tertib serta bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama
ini dinilai tidak menguntungkan perkembangan perdagangan internasional
tersebut.
Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi
ternyata tidaklah sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional
ke arah pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di
dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri,
khususnya di bidang produk non-migas. Tidak kalah pentingnya adalah
kebutuhan untuk makin mamantapkan berbagai sarana dan prasarana
penunjang ekspor, serta keterkaitan yang saling menguntungkan antara
produsen dan konsumen. Sementara itu, kebijaksanaan peningkatan
ekspor
non-migas
pembangunan
yang
nasional
diarahkan
pada
untuk
dasarnya
menunjang
juga
pelaksanaan
menghadapi
berbagai
hambatan dan tantangan yang memerlukan perhatian secara menyeluruh.
Hambatan dan tantangan tersebut dapat berupa ketidakpastian pasar
maupun persaingan antar negara yang semakin meningkat tajam. Secara
67
umum, ketidakpastian perkembangan ekonomi dunia juga dilatarbelakangi
oleh perubahan-perubahan yang terus terjadi secara cepat, baik dalam
kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional,
keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional
juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta
kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan
penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah
satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia, adalah
tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan
antar negara. Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and
Trade/GATT
(Persetujuan
Umum
mengenai
Tarif
dan
Perdagangan).
Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia telah ikut
serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Pebruari 1950.
General Agreement on Tariffs and Trade/GATT (Persetujuan Umum
mengenai Tarif dan Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan
multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan
membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna
mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan
tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. Dari segi tujuan, GATT
dimaksudkan
perdagangan
sebagai
upaya
bebas,
adil
untuk
dan
memperjuangkan
menstabilkan
sistem
terciptanya
perdagangan
internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta
meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.
Sebagai
tatanan
multilateral
yang
memuat
prinsip-prinsip
perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan
perdagangan
antar
negara
dilakukan
tanpa
diskriminasi
(non
discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam GATT
tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara
tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal
balik dalam hubungan perdagangan internasional. GATT berfungsi sebagai
forum
konsultasi
negara-negara
anggota
dalam
membahas
dan
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan
68
internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di
bidang perdagangan antara negara-negara peserta.
GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari
suatu negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak
adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya,
masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negaranegara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan
konsiliasi, serta hasilnya dibertahukan kepada GATT. Untuk mewujudkan
jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT
mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea masuk (tariff binding)
yang diberlakukan negara-negara peserta. Di samping itu, GATT juga
menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan
berdasarkan prinsip persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek
seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor.
Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan
proteksi terhadap industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh
dilakukan melalui proteksi tarif dan bukan melalui tindakan seperti
larangan impor atau kuota impor. GATT melarang pembatasan perdagangan
yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya penerapan kuota impor maupun
ekspor.
Meskipun
dimungkinkan
demikian,
sepanjang
pengecualian
pembatasan
atas
tersebut
larangan
tersebut
merupakan
tindakan
pengamanan guna mengatasi antara lain kesulitan neraca pembayaran.
Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya dapat berlangsung
dalam waktu yang terbatas, dan secara progresif harus dikurangi atau
dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran.
GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh
pengecualian
dari
suatu
bersangkutan
mengalami
perdagangan.
Untuk
kewajiban
tertentu
permasalahan
melindungi
dalam
industri
yang
apabila
negara
yang
bidang
ekonomi
dan
masih
dalam
tahap
pertumbuhan, GATT mengijinkan suatu negara untuk melarang impor atau
tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka
GATT untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat
dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain
69
dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan
kesulitan terhadap industri dalam negeri.
Pengelompokan sejumlah negara dalam kerjasama regional guna
menghapuskan
hambatan
perdagangan
di
antara
mereka
juga
diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan GATT. Ketentuan
GATT menyebutkan bahwa keberadaan kelompok regional diperbolehkan
untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara dalam kelompok
tersebut, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan perdaganagan bagi
negara-negara di luar kelompok regional tersebut.
Dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi negaranegara peserta GATT yang tidak memungkinkan terlaksananya berbagai
ketentuan dan disiplin yang telah diatur, GATT mengakui perlunya
perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Ketentuan
GATT yang mengatur perlakuan khusus ini mengakui adanya negara
berkembang yang memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya
mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara
maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer
dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara
berkembang, dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang.
Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik
dari negara-negara berkembang untuk mengurangi atau menghapuskan
hambatan yang berupa tarif atau non-tarif.
Selain itu ditegaskan pula prinsip mengenai perlakuan yang berbeda
dan lebih menguntungkan, timbal balik serta keikutsertaan penuh negara
berkembang, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemberian perlakuan
khusus
melalui
Sistem
Preferensi
Umum
(Generalized
System
of
Preferences/GSP) oleh negara maju kepada negara berkembang, serta
diperbolehkannya perlakuan perdagangan yang khusus bagi negara-negara
berkembang yang paling terkebelakang.
Perdagangan internasional sendiri merujuk pada kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah
sebagai regulator memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tidak
70
saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya tetapi juga
kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang atau jasa asal negara
lain yang akan masuk ke negaranya. Oleh karena itu adalah kurang tepat
apabila
mempresepsikan
perdagnagn
internasional
sebagai
transaksi
perdagangan (bisnis) dimana pelakunya adalah negara. Sebagai contoh ada
yang beragurmen bahwa negara dengan negara dapat melakukan transaksi
di
bidang
perdagangan,
seperti
pemerintah
Indonesia
melakukan
kesepakatan dengan pemerintah thailand untuk melakukan imbal beli
pesawat yang diproduksi oleh indonesia dengan 110.000 ton beras ketan
yang diproduksi di thailand. Namun setelah diperdalam hal tersebut
bukanlah transaksi perdagangan antarnegara.
Pertama, pesawat yang diproduksi di Indonesia bukan hasil produksi
dari pemerintah Indonesia melainkan hasil produksi badan hukum yang
dimiliki
oleh
pemerintah
Indonesia
(PT.
Industri
Pesawat
Terbang
Nusantara/IPTN). Sementara beras ketan tidak diproduksi oleh pemerintah
Indonesia melainkan oleh para pelaku usaha di Thailand. Sama halnya jika
contoh yang diberikan adalah pengadaan pesawat tempur oleh pemerintah
Indonesia yang diwakili oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat.
Adalah benar bahwa Departemen Pertahanan merupakan representasi dari
negara, namun pihak yang memproduksi pesawat tempur bukanlah
pemerintah Amerika Serikat melainkan badan usaha yang berada di
Amerika.
Perjanjian seperti ini disebut sebagai government contract dimana
salah satu pihaknya negara atau pemerintah. Negara disini harus dianggap
sebagai subyek hukum perdata bukan sebagai subyek hukum dalam
hukum publik. Hukum internasional sendiri memiliki subyek hukum
sendiri
antara
lain
negara,
organisasi
internasional,
palang
merah
internasional dan sebagainya. Sementara dalam konteks perdagangan
internasional
yang
mengatur
aturan-aturan
bagi
pemerintah
dalam
membuat kebijakan bidang perdagangan yang menjadi subyek hukum
adalah
subyek
hukum
internasional.
Dalam
hukum
perdagangan
internasional, orang dan badan hukum bukanlah subyek hukumnya. Disini
harus dipahami bahwa perdagangan internasional masuk dalam kategori
71
hukum internasional (publik), dan sama sekali bukan termasuk hukum
perdata internasional. Hubungan WTO dengan perjanjian internasional
merupakan
satu
kesatuan
khususnya
berkaitan
dengan
hukum
internasional mengingat peranannya semakin lama semakin meningkat
terlebih lagi di era globalisasi ekonomi seperti ini.
I. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Sebagai petunjuk teknis berenaan dengan pinjaman daerah, dalam
Pasal 3 ayat (1) dinyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan
pinjaman
langsung
kepada
pihak
luar
negeri.
Jelas
bahwa
dalam
melakukan kejasama internasional terkait pinjaman, pemerintah daerah
harus
berkonsultasi
dan
berkoordinasi
dengan
pemerintah
pusat.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam
hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena
kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal. Artinya terdapat pengecualian bagi daerah untuk
melakukan pinjaman langsung kepada luar negeri, namun jangan sampai
merugikan kepentingan Negara.
Selanjutnya dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah
Daerah tidak menyampaikan perjanjian pinjaman yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan/atau Pemerintah
daerah
membuat
perjanjian
pinjaman
yang
tidak
sesuai
dengan
pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dilarang melakukan
Pinjaman Daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
J. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006
tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan
Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
Berkenaan dengan peran Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah
daerah untuk melakukan pembuatan perjanjian internasional, dalam Pasal
3
Peraturan
Pemerintah
ini
dibatasi
yaitu:
“Kementerian
72
Negara/Lembaga/Pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam
bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan
pinjaman luar negeri”.
Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga
mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman
dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan. Dalam hal ini
harus diajukan usulan kegiatan termasuk kegiatan yang pembiayaannya
akan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan
modal negara kepada BUMN. Untuk kegiatan investasi, Pemerintah Daerah
mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan
pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan.
Pengaturan
mengenai
pinjaman
dan/atau
hibah
luar
negeri
tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan BUMN pelaksana kegiatan yang dibiayai
dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat mengajukan usulan
perubahan NPPLN/NPHLN kepada Menteri”. Selanjutnya dalam penetapan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri, Pasal 20 menyatakan Menteri
menetapkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri Pemerintah yang akan
diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah dan
diteruspinjamkan
atau
dijadikan
penyertaan
modal
kepada
BUMN.
Penetapan Menteri dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan
PPLN/PHLN. Sedangkan dalam menentukan penerusan pinjaman kepada
Daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah, Menteri memperhatikan
kemampuan membayar kembali daerah dan kapasitas fiskal daerah serta
pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
K. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
11
Tahun 2010
tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga Atau Badan
Di Luar Negeri
Dalam Peraturan Presiden
kerjsama,
tata
cara
kerjasama,
ini diatur secara jelas tentang prinsip
pendanaan
kerjasama,
pembinaan,
pengawasan, dan pelaporan, serta penyelelesaian perselisihan. Di provinsi
73
Aceh, kerja sama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar
negeri adalah bentuk hubungan antara Pemerintah Aceh sebagai bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lembaga atau badan di
luar negeri.
Rencana kerja sama merupakan ide atau gagasan dan rancangan
naskah kerja sama yang dibuat Pemerintah Aceh mengenai kerja sama
Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri, yang memuat
pokok pikiran, ruang lingkup, dan tujuan yang akan dicapai. Lembaga atau
badan di luar negeri adalah pemerintah negara bagian/pemerintah daerah,
kementerian/lembaga
pemerintah
non
kementerian,
lembaga
non
pemerintah, dan badan usaha milik negara atau swasta.
Dalam melakukan kerja sama, dituangkan dalam bentuk naskah
kerja sama yang merupakan kesepakatan tertulis dalam bentuk dan nama
tertentu, yang ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dengan lembaga atau
badan di luar negeri. Hal pokok yang menjadi batasan umum bagi Pemda
Aceh untuk kerjasama luar negeri yang diatur dalam Peraturan Presiden 11
Tahun 2010 adalah:
a. Kerja sama dilaksanakan dengan berpedoman pada standar dan
prosedur yang berlaku secara nasional sesuai dengan bidang kerja
sama.
b. Kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri, dilakukan oleh
Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri dari
negara
yang
telah
mempunyai
hubungan
diplomatik
dengan
Indonesia.
c. Kerja sama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar
negeri hanya meliputi bidang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan
Pemerintah
Aceh
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan.
Dalam tahapannya, setiap kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh
Pemda Aceh harus melalui tahapan berikut:
terlebih dahulu menyusun rencana kerja sama;
rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRA;
74
setelah disetujui rencana kerja sama tersebut disampaikan kepada
Menteri untuk mendapat pertimbangan;
sebelum memberikan pertimbangan, Menteri melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Aceh dan instansi terkait.
75
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945)
memuat
baik
cita-cita,
dasar-dasar,
maupun
prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara dengan istilah tujuan
nasional, tertuang dalam alinea keempat, yaitu (a) melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; (b) memajukan
kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut
melaksanakan
perdamaian
ketertiban
abadi,
dan
dunia
yang
keadilan
berdasarkan
sosial.
Cita-cita
kemerdekaan,
tersebut
akan
dilaksanakan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri
diatas lima dasar, yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Untuk
mencapai
penyelenggaraan
negara
cita-cita
berdasarkan
tersebut
dan
Pancasila,
UUD
melaksanakan
1945
telah
memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan
politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini karena para
pendiri bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara
penuh, bukan hanya kedaulatan politik.
UUD 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang
harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik
oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun pasar (market).
Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki peraturan
perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan
konstitusi mengharuskan adanya perubahan sistem dan kelembagaan,
serta pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu upaya
membangun sistem kelembagaan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai
dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil,
76
makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan kerjasama Bangsa
Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Secara filosofis, dalam
rangka
mencapai
tujuan
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana
tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
melindungi
segenap
bangsa
Indonesia
dan
seluruh
tumpah
darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara
Republik
Indonesia,
sebagai
bagian
dari
masyarakat
internasional,
melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang mewujudkan
dalam perjanjian internasional. Berdasarkan amandemen keempat UUD
1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 khususnya Pasal 11 ayat (2) dan ayat
(3) yang berbunyi:
“(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)
Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur
dengan undang-undang.”
Kerjasama internasional yang dilakukan antar negara, antara negara
dengan organisasi internasional ataupun antar negara dengan subyek
hukum internasional lainnya semakin gencar dilakukan dan dunia semakin
sempit seiring perkembagan teknologi informasi. Akan tetapi sebagai negara
berkembang, Indonesia terkadang dirugikan oleh perjanjian internasional
yang dilakukan dengan negara maju. Sebagai contoh adalah perjanjian
Sosek Malindo dan perjanjian ASEAN dengan Negara China yang disebut
ACFTA.
Saat
ini
perjanjian
Sosek
Malindo
dirasakan
masyarakat
Kalimantan sangat merugikan karena Warga Negara Indonesia dibatasi
77
hanya bisa melakukan transaksi pembelian produk Malaysia sampai
dengan 400 ringgit Malaysia, sedangkan Warga Negara Malaysia tidak
dibatasi nominal untuk melakukan pembelian produk Indonesia. Perjanjian
ACFTA antara ASEAN dengan Cina dirasakan sangat merugikan Indonesia
karena produk-produk China membanjiri pasar Indonesia dan mengambil
pasar produk-produk domestik dikarenakan secara harga lebih murah dan
tampilan lebih memikat daripada produk domestik Negara Indonesia.
Landasan untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain adalah adanya
hak dari setiap negara untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama
dengan negara-negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Komisi
Hukum Internasional/ International Law Commission PBB Tahun 1949.
Selain itu juga dilandaskan pada Kewajiban Negara yang juga diatur dalam
Komisi Hukum Internasional/ International Law Commission PBB Tahun
1949, yaitu:
“Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan
itikad baik (Pasal 13); dan
Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara
lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).”28
Praktik negatif pelaksanaan perjanjian internasional yang terjadi saat
ini adalah banyaknya perjanjian antara pihak Indonesia, baik Pemerintah
Indonesia
maupun
lembaga
pemerintah
dengan
subyek
hukum
internasional asing yang selalu merugikan pihak Indonesia. Sebagai contoh
pertambangan
Freeport di Papua dimana pihak asing telah mengambil
lebih dari 80 % dari hasil keuntungan , sementara pihak Indonesia hanya
bisa menikmati kurang dari 20 % dari hasil keuntungan. Adanya
pemberlakuan otonomi daerah juga belum diantisipasi UU No. 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian Internasional dimana Kabupaten/ Kota yang sudah
diperbolehkan untuk melakukan perjanjian internasional subyek hukum
internasional asing tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
provinsi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh
28
Parry and Grant, et.al., Encyclopaedic Dictionary of International Law, New York: Oceana Publications inc.,
1986, hlm. 374.
78
karena beberapa alasan tersebut di atas maka sangat diperlukan adanya
penggantian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
B.
Landasan Sosiologis
Adanya ketimpangan dimana dalam perjanjian internasional yang
dilakukan oleh Indonesia dengan pihak asing selalu merugikan rakyat dan
Bangsa Indonesia sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat. Rasa
keadilan
masyarakat
terhadap
perbaikan
pengaturan
hukum
dalam
perjanjian internasional tidak terlepas dari keinginan adanya perlindungan
hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Perbaikan
pengaturan hukum dalam pembuatan perjanjian internasional akan
membentuk budaya hukum (legal culture) baru yaitu apakah telah terdapat
sistem birokrasi yang tidak berbelit-belit, koruptif, dan lebih memberi
perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang hendak melakukan
perjanjian internasional dengan pihak asing sehingga membuat masyarakat
ingin melakukan perjanjian internasional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Oleh karena sering tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat
dalam
implementasi
UU
No.
24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian
Internasional sebagaimana terjadi dalam perjanjian Freeport dan Newmont
dimana hasil kekayaan alam Indonesia sudah dieksploitasi oleh pihak asing
dengan pembagian hasil yang sangat sedikit bagi pihak Indonesia maka
muncul
keinginan
masyarakat
yang
diwakili
oleh
anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia untuk melakukan penggantian atas UU No. 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan salah satunya
menambahkan masalah ekonomi dan keuangan sebagai hal-hal yang
memerlukan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan
undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 undang-undang
tersebut.
C.
Landasan Yuridis
Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis
79
merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah
ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut
persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur
sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.
Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah
ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis
peraturan
yang
lebih
rendah
dari
undang-undang
sehingga
daya
berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau
peraturannya memang sama sekali belum ada.
Jika pengertian mengenai landasan yuridis tersebut dikaitkan dengan
Rancangan Undang-Undang tentang Penggantian Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terdapat beberapa
ketentuan mengenai Perjanjian Internasional yang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan
ketatanegaraan, sebagai contoh dengan adanya dorongan dari masyarakat
untuk menambahkan masalah ekonomi dan keuangan sebagai hal-hal yang
memerlukan pengesahan perjanjian internasional untuk dilakukan dengan
undang-undang. Selain itu, dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kabupaten/ kota mulai melakukan perjanjian
internasional secara mandiri, akan tetapi tidak ada koordinasi dengan
pemerintah daerah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk
Undang-Undang tentang Penggantian atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Perjanjian Internasional.
80
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Berdasarkan kajian sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentu ke
depan perjanjian internasional harus mengarah dan menjangkau beberapa
hal yang perlu diimplementasikan yang sekarang ini belum dilaksanakan
sesuai dengan semangat konstitusi.
Perjanjian internasional harus senantiasa berpijak pada asas negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia
sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945,
yaitu mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan
tertib.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka negara Indonesia
akan senantiasa mengadakan perbuatan-perbuatan hukum dengan subjek
hukum internasional lainnya, antara lain dengan mengadakan perjanjian
internasional. Oleh karena itu, perjanjian internasional yang dibuat
tersebut juga harus senantiasa memperhatikan kepentingan nasional atau
kepentingan masyarakat, bahkan termasuk kepentingan masyarakat dari
suatu daerah manakala perjanjian internasional yang dibuat berimplikasi
kepada daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara
demokrasi, menerapkan sistem demokrasi perwakilan sehingga dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat lembaga perwakilan, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
ditentukan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 20A ayat (1) UUD
1945 ditentukan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Berdasarkan aturan
81
konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa peran Dewan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia cukup penting dan strategis, yakni sebagai
lembaga perwakilan rakyat yang akan bertindak dalam tiga fungsi
sekaligus, yaitu pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan.
Dalam hal ini jelas memiliki hubungan atau kaitan yang erat dengan
perjanjian internasional. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya
bahwa perjanjian internasional itu adalah sebuah dokumen hukum yang
juga mempunyai implikasi yang luas dan strategis bagi kepentingan
nasional, kepentingan rakyat, atau kepentingan negara. Bahkan tidak
jarang sebuah perjanjian internasional diratifikasi dengan undang-undang
sehingga kekuatan hukumnya menjadi sama dengan undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penguatan peran Dewan
Perwakilan
rakyat
dalam
kaitannya
dengan
perjanjian
internasional
menjadi sangat penting dalam sistem yang akan dibangun dalam UndangUndang Perjanjian Internasional. Penguatan peran Dewan Perwakilan
Rakyat dimaksudkan untuk diwujudkan dengan sebuat klausul, bahwa
setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah harus disertai
dengan pemberitahuan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Khusus perjanjian internasional di bidang atau yang menyangkut
dengan
pengelolaan
memberikan
sebuah
diperhatikan
oleh
sumber
garis
daya
acuan
Pemerintah
alam,
atau
Undang-Undang
rambu-rambu
manakala
melakukan
ini
yang
juga
perlu
perjanjian
internasional, khususnya menyangkut bidang pengelolaan sumber daya
alam, antara lain aspek ketersediaan kebutuhan nasional yang terkait
dengan ketahanan dan kedaulatan energi nasional serta yang menyangkut
kepentingan nasional lainnya.
Undang-Undang
Perjanjian
Internasional
ke
depan
juga
ingin
membuat aturan yang harus dipedomani oleh Pemerintah, yakni terkait
dengan keterlibatan daerah dalam suatu perjanjian internasional. Dalam
hal ini, manakala perjanjian internasional terkait atau menyangkut dengan
kepentingan
daerah
yang
bersangkutan,
maka
Pemerintah
harus
82
memberitahukan
dan
mengikutsertakan
daerah
dalam
pembuatan
perjanjian internasional.
Perjanjian internasional sebagai sebuah dokumen hukum perlu
memiliki sistem penyimpanan yang memadai dan mudah diakses oleh
setiap
orang
yang
memerlukan
internasional.
Oleh
karenanya,
naskah
atau
penyimpanan
dokumen
perjanjian
dokumen
perjanjian
internasional ke depan ditangani oleh lembaga arsip nasional.
Sebagaimana
telah
diuraikan
sebelumnya,
bahwa
perjanjian
internasional adalah sebuah instrumen hukum yang berdampak atau
berimplikasi kepada kepentingan masyarakat, maka perlu kiranya diatur
mengenai partisipasi masyarakat sehingga ke depan setiap perjanjian
internasional yang dibuat oleh Pemerintah perlu membuka atau memberi
ruang bagi adanya partisipasi masyarakat.
B. RUANG LINGKUP MATERI
Sebagaimana
diketahui
sitematika
undang-undang
penggantian
terdiri atas dua bagian, yaitu Pasal I yang berisi materi pokok dan Pasal II
sebagai penutup. Oleh karenanya, ruang lingkup materi Undang-Undang
Penggantian
Atas
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:
1. Pasal I: Materi Pokok Penggantian
a. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah dengan rumusan: Perjanjian
Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu,
yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis
oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara,
organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya
yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Selanjutnya juga ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 10 dengan
rumusan: Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR
83
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
1A: yakni mengenai asas atau prinsip dalam pembuatan perjanjian
internasional, yaitu
1) Itikad baik;
2) persamaan kedudukan;
3) saling menguntungkan;
4) kemanfaatan;
5) saling menghormati;
6) berkedaulatan; dan
7) berkeadilan.
c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional
dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau
subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan
para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut
dengan itikad baik.
(2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik
Indonesia
berpedoman
memperhatikan
baik
pada
kepentingan
hukum
nasional
nasional,
maupun
dan
hukum
internasional.
d. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Lembaga negara, lembaga pemerintah baik kementerian maupun
nonkementerian,
dan
pemerintah
daerah,
yang
mempunyai
rencana untuk membuat Perjanjian Internasional, terlebih dahulu
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
(2) Pemerintah
Republik
pembuatan
Perjanjian
Indonesia
Internasional,
dalam
terlebih
mempersiapkan
dahulu
harus
84
menetapkan
posisi
Pemerintah
Republik
Indonesia
yang
dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
(3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat
persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut :
a. latar belakang permasalahan;
b. analisis permasalahan, yang ditinjau dari aspek politis dan
yuridis
serta
aspek
lain
yang
dapat
mempengaruhi
kepentingan nasional Indonesia; dan
c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan
untuk mencapai kesepakatan.
(4) Perundingan rancangan suatu Perjanjian Internasional dilakukan
oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau
pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup
kewenangan masing masing.
(5) Dalam hal Perjanjian Internasional berdampak pada kepentingan
daerah maka Pemerintah Daerah harus diikutsertakan dalam
keanggotaan delegasi Republik Indonesia.
e. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga
Pasal 7 dirumuskan sebagai berikut:
(1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan
tujuan
menerimaan
atau
menandatangani
naskah
suatu
perjanjian atau mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional,
memerlukan Surat Kuasa.
(2) Pejabat
yang
tidak
memerlukan
Surat
Kuasa
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah:
a. Presiden; dan
b. Menteri.
(3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan,
dan/atau menerima hasil akhir suatu Perjanjian Internasional,
memerlukan Surat Kepercayaan.
(4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan
dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut
85
ketentuan dalam suatu Perjanjian Internasional atau pertemuan
internasional.
(5) Penandatangan suatu Perjanjian Internasional yang menyangkut
kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang
sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan
suatu
lembaga
kementerian
negara
atau
maupun
lembaga
nonkementerian,
pemerintah,
baik
dilakukan
tanpa
memerlukan Surat Kuasa.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Surat Kuasa
dan Surat Kepercayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
f. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Pengesahan
Perjanjian
Internasional
dilakukan
sepanjang
dipersyaratkan oleh Perjanjian Internasional tersebut.
(2) Pengesahan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
Undang-Undang
atau
Peraturan
Presiden.
g. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
9A dengan rumusan sebagai berikut:
Pengesahan
Perjanjian
Internasional
dengan
undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan terhadap
Perjanjian Internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar
bagi
kehidupan
keuangan
negara,
rakyat
dan/atau
yang
terkait
mengharuskan
dengan
penggantian
beban
atau
pembentukan undang-undang.
h. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf,
yakni huruf g dan huruf h dengan rumusan sebagai berikut:
Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan undangundang apabila materi Perjanjian Internasional berkenaan dengan :
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan
negara;
86
b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara
Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
g. perdagangan; dan
h. pengelolaan sumber daya alam.
i. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C dengan rumusan sebagai berikut:
Pasal 10A
(1) Pengesahan Perjanjian Internasional mengenai pinjaman luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f,
meliputi substansi perjanjian antara lain nominal pinjaman, bunga
pinjaman, jangka waktu pinjaman dan pengakhiran pinjaman.
(2) Perjanjian
Internasional
mengenai
hibah
luar
negeri
yang
dimintakan persetujuan kepada DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, meliputi antara lain substansi
perjanjian, jenis, dan jumlah hibah luar negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman dan/atau hibah luar
negeri diatur dengan Undang-Undang.
Pasal 10B
(1) Dalam
pembahasan
Rancangan
Undang-Undang
tentang
Pengesahan Perjanjian Internasional bersama dengan Pemerintah,
DPR dapat mengajukan usul Pensyaratan, dan Pernyataan
terhadap materi Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1).
(2) Usul Pensyaratan dan Pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dapat
diajukan
terhadap
substansi
Perjanjian
Internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
87
Pasal 10C
DPR berhak tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan
undang-undang
tentang
pengesahan
Perjanjian
Internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) jika merugikan
kepentingan nasional.
j. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12
dirumuskan sebagai berikut:
(1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga
pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga
pemerintah,
baik
kementerian
maupun
nonkementerian,
menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan
undang-undang, naskah akademik atau rancangan peraturan
presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud
serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
(2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan
lembaga pemerintah, baik kementerian maupun nonkementerian,
mengoordinasikan
pembahasan
rancangan
dan/atau
materi
permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya
dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.
(3) Prosedur
pengajuan
pengesahan
perjanjian
internasional
dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.
k. Ketentuan Pasal 13 diubah dengan rumusan sebagai berikut:
Setiap undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan
perjanjian
internasional
ditempatkan
dalam
Lembaga
Negara
Republik Indonesia.
l. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
17A dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Lembaga
negara,
nonkementerian,
dan
kementerian
pemerintah
maupun
daerah
yang
lembaga
membuat
88
Perjanjian Internasional menyerahkan naskah asli Perjanjian
Internasional kepada Menteri.
(2) Naskah asli Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Internasional.
2. Pasal II Penutup
Sebagai konsekuensi dari penggantian norma Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2000, maka dalam penutup penggantian undang-undang
tersebut dirumuskan dua hal, yaitu:
a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
89
BAB VI
PENUTUP
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945)
memuat
baik
cita-cita,
dasar-dasar,
maupun
prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara dengan istilah
tujuan nasional, tertuang dalam alinea keempat, yaitu (a) melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b)
memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan
(d)
ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai citacita tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat
internasional
melakukan
hubungan
dan
kerja
sama
internasional yang mewujudkan dalam bentuk perjanjian internasional.
Beberapa konsepsi dasar yang perlu menjadi pertimbangan untuk
penyelenggaran perjanjian internasional adalah sebagai berikut :
a. memperjelas dan mempertegas asas dan prinsip negara dalam
melakukan perjanjian internasional.
b. mempertegas keterlibatan DPR tersebut dalam pembuatan perjanjian
internasional;
c. membuat batasan dan acuan yang tegas dalam pembuatan setiap
perjanjian internasional di bidang-bidang tertentu, terutama di
bidang
perdagangan dan sumber daya alam, yang selama ini
dianggap kurang menguntungkan negara;
d. membuat batasan dan acuan tegas dalam pembuatan perjanjian
internasional
yang
terkait
dengan
pinjaman
yang
dilakukan
pemerintah dan hibah yang diterima pemerintah.
e. melibatkan
pemerintah
daerah
dan
masyarakat
daerah
dalam
pembuatan perjanjian internasional yang memiliki implikasi langsung
maupun tidak langsung terhadap daerah yang bersangkutan;
f. mempertegas partisipasi masyarakat dalam pembuatan perjanjian
internasional; dan
90
g. membuka
akses
bagi
publik
mengenai
dokumen
perjanjian
internasional.
Dengan dibuatnya penggantian atas undang-undang ini diharapkan
bahwa perjanjian internasional dapat dilaksanakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dan melindungi segenap bangsa dari segala bentuk
penjajahan dalam bentuk apapun dan keterpurukan.
91