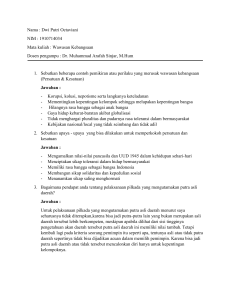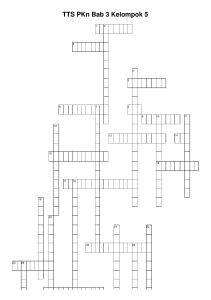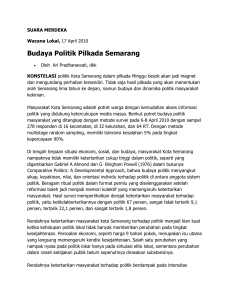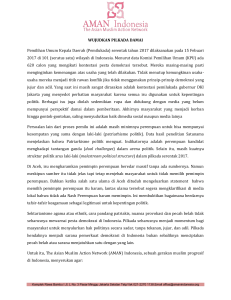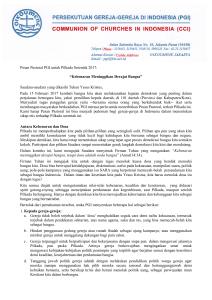Uploaded by
common.user109621
Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila: Polemik tentang Masa Depan Politik Indonesia
advertisement

i Sebuah Polemik Denny JA, Rocky Gerung, Christianto Wibisono, Ali Munhanif, Mun’im Sirry, Akhmad Sahal, Anick HT, Hatta Taliwang, Fahd Pahdepie, Taufan Hunneman, Zeng Wei Jian, Syaefudin Simon, Satrio Arismunandar, Jonminofri, Jojo Rahardjo, Dr. Umar S. Bakry, Hendrajit, Geisz Chalifah, Trisno S. Sutanto. Editor Anick HT Design & Layout Futih Aljihadi Cetakan Pertama, Juni 2017 Penerbit Inspirasi.co Book Project (PT CERAH BUDAYA INDONESIA) Menara Kuningan lt. 9G Jalan HR. Rasuna Said Kav V Blok X-7, Jakarta Selatan [email protected] | http://inspirasi.co ii Sebuah Polemik Denny JA, Rocky Gerung, Christianto Wibisono, Ali Munhanif, Mun’im Sirry, Akhmad Sahal, Anick HT, Hatta Taliwang, Fahd Pahdepie, Taufan Hunneman, Zeng Wei Jian, Syaefudin Simon, Satrio Arismunandar, Jonminofri, Jojo Rahardjo, Dr. Umar S. Bakry, Hendrajit, Geisz Chalifah, Trisno S. Sutanto. iii iv DAFTAR ISI Pengantar Paska Pilkada Jakarta: Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui: Denny JA | ix Bab I: Mengapa Demokrasi Pancasila Perlu Ditegaskan Kembali | 1 1. Analisis Survei Nasional LSI, 19 Mei 2017 Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila (Yang Diperbarui) - Denny JA | 3 2. Paska Pilkada Jakarta: Apakah Kebhinekaan Kita Terancam? - Denny JA | 11 3. Paska Pilkada Jakarta: Jangan Benturkan Keindonesiaan Versus KeIslaman - Denny JA | 21 4. Haruskah HTI Dibubarkan? - Denny JA | 29 5. Renungan Paska Pilkada dan Pengadilan Ahok: Pro Keberagaman Versus Pro Keberagaman di Pilkada Jakarta - Denny JA | 37 6. Bangkitnya Politik Identitas: Persepsi Terancam di Balik Aksi Lilin pro Ahok vs Demo Anti Ahok - Denny JA | 47 v Bab II: Pro Kontra Demokrasi Pancasila | 61 1. Demokrasi Pancasila yang Diperbarui, Apanya? Mun’im Sirry | 63 2. Memperbarui Cara Pandang Dan Cara Praktek Demokrasi Pancasila - M. Hatta Taliwang | 71 3. Meneguhkan kembali Demokrasi Pancasila yang Diperbarui - Taufan Hunneman | 101 4. Demokrasi Pancasila - Zeng Wei Jian | 107 5. Benarkah Kita Terbelah? - Anick HT | 113 6. Ahok Effect dan Pudarnya Demokrasi Pancasila Syaefudin Simon | 123 7. Upaya Memperbarui Demokrasi Pancasila - Satrio Arismunandar | 129 8. Momentum Pelembagaan Pancasila - Ali Munhanif | 143 9. Bug pada Demokrasi Pancasila - Jonminofri | 157 10. Membangun Demokrasi Pancasila Setelah Pilkada Jakarta 2017 - Jojo Rahardjo | 165 11. Memaknai Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui - Dr. Umar S. Bakry | 177 12. Pancasila, Kawah Candradimuka, dan Anti Absolutisme - Akhmad Sahal | 185 vi 13. Perlukah Kita Memperbarui Demokrasi Pancasila? - Fahd Pahdepie | 193 14. Saatnya Seluruh Komponen Bangsa Menggagas Rekonstruksi Nasional - Hendrajit | 199 15. Demokrasi Pancasila yang Diperbarui; Pancasila bukan Panacea - Rocky Gerung | 213 Pembaruan Demokrasi Pancasila dan Ancaman “NKRI Bersyariah” - Akhmad Sahal | 219 16. Demokrasi Pancasila yang Diperbarui; Indonesia 4.0 No 4 Sedunia Dalam Kualitas Pada Seabad 2045 - Christianto Wibisono | 229 17. Demokrasi Pancasila Dalam Praktek - Geisz Chalifah | 249 18. Membincang Ulang Demokrasi Pancasila Trisno S. Sutanto | 259 Epilog Indonesia Akan Dibawa Ke Mana? - Denny JA | 271 vii viii PENGANTAR Paska Pilkada Jakarta Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui Denny JA Juan Linz dan Alfred Stephan dua ahli dunia soal demokrasi. Mereka memberikan formula untuk mengenali negara yang masih dalam tahap transisi demokrasi, dan negara yang sudah dalam tahap konsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi masil labil dan masih mungkin kembali pada sistem lama yang otoriter. Sebaliknya konsolidasi demokrasi sudah stabil dan mengakar. Negara yang berada dalam tahap konsolidasi sukar untuk kembali ke era otoriter. Apa yang membedakan dua kondisi demokrasi itu? Ujar Linz dan Stephan, dalam negara konsolidasi demokrasi, aturan main demokrasi menjadi “the only game in town.” Para elit berpengaruh bisa berkompetisi mengenai segala hal. Namun mereka sepakat dan tidak mempertanyakan ix lagi bahwa mekanisme demokrasi yang menjadi aturan main bersama itu. Kuncinya demokrasi sebagai “the only game in town.” Bagaimana dengan Indonesia paska pilkada Jakarta 2017? Kebalikannya. Kita melihat masih “too many games in town.” Terlalu banyak gagasan yang dipertarungkan untuk menjadi aturan mainnya. Belum ada mekanisme tunggal yang dihormati sebagai “the only game in town.” Dan ini beresiko. Para elit, politisi berpengaruh, pemimpin pemerintahan, pengusaha, pemimpin partai, pemimpin ormas berpengaruh, pemimpin organisasi keagamaan, intelektual dan opinion makers yang didengar, mereka semua boleh saja berbeda pandangan dan kepentingan. Itu hanya tidak bermasalah, sekali lagi, itu hanya tidak merusak, jika mereka semua bersepakat untuk tunduk pada aturan main yang sama dan dihormati. Yang menjadi masalah jika aturan main bersama itu semakin kurang berwibawa, semakin dirasakan kurang akomodatif bagi perkembangan baru. Yang menjadi problem jika para elit ini jutru sedang menggugat aturan main bersama itu. Akibatnya konflik kepentingan dan perbedaan persepsi para elit justru akan membawa Indonesia pada ambang kehancuran. x Inilah renungan terjauh refleksi dari ruang publik Indonesia paska pilkada Jakarta. Persaingan antar kandidat dalam pilkada sudah selesai. Hasil KPUD soal pilkada sudah disahkan. Namun konflik gagasan dan embrio platform justru terus membara, berbeda bahkan bertentangan soal bagaimana aturan main bersama itu sebaiknya. Tulisan ini adalah renungan berisi empat pokok isu strategis paska pilkada Jakarta. Pertama, menjelaskan aneka embrio platform yang berbeda dan saling bertentangan yang ada saat ini mengenai kemana Indonesia harus dibentuk. Aneka platform itu ikut bertarung mewarnai pilkada DKI 2017. Kedua, argumen mengenai mengapa para elit perlu menegaskan komitmen pada demokrasi pancasila yang diperbarui. Juga dijelaskan apa beda demokrasi pancasila yang diperbarui dengan demokrasi Pancasila era Sukarno dan Suharto. Dijelaskan pula dimana bedanya Demokrasi Pancasila yang diperbarui dengan demokrasi liberal yang kini berlaku di dunia barat. Ketiga, penjelasan soal apa yang kurang dalam praktek demokrasi Indonesia saat ini agar mencapai platform ideal Demokrasi Pancasila yang diperbarui itu. xi Keempat, apa yang semua kita bisa kerjakan untuk ikut mengkonsolidasikan Demokrasi Pancasila yang dIperbarui. -000Empat platform gagasan terbaca ikut bertarung dalam pilkada Jakarta. Ada gagasan demokrasi modern seperti di negara maju yang sangat anti diskriminasi, dan juga sangat tidak suka dengan isu agama di ruang publik. Ada juga gerakan yang mencoba menyelinap untuk mengajak Indonesia kembali ke sistem sebelum amandemen UUD 45. Mereka mencari momentum agar dalam pilkada DKI terjadi pula breakthrough untuk memasukkan gagasan kembali pada demokrasi pancasila lama. Istilah yang populer di kalangan ini, demokrasi yang dipraktekkan sekarang sudah kebablasan dan terlalu jauh. Ada pula gerakan yang menjadikan momentum kasus Al Maidah untuk sekaligus memasukkan konsep negara Islam, atau setidaknya NKRI bersyariah. Ini gerakan yang menginginkan prinsip hukum agama semakin diterapkan dalam ruang publik. Ada pula platform gagasan yang mempertahankan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, namun xii perlu lebih diperbarui. Kita sebut saja ini gagasan Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Gagasan yang tidak berada di kubu Ahok hanya gagasan NKRI bersyariah ataupun negara Islam. Sedangkan di kubu Anies Baswedan, dan juga Agus Harimurti jauh lebih beragam. Semua penganut gagasan di atas juga berkumpul di belakang Anies dan Agus. Selesai pilkada, empat gagasan itu terus bertarung. Dugaan saya puncak pertarungan empat gagasan itu justru nanti di pilpres 2019. Sambil mendukung calon presidennya masing-masing, empat gagasan itu mencoba membuat agenda sendiri. Jika bisa membuat calon presiden berhutang budi pada mereka untuk menjadikan agenda gagasan itu sebagai program nasional. -000Langkah paling strategis paska pilkada Jakarta mengajak para elite yang berpengaruh untuk menegaskan komitmen kembali pada Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Dua alasannya. Mayoritas pemilih Indonesia ada di platform itu. Goresan agama yang mendalam pada batin publik Indonesia juga membuat platform itu lebih mengakar. xiii Demokrasi Pancasila yang diperbarui pastilah berbeda dengan negara Islam model Timur Tengah. Berbeda pula, ia dengan Demokrasi Pancasila sebelum amandemen UUD 45. Namun ia berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktekkan negara barat saat ini. Survei nasional dilakukan LSI Denny JA sejak 2005 sampai 2016. Juga survei Jakarta yang dilakukan terakhir di bulan April 2017. Ketika ditanya, apakah ibu bapak menginginkan Indonesia menjadi negara Islam seperti Timur Tengah, negara demokrasi liberal seperti negara barat, atau negara demokrasi pancasila (tak didefinisikan detail semua gagasan itu)? Jawaban pemilih. sejak 2005 sampai kini tak banyak berubah. Yang inginkan negara Islam selalu di bawah 10 persen. Yang inginkan demokrasi liberal juga selalu di bawah 10 persen. Yang inginkan Demokrasi Pancasila selalu di atas 70 persen. Negara Islam tidak mengakar dalam batin rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Demokrasi liberal barat juga masih asing bagi mayoritas publik Indonesia. Demokrasi Pancasila itu yang diidealkan. Jika soal Demokrasi Pancasila itu didetailkan, ingin kembali dalam sistem politik era Orde Baru tanpa kebebasan seperti sekarang, atau sistem demokrasi seperti xiv sekarang? Mayoritas memilih Demokrasi seperti saat ini. Negara Islam tidak akan cocok jika dipaksakan ke Indonesia. Ia ditolak oleh mayoritas pemilih Muslim sendiri. Dunia modern sudah pula sampai pada kultur citizenship. Siapapun warga negara, apapun agamanya, mereka punya hak politik yang sama dan perlindungan hukum yang sama. Negara modern tidak mendiskriminasikan hak warga negara semata karena identitas sosialnya, termasuk agama. Demokrasi Pancasila era Soekarno dan Suharto juga tidak pas jika dipaksakan kembali berlaku. Dwi fungsi militer, hadirnya utusan golongan yang tidak dipilih di MPR, presiden sebagai mandataris MPR, pembatasan pada kebebasan berasosiasi dan kebebasan berpendapat itu masa lalu. Mencoba membawa kembali Indonesia sebelum amandemen UUD 45 juga ditolak mayoritas pemilih dalam aneka survei nasional. Demokrasi liberal ala barat dengan civil liberty yang penuh, dan ruang publik yang kurang friendly dengan agama juga tidak mengakar. Memaksakan demokrasi liberal justru akan membuat antipati publik luas atas prinsip demokrasi secara menyeluruh. xv Harus diterima bahwa prinsip demokrasi hanya akan kuat jika ia dikawinkan dengan kultur lokal yang dominan di sebuah wilayah. Untuk kasus Indonesia, goresan agama dalam batin masyarakat sangat dalam. Demokrasi yang ingin mengakar harus mengakomodasi kondisi itu dalam sistem kelembagaannya. Hadirnya kementerian agama misalnya tak dikenal dalam demokrasi liberal barat. Namun untuk indonesia, kementrian agama sebuah kompromi yang seharusnya diambil. Evolusi kesadaran publik mayoritas Indonesia menghendaki pemerintah ikut mengurus agama publik. Itu yang tak ada dalam demokrasi liberal barat. -000Sungguhpun demikian, platform Demokrasi Pancasila yang diperbarui perlu dikonsolidasikan. Tiga isu di bawah ini yang perlu ditambahkan agar Demokrasi Pancasila yang diperbarui itu bisa diterima sebagai “the only game in town.” Ia akan diterima karena akomodatif terhadap aneka keberagaman yang ada. Pertama, justru karena demokrasi ini memberikan peran agama yang lebih besar di ruang publik, perlu dibuat sebuah undang undang Perlindungan Kebebasan dan Umat bergama. xvi UU ini mengatur bagaimana Pancasila yang sentral dalam demokrasi dioperasionalkan di ruang publik. Dengan demikian, praktek dan keberagaman paham agama yang ada terlindungi sangat kuat, sebagaimana yang dipahat dalam sila pertama Pancasila. Kementrian agama sudah mulai menyusun draftnya. Jika bisa, sebelum pilpres 2019, draft itu sudah disempurnakan dan final. Kita ingin dalam UU itu, aturan dibuat untuk lebih melindungi keberagaman agama dan kebebasan mereka beribadah dan bersosialisi di ruang publik. Kedua, mengakomodasi luasnya spektrum gagasan yang ada dalam masyarakat. Sejauh itu semua masih dalam bentuk gagasan, ia dibolehkan belaka untuk hidup di ruang publik. Yang dilarang hanya gagasan yang merekomendasikan kekerasan seperti terorisme. Atau gagasan yang dipaksakan dengan kekerasan. Akibatnya spektrum yang paling kanan dan yang paling kiri harus dibolehkan hidup. Melarang hak hidup gagasan, seberapapun ektremnya, kecuali yang merekomendasikan kekerasan dan kriminal, akan membuat aturan main bersama tidak akomodatif. Misalnya, pemerintah dan para elite harus menerima adanya kebebasan beropini bagi yang paling kanan: xvii gagasan negara Islam, dan yang paling kiri: gagasan LGBT, untuk menjadi wacana. Semua negara demokrasi modern membolehkan hak hidup aneka gagasan selucu dan senorak apapun. Prinsipnya ucapan Voltaire: Saya tak setuju pandangan tuan. Tapi hak tuan menyatakan pandangan itu akan saya bela. Yang dibela bukan isi gagasan itu tapi hak hidupnya untuk ikut mewarnai dan bertarung di ruang publik. Tak hanya pemerintah, tapi elite Indonesiapun kadang tak siap dengan prinsip Voltaire itu. Misalnya mereka yang mengaku pro keberagaman. Ketika diskusi LGBT dilarang, mereka marah dan melawan. Tapi ketika diskusi HTI soal khilafah Islam dilarang, mereka senang dan mendukung. Padahal prinsip Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Modern menjamin hak hidup aneka gagasan sejauh masih dalam bentuk gagasan, dan tidak menyerukan kekerasan ataupun tindakan kriminal. Mengapa negara demokrasi modern bahkan membolehkan gagasan intoleran di ruang publik? Sangat simpel alasannya. Di samping itu bagian dari Hak Asasi Manusia, gagasan ekstrem dan intoleran itu tak pernah mendapatkan dukungan mayoritas. Gagasan itu berhenti hanya menjadi estalase keberagaman saja. xviii Ketiga, prinsip kedua itu harus juga diikuti tegaknya law enforcement aparatur negara. Ini sepenuhnya harus disadari pemerintah. Ketika demokrasi masih labih seperti sekarang, pemerintah harus hadir! Pemerintah harus tegas dan keras melindungi keberagaman itu. Jika tidak, kebebasan yang ada justru digunakan untuk menindas yang lemah. -000Inilah buah paling manis selesai pilkada Jakarta 2017. Lahir hikmah keharusan kita untuk meneguhkan kembali komitmen pada Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Jika tidak, semua akan melawan semua. Masing-masing kita bisa berperan sesuai dengan pengaruh dan kapasitasnya. Satu saja targetnya. Kita ingin Demokrasi Pancasila yang diperbarui semakin lama semakin menjadi “the only game in town.” Dengan demikian, politik kita semakin stabil. Keberagaman gagasan yang ada juga terakomodasi, sesuai dengan evolusi kesadaran publik Indonesia. Tentu saja konsep demokrasi pancasila yang diperbarui di atas banyak kelemahannya. Tapi alternatif lain, akan lebih banyak lagi kelemahannya dan tidak mengakar. xix Kumpulan tulisan di buku ini langkah pertama untuk mewacanakan kembali pentingnya Pancasila sebagai perekat. Pancasila itu kemudian diterjemahkan ke dalam sistem kelembagaan pemerintahan. Sebanyak 18 penulis, aktivis, pemikir dan intelektual menyumbangkan gagasannya dalam buku ini. Sebuah survei nasional oleh LSI Denny JA pada bulan Mei 2017 sudah dibuat pula untuk menguji daya terima publik atas gagasan Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Buku ini diharapkan menstimulasi perumusan Demokrasi Pancasila yang lebih solid. Seperti yang dikatakan seorang filsuf: Tak ada kekuatan yang lebih powerful dibandingkan sebuah ide yang waktunya sudah datang. Mungkinkah waktu bagi ide “Demokrasi Pancasila (Yang Diperbarui) sudah datang? [] 1 Juni 2017 xx BAB I MENGAPA DEMOKRASI PANCASILA PERLU DITEGASKAN KEMBALI 1 2 Analisis Survei Nasional LSI, 19 Mei 2017 Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila (Yang Diperbarui) Denny JA Woodrow Wilson tipe pemimpin yang sangat jarang. Awalnya ia seorang akademisi ilmu politik yang dihormati dan kemudian menjadi presiden dari John Hopkins University (1902-1910). Namun situasi politik pelan pelan menuntunnya terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dua periode (1913-1921). Ia menjadi pemimpin politik dan akademik sekaligus. Ketika ditanya apa yang membuatnya sukses sebagai pemimpin, dan berhasil memimpin universitas dan negara, Wilson menjawab: Telinga seorang pemimpin harus terbuka dalam gelombang yang sama dengan suara komunitasnya dan suara rakyatnya. Dengarkan suara mereka yang kau pimpin. -Dengarkan dengan telinga yang benar. Itu kiat sederhana Wilson. 3 Saatnya kitapun membuka telinga, mendengar suara rakyat. Saatnya kita mendengar bagaimana pandangan rakyat seluruh Indonesia soal situasi muthakir? Bagaimana mereka melihat polarisasi masyarakat terutama setelah pilkada Jakarta. Selama ini yang kita dengar hanya suara elite saja. Atau suara rakyat Jakarta saja. Bagaimana dengan suara rakyat Indonesia di 34 propinsi? -000Mayoritas publik Indonesia, sebanyak 72.5 persen, tak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi masyarakat pro dan kontra Ahok. Polarisasi itu dinilai sudah melampaui persoalan pilkada dan potensial melonggarkan kebersamaan sebagai satu bangsa. Sebesar 75 persen rakyat menginginkan pemerintah beserta penentu kecenderungan masyarakat menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi pancasila sebagai perekat. Namun demokrasi pancasila yang dimaksud bukan pola kenegaraan era Orde Baru dan bukan sistem sebelum amandemen UUD 45. Demikianlah salah satu temuan survei nasional LSI Denny JA. Survei nasional ini dibuat khusus untuk membaca situasi nasional paska pilkada Jakarta. Res- 4 ponden sebanyak 1200 dipilih berdasarkan multi stage random sampling. Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 5-10 mei 2017. Survei ini dibiayai sendiri sebagai bagian layanan publik LSI Denny JA. Margin of error plus minus 2.9 persen. Survei dilengkapi dengan riset kualitatif seperti FGD, media analisis, dan depth interview nara sumber. -000Pilkada Jakarta menarik perhatian nasional. Sebanyak 75.8 persen penduduk Indonesia mengetahui dan mengikuti kontroversi yang muncul dalam pikada. Hanya 9. 5 persen yang menyatakan tak mengikuti dan tak tahu soal pilkada Jakarta. Sisanya, 14.3 persen menjawab rahasia atau tak menjawab. Berlarutnya kontroversi pilkada Jakarta hingga lahirnya gerakan lilin dan pro kontra membuat kekhawatiran. Sebesar 72.5 persen merasa tak nyaman. Mayoritas itu berpandangan polarisasi itu tak lagi sehat. Hanya sebesar 8.7 persen menyatakan polarisasi yang ada tidak mengkhawatirkan. Sisanya 18.8 rahasia dan tak jawab. Mayoritas publik ingin pemerintah dan penentu kecenderungan untuk lebih membuat upaya ekstra mere- 5 katkan masyarakat. Tapi sistem kenegaraan apa yang dipilh yang bisa merekatkan kembali masyarakat? Hanya 2.3 persen publik Indonesia menginginkan demokrasi liberal seperti yang dipraktekkan di Barat. Kecilnya prosentase ini sangat mengagetkan. Kata liberal dan kata barat di belakang kata demokrasi mungkin punya konotasi negatif dalam kesadaran publik. Hanya 8.7 persen yang menginginkan Indonesia mengadopsi negara Islam seperti di Timur Tengah. Sungguhpun 85 persen penduduk Indonesia Muslim namun hanya sedikit sekali menginginkan agama menjadi bentuk negara. Mayoritas publik 74 persen menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara dan perekat. Kata Pancasila di belakang demokrasi itu sudah sedemikian mengakar dalam benak publik. Sebanyak 15 persen rahasia dan tak menjawab. -000Besarnya rakyat Indonesia yang menginginkan demokrasi pancasila bervariasi di aneka segmen masyarakat. Namun di semua segmen itu, mayoritas menginginkan Demokrasi Pancasila. 6 Tapi apakah demokrasi pancasila yang dimaksud oleh responden? Yang pasti 68, 7 persen menyatakan itu bukan demokrasi pancasila era Orde Baru. Itu bukan demokrasi pancasila sebelum amanden UUD 45. Elemen penting demokrasi pancasila Orde Baru sudah ditinggalkan sejak era reformasi dan turunnya Suharto. Dwi fungsi militer, utusan golongan yang tak dipilih di MPR, presiden sebagai mandataris MPR, dan terbatasnya kebebasan berserikat serta beropini, itu elemen Orde Baru yang tidak disukai rakyat masa kini. Namun demokrasi pancasila yang lebih detail, yang disetujui publik luas, memang sulit dieksplor melalui kuesioner survei opini publik. Saya (Denny JA) mencoba menyusun konsep demokrasi pancasila yang diperbarui. Data survei dan instrumen riset lain menjadi fondasinya. Ini lima elemen demokrasi pancasila yang diperbarui. Tambahan kata “yang diperbarui” di belakang demokrasi pancasila sebagai pembeda dengan demokrasi pancasila era pak Harto. Bisa pula digunakan bahasa dunia digital. Jika demokrasi pancasila masa Pak Harto disebut demokrasi pancasila 7 1.0, maka demokrasi pancasila yang diperbarui, disebut demokrasi pancasila 2.0. Pertama, demokrasi pancasila mengadopsi mekanisme politik umumnya demokrasi seperti di negara maju. Demokrasi pancasila juga mengadopsi aneka hak asasi manusia yang dirumuskan PBB. Itu persyaratan minimal sebuah sistem kenegaraan untuk sah disebut demokrasi modern. Termasuk di dalam prinsip itu kesamaan hak sosial politik ekonomi semua warga negara, apapun identitas sosialnya. Hak persamaan kaum minoritaspun sentral untuk dilindungi. Kedua, namun berbeda dengan demokrasi di dunia barat, agama memainkan peran sentral dalam mayoritas perilaku warga. Hadirnya kementerian agama menjadi modifikasi demokrasi pancasila. Di negara demokrasi lain, tak mengenal kementerian agama. Ketiga, hadirnya UU yang melindungi kebebasan agama dan kepercayaan masyarakat. Justru karena peran agama yang lebih besar dalam prilaku masyarakat, perlu ada UU yang melindunginya. Aneka aturan soal agama saat ini berserak serak dalam aneka peraturan lain. Saatnya itu semua disatukan, namun dalam kerangka UU yang lebih melindungi kebe- 8 basan agama. UU itu belum ada dan sedang dimatangkan di kementrian agama. Keempat, Pancasila menjadi perekat bangsa. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai simbol kebersamaan. Masing-masing tokoh berpengaruh agama melihat Pancasila sebagai “common ground,” titik tengah yang bisa disepakati. Dan akan jauh lebih mengakar jika Pancasila dilegitimasi sebagai mutiara yang terdapat dalam ajaran agama dan kepercayaannya sendiri. Kelima, pemerintah di bawah presiden dimandatkan konstitusi dan undang undang menjaga dan melindungi keberagaman itu. Gagalnya pemerintah menjaga keberagaman dan persatuan dapat menjadi bahan untuk memecat presiden. -000Presiden Jokowi baru saja menyerukan masyarakat untuk menghentikan semua aksi yang memperuncing polarisasi. Ujar presiden, hentikan saling hujat, saling fitnah, saling demo, karena kita bersaudara. Seruan presiden itu sejalan dengan temuan survei LSI Denny JA yang ingin semua kita merekatkan kembali 9 kebersamaan. Tanggal 20 Mei 2017 menjadi momentum yang baik untuk kembali menegaskan demokrasi pancasila yang diperbarui untuk dijadikan aturan main bersama. Jangan terlalu lama kita berkubang dalam peristiwa yang sudah lewat. Segetir apapun peristiwa itu. Satukan enerji mencari titik temu aturan main bersama di ruang publik agar harmoni, bersatu dan damai menaungi aneka keragaman dan kepentingan. Kita jadikan “Demokrasi Pancasila yang diperbarui” (apapun namanya sejauh dengan substansi yang sama) sebagai “the only game in town.” [] 10 Paska Pilkada Jakarta Apakah Kebhinekaan Kita Terancam? Denny JA Keberagaman, ujar Robert Casey, harga yang harus kita bayar jika ingin hidup dalam dunia modern yang kompleks. Apa yang dikatakan Robert Casey sudah menjadi “common wisdom,” diaminkan oleh mayoritas. Merawat keberagaman, hidup damai dalam perbedaan, saling menghormati berbagai persepsi di ruang publik, menjadi fondasi utama bangunan demokrasi modern. Namun benarkah keberagaman di Indonesia kini terancam? Benarkah fondasi Pancasila goyah paska kalahnya Ahok dan menangnya Anies? Selesai pilkada Jakarta, saya membaca banyak kegelisahan. Aneka Isu negatif meluas terutama di social media: di facebook, twitter dan berbagai kelompok WA. Misalnya isu itu seperti ini. Setelah pilkada Jakarta, kini pilkada Jabar diserbu isu agama serupa. Bersiaplah. Isu 11 agama akan meluas dan digunakan untuk mengalahkan tokoh moderat di aneka pilkada lain. Mendung untuk keberagaman Indonesia. Atau, selamat merayakan kemenangan pilkada Jakarta. Bersenang-senanglah di atas runtuhnya fondasi keberagaman bangsa. Tanpa sadar mereka tak hanya merayakan kemenangan pilkada. Tapi sebenarnya mereka merayakan kalahnya fondasi keberagaman Indonesia. Atau, mereka yang memberi peluang politisasi agama, harap catat. Pada waktunya, mereka sendiri akan ditelan oleh gelombang itu. Mereka mengira politisasi agama hanya alat sesaat saja untuk pilkada. Mereka lupa, politisasi agama itu akan menjadi monster yang melahap mereka dan keberagaman kita. Dari nada dan aura aneka berita tersebut ada kekhawatiran yang meluas. Seolah kalahnya Ahok di Jakarta menjadi penanda kalahnya komunitas pro keberagaman. Atau menangnya Anies-Sandi di Jakarta akan membawa gerbong semakin dominannya syariah Islam di dunia publik. Benarkah kekhawatiran itu? Sedang terancamkah kebhinekaan kita? 12 Saya mengapresiasi kekhawatiran itu, dan positif atas upaya menjaga keberagaman. Namun saya membantah kekhawatiran itu dengan tiga hal. Pertama, data. Kedua, data. Ketiga, data! -000Saya memegang data sebelas kali survei Jakarta sejak Maret 2016 sampai April 2017. LSI melakukan survei paling banyak dibanding lembaga survei lain. Dinamika opini publik dan persepsi aneka segmentasi pemilih terbaca jelas dalam sebelas kali survei itu. Tak benar kalahnya Ahok berarti kalahnya semangat keberagaman. Yang mengalahkan Ahok di Jakarta adalah melting pot, kumpulan aneka kepentingan. Mereka disatukan oleh persepsi yang sama: Ahok harus dikalahan. Titik! Memang ada alasan tak ingin memilih Ahok semata karena Ahok berbeda agama. Namun jauh lebih banyak di segmen itu menolak Ahok bukan karena agama Ahok, tapi persepsi mereka atas arogansi Ahok. Bukan karena agama Ahok tapi karena Ahok dianggap menista agama mereka. Apakah benar Ahok menista agama? Pengadilan yang akan memutuskan. Namun mayoritas pemilih punya 13 persepsi Ahok menista agama, seperti yang terekam dalam survei berkali-kali. Mereka dengan sentimen agama adalah the angry voters, pemilih yang marah. Yang dominan di kalangan segmen ini bukanlah pemilih yang begitu taat dan saleh dengan agamanya. Umumnya mereka bukanlah pendukung syariat Islam di dunia publik. Banyak pula segmen anti Ahok yang justru aktivis keberagaman, HAM, dan demokrasi. Bagi mereka Ahok buruk untuk keberagaman. Demokrasi Indonesia masih labil. Di tangan pemimpin yang tak sensitif dengan pernyataan publik soal agama, akan membuat fondasi keberagaman yang labil itu semakin goyah. Bagi mereka, justru untuk meneguhkan keberagaman, Ahok harus dikalahkan. Tentu saja mereka pro Pancasila. Jika ditanya, ibu bapak sekalian, apakah ibu bapak inginkan demokrasi modern seperti barat, negara Islam seperti di Timur Tengah, atau negara Pancasila? Yang inginkan negara Islam, syariah Islam di ruang publik, di bawah 10 persen. Di atas 70 persen pemilih Jakarta, termasuk yang memilih Anies-Sandi menginginkan Pancasila. 14 Data membantah kekhawatiran itu. Yang mengalahkan Ahok bukan minoritas pendukung negara Islam, tapi justru mayoritas pendukung negara Pancasila! Itu adalah data, bukan teori, bukan harapan! -000Sering ditanyakan, mengapa pendukung Anies Sandi yang pro keberagaman bersedia bekerja sama dengan aneka kelompok intoleran? Bukankah ini berarti memberi panggung bagi membesarnya kelompok yang anti keberagaman? Jawaban atas pertanyaan ini adalah visi dan fakta sejarah, bukan lagi data. Demokrasi membolehkan semua warga negara yang sah untuk berkumpul, mendukung atau melawan siapapun. Begitulah mozaik isu publik yang terjadi dalam praktek demokrasi modern. Untuk satu isu, aneka kelompok yang berbeda bisa menyatu dalam satu posisi yang sama. Namun menghadapi isu lain yang berbeda, mereka yang bersatu itu bisa bahkan saling berhadapan. Bersatu atau berhadapan, itu tergantung dengan isu sosial yang datang. 15 Tak usah heran dan itu biasa saja jika dalam kubu yang anti Ahok itu berkumpul kelompok yang sebenarnya bertentangan. Ada FPI, HTI yang dianggap garis keras. Namun ada juga aktivis keberagaman dan HAM di sana. Ada NU. Ada Muhammadiyah. Visi demokrasi membolehkan mereka berkumpul dan bersatu. Tak ada prinsip demokrasi yang dilanggar. Namun bersatunya mereka hanya untuk isu pilkada saja. Mereka diikat kepentingan yang sama mengalahkan Ahok. Mengapa Ahok harus dikalahkan? Mereka punya alasan berbeda bahkan bertentangan. Survei LSI sudah mengujinya. Ketika ditanya apakah sebaiknya Indonesia menerapkan sistem negara Islam? Pendukung anti Ahok itu terpolarisasi pro dan kontra saling berhadapan. Di kalangan anti Ahok dan pendukung Anies, lebih banyak yang kontra negara Islam ketimbang yang pro. Ini juga data. -000Mengapa kelompok yang pro keberagaman di kubu Anies Sandi membiarkan garis keras mendapat panggung dan semakin eksis di ruang publik? 16 Begitulah visi demokrasi modern. Di Amerika Serikat, ada KKK yang rasialis kulit putih. Ada pula kelompok Elijah Mohammad yang rasialis kulit hitam. Mereka dibolehkan hidup di ruang publik. Merekapun dibolehkan ikut pemilu, ikut berkampanye. Mereka dibebaskan memilih siapa yang harus didukung dan dilawan. Yang dilarang kemudian, bukan gagasannya yang dianggap rasialis. Yang dilarang hanya jika mereka melakukan tindakan kriminal. Ujar John Rawls, jika kelompok toleran ternyata tidak toleran kepada kelompok intoleran, maka kelompok toleran itu berubah karakternya menjadi kelompok intoleran. Kelompok yang toleranpun harus ikhlas bahwa ruang publik itu milik bersama. Demokrasi dan HAM baik teori ataupun praktek, membolehkan kelompok intoleran di ruang publik. Sejauh masih dalam dunia gagasan, gagasan yang toleran dan intoleran sama-sama dibolehkan hidup. Dalam pasar bebas dunia gagasan, mereka dipersilahkan bersaing meyakin publik. Yang dilarang adalah tindakan kriminal, kekerasan dan hate speech. Namun larangan itu berlaku bukan hanya 17 untuk pelaku gagasan yang intoleran. Ia juga diterapkan untuk pelaku gagasan yang toleran. Mengapa demokrasi modern tidak takut dengan gagasan intoleran yang mungkin akan mematikan demokrasi itu sendiri? Dalam kurva pasar bebas dunia ide, gagasan intoleran umumnya hanya minoritas saja, di ekstrem kiri atau kanan. Mayoritas publik tetaplah pelaku gagasan toleran. -000Kemenangan Anies Sandi justru kemenangan isu kebhinekaan yang lebih kokoh. Kebhinekaan justru labil jika diwarnai ketimpangan sosial. Kebhinekaan justru negatif jika tidak disertai kuatnya rasa persatuan. Menang telaknya Anies-Sandi di putaran kedua justru karena gagasan itu: kebhinekaan yang berkeadilan sosial dan diwarnai rasa persatuan yang kuat. Dengan isu di atas, Anies-Sandipun menang dalam segmen pemilih kelas menengah. Tanpa isu kebhinekaan, semata isu agama, Anies-Sandi hanya menang di pemilih menengah bawah saja. Anies akan menang tipis atau bahkan kalah tipis. 18 Justru isu kebhinekaan yang membuat Anies-Sandi tak hanya menang, tapi menang telak. Ini juga data. Saya senang ikut merumuskan tema itu bersama Anies Baswedan. Digitroops di bawah Fahd Pahdepie membuatkan videonya. Digitroops memainkan isu itu secara massif di media sosial. Saya juga senang ikut membantu Prabowo tampil tegas sekali soal isu keberagaman itu. Digitroops juga membuat video Prabowo dengan pernyataan sangat tegas. Ujar Prabowo, saya menjadi orang pertama yang akan menurunkan Anies-Sandi jika tak setia pada kebhinekaan, Pancasila dan NKRI. Kebhinnekaan kita tidak terancam dengan kalahnya Ahok dan menangnya Anies. Kebhinekaan kita justru sedang dalam proses diperkokoh dgn isu keadilan sosial dan persatuan. Pilkada sudah selesai. Mari kita move on, melangkah ke depan. Yang menang didukung dan dibantu. Yang kalah dihormati dan dirangkul. Keberagaman akan terus tumbuh di Indonesia. Bahkan jika Batman, Superman, Ironman dan tokoh superhero lain bersatu sekalipun untuk menghapus keberagaman, mereka tak akan berhasil. [] 19 20 Paska Pilkada Jakarta Jangan Benturkan Keindonesiaan Versus KeIslaman Denny JA Marcus Garvey tokoh kontroversial. Namun tetap ada kutipan darinya yang layak dikenang. Ujarnya membangun sistem pada sebuah bangsa, tapi tidak mengambil elemen terbaik kultur dominan bangsa itu, sama dengan menegakkan pohon tanpa akar. Dengan kata lain, itu bukan saja pekerjaan yang sia-sia. Namun itu kebodohan paling elmenter. Sistem apapun yang akan ditegakkan disana justru akan dilawan oleh mayoritas masyarakatnya sendiri. Perlawanan itu akan sangat kokoh karena didukung oleh kultur yang sudah mengakar. Berangkat dari kutipan itu, kitapun melihat Indonesia paska pilkada Jakarta. Membangun Indonesia modern, membangun keberagaman, tanpa menegaskan kesamaannya dengan interpretasi terbaik dari kultur dominan di Jakarta (Indonesia), itu sebuah blunder yang fatal! 21 Mayoritas masyarakat harus justru harus diyakinkan. Sistem politik yang ingin kita bangun itu sejalan belaka dengan pemahaman terbaik keyakinannya. Platform nasional yang ingin ditegakkan hanyalah ekspresi berbeda dari interpretasi terbaik kulturnya sendiri. Namun apakah kultur dominan di Indonesia yang tak boleh diabaikan? -000LSI Denny JA sudah melakukan survei nasional berkalikali sejak tahun 2005 hingga tahun ini, 2017. Dua fakta kultural ini harus selalu dijadikan referensi. Pertama, agama dalam batin publik Indonesia sangat mendalam. Pemahaman mereka atas ajaran agama akan mewarnai orientasi, pilihan dan pedoman prilaku. Hanya di bawah 20 persen dari rakyat Indonesia yang menyatakan (self-claim) agama tidak menjadi bagian penting aktivitas pribadi dan publiknya. Kedua, Demokrasi Pancasila, apapun definisinya, dianggap lebih dari 70 persen rakyat Indonesia sebagai platform nasional Indonesia yang paling mereka pilih. Walaupun mayoritas rakyat itu Muslim, hanya di bawah 10 persen populasi Indonesia yang menginginkan nega- 22 ra Islam. Dan ternyata hanya di bawah 10 persen populasi Indonesia yang menginginkan demokrasi liberal seperti di dunia barat. Dari survei itu: Agama dan Demokrasi Pancasila menjadi kunci. Sistem apapun yang ingin kita jadikan platform nasional, harus dikemas sedemikian rupa bahwa sistem itu mengakar para interpretasi terbaik dari agama dan Demokrasi Pancasila. Sebanyak 85 persen dari populasi Indonesia beragama Islam. Mayoritas rakyat harus justru diyakinkan platform nasional yang akan ditegakkan berangkat dari nilai terbaik Islam sendiri. Karena itu ini juga warning untuk pemimpin, politisi, aktivis, ulama, opinion makers, dan penentu kecenderungan. Jangan pernah menghadap-hadapkan antara Keindonesiaan vesus keislaman, kebhinekaan versus Islam, Pancasila versus Islam, demokrasi versus Islam. Jangan pernah membuat publik luas seolah harus memilih antara Keindonesiaan atau Keislaman, Pancasila atau Islam, Kebhinekaan atau Islam, demokrasi atau Islam? Ini akan membuat dua hal. Platform nasional yang akan kita terapkan tak akan pernah mengakar dan ditolak. 23 Lebih jauh, Indonesia akan mengalami keretakkan kultural yang parah. -000Pancasila adalah platform yang simbolik. Ia bukan sistem politik ekonomi yang operasional seperti kapitalisme atau komunisme. Justru itu sekaligus juga kekuatannya. Pancasila lebih bisa diinterpretasi sesuai kemajuan peradaban. Dibandingkan semua platform lain, Pancasila menjadi ikon keindonesiaan yang sudah mengakar. Langkah berikutnya meyakinkan mayoritas Muslim bahwa Pancasila itu mutiara yang digali dari ajaran terbaik Islam sendiri. Di bawah ini, ikhtiar yang kuat secara konsep dan efek praktisnya. Aneka sila Pancasila disandingkan dengan ayat ajaran Al Quran sendiri. Sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat Al_Quran: Dialah Allah, yang Maha Esa (QS: Al Ikhlas- 1) Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 24 Ayat Al-Quran: Hendaklah kamu menjadi manusia yang adil (QS: An Nisa: 135) Sila ketiga: Persatuan Indonesia Ayat Al-Quran: Dan kami jadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal- mengenal (QS: Al Hujurat: 13) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayat Al-Quran: Sedangkan keputusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS: Asy Syuro: 38) Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ayat Al Quran: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan melakukan kebaikan (QS: An Nahl: 90) Penting untuk disebarkan seluasnya. Pancasila itu digali dari akar spiritual bangsa Indonesia sendiri. Dengan sendirinya, ia ikut digali dari ajaran Islam. Keindonesiaan menjadi mutiara dari Keislaman sendiri. -000- 25 Bagaimana dengan hak dan perlindungan hukum kaum minoritas? Dalam Pancasila, warga negara minoritas juga dilindungi dan diperlakukan sama. Melindungi dan memberikan hak hak kewarga negaraan yang sederajat itu bagian dari prinsip negara modern yang tak bisa dihindari dan harus terus dilindungi. Dalam Demokrasi Pancasila, semua warga negara apapun agamanya bisa menjadi pemimpin. Ini juga harga mati unruk membangun sistem demokrasi modern. Namun tentu saja setiap individu bebas memilih pemimpinnya, baik seagama ataupun tidak. Itu sepenuhnya hak individu, tergantung persepsi individu itu sendiri. Warga Kristen yang memilih pemimpin beragama Kristen, warga Muslim yang memilih pemimpin Muslim, wanita yang ingin memilih pemimpin wanita, kulit hitam yang ingin memilih pemimpin kulit hitam, itu semua sah saja. Itu bagian dari hak asasi manusia yang juga dilindungi. Bahkan mereka dibolehkan berkampanye atas pilihannya sebagai bagian dari kebebasan beropini dan berasosiasi. Seorang aktivis feminis boleh berkampanye untuk memilih pemimpin wanita yang dianggap akan lebih peka 26 dengan perjuangan wanita. Pendeta boleh berkhotbah di gereja menyerukan umat memilih domba Allah yang kini berjuang dalam pemilu. Hal yang sama untuk ulama yang juga dibolehkan berkampanye memilih pemimpin satu agama. Apakah dengan demikian mustahil terpilih pemimpin minoritas? Jawabnya semua serba mungkin. John F kennedy yang katolik terpilih di Amerika yang mayoritasnya Protestan. Obama yang kulit hitam terpilih dalam pemilu yang mayoritas pemilihnya kulit putih. Dan Teras Narang yang beragama minoritas di proponsi Kalimantan Tengah terpilih di sana yang mayoritas pemilihnya Muslim. Teras Narang terpilih dua kali pula untuk dua periode jabatan gubernur. Itu semua tergantung dari crafmanship tokoh yang bersangkutan -000Kapankah demokrasi modern di Indonesia stabil? Dengan mengacu pada uraian di atas, demokrasi modern akan stabil di Indonesia, ketika mayoritas publik Indonesia, yang minoritas ataupun Muslim, meyakini bahwa demokrasi dan Pancasila itu adalah mutiara dari ajaran agamanya sendiri. Dan bagi yang muslim, itu semua adalah mutiara dari ajaran Islam sendiri. 27 Ke sanalah para pemimpin, aktivis, intelektual, ulama, politisi harus berjuang. [] 28 Haruskah HTI Dibubarkan? Denny JA “Jika kita tak bisa menyamakan perbedaan, kita tetap bisa membuat dunia lebih aman agar perbedaan kita bisa tumbuh berdampingan dengan damai.” Itu kutipan John F Kennedy yang layak menjadi pedoman bagi siapapun yang ingin membangun negara modern dan peradaban. Suka atau tak suka, evolusi peradaban menuju pada semakin beragamnya gagasan dan gaya hidup. Semakin modern sebuah masyarakat, semakin ia mengalami diversity. Seruan paling bijak menghadapi hukum alam evolusi peradaban: Hiduplah damai dalam keberagaman itu. Musuh bersama bukan perbedaan gagasan. Apapun gagasan itu. Musuh bersama adalah kekerasan dan pemaksaan kehendak yang membuat keberagaman itu tak bisa berdampingan secara damai. Dengan prinsip di atas, saya menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati mengambil langkah hukum membubarkan sebuah organisasi. Harus direnungkan 29 dengan keras, langkah itu justru akan lebih mampu merawat keberagaman Indonesia? Atau justru akan mencabik-cabik keberagaman Indonesia lebih jauh. Adakah peluang HTI mengubah haluan negara Indonesia? Adakah peluang HTI mengubah NKRI menjadi khilafah? Adakah kekerasan sistematis yang dilakukan HTI yang membahayakan ruang publik kita? Dua alasan di bawah ini membuat saya menyarankan pemerintah lebih berhati-hati membubarkan sebuah organisasi. -000Pertama, adakah peluang HTI mengubah haluan negara? Mengubah haluan negara hanya bisa lewat parlemen dan pemerintahan. Membuat UU saja membutuhkan proses ketat lobi partai politik di DPR dan pemerintahan eksekutif. Bulak balik berbulan-bulan belum tentu DPR dan pemerintah selesai merumuskan sebuah UU. Apalagi untuk mengubah konstitusi negara. Selama era reformasi sejak 1998, hampir 20 tahun lalu, amandemen konstitusi hanya terjadi satu kali. 30 Tentu saja perangkat politik yang bisa mengubah haluan negara hanya partai politik. Tanpa partai politik, tak ada pintunya mengubah haluan negara. Sementara empat partai politik terbesar partai sangat kuat elemen nasionalisnya. PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, selaku empat partai terbesar harus ditaklukkan dulu untuk mengubah haluan negara. Mungkinkah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat mendukung Khilafah HTI misalnya? Itu hal yang mustahil. Atau dalam bahasa gaul, di balik itu “hil yang mustahal! Di luar DPR, opini publik Indonesia punya nada yang sama. Silahkan dilakukan survei nasional. Di atas 70 persen populasi Indonesia mengidealkan Demokrasi Pancasila. Hanya di bawah 10 persen yang inginkan negara Islam. Dari 10 persen itu, jauh lebih sedikit lagi yang menginginkan sistem khilafah meleburkan NKRI dalam pan nasionalisme yang menjadi gagasan HTI tersebut. Bagaimana bisa mengubah batin Indonesia yang sudah terbentuk mengakar ratusan tahun? Baik dari sisi politik formal, ataupun opini publik, tak ada celah mengubah haluan negara. 31 Satu satunya cara mengubah haluan negara dengan angkat senjata memimpin pemberontakan. Maukah dan mampukah HTI melakukannya? Yang akan dilawan oleh siapapun yang melakukan pemberontakan senjata tak hanya TNI. Mereka juga perlu melawan para pengusaha, media, civil society dan mayoritas penduduk Indonesia. Dengan melihat realitas praktis di atas, tak ada yang ditakutkan dengan gagasan ataupun eksistensi HTI. Ibarat taman bunga, kembang HTI hanya tumbuh kecil saja di pojok sana. Ia tak akan bisa memakan dan menyeragamkan ribuan bunga yang berbeda di taman itu. -000Kedua: Bukankah keberagaman itu tak terhindarkan? Saya tak setuju pandangan tuan. Tapi hak tuan menyampaikan pandangan itu akan saya bela sampai mati. Itu pernyataan terkenal dari Voltaire. Sikap Voltaire menjadi spirit demokrasi. Bahkan dalam khazanah yang lebih tua, Islampun punya prinsip yang sama: tak ada paksaan dalam agama. Jika agama saja tak perlu dan tak bisa dipaksa, apalagi gagasan yang lebih rendah dari sakralitas agama. 32 Keberagaman adalah ongkos yang tak terhindari untuk hidup di dunia modern. Apa daya begitu banyak gagasan dan gaya hidup, termasuk ideologi, pemikiran yang berbeda dan saling bertentangan. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi lahir justru untuk mengatur keberagaman itu agar bisa hidup berdampingan dengan damai. Pastilah yang fanatik sunni tak suka dengan fanatik syiah. Begitu pula sebaliknya. Yang fanatik percaya Tuhan tak suka yang fanatik anti Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Yang fanatik hetroseksual tak suka LGBT. Yang fanatik pro keberagaman tak suka gagasan yang anti keberagaman dan yang intoleran. Tapi apa daya? Itu semua evolusi kesadaran masingmasing individu. HAM lahir untuk melindungi hak individu meyakini semua gagasan di atas. Di dunia modern, yang unik, lucu, norak, ekstrem lahir tak terhindari. Suka atau tak suka, silahkan telan! Demokrasi lahir untuk memberikan semua gagasan itu kesempatan yang sama hidup dan bertarung di ruang publik secara damai. Yang ekstrem A punya hak hidup. Yang ekstrem anti A diberikan hak hidup yang sama. Silahkan bersinerji dengan cerdas dan non-kekerasan. 33 Justru dari sinergi ribuan gagasan yang berbeda, bahkan bertengangan, bisa saling kupas, saling isi, saling tambah, saling kurang, menjadi sintesa kultural yang lebih tinggi. Yang dilarang hanyalah pemaksaan dengan kekerasan dan tindakan kriminal. Itu sebabnya mengapa KKK yang sangat rasis dan memuja supremasi kulit putih tetap boleh hidup di Amerika Serikat. Hak hidup yang sama diberikan kepada Nation of Islam yang memuja supremasi kulit hitam. Pasar bebas demokrasi memiliki hukumnya sendiri. Mereka yang ekstrem selalu minoritas. Gagasan mereka akan dilawan bukan saja oleh ektrem di ujung lainnya. Mereka juga akan dilawan oleh mayoritas yang ada di tengah. Namun pertukaran gagasan antar mereka yang beragaman itu memajukan peradaban. Gerakan supremasi kulit hitam misalnya bisa tetap memberikan inspirasi pentingnya keadilan ekonomi bagi kulit hitam. Selalu mungkin ada akar ketimpangan ekonomi di balik gagasan ekstrem itu. Hadirnya kelompok ekstrem itu bisa menjadi simulasi perbaikan sistem makro. Satu satunya yang diharamkan dalam keberagaman adalah kekerasan, pemaksaan kehendak dan krimi- 34 nal. Pelaku kekerasan dari KKK yang membunuh dan menyalip kulit hitam dikejar aparat dan dihukum keras. Film Holywood Missipi Burning sangat epik menggambarkan itu. Tapi organisasi KKK dan gagasan supremasi kulit putih dibiarkan hidup. Individu tak boleh dipenjara hanya karena gagasannya. HTI, seaneh apapun gagasannya dapat diperlakukan serupa. Namun, sekali ada pimpinan dan pengikut HTI melakukan kekerasan, ia harus ditindak. Prinsip ini berlaku juga untuk organisasi lain. Bahkan pembela Pancasilapun jika melakukan kekerasan harus pula ditindak. Kekerasan, bukan gagasan, yang menjadi musuh bersama. -000Kita menghargai upaya pemerintah untuk merawat keberagaman. Justru karena kita cinta keberagaman. Justru karena kita membela Pancasila. Justru karena kita rindukan demokrasi. Kita memberi saran pemerintah untuk lebih berhati-hati membubarkan organisasi. Pikirkan presedennya. Pikirkan apa yang disebut “unintended consequence,” efek tak terduga. 35 Organisasi dapat dibubarkan. Tapi gagasan di dalamnya selalu bisa tumbuh justru dalam bentuk yang lebih berbahaya jika bergerak di bawah tanah. Gagasan apapun lebih baik resmi dan terpantau, ketimbang tak resmi dan gerilya diam diam. Kita tidak hidup 24 jam melalukan kebaikan dan keburukan. Lebih baik individunya yang dihukum jika ia terbukti melakukan kejahatan. Itupun harus lewat pengadilan. [] 36 Renungan Paska Pilkada dan Pengadilan Ahok Pro Keberagaman Versus Pro Keberagaman di Pilkada Jakarta Denny JA Huston Smith seorang scholar terpandang ahli perbandingan agama. Bukunya The World’s Religion terjual lebih dari 2 juta kopi. Ia mendalami aneka agama dan keberagaman pandangan di dalamnya. Kutipan yang terkenal dari Huston Smith: “All Isms end up in schism.” Semua paham yang ada, agama ataupun ideologi sekuler, ketika berevolusi dan membesar akan berakhir dalam spektrum penafsiran yang bertentangan. Selalu terjadi schism, polarisasi pandangan dalam batin internal agama atau ideologi itu. Dalam Islam, misalnya, lahir Sunni versus Syiah. Dalam Kristen, lahir Katolik versus Protestan. Dalam Marxisme, lahir komunisme versus Marxis yang anti komunisme. 37 Kadang pertengkaran Sunni versus Syiah, lebih keras ketimbang Islam vs Kristen. Hal yang sama terjadi dalam pertengkaran internal Protestan vs Katolik. Atau antar penganut paham Marxisme A VS Marxisme B, Kapitalisme A VS Kapitalisme B, Demokrasi A VS Demokrasi B, Nasionalisme A VS Nasionalisme B, dan aneka isme lainnya. Dalam pilkada Jakarta, kita juga menyaksikan pertengkaran dua jenis aktivis, intelektual yang keduanya mengklaim pro keberagaman. Pertengkaran dua kubu ini tak kalah sengitnya. Yang satu pro Ahok, yang satu anti Ahok. Yang satu mengharamkan digunakannya UU penistaan agama untuk Ahok, yang satu membolehkan bahkan menganjurkan. Yang satu menolak bekerja sama dengan kelompok yang dianggap intoleran, yang satu tidak mempermasalahkannya. -000Data sudah berbicara. Yang menangkan Anies-Sandi bukanlah semata Islam radikal, sebagaimana banyak diulas media barat. AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik) asosiasi lembaga survei pertama di Indonesia. Di tahun 2009, AROPI 38 berhasil mematahkan dua UU di MK yang melarang diumumkannya quick count di hari pemilu. Berkat perjuangan AROPI, kini kita menikmati quick count. Kita tahu siapa yang menang pemilu sebelum KPU memutuskan seminggu atau sebulan kemudian. AROPI baru saja mengumumkan temuannya. Penganut Islam Radikal, jika didefisinikan menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, hanyalah di bawah 10 persen dari populasi Jakarta. Mustahil komunitas 10 persen semata bisa memenangkan Anies-Sandi yang memperoleh 58 persen dukungan. Terdapat lebih dari 90 persen pemilih Jakarta yang tidak mengidealkan negara Islam. Mereka pro keberagaman. Mereka pro demokrasi. Justru di segmen ini, kontribusi paling besar kemenangan Anies Sandi. Dalam komunitas 90 persen populasi Jakarta, terdapatlah dua kubu pro keberagaman itu. 42 persen di kubu Ahok. 48 persen di kubu Anies. Pro keberagaman versus pro keberagaman. Ternyata populasi pro keberagaman yang memilih Anies-Sandi lebih banyak dibandingkan pro keberagaman yang memilih Ahok. 39 Mengapa? Apa perbedaan sesungguhnya dari konsep pro keberagaman pro Ahok vesus pro keberagaman kontra Ahok? Dua kubu pro keberagaman itu terpolarisasi dalam perbedaan atas tiga isu penting. Memang belum ada konsep utuh menyeluruh masing masing kubu untuk menggambarkan konsep mereka. Saya mencoba mengkonstruksikannya dari serpihan argumen yang berserakan. Untuk memudahkan analisa, saya sebut saja pro Keberagaman yang memilih Ahok dengan Kelompok A. Yang satunya kelompok kontra A. Isu satu: Ahok baik atau buruk untuk keberagaman? Kelompok A: Ahok baik untuk keberagaman. Jika ia terpilih apalagi di ibu kota akan menjadi contoh revolusioner. Bahwa mayoritas dan minoritas kini tak menjadi masalah di ruang publik. Ahok yang triple minority (agama, etnis, pendatang), dipilih oleh mayoritas populasi DKI dalam pemilu bebas dan langung. Ini lompatan signifikan bagi perjuangan tanpa diskriminasi. 40 Virus ini segera menjadi pesan ke suluruh air. Indonesia sudah berada dalam kultur demokrasi dan kebhinekaan yang matang. Sangat sangat matang. Kelompok kontra A: Ahok buruk untuk keberagaman. Justru untuk kepentingan keberagaman, Ahok harus dikalahkan. Ia tidak peka dengan emosi massa, apalagi yang sensitif soal agama. Kehadiran Ahok justru memberikan panggung kepada Islam garis keras untuk tampil dan membesar. Kita memang butuh tokoh minoritas untuk menang dalam teritori mayoritas sebagai contoh. Tapi tokohnya harus yang friendly, yang bersahabat, yang tidak dianggap mengancam. Ahok bukan tipe itu. Ia bahkan berkasus “menista” agama mayoritas. Ahok harus dikalahkan bukan karena ia minoritas. Ia harus dikalahkan karena dapat lebih merusak keberagaman yang masih labil. Jika yang dicap menista agama menang, polarisasi akan semakin merusak keberagaman yang masih labil. Kita harus menunggu tokoh minoritas lain yang lebih sesuai. Spirit mengalahkan Ahok justru untuk keberagaman jangka panjang yang lebih stabil. 41 Isu dua: Perlu atau Dilarang menerapkan UU Penistaan Agama? Kelompok A: Jangan pernah menggunakan UU penistaan agama. UU itu bertentangan dengan sistem demokrasi. Kali ini Ahok korbannya. Besok lusa pihak lain atau anda sendiri. Menggunakan UU penistaan agama merupakan penghianatan atas prinsip demokrasi, HAM dan Kebhinekaan. Siapapun yang mendukung penerapan UU penista agama penghianat keberagaman! Kelompok kontra A: Bahkan di negara demokrasi seperti Denmark, Kanada dan Jerman, UU Penistaan agama juga diterapkan. Itu hal yang sah saja. Sejarah masing masing negara menghasilkan nuansa demokrasi yang berbeda. Toh UU itu pernah diuji melalui proses lembaga demokratis di MK. Dalam proses ini UU itu diperkuat. UU itu hadir dalam hukum nasional. Law enforcement atas UU yang ada justru bagian demokrasi. Silahkan UU itu dibawa kembali untuk dibanding ke MK. Atau dihapus oleh UU Perlindungan Umat Beragama yang baru. Tapi sekali UU itu masih ada, masih berlaku pastilah ia sah, halal, dan sesuai dgn prinsip demokrasi untuk dieksekusi. 42 Isu Ketiga: Boleh atau dilarang bekerja sama dengan kelompok toleran dalam pilkada/pemilu? Kelompok A: Jangan pernah bekerja sama dengan kelompok intoleran, spt FPI, HTI, dll. Mereka anti keberagaman. Bekerja sama dengan mereka itu seperti memelihara anak macan. Ketika membesar, dirimu pun akan dilahapnya. Keberagaman dalam bahaya. Mereka yang bekerja sama dengan kelompok intoleran menghianati keberagaman. Itu sama dengan memelihara perusak di rumah sendiri. Kelompok kontra A: Demokrasi itu untuk semua, apalagi ormas yang berbadan hukum yang sah. Bekerja sama dengan siapapun yang dibolehkan hukum nasional adalah pilihan taktis yang valid belaka. Mereka yang dianggap intoleran punya hak sosial yang sama, yang dilindungi konstitusi. Apakah kerja sama dalam pilkada Jakarta akan membuat kelompok intoleran membesar? Pasar bebas dunia gagasan akan membuat kelompok apapun yang ekstrem tetap minoritas. Dunia modern selalu multi isu. Hal yang biasa di satu isu, aneka kelompok bersatu untuk sebuah kepentingan. 43 Untuk isu lain, kelompok yang bersatu itu bahkan bertentangan. Itulah demokrasi. Take it easy! Tak ada masalah membuat koalisi politik yang taktis untuk satu kepentingan. Itu hal yang lazim belaka. -000Para pendukung pro keberagaman harus mulai membuka mata. Bahwa ada schism, ada banyak mazhab dalam paham keberagaman sendiri. Mereka harus menyadari hukum gagasan seperti yang disebut Huston Smith: “Every ism end up in schism.” Jangan merasa gagasan kubu mereka sebagai satu satunya pewaris yang sah pejuang keberagaman. Di luar mereka seolah murtad belaka. Pada titik inilah kita mengaminkan John Rawls ketika ia mengatakan: Kelompok toleran yang tidak toleran kepada hak hidup gagasan yang berbeda dengan mereka (yang mereka anggap gagasan intoleran), sesungguhnya sudah mengubah watak mereka sendiri menjadi bagian dari kelompok intoleran. Apakah ini berarti kita harus mendukung gagasan intoleran? NO! Kita lawan gagasan mereka di ruang 44 publik. Namun kita hormati hak hidup mereka selama mereka memang ormas yang sah berdasarkan hukum Indonesia. Tapi pemerintah harus menjadi wasit yang tegas menghukum siapapun yang melakukan kekerasan, pemaksaan dan kriminal. Jika ruang publik seperti ini bisa terbentuk di Indonesia, saya menyebutnya sistem Demokrasi Pancasila yang diperbarui. [] 45 46 Bangkitnya Politik Identitas: Persepsi Terancam di Balik Aksi Lilin pro Ahok vs Demo Anti Ahok Denny JA George S Patton oleh sejarahwan dianggap satu dari panglima perang paling sukses dalam sejarah. Ia memimpin tentara Amerika Serikat sukses memenangkan perang dunia kedua. Ia membagi pengalamannya dalam perang. Ujarnya suatu ketika: rasa takut yang mengendap cukup dalam di hati seorang individu jusru bisa menjelma menjadi kekuatan ekstra untuk berjuang. Rasa takut yang dialami bersama oleh sebuah kelompok, karena merasa survival kelompoknya terancam, justru menjadi enerji luar biasa untuk melawan. Saya menggunakan kutipan Geoge S Patton untuk memahami gerakan anti Ahok ataupun pro Ahok. Lama saya merenung, enerji apakah gerangan yang membuat pilkada Jakarta sedemikian semarak, baik sebelum kampanye dimulai, dan setelah pilkada selesai. 47 Tak pernah terjadi sebelumnya, gerakan pro kontra seorang kandidat sepanas, seheboh, dan se “wow” kasus Ahok di Pilkada Jakarta 2017. Tak pernah terjadi sebelumnya di aneka pilkada, begitu banyak massa terlibat bahkan dari luar teritori yang mempunyai hak memilih untuk pilkada. Melalui renungan jenderal Patton di atas, saya menangkap adanya rasa takut, dan persepsi terancam baik di kubu pro Ahok ataupun Anti Ahok. Rasa takut dan terancam? Ya! Itu yang membuat gerakan pro dan kontra menjadi super heboh, melampaui rata rata. Aksi 411, 212 yang kontra Ahok, begitu emosional dan melibatkan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan massa. Hal yang sama, aksi lilin pro Ahok paska Ahok dipenjara juga emosional dan terjadi di banyak kota. Ini fenomena bangkitnya politik identitas paska reformasi. Sentimen politik berdasarkan agama dan etnik kembali mengemuka. Apakah sebabnya? Bagaimana menciptakan sistem kelembagaan makro agar sentimen politik identitas itu justru akhirnya bersinergi positif. -000- 48 Rasa takut dan persepsi terancam dialami oleh mereka yang pro Ahok ataupun anti Ahok. Memang belum ada abstraksi komprehensif menggambarkan jenis rasa takut di dua kubu yang bertentangan itu. Saya cukup beruntung karena mendengar batin kelompok ini. Sejak maret 2016 hingga tulisan ini dibuat, Mei 2017, saya (LSI Denny JA) melakukan sebelas kali survei opini publik Jakarta, dan satu survei nasional. Saya aktif membaca puluhan berita setiap hari sebagai peneliti ataupun konsultan politik soal pilkada Jakarta. Saya ikuti aneka sosial media: facebook, twitter dan WA grup dua kelompok yang bersebrangan pro dan kontra Ahok. Dari aktivitas saya menyelami batin pilkada Jakarta, tergambar jenis ketakutan dan persepsi terancam itu. Pertama, Rasa Takut dan Persepsi Terancam di kubu Pro Ahok Empat jenis rasa takut dan terancam ini berkombinasi. Setelah Ahok divonis penjara, di bulan Mei pula, membangkitkan sebagian akan memori Tragedi Mei 1998. Itu situasi ketika kekerasan menimpa etnis Tionghoa. Itu kondisi ketika etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. 49 Masih gelap hingga kini seberapa banyak korban yang sebenarnya, baik kurban nyawa terutama kurban kekerasan seksual. Banyak warga etnis Tionghoa yang migrasi ke luar negeri untuk sementara ataupun permanen. Memori tersebut menjadi penambah enerji kekuatan pro Ahok. Harus dilakukan reaksi yang agak ekstra agar kasus Ahok tidak menimpa etnis minoritas pada umumnya. Demikian yang terbaca. Tersingkirnya Ahok dalam pilkada Jakarta juga dikhawatirkan menjadi presden yang akan diulang di tempat lain. Kesempatan minoritas untuk ikut menjadi pemimpin dalam sebuah teritori akan tertutup. Isu minoritas agama dan etnis ternyata ampuh dimobilisasi terlepas sebagus apapun kinerja kandidat minoritas itu. Di balik itu, dikwatirkan pula berkuasanya aksi massa melampaui instrumen politik yang lebih tertata. Ada bayangan aksi massa ini yang berhasil menekan para hakim menjatuhkan vonis penjara buat Ahok melampaui tuntutan Jaksa. Ada kekhawatiran aksi massa ini menuntun pada mobokrasi, berkuasanya tokoh yang semata populer di mata aksi massa walau tidak kompeten. Yang paling dikwatirkan tentu bangkitnya Islam Politik. Kekalahan Ahok dianggap buah karya signifikan dari 50 politisasi isu agama. Pelan pelan Indonesia dikhawatirkan menjelama menjadi NKRI bersyariah. Karena itu, sebelum terlambat, hanya ada satu kata: Lawan! Jika perlu gunakan lobi internasional untuk menekan. Mereka juga khawatir pemerintahan Jokowi akhirnya tunduk pada sentimen massa dalam rangka pilpres 2019. Isu kebangsaan, keberagaman, kebebasan sipil, kesetaraan warga negara terlepas apapun identitas sosialnya, dikwatirkan mengendur. Kombinasi rasa takut dan persepi terancam di atas menjadi kekuatan luar biasa. Karena persepsi itu gerakan lilin, solidaritas Ahok, pawai kebhinekaan meluas ke banyak kota. Kedua, Rasa Takut dan Persepsi Terancam Kubu Kontra Ahok. Kubu kontra Ahok juga memiliki rasa ketakutan dan persepsinya sendiri. Ahok dianggap hanya fenomena dari ekonomi politik yang lebih besar. Ada kekwatiran munculnya dominant minority. Ahok jika terpilih sebagai gubernur akan menjadi pintu masuk paling signifikan bagi dominant minority. 51 Istilah itu mengacu pada lahirnya kelompok etnis minoritas tapi sangat dominan. Mereka tak hanya menguasai dan dominan atas ekonomi sebuah negara. Namun mereka juga mulai mengarah berkuasa untuk jabatan politik dan budaya. Sudah menjadi pengetahuan umum. Dari katakanlah 50 orang terkaya Indonesia, sangat dan sangat mayoritas datang dari warga etnis Tionghoa. Ada kekwatiran etnis Tionghoa tak hanya puas dengan dominasi bisnis, namun segera pula menguasai politik. Bangunan sebuah bangsa akan rentan jika yang dominan justru yang minoritas. Ini akan menjadi rumput kering yang mudah disulut menjadi keresahan emosional. Persepsi di atas bercampur pula dengan rasa kwatir mayoritas warga menjadi powerless majority. Mereka hanya banyak dalam jumlah, namun tak berdaya dalam ekonomi dan politik. Kekhwatiran ini menghinggapi tak hanya massa, namun juga elit. Tak hanya mereka yang kuat dan keras sentimen Islamnya. Tapi juga itu menghantui mereka yang menyebut dengan bangga kaum pribumi. Ketakutan ini semakin disulut oleh apa yang dipersepsikan dengan arogan minoritas. Di sinilah titik paling lemah dari Ahok. Bukan hanya ia minoritas secara etnik 52 dan agama. Tapi ia tercatat dan dipersepsikan sebagai minoritas yang arogan. Ia memaki seorang ibu dengan sebutan maling. Ia menyatakan bersedia membunuh 2000 orang demi 10 juta penduduk. Ibu yang menangis digusur dikatakannya bermain sinetron. Di TV enteng saja ia berulang menyebut taik taik. Persepsi minoritas yang arogan itu menemui puncaknya ketika Ahok bicara soal Al Maidah. Akumulasi kemarahan sebelumnya menjadikan kasus Al Maidah sebagai titik temu. Dibalik besarnya gelombang Al Maidah, itu tak hanya sentimen agama yang bekerja. Namun ia juga menjadi kanalisasi kemarahan publik luas atas “minoritas arogan” yang dipersepsikan ke Ahok. Kasus minoritas yang arogan menjadi lebih tersulut oleh kisah yang menimpa gubernur NTB Tuan guru bajang. Ia dimaki juga oleh seseorang dengan sebutan “dasar pribumi, tiko!” Kebetulan steven yang memaki itu seorang minoritas pula. Ada yang mengartikan tiko sebagai tikus kotor. Ada yang mengartikan babi dan anjing. Di era sosial media, segera kisah itu menyulut sensitivitas banyak orang 53 muslim dan pribumi. Mereka semakin kwatir minoritas tak hanya berkuasa tapi juga arogan, dan enteng saja menghina. Mentang-mentang! Bisa jadi kekhawatiran itu berlebihan. Namun dalam emosi massa, persepsi itu menyebar efektif. Kasus ini ikut pula menyumbangkan kekalahan telak Ahok. Hal di atas sempat terekam dalam batin komunitas pro dan kontra Ahok. Sebagian faktual. Mungkin juga sebagian ilusi. Sebagian nyata. Mungkin pula sebagian hanya imajinasi. Sebagian murni. Sebagian mungkin rekayasa. Namun semua itu bersinergi membentuk persepsi. Dan politik adalah persepsi. -000Rasa takut dan persepsi di atas sangat nyata. Emosi itu ikut membangkitkan kembali dan menyulut politik identitas. Sistem politik ekonomi bagaimana yang harus kita kembangkan untuk mengakomodasi sentimen di atas? Lalu bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi sinergi yang positif? Politik identitas adalah pengelompokan politik berdasarkan sentimen identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Ini identitas paling tua dalam 54 politik praktis. Kekuatan sentimen ini mengendur atau menguat sepanjang sejarah. Yang pasti ia tak pernah memudar hingga ke era digital dan post-modern. Kalangan Marxis pernah mengecam munculnya politik identitas. Ia dianggap mengaburkan pengelompokkan politik yang seharusnya bersandar pada kelas saja: buruh verus pemodal. Kalangan liberalis juga banyak mengecam tampilnya politik identitas. Bagi mereka sebaiknya pengelompokkan politik sudah bergeser hanya pada ideologi modern, partai politik, atau program kerja (public policy). Namun politik identitas menunjukkan sumbangan yang positif bagi munculnya kesetaraan warga negara. Politik kulit hitam bergerak menuntut persamaan hak. Kaum feminis bersuara soal emansipasi. Agamawan berseru dihapusnya diskriminasi. Kini kaum gay lesbian meminta perlindungan hukum bagi hak sosialnya. Rasa tak adil yang dialami sebuah grup identitas acapkali memicu lahirnya politik identitas. Kesetaraan warga negara apapun identitas sosialnya menjadi buah paling manis gerakan politik identitas. Suka atau tidak, kultur modern kesetaraan warga negara, apapun identitasnya, sumbangan gerakan ini, kini menjadi fondasi negara modern. 55 Umumnya politik identitas ini tumbuh di kalangan minoritas yang memang powerless. Lebih ironi lagi, sentimen itu kadang juga tumbuh di kalangan mayoritas yang powerless. Jika minoritas yang powerless, itu jamak belaka. Tapi jika mayoritas yang powerless itu kasus khusus dan berbahaya. Contohnya kulit hitam di Afrika Selatan, melawan dominant minority kulit putih. Atau Kelompok Syiah di Irak melawan dominan minority Sunni. Atau suku Hutus melawan dominan minority suku Tutsi di Rwanda. Namun jika politik identitas dimainkan berlebihan, disertai kekerasan, ia justru berpotensi merusak ruang publik sebuah negara yang beragam. Tantangan negara dan bangsa yang beragam membuat politik identitas itu tetap berada dalam porsi yang normal. Tapi apakah ukuran porsi normal itu? Bisakah politik identitas itu diakomodasi tapi tetap memberikan sinergi yang positif? Banyak yang bisa kita kerjakan bersama untuk Indonesia, termasuk proposal ini. Saya menyebutnya Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Empat komponen di bawah ini saling melengkapi. Satu tak terpisahkan dari yang lain. Ada yang bersifat kelem- 56 bagaan. Ada yang bersifat craftmanship peran aktor. Dan ada yang bersifat kultural. Ini empat unsur Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Pertama, menegaskan persamaan hak warga negara dan mengakui semua jenis hak asasi yang sudah disetujui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Di era demokrasi, semua warga, apapun identitas sosialnya, memiliki hak yang sama, bahkan untuk memimpin. Mengadopsi aneka hak asasi yang diakui PBB membuat Indonesia mengakomodasi puncak peradaban. Kedua, toleransi hadirnya peran agama di ruang publik. Berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi pancasila memiliki kementerian agama. Pemerintah ikut berperan menjaga harmoni agama warga. Ada satu hal yang perlu ditambahkan: UU Perlindungan Umat Beragama. Justru karena dosis agama di negeri Pancasila itu lebih dibandingkan negara demokrasi liberal, perlu ada aturan hukum tingkat tinggi. Namun UU itu lebih diarahkan untuk menjamin keberagaman agama serta kepercayaan. Ketiga, pemerintah diamanatkan bertindak tegas dan keras menjaga keberagaman itu. Seseorang tak boleh dipenjara hanya karena punya mimpi atau punya cita 57 cita sosial, atau memiliki gagasan senorak atau selucu apapun. Bahkan tak ada paksaan dalam agama. Apalagi untuk paham yang sekuler, tiada paksaan pula. Namun sekali individu atau kelompo melakukan kekerasan dan kriminal, mereka harus cepat ditindak negara. Bukan gagasan, tapi kekerasan yang membuat seseorang harus ditindak secara hukum. Keempat, kultur politik yang sabar untuk mematangkan demokrasi. Walau secara hukum, minoritas memiliki hak untuk memimpin, namun dibutuhkan kematangan kultural agak lama untuk membuat minoritas bisa memimpin mayoritas secara damai dan diterima. Amerika Serikat merdeka tahun 1776. Baru di tahun 1953, lebih 170 tahun kemudian bisa terpilih seorang presiden yang bukan protestan: John F Kennedy yang katolik. Baru di tahun 2008, lebih 230 tahun kemudian bisa terpilih yang bukan kulit putih: Obama yang kulit hitam. Dan kini 240 tahun kemudian, capres wanita di AS selalu kalah. Semua diterima sebagai evolusi kultural yang lumrah belaka. Hukum sudah mengatur persamaan hak sosial mayoritas dan minoritas. Namun kematangan kultur menerima minoritas menjadi pemimpin itu sebuah 58 proses yang lebih panjang. Itu juga membutuhkan jenis pemimpin minoritas yang tidak dianggap ancamam oleh mayoritas. -000Demokrasi itu seperti bunga Lisianthus. Ia cantik dan sangat berharga. Namun butuh kesabaran merawatnya. Merawat bunga Lisianthus memerlukan suhu yang pas, air yang cukup, dan tahapan perkembangan yang natural. Keinginan mempercepat mekarnya bunga Lisianthus justru bisa membuat bunga itu mati. Hal yang sama dengan demokrasi. Tak bisa kita menyatakan “bim salabim” lalu demokrasi yang ideal langsung tumbuh di Indonesia. Kasus pro dan kontra Ahok menjadi proses belajar yang berharga. Seperti yang dikatakan Jendral George S Patton, marilah kita mengenali rasa takut dan persepsi terancam di masing masing kubu. Marilah kita berdiri menggunakan sepatu pihak sana. Demokrasi Pancasila yang diperbarui bisa menjadi titik awal kita mencari solusi kelembagaan bersama untuk ruang publik Indonesia ke depan. [] 59 60 BAB II MENGAPA DEMOKRASI PANCASILA PERLU DITEGASKAN KEMBALI 61 62 Demokrasi Pancasila yang Diperbarui, Apanya? Mun’im Sirry Asisten Professor di Fakultas Teologi Universitas Notre Dame, USA Saya menyambut ajakan Sdr. Denny JA untuk merejuvenasi peran Pancasila setelah tampak meredup dan bahkan cenderung “menghilang” pasca Reformasi 1998. Ajakan Denny itu menjadi lebih signifikan karena dua alasan. Pertama, beberapa perkembangan mutakhir, terutama Pilkada Jakarta, telah memperlihatkan ancaman nyata tentang apa yang disebut Denny “Indonesia [yang] akan terkoyak dan tidak stabil.” Seperti diprediksi, dampak perseteruan antar-pendukung calon pasangan gubernur yang menyeret isu agama dan SARA secara umum ke dalam pusaran politik berjangkauan luas melampaui periode Pilkada itu sendiri. Kedua, absennya diskursus Pancasila dalam hampir dua dekade terakhir justeru dibarengi dengan menguatnya 63 radikalisme agama. Fenomena intoleransi agama belakangan sudah sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun tidak ada kekerasan agama yang massif seperti terjadi di Maluku pada awal runtuhnya Order Baru, tapi pelanggaran terhadap kelompok minoritas terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sinilah letak pentingnya meneguhkan komiteman pada Pancasila untuk menjaga dan memperkuat ke-bhinneka-an. Namun Sdr. Denny JA bukan sekedar menyerukan agar komitmen pada demokrasi Pancasila kembali diteguhkan, melainkan juga mengajak memikirkan kembali “Pancasila yang diperbarui.” Sepanjang tulisannya, Denny menggunakan kalimat pasif “Pancasila yang diperbarui”, dan bukan “memperbarui Pancasila”. Saya tidak ingin menebak-nebak pilihan kalimat pasif tersebut, tapi menarik didiskusikan lebih lanjut: Apanya dari demokrasi Pancasila yang perlu diperbarui? Proyek Demokrasi yang Belum Selesai Implisit dalam argumen Sdr. Denny JA adalah bahwa Pancasila merupakan proyek demokrasi yang belum selesai sehingga perlu terus diperbarui. Ini merupakan lompatan pemikiran yang pentingnya setelah sebelumnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyerukan agar Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka. Saya 64 melihat Cak Nur membuka jalan agar Pancasila terbuka untuk ditafsirkan ulang, dan Denny JA berijtihad merekonstruksi demokrasi Pancasila yang lebih relevan dalam konteks Indonesia saat ini di mana peran asertif Islam di ruang publik semakin tak terelakkan. Terlepas bahwa ijtihad Denny ini perlu penjabaran lebih detail, upaya meneguhkan demokrasi Pancasila yang diperbarui yang digagasnya perlu menjadi diskursus dan perdebatan publik. Dalam alam kebebasan pasca runtuhnya Order Baru, kata “Pancasila” menjadi istilah ingin terus dihindarkan dalam perbincangan publik. Jika ada yang menyebutnya, biasanya dimaksudkan untuk meledek atau memojokkan pihak tertentu. Penyebutan kata “Pancasila” diidentikkan dengan menghadirkan kembali rezim Order Baru (Orba). Kesan negatif seperti ini sepenuhnya dapat dipahami. Sepanjang zaman Orba, Pancasila telah dijadikan instrumen kekuasaan untuk menindas lawan-lawan politik. Ketika represi terhadap politik Islam tidak mempan dengan cara mereduksi aspirasi politik Muslim ke dalam satu partai politik yang dikontrol oleh negara, pemerintahan Orba mengharuskan semua partai politik dan organisasi massa untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penyeragaman ideologi yang dilakukan secara represif oleh Orba mendapat reaksi keras dari sebagian kalangan. Memang, organisasi-organisasi keagamaan 65 besar seperti NU dan Muhammadiyah tidak kesulitan menerima kebijakan asas tunggal Pancasila karena, bagi mereka, secara prinsipil Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Namun demikian, cara-cara represi rezim Orba untuk memaksakan penyeragaman ideologi tersebut telah menjadikan Pancasila berstigma negatif. Itulah sebabnya sesaat setelah Orba tumbang eforia keterbukaan diiringi dengan sentimen anti-kebijakan Orba terkait Pancasila. Misalnya, sidang Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR) pertama pasca Reformasi yang mengesahkan sistem multi-partai dan perluasan hak-hak sipil juga menghentikan indoktrinasi Pancasila (P4) yang digunakan rezim Suharto untuk mensosialisasikan Pancasila. Dengan banyaknya partai Islam yang lahir pasca Reformasi yang menjadikan Islam sebagai asasnya, maka filsafat negara multi-agama Pancasila tidak lagi menjadi “common denominator”. Dengan kata lain, penghapusan undang-undang yang mengharuskan asal tunggal hanya menambah momentum bagi menjamurnya dan menguatnya Islam politik. Perlu segera ditambahkan, menghidupkan kembali P4 bukanlah pilihan di era demokrasi seperti sekarang. Ketika Cak Nur menggagas supaya Pancasila menjadi ideologi terbuka, dia ingin mengatakan bahwa negara tidak lagi punya hak monopoli untuk menafsirkannya. Kini kita melihat buahnya: Seorang Denny JA menawarkan 66 tafsir “demokrasi Pancasila yang diperbarui”. Tiga aspek demokrasi Pancasila yang diperbarui yang disebutkan Denny (memberikan peran agama yang lebih besar di ruang; mengakomodasi luasnya spectrum gagasan; dan law enforcement) memberikan pijakan dasar tapi terlalu dini untuk dievaluasi karena perlu penjabaran lebih lanjut. Sambil menunggu penjabaran itu, saya ingin urun rembuk mendiskusikan “apanya” yang diperbarui. Diperbarui Dari dan Diperbarui Untuk… Apa yang akan saya tulis berikut ini diinspirasikan oleh wacana yang berkembang dalam kajian kebebasan beragama (religious freedom): bebas dari apa dan untuk apa (from dan for). Yang pertama disebut kebebasan dalam pengertian negatif (misalnya, bebas dari pemaksaan, persekusi) dan kedua disebut kebebasan positif (misalnya, kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama). Dari model “kebebasan negatif ” dan “kebebasan positif ” ini saya ingin mengelaborasi – walaupun sebagai singkat – demokrasi Pancasila yang diperbarui dari apa dan untuk apa. Kenapa distingsi ini penting? Sebab, pertama, penting agar kita dapat menyusun strategi yang tepat. Sdr. Denny JA menyebut beberapa platform untuk mengonsolisasikan gagasannya, tapi tanpa distingsi yang jelas saya khawatir strategi konsolidasi itu tidak 67 tepat sasaran. Kedua, distingsi itu diperlukan supaya kita tahu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan supaya dampak demokrasi Pancasila yang diperbarui berjangkauan luas. Misalnya, seseorang tidak mungkin dapat bebas untuk melaksanakan ajaran agama sebelum dia bebas dari restriksi dan persekusi. Kita masing-masing dapat membuat daftar dari apa saja demokrasi Pancasila perlu diperbarui. Misalnya, diperbarui dari kesan negatif yang melekat dari cara rezim Orba menerapkannya. Diperbarui dari tafsir tunggal yang monopolistik. Diperbarui dari identifikasi Pancasila sebagai proyek Orba. Diperbarui dari pemahaman bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup. Diperbarui dari kesan bahwa Pancasila sudah outdated dan perlu diganti dengan ideologi lain, dan seterusnya. Poin-poin ini bukan hanya dapat terus ditambahkan, tapi juga perlu dijabarkan lebih lanjut. Pemahaman terhadap dari apa demokrasi Pancasila diperbarui dapat memantapkan keimanan kita pada Pancasila sebagai ideologi yang dibutuhkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah berikutnya ialah aspek positif dari gagasan demokrasi yang diperbarui. Untuk apa Pancasila diperbarui? Lagi-lagi, kita dapat menyusun daftar apa yang ingin dicapai dari proyek (saya gunakan kalimat positif) “memperbarui demokrasi Pancasila.” Diperbarui untuk mengembalikan ruh dan nilai-nilai ideal yang dicita-ci68 takan oleh para pencetusnya. Diperbarui untuk menjaga keutuhan Indonesia yang plural. Diperbarui untuk membendung ideologi-ideologi lain yang mengancam ke-bhinneka-an kita sebagai bangsa dengan agama dan etnik yang beragam, dan seterusnya. Peneguhan aspek positif ini bermanfaat untuk menumbuhkan rasa bangga pada ideologi pemersatu tersebut. Tanpa rasa bangga dengan Pancasila mustahil kita akan betul-betul terpanggil untuk menjunjung dan memperjuangkannya. Akhirul kalam, tentu saja, skema “apanya” yang diperbarui dari demokrasi Pancasila di atas bukan satu-satunya model. Sebagai urun rembuk, model inipun perlu diperdebatkan. Tapi, tak ada yang meragukan bahwa ajakan Sdr. Denny JA untuk meneguhkan demokrasi Pancasila yang diperbarui perlu menjadi perbincangan publik yang luas. 69 70 Memperbarui Cara Pandang Dan Cara Praktek Demokrasi Pancasila M. Hatta Taliwang Direktur Institut Soekarno Hatta (ISH) Demokrasi Pancasila. “Karena pangkal tolak demokrasi Pancasila adalah kekeluargaan dan gotong royong, maka demokrasi tidak mengenal kemutlakan golongan, baik kemutlakan karena kekuatan fisik, kemutlakan karena kekuatan ekonomi, kemutlakan karena kekuasaan, *maupun kemutlakan karena besarnya jumlah suara. Kehidupan demokrasi Pancasila tidak boleh diarahkan utk semata mata mengejar kemenangan dan kepentingan pribadi atau golongan sendiri, apalagi ditujukan untuk mematikan golongan yang lain, selama golongan ini termasuk dalam warga Orde Baru, warga Pancasila dan UUD45 Azas demokrasi Pancasila sebenarnya telah diatur secara konstitusional, ialah mengikut sertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan jalan musyawarah untuk mufakat” 71 Presiden Soeharto dalam pidatonya di awal kekuasaannya pd 16 Agustus 1967. A. PENDAHULUAN Sejujurnya saya kurang memahami apa yang dimaksud Dr. Denny JA dengan frasa: Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui. Apa pembaruan dalam konsep atau pembaruan dalam cara prakteknya. Saya merasa bahwa dari segi konsep Demokrasi Pancasila sudah cukup komprehensif dan tak ada yang perlu kita perbarui. Urgensinya hemat kami adalah dalam cara pandang dan cara praktek Demokrasi Pancasila itu yang perlu selalu kita perbarui atau update. Mengacu kepada buku “Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila” karya Prof. Dr. Kaelan, M.S. maka Ideologi Pancasila sebagai filosofi bangsa dan dasar Negara Indonesia yang dengan susah payah dirumuskan dan diperjuangkan oleh pendiri bangsa, dewasa ini ditenggelamkan, dimarjinalkan dalam realisasi kebijakan kenegaraan. Tinggal hanya sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan dalam realisasi praksis justru mengagungkan dan mendasarkan pada filsafat liberal. Hal ini bisa kita lihat dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah/negara baik pusat maupun di daerah yang mendasarkan pada filosofi liberalisme. 72 Dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam bernegara saat ini jauh dari mencerminkan identitas kenegaraan yang berlandaskan filosofi Pancasila. Proses terbentuknya Negara Indonesia bukanlah sebagai proses kesepakatan individu karena adanya ‘homo homini lupus’, karena adanya penindasan individu lain dalam kebebasan alamiah, melainkan suatu proses kesepakatan, konsensus antar elemen bangsa yang membentuk suatu bangsa dan Negara Indonesia. Unsur-unsur tersebut meliputi suku bangsa, ras, golongan, budaya, agama bahkan juga kalangan kerajaan-kerajaan serta secara geografis terdiri atas beribu-ribu pulau dengan local-wisdom-nya masing-masing, yang unsur-unsur itu telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Proses terbentuknya ideologi bangsa Indonesia berbeda dengan ideologi-ideologi besar lainnya seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Pancasila digali dan dikembangkan oleh para pendiri negara dengan melalui pengamatan, pembahasan dan konsensus yang cermat. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri disublimasikan menjadi suatu prinsip hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan proses kau- 73 salitas perumusan dan pembahasan Pancasila tersebut maka sumber materi yang merupakan nilai-nilai kultural dan religius, pada hakekatnya dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan lain perkataan lain bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan kausa meterialis bagi Pancasila. I. BELAJAR DARI BUTON Untuk meyakinkan bahwa nilai nilai dasar Pancasila itu merupakan “produk” Indonesia asli kita telaah sejenak tentang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Bagi intelektual yang keranjingan ilmu dari BARAT atau dari NEGARA LAIN, mungkin bijak juga jika belajar kearifan dari lokal Indonesia yang nilainya tidak kurang mulia. Misalnya tentang kerajaan Buton yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Buton. Pelajaran Pertama: MENGHORMATI PEREMPUAN. Pada periode Kerajaan antara thn 1322 sd Abad ke 16, dipimpin oleh 6 Raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. 74 Kedua: KESULTANAN DEMOKRATIS. Pada periode kerajaan berubah jadi kesultanan (abad ke 16), demokrasi memegang peranan penting. Sultan bukan berdasarkan keturunan namun dipilih oleh Siolimbona, dewan yang terdiri dari 9 orang penguasa dan penjaga adat Buton. Ketiga, SULTAN PUASA SEX. Setiap sultan berjanji untuk tidak lagi tidur dengan permaisuri demi menghindari lahirnya putra mahkota saat mereka bertahta. Karena bila sampai lahir seorang putra, maka kesultanan tidak lagi melalui proses demokrasi melainkan diwariskan kepada keturunannya. Keempat: SANGGUP MENERIMA HUKUMAN MATI Saat pelantikan, sultan terpilih akan membuat sumpah untuk menjalankan UU negara yang disebut Murtabat Tujuh, dan menerima konsekuensi digantikan atau bahkan kehilangan nyawa bila melanggar UU tersebut (Sultan ke - VIII La Cila Maradan Ali (Gogoli yi Liwoto. 1647–1654), diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara leher dililit dengan tali) 75 Kelima: PATUH PADA FALSAFAH KESULTANAN Falsafah hidup Kesultanan Buton ini lahir pada akhir abad ke-16 M. Falsafah Hidup Kesultanan Buton meliputi: 1. Agama (Islam) 2. Sara (pemerintah) 3. Lipu (Negara) 4. Karo (diri pribadi/ rakyat) 5. Arataa (harta benda) Kita akan bahas falsafah diatas dibandingkan dengan PANCASILA. II. “PANCASILA” VERSI BUTON Soekarno adalah salah seorang pemimpin pejuang kemerdekaan yang gandrung menggali nilai-nilai perjuangan dari nilai-nilai luhur budaya bangsanya. Salah satu buah pemikirannya adalah tentang PANCASILA. Entah karena mmbaca riwayat Kesultanan Buton atau kebetulan, ternyata ada kemiripan antara Pancasila versi Soekarno dengan Pancasila versi Kesultanan Buton buah karya Sultan La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615 M), Sultan Buton ke-4. 76 Perhatikan Falsafahnya: 1. Taat pada ajaran Agama (Islam). Bandingkan dengan sila I Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Tegakkan pemerintahan (SARA) yang adil. Bandingkan dengan sila 2 Pancasila; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Negara(LIPU) Yang Utuh dan Bersatu. Bandingkan dengan sila 3 Pancasila: Persatuan Indonesia 4. Diri/Pribadi-Rakyat atau KARO yang bijak Bandingkan dengan sila 4 Pancasila: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Harta benda (ARATAA) harus dilindungi dan berguna bagi kepentinagn umum. Bandingkan dengan sila 5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Soekarno mendapat penghargaan dari Univ Al Azhar Kairo atas pemikirannya tentang Pancasila. Syeikh Mahmud Syaltut menyatakan: “penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Muslim). Malahan, Demokrasi Terpim- 77 pin, yang di dalam negeri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh Al-Azhar itu sebagai, “lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha al-Qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin” (tdk lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang djadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman). Pemimpin Arab berkata; kami satu ras tapi terpecah atas berbagai bangsa. Indonesia beragam ras/suku BERSATU karena PANCASILA. Mengapa kita kurang bangga dengan karya dan budaya bangsa kita yang telah dihargai sedemikian tinggi oleh bangsa luar? B. DEMOKRASI PANCASILA. I. Prinsip-prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.. 1. Kedaulatan ada ditangan rakyat (UUD 1945) 2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah 3. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 4. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilakukan dengan Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat. 78 5. Perlindungan hak asasi manusia 6. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional 10. Pemerintah patuh pada hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi: Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. II. Asas Demokrasi Pancasila Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas sebagai berikut: 79 1.Asas Kerakyatan. Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 2.Asas Musyawarah. Pengertian asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobarbanan untuk kebahagian bersama. C. DEMOKRASI PANCASILA SATU KESATUAN DENGAN UUD 45 YANG DISAHKAN TANGGAL 18 AGUSTUS 1945. Demokrasi Pancasila pada dasarnya penjabarannya secara garis besar sudah tertuang dalam UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu Demokrasi Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan UUD 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. 80 Demokrasi Pancasila tidak pernah akan klop atau tidak akan cocok dengan UUD 2002 hasil Amandemen. Mengapa? Karena Demokrasi Pancasila mensyaratkan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu: 1.Menetapkan UUD 2.Menetapkan GBHN; 3.Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Wewenang MPR 1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden 2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN 81 3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden 4. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD. serta melanggar undang-undang. D. INDIKATOR DAN FAKTA KEKACAUAN SISTEM KETATANEGARAAN KITA. Banyak intelektual yang masih percaya bahwa Jokowi akan mampu atasi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa. Kami yang sejak awal kritis terhadap Jokowi dianggap underestimate thdp Jokowi dan sering dikuliahi oleh pembela2 Jokowi. Berkali kali kami katakan bahwa persoalan bangsa kita bukan semata pada FIGUR PEMIMPIN/PRESIDEN tapi ada masalah berat pada sistem. Kami sering menganalogikan dengan mobil. Sebagus apapun SUPIRnya mobil Indonesia ini ada masalah di MESIN, di AC dll. Jadi yang dibutuhkan SUPIR dengan TIM MONTIR yang membenahi sistem mobil ini. Apakah SUPIR JOKOWI BISA MERANGKAP MONTIR? Kami sangsi karena SIM B saja mungkin belum punya. Itulah esensi yang membedakan cara pandang kami dengan sebagian teman terhadap JOKOWI. Jadi tak ada ketidaksukaan pribadi kami 82 terhadap JOKOWI. Beberapa waktu yang lalu kami pernah tulis fakta/ indikasi bahwa ADA MASALAH SERIUS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN KITA YANG SANGAT MEMPENGARUHI OUTPUT KITA SEBAGAI BANGSA. Dan juga tentu mempengaruhi KINERJA PRESIDEN. I. Fakta/Indikasi yang aneh: 1. Banyak orang orang pintar dan baik tetapi TIDAK TERSERAP oleh SISTEM KENEGARAAN KITA. Tapi banyak orang yang biasa-biasa saja bahkan bermasalah bisa mendapat POSISI MENENTUKAN. Salah satu sebabnya karena ada yang kurang baik dalam SISTEM KEPARTAIAN (sistem pendanaan, kaderisasi, rekruitmen, promosi dll. Masalah dalam sistem kepartaian ini bisa diulas khusus.). 2. Sudah belasan tahun kita punya LEMBAGA TINGGI NEGARA seperti DPD RI. Bukan salah anggotanya mereka tidak berfungsi optimal tetapi SISTEMnya yang tidak jelas sehingga praktis kita (NEGARA) mengeluarkan biaya untuk tugas simbolik saja. Ini pun bisa dibedah panjang lebar. 3. Pada saat PEMILU LEGISLATIF, semua caleg bernyanyi TINGGI GUNUNG SERIBU JANJI. Karena memang LIDAH TAK BERTULANG. Mereka dipi- 83 lih langsung OLEH RAKYAT. Sampai di SENAYAN yang dominan diperjuangkan adalah SUARA PARTAI karena distel oleh LEMBAGA FRAKSI. Partainya disetel oleh PEMILIK MODAL. Sehingga kami pernah tulis DEMOKRASI KITA: Dari Rakyat, Oleh Rakyat Untuk Konglomerat. Tak ada yang salah dengan kader partai dan caleg tapi lagi-lagi sistemnya. Lebih gila lagi WAKIL RAKYAT BISA DIGUSUR DARI SENAYAN OLEH PARTAI. Tentu saja semua situasi tersebut mempengaruhi output DPR yang berkaitan dengan fungsi PENGAWASAN, LEGISLASI DAN ANGGARAN. Tentu saja sangat MERUGIKAN RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA secara keseluruhan sebagai sebuah SISTEM. 4. DPR punya kewenangan lain: melakukan fit and proper test terhadap calon HAKIM AGUNG, calon GUB BI, calon KAPOLRI, Calon Panglima TNI, calon Dubes, calon KPK dll. Padahal rekruitmen calon anggota DPR saja oleh partai msh dipertanyakan kualitasnya. Tiba-tiba mereka menjadi PENGUJI utk jabatan2 strategis negara. Sehingga yang terjadi SANDIWARA dibiayai negara. Tak ada yang salah dengan anggota DPR, tapi SISTEM itu ANEH. Dan untuk keanehan itu NEGARA mesti membayar. Meskipun ada yang menyatakan bahwa peran DPR tsb untuk memberi legitimasi bahwa Pejabat penting tersebut sudah dapat stempel dari rakyat melalui 84 wakilnya. Namun tetap mengandung keanehan apalagi kalau direfer ke UUD 45 18 Agustus 1945 di mana kewenangan mengangkat pejabat pejabat tinggi tersebut merupakan eksklusif kewenangan Presiden. 5. Secara teoretis PRESIDEN butuh grip yang kuat ke Propinsi dan Daerah utk mensukseskan program yang disampaikan saat kampanye. Oleh sistem otonomi dan demokrasi liberal Presiden bisa berbeda partai dengan Gubernur/Bupati/Walikota. dalam banyak kasus, terkadang Gub atau Bupati lebih loyal kepada Ketua Partai daripada ke Presiden. Atau Bupati sering mengabaikan arahan Gubernur dll. Tidak tegas lagi rantai komando kepemimpinan. Bagaimana bisa menjadi PRESIDEN EFEKTIF atau GUBERNUR EFEKTIF kalau situasinya seperti itu. Lagi lagi ini masalah kesisteman. 6. Setelah amandemen UUD45 tidak dikenal lagi LEMBAGA TERTINGGI NEGARA yaitu MPR RI. Semua menjadi Lembaga Tinggi Negara(LTN). *Praktis LTN seperti Lembaga Kepresidenan, MA, BPK, DPR, DPD, MK, KPK dll jadi “KERAJAAN” masing2. Egocentrisme lembaga mengental. MPR sebagai tempat mempertanggungjawabkan tugas di masa akhir jabatan tidak diperlukan. Rakyat tidak tahu apa kerja mereka, tahu tahu bubar jalan. 85 Presiden yang memimpin 250 juta rakyat cukup di SK kan oleh KPU. Selesai tugasnya tidak merasa perlu pamit secara terhormat di depan MPR. Ya aneh saja. Sistem ini hemat kami TIDAK MEMBANGUN RASA BERTANGGUNG JAWAB Mau berhasil atau gagal. Tidak ada reward dan punishment*Tidak ada yang perlu dirisaukan. *Malah bisa ikut Pilpres atau kontes lagi. 7. Belum lagi bila bicara SISTEM EKONOMI YANG SUPER LIBERAL. Sejak LoI ditandatangani hingga lahir lk 115 UU yang diarahkan asing (Bank Dunia dkk) INDONESIA praktis tidak berdaulat lagi dalam SDA, Perbankan, Tanah, Air, Retail dll. Ambil contoh perbankan kalo Pemerintah mau membangun proyek besar, sementara bank-bank dikuasai asing, apa mungkin bisa dapat supporting dana. Padahal bank asing kerjanya menyedot sumber daya keuangan rakyat Indonesia bagaikan vacum cleaner menyedot debu. Seratus disedot paling banyak 18 yang diputar di Indonesia lagi. Selebihnya diputar di negeri yang lebih menguntungkan. Sistem ekonomi Neoliberal merusak sistem politik negara berdaulat. Mekanisme dan institusi demokrasi, seperti pemilihan umum, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik, dimanipulasi sedemikian rupa sekedar sebagai alat menciptakan konsensus dengan rakyat. Sementara proses pengambilan keputusan 86 politik secara real diambil alih oleh institusi-institusi global yang tidak pernah mendapat mandat rakyat, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan lain-lain. Kalau saya bertanya apakah bergabungnya Indonesia ke Masyarakat Ekonomi ASEAN atas persetujuan rakyat? Pasti jawabannya bingung. Sejak kapan rakyat ditanya. Dalam kampanye Pemilupun tak ada caleg yang bertanya. Tahu-tahu rakyat dicemplungin aja. Entah akan jadi apa rakyat Indonesia di MEA, ora mikir! 8. KPK dibentuk oleh DPR dan Pemerintah dengan UU. Pd saat UU mau diperbaiki terkesan KPK “ melawan” dengan berbagai cara lewat LSM yang mereka bina. Bahkan pernah mempermalukan Presiden ketika Presiden mengajukan calon Kapolri dengan buru buru mentersangkakan calon Kapolri. 9. MK dipilih oleh DPR dan disahkan dengan SK Presiden.Tapi 9 orang itu bisa membatalkan UU yang disahkan 560 orang anggota DPR dan disetujui Presiden. Saya bukan ahli hukum. Cuma merasa aneh saja. Kalau saya tulis semua tentang KEANEHAN-KEANEHAN DAN MASALAH SISTEM KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI ini pasti tidak cukup 50 halaman. 87 Saya tidak tahu apakah para profesor perancang amandemen UUD 45 menyadari atau tidak fakta-fakta ini. Kami sudah mencoba mengumpukan ahli-ahli tatanegara untuk mendiskusikan dan mencari SOLUSI atas problem SISTEM KONSTITUSI INI tapi mengundang ahli2 Tatanegara itu bagaikan mengangkat batu besar ke atas bukit. Hanya sedikit Profesor Tata Negara yang rendah hati dalam urusan ini. Problem konstitusi ini yang berat mengganjal kinerja Presiden, sehebat apapun Presiden itu. Inilah agenda prioritas kalau Indonesia sungguh mau berubah. Saya kira perlu kebesaran jiwa pendukung Jokowi untuk memahami kompleksitas masalah ini, agar tidak membabi buta membela tanpa memahami masalah besar(SISTEM) yang dihadapi Presiden. *II.*Cita cita pendiri negara kita dengan dicapainya kemerdekaan antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat. Setelah 70an tahun kemerdekaan cita cita tsb bukannya makin mendekat tapi malah makin menjauh dan meredup. Separuh penduduk Indonesia masih hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD/hari/kapita. Segelintir manusia hidup dengan kemakmuran luar biasa. Ada 40an orang punya kekayaan lbh dari 1000 trilyun. Ada 4 orang terkaya setara dengan 100 juta harta orang miskin. 88 Ini sebuah ironi dan tragedi di tengah melimpahnya kekayaan alam Indonesia. Ada yang sering dikesampingkan oleh politisi dan ahli ekonomi karena dihantui tuduhan rasialis bahwa sesungguhnya dari berbagai catatan sejarah salah satu tujuan kemerdekaan itu adalah untuk mengangkat derajat kaum inlander/pribumi (bumi putera) karena nasib mereka yang dianiaya oleh penjajahan Belanda dengan menempatkan mereka sebagai warganegara kelas tiga di negerinya sendiri. Ini bukan soal rasialisme tapi ini menyangkut keadilan politik dan keadilan ekonomi bagi mereka. Namun apa yang terjadi nasib kaum inlander/pribumi tetaplah menjadi kelas tiga secara ekonomi meskipun sdh 70 tahun merdeka. Apakah realitas itu hanya kesalahan kebijakan Penguasa? Atau semata karena penyimpangan dalam penegakkan aturan main? Saya kira bukan semata karena masalah masalah tsb. Henry Veltemeyer menyatakan: “Proses akumulasi kekayaan disatu sisi, penghisapan serta pemiskinan disisi lain, bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu desain kebijakan politik-ekonomi yang kini kita kenal sebagai Neoliberalisme dan Globalisasi Kapitalis” Jadi ada masalah masalah mendasar berkaitan dengan paham dan sistem dalam kita melaksanakan amanat Konstitusi Proklamasi 1945 khususnya dalam bidang 89 ekonomi. Kalau memang jalan, paham dan sistem yang kita pilih on the track maka seharusnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan ini makin mendekat. Bukannya makin menjauh dan meredup, menjadilkan mayoritas rakyat kehilangan harapan. Problem dan kontradilksi ini harusnya menjadi agenda utama kalau TRISAKTI mau dilaksanakan oleh Penguasa Baru secara konsekwen dan konsisten. 2. Makin banyak orang yang dipenjarakan makin meningkat jenis, kuantitas dan kualitas kejahatan di tingkat bawah maupun yang dilakukan elite (korupsi dan kejahatan krah putih). Secara teori mestinya makin banyak yang masuk penjara makin banyak yang takut berbuat jahat. Bagaimana menjelaskan realitas demikian? Ini sesuatu yang kompleks untuk dirinci dalam ruang terbatas ini. Secara sederhana kita bisa simpulkan telah terjadi kerusakan dalam sistem nilai karena ada yang keliru dalam pendidikan (termasuk pendidikan agama), kesalahan dalam sistem hukum dan penegakkannya, sistem budaya dll sehingga OUTPUTnya menghasilkan manusia MANUSIA YANG KEHILANGAN KEMANUSIAANNYA. 3. Di negara yang relatif sehat sistemnya, ekonomi tumbuh dari hasil kerja keras rakyatnya secara produktif karena pertanian, pariwisata, industri dll tumbuh sehat. Misalnya di Korea, Jepang, China, Malaysia dan Thailand 90 dll. Mayoritas rakyatnya MAKAN DARI KERINGAT MEREKA SECARA BENAR. Mereka tumbuhmemakai istilah alm Prof Dr Hartojo Wignyowijotodari EKONOMI FRONT OFFICE. Namun di Indonesia diduga sebagian rakyatnya hidup dari korupsi dan perputaran uang korupsi (terutama saat PILKADA, PILEG, PILPRES, PILKADES di mana banyak UANG GELAP BERPUTAR), sebagian hidup dari percikan jual beli narkoba, sebagian dari jual beli manusia (prostitusi dan TKW), sebagian dari uang PENYELUDUPAN, PERJUDIAN, PREMAN dll yang oleh Prof Hartojo Wignyowijoto disebut sebagai EKONOMI BACK OFFICE. Kita tidak tahu seberapa besar EKONOMI BACK OFFICE ini menopang ekonomi Indonesia. Baru-baru ini sebuah lembaga menyiarkan uang gelap berputar di Indonesia terus meningkat. Thn 2014 sj sekitar 250 triliun. Ini menjelaskan bgmana orang yang tidak kerja keras tapi bisa hidup makmur. Yang jelas makin besar sumbangan ekonomi back office berarti makin besar kerusakan moral dan kerusakan sistem dalam masyarakat Indonesia. Apa yang kami beberkan di atas, merupakan indikasi kegagalan sistem demokrasi liberal, yang sebenarnya kita sudah belajar dari kegagalan demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959 berdasarkan UUD 50. 91 Sebuah sistem yang telah dikritik secara pedas oleh Sekarno dengan kalimatnya yang terkenal “Berilah bangsa ini satu demokrasi yang tidak jegal-jegalan. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan akan menenggelamkan kepentingan nasional dalam arus malapetaka.” ujar Presiden Soekarno dalam pidatonya tahun 1957. Kritiknya makin pedas terhadap demokrasi liberal, yang dinilainya sebagai demokrasi dengan politik rongrong merongrong, rebut merebut, jegal menjegal dan fitnah memfitnah.” Sekitar tahun 1953 setelah berhenti dari KSAD (pasca 17 Okt 1952) Nasution menulis kritik terhadap demokrasi liberal: “Bahwa tangan yang harus memegang aparatur itu, yakni kekuasaan politik, adalah seharusnya teguh. Akan tetapi umum mengetahui bhw pemerintah kita adalah labil, karena belum pernah diadakan Pemilihan Umum dan adanya berpuluh puluh partai politik. Tiap pemerintah harus berkoalisi dan disusun dari selusin partai, sehingga kelahirannya berdasarkan kompromikompromi. Maka itu tak mungkin ada gezag (wibawa) tak mungkin ada kekuasaan yang tegas dan teguh, karena tiada satu partaipun yang dapat memerintah. Dan untuk memperbaiki aparatur negara perlu adanya kekuasaan politik 92 yang tegas. Yang menjadi syarat mutlak usaha usaha stabilisasi keamanan negara. Rakyat mengharapkan pimpinan dari Dwitunggal Soekarno Hatta yang disegani, dijunjung dan dihormati oleh seantero, akan tetapi Dwitunggal itu tak berdaya karena menurut UUDS 50 mereka cuma perlambang dan bukan penanggung jawab pemerintahan. Kekuasaan memerintah oleh UUDS50 diserahkan ke partai partai yang berbentuk sistem parlementer.” (Buku: MEMENUHI PANGGILAN TUGAS jilid 3 hal 245). Dalam halaman 252 Nasution menulis: “Sistem pemilu dan konstitusi kita th 50an merintangi slagordening (pengikatan persatuan semua kekuatan). Sistem ini selalu meluangkan kesempatan bagi masing masing kelompok bahkan masing masing tokoh untuk kepentingan sempit. Tidak mungkin tertegak suatu grand strategi, suatu strategi besar dengan kepemimpinan yang bernilai kenegarawanan.” E. TAWARAN SOLUSI. Untuk menghentikan proses kerusakan bangsa ini kami dan kawan-kawan telah coba tawarkan KEMBALI KE PEMIKIRAN AWAL DARI PENDIRI NEGARA KITA yakni yang tertuang dalam UUD45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Sudah panjang adu argumentasi soal ini. Kami yakin ini jalan yang bisa menyelamatkan NKRI. Bahwa ada kekurangan kami dkk juga sdh 93 tawarkan ada cara dan jalan untuk mengatasinya yang kami rangkum dalam kata bahwa UUD45 itu UNTUK DISEMPURNAKAN. Ini juga sdh melewati perdebatan panjang. Bila jalan ini pun tak bisa disepakati dan mau lanjut dengan jalan sesat monggo aja. F. KEMBALI KE UUD45 18 AGUSTUS 1945 SAMA DENGAN MASUK LAGI KE ERA KEGELAPAN? Hampir menjadi kesadaran umum bahwa praktek demokrasi liberal sekarang telah membuat bangsa kita menjadi tidak jelas arah dan tujuannya, nasionalisme menjadi buram, sekelompok orang menjadi sangat kaya raya, sebagian besar rakyat jadi miskin, manusia jadi serakah dan materialistik, hidup sangat individualistik. Budaya hedonisme, exibishionisme, narsisme mewabah. Semangat kekeluargaan, sopan santun, saling menghargai menjadi runtuh. Perpecahan bangsa setiap saat mengancam. Manusia Indonesia seakan kehilangan jati diri. Kedaulatan Pemodal lbh dominan dari Kedaulatan Negara dll Sekarang sejarah berulang kembali, UUD45 hasil Amandemen 2002, ternyata berimplikasi luas terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Secara politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan lain lain telah sangat liberal. Banyak kalangan resah dan gelisah. 94 Sehingga timbul anggapan KITA TELAH TERSESAT karena itu kita harus kembali ke TITIK AWAL kita berangkat, yaitu kembali ke roh perjuangan awal kita mendirikan negara ini, yaitu yang tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 45. Kita kembali kesini dulu, sebagai layaknya orang yang tersesat mencari titik start berangkatnya, agar bisa menyusur jalan benar. Maka makin menguat keyakinan bahwa kembali ke UUD45 18 AGUSTUS 1945 (UNTUK DISEMPURNAKAN ITU), adalah cara bijak. Bukan dengan melanjutkan Amandemen yang akan makin menyesatkan. Namun gagasan kembali ke UUD45 18 AGUSTUS 1945; selalu dicurigai sebagai upaya mengajak kembali ke era kegelapan, era penindasan, era fasisme, era militerisme, selama 32 tahun kekuasaan Soeharto atau kediktatoran seperti zaman jelang akhir kekuasaan Soekarno. Padahal penerapan UUD45 di era Soekarno juga mendapat kritik dari Bung Hatta dll. Demikian juga di era Soeharto mendapat kritik keras dari Jen AH Nasution, M Natsir, Ali Sadikin dll yang tergabung dalam Petisi 50 serta gerakan mahasiswa 1974 dan 1977/1978. Artinya apa yang diterapkan oleh Soekarno di akhir kekuasaannya maupun selama 32 tahun Soeharto berkuasa bukanlah yang IDEAL. 95 Dengan kata lain UUD45 18 Agustus 1945 BELUM PERNAH DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BENAR SEPENUHNYA SEHINGGA KITA MESTI BERJUANG TERUS UNTUK MELAKSANAKAN DENGAN MURNI DAN KONSEKWEN. Dalam hal demokrasi SOEKARNO pernah merumuskan istilah DEMOKRASI TERPIMPIN yang dalam penerapannnya dianggap berujung ke diktator. Soeharto dalam pidatonya diawal kekuasaannya pd 16 Agustus 1967 merumuskan DEMOKRASI PANCASILA dengan kalimat yang indah dan bagus seperti kutipan dalam pendahuluan diatas. Pidato tersebut sangat menyihir dan paling sering dikutip oleh Petisi 50. Pak Natsirpun tertarik dengan pidato awal Soeharto berkuasa ini, sehingga di awal kekuasaan Soeharto bekas Perdana Menteri dan Tokoh Partai Masyumi tsb mau mendukung Soeharto.Namun Natsir pun kecewa dengan Soeharto sehingga bergabung dengan PETISI 50 menentang Soeharto. Jadi adalah keliru besar bila ada anggapan bhwa kembali ke UUD45 18 Agustus 1945 sebagai upaya mengajak ke era diktator dan fasis militeristik. Apalagi zaman telah berubah, kesadaran atas hak azasi manusia, pemahaman akan hukum telah meningkat pesat. Militer Indonesia pun telah belajar banyak atas kekeliruan di masa lalu dan 96 melakukan redefinisi atas perannya di era yang makin terbuka ini, sehingga tidak mungkin mengulang sejarah kelam peran yang pernah dimainkan oleh Soeharto. Di era informasi yang serba terbuka ini di mana tidak ada lagi kekuatan yang memonopoli informasi, maka kekuasaan yang akan berlaku otoriter atau diktator akan selalu dibully (diejek) oleh publik nasional maupun internasional. Kita kembali ke UUD 45 18 Agustus 1945 adalah untuk menemukan kembali jatidiri kita sebagai bangsa yang hidup dalam alam musyawarah mufakat, kekeluargaan dan berjuang untuk kemajuan bersama, bukan untuk saling jegal menjegal dan mengejar kemajuan masing masing. Kembali ke UUD45 18 Agustus 1945 adalah upaya kita kembali ke titik start untuk menemukan roh murni dari makna terdalam perjuangan para pendiri bangsa kita, menegakkan nasionalisme kita, karena kita telah TERSESAT dalam arah yang keliru dalam mencapai tujuan kemerdekaan kita. Kembali ke UUD 45 18 Agustus 1945 bukan untuk mengkeramatkan Konstitusi karena kita tetap punya ruang UNTUK MENYEMPURNAKAN (misalnya pembatasan masa jabatan Presiden!) dengan cermat dan hati hati, bukan perubahan secara serampangan. 97 Karena konstitusi AS pun dirubah secara hati hati, kata perkata. Tidak asal buang atau memasukkan kalimat secara “borongan” sehingga kehilangan makna historis dan filosofis sebgmana yang dimaksud para pendiri bangsa. Di era di mana alat komunikasi dan informasi serba terbuka ini masih ada yang berpikir bahwa akan lahir diktator baru karena menggunakan sistem ketatanegaraan UUD 45 18 Agustus 1945 saya kira terlalu naif. Dulu Soeharto dengan militerismenya bisa dominan karena rezim antara lain menguasai komunikasi dan informasi secara telak (monopoli). Sekarang rakyat di Merauke bisa dalam sekejap tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta, bagaimana mau berlaku diktator atas mereka? Karena rakyat mampu mengcounter lewat alat komunikasi yang mereka miliki dari sudut sudut kamarnya? Jadi sangat konyol menyatakan kembali UUD45 18 Agustus 1945 sebagai upaya kembali ke sistem diktator. Yang dibutuhkan kesabaran kita untuk terus koreksi dan koreksi atas konsep ketatanegaraan dalam UUD45. Biarlah terus menerus terjadi dialektika seperti di era Soekarno yang dikritik Bung Hatta, atau di era Soeharto yang dikritik Petisi 50. 98 Dengan cara itu Konstitusi kita akan teruji dan makin kuat. Bukan dengan membantai seperti yang terjadi dengan Amandemen yang dilakukan sejak 1999 sd 2002 yang melahirkan UUD 2002 yang sekarang kita rasakan sebagai ancaman yang akan menghancurkan NKRI. [] Sumber Bacaan: 1. Prof DR Kaelan M.S. Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila. 2. Tulisan DR. Yudi Latif 3. Tulisan DR. Denny JA 4. Tulisan Haris Rusly 5. Tulisan Salamuddin Daeng. 6. Tulisan MHT yang lalu lalu. 7. Dll. 99 100 Meneguhkan Kembali Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui Taufan Hunneman Direktur Executive Indonesia Institute and Public Policy Setidaknya ada 3 hal yang bisa diklasifikasi dari tulisan Denny JA: 1. Fenomena paska pilkada DKI 2. Adanya benturan gagasan dalam ruang politik 3. Agenda ke depan untuk meneguhkan kembali demokrasi pancasila yang di perbaharui Sebelum membahas 3 hal ini, saya mengingatkan kembali melalui pendapat dari bapak demokrasi Moh. Hatta tentang 3 sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia: 1. Sosialisme barat yang membela prinsip prinsip humanisme 101 2. Ajaran Islam memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat 3. Kehidupan masyarakat dalam kolektivisme di desa-desa Ketiga inilah akar demokrasi yang mengakar dalam kehidupan bangsa indonesia. Ketiga sumber inilah sebenarnya akar dri demokrasi kita karena itu pemahaman barat-Islam dan kebudayaan lokal tidak bertentangan satu dengan lainnya namun mendapatkan tempatnya secara bersmaan dalam demokrasi pancasila Menyikapi soal fenomena pilkada dan adanya sisipan agenda yang dilihat oleh Denny JA, sebenernya ini di mulai dan disebabkan adanya politik identitas yang dimainkan dalam pilkada dki kali ini. Amrtya Sen pernah mengungkapkan bahwa setiap manusia tidak pernah punya identitas tunggal melainkan identitas yang beragam dalam dirinya karena itu maka setiap manusia mempunyai banyak persamaan. Karena itu pilkada DKI justru berbalik atas pengertian Amartya Sen karena pilkada DKI merumuskan persamaan atas identitas tunggal sebagai isu sentral dalam pilkada DKI. Selanjutnya Amartya Sen pun mengkritik pendapat Samuel Huntington terkait kategorikal peradaban yang saat ini dikategorikan sangat tidak tepat seperti identik India yang representatif dari budaya hindu. 102 Dalam pilkada DKI kali ini politik identitas begtu kental sekali aromanya. Jika di Amerika Serikat identitas politik yang di mainkan baik oleh komunitas kristen puritan, hispanik, afro amerika tidak memberikan dampak secara langsung kemasyarakat karena demokrasi amerika telah berabad abad perbaikan kualitas demokrasi. Politik identitas di Indonesia masih sangat rentan dampaknya dimasyarakat sebab setidaknya ada 2 argumentasi: 1. Umur demokrasi yang terbilang muda. Akibatnya masyarakat belum terbiasa adanya pendekatan kesamaan identitas dalam memilih paslon 2. Adanya bibit radikalisme dalam ideologi di masyarakat yang kemudian mendapatkan tempatnya dalam politik identitas Ideologi di masyarakat khususnya ideologi radikalisme selama 32 tahun era Suharto ternyata belum mati bahkan bekerja dalam ruang senyap dan mendapatkan momentumnya pada saat reformasi dan melalui demokrasi termanifestasi menjadi partai politik atau ormas. Benturan gagasan atau platform politik sesuatu yang tidak diharamkan dalam demokrasi sebagai diskursus atau proses dialog sangat dianjurkan namun gagasan 103 atau platform yang mengedepankan unsur unsur kebencian atau penghasutan atas dasar kebencian harus dieliminasi dalam ruang diskusi politik juga harus di eliminasi dalam demokrasi. Sebab demokrasi masih dapat dan diperbolehkan dilakukan pelarangan sebagai bagian dari preventif atas antisipasi supaya demokrasi tidak terbunuh oleh ideologi yang anti demokrasi. Tawaran Denny JA untuk kembali mengatur aturan main bersama harus dilihat dari setidaknya 2 kepentingan: 1. Apakah platform atau gagasan dimaksud bertentangan dengan demokrasi? 2. Aturan main dimaksud apakah kemudian mengesampingkan konsensus politik yang telah disepakati bersama baik saat awal berdirinya negara ini maupun dalam proses politik di kemudian hari? Sebab konsensus politik ini menyangkut soal soal prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang apabila di sentuh mengakibatkan proses perpecahan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 104 Agenda yang teramat penting saat ini bukan saja merumuskan kembali aturan main atw mempertegas ruang publik yang selama ini di kacaukan oleh sentimen agama melainkan keberanian menyelamatkam demokrasi pancasila dari rongrongan paham radikalisme atau cara-cara yang di lakukan untuk melemahkan demokrasi itu sendiri. Perjalanan bahkan perkembangan demokrasi pancasila dari era ke era memperlihatkan kompromistis akibat situasi politik dan ini tidak bisa dibenarkan untuk kestabilan watak demokrasi pancasila yang mempunyai akar sejarahnya. 20 tahun sudah era reformasi, di mana demokrasi berjalan mempunyai kecendrungan ke arah liberalisme dan ini harus dievaluasi agar paham liberalisme yang terlalu jauh dapat direvitalisasi untuk kembali ke dalam demokrasi pancasila yang mempunyai basis budaya. Inilah momentum yang sangat tepat untuk mulai menyusun agenda bersama untuk merumuskan demokrasi oancasila sebagaimana jatidiri bangsa ini. Ajakan Denny JA untuk meneguhkan kembali demokrasi pancasila yang diperbarui sebaiknya jangan dilihat dalam perspektif proses merevisi konsensus yang substantif untuk mencapai titik yang ideal sebab akan terjadi pengulangan kompromistis politik yang rentan tergerus 105 arus jaman. Namun sebaiknya mulai merumuskan agenda bersama untuk menyusun kembali demokrasi pancasila yang sebenar-benarnya sebagaimana jati diri bangsa. Keberanian untuk merumuskan demokrasi yang diperbarui hruslah dimulai dari menegakkan aturan yang jelas atas gagasan kelompok kelompok intoleransi maupun atas gagasan politik yang anti demokrasi. Karena itu kita harus sepakat bahwa tantangan kedepan adalah menyelamatkan demokrasi pancasila namun sebelum masuk dalam agenda merumuskan kembali demokrasi yang di perbaharui alangkah lebih baik jika kita mendorong penegakkan hukum atas kelompok, ormas maupun tindakan yang merongrong demokrasi, memanipulasi kebebesan dengan mempromosikan gagasan anti demokrasi, kebencian atas dasar suku, agama dan ras serta mengugat konsensus subtansi atas prinsip kenegaraan kita. [] 106 Demokrasi Pancasila Zeng Wei Jian Aktivis, penulis Senior kita, Denny JA, merilis ajakan merekonstruksi Demokrasi Pancasila “yang diperbarui”. Dia mengajak kita berpikir soal landasan filosofis bernegara. Sebuah ideal, a system, sebagai “the only game in town.” Baginya, pasca Ahok, ada sesuatu yang memprihatinkan. Sekali pun bagi saya, orang-orang yang berisik soal keberagaman sambil menuding-nuding kelompok Islam merupakan kelompok ahistoris. Mereka mengidap delusi. Ahok kalah bukan karena SARA. Itu cuma alasan dan alibinya. Raison d’être Ahok tumbang adalah keliru stratak, kalkulasi dan metodologi. Sejak 98, saya berpikir soal sistem terbaik bagi Indonesia. Semuanya anomali. Akhirnya, saya nyerah. Berhenti 107 memikirkan soal beginian. Perdebatan paling mendasar adalah sistem vs manusia. Menurut D. Edwards Deming, sistem lebih penting dari manusia. Angka perbandingannya 95:5. Kaum Marxis juga mementingkan sistem. Sedangkan penganut eksistensialis tidak peduli dengan sistem. Manusia jadi pusat segalanya. Bila manusianya baik, maka sistem apa pun akan menghasilkan end result yang baik. Begitu juga sebaliknya. Saya tidak tau mana yang benar. Segalanya relatif. Samasama benar, tergantung situasi dan kondisi partikelir. Indonesia penuh anomali. Sampe sekarang, saya mengira, adalah sebuah keajaiban Indonesia masih ada. Harry Tjan Silalahi pernah menulis “Indonesia negara bukan-bukan”. Bukan negara agama, bukan sekuler, bukan demokrasi, juga bukan negara totaliter. Indonesia juga bukan negara sosialistik, tapi juga bukan kapitalis. Hanya di Indonesia, empat peradaban hidup berdampingan secara bersamaan: tribal society, agraris, industri dan informasi teknologi. Eropa hanya punya masyarakat industri dan IT. Botswana, Mozambique, Lesotho dan sebagainya belum masuk negara industri. Masih tribal dan agrarian society. 108 Selain itu, ada 1300-an suku dengan lingua franca berbeda mendiami 1700 pulau Indonesia. Di samping 186 kerajaan masih eksis sampai sekarang. Diam-diam, berbagai faksi terlarang hidup berdampingan saat ini. Pengikut Sudisman, Tan Malakaist, Leninis, Maoist, Pecinta Che Guevara, Tan Ling Djiesme, Baperki, Stalinist, Rosa Luxemburg, anarco syndicalist, Trotskyist bergerak di samping marhaenis, wahabi, salafi, syiah, permusi, JI, LDII, kejawen, Jesuit, Freemasonry, Falun Dafa, animisme dinamisme dan ancient alien theorem. Faktor geografis dan tipologi antroplogis itu masih dibikin rumit dengan adanya berbagai macam aliran pemikiran, agama, mazhab dan sub sekte. Jurang antara si miskin dan kaya mengerikan. Menurut Oxfam, empat orang terkaya memiliki harta setara dengan kekayaan 100 juta penduduk. Jadi, tidak penting bentuk negara atau sistem apa yang mesti dianut. Masalah kesejahteraan itu esensinya. Islam sebagai kelompok mayoritas mesti ditempatkan di posisi sentral. Tirani minoritas sesuatu yang absurd. Pluralitas merupakan fakta. Namun fairness tidak berarti porsi sama rata antara mayoritas dan minoritas. Itu sama saja mengistimewakan minoritas. Sebuah ketidak-adilan bagi mayoritas. 109 Lieus Sungkharisma bilang, apalah arti sebuah nama. Serupa dengan William Shakepear yang berkata, “What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.” Lieus tidak sedang menjadi pujangga. Dia sedang bicara soal politik. Dia tidak keberatan bila Indonesia jadi negara Islam. Malah senang. Baginya, justeru minoritas akan lebih terlindungi. Contohnya Malaysia. Setau saya, tidak pernah ada pogrom atau hatze anti cina di sana. Namun definisi “negara Islam” pun multi-interpretasi. Lebih rumit dari communist state. Antara Soviet Union, PRC, North Korea dan Cuba saja sudah lain. Sekalipun sama-sama masuk communist camp. Benar kata Denny JA, hanya sedikit orang menginginkan negara islam dan liberal-sekuler. Paling-paling Gunawan Muhamad dan Salihara yang ngga keberatan dengan tarian telanjang. Mayoritas orang akan bilang, “That’s insane.” Ada kesadaran supra di balik alam bawah sadar manusia Indonesia. Mereka tau, ekstrimitas kiri dan kanan tidak tepat buat Indonesia. Kubu intoleran hanya ada dalam hayalan segelintir orang. Faktanya, di Indonesia tidak pernah ada perempuan minoritas disiram air dan dipukuli hanya karena dia pakai liontin salib. Justeru di Eropa dan Amerika kerap 110 ditemukan perempuan muslim dibully dan dipukuli di pinggir jalan. Hanya karena dia memakai hijab. Jadi, menurut saya, Demokrasi Pancasila versi “yang diperbarui” adalah stop menuding orang lain sebagai kelompok intoleran dan radikal sambil memasang foto Garuda Pancasila sebagai Profile WA. Menudingnuding orang lain seperti itu justru sebuah penghianatan Pancasila dan demokrasi itu sendiri. [] 111 112 Benarkah Kita Terbelah? Anick HT Penulis, Pemimpin Redaksi inspirasi.co Denny JA meluncurkan tantangan menarik (Denny JA: Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui) setelah hingar bingar Pilkada DKI Jakarta sedemikian menyita perhatian publik dan menaikkan isu-isu berbasis identitas yang agaknya memang masih kuat sebagai sentimen di negara demokrasi ini. Saya ingin menanggapi tulisan itu dalam tiga ranah: pertama, asumsi keterbelahan publik pasca-pilkada DKI Jakarta dan ancaman terhadap demokrasi. Kedua, tentang istilah demokrasi Pancasila yang diperbarui yang dilontarkan Denny JA. Dan ketiga; konten pembaruan demokrasi Pancasila tersebut yang intinya adalah memberi porsi lebih pada pendulum agama. --0-- 113 Tulisan Denny JA diawali dengan asumsi yang berlebihan tentang situasi demokrasi Indonesia pasca-pilkada. Menurutnya, “Dalam waktu dekat, bukan mustahil Indonesia akan terkoyak dan tidak stabil.” Bahkan, “bukan tak mungkin demokratisasi di Indonesia mengalami break-down dan kemunduran yang signifikan.” Bagi saya, itu asumsi yang sangat berlebihan. Betulkah isu SARA yang meruyak pada Pilkada DKI beberapa waktu lalu sebegitu kuat daya rusaknya terhadap fundamen ideologi berbangsa kita? Sebegitu rapuhkah tatanan demokrasi kita sehingga terancam hancur hanya karena politik Pilkada? Sebegitu lemahkah komitmen kebangsaan para elite politik kita sehingga hanya karena kepentingan kekuasaan sesaat membuat mereka menggadaikan ideologi besar kita? Mungkin saya salah. Tapi saya melihat dan menyimpulkan hingar bingar Pilkada DKI Jakarta agak berbeda dengan apa yang dikhawatirkan secara berlebihan dalam tulisan Denny JA tersebut. Apa yang disebut keterbelahan dalam Pilkada DKI Jakarta, bagi saya adalah keterbelahaan dalam konteks politik praktis. Isu SARA dan politik identitas yang terbukti efektif dalam konteks kasus Ahok bagi saya hanyalah kuda tunggangan kepentingan politik kecil. 114 Tentu ada sejumlah penunggang kuda yang dari awal ingin mendesain dan memanfaatkan momentum “kebangkitan” Islam politik ini dengan agenda-agenda yang lebih ideologis. Pengusung khilafah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi bagian dari orkestra besar Aksi Bela Islam salah satunya. Kelompok Bachtiar Nasir yang sejak awal juga identik dengan kelompok pengusung syariat Islam juga salah duanya. Tak kurang, Habie Rizieq pun terseret untuk mensofistikasi gerakannya sebagai gerakan ideologis dengan mendeklarasikan jargon NKRI Bersyariah. Namun jika dilihat lebih jauh, agenda-agenda ideologis itu tidak juga mendapatkan space yang cukup di dalam payung besar Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid tersebut. Segera setelah mereka merasa berhasil mempersatukan umat, mereka gagap sendiri merumuskan mau dibawa ke mana “umat yang telah bersatu”. Istilah pecah kongsi muncul tak begitu lama setelah Aksi 212. Demikian juga nampaknya ketika menyadari bahwa sebagian umat yang berlindung di bawah payung besar Aksi Bela Islam memiliki agenda ideologisnya sendiri, Habieb Rizieq serta merta merasa terancam kehilangan daya rekatnya. Untuk itulah nampaknya jargon NKRI Bersyariah kemudian dimunculkan. 115 Dalam kerangka seperti itu, terlalu simplistik ketika kita menyimpulkan bahwa agenda besar yang lebih ideologis tengah mengancam demokrasi kita. Jikapun terasa efek pengentalan politik identitas, itu memang terjadi di tingkat umat grassroot yang terlanjur terbakar sentimen keagamaannya. Dan itupun lebih nampak seperti euforia sementara. Saya tidak yakin jika euforia semacam ini bisa bertahan hingga pemilu presiden 2019. --0-Melalui tulisan pendek tersebut, Dennya JA menjelaskan empat platform gagasan yang turut bertarung dalam Pilkada Jakarta, yakni: kelompok yang menginginkan demokrasi modern ala negara maju; kelompok yang mengajak Indonesia kembali ke sistem sebelum amendemen UUD 1945; kelompok yang ingin mendesakkan agenda negara Islam atau setidaknya NKRI Bersyariah, dan kelompok yang ingin mempertahankan demokrasi yang ada saat ini, namun lebih diperbarui. Gagasan terakhir inilah yang dipilih oleh Denny JA dengan argumen kuat survei nasional LSI sejak 2005 hingga 2016, bahwa demokrasi Pancasila tetap menjadi pilihan terbesar masyarakat Indonesia, di tengah dua kutub ekstrem: negara Islam dan negara demokrasi ala Barat. 116 Nah, pada titik ini saya kira memasukkan istilah “diperbarui” dalam platform Demokrasi Pancasila yang diperbarui terlalu terburu-buru dan terkesan agak dipaksakan. Pertama, survei yang digunakan sebagai rujukan bahkan tidak memasukkan wording “diperbarui”. Survei-survei tersebut, ini juga disebutkan dalam tulisan Denny JA, menggunakan wording yang umum: “apakah ibu bapak menginginkan Indonesia menjadi negara Islam seperti Timur Tengah, negara demokrasi liberal seperti negara barat, atau negara demokrasi pancasila (tak didefinisikan detail semua gagasan itu)?” Kedua, Pancasila dan Demokrasi Indonesia, dalam sejarahnya adalah korpus terbuka yang bisa dimaknai agak lebih luas. Banyak analisis yang cenderung menyimpulkan bahwa meskipun Pancasila tetap bertahan sejak negara ini didirikan, namun bisa dibedakan corak pemaknaan Pancasila yang kemudian diterjemahkan dalam sistem demokrasi yang berlaku: pada masa Soekarno Pancasila bisa bermakna “kiri”; pada masa Orde Baru, Pancasila sama dengan liberalisme; pada masa SBY, Pancasila bermakna neo-liberalisme. Juga, tarik menarik pemaknaan Pancasila antara kalangan sekular nasionalis dan kalangan islamis juga terjadi sejak sidang BPUPKI. Saat inipun Hizbut Tahrir yang anti demokrasi menolak untuk disebut anti Pancasila, karena mere117 ka bisa memaknai Pancasila dengan cara lain: hanya sebagai falsafah negara, bukan sebagai ideologi. Di lain pihak, NU (dan Orde Baru) juga merumuskan sila-sila Pancasila dalam rumusan islami. Karena itu, bagi NU Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Jadi, apa yang disebut “pembaruan” dalam tantangan Denny JA bagi saya masih dalam spektrum perdebatan pemaknaan terhadap Pancasila yang pernah ada. Mungkin akan lebih tepat jika ia menyebutnya Demokrasi Pancasila saja, lalu merumuskan rekomendasi pemaknaan ulang terhadap demokrasi macam mana yang lebih pas untuk kondisi Indonesia saat ini. --0-Lalu, ketika mengulas landasan dan wujud pembaruan yang dimaksudkan dalam tulisan tersebut, Denny JA juga agak terjebak pada isu Pilkada DKI Jakarta yang telah saya bahas: “Harus diterima bahwa prinsip demokrasi hanya akan kuat jika ia dikawinkan dengan kultur lokal yang dominan di sebuah wilayah. Untuk kasus indonesia, goresan agama dalam batin masyarakat sangat dalam. Demokrasi yang ingin mengakar harus mengakomodasi kondisi itu dalam sistem kelembagaannya. 118 Hadirnya kementrian agama misalnya tak dikenal dalam demokrasi liberal barat. Namun untuk indonesia, kementrian agama sebuah kompromi yang seharusnya diambil. Evolusi kesadaran publik mayoritas Indonesia menghendaki pemerintah ikut mengurus agama publik. Itu yang tak ada dalam demokrasi liberal barat.” Ketika ia menulis bahwa “goresan agama dalam batin masyarakat sangat dalam” tentu kita sangat tahu dan mengerti. Survei yang dilakukan Pew Research Center tahun 2015 telah dengan nyata menunjukkan bahwa 95% masyarakat Indonesia merasa bahwa agama adalah hal terpenting dalam hidup mereka (nomor 3 di dunia setelah Ethiopia dan Senegal). Artinya, bukan hari ini saja goresan agama dalam batin masyarakat itu dalam. Bukan karena Almaidah dan Ahok. Bukan karena Pilkada Jakarta. Itupun sudah ditunjukkan Denny JA dalam tulisannya, tentang hadirnya Kementerian Agama. Kementerian Agama lahir pada era Soekarno sebagai kompromi politik. Tentu bisa dirunut lebih banyak lagi, bahwa beberapa hukum positif kita juga adalah hasil kompromi dengan ajaran Islam, terutama hukum-hukum perdata (pernikahan, waris). Juga pasal-pasal penodaan agama, misalnya, yang bias agama mayoritas. 119 Lalu di mana masalahnya? Di mana letak pembaruannya? Justru, yang terjadi, bagi para penggiat HAM, demokrasi Indonesia masih belum tuntas menyelesaikan persoalan berbasis agama ini, dan menganggap akomodasi hukum Indonesia terhadap agama (Islam) masih terlalu besar. Undang-undang Pernikahan 1974, Undang-undang PNPS 1965, Undang-undang Adminduk 2006, dan ratusan Perda-perda bernuansa syariat di berbagai daerah adalah beberapa contoh bahwa nuansa agama dalam hukum kita masih terhitung overdosis. Ironisnya, Indonesia adalah termasuk negara yang hampir tuntas merativikasi konvensi-konvensi internasional yang jika dikomparasikan menjadi tidak sinkron dengan beberapa produk hukum di atas. --0-- Di luar itu semua, saya mengamini ajakan Denny JA untuk mengkonsolidasikan ulang demokrasi Indonesia di tengah ancaman radikalisme dan potensi menguatnya islamisme dalam ranah publik kita. Ini adalah poin penting pasca Pilkada Jakarta yang seakan memberi angin segar bagi menguatnya sentimen agama dan etnis. Juga menegaskan bahwa Pancasila dan demokrasi adalah pilihan terbaik bangsa ini untuk mengelola negara yang dianugerahi kemajemukan yang luar biasa. 120 Dan kompatibiltas Islam dengan demokrasi harus terus menerus dikuatkan dalam kerangka merawat keberagaman yang Indah. [] 121 122 Ahok Effect dan Pudarnya Demokrasi Pancasila Syaefudin Simon Penulis Pilkada DKI yang mengharu biru nurani publik, meninggalkan “sesuatu” yang selama ini telah dianggap selesai: sentimen agama yang bersenggama dengan demokrasi. Deretan demo massif – baik pra maupun paska Pilkada – adalah pertunjukan telanjang dari komunitas tertentu yang mengatasnamakan agama untuk menekan demokrasi. Parahnya, demo massif yang menumpang “kendaraan demokrasi” itu dimanfaatkan pula oleh kelompok-klompok tertentu yang selama ini mengusung slogan antidemokrasi. Fenomena tersebut makin menguat di ranah publik karena adanya Ahok Effect. Yang mencemaskan Ahok Effect ini akan makin meluas lagi di masa depan. Ini terjadi, karena “kondisi Indonesia yang beragama (baik warna kulit maupun agama) merupakan lahan subur untuk menumbuhkan Ahok Effect. 123 Sebuah status dari Taufan Hidayat di Facebook, Jumat (5/5) lalu, menohok kelompok demonstran Hizbut Tahrir: Anda (Hizbut Tahrir) bisa berdemo dengan mengusung jargon khilafah di negeri demokrasi. Tapi apakah di negeri khilafah para aktivis demokrasi bisa berdemo dengan mengusung jargon demokrasi? Sebetulnya pertanyaan Taufan Hidayat di atas bisa ditujukan kepada komunitas lain–seperti FUI, FPI, dan kelompok pengusung Wahabi-Salafi. Kelompok-kelompok tersebut adalah beberapa contoh kelompok yang terus menerus berkampanye antidemokrasi di Indonesia (yang nota bene menganut sistem demokrasi) dengan menumpang kendaraan demokrasi itu sendiri. Jika Hizbut Tahrir tujuannya sudah terformulasikan dengan kelas–sistem khilafah, sebuah sistem kenegaraan sederhana di masa awal Islam–maka konsep negara yang ditawarkan FUI, FPI, dan Wahabi-Salafi masih belum terformulasi dengan jelas. Kenapa demikian? Mereka mungkin masih mencari “icon” negara yang non-demokrasi, tapi berhasil menyelenggarakan pemerintahan dengan bagus. Dalam arti, rakyat mepunyai saluran untuk merengkuh hakhak sipilnya di lembaga negara dan negara mempunyai sistem hukum yang mengakomodasi tuntutan rakyat. Sayangnya, icon negara semacam itu belum ada di negara yang menganut sistem Islam. Taufan Hidayat seharusnya bisa menantang lebih jauh: tunjukkan negara 124 Islam mana yang bisa menjalankan demokrasi ekonomi dan hukum seperti negara-negara sekuler di Skandinavia seperti Denmark, Norwegia dan Finlandia. Taufan bisa berteriak: Semua negara-negara yang memakai sistem Islam saat ini, jelas-jelas telah mengingkari prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan humanisme seperti yang tercantum dalam Piagam Madinah. Denny JA dalam tulisannya berjudul Jangan Benturkan Keindonesiaan Versus Keislaman, mengakui bahwa agama, khususnya Islam, menancap sangat dalam pada batin bangsa Indonesia. Pemahaman mereka atas ajaran agama akan mewarnai orientasi dan pedoman perilaku bangsa Indonesia. Pertanyaannya kemudian: apakah gambaran itu akan secara otomatis menyebabkan rakyat Indonesia niscaya memilih negeri bersistem Islam atau khilafah? Dalam survey LSI Denny, ternyata mendalamnya keiman-islaman bangsa Indonesia, tidak serta merta mempengaruhi pilihan dalam sistem bernegara. Dari 85% lebih umat Islam Indonesia kurang dari 10 persennya yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam. Meski demikian, kentalnya keislaman tersebut bisa dijadikan instrumen untuk menggiring massa dalam menolak ide-ide demokrasi sekuler yang muncul di ranah publik. Dan itulah yang terjadi ketika mengamati dem antiahok. Allan Nairn benar ketika menjelaskan bahwa agama adalah “penekan” demokrasi yang ampuh di Indonesia. Tapi 125 Allan salah ketika membuat kesimpulan linier bahwa agama dan sistem pemerintahan di Indonesia bersifat transaksional dan korelatif. Apa pun alasannya, kasus Pilkada Jakarta cukup menjelaskan bagaimana sentimen agama digunakan untuk menjatuhkan paslon gubernur non-Islam. Kaum Islamist yang kemudian memberikan contoh Ignasius Jonan dan Maria Elka Pangestu yang perjalanannya mulus di kabinet untuk membuktkan bahwa umat Islam masih komit dengan demokrasi – mereka lupa bahwa Jonan dan Elka adalah pembantu presiden yang dipilih atas dasar hak prerogatif presiden. Jelas beda dengan kasus Pilkada DKI. Benar bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Tapi sebagai anggota puak Melayu, bangsa Indonesia niscaya tercirikan dengan Islam seperti halnya rakyat Malaysia, Pathani (Thailand), dan Mindanau. Bambang Pranowo dalam disertasinya, Islamic Tradition in Rural Jawa (Monash University) menyatakan bahwa Islam kini teah menjadi identitas budaya Jawa dan Inonesia. Ini terjadi karena budaya Jawa telah terserap hampir di semua infrastrktur politik dan negara Indonesia. Kondisi inilah, yang mungkin, menyebabkan Denny JA menyarankan bahwa demokrasi di Indonesia harus memberikan peran agama yang besar di ruang publik. Untuk itu, tulis Denny, pemerintah harus membuat Undang-Undang 126 Perlindungan Kebebasan Umat Beragama. Undang-undang semacam itu sebetulnya sudah ada. Namun belakangan ini, ketika pemerintah harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik berbasis Islam untuk memikat konstituennya, undangundang perlindungan kebebasan beragama menjadi loyo. Energinya terserap oleh trik-trik partai-partai berbasis Islam yang mau tak mau harus “menyihir umat” yang bernostalgi ingin hidup di Negara Islam zaman Rasul. Itulah sebabnya organisasi semacam Hizbut Tahrir bisa survive bahkan mampu mengembangkan sayapnya di Indonesia. Celakanya, Hizbut Tahrir pun mengaku mengikuti demokrasi Pancasila yang mengakomodasi peran agama. Hizbut Tahrir tampaknya lupa bahwa Demokrasi Pancasila hanya melihat dan memandang agama sebagai esensi, bukan institusi yang menunggangi negara. Mungkin Hizbut Tahrir bisa belajar dari kaum Syiah ketika mengakui kekhilafahan Abu Bakar, padahal hadis Nabi menyatakan sepeninggal Rasul, khalifah adalah Ali. Kemudian timbul wacana, Abu Bakar adalah khalifah politik. Dan hadist Nabi yang dimaksud adalah khalifah spiritual. Esensi sistem sebuah negara dalam konsep Islam maupun demokrasi sebetulnya hampir sama. Keduanya menginginkan rakyat yang taat hukum sesuai kesepakatan berasama; rakyat yang hidup dalam platform 127 keadilan tanpa diskriminasi, dan tegaknya kesejahteraan bersama. Bedanya hanya pada, yang pertama menjunjung nama Allah sebagai rujukan tertinggi. Kedua, menjungung kemanusiaan sebagai rujukan tertinggi. Sebetulnya, keduanya bisa dipertemukan kalau kita mendalami dunia sufisme. Seperti dilantunkan Rumi: Aku mencari Tuhan, yang kutemukan adalah Diriku. Jika konsep khilafah menjejak pada khasanah sufime tadi, niscaya Hibut Tahrir pun dapat mengakomodasi demokrasi. Gibran menyebutkan Yesus sebagai Manusia Biasa, Qur’an menyebutkan Muhamad sebagai manusia Biasa, dan Islam meyebukan Manusia adalah khalifah Allah – atau pengganti Tuhan di muka bumi – maka kalau bangsa Indonesia mau membuka wawasan yang menembus langit, sebetulnya tak ada dikhotomi diametral antara Islam dan demokrasi. Tapi sayang, sumbu pendek telah membakar emosi umat sebelum tujuan esensi demokrasi yang (identik dengan Piagam Madinah) tumbuh berkembang. Pinjam istilah Kyai Hasyim Muzadi, inti demokrasi Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah adalah kesepakatan. Dan kesepakatan hanya bisa tercapai jika masing-masing pihak mau menghargai pendapat dan pikiran pihak lain, kemudian mengakomodasinya. Seperti kesepakatan para founding fathers bangsa Indonesia yang menyetujui Pancasila sebagai Dasar Negara dan kemudian mencoret tujuh kata (Piagam Jakarta) dalam preambul UUD 45. [] 128 Upaya Memperbarui Demokrasi Pancasila Satrio Arismunandar Penulis, praktisi media, peminat masalah sosial-politik dan hankam Sesudah sekian lama kita tidak bicara tentang ideologi, apalagi ideologi yang secara spesifik kita namai “Demokrasi Pancasila,” rasanya menyegarkan membaca bahwa Denny JA mengangkat lagi topik ini. Apapun latar belakangnya, karena isu ini bersifat cukup strategis bagi masa depan bangsa, inisiatif Denny patut kita apresiasi. Dulu pernah ada polemik cukup ramai. Tidak persis tentang ideologi Demokrasi Pancasila, tetapi tentang sesuatu yang lebih operasional atau turunan dari ideologi, yakni sistem “Ekonomi Pancasila.” Topik ini muncul dan dipelopori oleh ekonom senior UGM, Prof. Dr. Mubyarto. Namun, para ekonom dari UI, yang cukup dominan di pemerintahan Orde Baru waktu 129 itu, tampaknya tidak cukup mengapresiasi gagasan Mubyarto. Inisiatif Denny tidak muncul dari awang-awang, namun bersentuhan dengan konteks aktualitas, yakni Pilkada DKI Jakarta 2017 yang baru saja berlalu. Pilkada yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai Pilkada yang paling brutal, vulgar, kasar, memecah belah, dan menghalalkan segala cara. Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dieksploitasi habis-habisan di sini. Konteks Pilkada DKI ini secara implisit juga tersambung ke Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Denny memulai dengan narasi pasca Pilkada DKI Jakarta, yang dianggapnya telah membelah publik dan elit politik secara serius. Sehingga, dalam waktu yang tak lama, demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak Reformasi 1998 bisa jadi akan mengalami kemunduran yang signifikan. Artinya, dalam waktu dekat Indonesia akan terkoyak-koyak dan tidak stabil. Sedangkan dalam waktu yang tak lama, demokrasi Indonesia akan berada dalam ketidakpastian yang berlarut, serta memundurkan semua pencapaiannya. Ada rekan yang menganggap pernyataan Denny ini berlebihan. Ikatan yang merajut kebangsaan Indonesia dipandang cukup kuat dan ulet, tidak mudah untuk koyak atau putus begitu saja. Sejarah membuktikan bahwa 130 ikatan bangsa ini sudah melalui banyak ujian dan toh ternyata tetap bertahan. Ketika Uni Soviet dan Yugoslavia tercerai berai, pecah jadi beberapa negara, Indonesia yang bertubi-tubi dihantam krisis ekonomi dan politik ternyata bertahan. Namun, saya lebih condong ke pandangan Denny untuk bersikap lebih hati-hati. Di dunia yang kita huni sekarang, perubahan teknologi komunikasi terjadi begitu cepat, dan teknologi-teknologi baru lain juga telah mengubah dunia secara tak terduga. Generasi muda sekarang juga tidak mengalami pengalaman kesejarahan yang sama, yang jadi salah satu faktor pengikat bangsa, seperti generasi ayah dan kakeknya. Maka, lebih aman untuk tidak taken for granted dengan apa yang namanya “rajutan tenun kebangsaan.” Denny meneruskan dengan imbauan bahwa komitmen semua warga pada Demokrasi Pancasila perlu ditegaskan kembali. Tapi Demokrasi Pancasila yang diperlukan saat ini bukanlah “Demokrasi Pancasila” seperti yang diterapkan di zaman Orde Baru, tetapi adalah Demokrasi Pancasila yang sudah diperbarui dengan perkembangan baru. Menurut Denny, ada empat pokok isu strategis pasca Pilkada Jakarta. Pertama, menjelaskan aneka embrio 131 platform yang berbeda dan saling bertentangan yang ada saat ini, mengenai ke mana Indonesia harus dibentuk. Aneka platform itu ikut bertarung mewarnai Pilkada DKI 2017. Meski hasil KPUD soal Pilkada sudah disahkan, konflik gagasan dan embrio platform justru terus membara, berbeda, bahkan bertentangan. Yakni, tentang bagaimana sebaiknya aturan main bersama tersebut. Kedua, argumen mengenai mengapa para elit perlu menegaskan komitmen pada Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Juga dijelaskan, apa beda Demokrasi Pancasila yang diperbarui dengan Demokrasi Pancasila sebagaimana yang diterapkan di era Soekarno dan Soeharto. Dijelaskan pula, dimana bedanya Demokrasi Pancasila yang diperbarui dengan demokrasi liberal yang kini berlaku di dunia Barat. Ketiga, penjelasan soal apa yang kurang dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini, agar mencapai platform ideal Demokrasi Pancasila yang diperbarui itu. Keempat, apa yang semua kita bisa kerjakan, untuk ikut mengkonsolidasikan Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Denny melanjutkan, platform Demokrasi Pancasila yang diperbarui perlu dikonsolidasikan. Ada tiga isu yang perlu ditambahkan agar Demokrasi Pancasila yang diperbarui itu bisa diterima sebagai satu-satunya 132 ideologi yang kita operasionalkan. Pertama, justru karena demokrasi ini memberikan peran agama yang lebih besar di ruang publik, perlu dibuat sebuah Undang-Undang Perlindungan Kebebasan dan Umat Beragama. Pernyataan Denny ini sebetulnya sangat umum, sehingga perlu elaborasi. Peran agama yang lebih besar di ruang publik itu contohnya seperti apa? Kedua, mengakomodasi luasnya spektrum gagasan yang ada dalam masyarakat. Sejauh itu semua masih dalam bentuk gagasan, ia boleh tetap hidup di ruang publik. Yang dilarang hanya gagasan yang merekomendasikan kekerasan, seperti terorisme, atau gagasan yang dipaksakan dengan kekerasan atau tindakan kriminal. Padahal prinsip Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Modern menjamin hak hidup aneka gagasan sejauh masih dalam bentuk gagasan, dan tidak menyerukan kekerasan ataupun tindakan kriminal. Ketiga, prinsip kedua itu harus juga diikuti tegaknya “law enforcement” aparatur negara yang harus sepenuhnya disadari pemerintah. Ketika demokrasi masih labil seperti sekarang, pemerintah harus hadir. Pemerintah harus tegas dan keras melindungi keberagaman itu. Jika tidak, kebebasan yang ada justru digunakan untuk menindas yang lemah. *** 133 Untuk menanggapi Denny, saya mencoba menguraikan dulu apa yang dimaksud dengan ideologi politik. Dalam studi sosial, ideologi politik adalah seperangkat etik tertentu tentang hal-hal ideal, prinsip, doktrin, mitos, atau simbol dari gerakan sosial, lembaga, kelas, atau kelompok besar, yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus berjalan. Ideologi-ideologi politik, termasuk Demokrasi Pancasila, berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Antara lain: ekonomi, pendidikan, sistem peradilan, patriotisme, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Ideologi politik memiliki dua dimensi, yakni tujuan (bagaimana masyarakat harus berjalan) dan metodemetode. Metode yang dimaksud adalah cara-cara yang paling tepat untuk mencapai pengaturan yang ideal tersebut. Ideologi-ideologi juga mengidentifikasi dirinya lewat posisinya dalam spektrum politik (misalnya: kiri, tengah, kanan), walaupun presisi pemosisian ini bisa jadi kontroversial. Ideologi juga bisa dibedakan secara jelas dari strategi-strategi politik (misalnya, populisme). Maka, ketika Denny mengatakan Demokrasi Pancasila perlu diperbarui, ada pertanyaan besar yang butuh jawaban. Ada banyak aspek dari Demokrasi Pancasila. Aspek-aspek mana yang perlu diperbarui? Dan, sebelum 134 aspek-aspek itu diperbarui, apakah kita sudah cukup jelas atau berada dalam pemahaman yang sama, tentang apa yang dimaksud dengan “Demokrasi Pancasila” itu sendiri? Kalau kita melihat Demokrasi Pancasila dari praktik nyata yang dilakukan di setiap pemerintahan, sejak Proklamasi Kemerdekaan, maka Demokrasi Pancasila ternyata punya wajah yang berbeda-beda. Wujud Demokrasi Pancasila di zaman Soekarno sangat kontras dengan di zaman Soeharto. Belum lagi kita menyebut zaman presiden-presiden pasca Soeharto. Untuk benar-benar diterapkan, Demokrasi Pancasila harus mempunyai “rumus-rumus turunan” yang lebih membumi dan operasional. Misalnya, kalau kita bicara tentang penerapan demokrasi liberal di Amerika Serikat sebagai suatu ideologi, kita bisa menjabarkan konsepkonsep operasionalnya berupa sistem ekonomi kapitalis. Tetapi jika kita bicara tentang sistem Ekonomi Pancasila, sebagai salah satu konsep operasional dari Demokrasi Pancasila, ternyata belum ada kesatuan pandangan bagaimana mewujudkan Ekonomi Pancasila. Hal yang sering disebut sebagai ciri Ekonomi Pancasila biasanya adalah merujuk ke pasal 33 UUD ’45, yakni: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang 135 penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tetapi apakah sistem Ekonomi Pancasila itu memang benar-benar terwujud dalam praktik? Nyatanya, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia yang ber-Demokrasi Pancasila menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Dengan ciri antara lain: Keterbukaan dan ketergantungan pada kapital asing, ketergantungan pada utang luar negeri, liberalisasi arus keuangan, privatisasi besar-besaran pada perusahaan negara, penyerahan layanan publik pada mekanisme pasar, dan liberalisasi perdagangan. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus diperbarui dari Demokrasi Pancasila? Jika yang diperbarui adalah tentang tujuannya, maka saya berpendapat, hal itu terlalu prinsipil untuk disebut sebagai sekadar “pembaruan.” Mengubah tujuan bukanlah sekadar upgrading, seperti kita merenovasi sebuah bangunan. Tetapi ini sudah 136 mengubah total bangunan itu sendiri, sehingga kita mungkin sudah tidak mengenali sisa-sisa bangunan lama di dalam wujud bangunan yang baru. Maka, yang masih dimungkinkan dengan sebutan “pembaruan” itu adalah dalam hal metode-metode. Yakni, bagaimana cara-cara yang paling pas untuk mencapai ideal yang diidamkan. Di sini Denny memasukkan peran agama. Demokrasi Pancasila yang diperbarui ini memberikan peran agama yang lebih besar di ruang publik. Sayang, tidak ada penjelasan yang memadai tentang apa yang dimaksud Denny dengan “peran agama yang lebih besar” di ruang publik. Apakah itu berarti dominasi perspektif keagamaan dalam memandang, menilai, mengevaluasi, bahkan menghakimi berbagai isu-isu kemasyarakatan? Apakah “penerapan perda syariat” termasuk dalam “peran agama yang lebih besar,” yang dimaksud Denny tersebut? Isu perda syariat ini pernah ramai di media sosial pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ada tudingan seolah-olah pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah membuat “komitmen” dengan ormas-ormas Islam tertentu yang mendukungnya, untuk menerapkannya di Jakarta. Buat perbandingan, coba kita lihat contoh Iran. 137 Di Republik Islam Iran, kita kenal konsep velayat-e fakih (pemerintahan oleh para ahli hukum agama yang adil), yang menjadi landasan didirikannya rezim gabungan demokratis dan teokratis di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Ada pemilu parlemen dan pemilihan Presiden yang berlangsung demokratis. Namun, jika ada undang-undang yang oleh ulama dianggap bertentangan dengan hukum atau ajaran Islam, undang-undang itu bisa dibatalkan oleh ulama Iran. Jadi Iran adalah negara yang demokratis di Timur Tengah. Jauh lebih demokratis daripada Arab Saudi atau monarki-monarki Arab lainnya, dimana kekuasaan diwariskan turun-temurun. Namun, peran agama juga sangat besar dan menentukan di Iran. Sebelum ada pembaruan yang disebutkan Denny, peran agama pasti sudah ada di ruang publik, meski tidak sangat dominan. Jadi, sebetulnya tidak ada perubahan prinsipil dari “Demokrasi Pancasila” format lama. Bedanya hanya dalam gradasi atau level dominasi peran agama tersebut. Saya menduga, peningkatan peran agama yang dimaksud Denny itu tidak sampai ke level seperti di Iran. Jadi peningkatan perannya sebetulnya juga tidak terlalu drastis. Ideologi politik sebagian besar berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan kekuasaan dan ke arah tujuan 138 mana kekuasaan itu harus digunakan. Masing-masing ideologi politik mengandung ide-ide tertentu tentang apa yang dianggap sebagai bentuk sistem pemerintah terbaik (demokrasi, monarki, teokrasi, khilafah, dan sebagainya) dan sistem ekonomi terbaik. Nah, dalam “pembaruan” yang digagas Denny, apakah ada yang berubah dalam alokasi kekuasaan atau arah tujuan di mana kekuasaan itu digunakan? Sejauh yang saya tangkap, tampaknya tidak ada perbedaan yang jelas atau signifikan, antara kondisi sebelum dan sesudah pembaruan. Demokrasi Pancasila sebelum dan pasca pembaruan Denny sebetulnya tidak mengalami perubahan, dalam hal alokasi kekuasaan dan arah tujuan dimana kekuasaan itu digunakan. Sedangkan, tentang sistem pemerintah terbaik dan sistem ekonomi terbaik, pasca pembaruan yang diusulkan Denny, saya juga belum menangkap gambaran yang jelas. Tapi tampaknya, tidak ada perubahan berarti dalam sistem pemerintahan. Kita masih punya lembaga Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Tentang sistem ekonomi, juga belum ada penjelasan lebih jauh. Padahal sistem ekonomi ini bersifat krusial. Namun, dalam hal ini tampaknya juga tidak ada perubahan signifikan. 139 Dari semua uraian di atas, saya berpendapat, gagasan Denny yang mengusulkan “pembaruan” pada Demokrasi Pancasila, tetap harus diapresiasi. Hal ini karena memang demokrasi kita harus selalu siap merespon perkembangan zaman, baik karena dinamika internal (domestik) maupun perubahan global. Demokrasi kita, apakah mau disebut dengan Demokrasi Pancasila atau sebutan lainnya, harus menjadi ideologi terbuka yang bisa selalu ditafsirkan ulang, untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, “pembaruan” yang digagas Denny adalah sebuah kerja besar dan cukup berat. Denny tentu menyadari hal itu. Bisa dipahami, tidak cukup ruang bagi Denny untuk menjelaskan gagasan besarnya dalam sebuah artikel pendek, sehingga wajar jika muncul banyak pertanyaan. Barangkali, Denny perlu meluangkan lebih banyak waktu, untuk merinci gagasannya tentang “pembaruan” Demokrasi Pancasila. Hal yang harus dijawab, adalah: Aspek-aspek dan komponen-komponen apa dari Demokrasi Pancasila itu yang mengalami pembaruan? Bagaimana bentuk dan isi pembaruan itu? Dan, seberapa mendalam level atau tingkatan perubahannya? Jika Denny sudah menjabarkan jawaban (paling tidak secara kasar atau garis besar) atas pertanyaan-per140 tanyaan ini, barulah kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Yakni, untuk mengangkat isu pembaruan Demokrasi Pancasila ini ke tingkatan yang lebih tinggi (new level). Seperti yang saya nyatakan di atas, ini memang sebuah kerja besar dan kerja berat. Denny sudah mengawali dengan langkah pertama. Tugas kita mendorong Denny, sekaligus ikut berpartisipasi, dalam menjalani langkahlangkah berikutnya. [] 141 142 Momentum Pelembagaan Pancasila Ali Munhanif Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP), Pengajar Ilmu Politik UIN Jakarta Ketika Denny JA mengundang saya untuk menulis sebuah tanggapan tentang gagasan Pembaruan Demokrasi Pancasila, sulit bagi saya untuk menyikapi bagaimana harus menyambut undangan ini. Undangan itu tentu saja sekaligus tantangan, dan tujuannya juga mulya. Tetapi segera setelah merenungkan secara mendalam tantangan itu, perasaan saya diliputi sejumlah kebimbangan. Pertama, untuk pertamakalinya sejak rezim Orde Baru beserta perangkat kelembagaannya tumbang pada 1998, ajakan memperbincangkan kembali Pancasila secara serius dibuka. Tapi bagi kalangan yang mengamati bagaimana Pancasila diposisikan dalam diskursus politik In- 143 donesia, perbincangan tentang itu seperti menghadapi dua tabu sekaligus. Tabu karena Pancasila hampir identik dengan alat kelembagaan Orde Baru untuk melegitimasi perilaku rezim, sehingga membuka kembali perbincangan tentangnya sudah pasti akan dibaca sebagai upaya menghidupkan kembali otoritarianisme, kekerasan, dan penindasan politik. Tabu yang lain adalah Pancasila terlanjur menjadi kesepakatan oleh hampir semua komponen politik bangsa—baik di partai politik, perkumpulan kedaerahan, maupun ormas Islam, atau organisasi civil society lain— sebagai “bentuk final” dari cita-cita kenegaraan. Begitu idealnya mereka memosisikan Pancasila, sehingga perbincangan kembali Pancasila bisa dituduh sebagai pelanggaran kesepakatan nasional tadi. Menyambut niat baik Denny JA tidaklah cukup mengiyakannya saja, tetapi juga mencari celah yang tepat di mana saya bisa menyumbangkan sisi penting dalam menemukan visi baru demokrasi Pancasila. Kedua, undangan Denny JA bisa dibilang datang tepat waktu. Meskipun isu Pancasila adalah isu klasik tentang hubungan Islam dan negara, undangan tadi datang ketika 144 akhir-akhir ini bangsa Indonesia seperti terbelah akibat gejolak sosial, politik dan keagamaan yang diakibatkan oleh proses Pilkada DKI 2017. Kegelisahan utama akan kebangkitan isu SARA dipicu oleh meningkatnya mobilisasi agama untuk tujuan-tujuan politis. Pilkada yang pada awalnya bertujuan memilih pemimpin daerah telah berubah jauh menjadi pintu masuk mobilisasi SARA yang sudah pasti berpotensi memecah belah sentimen kebangsaan masyarakat. Pilkada memang berjalan lancar, dan pemenangnya juga sudah ditetapkan. Tapi efek mobilisasi SARA dalam Pilkada tadi tampaknya akan mewariskan persoalan sosial politik dan kebudayaan yang jauh melampaui tujuan Pilkada itu sendiri. Ia memberi pertanda bahwa, jika tidak ditata ulang apa makna demokrasi Pancasila, bukan tidak mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi ancaman serius di mana ketegangan hubunganAgama dan Negara akan terus timbul. Di tingkat ini, bukan saja kita sulit merajut kembali ketegangan di antara keduanya, perpecahan NKRI yang bersumber pada konflik SARA pun tak terelakkan. Di situ, ajakan Denny JA untuk membuka diskursus baru tentang demokrasi Pancasila patut diapresisasi. 145 Isu penting yang diunggah Denny JA adalah posisi agama dalam visi dan praktik demokrasi Pancasila. Benarkah mobilisasi agama akan terus meningkat di masa depan dan menjadi batu loncatan bagi politik Islam untuk melembagakan visi keagamaan yang melekat dalam ideologi “Negara Islam”? Akankah kekuatan mobilisasi agama berlanjut, dan bisa direproduksi untuk artikulasi kepentingan-kepentingan politik-agama dalam koridor demokrasi Indonesia? Harus diakui, mobilisasi agama di ruang publik berkenaan Pilkada DKI Jakarta sangatlah mengagumkan, sekaligus memilukan. Bukan saja berhasil memenangkan Calon Gubernur dan Wakilnya dalam meraih kursi pimpinan daerah di DKI Jakarta, tetapi juga menghasilkan sebuah capaian politik-keagamaan yang akan dikenang sepanjang masa dalam sejarah politik di tanah air, yakni Aksi Bela Islam 212. Tetapi jika dilihat dari pentingnya isu protes yang melandasi dukungan terhadapnya, keberhasilan Aksi 212 mengisyaratkan cerita lain. Yaitu bahwa, telah terjadi penyempitan agenda politik dari perjuangan mendirikan negara Islam, penerapan shari’ah, menolak sekularisme, dll., menjadi keprihatinan pada aspek-aspek 146 inti (core issues) dari doktrin agama, termasuk isu tentang penodaan agama, Muslim vs. kafir, menolak shalat jenazah dan semacamnya. Karakter mobilisasi politik Islampun bergeser secara substantif. Di masa lalu politik Islam didefiniskan sebagai “perjuangan ideologis” yang bertujuan menegakkan konstitusi Islam pada negara nasional, di mana institusi dan otoritas agama mengambil peran dalam tata kelola negara, hukum dan kebudayaan. Dewasa ini politik Islam telah bertransformasi menjadi “pergulatan identitas kultural” yang memosisikan diri sebagai aspirasi menjaga publik dari efek buruk modernisasi, seperti pudarnya tradisimasyarakat relijius, meluasnya gaya hidup urban, dan perbaikan akhlaq. Oleh karenanya, sukses Aksi 212 yang didukung oleh hampir seluruh komponen ormas Islam itu terlihat kontras ketika dibenturkan dengan realitas pahit politik Islam dalam mengarungi demokrasi sejak 1999. Pertama, dari pemilu ke pemilu perolehan suara partai Islam tidak pernah meningkat—untuk tidak mengatakan merosot. Kekuatan elektoral gabungan partai-partai Islam (PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB) tidak beranjak antara 32 dan 36 persen. Artinya, keberhasilan mobilisasi massa dengan menggunakan simbol dan ritual keagamaan tadi tidak tercermin dalam mobilisasi elektoral Islam. 147 Kedua, makin terserapnya civil society berbasis Islam ke dalam pusaran dunia teknokratik akibat terjadinya konvergensi politik (political convergence) antara Islam dan negara. Konvergensi di sini merujuk pada proses politik dan kelembagaan di mana agenda kultural dari ideologi Islam semakin terwadahi dalam institusi penyelenggaraan negara. Gejala ini memberi jalan bagi aktivis Muslim berpartisipasi dalam urusan birokrasi dan administrasi negara, baik di kementerian, parlemen maupun lembaga lain. Akibatknya, kepemimpinan sosial-keagamaan di akar rumput kehilangan daya tarik, yang untuk kemudian diambil alih oleh golongan Muslim baru yang bermunculan. Inilah yang menjelaskan mengapa ormas Islam yang dipandang radikal seperti FPI, FUI dan HTI, atau da`i tak dikenal pada basis institusi sosial lama seperti NU dan Muhamnmadiyah, memenangkan hati umat akhir-akhir ini. Di era Orde Baru, konvergensi Islam dan negara difasilitasi oleh langkah rezim untuk mengakomodasi kepentingan umat dalam struktur dan lembaga negara. Di era reformasi, meski partai Islam gagal mencantumkan kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945, konvergensi politik dilangsungkan pada institusi di bawahnya dan dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. 148 Memang tidak akan terjadi transformasi konstitusional menuju negara Islam, tetapi pelembagaan identitas agama pada institusi-institusi publik kian hari kian mewarnai tata kelola pemerintahan kita. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2015) mencatat, sejumlah UU yang secara eksplisit bermuatan Islam disahkan antara 2004 dan 2013: UU Peradilan Agama, UU Pendidikan Tinggi, UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU Pengelolaan Haji, UU Pornografi, dan UU Perbankan Syariah. Trend ini berjalan paralel dengan disahkannyasekitar 367 legislasi daerah dalam bentuk Perda bernuansa agama (2005-20013). Tak terhitung lagi jumlah Peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota yang meneguhkan pelembagaan identitas Islam di berbagai daerah. *** Di sinilah meningkatnya mobilisasi agama akhir-akhir ini harus dimaknai: ia menjadi jembatan bagi arah baru transformasi, di mana aspek-aspek yang terkait dengan ideologi negara Islam mengelupas (dislodged) menanggalkan atau tepatnya menyisakan isu-isu inti doktrinal semisal penodaan agama dan membela fatwa ulama. Menariknya, isu-isu tadi masih menjadi concernbagi sebagian elit Islam yang, pada situasi tertentu, berhasil 149 mengolahnya untuk artikulasi kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan. Saya berpendapat bahwa proses-proses demokratis dalam mobilisasi agama—sekeras apapun--berjalin kelindan dengan makin kuatnya komitmen umat Islam pada NKRI dan Pancasila sebagai bentuk final dari cita-cita kenegaraan. Ini berarti konflik konstitusional antara Islam dan negara sekuler telah selesai (settled). Proses historis yang turut menyumbangkan settlement tersebut adalah gerakan Pembaruan Islam pada 1970an dan warisan kebijakan Orde Baru. Namun karena penataan desain kelembagaan pada institusi-institusi di bawah konstitusi terus berjalan, mobilisasi agama untuk kepentingan politik akan tetap mewarnai pola kompetisi antar partai dan kelompok identitas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsial. Demokrasi tetap membuka ruang bagi kelompok politik manapun untuk semakin bergerak ke tengah, prgamatis dan menjadi moderat. Sehingga kemungkinan mobilisasi identitas agama akan melemahkan komitmen pada Pancasila, masih jauh hal itu terjadi. 150 Apa yang perlu ditekankan dalam perdebatan tentang “Demokrasi Pancasila yang Diperbarui” adalah proses yang menegangkan dalam Pilkada DKI yang baru lalu itu dijadikan momentum untuk mencari format “jalan demokratis melembagakan Pancasila”. Karenanya, bukan soal kesesuaian demokrasi dengan norma-norma Islam Indonesia yang menjadi perbincangan, tetapi bagaimana negara yang berdaulat seperti NKRI menyelesaikan gerakan-gerakan intoleran yang selama dua dasawarsa ini menghantui praktik demokrasi kita. Pertumbuhan pesat gerakan sosial keagamaan yang mengusung ideologi kekerasan dan revolusi agama menjadi ancaman serius bagi daya tahan NKRI. Para pemangku kebijakan dan cendekiawan harus menyadari bahwa aksi intoleran yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah bentuk dari upaya menghidupkan ikatan ideologis dan primordial yang terbingkai dalam imaginasi tentang “negara alternatif ”. Sentimen akan tatanan alternatif ini terus muncul bersamaan dengan kekecewaan masyarakat akibat buruknya institusi-institusi kenegaraan yang kita bangun lewat demokrasi. Di mata masyarakat bawah, pemerintahan demokratis bukan saja belum mampu memenuhi janjinya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga gagal 151 dalam menjaga wibawanya akibat lemahnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan mencegah kekerasan di ruang publik. Perpaduan antara kekecewaan dan kebebasan inilah yang menjadi akar dari mudahnya masyarakat dimobilisir untuk bergabung kedalam organisasi dan gerakan intoleran. Dan mengamati artikulasi kelompok-kelompok intoleran, terdapat benang merah antara kekerasan yang timbul dengan sentimen negara alternatif yang diimpikan. Joel Migdal, sarjana sosial terkemuka yang mengamati proses pembentukan negara baru, mengingatkan: akan terjadi pertarungan visi antara “kekuatan tradisional seperti agamawan dan ulama” melawan “pemimpin negara yang baru merdeka” pada pasca Perang Dunia II. Pertarungan itu memaksa para negarawan untuk menyelesaikan ketegangan antara keterikatan primordial seperti Islam versus negara yang berorientasi civic. Jika berhasil, negara tersebut akan tumbuh menjadi negara civic. Namun jika gagal, ia akan terjebak menjadi negara lemah (weak state) berhadapan dengan loyalitas tradisional masyarakatnya. 152 Tantangan kita semua dengan demikian adalah menyikapi dengan tegas aksi-aksi intoleransi atas nama negara alternatif tadi. Berkaca pada pengalaman seperti Pakistan, merosotnya otoritas negara dan pemerintah Pakistan berjalan paralel dengan tingginya mobilisasi organisasi Islam garis keras yang mengedepankan “sistem Islami” sebagai alternatif dari sistem kenegaraan, meskipun secara formal negara ini memproklamirkan diri sebagai Republik Islam Pakistan. *** Ada sejumlah strategi yang bisa diambil sebagai landasan untuk memulai memikirkan secara serius mengenai pelembagaan Pancasila—yakni menerjemahkan nilainilai kemanusiaan universal versi Indonesia tadi ke dalam kebijakan dan lembaga negara. Pertama, memperkuat pemerintah daerah dengan visi pentingnya menjaga otoritas negara dari rongrongan intoleransi. Intoleransi di daerah mengambil bentuk yang bervariasi, bergantung pada konfigurasi kekuatan sosial, politik dan kultural di daerah itu. Sehingga sudah semestinya pencegahan dini terhadap potensi intoleransi tidak semata-mata bersandar pada inisatif pusat, melainkan kepala daerah dan jajarannya di lini terdepan penangan konflik-konflik intoleran. 153 Pelembagaan Pancasila juga berarti memberdayakan institusi yang menjadi garda terdepan untuk ketertiban dan keamanan. Pada tingkat kementerian, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), dituntut untuk bisa lebih tegas terhadap perkumpulan, pergerakan dan organisasi yang jelas-jelas berseberangan dengan Pancasila. Pada tingkat lembaga dibawahnya, ketegasan itu bisa dilimpahkan pada institusi kepolisian. Meskipun pemahaman Polisi tentang managemen penanganan organisasi intoleran masih perlu ditingkatkan, nilai strategis polisi terletak pada dua hal. Selain mempunyai kewenangan memaksa untuk penegakan ketertiban masyarakat, polisi juga hadir di unit pemerintahan terendah dalam NKRI, yaitu kecamatan. Selain itu, untuk kepentingan jangka panjang, pendidikan nilai-nilai civic keindonesiaan sudah saatnya dihidupkan kembali. Pemerintah perlu memiliki cetak biru kurikulum pendidikan civic yang melandasi terbentuknya NKRI, seperti memperkuat kemajemukan, kesatuan, dan identitas kebangsaan. Dalam sejarah masyarakat apapun, pendidikan menjadi sarana paling efektif dan beradab untuk menyemaikan norma sosial dan budaya bersama. Bahkan, dengan 154 strategi kurikulum yang baik, pendidikan agama sekalipun bisa diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai civic kebangsaan. Tanpa sikap tegas soal intoleransi, bukan tidak mungkin NKRI berdasarkan Pancasila ini gagal menerjemahkan visinya mengenai negara modern yang maju dan berperadaban dan semakin terjebak menjadi negara lemah; suatu keadaan di mana negara atau pemerintahan tidak punya kapasitas kelembagaan untuk menginstitusionalisasikan warganya kedalam visi baru tentang tujuan bernegara. [] 155 156 Bug pada Demokrasi Pancasila Jonminofri Penulis, praktisi media Demokrasi Pancasila tidak berjalan mulus di Indonesia di mata Denny JA. Seperti pada dunia teknonologi informasi, diduga ada bug pada demokrasi yang berjalan di Indonesia sejak zaman reformasi. Karena itu, Denny menawarkan up date untuk menghilangkan bug pada Demokrasi Pancasila yang diberi nama Demokrasi Pancasila yang Diperbarui. Seperti pada aplikasi komputer, bug pada Demokrasi Pancasila sangat mengganggu. Ini kata Denny JA: Indonesia akan berada dalam ketidakpastian yang berlarut dan memundurkan semua pencapaiannya… jika para elite yang berpengaruh di negri ini tidak meneguhkan komitmennya kembali pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui. Mengerikan, kan? Para penyusun aplikasi di komputer, sering tidak menjelaskan dengan pasti apa persisnya bug yang meng157 ganggu itu. Mereka hanya mengatakan, “ini ada bug, harap di-up-date.” Denny pun begitu: tidak menjelaskan secara tegas apa yang salah pada Demokrasi Pancasila, dia hanya mengatakan ini penawarnya. Nah, bedanya dengan aplikasi: up date selalu diberikan oleh penyusun aplikasi itu, bukan oleh user. Tapi, Demokrasi Pancasila bukan aplikasi komputer, siapa saja bisa membuat update-nya jika diterima oleh masyarakat Indonesia. Untuk menerima atau menolak tawaran Denny ini tentu kita mencari jawaban atas dua pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apakah benar ada bug di dalamnya? Jangan-jangan kita hanya “gaptek” memainkan Demokrasi Pancasila, lalu kita menyalahkan demokrasi Pancasila sebagai aplikasi? Atau ada pihak yang menyalahgunakan Demokrasi Pancasila untuk tujuan lain atau tujuan jangka pendek yang mementingkan kelompok sendiri? Denny memberikan tiga isu yang harus ada pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui itu. Isu pertama: memberikan peran agama yang lebih besar di ruang publik karena itu perlu dibuat UU Perlindungan Kebebasan dan Umat beragama. Hmmm… isu ini mengundang pertanyaan lebih jauh, seperti apa peran agama yang lebih besar di ruang publik itu? Bukankah gagasan yang berkembang sekarang ini adalah mari kita 158 beramai-ramai membawa agama ke dalam hati masing-masing, bukan ke ruang publik? Di ruang publik seyogianya kita mengedepankan aneka kesamaan sebagai sesama warga negara Indonesia. Jika mengedepankan perbedaaan, kita cenderung bertikai terus seperti perilaku pendukung calon gubernur DKI di media sosial. Apa pun yang dilakukan pihak sana, disalahkan pihak sini. Dan sebaliknya. Mestinya kita berperilaku seperti anggota keluarga bahagia: selalu mencari kesamaan agar saling menyayangi berlangsung panjang. Praktik Pilkada Jakarta baru-baru ini memberikan pelajaran berharga untuk Indonesia: membawa agama ke ruang publik membuat luka baru di atas rasa benci lama pada pihak yang berbeda agama dan ras yang belum sembuh juga. Sampai kini pihak yang membawa iman dan agamanya di Pilkada masih bertikai dengan pihak yang menomorsatukan program. Pilihan membawa agama ke ruang publik hanya akan mempertebal lapisan diskriminasi pada masyarakat Indonesia. Buntutnya: warga nonmuslim tidak akan bisa menjadi pemimpin di negara ini. Hanya perlu mengatakan “pemilih pemimpin nonmuslim masuk neraka”, seorang pemimpin “kafir” yang mereka anggap telah bekerja sangat baik pun terjungkal dari kursi jabatannya. 159 Persoalan buat kita adalah bukan saja nasib pemimpin baik itu yang terjungkal. Lebih dari itu, rasa persatuan kita menjadi rusak. Keberagaman berubah arti dari menghargai perbedaan menjadi mencari-cari perbedaan. Sehingga kita menjadi seperti anggota keluarga yang selalu mengedepankan perbedaan, yang membuat semua anggota keluarga itu bertikai tanpa henti. Karena negara bukan keluarga, penyelesaiannya tidak bisa dengan “pisah ranjang” atau “bercerai”. Indonesia adalah keluarga sangat besar yang disatukan oleh Tuhan dengan Pancasila dan tidak bisa dipisahkan kecuali terjadi perang suadara. Ini makna NKRI harga mati yang sering diteriakan banyak orang belakangan ini. Isu kedua dalam gagasan Demokrasi Pancasila yang Diperbarui juga mengundang perdebatan panjang. Sebab, dalam isu ini, menurut Denny, kita harus memberikan tempat pada gagasan intoleran dalam Demokrasi Pancasila. Kata Denny, sepanjang masih dalam bentuk gagasan, tidak masalah kaum intoleran mengembangkan pahamnya. Nah, kaum intoleran ini bekerja seperti virus komputer. Virus komputer dirancang untuk mudah berkembang biak di dalam sistem. Mereka tidak punya toleransi. Apa saja yang mereka anggap salah, menyimpang, atau tidak sesuai dengan aturan mereka, akan disikat dengan kekuatan yang ada pada mereka. Jika kekuatan mereka 160 besar, seperti virus pada komputer, mereka benar-benar bisa melumpuhkan sistem di mesin pintar itu. Tidak ada toleransi pada virus. Untuk mengamankan sistem, virus harus di-delete habis menggunakan program antivirus yang ampuh. Jika Anda pengguna komputer, jangan sekali-sekali memasukkan virus ke dalam komputer, apalagi memberi ruang untuk virus berkembang. Cara bekerja gagasan intoleran persis seperti virus pada komputer. Mereka tidak membolehkan atau tidak membiarkan atau melarang hal-hal yang mereka anggap terlarang, atau salah, atau berbeda dengan mereka. Mereka tidak pernah istirahat menilai orang. Hidupanya sibuk memberi label pada teman, tetangga, tokoh, atau siapa saja yang terlihat salah di mata mereka atau melintas di media. Bila Natal tiba, mereka bergerombol keliling kota mencari pramuniaga muslim yang mengenakan pakaian warna merah ala sinterklas. Bila Ramadan datang mereka kerap menutup warung makan yang buka pintu di siang hari. Di luar Natal dan Ramadan mereka mecari penjual minuman keras di kafe, restoran, dan tempat lain. Intinya, mereka sering main hakim sendiri. Mereka berdalih bahwa Tuhan bersama mereka memerangi maksiat di tengah masyarakat. Bukankah perang saudara di beberapa negara terjadi karena kaum intoleran merasa cukup kuat. Sebelum terjadi perang saudara, mereka tumbuh dari kecil dan 161 membesar. Pada saat mereka semakin kuat, negara dan kaum toleran akhirnya kewalahan dan kalah menghadapi mereka. Sedangkan isu ketiga, isu terakhir: ajakan kepada pemerintah menegakkan Law Enforcement. Sebenarnya bagus juga gagasan Demokrasi Pancasila Diperbarui ini dilemparkan ke masyarakat. Setidaknya tulisan ini akan mengajak orang berfikir: bila masyarakat terbelah di dua kutub yang berseberangan seperti sekarang apa penyebabnya? Apakah benar ada “bug” pada konsep Demokrasi Pancasila sehingga kita membutuhkan konsep baru bernama Demokrasi Pancasila yang Diperbarui? Atau yang terjadi sebenarnya adalah kita lupa bahwa kita punya Pancasila? Yang kita ingat hanya bahwa kita adalah orang yang beriman dan bergama yang takut masuk neraka? Celakanya, ada orang yang bekerja dengan bayaran untuk meniupniupkan pilih jagoan seiman agar Anda bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur: siapa pilihan Anda dalam Pemilu/Pilkada? Jika akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa Demokrasi Pancasila perlu up date, salah satu isu yang harus disodorkan adalah elit politik harus mengedepankan kepentingan publik di atas segala-galanya, dan elit politik membuat karangan bunga ketika menerima 162 jabatan baru dengan pesan: Saya berjanji tidak akan korupsi. [] 163 164 Membangun Demokrasi Pancasila Setelah Pilkada Jakarta 2017 Jojo Rahardjo Penulis, bekerja untuk disasterchannel.co Ilmu pengetahuan terus berkembang. Teknologi juga berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling mempengaruhi. Jika teknologi berkembang, maka ilmu pengetahuan juga akan terdorong untuk berkembang. Begitu juga neuroscience juga berkembang pesat karena teknologi untuk menganalisa kerja otak sudah berkembang jauh. Electroencephalography (EEG), Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), dan Magnetoencephalography (MEG) adalah beberapa teknologi yang sudah berkembang lebih dahulu dan kemudian mendorong perkembangan neuroscience menjadi lebih jauh lagi. 165 Apa kaitan itu semua dengan Membangun Demokrasi Pancasila? Baru-baru ini Denny JA melempar keprihatinannya tentang Indonesia yang tidak mustahil akan terkoyak dan tidak stabil. Denny dalam tulisannya yang berjudul Tentang “Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui” menyampaikan bahwa dalam waktu tak lama, bukan tak mungkin demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak Reformasi 1998 mengalami break-down dan kemunduran yang signifikan. Sebagaimana kita tahu, Pilkada Jakarta yang baru saja berlalu adalah pilkada paling panas dan menyita waktu dan energi semua orang di negeri ini. Di bawah ini adalah beberapa peristiwa menonjol dalam pilkada Jakarta kemarin. Semua peristiwa ini mungkin akan berulang lagi pada pilkada lain atau pilpres berikutnya, sehingga perlu merenungkan tesis Denny di atas. 1. Ujaran kebencian dan permusuhan bebas disebarkan baik secara langsung maupun melalui berbagai media oleh timses ataupun oleh siapa pun. Padahal sudah ada aturan yang melarang itu. Seorang paslon bisa disebut kafir saat kampanye atau saat dikaitkan dengan kampanye, padahal kata “kafir” memiliki konotasi negatif atau sebuah stigma. Mungkin kata kafir boleh 166 saja disebut saat pengajian di mesjid yang dihadiri secara tertutup. Paslon tertentu juga sering disebut di tempat terbuka sebagai orang yang menghalangi masyarakat untuk masuk surga. Itu tentu juga ujaran kebencian dan permusuhan. 2. Ancaman atau perbuatan kriminal bebas dilakukan. Paslon tertentu dianjurkan atau didorong untuk dibunuh muncul di berbagai tempat umum. Di hadapan polisi atau penegak hukum itu bisa dilakukan, juga termasuk di depan kamera yang merekamnya. Sangat mungkin perbuatan ini akan meluas dilakukan oleh masyarakat umum. 3. Muncul pertentangan antara dalil agama dan hukum positif saat kampanye atau saat dikaitkan dengan kampanye. Dalil agama yang bertentangan dengan hukum positif bebas dikampanyekan, misalnya dalil agama yang mengatakan: “tidak boleh memilih kafir untuk menjadi pemimpin”. 4. Penegakan hukum tidak dilaksanakan. Penegak hukum menunggu laporan dari masyarakat, karena nampaknya penegak hukum tidak memiliki “pegangan” yang pasti dalam kasus seperti di nomor 1, 2, dan 3. 167 Menurut Denny Ada 4 platform gagasan yang ikut bertarung dalam Pilkada Jakarta yang baru berlalu kemarin. Pertarungan 4 platform itu akan semakin mengemuka pada pilpres 2019 nanti. Empat gagasan itu adalah: 1. Demokrasi modern, 2. Sistem sebelum amandemen UUD 1945, 3. Konsep negara Islam, 4. Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Keadaan yang memprihatinkan bakal terjadi jika para elit yang berpengaruh di negeri ini tidak meneguhkan komitmennya kembali pada demokrasi pancasila yang diperbarui. Itu akan terbukti jika semakin tak ada aturan main bersama yang berwibawa, akomodatif, dan disepakati sebagai “the only game in town.” Demikian tambah Denny. Berdasarkan pada survey nasional yang dilakukan LSI Denny JA sejak 2005 sampai 2016 dan juga survei Jakarta yang dilakukan terakhir di bulan April 2017, Denny ingin mengajak para elit yang berpengaruh untuk menegaskan komitmen kembali pada Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Sejak 2005 sampai kini hasil survey itu tak banyak berubah. Yang meinginkan negara Islam selalu di bawah 10 persen. Yang inginkan demokrasi liberal juga selalu di bawah 10 persen. Yang inginkan Demokrasi Pancasila selalu di atas 70 persen. 168 Apa yang Perlu Dilakukan? Martin Seligman, pelopor neuroscience dalam 2 dekade lebih menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan kurang mempelajari apa yang positif atau potensi positif yang terpendam selama ini dari manusia. Neuroscientist yang lain seperti Shawn Achor menyebutkan, bahwa jika potensi positif itu ditumbuhkan maka kita bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, lebih memiliki solusi, cenderung pada kebajikan, tidak mudah depresi, mudah pulih dari gangguan psikologi dan tubuh menjadi lebih sehat. Potensi positif itu sangat berkaitan dengan kondisi di otak kita. Jika otak kita memiliki kondisi yang maksimal maka otak kita disebut memiliki positivity. Dari berbagai penelitian neuroscience sepanjang 2 dekade lebih itu ditemukan adanya lima unsur positivity yang perlu ditumbuhkan oleh kita menurut Martin Seligman, yaitu PERMA: 1. Positive emotions, 2. Engagement, 3. Relationships, 4. Meaning, 5. Accomplishment. Jika kita memiliki semua 5 unsur positivity, maka kita disebut memiliki positivity atau kebahagiaan yang penuh. Kelima unsur positivity ini dapat menjadi dasar bagi penjabaran dari 5 pasal dalam Pancasila, karena penjabaran Pancasila harus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah neuroscience. Penjabaran itu sebagai berikut: 169 1. Pasal 1, Ketuhanan yang maha esa menggambarkan perlunya memiliki sifat-sifat baik tuhan yang perlu dimiliki oleh manusia. Neuroscience menyebutkan bahwa kegiatan spirituality adalah kecenderungan paling mendasar dalam diri manusia yang menghasil positivity yang besar dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. 2. Pasal 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan oleh neuroscience dan Golden Rule: “Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan pada kamu.” Neuroscience menjabarkannya sebagai perlunya melakukan kebajikan, karena menghasilkan positivity yang besar. Itu juga berarti: kita tidak bisa melakukan apa yang kita tidak ingin orang lain melakukan pada kita (kejahatan, permusuhan atau kebencian). Golden Rule dinyatakan oleh para antropolog sebagai dasar dari hukum positif. Kita tidak bisa menyatakan atau mengajarkan secara terbuka di muka umum (pada mereka yang berbeda-beda keyakinan) misalnya tentang orang lain sebagai kafir (punya konotasi buruk) atau orang lain tidak akan masuk surga atau agama tertentu lebih baik atau juga yang semacam itu. Alasannya sederhana, karena itu tidak mencerminkan Golden Rule. Itu juga tidak mencerminkan kebajikan yang idealnya dilakukan oleh kita untuk orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh neuroscience. 170 3. Pasal 3, Persatuan Indonesia dijabarkan oleh neuroscience sebagai perlunya bekerja sama secara terus-menerus sebagai makhluk sosial yang menghasilkan rasa secure yang menghasilkan positivity. 4. Pasal 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dijabarkan dengan neuroscience, yaitu relationships menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan atau dalam menentukan kebijakan negara. Relationships dalam neuroscience berarti hubungan timbal-balik atau saling membutuhkan yang menghasilkan positivity. Semua sederajat dalam pengambilan keputusan atau bukan di tangan individu atau segolongan yang memiliki otoritas lebih tinggi. Cara pengambilan keputusan dan definisi perwakilan menjadi lebih dinamis selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. 5. Pasal 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut neuroscience adalah tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan manusia sejak awal peradaban manusia yang pertama kali, yaitu perasaan positif atau juga perasaan bahagia yang penuh. Pasal kelima ini ini menggambarkan tercapainya lima unsur positivity yang disebutkan di atas yang menjadi tujuan akhir untuk dicapai atau diperoleh bagi seluruh rakyat Indonesia. 171 Dari penjabaran Pancasila di atas, maka setidaknya perlu dibuat aturan baru atau merevisi aturan yang sudah ada yang berkaitan dengan pilkada atau pilpres sebagaimana berikut ini: 1. Mengatur soal-soal apa yang boleh dilakukan saat pilkada, meski itu bertentangan dengan dalil-dalil agama: a. Ada penegasan melalui UU, bahwa dalil-dalil agama derajatnya berada di bawah hukum positif. b. Tidak menggunakan dalil-dalil agama untuk mendiskreditkan calon. c. Tidak menggunakan dalil-dalil agama untuk menyebar kebencian atau permusuhan. d. Kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan politik hanya bisa dilakukan di tempat ibadah yang tertutup, bukan di tempat umum. 2. Mengatur tentang bagaimana penegak hukum bertindak: a. Memproses hukum dengan cepat bagi mereka yang melakukan pelanggaran aturan nomor 1 agar pelanggaran tidak merebak atau tidak menghasilkan ekses yang berbahaya. 172 b. Melarang penegak hukum menggunakan simbol atau atribut keagamaan dalam tugasnya seharihari, karena penegak hukum bekerja untuk semua, maka ia harus bebas dari pengaruh agama apa pun. c. Membuat tim khusus yang bertugas mencari pelanggaran yang disebut dalam pasal-pasal di huruf 1. 3. Mengembangkan neuroscience sebagai program nasional untuk menumbuhkan positivity secara luas di masyarakat. a. Masuk ke sekolah dan universitas sebagai pelajaran ekstrakurikuler b. Sosialisasi melalui media elektronik dan media lainnya seperti program keluarga berencana dulu dilaksanakan. c. Pejabat pemerintah di tingkat atas dan wakil rakyat mendapat pembekalan positivity. Penutup Positivity atau neuroscience adalah salah satu ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pesat. Kehidupan modern sekarang ini terbentuk oleh ilmu pengetahuan 173 yang berkembang. Sehingga idealnya demokrasi Pancasila juga dijabarkan dengan ilmu pengetahuan. Neuroscience sejak 2 dekade lebih telah diaplikasi pada banyak aspek kehidupan. Salah satu yang paling populer adalah untuk menghasilkan produktifitas di perusahaanperusahan besar. Badan dunia seperti PBB pun mulai mengkaitkan GDP, persoalan sosial, kesejahteraan atau kemajuan sebuah negeri dengan neuroscience. Sejak tahun 2013, World Happiness Report diterbitkan setiap tahun. Dalam laporan ini terlihat kaitan Positivity atau Happiness dengan pencapaian sebuah negeri dalam berbagai soal. Inggris sudah menerapkan positivity untuk menjadi program nasional, yaitu di sekolah-sekolah. Setidaknya siswa mendapat ilmu pengetahuan tentang bagaimana memaksimalkan otaknya saat di sekolah dan nanti saat mereka bekerja untuk masyarakat. Demikian juga negeri-negeri maju lainnya sudah menerapkan neuroscience. Bahkan neuroscience mengungkap perbuatan-perbuatan yang menghasilkan positivity ternyata sudah diajarkan oleh spirituality sejak ribuan tahun lalu. Spirituality harus terus dihidupkan karena berakar sangat kuat di Indonesia. Neuroscience menyebut bahwa kebajikan akan menghasilkan positivity dan positivity akan meng174 hasilkan kebajikan. Begitu seterusnya. Jika itu sebuah lingkaran, maka lingkaran itu akan semakin besar dan kuat setiap hari. [] 175 176 Memaknai Demokrasi Pancasila Yang Diperbarui Dr. Umar S. Bakry Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Lewat tulisan berjudul “Paska Pilkada Jakarta: Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui”, Denny JA membawa kita pada suasana kebatinan politik dalam sidang BPUPKI 1945. Saat itu para tokoh bangsa bahu membahu merumuskan dasar negara sebagai pedoman bersama untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Perdebatan keras terjadi, terutama antara kelompok tokoh Islam dan Nasionalis-sekuler. Kalangan Islam berprinsip bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena Islam menurut mereka tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta. Kalangan Nasionalis adalah kelompok yang berprinsip bahwa ad-Din wa ad-Daulah (agama dan negara) harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, 177 dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurusi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja. Negara merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi. Kala itu Soekarno sudah mengungkapkan kekhawatirannya secara terbuka mengenai implikasi negatif yang akan muncul jika kalangan Islam memaksakan kehendaknya. Ia cemas kalau banyak bagian dari negara ini akan memisahkan dari Republik Indonesia yang mendasarkan diri pada agama Islam. Tokoh Nasionalis-sekuler, Soepomo, juga menegaskan bahwa jika negara Islam diciptakan di Indonesia maka sudah pasti persoalan minoritas dan masalah-masalah kelompok kecil agama dan yang lainnya akan muncul. Meskipun Islam menjamin kelompok agama lain sebaik mungkin, kelompok-kelompok minoritas tersebut tetap tidak merasakan keterlibatannya dalam negara. Akhirnya para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Rezim Soekarno menetapkan Demokrasi Pancasila sebagai satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Rezim Soeharto selama 30 tahun juga mendasarkan diri pada Demokrasi Pancasila. Namun demikian pemerintahan otoritarian Soekarno maupun Soeharto mengimplementasikan Demokrasi Pancasila sesuai dengan penafsirannya sendiri. Bukan berdasar178 kan kesepakatan nasional yang bersumber dari dialog pemikiran dari berbagai elemen bangsa. Akibatnya, baik Demokrasi Pancasila semasa Soekarno maupun Soeharto mendapatkan penolakan warga dalam bentuk runtuhnya kedua rezim tersebut. Kegagalan Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto membangunkan kembali wacana tentang Islam dan Negara, termasuk isu tentang Negara berazaskan Islam. Setidaknya diskursus tentang perlunya kejelasan relasi antyara Islam dan Negara mencuat kembali pada awal era Reformasi. Indikator paling jelas diantaranya adalah menguatnya gagasan pencantuman syariat Islam dalam dalam amandemen UUD 1945 setiap kali dilaksanakan sidang tahunan MPR hasil Pemilu 1999. Di lain pihak upaya perlawanan dari kaum Nasionalis-sekuler terhadap integrasi Islam dan Negara juga tidak pernah redup. Salah satu contohnya ketika Presiden PKS Hidayat Nur Wahid akan dilantik menjadi Ketua MPR konon sempat diminta bersumpah untuk setia pada Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Pilkada DKI Jakarta 2017 sekali lagi telah menjadi manifestasi nyata dari masih adanya pergulatan antara kalangan Islam dan Nasionalis-sekuler dalam kehidupan politik di Republik ini. Tak dapat disangkal, Pilkada Jakarta telah membuat warga terbelah. Apa yang dikhawatirkan Soepomo dan Soekarno menjadi nyata. Sebab 179 itu saya sepakat dengan Denny JA, dalam waktu dekat bukan mustahil Indonesia akan terkoyak dan tidak stabil, jika kita tidak berusaha keras merumuskan kembali sistem berbangsa dan bernegara dalam bentuk aturan main yang berwibawa, akomodatif, dan disepakati sebagai “the only game in town”. Setelah hampir dua dasawarsa hidup di era Reformasi, kita baru menyadari bahwa Republik ini ternyata belum memiliki sebuah sistem politik yang disepakati dan dihormati oleh semua elemen bangsa. Sebuah sistem yang semua warganya merasa terlibat dalam ruh yang sama. Pilkada Jakarta tiba-tiba menyentak kesadaran bersama kita sebagai bangsa bahwa masih ada masalah mendasar dalam kehidupan bersama yang belum kita selesaikan. Yakni membangun sebuah sistem yang menjadi landasan bersama yang dapat menjadi common denominator seluruh warga, semua kelompok, semua agama, dan semua kepentingan. Denny JA menawarkan sebuah konsep yang diberi nama “Demokrasi Pancasila yang Diperbarui”. Menurut Denny, konsep demokrasi ini berbeda dengan Demokrasi Pancasila era Soekarno maupun Soeharto. Demokrasi Pancasila yang Diperbarui juga tidak dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi liberal seperti yang berlaku di Barat, juga bukan mengarahkan menjadi negara Islam seperti 180 di Timur Tengah. Semua sistem tersebut tidak cocok dipaksanakan di Indonesia. Dalam berbagai survei yang dilakukan LSI maupun LSN, terbukti tidak lebih dari 10 persen publik yang menghendaki sistem demokrasi liberal, bentuk negara Islam, maupun sistem Demokrasi Pancasila era Soekarno dan Soeharto. Paska Pilkada Jakarta, Denny JA mengajak kita merenung dan mendiskusikan akan dibawa kemana negara Indonesia dengan konsep Demokrasi Pancasila yang diperbarui. Para elit, politisi berpengaruh, pemimpin pemerintahan, pengusaha, pemimpin partai, pemimpin ormas berpengaruh, pemimpin organisasi keagamaan, intelektual dan opinion makers yang berbeda pandangan, perlu didengar. Demokrasi Pancasila yang diperbarui tidak boleh menjadi sistem yang rapuh sebagaimana Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto yang dibangun semata-mata dari pemahaman subyektif penguasa. Demokrasi Pancasila yang diperbarui hendaklah dirumuskan berdasarkan pemahaman intersubyektif seluruh elemen bangsa (termasuk yang selama ini kita identifikasi sebagai kelompok garis keras). Sehingga dengan demikian sistem Demokrasi Pancasila kita yang baru benar-benar dapat menjadi rule of the game yang berwibawa dan tahan lama. Menurut Denny JA prinsip demokrasi apapun hanya akan kuat jika dikawinkan dengan kultur lokal yang 181 dominan. Untuk konteks Indonesia, goresan agama dalam batin masyarakat terbukti sangat mendalam. Sebab itu Demokrasi Pancasila yang kita perbaharui baru akan bisa mengakar dan memiliki daya tahan jika mengakomodasi kondisi itu dalam sistem kelembagaannya. Saya menafsirkan kultur lokal yang dominan itu sebagai keyakinan mayoritas masyarakat. Sebab itu Demokrasi Pancasila yang diperbarui (jika tidak cepat lapuk seperti Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto) harus akomodatif terhadap keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Pergulatan panas kelompok Islam dan Nasionalissekuler, sebagaimana terjadi dalam Pilkada Jakarta 2017, menurut saya akan terus berulang atau menyebar ke daerah-daerah lain apabila kita tidak segera memiliki aturan main yang akomodatif terhadap keyakinan mayoritas. Dalam konteks ini, saya setuju dengan gagasan Denny JA yang merekomendasikan peran agama yang lebih besar di ruang publik, sehingga praktek dan keberagaman paham agama yang ada terlindungi sangat kuat. Saya juga setuju bahwa pemerintah perlu membuat UU untuk lebih melindungi keberagaman agama dan kebebasan mereka beribadah dan bersosialisasi di ruang publik. Spektrum gagasan yang ada dalam masyarakat juga harus diakomodasi. Tidak boleh di Republik ini orang dihukum karena memiliki gagasan atau opini yang berbeda. 182 Namun dalam konteks mengakomodasi kultur dominan atau keyakinan mayoritas masyarakat, saya sedikit gagasan saya yang berbeda dengan Denny JA. Menurut saya, mengakomodasi keyakinan mayoritas berarti menjadikan nilai-nilai (values) mayoritas publik sebagai sumber perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian jika keyakinan atau values yang diyakini mayoritas publik menolak perilaku LGBT (misalnya), kita harus dapat menghormati keyakinan atau values tersebut. Dengan kata lain, kebebasan berekspresi sebagaimana kita rekomendasikan dalam sistem Demokrasi Pancasila yang diperbarui tetap harus peka terhadap keyakinan agama dari mayoritas publik. Jika Negara mentoleransi berbagai bentuk perilaku dan ekspresi kebebasan yang tidak parallel dengan values mayoritas maka kelompok mayoritas akan merasa tergores karena diabaikan keyakinannya. Kelompok mayoritas yang merasa tidak nyaman hidup dalam sistem yang berlaku, berpotensi menimbulkan instabilitas dalam sistem itu sendiri. Menurut saya, Demokrasi Pancasila yang diperbarui akan bernasib sama dengan Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto jika tidak mengakomodasi keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sudah jelas bahwa mayoritas ummat Islam Indonesia 183 menolak bentuk negara Islam. Yang mereka harapkan adalah penghormatan terhadap nilai-nilai dan keyakinan keagamaan mereka. Ini hanya merupakan salah satu contoh dari koreksi kecil saya terhadap pemikiran besar Denny JA. Berbagai wacana dari aneka kelompok masyarakat terbuka untuk diberikan guna memaknai, mengisi dan melengkapi gagasan Demokrasi Pancasila yang diperbarui yang dilontarkan pendiri LSI tersebut. Bagi saya, Denny JA dengan gagasannya itu dapat disebut sebagai seorang negarawan yang selalu peduli pada keselamatan negara dan bangsanya. Jika ide besar Denny JA ini dianggap angin lalu oleh semua elemen bangsa, terutama oleh para politisi berpengaruh, bukan mustahil masyarakat Indonesia bisa terbelah seperti warga Jakarta selama Pilkada. [] 184 Pancasila, Kawah Candradimuka, dan Anti Absolutisme Akhmad Sahal Kandidat PhD, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika Dalam pidatonya tentang Pancasila yang masyhur itu, Sukarno berbicara tentang Pancasila sebagai Weltanschauung, sebuah pandangan tentang dunia dan kehidupan. Di mata Bung Karno, Pancasila merupakan “dasar filsafat”, philosophische grondslag. Yakni, sebuah fondasi yang berfungsi sebagai perekat kebhinnekaan, sekaligus sebagai payung persatuan kebangsaan. Tapi di sisi lain, Bung Karno juga menyadari bahwa kehidupan politik senantiasa mengandung “perjuangan faham.” Kehidupan politik meniscayakan bukan hanya pertukaran tapi juga pertarungan ide-ide, bukan hanya deliberasi, tapi juga kontestasi gagasan. Secara berseloroh Bung Karno pernah berkata, “tak ada sebuah negara 185 yang hidup yang tak mengandung ‘kawah Candradimuka’ yang ‘mendidih’di mana pelbagai ‘faham’ beradu di dalam badan perwakilannya. Tak ada sebuah negara yang dinamis ‘kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya’. Bertolak dari pandangan Sukarno di atas, bisa kita simpulkan bahwa sejak awal, Pancasila tak pernah diniatkan untuk menjadi ideologi yang kekal, tertutup, dan absolut. Sebagai Weltanchauung bangsa Indonesia, Pancasila senantiasa berada dalam “kawah candradimuka” politik yang diwarnai oleh “perjuangan faham.” Artinya, Bung Karno sedari awal mengakui bahwa Pancasila mesti dilihat sebagai ideologi yang fleksibel, senantiasa diperbarui di tengah konteks sosial politik yang senantiasa berubah, dan membuka diri terhadap perkembangan dan modifikasi diri, karena adanya kesadaran bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan “tatanan-dalam-proses.” Dengan kata lain, penerimaan terhadap Pancasila mengandaikan sikap penolakan terhadap faham politik yang mengklaim berlaku mutlak dan absolut. Pancasila menampik absolutisme. Sebagai rumusan yang mangkus dan sangkli dari ikhtiar bangsa kita untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, Pancasila menegaskan dirinya sebagai paham yang bertentangan secara diematral dengan absolutisme. 186 Perspektif Bung Karno tentang Pancasila sebagai “anti absolutisme” di atas menarik untuk ditengok kembali manakala kita hendak berbicara tentang “demokrasi Pancasila yang diperbarui,” seperti diusulkan oleh Denny J.A dalam tulisannya baru-baru ini. Upaya memperbarui demokrasi Pancasila ini penting dan mendesak untuk dilakukan, setidaknya karena dua hal: Pertama, untuk waktu yang lama, telah terjadi semacam disenchantment of Pancasila, lenyapnya marwah Pancasila, akibat ulah Orde Baru yang secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan manipulasi terhadap dasar negara kita Di masa Orde Baru, Pancasila dikeramatkan dan di-sakti-kan. Pada saat yang sama, penafsirannya dimonopoli penguasa, dan dianggap identik dengan penguasa. Siapapun yang menentang penguasa langsung dicap menentang Pancasila. Kedua, makin maraknya wacana “negara Islam, “NKRI bersyariah,” atau “Khilafah” yang mendasarkan diri pada paham keagamaan yang absolutis dan mutlak-mutlakan. Mereka gemar mengklaim, lebih baik memilih dasar Syariah karena syariah datang dari Allah, sedang Pancasila itu hasil buatan manusia. Di mata mereka, jika hukum Allah adalah hukum yang hendak diterapkan, mau tak mau hasil yang akan tercipta adalah sebuah kehidupan sosial yang tanpa cacat. Probemnya adalah, mereka seringkali merasa mewakili suara Tuhan, meski187 pun tak jelas dari mana dan bagaimana ‘mandat’ itu bisa mereka perolah. Akibatnya, mereka merasa berhak untuk memaksakan paham keIslamannya sebagai satu-satunya “the law of the land” di Indonesia. Inilah sikap yang mencerminkan apa yang disebut Bung Karno sebagai ‘egoisme-agama’ yang menafikan karakter dasar Indonesia yang berbhinneka. Dalam situasi semacam itulah kita membutuhkan penyegaran kembali pancasila: untuk menangkis sikap absolut yang sewenang-wenang: sikap mereka yang mengklaim kesempurnaan karena merasa mewakili suara Tuhan. Dalam perspektif yang lebih luas, upaya memperbarui demokrasi Pancasila seperti diusulkan Denny J.A. bisa juga dikaitkan dengan falsafah dan karakteristik demokrasi modern itu sendiri. Sejarah demokrasi modern adalah sejarah kebebasan individu modern dan pembebasannya dari absolutisme kekuasaan sistem feodal dan aristoktat yang mencirikan Abad Pertengah-an. Sejak akhir abad ke 17, seiring dengan semakin kokohnya perdagangan dan Pencerahan di tanah Eropa, muncul kesadaran di kalangan masyarakat Barat akan pentingnya kebebasan dan persamaan individu. Mereka merasa letih dengan perang Katolik dan Protestan yang berlarut-larut, di samping juga sudah muak dengan tatanan sosial politik yang represif. 188 Mereka kemudian merancang suatu tatanan baru berdasarkan rasionalitas, yang melindungi hak dan kebebasan warga negara, mengakhiri perang agama dan mencegah bercokolnya kembali absolutisme. Untuk itu, kedaulatan mesti bersumber pada rakyat; pluralisme dan toleransi mesti dijaga; serta kekuasaan mesti dibatasi dan dikontrol. Demokrasi merupakan pengejawantahan tiga inti modernitas, yakni rasionalitas, kebebasan, dan persamaan. Demokrasi pada intinya adalah mekanisme pengaturan kehidupan publik yang mendasarkan diri pada kontrak sosial. Karena itu, ia bersandar pada aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, ia niscaya berwatak sekuler karena dasar legitimasinya bukanlah kitab suci agama tertentu, melainkan rasionalitas publik. Tujuannya agar kekuasaan bisa dikontrol dan dikoreksi, juga agar absolutisme yang menyulut perang agama tidak terulang lagi. Demokrasi merayakan pluralisme dan toleransi, karena pertukaran dan pertengkaran pikiran dalam pasar bebas ide-ide justru memungkinkan masyarakat untuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan berkembang maju. Suara minoritas mendapat hak hidup yang sama dengan pendapat mayoritas. Politik di sini bukan ajang pertarungan antara “kawan” dan “musuh” yang gampang menyulut kerelaan untuk mati demi keyakinan buta ter189 hadap agama tertentu. Politik dalam arti liberal adalah ajang bagi kompromi dan negosiasi. Dasar filsafatnya bertumpu pada kombinasi dari dua cara pandang terhadap manusia, katakan saja cara pandang yang optimistis dan pesimistis. Optimisme yang saya maksud adalah pandangan yang melihat manusia sebagai makhluk yang bisa mengatur diri mereka sendiri dan pada saat yang sama bisa berkembang ke arah kemungkinannya yang paling kaya. Optimisme inilah yang mendasari demokrasi karena esensi demokrasi adalah mengatur diri sendiri (self rule). Optimisme ini pula yang oleh John Stuart Mill, dalam traktatnya, On Liberty, dianggap sebagai alasan kenapa kebebasan individu dan pluralisme harus dipertahankan dari ancaman tirani mayoritas. Karena, hanya dengan kebebasan dan keragaman pandanganlah manusia bisa selalu memperbaiki kesalahannya. Namun, bersamaan dengan itu, demokrasi modern juga melantunkan semacam ketidakpercayaan (distrust) terhadap manusia, termasuk mereka yang berkuasa. Demokrasi memandang manusia dengan tatapan curiga. Manusia tidak digambarkan sebagai sosok yang ikhlas tanpa pamrih dan memikirkan orang lain, melainkan sosok yang bisa culas, ambisius, dan hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang saya sebut pandangan pesimistis terhadap manusia (atau realistis?). 190 Atas dasar kecurigaan semacam inilah tatanan republik melembagakan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan. Ungkapan James Madison, salah satu founding fathers Amerika, di dalam The Federalist Papers menarik untuk disimak. “If men were angels no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal control on government would be necessary.” Karena manusia bukan malaikat, maka kontrol internal dan eksternal terhadap kekuasaan menjadi niscaya. Kombinasi antara optimisme dan pesimisme inilah yang mendasari tatanan demokrasi modern. Yakni sistem yang menampung kepercayaan terhadap kebaikan manusia, melembagakan kecurigaan terhadap watak manusia, dan mengakui bahwa manusia bisa korup dan salah. Karena itu, rule of law sebagai sistem kontrol terhadap negara maupun masyarakat agar tak sewenang2 menjadi hal yang niscaya. Yang khas dari demokrasi modern: tak ada pretensi untuk menjadi sistem yang sempurna, absolut, dan berlaku abadi. Demokrasi justru bertolak dari ketidaksempurnaan, sehingga selalu ada peluang untuk koreksi dan perbaikan di kemudian hari. Inilah yang membedakannya dengan absolutisme dlam Islamisme, misalnya, yang mengklaim bersifat lengkap dan berlaku abadi karena bersandar pada Kedaulatan Tuhan (Hakimiyyah). 191 alhasil, upaya menyegarkan kembali demokrasi PanW casila adalah suatu penegasan bahwa Pancasila merupakan proses negosiasi terus menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah tunggal dan seragam, dan tak perlu ditunggalkan dan diseragamkan. Sebagaimana dinyatakn Bung Karno, Pancasila merupakan Weltanschauung bangsa Indonesia yang tak bisa dipahami sebagai sesuatu yang absolut, kekal dan kedap dari perkembangan zaman, karena Pancasila berada dalam “kawah candradimuka” kehidupan sosial politik yang selalu berkembang. Masyarakat selalu merupakan tatanan dalam proses yang mengakui ketaksempurnaan sistem apapun yang diciptakan manusia dan menampik ilusi tentang kesempurnaan yang menjadi ciri utama absolutisme. [] 192 Perlukah Kita Memperbarui Demokrasi Pancasila? Fahd Pahdepie Penulis, pegiat komunitas diskusi Ciputat School Beberapa waktu yang lalu, Denny JA melemparkan sebuah wacana mengenai pentingnya memperbarui gagasan demokrasi Pancasila. Denny JA menyebutnya sebagai “Demokrasi Pancasila yang Diperbarui” (Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui, 2017). Berpijak pada asumsi “terbelahnya” masyarakat Indonesia, terutama terpotret dalam fenomena Pilkada DKI Jakarta yang seolah memisahkan dua kubu pro-Ahok dan anti-Ahok, Denny JA mengemukakan kegelisahannya mengenai klaim Pancasila yang hanya dinisbatkan pada kubu pro-Ahok saja, sementara kubu yang tidak mendukung Ahok lantas dianggap sebagai kelompok yang anti-Pancasila (Baca tulisan Denny JA lainnya, Jangan Benturkan Keindonesiaan versus Keberagaman, 2017). 193 Hal tersebut dilandasi fenomena menguatnya politik identitas pasca-Pilkada DKI yang mencuatkan dua sentimen: Pertama, kelompok pro-Ahok yang mengklaim mereka pembela NKRI dan Pancasila. Kedua, berlawanan dengan kelompok anti-Ahok, digawangi kelompok-kelompok dengan basis massa muslim, adalah mereka yang dianggap terlalu banyak membawa agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara—bahkan ditengarai ingin membentuk NKRI Bersyariah. Pada gilirannya kedua kubu ini berseteru dan saling memperdebatkan platform apa yang paling tepat untuk dipakai dalam berbangsa dan bernegara? Melalui tulisannya, Denny JA berusaha membentangkan spektrum gagasan bernegara yang muncul pasca-Pilkada DKI Jakarta yang dipertarungkan dua kubu besar tadi. Ia menyebutnya sebagai empat platform yang bertarung dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Pertama, platform yang mengandaikan demokrasi liberal seperti di negara-negara maju di mana agama dipaksa absen sepenuhnya dalam urusan politik dan pemerintahan. Kedua, yang mencoba menyelinap dengan menguatkan kembali gagasan kembali pada UUD 1945. Ketiga, platform yang mengandaikan masuknya sistem dan tata nilai Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Mulai dari kelompok HTI yang ingin mendi194 rikan khilafah, hingga gagasan Bachtiar Natsir dan Habib Rizieq mengenai NKRI Bersyariah. Dan yang keempat, yang kemudian dipilih Denny JA, platform yang ingin mempertahankan pola dan gaya demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini, namun dengan beberapa pembaruan; Demokrasi Pancasila yang Diperbarui. Sepaham dengan Denny JA, platform keempat inilah yang ingin kita konsolidasikan sebagai the only game in town. Namun, bagaimana memahami ‘Demokrasi Pancasila yang Diperbarui’ ini? Manurut hemat saya, agaknya kosa pembaruan dalam ‘Demokrasi Pancasila yang Diperbarui’ harus merujuk pada kebutuhan untuk menentukan posisi ‘demokrasi’ dan ‘Pancasila’ dalam demokrasi Pancasila itu sendiri. Apakah demokrasi menjadi poros utamanya atau justru Pancasila menjadi kalibrator? Apakah keduanya harus selalu bersifat atas-bawah? Bagi Denny JA, demokrasi Pancasila harus menganut prinsip-prinsip demokrasi modern seperti diterapkan di berbagai negara maju, sementara Pancasila (termasuk aspek agama di dalamnya, sebagaimana terdapat dalam sila pertama) diperlakukan sebagai nilai yang mendampingi prinsip demokrasi tersebut, atau mewarnainya. Ia menulis, “Harus diterima bahwa prinsip 195 demokrasi hanya akan kuat jika ia dikawinkan dengan kultur lokal yang dominan di sebuah wilayah. Untuk kasus Indonesia, goresan agama dalam batin masyarakat sangat dalam. Demokrasi yang ingin mengakar harus mengakomodasi kondisi itu dalam sistem kelembagaannya.” Melalui pernyataan, saya menduga bahwa Denny JA meyakini bahwa prinsip demokrasi (dan HAM) harus selalu lebih tinggi daripada Pancasila ketika diperlakukan sebagai jangka ukur tertentu dalam menilai sesuatu. Jika terdapat persoalan baru yang dihadapi bangsa, misalnya, pertama-tama ia harus dipertanyakan: Apakah bertentangan dengan prinsip demokrasi? Jika tidak, ia barus bisa lolos ke pertanyaan kedua: Apakah ia sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah memosisikan demokrasi dan pancasila dengan komposisi semacam ini sudah tepat? Agaknya saya memiliki pendapat yang berbeda. Dalam hemat saya, mungkin menarik untuk menemukan konsensus baru dalam memahami perkawinan demokrasi dan Pancasila ini jika kita meminjam istilah ‘Jalan Ketiga’-nya Keynesianisme. Jika kita tempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang bersifat final dan demokrasi sebagai gagasan pembandingnya yang terus berkembang sesuai zaman, maka ada tiga jenis pendekatan untuk memperlakukan keduanya. 196 Pertama, mereka yang menganggap bahwa Pancasila sudah menjadi korpus tertutup dan segala hal di sekeliling Pancasila harus menyesuaikan kepadanya. Spektrum paling kanan kelompok pertama ini mungkin diwakili oleh mereka yang menginginkan kembali pada UUD 1945 dan berusaha memusnahkan golongan apapapun yang tidak sejalan dengan Pancasila. Menurut saya istilah ‘NKRI Harga Mati’ atau ‘Pancasila Harga Mati’, dalam konteks gagasan, agaknya sangat fundamentalistik. Meskipun jika kita bicara nasionalisme, tentu itu akan sangat penting. Kedua, mereka yang menganggap Pancasila harus menyesuaikan pada apa yang terjadi dalam dunia demokrasi yang terus berkembang. Demokrasi harus menjadi panglima dan Pancasila bertugas mendampinginya saja. Denny JA menurut saya berada pada posisi ini. Bukankah agak rancu membayangkan Pancasila yang melahirkan demokrasi Indonesia dipaksa harus sesuai dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat? Bagi mereka yang mengimani Pancasila secara kaffah dan tak bisa ditawar lagi, tentu ateisme tak boleh hidup di Indonesia karena tak sejalan dengan sila pertama. Tetapi, bukankah demokrasi modern seperti di Amerika Serikat membolehkannya? Bagaimana dengan LGBT? Khilafahisme? Ini problem dari jalan kedua. 197 Bagi saya, mungkin kita perlu jalan ketiga. Demokrasi dan Pancasila didudukkan sejajar dan saling berdialog satu sama lain. Tidak patrimonial. Pancasila dianggap sebagai korpus terbuka dan demokrasi modern tidak dianggap sebagai jangka ukur, tetapi sebagai referensi saja untuk menemukan keselarasan-keselarasan. Semua yang dibolehkan demokrasi moderen tidak mesti dibolehkan Pancasila, begitu juga sebaliknya. Tetapi dicari mana yang paling relevan dan sesuai dengan konteks yang berlaku. Dengan mendudukkan Pancasila dan demokrasi pada posisi yang sejajar, maka Demokrasi Pancasila akan terus menjadi platform yang berkembang. Ia akan menjadi gagasan yang selalu membelum, tidak final, dan terus menerus berusaha menemukan format yang sesuai seiring perkembangan zaman. Dengan demikian, barangkali memang tak perlu ada pembaruan apapun. Sebab dalam dirinya sendiri Demokrasi Pancasila adalah sebuah platform yang selalu memperbarui dirinya sendiri. [] 198 Saatnya Seluruh Komponen Bangsa Menggagas Rekonstruksi Nasional Hendrajit Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute. Meskipun belum terang benar ihwal gagasan seputar Demokrasi Pancasila yang diperbarui, saya menyambut baik prakarsa Bung Denny JA membahas wacana ini. Setidaknya Bung Denny telah memberi ruang bagi berbagai komponen strategis bangsa, untuk membincangkan kembali Pancasila, Dasar Falsafah bangsa yang sepertinya sejak era Pasca Reformasi terkesan mati suri. Ada dalam tiada. Dalam keikutsertaan saya secara pribadi dengan berbagai kalangan yang menghendaki kaji ulang Undang-Undanbg Dasar 1945 hasil empat kali amandemen dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah krusial bangsa kita saat ini bukan soal demokrasi. Melainkan 199 adanya gerakan secara sistematis untuk mematikan jatidiri dan karakter khas kita sebagai bangsa. Maka itu, untuk melengkapi beberapa pandangan dan tanggapan yang dipresentasikan beberapa kawan lainnya, izinkan saya untuk fokus mengulas sekilas Pancasila itu sendiri. Sebab setelah menyelami ihwal Pancasila berikut sejarah dan asal-usulnya sejak para founding fathers (bapak Pendiri Bangsa) berkumpul dan bermusyawarah untuk mufakat sejak Mei hingga 18 Agustus 1945 Dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tak berlebihan jika saya katakan bahwa lahirnya Pancasila sebagai falsafah negara atau dasar negara, sejatinya merupakan buah dari lokal jenius bangsa Indonesia. Yang lahir dari pertemuan pikiran sadar dan alam bawah sadar kearifan lokal bangsa Indonesia. Sehingga kalaupun Bung Denny JA berpandangan perlunya memperbarui Demokrasi Pancasila, yang tentunya saya belum punya bayangan sama-sekali model dan formatnya seperti apa, saya kira kita harus bertumpu pada pola pikir dan cara pandang yang tadi saya maksud. Pancasila adalah personfikasi dari kekuatan kepribadian bangsa. Maka sudah seharusnya jika dalam merancang dan menggagas sistem politik baru apakah Demokrasi Pancasila atau apapun namanya, harus bertumpu pada 200 kesadaran bahwa Pancasila adalah wujud dari kearifan lokal bangsa. Wujud dari sebuah keyakinan yang telah menjelma menjadi sebuah kenyataan yang membara. Menyadari hal itu, bukan suatu kebetulan ketika salah seorang founding fathers kita Bung Karno berpidato di rapat pleno BPUPKI pada 1 Juni 1945, justru menawarkan pokok bahasan tentang apa landasan dan fondasi bangsa yang mau didirikan, dan bukannya membahas apa bentuk negara seperti kerajaaqn atau republik. Sebab sebagai seorang arsitek, saya bisa bayangkan imajinasi yang ada di benak Bung Karno. Bahwa kalau dianalogikan sebagai rumah, maka Pancasila itu fondasi. Bukan pilar atau pancangan bangunan yang modelnya bisa disesuaikan dengan model bangunan rumah itu sendiri. Itu sebab saya tidak setuju dengan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar, yang mana Pancasila dan UUD 1945 diposisikan tidak dalam satu persenyawaan dan satu tarikan nafas. Padahal dalam Pembukaan UUD 1945 secara tersurat nyata jelas bahwa Pancasila itulah yang menjadi ruh dari UUD 1945. Yang menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bagaimana mungkin muncul logika empat pilar sehingga Pancasila dan UUD 1945 dalam posisi paralel? Dalam kekacauan pola pikir dan cara padang seperti 201 itu, pada perkembangannya Pancasila telah keluar dari jatidirina sebagai dasar falsafah negara dan fondasi. Praktis, negeri kita merupakan negara tanpa filsafat. Padahal, kalau menilik kesejarahannya, Pancasila sebagai fondasi atau dasar negara sejak periode 1945-1965 di era Sukarno, maupun yang kemudian berlanjut pada periode 1967-1998, maka Pancasila berhasil membuktikan dirinya bukan saja merupakan ketahanan budaya, melainkan juga mampu menjelma menjadi ketahanan nasional. Dalam tataran ini kontribusi para pemuka agama, utamanya dari kalangan tokoh pergerakan kemerdekaan yang punya otoritas keagamaan seperti Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Haji Agus Salim, nyatanya cukup besar dalam ikut mengisi kandungan dari yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Para founding fathers telah berhasil kut andil mempersenyawakan daya spiritual agama (ruh) ke dalam Pancasila. Bukan mempersenyawakan agama dan negara dalam kerangka ideologis sebagaimana sangkaan banyak kalangan dan para sejarawan sejak dulu hingga kini. 202 Maka itu ketika muncul pandangan mengenai urgensi untuk memperbahrui Demokrasi Pancasila atas dasar adanya pandangan bahwa telah terjadi ketidakserasian antara agama dan negara, saya kira kurang tepat sasaran. Suasana kebatinan bangsa sejauh yang saya serap saat ini, bukan pada perlunya Demokrasi Pancasila diperbarui. Melainkan adanya kegelisahn yang semakin menguat bahwa sejak reformasi 1998 hingga kini, para elit strategis bangsa justru semakin menjauhi dan menafikan kodrat Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang saya ibaratkan seperti fondasi rumah itu tadi. Celakanya, tren ini justru berlangsung dan semakin intensif di bawah payung produk-produk hukum dan perundang-undangan sebagai derivasi atau turunan langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil empat kali amandemen. Perkembangan inilah yang terus-terang sungguh merisaukan. Sebab sontak, saya teringat penulis Swedia, Jury Lina. Dalam bukunya Architects of Deception the Concealed History of Freemasonry berpandangan bahwa ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri: · Kaburkan sejarahnya. 203 · Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. · Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Barang tentu yang dimaksud Jury Lina adalah ketika negara asing berupaya menaklukkan sebuah bangsa melalui cara dan sarana-sarana non-militer, atau yang kerap saya istilahkan sebagai Perang Nir-Militer. Dengan makna lain, penaklukkan suatu negara melalui serangan-serangan non-militer ke sektor ideologi, politik-ekonomi, dan sosial-budaya. Ironisnya, seperti diutarakan oleh Profesor. Dr. Kaelan, M.S, dalam bukunya bertajuk Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada itu menulis bahwa justru Bangsa Indonesia sendirilah yang saat ini merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang telah mengubur jatidirinya dalam-dalam. Meskipun provokatif, namun pandangan Prof Kaelan tersebut rasa-rasanya beralasan untuk menggugah kembali kesadaran dan keterlenaan kita saat ini akibat eforia reformasi sejak 1998. 204 Betapa perkembangan saat ini bukan karena Demokrasi Pancasila mengalami stagnasi. Justru karena sebagai fondasi negara Pancasila telah diabaikan dibuat mati suri. Dibilang mati belum, namun dibilang hidup dia kehilangan daya hidup dan vitalitasnya. Maka yang mengkhwatirkan kemudian, bangsa dan negara kita saat ini justru mengalami de-spiriualisasi agama. Dan demoralisasi spiritual. Itulah hakekat sesungguhnya dalam memaknai dan membaca serangkaian peristiwa dan rentetan episode menyusul merebaknya kasus Surah al Maidah ayat 51 yang bermuara pada Aksi bela Islam 411 212. Kalau mau membuat Demokrasi Pancasila sesuai ajakan bung Denny JA, saya kira ini merupakan sebuah momentum yang amat bagus bagi semua komponen strategis bangsa untuk kembali berpaling pada sejarah asal usul Pancasila. Sebagai dasar untuk secara bersamasama melakukan Rekonstruksi Nasional. Kenapa? Banyak kalangan boleh saja tahu sejarah muasal lahirnya Pancasila. Namun hanya segelintir orang yang menyadari betapa lahirnya Pancasila sejatinya merupakan pertemuan antara pikiran sadar dan bawah sadar masyarakat di bumi nyusanbtara, yang dilahirkan melalui wasilah berbagai komponen strategis masyarakat di bumi nusantara yang dipercaya kala itu sebagai para 205 utusan di Sidang BPUPKI dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Sehingga tal berlebihan jika Pancasila kita pandang sebagai maha karya yang lahir dari local genius atau kearifan lokal bangsa. Dengan makna lain, Pancasila merupakan hasil daya cipta para bapak pendiri bangsa, utamanya Bung Karno. yang kelak menjadi presiden pertama RI. Maka selain cukup beralasan, dalam perkembangan kesejarahannya, sejarah telah membuktikan ketika fondasi rumah tidak beres maka krisis dan kekacauan memancar di bangunan rumah dan interior design dalam rumah. Itulah akar masalah di permukaan yang berlangsung saat ini yang titik puncaknya menjelma dalam Aksi Bela Islam 411 dan 212. Menyadari hal itu solusinya bukan pembaruan tapi rekonstruksi nasional. Mengembalikan Pancasila pada kodrat dan jatidirinya sebagai dasar negara atau fondasi, dan bukan sebagai salah satu dari empat pilar. Lantas, bagaimana solusi yang kiranya bisa menjembantani upaya ke arah rekonstruksi nasional seperti yang saya maksud? Usul sederhana saya, hidupkan kembali filsafat Pancasila. Tanpa dijembatani oleh hidupnya filsafat Pancasila, 206 maka kalau dianalogikan dalam Islam, Pancasila hanya berhenti sebagai syariat. Tapi tidak pernah beranjak jadi tarekat, hakekat dan makrifat. Kita sebagai bangsa akan gagal menyerap hikmah dan ibrah dari Pancasila. Maka kita perlu menggagas gerakan yang mana berbagai komponen strategis bangsa tergugah kesadarannya untuk menghidupkan kembali Filsafat Pancasila. Apalagi negara kita ini, sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit, filsafat kita pun pada gilirannya ikut punah bersamanya. Padahal kalau kita pelajari sejarah pergolakan politik Jepang, sekadar sebagai rujukan perbandingan, yang kemudian mengubah era Shogun Tokugawa ke era Restorasi Meiji pada 1867, ternyata bukan dengan serta merta gara-gara tekanan dan paksaan dari Komodor Perry. Melainkan karena para elit Jepang sudah siap lahir-batin. Sudah punya kontra skema untuk menghadapi skema Komodor Perry yang semangatnya adalah hendak menjajah atau mengkolonisasi Jepang. Tekanan eksternal Komodor Perry justru dijadikan stimulator bagi kalangan progresif di internal para elit nasional Jepang dan memanfaatkan momentum untuk melakukan gerakan progresif revolusioner di internal Jepang itu sendiri, seraya menyingkirkan kaum konservatif dan reaksioner yang selama ini bersembunyi dan mengatas-namakan Shogun Tokugawa. 207 Sebab sebelum adanya ancaman dari Komodor Perry, di kalangan intelektual Jepang sudah terjadi pergolakan pemikiran dan filsafat. Sehingga ketika Jepang akhirnya tunduk pada desakan Komodor Perry untuk membuka daerah-derah pelabuhannya kepada Barat, Jepang justru memanfaatkan terjalinnya kontak dengan Barat, untuk mempelajari kekuatan rahasia keberhasilan negara negara Eropa dan Amerika. Sebab para elit progresif Jepang sudah punya skema, strategi dan sistem untuk menangkal pengaruh asing. Sehingga Jepang sebagai kekuatan kolektif bangsa sudah siap lahir-batin untuk berubah dan berhadapan dengan pengaruh budaya dan peradaban dari negeri dan bangsa asing, yang dalam hal ini berasal dari budaya dan peradaban Barat. Sehingga akhirnya Jepang bukan saja mampu menyerap keunggulan Barat, namun saat yang sama malah mengilhami Jepang untuk menghidupkan jatidiri dan budaya bangsanya untuk pergerakan maju ke depan yang bersifat progresif. Bukan mundur ke belakang yang bersifat retrogresif. Dengan begitu, Jepang berhasil jadi negara maju dan modern, seraya tetap jadi Jepang dan tidak jadi kebarat-baratan. 208 Suasana kebatinan seperti di Jepang inilah yang tidak ada di kalangan para elit strategis bangsa kita menjelang kejatuhan Suharto pada Mei 1998. Alhasil, berbede dengan succes story Restorasi Meiji 1867, lengsernya Suharto justru jadi pintu masuk liberalisasi politik dan ekonomi yang sejatinya atas tuntunan dari skema kepentingan beberapa korporasi multinasional dari Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan bahkan saat ini Cina. Dengan kata lain, Indonesia Pasca Suharto, ditandai oleh ketidaksiapan para elit strategis untuk menyusun kontra skema terhadap kepentingan kapitalisme global sehingga kita tidak punya skema, strategi dan sistem. Dalam konteks inilah, menarik jika bung Denny JA menggulirkan sebuah wacana menarik tentang Pembaruan Demokrasi Pancasila. Jangan-jangan, urgensi pembaruan Demokrasi Pancasila disebabkan karena reformasi sejak 1998 berjalan tanpa tuntunan skema, stretegi dan sistem. Kembali ke perbandingannya dengan Jepang. Mengapa Jepang bisa begitu sedangkan kita ketika jalin kontak dengan Barat malah jadi orang yang kehilangan jatidiri? Jawabnya sederhana, karena kita tidak punya filsafat, begitu masuk pengaruh luar, malah memicu pikiran dan jiwa kita semakin kacau dan tidak tertata. 209 Maka itu, Filsafat Pancasila bisa jadi jembatan menuju rekonstruksi nasional atas dasar rujukan dan landasan yang tepat. Sebab melalui Filsafat Pancasila, kita akan disadarkan kembali betapa Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dan telah melekat pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa (Founding Fathers) diolah yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Berdasarkan itu, maka pada hakekatnya bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara (menurut istilah Prof Notonegoro) yang rinciannya adalah sebagai berikut: Pertama, Bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan secara yuridis menjadi dasar filsafat negara, sudah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas Kebudayaan). Kedua, Demikian juga unsure-unsur Pancasila telah terdapat pada Bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai religius) (Pancasila Asas Religius). 210 Ketiga, Unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam Sidang-Sidang BPUK, Panitia Sembilan. Setelah bangsa Indonesia merdeka rumusan Pancasila calon dasar negara tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia dan terwujudlah Pancasila sebagai asas kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan). (Kaelan: hal 42, 2015). Dengan begitu jelaslah sudah, bahwa agenda strategis yang mendesak adalah Rekonstruksi Nasional atas dasar Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau fondasi bangunan rumah, baru kemudian kita musyawarahkan bangunan dan interior desgin baru macam apa yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Selain daripada itu, sudah saatnya untuk menggagas kembali gerakan sadar geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional. Geopolitik yang secara sederhananya bersendikan pemahaman tentang geoekonomi, geostrategic (lokasi dan letak geografis negeri kita dengan negara lain) dan geokultural, pada perkembangannya sangat membantu kita untuk kembali kenal diri, tahu diri, dan tahu harga diri. Terkait gagasan tersebut, maka gagasan Bung Denny JA untuk menggulirkan wacana memperbarui Demokrasi Pancasila, kiranya patut kita beri apresiasi yang setinggi211 tingginya. Setidaknya, Pancasila akan kembali jadi pokok bahasan publik setelah sekian lama kita abaikan, sehingga seolah-olah tidak ada. [] 212 Demokrasi Pancasila yang Diperbarui; Pancasila bukan Panacea Rocky Gerung Dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI) I Setiap kali kita menghadapi krisis politik, acuan penyelesaiannya adalah Pancasila. Seolah-olah ia adalah Panacea, diminta “turun tangan” mengobati segala penyakit. Tetapi realisasi dari “turun tangan” itu pernah justru sangat menyakitkan: Orde Baru sangat ringan tangan menghukum oposisi dengan Pancasila. Memang, dalam sejarah politik kita, Pancasila lebih dipraktekkan sebagai ideologi penutup kritik, ketimbang sebagai pembuka dialog. Bahkan setelah reformasi, ideologi ini terasa atavistik, karena klaim Sukarnoistik-nya tampil dominan. 213 Kini, di hari-hari ini, ia juga terasa eksklusif karena dijadikan batas untuk mendefinisikan pendukung rezim dan pengeritiknya. Bahkan diperluas menjadi penentu: siapa yang pluralis, siapa yang fundamentalis. Pancasila jadi alat ukur politik. Alat ukur yang kaku bagi kebinekaan. Akibatnya kelenturan kulturalnya hilang. Ia mengalami reifikasi. Lalu, ada upaya melenturkan kembali hari-hari ini. II Terbuka atau terselubung, ada psikologi lama yang kini diedarkan lagi di masyarakat: pengeritik rezim adalah anti pluralisme, juncto Pancasila. Psikologi ini tumbuh dari arogansi yang memandang kritik kepada rezim sebagai ancaman pada kebinekaan. Suatu psikologi yang tadinya menyudutkan, lalu kini membelah masyarakat, karena kalkulasi politik yang terbalik di Ibukota. Intelektualisasi bahkan diperlihatkan untuk menebalkan batas antara pendukung dan pengeritik rezim. Dibungkus dengan slogan-slogan teoretis, Pancasila dijadikan alat “fit and proper test” kebinekaan. Suatu metode naif dalam berpolitik. 214 Bila pada zaman Orba teknik ini dipraktekkan dengan bantuan kaum intelektual yang dikendalikan negara, di era ini teknik yang sama justeru dikerjakan oleh elemen-elemen masyarakat sipil (yang juga terpelajar) yang panik terhadap gejala delegitimasi rezim. Semacam voluntarisme kekanak-kanakan memang sedang merebak di kalangan ini karena gugup dan gagap melihat kapasitas rezim yang ternyata tak cukup “fit and proper”. Reaksi protektif itu menghasilkan sikap eksklusivisme. Sikap inilah yang justeru makin menutup “percakapan kewarganegaraan” untuk mencari “cara hidup bersama” melalui Pancasila. III Memang hanya “cara hidup bersama” itu yang maksimal dapat diupayakan melalui Pancasila. Bukan “tujuan hidup bersama”. Jadi, obsesi untuk merumuskan “tujuan hidup bersama” adalah fatalistik karena Pancasila itu sendiri bukan suatu ideologi yang koheren. Hermeneutiknya menyebar kemana-mana. Bahkan bisa paradoksal. Misalnya, preskripsi “Ketuhanan” dalam sila ke-1 dapat dibatalkan oleh prasyarat “Kerakyatan” pada sila ke-4. Secara filosofis “Ketuhanan” dan “Kerakyatan” adalah 215 dua imperatif yang bertolak belakang. Sangat unik tentu bila sintesanya adalah: “Kerakyatan yang berketuhanan” atau “Ketuhanan yang berkerakyatan”. Tidak saja unik, tapi juga aneh. Apakah kita siap masuk dalam suatu debat konseptual yang tajam seperti itu demi memperoleh kedalaman diskursus tentang Pancasila, atau kita hindari itu demi dalil “harga mati”? Sebaliknya, bila Pancasila dibebaskan terbuka mengalami penafsiran, maka semua ideologi politik besar dapat memilih bermukim di salah satu silanya. Hizbut Tahrir misalnya, bila mau, dapat mengajukan argumen bahwa sebagai aspirasi politik ia sejalan dengan sila ke-1 dan sila ke-5. Islam mencakup aspek teologis sekaligus sosiologis. Demikian halnya penganut Marxisme. Ia berhak mendalilkan aspirasi sosialnya sebagai sejalan dengan jiwa sila ke-2 dan ke-5, misalnya. Tetapi bagaimana mungkin itu dimungkinkan, bila yang mungkin hanyalah versi “bukan ini, bukan itu”, versi rezim yang kini diikuti oleh para intelektualnya, yang sebetulnya bertujuan “politics of exclusion”. Bukan negara agama tapi bukan negara sekuler, bebas berbeda tapi bukan liberal. Titik! 216 IV Hambatan untuk memulai suatu pemaknaan baru dan pengayaan Pancasila adalah mental atavistik yang kini beredar justru di kalangan terpelajar. Jadi, upaya membuka dialog politik dengan platform Pancasila, sudah dibatasi sejak awal oleh kondisi eksklusivisme tadi. Padahal, suatu dialog otentik membutuhkan kesetaraan posisi warganegara. Tak ada kejujuran mencapai konsensus bila satu pihak menyandang stigma fundamentalis, dan yang lain menikmati arogansi pluralis. Saya simpulkan begini: Pancasila bukan ideologi yang koheren. Ia mengandung dalam dirinya kondisi hermeneutik. Justru bagus untuk memulai percakaan demokratis. Tetapi mental atavistik justeru terbawa dalam cara menafsirkannya hari-hari ini. Justru buruk untuk mengawali percakapan demokratis itu. Tetapi, hal yang lebih urgen sebetulnya bukan soal kapasitas Pancasila sebagai ideologi, melainkan praktek material kehidupan berbangsa. Ideologi tak pernah mampu menghasilkan keadilan. Kebijakan negaralah yang harus menyediakannya. Dan kebijakan itu adalah hasil dari kapasitas konseptual kepala negara. [] 217 218 Pembaruan Demokrasi Pancasila dan Ancaman “NKRI Bersyariah” Akhmad Sahal Kandidat PhD, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika Dalam tulisannya “Perlunya Menegaskan Komiten pada Demokrasi Yang Diperbarui,” Denny J.A. mengajukan platform pembaruan demokrasi Pancasila sebagai alternatif yang dipilihnya ketimbang platform-platform politik lain yang menyeruak belakangan ini, termasuk platform Negara Islam atau NKRI Bersyariah. Di mata Denny J.A., platform Negara Islam yang menghendaki agar prinsip hukum Islam diterapkan dalam ruang publik tidak cocok jika dipaksakan di Indonesia. Bukan hanya karena mayoritas muslim Indonesia yang moderat lebih memilih mendukung Pancasila dan menolak ide Negara Islam. Tapi juga karena NKRI berdiri di atas faham kebangsaan modern, di mana basis keang- 219 gotaannya ditentukan bukan oleh agama seperti pada masa pra modern, melainkan nasionalitas. Dan prinsip kesetaraan warga negara yang terangkum dalam konsep citizenship adalah pilar utama kebangsaan kita. Pembaruan demokrasi Pancasila seperti diusulkan Denny J.A. memang merupakan suatu keniscayaan saat ini apabila kita ingin membela Pancasila dan NKRI di tengah maraknya radikalisme Islam yang ingin menegakkan Khilafah dan membuang NKRI sama sekali, atau masih tetap memakai NKRI tapi dengan diganti karakter kebinekannnya menjadi NKRI Bersyariah. Wacana tentang NKRI Bersyariah gencar dikampanyekan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan ormas radikal lain. Dalam berbagai kesempatan, imam besar FPI Rizieq Shihab menyatakan tekadnya untuk mewujudkan penerapan syariah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi FPI, NKRI Bersyariah merupakan manifestasi pelaksanaan sila pertama Pancasila, yang menurut mereka merupakan sila tentang tauhid. Dalam salah satu ceramahnya, Rizieq Shihab menyatakan: “Ketuhanan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah laa ilaaha illallah (tiada Tuhan selain Allah). Nah jika asas-nya sudah tauhid, maka segala bentuk perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa secara otomatis harus dibatalkan.” 220 Dengan mengibarkan panji “NKRI bersyariah,” FPI selintas tampak mengakui keabsahan NKRI, berbeda dengan HTI yang memvonis NKRI sebagai thaghut dan kafir. Namun pengakuan tersebut hanyalah pintu masuk bagi FPI cs untuk menggolkan agenda penerapan syariah sebagai hukum nasional. Bisa dikatakan, Negara bersyariah adalah Piagam Jakarta dalam versinya yang baru. Dengan demikian, perbedaan antara FPI dan HTI sejatinya hanya pada level taktik/ metode. Tujuan mereka sebenarnya sama, yakni penegakan Negara Syariah, entah dengan nama Khilafah (yang melampaui sekat-sekat nation-state), atau negara dalam kerangka nation-state. Pancasila: Bertuhan Tuhannya Sendiri Problem utama platform NKRI Bersyariah bukanlah pada pemahaman para pendukungnya bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan tauhid, melainkan pada pemutlakan pemahaman tersebut sebagai satu-satunya makna sila pertama Pancasila. Lebih-lebih lagi kalau dari situ kemudian disimpulkan bahwa konsekuensi dari sila pertama adalah bahwa NKRI mesti berdasarkan syariah, yang dianggap sebagai buah dari keyakinan tauhid itu sendiri. Muslim yang mengakui Pancasila juga banyak yang memaknai sila pertama sebagai sejalan dengan prinsip tauhid. Masalah baru mun221 cul ketika pemahaman itu dimutlakkan sebagai ukuran tunggal dalam memaknai sila pertama Pancasila. Dan itulah sikap para pendukung NKRI Bersyariah. Pemonopolian tafsir sila pertama semacam itu jelas bertentangan secara diametral dengan ide dasar Pancasila itu sendiri, yang merupakan common platform bagi bangsa Indonesia yang berbineka. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dengan cara itulah kebhinnekaan terjaga. Ikatan politik yang mendasarinya bukanlah sentimen primordial, melainkan kesatuan sebagai bangsa. Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan. Para pendiri bangsa kita menyadari, tuntutan menerapkan Piagam Jakarta dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik. Watak Pancasila sebagai common platform kebhinnekaan tercermin, misalnya, pada rumusan Sukarno dalam pidatonya tentang Pancasila yang monumental pada 1 Juni 1945: “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.” 222 Dengan menyatakan “bertuhan Tuhannya sendiri,” Sukarno tak hanya mengakui karakter keberagamaan bangsa Indonesia yang beragam. Sang proklamator juga menegaskan kesetaraan hak penganut agama. Seorang penganut agama, sembari meyakini kebenaran agamanya, dituntut juga untuk mengakui hak para penganut agama lain untuk meyakini kebenaran agama mereka. Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak berhak mendesakkan sudut pandang agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain. Tak ada sudut pandang agama apa pun yang boleh mendominasi sudut pandang agama lain. Tak ada satu kelompok agama mana pun yang berhak menilai agama lain dari sudut pandang sendiri. Bung Karno lantas mewanti-wanti agar bangsa Indonesia “berTuhan secara kebudayaan” dengan saling menghormati antar pemeluk agama, dan tak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “egoisme agama.” Egoisme agama semacam ini niscaya bertentangan dengan visi Bung Karno tentang Negara Indonesia sebagai “semua milik semua,” bukan hanya menjadi milik satu golongan tertentu, mayoritas atau minoritas. Kata Bung Karno: “Kita hendak mendirikan suatu negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan 223 Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua.” Ketuhanan yang maha Esa mesti dipahami secara kebudayaan. Kata Bung Karno: “Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.” Dari sini menjadi jelas, pemutlakan pemahaman tentang sila pertama seperti yang dilakukan FPI cs dengan NKRI Bersyariah pada dasarnya adalah “egoisme-agama” yang justru membatalkan karakter kebhinnekaan yang note bene adalah raison d’etre NKRI. Negara Pancasila Sudah Syar’i Probem serius lain: jargon “NKRI Bersyariah” mengasumsikan bahwa NKRI yang mendasarkan diri pada Pancasila tak sejalan dengan Syariah, bahkan mungkin dianggap bertentangan dengan Syariah. Karena itu mereka mendesakkan platform NKRI Bersyariah. 224 Pandangan semacam ini jelas menyelisihi sikap dan pandangan mayoritas musli Indonesia yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah. Bagi dua ormas islam terbesar Indonesia tersebut, Negara Pancasila untuk konteks Indonesia justru sesuai dengan prinsip Syariah, justru syar’i. Dengan keputusannya itu, NU dan Muhammadiyah selintas tampak tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Tapi itu hanya lahiriahnya saja. Dari segi substansi, mereka justru menerapkan tujuan utama syariah, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang notabene merupakan tujuan syariah. NU dan Muhammadiyah menyadari, tuntutan menegakkan dawlah Islamiyah atau khilafah dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik yang justru bertentangan dengan prinsip maslahat. Dalam Sidang Tanwir 2012 di Bandung, Muhammadiyah menegaskan posisinya bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik untuk bangsa yang majemuk untuk mencapai cita-cita nasional. NKRI bagi Muhammadiyah merupakan negara perjanjian atau kesepakatan (Darul ‘Ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (Darus Syahadah), dan negara yang aman dan damai (Darussalam). 225 Negara Perjanjian adalah negara yang didirikan atas tegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian dan kesepakatan di antara warganya. Selain sebagai Negara Perjanjian, NKRI juga merupakan Negara Kesaksian atau Darus Syahadah. Syahadah yang merupakan kata dalam bahasa Arab mengandung arti kesaksian, tapi juga bisa berarti pembuktian. Dengan begitu, Darus Syahadah adalah negara di mana warga negara atau kelompok warga negara berlomba-lomba memberikan kesaksian dan pembuktian kepada warga atau kelompok warga negara lain tentang usaha dan kontribusi mereka dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam istilah Al-Qur’an yang sangat popular di Muhammadiyah, fastabiqul khairat (berlomba-lombalah dalam kebaikan). Dengan begitu, Negara Kesaksian secara normatif menuntut warganya untuk memberikan pengabdian mereka bagi negara, sebagai manifestasi komitmen mereka terhadap cita-cita bersama. Pengabdian warga Negara ini termanifestassikan, misalnya, dalam sikap taat hukum dan taat konstitusi. Begitu juga dengan NU. Berdasarkan pertimbangan keagamaan yang diyakini oleh para ulama NU, NU mengambil sikap secara tegas menerima Pancasila, dan sikap itu diambil berdasar pertimbangan fikih (hukum Islam). Dengan demikian, menurut NU, tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara Islam dan Pancasila sebagai bentuk final. NU tidak lagi mempersoalkan 226 antara negara Pancasila dengan negara Islam. Gus Dur dalam artikelnya “NU dan Negara Islam,” menegaskan penolakannya terhadap ide negara Islam karena hal itu memberangus heterogenitas Indonesia. Ia juga memaparkan bahwa sikap NU yang menerima keabsahan NKRI bersandar pada keputusan Muktamar NU tahun1935 di Banjarmasin bahwa kawasan Hindia Belanda wajib dipertahankan secara agama. Alasannya: kaum muslim bisa bebas menjalankan ajaran Islam. Selain itu, di kawasan itu dahulu sudah ada Kerajaan Islam. Atas dasar itulah NU menyatakan komitmennya kepada republik kita, yang berdasarkan Pancasila dan bukan Islam. Ini ditunjukkan, misalnya, dengan Resolusi Jihad mempertahankan republik yang dikeluarkan PBNU pada 22 Oktober 1945. Walhasil, NKRI tidak dirancang untuk mengistimewakan satu keompok agama di atas kelompok agama lain. NKRI tak diniatkan untuk memperlakukan kaum minoritas sebagai the others. Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama-sama menjadi pemilik yang sah republik kita, republik yang dalam bahasa Sukarno disebut sebagai “negara semua untuk semua,” di mana egoisme agama melalui platform NKRI Bersyariah tak mendapat tempat. Menegakkan NKRI Bersyariah sama halnya dengan menabuh lonceng kematian bagi NKRI. [] 227 228 Demokrasi Pancasila yang Diperbarui; Indonesia 4.0 No 4 Sedunia Dalam Kualitas Pada Seabad 2045 Christianto Wibisono Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia Pollster terkemuka Denny JA mengusulkan pembaruan Demokrasi Pancasila untuk rekonsiliasi pasca kemelut konflik SARA pilgub DKI yang bekepanjangan dengan pola intrik makar ala Ken Arok 1182-1227 abad 13 yang memakan korban Ken Ahok modern abad 21. Denny mengandalkan pembaruan Pancasila untuk bisa mengatasi konflik antar agama myoritas dan agama minoritas dengan sistim demokrasi “kuantitatif ” dalam supremasi hukum yang menjamin HAK minoritas. DR Rocky Gerung mengingatkan agar jangan terlalu mensakralkan Pancasila menjadi sangat atavistic dan 229 menganggap sebagai panacea, obat generic untuk segala simtom penyakit tanpa memahami akar masalah dan sumber penyakit yang diderita oleh nation state Indonesia. Hemat saya, tidak ada ideology yang khas local, domestic, kabalistic semuanya pasti ada essensi dan substansi universalnya. Benci, cemburu, dengki dan iri adalah suatu gejala manusia universal yang ada pada manusia segala bangsa, suku, agama, ras, keturunan ditambah factor perbedaan kelas yang baru di teorikan secara massif dalam Marxisme oleh Karl Marx. Tapi benih nya sudah dikenal sejak zaman baheula dimana saja, termasuk ideology menggantungkan diri pada ratu adil sebagai penguasa baru menggantikan pengusaha lama. Biasanya yang baru itu kemudian juga akan menjadi tamak, rakus, korup dan bangkrutlah rezim itu justru karena KKN dari dalam tubuhnya sendiri, bukan oleh invasi atau agresi dari luar. Yang barangkali hanya berupa pemicu atau paku terakhir di peti mati rezim lama yang bangkrut total. Maka terjadilah suksesi antar dinasti pada pelbagai imperium baik pada tingkat sub regional kawasan maupun imperium raksasa seperti dinasti Tiongkok, Mongol, Romawi, Persia, Turki, Mogul hingga akhir abad pertengahan; abad XVI. 230 Ketika Eropa Barat mengalami skisma besar setengah millennium, 5 abad atau 500 tahun lalu dengan munculnyaMartin Luther di tahun 1517 mematerikan doktrinnya merevisi altar fundamental gereja Katolik Roma. Menarik untuk dicatat bahwa dualism Tuhan vs Setan muncul sejak Torat Yahudi ditulis Musa dan mengilhami Zarathustra memakai dualism Ahura Mazda The Good dan Angra Manyu The Devil. Spirit konflik antara Good dan Evil dalam “dongeng” Kabil membunuh adiknya Habil karena cemburu kinerja Habil lebih diperkenan oleh Tuhan, menjadi sumber “hatred ideology” para pelaku kekerasan terorisme politik bernuansa agama abad 21. Dalam konteks konflik ideology dan filsafati itulah kita melihat itikad unifikasi Bung Karno untuk menyatupadukan bangsa Indonesia dari pelbagai suku dan etnis menempa solidaritas suatu nation state modern yang melampaui etnis, suku, ras dan agama. Ini memang suatu lompatan luarbiasa karena nation state modern di Eropa juga baru dikenal setelah Treaty of Wesphalia 15 Mei 1648 setelah Perang Agama berkepanjangan di Eropa pasca Reformasi Kristen Protestan Martin Luther. Perhatikan juga bahwa Perang Salib antara penganut Kristen dan Islam sudah ber231 langsung hampir 200 tahun 1095-1291 memperebutkan Eropa Selatan dan wilayah Israel Palestina. Presiden Richard Nixon menulis buku Leaders mengingatkan bahwa tradisi demokrasi dengan suksesi tertib memang diawali dari Barat yaitu Magna Charta 15 Juni 1215 yang membatasi kekuasaan absolut raja oleh elite aristokrasi. Sementara di Timur Genghis Khan 11621227 menegakkan imperium otoriterMongolia dan Ken Arok mendirikan dinasti Singasari. Kublai Khan cucu Genghis Khan akan mengirim ekspedisi untuk menghukum raja Singasari, Kertanegara yang berani memotong hidung utusan nya 1293. Karena inteligen Kublai tidak cerdas mereka tidak sadar bahwa, Kertanegara sudah lengser oleh raja Kediri, Jayakatwang. Ekspedisi Kublai diarahkan oleh Raden Wijaya menghukum Jayakatwang dan meruntuhkan Kediri. Ekspedisi Kublai pulang ke Tiongkok sedang Raden Wijaya mendirikan imperium Majapahit yang bertahan 134 tahun (1293-1527). Pada periode Majapahit itulah Laksamana ZhengHe (1371-1433) memimpin ekspedisi pada dinasti Ming (1368-1644) dan sebagian Wali Sanga pendakwah agama Islam memimpin pengIslaman Jawa berbuntut runtuhnya Majapahir dan lahirnya kerajaan local Islam Nusantara. 232 Semua kesultanan local itu dalam visi Bung Karno tidak mampu membangun imperium ketiga mengikuti jejak Sriwijaya dan Majapahit.Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 jelas memastikan bahwa Indonesia merdeka adalah nation state modern, bukan teokrasi kafilah dan juga tidak mutlak steril sekuler melainkan menghormati agama dan pemeluknya sebagai perwujudan hak asasi manusia yang paling fundamental yang tidak dicampuri negara. Inilah trobosan Indonesia sebagai negara non teokrasi non kalifah meskipun mayoritas penduduknya Muslim. Sementara pada tingkat global dan universal juga terjadi pertarungan antara kekuatan yang mengacu pada “Pancasila” dan kekuatan kalifah syariah seperti yang terjadi di Turki dan Mesir. Ataturk adalah penegak ideology non kafilah diikuti oleh Nasser di Mesir. Sementara itu riwayat skisma internal Syiah dan Sunni, antara Iran dan Saudi Arabia masih terus berlangsung hingga era Donald Trump yang 21 Mei 2017 ini akan mengadakan KTT dengan Arab Saudi, GGC dan sekaligus ber KTT dengan Sri Paus dan Israel untuk mengupayakan perdamaian tuntas Israel Palestina. Dalam masalah konflik Islam religi vs Islam politik yang menyangkut factor sangat eksistensial bagi negara ini, maka jelas Pancasila memang harus menjadi ideology 233 yang kuat untuk melawan tarikan “syariahime dan kilafahsime”. Bila tidak, maka Indonesia tidak akan survive bila dipaksa memilih antara Pancasila dan “Piagam Jakarta”. Pancasila itu sendiri memang tidak untuk di sacral kan. Justru harus diterapkan dalam kehidupan sehari hari, dengan pelbagai political behavior yang mencerminkan nilai luhur yang terkandung dalam istilah yang sebetulnya tidak muluk muluk tapi sangat esensial bagi masyarakat di tingkat grass roots. Sayang memang bila Pancasila itu dijadikan semacam “keris Empu Gandring” yang hanya dipakai untuk menikam lawan politik tapi bukan dijadikan “tolok ukur” atau benchmasking pelaksanaan ideology negara secara konkret membumi. Sama dengan San Min Chu I di Tiongkok yang gagal karena rezim Kuo Min Tang yang mencetuskan gagasan itu di bawah Sun Yat Sen, dibajak oleh rezim warlord Chiang KaiShek dan korup membangkrutkan Tiongkok hingga tergusur oleh rezim Kung Chan Tang Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Zedong. Tapi setelah 30 tahun menerapkan Marxisme, Deng Xiao Ping kapok dengan kegagalan rezim leninis Marxis untuk mendeliver sembako di pasar, maka Deng tegas menyatakan bahwa Tiongkok akan kembali ke pasar, 234 sebab pasar lebih tua dari Marxisme. Sedang Marxisme yang dibajak oleh oligarki partai yang korup gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi Tiongkok. Kita di Indonesia tidak bisa lepas dari konflik ideology dan konflik political behavior elite politik yang bersumber pada dikotomi “good vs evil” yang bersifat universal, generic dan tidak bisa di stereotyping sebagai politik identitas, suku, ras, agama, kelas, nation state. Orang, dinasti, nation state bisa berubah behaviournya dari baik menjadi buruk, dari good menjadi evil. Akhirnya golden rule Jayabaya yang akan berlaku, bahwa at the end of the day, di ujungnya yang salah akan terhukum, yang benar akan terselamatkan meskipun mengalami penzoliman sementara. Golden rule hukum karma sangat valid dan kita harus percaya bahwa dalam sejarah ummat manusia dari pelbagai imperium Tuhan itu tidak pilih kasih memilih suatu bangsa atau ras dan agama tertentu untuk memperolah berkat berlimpah secara tidak “adil”. Sampai abad ke XVI semua bangsa pernah diberi “kenikmatan” memiliki penguasa local yang “direstui” oleh kekuatan supranatural Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejarah mengenal imperium Accadia, Assiria, Babilonia, 235 Cartago, Mesir, Persia, Romawi, Tiongkok, Yunani bahkan Sriwijaya dan Majapahit dengan bukti kinerja candi Borobudur didirikan 830 setara piramida Mesir dan Tembok Besari Tiongkok. Sejak abad XVI muncul imperium global yang diawali oleh penjarahan harta karun Indian Amerika di Amerika Selatan oleh Spanyol. Prof Paul Kennedy menyebut ini era Pax Hispanica, Spanyol menjadi negara terkaya dunia karena menjarah harta karun emas berlian Indian Amerika. Harta karun itu akan membuat Spanyol malas dan dilanda inflasi serta akan merosot setelah kekalahan oleh Inggris. Setelah itu Pax Neerlandica, Belanda memonopoli perdagangan rempah rempah Nusantara, menjadi negara terkaya didunia. Sejarah juga mencatat Indonesia adalah satu satunya negara bekas terjajah yang justru dibebani melunasi utang kepada negara induk kolonialnya senilai US$ 1,130 milyar dalam perjanjian KMB Desember 1949. Ini suatu ironi dan blunder demokrasi akibat terlalu percaya janji AS bahwa AS akan mengucurkan bantuan besar besaran untuk RI setelah berdamai dengan Belanda. Ternyata yang direalisasi hanya feasibility dan kredit ekspor lunak untuk Semen Gresik dan Pupuk Sriwijaya. 236 Utang itu akan dilunasi hingga sisa US$ 171 juta pada 1956. Kemudian pada 1967 Indonesia menasionalisasi semua perusahaan Belanda yang akan menjadi blunder juga karena berakibat menghancurkan sistim logistic nasional ketika KPM diambil alih tanpa persiapan. Sejak itu ongkos angkut dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari Shanghai Jakarta dan hingga detik ini beaya logistic antar pulau di Indonesia menjadi komponen logistic termahal sedunia. Ini yang akan ditrobos oleh Presiden Jokowi dengan strategi pembangunan Poros Maritim. Secara geopolitik juga akan menghasilkan sinergi dengan Belt Road Initiative Presiden Xi Jin Ping yang baru diresmikan 15 Mei 2017 dengan pelbagai proyek infrastruktur Transeurasia lewat darat maupun maritime. Dalam konteks perjalanan hidup bangsa kita, maka pada era Indonesia 1.0 periode 1945-1966 meskipun konstitusi mengalami amandeman dan perubahan, tapi modul dasar Pancasila, tetap substansi dan essensinya. Era 1.0 di bawah Presiden Sukarno ini mengalami pelbagai adaptasi konsitusi, mulai dari Maklumat Wk Presiden no X 16 Oktober 1945 yang merubah sistim cabinet presidensial ke parlementer sehingga Presiden Sukarno diganti oleh PM Sutan Syahrir pada 14 November 1945. 237 Dibalik formalitas itu ada “black campaign” isu bahwa Bung Karno dan Bung Hatta, tidak disukai oleh Sekutu karena dianggap kolaborator Jepang karena keduanya terkait dengan Putera, lembaga mobilisasi rakyat pengerah romusha Jepang. Dalam konteks political behavior ini memang harus diakui bahwa sulit memahami “kompromi” maupun toleransi yang dipraktekkan oleh para tokoh elite nasional Indonesia dizaman perjuangan kemerdekaan sebelum dan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum kemerdekaan, sejak Belanda memberi kesempatan kepada elite nasional untuk ikut dalam Volksraad atau Dewan Rakyat 1908 maka elite terpecah dua. Golongan yang menyambut baik dan menerima tawaran dan peluang untuk duduk dalam badan “legislative” itu disebut golongan ko(operatif). Di pihak lain, Bung Karno, Hatta, Syahrir dan lain lain yang menolak disebut golongan non ko. Dalam perspektif jangka panjang, kita sekarang tentu tidak boleh dan tidak bisa lagi mencap golongan ko sebagai “antek kolonialis Hindia Belanda”. Sebab diantara mereka ada tokoh pejuang kepentingan rakyat seperti Mohamad Husnie Thamrin yang harus dihargai perjuangannya melalui jalur Volksraad untuk masyarakat Jakarta. Karena itulah namanya diabadikan dalam proyek perbaikan kampong 238 yang menjadi percontohan Bank Dunia, oleh Gubernur Ali Sadikin. Dalam konteks sejarah kita maka posisioning elite kita yang tidak bisa mengelak dari turbulensi geopolitik dan tekanan opini internasional tidak hanya terjadi di era digital medsos 2017 tapi juga sudah berlangsung sejak perjuangan kemerdekaan dan ditengah negosiasi dengan Belanda pun terjadi konflik internal dikalangan elite kita yang saling mempergunakan propaganda populisme dan xenophobia. Pada era Indonesia 1.0 ini selama 5 tahun pertama, berperan dwitunggal Sukarno Hatta memayungi dwitunggal Syahrir Amir Syarifuddin. Presiden Sukarno menjadi Perdana Menteri cabinet presidensial pertama kemudian diganti oleh Syahrir lalu Amir Syarifudin yang tragis ikut pemberontakan PKI Madiun 1948 dan diganti oleh Bung Hatta sampai RIS diakui melalui KMB. Setelah itu Natsir dan Sukiman dari Masyumi jadi PM ke 5 dan ke 6 disusul Wilopo dan Ali Sastroamijoyo dari PNI sebagai PM ke 7 dan ke 8. PM ke 9 Burhanudin Harahap dari Masyumi menyelenggarakan pemilu terbersih dalam sejarah RI menghasilkan 4 besar partai pemenang PNI, Masyumi, NU, PKIdan Ali Sastroamijoyo menjadi satu satunya orang Indonesia yang sampai waktu itu survive dan sukses menjadi PM tidak berurutan. 239 Biasanya kultur Indonesia sekali berkuasa bila turun akan sulit untuk “come back” apalagi bila system politiknya semakin otoritarian. Pada tahun 1957 kabinet Ali Sastroamijoyo bubar dan Presiden Sukarno menunjuk dirinya sendiri menjadi formatur serta mengangkat tokoh non partai Ir Djuanda sebagai Perdana Menteri RI ke-10 dan mulai memasukkan militer dalam kabinet. KSAD Nasution malah diangkat jadi Penguasa Perang Pusat sebab negara dinyatakan dalam keadaan perang sejak jatuhnya kabinet Ali II hasil pemilu 1955. Konstituante gagal menyelesaikan tugas karena dead lock voting 4 kali antara kubu Pancasila vs kubu Piagam Jakarta dan Presiden Sukarno mendekritkan kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dan mulai memimpin langsung sistim presidensial sebagai PM sejak Kabinet Kerja 10 Juli 1959. Bung Karno akanmembubarkan DPR hasil pemilu diganti dengan DPRGR yang sebagian besar anggotanya diangkat oleh Presiden dan hanya sebagian kecil anggota DPR terpilih 1955. Bung Karno hanya akan menjadi “presiden otoriter” praktis selama 5 tahun, sebab sejak 1 Oktober 1965 ketika Pangkostrad Mayjen Soeharto mbalelo menolak 240 lapor ke Halim sebetulnya wangsit kepresidenan sudah berangsur pindah ke capres RI ke-2 yang akan menerima Supersemat pada 11 Maret 1966. Yang terjadi di Indonesia 1966 adalah turbulensi domestic nasional yang berdampak durian runtuh bagi Paman Sam yang sedang terpojok di Vietnam oleh invasi Vietcong. Dalam sekejap RI berubah dari poros Jakarta Pnom Penh Hanoi Beijing Pyongyang, menjadi anti komunis, anti RRT dan memutuskan hubungan dengan Beijing. Indonesia 2.0 yang anti komunis, akan survive 32 tahun dengan slogal Demokrasi Pancasila yang menertibkan partai menjadi 2 buah dan 1 Golkar yang enggan disebut partai karena merasa lebih “bersih” dari citra partai yang gagal era Orde Lama. Soeharto secara otoriter berkuasa 32 tahun sejak 1966 ditengah gelombang Perang Dingin dan “dipelihara” oleh 7 presiden AS sejak Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush hingga Clinton. Presiden Soeharto memobilisasi ideologi Pancasila melekat dengan eksistensi pribadinya. Dalam suatu pidato yang memicu reaksi Petisi 50 Soeharto mempersonifikasi dirinya sebagai satu satunya yang bisa mempertahankan ideology Pancasila. 241 Lebih baik menculik seorang anggota MPR supaya tidak tercapai quorum 2/3 untuk merubah Pancasila (baca: yang mau mengganti dirinya sebagai Presiden adalah lawan Pancasila). P4 yang berlangsung 20 tahun, tidak bisa mempertahankan Soeharto yang akan mengalami tekanan politik dan lengser 21 Mei 1998. Elite politik meninggalkan Soeharto yang mengalami hukum karma unik dari pre destinasi supranatural. Pada 18 Maret 1966 Soeharto menggunakan supersemar untuk menahan 15 menteri cabinet Dwikora II. Pada 20 Mei 1997 Soeharto ditinggalkan oleh 15 menteri kabinetnya yang mbalelo tidak mau duduk dalam cabinet lagi, sehingga Soeharto lengser 21 Mei 1998. Kembali terjadi siklus daur ulang Ken Arok, Soeharto sangat marah dengan perilaku Wapresnya Habibie yang dinilai mengkhianati sehingg sampai wafatnya Soeharto tidak bersedia di bezoek oleh Habibie. Dalam situasi seperti itulah Habibie secara ajaib memimpin Indonesia 3.0 transisi menuju kematangan demokrasi yang mendadak lahir setelah Soeharto berhenti diluar dugaan dan scenario pakar manapun. Habibie segera memperlihatkan jiwa besar dengan membebaskan tahanan politik, mengizinkan terbitnya kembali Tempo yang dibreidel karena memberitakan korupsi pembelian kapal selam ex Jerman oleh dirinya, tidak bersedia dicalonkan karena ditolak laporan pertanggunganjawabnya oleh MPR hasil pemilu 1999. 242 Justru yang terjadi pada pergantian presiden ke-3 oleh presiden ke-4, terjadi lagi maneuver politik yang diluar “fatsoen (kepatutan) politik. Abdurahman Wahid dari PKB yang lebih kecil dari PDIP justru menang dalam voting di MPR karena maneuver Poros Tengah ciptaan Ketua MPR Amien Rais. Tapi anomaly ini hanya berlangsung 21 bulan sebab pada Juli 2001, MPR yang sama akan memakzulkan Gus Dur dan mendudukkan Megawati sebagai presiden RI ke-5 yang memang berhak sebagai ketum partai pemenang kursi terbanyak di MPR. Meskipun putra proklamator dan presiden pertama, Megawati sebagai petahana akan dikalahkan oleh mantan Menko nya SBY sebagai presiden RI ke-6 dalam 2 kali pemilu 2004 dan 2009. SBY akan survive menjalani 2 masa jabatan dengan mengganti pasangan wapresnya dari Jusuf Kalla ke Boediono. Secara ajaib, Jusuf Kalla akan come back pada pemilu 2014 sebagai wapres mendampingi presiden ke-7 Joko Widodo. Semua ini masih era Indonesia 3.0 pasca Reformasi 1998. Bagaimana prospek dan perspektif Indonesia 4.0 suatu Indonesia yang diharapkan bisa mendeliver ideology Pancasila secara konkret. Bukan sebagai ideology atavistic muluk luhur yang tidak mampu memproduksi deliverables, kerja nyata yang dinikmati rakyat banyak. 243 Tercermin dari behavior elitenya mempraktekkan nilai luhur Pancasila. Pusat Data Bisnis Indonesia sudah menelusuri sejarah politik ekonomi bisnis Indonesia danmenemukan bahwa kata kuncinya adalah bagaimana menekan ICOR yang 6,4 menjadi 2 atau 3. Mengamati semua rezim ekonomi politik sejak etatisme sosialistis kiri Orla Indonesia 1.0, rezim developmentalis Orba Indonesia 2.0 dan turbulensi Indonesia 3.0 maka bila elite Indonesia mawas diri untuk menerapkan golden rule, meritocracy, maka Indonesia akan melampaui era transisi dan bertransformasi menjadi negara demokrasi matang, dewasa dan modern dan mentas menjadi negara kelas menengah berpendapatan US$ 50.000 pada usia seabad 2045. Dalam pameo elite sebetulnya oposisi juga menikmati kompensasi sama dengan partai pendukung pemerintah. Boleh dan bisa pendapat debat sengit di DPR, asal pendapatan nya sama (artinya gaji, remunerasi, insentif proyek dsb dsb) oposisi menerima bagian yang sama dengan pendukung pemerintah. Jadi yang diminta adalah kesadaran untuk menghormati aturan main, khususnya kesabaran menunggu term masa jabatan kepresidenan. Ibarat main sepak bola, tentu orang harus menghormati masa 2x 45 menit serta 244 jedah untuk mengganti pemain dan tidak setiap detik, menit waktu minta paksa ganti pemain menggotong petahana keluar lapangan. Sekarang kansudah dibatasi 2 kali masa jabatan 10 tahun jadi harus bersabar tidak sembarangan memakzulkan petahana presiden ataupun gubernur. Sportivitas, keksatriaan, itu yang menjadi suri tauladan dari elite panutan kepada masyarakat. Tentunya bukan hanya dalam adegan dilayar TV saling berpelukan tapi di lapangan grass roots terjadi clack campaign dan fitnah yang bermuara pada kebencian antar sara yang menyulut ideology kebencian yang bila meledak menjadi SARA ala Mei 1998 akan bisa menghancurkan Indonesia bahkan melenyapkannya seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Sungguh tidak nyaman ketika mendengar emosi Presiden RI ke7 Rabu 17 Mei 2017 yang menggunakan istilah gebuk terhadap mereka yang mau mengkudeta secara inkonstitusional persis seperti adegan emosional Presiden ke-2 di pesawat setelah melawat ke Yugoslavia dan Uni Soviet pada 13 September 1989. Dengan segala hormat kepada seluruh elite, sudah tiba waktunya elite Indonesia mawas diri dan mengentaskan diri dari penyakit Ken Arok abad primitive, menghalal- 245 kan segala cara untuk berkuasa dengan memfitnah adu domba dan mempermainkan kebencian emosi rakyat secara tidak terkendali sebab dampaknya bisa seperti api bunuh diri yang membakar rumah kita sendiri. Jika seluruh energy hiruk pikuk sekitar pilgub ini dikerahkan secara positif pastilah pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 7 % atau bahkan double digit. Dengan pertumbuhan 7 % saja, pendapatan per kapita kita bakal double setiap 7 tahun. Itu artinya dalam 28 tahun sejak 2017 sampai 2045 pendapatan per kapita kita akan mencapai US$7.000 pada 2024, US$ 14.000–2031, US$ 28.000-2038 dan US$ 56.000 tepat seabad RUI 2045. Jawaban dan tanggungjawab atas pencapaian itu bukan tergantung pada Donald Trump, Xi JinPing atau Putin atau seorang Jokowi, tapi juga pada seluruh elite yang terlibat dalam pengelolaan nation state Indonesia. Anda ini sedang menjadi salah satu dari 10.000 elite yang menentukan nasib Indonesia dengan behavior anda sebagai politisi “bunuh diri” atau ikut dalam barisan negarawan melestarikan eksistensi Indonesia. Apakah kita akan menjadi Indonesia 4.0 yang mampu mengorbitkan RI menjadi no 4 sedunia dalam kualitas pada usia seabad 2045 dan bukan sekedar kuantitas seperti sekarang dengan peringkat kinerja yang terpuruk 246 disbanding negara lain karena tingkah laku elite politik yang tidak terpuji dan tidak mendukung kinerja optimal nation state modern Indonesia. Jangan salahkan Tuhan bila RI jadi Yugoslavia atau Uni Soviet, salahkan diri anda sendiri karena surat Al Rad yang jadi favorit Bung Karno mengingatkan: “Tuhan tidak akan memperbaiki nasib suatu bangsa bila bangsa itu sendiri tidak ingin memperbaiki nasibnya.” Saya sendiri percaya bahwa jumlah elite dan massa yang “baik” lebih banyak dari keluarga Lot. Yang menyebabkan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena jumlah orang baik “kurang sari 5 orang”. Kita percaya bahwa Indonesia masih memenuhi syarat kuantitatif untuk bertobat dan diselamatkan seperti Niniwe dizaman Nabi Junus. Syaratnya mudah, laksanakan Pancasila secara praktis, sehari hari, perilaku yang tidak munafik, yang mendeliver, janji, program dan kinerja secara tuntas, lugas dan konkret. Tidak perlu di teorikan, dikeramatkan, dimobilisasi, indoktrinasi lagi, malah sudah memuakkan dan menjengkelkan. Hanya perlu didelivery konkret seperti makanan yang disajikan ojek Uber sesuai kebutuhan dan timing. Jangan tunggu sampai 2019, tapi harus di deliver sekarang juga. 247 Tantangannya adalah apakah kita terpuruk lenyap dari peta geopolitik seperti Yugoslavia dan Uni Soviet atau kita melejit jadi nation state no 4 sedunia dalam kualitas pada Seabad Indonesia 2045. [] 248 Demokrasi Pancasila Dalam Praktek Geisz Chalifah Pengamat politik, Mantan pengurus KAHMI Denny JA menulis poin-poin gagasan wacana demokrasi Pancasila yang diperbarui, untuk diskusikan bersama agar mendapat rumusan demokrasi pancasila yang disepakati bersama secara kekinian. Tulisan itu merujuk pada konteks pilkada DKI Jakarta dimana pertarungan gagasan dan kompetisi antar pasangan calon maupun pendukung berlangsung sengit dan mendebarkan. Sengit karena media sosial menjadi ladang ekspresi kebencian dan ratusan berita hoax yang dikirim dan di viralkan ke segenap pendukung maupun lawan politik. Mendebarkan karena ada kekhawatiran Pilkada DKI akan berujung pada kericuhan sosial dan disintegrasi bangsa. 249 Sesungguhnya Indonesia sudah terbiasa mengadakan pesta demokrasi yang rutin dilakukan baik pemilihan Presiden maupun pemilihan Gurbernur maupun Bupati dan Walikota. Perbedaan pilihan di masyarakat sudah rutin terjadi dan tak memiliki efek apapun setelah pilpres maupun pilkada selesai. Kehidupan kembali berjalan normal, semua konflik berujung di Mahkamah Konstitusi dan ketika palu di ketuk maka semua kembali pulang baik yang kalah maupun yang menang menerima. Kembali bekerja dalam profesinya masing-masing. Kesadaran rakyat untuk tidak memperpanjang persoalan dalam setiap Pilpres maupun pilkada merupakan peradaban yang sehat, karena berbeda dalam pilihan adalah hal biasa yang menang maupun yang kalah telah ditentukan nasibnya dalam kotak suara. Namun yang tak biasa adalah dalam menyikapi perbedaan itu sendiri dan lebih aneh lagi ketika elit politik dan aparat Negara malah menunjukkan sikap sebaliknya. 250 Kasus Pilkada DKI Berkaca Dengan Sikap SBY Dalam pilpres 2014 pertarungan antara Prabowo dan Jokowi juga merupakan pertarungan yang sengit, saling mengklaim sebagai paling NKRI disatu sisi dan paling Islam disisi lainnya. Klaim-klaim sepihak itu memasuki ranah masyarakat luas, berbagai keluarga dan komunitas terbelah. Namun kemanan dan kenyamanan tetap kondusif. SBY sebagai Presiden melakukan tugas menjaga segalanya berlangsung dengan proporsional . Tidak nampak secara kasat mata ada pemihakan dari aparat maupun birokrasi terhadap salah satu pasang calon. Dengan segala kekurangannya SBY telah menunjukkan dirinya sebagai presiden dengan bersikap proporsional, aparat kepolisian dan birokrasi tetap sebagai fungsinya tidak nampak dalam kepermukaan dengan berfihak pada salah satu pasangan calon. SBY menjaga agar turunnya dia sebagai presiden dalam mengakhiri masa jabatan dengan terhormat dan berwibawa. 251 Berbeda dengan pilkada kali ini, aparat kepolisian sangat nampak dan kasat mata memberikan dukungan pada Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Situasi yang memanas di lapisan bawah di perparah dengan aparat birokrasi yang terkesan memberikan pemihakan, kartu Jakarta Lansia yang belum di agendakan dan disetujui oleh DPRD tiba-tiba sudah mulai di berikan melalui Bank DKI tanpa ada legalitas, aparta kepolisian berkali-kali melakukan panggilan pada pasangan calon Agus-Sylvi maupun Anies-Sandi dengan kasus-kasus yang sumir dan terkesan dipaksakan. Hanya sekedar untuk memberi kesan negativ dimata pemilih tapi berlaku sebaliknya terhadap pasangan Basuki dan Djarot, bahkan aparat polisi ikut terlibat dalam mengamankan pembagian sembako diminngu tenang yang jelas – jelas melanggar aturan KPUD. Jokowi Dalam Praktek Demokrasi Presiden Jokowi yang dipilih dalam pilpres 2014 dan salah satu alasan masyarakat memilihnya adalah dia dari masyarakat sipil biasa akan lebih mengamankan hak – hak rakyat, yang dinilai jauh berbeda dengan Prabowo yang berlatar belakang militer dan punya kasus-kasus masa lalu. 252 Ada ketakutan bila memilih Prabowo maka demokrasi yang sedang dibangun akan mundur kembali mengingat Prabowo adalah salah satu jendral dimasa orba yang sepak terjangnya memiliki banyak persoalan dimasa lalu. Namun demikian ternyata persepsi yang digaungkan di masa pilpres menjadi bertolak belakang setelah pilpres selesai. Prabowo dalam berbagai persoalan politik yang hangat terkesan tampil sebagai negarawan yang mendinginkan suasana dan tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi untuk membalas kekalahan didalam pilpres. Menariknya Presiden Jokowi yang dicitrakan moderat karena berlakang belakang sipil malah tidak terampil dalam menunjukkan sisi kenegarawanan. Sebagai Presiden yang selayaknya netral dan menjadi pemimpin untuk semua namun bersikap sebaliknya. Jokowi baik secara implisit maupun eksplisit secara terang benderang memberikan dukungan pada Basuki Tjahaya Purnama. Dalam berbagai kesempatan Jokowi member signal pada masyarakat melalui media atas dukungannya pada BTP. Sikap Jokowi yang demikian itu menjadikan aparat kepolisian di bawah kendalinya maupun Luhut Binsar 253 Panjaitan sebagai menteri kordinator tanpa malu-malu memberikan pengamanan dan dukungan dalam pilkada DKI ini yang terefleksi dalam berbagai kesempatan. Demokrasi Pancasila menurut Denny perlu diperbahrui Saya tak begitu tertarik dengan wacana pembaruan Pancasila, karena pancasila sebagai ideologi Negara sudah diterima secara mutlak oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapaun sekat – sekat perbedaan politik dan segmentasi didalam masyarakat dalam kejadian pilkada kemarin lebih kepada tidak taatnya elit politik dalam aturan main yang telah disepakati bersama. Partai politik yang menjadi alat kontrol pemerintah menjadi lemah, karena penguasa dan partai berada dalam satu barisan bekerja sama untuk memenangkan calon tertentu. Demokrasi yang sudah berlangsung sejak di praktekkan pasca reformasi dan secara gradual mulai berlangsung dalam koridor, kembali mundur secara etika karena pemerintah (Penguasa/Presiden) tidak komited terhadap etika demokrasi yang selayaknya dijaga dan dikembangkan secara formal maupun non formal. 254 Adapun sekat-sekat politik aliran dan sebagainya adalah keniscayaan dalam sebuah Negara yang bhineka. Tak ada di Negara demokrasi manapun ada batasan dalam memilih seorang calon gurbernur berdasarkan, kedekatan kelompok, suku, agama, maupun isu primordial lainnya. Bahkan isu perempuan dalam kompetisi politik seringkali menjadi pertimbangan untuk menetapkan pasangan calon. Pemilih tidak bisa dikurung pikirannya dengan batasan hanya boleh memilih dengan krteria tertentu seperti kinerja dan kompetensi. Ada banyak spektrum dalam benak pemilih dalam menjatuhkan pilihan. Dalam semua segi itu yang menjadi acuan utama adalah aturan main yang adil dan proporsional. Untuk itu di perlukan sikap pemerintah yang jelas, tegas dan taat pada aturan main yang telah disepakati bersama. Islam Sebagai Agama Mayoritas Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas dalam setiap moment politik selalu menjadi wacana, ada 255 yang bersikeras untuk memisahkan agama dalam politik namun dalam situasi dan kesempatan lain yang mewacanakan hal demikian bersikap sebaliknya dengan membangun opini bahwa calon yang didukungnya itu adalah calon yang berkesesuaian dengan etika maupun prasarat yang didengungkan dalam Islam. Penolakan Islam dalam politik dalam prakteknya hanyalah soal siapa calon yang diunggulkan, karena siapapun elite di republik ini faham bahwa islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Bahkan sejarah negeri ini dipenuhi oleh heroisme yang berlatar belakang agama dalam melawan penindasan kolonial. Namun isu pemilahan maunpun wacana demikian akan selalu ada sesuai kepentingan situasi pemilu maupun dalam kepentingan lain. Bangunan wacana Ahistoris itu saat ini menariknya dibenturkan oleh wacana kebhinekaan. Solah kebhineka-an menjadi hal suci dan menjadi kotor bila islam ditampilkan diruang publik, provokasi lucu dan konyol semacam itu, sudah lama terjadi dan bila dirunut keberbagai kasus tidak ada satupun yang konsisten dalam meyulut isu demikian. BTP yang dikesankan tokoh kebhinekaan dan dipropangadakan dengan alasan kinerja, berkali-kali mendapat ruang dan diperjuangkan dengan wacana keislaman di ruang publik, seperti gelar sunan, santri dan lain sebagainya. 256 Juga berbagai acara zikir akbar juga forum-forum shalawatan yang dibuat dan diacarakan demi memikat hati pemilih Islam. Demokrasi Pancasila Tak Perlu Menolak Politik Aliran Demokrasi Pancasila yang hidup dinegara dengan berbagai keberagaman menjadi absur kehadirannya bila menolak politik aliran karena politik aliran adalah bagian dari keberagaman itu sendiri. Demokrasi Pancasila sebaliknya harus memberikan ruang yang lebar untuk semua segmen saling beradu gagasan secara rasional, argumentatif. Semua kelompok memiliki cara pandang dan ide untuk membangun sebuah Negara modern namun ditengah ide dan gagasan itu maka aturan main harus ditegakkan. Aturan main tentu saja dikawal oleh lembaga yudikatif yang kompeten dan berwibawa. Tak boleh lagi penguasa ikut bermain dalam sebuah kontestasi dan berfihak pada pasangan calon tertentu dengan melibatkan aparat di bawah untuk member dukungan karena bila demikian maka demokrasi yang baru dibangun belasan tahun akan kembali surut kebelakang dan butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. 257 Kepercayaan masyarakat dalam mengikuti aturan bergantung dari elit politik dalam mentaatinya. Karena elite politik lah yang dilihat dan menjadi contoh nyata, bukan teks aturan berupa undang-undang yang hanya di atas kertas. [] 258 Membincang Ulang Demokrasi Pancasila Trisno S Sutanto Pendiri MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama) Agaknya efek gempa politik yang diakibatkan oleh Pilkada DKI tanggal 19 April lalu masih akan dirasa sampai jangka waktu cukup panjang. Paling tidak sampai Pilpres 2019. Alasannya jelas. Pilkada DKI yang baru lalu merupakan Pilkada dengan “aroma Pilpres” sangat kuat sejak putaran pertama. Ketiga figur yang bersaing, setidaknya dalam pandangan publik, semacam mewakili ketiga figur yang mewarnai Pilpres 2014: SBY, Jokowi, dan Prabowo. Dan kesan ini makin kuat saat putaran kedua yang seakan mengulang sejarah pertarungan Pilpres lalu itu. Tidak heran bila banyak orang menyebut, Pilkada DKI merupakan ajang foreplay bagi Pilpres 2019. 259 Tetapi ada soal lain yang membuat gempa politik Pilkada DKI itu akan bergema lebih panjang. Pertarungan politik yang baru berlalu itu telah memecah belah kelompok-kelompok masyarakat karena politisasi SARA yang brutal dan penyebaran kebencian (hate spin) lewat media-media sosial. Sudah banyak tali pertemanan dan grup-grup chatting WA bubar hanya karena perbedaan calon yang didukung. Sementara status-status di Facebook dan kicauan di Twitter dipenuhi oleh sumpah serapah dan maki-makian yang tersebar luas dan cepat. Pada titik ini muncul kegelisahan–atau bahkan ketakutan–di kalangan masyarakat luas, apakah eksistensi Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika masih mampu bertahan? Jika saat Pilkada DKI saja sudah sedemikian parah perpecahan yang terjadi, bagaimana nanti dalam Pilpres 2019? Bukankah politisasi SARA dan penyebaran kebencian akan berlipat ganda? Lalu apakah demokrasi Pancasila masih akan mampu bertahan sebagai model pengelolaan politik? Jika tidak, haruskah kita mencari alternatif lainnya? Jika ya, perlukah demokrasi Pancasila itu diperbarui? 260 Bukan Hanya Mangkok Kosong Tentu saja sangat sulit, kalau bukannya mustahil, memberi jawaban serba pasti terhadap rentetan pertanyaan yang kini menggelisahkan banyak orang itu. Sementara, pada saat bersamaan, beredar luas lewat media-media sosial kampanye kelompok-kelompok yang menawarkan alternatif terhadap Pancasila di satu pihak, dan seruan-seruan untuk mempertahankannya (plus “NKRI harga mati”) di pihak lain. Di dalam konteks itulah ajakan Denny JA untuk membicarakan ulang apa yang disebutnya sebagai “demokrasi Pancasila yang diperbarui” perlu disambut, walau terasa problematis. Dan persoalan utama dari ajakan itu justru terletak pada kata “Pancasila”. Sebab, seperti tampak dalam sejarah, imbuhan Pancasila bisa dilekatkan pada berbagai bentuk rezim pemerintahan, mulai dari demokrasi terpimpin Soekarno, rezim otoriter-militeristik Soeharto, sampai euforia – ada yang menyebutnya democrazy – pasca Mei 1998. Tidak heran jika seorang peneliti asal Belanda, Justus van der Kroef, dulu pernah mengibaratkan Pancasila seperti “mangkok kosong”: Anda bisa mengisinya dengan model pemerintahan apa saja! 261 Penilaian van der Kroef itu memang kontroversial, dan pernah memancing kritik tajam dari alm. Pdt. Eka Darmaputera dalam disertasinya yang terkenal (Darmaputera, 1988). Namun, terlepas dari kritik itu, apa yang ditunjuk van der Kroef ada benarnya juga. Maksud saya begini: Pada satu sisi harus ditegaskan, Pancasila sebenarnya merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang, boleh dibilang, akan disepakati oleh semua orang: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Rasanya sulit dibantah bahwa nilai-nilai itu merupakan aspirasi bagi setiap orang, apapun latar belakang suku, agama, ras, budaya, dstnya. Dengan cara yang jenius itulah Soekarno mampu memberi landasan yang mempersatukan kebhinnekaan, dan mengolahnya sebagai energi politik yang maha dahsyat guna mencapai kemerdekaan. Tetapi, pada sisi lain, kita segera menyadari betapa problematisnya ketika nilai-nilai luhur itu akan diterjemahkan menjadi sistem kehidupan bersama. Masing-masing nilai luhur itu membuka ruang interpretasi sangat luas dan beragam, yang bentuk akhirnya sangat ditentukan oleh wawasan kebangsaan maupun situasi pertarungan politik yang riil pada setiap masa. 262 Ambillah contoh nilai luhur yang sudah kerap diperbincangkan: sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika kita menelusuri latar sejarah perumusannya, setidaknya kita akan menemukan tiga pemahaman berbeda mengenai frase itu. Pertama, visi Soekarno, sebagaimana dituangkan dalam Pidato 1 Juli 1945 yang mahsyur, yakni suatu visi tentang negara yang ber-Tuhan secara kebudayaan dengan “tanpa egoisme agama”. Visi kedua tampil sebagai hasil deliberasi “Panitia Sembilan” yang mempersiapkan bahan untuk pleno dalam masa persidangan kedua BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan)--apa yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”. Akhirnya, visi ketiga, adalah rumusan yang kita terima sampai sekarang sebagai hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945 yang sekaligus mengesahkan UUD 1945 (uraian lebih rinci dapat ditemukan dalam Sutanto, 2016). Yang lebih menarik adalah ketika menelisik perdebatan bagaimana nilai luhur itu diterjemahkan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam persidangan tanggal 13 Juli 1945, K.H. Wachid Hasjim mengingatkan bahwa “buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara Pemerintah dan masyarakat”. Karena itu ia 263 mengusulkan dua usulan perubahan yang kemudian menimbulkan perdebatan: (1) bahwa yang dapat menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli “yang beragama Islam”; dan (2) ada penegasan bahwa “Agama negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dsb.” Usulan itu didukung oleh Soekiman. Tetapi tokoh Muslim lainnya dan pejuang kemerdekaan, H. Agus Salim langsung menolak usulan itu yang, menurut dia, akan mementahkan kompromi yang sudah dicapai. “Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta, dsbnya,” tanya Agus Salim. “Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain?” (Lihat rekaman perdebatannya dalam Kusuma, ed., 2009, h. 314. Cetak miring ditambahkan.) Pertanyaan Agus Salim itu sungguh menohok. Memang benar, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, perlu mendapat tempat di negara yang baru diproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi hal itu tidak boleh menafikan kelompok-kelompok keagamaan lainnya – atau bahkan kelompok yang “meniadakan Tuhan” (ateis) maupun mereka yang meyakini banyak Tuhan (politeis). 264 “Dapatkah dengan asas negara itu kita mengakui kemerdekaan keyakinan orang yang meniadakan Tuhan? Atau keyakinan agama yang mengakui Tuhan berbilangan atau berbagi-bagi?” tulis Agus Salim. “Tentu dan pasti! Sebab undang-undang dasar kita, sebagai juga undang-undang dasar tiap-tiap negara yang mempunyai adab dan kesopanan mengakui dan menjamin kemerdekaan keyakinan agama, sekadar dengan batas yang tersebut tadi itu, yaitu asal jangan melanggar hak-hak pergaulan dan orang masing-masing, jangan melanggar adab kesopanan ramai, tertib keamanan dan damai” (Salim, 1951/52, h. 125). Mengelola Kebhinnekaan Saya sengaja mengambil contoh perdebatan tentang sila pertama Pancasila itu, yakni tentang tempat dan peran agama dalam suatu tatanan negara yang demokratis. Dan kita melihat dari perdebatan para pendiri negara adanya semangat dan imperatif untuk menjamin kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok keagamaan. 265 Persoalan itulah yang dewasa ini, pasca Pilkada DKI, menantang kehidupan dan praktik demokrasi kita sebagai akibat politisasi SARA yang brutal dan penyebaran kebencian. Karena itu, seperti dianjurkan Denny JA, upaya untuk menemukan “demokrasi Pancasila yang diperbarui” juga harus menjawab tantangan fundamental tersebut. Untuk itu dibutuhkan niat dan upaya politik kenegaraan yang sungguh-sungguh guna menegaskan prinsip-prinsip dasar tatanan demokratis, yang setidaknya mencakup tiga asas penting ini. Pertama, asas inklusif dan non-diskriminatif, di mana semua kelompok masyarakat, di dalamnya termasuk kelompok keagamaan, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional yang sama oleh karena mereka merupakan warga negara yang setara. Kedua asas ini merupakan terjemahan lebih lanjut dari prinsip kewarganegaraan (citizenship) yang menjadi landasan tatanan demokratis. Kedua, asas kebebasan dan toleransi beragama, sebab kebebasan tidak boleh mengancam toleransi dan sebaliknya toleransi tidak boleh mematikan kebebasan. Di sini dibutuhkan law enforcement yang sungguh-sungguh guna menjaga baik kebebasan pada satu pihak, 266 maupun toleransi pada pihak lain. Dan hanya dengan ini kemajemukan agama di Indonesia tidak perlu menjadi ancaman yang dapat membuyarkan persatuan. Terakhir, asas ketiga, adalah meritokrasi sebagai satu-satunya tolok ukur yang diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Itu berarti, seorang (calon) pemimpin publik hanya boleh dinilai berdasarkan karya nyata dan pengabdiannya bagi masyarakat luas, bukan oleh karena asal usul suku, ras, keyakinan, atau bahkan orientasi seksualnya. Karena itu, politisasi SARA dan penyebaran kebencian seharusnya tidak mendapat tempat dalam mekanisme demokratis. Menurut saya, itulah arah perjuangan politik kenegaraan ke depan jika memang serius ingin memperbarui demokrasi Pancasila. Dan hanya melalui itulah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dapat terus dipertahankan! [] Rujukan Darmaputera, Eka, 1988, Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis, Leiden: E.J. Brill. 267 Kusuma, RM. A.B. (ed.), 2009, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, edisi revisi, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Salim, H. Agus, 1951/52, “Kementerian Agama dalam Republik Indonesia”, diterbitkan dalam buku Agenda Kementerian Agama, Jakarta: Departemen Agama, 1951/1952, h. 123 – 128. Teks asli yang lengkap dapat diunduh lewat tautan https://app.box.com/s/f1oo2bqtp08v1b08gdxb. Sutanto, Trisno S., 2016, “Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Membaca ulang Hubungan Agama-Negara di Indonesia”, dalam Alamsyah M. Dja’far dan Atikah Nur’aini (eds.), Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Buku Sumber, Jakarta: Wahid Foundation, h. 15 – 82. 268 EPILOG 269 270 Indonesia Akan Dibawa Ke Mana? Denny JA Victor Hugo suatu ketika berkata: Nothing is more powerful than an idea whose time has come. Tak ada yang lebih berkuasa dari sebuah gagasan yang waktunya sudah datang. Waktu bagi Demokrasi Pancasila yang diperbarui sudah datang. Kita membutuhkan aturan main bersama di ruang publik sebagai the only game in town. Saya buatkan kesimpulan dalam bentuk pointers. Di bawah ini lima hal pokok percakapan kunci yang penting ke depan mengenai kebersamaan kita selaku satu bangsa. 1) Sudah pasti kita tak bisa sepakat mengenai kemana negara harus diarahkan? Tak ada masalah jika setiap partai dan individu mengembangkan mimpinya sendiri. Mimpi tak bisa dipaksa untuk diseragamkan. Agama saja tak bisa dipaksakan, apalagi gagasan dan mimpi. 271 2) Tapi kita bisa dan harus mensepakati cara main bersama di ruang publik. Harus bersetuju mengenai rule of the game, bagaimana mempertarungkan aneka policy dan mimpi. Harus ada cara main di ruang bersama yang mesti dihormati dan dihayati. Dan cara main bersama di ruang publik itu kita upayakan menjadi “the only game in town” Amandemen konstitusi UUD 45 sudah memberi arah: aturan mainnya sistem demokrasi (yang tahapannya disesuaikan dengan evolusi kesadaran kolektif Indonesia) 3) Dalam aturan main itu - Hak asasi manusia tak bisa dilanggar. Termasuk hak berpendapat dan hak berorganisasi. Setiap individu boleh menyatakan pendapatnya berdasarkan paham yang ia yakini, termasuk agama. Tak bisa dilarang, bahkan harus dihormati, orang bepolitik dengan gagasan, termasuk gagasan agama. 272 - Di Indonesia, gagasan agama menggores sangat dalam. Mustahil menciptakan sistem apapun yang mengakar tanpa mempertimbangkan agama di ruang publik - Yang kita larang hanya kekerasan dan kriminal, apapun gagasan di baliknya. - Pemerintah perlu hadir lebih tegas dan keras tapi tetap tunduk pada aturam hukum. Pemerintah berada dalam hukum, bukan di luar hukum. 4) Agar aturan main itu punya legitimasi dan bermakna, ia harus berangkat dari realitas Indonesia dan berbuah baik - Menghormati keberagaman yang ada, baik prinsip mayoritas ataupun hak minoritas Terasa keadilan sosialnya, kuat rasa persatuannya, dan berbuah kemakmuran 5) Mayoritas publik menyukai jika sistem yang merangkum elemen di atas diberi nama Demokrasi Pancasila (yang diperbarui karena yang publik maksud bukan demokrasi pancasila era Pak Harto: dwi fungsi ABRI, dll) 273 Ini percakapan yang sebisa mungkin tuntas dalam lima tahun ini. Semoga 25 tahun reformasi (5 pemilu) di tahun 2023, demokrasi pancasila sudah mengalami konsolidasi. [] Jika kita tak ingin Indonesia berubah menjadi negara Islam, atau negara sekuler yang ekstrem, atau kembali ke negara otoriter, saatnya kita tegaskan kembali komitmen untuk demokrasi pancasila yang diperbarui. Langkah pertama kerja penting itu mendetailkan dan menyepakati elemen fundamental bangunan kelembagannya. Buku kecil itu awal dari kerja besar itu. 274 275 276