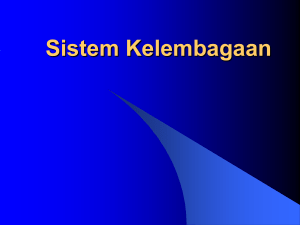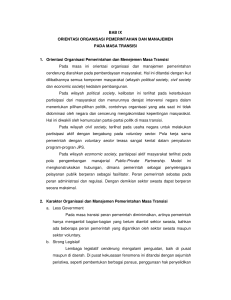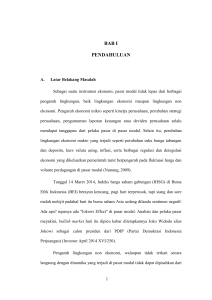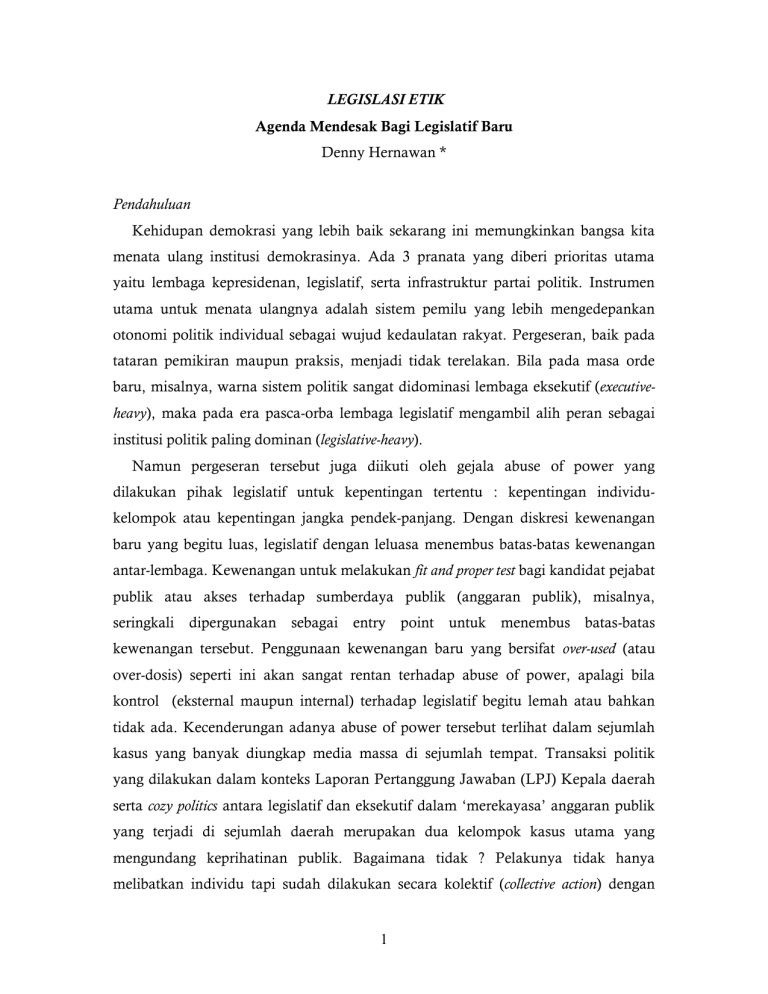
LEGISLASI ETIK Agenda Mendesak Bagi Legislatif Baru Denny Hernawan * Pendahuluan Kehidupan demokrasi yang lebih baik sekarang ini memungkinkan bangsa kita menata ulang institusi demokrasinya. Ada 3 pranata yang diberi prioritas utama yaitu lembaga kepresidenan, legislatif, serta infrastruktur partai politik. Instrumen utama untuk menata ulangnya adalah sistem pemilu yang lebih mengedepankan otonomi politik individual sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pergeseran, baik pada tataran pemikiran maupun praksis, menjadi tidak terelakan. Bila pada masa orde baru, misalnya, warna sistem politik sangat didominasi lembaga eksekutif (executiveheavy), maka pada era pasca-orba lembaga legislatif mengambil alih peran sebagai institusi politik paling dominan (legislative-heavy). Namun pergeseran tersebut juga diikuti oleh gejala abuse of power yang dilakukan pihak legislatif untuk kepentingan tertentu : kepentingan individukelompok atau kepentingan jangka pendek-panjang. Dengan diskresi kewenangan baru yang begitu luas, legislatif dengan leluasa menembus batas-batas kewenangan antar-lembaga. Kewenangan untuk melakukan fit and proper test bagi kandidat pejabat publik atau akses terhadap sumberdaya publik (anggaran publik), misalnya, seringkali dipergunakan sebagai entry point untuk menembus batas-batas kewenangan tersebut. Penggunaan kewenangan baru yang bersifat over-used (atau over-dosis) seperti ini akan sangat rentan terhadap abuse of power, apalagi bila kontrol (eksternal maupun internal) terhadap legislatif begitu lemah atau bahkan tidak ada. Kecenderungan adanya abuse of power tersebut terlihat dalam sejumlah kasus yang banyak diungkap media massa di sejumlah tempat. Transaksi politik yang dilakukan dalam konteks Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala daerah serta cozy politics antara legislatif dan eksekutif dalam ‘merekayasa’ anggaran publik yang terjadi di sejumlah daerah merupakan dua kelompok kasus utama yang mengundang keprihatinan publik. Bagaimana tidak ? Pelakunya tidak hanya melibatkan individu tapi sudah dilakukan secara kolektif (collective action) dengan 1 besaran angka yang cukup besar : bila diakumulasikan jumlahnya bisa mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan, milyar rupiah. Hak publik terhadap anggaran dalam bentuk program atau proyek yang menyangkut kebutuhan mereka dipaksa untuk di-disalokasikan atas nama hak budget yang secara inheren merupakan hak istimewa mereka. Implikasi dari gejala yang dipaparkan di atas sangat mengerikan : erosi, bahkan kehilangan, kepercayaan publik baik pada individu anggota dewan maupun lembaga dewan secara keseluruhan. Indikasi ke arah itu cukup jelas : tingkat kepedulian dan kemampuan yang rendah. Sering muncul public criticism menyangkut fasilitas bagi dewan yang dianggap ‘tidak pantas’ (improper) seperti fasilitas kredit tanpa bunga yang cukup besar, uang purna-bakti, dsb. Padahal peraturan perundangan yang ada secara jelas mengatur sedikitnya 9 jenis tunjangan atau pengeluaran lain bagi anggota dewan. Perilaku kolektif seperti itu mencerminkan ketidak-pedulian dan ketidak-pekaan legislatif terhadap kondisi masyarakat yang sedang ditimpa krisis. Selain itu, tidak sedikit masalah publik yang begitu kompleks tidak bisa diselesaikan karena rendahnya kinerja dan kemampuan dalam merumuskan dan mengontrol agenda publik. Rendahnya kepercayaan publik ini, bila diabaikan, hanya akan membuat demokrasi menjadi kehilangan maknanya yang hakiki. Untuk mencegah hal itu perlu ditanamkan pemikiran bahwa semua posisi publik, termasuk menjadi anggota legislatif, adalah amanah atau “public office is public trust’. Dalam mewujudkan hal terakhir itulah perlu ada komitmen kuat dari legislatif (baik secara individual maupun kelembagaan) untuk melakukan perubahan atau transformasi fungsional. Dewan secara sistematis harus melakukan sejumlah upaya pemulihan citra yang dapat mengangkat kembali kepercayaan publik terhadap mereka. Selain lebih mengefektifkan kontrol internal, misalnya lewat penataan-ulang tatib Dewan, ada urgensi mendesak untuk mengkaji alternatif lain yaitu legislasi etik. Hal ini dipandang relevan mengingat salah satu fungsi utama dewan adalah legislasi. Bila dewan bisa mencitrakan diri sebagai institusi politik yang punya komitmen untuk melakukan kontrol-diri dengan berdasar pada nilai-nilai etika publik yang dilegalkan, merupakan sebuah keniscayaan bila hal tersebut dapat memberikan credit point tersendiri di mata publik. Mengapa demikian ? Bila itu mampu 2 diwujudkan, dewan hakekatnya telah memberikan sesuatu yang jarang dilakukan di negeri ini yaitu exemplary leadership atau kepemimpinan dengan memberikan teladan, dan itu hendaknya dimulai dari dewan sendiri. Ekspektasi itu didorong oleh kemungkinan terjadinya citra baru dewan sebagai hasil pemilu legislatif 2004 yang lebih mencerminkan pluralisme dalam peta kekuatan politik dan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengkaji legislasi etik baik pada tataran normatif maupun kelembagaan. Pengkajian model bagi pelembagaan komisi etik, sebagai bagian tidak terpisahkan dari legislasi etik, juga akan dianalisis secara kritis dengan melihat pentingnya deliberasi publik (public deliberation) sebagai prasyarat awal. Pada bagian akhir akan dibahas prospek dari legislasi etik ke depan termasuk alternatif strategi untuk mencapainya. Legislasi etik : sebuah pendekatan normatif Salah satu bentuk reformasi yang coba diegendakan pada era pasca-orba adalah reformasi hukum menuju kearah penegakan nilai-nilai keadilan bagi publik sesuai prinsip rule of law yang menjadi pilar utama demokrasi. Legislasi etik atau ethics law, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi hukum, dipandang urgen dan relevan untuk diagendakan sekurang-kurangnya karena 3 alasan pokok. Pertama, salah satu sumber utama dari krisis multi-dimensional yang berkepanjangan adalah krisis etika atau moral dalam organisasi publik. Ekses dari krisis etik ini bukan hanya merugikan negara secara ekonomis sejumlah ratusan triliun rupiah, namun lebih dari itu – dan ini yang tidak ternilai harganya – telah melemahkan tingkat kepercayaan publik pada organisasi publik yang ada. Karena itu legislasi etik harus dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai etik melalui upaya law enforcement sehingga aplikasinya mempunyai kekuatan memaksa. Kedua, seperti telah dipaparkan terdahulu, dalam banyak kasus adanya kebutuhan untuk mempromosikan perilaku etik pada dasarnya merupakan kombinasi dari 2 faktor utama, yaitu korupsi yang dilakukan anggota dewan dan turunnya kepercayaan terhadap legislator. Dalam hal kedua ini ethics law harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik tersebut. Ketiga, semakin berpengaruhnya civil soceity organization (CSO), seperti sejumlah LSM dan watchdog 3 groups lainnya, serta tekanan dari publik , terutama attentive public, membuat legislative bodies (baca : eksekutif dan yudikatif secara bersama-sama) didorong untuk melakukan perubahan dalam hal prosedur internalnya. Tutuntan dari sejumlah kalangan CSO terhadap proses legislasi anggaran (APBD maupun APBN) telah mendorong perubahan prosedur internal pada tahapan prosesnya baik dalam bentuk public hearing mapun public expose. Adanya perubahan dalam prosedur internal ini harus dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari ethics law untuk menghindari kemungkinan abuse of power terhadap anggaran publik. Secara fundamental ethics law, atau bentuk perundangan lain yang dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan, bertujuan untuk mencegah setiap pejabat publik menyalahgunakan – atau sekurang-kurangnya berniat untuk menyalahgunakan – kekuasaan dan status jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian setiap bentuk ethics law harus selalu memperhatikan 2 elemen penting. Pertama, bersifat mencegah (preventive) penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik bukan kepentingan atau manfaat pribadi. Melihat asumsi dasarnya yang lebih bersifat membatasi (restrictive) sangat mudah dipahami bila upaya mencapai tujuan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Ini disebabkan karena pada hakekatnya manusia bukan hanya sekedar homo religius namun juga homo economicus sekaligus. Status terakhir menempatkan manusia sebagai sosok yang lebih mengedepankan self-interest dan profit maximizer. Sangat kontradiktif bukan ? Dalam konteks terakhir inilah kita menengarai adanya sejumlah masalah yang secara potensial dapat menghambat komitmen terhadap urgensi legislasi etik ini. Pertama, bila penentuan standar etik bersifat terlalu membatasi (strict), hal itu justru akan membuat jabatan publik menjadi tidak begitu menarik. Dikombinasikan dengan peliputan media yang begitu intensif, ethics law yang terlalu ketat hanya akan menyebabkan keengganan, kecuali mungkin bagi mereka yang secara politis sangat ambisius. Selain itu, pelaksanaan ethics law yang terlalu ketat bagi sebagian legislator dipandang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kinerja mereka. Hal ini terutama applicable bagi anggota legislatif paruh waktu (part-time legislators), legislator yang menjadikan legislatif bukan sebagai profesi tapi sebagai ‘pekerjaan 4 sampingan’. Kedua, bertentangan dengan pandangan pertama, bila legislasi etik sifatnya sangat tersamar (vague), hal itu justru akan membuatnya menjadi tidak bermakna (meaningless). Jika pembatasan tidak dilakukan secara spesifik, atau tindakan tidak dirinci secara jelas, maksud dari ethics law akan menjadi bersifat terbuka untuk ditafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Ketiga, masalah independensi. Seperti dipahami bersama bahwa secara legal-formal legislatif memiliki independensi yang tinggi karena memiliki kewenangan yang bersifat eksklusif dalam law making, budgeting dan controlling, serta sejumlah hak kelembagaan lain yang bersifat istimewa (priviledges) seperti perlindungan dalam kebebasan berbicara, perlindungan istimewa dari pemeriksaan dan penahanan, kekuasaan untuk menentukan kualifikasi setiap anggotanya serta kekuasaan untuk mendisiplinkan bahkan mengeluarkan anggotanya. Dengan adanya legislasi etik kewenangan tersebut secara signifikan akan berkurang karena diambil alih secara kelembagaan oleh komisi etik ekstra-legislatif yang diberi kewenangan investigasi dan kekuasaan penegakan hukum berupa sanksi pidana maupun perdata. Kekhawatiran seperti ini hanya akan membuat meningkatkan potensi resistensi dari legislatif bodies terhadap ethics law dengan dalih mempertahankan independensi mereka. Bila memang ethics law telah menjadi keputusan, apa yang secara normatif harus diatur didalamnya ? Karena ethics law sifatnya preventif dan bersifat membatasi, maka secara prinsipil ada 5 kategori pembatasan (restrictions) yang harus dipertimbangkan dalam isi ethics law. Pertama, prinsip hal-hal yang bersifat resmi (official matters), yaitu restriksi terhadap penggunaan jabatan untuk keuntungan ekonomi, kontrak, pekerjaan dan hak-hak istimewa bagi legislator dan rekanan dekatnya. Kedua, prinsip keuntungan pribadi (personal gain), yaitu restriksi terhadap partisipasi legislatif dalam sidang atau tindakan komisi bila hal itu menyangkut kepentingan pribadi legislator maupun rekanannya. Ketiga, prinsip keuntungan privat (private gain), yaitu restriksi terhadap penggunaan sumberdaya publik untuk kepentingan privat. Keempat, prinsip hadiah (gifts), yaitu restriksi terhadap penerimaan hadiah, layanan dan hal menguntungkan lainnya (favoritsm) bagi legislator atau rekanannya. Kelima, prinsip ketidak-patutan (improper), yaitu restriksi 5 terhadap representasi klien didepan legislator dan agensi pemerintah bila hal itu menyangkut kepentingan rekanan legislator. Kelima prinsip tadi dimaksudkan sebagai pedoman (guidelines) bagi para pejabat publik pada umumnya dan legislator pada khususnya dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kejelasan prinsip tersebut juga diyakini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya konflik tanggungjawab (conflict of responsibility) dari para pejabat publik yang diakibatkan oleh adanya conflict of role, conflict of authority dan conflict of interest. Komisi Etik : Perspektif Kelembagaan Dalam hal ethics law telah diadopsi pertanyaan mendasar berikutnya adalah : siapa yang akan mengawal dan menegakan law tersebut ? Disinilah kita bersinggungan dengan aspek kelembagaan, karena nilai-nilai yang ada dalam law harus dapat melembaga dalam praktek. Ada beberapa pendekatan atau model berbeda yang dapat dipergunakan dalam mengelola dan menegakan legislasi etik. Pertama, menciptakan komisi etik didalam legislatif itu sendiri. Model ini dipandang sebagai model tradisional dan konservatif karena keanggotaan komisi etik hanya terbatas pada legislator saja. Berdasarkan model ini problem etika lebih dipandang sebagai urusan interen legislatif. Walaupun disatu sisi model ini sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena secara jelas dapat melindungi independensi legislatif, namun disisi lain oleh sejumlah pihak (publik dan anggota dewan yang reformis) dianggap tidak efektif dan kurang independen dalam memutus masalah etis yang ada. Kedua, melalui amandemen konstitusi dan peraturan perundangan lain dapat dibentuk sebuah komisi etik sebagai bagian dari eksekutif atau sebuah agensi independen yang diberi kewenangan luas untuk mengawasi penegakan hukum etik yang berlaku tidak hanya bagi legislator saja tetapi juga pejabat dan pegawai publik bahkan pejabat yudikatif. Berkaitan dengan anggota komisi etik, hal ini sangat tergantung pada pilihan model. Bila model pertama yang dipilih, akan muncul kecenderungan kuat untuk sedikit memberi ruang partisipasi publik sebagai anggota komisi karena telah terjadi internalisasi masalah etik di legislatif. Sebaliknya, ruang bagi partisipasi publik sebagai anggota komisi akan lebih terbuka bila model kedua yang dipilih, apalagi 6 bila bentuk kelembagaannya adalah agensi independen. Siapa pun yang dipilih sebagai anggota komisi ia sepatutnya mempunyai integritas moral, kompetensi serta sikap independen atau non-partisan, sehingga dapat secara objektif dan proporsional memutus masalah pelanggaran etik yang ada. Deliberasi Publik : Prasyarat Awal Melihat solusi tuntas dan komprehensif tentang penegakan hukum etik ini baru sebatas ekspektasi publik sementara dalam ragam tindakan tidak etik sudah demikian akut dalam lembaga-kekuasaan, maka harus ditempuh berbagai cara untuk membangun semacam common ground diantara publik dengan mereka. Lord Lindsay pernah menulis bahwa kunci demokrasi adalah adanya potensi atau peluang bagi diskusi. Diskusi yang baik akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Dalam konteks ini publik dapat merencanakan tercapainya common ground tersebut melalui diskusi yang fokus pada nilai dan pemahaman bersama. Tanpa ada keduanya (nilai dan pemahaman bersama) seringkali diskusi hanya akan menghasilkan debat kusir. Untuk itu perlu adanya ukuran-ukuran persamaan sosial dan persamaan akses terhadap informasi karena diskusi yang ideal terjadi hanya pada pihak-pihak yang dipandang sederajat. Tidak ada hubungan subordinasi. Disinilah letak pentingnya deliberasi publik sebagai upaya sadar dalam menentukan tujuan-tujuan publik dan menemukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai tahapan awal setidaknya ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan dalam deliberasi publik ini. Pertama, fokus. Prasyarat paling mendasar dari deliberasi publik adalah publik atau masyarakat luas setuju untuk memfokuskan debat pada masalah yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu maupun kelompok. Sebelum suatu posisi diambil harus ada persetujuan yang luas tentang hakekat dari masalah utama yang dihadapi publik. Penyelewengan dana APBD, misalnya, yang tidak menyentuh langsung kepentingan publik seperti anggaran untuk purna bakti, dana operasional, dana studi banding ke luar negeri dsb dapat dijadikan sebagai entry point. Mengapa ? Karena publik setuju bahwa tindakan penyelewengan kekuasaan tidak ada alasan pembenarnya baik secara legal, politik apalagi secara etik dan moral. Selain itu, wujud 7 dari penyelewengan itu bisa diukur besarannya. Angka kumulatif dari besaran penyelewengan APBD di sejumlah daerah seperti Padang, Payakumbuh, Palembang, Bandar Lampung, Garut dan daerah lain menurut perkiraan mencapai ratusan milyar rupiah. Lebih jauh lagi, hakekat dan akar masalahnya pun cukup jelas : tanggungjawab (responsibility). Tindakan tidak bertanggungjawab mereka disebabkan oleh kombinasi dari konflik kepentingan, konflik peran dan konflik kewenangan yang dimiliki secara tidak proporsional. Bila pada sisi publik deliberasi bisa menghasilkan kesepakatan luas tentang public-interest focused dan hakekat masalahnya, maka untuk meningkatkan leverage effect dibutuhkan peran sentral media massa. Hal ini disebabkan karena perbincangan tentang banyak masalah publik, terutama antara pejabat dengan warganya, seringkali menggunakan komunikasi media massa. Sepanjang media massa mempunyai concern yang kuat terhadap public interest melalui konsistensi peliputannya serta efek teknologis yang dimilikinya terhadap perubahan sosiopolitik, maka pengaruh media massa terhadap proses pembuatan kebijakan publik terlalu signifikan untuk diabaikan. Pada titik inilah kita berharap bahwa kesepakatan publik hasil deliberasi dapat didorong lebih lanjut dalam agenda kebijakan, apakah agenda sistemik maupun agenda institusional. Kedua, norm-setting. Norm-setting berkaitan dengan upaya untuk menentukan kapan kondisi tertentu dapat dianggap sebagai masalah kebijakan. Bila publik telah bersepakat bahwa penyelewengan yang dilakukan legislatif, baik secara individual dan institusional, merupakan bentuk pelanggaran berat sementara pihak legislatif menganggapnya bukan sebagai unethical behaviour karena telah berdasarkan UU atau PP yang mengaturnya, itu merupakan cermin bahwa norm-setting belum terbentuk. Karena itu sangat diperlukan adanya pertukaran gagasan dan sikap kritis bersama agar tercipta kondisi dimana masalah yang dihadapi adalah masalah bersama yang mencakup lintas segmen sosial dan lintas kepentingan. Sebenarnya proses diskusi atau deliberasi publik dilakukan secara segmented dalam sejumlah forum, namun satu sama lain saling terkait. Partai politik mendiskusikan rumusan program dan mengidentifikasi sejumlah masalah bagi kepentingan pemilu; Pemilih mendiskusikan masalah dan kandidat; Legislatif 8 mencoba menterjemahkan program ke dalam perundangan setelah melakukan serangkaian debat dengan pihak-pihak yang berbeda kepentingan; Eksekutif mendiskusikan bagaimana melaksanakan kebijakan; dan pengadilan yang menyediakan dorongan bagi agensi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyajikan argumen mereka yang paling kuat dalam kasus terjadi perselisihan hukum. Pendeknya, debat dan persuasi terjadi di setiap level proses dengan fungsi khusus oleh masing-masing organ deliberasi publik, dalam hal ini parpol, pemilih, legislatif, eksekutif dan pengadilan. Mereka berdebat dalam bentuk dan sudut pandang yang berebeda. Namun karena mereka mendiskusikan masalah yang sama yang saling berkaitan, maka semuanya akan memberikan kontribusi terhadap solusi secara keseluruhan. Untuk itulah menjadi urgen upaya untuk melakukan pelembagaan deliberasi publik ini. Disini diperlukan sejumlah prosedur yang disusun dengan maksud menjamin bahwa setiap opini dari pihak manapun didengarkan tanpa harus ada kewajiban untuk sampai pada kesimpulan bersama. Bentuk-bentuk seperti public hearing, public expose, public dialogue dan forum pengungkapan informasi lain secara terbuka perlu dikembangkan. Dalam tahapan kedua ini diharapkan ada semacam collective awareness bahwa kasus-kasus yang menyangkut penyelewengan dan APBD, misalnya, akan memberikan dampak negatif berupa arus balik kritik publik terhadap keberadaan legislatif sebagai lembaga yang mewakili aspirasi dan kepentingan publik. Munculnya beragam demonstrasi atas kinerja dewan dan expose media massa atasnya harus dimaknai sebagai ekspektasi publik untuk mengembalikan legislatif pada fungsi pokoknya yang hakiki : responsible law-making and representing public interest. Harus ada kesadaran baru dari legislatif untuk back to basics melalui kesepakatan bersama untuk mencari solusi masalah yang dihadapi dengan menentukan norma-norma yang sifatnya mengatur dan mengikat, baik secara individual maupun kelembagaan. Langkah awal untuk mewujudkannya adalah melalui legislasi etik yang didalamnya mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sebagai wakil rakyat. 9 Prospek Difahami bahwa mendorong komitmen yang kuat dari legislatif untuk mau melakukan self-regulated melalui legislasi etik bukan merupakan tugas yang mudah. Sejumlah indikasi menunjukan derajat resistensi yang cukup tinggi untuk melakukan legislative reform karena hal itu hakekatnya hanya akan mengurangi power yang begitu besar mereka miliki sekarang. Namun penulis melihat ke depan prospek legislasi etik ini cukup terbuka melihat momentum dan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Ada sejumlah hal yang mengukuhkan optimisme tersebut. Pertama, ekspos media massa yang cukup intens terhadap unethical behaviour yang dilakukan legislatif. Media massa nasional maupun daerah selama bulan-bulan terakhir ini cukup intens mengungkap sejumlah kasus legislative abuse of power, baik dalam bentuk news maupun editorial. Mayoritas penyimpangan berbentuk penyalahgunaan dana publik (APBN/APBD) serta bentuk transaksional lainnya untuk sejumlah aktivitas yang secara langsung lebih menguntungkan mereka (secara pribadi atau lembaga) dibanding kepentingan publik. Ternyata peliputan tersebut telah turut mendorong reaksi dan tindakan publik yang terorganisasi. Beberapa diantara kasus (seperti sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah, anggota DPR/DPRD, serta beberapa Ketua Umum Partai) upaya penegakan hukumnya sudah sesuai dengan ekspektasi publik. Sanksi pidana yang dijatuhkan bukan hanya cukup berat, tepai juga disertai dengan pencabutan hak politik mereka. Kedua, hasil pemilu Legislatif. Ada secercah harapan melihat hasil pemilu legislatif april lalu. Di tingkat nasional maupun di tingkat lokal komposisi legislatif melibatkan lebih banyak pihak dengan perubahan komposisi yang cukup signifikan. Adanya sirkulasi anggota legislatif dengan muka baru memunculkan optimisme akan adanya potensi dorongan perubahan karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kaitan langsung dengan sistem lama. Selain itu, komposisi SDM anggota legislatif baru secara kualitatif (setidaknya berdasarkan taraf pendidikan) dipandang lebih baik. Idealnya kondisi ini akan memberikan citra berbeda dalam proses diskusi dan deliberasi publik ke depan sehingga kebijakan publik yang dihasilkan diharapkan akan lebih aspiratif lagi. 10 Ketiga, masyakat yang semakin well-educated dan well-informed. Publik sekarang ditandai oleh tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi yang lebih baik. Terima kasih terhadap akses pendidikan yang lebih terbuka luas serta perkembangan teknologi informasi (TI) yang begitu cepat. Setiap bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh legislatif di suatu daerah, misalnya, akan begitu cepat dikritisi dan disebarluaskan pada masyarakat luas. Dengan sentralitas media massa, adanya efek domino ke daerah lain menjadi sebuah keniscayaan. Kondisi ini tentu mengharuskan legislatif untuk selalu menunjukan daya tanggap (responsiveness) terhadap kecenderungan tuntutan perubahan yang diinginkan publik. Dengan tiga kecenderungan tersebut terdapat cukup alasan bila kita mendesak pada legislatif baru untuk tidak hanya sekedar mempertimbangkannya namun lebih jauh mengagendakan legislasi etik sebagai salah satu agenda mendesak karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk mewujudkan trustworthy government atau pemerintahan yang amanah. -------------------Dosen Senior di FISIP Universitas Djuanda, Bogor dan alumnus University of Wisconsin-Madison, USA. Alamat email ; [email protected]. 11