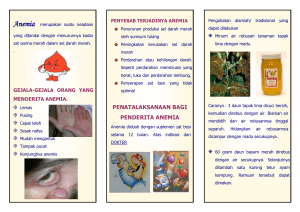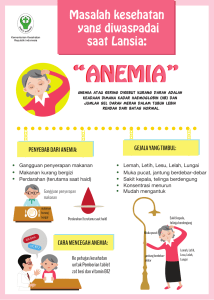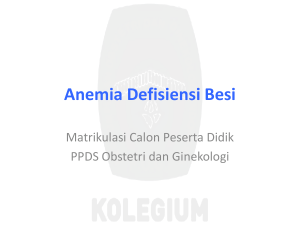PRESENTASI KASUS CHRONIC KIDNEY DISEASE DENGAN ANEMIA Pembimbing : dr. Much. Maschun Syarifudin, Sp.PD Disusun oleh : Ilham Pribadi 1710221089 Irma Rizki Hidayati 1710221069 Karunia Putri Amalia G4A016078 Erine Della Aprila G4A016074 Ika Tyas Agus Pratiwi G4A016076 FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN SMF ILMU PENYAKIT DALAM RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARDJO PURWOKERTO 2018 LEMBAR PENGESAHAN CHRONIC KIDNEY DISEASE DENGAN ANEMIA Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti program profesi dokter di Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Disusun oleh : Ilham Pribadi 1710221089 Irma Rizki Hidayati 1710221069 Karunia Putri Amalia G4A016078 Erine Della Aprila G4A016074 Ika Tyas Agus Pratiwi G4A016076 Telah dipresentasikan pada Tanggal, Februari 2018 Pembimbing, dr. Much. Maschun Syarifudin, Sp.PD 2 I. PENDAHULUAN Perubahan pola penyakit tanpa disadari telah memberi pengaruh terhadap terjadinya transisi epidemiologi, dengan semakin meningkatnya kasus-kasus tidak menular. Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2005 proporsi kesakitan dan kemaitan di dunia yang disebabkan oleh penyakit tidak menular sebesar 47% morbiditas dan 54% mortalitas, dan diperkirakan pada tahun 2020 proporsi morbiditas ini akan meningkat menjadi 60% dan proporsi mortalitas menjadi 73%. Angkat penyakit tidak menular yang juga mengalami peningkatan adalah penyakit ginjal kronik (PGK) (Bustan, 2015). Ginjal merupakan organ penting yang berfungsi menjaga komposisi darah dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh, mejaga level elektrolit seperti natrium, kalium dan fosfat tetap stabil, serta memproduksi hormon dan enzim yang membantu dalam mengendalikan tekanan darah, membuat sel darah dan menjaga tulang tetap kuat (Kemenkes RI, 2017). Penyakit ginjal kronis (PGK) merupakan masalah kesehatan global dengan prevalens dan insidens gagal ginjal yang meningkat, prognosis yang buruk dan biaya yang tinggi. Prevalensi PGK meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kejadian penyakit diabetes melitus serta hipertensi. Sekitar 1 dari 10 populasi dunia mengalami PGK pada stadium tertentu. Hasil systematic reiew dan metanalisis yang dilakukan oleh Hill et al., 2016 mendapatkan prevalensi global PGK sebesar 13,4%. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010. Jumlah penderita PGK di Indonesia pada tahun 2011 tercatat 22.304 dengan 68,8% kasus baru dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 28.782 dengan 68,1 kasus baru (PERNEFRI, 2012). Menurut dara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, PGK masuk dalam daftar 10 penyakit tidak menular. Sedangkan di Indonesia, perawatan penyakit ginjal merupakan ranking kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung (Kemenkes RI, 2017). 3 PGK biasanya tidak memiliki gejala atau asimtomatik, tetapi dapat terdeteksi, dan tes untuk menguji PGK sangat mudah dan tersedia di berbagai tempat. terdapat bukti bahwa tatalaksana dapat mencegah atau menunda progresitas dari PGK, mengurangi atau mencegah perkembagan komplikasi dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bagaimanapun juga PGK sering tidak dapat diketahui karena tidak ada gejala yang spesifik, dan sering tidak terdiagnosis atau terdiagnosis pada stadium akhir (NICE, 2014). 4 II. STATUS PASIEN A. IDENTITAS PENDERITA Nama : S Umur : 39 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Gumiwang RT 4 RW 9, Purwanegara Pekerjaan : Wiraswasta Agama : ISLAM No RM : 02018604 Tgl. Masuk RS : 19/02/2018 Tgl Periksa : 22/02/2018 Bangsal : Asoka B. ANAMNESIS 1. Keluhan utama : lemas 2. Riwayat Penyakit Sekarang Pasien datang ke poli penyakit dalam Rumah sakit margono soekarjo pada tanggal 19 Januari 2018 dengan keluhan utama lemas. Lemas dirasakan sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit. Selain itu, pasien juga mengeluhkan nyeri pada ulu hati disertai mual. Keluhan mual timbul ketika pasien sedang akan makan maupun tidak. Keluhan tersebut sangat mengganggu pasien hingga pasien muntah. Keluhan membaik ketika pasien meminum obat antimual namun tidak lama setelah itu akan timbul kembali. Keluhan memberat ketika pasien akan makan. Pasien juga mengeluhkan kepala terasa pusing, pusing dirasakan seperti pasien akan jatuh. 3. Riwayat Penyakit Dahulu a. Riwayat hipertensi : diakui b. Riwayat DM : disangkal c. Riwayat penyakit jantung : disangkal 5 d. Riwayat penyakit ginjal : diakui, rutin HD e. Riwayat alergi : disangkal ` f. Riwayat sakit kuning : disangkal g. Riwayat stroke : disangkal 4. Riwayat Penyakit Keluarga a. Riwayat hipertensi : disangkal b. Riwayat DM : disangkal c. Riwayat penyakit jantung : disangkal d. Riwayat penyakit ginjal : disangkal e. Riwayat alergi : disangkal ` 5. Riwayat Sosial Ekonomi a. Community Pasien tinggal bersama dengan istri dan anaknya. Pasien tinggal di rumah yang berukuran 18x10 m dan berisikan 4 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dapur. Lantai rumah sudah menggunakan keramik dan pencahayaan rumah diakui pasien cukup. b. Occupational Pasien adalah seorang wiraswasta yang bekerja pada pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 16.00 WIB. c. Personal Habit Pasien memiliki kebiasaan olahraga sewaktu muda. Kebiasaan merokok diakui oleh pasien. d. Drugs and Diet Pasien rutin hemodialisa. Pasien tidak pernah mengkonsumsi minuman beralkohol. Menu makan pasien terdiri dari nasi, banyak sayurmayur, dan lauk-pauk. Pasien makan 3 kali sehari. 6 C. PEMERIKSAAN FISIK Keadaan Umum : Tampak sakit sedang Kesadaran : Compos mentis Vital Sign : TD : 190/100 mmhg N : 77x/menit RR : 20 x/menit S : 36.5 OC BB/TB : 48 kg/163 cm Status Generalis Pemeriksaan Kepala Bentuk Kepala : Mesochepal, simetris, venektasi temporal (-) Rambut : Warna hitam, mudah rontok (-), distribusi merata Pemeriksaan Mata Palpebra : Edema (-/-), ptosis (-/-) Konjunctiva : Anemis (+/+) Sklera : Ikterik (-/-) Pupil : Reflek cahaya (+/+), isokor Ø 3 mm Pemeriksaan Telinga : Otore (-/-), deformitas (-/-), nyeri tekan (-/-) Pemeriksaan Hidung : Nafas cuping hidung (-/-), deformitas (-/-), rinore (-/-) Pemeriksaan Mulut : Bibir sianosis (-), tepi hiperemis (-), bibir kering (-), lidah kotor (-), tremor (-), ikterik (-), sariawan (-) Pemeriksaan Leher Trakea : Deviasi trakea (-) Kelenjar Tiroid : Tidak membesar Kel. Limfonodi : Tidak membesar, nyeri tekan (-) JVP : Dalam batas normal, 5+2 cmH2O Status Lokalis Paru-Paru 7 Inspeksi : Hemithorax dextra = sinistra, ketinggalan gerak (-) Palpasi : Vocal fremitus apex dextra = sinistra Vocal fremitus basal dextra = sinistra Perkusi : Sonor, batas paru hepar SIC V LMCD Auskultasi : SD vesikuler +/+, Ronkhi -/-, Wheezing -/- Jantung Inspeksi : Ictus cordis tidak tampak Palpasi : Ictus cordis teraba di SIC VI 2 jari medial LMCS, kuat angkat (-) Perkusi Auskultasi : Batas Jantung Kanan atas : SIC II LPSD Kanan bawah : SIC V LPSD Kiri bawah : SIC VI, 2 jari medial LMCS : S1>S2 Reguler, Murmur (-), Gallop (-) Abdomen Inspeksi : Cembung Auskultasi : Bising usus (+) normal Perkusi : Timpani, pekak sisi (-), pekak alih (-) Palpasi : Supel, nyeri tekan (-), undulasi (-) Hepar : Tidak teraba pembesaran Lien : Tidak teraba pembesaran 8 Extremitas Pemeriksaan Ekstremitas superior Ekstremitas inferior Dextra Dextra Sinistra Sinistra Edema - - - - Sianosis - - - - Kuku kuning (ikterik) Akral dingin - - - - - - - - + + + + Reflek fisiologis Bicep/tricep Patela Reflek patologis Reflek babinsky Sensoris - - - - D=S D=S D=S D=S D. PEMERIKSAAN PENUNJANG Pemeriksaan Laboratorium DL 15/02/18 08:11 Pemeriksaan Darah Lengkap Hemoglobin Leukosit Hematokrit Eritrosit Trombosit MCV MCH MCHC RDW MPV Hasil Nilai Rujukan 5.3 L 5300 L 16 L 2.1 L 92000 L 77 L 25 L 33 50.0 H 6.6 L 11,2 – 17,3 g/dL 3800 –10600 U/L 40– 52 % 4,4 – 5,9 ^6/uL 150.000– 440.000 /uL 80 – 100 fL 26 – 34 Pg/cell 32 – 36 % 11,5 – 14,5 % 9,4 – 12,4 fL 9 Kimia Klinik Ureum Darah Kreatinin Darah 171.6 H 14.00 H 14,98 – 38,52 mg/dL 0,80 – 1,30 mg/dL Pemeriksaan Laboratorium DL 22/02/18 Pemeriksaan Darah Lengkap Hemoglobin Leukosit Hematokrit Eritrosit Trombosit MCV MCH MCHC RDW MPV Hasil Nilai Rujukan 8.2 L 3680 24 L 3.0 L 105000 80.0 27.8 34.7 15.8 H 8.5 L 11,2 – 17,3 g/dL 3800 –10600 U/L 40– 52 % 4,4 – 5,9 ^6/uL 150.000– 440.000 /uL 80 – 100 fL 26 – 34 Pg/cell 32 – 36 % 11,5 – 14,5 % 9,4 – 12,4 fL E. DIAGNOSIS KERJA - CKD - Anemia 10 F. TERAPI - Inf kidmin 200cc/24 jam - Inj furosemid 1 amp/24 jam - Transfusi prc hingga hb>10 dengan premedikasi lasik 1 amp - Po asam folat 3x1 - Po calos 3x1 - Po adfer 3x1 - Po valsartan 1x160 mg - Po Amlodipin 1x10 mg - HD G. PROGNOSIS a. Ad vitam : dubia ad malam b. Ad functionam : dubia ad malam c. Ad sanationam : dubia ad malam HASIL FOLLOW UP Tanggal 23/02/18 S-O A P Subyektif: CKD - Inf kidmin 200cc/24 jam Badan masih Anemia - Inj furosemid 1 amp/24 jam terasa lemas, - Po asam folat 3x1 mual dan muntah - Po calos 3x1 berkurang - Po adfer 3x1 - Po valsartan 1x160 mg Obyektif: - Po Amlodipin 1x10 mg TD : 160/100 BLPL: mmHg - Po asam folat 3x1 Nadi : 82x/menit - Po calos 3x1 11 RR : 20x/menit - Po adfer 3x1 Suhu: 37.1 C - Po valsartan 1x160 mg - Po Amlodipin 1x10 mg 12 III. TINJAUAN PUSTAKA A. CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD ) 1. Definisi Chronic Kidney Disease (CKD) adalah kerusakan fungsi ginjal ireversibel yang memberikan efek pada hampir seluruh sistem organ. Kidney Disease Quality Outcome Initiative (K/DOQI) mendefinisikan CKD sebagai kerusakan ginjal atau Glomerular Filtration Rate (GFR) < 60 mL/min/1.73 m2 selama 3 bulan atau lebih (Levey et., al., 2005). Pasien dengan CKD akan memiliki perjalanan penyakit yang progresif menuju End Stage Renal Disease (ESRD) (McCance dan Sue, 2006). 2. Klasifikasi Chronic Kidney Disease diklasifikasikan menjadi 5 derajat yang dilihat dari derajat penyakit dan nilai GFR/LFG, semakin besar derajat CKD prognosis penyakit akan semakin buruk. Tabel 3.1. Klasifikasi CKD (Eknoyan, 2009; Levey et., al., 2005) Derajat Deskripsi 1 4 Kerusakan ginjal dengan GFR Normal atau meningkat Kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan Penurunan GFR sedang Penurunan GFR berat 5 Gagal ginjal 2 3 Klasifikasi Berdasarkan Keparahan GFR Keadaan Klinis mL/min/1.73 m2 Albuminuria, ≥ 90 proteinuria, hematuria Albuminuria, 60-89 proteinuria, hematuria Insufisiensi ginjal 30-59 kronik Insufisiensi ginjal 15-29 kronik, pre-ESRD < 15 Gagal ginjal, Atau dialisis uremia, ESRD 13 3. Etiologi Beberapa penyebab terjadinya CKD antara lain (Sudoyo, 2006) : a. Gangguan imunologis 1) Glomerulonefritis 2) Poliartritis nodosa 3) Lupus eritematous b. Gangguan metabolik 1) Diabetes Mellitus 2) Amiloidosis 3) Nefropati Diabetik c. Gangguan pembuluh darah ginjal 1) Arterisklerosis 2) Nefrosklerosis d. Infeksi 1) Pielonefritis 2) Tuberkulosis e. Gangguan tubulus primer Nefrotoksin (analgesik, logam berat) f. Obstruksi traktus urinarius 1) Batu ginjal 2) Hipertopi prostat 3) Konstriksi uretra g. Kelainan kongenital 1) Penyakit polikistik 2) Tidak adanya jaringan ginjal yang bersifat kongenital (hipoplasia renalis) 4. Epidemiologi Insidens penyakit CKD di Amerika Serikat diperkirakan sejumlah 100 juta kasus perjuta penduduk per tahun, dan angka ini meningkat sekitar 14 8% setiap tahunnya. Terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal pertahunnya di Malaysia, dandi negara berkembang lainnya, insidensi ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus perjuta penduduk per tahun.Penyakit gagal ginjal kronik lebih sering terjadi pada pria daripada wanita.Insidennya pun lebih sering pada kulit berwarna hitam daripada kulit putih(Suwitra, 2007). Beberapa penyebab CKD yang menjalani hemodialisis di Indonesia pada tahun 2000 antara lain Glomerulonefritis(46,39%), Diabetes Mellitus(18,65%), Obstruksi dan infeksi (12,85%), Hipertensi(8,46%), dan penyebab yang lain dengan presentase sebesar (13,65%) (Murray et al, 2007). 5. Patofisiologi CKD merupakan keadaan gangguan fungsi ginjal progresif yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, namun hipertensi dan diabetes mellitus merupakan 2 buah penyebab yang paling sering mendasari terjadinya CKD (McCance dan Sue, 2006). Penyebab lain yang dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal progresif adalah reduksi massa ginjal dikarenakan infeksi dan obstruksi ginjal (Lopez-Novoa et., al., 2010). Nefropati Hipertensif Hipertensi dapat mengakibatkan terjadinya CKD melalui beberapa mekanisme: a. Vaskulopati ginjal yang terjadi pada arteri dan arteriol preglomerular. Vaskulopati yang terjadi diakibatkan oleh aterosklerosis, disfungsi endotel, penebalan dinding pembuluh darah, serta fibrosis pada hipertensi b. Kerusakan mikrovaskuler pada kapiler glomerulus c. Kerusakan barrier filtrasi (podosit, sel mesangial, dan membrana basalis) di glomerulus karena glumerulosklerosis. d. Fibrosis interstitial. 15 Hipertensi dapat meningkatkan aliran darah ginjal pada glomerulus yang secara progresif akan menyebabkan kerusakan endotel dan barrier filtrasi glomerulus. Kerusakan sel tersebut akan diikuti inflamasi yang menyebabkan kematian sel podosit dan sel mesangial. Disfungsi endotel akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga mengurangi aliran darah ke glomerulus ginjal. Penurunan aliran darah akan diikuti penurunan tekanan glomerulus yang mengakibatkan penurunan pada GFR. Inflamasi dan kematian sel yang terjadi akibat kerusakan pada ginjal akan menyebabkan fibrosis dan glomerulosklerosis(Lopez-Novoa et., al., 2010). Fibrosis dan glomerulosklerosis menyebabkan tereduksinya kemampuan ginjal untuk melakukan fungsinya. Keadaan ini dikompensasi oleh tubuh dengan mengeluarkan zat vasoaktif dan growth factor yang menyebabkan hipertrofi structural dari neuron yang tersisa.Usaha tersebut dalam tujuan mengembalikan fungsi normal ginjal, dalam keadaan ini LFG dapat normal atau bahkan meningkat. Hipertrofi ginjal secara progresif akan berubah menjadi fungsi yang tidak sesuai oleh Karena tingginya beban kerja yang harus ditanggung. Hipertrofi glomerulus berlanjut menjadi glomerulosklerosis sehingga menurunkan aliran darah ginjal. Penurunan aliran darah ginjal tersebut akan diikuti penurunan tekanan darah pada glomerulus yang menyebabkan penurunan GFR (Lopez-Novoa et., al., 2010). Perjalanan penyakit CKD secara umum terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu (McCance dan Sue, 2006): a. Penurunan Fungsi Ginjal. Penurunan fungsi ginjal ditandai dengan GFR < 50%. Pada keadaan ini, tanda dan gejala CKD belum muncul, namun sudah terdapat peningkatan pada ureum dan kreatinin darah. b. Insufisiensi Ginjal. Insufisiensi ginjal menandakan bahwa ginjal sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara normal, pada keadaan ini GFR 16 mengalami penurunan yang bermakna. Tanda dan gejala serta disfungsi ginjal yang ringan sudah muncul. Nefron yang masih berfungsi akan melakukan kompensasi untuk memaksimalkan fungsi ginjal. Kelainan konsentrasi urin, nokturia, anemia ringan, dan gangguan fungsi ginjal saat stres dapat terjadi pada tahapan ini. c. Gagal Ginjal. Keadaan gagal ginjal dikarakteristikan dengan azotemia, asidosis, ketidakseimbangankonsentrasi urin, anemia berat, dan gangguan elektrolit (hipernatremia, hiperkalemia, dan hiperpospatemia). Keadaan gagal ginjal terjadi saat GFR < 20% dan penyakit mulai memberikan efek pada sistem organ lain. d. ESRD. End Stage Renal Disease merupakan tahapan terakhir dari gangguan fungsi ginjal. Fungsi filtrasi ginjal mengalami gangguan yang berat. GFR hampir tidak ada lagi. Kemampuan reabsorbsi dan ekskresi juga terganggu, dikarenakan perubahan yang besar dari elektrolit, regulasi cairan, dan gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan kardiovaskuler, hematologi, neurologi, gastrointestinal, endokrin, metabolik, gangguan tulang dan mineral juga dapat terjadi. 17 Jumlah Nefron ↓ Hiperfiltrasi Adaptative Glomerolus ↑ Permeabilitas Glomerolus ↑ RAAS ↑ SNGFR HT ↑ Filtrasi Makromolekul dan Protein Protenuria Inflamasi nefrotoksik atau remodelling Fibrosis tubulointerstisial dan focal glomerulosclerosis ↓ GFR ↓ EPO Anemia Uremia Disfungsi Platelet ↑ Tendensi Perdarahan ↓ Urine Output Gangguan ekskresi Na, Air dan K Edema perifer dan pulmo Komplikasi Sistemik Gangguan kadar serum PO4, vit D, PTH Hiperparathyroidism sekunder Gambar 3.1. Patofisiologi CKD(Lopez-Novoa et., al., 2010) 6. Manifestasi Klinis Manifestasi klinis CKD terdiri dari kelainan hemopoeisis, saluran cerna, mata, kulit, selaput serosa, dan kelainan kardiovaskular (Murray et al., 2007). 18 a. Kelainan hemopoeisis Anemia normokrom normositer dan normositer (MCV 78-94 CU), sering ditemukan pada pasien gagalginjalkronik. Anemia pada pasien gagal ginjal kronik terutama disebabkan oleh defisiensi eritropoetin. Hal lain yang ikut berperan dalam terjadinya anemia adalah defisiensi besi, kehilangan darah (misal perdarahan saluran cerna, hematuri), masa hidup eritrosit yang pendek akibat terjadinya hemolisis, defisiensi asam folat, penekanan sumsum tulang oleh substansi uremik, proses inflamasi akut ataupun kronik (Suwitra, 2007). Evaluasi terhadap anemia dimulai saat kadar hemoglobin < 10 g/dL atau hematokrit < 30 %, meliputi evaluasi terhadap status besi (kadar besi serum / serum iron, kapasitas ikat besi total / Total Iron binding Capacity(TIBC), feritin serum), mencari sumber perdarahan, morfologi eritrosit, kemungkinan adanya hemolisis dan sebagainya (Murray et al., 2007; Suwitra, 2007). Penatalaksanaan terutama ditujukan pada penyebab utamanya, di samping penyebab lain bila ditemukan. Pemberian eritropoetin (EPO) merupakan hal yang dianjurkan. Pemberian tranfusi pada penyakit ginjal kronik harus dilakukan hati-hati, berdasarkan indikasi yang tepat dan pemantauan yang cermat. Tranfusi darah yang dilakukan secara tidak cermat mengakibatkan kelebihan cairan tubuh, hiperkalemia, dan perburukan fungsi ginjal. Sasaran hemoglobin menurut berbagai studi klinik adalah 11-12 g/dL (Suwitra, 2007). b. Kelainan saluran cerna Mual dan muntah sering merupakan keluhan utama dari sebagian pasien gagal ginjal kronik terutama pada stadium terminal. Patogenesis mual dan muntah masih belum jelas, diduga mempunyai hubungan dengan dekompresi oleh flora usus sehingga terbentuk amonia. Amonia inilah yang menyebabkan iritasi atau rangsangan mukosa lambung dan usus halus. Keluhan-keluhan saluran cerna ini akan segera mereda atau 19 hilang setelah pembatasan diet protein dan antibiotika(Murray et al., 2007). c. Kelainan mata Visus hilang (azotemia amaurosis) hanya dijumpai pada sebagian kecil pasien gagal ginjal kronik. Gangguan visus cepat hilang setelah beberapa hari mendapat pengobatan gagal ginjal kronik yang adekuat, misalnya hemodialisis. Kelainan saraf mata menimbulkan gejala nistagmus, miosis dan pupil asimetris. Kelainan retina (retinopati) mungkin disebabkan hipertensi maupun anemia yang sering dijumpai pada pasien gagal ginjal kronik. Penimbunan atau deposit garam kalsium pada conjunctiva menyebabkan gejala red eye syndrome akibat iritasi dan hipervaskularisasi. Keratopati mungkin juga dijumpai pada beberapa pasien gagal ginjal kronik akibat penyulit hiperparatiroidisme sekunder atau tersier(Murray et al., 2007). d. Kelainan kulit Gatal sering mengganggu pasien, patogenesisnya masih belum jelas dan diduga berhubungan dengan hiperparatiroidisme sekunder. Keluhan gatal ini akan segera hilang setelah tindakan paratiroidektomi. Kulit biasanya kering dan bersisik, tidak jarang dijumpai timbunan kristal urea pada kulit muka dan dinamakan urea frost(Kumar et al., 2007). e. Kelainan kardiovaskular Patogenesis Gagal Jantung Kongestif (GJK) pada gagal ginjal kronik sangat kompleks. Beberapa faktor seperti anemia, hipertensi, aterosklerosis, kalsifikasi sistem vaskular, sering dijumpai pada pasien gagal ginjal kronik terutama pada stadium terminal dan dapat menyebabkan kegagalan faal jantung(Murray et al., 2007). 20 7. Penegakan Diagnosis Penegakan diagnosis CKD berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik mengenai manifestasi klinis yang ada pada pasien dan dibantu hasil pemeriksaan penunjang. a. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 1) Sesuai dengan penyakit yang mendasarinya seperti DM, infeksi traktus urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, hiperurikemi, lupus Eritomatosus Sistemik (LES), dan lain sebagainya. 2) Sindrom uremia, yang terdiri dari lemah, letargi, anoreksia, mual, muntah, nokturia, kelebihan volume cairan, neuropati perifer, pruritus, perikarditis, kejang sampai koma. 3) Gejala komplikasinya, seperti anemia, asidosis metabolik, dan sebagainya. b. Pemeriksaan Laboratorium 1) Pemeriksaan darah Pada pemeriksaan darah ditemukan anemia normositik normokrom dan terdapat sel Burr pada uremia berat. Leukosit dan trombosit masih dalam batas normal. Klirens kreatinin meningkat melebihi laju filtrasi glomerulus dan turun menjadi kurang dari 5 ml/menit pada gagal ginjal terminal. Dapat ditemukan proteinuria 200-1000mg/hari. 2) Penurunan fungsi ginjal berupa peningkatan ureum dan kreatinin serum. 3) Kelainan biokimiawi darah seperti penurunan kadar hemoglobin dan asam urat. 4) Kelainan urinalisis meliputi proteinuria, hematuria dan leukosuria. c. Gambaran radiologis; 1) Foto polos abdomen, bisa tampak batu radio-opak 21 2) USG bisa memperlihatkanukuran ginjal yang mengecil, korteks yang menipis adanya hidronefrosis atau batu ginjal, kista, massa, kalsifikasi. d. Biopsi Biopsi dan pemeriksaan histopatologi ginjal dapat dilakukan pada penderita dengan ukuran ginjal yang masih mendekati normal, dimana diagnosis secara invasif sulit ditegakkan (Suwitra, 2007). 8. Penatalaksanaan Diagnosis CKD harus dilakukan berdasarkan klasifikasi etiologi dan patologi sehingga petugas kesehatan dapat merencanakan terapi yang tepat untuk mencegah progresi penyakit dan memperbaiki keadaan umum. Tujuan dari terapi CKD adalah (K/DOQI, 2002): a. Terapi Spesifik terhadap Penyakit Dasarnya Waktu yang paling tepat untuk terapi penyakit dasarnya adalah sebelum penurunan LFG, sehingga pemburukan fungsi ginjal tidak terjadi.Pada ukuran ginjal yang masih normal secara ultrasonografi, biopsi dan pemeriksaan histopatologi ginjal dapat menentukan indikasi yang tepat terhadap terapi spesifik.Sebaliknya, bila LFG sudah menurun sampai 20-30% dari normal, terapi terhadap penyakit dasarnya sudah tidak banyak bermanfaat (Suwitra, 2006). b. Pencegahan dan Terapi terhadap Kondisi Komorbid Penting untuk mengikuti dan mencatat kecepatan penurunan LFG pada pasien penyakit ginjal kronik.Hal ini untuk mengetahui kondisi komorbid yang dapat memperburuk keadaan pasien. Faktorfaktor komorbid ini antara lain gangguan keseimbangan cairan, hipertensi yang tidak terkontrol, infeksi traktus urinarius, obat-obat nefrotoksik, bahan radiokontras, atau peningkatan aktivitas penyakit dasarnya (Suwitra, 2006). c. Memperlambat Pemburukan Fungsi Ginjal 22 Faktor utama penyebab perburukan fungsi ginjal adalah terjadinya hiperfiltrasi glomerulus. Dua cara penting untuk mengurangi hiperfiltrasi glomerulus ini adalah dengan (Suwitra, 2006): 1) Pembatasan asupan protein Pembatasan mulai dilakukan pada LFG ≤ 60 ml/menit, sedangkan di atas nilai tersebut, pembatasan asupan protein tidak selalu dianjurkan. Protein diberikan 0,6-0,8/kgBB/hari, yang 0,350,50 gr di antaranya merupakan protein nilai biologi tinggi. Jumlah kalori yang diberikan sebesar 30-35 kkal/kgBB/hari.Bila terjadi malnutrisi, jumlah asupan kalori dan protein dapat ditingkatkan(Suwitra, 2006). Berbeda dengan lemak dan karbohidrat, kelebihan protein tidak disimpan dalam tubuh tapi dipecah menjadi urea dan substansi nitrogen lain, yang terutama diekskresikan melalui ginjal.Selain itu, makanan tinggi protein yang mengandung ion hydrogen, fosfat, sulfat, dan ion nonorganic lain juga diekskresikan melalui ginjal. Oleh karena itu, pemberian diet tinggi protein pada pasien penyakit ginjal kronik akan mengakibatkan penimbunan substansi nitrogen dan ion anorganik lain dan mengakibatkan gangguan klinis dan metabolic yang disebut uremia, dengan demikian pembatasan protein akan mengakibatkan berkurangnya sindrom uremik (Suwitra, 2006). Masalah penting lain adalah asupan protein berlebih akan mengakibatkan perubahan hemodinamik ginjal berupa peningkatan aliran darah dan tekanan intraglomerulus yang akan meningkatkan progresivitas pemburukan fungsi ginjal. Pembatasan asupan protein juga berkaitan dengan pembatasan asupan fosfat, karena protein dan fosfat selalu berasal dari sumber yang sama. Pembatasa fosfat perlu untuk mencegah terjadinya hiperfosfatemia (Suwitra, 2006). 2) Terapi farmakologis untuk mengurangi hipertensi intraglomerulus 23 Pemakaian obat antihipertensi, selain bermanfaat untuk memperkecil risiko kardiovaskular juga sangat penting untuk memperlambat pemburukan kerusakan nefron dengan mengurangi hipertensi intraglomerulus dan hipertrfi glomerulus.Selain itu, sasaran terapi farmakologis sangat terkait dengan derajat proteinuria, karena proteinuria merupakan factor risiko terjadinya pemburukan fungsi ginjal. Beberapa obat antihipertensi terutama golongan ACE inhibitormelalui berbagai studi terbukti dapat memperlambat proses pemburukan fungsi ginjal (Suwitra, 2006). d. Pencegahan dan Terapi terhadap Penyakit Kardiovaskular 40-45% kematian pada penyakit ginjal kronik disebabkan oleh penyakit kardiovaskular.Hal-hal yang termasuk dalam pencegahan dan terapi penyakit kardiovaskular adalah pengendalian diabetes, hipertensi, dislipidemia, anemia, hperfosfatemia, dan terapi terhadap cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit.Semua ini terkait dengan terapi dan pencegahan terhadap koplikasi penyakit ginjal kronik secara keseluruhan (Suwitra, 2006). e. Pencegahan dan Terapi terhadap Komplikasi Penyakit ginjal kronik mengakibatkan berbagai komplikasi yang manifestasinya sesuai dengan derajat penurunan fungsi ginjal yang terjadi, yaitu sebagai berikut (Suwitra, 2006): 1) Kerusakan ginjal dengan penurunan LFG ringan (LFG 60-89 ml/menit) : tekanan darah mulai meningkat 2) Penurunan LFG sedang (LFG 30-59 ml/menit) : hiperfosfatemia, hipokalsemia, anemia, hiperparatiroid, hipertensi, dan hiperhomosisteinemia 3) Penurunan LFG berat (LFG 15-29 ml/menit) : malnutrisi, asidosis metabolik, kecenderungan hiperkalemia, dan dislipidemia 4) Gagal ginjal (LFG < 15 ml/menit) : gagal jantung dan uremia f. Terapi Pengganti Ginjal berupa Dialisis atau Transplantasi 24 Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium 5, yaitu pada LFG ≤ 15 ml/menit.Terapi pengganti tersebut dapat berupa hemodialisis, peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2006).Monitoring balance cairan, tekanan darah, ureum, kreatinin, Hb, dan Gula darah juga perlu dilakukan untuk mecegah progresivitas penyakit untuk berkembang lebih cepat (K/DOQI, 2002). 9. Komplikasi Pasien dengan CKD akan mengalami peningkatan kadar urea dan serum darah karena gagalnya sekresi yang disebabkan oleh penurunan fungsi filtrasi pada glomerulus. Kalium juga merupakan ion yang disekresikan melalui ginjal. Pasien CKD akan mengalami keadaan hiperkalemia. Pasien CKD dapat mengalami veskulopati serta retensi cairan dalam tubuh. Vaskulopati dapat menyebabkan kerusakan endotel serta respon vasokonstriksi pembuluh darah yang berujung pada keadaan hipertensi. Retensi cairan yang terjadi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan overload cairan. Hasil limbah nitrogen (ureum dan kreatinin) dapat memicu reaksi inflamasi pada organ organ di sekitar ginjal. Reaksi inflamasi pada jantung yang diikuti dengan hipertensi dan overload cairan akan membebani kerja jantung. Jantung yang tidak dapat mengkompensasi akibat dari CKD dapat berakhir pada keadaan gagal jantung kongestif (CHF). CHF yang berkelanjutan dapat mengakibatkan edema pulmo apabila tidak ditangani (McCance dan Sue, 2006). Pasien CKD harus mendapatkan monitoring terhadap kemungkinan adanya DM, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, kanker, dan penyakit kronis lainnya pada pasien tersebut. Monitoring tersebut penting untuk dilakukan karena keadaan gagal ginjal dapat memperburuk progresifitas penyakit yang ada dan sebaliknya (Eknoyan, 2009). 25 10. Prognosis Pasiendengangagalginjalkronikumumnyaakanmenujustadium terminal ataustadium V. Angka progesivitasnyatergantungdari diagnosis yang mendasari, keberhasilanterapi, dan juga dariindividumasing-masing. Pasien yang menjalanidialisiskronikakanmempunyaiangkakesakitan dan kematian yang tinggi. Pasiendengangagalginjalstadiumakhir menjalanitranspantasiginjalakanhiduplebih menjalanidialisiskronik. lama daripada yang yang Kematianterbanyakadalahkarenakegagalanjantung (45%), infeksi (14%), kelainanpembuluhdarahotak (6%), dan keganasan (4%) (Medscape, 2011). B. ANEMIA PADA CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) 1. Definisi a. Definisi Anemia: jika kadar hemoglobin (Hb) <14 g/dl (laki-laki) atau <12 g/dl (perempuan) b. Definisi Anemia renal: anemia pada CKD yang terutama disebabkan penurunan kapasitas produksi eritropoietin. Faktor anemia renal seperti defisiensi besi, umur eritrosit yang memendek, hiperparatiroid sekunder, dan infeksi inflamasi. c. Definisi anemia defisiensi besi pada CKD: 1) Anemia defisiensi besi absolut: bila saturasi transferin (ST) <20% dan feritin serum (FS) <100 ng/ml (CKD non dialisis, CKD peritoneal dialisis) dan <200 ng/ml (CKD HD). 2) Anemia defisiensi besi fungsional: bila ST <20% dan FS ≥100 ng/ml (CKD non dialisis, CKD peritoneal dialisis) dan ≥200 ng/ml (CKD HD). 2. Etiologi Anemia Renal Pemeriksaan laboratorium awal ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab lain dari anemia renal karena selain defisiensi eritropoietin sebagai 26 penyebab utama, banyak faktor lain yang berkontribusi pada anemia renal. Berikut faktor lain yang berkontribusi pada anemia renal (Perneferi, 2011) yaitu: a. Defisiensi besi b. Umur eritrosit yang memendek c. Hiperparatiroid berat d. Inflamasi dan infeksi e. Toksisitas aluminium f. Defisiensi asam folat g. Hipotiroid h. Hemoglobinopati 3. Evaluasi anemia renal Skrining Hb pada pasien CKD dilakukan minmal satu kali setahun. Jika didapatkan anemia dilanjutkan dengan pemeriksaan darah lengkap (Hb, Ht, Indeks eritrosit, leukosit dan hitung jenis, hitung trombosit), apusan darah tepi, hitung retikulosit, uji darah samar feses, evaluasi status besi (besi serum, kapasitas ikat besi total, saturasi transferin, feritin serum). Anemia renal umunya mulai terjadi pada CKD satidum 3 dan hampir selalu ditemukan pada CGK stadium 5. Pemeriksaan kadar Hb lebih dianjurkan daripada Ht, oleh karena variabilitas pemeriksaan Hb antar laboratorium lebih kecil, dan kadar Hb tidak dipengaruhi oleh waktu penyimpanan darah ataupun kadar glukosa serum. Pada pasien CKD waktu yang dianjurkan untuk pemeriksaan Hb adalah sebelum tindakan hemodialisis dilakukan (pre-HD). Umumnya anemia renal merupakan anemia normositik normokromik. Karakteristik anemia renal adalah hipoproliferatif, dimana aktivitas eritropoiesis rendah karena stimulasi eritropoietin kurang. Hitung retikulosit absolut merupakan petanda semikuantitatif terhadap aktivitas eritropoiesis. 27 4. Terapi anemia defisiensi besi a. Indikasi terapi besi: anemia defisiensi besi absolut, anemia defisiensi besi fungsional, tahap pemeliharaan status besi b. Kontraindikasi terapi besi: hipersensitifitas terhadap besi, gangguan fungsi hati berat, kandungan besi tubuh berlebih (iron overload) c. Sediaan besi: 1) parenteral (iron sucrose, iron dextran): diindikasikan pada pasien CKD HD 2) oral (ferrous gluconate, ferrous sulphate, ferrous fumarate, iron polysaccharide): diindikasikan pada pasien CKD non dialisis, CKD peritoneal dialisis dengan anemia defisiensi besi. Jika setelah tiga bulan ST tidak dapat dipertahankan ≥ 20% dan atau FS ≥100 ng/ml, maka dianjurkan untuk pemberian terapi besi parenteral. Absorbsi besi dipengaruhi oleh makanan dan antasida, karena itu besi oral diberika dinatara dua waktu makan. Dosis minimal 200 mg besi elemen/hari, dalam dosis terbagi 2-3x/hari. Sediaan generic ferrous sulphate 325 mg (besi elemental 65 mg), iron polysaccharide (besi elemental 50-300 mg), ferrous gluconate 325 mg (besi elemental 35 mg), ferrous fumarate 325 mg (besi elemental 108 mg). 28 Gambar 1. Algoritma terapi besi(Perneferi, 2011). 5. Target Hb pada terapi Erythropoietin Stimulating Agent (ESA) a. Terapi ESA dimulai pada kadar Hb <10g/dl b. Target Hb pada pasien CKD-HD, CKD peritoneal dialisis, dan CKD non dialisis yang mendapat terapi ESA adalah 10-12 g/dl. c. Kadar Hb tidak boleh >13 g/dl. 29 Gambar 2. Terapi ESA (Perneferi, 2011). 6. Indikasi dan kontraindikasi ESA a. Indikasi Bila Hb <10 g/dl dan penyebab lain anemia sudah disingkirkan. Syaratnya yaitu tidak ada anemia defisiensi besi absolut (ST <20% dan FS <100 ng/ml pada CKD non dialisis, CKD peritoneal dialisis, <200 ng/ml CKD HD), tidak ada infeksi yang berat. b. Kontraindikasi Hipersensitivitas terhadap ESA. 7. Efek samping terapi ESA a. Hipertensi b. Trombosis c. Kejang 30 d. Pure red cell aplasia (PRCA) 8. Transfusi darah a. Indikasi: Hb <7 g/dl dengan atau tanpa gejala anemia, Hb <8 g/dl dengan gangguan kardiovaskular yang nyata, perdarahan akut dengan gejala gangguan hemodinamik, pasien yang akan menjalani operasi b. Target Hb: Target pencapaian Hb dengan transfusi 7-9 g/dl (tidak sama dengan target Hb pada terapi ESA). 9. Patofisiologi anemia pada CKD Pasien GGK biasanya mengalami anemia. Penyebab utamanya adalah defisiensi produksi eritropoietin (EPO) yang dapat meningkatkan risikokematian,uremia penghambat eritropoiesis, pemendekan umur eritrosit, gangguanhomeostasis zat besi. Antagonis EPO yaitu sitokin proinflamasi bekerja denganmenghambat sel-sel progenitor eritroid dan menghambat metabolisme besi.Resistensi EPO disebabkan oleh peradangan maupun neocytolysis. Beberapamekanisme patofisiologi mendasari kondisi ini, termasuk terbatasnya ketersediaan besi untuk eritropoiesis, gangguan proliferasi sel prekursor eritroid, penurunan EPOdan reseptor EPO, dan terganggunya sinyal transduksi EPO. Penyebab lainanemia pada pasien CKD adalah infeksi dan defisiensi besi mutlak. Kehilangandarah adalah penyebab umum dari anemia pada CKD. Hemolisis, kekuranganvitamin B12 atau asam folat, hiperparatiroidisme, hemoglobinopati dan keganasan,terapi angiotensinconverting-enzyme (ACE) inhibitor yang kompleks dapatmenekan eritropoiesis (Perneferi, 2011). Pasien CKD mengalami defisiensi zat besi yang ditunjukkan denganketidakseimbangan pelepasan zat besi dari penyimpanannya sehingga tidak dapatmemenuhi kebutuhan untuk eritropoiesis yang sering disebut jugareticuloendothelial cell iron blockade. Reticuloendothelial cell iron blockade dangangguan keseimbangan absorbsi zat besi dapat disebabkan oleh 31 kelebihanhepsidin. Hepsidin merupakan hormon utama untuk meningkatkan homeostasissistemik zat besi yang diproduksi di liver dan disekresi ke sirkulasi darah. Hepsidinmengikat dan menyebabkan pembongkaran ferroportin pada enterosit duodenum,retikuloendotelial makrofag, dan hepatosit untuk menghambat zat besi yang masukke dalam plasma. Peningkatan kadar hepsidin pada pasien CKD dapat menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia (Perneferi, 2011). 32 DAFTAR PUSTAKA Bustan NM. 2015. Manajeman Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Rineka Cipta. Eknoyan, Garabed. 2009. Definition and Classification of Chronic Kidney Disease. US Nephrology: 13-7. IDI. 2013. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Jakarta : IDI. Kemenkes RI. 2017. Pusat Data dan Informasi : Situasi Penyakit Ginjal Kronis. Jakarta. ISSN 2442-7659. Kidney Disease Outcome Quality Initiative. 2002. Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification. New York: National Kidney Foundation. Kumar, Vinay., Cotran, Ramzi S., Robbins, Stanley L. 2007. Robbins buku ajar patologi volume 2 edisi 7. Jakarta: EGC. Levey, Andrew S., Kai-Uwe E., Yusuke T., Adeera L., Josef C., Jerome R., Dick DZ., Thomas H. H., Norbert L., Garabed E. 2005. Definition and Classification of Chronic Kidney Disease: A Position Statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney International: 67; 2089-2100. Lopez-Novoa, Jose M., Carlos MS., Ana B. RP., Francisco J. L. H. 2010. Common Pathophysiological Mechanism of Chronic Kidney Disease: Therapeutic Perspectives. Pharmacology and Therapeutics: 128; 61-81. McCance, K. L., Sue E. Huether. 2006. Pathophysiology: The Biologic of Disease in Adults and Children. Canada: Elsevier Mosby. Murray L, Ian W, Tom T, Chee KC. Chronic Renal failure in Ofxord Handbook of Clinical Medicine. Ed. 7th. New York: Oxford University; 2007. 294-97. NICE. 2014. Chronic Kidney Diasease in Adults: assessment and management. Price, Sylvia A, Lorraine M. Wilson. 2005. Patofisiologi : konsep klinis proses perjalanan penyakit, volume 1, edisi 6. Jakarta: EGC. Sudoyo, Aru W, dkk. 2006. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi Keempat. Jilid I. Jakarta Balai Penerbit FKUI. p. 725 – 33 ; 766 – 71. 33 Suwitra, K.2007. Penyakit Ginjal Kronik. Aru WS, Bambang S, Idrus A, Marcellus SK, Siti S, editor. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed. 4 Jilid I. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.hlm 570-3. Perneferi. 2011. Konsensus manajemen anemia pada penyakit ginjal kronik. Edisi 2, Educational Grant: Jakarta 34