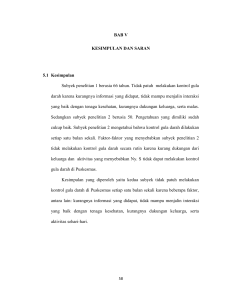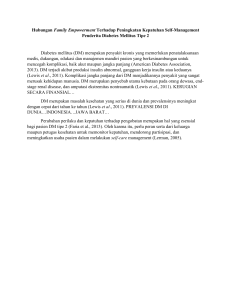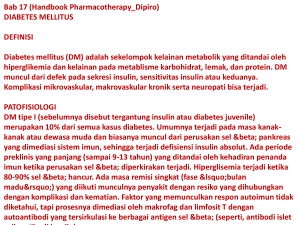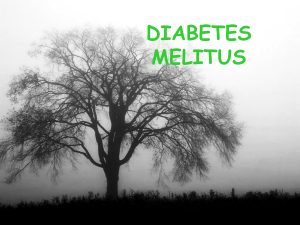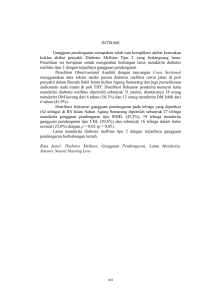ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA MEDIS DIABETES MELLITUS TIPE 2 DENGAN GANGUAN POLA NAPAS INEFEKTIF DI RUANG PANDAN WANGI RSUD DR SOETOMO SURABAYA Oleh: Kelompok 9 1. Nurullia Hanum Hilfida (131613143020) 2. Lintang Kusuma Ananta (131613143063) 3. Jen Riko Dewantoro (131613143086) 4. Arista Sulistyowati (131613143093) 5. Kusumastuti (131613143096) 6. Jaka Surya Hakim (131613143102) PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 LEMBAR PENGESAHAN Laporan praktik klinik Keperawatan Dasar Profesi Pendidikan Ners Angkatan A12 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya di Ruang Pandan Wangi Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 17 September 2016 telah dilaksanakan sebagai laporan praktik atas nama: 1. Nurullia Hanum Hilfida (131613143020) 2. Lintang Kusuma Ananta (131613143063) 3. Jen Riko Dewantoro (131613143086) 4. Arista Sulistyowati (131613143093) 5. Kusumastuti (131613143096) 6. Jaka Surya Hakim (131613143102) Surabaya, 16 September 2016 Pembimbing Akademik Pembimbing Ruangan Andri Setiya Wahyudi, S.Kep., Ns., M.Kep. NIP. 198206192015041001 Lilik Mudayatin, S.Kep., Ns. 196710311989032004 Mengetahui, Kepala Ruangan Pandan Wangi Lilik Mudayatin, S.Kep., Ns. 196710311989032004 ii DAFTAR ISI Halaman Sampul ...................................................................................................... i Lembar Pengesahan ................................................................................................ ii Daftar Isi................................................................................................................. iii BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2 Tujuan dan Manfaat .................................................................................. 3 1.2.1 Tujuan Umum ................................................................................... 3 1.2.2 Tujuan Khusus .................................................................................. 3 1.3 Manfaat ..................................................................................................... 3 BAB 2 RESUME KASUS ...................................................................................... 4 2.1 Identitas Pasien ......................................................................................... 4 2.2 Pengkajian Pasien ..................................................................................... 4 2.3 Analisa Data ............................................................................................. 7 2.4 Implementasi Keperawatan ...................................................................... 8 BAB 3 KONSEP DASAR ................................................................................... 10 3.1 Diabetes Mellitus .................................................................................... 10 3.1.1 Definisi Diabetes Mellitus .............................................................. 10 3.1.2 Anatomi dan Fisiologi Pankreaas ................................................... 10 3.1.3 Etiologi Diabetes Mellitus .............................................................. 12 3.1.4 Patofisiologi Diabetes Mellitus ....................................................... 14 3.1.5 Manifestasi Klinik Diabetes Mellitus.............................................. 16 3.1.6 Komplikasi Diabetes Mellitus ......................................................... 16 3.1.7 Penatalaksanaan Diabetes Mellitus ................................................. 18 3.1.8 Pemeriksaan Penunjang .................................................................. 20 3.1.9 Web of Causation Diabetes Mellitus ............................................... 21 3.1.10 Fokus Pengkajian ............................................................................ 23 3.2 Konsep Pola Napas Inefektif .................................................................. 24 3.2.1 Definisi pola napas inefektif ........................................................... 24 3.2.2 Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan oksigen..................... 25 3.2.3 Patofisiologi pola napas inefektif .................................................... 26 iii 3.2.4 Pemeriksaan diagnostik ................................................................... 26 3.2.5 Penatalaksanaan medis pola napas inefektif ................................... 27 3.2.6 Pengkajian pola napas inefektif ...................................................... 27 3.2.7 Asuhan keperawatan pola napas inefektif ....................................... 28 3.3 Konsep Terapi Oksigenasi...................................................................... 31 3.3.1 Definisi terapi oksigenasi ................................................................ 31 3.3.2 Faktor yang memengaruhi oksigenasi (Aziz, 2006) ....................... 31 3.3.3 Alat terapi oksigen .......................................................................... 33 3.3.4 Standar operasional prosedur pemberian terapi oksigenasi ............ 35 3.4 Konsep Kenyamanan .............................................................................. 36 3.3.1 Definisi kenyamanan ....................................................................... 36 3.4.2 Aspek dalam kenyamanan............................................................... 37 3.4.3 Faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan .............................. 37 3.4.4 Asuhan keperawatan gangguan rasa nyaman .................................. 39 BAB 4 PENUTUP ................................................................................................ 43 4.1 Kesimpulan ............................................................................................. 43 4.2 Saran ....................................................................................................... 43 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 44 Lampiran .............................................................................................................. 46 iv BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Diabetes Mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik yang di tandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau ganguan fungsi insulin (resistensi insulin) (Fatimah 2015). Diabetes Mellitus dibedakan menjadi dua, yakni tipe 1 yang terjadi karena sel-sel pankreas yang memproduksi insulin dirusak oleh sistem pertahanan tubuh /autoimun akbatnya hormon insulin tidak lagi diproduksi oleh tubuh. Untuk dapat bertahan hidup penderita diabetes tipe 1 perlu mendapat suntikan insulin secara teratur sepanjang hidupnya. Diabetes tipe 2 terjadi karena insulin yang diproduksi tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Penyebabnya bisa karena insulin yang diproduksi tidak cukup atau cacat, atau sel tidak lagi sensitif dengan insulin (insulin resisten). Diabetes tipe 2 cenderung timbul di usia di atas 30 atau 40 tahunan dan angka kejadiannya meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Diabetes Mellitus tipe 2 lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan tipe 1, dari populasi dunia yang menderita diabetes mellitus sebanyak 95% diantaranya merupakan Diabetes Mellitus tipe 2 dan hanya 5% dari jumlah tersebut menderita Diabetes Mellitus tipe 1 (Fatimah, 2015). Penderita Diabetes Mellitus di seluruh dunia pada tahun 2025 berkisar 333 juta orang (5,4%). Hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2007 menunjukan bahwa prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia meningkat sampai 57% (Fatimah, 2015). Menurut catatan organisasi kesehatan dunia tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat keenam dengan jumlah penderita diabetes terbanyak setelah India, Cina, Rusia, Jepang, dan Brasil (Soegondo, 2003). Penderita Diabetes Mellitus di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 1995 terdapat lebih kurang 5 juta penderita Diabetes Mellitus di Indonesia dengan peningkatan sekitar 230 ribu penderita setiap tahun (Depkes RI, 2003). Berdasarkan data Riskesdas 2013 diperkirakan sebanyak 12 juta orang menderita Diabetes Mellitus, data tersebut menunjukkan bahwa 1 2 proporsi penderita Diabetes Mellitus meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2007. Diabetes Mellitus dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari oleh penderita dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. Hiperglikemia yang terjadi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan berbagai kerusakan sistem tubuh terutama saraf dan pembuluh darah. Pada kerusakan saraf, hiperglikemia dapat menyebabkan neuropati yang meningkatkan kejadian ulkus kaki dan infeksi, retinopati yang dapat menyebabkan kebutaan serta nefropati yang menyebabkan gagal ginjal. Pada kerusakan pembuluh darah kondisi hiperglikemi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, serta berbagai penyakit pembuluh darah lainnya (Infodatin, 2014). Secara normal, sel menggunakan glukosa untuk dimetabolisme dan diubah menjadi energi, namun pada kondisi hiperglikemia glukosa tidak dapat diserap oleh sel dan produksi energi menjadi menurun. Tubuh akan berespon untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memecah cadangan glukosa pada glikogen (glikogenolisis) maupun dengan memproduksi glukosa baru melalui katabolisme lemak dan protein (glukoneogenesis). Pada proses katabolisme akan dihasilkan produk sisa berupa keton yang dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi asidosis metabolik. Penurunan pH serum, peningkatan CO2 dan pCO2 akibat kondisi asidosis metabolik akan dikompensasi oleh tubuh, salah satunya dengan napas cepat dalam (Kussmaul). Napas cepat dan dalam merupakan salah satu manifestasi pola napas infektif pada diagnosa keperawatan NANDA. Pola napas inefektif didefinisikan sebagai inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang cukup (NANDA, 2014). Masalah pola napas inefektif memerlukan intervensi segera karena jika dibiarkan akan menyebabkan CO2 di dalam tubuh akan terkuras. CO2 merupakan bahan penting pembentuk bikarbonat yang merupakan penyangga asam-basa tubuh, sehingga jika CO2 terkuras maka regulasi asam-basa tubuh dapat terganggu. Berdasarkan penjelasan di atas kelompok kami mengangkat pola napas inefektif sebagai masalah keperawatan utama pada Ny L. 3 1.2 Tujuan dan Manfaat 1.2.1 Tujuan Umum Mahasiswa diharapkan dapat mengerti konsep diabetes melitus secara menyeluruh termasuk apa penyebab terjadinya diabetes melitus dan bagaimana cara mencegah terjadinya diabetes melitus serta dapat melakukan asuhan keperawatan terhadap klien dengan Diabetes Mellitus 1.2.2 Tujuan Khusus 1. Mengidentifikasi konsep Diabetes Mellitus 2. Mengidentifikasi konsep Pola Napas 3. Mengidentifikasi konsep Oksigenasi 4. Mengidentifikasi konsep Kenyamanan 5. Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus dengan masalah keperawatan Pola Napas Inefektif 6. Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus dengan masalah keperawatan Gangguan Rasa Nyaman 1.3 Manfaat 1. Bagi penderita Diabetes Mellitus Laporan ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi penderita Diabetes Mellitus mengenai penyakitnya, komplikasi serta tatalaksana sehingga mampu mengontrol kondisi sakitnya 2. Bagi pembaca Menambah pengetahuan mengenai Diabetes Mellitus, tanda gejala, efek yang ditimbulkan dan tatalaksananya, serta asuhan keperawatan Pola Napas Inefektif dan Gangguan Rasa Nyaman pada pasien Diabetes Mellitus. 3. Bagi penulis Menambah pengetahuan tentang penyakit Diabetes Mellitus, masalah keperawatan yang timbul serta asuhan keperawatan u Pola Napas Inefektif dan Gangguan Rasa Nyaman pada pasien Diabetes Mellitus. 4 BAB 2 RESUME KASUS 2.1 Identitas Pasien Nama :Ny. L Umur : 70 tahun Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Status : Menikah Pendidikan : Tamat SD Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Suku Bangsa : Indonesia Alamat : Kalijaran Sambikerep, RT 06/RW 05 Surabaya, Tanggal Masuk : 14 – 09 - 2016 Tanggal Pengkajian : 15 – 09 - 2016 No. Register : 1253.xx.xx Diagnosa Medis : DM Tipe 2+Hiperglikemia+Sepsis+Post stroke+AKI 2.2 Pengkajian Pasien 1. Status Kesehatan Ny. R berusia 70 tahun pada tanggal 12 september 2016 merasakan pusing, lalu kaki kaku tidak dapat bergerak dan berjalan, badan terasa lemah dan panas, lalu Ny. R mengatakan keluhan kepada anaknya. Setelah itu anak Ny, R membawanya ke RS. Wijaya. Setelah 24 jam dirawat, anak Ny. R mendapatkan informasi dari perawat bahwa peralatan di Rumah sakit tersebut kurang lengkap sehingga Ny, R harus dirujuk Ke RSDS. Pada tanggal 13 September Ny. R dibawa ke RSDS, diterima di IRD lalu dipindahkan ke Ruang Pandan Wangi pada hari yang sama. Saat ini keluhan yang dirasakan oleh Ny. R adalah pusing, merasa kurang nyaman berada di ruangan karena berisik, sesak nafas, ingin segera pulang dan kurang bisa tidur karena tidak nyaman tersebut. Dulu pada tahun 2004 Ny. R juga pernah dirawat di RSDS dikarenakan sakit stroke ringan. 5 Ny. R tidak memiliki alergi apapun, baik makanan, udara, debu, maupun obat-obatan. Kebiasaan Ny. R di rumah adalah mengonsumsi minuman manis di pagi hari seperti es teh. Selain itu Ny, R juga sangat suka camilan dan makan berat di sela-sela waktu. Dari anggota keluarga Ny. R tidak ada yang mengalami sakit Diabetes Melitus seperti Ny. R, namun ada dari orang tua Ny. R yang mengalami hipertensi. Saat ini dokter mendiagnosa Ny. R DM Tipe 2+Hiperglikemia+ Sepsis+Post stroke+ AKI. 2. Pola kebutuhan dasar (Bio-Psiko-Sosio-Kultural-Spiritual) Sebelum sakit klien tidak mengalami msalah dalam pernafasan, namun setelah sakit klien merasakan sesak, sehingga aktivitasnya pun terbatas. Saat ini klien terpasang NGT dengan diet 150ml susu per 3 jam untuk membantu dalam kebutuhan nutrisi klien, karena klien tidak mau makan. Sebelum sakit tidak ada permasalahan dalam pola makan klien, klien makan 3x dalam sehari disertai camilan seperti gorengan dan teh di pagi hari. Saat ini klien terpasang kateter, dengan haluaran urin sekitar 1000cc per 24 jam menurut keterangan dari anak klien. Sebelum sakit pola eliminasi klien tidak terganggu, klien juga mampu pergi ke toilet secara mandiri untuk BAK maupun BAB. Aktivitas klien sehari-hari sebelum sakit adalah menyapu rumah dan terkadang halaman setiap pagi, klien juga mampu melakukan ADL secara mandiri seperti mandi, makan, mengganti pakaian dan sikat gigi, maupun ke toilet. Sedangkan saat ini aktivitas klien hanya berbaring di kasur tanpa melakukan aktivitas apapun, saat akan duduk dari tidur pun klien memerlukan bantuan dari anak atau anggota keluarga yang menjaga klien di rumah sakit. Keluarga klien mengatakan bahwa setiap malam klien susah tidur karena kurang nyaman dengan suasana ruangan yang berisik, sebelum sakit klien tidak mengalami permasalahan pola tidur, biasanya klien tidur jam 21.00-22.00 dan bangun sekitar subuh. Setiap harinya klien mengganti pakaian 2x sehar dan mandi secara mandiri 2x sehari, namun saat sakit klien tidak mengenakan pakaian, dan hanya menutup tubuh menggunakan sarung saja dan mandi klien hanya dengan diseka oleh anak klien. 6 Saat ini perawat sedikit kesulitan untuk berkomunikasi dengan klien, karena klien terpasang NGT sehingga kurang bisa berbicara secara jelas, namun klien kooperatif saat ditanya maupun diajak berkomunikasi oleh perawat. Sebelum sakit klien tidak mengalami permaslahan komunikasi. Pola beribadah klien saat ini hanya membaca doa saja tiak seperti sebelum sakit klien selalu sholat 5 waktu dan terkadang sholat malam juga menurut keterangan dari anak klien. Saat berada di rumah klien suka menonton TV sebagai hiburan di rumah, untuk saat ini klien tidak ada hiburan dan hanya berbincang dengan keluarga untuk sesekali waktu. 3. Pemeriksaan Fisik Keadaan fisik klien saat dilakukan pengkajian didapatkan tingkat kesadaran yang compos mentis dengan GCS 456 dan tanda-tanda vital klien nadi: 90x/menit, suhu: 37oC, tekanan darah: 120/80mmHg, RR= 24x/mnt. Permasalahan keadaan fisik klien terdapat pada ekstrremitas bagian kiri yang sulit untuk digerakkan karena klien pernah mengalami stroke, terlebih pada jari-jari tangan kiri klien, kaku dengan jari setengah menggenggam tidak bisa digerakan. Untuk keadaan kepala dan leher, tidak ada masalah, paru didapatkan pernafsan cepat dan dangkal, jantung suara S1 dan S2 reguler, abdomen tidak ada masalah, Genetalia bersih, memakai pampers, integumen Gatal-gatal di bagian paha dan lutut sebelah kanan. Pengkajian neurologis pada saraf kranial dan refleks tidak terkaji, namun pada permasalahan emosi klien, klien terlihat bosan, ingin pulang, tidak merasa nyaman terlihat dari ekspresi wajah klien dan keluhan klien mengatakan ingin pulang. 4. Pemeriksaan Penunjang Jenis Pemeriksaan Indikator Nilai Kimia Klinik HDL 230 U/L Albumin 3.68 g/dl Direk Bilirubin Bilirubin Direk 0.23 mg/dl Total Bilirubin 0.49mg/dl Hematologi Nilai Normal 7 APTT 33.1 detik Kontrol APTT 24 detik PTT 14.5 detik Kontrol PTT 11 detik HBS-Ag Reaktif HIV Rapid Test Non reaktif Elektrolit Analisa Gas Darah Urine Lengkap Radiologi Natrium 141 mmo/l Kalium 3.8 mmo/l Klorida 105 mmo/l pH 7.383 pCO2 29.7 mmhg pO2 105 mmhg HCO3- 17.9 mmol/l TCO2 18.8 mmpl/l SO2 98.1 aADO2 6.8 mmhg PO2/FiO2 500.2 mmHg GLU 2+ BIL Negatif PRO 1+ URO 3.2 Eritrosit 0-2 Leukosit Foto dada dan 0-2 thoraks normal Hasil konsultasi 2.3 Terapi insulin 8 unit Analisa Data Data DS : Pasien mengeluh sesak napas DO : 1. Pola napas pasien yaitu 36x/menit 2. Pasien tampak gelisah Etiologi Defisiensi Insulin ↓ ↑ Lipolisis ↓ ↑ Gliserol ↓ ↑ Katabolisme ↓ ↑ Keton (BUN) Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Pola Napas 8 3. Menggunakan alat bantu napas O2 nasal 3 lpm DS : Pasien mengatakan lelah, ingin beristirahat, namun lingkungan berisik DO : 1. Pasien terlihat tidak bisa beristirahat 2. Situasi lingkungan berisik 3. Terdapat tandatanda stres (mata merah, gelisah, sering memindahkan tangannya yang terpasang infus) 4. Pasien tidak tenang 2.4 ↓ Ketoasidosis ↓ Hiperventilasi ↓ MK : Ketidakefetifan Pola Napas Hospitalisasi ↓ Lingkungan tidak kondusif ↓ Istirahat terganggu ↓ MK : Gangguan Rasa Nyaman Gangguan Rasa Nyaman Implementasi Keperawatan Hari/Tanggal/ Jam Kamis/19 September 2016/11.45 No.Dx Implementasi 1 1. Mengkaji kebutuhan klien untuk dilakukan relaksasi 2. Menjelaskan fungsi relaksasi 3. Menjelaskan teknik relaksasi yang dapat dilakukan oleh keluarga 4. Mengajarkan teknik relaksasi kepada keluarga 5. Menganjurkan keluarga untuk memosisikan klien senyaman mungkin 6. Mengkaji pemijatan pada klien untuk meningkatkan kenyamanan pada diri 7. Menjelaskan kepada keluarga bahwa tehnik massage (pemijatan) dapat membuat rileks tubuh 8. Menunjukkan kepada keluarga bagaimana melakukan massage yang tepat. 9. Memilih anggota tubuh yang dapat dilakukan pemijatan 10. Setelah mengajarkan keluarga cara untuk memijat, bisa 9 Jumat/20 September 2016/10.30 2 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. menggunakan minyak atau lotion saat memijat atau mencuci tangan dengan air hangat Monitoring penggunaan alat bantu napas Mengevauasi kebutuhan pasien untuk relaksasi Menganjurkan keluarga untuk memosisikan pasien senyaman mungkin Ajarkan latihan nafas dalam, dan cara batuk efektif Monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan Monitoring ritme napas Membantu pasien mendapatkan posisi yang nyaman dan optimal untuk mendapatkan ventilasi optimal Memonitoring keadaan dan penggunaan alat bantu napas (nasal kanul) Observasi tanda-tanda hiperventilasi BAB 3 KONSEP DASAR 3.1 Diabetes Mellitus 3.1.1 Definisi Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus adalah gangguan metabolisme secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat (Price, 2000). Brunner dan Suddarth (2000) mendefinisikan Diabetes Mellitus sebagi sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Diabetes Mellitus adalah keadaan hiperglikemi kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah, disertai lesi pada membran basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskopik elektron (Mansjoer, 2001). Berdasarkan berbagai pendapat ahli mengenai Diabetes Mellitus dapat diambil kesimpulan bahwa Diabetes Mellitus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan hormonal (dalam hal ini adalah hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas) dan melibatkan metabolisme karbohidrat sehingga seseorang tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. 3.1.2 Anatomi dan Fisiologi Pankreaas Pankreas adalah sekumpulan kelenjar yang strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah panjangnya kira-kira 15 cm mulai dari duodenum sampai ke limpa dan beratnya rata-rata 69-90 gr.terbentang pada vertebra lumbalis I dan II dibelakang lambung, 1. Anatomi pankreas a. Kepala pankreas, terletak disebelah kanan rongga abdomen dan didalam lekukan duodenum. b. Badan pankreas, merupakan bagian utama dari organ letaknyadibelakang lambung dan didepan vertebra lumbalis pertama. c. Ekor pankreas, bagian runcing disebelah kiri yang menyentuh limfa. 10 ini 11 2. Fungsi pankreas Fungsi eksokrin yaitu membentuk getah pankreas yang berisi enzim dan elektrolit. Sel F pada pulau Langerhans menghasilkan polipeptida dan pankreatik yang berperan mengatur fungsi eksokrin pankreas. Pulau langerhans terdiri atas sel-sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel-sel beta yang menghasilkan insulin. Insulin adalah hormon hipoglikemik (menurunkan gula darah) sedangkan glukagon bersifat hiperglikemik (meningkatkan gula darah). Selain sel alfa dan beta pulau Langerhans juga memiliki sel-sel delta yang menghasilkan somastostatin yang dapat menghambat pelepasan insulin dan glukagon. Gambar 1.1 Anatomi Pankreas Sumber: www.pancreas.com 3. Mekanisme keseimbangan glukosa darah Jumlah glukosa yang diambil dan dilepaskan oleh hati dan yang dipergunakan oleh jaringan perifer tergantung dari keseimbangan fisiologis hormone insulin dan glukagon dengan mekanisme sebagai berikut: a. Insulin yaitu merupakan hormon yang menurunkan glukosa darah dengan cara kerja membantu glukosa darah masuk ke dalam sel. 12 b. Hormon yang meningkatkan kadar gula darah dengan cara kerja memecah glikogen/ gula otot (glkogenolisis) maupun meningkatkan pembentukan glukosa darah baru dari lemak dan protein (glukoneogenesis) antara lain : 1) Glukagon yang disekresi oleh sel alfa pulau langerhans 2) Epinefrin yang disekresi oleh medula adrenal dan jaringan kromafin 3) Glukokortikoid yang disekresikan oleh korteks adrenal. 4) Growth hormone yang disekresi oleh kelenjar hipofisisanterior. Glukagon, epinefrin, glukokortikoid, dan growth hormone membentuk suatu mekanisme counfer-regulator yang mencegah timbulnya hipoglikemia akibat pengaruh insulin. 3.1.3 Etiologi Diabetes Mellitus Klasifikasi Diabetes Mellitus menurut (Brunner dan Suddart, 2000) berdasarkan penyebabnya yaitu : 1. Diabetes Mellitus tipe 1/ IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) Diabetes Mellitus tipe 1 ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas; faktor genetik; imunologi; dan mungkin pula lingkungan (virus) diperkirakan turut menimbulkan distruksi sel beta. a. Faktor genetik Penderita Diabetes Mellitus tipe 1 mewarisi kecenderungan genetik kearah Diabetes Mellitus tipe kecenderungan ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe HLA (Human Leucocyt Antigen) tertentu. Resiko meningkat 20X pada individu yang memiliki tipe HLA DR3 atau DR4. b. Faktor Imunologi Respon abnormal dimana anti bodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi jaringan tersebut sebagai jaringan asing. c. Faktor lingkungan Virus /toksin tertentu dapat memacu proses yang dapat menimbulkan destruksi sel beta. 2. Diabetes Mellitus tipe II/NIDDM (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus) Mekanisme yang tepat menyebabkan resistensi insulin dan sekresi insulin pada Diabetes Mellitus tipe II masin belum diketahui, namun Diabetes tipe 2 dapat 13 disebabkan oleh berbagai faktor risiko sebagai berikut (Infodatin, 2014): a. Faktor yang tidak dapat diubah 1) Ras Bedasarkan penelitian yang dilakukan di Institut of Cardiovasculer and Medical Sciences, University of Glasgow, Inggris orang dengan ras negroid dan Asia dua kali lipat lebih berisiko menderita Diabetes Mellitus dibandingkan dengan ras Kaukasia (Tempo.co, 2014) 2) Jenis kelamin Kejadian DM Tipe 2 pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki.Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih besar (Fatimah, 2015). 3) Usia Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena Diabetes Mellitus adalah > 45 tahun dan resistensi insulin cenderung meningkat pada usia > 65 tahun 4) Genetik Secara emperis Diabetes Mellitus tipe 2 akan meningkat dua sampai enam kali lipat jika orang tua atau saudara kandung mengalami penyakit ini. 5) Riwayat melahirkan bayi >4 kg 6) Lahir dengan berat badan <2,5 kg b. Faktor dapat diubah, erat kaitannya dengan gaya hidup 1) Obesitas Pada derajat kegemukan dengan IMT > 23 dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200mg%. 2) Konsumsi alkohol Alkohol akan menganggu metabolisme gula darah terutama pada penderita Diabetes Mellitus, sehingga akan mempersulit regulasi gula darah dan meningkatkan tekanan darah. 3) Kebiasaan merokok Kandungan zat pada rokok menimbulkan aterosklerosis atau terjadi 14 pengerasan pada pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penumpukan zat lemak di arteri, lemak dan plak memblok aliran darah dan membuat penyempitan pembuluh darah dan memicu hipertensi. 4) Hipertensi Kondisi hiperglikemi dapat menghambat pembentukan endothelium dan merentensi natrium. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan darah. 5) Diet tidak sehat Konsumsi makanan tinggi lemak dan garam dapat menyebabkan hipertensi yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya diabetes 6) Dislipidemia Kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL (< 35 mg/dl) dan tingginya Trigliserida (>250 mg/dl) sering didapat pada pasien Diabetes. 7) Aktivitas fisik Konsumsi makanan tidak seimbang dengan aktivitas yang dilakukan akan memicu terjadinya obesitas. 3. Diabetes Gestasional Diabetes Gestasional adalah intoleransi glukosa yang mulai timbul atau mulai diketahui selama pasien hamil. Karena terjadi peningkatan sekresi berbagai hormon disertai pengaruh metabolik terhadap toleransi glukosa, maka kehamilan dapat menjadi keadaan diabetogenetik. 3.1.4 Patofisiologi Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus merupakan suatu keadaan hiperglikemia yang bersifat kronik yang dapat memengaruhi metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Diabetes Mellitus disebabkan oleh sebuah ketidakseimbangan atau ketidak adanya persediaan insulin atau tak sempurnanya respon seluler terhadap insulin ditandai dengan tidak teraturnya metabolisme orang dengan metabolisme yang normal mampu mempertahankan kadar glukosa darah antara 80-140 mg/dl (euglikemia) dalam kondisi asupan makanan yang berbeda-beda pada orang non diabetik kadar glukosa darah dapat meningkat antara 120-140 mg/dl setelah makan (post prandial) namun keadaan ini akan kembali menjadi normal dengan cepat. 15 Sedangkan kelebihan glukosa darah diambil dari darah dan disimpan sebagai glikogen dalam hati dan sel-sel otot (glikogenesis). Kadar glukosa darah normal dipertahankan selama keadaan puasa, karena glukosa dilepaskan dari cadangancadangan tubuh (glikogenolisis) dan glukosa yang baru dibentuk dari trigliserida (glukoneogenesis). Glukoneogenesis menyebabkan metabolisme meningkat kemudian terjadi proses pembentukan keton (ketogenesis) terjadi peningkatan keton didalam plasma akan menyebabkan ketonuria (keton didalam urine) dan kadar natrium serta pH serum menurun yang menyebabkan asidosis metabolik (Price, 2000). Resistensi sel terhadap insulin menyebabkan penggunaan glukosa oleh sel menjadi menurun sehingga kadar glukosa darah dalam plasma tinggi (hiperglikemia). Jika hiperglikeminya parah dan melebihi ambang ginjal maka timbul glikosuria. Glukosuria ini akan menyebabkan diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran kemih (poliuri) dan timbul rasa haus (polidipsi) sehingga terjadi dehidrasi. Glukosuria menyebabkan keseimbangan kalori negatif sehingga menimbulkan rasa lapar (polifagi) Selain itu juga polifagi juga disebabkan oleh starvasi (kelaparan sel). Pada pasien Diabetes Mellitus penggunaan glukosa oleh sel juga menurun mengakibatkan produksi metabolisme energi menjadi menurun sehingga tubuh menjadi lemah. Hiperglikemia juga dapat mengganggu fungsi pembuluh darah kecil (arteri kecil). Kadar gula darah yang tinggi menyebabkan kekentalan darah meningkat, menghambat aliran darah sehingga suplai makanan dan oksigen ke perifer menjadi berkurang. Jika penderita mengalami luka kondisi hiperglikemi akan mempersulit proses penyembuhan, menjadikan luka sebagai tempat berkembangnya bakteri sehingga dapat memicu infeksi dan terjadi ganggren atau ulkus. Gangguan pembuluh darah juga menyebabkan aliran darah ke retina menurun, akibatnya pandangan menjadi kabur. Akibat perubahan mikrovaskuler adalah perubahan pada struktur dan fungsi ginjal sehingga terjadi nefropati. Diabetes juga mempengaruhi saraf-saraf perifer, sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat sehingga mengakibatkan neuropati (Price, 2000) 16 3.1.5 Manifestasi Klinik Diabetes Mellitus Menurut Mansjoer (2001) menifestasi Diabetes Mellitus adalah sebagai berikut: 1. Poliuri (sering kencing dalam jumlah banyak) 2. Polidipsi (banyak minum) 3. Polifagi (rasa lapar yang semakin besar) 4. Lemas 5. Berat badan menurun 6. Kesemutan 7. Mata kabur 8. Impotensi pada pria 9. Gatal (Pruritus) pada vulva 10. Mengantuk (somnolen) yang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu. 3.1.6 Komplikasi Diabetes Mellitus Komplikasi Diabetes Mellitus menurut Smeltzer (2002) dibagi menjadi dua yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronik. 1. Komplikasi akut, adalah komplikasi pada Diabetes Mellitus yang penting dan berhubungan dengan keseimbangan kadar glukosa darah dalam jangka pendek, ketiga komplikasi tersebut adalah: a. Diabetik Ketoasedosis (DKA) Ketoasidosis diabetik merupakan defesiensi insulin berat dan akut dari \ perjalanan penyakit Diabetes Mellitus. Ketoasidosis diabetik ditandai oleh adanya hiperglikemia, asidosis metabolik, dan peningkatan konsentrasi keton yang beredar dalam sirkulasi. Diabetik ketoasidosis disebabkan oleh tidak adanya insulin atau tidak cukupnya jumlah insulin dalam tubuh. Hiperglikemia terjadi akibat peningkatan produksi glukosa (glukoneogenesis dan glikogenolisis) dan penurunan penggunaan glukosa pada jaringan perifer. Pada glukoneogenesis dihasilkan produk sisa berupa keton yang dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi asidosis metabolik. 17 b. Koma Hiperosmolar Non Ketotik (KHHN) Koma Hipermosolar Non Ketonik merupakan keadaan yang didominasi oleh hiperosmolaritas dan hiperglikemia dan disertai perubahan tingkat kesadaran. Salah satu perubahan utamanya dengan DKA adalah tidak tepatnya ketosis dan asidosis pada KHHN c. Hipoglikemia Hipoglikemia terjadi kalau kadar gula dalam darah turun dibawah 50-60 mg/dl keadaan ini dapat terjadi akibat pemberian preparat insulin atau preparat oral berlebihan, konsumsi makanan yang terlalu sedikit 2. Komplikasi Kronik Efek samping Diabetes Mellitus pada dasarnya terjadi pada semua pembuluh darah diseluruh bagian tubuh (Angiopati Diabetik) dibagi menjadi 2 : a. Komplikasi Mikrovaskuler 1) Penyakit Ginjal Salah satu akibat utama dari perubahan–perubahan mikrovaskuler adalah perubahan pada struktural dan fungsi ginjal. Bila kadar glukosa dalam darah meningkat, maka sirkulasi darah keginjal menjadi menurun sehingga pada akhirnya bisa terjadi nefropati. 2) Penyakit Mata Penderita Diabetes Mellitus akan mengalami gejala penglihatan sampai kebutaan keluhan penglihatan kabur tidak selalu disebabkan retinopati. Katarak juga dapat disebabkan karena hiperglikemia yang berkepanjangan menyebabkan pembengkakan lensa dan kerusakan lensa. 3) Neuropati Diabetes dapat mempengaruhi saraf- saraf perifer , sistem saraf otonom medulla spinalis atau sistem saraf pusat. Akumulasi sorbitol dan perubahan-perubahan metabolik lain dalam sintesa fungsi myelin yang dikaitkan dengan hiperglikemia dapat menimbulkan perubahan kondisi saraf. 18 b. Komplikasi Makrovaskuler 1) Penyakit Jantung Koroner Kadar gula darah yang tinggi mengakibatkan kekentalan darah meningkat sehingga aliran darah melambat akibatnya terjadi penurunan kerja jantung untuk memompakan darahnya ke seluruh tubuh sehingga tekanan darah akan naik. Lemak yang menumpuk dalam pembuluh darah menyebabkan mengerasnya arteri (arteriosclerosis) dengan resiko penderita penyakit jantung koroner atau stroke. 2) Pembuluh Darah Kaki Timbul karena adanya anesthesia fungsi saraf- saraf sensorik keadaan ini berperan dalam terjadinya trauma minor dan tidak terdeteksinya infeksi yang menyebabkan ganggren. Infeksi di mulai dari celah-celah kulit yang mengalami hipertropi, pada sel-sel kuku kaki yang menebal dan kalus demikian juga pada daerah-daerah yang terkena trauma. 3.1.7 Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Penatalaksanaan Diabetes mellitu secara teori menurut Sarwono (1998) adalah : 1. Pengobatan a. Obat Hipoglikemik Oral 1) Golongaan Sulfonilurea / sulfonyl ureas Obat ini paling banyak digunakan dan dapat dikombinasikan denagan obat golongan lain, yaitu biguanid inhibitor alfa glukosidase atau insulin. Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan produksi insulin oleh sel- sel beta pankreas ,karena itu menjadi pilihan utama para penderita Diabetes Mellitus tipe 2 dengan berat badan berlebihan 2) Golongan Binguanad /metformin Obat ini mempunyai efek utama mengurangi glukosa hati, memperbaiki pengambilan glukosa dari jaringan (glukosa perifer) dianjurkan sebagai obat tinggal pada pasien kelebihan berat badan. 19 3) Golongan Inhibitor Alfa Glikosidase Mempunyai efek utama menghambat penyerapan gula di saluran pencernaan sehingga dapat menurunkan kadar gula sesudah makan. Bermanfaat untuk pasien dengan kadar gula puasa yang masih normal. b. Pemberian Insulin 1) Indikasi pemberian insulin Pada Diabetes Mellitus tipe 1 Human Monocommponent Insulin (40 UI dan 100 UI/ml injeksi) yang beredar adalah actrapid.Injeksi insulin dapat diberikan kepada penderita Diabetes Mellitus tipe II yang kehilangan berat badan secara drastis. Yang tidak berhasil dengan penggunaan obat-obatan anti Diabetes Mellitus dengan dosis maksimal atau mengalami kontra indikasi dengan obatobatan tersebut. Bila mengalami ketoasidosis, hiperosmolar asidosis laktat, stress berat karena infeksi sistemik, pasien operasi berat, waita hamil dengan gejala Diabetes Mellitus yang tidak dapat dikontrol dengan pengendalian diet. 2) Jenis insulin a) Insulin kerja cepat : reguler insulin cristalinzink, dan semilente b) Insulin kerja sedang : NPH (Netral Protamine Hagerdon) c) Insulin kerja lambat : Jenisnya adalah PZI (Protamine ZincInsulin) 3) Diet Salah satu pilar utama pengelolaan Diabetes Mellitus adalah perencanaan makanan. Penderita Diabetes Mellitus sebaiknya mempertahankan menu yang seimbang dengan komposisi Idealnya sekigtar 68% karbohidrat, 20% lemak dan 12% protein. Karena itu diet yang tepat untuk mengendalikan dan mencegah agar berat badan ideal dengan cara : kurangi kalori, kurangi lemak, kurangi karbohidrat komplek, hindari makanan manis, dan perbanyak konsumsi serat. 20 4) Olahraga Olahraga selain dapat mengontrol kadar gula darah karena membuat insulin bekerja lebih efektif. Olahraga juga membantu menurunkan berat badan, memperkuat jantung dan mengurangi stress .Bagi pasien Diabetes Mellitus melakukan olahraga dengan teratur akan lebih baik tetapi jangan melakukan olah raga terlalu berat. 5) Kontrol gula darah secara rutin 6) Pemberian penyuluhan kesehatan Diabetes Mellitus diantarnya tentang perawatan kaki dan luka. 3.1.8 Pemeriksaan Penunjang Menurut Doenges (1999) pemeriksaan penunjang untuk pasien Diabetes Mellitus ialah sebagai berikut 1. Glukosa serum : peningkatan 200 – 1000 mg/dl atau lebih 2. Aseton plasma (ketones) positif 3. FFA : lipit dan klesterol meningkat 4. Osmolalitas serum : meningkat kurang lebih 330 m Osm/1 5. Elektrolit 1. Serum : normal, meningkat / menurun 2. Kalium : normal, menigkat (seluller shif) 3. Phosphorus : sering menurun 6. AGD ( Analisa gas darah ) : pH menurun dan HCO3 menurun 7. Hematokrit meningkat 8. Kreatinin : normal atau meningkat 3.1.9 Web of Causation Diabetes Mellitus 1. Kelainan sel β pankreas 2. Kelainan insulin/resistensi 3. Autoimun 4. Faktor lingkungan (infeksi, diet tinggi KH, obesitas, kehamilan) Defisiensi Insulin Starvasi sel ↓ Ambilan glukosa sel Kelemahan MK: Gangguan \ Pemenuhan ADL ↑ Metabolisme protein Asam amino dan glukoneogenesis HIPERGLIKEMIA ↑ Lipolisis ↑ Katabolisme ↓ BB ↑ Keton (BUN) MK: Gangguan Pemenuhan Nutrisi Kurang dari Kebutuhan Tubuh Ketoasidosis Penumpukan glukosa sel dan jaringan Glikosilasi Protein Peningkatan viskositas darah ↓ Kesadaran Asidosis Metabolik Hospitalisasi MK : Risiko cidera MK. Gangguan Rasa Nyaman 21 Glukosa Reduktase ↑Asam lambung Neuropati Angiopati MK : Mual ↑ Sorbitol Kerusakan dan perubahan fungsi sel dan jaringan MK :Nyeri Gangguan aliran darah Gangguan sensorik Gangguan Motorik ↓ Nutrisi dan O2 sel dan jaringan ↓ Sensasi nyeri Atrofi otot kaki Trauma tidak terasa Perubahan titik tumpu Kerusakan neurovaskuler Luka sulit sembuh Glukosuria Kehilangan kalori Rangsang lapar Polifagi Nefropati Retinopati ↓ Peristaltik ↓ Absorbsi cairan Ulserasi Infeksi MK: Gangguan Perfusi Jaringan Kelemahan MK: Intoleransi Aktivitas MK: Gangguan Pemenuhan ADL MK : Ketidakefektifan pola napas Intestinal Diare ↓ Absorbsi Glukosa Hiperventilasi GANGREN/ ULKUS DIABETIKUM Pandangan kabur MK : Risiko cidera Polidipsi ↑ Rangsang Haus MK: Gangguan Integritas Kulit Risiko penyebaran infeksi Cairan keluar banyak Diuresis Osmotik Poliuri Kehilangan Na, Cl, K, P (Elektrolit) MK: Gangguan Keseimbangan Cairan dan Elektrolit 22 23 3.1.10 Fokus Pengkajian Fokus pengkajian pasien Diabetes Mellitus secara teori menurut Doenges (1999) 1. Pengkajian Demografi Diabetes Mellitus banyak diderita oleh perempuan dewasa. Usia kurang lebih 40 tahun 2. Pengkajian Riwayat penyakit dahulu Penyakit infeksi pada pankreas, tumor pada pankreas, hipertensi, riwayat Diabetes Mellitus sebelumnya. 3. Pengkajian Riwayat kesehatan keluarga : Adakah penyakit Diabetes Mellitus dikeluarga klien 4. Pengkajian data dasar pasien Diabetes Mellitus a. Aktivitas / istirahat Gejala : Lemah, letih, sulit bergerak / berjalan, kram otot, tonus otot menurun, gangguan tidur / istirahat Tanda : Takikardi dan takipnea pada keadaan istirahat atau dengan aktivitas, letargi / disorentasi, koma, penurunan kekuatan otot b. Sirkulasi Gejala : Kebas, kesemutan ekstemitas, ulkus pada kaki, penyembuhan yang lama Tanda : Takikardi, perubahan tekanan darah postural, hipertensi, nadi yang menurun / tak ada, disritmia, krekels, kulit panas, kering dan kemerahan, bola mata cekung c. Integritas ego Gejala : Stress, tergantung orang lain, masalah finansial yang berhubungan dengan kondisi Tanda : Ansietas, peka rangsang d. Eliminasi Gejala : Perubahan pola berkemih (poliuria), nokturia, rasa nyeri / terbakar, kesulitan berkemih (infeksi) e. Makanan/ Cairan Gejala : Hilang nafsu makan, mual, muntah, tidak mengikuti diit, 24 peningkatan masukan glukosa/karbohidat, penurunan berat badan, haus, penggunaan diuretic (tiazid) Tanda : Kulit kering/ bersisik, kekakuan/ distensi abdomen, muntah, pembesaran tiroid (peningkatan kebutuhan metabolik dengan peningkatan gula darah), bau keton/ manis, bau nafas acetone. f. Neuro sensori Gejala : Pusing/ pening, sakit kepala, kesemutan, porestesia, gangguan penglihatan , penggunaan diuretik (tiazid) Tanda : Disorentasi, mengantuk, letargi, stupor/koma, (tahap lanjut), gangguan memori (baru, masa lalu), reflek tendon dalam (DTD) menurun. g. Nyeri/ kenyamanan Gejala : Abdomen yang tegang/ nyeri (sedang/ berat) Tanda : Wajah meringis dengan palpasi, tampak berhati-hati h. Keamanan Gejala :Kulit kering, gatal, ulkus kulit Tanda : Demam, diaforesis, kulit rusak, lesi/ ulserasi, menurunnya kekuatan umum/ rentang gerak, parestesia/ paralysis otot termasuk otot-otot pernafasan (jika kalium menurun dengan) i. Seksualitas Gejala : Gatal pada vagina (cenderung infeksi) 3.2 Konsep Pola Napas Inefektif 3.2.1 Definisi pola napas inefektif Pola nafas tidak efektif adalah kondisi dimana pola inhalasi dan ekshalasi pasien tidak mampu karena adanya gangguan fungsi paru (Tarwoto&Wartonah, 2010). Pola nafas tidak efektif adalah keadaan dimana seseorang individu mengalami kehilangan ventilasi yang aktual atau potensial yang berhubungan dengan perubahan pola nafas (Carpenito, 2001). 25 3.2.2 Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan oksigen Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen adalah (Wahit,2007): 1. Faktor Fisiologis a. Menurunnya kemampuan meningkatkan O2 seperti pada anemia. b. Menurunnya konsentrasi O2 yang di inspirasi seperti obstruksi saluran pernafasan bagian atas. c. Hivopolemia sehingga tekanan darah menurun yang mengakibatkan terganggunya O2. d. Meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil. e. Kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, muskulus skeletor yang abnormal, penyakit kronis seperti TBC paru. 2. Faktor Perkembangan a. Bayi prematur, yang disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan. b. Bayi dan Toddler, adanya resiko infeksi saluran pernafasan akut. c. Anak usia sekolah dan remaja, resiko infeksi saluran pernafasan dan merokok. d. Dewasa muda dan pertengahan, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres yang mengakibatkan penyakit jantung dan paru. e. Dewasa tua, adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan arteriosklerosis, elastisitas menurun, ekspansi paru menurun. 3. Faktor Perilaku a. Exercise: exercise akan meningkatkan kebutuhan oksigen b. Merokok: nikotin menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah perifir dan koroner. c. Substance abuse (alkohol dan obat-obatan) d. Kecemasan e. Nutrisi 26 4. Faktor lingkungan a. Tempat kerja (polusi) b. Suhu lingkungan c. Ketinggian dari permukaan laut 3.2.3 Patofisiologi pola napas inefektif Berhubungan dengan adanya obstruksi tracheobroncial oleh skret yang banyak, penurunan ekspansi paru dan proses inflamasi maka pasien mengalami kesulitan dalam bernafas menyebabkan pemasukan O2 berkurang sehingga pemenuhan kebutuhan O2 dalam tubuh tidak mencukupi yang ditandai dengan : 1. Perubahan kedalaman dan/atau kecepatan pernafasan 2. Gangguan perkembangan dada 3. Bunyi nafas tidak normal misalnya mengi 4. Batuk dengan atau tanpa produksi sputum 3.2.4 Pemeriksaan diagnostik Pemeriksaan diagnostik penting dalam menegakkan diagnosa yang tepat sehingga kita dapat memberikan obat yang tepat. Pemeriksaan diagnostik yang tepat adalah : 1. Test untuk menentukan keadequatan sistem konduksi jantung. a. EKG b. Exercise stress test 2. Test untuk menentukan kontraksi miokardium aliran darah a. Echocardiographi b. Kateterisasi jantung c. Angiographi 3. Test untuk mengukur ventilasi dan oksigenisasi a. Test fungsi paru-paru dengan spirometri b. Test astrup c. Oksimetri d. Pemeriksaan darah lengkap 4. Melihat struktur sistem pernafasan a. X-ray thorax 27 b. Bronchoskopi c. CT scan paru 5. Menentukan sel abnormal/infeksi sistem pernafasan a. Kultur apus tenggorok b. Sitologi c. Spesimen sputum (BTA) 3.2.5 Penatalaksanaan medis pola napas inefektif Pengobatan yang dilaksanakan pada pasien dengan gangguan pola nafas tidak efektik yaitu : 1. Pemberian nebuleser 2. Pemberian kebutuhan O2 3. Mengukur tanda-tanda vital 4. Memberikan posisi yang nyaman 5. Mengajarkan batuk efektif 6. Pemberian input cairan baik melalui minuman maupun cairan infus 3.2.6 Pengkajian pola napas inefektif Pengkajian merupakan tahap awal dalam mengumpulkan informasi dan pengumpula data sesuai respon manusia terhadap penyakit yang dapat berupa keluhan subyektif dan obyektif. a. Data Subyektif Merupakan informasi lansung didapatkan dari pasien seperti sesak nafas, batuk, nafas berbunyi, dada terasa berat. b. Data obyektif Data yang didapat melalui pemeriksaan fisik, observasi, serta pemeriksaan penunjang seperti respirasi 30x/menit, nadi 90-92x/menit, tekanan darah 130/80 mmhg, suhu tubuh 360c, terdengar wheezing, pasien tampak gelisah dan pasien tampak sesak. Dari data tersebut maka diagnosa keperawatan yang muncul yaitu pola nafas tidak efektif. 28 3.2.7 Asuhan keperawatan pola napas inefektif Ketidakefektif Pola Nafas (00032) Definisi Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak dapat memberi ventilasi yang adekuat. Batasan karakteristik: 1. Gangguan pernafasan abnormal (frekuensi, irama, kedalaman) 2. Perubahan pergerakan dada 3. Bradipnea 4. Penurunan tekanan ekspirasi 5. Penurunan tekanan inspirasi 6. Penurunan ventilasi per menit 7. Penurunan kapasitas vital 8. Dispnea 9. Peningkatan anterior posterior diameter dada 10. Pernafasan cuping hidung 11. Ortopnea 12. Fase ekspirasi 13. Pernafasan bibir 14. Takipnea 15. Penggunaan otot bantu pernafasan 16. Menggunakan posisi tiga titik Faktor yang berhubungan: 17. Ansietas 18. Posisi badan yang menghambat ekspansi paru 19. Deformitas tulang 20. Deformitas dinding dada 21. Kelelahan 22. Hiperventilasi 23. Sindrom hipoventilasi 24. Gangguan musculoskeletal 25. Neurologi imatur 26. Gangguan neurologis (EEG positif, trauma kepala, kejang) 29 27. Gangguan neuromuskular 28. Obesitas 29. Nyeri 30. Kelelahan otot respirasi 31. Spinal cord injuri NOC NIC Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama … x 24 jam pola nafas dapat efektif, dengan kriteria hasil : 1. Respiratory status: Ventilation (0403) 1. RR (5) 2. Irama nafas (5) 3. Kedalaman inspirasi (5) 4. Penggunaan otot bantu nafas (5) 5. Pernafasan bibir (5) 2. Respiratory status: Airway patency (0410) 1. Ansietas (5) 2. Cuping hidung (5) 3. Batuk (5) 3. Vital signs status (0802) 1. Suhu tubuh (5) 2. Irama nafas (5) 3. TD (5) 4. Nadi (5) Airway Management (3140) 1. Buka jalan nafas dengan menggunakan tehnik chin lift atau jaw thrust, jika diperlukan 2. Posisikan pasien memaksimalkan potensial ventilasi 3. Identifikasikan pasien kebutuhan actual atau potensial dalam insersi jalan nafas 4. Lakukan fisioterapi dada 5. Anjurkan mengeluarkan secret dengan batuk dan suction 6. Ajarkan latihan nafas dalam, dan cara batuk efektif 7. Auskultasi suara nafas, catat area yang mengalami penurunan atau ketiadaan ventilasi dan adanya suara tambahan 8. Kolaborasi pemberian bronkodilator, jika diperlukan 9. Monitor status RR dan oksigenasi Vital signs monitoring (6680) 1. Monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan 2. Catat tren dan fluktuasi tekanan darah 3. Monitor tekanan darah saat berbaring, duduk dan berdiri sebelum dan sesudah perubahan posisi 4. Monitor tekanan darah setelah pasien minum obat 5. Auskultasi tekanan darah di kedua tangan dan bandingkan, jika diperlukan 6. Monitor tekanan darah, nadi, dan 30 pernafasan sebelumnya, selama, dan setelah beraktifitas 7. Monitor unrtuk laporan tanda gejala hipotermia dan hipertermia 8. Monitor adanya dan kualitas nadi 9. Monitor suara jantung 10. Monitor frekuensi dan irama pernafasan 11. Monitor suara paru 12. Monitor oksimetri nadi 13. Monitor untuk pernafasan abnormal (seperti cheyne stokes, kusmaul, apnea) 14. Monitor warna kulit, suhu dan kelembapan 15. Monitor clubbing finger pada kuku 16. Identifikasi penyebab perubahan tanda-tanda vital Oxygen Therapy (3320) 1. Jaga kepatenan jalan napas 2. Instruksikan klien dan keluarga menjauhi sumber bau menyengat 3. Salurkan selang udara/alat bantu napas ke humidifier untuk menciptakan udara yang hangat untuk klien 4. Observasi tanda hipoventilasi atau hipertentilasi 5. Bersihkan jalan napas, mulut, hidung, sekret pada trakea, jika memungkinkan 6. Monitoring penggunaan alat bantu napas Emotional support (5270) 1. Diskusikan tentang pengalaman emosi pasien 2. Buat dukungan dan pernyataan empati 3. Beri dukungan dan sentuhan secara suportif 4. Bantu pasien untuk menjelaskan perasaannya, seperti ansietas, marah, atau sedih 5. Dorong pasien untuk menyatakan perasaannya 31 6. Fasilitasi pasien mengidentifikasi kebiasaan dalam merespon koping 7. Tetap bersama pasien dan jaga keamanan selama pasien merasa ansietas 8. Bantu dalam pengambilan keputusan 9. Lihat untuk konsultasi, jika diperlukan 3.3 Konsep Terapi Oksigenasi 3.3.1 Definisi terapi oksigenasi Terapi oksigen adalah memasukkan oksigen tambahan dari luar ke paru melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat sesuai kebutuhan. (Standar Pelayanan Keperawatan di ICU, Dep.Kes. RI, 2005). Terapi oksigen pertama kali dipakai dalam bidang kedokteran pada tahun 1800 oleh thomas Beddoes, kemudian dikembangkan oleh Alvan Barach pada tahun 1920 untuk pasien dengan hipoksemia dan penyakit paru obstruktif kronik. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen lebih dari udara atmosfer atau FiO2 > 21%. Oksigen (O2) adalah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel-sel tubuh. Oksigenasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung Oksigen (O2) ke dalam tubuh serta menghembuskan Karbondioksida (CO2) sebagai hasil sisa oksidasi. Penyampaian oksigen ke jaringan tubuh ditentukan oleh sistem respirasi (pernafasan), kardiovaskuler dan hematologi (Aziz, 2006). 3.3.2 Faktor yang memengaruhi oksigenasi (Aziz, 2006) 1. Faktor Fisiologi a. Menurunnya kapasitas pengikatan O2 seperti anemia b. Menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran napas bagian atas c. Hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transpor O2 terganggu d. Meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, luka dan lain-lain. 32 e. Kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, musculus skeleton yang abnormal, penyakit kronik seperti TBC paru. 2. Faktor Perkembangan a. Bayi prematur : disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan b. Bayi dan toodler : adanya resiko infeksi saluran pernafasan akut c. Anak usia sekolah dan remaja , resiko saluran pernafasan dan merokok d. Dewasa muda dan pertengahan : diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stress yang mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru e. Dewasa tua : adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan arteriosklerosis, elastisitas menurun, ekspansi paru menurun. 3. Faktor Perilaku a. Nutrisi : misalnya pada obesitas mengakibatkan penurunan ekspansi paru, gizi yang buruk menjadi anemia sehingga daya ikat oksigen berkurang, diet yang terlalu tinggi lemak menimbulkan arteriosklerosis, konsumsi makanan mengandung CO (carbon monoksida) b. Exercise (olahraga berlebih) : Exercise akan meningkatkan kebutuhan oksigen c. Merokok : nikotin menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner d. Substance abuse (alkohol dan obat-obatan) : menyebabkan intake nutrisi (Fe) menurun mengakibatkan penurunan hemoglobin, alkohol menyebabkan depesi pusat pernafasan e. Kecemasan : menyebabkan metabolisme meningkat 4. Faktor Lingkungan a. Tempat kerja (polusi) b. Suhu lingkungan c. Ketinggian tempat dari permukaan laut 33 3.3.3 Alat terapi oksigen 1. Nasal kanul Pemberian oksigen pada klien yang memerlukan oksigen secara kontinyu dengan kecepatan aliran 1-6 liter/menit serta konsentrasi 20-40%. Selang yang terbuat dari plastik dimasukkan ke dalam hidung dan dikaitkan di belakang telinga. Panjang selang yang dimasukan ke dalam lubang dihidung hanya berkisar 0,6-1,3 cm. Pemasangan nasal kanula merupakan cara yang paling mudah, sederhana, murah, relatif nyaman, mudah digunakan cocok untuk segala umur, cocok untuk pemasangan jangka pendek dan jangka panjang, dan efektif dalam mengirimkan oksigen. Pemakaian nasal kanul juga tidak mengganggu klien untuk melakukan aktivitas, seperti berbicara atau makan (Aryani, 2009). a. Tujuan 1) Memberikan oksigen dengan konsentrasi relatif rendah saat kebutuhan oksigen minimal. 2) Memberikan oksigen yang tidak terputus saat klien makan atau minum (Aryani, 2009). b. Indikasi Klien yang bernapas spontan tetapi membutuhkan alat bantu nasal kanula untuk memenuhi kebutuhan oksigen (keadaan sesak atau tidak sesak). (Suparmi, 2008). c. Prinsip 1) Nasal kanula untuk mengalirkan oksigen dengan aliran ringan atau rendah, biasanya hanya 2-3 L/menit 2) Membutuhkan pernapasan hidung 3) Tidak dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi >40% (Suparmi, 2008) 2. Masker Pemberian oksigen kepada klien dengan menggunakan masker yang dialiri oksigen dengan posisi menutupi hidung dan mulut klien. Masker oksigen umumnya berwarna bening dan mempunyai tali sehingga dapat mengikat kuat mengelilingi wajah klien. Bentuk dari face mask bermacam-macam. Perbedaan 34 antara rebreathing dan non-rebreathing mask terletak pada adanya vulve yang mencegah udara ekspirasi terinhalasi kembali. (Aryani, 2009). a. Macam bentuk masker 1) Simple face mask mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 40-60% dengan kecepatan aliran 5-8 liter/menit. 2) Rebreathing mask mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 60-80% dengan kecepatan aliran 8-12 liter/menit. Memiliki kantong yang terus mengembang baik, saat inspirasi maupun ekspirasi. Pada saat inspirasi, oksigen masuk dari sungkup melalui lubang antara sungkup dan kantung reservoir, ditambah oksigen dari kamar yang masuk dalam lubang ekspirasi pada kantong. Udara inspirasi sebagian tercampur dengan udara ekspirasi sehingga konsentrasi CO2 lebih tinggi daripada simple face mask. (Tarwoto&Wartonah, 2010). Indikasi : klien dengan kadar tekanan CO2 yang rendah. (Asmadi, 2008). 3) Non rebreathing mask, mengalirkan oksigen dengan konsentrasi sampai 80-100% dengan kecepatan aliran 10-12 liter/menit. Pada prinsipnya, udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi karena mempunyai 2 katup, 1 katup terbuka pada saat inspirasi dan tertutup saat pada saat ekspirasi, dan 1 katup yang fungsinya mencegah udara kamar masuk pada saat inspirasi dan akan membuka pada saat ekspirasi (Tarwoto& Wartonah, 2010). Indikasi : klien dengan kadar tekanan CO2 yang tinggi. (Asmadi, 2008). b. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Perhatikan reaksi klien sebelum dan sesudah pemberian O2 2) Penggunaan nasal kateter hendaknya diganti tiap 8 jam 3) Hindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan pasien 4) Jauhkan dari hal-hal yang dapat membahayakan 5) Harus selalu menggunakan humidifier untuk menghindari iritasi selaput lender pernafasan 6) Tidak boleh lebih dari 6 liter 7) Berikan O2 sesuai intruksi dokter 35 3.3.4 Standar operasional prosedur pemberian terapi oksigenasi 1. Persiapan alat Menyiapkan alat antara lain : a. Nasal kanul / masker sederhana / masker NRBM, sesuai ukuran pasien b. Selang oksigen c. Tabung oksigen dengan manometernya d. Humidifier e. Water steril (aquadest) / air matang / air mineral f. Flowmeter (pengukur aliran) g. Plester h. Gunting plester i. Alat tulis 2. Persiapan pasien 3. Persiapan tindakan a. Memberikan salam dan memperkenalkan diri b. Menempatkan pasien / keluarga dalam kondisi nyaman dan kondusif c. Menjelaskan tujuan dan proses pemberian terapi oksigenasi pada keluarga pasien d. Petugas menyiapkan inform concent untuk ditandatangani 4. Prosedur Pemasangan a. Alat-alat didekatkan pasien b. Cuci tangan c. Pasang manometer pada tabung oksigen d. Pasang flowmeter dan pastikan alirannya mati terlebih dahulu e. Pasang botol humidifier f. Sambung selang oksigenasi dengan humidifier g. Buka aliran flowmeter untuk mengecek aliran oksigen h. Atur aliran oksigen sesuai indikasi i. Pasang alat terapi oksigen pada pasien j. Amati respon pasien 36 k. Pasang plester untuk fiksasi l. Rapikan pasien dan alat-alat m. Dokumentasikan prosedur dan respon pasien 3.4 Konsep Kenyamanan 3.3.1 Definisi kenyamanan Konsep tentang kenyamanan (comfort) sangat sulit untuk didefinisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu (Oborne, 1995). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar; sehat sedangkan kenyamanan adalah keadaan nyaman; kesegaran; kesejukan. Kolcaba (2003) menjelaskan bahwa kenyamaan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebakan perasaan sejahtera pada diri individu tersebut. Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap lingkungannya. Manusia menilai kondisi lingkungan berdasarkan rangsangan yang masuk ke dalam dirinya melalui keenam indera melalui syaraf dan dicerna oleh otak untuk dinilai. Dalam hal ini yang terlibat tidak hanya masalah fisik biologis, namun juga perasaan. Suara, cahaya, bau, suhu dan lain-lain rangsangan ditangkap sekaligus, lalu diolah oleh otak. Kemudian otak akan memberikan penilaian relatif apakah kondisi itu nyaman atau tidak. Ketidaknyamanan di satu faktor dapat ditutupi oleh faktor lain (Satwiko, 2009). Sanders dan McCormick (1993) menggambarkan konsep kenyamanan bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan dan sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain secara langsung atau dengan observasi melainkan harus menanyakan langsung pada orang tersebut mengenai seberapa nyaman diri mereka, biasanya dengan menggunakan istilah-istilah seperti agak tidak nyaman, mengganggu, sangat tidak nyaman, atau mengkhawatirkan. Menurut Sugiarto (1999), nyaman adalah rasa yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya, serta senang dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga seseorang akan merasakan kenyamanan. Lain halnya dalam kamus 37 Indonesia, pengertian nyaman mempunyai arti enak dan aman, sejuk dan bersih, tenang dan damai. Sedangkan pengertian ketidaknyamanan adalah ketidaksenangan seseorang terhadap situasi dan kondisi tertentu sebab kondisi tersebut menyimpang dari batas kenyamanan, sehingga orang akan mengalami ketidaknyamanan (Sastrowinoto, 1981). 3.4.2 Aspek dalam kenyamanan Menurut Kolcaba (2003) aspek kenyamanan terdiri dari: 1. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan oleh individu itu sendiri. 2. Kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal diri, yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi. 3. Kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu, pencahayaan, suara, dll. 4. Kenyamanan sosial kultural berkenaan dengan hubungan interpesonal, keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, perawatan kesehatan individu, kegiatan religius, serta tradisi keluarga). 3.4.3 Faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan Faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan menurut Wingjosoebroto (2000) ialah sebagai berikut: 2. Sirkulasi Kenyamanan dapat berkurang karena sirkulasi yang kurang baik, seperti, atau tidak ada pembagian sirkulasi antara ruang satu dengan lainnya. Sirkulasi dibedakan menjadi dua yaitu sirkulasi di dalam ruang dan sirkulasi di luar ruang atau peralihan antara dalam dan luar. Udara disekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen, 0,03% karbondioksida, dan 0,9% campuran gas-gas lain. Kotornya udara disekitar kita dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan mempercepat proses kelelahan. Sirkulasi udara akan menggantikan udara kotor dengan udara yang bersih. Agar sirkulasi terjaga dengan baik, dapat ditempuh dengan memberi ventilasi yang 38 cukup (lewat jendela), dapat juga dengan meletakkan tanaman untuk menyediakan kebutuhan akan oksigen yang cukup (Wignjosoebroto,1995). 3. Iklim Suhu yang diperkirakan cukup nyaman untuk ruang istirahat diberbagai keadaan ialah 24°C. Rumah sakit merupakan sumber dari terjadinya penularan penyakit, jika suhu telah rendah dan kelembaban terlalu tinggi akan dapat mempermudah berkembangbiaknya bakteri, jamur, virus dan berbagai macam bibit penyakit yang lain (Suyatno,1981). 4. Kebisingan Kebisingan adalah salah satu masalah pokok yang bisa mengganggu kenyamanan. 5. Bau-bauan Adanya bau-bauan yang dipertimbangkan sebagai “polusi” akan dapat mengganggu kenyamanan seseorang. Temperatur dan kelembaban adalah dua faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian air conditioning yang tepat adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu (Wignjosoebroto, 1995). 6. Keamanan Keamanan merupakan masalah terpenting, karena ini dapat mengganggu dan menghambat aktivitas yang akan dilakukan. Keamanan bukan saja berarti dari segi kejahatan (kriminal), tapi juga termasuk kekuatan konstruksi, bentuk ruang, dan kejelasan fungsi. 7. Kebersihan Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi, juga menambah rasa nyaman karena bebas dari kotoran sampah ataupun bau-bauan yang tidak sedap. 8. Penerangan Untuk mendapatkan penerangan yang baik dalam ruang perlu memperhatikan beberapa hal yaitu cahaya alami, kuat penerangan, kualitas cahaya, daya penerangan, pemilihan dan perletakan lampu. Tata pencahayaan dalam ruang rawat inap dapat mempengaruhi kenyamanan pasien selama menjalani rawat inap, disamping juga berpengaruh 39 bagi kelancaran paramedis dalam menjalankan aktivitasnya untuk melayani pasien (Santosa, 2004). Penerangan di rumah sakit, merupakan hal yang sangat penting. Hal ini, karena penerangan di rumah sakit berhubungan dengan keselamatan pasien yang sedang dirawat, petugas dan pengunjung rumah sakit. Selain itu penerangan yang mencukupi akan meningkatkan pencermatan, kesehatan yang lebih baik dan suasana yang nyaman (Sastrowinoto, 1985). Dalam Kepmenkes No 1204 tahun 2004, standar pencahayaan pada rumah sakit intensitas pencahayaan untuk ruang pasien saat tidak tidur sebesar 100-200 lux dengan warna cahaya sedang, sementara pada saat tidur maksimum 50 lux dan toilet minimal 100 lux. 3.4.4 Asuhan keperawatan gangguan rasa nyaman Gangguan Rasa Nyaman (00214) Definisi Merasa kurang nyaman, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, budaya, dan atau sosial. Batasan karakteristik: 1. Ansietas 2. Berkeluh kesah 3. Gangguan pola tidur 4. Gatal 5. Gejala distres 6. Gelisah 7. Iritabilitas 8. Ketidakmampuan untuk relaks 9. Kurang puas dengan keadaan 10. Menangis 11. Merasa dingin 12. Merasa kurang senang dengan situasi 13. Merasa hangat 14. Merasa lapar 15. Merasa tidak nyaman 16. Merintih 40 17. Takut Faktor yang berhubungan: 1. Gejala terkait penyakit 2. Kurang kontrol situasi 3. Kurang pengendalian lingkungan 4. Kurang privasi 5. Program pengobatan 6. Stimuli lingkungan yang mengganggu 7. Sumber daya tidak adekuat (mis., finansial, pengetahuan dan sosial) NOC NIC Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam pasien dapat merasa nyaman Environment Managemet : Comfort (6482) 1. Memudahkan transisi pasien dan keluarga dengan hangat menyambut mereka dengan lingkungan baru 2. Mencegah gangguan yang tidak perlu dan memungkinkan untuk waktu istirahat 3. Buat tenang dan lingkungan yang mendukung 4. Menyediakan lingkungan yang aman dan bersih 5. Menentukan sumber ketidaknyamanan, seperti dressing lembab, posisi tabuh, dressing tidak adekuat, seprai lucek, dan gangguan lingkungan 6. Sesuaikan suhu kamar dengan yang paling nyaman bagi individu, jika memungkinkan 7. Memfasilitasi langkah-langkah kebersihan untuk menjaga nyaman individu (misalnya, menyeka alis, menerapkan krim kulit, atau membersihkan tubuh, rambut, dan rongga mulut) 8. Posisi pasien untuk memfasilitasi kenyamanan 9. Pantau kulit, terutama di lipatan tubuh, tanda-tanda tekanan atau iritasi Kriteria Hasil : 1. Comfort Status: Environment (2009) (1) Lingkngan kondusif untuk tidur (5) (2) Kebersihan lingkungan (5) (3) Kenyamanan fisik (5) (4) Tempat tidur yang nyaman (5) 41 Relaxation Therapy (6040) 1. Jelaskan alasan untuk relaksasi dan manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (misalnya, terapi musik, meditasi, bernapas dalam, dan relaksasi otot progresif) 2. Tentukan apakah intervensi relaksasi dapat dilakukan pada klien 3. Pertimbangkan kesediaan individu untuk berpartisipasi, kemampuan untuk berpartisipasi, pengalaman masa lalu, dan kontraindikasi, sebelum memilih strategi relaksasi tertentu 4. Memberikan penjelasan rinci tentang intervensi relaksasi yang dipilih 5. Anjurkan pasien untuk bersantai dan membiarkan masalah (penyakit) terjadi 6. Gunakan suara yang lemah lembut ketika mengajak berinteraksi 7. Meminta klien demonstrasikan kembali teknik relaksasi, jika memungkinkan Massage (1480) 1. Kaji kontrandikasi intervensi pijat (seperti penurunan integritas kulit, peradangan, hipersensitivitas kulit) 2. Tanyakan kesediaan klien untuk di pijat 3. Buatlah kontrak waktu untuk pijat 4. Pilih area tubuh yang akan dipijat 5. Posisikan klien senyaman mungkin sebelum pijat 6. Gunakan lotion, minyak, bedak untuk mnegurasi gesekan tangan pemijat kan kulit klien 7. Pijat secara perlahan dan terusmenerus 8. Minta klien untuk menikmati pijatan pada fase akhir pijatan sebelum melakukan perubahan 42 posisi atau aktivitas lain 9. Mengevaluasi respon intervensi dan dokumentasi hasil Positioning (0840) 1. Berikan posisi yang nyaman kepada klien 2. Dorong klien untuk berpartisipasi dalam perubahan posisinya 3. Posisikan klien untuk engurangi dispnea, jika memungkinkan 4. Hindari memosisikan klien yang dapat memicu nyeri 5. Minimalkan gesekan saat merubah posisi klien 6. Ubah posisi klien minimal setiap 2 jam untuk menghindari komplikasi BAB 4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang menimbulkan banyak menimbulkan efek bagi tubuh serta berisiko menimbulkan berbagai komplikasi. Kebutuhan dasar pasien Diabetes Mellitus mulai dari pernapasan, sirkulasi hingga eliminasi dapat mengalami gangguan akibat proses penyakit, sehingga pasien memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya tersebut. 4.2 Saran Tenaga kesehatan khususnya perawat diharapkan mampu memberikan asuhan secara holistik, tidak hanya dari aspek fisik namun juga seluruh aspek kebutuhan dasar manusia meliputi aspek psikologi, sosial, kultural dan spiritual. 43 44 DAFTAR PUSTAKA Aryani, R. dkk., 2009. Prosedur Klinik Keperawatan Pada Mata Ajar Kebutuhan Dasar Manusia. Jakarta : C.V. Trans Info Media. Asmadi. 2008. Teknik Prosedural Keperawatan dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien. Jakarta: Salemba Medika. Aziz, Alimul. 2006. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia vol.1. EGC: Jakarta. Boedisantoso, R.A., Soegondo, S., Suyono, S., Waspadji, S., Yulia, Tambunan dan Gultom. 2009. Penatalaksanaan Diabetes Melitus Terpadu. Jakarta: FKUI. Bulechek, G., Butcher, H. and Dochterman, J. (2013). Nursing Interventions Classification (NIC) Sixth Edition. USA: Mosby Elsevier. Carpenito, L. J. 2001. Buku Saku Diagnosa Keperawatan. Terjemahan oleh Monica Ester.Jakarta: EGC. Direktur Gizi Masyarakat Dirjen BinKesMasy DepKes RI. 2003. Diabetes dan Pencegahannya. Eliana, F. 2015. Penatalaksanaan DM Sesuai Konsesnsus PERKENI 2015. [Manuscript]http://www.pdui-pusat.com/wpcontent/uploads/2015/12/SATELIT-SIMPOSIUM-6.1-DM-UPDATE-DAN-Hb1C-OLEH-DR.Dr.-Fatimah-Eliana-SpPD-KEMD.pdf, Jakarta. Fatimah, R.N. 2015. Diabetes Melitus Tipe 2. J. Majority 4(5). Health Care And Research: New York: Spinger Publishing Company. Kolcaba, Katherine. 2003. Comfort Theory And Practice: A Vision For Holistic Masjoer, Arief. 2000. Kapita Selekta Kedokteran Edisi 3 Jilid 1. Jakarta: Media Aesculapius, FKUI. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan. Moorhead, Sue., Johnson, M. et., al. (2013) Nursing Outcomes Classifications (NOC) Measurement of Health Outcomes Fifth Edition. USA: Mosby Elseiver Mubarak, Wahit Iqbal, dkk. 2007. Kebutuhan Dasar Manusia : Teori & Aplikasi dalam Praktik. Gresik : EGC. NANDA. 2014. Nursing Diagnosis: definitions and Classification 2015-2017. Tenth Edition. NANDA International Ndraha, S. 2014. Diabetes Melitus Tipe 2 Dan Tatalaksana Terkini. Medicinus, 27(2). Oborne, David J. 1995. Ergonomic at Work: Human Factors in Design and Development. England: John Wiley and Sonds Ltd. 45 Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. 2011. Konsensus Pengendalian dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. PB PERKENI: Jakarta Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. Situasi dan Analisis Diabetes. Infodatin. Riset Kesehatan Dasar. 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sanders, Mark S & McCormick, Ernest J. 1993. Human Factor in Engineering and Design. New York: McGraw-Hill,Inc. Santoso, Gempur. 2004. Ergonomi Manusia, Peralatan dan Lingkungan. Sastrowinoto, Suyatno. 1981. Meningkatkan Produktivitas dengan Ergonomi. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. Satwiko. 2009. Pengertian Kenyamanan Dalam Suatu Bangunan. Yogyakarta: Wignjosoebroto. Soegondo. 2003. Penderita Diabetes di Indonesia Capai 12 Juta Orang. Banjarmasin Post. Kamis, 13 Januari 2005 15:56:22 WIB. Available: http://pdpersi.pdpersi. co.id/pdpersi/news/ cakrawala.php3? id=2994. Diakses tanggal 22 September 2016 Sugiarto, Endar 1999. Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Suparmi, Yulia. 2008. Kebutuhan Dasar Manusia. Yogyakarta : PT Citra Aji Parama. Wahyudi, A.S, Wahid, A, 2016. Ilmu Keperawatan Dasar, Jakarta: Mitra Wacana Media. Wignjosoebroto, Sritomo. 1995. Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu. Surabaya: PT. Guna Widya. Wignjosoebroto,S. 2000. Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu Teknik Analisis untuk Peningkatan Produktivitas Kerja. Edisi I cetakan Kedua, Penerbit Guna widya, Surabaya. Zulmiar Y, Harjani S, Yusuf M. Himpunan Peraturan Perundangan Kesehatan Kerja. PT. Citratama Bangun Mandiri, Jakarta ,editor 1999. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/5/jtptunimus-gdl-s1-2008-agussoekar-2382-bab2.pdf> diakses pada 21 Sepetember 2016 46 Lampiran 1 FORMAT LAPORAN ASUHAN KEPERAWATAN BERDASARKAN FORMAT HENDERSON ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN NY. L DENGAN DIAGNOSA MEDIS DM TIPE 2 + HIPERGLIKEMIA + SEPSIS+ POST STROKE + AKI DENGAN GANGGUAN RASA NYAMAN DI RUANG PANDAN WANGI TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016 PENGKAJIAN 1. Identitas a. Identitas Pasien Nama : Ny. L Umur : 70 tahun Agama : Islam Jenis Kelamin : Perempuan Status : Kawin Pendidikan : Tamat SD Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Suku Bangsa : Indonesia Alamat : Kalijaran Sambikerep, RT 06/RW 05 Surabaya, Tanggal Masuk : 14 – 09 - 2016 Tanggal Pengkajian : 15 – 09 - 2016 No. Register : 1253.xx.xx Diagnosa Medis : DM Tipe 2 + Hiperglikemia + Sepsis + Post stroke + AKI b. Identitas Penanggung Jawab Nama : Ny. R Umur : 38 tahun Hub. Dengan Pasien : Anak Pekerjaan : Wiraswasta 47 Alamat : Kalijaran Sambikerep 2. Status Kesehatan a. Status Kesehatan Saat Ini 1) Keluhan Utama (Saat MRS dan saat ini) Saat MRS : Penurunan kesadaran dan febris, lemas, pasien cenderung tidur terus, demam sejak 2 hari, naik turun, batuk (-), muntah (+) Saat ini : Merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah sakit sehingga merasa gelisah dan terlihat tanda gejala gelisah yaitu mata merah dan sering merubah posisi tangannya yang terpasang infus 2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya Membawa keluarga ke Rumah Sakit dan saat dirumah sakit mengikuti prosedur rejimen erapeutik yaitu pemasangan alat bantu napas (nasl kanul) b. Status Kesehatan Masa Lalu 1) Penyakit yang pernah dialami Stroke 11 tahun yang lalu, hipertensi ± 20 tahun Pernah dirawat : Pernah Alergi : Tidak ada 2) Kebiasaan (merokok/kopi/alkohol dll) Minum marimas setiap hari 3) Riwayat Penyakit Keluarga Tidak ada 4) Diagnosa Medis dan therapy DM Tipe 2 + Hiperglikemia + Sepsis E.C + Post stroke + AKI 5) Terapi : - Diet B1 2100 kkal/hari - Terpasang infus : PZ 21 tpm - Injeksi ceftriaxone 2 x 1 gram - Injeksi ranitidin 2 x 1 gram - Injeksi Novorapid 3 x 8 unit SC - Diet sonde 150 ml susu/6x/hari - Injeksi Alkalamin F 2 x 1 amp IV 48 - O2 nasal 3 lpm 3. Pola Kebutuhan Dasar (Bio-psiko-sosio-kultural-spiritual) a. Pola bernapas Sebelum sakit : Tidak ada masalah Saat sakit : Sulit bernafas, RR = 36x/mnt, memakai O2 nasal kanul 3 lpm b. Pola makan-minum Sebelum sakit : Makan sehari 3 kali sehari, kadang nyamil gorengan, minum minuman rasa-rasa saat panas Saat sakit : Menggunakan bantuan sonde susu 150 ml/6x/hari untuk makan dan minum. BB : 70 Kg c. Pola eliminasi Sebelum sakit : Tidak ada masalah Saat sakit : ± 1000 ml/hari, terpasang kateter 13 September 2016, urin bening tidak ada darah, beum melakukan BAB selama 2 hari terakhir d. Pola aktivitas dan latihan Sebelum sakit : biasanya pasien mampu berjalan-jalan, menyapu halaman setiap pagi Saat sakit : Tidak bisa beraktivitas, berbaring di bed e. Pola istirahat dan tidur Sebelum sakit : Tidak ada masalah, tidur pukul 20.00-05.00 Saat sakit : Sulit tidur karena tidak nyaman, disebabkan karena bising f. Pola berpakaian Sebelum sakit : Sehari mengganti baju sekali secara mandiri Saat sakit : Tidak menggunakan baju, menutupi tubuhnya dengan sarung g. Pola rasa nyaman Sebelum sakit : Tidak ada masalah Saat sakit : Pasien mengeluh ingin pulang karena tidak nyaman yang disebabkan suara bising di ruangan h. Pola aman Sebelum sakit : Tidak ada masalah Saat sakit : Pasien gelisah ingin segera pulang ke rumah i. Pola Kebersihan Diri 49 Sebelum sakit : Pasien mandi sehari 2x, sikat gigi sehari 2x, keramas seminggu 3x Saat sakit : Hanya diseka saja sehari 2x, tidak sikat gigi j. Pola Komunikasi Sebelum sakit : Bisa berkomunikasi dengan baik, merespon pertanyaan dengan baik Saat sakit : Kadang-kadang mengigau dan marah-marah k. Pola Beribadah Sebelum sakit : Sholat 5 waktu dalam sehari Saat sakit : Hanya mengucap istighfar, tidak sholat l. Pola Produktifitas Sebelum sakit : Dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik Saat sakit : Pekerjaan sehari-hari terganggu karena sakit m. Pola Rekreasi Sebelum sakit : Tidak ada masalah Saat sakit : Butuh dukungan dari, keluarga, saudara, dan teman n. Pola Kebutuhan Belajar Sebelum sakit : Klien jarang menonton televisi dan tidak pernah membaca koran Saat sakit : Tidak melakukan proses belajar dan petugas kesehatan memberikan langsung penjelasan pengobatan dan penyakit diberikan kepada keluarga klien 4. Pengkajian a. Keadaan umum : Tingkat kesadaran : komposmetis / apatis / somnolen / sopor/koma GCS : Mata : 4 Verbal: 5 Psikomotor : 6 b. Tanda-tanda Vital : Nadi = 90 x/mnt, Suhu = 37oC, TD =120/80 mmhg, RR = 36x/mnt c. Keadaan Fisik 1) Kepala dan leher : Tidak ada lesi, tidak ada masalah 2) Dada Paru Jantung : Tidak ada masalah, takipnea : Suara S1 dan S2 reguler 50 3) Payudara dan ketiak : Tidak ada masalah 4) Abdomen : Tidak ada asites 5) Genetalia : Genetalia bersih, memakai pampers 6) Integumen : Gatal-gatal di bagian paha dan lutut sebelah kanan 7) Ekstremitas Atas : Tangan kiri beserta jari-jarinya lumpuh Bawah : Kaki sebelah kiri lumpuh 8) Neurologis Status mental dan emosi : Saat malam hari pasien marah-marah ingin pulang Pengkajian saraf kranial : Tidak terkaji Pemeriksaan refleks : Tidak terkaji d. Pemeriksaan Penunjang 1) Data laboratorium yang berhubungan Jenis Pemeriksaan Indikator Hasil Nilai Normal Kimia Klinik LDH-P HDL 230 U/L 125-220 U/L Albumin 3.68 g/dl 3.40-5.00 g/dl Direk Bilirubin Bilirubin Direk 0.23 mg/dl Total Bilirubin 0.49mg/dl CRP Kimia Hematologi Elektrolit Lain-lain Analisa Gas Darah CRP Kimia 205,38 0.00-10.00 mg/L APTT 33.1 detik 23-33 detik Kontrol APTT 24 detik PTT 14.5 detik Kontrol PTT 11 detik Natrium 141 mmol/l 136-144 mmol/l Kalium 3.8 mmol/l 3.8-5.0 mmol/l Klorida 105 mmol/l 97-103 mmol/l HBS-Ag Reaktif Reaktif HIV Rapid Test Non reaktif Non reaktif pH 7.383 9-12 detik 51 Urine Lengkap pCO2 29.7 mmhg pO2 105 mmhg HCO3- 17.9 mmol/l TCO2 18.8 mmol/l SO2 98.1 aADO2 6.8 mmhg BE-b -4.8 mmol/l SBC 20.6 mmol/l a/A 0.9 RI 0.1 PO2/FiO2 500.2 mmHg TempP 37.0 deg C TempH 37.0 deg C GLU BIL KET SG BLD pH Negatif Negatif 1010-1015 1020 Negatif 6-8 5.5 1+ Negatif URO 3.2 <17 umol/L Negatif LEU Negatif Negatif Negatif Eritrosit 0-2/ Lp 0-2/ Lp Leukosit 0-2/ Lp 0-5/ Lp Color Yellow Clarity Clear Epitel Foto dada dan thoraks Sedikit/ Lp normal Hasil konsultasi Negatif Negatif PRO NIT Radiologi Negatif 2+ Terapi insulin 8 unit Sedikit 52 Pemeriksaan EKG - Sinus Tachikardi Axis Normal - HR 115 bpm - PR interval 162 ms - QRS duur. 70 - QT/QTc 286/393 ms - P-R-T Akses 59 20/141 diagnostik lain e. Analisa Data DATA INTERPRETASI (sesuai dengan patofisioligi) DS : Pasien mengeluh sesak napas Diabetes Melitus DO : 4. Pola napas pasien yaitu 36x/menit 5. Pasien tampak gelisah 6. Menggunakan alat bantu napas O2 nasal 3 lpm Peningkatan gliserol Lipolisis Peningkatan keton (BUN) Ketoasidosis Asidosis Metabolik Hiperventilasi Ketidakefektifan pola napas MASALAH KEPERAWATAN Ketidakefektifan Pola Napas 53 DS : Pasien mengatakan lelah, ingin beristirahat, namun lingkungan berisik Hospitalisasi Gangguan Rasa Nyaman Lingkungan tidak kondusif Istirahat terganggu DO : 5. Pasien terlihat tidak bisa beristirahat 6. Situasi lingkungan berisik 7. Terdapat tanda-tanda stres (mata merah, gelisah, sering memindahkan tangannya yang terpasang infus) 8. Pasien tidak tenang f. Gangguan rasa nyaman Daftar Diagnosa Keperawatan/Masalah Kolaboratif Berdasarkan Prioritas No 1. Tanggal/jam 15 September 2016 Diagnosa Keperawatan Ketidakefektifan pola napas (000032) berhubungan dengan hiperventilasi Tanggal Teratasi Belum teratasi 2. 15 September 2016 Gangguan rasa nyaman (000214) berhubungan dengan perasaan tidak nyaman, perasaan terganggu, tidak dapat beristirahat Belum teratasi g. Rencana Tidakan Keperawatan Rencana Tindakan Hari/tanggal 15 September 2016 NOC NIC Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam pola napas klien menjadi adekuat Airway Management (3140) 1. Buka jalan nafas dengan menggunakan tehnik chin lift atau jaw thrust, jika diperlukan 2. Posisikan pasien memaksimalkan potensial ventilasi 3. Identifikasikan pasien kebutuhan actual atau potensial dalam insersi jalan nafas 4. Lakukan fisioterapi dada 5. Anjurkan mengeluarkan secret dengan batuk dan suction 6. Ajarkan latihan nafas dalam, dan Kriteria Hasil : 1. Status respirasi (0415) (1) Ritme pernapasan (5) (2) Kepatenan jalan napas (5) (3) Respiartory Rate (5) 54 cara batuk efektif 7. Auskultasi suara nafas, catat area yang mengalami penurunan atau ketiadaan ventilasi dan adanya suara tambahan 8. Kolaborasi pemberian bronkodilator, jika diperlukan 9. Monitor status RR dan oksigenasi Vital signs monitoring (6680) 1. Monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan 2. Catat tren dan fluktuasi tekanan darah 3. Monitor tekanan darah saat berbaring, duduk dan berdiri sebelum dan sesudah perubahan posisi 4. Monitor tekanan darah setelah pasien minum obat 5. Auskultasi tekanan darah di kedua tangan dan bandingkan, jika diperlukan 6. Monitor tekanan darah, nadi, dan pernafasan sebelumnya, selama, dan setelah beraktifitas 7. Monitor unrtuk laporan tanda gejala hipotermia dan hipertermia 8. Monitor adanya dan kualitas nadi 9. Monitor suara jantung 10. Monitor frekuensi dan irama pernafasan 11. Monitor suara paru 12. Monitor oksimetri nadi 13. Monitor untuk pernafasan abnormal (seperti cheyne stokes, kusmaul, apnea) 14. Monitor warna kulit, suhu dan kelembapan 15. Monitor clubbing finger pada kuku 16. Identifikasi penyebab perubahan tanda-tanda vital Oxygen Therapy (3320) 1.Jaga kepatenan jalan napas 2. Instruksikan klien dan keluarga menjauhi sumber bau menyengat 3. Salurkan selang udara/alat bantu napas ke humidifier untuk menciptakan udara yang hangat untuk klien 4. Observasi tanda hipoventilasi atau 55 hipertentilasi 5. Bersihkan jalan napas, mulut, hidung, sekret pada trakea, jika memungkinkan 6. Monitoring penggunaan alat bantu napas 15 September 2016 Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam pasien dapat merasa nyaman Kriteria Hasil : 2. Comfort Status: Environment (2009) (5) Lingkngan kondusif untuk tidur (5) (6) Kebersihan lingkungan (5) (7) Kenyamanan fisik (5) (8) Tempat tidur yang nyaman (5) Emotional support (5270) 1. Diskusikan tentang pengalaman emosi pasien 2. Buat dukungan dan pernyataan empati 3. Beri dukungan dan sentuhan secara suportif 4. Bantu pasien untuk menjelaskan perasaannya, seperti ansietas, marah, atau sedih 5. Dorong pasien untuk menyatakan perasaannya 6. Fasilitasi pasien mengidentifikasi kebiasaan dalam merespon koping 7. Tetap bersama pasien dan jaga keamanan selama pasien merasa ansietas 8. Bantu dalam pengambilan keputusan 9. Lihat untuk konsultasi, jika diperlukan Environment Managemet : Comfort (6482) 10. Memudahkan transisi pasien dan keluarga dengan hangat menyambut mereka dengan lingkungan baru 11. Mencegah gangguan yang tidak perlu dan memungkinkan untuk waktu istirahat 12. Buat tenang dan lingkungan yang mendukung 13. Menyediakan lingkungan yang aman dan bersih 14. Menentukan sumber ketidaknyamanan, seperti dressing lembab, posisi tabuh, dressing tidak adekuat, seprai lucek, dan gangguan lingkungan 15. Sesuaikan suhu kamar dengan yang paling nyaman bagi individu, jika memungkinkan 16. Memfasilitasi langkah-langkah kebersihan untuk menjaga 56 nyaman individu (misalnya, menyeka alis, menerapkan krim kulit, atau membersihkan tubuh, rambut, dan rongga mulut) 17. Posisi pasien untuk memfasilitasi kenyamanan 18. Pantau kulit, terutama di lipatan tubuh, tanda-tanda tekanan atau iritasi Relaxation Therapy (6040) 8. Jelaskan alasan untuk relaksasi dan manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (misalnya, terapi musik, meditasi, bernapas dalam, dan relaksasi otot progresif) 9. Tentukan apakah intervensi relaksasi dapat dilakukan pada klien 10. Pertimbangkan kesediaan individu untuk berpartisipasi, kemampuan untuk berpartisipasi, pengalaman masa lalu, dan kontraindikasi, sebelum memilih strategi relaksasi tertentu 11. Memberikan penjelasan rinci tentang intervensi relaksasi yang dipilih 12. Anjurkan pasien untuk bersantai dan membiarkan masalah (penyakit) terjadi 13. Gunakan suara yang lemah lembut ketika mengajak berinteraksi 14. Meminta klien demonstrasikan kembali teknik relaksasi, jika memungkinkan Massage (1480) 10. Kaji kontrandikasi intervensi pijat (seperti penurunan integritas kulit, peradangan, hipersensitivitas kulit) 11. Tanyakan kesediaan klien untuk di pijat 12. Buatlah kontrak waktu untuk pijat 13. Pilih area tubuh yang akan dipijat 14. Posisikan klien senyaman mungkin sebelum pijat 15. Gunakan lotion, minyak, bedak 57 untuk mnegurasi gesekan tangan pemijat kan kulit klien 16. Pijat secara perlahan dan terusmenerus 17. Minta klien untuk menikmati pijatan pada fase akhir pijatan sebelum melakukan perubahan posisi atau aktivitas lain 18. Mengevaluasi respon hasil intervensi dan dokumentasi Positioning (0840) 7. Berikan posisi yang nyaman kepada klien 8. Dorong klien untuk berpartisipasi dalam perubahan posisinya 9. Posisikan klien untuk engurangi dispnea, jika memungkinkan 10. Hindari memosisikan klien yang dapat memicu nyeri 11. Minimalkan gesekan saat merubah posisi klien 12. Ubah posisi klien minimal setiap 2 jam untuk menghindari komplikasi h. Implementasi Keperawatan Hari/Tanggal/ Jam Kamis/15 September 2016/11.45 No.Dx Implementasi 1 Evaluasi Proses 1. Menganjurkan keluarga 1. Pasien menolak untuk memosisikan pasien diposisikan senyaman mungkin semi-fowler 2. Ajarkan latihan nafas karena merasa dalam, dan cara batuk tidak nyaman efektif 3. Monitor tekanan darah, 2. Pasien mengerti nadi, suhu, dan status dan menerapkan pernafasan napas dalam 4. Monitoring ritme napas 5. Membantu pasien mendapatkan posisi yang nyaman dan optimal untuk mendapatkan ventilasi optimal 6. Memonitoring keadaan dan penggunaan alat bantu napas (nasal kanul) 7. Observasi tanda-tanda hiperventilasi TTD 58 Jumat/16 September 2016/11.45 i. 1 1. Mengkaji kebutuhan klien 1. Keluarga baru untuk dilakukan relaksasi memahami apa 2. Menjelaskan fungsi itu relaksasi relaksasi 3. Menjelaskan teknik 2. Keluarga memeraktekkan relaksasi yang dapat dilakukan oleh keluarga teknik pemijatan 4. Mengajarkan teknik kepada klien relaksasi kepada keluarga setelah 5. Menganjurkan keluarga dicontohkan untuk memosisikan klien senyaman mungkin 6. Mengkaji pemijatan pada klien untuk meningkatkan kenyamanan pada diri 7. Menjelaskan kepada keluarga bahwa tehnik massage (pemijatan) dapat membuat rileks tubuh 8. Menunjukkan kepada keluarga bagaimana melakukan massage yang tepat. 9. Memilih anggota tubuh yang dapat dilakukan pemijatan 10. Setelah mengajarkan keluarga cara untuk memijat, bisa menggunakan minyak atau lotion saat memijat atau mencuci tangan dengan air hangat 11. Monitoring penggunaan alat bantu napas Evaluasi No Hari/Tanggal/Jam No. Evaluasi Dx 1 Jumat/ 16 Sep 1 2016/ 13.45 S : pasien menyatakan sesak berkurang, namun belum hilang, O : RR = 27x/menit, pasien nampak sesak, penggunaan otot bantu napas A : masalah belum teratasi P : intervensi dilanjutkan 2 Jumat/ 16 Sep 2 S : pasien merasa nyaman setelah diberikan relaksasi : pijat TTD 59 2016/ 13.45 O : pasien tampak nyaman saat diberikan pemijatan A : masalah belum teratasi P : intervensi dilanjutkan