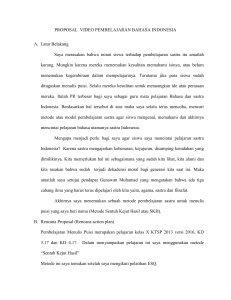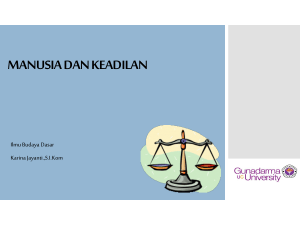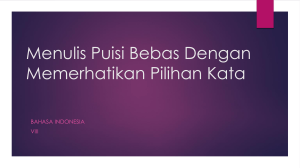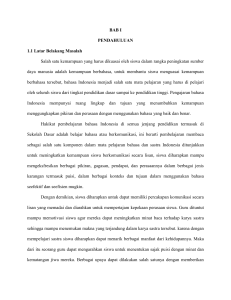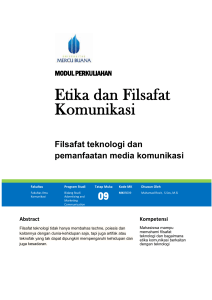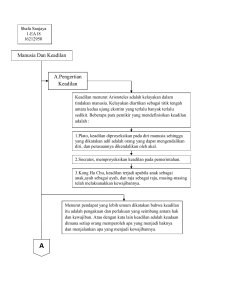Uploaded by
Shiny Ane El'poesya
Plato tells us what this bringing is in a sentence from the Symposium
advertisement

“Plato tells us what this bringing is in a sentence from the Symposium (205b): he gar toi ek tou me onton eis to on ionti hotoioun aitia pasa esti poiesis. ‘Every occasion for whatever passes over and goes forward into presencing from that which is not presencing is poiesis, is bringingforth [Her-vor-bringen].’” (Heidegger, The Question Concerning Technology). ANDAI kita sekadar bermain-main saja dan bertanya pada banyak orang–pada para pegiat sastra dan literasi, atau membaca buku-buku soal pembelajaran sastra hingga saat ini, “Apa puisi itu?”, maka bisa jadi hampir 99,75% mereka akan menjawab, puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang bukan prosa dan bukan drama. Atau ada yang coba menjawab secara definitif, bahwa puisi adalah satu jenis karya sastra yang dalam segi penulisannya ditentukan oleh aturan-aturan rima, metrum, metafora, kata-kata “indah-berbunga”, dst.. Atau mungkin ada satu dua orang yang hendak coba menjawabnya dengan menggunakan pendekatan etimologis, bahwa puisi berasal dari kata Poiesis (Yunani) yang artinya “menciptakan”, yang dalam kelanjutannya, kembali dirujuk pengertian terminologis: penyair adalah pencipta sajak, syair, dst. padahal jelas, pengertian yang kesemuanya itu amat lebih dekat pada kekeliruan. Benar, bahwa akar kata puisi yang selama ini kita gunakan adalah berasal dari kata Poiesis (Yunani), namun alih bahasa yang tepat dari Poiesis adalah “membuat” (in making) dan bukan “mencipta” (creating). Sebab kata “membuat” berarti mengandung makna pekerjaan mengolah kembali (membentuk kembali) sebuah bahan dasar, sedangkan kata “mencipta” berarti benarbenar memulai sesuatu dari nol. Dan dalam sejarah pembentukan teori soal Poiesis ini, di Yunani, persoalan “menciptakan dari nol” tidak mendapatkan tempat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia; menciptakan adalah pekerjaan dewa. Meskipun pula, dalam sejarah Yunani, ada yang mengembangkan gagasan bahwa seorang penggubah “sajak”, sebagiannya adalah mereka yang telah dipengaruhi oleh kekuatan “setengah dewa”, seperti misalnya dalam dialog tentang Ion; Plato sempat merekam pendapat Ion kepada Socrates yang menekankan bahwa ia hanyalah seorang rhapsodist yang hanya mengikuti “pengetahuan” seorang penggubah sajak epik (Homerus) yang telah mendapatkan pengaruh langsung dari dewa. Namun dalam bagian yang lain dialog Ion, Plato membatasi pengaruh itu hanya sebatas ermeneus tou theou, yang artinya hanya sebagai “penafsir” dari isyarat yang diberikan para dewa (534 e). Sebagian kecil (sekali) dari antara kita mungkin sudah bisa mengucapkan bahwa puisi (Poiesis) adalah satu genre (tipe) sepertihalnya Drama, dan bukan merupakan satu model cara ungkap (bentuk) seperti sajak (persajakan), di mana puisi (juga Drama) bisa ditulis baik dalam bentuk prosa, maupun sajak, meskipun pernyataan kategoris demikian pula belum sepenuhnya tepat. Sebab, kata Poiesis sendiri berasal dari kata “Poiein” (: buat) dengan tambahan “is” di akhir, yang memberi efek arti sebagai sebuah “kerja” (ex. Mime: Tiru. Mime-sis: Aktivitas meniru), sehingga Poiesis akan lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah aktivitas membuat sebuah karya melalui teknik dan keahlian tertentu–pada saat itu keahlian mimetik. Soal kategorisasi, Aristoteles telah coba menjelaskannya dalam “Poetics”, bahwa Poiesis dalam wujudnya saat itu telah mengambil berbagai macam bentuk yang termasuk di dalamnya adalah Drama; (i) Komedi, (ii) tragedi, (iii) epik, (iv) dithyramb, (v) iambik, (vi) poemata, (vii) drama, dsb. Dan yang menarik kemudian adalah, sampai Aristoteles menulis Poeticsnya, di Yunani sendiri belum ada pembedaan secara khusus, soal kata Poiesis yang digunakan untuk hal yang berurusan dengan aktivitas ke-bahasa-an atau dalam hal kegiatan yang non-kebahasaan. Bukan satu hal yang tak dapat diabaikan pula jika pada saat itu (perkembangan) wacana “kritik seni” pada akhirnya lebih banyak berurusan dengan poetica kebahasaan, sebab watak dari masyarakat (intelektual) Yunani yang memang memiliki perhatian khusus pada segala yang berkaitan dengan logos. Terlebih dalam Poeticsnya itu, Aristoteles belum sepenuhnya menunjukkan kepada kita ada distingsi yang tegas soal Poiesis yang berkaitan hanya dengan “bahasa” dalam kedudukannya sebagai literature (sastra–tulis) dan “bahasa” yang diperlakukan sebagai media representasi dalam seni bernyanyi, sebagai bagian alat pertunjukan, pemujaan dsb., seperti yang ada pada dithyrambh dan nomes, kecuali hanya ditunjukkan kesamaannya sebagai seni yang sama bermatra dengan bentuk persajakan lain; sekaligus telah dibedakannya dengan diktat filsafat dan seni retorika sebagai respon atas komentar Plato atas fenomena puisi yang disikapi sebagai perkara yang punya kecenderungan menjauh dari kebenaran. Yang tak kalah penting selanjutnya adalah, bahwa kita menemukan dalam bagian awal Poetics Aristotles, soal kenyataan masih simpang-siurnya penyebutan masyarakat Yunani kepada siapa mereka-mereka yang patut disebut sebagai pelaku puisi dan mereka-mereka yang hanya sekadar mengerjakan risalatnya dalam bentuk persajakan bermatra; Pada bagian awal kumpulan makalah kuliah tersebut, Aristoteles terlihat masih hanya menghimbau para pembaca Poeticsnya akan penyematan status antara menyebut Homerus sebagai seorang penggubah sajak–epik, dan Empedokles yang lebih baik disebut sebagai filsuf saja, sebab tidak dapat ditemukan kesamaan (keahlian) antara keduanya–dalam Poiesis, kecuali Empedokles hanya menulis diktatnya dalam bentuk sajak; bermatra. Sehingga dengan kata lain, bahwa dari Aristoteles lah, selain usaha untuk memberi introduksi dalam mengkategorisasikan (memetakan keilmuan) soal seni Poiesis ini, sekaligus ada indikasi munculnya ekses penyempitan makna dari Poiesis kepada hanya perhatian atas berbagai pandangan soal estetika komposisi kebahasaan(baca: literer)nya. Dan pada waktu yang lebih kemudian (oleh perjalanan sejarah) hanya terbatas pada definisi Poiesis sebagai sebuah pekerjaan membuat berbagai jenis sajak. Dalam konteks ini, sebenarnya kita perlu pula melihat bahwasanya, orang-orang Yunani kuno memiliki dan menggunakan kata Poiesis dengan makna yang amat sangat luas ketimbang pengertian-pengertian reduktif yang kita kenal saat ini–seperti itu. Pemaknaan meluas soal kata Poiesis ini misalnya bisa kita lihat dalam pendapat seorang pendeta wanita, Diotama, yang sempat diretrospeksi oleh Socrates dalam debatnya melawan Agathon (yang direkam oleh Plato dalam Symposium), bahwa paling tidak ada tiga macam proses Poiesis: (i) Natural Poiesis yang melibatkan proses prokreasi-seksual untuk melahirkan keturunan, (ii) Poiesis in the city, yang melibatkan “politik masyarakat negara-kota” untuk melahirkan sosok pahlawan–atau mungkin juga negarawan, (iii) Poiesis yang terjadi di dalam jiwa seseorang untuk melahirkan sebuah virtue (keutamaan diri) dan pengetahuan (baca: kebijaksanaan). Dengan ini, makna sebenarnya Poiesis–sekali lagi kembali hendak ditekankan–dalam dirinya telah menyimpan satu cakupan yang amat begitu luas dalam setiap aktivitasnya (baik cara, media bahkan subjeknya) yang mendahului sebuah usaha pendefinisian secara intelektual pada zaman awal pembentukan keilmuannya secara teoritik, yang mana, bahkan telah mendahului satu perwujudan peradaban literer(teks tulis)nya; Email: [email protected] Telegram Poetry Club: t.me/sainsPuisi_Lab