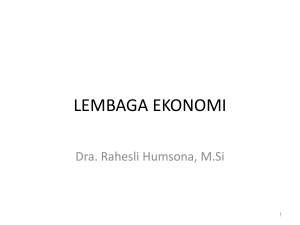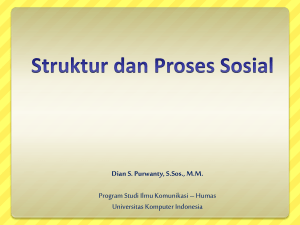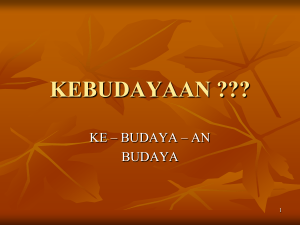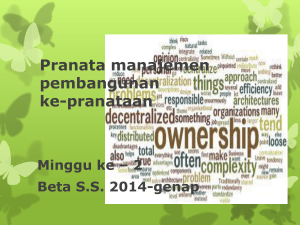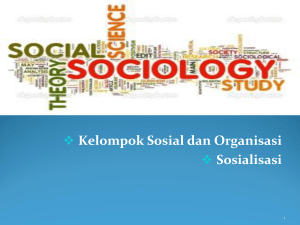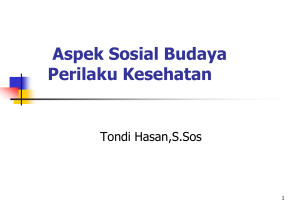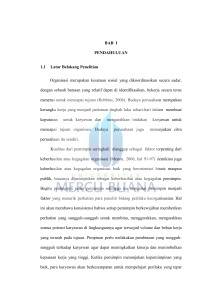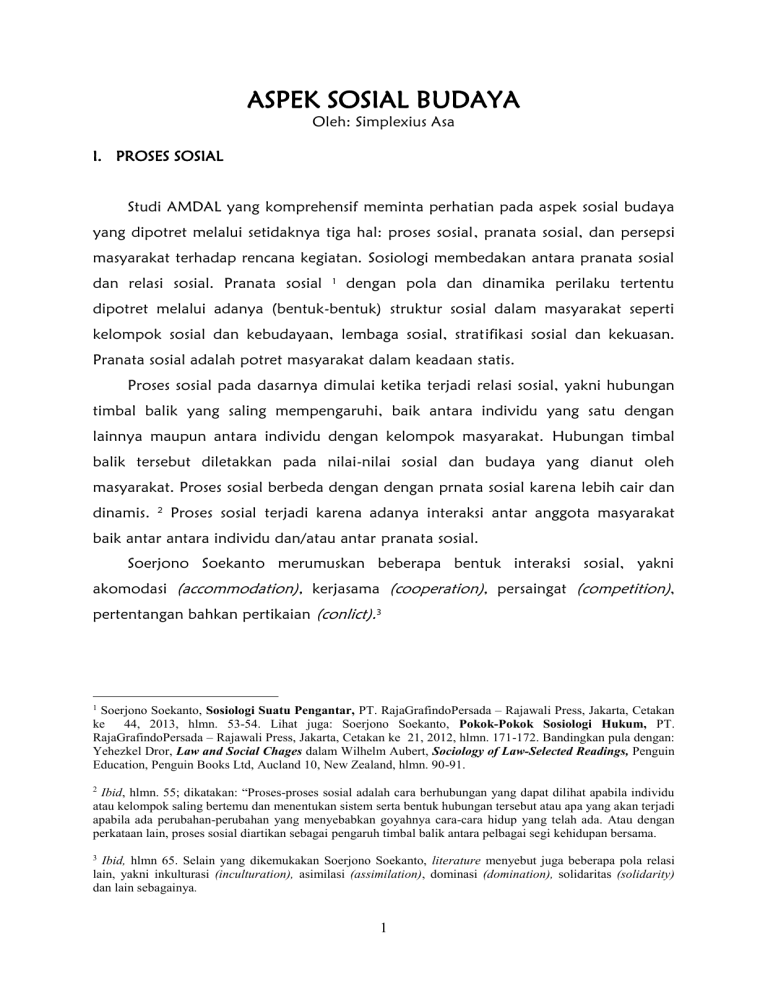
ASPEK SOSIAL BUDAYA Oleh: Simplexius Asa I. PROSES SOSIAL Studi AMDAL yang komprehensif meminta perhatian pada aspek sosial budaya yang dipotret melalui setidaknya tiga hal: proses sosial, pranata sosial, dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan. Sosiologi membedakan antara pranata sosial dan relasi sosial. Pranata sosial 1 dengan pola dan dinamika perilaku tertentu dipotret melalui adanya (bentuk-bentuk) struktur sosial dalam masyarakat seperti kelompok sosial dan kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial dan kekuasan. Pranata sosial adalah potret masyarakat dalam keadaan statis. Proses sosial pada dasarnya dimulai ketika terjadi relasi sosial, yakni hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, baik antara individu yang satu dengan lainnya maupun antara individu dengan kelompok masyarakat. Hubungan timbal balik tersebut diletakkan pada nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Proses sosial berbeda dengan dengan prnata sosial karena lebih cair dan dinamis. 2 Proses sosial terjadi karena adanya interaksi antar anggota masyarakat baik antar antara individu dan/atau antar pranata sosial. Soerjono Soekanto merumuskan beberapa bentuk interaksi sosial, yakni akomodasi (accommodation), kerjasama (cooperation), persaingat (competition), pertentangan bahkan pertikaian (conlict).3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindoPersada – Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ke 44, 2013, hlmn. 53-54. Lihat juga: Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindoPersada – Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ke 21, 2012, hlmn. 171-172. Bandingkan pula dengan: Yehezkel Dror, Law and Social Chages dalam Wilhelm Aubert, Sociology of Law-Selected Readings, Penguin Education, Penguin Books Ltd, Aucland 10, New Zealand, hlmn. 90-91. 1 Ibid, hlmn. 55; dikatakan: “Proses-proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila individu atau kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. 2 3 Ibid, hlmn 65. Selain yang dikemukakan Soerjono Soekanto, literature menyebut juga beberapa pola relasi lain, yakni inkulturasi (inculturation), asimilasi (assimilation), dominasi (domination), solidaritas (solidarity) dan lain sebagainya. 1 Steven Vago menguraikan dan menandaskan bahwa secara umum diskusi tentang hukum dan masyarakat bertalian erat dengan satu dari dua konsepsi idial, yakni integration-consensus 4 dan conflict-coercion.5 Sependapat dengan Vago, Akers menyebut dua konsep di atas dengan istilah yang berbeda, yakni social organization dan social disorganization. 6 Keadaan suatu masyarakat disebut social organized jika potret sistem sosial dalam masyarakat menggambarkan adanya integrasi dan kesesuaian (conformity) dengan norma dan nilai yang dianut, terjadi kohesi sosial yang kuat diantara individu yang menjadi anggota masyarakat dan interaksi sosial dilaksanakan menurut tatacara yang telah diatur. 7 Sebaliknya keadaan masyarakat dikatakan sedang terjadi social disorganized jika potret dalam masyarakat menggambarkan adanya gangguan atau kekacauan terhadap integrasi dan kohesi sosial, kontrol sosial sulit dilaksanakan dan diantara elemen pranata sosial yang satu dengan lainnya dalam masyarakat terjadi pertentangan dan pertikaian .8 Uraian tentang pandangan dan istilah yang oleh Vago disebut sebagai integration-consensus dan conflict-coercion maupun yang oleh Akers disebut sebagai social organization dan social disorganization sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya potret dari dua dimensi interaksi sosial tersebut dalam suatu proses sosial. Kedua dimenasi dimaksud adalah proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif, yang diperkenalkan oleh Gillin dan Gillin. 9 4 Steven Vago, Law and Society, 3rd Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, US, 1998, hlmn. 16. “integration-consensus … describes society as a functionally integrated, relatively stable system held together by a basic consensus of values. Social order is considered as more or less permanent, and individuals can best achieve their interests through cooperation.” Ibid, hlmn. 16. “conflict-coercion … perspective, in direct opposition, considers society as consisting of individuals and groups characterized by conflict and dissension and held together by coercion. Order is temporary unstable because every individual and groups strives to maximize its own interest in a world of limited resources and goods.” 5 6 Ronald L. Akers, Criminological Theories, University of Florida, Fitzroy Dearborn Publisher, Chicago and London, 1999, hlmn. 115. Ibid. Dikatakan: “A social system (a society, community, or subsystem within society) is described as socially disorganized and integrated if there is sn internal consensus on its social interaction proceeds in an orderly way”. 7 Ibid. Dikatakan: “Conversely, the system is described as disorganized or anomic if there is a disruption in its social cohesion or integration, a breakdown in social control, or malalignment among its elements”. 8 9 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlmn. 65. Tentang Gillin and Gillin, lihat selengkapnya dalam Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sociology, The Macmillan Company, New York, 1954. 2 Meminjam istilah Gillin and Gillin di atas, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu proses sosial disebut sebagai proses yang asosiatif jika dalam suatu masyarakat terjalin adanya kerjasama (cooperation), baik sebagai interaksi sosial yang pokok maupun sebagai proses yang utama dan akomodasi (accommodation).10 Sedangkan di sisi lain, suatu proses disebut disosiatif jika terjadi persaingan (competition) dan kontraversi (contraversion).11 A. Proses Sosial Asosiatif Wilayah studi ini meliputi tiga Desa/Kelurahan di Kecamatan Kupang Timur, kabupaten Kupang yakni, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Babau dan Desa Nunkurus yaitu wilayah yang dijadikan lokasi rencana pembangunan pabrik garam oleh PT. Puncak Keemasan Garam Dunia. Secara geografis, letak wilayah rencana pembangunan pabrik garam relatif sangat dekat (20-30 kilometer) dengan Kota Kupang, Ibukota sekaligus kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersbut mempengaruhi proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi antar sesama warga yang diletakkan di atas kesamaan kepentingan sebagai sesama warga masyarakat. Warga yang mendiami ketiga Desa/Kelurahan terdiri atas beberapa etnis, yaitu etnis Timor atau orang Timor, etnis Sabu atau orang Sabu, etnis Rote atau orang Rote, etnis Alor atau orang Alor, etnis/orang Bugis-Makassar dan warga eks Timor-Timur yang sekarang sudah menjadi negara Timor Leste, serta beberapa etnis lain dalam jumlah yang sangat kecil. Etnis yang dominan mendiami wilayah rencana pembangunan pabrik garam adalah orang Timor, orang Rote dan orang Sabu. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan, berturut-turut diikuti oleh yang beragama Katholik, Islam, Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk di wilayah studi bekerja sebagai petani dan/atau nelayan, pedagang hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan di Pasar Tradisional. Hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja pengusaha, pegawai pada instansi pemerintah, sektor informal lainnya. 10 11 Lihat selengkapnya dalam Soerjono Soekanto, Ibid, hlmn. 65-81. Ibid, hlmn. 81-97. 3 Meskipun masyarakat di wilayah rencana pembangunan pabrik garam berasal dari etnis yang berbeda, proses sosial yang asosiatif atau integrasi sosial terjadi karena adanya ikatan kesamaan agama dan kepercayaan (sesama umat Kristani), kesamaan profesi dan/atau pekerjaan/mata pencaharian. Kekhasan adat istiadat yang diwariskan/dibawa oleh etnis tertentu dipertahankan sepanjang urusannya terkait perkawinan atau kematian sesama warga. Kekhasan lainnya sudah melebur karena adanya proses asimilasi dan inkulturasi, terutama melalui jaringan kekerabatan dan solidaritas karena perkawinan (kawin-mawin), serta toleransi diantara sesama warga. Hingga studi ini dilaksanakan, warga masyarakat setempat tetap menjaga keharmonisan hubungan sosial dan berusaha menghindari terjadinya konflik sosial dan konflik kepentingan diantara mereka. Kohesi atau ikatan sosial tersebut selanjutnya menjadi jiwa dalam mengembangkan semangat gotong royong dan tolong menolong dalam suasana persaudaraan (katong samua basodara) dalam berbagai segi kehidupan sosial, seperti gotong-royong membangun rumah ibadat, gotong royong menyiapkan lahan pertanian, saling menghargai dan menghormati dalam kegiatan atau upacara keagamaan, termasuk pula ketika sesame warga mengalami musibah atau bencana. Kondisi ini juga didukung oleh masih kuatnya loyalitas warga setempat terhadap elit tradisional dari masing-masing etnis dalam komunitas. Peran tokoh atau elit tradisional dalam menjaga harmoni sosial di wilayah ini masih nampak dalam pengaturan pembagian air untuk pertanian, pelaksanaan adat perkawinan serta ketika menengahi konflik sosial antar warga. Hasil wawancara dan informasi dari wilayah studi menunjukkan bahwa di lokasi / wilayah rencana pembangunan pabrik garam tidak pernah terjadi konflik sosial yang berkepanjangan dan tidak terkontrol serta berdampak luas. B. Proses Sosial Disosiatif Proses sosial dissosiatif adalah proses yang mengarah kepada terjadinya pertentangan atau konflik di dalam masyarakat. Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini jarang terlibat dalam konflik-konflik terbuka, baik antar sesama warga setempat maupun dengan pihak lain, khususnya 4 penduduk pendatang. Kendatidemikian, hal potensial yang dapat memicu terjadinya proses sosial disosiatif dalam masyarakat di wilayah rencana pembangunan pabrik garam adalah adanya indikasi persaingan antar warga maupun kelompok masyarakat dalam memperoleh keuntungan ekonomis dari adanya potensi alam yang akan diusahakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci (key informants) yang berasal dari kalangan pemerintahan, tokoh adat maupun warga masyarakat biasa, diperoleh gambaran bahwa potensi keresahan dan konflik antar warga menyangkut penguasaan tanah relatif kecil. Hal ini disebabkan karena semua warga desa memiliki pemahaman mengenai kelompok-kelompok suku yang menguasai lahan-lahan serta memiliki ketaatan yang tinggi terhadap tokoh adat (fukun) yang juga memiliki kewenangan mengatur urusan tanah di desa-desa ini. Sehubungan dengan rencana pembangunan pabrik garam yang akan dilaksanakan oleh PT. Puncak Keemasan Garam Dunia, potensi-potensi konflik yang dapat terjadi, baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi maupun operasi adalah masalah pelibatan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemrakarsa, pemerintah setempat dan semua pihak terkait lainnya. C. Pranata/Kelembagaan Masyarakat Secara sosiologis, lembaga keagaamaan adalah pranata sosial yang sangat kuat dalam masyarakat. Sebahagian besar penduduk di wilayah studi menganut agara Kristen Protestan dan Kristen Katholik dimana kekristenan telah disebarluaskan sejak tahun 1.500-an. Masyarakat setempat sangat menaruh hormat dan percaya serta taat terhdap pemimpin agama. Lembaga agama dan para peminpinnha ikut memainkan peran yang cukup menentukan dalam menata perilaku individu dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Pranata lainnya adalah organisasi sosial yang didirikan oleh pemerintah seperti BPD dan LKMD. Pranata sosial yang saat ini paling dominan peranannya dalam kehidupan masyarakat setempat adalah lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah kecamatan dan desa. Hal ini dapat dipahami mengingat struktur masayarakat di wilayah studi sesungguhnya adalah komunitas subculture perkotaan. 5 Studi mengonfirmasi adanya kelompok masyarakkat berdasarkan kesamaan profesi / pekerjaan atau kelompok kepentingan tertentu seperti kelompok tani dan nelayan, kelompok petukangan serta kelompok arisan pedagang di Pasar Tradisional. Hasil studi juga menunjukkan bahwa kelembagaan/pranata masyarakat tradisional setempat masih ada dan terpelihara secara turun temurun serta mengikat warga dari etnis pemilik pranata tersebut, khususnya dalam uerusan perkawinan dan kematian warga. Basis dari pranata dimaksud adalah norma dan nilai-nilai budaya. D. Warisan Budaya Sebagaimana tergambar dalam pembahasan tentang proses sosial, secara sosial budaya, corak kehidupan masyarakat yang bernuansa budaya tradisional warisan leluhur yang khas dari masing-masing etnis dalam komunitas sepanjang terkait perkawinan dan kematian sesama warga masih tetap ditahankan. Demikian juga dengan spirit dan semangat solidaritas dalam budaya gotong-royong serta tolongmenolong. Diakui bahwa lunturnya berbagai upacara yang diwariskan oleh para leluhur dipengruhi oleh masuknya agama Kristen dan menyebarnya semangat kekristenan. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi dipengaruhi pula oleh kondisi sosial masyarakat yang cenderung telah menganut pola relasi subculture perkotaan Hasil penelusuran lapangan menunjukkan bahwa di wilayah rencana pembangunan pabrik garam sudah tidak ditemukan lagi situs adat peninggalan leluhur di wilayah ini. baik berupa bangunan (Rumah Adat / Rumah Pemali), Situs Pekuburan Adat maupun hutan dan tanah yang dijadikan tempat keramat. E. Sikap dan Persepsi Masyarakat Hasil konsultasi publik bersama dengan wakil-wakil pemerintah, tokoh adat serta warga masyarakat terkena dampak yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat, Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,pada tanggal 08 Mei 2019, serta wawancara dengan sejumlah warga yang dianggap sebagai informan kunci (key informants), ketika melakukan kunjungan lapangan menunjukkan bahwa sikap 6 dan persepsi masyarakat setempat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan ini, untuk sebagian dapat dikatakan cukup positif, dalam arti dapat menyetujui dan mendukung kehadiran PT. Puncak Keemasan Garam Dunia yang berencana membangun pabrik garam di wilayah studi. Meskipun demikian, sebagaimana terurai dalam catatan Hasil Konsultasi Publik dan Transkrip Rekaman Proses Sosialisasi (terlampir), masih ada beberapa hal atau permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah daerah setempat (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), maupun oleh pihak pemrakarsa, yakni: 1) Perekrutan tenaga kerja harus mendapat rekomendasi dari warga dan tokoh masyarakat di Desa Nunkurus, Lurah babau dan Kelurahan babau sebelum diumumkan secara terbuka dengan catatan perlu menguutakan masyarakat Kelurahan Merdeka, Kelurahan Babau Dan Desa Nunkurus; 2) Pembangunan tanggul harus mempertimbangkan bencana banjir yang mungkin dapat terjadi; 3) Perlu disosialisasikan tentang (letak, luas, batas dan peruntukan) terutama aspek yuridis teknis untuk kegiatan di Tambak dan Pabrik Garam Kelurahan Merdeka, Kelurahan Babau Dan Desa Nunkurus, dengan melibatkan Kepala Desa dan/atau Lurah, Tokoh Masyarakat, Petani, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkunga Hidup, Badan Pertanahan Nasional UPT Kehutanan Kabuaten Kupang dan/atau stakeholders lainnya; 4) Perlu menunjuk wakil dari wilayah kegiatan Pabrik dan tambak Garam; References Dominikus Rato, Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial, LaksBang Mediatama, Sleman Yoyakarta, Tahun 2009. Dragan Milovanovic, A Primer in the Sociology of Law, Second Edition, Harrow and Hesston Publisher, New York, USA, Year 1994. Gillin and Gillin, lihat selengkapnya dalam Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sociology, The Macmillan Company, New York, Year 1954. 7 Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, Editor, Paranata Hukum – Sebuah Telaah Sosiologis, Kumpulan Tulisan Esmi Warassih, PT. Suryandaru Utama, Semarang, Tahun 2005. Ronald L. Akers, Criminological Theories, University of Florida, Fitzroy Dearborn Publisher, Chicago and London, Year 1999. Steven Vago, Law and Society, 3rd Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, US, Year 1998. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindoPersada, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ke 44, Tahun 2013. ---------------------------, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Rajawali Press, Jakarta, Cetakan ke 21, Tahun 2012. RajaGrafindoPersada, Wilhelm Aubert, Sociology of Law-Selected Readings, Penguin Education, Penguin Books Ltd, Auckland 10, New Zealand, Year 1980. Dokumen 1. 2. 3. 4. 5. Kuisioner yang telah diisi dan ditandatangani oleh responden. Dokumen Hasil Konsultasi Publik. Rekaman dan Transkrip Hasil Rekaman Sosialisasi dan Konsultasi Publik. Notulensi Hasil Rapat dan Sosialisasi / Konsultasi Publik. Daftar Hasil Konsultasi Publik 8