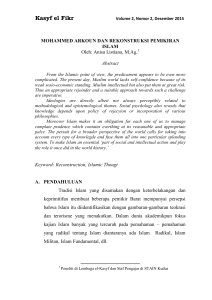PERAN ILMU-ILMU SOSIAL
advertisement
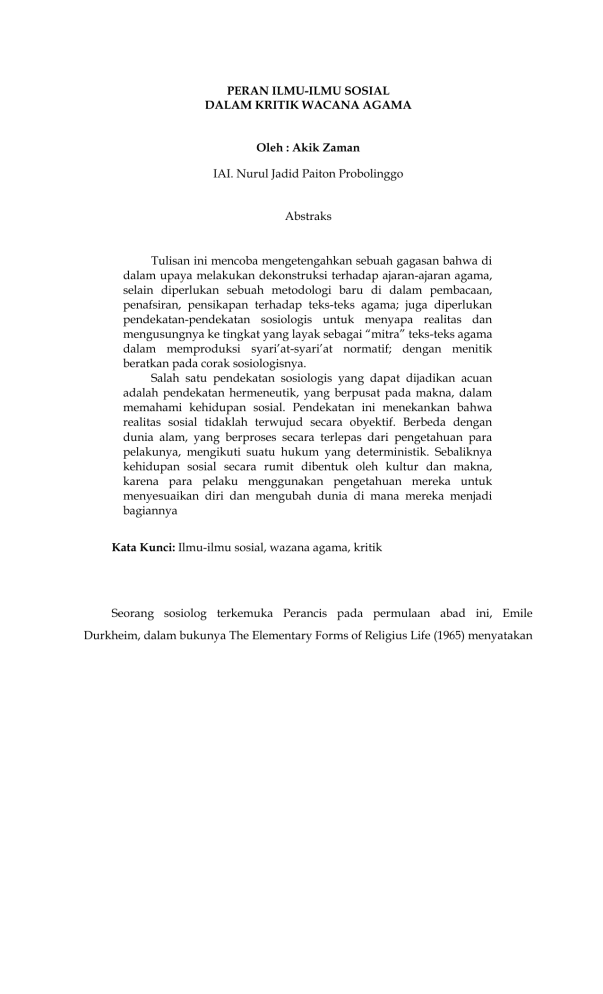
PERAN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM KRITIK WACANA AGAMA Oleh : Akik Zaman IAI. Nurul Jadid Paiton Probolinggo Abstraks Tulisan ini mencoba mengetengahkan sebuah gagasan bahwa di dalam upaya melakukan dekonstruksi terhadap ajaran-ajaran agama, selain diperlukan sebuah metodologi baru di dalam pembacaan, penafsiran, pensikapan terhadap teks-teks agama; juga diperlukan pendekatan-pendekatan sosiologis untuk menyapa realitas dan mengusungnya ke tingkat yang layak sebagai “mitra” teks-teks agama dalam memproduksi syari’at-syari’at normatif; dengan menitik beratkan pada corak sosiologisnya. Salah satu pendekatan sosiologis yang dapat dijadikan acuan adalah pendekatan hermeneutik, yang berpusat pada makna, dalam memahami kehidupan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas sosial tidaklah terwujud secara obyektif. Berbeda dengan dunia alam, yang berproses secara terlepas dari pengetahuan para pelakunya, mengikuti suatu hukum yang deterministik. Sebaliknya kehidupan sosial secara rumit dibentuk oleh kultur dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia di mana mereka menjadi bagiannya Kata Kunci: Ilmu-ilmu sosial, wazana agama, kritik Seorang sosiolog terkemuka Perancis pada permulaan abad ini, Emile Durkheim, dalam bukunya The Elementary Forms of Religius Life (1965) menyatakan bahwa agama ada karena agama dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial tertentu yang penting yang tidak dapat dipenuhi tanpa agama. Bahwa agama berperan utama sebagai integrator kemasyarakatan, di mana komponen ritualistik agamalah yang paling penting, karena melalui rituallah kekuatan mengikat komunitas itu disimbolkan. Karenanya, ada semacam kekhawatiran yang menghinggapi ruang nalar Durkheim, jika nantinya ilmu Pengetahuan dan teknologi modern perlahanlahan akan menggerus kekuatan integrator agama1. Kekhawatiran semacam ini cukup beralasan manakala ketaatan manusia atas agama, dengan segala ajaran yang mengikatnya, mengalami pendangkalan. Dalam arti bahwa manusia mulai tidak percaya (tidak mengindahkan) untuk tunduk pada aturan-aturan agama yang notabene hanya memberikan sanksi-sanksi moral (idealis) dalam bentuk ancaman pembalasan di Hari Kemudian. Sanksi-sanksi moral semacam ini semakin diabaikan karena tidak memberikan kejelasan nasib bagi para pelaku. Orang kemudian lebih taat kepada aturan hukum positif yang memberlakukan sanksi nyata (itupun dalam batas-batas tertentu). ; terjadilah kemudian pelanggaranpelanggaran atas norma-norma sosial, sebab pada titik ini upaya yang dilakukan pun seringkali tidak dapat maksimal. Kekhawatiran yang lain juga terjadi bersamaan dengan terjadinya proses sekularisasi di mana agama yang pada awalnya terlibat menjadi faktor-faktor kausal dalam pembentukan dunia sekuler modern. Namun begitu terbentuk, ia justru menghalangi kelanjutan keampuhan agama sebagai suatu kekuatan kekuatan formatif. Dalam sejarah hubungan agama dengan sekularisasi abad modern pada tataran berikutnya kemudian terjadi proses yang sangat ironis, yakni bagaimana agama lambat laun akan “menggali kuburnya sendiri”2. Manakala ia tidak mampu mengaktualisasi dirinya dengan benar. Sebab terjadinya perubahan merupakan suatu yang niscaya, tak dapat dielakkan, dan harus didikapi. Lantas kerangka kerangka metodolis apakah yang dapat dilakukan dalam rangka reaktualisasi ajaran agama ini. Tulisan ini mencoba mengetengahkan sebuah gagasan bahwa di dalam upaya melakukan dekonstruksi terhadap ajaran-ajaran agama, selain diperlukan sebuah metodologi baru di dalam pembacaan, penafsiran, pensikapan terhadap teks-teks agama; juga diperlukan pendekatan-pendekatan sosiologis untuk menyapa realitas dan mengusungnya ke tingkat yang layak sebagai “mitra” teks-teks agama dalam memproduksi syari’at-syari’at normatif; dengan menitik beratkan pada corak sosiologisnya. Tom Cambel, Tujuh Teori Sosial; Sketsa Penilaian, Perbandingan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 31. 2 Berger, Peter L, Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial, LP2ES Jakarta, cet. Ke-2, April 1994, hlm. 153. 1 DINAMIKA SOSIAL- BUDAYA Sebagai mahluk sosial, manusia tidak mungkin untuk (dapat) hidup sendirian, tanpa membutuhkan orang lain; maka interaksi dengan individu-individu lain segera menjadi sebuah kepastian yang tak dapat dinafikan. Dari sinilah kemudian tercipta kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang mencoba merangkai sistem kehidupan bersama. Masyarakat, atau sebuah kelompok yang ada di dalam masyarakat, adalah sebentuk tatanan; ia mencakup pola interaksi antar manusia yang berulang secara simultan. Lantas nilai-nilai apakah yang dipegangi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupan bersamanya tadi? Banyak teoritikus menekankan makna sosial dari kemampuan-kemampuan manusia yang mencolok, seperti bertutur dan rasionalitas, yang memungkinkan manusia belajar dan mengubah standar-standar prilaku dan sikap-sikap yang diharapkan, yang lazim di dalam kelompok sosial khusus mereka sendiri. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai suatu masyarakat, diharuskan menghasilkan suatu kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa dan cipta. Kebudayaan tersebut yang merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, oleh karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Khusus di dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula suatu struktur normatif atau menurut Ralph Linton, design for living. Artinya, aspek kebudayaan tersebut merupakan suatu garis pokok tentang prilaku atau blue print for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan menganai apa yang harus dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan, dan seterusnya3. Tom Cambel, Tujuh Teori Sosial; Sketsa Penilaian, Perbandingan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 31. 3 Hal ini mengarah pada pandangan bahwa sebuah masyarakat disusun oleh aturan-aturan atau norma-norma yang diungkapkan dalam kode-kode moral dan legalnya, konvensi-konvensi sosial dan perintah-perintah religius. Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat manusia didasarkan pada kebudayaan, bukan naluri. Pandangan ini diungkapkan dengan mengatakan bahwa kehidupan masyarakat manusia didasarkan pada kebudayaan, bukan naluri; berbeda dengan binatang, tergantung sangat sedikit pada pola-pola tingkah laku yang diwariskan secara genetis. Karena ini pula, norma-norma yang dijadikan pegangan tersebut bukan tidak mungkin berbeda, berubah; sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya4 (diantaranya, penerapan ajaran agama). Sedangkan penentuan unsur yang menyebabkan perubahan sosial ini secara khusus, banyak perbedaan pendapat dari para sosiolog; Karl Marx misalnya, ia menyatakan bahwa penyebab yang hakiki dari perubahan sosial adalah kekuatan material dari proses produksi 5. Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan menelorkan perubahan-perubahan sosial6. Lantas pada wilayah apa sajakah perubahan sosial itu dapat terjadi? Perubahan sosial tidak dapat dibatasi pada bidang-bidang tertentu saja, misalnya pada bidang material atau spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Di tingkat kelembagaan, perubahan sosial yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena lembaga-lembaga sosial tadi sifatnya independen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga tertentu saja. Proses awal dan prosesproses selanjutnya merupakan suatu mata rantai7. AKULTURASI BUDAYA DAN KRITIK WACANA AGAMA Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pada sifat dasarnya masyarakat adalah berkembang, sementara dalam perkembangannya kehidupan sosial pun terwarnai Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Cet. Ke sembilan, 1999, hlm. 176. 5 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta. Cet. Ke duapuluh tujuh, 1990, hlm. 338. 6 Karl Manheim, Sosiologi Sistematis, Bina Aksara Jakarta, 1987, hlm. 154. 4 dinamikanya sehingga terjadi perubahan-perubahan sosial di dalamnya. Maka, agama sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat juga mengalami pembaharuan-pembaharuan nilai dalam ajarannya ketika unsur-unsur sosial yang lain juga berubah, seperti teritotial-geografis, kebudayaan, struktur perekonomian, dll. Disamping itu, bahwa proses pertemuan, interaksi, antara para pemeluk lama yang membawa ajaran Islam pada para pemeluk baru, baik sebagai sebuah komunitas masyarakat ataupun individu, tentunya akan mengalami proses-proses sosial yang membutuhkan waktu yang cukup lama; dan akan melahirkan proses assimilasi antar keduanya, saling bersilang budaya, dan di sinilah proses akulturasi budaya itu terjadi. Dari sekian abad perjalanan Islam yang telah melewati berbagai wilayah yang cukup beragam, tentunya Islam telah dipeluk oleh sekian masyarakat yang beragam pula. Dengan demikian, normatifitas ajaran agama (Islam) dalam konstruksi awalnya (al-Qur’an, al-Hadits, al-Sunnah dan tradisi Sahabat) hingga konstruksi pemahaman, penafsiran awal (fiqh, tafsir) meniscayakan pemaknaan kembali kepada sebuah bentuk fiqh-normatif yang selaras dengan kondisi sosio-kultural pemeluknya. Terjadi suatu proses akulturasi antara inti ajaran Islam dan sosio- kultur lokal yang kemudian membuahkan formulasi-formulasi baru. Agama dalam hal ini memasuki wilayah realitas ajaran awal- penganut awal- pengikut berikutnya-ajaran baru. Sebab apabila ajaran imanen-normatif yang ada pada awal mula Islam yang diberlakukan bagi masyarakat Arab waktu itu dipaksakan pada para pemeluk di berbagai wilayah yang notabene berbeda kultur, geografis, struktur masyarakatnya; maka tentunya Islam tidak layak lagi dinyatakan sebagai sebuah agama yang membawa misi rahmatan lil’alamin. Padahal, kehadiran agama Islam pada umat manusia adalah bertujuan untuk memberikan rahmat bagi segenap alam, sebagai 7 Soerjono, opcit. penyejuk jiwa, dan sebagai petunjuk dan norma penyelaras kehidupan manusia; sebagaimana firman Allah8: “Wahai orang-orang yang beriman! telah datang kepadamu suatu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi sesuatu di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang mukmin”. Dan dalam firmanNya9: “Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Jika memang begitu peta persoalan dan permasalahannya, maka hasil rumusan pemikiran keagamaan pada era tertentu—entah itu namanya klasik, skolastik, abad tengah, bahkan modern sekalipun, atau pemikiran keislaman yang muncul di daerah tertentu—belum tentu harus dikekalkan, diabadikan, dipaksakan apalagi kalau sampai disakralkan. Jangan-jangan, rumusan atau konsepsi keagamaan Islam pada era dan penggal sejarah tertentu, sebenarnya sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan pada era tantangan zaman yang telah berbeda10. Tidak hanya itu, wilayah “sejarah”, yakni historisitas-normatif adalah sangat berbeda dengan wilayah idealitas-transendeltal nilai-nilai agama apapun jua—untuk tidak hanya menyebut Islam. Dengan begitu rumusan-rumusan teks-teks keagamaan Islam pada era tertentu tidak bisa luput dari adanya anomali-anomali yang sulit dipecahkan dan didiamkan dengan begitu saja, jika tantangan dan keprihatinan zaman telah jauh berbeda. Panggilan sejarah sebenarnya bersifat “lokal”, “partikular” dan tidak mudah untuk begitu saja diuniversalkan dalam artian yang sesungguhnya, apalagi untuk diamini atau disetujui saja tanpa catatan-catatan tertentu. Dengan lain ungkapan, perlu mamahami aspek “ruang” dan “waktu” untuk memperoleh pemahaman keagamaan Islam yang tepat. “Ruang” yang dimaksud di sini adalah muatan lokal-partikular, yang ikut mewarnai keberagamaan Islam di manapun berada; dan “waktu” yakni sejarah peradaban era peradaban klasik-skolastik maupun modern yang diukir oleh manusia Muslim11. Sedangkan pengertian “ruang” dan “waktu” seperti itu hanya bisa dirasakan dan dinikmati secara “subyektif”. Nah, untuk memahami makna autentisitas dan spiritualitas keberagamaan Islam yang bersifat objektif-transendental, yang intinya bermuara pada kebijaksanaan, kesabaran, moralitas yang fungsional-imperatis, perlu dilakukan “pembacaan” dialogis-dialektik-kritis terhadap teks-teks agama, dan melakukan pembacaan yang cerdas terhadap realitas untuk dijadikan sebagai pijakan utama dalam menentukan, merumuskan dan menetapkan hukum syariat selanjutnya. Upaya yang pertama, pembacaan dialogis-dialektik-kritis terhadap teks-teks agama lebih merupakan kritik terhadap metodologi tafsir lama, di mana pembacaan Ibid, hlm. 344 Al-Qur'an, 10:57 10 Ibid, 21:107. 11 Abdullah, M. Amin, Arkoun dan Nalar Islam, dalam Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun, Peny. Johan Hendrik Meuleman, LkiS Yogyakarta, Cet. II 8 9 terhadap teks hanya bermaksud untuk menjelaskan. Prinsip dasarnya, teks asl (utama) memiliki otoritas yang dominan sehingga segenap aktifitas bermuara pada teks (wahyu) sebagai asl-nya dalam tiga kategori: bertitik tolak pada asl (dengan melakukan Istimbath), berakhir pada asl (dengan menerapkan analogi, qiyas), dan atas petunjuk asl12. Pembacaan ini bukan berarti tidak benar, tetapi ketika terjadi realitas yang belum pernah terbayangkan oleh teks asl, yang terjadi adalah pemaksaan pensikapan terhadap realitas berdasarkan konsepsi-konsepsi yang ada dalam asl saja. Sehingga kerap kali justru tampak bertentangan dengan semangat universalitas nash itu sendiri. Karenanya kemudian, upaya yang dilakukan adalah menjadikan realitas sebagai pijakan utama dalam merumuskan normatifitas ajaran dengan memberikan peran yang lebih pada akal dalam menganalisis linguistik atas teks-teks qur’ani13. Banyak para pemikir Islam menawarkan gagasan metodologisnya dalam pembacaan teks ini, Mohammad Arkoun misalnya menawarkan konsep hermeneutika14 sebagai kaca pandang dalam melakukan kritik wacana agama. RELEVANSI SOSIOLOGI SEBAGAI JEMBATAN Mandat kedua dari upaya mendekonstruksi ajaran-ajaran agama untuk mencapai tingkat obyektif-transendental adalah dengan melakukan pembacaan atas realitas. Untuk dapatnya melakukan hal ini, perlu kiranya untuk dilakukan penelitian-penelitian antropologis terhadap struktur sosial masyarakat dan berbagai November 1996, hlm. 16 12 Ibid. 13 Pembacaan semacam ini diistilahkan oleh al-Jabiri dengan tradisi Bayani. Tentang epistemologi ini selengkapnya dapat di baca pada karangannya yang berjudul: “Bunyah al Aql al ‘Araby, Dirosat Tahliliyah Naqdiyyah li Nadzmi al Ma’rifah fi al Tsaqafah”, Beirut, Markaz al Tsaqafi al Arabi, 1993. 14 Upaya menempatkan realitas sebagai pijakan utama ini disebut sebagai epistemologi Burhany, demontratif. Ibid. fenomena sosial untuk dijadikan pijakan utama, bahan rujukan dalam menganalisis problem yang akan disikapi, dicarikan solusinya berdasarkan ajaran-normatifitas agama. Persoalan agama dalam konteks ini sangatlah empiris, partikular dan lokal. Berpijak pada hal ini, maka dibutuhkan sebuah “teologi” (teori) sosial untuk dapat menjembatani kebutuhan-kebutuhan pembacaan atas realitas sosial-kultural dan menjelaskan peristiwa-peristiwa fenomenal yang ada. Sungguhpun demikian, tidak mudah rasanya untuk menentukan pendekatan sosiologis mana yang akan dijadikan sebagai pisau analisisnya. Salah satu pendekatan sosiologis yang dapat dijadikan acuan adalah pendekatan hermeneutik, yang berpusat pada makna, dalam memahami kehidupan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas sosial tidaklah terwujud secara obyektif. Berbeda dengan dunia alam, yang berproses secara terlepas dari pengetahuan para pelakunya, mengikuti suatu hukum yang deterministik. Sebaliknya kehidupan sosial secara rumit dibentuk oleh kultur dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia di mana mereka menjadi bagiannya15. Pada awalnya, penekanan kembali atas masalah makna ini memberi pengaruh positif terhadap semangat ilmu sosial yang historis dan komparatif. Bukannya memeras fakta-fakta untuk dijadikan suatu kerangka umum. Pendekatan ini mendorong pada peneliti untuk memperhatikan sejarah dan budaya lokal, dan mengembangkan model-model perubahan sosial dari bawah ke atas (bottom-up). Bukan melalui deduksi dari pernyataan-pernyataan abstrak. Penekanan ini memberikan kekuatan kembali pada etnografi dan sejarah sosial, yang menempatkan realitas tingkat lokal pada inti penelitian. Seiring tumbuhnya perhatian terhadap masalah makna, sejumlah metode analisis kebudayaan yang baru dan lebih canggih berkembang di bidang linguistik, sosiologi, sejarah, dan antropologi16. Banyak gagasan tentang sosiologi yang layak untuk dijadikan “teologi sosial” dalam persoalan ini. Kuntowijoyo misalnya menawarkan gagasan “Ilmu Sosial Profetik” dalam melakukan transformasi17. Hassan Hanafi, seorang pemikir agama di Mesir, dalam rangkaian gagasan ‘kiri Islam’nya menawarkan sebuah sosiologi baru yang ia sebut dengan “Oksidentalisme”, dengan sebuah proyek besar “Pembangunan Kemandirian Peradaban Islam”18. Sedemikian pesatnya ilmu-ilmu sosial merambah ke dalam wacana agama, bukan mustahil ke depan akan semakin banyak pendekatan yang ditawarkan. lebih jelasnya tentang udar gagasan ini dapat di lihat pada bukunya yang berjudul “Rethingking Islam”, telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta. 16 Marcus, George, and Michael Fischer. 1986. Antrhropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago, University of Chicago Press. P.43. 17 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Mizan, Bandung, 1993. Hlm. 286 18 Lebih detail tentang gagasan ini dapat ditelusuri dalam buku dengan judul yang sama, Oksidentalisme, Paramadina Jakarta, 2000. 15 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Amin, Arkoun dan Nalar Islam, dalam Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme, Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun, Peny. Johan Hendrik Meuleman, LkiS Yogyakarta, Cet. II November 1996. Al-Jabiri, Muhammad Abid. Bunyah al Aql al ‘Araby, Dirosat Tahliliyah Naqdiyyah li Nadzmi al Ma’rifah fi al Tsaqafah, Beirut, Markaz al Tsaqafi al Arabi, 1993. Arkoun, Muhammed, Rethingking Islam, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997. Hassan Hanafi, Oksidentalisme, Paramadina Jakarta, 2000. Hefner, Robert W. Geger Tengger, Lkis Yogyakarta, Juni 1999. Karl Manheim, Sosiologi Sistematis, Bina Aksara Jakarta, 1987. Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Mizan, Bandung, 1993. Marcus, George, and Michael Fischer. 1986. Antrhropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago, University of Chicago Press. Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Cet. Ke sembilan, 1999. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta. Cet. Ke duapuluh tujuh, 1990. Tom Cambel, Tujuh Teori Sosial; Sketsa Penilaian, Perbandingan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994.
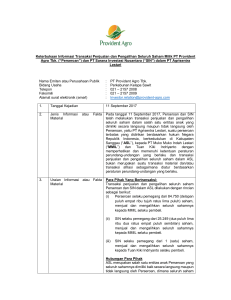
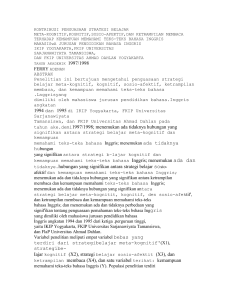



![Fawaizul Umam[**]](http://s1.studylibid.com/store/data/000129277_1-35721e95833eb90858cdda0f803e489f-300x300.png)