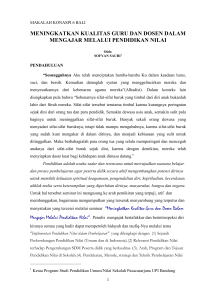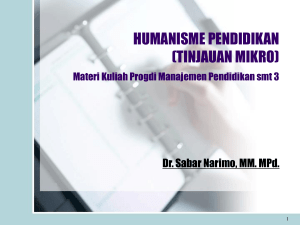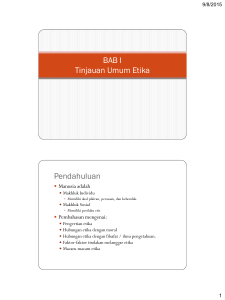BAB VII
advertisement

TREND SUFASTAIYAH (SUBJEKTIVISME) MODERN DAN DAMPAKNYA KEPADA ILMU DAN MORAL Ahmad Syukri Abstrak Abstract: Recently, modern subjectivism has rooted and become a hegemony in the thought of mankind’s inclination. This has been a global action where, in one hand, it drives mankind’s advancement beyond (without) limit and free of values. On the other hand, it could lead to serious anxiety and devastation. In other words, man could reach an advancement of science and technology in fulfilling his life’s demand, and at the same time, he would be able to uncover a secret of natural law. However, this trend would bring about clash of culture (civilization) and serious crisis in humans activity and their religious belief. Consequently, modern community would run into crisis since it was established on the basis of subjectivism while Islam puts mankind as one of God creatures and becomes a part of the universe and has been given a mandatory to manage this world. Keywords: Subyektivisme, modern, ilmu, moral I. Pendahuluan Sufastaiyah (subjektivisme) modern telah mengakar dan menjadi hegemoni dalam kecenderungan pemikiran umat manusia pada era dewasa ini. Sehingga dapat dikatakan hal itu telah mempengaruhi penilaian, sikap dan perbuatan manusia. Ia tidak hanya menjadi trendnya orang Eropah atau Barat tetapi juga mempengaruhi suku, bangsa, negara dan agama lainnya di dunia. Trend ini telah menjadi suatu gerakan global yang pada satu sisi telah menggerakkan kemajuan manusia tanpa batas dan bebas nilai dan di sisi lain telah memunculkan kekhawatiran akan kehancuran. Manusia mampu mencapai ketinggian ilmu dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mengungkap dan menguasai rahasia dan hukum-hukum alam. Di sisi lain trend ini telah mengakibatkan benturan kebudayaan dan krisis dalam perbuatan manusia dan keyakinan keagamaan. Trend Sufastaiyah ini telah disikapi dengan berbagai tanggapan oleh umat Islam. Di antaranya, pertama ada kelompok yang mencoba mentransformasikannya dengan kesiapan terhadap implikasi yang ditimbulkan karena melihat sisi positifnya. Kedua kelompok yang selektif dengan melakukan sintesis atau mencari referensi ke dalam diri dan budayanya. Ketiga kelompok yang menolaknya dengan curiga karena menganggap trend itu berasal dari luar diri dan budayanya. Munculnya berbagai sikap tersebut dibutuhkan suatu kajian dan bahasan terhadap subjektivisme yang lahir dari gerakan sujektivitas modern yang telah memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu dan moral. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan subyektivisme modern, subjektivisme dan hubungannya dengan masyarakat modern, serta dampak subyektivisme terhadap ilmu dan moral dewasa ini. Untuk melihat Subjektivisme modern dan dampaknya, diperlukan dua pendekatan Pertama, memakai perangkat analisis sosiologi. Kedua, memakai 1 2 analisis filsafat itu sendiri. Yang pertama lebih cenderung melihat subjektivisme modern sebagai gejala sosial di mana transformasi masyarakat bergerak maju ditentukan oleh determinasi ekonomi dan ilmu/teknologi yang dibangun bersamaan dengan gerakan subjektivitas modern. Yang kedua lebih melihat subjektivisme sebagai bentuk kesadaran/pemikiran manusia. Dengan kata lain, subjektivisme dipandang dari sisi internal yang menekankan paradigma epistemologi. II. Sekitar subyektivisme modern Secara terminologi subjektifisme berasal dari bahasa Inggris subjective. Loren Bagus (2002:1046) dalam Kamus Filsafat menjelaskan beberapa pengertian dari subjektif yaitu: 1. mengacu ke apa yang berasal dari pikiran (kesadaran, ego, diri, persepsi-persepsi kita, putusan pribadi kita) dan bukan dari sumber-sumber objektif, luar. 2. Apa yang ada dalam kesadaran tetapi tidak mempunyai acuan objektif di luar atau konfirmasi yang mungkin. 3. Yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman (pencerapan-pencerapan, persepsi-persepsi, reaksi-reaksi pribadi, sejarah, keistimewaan-keistimewaan) individual yang tahu. Sementara menurut Titus, dkk. (1984:518), Subjektif sesuatu yang bertalian dengan subyek, dengan aku, dengan yang mengetahui; sesuatu yang berada dalam kesadaran tetapi tidak terpisah dari kesadaran. Istilah ini berlawanan dengan obyektif. Sedangkan subjectivisme, menggunakan istilah Loren Bagus (2002:1046) adalah, suatu katagori umum yang meliputi semua doktrin yang menekankan unsur-unsur subjektif pengalaman. Hal tersebut bisa ditemukan dalam epistemologi1, doktrin yang membatasi pengetahuan pada kesadaran pikiran akan keadaannya sendiri, dalam metafisika idealisme subjektif, dalam estetika, doktrin bahwa putusan estetis tidak lain dari suatu ekspresi status individual, dst. Pembicaraan subjektivisme tidak dapat dilepaskan dari tiga gerakan yang melahirkan masyarakat modern. Gerakan tersebut dijelaskan oleh Franz Magnis Suseno dalam bukunya, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (1992:59) Satu dalam bidang ekonomi sosial, dua dalam cara manusia berfikir; 1. Kapitalisme dengan teknik modern yang memungkinkan industrialisasi. 2. Penemuan subyektivitas manusia modern, 3. Rasionalisme. Dalam hubungan ini dapat dikatakan subjektivisme merupakan buah dari ketiga gerakan tersebut. Sementara ketiga gerakan tersebut dalam hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dan penjelasan dari humanisme dan latar belakangnya yang dapat dilihat dari dua sisi; sisi historis dan sisi aliran-aliran di dalam filsafat. Dari sisi historis, humanisme berarti suatu gerakan intelektual dan kesusastraan yang awalnya muncul di Italia pada paruh kedua abad ke-14 M. 1 Subjektivisme Epistemologis memuat beberapa pengertian: 1. Teori bahwa seluruh pengetahuan (a) Mempunyai sumber dan keabsahannya dalam keadaan mental subjektif orang yang tahu (knower) dan (b) Pengetahuan yang apapun tentang yang objektif atau real secara eksternal diandaikan atau didasarkan pada penyimpulan dari keadaan mental subjektif ini. 2. Segala sesuatu yang diketahui adalah (a) Produk yang distruktur secara selektif dan diciptakan oleh yang tahu itu, dan (b) Tidak dapat dikatakan bahwa ada satu dunia nyata secara eksternal yang berkorespondensi dengan yang tahu. 3 Gerakan ini boleh dikatakan sebagai motor penggerak kebudayaan modern, khususnya Eropa. Berapa tokoh yang sering disebut-sebut sebagai pelopor gerakan ini di antaranya, Dante, Petrarca, Michelangelo. Kebudayaan Barat modern juga terlahir dari rahim gerakan intelektual dan kesesusastraan ini. (Listiyono Santoso, 2003:33) Sementara dari sisi aliran filsafat, humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sangat tinggi, sentral dan penting, baik dalam perenungan teoretis-filsafati maupun dalam praktis hidup sehari-hari. Kedua sisi humanisme tersebut kalau dicermati sesungguhnya bermakna mendasar berupa pengakuan atas munculnya sinyal otonomisasi manusia, sebagai ukuran bagi setiap penilaian, dan referensi utama dari setiap kejadian di alam semesta. Manusia adalah pusat dari realitas. Prinsip ini kemudian berhasil membongkar segala bangunan dogma-dogma agama dan otoritas gereja abad Pertengahan yang membelenggu manusia untuk mengembangkan fitrah kemanusiaannya. Belenggu otoritas gereja abad Pertengahan disadari telah mematikan potensi kemanusiaan, otonomisasi, kreativitas dan kemerdekaan berpikir manusia. Rasionalitas manusia menjadi tidak ada gunanya, karena gereja lah ‘memasung’ mereka ke dalam penjara dogma agama. Hal terserbut memunculkan resistensi dan kegelisahan para filsuf/pemikir dan melakukan ‘perlawanan’ atas kondisi yang demikian. Maka lahirlah prinsip-prinsip humanisme (modern) sebagai awal munculnya epsitemologi rasional yang menjadi pondasi filasafat Barat modern. Meskipun demikian tetap harus disadari bahwa prinsip-prinsip ini telah dicoba dikembangkan oleh para filsuf awal atau filsuf sebelumnya (misalnya para filosof muslim red.). Gerakan ini kemudian berhasil juga membangunkan manusia dari tidur dogmatisnya, bahwa manusia tidak sekedar objek/benda di dunia yang berfungsi sebagai viator mundi (peziarah di muka bumi), melainkan sebagai vaber mundi (pekerja atau pencipta dunianya) (Zainal Abidin, 2000: 26). Gerakan seperti ini jelas merupakan gambaran gerakan Renaisans (abad ke-14 sampai abad ke-16 M) yang diawali dari Italia kemudian secara luar biasa menyebar secara pervasive ke segenap penjuru Eropa. Gerakan ini dijalankan melalui pengembangan pendidikan liberal, dengan satu prinsip bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas dan berkuasa penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya. Maka dalam keadaan tertentu, kekuatan-kekuatan dari luar manusia yang membelenggu kebebasan manusia harus segera dipatahkan. Prinsip-prinsip ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai subjektivitas modern. (Listiyono, Patologi Humanisme (Modern) yang berikutnya akan melahirkan subjektivisme yang bermacam-macam. Menurut Magnis Suseno prinsip subjektivitas modern pada dasarnya mencoba meletakkan manusia dalam subjektivitasnya, dalam artian bahwa manusia, dalam memandang alam, sesama dan Tuhan, mengacu pada dirinya sendiri. Manusia dalam subjektivitasnya, dengan kesadarannya, dalam keunikannya menjadi titik acuan pengertian realitas. Jadi subjektivitas di sini bukan suatu yang negatif, melainkan keunggulan. Dalam arti ini Hegel dan Sartre 4 mempergunakan kata subjek. Menurut Hegel (1770-1832) manusia itu bukan substansi (di sini dimaksud sebagai kepadatan kebendaan, sebagai sesuatu yang berada di dunia bagaiakan sebongkah batu di tengah-tengah sawah), melainkan subjek (adalah pusat kesadaran, kesadaran akan kesadaran, pusat yang secara kritis melawankan diri terhadap realitas, terhadap dunia) (Franz Magnis Suseno, 1998:60). Bahwa manusia adalah subjek mau mengatakan bahwa manusia tidak sekedar hadir dalam dunia, melainkan hadir dengan sadar, dengan berfikir, dengan berefleksi, dengan mengambil jarak, secara karitis, dengan bebas. (Franz Magnis Suseno, 1998:61) Meski demikian kita juga tidak bisa menghindar dari ekses yang ditimbulkannya. Lebih lanjut dijelaskan Franz Magnis Suseno (1998:60-64), subjektivitas modern ini mempunyai beberapa segi: Pertama, Subjektivitas modern bertolak dari suatu perubahan perspektif manusia yang fundamental. Cara memandang para filsuf Yunani bersifat kosmosentris2. Dalam abad pertengahan pandangan kosmosentris disingkirkan oleh pandangan theosentris3. Pandangan Theosentris ini mulai didesak ke samping oleh pandangan antroposentris dalam masa Renaisance yang lahir di Italia abad ke-14. Renaisance menemukan serta menghargai kembali kebudayaan prakristiani Yunani dan Romawi, tetapi tidak dengan masuk kembali ke alam kosmosentris mereka. Bagi Renaisance alam Yunani dan Romawi membuka pandangan mereka tentang manusia. Manusia ditempatkan ke dalam pusat dunia. Lahirlah humanisme dengan homo universale, manusia universal, sebagai citacitanya. Statika faham realitas sebagai tatanan semesta theosentris yang selaras diganti dengan dinamika perkembangan di mana sebagai subyek mengangkat kepalanya berhadapan dengan ciptaan lain. Manusia bukan lagi sebagai salah satu substansi dalam dunia, melainkan sebagai subjek berhadapan dengan dunia. Kedua, Langkah berikut dalam drama perkembangan manusia modern dapat dipahami sebagai jawaban dialektis terhadap humanisme Renaisance. Yaitu subyektivisme religius yang mendapatkan ungkapannya dalam reformasi Kristen Protestan, terutama aliran Martin Luther4. Waktu ia pada tahun 1521 dihadapan Kaisar dan para Pangeran Jerman disuruh untuk menarik kembali ajarannya, ia menjawab dengan kata-kata termasyur: “disinilah aku berdiri dan tidak dapat lain!”. Kata “aku” dalam ucapan ini adalah kunci bagi pengertian subyektivitas manusia modern. Kesadaran hati religius menjadi ukuran dan dasar kepercayaan seseorang. Manusia tidak dapat dipaksa untuk mempercayai sesuatu. Pada Luther keyakinan itu terungkap dalam tuntutan bahwa setiap orang kristiani berhak untuk membaca Kitab Suci serta untuk memahaminya sendiri. Tafsiran arti Kitab Suci 2 Artinya mereka mencari dasar realitas dalam unsur-unsur kosmos atau alam raya. 3 Semuanya dilihat dari segi Allah. Manusia memahami diri sebagai salah satu unsur, meskipun yang tertinggi, dalam ordo atau tatanan hirarkis alam semesta yang diciptakan Allah. 4 Luther adalah seorang bekas biarawan dan teolog dari Jerman Tengah. Melawan pimpinan Gereja dan para penguasa Luther mempermaklumkan “kebebasan orang Kristen”, artinya hak untuk tidak mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. 5 bukan lagi hak para pemimpin gereja, melainkan setiap orang kristiani berhak untuk membaca, merenungkan, mengartikan Kitab Suci sendiri. Apa yang dicetuskan oleh martin Luther masih membutuhkan dua ratus tahun sampai betul-betul menjadi milik “manusia Barat”. Baru sesudah Enersi Eropa seakan-akan habis, pada akhir perang 30 tahun yang menghancurkan sebagian besar Eropa Tengah (1648) disebabkan perang antar agama yang bermuatan politis, implikasi prinsip subjektivitas religius Luther mulai disadari. Yaitu bahwa apa yang menjadi kepercayaan dan agama seseorang bukan urusan penguasa politiknya. Politik dilihat sebagai urusan duniawi dan sebagai suatu urusan duniawi jangan dimutlakkan oleh orang yang percaya bahwa keselamatannya terletak dalam tangan Tuhan. Keyakinan itu mendapat segala macam ungkapan, misalnya dalam ajaran toleransi John Locke, dalam Pietisme Protestan dan dalam perpisahan antara Gereja dan Negara di Amerika Serikat yang justeru berdasarkan keyakinan religius (dan bukan sekularistik). Sebagai salah satu contoh dari kutipan yang dipermaklumkan oleh raja Friedrich II (Friedrich Agung) (1740-1786) sesuadah ia menjadi raja di Prusia: “Semua agama adalah sama dan baik asal saja mereka yang mengakui agama-agama itu adalah orang yang jujur. Dan andaikata ada orang Turki atau orang kafir datang dan ingin menetap di negara kami, kami akan membangun masjid-masjid dan gereja-gereja bagi mereka. Pada saya setiap orang dapat mempercayai apa yang dikehendakinya asal saja ia jujur.” Ketiga, Keyakinan akan hak manusia untuk mengikuti kepercayaan yang diyakininya, ditampung dan diuniversalisasikan secara etis oleh Immanuel Kant (1724-1804). Kant membedakan antara moralitas dan legalitas. Sikap moral yang sebenarnya tidak lagi dapat diukur dari apakan seseorang melakukan tindakan yang menurut norma moral harus dilakukannya, melainkan tergantung dari motivasinya. Seseorang dapat bertindak sesuai dengan kewajibannya semata-mata karena hal ini menguntungkan, misalnya karena ia akan dipuji dan dipercayai dan dianggap orang baik. Sikap ini tidak lebih dari legalitas semata-mata, suatu kesesuaian lahiriah antra tindakan dan hukum. Moralitas, atau sikap moral terpuji mesti terletak dalam hati. Orang hanya bersikap baik dalam arti moral apabila ia bertindah sesuai dengan kewajibannya karena ia mau menghormati kewajibannya, jadi lepas dari segala pertimbangan untukng rugi. Dengan demikian Kant menempatkan moralitas ke dalam hati manusia. Tidak mungkin lagi untuk melihat dari luar apakah seseorang baik atau buruk. Yang melihat hanyalah Allah yang dpat melihat ke dalam lubuk hati. Kalau ajaran Martin Luther membawa konsekuensi (yang belum ditariknya sendiri) bahwa keagamaan seseorang bukan urusan negara dan masyarakat. Maka dari Kant ditarik kesimpulan yang tidak kalah pentingnya bahwa moralitas seseorang bukan urusan negara dan masyarakat. Perpisahan yang semakin tajam antara hukum sebagai aturan masyarakat yang akan dipaksakan kepada semua anggota, dan sikap-sikap moral yang menetukan nilai seseorang sebagai manusia merupakan ciri yang khas bagi kesadaran manusia modern. 6 Keempat, dalam bidang filsafat politik perhatian pada subyektivitas manusia menghasilkan individualisme dan penghargaan tinggi terhadap kebebasan individu. Paham hak-hak asasi manusia, terutama yang bersifat kebebasankebebasan liberal dan hak-hak demokratis, mengungkapkan kesadaran itu terujud dalam teori tentang perjanjian negara. Itulah anggapan bahwa negara berasal dari suatu perjanjian antara individu-individu yang sebelumnya belum bernegara. Mereka bersama-sama menciptakan negara agar dapat memecahkan masalahmasalah di antara mereka dengan lebih baik. Kiranya jelas bahwa bahwa ajaran perjanjian negara melawan semua paham yang menempatkan nilai manusia konkret di bawah kepentingan negara. Negara adalah demi manusia dan bukan manusia demi negara. Dalam filsafat pada umumnya subjektivitas modern menempatkan AKU manusia pada pusat perhatiannya. (Toety Heraty Noerhadi, 1984) III. Subjektivisme dan masyarakat modern A. Perspektif Sosiologis Dari sudut sosiologis, subjektifitas modern yang melahirkan subjektivisme merupakan di antara dasar pemikiran Barat yang turut membentuk masyarakat modern. Hal ini terlihat hampir di segenap bangunan peradaban modern. Termasuk peradaban lainnya, ia selalu meletakkan ‘manusia’ sebagai subjek otonom, pusat kesadaran dunia yang mempunyai ‘hak’ penuh secara bebas mengembangkan kreativitasnya tanpa belenggu otoritas apapun, termasuk otoritas agama. Awal lahirnya dasar pemikiran ini ditegaskan oleh Franz Magnis (1998:59): zaman yang memutuskan untuk kemajuan ilmu zaman sekarang dan demikian juga untuk kebudayaan modern adalah perkembangan ilmu sejak abad ke-17 dan 18. Abad tersebut adalah abad peletakan dasar-dasar spiritual gerakan modernisme. Dijelaskannya juga sebelum diletakkan dasar-dasar spiritual gerakan modernisme dan terbentuk dan berkembangnya masyarakat modern setidaknya ada tiga penemuan di Eropa abad ke-15 yang boleh dikatakan merupakan prasyarat bagi berkembangnya masyarakat modern, yaitu pemakaian mesiu, mesin cetak, dan kompas. Penemuan mesiu berarti titik akhir kekuasaan feodal yang dipusatkan dalam benteng-benteng feodalisme yang mulai tidak aman lagi. Penemuan mesin cetak berarti bahwa pengetahuan tidak lagi milik eksklusif suatu elite kecil melainkan terbuka untuk banyak orang. Penemuan kompas berarti bahwa navigasi mulai aman, sehingga dimungkinkan perjalanan-perjalanan jauh yang membuka suatu dunia baru, tiba-tiba horison manusia Barat jauh lebih luas. Lebih lanjut dijelaskan Oleh Magnis (1998:59) Tiga penemuan itu memungkinkan suatu perkembangan dinamis dan menjadi kenyataan berhubungan dengan tiga gerakan. Satu dalam bidang ekonomi sosial, dua dalam cara manusia berfikir; 1. Kapitalisme dengan teknik modern yang memungkinkan industrialisasi. 2. Penemuan subyektivitas manusia modern, 3. Rasionalisme. Ketiga gerakan sekaligus juga merupakan sumber-sumber etika masyarakat modern yang kalau dilihat melalui teori nilai Takdir (nilai ilmu/teori, ekonomi, 7 solidaritas, politik, seni dan agama), sumber-sumber masyarakat modern itu didominasi oleh nilai teori ilmu dan ekonomi atau dalam filsafat kebudayaannya adalah kebudayaan progresif (seni dan agama: budaya ekspresif, solidaritas dan politik: budaya organisatoris). Dalam hal ini dapatlah dikatakan nilai teori ilmu dan ekonomi yang telah melahirkan kemajuan teknologi dan industri serta tiga gerakan tersebut telah menjadi dasar etika bagi masyarakat modern. Etika masyarkat modern yang dipengeruhi subyektifitas modern dewasa ini merupakan perluasan dari etika masyarakat Eropa setelah renaisance dan telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi dunia global. Modernisasi yang dibawanya merupakan proses raksasa yang menyeluruh. Tak ada bangsa atau masyarakat yang dapat menolak atau menghindar dari padanya. Ia merupakan proses yang selalu berjalan terus entah kita menyetujui atau tidak yang dalam perkembangannya telah memunculkan masyarakat dan kebudayaan industri atau masyarakat dan kebudayaan teknokratis yang selanjutnya menciptakan masarakat informasi atau global. Untuk melihat subyektifisme modern dalam masyarakat modern dalam perspektif sosiologi, berikut ini perlu dipaparkan masyarakat mana yang disebut modern? Berikut ini disebutkan beberapa ciri-ciri sesuai dengan perkembangannya dan dianggap khas sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno (1998:56-58) Pertama, Masyarakat modern pertama-tama adalah masyarakat yang berdasarkan industrialisasi. Hal itu menjadi darah daging masyarakat modern. Ia bukan hanya menentukan bidang ekonomi, melainkan kehidupan seluruh masyarakat, termasuk way of life-nya. Di antara akibat industrialisasi tenaga kerja manusia dilipatgandakan. Manusia berhasil mengabdikan enersi-enersi alam bagi kepentingannya. Sekian banyak pekerjaan manusia dapat diserahkan kepada mesin, robot, otomat dst. Kedua, Industrialisasi dengan demikian menghasilkan suatu perubahan total dan amat mendalam dalam gaya hidup manusia. Perubahan itu menyangkut semua bidang kehidupan. Yang paling mencolok ialah penciptaan jalur-jalur komunikasi lokal, regional dan global yang amat padat dan cepat. Sarana lalu lintas mengalami perkembangan yang revolusioner. Ketiga, Industrialisasi tingkat pertama sudah dilalui oleh negara-negara industri. Teknologi menjadi ilmu baru, yaitu ilmu yang secara khusus meneliti kekuatan-kekuatan alam dengan maksud untuk dimanfaatkan untuk produksi industri. Gelombang pasca industri kiranya akan menciptakan masyarakat informasi. Keempat, Masyarakat modern adalah masyarakat yang –kecuali dalam keadaan darurat dan luar biasa—tidak mengalami lagi ketergantungan dari alam. Hal itu merupakan perubahan yang sangat besar dari semua bentuk kebudayaan dulu. Terjadi kesan bahwa apa saja dapat diciptakan manusia, bahwa semua masalah dapat dipecahkan. Kesadaran akan batas eksistensi manusia seakan-akan hilang. Bahwa cara berfikir ini sebenarnya malah membahayakan masa depan umat manusia, baru mulai disadari sejak 20 tahun terakhir. Baru akahir-akahir ini 8 kita memperhatikan tetapan fundamaental bahwa manusia termasuk biosistem bumi yang oleh industrialisasi semakin dibahayakan. Kelima, Masyarakat modern menghasilkan perubahan mendalam dalam cara manusia berfikir. Perubahan itu dicirikan oleh diferensiasi. Lingkaran masing-masing fungsi melepaskan diri dari kaitan keseluruhan dan berkembang menurut logika dan fungsi khas masing-masing. Masyarakat, alam dan realitas transenden dihayati oleh manusia sebagai tiga bidang yang tidak ada sangkut pautnya satu sama yang lain. Masing-masing didekati dengan metode-metode dan ilmu-ilmu sendiri. Begitu pula terjadi pergeseran dalam perhatian. Manusia modern lebih terarah pada yang indrawi, langsung, duniawi daripada yang rohani, tak langsung, adiduniawi. Bidang yang didekati menurut kriteria moral terdesak oleh bidang yang dilihat menurut kriteria manfaat. Keyakinan pribadi menyatakan diri terhadap adat istiadat dan norma-norma sosial. Pola kehidupan sosial, kesadaran moral dan penghayatan keagamaan sangat berubah. Itulah beberapa ciri khas masyarakat modern. Proses perubahan-perubahan masyarakat tradisional ke arah pola masyarakat modern itu kelihatan dalam semua kota di seluruh dunia dan sering sudah menjalar sampai ke desa-desa. Dari ciri-ciri masyarakat modern tersebut mengandung domonasi subjektifitas yang mengukuhkan subjektifisme. Ciri pertama meski bersifat teknologi tapi kegiatan tersebut telah memunculkan rasa super manusia. Teknologi telah berhasil melipatgandakan kekuatan manusia yang kalau kita amati secara fisik manusia adalah makhluk yang paling lemah dari makhluk lainnya misalnya lemah dari harimau dan kalah dari burung. Dengan teknologi dan industrialisasi manusia mampu menaklukkan alam dan memanjakan dirinya dengan menciptakan robot-robot. Kemampuan tersebut telah melahirkan subjektifitas manusia, dan meletakkan persoalan pada manusia. Manusia menjadi hal yang sentral, yang lainnya dipinggirkan bahkan disingkirkan. Dalam kehidupan sosial semuanya diabdikan untuk kepentingan manusia dan kesejahteraan manusia. Tuhan ditundukkan kepada kepentingan manusia, begitu juga alam. Manusia adalah penguasa alam, manusia berbeda dari alam. Agama yang yang tidak memenuhi kehendak manusia adalah agama yang salah sehingga muncul penolakan terhadap agama atau kalaupun mau diterima agama tersebut harus direformasi. Subjektivisme terlihat kental pada ciri ke lima masyarakat modern menghasilkan perubahan mendalam dalam cara manusia berfikir. Perubahan itu dicirikan oleh diferensiasi. Diferensiasi terjadi secara tajam dalam berbagai bidang. Lembaga-lembaga politik di Barat misalnya melepaskan diri dari segala penguasaan oleh gereja dan mengorganisasikan diri secara otonom menurut kepentingan sendiri. Bidang ekonomi dibiarkan mengurus diri menurut hukum pasar. Begitu juga kebudayaan di Barat, melepaskan diri dari pandangan Kristiani. Orang dapat berpartisipasi di dalamnya dengan tidak perlu melibatkan diri pada keagamaan tertentu. Program budaya modern adalah “pencerahan”, rasionalaitas perkembangan semua bidang kemanusiaan menurut ke khasan sendiri. B. Perspektif Philosofis 9 Karakter khas dalam filsafat modern adalah memasukkan kesadaran bukan sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai proyek utama. Ada tiga hal yang memperlihatkan hal ini, yaitu: subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjectum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Hardiman memberikan satu ilustrasi dalam konteks apa subjektivitas modern itu lahir. Sembari mengutip karya Jacob Burckhart (1859), seorang sejarawan Swiss, Eropa pada abad pertengahan lebih mengenali dirinya sebagai ras, rakyat, partai, keluarga, atau kolektif. Lewat modernisasi yang dimulai di Italia di zaman Renaisans manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Menjelang akhir abad ke-13, kata Jacob, sekonyong-konyong Italia dipenuhi pribadi-pribadi; penghalang individualisme telah dibobol; ribuan wajah individual menspesialisasikan dirinya tanpa batas. (Faiz Manshur, 2005) Menyimak sejarah filsafat modern, terasa bahwa proses dalam pemikiran manusia tidak mengenal terminal. Setiap lahir satu pemikiran yang baru, di masa kemudian akan lahir kritik sebagai paham pemikiran yang baru. Ragam pemikiran silih berganti tanpa mengenal kebenaran tunggal. Oleh karena itu kita hendaklah tidak berpuas diri atas satu aliran pemikiran, sebab sebuah pemikiran hanya relevan untuk masa tertentu. (Faiz Manshur, 2005) Selanjutnya dari sudut filosofis, kaitan subyektifitas modern dan masyarakat modern dapat dilihat dari Sisi ‘mentalitas modern’. Hal itu perlu dilihat secara khusus dan mendetail, sebab sains, teknik, ekonomi kapitalis, negara hukum, dan demokrasi modern berpangkal dari sebuah pemahaman filosofis yang lalu menjadi elemen modernitas, yakni: subjektivitas dan rasionalitas, yang mendorong lahirnya ide kemajuan (the idea of progress), dan kritik yang telah melahirkan banyak aliran pemikiran mulai dari humanisme renaisans, rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, materialisme, sampai dengan vitalisme. IV. Pengaruh subyektivisme modern terhadap ilmu dan moral A. Terhadap Ilmu Dalam sejarah filsafat Barat penemuan subjektivitas dari prinsip humanistis oleh Descartes sekaligus merupakan awal filsafat modern, yang menggugah perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan serta gejolak perkembangan teknologi. Sehingga dikatakan, pada dataran epistemologis, mega-proyek modernisme didirikan di atas pondasi rasionalisme Cartesian yang berpijak pada subjektivisme. Hal tersebut pada urutannya mengajak masyarakat modern untuk melihat realitas dunia ini, tidak ubahnya bagaikan sebuah mesin jam raksasa tanpa elemen spiritual yang terlihat menggerakkan. Epistemologi adalah cara pandang untuk memahami dan menangkap realitas. Epistemologi rasionalisme Cartesian yang sangat memuja subjek ‘aku’ yaitu I am the thinking thing, telah melahirkan semacam keangkuhan epistemologi bahwa realitas itu bisa ditaklukkan melalui pendefinisian secara positif. Tatkala rasionalitas positivisme diproklamirkan sebagai satu-satunya cara pandang terhadap realitas, yang muncul kemudian adalah mistifikasi terhadap validitas paham Cartesian, dan di luar itu tidak benar. 10 Maka sejak itu terjadilan imperalisme cultural epistemologis (Komarudin Hidayat, dalam Suyoto, dkk, (ed), 1994: 62). Kekejaman perang, perusakan lingkungan, dan sebagainya dapat dikatakan diawali oleh penerapan paradigma epistemologi rasional tersebut. Pengaruh subyektivisme modern terhadap ilmu dapat dilihat dari asumsi paradigma Cartesian-Newtonian yakni: 1. Subjektivisme-Antroposentristik Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai pusat dunia. Descartes melalui pernyataanya cogito ergo sum, mencetuskan kesadaran subjek yang terarah pada dirinya sendiri, dan ini adalah basis ontologis terhadap eksistensi realitas eksternal di luar diri si subjek. Selain itu, subjektivisme ini juga tampak pada pandangan Francis Bacon mengenai dominasi manusia terhadap alam. Letak subjektivisme Newton ada pada ambisi manusia untuk menjelaskan seluruh fenomena alam raya melalui mekanika yang dirumuskan dalam formula matematika. Hal tersebut telah menghasilkan ekspolorasi besar-besaran terhadap alam dan manusia. Bahkan Tuhan pun ditaklukkan di bawah subjektivisme manusia 2. Dualisme Pandangan mengenai dualisme ini tampak pada pemikiran Descartes. Dalam hal ini, realitas dibagi menjadi subjek dan objek. Subjek ditempatkan sebagai yang superiortas atas objek. Dengan ini, manusia (subjek) dapat memahami dan mengupas realitas yang terbebas dari konstruksi mental manusia. Subjek pun dapat mengukur objek tanpa mempengaruhi dan tanpa dipengaruhi oleh objek. Paham dualisme ini kemudian mempunyai konsekuensi alamiah dimana seolah-olah “menghidupkan” subjek dan “mematikan” objek. Hal didasarkan pada pemahaman bahwa subjek itu hidup dan sadar, sedangkan objek itu berada secara diametral dengan subjek, sehingga objek haruslah mati dan tidak berkesadaran. 3. Mekanistik-deterministik Alam raya dipandang sebagai sebuah mesin raksasa yang mati, tidak bernyawa dan statis. Malahan, segala sesuatu yang di luar kesadaran subjek lalu dianggap sebagai mesin yang bekerja menurut hukum matematika yang kuantitatif, termasuk tubuh manusia. Dalam pandangan mekanistik ini, realitas dianggap dapat dipahami dengan menganalisis dan memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Hasil dari penyelidikan terhadap bagian-bagian yang kecil itu lalu digeneralisir untuk keseluruhan. Dengan demikian, keseluruhan itu berarti sama atau identik dengan penjumlahan atas bagian-bagiannya. Pandangan yang deterministik juga tampak pada sikap dimana alam sepenuhnya itu dapat dijelaskan, diramal, dan dikontrol berdasarkan hukumhukum yang deterministic (pasti) sedemikan rupa sehingga memperoleh kepastian yang setara dengan kepastian matematis. Dengan kata lain, masa depan suatu 11 system, pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat terhadap kondisi system itu sekarang. Prinsip kausalitas pada dasarnya merupakan prinsip metafisis tentang hukum-hukum wujud. Determinisme ini juga didukung oleh Laplace. Ia mengatakan bahwa jika kita mengetahui posisi dan kecepatan setiap partikel di alam semesta, kita akan dapat/sanggup memprediksi semua kejadian pada masa depan. 4. Reduksionis Dalam hal ini, alam semesta hanya dipandang sebagai mesin yang mati, tanpa makna simbolik dan kualitatif, tanpa nilai, tanpa cita rasa etis dan estetis. Paradigma ini memandang alam raya (termasuk di dalamnya realitas keseluruhan) tersusun/terbangun dari balok-balok bangunan dasar materi yang terdiri dari atomatom. Perbedaan antara materi yang satu dengan lainnya hanyalah soal beda kuantitas dan bobot. Selain itu, pandangan reduksionis ini berasumsi bahwa perilaku semua entitas ditentukan sepenuhnya oleh perilaku komponen-komponen terkecilnya. Pada jaman phytagoras maupun Plato, matematika itu mempunyai symbol kualitatif. Namun pada masa modern ini, matematika hanya dibatasi pada soal numeric-kuantitatif, unsure-sunsur simbolik ditiadakan. 5. Instrumentalisme Fokus pertanyaan di sini adalah menjawab soal ‘bagaimana’ dan bukan “mengapa”. Newton bersikukuh dengan teori gravitasi karena ia sudah dapat merumuskannya secara matematis meskipun ia tidak tahu mengapa dan apa penyebab gravitasi itu. Yang lebih penting menurutnya adalah dapat mengukurnya, mengobservasinya, membuat prediksi-prediksi berdasarkan konsep itu, daripada soal menjelaskan gravitasi. Modus berpikir yang instrumentalistik ini tampak pada kecondongan bahwa kebenaran suatu pengetahuan atau sains itu diukur dari sejauh mana hal itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan material dan praktis. Semuanya diarahkan pada penguasaan dan dominasi subjek manusia terhadap alam. 6. Materialisme-saintisme Saintisme adalah pandangan yang menempatkan metode ilmiah eksperimental sebagai satu-satunya metode dan bahasa keilmuan yang universal sehingga segala pengetahuan yang tidak dapat diverifikasi oleh metode tersebut dianggap tidak bermakna. Pada Descartes, Tuhan itu bersifat instrumentalistik karena sebagai penjamin kesahihan pengetahuan subjek terhadap realitas eksternal. Pada Newton, Tuhan hanya diperlukan pada saat awal pencitpaan. Tuhan menciptakan partikel-partikel benda, kekuatan antar partikel, hukum gerak dasar, dan sesudah tercipta lalu alam ini terus bergerak seperti sebuah mesin ayng diatur oleh hukum-hukum deterministic. Bagi kaum materialis, pada prinsipnya setiap fenomena mental manusia dapat ditinjau dengan menggunakan hukum-hukum fisikal dan bahan-bahan mentah yang sama, yang mampu menjelaskan fotosintesis, nutrisi, dan pertumbuhan. 12 Dari uraian berlalu dapat dikatakan lahirnya ilmu-ilmu modern masa Renaisans merupakan suatu kondisi yang merupakan prinsip humanistis; yang merupakan titik tolak subyektivisme modern yang sekaligus sebagai suatu konsekuensi logis atas ‘dibebaskannya’ manusia untuk berpikir, merasakan dan bertindak. Doktrin tersebut telah berkembang pada masa Renaisans dengan memberikan keleluasaan bagi manusia untuk bereksperementasi, lepas dari doktrin dan pengaruh gereja memungkinkan berkembangnya ‘nuansa’ humanisme yang dikedepankan. Melalui dua aspek dasar manusia; yaitu bertubuh dengan panca indranya dan berjiwa dengan akal budinya, manusia kemudian sanggup menemukan ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Kenyataan ini jelas semakin memberikan bukti betapa ‘manusia’ dengan segala nilai kemanusiaannya merupakan titik sentral pemunculan ilmu modern, dan juga pusat dari pemahaman atas realitas yang telah menunculkan krisis epistemologis manusia modern. Ilmu telah diabdikan untuk manusia demikian juga alam dan Tuhan. Cogito ergo sum (saya berfikir maka saya ada) telah menghapuskan keberadaan Tuhan yang seharusnya dalam kehidupan manusia ”Tuhan ada maka saya ada”. Manusia sebagai bahagian dari alam telah menjadi manusia penakluk dan penguasa alam. Manusia mengambil jarak dari alam sehingga manusia teralineasi dari alam. B. Terhadap Moral Subjektivisme juga memberikan pengaruh yang besar terhadap moral. Hal ini terlihat dari modernitas sebagai salah satu keberhasilan ‘proyek’ humanisme (dibaca subjektivitas). Ia mempunyai kontribusi yang besar terhadap pengalienasian nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah budaya modernitas, agama sebagai contoh terpojok antara ideologi-ideologi besar produk kemodernan yang hanya menghasilkan kondisi-kondisi kemanusiaan yang terkooptasi oleh aspekaspek material yang berdampak pada nilai-nilai negatif yang dihasilkan oleh sains dan teknologi dan mendewakannya. Hal tersebut terlihat nyata dengan lahirnya hedonisme, materialisme, individualisme, bahkan sosialisme dan kapitalisme yang munculnya dibidani oleh kesanggupan manusia, termasuk tafsiran manusia dalam memaknai kemanusiaannya. Masalah subjektivisme modern dan pengaruhnya terhadap moral dapat dilihat dari hubungan subjek dalam lingkungan objek, yaitu tiga bentuk hubungan: pertama hubungan aku mitik, dimaksudkan aku pada sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatran gaib di sekitarnya. Suatu aku melebur dengan kekuatan mencekam di luar dan di dalam dirinya. Manusia menyadari keterbatasan, kelemahan dan kekhilafan. Kedua, hubungan aku ontologik dijumpai pada sikap manusia yang mampu mengambil jarak dari lingkungan serta secara bebas meneliti hakekat hal ihwal di sekitarnya. Ketiga, hubungan aku fungsional terdapat pada sikap yang sadar mengadakan relasi-relasi baru, suatu kebertautan tampa terkurung lagi oleh pesona lingkungan, tetapi tidak pula dingin mengambil jarak dari lingkungan. (Toeti Heraty, 1984: 20-21) 13 Subjektivisme modern dapat dilihat sebagai dominasi subjek dalam tiap hubungan tersebut. Misal aku mitik yang merupakan sikap manusia yang merasa dirinya terkepung oleh suatu kekuatan gaib di sekitarnya yang menjadikan manusia menyadari keterbatasan, kelemahan dan kekhilafan. Dalam masyarakat modern hubungan ini terliahat dalam superioritas subjek yang mencoba menaklukkan semua misteri yang melahirkan keberanian-keberanian yang gila dalam eksperimen dan dalam bentuk lain adalah keputusasaan manusia yang mengarah kepada nihilisme seperti tergambanr dalam karya sastra kelompok eksistensialisme misalnya dalam karya ”Pintu Tertutup” karya Sartre yang melihat akhir kehidupan manusia adalah kesiasiaan, kematian dst. Ekses tersebut telah menjadikan manusia dalam bentuk kepribadian yang terpecah. Subjektivisme telah melahirkan manusia paradok, keberanian luar biasa dari subjek sebagai supermen, penolakan realitas di luar subjek (Tuhan), relativisme suatu kebenaran (yang ada hanya kebenaran subjek), terfragmentasinya kehidupan. Dominasi subjek dalam hubungan aku ontologik dapat dilihat dari historis, pemunculan humanisme (modern) sebagai gerakan pemikiran yang bersumberkan pada keinginan manusia untuk mengembalikan fitrah dasar kemanusian, sebagai makhluk yang otonom dengan kemampuan rasionalitasnya dan kemerdekaan berpikirnya. Gerakan ini bisa jadi juga lahir sebagai sebuah semangat perlawanan terhadap setiap kekuatan yang ‘memasung’ kemampuan dasar alami manusia. Humanisme –kemudian- pada dasarnya terlahir dari keinginan untuk memanusiakan manusia sebagai manusia, sebagai subjek dengan kesadarannya, bukan sebagai objek tanpa kesadaran. Persoalannya adalah bangunan peradaban yang meletakkan manusia sebagai pusat dan ukuran semua ‘ada’ (beings) (Levin, 1988: 3) telah memunculkan sejumlah problem serius justru terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan oleh humanisme itu sendiri. Epistemologi humanisme yang bersandarkan diri pada kemampuan rasionalitas manusia dengan segala otoritasnya –utamanya di abad modern ini- melahirkan problem akut kemanusiaan; seperti penindasan, keterbelakangan, masalah lingkungan, politik apartheid, tirani, peperangan yang berkepanjangan, bahkan kasus genocide, sebagai pembunuhan total suatu bangsa oleh Nazisme Hitler terhadap orang-orang Yahudi, oleh Loytard disebut sebagai “Auschwitz’ (lambang pembantaian) dalam banyak hal lahir dari rahim ‘keangkuhan’ epistemologi rasional-humanis. Keangkuhan epistemologi rasional ini pada perkembangan selanjutnya memunculkan ‘keangkuhan’ manusia untuk bebas menawarkan dan menebarkan prinsip-prinsip rasionalisme ke dalam seluruh realitas. Manusia sebagai subjek otonom atas rasionalitas itu justru mengalami alienasi, keterasingan dan keterbelengguan oleh paradigma yang dicoba dikembangkannya. Subjektivisme sebagai pemahaman atas manusia sebagai individu yang ‘berhak’ untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk membuat sejarahnya sendiri berimplikasi positif bagi tumbuh kembangnya filsafat Barat modern yang memberikan perubahan secara revolusioner bagi wajah peradaban umat manusia. Implikasi positif tersebut tentu saja terletak pada aspek humanisasi atas diri 14 manusia; untuk secara sadar menemukan potensi kemanusiaannya, sehingga kualitas homo faber dapat dimunculkan. Namun demikian, dari sejumlah implikasi positif tersebut, dalam perkembangan selanjutnya, subjektivisme juga menghadirkan sejumlah problema terutama berkaitan dengan problem epistemologik atas bangunan filsafat Barat modern yang masih tetap ‘angkuh’ untuk mengedepankan epsitemologi rasional yang justru menjadi sebuah imperialisme kultural epistemologis. Pendasaran atas rasional dan juga ilmiah pada akhirnya ‘mematikan’ munculnya situasi-situasi kemanusiaan yang dianggap tidak rasional dan tidak ilmiah. Segala peristiwa yang anomali dan menyimpang dari ‘tatanan’ misalnya, akan dianggap wajar apabila dilegitimasi dengan rasionalitas dan ilmiah tersebut. Keadaan ini yang tidak disadari, betapa setiap kebudayaan mempunyai language game (permainan bahasanya) sendiri-sendiri, yang tidak mungkin dipaksakan kepada pihak lain. Keangkuhan epistemologik inilah yang kemudian menjadi ‘malapetaka’ bagi nilai-nilai kemanusiaan, bagi munculnya dehumanisasi, peperangan, pembunuhan, hedonisme, politik aparthaeid, perang antar agama dan baru-baru ini dengan stigmatisasi fundamentalisme dan terorisme secara tidak adil. V. Simpulan Subjektivisme meletakkan pendasaran epsitemologinya pada rasionalitas ‘manusia’ sebagai ukurannya, atau minimal menjadikan manusia (subjek) sebagai awal dari setiap penjelasan atas objek (realitas) secara otonom. (manusia subjek dan objek). Ciri mendasarnya yang mengedepankan; kebebasan berpikir, skeptisisme, rasionalisme naturalistik dan pemenuhan diri sendiri. Prinsip subjektivisme ini telah memunculkan paham-paham tentang manusia yang sempit dan terfragmentasi yang membawa krisis kemanusiaan seperti Marxisme dalam bentuk otoritarianisme, telah memunculkan pertentangan klas dan pemaksaan manusia ke dalam masyarakat tanpa klas. Begitu juga dengan aliran pragmatisme dan eksistensialisme, yang tetap memberikan ‘ruang’ bagi manusia sebagai subjek atau individu kongkret serta ukuran bagi segala-galanya. Subjektivisme telah menampilkan dirinya sebagai sebuah kebebasan (sains dan pengetahuan serta logika) tanpa kendali yang mereduksi nilai-nilai kemanusiaan pada tingkatan paling akut. Manusia yang dicoba diangkat dari keterasingannya hal ini terlihat pada humanisme-Marxisistis justru semakin terasing oleh produksi-produksi dan kerja yang membelenggu, sementara humanisme liberal yang mencoba membebaskan manusia dari pengaruh-pengaruh institusi birokrasi dan dominasi gereja misalnya, justru menampilkan dirinya sebagai kekuatan tiranik baru yang bersembunyi di balik terminologi ‘liberalisasi’. Subjektivisme sarat dengan kekaburan dan paradoks, oleh karena, di satu pihak, penyanjungan kemampuan akal budi manusia, yang menjadikan manusia sebagai subjek yang merdeka, self-determination dan self affirmation merupakan awal dari keterputusan manusia dari Tuhan. Manusia kemudian hanya dihargai sebagai pengedepanan nilai-nilai rasionalitas, padahal sisi ini hanya satu bagian dari bagian lain nilai kemanusiaan. Akhirnya, dominasi rasionalitas ini ‘mematikan’ aspek spiritualitas kemanusiaan, bahkan nilai kemanusiaan itu sendiri. 15 Subjektivisme telah munculnya bangunan peradaban yang memandang manusia sebagai subjek, yang menentukan landasan nilai dan kriteria-kriteria dalam kehidupannya di dunia. Manusia modern tidak lagi memerlukan landasan nilai, kebenaran atau legitimasi selain dari dalam dan untuk dirinya sendiri, sebab manusia modern bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Bagi Hegel (1988:9) tidak ada landasan lain yang menopangi subjek yang merdeka selain dari 'akal budi; sang subjek itu sendiri, akal budi yang mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Baginya, ilmu pengetahuan menjadi mahkota dari apa yang disebutnya ‘Kebenaran Ideal’ (spirit), menggantikan mitos, legenda atau wahyu. Perkembangan sains dan teknologi sebagai bagian integral dari proyek Subjektivisme modern, untuk menunjukkan keunggulan manusia, semakin hari kian menakutkan. Perlombaan senjata, kompetisi yang tidak pernah berhenti, media komunikasi yang hegemonik, pada akhirnya adalah cerminan dari ‘ruang’ kebebasan yang diberikan terhadap manusia; untuk bereksperimentasi tiada henti. Pada titik selanjutnya, terjadilah proses penghancuran martabat kemanusian justru oleh manusia itu sendiri. Subjektivisme justru melahirkan anti manusia; dan epistemologi rasional yang menjunjung kebebasan dan kemerdekaan berpikir manusia justru menjadi ‘penjara’ baru, bahkan menjadi kekuatan ideologis baru yang ‘mengukung’ kebebasan manusia. Akhirnya, justru gerak subjektivitas modern melahirkan sejumlah ketidakpastian eksistensial manusia; untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia, bahkan untuk menjadi manusia. Krisis manusia akibat dari subjektivisme yang yang melupakan posisi manusia sebagai hamba Tuhan, bahagian dari alam yang mendapat mandat dari Tuhan untuk mengelola alam. 16 DAFTAR PUSTAKA Abidin, Zainal, 2001, Filsafat Manusia, Rosdakarya, Bandung Alisjahbana, Sutan Takdir, Pemikiran Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Masa Depan Umat Manusia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992) Bagus, Lorens, 2000, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta Gandhy, Leela , 1998, Postcolonial Theory; A Critical Introduction, Allen & unwin, Sidney Hegel, GWF, 1988, Phenomenology of Spirit, Oxford University Press, London Hidayat, Komaruddin, 1994, Postmodernisme dan Keangkuhan Epistemologi Rasional, dalam Sutoyo, dkk, (ed), Postmodernisme dan Masa DepanPeradaban, Aditya Media, Yogyakarta Lash, Scott, 2000, Posmodernisme sebagai Humanisme ? Wilayah Urban dan Teori Sosial, dalam Bryan Turner, Teori-Teori Sosial Modernitas dan Postmodernitas, terj. Imam Baehaqi dan Ahmad Baidlowi, Pustaka Pelajar,Yogyakarta Levin, David Michel, 1988, The Opening of Vision: Nihilism and the Postmodernism Situation, Routledge, London Manshur, Faiz, Harian Media Indonesia 14 Mei 2005 Noerhadi, Toety Heraty: Aku dalam Budaya, Suatu Telaah Filsafat Mengenai Hubungan Subyek Obyek. Jakarta: Pustaka Jaya Piliang, Yasraf Amir Piliang, 1999, Hiper-Realitas Kebudayaan, LKiS, Yogyakarta Santoso, Listiyono, Jurnal Filsafat, April 2003, jilid 33. No. 1 Sartre, Jean Paul, 1948, Existensialis and Humanism, terj. Philip Mairet; Methuen, London Sugiharto, I. Bambang, 1996, Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat Kanisius, Yogyakarta Suseno, Frans Magnis, 1992, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Yogyakarta. Syariati, Ali, 1996, Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat, terj. Afif Muhammad, Pustaka Hidayah, Bandung Tim Penulis Rosda, 1999, Kamus Filsafat, Rosdakarya, Bandung