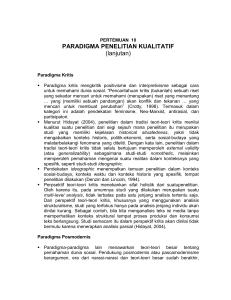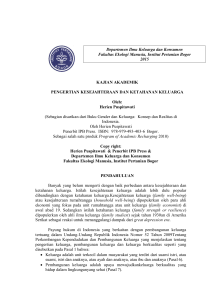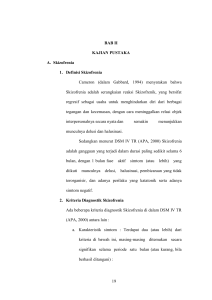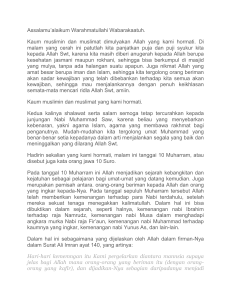Being, Wujūd
advertisement

An Inquiry on the Possibility of Man’s Authenticity in Transcendent Philosophy Husain Heriyanto Salam, Para aktivis ACRoSS ICAS yang selalu giat dan menggiatkan aktivitas keilmuan-kearifan, di mana pun kalian kini ada dan mengada... Saya bersyukur bahwa semua aktivis ACRoSS kini berkiprah di dunia keilmuan dan aktivisme intelektual Islam, Alẖamdulillāh... Seperti yang saya janjikan sebelumnya saya akan mengirim tulisan hikmah sebagai hadiah kepada Ms Ista yang baru saja memperoleh amanah dan anugerah Allah SWT berupa kehadiran seorang putri, yang mudahmudahan menambah barisan orang-orang yang mencintai hikmah dan kearifan. Semoga hadiah hikmah ini bermanfaat..! 27 Maret lalu, dalam sebuah seminar di ICAS Jakarta, saya mempresentasikan paper dengan judul “An Inquiry on the Possibility of Man’s Authenticity in Transcendent Philosophy (ẖikmah muta’āliyah)”; sebuah topik yang –sejauh saya ketahui melalui buku-buku/jurnal-jurnal dan seminarseminar nasional/internasional- belum pernah dikemukakan oleh siapapun. Tentu saja, topik otentisitas sudah kerap dibahas khususnya dalam filsafat eksistensialisme modern, tapi tak pernah dalam ẖikmah muta’āliyah. Hal ini bisa dimengerti mengingat konteks kelahiran ẖikmah yang merupakan hasil dari pengalaman dan perenungan Mullā Shadrā yang sepenuhnya metafisis tentang makna eksistensi (wujūd, being), bukan berangkat dari problem sosial kemanusiaan sebagaimana yang terjadi pada kemunculan eksistensialisme modern. Itu sebabnya, saya menggunakan kata “An Inquiry”(sebuah penyelidikan) yang hendak menguji apakah ẖikmah bisa ditawarkan sebagai kandidat aliran filsafat yang turut menyumbang menjawab salah satu problem akut manusia modern hari ini, yakni kemampuan menapaki hidup dalam keotentikan sebagai manusia, yang ternyata gagal dijawab oleh eksistensialisme modern. Husain Heriyanto Page 1 of 19 Meski awalnya bimbang apakah dimengerti oleh audiens, mengingat sulitnya persoalan ini untuk dikupas dalam presentasi yang singkat, Alhamdulillah, sejumlah hadirin termasuk beberapa presenter seminar sendiri menyatakan bahwa mereka sungguh tercerahkan dengan presentasi saya itu. Beberapa peserta pun meminta paper dan mengajukan sejumlah pertanyaan di luar seminar karena tidak ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin ada baiknya juga ‘ketercerahan’ itu bisa ditularkan kepada kalian semua, pegiat dan pencinta ilmu dan kearifan, insya Allah.. Quo Vadis Filsafat Islam? Salah satu kerisauan saya terhadap status filsafat Islam hari ini adalah adanya anggapan (dan perlakuan oleh banyak pengkajinya) bahwa ia hanya berurusan dengan hal ihwal metafisis tanpa berkorelasi dengan kehidupan di dunia profan yang kita huni ini. Ia fasih berbicara tentang pelik-pelik wujud tapi bisu seribu bahasa tentang pelik-pelik kemanusiaan. Saya berpikir jika bukan para filsuf yang berbicara manusia, lalu siapa? Ekonom? Politisi? Pengusaha? Pengacara? Mereka ini hanya memandang manusia dari perspektif sempit mereka sendiri. Hanya filsuf-lah yang paling layak dan mendalam mengupas apa makna menjadi manusia. Persoalannya, mengapa filsafat Islam justru tampak tak tertarik dengan isu ini. Apa artinya berbicara tinggi-tinggi tentang hikmah dan empat perjalanan fanā’-baqā’-fi-l-Ḫaqq-bi-l-Ḫaqq jika fitrah kemanusiaan kita tergerus oleh kejumudan dan tumpulnya kepekaan. Ibarat air hujan yang esensinya adalah karunia akan menjadi sia-sia bahkan malapetaka jika tanah tak mampu menyimpan/mengolah air, begitu pula mutiara hikmah akan mubazir belaka bahkan menjadi beban (ẖijāb) jika karakter kemanusiaan kita sudah tumpul karena obyektivikasi dan reifikasi. Tesis pokok saya adalah bahwa filsafat Islam mestinya harus mampu diarahkan untuk menjawab isu-isu aktual kemanusiaan. Ibn Sīnā, Suhrawardī, Mullā Shadrā sudah membekali kita dengan pemikiran-pemikiran mereka yang otentik dan cemerlang. Lalu apakah kita hanya mengulang-ulang dan membangga-banggakan doktrin-doktrin mereka tanpa kemampuan berpikir sendiri untuk menghadapi problema zaman? Jika dikatakan bahwa al-Asfār ditulis Mullā Shadrā setelah mengalami kasyf dan pencerahan jiwa, dan Husain Heriyanto Page 2 of 19 karenanya tidak bisa dimaknai secara profan seperti isu-isu kemanusiaan, maka saya katakan apakah al-Qur’ān tidak kurang sakral dan transendental? Faktanya, al-Qur’ān yang jelas-jelas wahyu dan diterima oleh al-Musthafā Yang Suci SAWW, berbicara lantang tentang isu-isu profan kemanusiaan. Nah, apakah al-Asfār lebih sakral daripada al-Qur’ān? Apakah Mullā Shadrā lebih suci-transendental daripada Nabi Mulia SAWW yang menangis memikirkan umatnya? Dalam paparan berikut banyak uraian teknis yang saya lewatkan. Melalui milis ini saya hanya hendak menyampaikan poin-poin pokok saja, yang terkadang perlu saya tambahkan penjelasannya atau memberi ilustrasi/contoh untuk mempermudah pemahaman pengertian/konsep tertentu. Demi kepraktisan, saya juga meng-‘copy and paste’ beberapa bagian presentasi saya yg kebetulan tertulis dalam English. Saya akui, memang untuk menulis tentang (lebih tepatnya bertutur dari) misteri Being perlu momen ketercerahan jiwa juga, tapi biarlah saya tulis apa adanya saja sekarang. Pengalaman saya ketika seminar riset sebulan di Washington 2008 lalu, saya perlu 3 hari bersunyi (terpaksa minta izin tak menghadiri sejumlah kegiatan termasuk makan kebab di restoran Arab di akhir pekan) sebelum mempresentasikan makna Being menurut Mullā Shadrā, yang saya bandingkan dengan gagasan linguisticality of being-nya Gadamer (dalam Truth and Method). Alhamdulillah, usai presentasi itu, Prof. McLean berkata, “It is amazingly unbelievable. Your presentation deeply enlightens me”. Dua kali beliau berkomentar seperti itu. Padahal, sebagaimana rekan-rekan ACRoSS ketahui, bahasa Inggris saya sangat minimal dan Indonesia banget. 1. Apakah Tak-Terelakkan untuk Menapaki Hidup yang bukan Pilihan Bebas Kita? Gugatan ini banyak digemakan oleh pemikir yang mendambakan kebebasan dan kemuliaan manusia. Kemuakan sejumlah pemikir eksistensialis terhadap kondisi kepengapan dan kesempitan horizon kemanusiaan yang didera manusia modern semakin deras disuarakan dalam kehidupan sekarang yang serba teknokratis, uniform, pragmatis, mekanis, serba terstruktur. Jika Husain Heriyanto Page 3 of 19 dulu teknologi menyesuaikan dengan manusia, maka kini manusialah – sang pencipta teknologi- yang harus menyesuaikan diri. Paham-paham kapitalisme, positivisme, sekulerisme, liberalisme, fungsionalisme, strukturalisme, dan isme-isme lain termasuk fundamentalisme, mullahisme, puritanisme, dan terorisme semakin menggerus kapasitas keunikan diri kita untuk mengada secara otentik. The current condition of the global age of the world, with many rapid changes taking place and too much crowded news, makes more difficult for anyone to dwell in his/her presence of self-awareness and self-determination. Modern man, then, suffers self-alienation (alienation of a self from itself through itself). Hidup otentik adalah hidup dengan kehadiran keseluruhan eksistensi kita. Apa yang kita lakukan merupakan manifestasi kesadaran kita yang dioperasikan melalui kehendak bebas. Yang kita kerjakan adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jiwa yang sadar senantiasa hadir dalam segenap tindakan dan perjumpaan kita dengan ‘yang lain’ entah itu kawan, pengamen, sarjana, ustad, pepohonan, langit, kerumunan orang di mall, kerusuhan massa, sebagaimana juga melewati keheningan malam menatap Supermoon. Akan tetapi, menurut tokoh-tokoh eksistensialis, sebagian besar manusia hidup dalam ke-tak-otentikan. Kebanyakan manusia menjalani hidup dalam keterpaksaan, kepura-puraan, kepalsuan, dan penuh topeng menjaga citra. Kita terperangkap dalam pilihan-pilihan yang bukan pilihan asli jiwa kita, terpaksa berdamai dengan kondisi yang mengobyekkan diri, dan bahkan ikut arus dan arah angin (tunduk pada keadaan). Kita tidak lagi berperan sebagai subyek sepenuhnya dari pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan kita, melainkan cuma obyek, predikat atau pelengkap penderita dari peristiwa-peristiwa yang melingkupi kita sedemikian sehingga kita merasa bahwa tindakan kita bukanlah bagian dari keberadaan diri; bahwa ucapan kita bukanlah bagian dari diri kita; bahwa pikiran kita bukanlah eksistensi kita; semuanya mengalami reifikasi (obyektivikasi) total, yang jika berlarut akan membuat diri kita terasing dari kedalaman eksistensi kita sendiri. Kita tak lagi sadar apa yang dikejar dalam hidup ini. Kita menjadi lupa dengan Husain Heriyanto Page 4 of 19 visi dan misi hidup yang mungkin telah dicanangkan sewaktu muda dulu dengan idealisme yang menyala atau ketika mencium ẖajar aswad yang berikrar kepada Tuhan Wujūd Murni untuk mengisi hidup menyingkap NamanamaNya. We live in absence with the reflective-consciousness, self-awareness, and contemplation. Rather we behave mechanically, do anything habitually, act pragmatically, and react impulsively without employing critical thinking, attentive heart, and caring soul. We have been trapped in daily routine with repetitive activities. Ya, rutinitas dan banalitas keseharian telah menjebak keberadaan kita sehingga tak lagi peka dengan keindahan dan keagungan Being, Wujūd. Kita tak tersentuh oleh keindahan dedaunan yang jatuh dari pohon. Air yang bening dan sejuk tak lagi memesona jiwa. Bintang cemerlang di ufuk hilang begitu saja tanpa menghangatkan jiwa. Benda-benda adalah stok barang-barang, bukan tangan-tangan sapaan Tuhan. Manusia pun telah direduksi sebagai salah satu sumber daya yang selevel dengan flora dan fauna; atau paling tinggi diidentifikasi sebagai anggota (member) kelompok ini, pengikut (follower) kelompok itu, dan pendukung (supporter) partai itu. Dunia hari ini adalah pasaraya raksasa, yang semuanya dikategorikan dalam laci-laci komoditas yang siap ditransaksikan. Semua peristiwa menjadi transaksional. Pun ibadah dan praktek-praktek keagamaan. Penderitaan orang dikemas dalam kalkulasi, yang mungkin bisa dijadikan bahan proposal pengajuan dana pendirian LSM. Persahabatan antar manusia- yang demikian indah dideskripsikan oleh Plato- hilang dan diganti dengan interaksi yang transaksional. Relasi yang terjadi adalah “Saya” dan “Ia” (I-It), bukan “Saya” dan “Engkau” (I-Thou), atau dalam rumusan lain “Subyek-Obyek”, bukan “Subyek-Subyek”. Di dunia kerja, relasi yang terjadi adalah “Tuan-Budak”, bukan hubungan “Pekerja-Pekerja” sebagaimana Imām ‘Alī ajarkan atau Khalil Gibran lukiskan; sedang di dunia politik terjadi transaksi “Pembeli SuaraPenjual Suara”, bukan relasi “Warga-Warga”. Nah, dalam konteks inilah, Heidegger menukas, “We are inevitably caught up and dragged into everyday banalities (fallennes and inauthenticity); the self-awareness is lost.” Tapi, dia juga menandaskan, “Authentic existence is Husain Heriyanto Page 5 of 19 aware of the meaning of being whereas the inauthentic (they-self) is not.” Ini artinya, di satu sisi, Heidegger mengafirmasi adanya eksistensi yang autentik dengan syarat harus ‘sadar tentang makna Being’. Tetapi, di lain sisi, dia mengeluh bahwa kita tak terelakkan terperangkap dalam banalitas keseharian yang tak-otentik di mana ‘kesadaran-diri hilang’. Kenapa demikian? Karena Heidegger memiliki prinsip ‘Being-in’ dan ‘Being-with’ (Mitsein). Nah, karena ‘Being-in’ (hidup di dalam dunia/horison tertentu) dan ‘Being-with’ (hidup bersama pengada-pengada lain) ini merupakan modus dasar eksistensi manusia (Dasein), maka menurutnya manusia tak bisa melepaskan diri dari ke-tak-otentikan. Dengan kata lain, manusia sudah dikutuk untuk menjadi pengada yang tak-otentik. Eksistensialis Sartre lebih radikal lagi. Baginya, “hell is other people”. Sartre berpandangan bahwa satu-satunya cara mengada yang otentik adalah dalam kesendirian total di mana tak satupun orang melihat, menilai, dan memosisikan saya sebagai obyek. Menurutnya, ketika orang lain memperhatikan dan menyapa saya, maka saya telah mengalami obyektivikasi dan saya tak lagi menjad subyek. Dengan demikian, manusia otentik menjadi hal yang mustahil ditemukan dalam kehidupan nyata kecuali hidup sendirian di planet Saturnus nun jauh di sana. Walhasil, tokoh-tokoh utama eksistensialis modern pun seperti Heidegger dan Sartre akhirnya tiba pada pesimisme akan kemungkinan kita bisa menapaki hidup secara otentik. Padahal eksistensialisme modern sebagai gerakan filsafat, yang dirintis oleh Kierkegaard, lahir dari pemberontakan terhadap aliran-aliran/isme-isme di muka yang dianggap telah menjatuhkan manusia menjadi mesin, robot, dan zombie. Nah, bagaimana halnya dengan ẖikmah muta’āliyah? Apakah aliran yang dibangun oleh Mullā Shadrā ini bisa meniupkan angin optimisme kita terhadap kemungkinan menjadi manusia yang otentik? Ataukah ia hanya hidup dalam kelas-kelas metafisika atau sorogan al-Asfār al-Arba’ah dan karya-karya Shadrā lain tanpa mampu berkontribusi dalam kehidupan nyata? Apakah ẖikmah bisa mencerahkan kehidupan konkret kita ataukah cuma dijadikan komoditas yang ditransaksikan melalui kelas-kelas dan seminar-seminar filsafat, yang berguna untuk memoles citra, menyerap dana dan memproduksi penghasilan? Husain Heriyanto Page 6 of 19 Termasuk dengan institusi ICAS Jakarta kita ini, yang saya turut membangunnya sejak awal from some of things to be something, from unknown to be known, apakah diarahkan untuk membangun kultur ilmiah yang ikut mencerahkan masyarakat lokal berdasarkan ẖikmah, ataukah hanya berguna untuk mengkaryakan elemen-elemen akademisi tertentu dan memproduksi sarjana yang gagap memahami dan merespons tantangan zaman? 2. Filsafat Mullā Shadrā tentang Being (Wujūd) • The foundation of Sadrā’s existential philosophy is his doctrine of Being (Wujūd) • The univocal meaning of being (ishtirāk ma’nawī) • Nothing but being is real • Principiality of existence (aṣālat al-wujūd) • The gradation of being (tashkīk al-wujūd). Saya kira Anda semua, aktivis ACRoSS, sudah mempelajari prinsip-prinsip filsafat Mullā Shadrā di kelas-kelas ICAS lalu, sehingga saya tak perlu menguraikannya lagi karena terlalu banyak waktu dan tempat menjelaskannya. Saya hanya hendak mengingatkan Anda semua tentang prinsip-prinsip ini dan keterkaitannya dengan uraian saya secara bebas di bawah ini, khususnya yang berhubungan dengan topik yang kita bicarakan. Mari kita mulai dengan proposisi sederhana berikut: I exist (Saya ada). Dalam logika formal, subyek kalimat itu adalah ‘I’, dan predikatnya adalah “existence’. Tetapi, dalam perspektif ashālat al-wujūd, yang berimplikasi pada waẖdat al-wujūd (Oneness of Being: OB1), subyek yang real adalah eksistensi sementara ‘saya’ adalah predikat, atribut atau secara umum disebut sebagai sebuah modus eksistensi. Diri kita sesungguhnya adalah manifestasi Being. Eksistensi kita adalah bagian dari lautan eksistensi. Husain Heriyanto Page 7 of 19 Digabung dengan prinsip tasykik al-wujūd (ini transliterasi ArabIndonesia ya..), kesadaran ini menyingkap kesadaran lainnya, yakni, kesadaran akan ‘turut menjadi bagian dalam semesta Being’, apa yang saya sebut sebagai Ocean of Being (OB2). Saya teringat sebuah petikan doa, yang menggetarkan kesadaran eksistensial kita semua, di kitab Mafātīh al-Jinān, Allāhumma adkhilnī fī lujjati baẖri aẖadiyyatik (“Ya Allah, masukkan aku ke dalam kedalaman samudera ketunggalanMu”). Kita adalah tetes-tetes air di samudera luas nan tak terbatas ..... .... ... .. . 3. Cara Menjumpai Being • Related to the way of perceiving (meeting) Being, i.e., through unveiling (kashf), by experience, it comes to the next OB (Opennes of Being) • Beings cannot be encountered, experienced and known as beings unless they are unconcealed, disclosed, unveiled. Oleh karena cara/jalan yang kita tempuh dalam ‘menjumpai’ Being melalui proses penyaksian dan penyingkapan (kasyf)- topik ini akan saya kupas sedikit nanti-, maka kesadaran uniter tadi meingimplikasikan karakter keterbukaan Being (Openness of Being; OB3). Being tidak di depan dan juga tidak di belakang, tapi selalu hadir membuka diri bersama kita. Sebaliknya, dari perspektif ‘kepengadaan’ kita, keterbukaan adalah sebuah kemungkinan; mungkin kita membuka diri untuk disapa Being dan mungkin juga tidak. Nah, penyingkapan itu sebetulnya adalah momen keterbukaan diri kita untuk menjumpai Being. Jadi, keterbukaan tersebut memiliki dua arah, yaitu Openness of Being dan Openness to Being (OB4). Keempat modus kesadaran uniter tadi (OB1, OB2, OB3, OB4) pernah saya presentasikan dalam pertemuan perpisahan (farewell meeting) dengan sejumlah akademisi dan pastor Catholic University of America di Washington 2008 lalu. Salah seorang pastor yang juga profesor, kalau tak salah namanya John Hogan, menyatakan ‘ketercerahannya’ dengan mengatakan (seingat saya), “Your words resonate me to remind the words of Santo Agustinus saying ‘To hear the truth, we dwell in’. Excellent, thanks.” Ucapan Santo Agustinus itu juga sempat saya baca dalam kaligrafi yang terpahat di dinding gedung utama Husain Heriyanto Page 8 of 19 kampus CUA. Lalu, pastor Hogan ini menjelaskan bahwa kita terlalu banyak mengkhutbahkan tentang kebenaran tapi tidak peduli dengan bagaimana ‘mendengar kebenaran’. Nah, bagaimana ‘mendengar kebenaran’ inilah yang dimaksudkan oleh para filsuf-sufi Islam tentang kasyf (penyingkapan). Term kasyf ini merupakan salah satu karakter khas epistemologi Islam sebagai metode ‘perjumpaan’ dengan Being. Hanya saja istilah ini lalu dipopulerkan sehingga terkadang mengalami distorsi atau pendangkalan makna. Bahkan sering term kasyf ini dipakai untuk pengalaman mistis yang aneh-aneh, yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, kasyf adalah metode untuk ‘mendengar kebenaran’, ‘menghayati kebenaran’. Banyak orang yang terlalu sibuk berbicara tentang kebenaran tapi mereka kehilangan kepekaan untuk disapa oleh Being. Kisah nyata berikut mudah-mudahan mempermudah apa yang saya maksud. Kisah Nyata: Kita Hidup dalam Ke-tak-hadiran Ada seorang pengamen yang pintar memainkan biola. Dia bermain di sebuah sudut stasiun KA Metro di Washington pada Januari 2007. Dia memainkan 6 aransemen Bach selama 45 menit. Sekitar 2000 orang melewatinya. Setelah 3 menit dia mulai bermain biola, ada seorang separuh baya memperhatikannya namun lalu meninggalkannya. Pada menit ke-4, seorang wanita melemparkan 1 dolar tanpa memperhatikannya; ini adalah dolar pertama yang dia terima. Pada menit ke-6 ada anak muda yang bersandar pada dinding untuk memperhatikannya, tapi lalu pergi. Pada menit ke-10 anak kecil 3 tahun berhenti mendengarnya tetapi ibu anak itu segera menarik tangan anaknya untuk bergegas; dan peristiwa seperti ini beberapa kali terjadi, setiap orang tua mendesak anaknya untuk terus berlalu meski sang anak tertarik untuk mendengar biola. Setelah 45 menit berlalu, hanya 6 orang (dari 2000 orang) yang tertarik mendengar musik biolanya. Dan pada menit ke-60, dia berhenti bermain biola dan keheningan menyergap dirinya. Tidak ada seorangpun yang memperhatikannya; tidak ada applaus, tidak ada pengakuan. Husain Heriyanto Page 9 of 19 Padahal kenyataannya adalah: pengamen itu adalah Joshua Bell, salah seorang musisi terbesar di dunia. Dia memainkan salah satu aransemen musik yang tersulit dan tercanggih dengan biola yang berharga 3,5 juta dollar (sekitar Rp 35 milyar). Dua hari sebelumnya, tiket pertunjukannya terjual habis dengan harga tiket rata-rata 200 dolar (Rp 2 juta). Kisah di atas adalah sebuah eksperimen untuk menguji sejauh manakah kesadaran dan kepekaan orang dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Narasi yang saya peroleh dari sebuah milis ini ([email protected]) tak hanya menggambarkan kelemahan persepsi kita akan keindahan (cita rasa estetis) tapi juga mengungkapkan bahwa kita hidup dalam ke-tak-hadiran jiwa dan kesadaran. Oleh milis ini, kisah yang profan dengan konteks banalitas keseharian itu diangkat menjadi sebuah kisah kehidupan manusia modern umumnya, yang ditandai oleh ke-tak-hadiran jiwa, ke-tak-sadaran, ke-takotentikan, ke-tak-pedulian dengan ‘yang lain’ di luar dirinya. Di akhir refleksinya, penulis milis itu bertanya kepada kita, “Jika kita tidak memiliki momen untuk berhenti dan mendengar salah seorang musisi terbaik di dunia, yang memainkan aransemen musik terbaik yang pernah ditulis, dengan menggunakan salah satu instrumen musik terbaik di dunia, maka betapa banyak hal yang lain yang hilang dalam sepanjang kesibukan hidup kita?” (.... how many other things are we missing as we rush through life?...) Yang diacu oleh penulis milis itu adalah kita kehilangan banyak momen yang bermakna sepanjang hidup yang kita lalui. Mengapa demikian? Karena kita hari ini hidup dalam situasi yang Anthony Giddens sebutkan sebagai ‘ketakpastian yang terindustrialisasikan’ (manufactured uncertainty) yang ditandai oleh hadirnya kecemasan yang tak bertujuan atau tak-transformatif, sikap dan tujuan yang tertawan oleh siklus stimulus-respons sehingga cenderung bertindak reaktif, alih-alih kreatif. Berkat teknologi modern yang telah berhasil memampatkan ruang-waktu sedemikian singkat-flat dalam ruang bumi yang tetap, kita kehilangan kesadaran bahwa kita sesungguhnya telah melalui terowongan ruang-waktu yang panjang-multidimensi. Arus Husain Heriyanto Page 10 of 19 informasi yang sedemikian deras menerjang kita setiap saat juga memperkecil ruang otonomi kita untuk memaknai dunia dan peristiwa. Kita berkubang dalam beragam kesibukan yang tak ada habis-habisnya karena berkejaran dengan waktu dan target; lebih celaka lagi target itu adalah sesuatu yang didesain, dipatok dan didesakkan oleh orang lain kepada kita, entah mereka itu bos, rekan bisnis, debt collector, customer, penagih janji, koalisi partai, pimpinan parpol, simpatisan, jama’ah/pengikut, muballigh, ustadz pimpinan pengajian, rektor, dosen, aktivis mahasiswa, LSM, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena target bisnis, kita harus memalsukan barang atau menipu orang. Karena target politik, kita harus mencampakkan komitmen dan persahabatan. Karena mengejar karier, kita memalsukan dokumen. Karena hendak mencari muka, kita harus memproduksi kebohongan dan bersikap palsu. Karena kelemahan diri, kita mencari-cari kesalahan orang lain dan bahkan merekayasa fitnah. Karena kebutuhan mendesak, kita melacurkan pengetahuan dan harga diri. Karena dorongan emosi, sebagian orang membakar tempat-tempat ibadah kelompok lain. Karena ini,...karena itu,.. kita terperangkap dalam hidup yang senantiasa mengobyekkan orang lain sekaligus jati diri kita yang bening. Dalam kehidupan seperti itu, akal pikiran kita hampir tak pernah berkesempatan ‘menarik napas panjang’ mengambil pelajaran sedemikian sehingga jiwa kita tak lagi peka dengan kemuliaan dan keindahan Being, yang sesungguhnya selalu hadir bersama dan menaungi kehidupan kita. Hidup yang kita lakoni tidak lagi menyingkap makna Being tapi justru kian menghindari dan melupakan Being. Nah, dalam model kehidupan seperti ini, tentu saja banyak momen hidup yang bermakna hilang begitu saja lewat di hadapan kita. Karena, kekuatan jiwa untuk mempersepsi ‘keagungan dan keindahan’ Being sudah luruh dan mungkin punah. Imām ‘Alī pernah berkata, “Seandainya ditawarkan kepadaku langit dan bumi beserta isinya tetapi dengan cara merampas pelepah daun makanan seekor semut, aku menolaknya”. Menurut Murtadha Muthahhari, pernyataan sahabat yang dijuluki oleh Nabi Suci SAWW sebagai ‘si pintu kota ilmu’ ini bukanlah ekspresi remeh atau rasa keprihatinan tertentu sebagaimana yang mungkin juga disuarakan kalangan aktivis sosial (atau dalam konteks terkini aktivis lingkungan). Pernyataan Imām ‘Alī itu merupakan sebuah ekspresi mendalam dari kesadarannya tentang keindahan dan keagungan Tuhan berikut Husain Heriyanto Page 11 of 19 segenap manifestasiNya, Nama-namaNya. Kita dan semut adalah sama-sama pengada yang mengambil bagian dari semesta Being; semut adalah manifestasi indah Being; menzalimi semut berarti memutuskan hubungan dengan semesta Being. Bandingkan dengan kondisi kita? Jangankan makanan semut, harta orang lain bahkan harga diri dan jiwa orang lain pun siap kita korbankan demi sesuatu yang kita anggap sebagai ‘eksistensi diri’, padahal yang sesungguhnya adalah, dengan melakukan hal itu, kita telah mengkhianati Diri sendiri yang bening dan otentik. Sekali Lagi: Being dialami, bukan dibicarakan Kita tidak bisa mengenal Being melalui abstraksi rasional-diskursif apalagi persepsi indrawi. Being hanya bisa kita jumpai melalui pengalaman, penghayatan, penderitaan, kepedulian, tanggung jawab, keotentikan jiwa, dan cinta kasih yang tulus. Being sebagai konsep, ya, tentu saja merupakan subyek pemikiran, namun realitas hakiki Being itu sendiri tidak mungkin dikonseptualisasikan atau diobyektivikasi. Apapun pemahaman, bayangan dan pengertian tentang Being bukanlah Being itu sendiri; itu adalah konsep tentang Being, bukan realitas Being. Bagaimana mungkin kita memahami (mengonsepsi) Being sementara eksistensi kita adalah tetes pengada yang mengambil bagian samudera Being yang tak-terbatas? Izinkan saya mengutip kembali kisah Imām ‘Alī. Saya gagal menemukan contoh lain dalam sejarah Islam yang mengaitkan persoalan tentang makna Wujud dengan kehidupan konkrit kecuali pada tokoh ini, yang dijuluki para sufi sebagai tāj-l ‘ārifīn (puncak mahkota orang-orang bijak). Alkisah, suatu ketika seseorang mengantarkan surat Mu’awiyah kepada Imām ‘Alī. Dalam surat tersebut ada sebuah pertanyaan ‘apakah itu wujud?’. Ketika itu, Imām ‘Alī langsung menukas, “Orang semacam Mu’awiyah tidak akan mungkin mengajukan pertanyaan ini.” Setelah diselidiki, ternyata memang itu bukan berasal dari Mu’wiyah tetapi dia menyelipkan saja pertanyaan itu yang dikutip dari percakapan orang Syam (ketika itu Syam memang merupakan wilayah peradaban tua seperti di Nedessa dan Harran, yang banyak dikunjungi sarjana filsuf Yunani yang diusir dan dikejar-kejar oleh kerajaan Romawi yang melarang filsafat). Husain Heriyanto Page 12 of 19 Nah, pertanyaannya, mengapa Imām ‘Alī berkata demikian? Dari mana dan bagaimana dia tahu bahwa pertanyaan itu tidak mungkin terlontar dari kesadaran Mu’awiyah (kalau dilafazkan mungkin saja karena dia telah menuliskannya). Seraya meminta maaf kepada rekan-rekan ACRoSS yang mungkin masih memuliakan Mu’awiyah, saya harus menyatakan bahwa Imām ‘Alī tiba pada pernyataan tadi berdasarkan pemahamannya yang mendalam tentang Wujūd, Being bahwa orang yang berperilaku seperti Mu’awiyah (suka ingkar janji, berbohong, memfitnah, membunuh tanpa alasan kecuali karena hasrat kekuasaan, mengadu domba kaum Muslimin, dan sejenisnya) tidak akan mungkin muncul pada dirinya kesadaran tentang Wujūd. Cukup panjang untuk menjelaskan hal ini; mungkin perlu seminar khusus untuk mempresentasikan argumen dengan pendekatan fenomenologis dan hermeneutika-eksistensial. Tetapi, secara ringkas, bisa saya jelaskan bahwa cara berada Mu’awiyah itu sendirilah yang membuatnya terisolasi dari kesadaran tentang Being. Tidak mungkin orang yang zhalim seperti Mu’awiyah itu bisa hadir dalam dirinya persepsi tentang Wujūd sebagaimana juga tidak mungkin kehadiran persepsi Wujūd dalam diri seseorang bisa melahirkan kezhaliman seperti Mu’awiyah itu (yang telah lama direncanakan secara sistematis). Kisah ini – yang diriwiyatkan oleh sejumlah buku- mengajarkan kita bahwa kezhaliman sebagai keburukan etis berkorelasi eksistensial dengan praktek obyektivikasi secara ontologis. Maksud saya, kezhaliman itu tidak hanya berada pada wilayah praktis dan etis sebagaimana diduga banyak orang, melainkan ia juga terkait dengan cara berada yang bersifat ontologis. Kezhaliman merupakan bentuk obyektivikasi sosial yang kasar; memaksa dan memperlakukan orang lain sebagai obyek. Kezhaliman merupakan selubung atau hijab yang membuat diri kita tak lagi mengenal Being bahkan Diri kita yang otentik. Saya akan jelaskan argumennya dalam uraian “The Relationality is a mode of Being” nanti. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan otentik tentang Being harus diverifikasi oleh sebuah transformasi diri secara eksistensial yang holistik. Pemahaman yang benar tentang Wujūd pastilah berimplikasi (implikasi ontologis, bukan implikasi logis) kepada pembentukan diri yang mengarah pada penyingkapan makna Being, atau dalam bahasa teologiHusain Heriyanto Page 13 of 19 filosofis, menyingkap Nama-Nama Tuhan; atau dalam bahasa Nabi Suci SAWW “takhalluq bi akhlāqillāh” (berkarakter dengan Nama-nama Allah SWT). Kembali pada sub-topik kita di muka, Being memang harus dialami dan dihayati. Satu-satunya cara mengenal Being adalah dengan menyelami dan menyingkap maknanya, bukan memperlakukannya sebagai obyek pemikiran apalagi obyek tindakan. Ketika kita mengobyekkannya, kita berarti telah mengambil jarak. Dan dengan mengambil jarak dari Being, kita tak lagi mengenalnya. Yang dimaksud menyelami Being itu adalah ‘mendengar, menyaksikan, dan merasakannya’. Saya ingin mengulang apa yang ditulis sebelumnya, “... Being hanya bisa kita jumpai melalui pengalaman, penghayatan, penderitaan, kepedulian, tanggung jawab, keotentikan jiwa, dan cinta kasih yang tulus...” Jadi, tugas kita adalah ‘mendengar Being’. Sebagaimana pendengaran fisik bahwa telinga kita akan lebih peka mendengar bebunyian dalam keheningan dan jauh dari kebisingan, maka jiwa kita pun akan lebih berkemampuan mendengar Being dalam kebeningan dan keotentikan jiwa dan jauh dari desakan-desakan eksternal yang mengintervensi kebebasan eksistensial kita. Kita harus menjumpai Being dalam lautan kehidupan yang real; itulah makna denotatif dari penyingkapan (kasyf). Being menghadirkan makna kepada Hidup dan pada saat yang sama Hidup menyingkap makna Being. Kita harus bergelut dengan kisah kehidupan dan bergulat dengan pelikpelik persoalan kehidupan. Saya tidak hendak melanjutkan pembahasan ini; Anda baca saja karya Toshihiko Izutsu mengenai perjumpaan Being dalam bukunya The Concept and Reality of Existence dengan bahasa uraiannya yang mengalir dan fasih. Seyyed Mohammed Khamenei, ketua SIPRIn (Sadra Islamic Philosophy Research Institute) dan juga kakak pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei, pernah memuji Izutsu dalam pembukaan Konperensi Filsafat Islam di Teheran 2009 lalu, sebagai sarjana yang pemahamannya mendalam tentang filsafat Mullā Shadrā. Nah, sampai di sini, pandangan eksistensial Mullā Shadrā dan kaum eksistensialis modern, khususnya Heidegger, sama-sama memiliki perhatian yang mendalam tentang Being. Mereka juga sepakat bahwa metode yang Husain Heriyanto Page 14 of 19 sesuai untuk mengenal Being adalah melalui keterlibatan eksistensial; yang dalam istilah Heidegger sebagai fenomenologi-eksistensial melalui Denken. Berkaitaan dengan isu otentisitas, Heidegger secara eksplisist mengatakan, “kesadaran tentang makna Being merupakan karakter kehidupan yang otentik”. Namun, mereka berpisah dalam penerapannya di kehidupan sosial. Sejalan dengan prinsip Being-in dan Being-with yang dia gagas, maka menurut Heidegger manusia tak terelakkan hidup dalam ke-tak-otentikan. Heidegger pesimistik terhadap kemungkinan kemunculan manusia yang otentik, meski dia sesungguhnya concern sekali dengan keotentikan eksistensial Dasein (manusia). Nah, bagaimana halnya dengan Mulla Shadra, yang sepengetahuan saya, tak pernah berbicara dalam konteks problem eksistensial kemanusiaan ini? Dia mengulas banyak tentang wujūd dalam perspektif murni metafisika. Riwayat menyebutkan Shadra mengalami pencerahan dan perjumpaan Being melalui penyingkapan yang mendorongnya melakukan sistematisasi pengalamannya itu dalam karya-karyanyanya seperti al-Asfār al-Arba’ah, alShawāhid al-Rubūbiyyah, dan al-Ḫikmah al-‘Arshiyyah. 4. The relationality is a mode of being Sejauh yang saya pahami, dalam pandangan eksistensialis Mullā Shadrā, relasionalitas adalah modus Being. Kalau boleh menulisnya dengan ungkapan saya sendiri, tesis itu bisa berbunyi “to exist is to relate”, ‘mengada adalah berkorelasi’. Prinsip interrelasi, interkoneksi dan interdependensi, yang kini disuarakan oleh pemikir global, memperoleh basis filosofisnya dalam pandangan Shadrā. Setidaknya, ada 2 argumen untuk membuktikan tesis ini, yaitu melalui pendekatan analitis dan pendekatan fenomenologis. Keduanya saya uraikan secara singkat. Kita mulai dengan proposisi berikut: “Kertas itu (adalah) putih” Husain Heriyanto Page 15 of 19 Melalui proposisi ini, kita hendak merelasikan dua konsep, yaitu ‘kertas’ (sebagai subyek) dan ‘putih’ (sebagai predikat). Sedangkan kata ‘adalah’ berfungsi sebagai penghubung, yang tanpanya tidak ada proposisi. Bahkan, esensi proposisi sebetulnya terletak pada kopula ‘adalah’ itu karena esensi proposisi adalah menghubungkan kedua pengertian (quiddity). Kertas adalah satu hal, sedang putih adalah lain hal. Nah, dengan kalimat “Kertas itu adalah putih” kita menghubungkan dua pengertian tersebut. Padahal, dalam kenyataannya di realitas eksternal, apa yang di depan kita adalah satu kesatuan (satu instanta), yaitu sebuah benda yang ringan dan tipis yang bisa dipakai untuk menulis dan berwarna putih. Pikiran kitalah yang membuatnya menjadi konsep-konsep ‘kertas’, ‘putih’, ‘ringan’, ‘mudah terbakar’, ‘tipis’ dan sebagainya. Nah, proposisi “Kertas itu adalah putih” itu merupakan ungkapan tindakan jiwa; itu sebabnya proposisi diterjemahkan dengan ‘putusan’ dalam bahasa Indonesia. Jiwa kita menyingkap sebuah hubungan yang ditandai dengan kopula ‘adalah’. Memang kita sering menulisnya dengan “Kertas itu putih” tanpa kopula ‘adalah’. Akan tetapi, meski tanpa kopula itu, kita memahami kalimat itu sebagai sebuah putusan/penilaian bahwa kertas itu bersifat putih. Satu lagi yang menarik adalah penggunaan kata ‘adalah’ itu sendiri. Kata dasar ‘adalah’ adalah ‘ada’, yang merupakan terjemahan dari Being atau Wujud. Secara tak semena-mena, penggunaan kata yang terkait dengan eksistensi sebagai kopula juga terjadi dalam bahasa Inggris. Kalimat itu menjadi “The paper is white”. Kopula ‘is’ berfungsi sebagai relasi antara subyek dan predikat. Bahkan dalam bahasa Inggris, kopula ‘is’ bersifat niscaya harus hadir dalam kalimat kategoris seperti itu. Dan kata ‘is’ termasuk ke dalam kelompok ‘to be’, yang berarti ‘adalah’, ‘mengada’. Memang ada jenis bahasa yang menyembunyikan relasi tersebut. Dalam bahasa Arab, misalnya, proposisi itu adalah “Al-qirthas-l-abyadh”. Di sini tidak ada kata khusus yang berfungsi sebagai kopula. Tetapi, penutur dan petutur memahami bahwa proposisi itu terdiri dari subyek dan predikat di mana ‘putih’ merupakan atribut dari ‘kertas’. Husain Heriyanto Page 16 of 19 Dalam bahasa Persia, relasi itu dieksplisitkan dengan term ‘ast’, bentukan dari kata ‘hasti’ (eksistensi). Jadi, proposisi di atas menjadi “On qaghaz safid ast”. Uniknya, kopula dalam bahasa Persia baik yang afirmatif (ast) maupun negatif (nis), ditulis belakangan setelah subyek dan predikat. Boleh jadi, perbedaan penggunaan kopula dalam kalimat dalam beberapa bahasa ada hubungannya juga dengan corak pikir dan kebudayaan pengguna bahasa tersebut. Jika makna ‘ada’ bagi orang Inggris terlalu jelas dan eksak sehingga ‘saking jelasnya’ orang Inggris cenderung memahami yang jelas secara indrawi sebagai ‘ada’ yang pokok. Sedang dalam bahasa Arab, kopula tersembunyi sehingga memerlukan refleksi lebih lanjut untuk menemukan ‘ada’. Dan bahasa kita, bahasa Indonesia, kopula itu kadang tampak dan kadang tersembunyi; jadi, posisi bahasa kita berada di tengah antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sebetulnya masih ada penyingkapan-penyingkapan kognitif (kasyf ‘ilmī) lain yang lebih dalam melalui refleksi dari proposisi sederhana di atas, tetapi saya harus berhenti di sini untuk masuk langsung ke pokok pembahasan kita. Analisis proposisi –sebagai ekspresi putusan jiwa yang sadar- di atas menunjukkan bahwa ‘ada’ (is, ast) merupakan penghubung kedua pengertian/konsep. Kata ‘adalah’ atau ‘is’ atau ‘ast’ merupakan eskplisitasi dari kesadaran bahwa eksistensi berkarakter merelasikan kuiditas-kuiditas atau apa-apa yang dipahami sebagai sesuatu. Eksistensi adalah menghubungkan. Secara fenomenologis, prinsip relasionalitas sebagai modus Being ini bisa dipaparkan ringkas sebagai berikut. Kita semua mungkin pernah kehilangan barang, katakanlah sebuah pena. Pertanyaan yang muncul adalah “Di mana pena itu?” Mungkin ada sejumlah pertanyaan lain yang menyertainya, seperti “Kapan kira-kira ia hilang?”, “Siapa yang mengambilnya?”, “Bagaimana ia bisa hilang?”, dan seterusnya. Semua pertanyaan ini berangkat dari kesadaran intuitif bahwa ‘pena itu ada’. Kesadaran ‘pena itu ada’ bersumber dari keyakinan ‘ada sesuatu yang bernama pena’, yang pada gilirannya juga berasal dari kesadaran priomordial ‘ada sesuatu’, dan akhirnya berakhir pada kesadaran transendental ‘ada’. Mari kita refleksikan fenomena keseharian itu dalam bingkai epistemologi eksistensial Mullā Shadrā. Berbagai pertanyaan tadi merupakan Husain Heriyanto Page 17 of 19 ekspresi pencarian ‘sesuatu yang ada’, sebuah kehendak (volition) untuk mengungkap ‘realitas ada’: ia ada tapi tak ada (tak hadir) atau ia tidak ada tapi sesungguhnya ia ada. Terdapat relasi intensionalitas antara kesadaran transendental akan ‘ada’ dan kehendak mengungkap ‘ada’. Dalam teori pengetahuan Mullā Shadrā yang mengupas pengetahuan hudhuri sebagai basis semua pengetahuan manusia termasuk tindakan intensional, pengetahuan dan kehendak adalah satu dan hal yang sama. Oleh karena itu, perhatian jiwa intensional (iltifat al-nafs) terhadap sesuatu (realitas eksternal) merupakan sebab memadai (sufficient cause) kehadiran bentuknya (form) dalam pikiran. Dengan demikian, terdapat relasi intensional antara pengetahuan/kehendak jiwa (subyek) dan realitas eksternal (obyek). Dan relasi ini hanya terjadi karena kesadaran transendental ‘ada’. Dengan demikian, relasionalitas itu sejatinya memang karakter Being. Oleh karena itu, penggunaan term Being-in dan Being-with oleh Heidegger, yang makna referensialnya adalah Dasein (manusia), akan lebih sesuai dalam filsafat wujud Mullā Shadrā; atau –meminjam istilah Henry Corbin- prinsip Heidegger itu bisa menjadi ulasan tambahan (catatan kaki) bagi eksistensialisme Mullā Shadrā. Nah, oleh karena relasionalitas itu adalah modus Being, maka prinsip Being-in dan Being-with tidak mesti menjadi alasan untuk menepis kemungkinan manusia untuk mengada secara otentik sebagaimana yang dikeluhkan Heidegger. Dia sendiri adalah pendamba manusia otentik tapi karena pemikirannya seperti itu maka tampak bagi kita terjadi kesenjangan antara pemikiran dasariahnya dengan prinsip-prinsip lain yang dia ajukan. Dengan kata lain, terdapat lubang yang menganga antara premis mayor dengan konklusi karena premis minornya yang tidak ‘nyambung’ (dalam istilah logika, argumen Heidegger tidak memiliki term tengah). 5. Implikasi Praktis The Implication in Practice • The way of unveiling of Being is not an instrument, rather it is the ontological route, existential means Husain Heriyanto Page 18 of 19 • • • • • Care Responsibility Suffering in self-determination Respect Freedom in interdependence Berdasar uraian tadi mengenai ‘relasionalitas sebagai modus Being’; bahwa Being berkarakter relasional, maka kita bisa lebih memahami latar belakang mengapa Imām ‘Alī berkata, “Orang semacam Mu’awiyah tidak akan mungkin mengajukan pertanyaan ini (tentang wujud).” Dalam pandangan Imām ‘Alī, perilaku Mu’awiyah yang penuh dengan keculasan, kemunafikan, dan kebohongan telah membuat dirinya terasing dari Being karena kezhaliman merupakan tindakan yang memutuskan hubungan dengan Being. Pelbagai bentuk kezhaliman terutama kepada sesama manusia merupakan obyektivikasi kasar terhadap Being. Human relationship • To be authentic, we should apply the sense of respect each other • We must establish co-existence relationship, interdependence relation, free interconnectedness • Hence, humiliation and oppression of human being and any existent in the world destroy the relation and veil Being Epilog Kembali ke pertanyaan awal yang mendorong penyelidikan ini: Apakah ẖikmah muta’āliyyah dapat menawarkan pencerahan bagi manusia modern untuk berkemampuan mengada menjadi manusia yang merdeka, asli, dan otentik? Silakan Anda semua menjawab pertanyaan tersebut dengan mengacu kepada apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya telah cukup banyak ‘berbicara tentang’ Being, saatnya kini ‘mendengar’ Being ... Husain Heriyanto Page 19 of 19