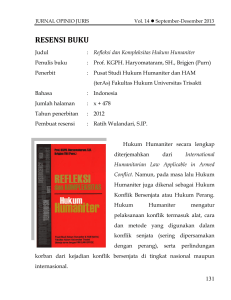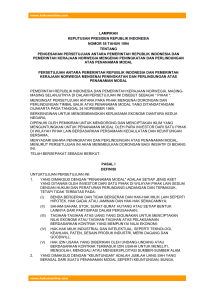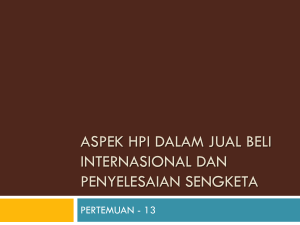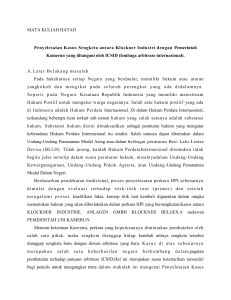ARTIKEL Pengembalian Aset Kejahatan Eddy OS Hiariej Keputusan
advertisement

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA Volume 13 Mei—Agustus 2013 ARTIKEL Pengembalian Aset Kejahatan Eddy O.S Hiariej Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi Nasib Perjanjian Lainnya Damos Dumoli Agusman Konsepsi Kedaulatan Negara dalam Borderless Space Purna Cita Nugraha Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional Harry Purwanto Implementasi Konvensi New York 1958 dalam Perkara-Perkara Arbitrase Internasional di Indonesia Mutiara Hikmah RESENSI BUKU Hukum Tentang Ekstradisi AM. Sidqi ISTILAH HUKUM i JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional OPINIO JURIS Volume 13 Mei—Agustus2013 DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2013 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional OPINIO JURIS Volume 13 Mei—Agustus 2013 Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Sejak Oktober 2009 Penanggung Jawab Linggawaty Hakim, SH, LL.M Raudin Anwar, SH, LL.M Redaktur Yoshi Iskandar, SH; Kemal Haripurwanto, SH, LL.M; Amrih Jinangkung, SH, LL.M; Elmar Iwan Lubis, SH; ADH. Irfan, SH; Drs.Sukarsono; Sudarsono, SH., MM.; Rofita, SH.; Hendrar Pramudyo, SH. Editor AM. Sidqi, SIP; Santa Marelda Saragih, SH, MH.; Ratih Wulandari, SIP; Vina Novianti, S.Hum; M. Ferdien, SH; Bibid Kuslandinu, SH.; Rike Octaviany, SH, LL.M. Disain Grafis AM. Sidqi, SIP; Drs. Didi Achmadi; Sekretariat Siti Fatimah, SH; Uki Subki, S.Sos, M.Si; Tasunah; Maisaroh, S.Sos Alamat Redaksi: Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat Telp. +62 21 3846633 Fax. +62 21 3858044; Email: [email protected] Jurnal Opinio Juris versi digital dapat diunduh di website http://pustakahpi.kemlu.go.id/ Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Opinio Juris adalah pendapat dan analisis pribadi dari para penulis dan tidak mewakili pandangan/posisi Kementerian Luar Negeri dan/atau Pemerintah Republik Indonesia. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................ i Pengantar Redaksi...........................................................................................ii Pengembalian Aset Kejahatan ..................................................................... 1 Eddy O.S Hiariej Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting Bagi Perjanjian Internasional Lainnya ..................................... 16 Damos Dumoli Agusman Konsepsi Kedaulatan Negara dalam Borderless Space ......................... 22 Purna Cita Nugraha Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional .......................................................................................................................... 47 Harry Purwanto Implementasi Konvensi New York 1958 dalam Perkara-Perkara Arbitrase Internasional di Indonesia ....................................................... 81 Mutiara Hikmah Resensi Buku .................................................................................................. 95 Hukum Tentang Ekstradisi AM. Sidqi Istilah Hukum .............................................................................................. 100 Tentang Penulis ........................................................................................... 103 i JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 PENGANTAR REDAKSI Setelah dua volume sebelumnya mengangkat tema khusus yaitu: Asset Recovery dan Hukum Laut, maka volume kali ini memuat tulisantulisan hukum dengan tema yang bervariasi. Hal ini merupakan pertimbangan dari Redaksi guna menampilkan keanekaragaman isu hukum internasional dan menjaga antusiasme serta ketertarikan para pembaca. Pada volume 13 tahun 2013 ini, redaksi menyajikan dua tulisan bertemakan perjanjian internasional yaitu “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional” oleh Harry Purwanto dan “Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi Perjanjian Lainnya” oleh Damos Dumoli Agusman dan tulisan dengan tema yang bervariasi yaitu: “Pengembalian Aset Kejahatan” oleh Eddy O.S. Hiariej, “Implementasi Konvensi New York 1958 dalam Perkara-Perkara Arbitrase Internasional di Indonesia” oleh Mutiara Hikmah dan “Konsepsi Kedaulatan Negara dalam Borderless Space” oleh Purna Cita Nugraha. Dari sejumlah tulisan yang disajikan pada volume kali ini, terdapat tulisan yang cukup aktual seperti tulisan tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN. Pada kesempatan ini, Redaksi Opinio Juris tetap mengajak para pembaca untuk turut berkontribusi serta memberikan saran dan masukannya demi peningkatan kualitas Opinio Juris di masa mendatang melalui email [email protected]. Jurnal Opinio Juris volume 13 tahun 2013 dan volume sebelumnya dapat pula dibaca dalam bentuk e-journal melalui website http://pustakahpi.kemlu.go.id. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca yang tidak memperoleh hard copy-nya dapat mengakses dan terb uka luas untuk publik. ii JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Akhir kata, Redaksi Opinio Juris berharap agar jurnal ini dapat menjadi sarana dalam menyebarluaskan berbagai informasi, wacana dan wadah sumbangsih pemikiran di bidang hukum dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri. Redaksi Opinio Juris iii JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 PENGEMBALIAN ASET KEJAHATAN1 Eddy O.S Hiariej Abstrak Sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah, negara pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, dan peserta aktif dalam inisiatif pengembalian aset yang dicuri, Indonesia perlu melakukan lebih banyak upaya dalam mengembalikan aset-asetnya yang dicuri sebagai suatu bagian dari kebijakan nasional untuk memerangi korupsi. Artikel ini membahas tiga hal yang diperlukan untuk dipertimbangkan oleh Indonesia dalam pengembalian aset yang dicuri, yaitu prasyarat pengembalian aset yang dicuri, urgensi untuk membentuk hukum tentang pengembalian aset yang dicuri dan rezim pengembalian aset yang dicuri. Dalam prasyarat pengembalian aset yang dicuri, terdapat enam elemen yang dapat mendukung pengembalian aset tersebut. Artikel ini juga memaparkan urgensi pembentukan undang-undang tentang pengembalian aset yang dicuri. Sementara dalam rezim pengembalian aset yang dicuri, dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendukung pengembalian aset yang dicuri. Kata Kunci: Piagam ASEAN, organisasi internasional, pengembalian asset, korupsi. Abstract As a country with a low rating in corruption perception index, a State Party to the United Nations Convention Against Corruption, and an active participant in the Stolen Asset Recovery Initiative, Indonesia needs to take more efforts in recovering its stolen asset as a part of national measure to fight against corruption. 1 Artikel ini disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Pengembalian Aset Curian dan Praktik Pelaksanaannya di Indonesia,” kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dengan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu, 4 Desember 2012. 1 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 This paper will discuss three things that need to be considered by Indonesia in recovering its stolen asset, i.e. the stolen asset recovery prerequisites, the urgency of having stolen asset recovery laws, and the regime of asset recovery. In the stolen asset recovery prerequisites, there are six items that will support stolen asset recovery. This paper will elaborate the urgency of having stolen asset recovery laws. While in the stolen asset recovery law regime, it is explained which measures that must be taken to succeed stolen asset recovery. Keywords: ASEAN Charter, international organization, asset recovery, corruption. Pengantar Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Padahal salah satu sifat kejahatan korupsi adalah kemampuan pelakunya memanfaatkan 2 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kemajuan teknologi di bidang perbankan karena transaksinya yang bersifat rahasia, cepat, mudah dan tidak memerlukan uang kartal2. Di Indonesia, korupsi menyebabkan kerugian besar keuangan negara. Dicurigai, setidaknya ada empat negara maju – Singapura, Australia, Amerika dan Swiss – sebagai tempat menyembunyikan ‘harta curian.’ Bahkan, harta tersebut seakan-akan dilindungi oleh aturan legal procedure negara setempat yang mengaturnya sebagai bagian dari kerahasiaan bank (bank secrecy act). Dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset kejahatan tersebut apabila negara-negara maju tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, makalah ini akan mengulas tiga hal penting dalam rangka pengembalian aset negara, yakni prasyarat pengembalian aset, urgensi undang-undang pengembalian aset, dan rezim hukum pengembalian aset. Prasyarat Pengembalian Aset Pengembalian aset suatu negara yang telah dicuri, kendatipun tidak selamanya terkait erat dengan hasil kejahatan, yang paling dominan biasanya berhubungan dengan berbagai kejahatan ekonomi yang meliputi korupsi, kejahatan perpajakan, kejahatan perbankan, perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang serta kejahatan pencucian uang. Pencurian aset juga sering kali bertalian dengan suatu rezim otoriter yang korup. Oleh karena itu, untuk mengembalikan aset-aset yang telah dicuri, salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara3. 2 Sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pembukaan Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional, BPHN Depkumham RI dan FH Universitas Udayana, Denpasar-Bali, 14 Juni 2006. 3 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Tidak hanya kemauan politik pemerintah semata sebagai eksekutif, tetapi juga kemauan politik dari parlemen dan lembaga yudikatif. Kemauan politik dari parlemen terkait dengan seperangkat aturan hukum yang harus disiapkan mulai dari pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset sampai pada pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Demikian pula yang berkaitan dengan pengaturan mengenai hubungan kerja sama timbal balik antarnegara. Dalam konteks yang demikian, peranan parlemen untuk membentuk undang-undang sangat dominan. Sudah barang tentu undang-undang yang dibentuk seyogyanya memudahkan kinerja aparat penegak hukum dalam rangka pengembalian aset tersebut. Sementara kemauan politik dari lembaga yudikatif terkait dengan sistem peradilan yang transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Apabila kemauan politik dari parlemen dan lembaga yudikatif tersebut telah ada, barulah kemudian yang dibutuhkan adalah kemauan politik pemerintah yang biasanya ditindaklanjuti dengan langkah hukum. Kemauan politik negara yang sungguh-sungguh dalam rangka pengembalian aset merupakan jaminan utama bagi para aparat penegak hukum untuk bertindak secara leluasa berdasarkan seperangkat aturan yang ada tanpa tekanan atau beban psikologis apapun. Pengalaman beberapa negara yang berhasil mengembalikan aset-aset yang telah dicuri oleh rezim yang korup dan otoriter menunjukan bahwa kemauan politik negara sangat menentukan. Di Filipina, beberapa hari setelah runtuhnya rezim Ferdinand Marcos, Pemerintah Filipina di 3 Negara di sini meliputi tiga kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebagaimana sistem separation of power atau pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Lihat selanjutnya dalam Montesquieu, 2007, The Spirit of Laws, diterjemahkan oleh M. Khoril Anam, Nusamedia, Bandung, hlm. 106. 4 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 bawah kepemimpinan Corazon Aquino membentuk The Presidential Commission on Good Government (PCGG) yang bertugas mengembalikan aset yang telah dicuri Marcos. Langkah pertama yang dilakukan PCGG adalah membuka perwakilan informal di pengadilan Amerika dan Swiss untuk mendapatkan informasi dan kemudian meminta membekukan aset Marcos. Syarat yang diajukan oleh kedua negara tersebut adalah agar pengadilan di Filipina mengajukan gugatan yang intinya untuk mengambil alih simpanan Marcos. Selanjutnya, PCGG mengajukan gugatan perdata ke Sandiganbayan4 dan setelah itu asetnya dapat dikembalikan dalam kurun waktu kurang lebih 17 tahun. Demikian pula yang terjadi di Nigeria setelah berakhirnya rezim Sani Abacha. Presiden Obasanjo membentuk Special Police Investigation (SPI) untuk mengembalikan aset yang dicuri Abacha. Lebih sederhana dari apa yang pernah ditempuh Filipina, SPI meminta bantuan Swiss Law Firm, Mofrini And Partners. Begitu juga yang terjadi di Peru, Presiden Alberto Fujimori membentuk Special Prosecutor untuk menyelidiki kasus Vladimiro Montesinos yang mencuri aset negara sekitar US$ 2 miliar. Jauh lebih mudah dari apa yang terjadi di Filipina dan Nigeria, pengembalian aset di Peru dengan cepat dilakukan karena Vladimiro Montesinos sebagai pelaku utama masih hidup5. Selain masalah political will, harmonisasi peraturan perundangundangan dan sistem peradilan adalah hal penting dalam rangka pengembalian aset. Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa pengembalian aset tidak selalu berkaitan dengan kejahatan korupsi tetapi 4 Sadiganbayan adalah pengadilan khusus di Filipina untuk mengadili kejahatan korupsi dan penyelewenagan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik. 5 Peter Mahmud Marzuki, 2007, StAR Initiative Dalam Perspektif Hukum Perdata, Newsletter KHN, Vol. 8, No. 1, Januari – Februari 2008, hlm. 14. 5 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 juga dengan kejahatan lainnya. Bahkan tidak selamanya pengembalian aset terkait perkara pidana, namun dapat juga perkara perdata. Oleh karena itu, masalah pengembalian aset membutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan yang tepat. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antara ketentuan undang-undang yang satu dengan ketentuan undang-undang yang lain. Dalam konteks Indonesia, kejahatan-kejahatan yang berpotensi menimbulkan pencurian aset negara, seharusnya memiliki rezim hukum tersendiri. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, penegakan hukum untuk memproses kejahatankejahatan tersebut secara prosedural dapat berbeda dengan yang telah ada. Selanjutnya yang akan diulas adalah sistem peradilan. Berkaitan dengan sistem peradilan, tidak mungkin dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajaran sebab sistem peradilan adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan, yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut6. Secara sederhana, sistem peradilan, dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana, adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana 6 Eddy, O.S Hiariej, 2005, Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute, hlm. 25. 6 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 adalah ”A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court”7. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain8. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem peradilan pidana dengan model due process mendominasi sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia karena dianggap lebih menjamin hak asasi manusia, lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan suatu kejahatan juga mulai menggunakan due process of law dalam sistem beracaranya. Mengingat proses pengembalian aset akan berhadapan dengan lebih dari satu sistem hukum, Indonesia sebaiknya menggunakan sistem peradilan dengan model yang diterima secara universal, yakni due process of law. Sementara dalam sistem peradilan perdata, pada hakekatnya memiliki karakteristik yang sama hampir di seluruh dunia, yaitu inisiatif beracara datang dari para pihak, hakim bersifat pasif dan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal yang terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Prasyarat pengembalian aset berikutnya adalah kerja sama kelembagaan, yakni kerja sama antarlembaga yudisial dan lembaga- 7 Michael Cavadino and James Dignan, 1997, The Penal Sistem An Introduction, SAGE Publication Ltd. hlm. 7. 8 University Of Leicester, 1998, Modul 5, “Issues In The Criminal Justice Process”, Scarman Center, University Of Leicester, hlm.24. 7 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 lembaga ekstrayudisial. Hal ini mengingat beberapa hal: Pertama, pengembalian aset tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan atau pidana, dapat saja aset yang akan dikembalikan berada dalam wilayah rezim hukum keperdataan. Kedua, tidak selamanya pula aset yang akan dikembalikan, disimpan dalam bentuk uang, deposito, giro, saham atau sejenisnya, namun juga aset yang dicuri dalam wujud benda, misalnya tanah. Ketiga, kendatipun aset yang akan dikembalikan tersebut dalam bentuk uang, deposito, giro atau sejenisnya, kerja sama antarlembaga tetap dibutuhkan dalam rangka mempermudah pengembalian aset. Jika aset yang akan dikembalikan berada dalam rezim hukum keperdataan, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan pihak ketiga terhadap aset tersebut. Demikian pula jika aset yang dicuri dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, maka dalam rangka pembekuan, penyitaan dan pengembalian aset, dibutuhkan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional. Sementara jika aset yang dicuri kemudian ‘dicuci’ seolah-olah merupakan aset yang diperoleh secara legal, maka kerja sama dengan lembaga lainnya seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mutlak dibutuhkan. Prasyarat terakhir pengembalian aset adalah kerja sama internasional yang meliputi kerja sama bilateral maupun kerja sama multilateral. Pengembalian aset yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia tentunya memerlukan kerja sama bilateral antarnegara. Pengembalian aset merupakan tujuan dan salah satu prinsip dalam Konvensi PBB mengenai antikorupsi dengan tujuan utama kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Pengembalian aset erat terkait dengan kejahatan korupsi, dan menurut konvensi tersebut, korupsi merupakan kejahatan internasional. Terlebih saat ini, Komisi Hukum PBB sedang membahas untuk memasukkan korupsi dan narkotika sebagai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jika hal tersebut disetujui, maka konsekuensi selanjutnya yang berlaku adalah asas universal yang berarti 8 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 bahwa setiap negara berhak melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Urgensi Undang-Undang Pengembalian Aset di Indonesia Paling tidak ada enam alasan yang mendasari perlunya undangundang pengembalian aset di Indonesia. Pertama, indeks prestasi korupsi di Indonesia cukup mencengangkan dalam beberapa tahun terakhir ini dan hanya bisa disamai oleh Mexico. Sudah barang tentu uang yang dikorupi sebagian besar tidak berputar di Indonesia tetapi dilarikan ke luar negeri. Kedua, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mana asset recovery merupakan salah satu prinsip dasar dari konvensi tersebut. Konsekuensi lebih lanjut, Indonesia harus segera menghasilkan sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksana – termasuk undangundang pengembalian aset – sesuai dengan konvensi tersebut. Ketiga, Indonesia telah mengatur tentang mutual legal assistance dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yang mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal. Jika Indonesia menginginkan asetnya yang telah dicuri dan dibawa ke luar negeri dikembalikan, maka Indonesia pun harus mempunyai pengaturan yang jelas mengenai pengembalian aset yang juga menjamin pengembalian aset dari negara lain yang disimpan di Indonesia. Keempat, Indonesia berperan aktif dalam Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang mana dibutuhkan kerja sama internasional, baik bilateral, maupun multilateral dalam rangka pengembalian aset tersebut. Keberadaan undang-undang pengembalian aset, berdasarkan sejumlah instrumen hukum internasional maupun hukum nasional yang ada, merupakan suatu keniscayaan yang harus segera dibentuk sebagai bagian dari paket undang-undang antikorupsi. 9 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Kelima, banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini menimbulkan kerugian yang besar bagi keuangan negara, termasuk kejahatan-kejahatan yang menghasilkan aset yang cukup besar. Kejahatan-kejahatan yang asetnya menjadi ruang lingkup pengembalian aset adalah korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, narkotika, psikotropika, hak kekayaan intelektual, kepabeanan dan cukai, kehutanan serta perikanan. Keenam, pengembalian aset merupakan salah satu “missing link” dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Rumusan dan implementasi yang efektif tentang pengembalian aset hasil korupsi memiliki makna ganda bagi pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia. Pertama, implementasi yang efektif dari ketentuan tentang pengembalian aset tersebut akan membantu negara dalam upaya menanggulangi dampak buruk dari kejahatan korupsi. Kedua, adanya legislasi yang memuat klausula tentang pengembalian aset hasil kejahatan korupsi merupakan pesan jelas bagi para pelaku korupsi bahwa tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi (no safe haven), baik harta kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri maupun harta kekayaan luar negeri yang ada di Indonesia. Rezim Hukum Pengembalian Aset Dalam kaitan dengan rezim hukum pengembalian aset, pertanyaannya adalah apakah hukum pengembalian aset termasuk ke dalam rezim hukum perdata ataukah pidana. Hukum privat atau perdata, adalah hukum yang mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula perhubungan hukum yang diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara, bilamana badan 10 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai atau seolah-olah individu”9. Sedangkan hukum publik, yang mana di dalamnya termasuk pula hukum pidana, mengatur hubungan antara individu dengan negara. Secara lebih spesifik, hukum pidana merupakan “hukum yang melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat atau perdata maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa”10. Dalam konteks yang demikian, rezim hukum pengembalian aset tentunya tidak dapat dikualifikasi sebagai hukum pidana. Akan tetapi, mengingat pengembalian aset berkaitan dengan aset-aset yang dihasilkan atau digunakan dalam suatu kejahatan tertentu, maka sangat erat kaitannya dengan hukum acara pidana, yang juga merupakan bagian dari rezim hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berdasarkan hal-hal di atas dan dengan memperhatikan hukum pengembalian aset sebagai suatu ketentuan hukum yang mengatur tata cara negara untuk mengembalikan dan mengelola aset yang digunakan atau dihasilkan dari suatu tindak pidana, maka ketentuan yang mengatur tata cara pengembalian aset haruslah merupakan ketentuan hukum yang masuk ke dalam rezim hukum publik yang memiliki karakteristik tersendiri dan dinamakan sebagai Hukum Acara Pengembalian Aset. Secara garis besar hukum acara pengembalian aset dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengembalian aset yang diduga terkait dengan kejahatan dan dalam waktu yang bersamaan pokok perkara pidananya sedang diproses. Kedua, pengembalian aset yang diduga terkait dengan 9 E.Utrecht, 1956, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, hlm. 94. 10 Ibid., hlm. 108. 11 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kejahatan, dengan tidak ada pokok perkara pidananya. Akan tetapi, pemeriksaan pengembalian aset yang diduga terkait dengan kejahatan, baik yang pertama maupun yang kedua, adalah hal yang terpisah pemeriksaannya dengan pokok perkara pidana yang sedang disidangkan. Dalam hal yang pertama, kewenangan untuk melacak, membekukan dan menyita ada pada penyidik, baik penyidik Polri, Kejaksaan, maupun penyidik pegawai negeri sipil lainnya yang diperintah oleh undangundang atas kejahatan yang merupakan cakupan dari rezim hukum pengembalian aset. Dalam melakukan pelacakan, penyidik dapat meminta bantuan lembaga pengelola aset. Sedangkan dalam hal pembekuan – selama aset tersebut berupa uang atau saham – dan penyitaan, dilakukan oleh penyidik setelah mendapat izin berupa penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya, terkait pengelolaan, penyerahan sampai pada pengawasan terhadap aset tersebut dilakukan oleh lembaga pengelolan aset. Pengelolaan aset dilakukan selama putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara penyerahan aset dilakukan jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada saat pengelolaan tersebut, dimungkinkan gugatan dari pihak ketiga atas aset tersebut, dan jika dikabulkan, maka setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, barulah diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak dan juga kepada negara. Dalam hal yang kedua, pengembalian aset dilakukan oleh jaksa pengacara negara dengan mengajukan “Permohonan Penyitaan, Perampasan dan Pengembalian Aset” kepada pengadilan negeri yang berwenang. Pada saat melakukan pemeriksaan atas permohonan jaksa pengacara negara, intervensi dari pihak ketiga juga dimungkinkan. 12 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Selain itu, ada pemikiran lain perihal proses acara pengembalian aset, yakni dengan afdoening buiten process11 atau penyelesaian di luar proses. Kendatipun tetap diakomodasi dalam hukum acara pidana, namun afdoening buiten process tidak serumit “Permohonan Penyitaan, Perampasan dan Pengembalian Aset”. Afdoening buiten process memiliki dua bentuk, yaitu submissie dan compositie. Pada submissie, jika terdakwa dan jaksa penuntut umum memaparkan persoalan kepada hakim karena sulitnya pembuktian, maka akan diambil keputusan tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan compositie dipergunakan oleh jaksa penuntut umum. Di sini terdakwa dapat mencegah atau menghentikan proses penuntutan dengan cara membayar sejumlah uang tertentu12. Dalam konteks pengembalian aset, kiranya afdoening buiten process yang lebih tepat adalah bentuk submissie. Jika pengembalian aset terkait dengan pokok perkara pidana yang sedang disidangkan, maka terdakwa yang hartanya akan disita bersama-sama dengan dengan penuntut umum mengajukan permohonan kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan agar harta tersebut disita dan diserahkan kepada lembaga pengelolaan aset tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut karena sulitnya pembuktian dari kedua belah pihak. Terhadap terdakwa yang hartanya telah disita dan dikembalikan maka dapat dijatuhkan pidana yang lebih ringan. Sementara jika pengembalian aset yang diduga terkait dengan kejahatan tanpa pokok perkara pidana yang sedang diperiksa, maka orang atau pihak yang hartanya akan disita bersama-sama dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan agar harta tersebut disita dan diserahkan kepada lembaga 11 Afdoening buiten process diatur dalam pasal 82 sampai pasal 84 WvS 1993 dan hanya dikhususkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang ancaman pidananya hanya denda. 12 Jan Remmelink, Op.Cit., hlm.442 – 443. 13 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 pengelolaan aset tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut karena sulitnya pembuktian dari kedua belah pihak. Dalam rangka mempermudah pembuktian pengembalian aset berdasarkan “positive wettelijk bewijs teorie”, beban pembuktian atau bewijslast yang harus diterapkan adalah omkering van bewijslast atau pembuktian terbalik. Dalam konteks pengembalian aset, jika negara yang diwakili oleh jaksa pengacara negara akan meminta pembekuan, penyitaan bahkan sampai pada pengembalian aset, orang atau pihak yang mendaku bahwa aset tersebut adalah miliknya, dialah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal. Artinya, aset tersebut diperoleh bukan dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Apabila orang atau pihak yang mendaku memiliki hak atas aset yang akan disita dapat membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah, maka jaksa pengacara negara dibebani kewajiban untuk membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, jika orang atau pihak yang mendaku memiliki hak atas aset yang akan disita tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah, maka pengadilan menjatuhkan putusan untuk menyatakan aset tersebut adalah milik negara dan memerintahkan pembekuan, penyitaan dan pengembalian aset tersebut. Daftar Pustaka Atmasasmita, Romli, 2003, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam Makalah Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Diselenggarakan oleh; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, di Bali tanggal; 14-15 Juni 2006. ________________, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung. Bassiouni, Cherif M., 2003, Introduction to International Criminal Law, Transnational Publishers, Inc., Ardsley, New York. Cavadino, Michael and Dignan James, 1997, The Penal Sistem An Introduction, SAGE Publication Ltd. 14 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Hiariej, Eddy O.S., 2005, Crimnal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sambutan Pembukaan Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional, BPHN Depkumham RI dan FH Universitas Udayana, Denpasar-Bali, 14 Juni 2006. Marzuki, Peter Mahmud, 2007, StAR Initiative Dalam Perspektif Hukum Perdata, Newsletter KHN, Vol. 8, No. 1, Januari – Februari 2008. Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Montesquieu, C.S.B.D., 2007, The Spirit Of Laws, diterjemahkan oleh M.khoril Anam, Nusamedia, Bandung. Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Stolpe, Oliver, 2008, Legal Framework on Asset Recovery – The UN Convention Against Corruption. The International Bank For Reconstruction and Development / The World Bank, 2007, Stolen Asset Recovery ( StAR) Initiatives: Challenges, Opportunities and Action Plan, Washington, 2007. United Nations Convention Against Corruption. University Of Leicester, 1998, Modul 5, “Issues In The Criminal Justice Process”, Scarman Center, University Of Leicester. Utrecht, E., 1956, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia. 15 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PIAGAM ASEAN: ARTI PENTING BAGI PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA Damos Dumoli Agusman Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang apakah Piagam ASEAN bertentangan dengan UUD 1945 telah memberikan gambaran lebih mengenai politik hukum Indonesia terhadap hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional. Dalam putusan MK, yang disertai dengan opini berbeda (dissenting opinion) dari beberapa hakim, dinyatakan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji Piagam ASEAN secara materiil. Pernyataan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam perspektif hukum formal, Piagam ASEAN dipandang telah menjadi bagian dari hukum nasional dengan ratifikasi melalui undang-undang. Alasan ini yang kemudian dikaji oleh penulis berdasarkan teori-teori di dalam hukum internasional dan praktik-praktik di negara lain. Kata kunci: Piagam ASEAN, Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, ratifikasi, hukum nasional, teori monisme, teori dualisme. Abstract The decision of Indonesian Judicial Court on the case that questioning whether the ASEAN Charter is inconsistent with the Indonesian Constitution has given more views on Indonesian legal politics regarding the relation between treaty and national law. In the Judicial Court’s decision, with dissenting opinion from some of the judges, it is stated that the Judicial Court has legal standing to materially examine the ASEAN Charter. Such statement resulted from the consideration that in formal legal perspective, the ASEAN Charter has become a part of national law through ratification by law. This reasoning that will be then analyzed by the writer of this article based on theories in international law and practices in other countries. Keywords: ASEAN Charter, Judicial Court, international treaty, ratification, national law, theory of dualism, theory of monism. 16 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Setelah ditunggu hampir 2 tahun pasca diajukannya gugatan oleh sejumlah LSM tanggal 5 Mei 2011, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 26 Februari 2013 menentukan sikap terhadap nasib Piagam ASEAN. Dalam amar putusannya, MK menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, Piagam ASEAN tidak bertentangan dengan UUD. Putusan ini mungkin melegakan Pemerintah karena menjadi terhindar dari kemungkinan pelanggaran kewajiban internasionalnya, namun bukan berita yang menggembirakan bagi para pakar hukum khususnya hukum internasional. Bagi kalangan ini, bukan hasil putusannya yang penting namun argumen yang menggiring ke arah putusan itu, karena argumen ini (sering disebut ratio decidendi) kelak akan menentukan nasib perjanjian-perjanjian internasional lainnya. MK mengatakan bahwa lembaga ini berwenang untuk menguji Piagam ASEAN karena dokumen ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian yang tak terpisahkan dari UU yang merupakan objek yang sah untuk diuji oleh MK. Karena secara formal Piagam ini adalah UU maka tidak ada alasan bagi MK untuk tidak dapat mengujinya. Setelah memutuskan bahwa MK berwenang, selanjutnya para Hakim masuk ke materi Piagam ASEAN dan menemukan bahwa Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah kebijakan makro dan belum berlaku efektif. Secara nasional berlakunya kebijakan makro tersebut tergantung kepada masing-masing negara anggota ASEAN untuk melaksanakan. Atas argumen ini maka gugatan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Argumen ini telah menguak politik hukum Indonesia tentang perjanjian internasional yang selama ini masih misteri dan dalam literatur masih diperdebatkan. Dengan tegas MK memberi pesan bahwa selama perjanjian internasional dibuat dalam bentuk UU maka semua perjanjian internasional dapat diuji oleh MK. Artinya, semua perjanjian 17 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD. Argumen ini sangat logis dan dapat dipahami. Namun yang lebih menarik adalah bahwa MK telah memilih aliran hukum yang menjadi kontroversi selama ini bahwa UU yang meratifikasi Piagam ASEAN tidak berbeda dengan UU lainnya dan tidak menemukan alasan yang meyakinkan mengapa UU ini harus dibedakan dengan UU lainnya, sekalipun tersedia doktrin yang menyatakan sebaliknya. Argumen apakah Piagam ASEAN ini merupakan UU sudah sering diperdebatkan dalam dunia akademis. Kontroversi ini tampaknya mengemuka dalam perdebatan para hakim konstitusi. Dua hakim Konstitusi melalui dissenting opinion keberatan dengan argumen yang mengidentikkan UU No. 38/2008 dengan UU pada umumnya. Menurut kedua hakim ini: ‘memang benar, formil UU 38/2008 adalah UndangUndang, tetapi materilnya bukanlah Undang-Undang dan tidak dapat dijadikan obyek pengujian undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah. Selanjutnya ditegaskan bahwa UU ini bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif, yang adressat normanya dapat secara langsung ditujukan kepada setiap orang, tetapi merupakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 UUD 1945, dan diberi ”baju” dengan UU. Kontroversi tentang status UU yang meratifikasi suatu perjanjian internasional juga melanda sistem hukum lainnya. Pengadilan Belanda pernah mengalami perdebatan ini. Beberapa ahli menilai UU (Wet) ratifikasi memiliki 2 fungsi yaitu, menyetujui Raja/Ratu melakukan ratifikasi terhadap perjanjian dan sekaligus menjadikan perjanjian itu menjadi hukum nasional yang setara dengan UU. Namun pengadilan Belanda pada 2 Januari 1899 menolak argumen ini dalam kasus ”Konvensi Manhnheim on Rhine Navigation (1868) dengan menyatakan bahwa kekuatan hukum Konvensi ini tidak bersumber dari Wet yang 18 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 mengesahkannya melainkan pada tindakan pertukaran instrumen ratifikasi antara kedua negara (Belanda dan Jerman). Jurisprudensi ini menyelesaikan perdebatan pada waktu itu dan kemudian menjadi politik hukum dalam revisi Konstitusi Belanda tahun 1953 yang secara tegas menempatkan perjanjian berada di atas hukum nasional Belanda dan bahkan di atas Konstitusi. Negara berkembang seperti Kolombia juga telah menuntaskan persoalan klasik ini pada awal abad 20. Duduk perkaranya sama dengan yang dialami oleh MK saat ini. UU No. 14 Tahun 1914 yang meratifikasi Treaty antara AS dan Kolombia tentang pengakuan kedaulatan Panama digugat ke Pengadilan Kolombia karena bertentangan dengan UUD. Pengadilan Kolombia tidak tertarik mengulas tentang apakah benar treaty ini bertentangan dengan UUD, melainkan hanya menjawab apakah Pengadilan memiliki kewenangan untuk menguji UU No. 14 Tahun 1914 dan treaty. Pengadilan ternyata berpendapat bahwa sekalipun UU ini adalah produk legislatif namun tetap harus dibedakan dengan UU pada umumnya. UU ini hanya merupakan wujud ekspresi unilateral dari Kolombia untuk mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian dan tidak menjadikan perjanjian itu berkekuatan mengikat karena masih tergantung pada tindakan yang sama dari negara pihak lainnya. MK dalam pengujian Piagam ASEAN ternyata mengambil sikap yang sangat berbeda dengan kedua negara di atas. Tampaknya terdapat kesulitan juridis bagi sebagian besar hakim konstitusi untuk keluar dari asas legalitas bahwa UU yang meratifikasi suatu perjanjian tidak lain dan tidak bukan adalah UU. Kesulitan ini dapat terbaca karena di bagian lain MK mengatakan bahwa pilihan bentuk hukum ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk formil Undang-Undang perlu ditinjau kembali. Namun sayangnya, kesimpulan ini dibangun dari premis yang agak lain dan terkesan bahwa mengambil bentuk UU adalah sistem yang keliru. Pilihan bentuk UU untuk persetujuan DPR bukan hal yang baru dalam praktek negara-negara. Belanda, Kolombia, Jerman dan banyak 19 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 negara lainnya memilih bentuk formil UU untuk persetujuan DPR. Dalam hal ini, bukan bentuk formil UU ini yang menjadi akar masalah namun bagaimana MK memberi makna terhadap UU ini yang menjadi faktor penentu. Dalam hal ini, Prof. Utrecht, seorang pakar hukum di awal kemerdekaan, mengartikan lain bahwa suatu perjanjian internasional yang disetujui DPR dan dituangkan dalam suatu undang-undang persetujuan (goedkeuringswet) adalah UU yang bersifat formil saja. Di lain pihak terdapat pula argumentasi MK yang kelihatannya logis dari sisi hukum tata negara namun menjadi tidak logis dalam hukum internasional. Bagi MK, pemuatan Piagam ASEAN di Jakarta ke dalam UU 38/2008 dinilai sebagai pemindahan format treaty ke dalam format UU yang memiiki konsekuensi bahwa negara pihak harus terikat pada UU ini. Padahal dalam konsepsi hukum publik dikenal suatu model masuknya perjanjian internasional ke dalam hukum nasional melalui proses transformasi. Teori transformasi menjelaskan bahwa Piagam ASEAN dalam formatnya sebagai treaty mengikat semua negara pihak dalam tataran hukum internasional, sedangkan UU 38/2008 jika hendak dianggap sebagai UU transformasi maka hanya diartikan sebagai Piagam ASEAN yang ditransformasikan ke dalam hukum nasional dan bertujuan hanya untuk mengikat subyek-subyek dalam hukum nasional. Menurut teori di atas, pemuatan Piagam ASEAN ke dalam format UU 38/2008 adalah murni urusan hukum nasional dan tidak ada sangkut pautnya dengan status Piagam sebagai treaty menurut hukum internasonal, yang tetap tentunya mengikat negara pihak lainnya sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, argumen MK yang menyatakan bahwa negara lain harus terikat pada UU 38 Tahun 2008 sangat tidak mendasar dan bukan sebagaimana yang dimaksud oleh teori transformasi. Namun terlepas dari itu, saran MK agar pilihan bentuk UU untuk Perjanjian Internasional ditinjau kembali sangat menarik. Dengan saran ini terdapat kecederungan bahwa seyogianya perjanjian internasional 20 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 tidak dapat diuji oleh MK. Dapat tidaknya perjanjian internasional diuji oleh pengadilan nasional hanya dapat dijawab setelah Indonesia menetapkan status perjanjian internasional dalam hukum nasional1. Sayangnya UUD 45 yang telah diubah di era reformasi ini tidak menyediakan politik hukum ini. MK telah mengisi sebagian kekosongan konstitutional ini. Menurut penulis, saran MK ini harus ditindaklanjuti dengan amandemen Pasal 11 UUD 45 karena materi putusan MK ini adalah materi Konstitusi. 1 Damos Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik, Bandung, 2010. 21 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 KONSEPSI KEDAULATAN NEGARA DALAM BORDERLESS SPACE Purna Cita Nugraha Abstrak Teknologi komunikasi dan informasi telah merubah tingkah laku masyarakat dan kebudayaan secara global. Lebih lanjut, pengembangan teknologi informasi telah mengarah kepada suatu dunia baru tanpa batas dan menyebabkan perubahan-perubahan social yang terjadi dengan pesat. Internet mengalihkan cara komunikasi yang bersifat konvensial kepada suatu fenomena sosial dalam Ruang publik untuk berkomunikasi, suatu dunia baru yang dinamakan dengan dunia maya dimana satu pihak capat berkomunikan dengan yang lain tanpa dibatasi oleh batas-batas atau bahkan lintas negara (transnasional). Proses yang mengarah pada kemudahan dan manfaat dalam internet tidak selalu menjadi permasalahan karena dalam dunia maya juga terdapat permasalahan hukum yang timbul dalam bentuk kejahatan telematika. Dalam hal ini, negara perlu bekerjasama bersama-sama dalam menetapkan rejim yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum telematika untuk menetapkan kepastian hukum dalam implementasi dari peraturan hukum untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam dunia maya. Kata kunci: Kedaulatan negara, ruang tanpa batas, dunia maya Abstract Information and communication technology (ICT) has changed the behavior of human society and civilization globally. In addition to that, the development of information technology has led to a new world without borders (borderless) and cause significant social changes occurred too rapidly. The internet shifts the conventional way of communication to a new social phenomenon in the public space to communicate, a new world called the cyberspace where one party can communicate with others without being limited by borders or even cross country (transnational). The process leading to simplicity and goodness in the internet was not always the case because in cyberspace there are also legal issues that arise in the form of cybercrime. In this 22 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 regard, the sovereign states needs to cooperate together in establishing extraterritorial jurisdiction regime in cyberlaw to create legal certainty in the implementation of the rule of law for all activities carried out in cyberspace. Key words : State Sovereignty, Borderless Space, cyber space Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.1 Pengembangan dan penerapan teknologi informasi telah mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi diserap, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi tanpa terkendala batas ruang dan waktu. Sebagaimana dinyatakan oleh Melville J. Herskovits bahwa teknologi merupakan salah satu unsur utama dari kebudayaan manusia.2 Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.3 Pada prinsipnya, teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat 1 Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 1 2 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiolofi, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, hlm. 115 3 Francis Lim, Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 44 23 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja. Teknologi memiliki ruang lingkup yang luas, karena mencakup : 1) tools and techniques; 2) organized systems such as factories; 3) applied science; 4) those methods that achieve, or are intended to achieve, a particular goal such as efficiency, the satifaction of human needs and wants, or control over the environment; and 5) the study of or knowledge about such things.4 Istilah teknologi juga dapat diartikan sebagai berikut: “Technology thus sometimes includes what might also be called technique; making organization, bereaucracy, and even law itself into technologies. Such extended meanings of the term technology are not, however, what law journals focused on technology usually mean by the term.”5 Dalam hal tersebut di atas dijelaskan bahwa teknologi kadang-kadang mencakup apa yang juga bisa disebut teknik, pembuatan organisasi, birokrasi, dan bahkan hukum itu sendiri menjadi teknologi. Makna yang diperluas dari istilah teknologi tersebut tidak, bagaimanapun, seperti yang jurnal hukum biasanya maksud dalam penggunaan istilah. Di lain pihak, hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Keadilan dan ketertiban tersebut dicapai dengan menjaga kepentingan tertentu, baik individu maupun kolektif. Di dalam masyarakat terjadi dinamika dan di dalam masyarakat 4 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 32 5 Ibid. 24 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 pula muncul kejahatan. Teknologi dan masyarakat bersifat dinamis karena terus berkembang, sedangkan hukum bersifat statis. Teknologi menuntut respon hukum dan hukum berada di persimpangan, di satu sisi berusaha mengakomodir perkembangan teknologi demi kepentingan masyarakat, di sisi lain hukum memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga teknologi yang ada sekarang, sehingga tetap menjaga berbagai kepentingan atau kebutuhan masyarakat luas yang telah terpenuhi dengan teknologi yang telah ada itu.6 Pada permulaan abad ke-20, salah satu penemuan revolusioner di bidang teknologi informasi yang sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian adalah ditemukannya internet (interconnection networking), sebagai media komunikasi yang cepat dan handal. Fasilitas internet adalah suatu jaringan computer yang sangat besar, terdiri atas jaringanjaringan kecil yang menjangkau seluruh dunia.7 Adanya internet melahirkan suatu fenomena ruang sosial baru dalam masyarakat untuk berkomunikasi, suatu dunia baru yang dinamakan dengan cyberspace (ruang siber) dimana pihak yang satu dapat berkomunikasi dengan pihak lainnya tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless) atau bahkan lintas negara (transnasional). Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil, lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat menuju suatu sistem global.8 6 Ibid. Miranda dan Imelda, Mengenal E-Commerce, M-Commerce, dan M-Business, Harvindo, Jakarta, 2004, hlm. 1 8 Didik J. Rachbini, “Mitos dan Implikasi Globalisasi” : Catatan untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Jakarta, Yayasan Obor, 2001, hlm. 2 7 25 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Seperti yang ditulis dalam International Review of Law Computer and Technology: Global information and communication networks are now an integral part of the way in which modern governments, business, education and economies operate. However, the increasing dependence upon the new information and communication technologies by many organizations is not without its price, they have become more exposed and vunerable to an expanding array of computer security risks or harm and inevitably to various kinds of computer misuse.9 Dalam hal ini, informasi global dan jaringan komunikasi yang sekarang merupakan bagian integral dari cara pemerintah modern, bisnis, pendidikan dan ekonomi beroperasi. Namun, meningkatnya ketergantungan pada informasi baru dan teknologi komunikasi oleh banyak organisasi bukan tanpa konsekuensi, salah satunya adalah menjadi lebih terekspos dan rentan dalam memperluas risiko keamanan komputer termasuk terhadap berbagai macam penyalahgunaan komputer. Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. 9 International Review of Law Computers and Technology, Insider Cyber-Threat: Problems and Perspectives, Volume 14, 2001, hlm. 105-113. 26 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).10 Netizens11 atau para pengguna internet merupakan para penghuni dari konsep cybernetics yang telah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan istilah cyberspace, global village, atau internet. Sama seperti dalam dunia konvensional, maka dalam cyberspace “hidup” masyarakat (cybersociety) yang terdiri dari milyaran pengguna internet dari segala penjuru dunia yang berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain melalui jaringan komputer. Sama seperti dalam dunia fisik kita sekarang, dalam cyberspace masyarakat memerlukan pengaturan baik inter-masyarakat maupun antar masyarakat, mulai dari norma sampai kepada hukum (cyberlaw).12 Indeks penggunaan internet di dunia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari angka peningkatan yang mencapai 566.4% dalam kurun waktu 12 tahun (2000—2012). Pengguna internet (netizens) di benua Asia merupakan 44.8% dari pengguna internet di seluruh dunia, atau sejumlah 1,076,681,059 jiwa. China menduduki peringkat pengguna terbesar dalam peringkat pengguna internet di Asia yaitu sejumlah 538 juta jiwa pengguna internet, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah 55 juta jiwa pengguna internet.13 Sejalan dengan pemikiran bahwa cyberspace memerlukan pengaturan baik inter-masyarakat maupun antar masyarakat, mulai dari norma 10 Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20 11 Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/netizen.html, netizen is citizen of cyberspace a dedicated internet user, diakses pada tanggal 31 Desember 2012 pukul 16.58 WIB 12 Josua Sitompul, op.cit, hlm. 31 13 Internet World Stats, World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, http://www.internetworldstats.com/stats, diakses pada tanggal 31 Desember 2012 pukul 15.24 WIB 27 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 sampai kepada hukum (cyberlaw) dan apabila dikaitkan dengan kewenangan suatu negara dalam melakukan pengaturan, hal tersebut tentu saja berhubungan langsung dengan yurisdiksi negara tersebut, misalnya saja mengenai kewenangan suatu negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya atau dalam hal ini ruang siber. Internet adalah dunia yang ubiquotus (terhubung dan terbuka pada saat yang bersamaan di mana-mana), maka teori yurisdiksi yang menekankan pada locus dan tempus delicti sudah tidak memadai lagi untuk digunakan.14 Kondisi di atas menimbulkan suatu pertanyaan mendasar tentang bagaimana sistem hukum mengatur ruang siber yang notabene borderless tersebut. Lebih jauh lagi, harus juga dipikirkan bagaimana hubungan kewenangan negara dikaitkan dengan pengaturan terhadap setiap perbuatan/interaksi para pengguna internet yang tidak dibatasi oleh batas wilayah (borderless) tersebut. Hal ini tentu menimbulkan suatu kebutuhan dari hukum untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman dalam menjawab adanya pertanyaan-pertanyaan seputar kewenangan dan yurisdiksi negara atas internet dan ruang siber tersebut. Adanya urgensi hukum dalam meregulasi ruang siber telah membentuk suatu rezim hukum baru di Indonesia. Dalam hal ini, perlu pula terlebih dahulu dipahami peristilahan dan ruang lingkup cyberlaw yang telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Peristilahan yang digunakan untuk hukum yang mengatur kegiatan di dalam cyberspace adalah the law of the 14 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 304 28 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 internet; the law of information technology; the telecommunication law; dan lex informatica.15 Pada sudut pandangan secara praktis, dapat dipahami misalnya dalam kegiatan e-commerce memerlukan “sense of urgency” untuk dicarikan jalan keluar atas akibat-akibat atau permasalahan hukum yang muncul. Di sisi lain, dengan memperhatikan pula praktik di negara lain, nampaknya akan lebih bijaksana apabila tidak dibatasinya secara sempit ruang lingkup dari cyberlaw itu sendiri.16 Cyberlaw sebagai suatu rezim hukum yang baru akan lebih memudahkan untuk dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya. Cyberlaw dengan bentuk pengaturan yang bersifat khusus (sui generis) atas kegiatan-kegiatan di dalam cyberspace (ruang siber), antara lain mencakup hak cipta, merek (trademark), fitnah atau pencemaran nama baik (defamation), privacy, duty of care, criminal liability, procedural issues, electronic contracts, digital signature, electronic commerce, electronic government, pornografi, dan pencurian (theft).17 Ruang siber dengan realitas virtual, di satu sisi memang menawarkan manusia untuk hidup dalam dunia alternatif, dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang bahkan dapat lebih nyata dari realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Ruang siber telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan, dan penjelajahan seperti teleshoping, 15 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi), Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 129 16 Ibid. 17 Ibid. 29 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 teleconference, teledildonic, virtual café, virtual architecture, virtual museum, cybersex, cyberparty, dan cyberorgasm.18 Cyberspace atau internet juga terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), hal ini dikarenakan nature dan struktur dari internet yang membuat media ini secara luar biasa dapat memasukkan kreatifitas ke dalam komunitas global. Kreativitas yang timbul dari media ini dan kemampuan untuk menggunakan internet sebagai cara untuk mentransfer hasil karya kreatif memunculkan suatu kebutuhan akan pengaturan dan peraturan dari semua pemerintah, yaitu melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta memandang internet sebagai media yang bersifat low-cost distribution channel atau saluran distribusi yang murah bagi penyebaran informasi dan produk-produk entertainment seperti film, musik, dan buku. Hal ini disebabkan internet memungkinkan data-data tersebut untuk diunduh secara mudah oleh konsumen.19 Christoper Millard mencatat tiga pertanyaan yang paling mendasar mengenai pelanggaran hak cipta di internet, yaitu: 1) siapa yang mungkin dapat bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta di internet; 2) hukum dan yurisdiksi apa yang paling tepat/pantas diberlakukan; 3) perbuatan pelanggaran hukum seperti apa yang dapat termasuk ke dalam hukum yang berlaku saat ini. Menurutnya, para pelaku 18 Agus Raharjo, Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 6-7 19 Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 3-4 lihat juga Atip Latifulhayat, Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Cyberlaw, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000, hlm. 10 30 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 pelanggaran dapat masuk ke dalam tiga kategori, yaitu pengirim, penerima, dan operator jaringan yang ada di internet.20 Hak Kekayaan Intelektual telah dapat dijamin secara ekstensif di dalam literatur atau karya kesusastraan. Namun, sebahagian orang menganggap bahwa internet sebagai pertanda matinya hak cipta (copyright). Dalam hal ini, Ginsburg mencatat beberapa permasalahan dalam menegakkan Hak Kekayaan Intelektual di dalam internet, sebagai berikut: Should one look to the country where copies were (first) recieved? To the country from which the author uploaded the work? To the country in which is localized the website from which the work first becomes available to the public? What are the consequences of these different characterizations of publication and country of origin?21 Internet juga dapat digunakan untuk melanggar atau bahkan merampok para pemilik hak cipta dari keuntungan hak cipta, internat juga telah digunakan dalam mencegah pengakuan atau pemberian suatu paten. Sebagai contoh Human Genome Project mempublikasikan atau mengunggah peta dari human genome dengan niat untuk membuat informasi dan data tersebut sebagai informasi publik/pengetahuan umum dan mencegah Celera Genomics, sebuah perusahaan swasta, untuk mendapatkan hak paten. Dari contoh ini, dapat diketahui bahwa penentuan yurisdiksi di internet khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual di internet sebagai sesuatu yang amat penting.22 20 Christopher Millard, et. al., Computer Law, Bantam, London, 2000, hlm. 201 Samuel F. Miller, Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty, Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 10: Iss 2, 2003, hlm. 249 22 Ibid, hlm. 259-260 21 31 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Di sisi lain, proses siberisasi yang menimbulkan kemudahan dan kebaikan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam cyberspace juga terdapat persoalan hukum yang muncul berupa sisi gelap yang perlu kita perhatikan yaitu cybercrime dengan berbagai macam bentuknya. Sebagai contoh, carding, merupakan kasus yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkenal dalam cybercrime. Selain itu adalah hacking, sebagai bentuk baru dalam mengekspresikan kekecewaan, kekesalan dalam dunia bisnis dan politik, seperti kasus hacking terhadap situs-situs (websites) milik Malaysia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan negara itu dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI).23 Kejahatan yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-assisted crime, computer-related crime, atau computer crime.24 Barda Nawawi Arief mengatakan dalam bukunya bahwa pengertian computer-related crime sama dengan pengertian cybercrime.25 TB Ronny R. Nitibaskara berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut cybercrime. Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (computerrelated crime), yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.26 23 Ibid. hlm. 7 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 23 25 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 259 26 Widodo, loc.cit. 24 32 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Dalam background paper workshop on crimes related to the computer network, pada Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, di Wina tanggal 10-17 April 2000, disebutkan sebagai berikut: “Cyber crime in a narrow sense (“computer crime”): any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them; and Cyber crime in a broader sense (“computer-related crime”): any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.”27 Di sisi lain, dapat diperoleh informasi bahwa serangan siber di seluruh dunia mencapai 5,5 Milyar serangan dalam setahun. Sedangkan serangan siber (cyber attack) terhadap situs-situs Indonesia mencapai 40 ribu serangan per hari. Jenis serangan tersebut bermacam-macam seperti malware (piranti lunak berbahaya) dan spyware (piranti lunak mata-mata). Dalam hal ini, motif penyerangan ke situs-situs Indonesia bukan tergolong motif serius, seperti motif bersifat keamanan atau ekonomis.28 Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyebut jumlah serangan siber ke situs-situs berdomain go.id (situs milik lembaga/instansi pemerintah) lebih dari 3 juta kali pada tahun 2011.29 27 Background paper workshop on crimes related to the computer network, pada Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, di Wina tanggal 10-17 April 2000 28 Rudi Lumanto, Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, Serangan Siber ke Situs Indonesia 40 Ribu Kali/Hari, http://www.antaranews.com/berita/321960/serangan-siber-ke-situs-indonesia-40-ribukalihari, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB 29 Ibid. 33 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Pada tahun 2012 yang lalu, New York Times, sebuah media massa terkemuka AS melaporkan serangan siber yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran, bahkan Presiden Barack Obama secara langsung dan diamdiam memerintahkan serangan cyber menggunakan virus komputer Stuxnet terhadap Iran untuk melumpuhkan program nuklir Iran.30 Bukti lain adalah serangan Malware Stuxnet pada instalasi pengayaan nuklir di Natanz, Iran tahun 2009. Stuxnet mampu menyusup masuk dan menyabotase sistem dengan cara memperlambat atau mempercepat motor penggerak, bahkan membuatnya berputar jauh di atas kecepatan maksimum yang bisa menghancurkan sentrifuse sehingga tidak dapat memproduksi bahan bakar Uranium. Malware Stuxnet diakui sebagai serangan paling cerdas, paling canggih, dan paling hebat yang pernah dibuat yang pernah dibuat manusia.31 Menteri Telekomunikasi Republik Islam Iran, Reza Taghipour menyatakan akan melayangkan gugatan atau membawa masalah ini ke tingkat internasional atas serangan siber ke lembaga pemerintah Iran yang dianggapnya sebagai “state cyberterrorism against the country” tersebut kepada organisasi internasional terkait. Pengaduan Iran atas serangan siber tersebut akan dilayangkan kepada organisasi internasional terkait melalui Kementerian Luar Negeri Iran dan di berbagai pertemuan khusus seperti dalam sidang the International Telecommunication Union di Jenewa, dimana wakil Iran akan menyatakan protes resmi Tehran terkait masalah ini.32 30 http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/06/01/president-obama-ordered-cyber-attacks iran_n_1561730.html, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB 31 http://abcnews.go.com/Politics/OTUS/report-obama-ordered-wave-cyberattacks iran/story?id=16474164#.UOfR9OQ3vx8, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB 32 http://www.presstv.ir/detail/2012/06/20/247120/iran-protests-state-cyberterrorism/, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB 34 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Hal ini dilakukan Iran karena beberapa instansi pemerintah Iran mendapat serangan siber yang dilakukan sejumlah negara asing dan serangan ini sebagai ancaman keamanan siber dan terorisme siber terhadap negara. Dugaan sementara bahwa serangan ini dilakukan oleh AS, sesuai dengan fakta dan pernyataan Presiden Obama yang berhasil di blow-up oleh media bahwa Presiden Obama secara diam-diam memerintahkan serangan siber dengan komputer virus Stuxnet terhadap Iran untuk menyabotase program nuklir negara tersebut. Aksi serangan ini diduga dilakukan AS bekerjasama dengan unit intelejen rahasia Israel sebagai bagian dari gelombang serangan digital AS terhadap Iran. Dari paparan-paparan di atas, dapat diketahui bahwa persitiwa tersebut menandai era baru penggunaan dunia siber sebagai media untuk melakukan serangan siber dengan menggunakan cyber weapons terhadap bukan hanya infrastruktur dunia maya, tetapi juga instalasi dan insfrastruktur di dunia nyata. Belum terdapatnya organisasi internasional atau forum internasional yang diberi mandat untuk membahas masalah ini secara serius di tingkat internasional dikhawatirkan dapat membuat adanya ketidakpastian existing law (ius constitutum) maupun arah politik hukum ke depan (ius constituendum) dalam pembentukan hukum siber dan penegakan hukumnya di dunia siber. Hal tersebut terlihat dari Iran yang hanya dapat melakukan langkah politis dengan membawa masalah tersebut ke forum/tingkat internasional yang sifatnya konsultatif daripada menempuh jalur hukum dikarenakan kurang dan belum jelasnya infrastruktur hukum nasional dan internasional yang mengatur masalah tersebut. Dunia siber kini dapat dikatakan menjadi matra perang ke-5 selain darat, laut, udara, dan angkasa luar. Iran dengan segala bentuk 35 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 keterbatasannya telah mampu menginovasi kemajuan teknologi komunikasi dan informasi taktik dalam konflik modern dengan AS dan Israel. Bagi Iran, dengan adanya serangan siber yang dilakukan AS, maka dunia maya pun menjadi medan perang terbaru. Banyak perangkat mutakhir mulai dibuat para insinyur Iran untuk keperluan ini. Pertempuran elektronik telah tercipta dan membuat banyak negara melihat perang dunia siber sebagai ancaman terbesar di masa depan. Dalam tatanan pranata hukum nasional, pengaturan ruang siber dalam hal ini pelanggaran hukum (computer-related crime atau cybercrime) misalnya, seringkali sulit dijerat oleh hukum dan pengadilan di Indonesia karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi di dalam ruang siber tersebut, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia.33 Untuk mengakomodir adanya kebutuhan akan infrastruktur hukum dan pengaturan nasional dalam meregulasi kegiatan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin, Pemerintah Indonesia mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur kegiatan informasi dan transaksi elektronik termasuk aktivitas pada ruang siber. Setelah melalui pembahasan yang panjang akhirnya RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disetujui menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ditempatkan pada Lembaran Negara Nomor 58 pada tanggal 21 April 2008. 33 Ahmad M. Ramli, op.cit, hlm. 19 36 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 UU ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber (cybercrime). Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime, EU Directives on Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic Signature. Ketentuanketentuan tersebut adalah intrumen internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.34 Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan menyatukan materimateri tersebut dalam satu undang-undang. Pertama, penyatuan ini menghemat waktu karena jika tiap materi diatur dalam undang-undang sendiri, akan membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas di DPR. Kedua, para pemangku kepentingan dapat melihat keseluruhan secara holistik dan keterkaitan materi-materi tersebut secara komprehensif.35 Substansi pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE mencakup hukum pidana materil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber; pedoman yang digunakan adalah Convention on Cybercrime. UU ITE juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana siber.36 UU ITE merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan cyberspace di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai aspek yurisdiksi yang menggunakan prinsip perluasan yurisdiksi (extraterritorial jurisdiction) dikarenakan aktivitas pada ruang siber 34 Josua Sitompul, op.cit., hlm. 135-136 Ibid, hlm. 136 36 Ibid. 35 37 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan konvensional.37 Dunia siber, meskipun telah dapat diatur, tetapi masih sulit untuk dijinakkan. Cyberspace merupakan dunia virtual yang lokasinya tidak akan pernah kita temukan dalam Atlas, tetapi dapat dikunjungi oleh milyaran pengguna yang tersebar di seluruh dunia setiap saat. Karakteristik ubiquitous dan borderless ini mempengaruhi tindak pidana yang terjadi di dalamnya bahwa pada kenyataannya tindak pidana siber sering bersifat lintas negara sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi yang berlaku atas perbuatan atau akibat tindak pidana serta atas pelakunya. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menyadari keterbatasan perundang-undangan konvensionalnya untuk menjawab permasalahan ini sehingga memandang perlu untuk menyesuaikan hukumnya untuk tetap menjaga kedaulatan negara serta kepentingan negaranya dan warganya.38 Keberlakuan undang-undang pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP didasarkan pada asas-asas yang berlaku secara internasional, antara lain asas teritorialitas, asas nasionalitas, dan asas nasionalitas pasif. Pada prinsip awalnya, undang-undang pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang-pribadi kodrati, baik warga negara itu maupun warga negara asing yang berada di dalam wilayah wilayah negara tersebut, baik wilayah darat maupun laut. Setiap negara memiliki kedaulatan dan otoritas tertinggi untuk menegakkan hukum dalam wilayah negaranya. Asas ini dikenal dengan asas teritorialitas. Kemudian, sesuai dengan kebutuhan, ruang lingkup teritorial ini diperluas dengan menyamakan kendaraan air dan pesawat udara yang menggunakan bendera suatu negara sebagai bagian dari wilayah negara itu. Dalam KUHP, asas 37 38 Danrivanto Budhijanto, op.cit., hlm. 133 Josua Sitompul, op.cit., hlm.137 38 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 teritorial yang dimaksud diatur dalam Pasal 2 KUHP, sedangkan perluasan dari asas ini diatur dalam pasal 3 KUHP.39 Dalam perkembangan penerapannya, asas teritorialitas ini memiliki keterbatasan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan asas lain agar perundang-undangan pidananya tetap berlaku dalam kondisi-kondisi yang tidak dapat dijangkau dengan asas teritorialitas, khusunya dalam kondisi dimana pelaku tidak hadir dalam wilayah negara yang bersangkutan. Asas ini lebih dikenal dengan asas ekstrateritorial.40 Asas ekstrateritorial ini diwujudkan dalam pasal 4 KUHP dan pasal 5 KUHP. Pasal 4 KUHP memuat asas nasionalitas pasif. Maksudnya undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang – baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing – yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Sedangkan, pasal 5 KUHP mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu perundang-undangan pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia di manapun ia berada.41 Dalam konteks kaitannya dengan regionalisme, kebutuhan adanya kriminalisasi yang mengatur tindak pidana siber secara tegas melahirkan gagasan untuk membentuk suatu konvensi regional yang diprakarsai oleh Council of Europe atau Dewan Eropa. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Convention on Cybercrime 2001, yang dalam pembukaan dinyatakan sebagai berikut: “Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against cybercrime, 39 Ibid. Ibid. 41 Ibid. 40 39 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 inter alia, by adopting appropriate legislation and fostering international co-operation.” 42 Dalam hal ini disebutkan keyakinan akan adanya kebutuhan untuk mencapai, sebagai suatu prioritas, kebijakan kriminal bersama yang ditujukan pada perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana siber, antara lain dengan memberlakukan perundang-undangan yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional.43 Untuk mengaksesi Konvensi Dewan Eropa 2001 tersebut, suatu negara terlebih dahulu harus melakukan harmonisasi pengaturan tindak pidana siber dalam hukum nasionalnya dengan konvensi tersebut. Konvensi Dewan Eropa 2001 menjadi rujukan dalam pengaturan tindak pidana siber mengingat konvensi tersebut merupakan satu-satunya konvensi yang mengatur tindak pidana siber dan bersifat terbuka sehingga negara-negara lain yang bukan anggota Dewan Eropa dan tidak menjadi peserta konvensi dapat mengikatkan diri pada konvensi tersebut.44 Namun, walaupun konvensi tersebut bersifat terbuka, konvensi yang dihasilkan dari bentuk paham regionalisme atau kawasan tertentu cenderung akan mendapatkan resistensi khususnya dari negaranegara dari kawasan yang berbeda. Sehingga suatu keniscayaan bahwa konvensi yang dapat diterima oleh semua kalangan adalah konvensi/traktat/perjanjian internasional yang dihasilkan oleh forum multilateral atau dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. 42 Sigid Suseno, Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber dalam Perundang-Undangan Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa 2001, dalam Buku Yudha Bhakti, et. al, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 518 43 Ibid. 44 Ibid, hlm. 520 40 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Dalam konteks pengaturan yurisdiksi dalam ruang siber, setiap negara mau tidak mau harus dilibatkan karena karakteristik dari ruang siber yang berdimensi transnasional dan borderless. Disamping itu juga semua negara termasuk Indonesia harus dilibatkan dalam membentuk hukum siber dalam rangka terwujudnya kerjasama internasional yang efektif dan efisien dalam mengatur ruang siber khususnya tindak pidana siber. Di sisi lain, dalam tatanan hukum internasional, belum adanya posisi atau international regime yang jelas dalam mengatur tentang kedaulatan, kewenangan, dan yurisdiksi negara atas ruang siber dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan prinsip extraterritorial jurisdiction terhadap pelanggaran di ruang siber. Lebih lanjut, praktik negara-negara selama ini yang secara sepihak dalam memberlakukan hukum nasionalnya (unilateral act) dikhawatirkan akan melahirkan kesewenang-wenangan, khususnya pada penegakan hukum yang dilakukan dengan dasar kekuatan dan kekuasaan politik bukan dengan legitimasi hukum. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu kiranya menentukan kebijakan yang jauh kedepan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan hukum tersebut lewat politik hukum (legal policy) yang tepat dan sesuai dalam membentuk infrastruktur hukumnya khususnya di bidang cyberlaw. Berdasarkan paparan-paparan tersebut di atas, dapat dilihat belum adanya adanya politik hukum yang sinergis baik dalam pengaturan hukum nasional maupun hukum internasional tentang politik hukum dan kedaulatan negara dalam membentuk rezim extraterritorial jurisdiction dalam cyberlaw untuk menciptakan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di ruang siber. Terkait dengan hal masalah kedaulatan negara, Milton J. Esman mengatakan ada 2 (dua) dimensi pelaksanaan kedaulatan setiap negara, yaitu 1) dimensi pelaksanaan kedaulatan ke dalam (internal sovereignty), 41 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 which covers the behavior of persons and control of resources within the territorial boundaries of the state; dan 2) dimensi pelaksanaan kedaulatan ke luar (external sovereignty), which precludes any interfence by outsiders in domestic affairs unless these are conceded voluntarily by its government.45 Negara berdaulat ke dalam berarti berdaulat dalam mengurus urusan internal organisasi negaranya, yang mencakup wewenang dan kedaulatan kesatuan kekuasaan negara. Kedaulatan wewenang yang dimaksud adalah kesanggupan dan hak negara untuk melakukan segala sesuatu di dalam negara yang bersangkutan. Dalam hal ini negara tidak hanya mempunyai banyak wewenang, tetapi juga negara berwenang untuk menambah atau mengurangi wewenang itu. Artinya, bahwa di dalam wilayah suatu negara tidak ada lembaga lain yang juga memiliki kedaulatan wewenang selain pemerintahan negara itu sendiri. Di dalam satu wilayah negara hanya terdapat satu pusat kekuasaan, sementara semua wewenang lain tunduk terhadap pusat kekuasaan tersebut.46 Di sisi lain, kedaulatan negara ke luar dapat diartikan bahwa tidak ada pihak lain dari luar negara yang berhak untuk mengatur sesuatu dalam wilayah negara yang bersangkutan. Kedaulatan ke luar diwujudkan dalam dua prinsip utama, yaitu 1) prinsip kekebalan; 2) prinsip kesamaan kesanggupan semua negara untuk menciptakan hukumnya sendiri dan untuk bertindak menurut hukumnya itu. Sementara prinsip kekebalan maksudnya bahwa setiap negara tidak boleh dimasuki dalam bentuk apapun oleh negara lain. Artinya negara dilarang mengambil tindakan hukum atau kekuasaan dalam wilayah 45 J. D. Montgomery, Sovereign in Transtition, How Governments Respond Sovereignty under Challange, Transaction Publishers, USA and UK, 2002, hlm. 3 46 Max Boli Sabon, Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materil, Disertasi pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung 2006, hlm. 197 42 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kekuasaan negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Semua negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk menetapkan undang-undang dalam wilayahnya dan bertindak atas nama negaranya sendiri ketika berhadapan dengan negara-negara lain.47 Dari paparan-paparan tersebut di atas, dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa apabila diteliti secara seksama pemaknaan pelaksanaan kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar, konteksnya adalah ketika negara berhadap-hadapan dengan negara, dalam konteks terdesak, terganggu, atau terancamnya kedaulatan negara yang bersangkutan. Makna kedaulatan sebagaimana dipaparkan di atas sudah tidak relevan lagi diterapkan secara mutlak. Artinya pengertian kedaulatan sebagai sesuatu yang tidak dapar dibagi-bagi hanya tepat ketika hubungan internasional antar negara belum sehebat, seintensif, dan serumit saat ini, yang ditandai dengan dunia yang semakin tanpa batas (borderless state). Pemahaman kedaulatan di era globalisasi harus diubah sesuai dengan tuntutan zamannya, tanpa harus meruntuhkan nilai-nilai kedaulatan itu sendiri. Pandangan tersebut di atas sejalan dengan yang dikatakan John D. Montgomery sebagai berikut: “Four centuries ago, sovereignty had the ambitious goal of providing absolute security for the state as part of accepted internasional system. It erected the strongest possible legal barricade against foreign invasion or lesser interference with the will of the sovereign. A respected twentieth-century political philosopher described its original function in these vigorous terms: non est potestas super terram quae comparetur ei [there is no power on earth to compare to it] (Maclver, 1926: 15). Today its objectives are subtler but more attainable: it accepts and 47 Ibid. 43 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 adapts to foreign and domestic influences even when they challange the very nature of the state (Esman, chapter 14 this volume). Its claims rest on ethical as well as legal grounds. Contemporary theorists of international jurisprudence argue that the highest moral justification for sovereignty today is its potential to protect human dignity and human right, not just the state itself (McCorquodale, 1996). These aspirations expand and trancend the philosophical roots of traditional conservative, state-bounded sovereignty (huntington, 1999/2000).”48 Adanya internet melahirkan suatu fenomena ruang sosial baru dalam masyarakat untuk berkomunikasi, suatu dunia baru yang dinamakan dengan cyberspace (ruang siber) dimana pihak yang satu dapat berkomunikasi dengan pihak lainnya tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless) atau bahkan lintas negara (transnasional). Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mempunyai pengaturan yang jelas dan tegas terutama dalam penentuan kedaulatan negara atas ruang siber karena sifat ruang siber yang borderless. Ruang siber tidak dapat ditaklukkan sendiri oleh satu negara, dengan sifatnya yang borderless, maka kerja sama di antara negara-negara adalah suatu keniscayaan dan keharusan. Daftar Pustaka Buku Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam system hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006 Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Christopher Millard, et. al., Computer Law, Bantam, London, 2000 48 John D. Montgemery, op.cit. 44 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2010 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Francis Lim, Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2012 J. D. Montgomery, Sovereign in Transtition, How Governments Respond Sovereignty under Challange, Transaction Publishers, USA and UK, 2002 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012 Miranda dan Imelda, Mengenal E-Commerce, M-Commerce, dan M-Business, Harvindo, Jakarta, 2004 Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiolofi, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2001 Yudha Bhakti, et. al, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012 Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009 Disertasi Agus Raharjo, Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 Max Boli Sabon, Kongruensi Hak atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materil, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung 2006 Jurnal Atip Latifulhayat, Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Cyberlaw, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000 Background paper workshop on crimes related to the computer network, pada Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, di Wina tanggal 10-17 April 2000 International Review of Law Computers and Technology, Insider Cyber-Threat: Problems and Perspectives, Volume 14, 2001 Samuel F. Miller, Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty, Indiana Journal of Global Legal Studies: Vol. 10: Iss 2, 2003 45 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Websites www.internetneutral.com/terms.htm, diakses tanggal 11 November 2011 http://www.presstv.ir/detail/2012/06/20/247120/iran-protests-state-cyberterrorism/, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB http://abcnews.go.com/Politics/OTUS/report-obama-ordered-wave-cyberattacks iran/story?id=16474164#.UOfR9OQ3vx8, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/06/01/president-obama-ordered-cyber-attacks iran_n_1561730.html, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB http://www.antaranews.com/berita/321960/serangan-siber-ke-situs-indonesia-40-ribukalihari, diakses pada tanggal 05 Januari 2013 pukul 13.42 WIB Internet World Stats, World Internet Usage Statistics News and World Population Stats, http://www.internetworldstats.com/stats, diakses pada tanggal 31 Desember 2012 pukul 15.24 WIB Kamus Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, M.A., Fifth Edition, St.Paul Minn, West Publishing Co, 1979 46 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 KEBERADAAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL1 Harry Purwanto Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menelusuri dinamika dari prinsip rebus sic stantibus dalam hukum perjanjian. Artikel ini akan membahas bagaimana para ahli berpandangan terhadap prinsip ini, bagaimana kaitan hukum internasional dengan prinsip tersebut dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat internasional. Pada akhirnya, prinsip rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk memutuskan, membatalkan atau menangguhkan implementasi suatu perjanjian internasional. Kata Kunci: Perjanjian, Prinsip, Rebus Sic Stantibus Abstract This article aims to explore the dynamics of the principle of rebus sic stantibus in the law of treaty. It will explore how experts view toward this principle, how the international law deals with it, and how it is implemented in reality in international society. Finally, it is concluded that the principle of rebus sic stantibus may be invoked as a ground in terminating, withdrawing or suspending the implementation of a treaty. Keywords: treaty, principles, rebus sic stantibus 1 Artikel ini pernah dimuat di Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edisi Khusus, November 2011. 47 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Negara merupakan aktor utama dan pertama dalam memainkan hubungan kerja sama internasional. Di era globalisasi2 hubungan kerja sama internasional semakin ramai dengan keberadaan dan diakuinya organisasi internasional sebagai salah satu pelaku dalam hubungan internasional. Hubungan kerja sama internasional yang dilakukan antar subyek hukum internasional utamanya antar negara pun semakin meningkat. Adanya perbedaan sistem kenegaraan, bentuk negara, 2 Sebenarnya tidak cukup jelas, kapan era globalisasi dimulai. Ada pendapat, bahwa apa yang terjadi dalam globalisasi bukan merupakan sesuatu yang baru. Hubungan antar negara dengan negara lain dalam berbagai bidang sudah dimulai sejak banyaknya negara-negara merdeka, yaitu setelah diadakanya Perjanjian Westphalia tahun 1648. Pendapat lain mengatakan bahwa, globalisasi merupakan fenomena baru dalam masyarakat internasional. Karena globalisasi merupakan revolusi global pertama dan merupakan lompatan yang signifikan menuju kenyataan baru ditandai dengan ditemukannya pesawat jet dan komputer yang kemudian dipergunakan secara meluas, dan pada gilirannya memudahkan manusia berkomunikasi atau berinteraksi dari manapun mereka berasal. Dari sisi ekonomi, globalisasi ditandai oleh adanya intensitas perdagangan antar negara meluas dan migrasi serta investasi ekonomi meningkat. Globalisasi mempunyai makna yang bermacam-macam, seperti internasionalisasi, yaitu meningkatnya intensitas interaksi lintas batas dan saling ketergantungan antar negara; Liberalisasi, yaitu sebagai suatu proses untuk memindahkan larangan-larangan yang dibuat oleh negara dalam rangka membentuk ekonomi dunia yang lebih terintegrasi; Universalisasi yaitu menyebarnya berbagai macam obyek dan pengalaman dari masyarakat di seluruh dunia; Westernisasi yaitu proses peniruan budaya barat atau bahkan proses memaksakan sistem budaya, sistem politik dan sistem ekonomi negaranegara Barat dalam panggung dunia. Oleh Sheila L. Croucher, globalisasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai “a process of blending or homogenization by which the people of the world are unified into a single society and function together. This process is a combination of economic, technological, socialculture and political forces”. Sheila L Croucher, Globalization and Belonging: The politics of identity in a Changing World, Roman & Littlefield, hlm. 10. Yulius P. Hermawan (editor), Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional; Aktor, Isu dan Metodologi,2007, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 130-132. 48 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 perbedaan pandangan hidup, kebudayaan, agama atau kepercayaan bukan merupakan penghalang untuk menjalin kerja sama, bahkan dapat meningkatkan intensifnya hubungan antar negara. Demikian juga persoalan yang menjadi sasaran pengaturan dalam perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah yang ada dipermukaan bumi saja, namun sudah meluas pada masalah-masalah yang ada di dalam perut bumi dan juga yang ada di luar planet bumi (di ruang udara dan ruang angkasa). Oleh karena itu dengan didukung oleh kenyataan yang demikian3, mendorong dibuatnya aturan-aturan secara lebih tegas dan pasti, yaitu dalam bentuk perjanjian internasional (treaty)4. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih berlangsungnya hubungan-hubungan antar negara atau hubungan internasional, selama itu pula akan melahirkan berbagai perjanjian internasional dalam berbagai bidang yang di aturnya seperti bidang sosial dan budaya, politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, perdagangan, teknologi, pertanian, perbatasan, dan sebagainya. Melalui perjanjian internasional pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai anggota masyarakat internasional akan lebih terarah dan terjamin. Hal demikian pada gilirannya menjadikan perjanjian internasional mempunyai peranan penting dalam hubungan internasional. Dalam 3 4 Sebagaimana dikutip oleh Sam Suhaedi Admawiria, bahwa hukum internasional adalah fakta, karena ada fakta pergaulan hidup bangsa-bangsa. State cannot live a life to itself alone. It is a member of community of states. Sam Suhaedi Admawiria, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1968, hlm.xvi. Treaty merupakan istilah umum untuk menyebut Perjanjian Internasional. Istilah lain untuk menyebut perjanjian internasional adalah Convention, Agreement, Arangement, Declaration, Protokol, Proces Verbal, Modus Vivendi, Exchane of Notes, dan sebagainya. Penggunaan istilah dalam pembuatan perjanjian internasional tergantung kesepakatan Negara-negara pihak, Konvensi Wina 1969 sebagai sumber hukum pembuatan perjanjian internasional tidak mewajibkan kepada pembuat perjanjian internasional untuk menggunakan istilah tertentu. 49 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 konteks hukum internasional menaikan peringkat perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang pertama kali diperhatikan oleh hakim-hakim di Mahkamah Internasional (International Court of Justice)5. Dengan demikian sebagai salah satu fungsi perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Dapat pula dikatakan bahwa di dalam tubuh hukum internasional terdapat perjanjian internasional. Di dalam tubuh hukum internasional sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Starke, terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negaranegara dan oleh karenannya ditaati dalam hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi juga; 1. kaidah-kaidan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional serta hubungannya antara negara-negara dan individu-individu, 2. kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan individuindividu dan kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban dari individu-individu dan kesatuan bukan negara 5 Sebelum dikeluarkanya Statuta Mahkamah Internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Starke bahwa ; “The material sources of international law fall into five principles categories or forms: custom, treaties, decisions of judicial or arbitral tribunals, juristic works, and decisions or determinations of organs of international constitutions”. Kemudian berdasarkan Article 38 par. 1 of International Court of Justice, that : The Court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: 1). international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; 2). international custom, as evidence of a general practice accepted as law; 3). the general principles of law recognized by civilized nations; 4). subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. Starke, 1989, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterworth, London, page 32; Article 38 par. 1, Statute of International Court of Justice. 50 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 tersebut hasil kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dengan semakin besar dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar negara, akan mendorong diadakannya kerjasama internasional, yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Dalam pembuatan perjanjian internasional negara-negarapun tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional. Dewasa ini ada dua aturan internasional yang digunakan untuk mengatur pembuatan perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention on The Law Of Treaties, 19696 dan Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 19867. Perbedaan di antara kedua konvensi tersebut hanya terletak pada subyek pembuat perjanjian internasional, sehingga beberapa asas atau prinsip umum dalam pembuatan perjanjian internasional adalah kurang lebih sama. Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan species dari genus yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjajian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Sebagai 6 7 Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara (subyek perjanjian adalah Negara) Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional lain. 51 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 pasangan dari asas pacta sunt servanda adalah asas itikad baik. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan8. Oleh karena itu, demi untuk menghindari atau mencegah timbulnya sengketa, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap asas-asas dari perjanjian atau perjanjian internasional. Di pihak lain berlakunya atau beroperasinya suatu perjanjian, termasuk juga perjanjian internasional juga dapat dipengaruhi atau harus memperhatikan asas hukum yang lain, seperti asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt9, asas non-retroaktive10, asas rebus sic stantibus11, dan norma jus 8 9 52 Lihat juga pendapat dari Wery dan Subekti, sebagaimana dikutip oleh Siti Ismijati Jenie dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, dengan judul Pidatonya Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm.5-6. Menurut Wery, bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, bahwa kedua belah pihak (pihak-pihak peserta perjanjian) harus berlaku satu sama lain seperti patutnya di antara orangorang (pihak-pihak) yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akalakalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja namun juga melihak kepentingan pihak lain. Cetak miring merupakan penegasan dari penulis dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Sedangkan menurut Subekti, bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif. Atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar. Bahwa perjanjian hanya membebankan hak dan kewajiban bagi para pihak perjanjian internasional, bukan pada pihak ketiga, dalam hukum perjanjian sering disebut dengan prinsip Pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Lihat Brownlie, Principles of Public International Law, ELBS Oxford University Press, 1979, hlm. 619. Asas ini telah menjadi bagian dari hukum internasional positif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Pasal 34 Konvensi Wina 1969 “A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.” JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 cogens12. Dikatakan beberapa asas hukum tersebut mempengaruhi keberlangsungan perjanjian, karena sekalipun sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut mengikat bagi para pihak, bila kemudian terjadi suatu peristiwa atau karena berlakunya suatu asas hukum yang lain maka dapat berakibat berlakunya perjanjian tersebut ditunda atau bahkan dibatalkan. Seperti misalnya, dengan munculnya norma dasar hukum internasional yang baru (norma jus cogens) di mana norma tersebut bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut akan batal. Demikian juga atas suatu perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental (rebus sic stantibus), keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi 10 11 12 Pasal 34 Konvensi Wina 1986 A treaty does not create either obligations or rights for a third State or a third organization without the consent of that State or that organization Ketentuan hukum tidak dapat diterapkan atau diberlakukan atas suatu peristiwa hukum masa lampau, yaitu masa sebelum ketentuan hukum itu dinyatakan berlaku. Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 keberadaan asas Non-retroactive terdapat dalam Pasal 4 jo Pasal 28. Pasal 4 Konvensi Wina 1969 dan 1986, .......the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States. Pasal 28 Konvensi Wina 1969 dan 1986, Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provision do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party Pengertian dan makna asas rebus sic stantibus akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya dalam paper ini. Norma jus cogens merupakan suatu norma dasar hukum internasional umum (peremtory norm of general international law). Dalam Pasal 53 jo Pasal 64 Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa suatu perjanjian batal apabila pada saat pembentukan perjanjian tersebut bertentangan dengan suatu norma dasar hukum internasional umum. 53 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Dengan kata lain berlakunya perjanjian internasional dapat ditangguhkan, bahkan dapat dibatalkan karena adanya perubahan keadaan yang sangat fundamental. Jadi dengan berlakunya asas rebus sic stantibus maka para pihak dapat melepaskan atau mengingkari janji-janji yang telah mereka berikan. Khusus berkenaan dengan asas rebus sic stantibus yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian, sekalipun asas ini telah diterima di dalam masyarakat internasional, namun dalam beberapa hal masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Dalam paper ini fokus utama pembahasannya adalah keberadaan asas rebus sic stantibus dalam perjanjian internasional. B. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas dalam tulisan ini akan dikaji : 1. Bagaimana eksisitensi asas rebus sic stantibus dalam masyarakat internasional. 2. Bagaimanakah penerapan asas rebus sic stantibus dalam masyarakat internasional. II. P E M B A H A S A N A. Ruang lingkup Perjanjian internasional Sebagaimana di singgung di atas, bahwa dengan semakin intensifnya hubungan antar negara, perjanjian merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak pembuat perjanjian13. Kata ”perjanjian” menggambarkan adanya kesepakatan antara anggota 13 54 Praktek negara-negara mengadakan perjanjian internasional sudah lama dikenal di dalam masyarakat internasional. Seperti hasil kesepakatan atau perdamaian Westphalia yang dituangkan dalam bentuk konvensi multilateral. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 masyarakat14 tentang suatu keadaan yang mereka inginkan. Juga mencerminkan hasrat mereka, dan memuat tekad mereka untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan hasrat mereka. Kata ”perjanjian” yang diikuti kata sifat ”internasional”, yang merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh para aktor yang bertindak selaku subyek hukum internasional, juga kata ”internasional” di sini untuk menggambarkan bahwa perjanjian yang dimaksud bersifat lintas-batas suatu negara, para pihak masing-masing bertindak dari lingkungan hukum nasional yang berbeda15. Dalam perkembangannya, perjanjian internasional telah dijadikan sumber hukum dalam hubungan internasional dan telah menjadi bagian utama dalam hukum internasional. Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser posisi hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Dalam merumuskan hasil kesepakatan dalam suatu perjanjian internasional, praktek negara-negara telah menuangkan ke dalam berbagai bentuk dengan berbagai macam sebutan atau nama, mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana. Namun apapun bentuk dan sebutan yang diberikan pada perjanjian internasional yang merupakan hasil kesepakatan tersebut tidak mengurangi kekuatan mengikatnya suatu perjanjian bagi para pihak. 14 15 Dalam konteks perjanjian internasional, tentunya yang dimaksud dengan anggota masyarakat adalah anggota masyarakat internasional yang beranggotakan Negaranegara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003. Ko Swan Sik, Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional, dalam Jurnal Hukum Internasional, Volume 3 Nomor 4, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2006, hlm. 474 – 476. 55 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Sampai dengan tahun 1969 pembuatan perjanjian antar negara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang berlaku dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut kemudian oleh Komisi Hukum Internasional disusun dalam bentuk pasal-pasal sebagai draft suatu perjanjian internasional tentang pembuatan perjanjian internasional. Kemudian pada tanggal 26 Maret 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April - 22 Mei 1969 diadakanlah Konferensi Internasional di Wina untuk membahas draft yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional tersebut. Konferensi tersebut kemudian melahirkan Vienna Convention on The Law of Treaties yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 196916. Pengertian perjanjian internasional sendiri dapat ditinjau dari sudut pandang teoritis maupun sudut pandang yuridis. Tinjauan dari sudut pandang teoritis artinya melihat pendapat di antara beberapa sarjana, seperti pendapat Oppenheim, O’Connell, Mochtar Kusumaatmadja, Starke, dan masih banyak lagi17. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang 16 Konvensi ini mulai berlaku efektif dan telah menjadi hukum internasional positif pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen ke tiga puluh ratifikasi atau keikutsertaan, yaitu tepatnya sejak tanggal 27 Januari 1980. Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum, yanpa tahun, hlm. 10. 17 Beberapa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Mohd. Burhan Tsani, dalam bukunya Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty Yogyakarta, 1990, hlm. 64-65. Sumaryo Suryokusumo, Loc. Cit., hlm. 11. Menurut Oppenheim, International treaties are conventions, or contracts, between two or more states concerning various matters of interest. D.P. O’Connell, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum pembuatan perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting. 56 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundangan RI18. Berdasarkan berbagai pengertian perjanjian internasional baik berlandaskan pada pengertian teoritis maupun yuridis, dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila 18 Mochtar Kusumaatmadja: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. JG Starke: Traktat adalah suatu perjanjian di mana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan di antara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang perjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional. Menurut Schwarzenberger, Perjanjian adalah persetujuan di antara subyek hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional. Konvensi Wina 1969 Pasal 2 (1.a): Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antarnegara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam bentuk satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya. Konvensi Wina 1986 Pasal 2 (1.a): Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis: - antara satu negara atau lebih dan antara satu organisasi internasional atau lebih, atau - antarorganisasi internasional. UU No.37 Th.1999 Pasal 1 (3): Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yg diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek HI lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik. UU No.24 Tahun 2000, Pasal 1.a.: Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik 57 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 dibuat oleh subyek hukum internasinal dalam bentuk tertulis serta dalam pembuatannya tunduk pada rejim hukum internasional. Tentang isi suatu perjanjian menyangkut apapun yang disepakati oleh para pihak, sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan norma-norma atas asas-asas hukum internasional. B. Keberadaan Asas Rebus sic Stantibus 1. Pengertian asas Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa dalam hukum perjanjian terdapat berapa asas penting dalam perjanjian internsaional salah satunya adalah asas rebus sic stantibus. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang keberadaan asas rebus sic stantibus, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu pengertian asas dan arti pentingnya asas dalam hukum. Oleh beberapa sarjana penggunaan kata asas disamakan artinya dengan prinsip (principle)19. Arti dari asas itu sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai tiga pengertian, yaitu berarti: a. Dasar, alas, pedoman; b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir c. Cita-cita yang menjadi dasar20. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau tempat tumpuan berpikir dalam memperoleh kebenaran. 19 20 58 Mochtar Kusumaatmadja, menterjemahkan general principle of law dengan asas hukum umum. Vadross, beliau mengatakan bahwa asas pacta sunt servanda merupakan suatu asas hukum umum (general principle of law). Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003, hlm.148; Sam Suhaedi Atmawiria, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1968, hlm.58. Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 32. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.21 Berdasakan pendapat Paton yang demikian dapat dikatakan bahwa adanya norma hukum itu berlandaskan pada suatu asas. Sehingga setiap norma hukum harus dapat dikembalikan pada asas. Pendapat senada dikemukakan oleh van Erkema Hommes bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.22 Pendapat lain tentang asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ron Jue bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum.23 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan kaidah hukum, bersifat umum maupun universal24 dan abstrak, tidak bersifat konkrit. Bahkan oleh Scholten dikatakan bahwa asas hukum itu berada baik dalam sistem hukum maupun di belakang atau di luar sistem hukum. Sejauh nilai asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Demikian sebaliknya, sejauh nilai asas hukum itu 21 22 23 24 Sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.36. Dalam Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm.5. Mr. drs. J.J. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.121. Asas hukum umum menunjuk berlakunya asas tersebut pada seluruh bidang hukum. Sedangkan asas hukum universal menunjuk berlakunya asas tersebut kapan saja dan di mana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Oleh Scholten ditunjukan adanya asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum saja. Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit., hlm. 6. 59 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 tidak diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di belakang sistem hukum25. Berdasarkan pemikiran Scholten yang demikian, maka bisa dijumpai adanya beberapa asas hukum yang dituangkan dalam kaidah hukum, baik yang berupa undang-undang maupun perjanjian internasional. Demikian sebaliknya, ada beberapa asas hukum yang tidak dituangkan dalam peraturan perundangan atau perjanjian internasional. 2. Keberadaan dan Pandangan para ahli terhadap asas Rebus Sic Stantibus. Keberadaan asas Rebus Sic Stantibus26 telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan27, dan bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam sistem hukum internasional. Masyarakat Eropa, khususnya melalui hukum Gereja mengatakan bahwa: ”pengaruh hukum Gereja yang kekal dapat terlihat dalam pemasukan asas rebus sic stantibus kedalam tubuh hukum internasional”. Diterimanya asas rebus sic stantibus tersebut pada awalnya untuk melunakkan sifat ketat hukum privat Roma28. Bahkan sejak abad XII dan XIII ahli-ahli hukum kanonik telah mengenal asas ini yang dalam bahasa Latin-nya diungkapkan sebagai : contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur, yang 25 26 27 28 60 Ibid., hlm.122. Makna dari asas tersebut adalah;” perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat selama tidak ada perbahan vital dalam keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu traktat diadakan”. RC Hengorani, Modern International Law, Second Edition, Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi, 1982, hlm. 232. Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional I, Binacipta, Bandung, 1969, hlm. 90, 123. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 artinya bahwa ”perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama” 29. Melalui ungkapan dari para ahli hukum kaum kanonik dapat dipahami bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan janjinya, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perubahan keadaan dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian dapat menyatakan untuk tidak terikat lagi pada atau keluar dari perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian tidak lagi mengikat baginya. Asas Rebus Sic Stantibus pertama kali diterapkan oleh peradilan keagamaan. Diterapkannya asas Rebus Sic Stantibus oleh peradilan keagamaan karena situasi yang terjadi pada waktu itu adanya pemisahan antara urusan gereja dengan urusan negara, dan ini merupakan salah satu karakteristik penting dari Kode Napoleon. Untuk selanjutnya asas Rebus Sic Stantibus diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum. Asas ini kemudian telah diterima secara luas pada akhir abad XIII30. Dalam perkembangannya keberadaan asas rebus sic stantibus mendapat dukungan dari beberapa ahli dan pendapat para ahli telah membantu eksistensi asas rebus sic stantibus dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Machiavelli bahwa; ”segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang 29 http://perjanjian internasionalhilawyers.com/blog/?p=16, Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Perjanjian, diakses tanggal 22 Pebruari 2008 30 Ibid. 61 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 dihadapi oleh penguasa negara”31. Sikap Machiavelli yang demikian tentunya tidak jauh dari makna yang terkadung dalam asas rebus sic stantibus. Demikian juga Alberico Gentili menyatakan bahwa: ”yang paling penting atas hukum traktat ialah dalil bahwa perjanjian (perdamaian) selalu mengandung syarat tersimpul, jaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya tidak berubah”32. Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan syarat tersimpul oleh Aliberco Gentili adalah asas rebus sic stantibus. Lain halnya dengan Bynkershoek dalam salah satu karyanya yang berkaitan dengan traktat, walau pada awalnya ia menolak asas rebus sic stantibus, namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana ia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji itu33. Di tegaskan pula oleh Bierly, bahwa dalam setiap perjanjian internasional ada tersirat suatu syarat tambahan yang menentukan bahwa perjanjian itu hanya mengikat selama keadaan-keadaan masih seperti semula. Katakata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan di antara para pihak namun mengandung suatu syarat, yaitu apabila tidak terjadi suatu perubahan keadaan yang penting terjadi. Bila terjadi suatu perubahan keadaan yang penting maka hilanglah syarat berlakunya perjanjian, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi34. Rebus Sic Stantibus merupakan salah satu asas dalam hukum. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana ungkapan ubi 31 32 33 34 62 Op. Cit., hlm. 102 Op. Cit.., hlm 123. Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional II, Binacipta, Bandung, 1970, hlm. 78. Bierley, Hukum Bangsa-Bangsa, terjemahan Moh. Radjab, Bhratara, Jakarta, 1963, hlm.244 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 societas ibi ius, bahwa di mana ada masyarakat disana ada hukum. Demikian juga terhadap penerimaan asas rebus sic stantibus berdasarkan sejarah hukum mengalami pergeseran seiring dengan berjalannya waktu. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Rosenn: ”Pada awal abad kelimabelas, popularitas asas rebus sic stantibus mulai memudar, sebagian karena adanya protes untuk kepentingan komersial terhadap peningkatan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh penerapan secara luas asas tersebut. Pada akhir abad delapanbelas, asas pacta sunt servanda mencapai puncaknya, dan asas rebus sic stantibus telah menghilang hanya menjadi doktrin yang usang. Yang ikut mendorong kepudaran asas rebus sic stantibus adalah munculnya positivisme scientific, dan meningkatnya penekanan pada otonomi individual dan kebebasan berkontrak”35. Di pihak lain, sebagaimana juga dikemukakan oleh kaum kanonis yaitu munculnya paham liberalisme yang mendominasi di abad XVIII, membawa ide baru dalam penerapan asas rebus sic stantibus yang kurang tegas dan terbatas. Mereka beranggapan bahwa asas pacta sunt servanda sangat sesuai dengan konsep lasse faire, lassez passe. Oleh karena itu kitab undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu, yaitu Kode Napoleon dan Italian Civil Code tidak mengadopsi asas rebus sic stantibus. Tidak diakuinya asas rebus sic stantibus nampak dalam artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi: Agreements legally made take the place of law for those who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law authorize. They must be executed in good faith36. 35 36 http://perjanjian internasionalhilawyers.com/blog/?p=16, Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Perjanjian, diakses tanggal 22 Pebruari 2008 Ibid. 63 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Kondisi yang demikian berlangsung terus hingga pecah Perang Dunia I. Setelah Pecah Perang Dunia I, para ahli hukum Eropa mencari alasan pembenar atau teori hukum apa yang tepat untuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk melaksanakan perjanjian yang ternyata sangat sulit dilaksanakan, karena adanya perubahan keadaan. Perubahan yang terjadi adalah adanya perang yang cukup lama dan membawa kerusakan yang demikian hebat di berbagai Negara di Eropa, yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan perjanjian. Menghadapi situasi yang demikian para ahli hukum Eropa akhirnya mendaur ulang atau kembali pada asas atau prinsip rebus sic stantibus, dengan nama atau rumusan yang berbeda. 2. Perwujudan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Positif Seperti halnya asas pacta sunt servanda, asas rebus sic stantibus telah menjadi bagian dari asas hukum umum, yang kemudian dalam perkembangannya (dengan modifikasi dalam perumusanya) juga diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, sehingga asas hukum itu berada di dalam sistem. Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur, yang salah satunya adalah perjanjian internasional. Dalam hukum internasional positif asas rebus sic stantibus mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Wina 1969, yaitu dalam Seksi 3 tentang Pengakhiran dan Penundaan bekerjanya perjanjian internasional, khususnya Pasal 62. Pengaturan asas rebus sic stantibus bersamaan dengan berakhirnya atau penundaan berlakunya perjanjian, karena memang asas rebus sic stantibus merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakiri atau menunda berlakunya suatu perjanjian. Pasal 62 dengan judul perubahan mendasar atas keadaan-keadaan menentukan: 64 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 1) Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa: a) keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi setujunya pihak-pihak untuk terikat pada traktat; dan b) pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan di bawah traktat itu. 2) Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, jika: a) traktat itu menetapkan perbatasan; atau b) perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban di bawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya pada traktat tersebut. 3) Jika sesuai dengan ayat-ayat di atas, suatu pihak boleh menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu. Penggunaan kata-kata rebus sic stantibus tidak nampak dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Hal ini memang nampaknya dihindari oleh International Law Commission, dengan maksud untuk menekankan sifat obyektif dari ketentuan yang ada dan juga guna menghindarkan implikasi doktriner dari istilah tersebut. Sebagaimana juga dikemukakan oleh D.J. Harris, bahwa Komisi Hukum Internasional dalam sidangnya yang ke-18 tahun 1966 menolak teori yang tersirat tentang klausula rebus 65 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 sic stantibus itu, dan lebih suka mendasarkan pada doktrin ”perubahan keadaan yang fundamental” (fundamental change of circumtances) dengan alasan persamaan derajat dan keadilan serta membuang kata-kata rebus sic stantibus, karena menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan37. Oleh karena itu pada akhirnya makna yang terkandung dalam asas rebus sic stantibus oleh Konvensi Wina dirumuskan dengan menggunakan istilah ”fundamental change of circumtances” (perubahan fundamental atas suatu keadaan). Bahkan oleh Mahkamah Internasional, dalam kasus Fisheries Jurisdiction, dikatakan bahwa keberadaan asas rebus sic stantibus dalam Pasal 62 tersebut hanyalah bersifat merumuskan hukum kebiasaan38. Dalam peraturan perundangan Indonesia, keberadaan asas rebus sic stantibus mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional. Dikatakan oleh Pasal 18 bahwa: ” perjanjian internasional berakhir apabila terdapat purubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”39. 37 D.J. Harris, Case and Materials in International Law, Maxwell, London, 1983, hlm. 624. 38 39 66 Peter malanczuk, Akehurst’s Medern Introduction to International Law, Routledge, London and New York, 1997, hlm. 145. Bunyi Pasal 18 UU No.24 tahun 2000 selengkapnya adalah, “Perjanjian internasional berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para perjanjian internasionalhak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; d. salah satu perjanjian internasionalhak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat suatu perjanjian baru yang mengantikan perjanjian lama; f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; g. obyek perjanjian hilang; h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Namun dalam undang-undang tersebut tidak memberikan batasan tentang apa itu asas rebus sic stantibus. Melalui asas ini Pemerintah Indonesia dapat menyatakan berakhirnya suatu perjanjian internasional yang dibuat dengan negara lain, sekalipun pelaksanaan asas tersebut masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dalam lapangan hukum perdata, khususnya yang bersumberkan pada Kitab undang undang Hukum Perdata, nampaknya tidak mengakui keberadan asas rebus sic stantibus. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian antara lain, dengan judul hapusnya perikatan sebagaimana di atur dalam Pasal 1381 KUH Perdata40. C. Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus a. Kaitan antara Asas Rebus sic Stantibus dengan asas Pacta Sunt Servanda dan Force Majeure. Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa atas suatu perjanjian internasional mulai dari pembentukannya sampai pada tataran beroperasinya perjanjian internasional tersebut selalu diliputi berlakunya asas-asas hukum. Dua di antara asas-asas hukum yang menyertai perjanjian internasional tersebut adalah Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Rebus Sic Stantibus. Asas pacta sunt servanda menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas pacta sunt servanda pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati 40 Pasal 1381 Perikatan hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan karena kadaluwarsa. 67 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 dalam perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas pacta sunt servanda yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus melaksanakan sesui dengan janjinya. Karena keberadaan asas tersebut juga dilandasi oleh ajaran agama. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa asas pacta sunt servanda merupakan norma dasar (grundnorm). Asas pacta sunt servanda yang lahir di negara-negara Eropa Kontinental sebagai negara penganut civil law, dalam perkembangannya mengalami pergeseran dalam mempertahankan berlakunya suatu perjanjian. Sebab pada kenyataannya berlakunya suatu perjanjian terpengaruh oleh suatu situasi yang terjadi pada saat itu dan pada gilirannya akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban para pihak. Bila demikian jadinya maka berlakunya perjanjian akan terganggu dan dibutuhkan jalan keluar pemecahannya. Situasi yang demikian dapat menimbulkan problem yang lebih komplek, yaitu adanya pertentangan antara daya laku hukum secara kekal yang mempertahankan keadaan berlakunya suatu perjanjian dengan kekuatan-kekuatan yang menghendaki adanya perubahan. Oleh Gentili dikatakan untuk mengatasi pertentangan itu asas rebus sic stantibus-lah yang dapat melegalisir tantangan itu. Ini artinya bahwa berlakunya asas pacta sunt servanda dapat disimpangi oleh asas rebus sic stantibus41. Sehingga keberadaan rebus sic stantibus diperhatikan lagi setelah pecah Perang Dunia I, di mana para ahli hukum Eropa mencari justifikasi teori guna memberi kelonggaran kepada pemberi janji karena adanya perubahan keadaan yang fundamental dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan janji-janji. 41 Sam Suhaedi Admawirea, Loc.Cit, hlm. 122. 68 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Namun demikian, sekalipun telah diterima baik melalui hukum internasional positif maupun dukungan dari para ahli, penggunaan asas rebus sic stantibus perlu hati-hati sekali agar tidak disalah gunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam perjanjian. Hal ini mengingat bahwa dalam menerapkan asas rebus sic stantibus kadang-kadang masih menimbulkan kekaburan di dalam pelaksanannya. Apa yang dimaksud dengan perubahan vital, dapat ditafsirkan bermacam-macam dalam praktek hubungan antar negara. Seperti Jerman pada tahun 1941 pernah berlindung di balik asas rebus sic stantibus untuk membenarkan pelanggarannya terhadap kenetralan Belgia, dengan jaminan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian London 183142. Para ahli hukum internasional sendiri merasa enggan untuk menentukan dan membatasi lingkup asas rebus sic stantibus tersebut dan enggan mengatur secara ketat, demi keamanan perjanjian43. Lebih lagi bila asas rebus sic stantibus dikaitkan dengan konsep hukum yang berupa force majeure, bahwa penggunaan asas Rebus Sic Stantibus sebagai alasan pembenar untuk membatalkan atau menunda berlakunya perjanjian tidak boleh dicampur adukkan dengan force majeure atau vis major44, yang juga merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan juga telah diterima sebagai prinsip dalam hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya. Dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa force majeure atau vis major merupakan suatu keadaan ke-tidak mungkinannya salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian (impossibility of performance). Alasan tersebut dapat 42 43 44 Bierly, loc.cit., hlm 245. Hugh M Kindred, International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, Emond Montgomery Publications Limited, 1987, hlm. 171. Mochtar Kusumaatmadja, op. cit., hlm. 140. 69 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 dikemukakan apabila pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena lenyapnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian45. Keadaan force majeure atau vis major dapat menyampingkan kewajiban pelaksanaan perjanjian hanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat diduga sebelumnya. Suatu keadaan force majeure atau vis major terjadi apabila pelaksanaan tidak dimungkinkan secara fisik dan secara hukum, dan bukan semata-mata karena adanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Jadi di sini tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam perjanjian bukan karena adanya kesulitan ekonomis bahkan ketidak mungkinan secara ekonomi. Akhirnya Mochtar Kusumaatmadja pun berpendapat bahwa dirasa perlu untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan asas rebus sic stantibus sebagai alasan untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian internasional dengan saksama46. Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang demikian, menurut Mieke Komar Kantaatmadja jika terjadi perubahan yang mendasar sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 dan para pihak akan menghentikan perjanjian internasional atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional apabila dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1) perubahan suatu kedaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian, 2) perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut, 3) perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak, 45 46 70 Ibid. Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit, hlm. 141 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 4) akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu, 5) penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan47. b. Penerapan Asas rebus sic stantibus dalam masyarakat internasional. Prinsip hukum rebus sic stantibus nampaknya tetap menjadi bahan telaah dan sering digunakan oleh negara-negara di dunia untuk melakukan penundaan terhadap sebuah perjanjian internasional. Bentuk yang cukup terkenal yang dianggap oleh beberapa ahli hukum dan praktek internasional sebagai salah satu bentuk dari rebus sic stantibus adalah pertikaian bersenjata atau perang. Konflik senjata sebagai salah satu bentuk rebus sic stantibus untuk melakukan penundaan sebuah perjanjian telah digunakan di dalam tiga kasus, yaitu ketika Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah perubahan keadaan yang mencukupi untuk melakukan penundaan atas jurisdiksi Permanent Court of International Justice pada tahun 1939, Pengadilan Paris yang menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan yang menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi negara belligerent dan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt yang menunda pelaksanaan kewajiban Amerika 47 Mieke Komar Kantaatmadja, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional, makalah, Fakultas Hukum UNPAD, 1981; Pasal 62 Konvensi Wina 1969 71 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Serikat kepada International Load Line Convention pada tahun 1930 karena perang dunia kedua48. Berdasarkan doktrin dan praktek diatas, kemudian muncul pernyataan, apakah sebuah konflik senjata dapat serta merta menyebabkan terhentinya atau memunculkan penundaan berlakunya perjanjian internasional ? Jawaban untuk pertanyaan ini dapat dilihat dari beberapa praktek negara-negara dan konflik senjata yang terjadi setelah perang dunia kedua. Negara Perancis dapat dikatakan menganut faham yang cukup keras, di mana menurut beberapa pendapat hukum di Perancis, deklarasi perang saja cukup untuk memberikan dampak bagi sebuah perjanjian internasional. Dapat dikatakan bahwa Perancis tidak akan menunggu terjadinya konflik senjata untuk mengambil keputusan baik menunda maupun melakukan penundaan terhadap sebuah perjanjian internasional. Faham ini sedikit berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh Inggris di mana dampak terhadap sebuah perjanjian internasional akan muncul jika terjadi konflik senjata. Inggris melakukan penundaan perjanjian internasional atas dasar konflik senjata pada tahun 1795 ketika Inggris menyatakan bahwa Konvensi Nootka Sound 1790 tidak berlaku lagi karena perang yang terjadi antara Inggris dan Spanyol. Lain halnya dengan Perancis dan Inggris, negara Belanda menganut faham yang cenderung lebih lunak. Hal ini dapat dilihat dari praktek negara Belanda yang menunda pelaksanaan seluruh perjanjian internasional bilateral dengan negara Suriname ketika terjadi pergolakan pada tahun 1982. Sementara itu, negara Italia, berdasarkan putusan Pengadilan Kasasi yang menyatakan bahwa konflik senjata dapat menyebabkan terjadinya perubahan keadaan yang kemudian 48 72 Indonesia and Law, Perjanjian Internasional dan Konflik Bersenjata, http:// forums.blogspot.com/2007/03. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kemungkinan penggunaan prinsip rebus sic stantibus. Lebih jauh, Pengadilan di Italia pada masa perang dunia kedua memutuskan bahwa perjanjian ekstradisi tidak berlaku lagi atas dasar perang yang terjadi49. Selain praktek negara-negara di dunia, beberapa konflik senjata yang terjadi setelah perang dunia kedua juga dapat dijadikan acuan apakah konflik senjata dapat serta merta menyebabkan terhentinya atau memunculkan penundaan sebuah perjanjin internasional. Acuan pertama adalah ketika negara Mesir melakukan penundaan atas perjanjian Suez Canal Base dengan negara Inggris di tahun 1956. Keputusan Mesir ini disebabkan atas serangan udara Inggris dan Perancis terhadap Mesir di tahun 1956. Acuan kedua adalah konflik senjata yang terjadi antara negara Cina dan negara India yang berkenaan tentang masalah perbatasan di tahun 1962. Menarik untuk dicermati adalah bahwa walaupun terjadi konflik senjata, hubungan diplomatik kedua negara ini tetap ada. Acuan yang ketiga adalah konfik senjata Iran-Irak pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Di dalam konflik senjata ini kedua belah negara telah secara sepihak membatalkan perjanjian internasional tentang batas negara. Iran membatalkan perjanjian internasional Batas Shatt-alArab yang dibuat tahun 1937 sementara Irak membatalkan perjanjian internasional Baghdad yang dibuat pada tahun 197550. Dari beberapa contoh praktek negara-negara di dunia dan beberapa konflik senjata yang terjadi, dapat diambil beberapa kesimpulan yang patut dicermati, yaitu antara lain adalah bahwa untuk beberapa kasus, sebuah perjanjian internasional tetap berlaku walaupun terjadi konflik senjata; bahwa sebuah perjanjian internasional tidak serta merta berhenti berlaku walaupun terjadi konflik senjata, melainkan mengalami penundaan pelaksanaan; dan bahwa untuk kasus-kasus tertentu sebuah 49 50 Ibid. Ibid. 73 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 perjanjian internasional tidak berlaku lagi atau terjadi penundaan yang disebabkan oleh konflik senjata baik antara para pihak perjanjian internasional dari perjanjian internasional tersebut maupun pihak ketiga. Di Indonesia sendiri penerapan asas rebus sic stantibus dapat dilihat dari dua kasus, yaitu kasus berkaitan dengan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, dan kasus keberlangsungan perjanjian internasional antara Australia dengan Indonesia tentang Zona Kerja Sama di Celah Timor. Kasus Pertama, dalam hal ini berkaitan dengan adanya Perjanjian sebagai hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), di mana Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dengan penangguhan penyelesaian wilayah Irian Barat (kini Papua). Namun Perjanjian KMB ternyata tidak mampu menjalin hubungan baik antara Indonesia dan Belanda, bahkan tidak membawa penyelesaian mengenai masalah Irian Barat. Setelah pembubaran Uni Indonesia – Belanda kemudian pemerintah Indonesia memutuskan secara sepihak keseluruhan perjanjian KMB. Pemutusan yang demikian mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 22 Mei 1956 dan dimuat dalam Undang Undang nomor 13 tahun 1956. Adapun alasan yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia dalam membatalkan perjanjian KMB adalah sebagai berikut: Maka di dalam keadaan yang sudah begitu berubah dan mendesak sekali untuk membatalkan perjanjian KMB demi kepentingan nasional, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain daripada membatalkan perjanjian tersebut atas dasar rebus sic stantibus yang berlaku di dalam hukum internasional. Menurut asas rebus sic stantibus yang berarti atas dasar kenyataan adanya perubahan-perubahan yang vital di dalam negeri daripada salah satu pihak yang menandatangani, maka pihak tersebut berhak untuk menarik diri dari ikatan perjanjian itu. Dengan lain 74 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 perkataan di dalam keadaan demikian, maka prinsip rebus sic stantibus bisa dibuat sebagai dasar untuk meniadakan asas pacta sunt servanda tersebut51. Melihat pada kasus di atas, di mana dengan bubarnya Uni-Indonesia – Belanda dianggap telah terjadi perubahan keadaan yang fundamental di wilayah Indonesia, sehingga pihak dalam perjanjian dalam KMB dapat menyatakan untuk mengundurkan diri dari perjanjian KMB. Dibentuknya Uni Indonesia – Belanda sebagai salah satu sarana dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Maka di sini dipenuhi ukuran obyektif sebagai dasar untuk menarik diri dari perjanjian dengan alasan berlakunya asas rebus sic stantibus. Sedangkan ukuran kedua yang harus dipenuhi adalah ukuran obyektif, yaitu dengan bubarnya Uni Indonesia – Belanda, ternyata mempengaruhi kemampuan para pihak. Kasus kedua, sebagaimana diketahui bahwa dengan belum tercapainya kesepakatan mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dengan Australia di selatan Timor Timur (Celah Timor) maka pada tanggal 11 Desember 1989 ditanda-tangani perjanjian antara Indonesia dan Australia52 mengenai Zona Kerjasama di daerah antara Timor Timur dan Australia Bagian Utara, yang lebih dikenal ”Perjanjian Celah Timor”53. Perjanjian tersebut merupakan pengaturan sementara yang bersifat 51 52 53 Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan), Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penerbit Diadit Media, Jakarta, Cetakan ke-2, 2006, hlm. 182. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian antara Indonesia dan Australia ini, wilayah Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia, sehingga wilayah landas kontinen di sebelah selatan Timor Timur berada di bawah kedaulatan Indonesia. Dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan secara rinci tentang apa isi perjanjian Celah Timor, karena penekanan dalam tulisan ini adalah terjadinya perubahan keadaan yang fundamental yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian internasional yang dalam hal ini adalah perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. 75 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 praktis untuk memungkinkan dimanfaatkannya potensi sumber daya miyak dan gas bumi tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan batas landas kontinen. Juga, perjanjian tersebut mengatur mengenai ”Zona Pengembangan Bersama” (Joint Development Zone) di daerah ”tumpang tindih” negara-negara yang bersangkutan (dispute area). Diadakannya perjanjian Celah Timor berlandaskan pada Pasal 83 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 198254. Kemudian dengan berjalannya waktu, pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan jajak pendapat rakyat Timor Timur apakah akan menerima status otonomi khusus atau memisahkan diri dari Indonesia untuk merdeka. Beradaskan hasil jajak pendapat yang diumumkan pada tanggal 4 September 1999 sebagian besar rakyat Timor Timur menghendaki untuk berpisah dari Indonesia menjadi negara merdeka. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002 rakyat Timor Timur menyatakan kemerdekaannya dan menjadi Negara Timor Leste. Sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur, maka wilayah landas kontinen yang berada disebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, namun berada di bawah kedaulatan Timor Leste. Sehubungan dengan hal itu, dalam hukum perjanjian dikenal asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt55. Demikian juga dengan merdekanya Timor 54 55 76 Pasal 83 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa: ”sementara persetujuan penetapan batas landas kontinen belum tercapai negara-negara yang bersangkutan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama hendaknya berupaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama berlangsungnya masa transisi ini tidak boleh membahayakan atau menghambat upaya untuk mencapai persetujuan akhir. Pengaturan semacam ini tidak boleh merugikan penetapan garis batas landas kontinen yang final”. Bahwa perjanjian tidak membebankan hak dan kewajiban bagi pihak ke-tiga. Dalam kasus ini perjanjian Celah Timor tidak akan berlaku bagi Timor Leste sebagai pihak ke-tiga, karena perjanjian tersebut hanya menikat bagi Indonesia dan Australia. JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Timur maka menurut hukum internasional telah terjadi suksesi, yang dalam hal ini suatu wilayah Timor Timur yang dalam hubungan internasional semula menjadi tanggung jawab Indonesia, setelah tanggal 20 Mei 2002 berubah menjadi wilayah negara baru, yaitu negara Timor Leste sebagai negara berdaulat56. Dengan terjadinya suksesi negara dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu perubahan keadaan yang fundamental (rebus sic stantibus) di wilayah Indonesia, yang pada akhirnya berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Australia diadakan peninjauan kembali atas berlakunya perjanjian Celah Timor. III. K E S I M P U L A N Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan keberadaan asas dalam perjanjian intenasional, khususnya asas rebus sic stantibus, dapat tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa keberadaan kedua asas tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Bahkan beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, baik dalam taraf nasional Indonesia maupun dalam taraf internasional. Ini artinya keberadaan asas rebus sic stantibus barada dalam sustu sistem hukum. Penerimaan, keberadaan dan penggunaan asas pacta sunt servanda adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian. Artinya keberadaan dan penerimaan asas pacta sunt servanda dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya suatu perjanjian. Tanpa adanya 56 Article 2 point 1b, Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties,1978: “succession of states means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory”. 77 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka perjanjian tidak akan dapat beroperasi atau berlaku sebagaimana mestinya. Lain halnya dengan asas rebus sic stantibus, di mana dengan berlandaskan pada asas ini pihak-pihak perjanjian dapat menyatakan menunda atau menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian yang telah disepakati, sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969. 2. Sebagaimana disinggung pada urian di atas, bahwa penerimaan dan pengakuan asas rebus sic stantibus sebagai upaya untuk melegalsir tindakan pihak-pihak peserta perjanjian untuk mengakiri atau menunda berlakunya perjanjian yang telah mereka buat. Perubahan keadaan yang fundamental dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak lagi melaksanakan perjanjian, sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu, yaitu bila terjadi perubahan keadaan, di mana keadaan yang berubah itu menjadi dasar diadakannya perjanjian; dan adanya perubahan keadaan yang fundamental tersebut menyebabkan terjadi perubahan pelaksanaan kewajiban dari para pihak sebagaimana yang pernah dijanjikan. Beberapa kasus yang dianggap telah terjadinya perubahan keadaan yang fundamental, yang pada gilirannya merubah pelaksanaan apa yang telah diperjanjikan yaitu terjadinya konflik bersenjata, terjadinya konflik kepentingan di antara para pihak yang berjanji, atau karena adanya perubahan keadaan yang menyangkut status wilayah yang diperjanjikan (karena terjadi suksesi). 78 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Daftar Pustaka Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999 Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional I, Binacipta, Bandung, 1969. Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Admawiria, Sejarah Hukum Internasional II, Binacipta, Bandung, 1970. Bierley, Hukum Bangsa-Bangsa, terjemahan Moh. Radjab, Bhratara, Jakarta, 1963. Brownlie, Principles of Public International Law, ELBS Oxford University Press, 1979, Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986. Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 D.J. Harris, Case and Materials in International Law, Maxwell, London, 1983 . Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, Hingorani, Modern International Law, Second Edition, Oxford & IBH Publishing Co, New delhi, 1982. Hugh M Kindred, International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, Emond Montgomery Publications Limited, 1987 Madjedi Hasan, Pacta Sunt Servanda, The Principle and its application in Petroleum Production Sharing Contract, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2005 Martin Dixon and Robert MC Corquodale, Cases and Materials on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, Aldine Place, London, 2000. Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990. Mieke Komar Kantaatmadja, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional, makalah, Fakultas Hukum UNPAD. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni Bandung, 2003, Peter Malanczuk, Akehurst’s Medern Introduction to International Law, Routledge, London and New York, 1997. Professor Aziz T Saliba LLM dari Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul Comparative Law Europe pada Contracts Law and Legislation Volume 8, Number 3 September 2001, dalam http://Pihilawyers.com/blog/?p Sam Suhaedi Atmawiria, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1968 Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan Bernagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan), Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penerbit Diadit Media, Jakarta, Cetakan ke-2, 2006 . Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2007. Starke, Introduction to International Law, Butterword, London, 1989, 79 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2001. Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum (S-2), tanpa tahun. Wayan Partiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, Mandar Maju, Bandung, 2005. Dokumen: Jurnal Hukum Internasional, , Volume 3 Nomor 4, Juli 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. Kamus Umum Bahasa Indonesia http://perjanjian internasionalhilawyers.com/blog/?p=16, diakses tanggal 22 Pebruari 2008 Undang Undang Nomor 37 Tahuhn1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. United Nations Convention on the Law of The Sea 1982. Vienna Convention on The Law Of Treaties, 1969. Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978. 80 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 IMPLEMENTASI KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM PERKARA-PERKARA ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Mutiara Hikmah Abstrak Dengan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, penegakan putusan arbitrase internasional dapat diberlakukan di Indonesia, karena hukum acara yang mengatur tentang putusan arbitrase telah menjadi jelas. Untuk pengelolaan masalah keputusan arbitrase internasional yang lebih baik dalam hierarki perundangundangan, pada tanggal 12 Oktober 1999 diundangkan UndangUndang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat bagian khusus yang membahas Arbitrase Internasional. Artikel ini membahas bagaimana perkembangan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia sebelum Indonesia menjadi anggota Konvensi New York 1958 hingga saat ini, dengan menganalisis putusan arbitrase internasional dan perintah pengadilan setelah berlakunya UndangUndang Arbitrase. Kata kunci: arbitrase internasional, alternatif penyelesaian sengketa, konvensi New York 1958, UU Arbitrase. Abstract With the enactment of Supreme Court Law No. 1 Year 1990 on the Procedures for the Implementation of Foreign Arbitral Awards, the enforcement of international arbitral awards can begin to be implemented in Indonesia, because the procedural law governing the procedure of the arbitration decision is clear. To better manage the problem of international arbitral decision in the hierarchy of legislation, on 12 October 1999 promulgated the Law of Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In that Law, there is a special section that discusses the International Arbitration. This article examines how the development of the implementation of international arbitral awards in Indonesia before Indonesia became a member of New York 81 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Convention 1958, to date, by analyzing the international arbitration decisions and court order after the enactment of the Law of Arbitration. Keywords: international arbitration, alternative dispute settlement, New York Convention 1958, Law on Arbitration. Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 34 Tahun 1981 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 40. Dengan ikut sertanya negara Indonesia dalam Konvensi New York 1958, maka Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada awalnya, sikap Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung RI), tidak mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, kesadaran bahwa negara Indonesia akan terus tumbuh menjadi bagian dari aktivitas bisnis dunia, maka Pemerintah Indonesia harus memikirkan langkah ke depan untuk dapat mengakui dan melaksanakan putusan-putusan arbitrase internasional. Khususnya dalam upaya menarik perhatian para investor untuk memilih Indonesia sebagai tempat utama dalam aktivitas investasinya. Maka negara Indonesia harus membuka diri untuk mengikuti trend penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diikuti dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasionalnya1. Apalagi jika melihat tendensi yang terjadi pada akhir-akhir ini, dalam kontrak-kontrak yang ditanda tangani oleh Badan Usaha Milik Negara 1 Ricardo Simanjuntak, “Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri”, dalam Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 21, Oktober-November 2002), hal. 85. 82 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 (BUMN) atau Perusahaan Negara di satu pihak dengan pihak asing, baik dalam bentuk Kerja Sama Operasi(KSO)/Joint Operation Contract (JOC) atau lain-lain usaha bersama dan perjanjian yang bersifat ”internasional”, dipakai klausul mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan umumnya arbitrase ditentukan akan dilangsungkan di luar negeri2. Walaupun dalam kontrak ditentukan bahwa hukum Indonesia yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa, namun pelaksanaan pemeriksaan arbitrasenya dilangsungkan di luar negeri. Jika pelaksanaan pemeriksaan dan proses arbitrase berlangsung di luar negeri, ketika putusan arbitrase diucapkan dan pihak yang kalah dalam proses tersebut adalah pihak dari Indonesia, maka hal ini akan berakibat pihak yang menang dalam proses arbitrase tersebut memohon pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut di Indonesia. Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan. Pengadilan-pengadilan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan melalui lembaga arbitrase. Pengadilan diminta campur tangan manakala proses arbitrase telah selesai dan salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut3. Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya4, melainkan lembaga pengadilan 2 Sudargo Gautama (a), Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 1. 3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata Internasional, cetakan kedua, (Jakarta : N.V. Van Dorp & Co, 1954), hal. 74. 4 Lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan: 83 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 yang harus memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut5. Dalam prakteknya, pengadilan dapat sewaktu-waktu campur tangan dalam hal pemeriksaan proses arbitrase sedang berjalan. Campur tangan pengadilan itu bisa berupa menunjuk arbiter ketiga, apabila dua arbiter pertama gagal menunjuk arbiter ketiga. Bentuk campur tangan yang lain misalnya membantu proses arbitrase mendapatkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Berbeda dengan arbitrase, mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing, kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing. Kecenderungan ini berlaku di negara-negara yang menganut sistem Civil Law dan sistem Common Law. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep 1. Lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga lembaga tersebut tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain; 2. Tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri; 3. Lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi. Lihat: Tin Zuraida, Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, Teori dan Praktek yang Berkembang, cetakan pertama, (Surabaya: PT. Wastu Lanas Grafika, 2009), hal. 222. 5 Di dalam Konvensi New York 1958, diatur mengenai peran pengadilan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Peran Pengadilan ini dapat dilihat juga di dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration yang menjadi rekomendasi Majelis Umum PBB kepada para anggota pada tahun 1985 sebagai standar hukum yang modern dalam arbitrase. Dibeberapa negara, campur tangan Pengadilan dimungkinkan pada waktu proses arbitrase sedang berjalan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan. Di Singapura, pengadilan dapat mengenyampingkan putusan arbitrase dalam keadaan-keadaan yang amat terbatas, dengan mengangkat ketentuan-ketentuan yang sama dengan Model Law. 84 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kedaulatan negara. Sebuah negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali negara tersebut sukarela menundukkan diri. Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada pada suatu negara, maka wajar apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing. Pendirian ini sesuai dengan asas kedaulatan territorial (principle of territorial souvereignty), berarti keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri. Dengan tidak adanya perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain, tidak dapat diadakan pelaksanaan keputusan-keputusan asing di wilayah RI (Pasal 436 RV). Pelaksanaan putusan arbitrase internasional mendapat pengaturan dalam perjanjian internasional karena dalam hukum internasional dikenal adanya kedaulatan dan yurisdiksi. Pelaksanaan yurisdiksi kekuasaan negara hanya dapat dilakukan di wilayah teritorialnya. Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara di negara lain harus seizin otoritas yang berwenang di negara lain tersebut. Putusan arbitrase internasional yang dibuat di suatu negara dan hendak dilaksanakan di negara lain, maka harus ada pengakuan dan pelaksanaan dari negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan. Oleh karena itu pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan dalam bentuk perjanjian internasional, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk perundang-undangan nasional6. Sejak Indonesia menjadi anggota Konvensi New York 1958 pada tahun 1981, pada kurun waktu sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan 6 Hikmahanto Juwana (a), “Pembatalan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional”, dalam Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 21, Oktober-November 2002), hal. 72. 85 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Perma), masih terdapat hambatan-hambatan bagi pelaku usaha asing dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia berpendirian bahwa putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI yang menolak eksekusi putusan arbitrase internasional pada perkara PT Nizwar vs. Navigation Maritime Bulgare7, putusan Mahkamah Agung RI No.2944 K/Pdt/1983 yang diputus pada tanggal 29 November 1984. Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak dapat diterima, karena belum ada peraturan pelaksana mengenai ketentuanketentuan yang terdapat dalam Konvensi New York 1958. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat, yang menerima pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sikap Mahkamah Agung RI pada saat itu tetap menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional, walaupun saat itu Indonesia sudah menjadi anggota Konvensi New York 19588. Menurut Sudargo Gautama, Konvensi New York 1958 bersifat self executing, artinya tidak diperlukan lagi suatu peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, karena di dalam konvensi tersebut tercantum bahwa cara pelaksanaan putusan arbitrase yang diucapkan di luar negeri ini adalah sama dengan cara pelaksanaan arbitrase yang diucapkan dalam negeri anggota peserta konvensi. Hal tersebut seperti yang tercantum di dalam Pasal III Konvensi New York 1958 yang menyatakan: 7 Erman Rajagukguk (Lihat: Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), hal. 38-40. 8 Sudargo Gautama (b), Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 2. 86 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 ”Each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the condition laid down in the following articles. There shall nor imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbiral to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards”. (Terjemahan bebas dari penulis: Setiap negara anggota dapat mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan tata cara di wilayah dimana putusan tersebut dimintakan, sesuai dengan keadaan yang diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Tidak diperbolehkan mengenakan secara substansi yang lebih berat atau lebih tinggi biaya untuk pengakuan dan pelaksanaan putuan arbitrase yang diterapkan dalam konvensi ini dari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik/nasional). Contoh lain mengenai penolakan putusan arbitrase internasional oleh Mahkamah Agung RI terlihat pada perkara PT. Bakrie Brothers vs. Trading Corporation of Pakistan Limited. Pakistan Trading yang berkedudukan di Karachi Pakistan, telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, Award of Arbitration yang ditetapkan oleh Federation of Oils, Seed and Fats Association Limited, No. 2282 tanggal 8 September 1981 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT. Bakrie Brothers yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Permohonan mana telah dikabulkan dengan Ketetapan Eksekusi No.fol.22/48/JS/1983 tanggal 13 Februari 19849. Namun pihak PT. Bakrie Brothers mengajukan 9 Dalam kasus ini, Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan asas resiprositas yang dianut di dalam Konvensi New York 1958. Untuk mempelajari perkara ini, lihat: Tineke L.T. Longdong, Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 227. 87 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 bantahan. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima bantahan dari Pihak PT Bakrie Brothers yang mendalilkan, bahwa putusan arbitrase asal London tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena diajukan oleh perusahaan asal Pakistan (yang bukan anggota peserta Konvensi New York 1958) sehingga tidak memenuhi asas resiprositas yang dianut di dalam Konvensi New York 1958. Dan bantahan tersebut diterima oleh Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Kemudian Mahkamah Agung RI menguatkan putusan-putusan yang lebih rendah tingkatannya yang menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Contoh lain dapat dilihat pada perkara Safic-Alcan & Cie, vs. PT Foursa Tani Nusa. Sengketa ini adalah antara Alcan yang berkedudukan di Perancis, Pemohon (Pembeli) lawan Foursa Tani berkedudukan di Surabaya, sebagai Termohon (Penjual) yang mengadakan jual beli 20.000 metric tonnes Indonesian tapioce chips, yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Foursa Tani, sehingga dituduh ingkar janji. Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 1993 karena adanya bantahan yang diajukan oleh PT Foursa Tani Nusa, maka pelelangan eksekusi atas aset PT tersebut, sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 065/1992 Eks ditangguhkan10. Contoh perkara lain adalah antara Sikinos Maritime Ltd., vs. PT Perdata Lot. Memorandum of Agreement, tanggal 20 September 1991, antara PT Perdata Lot, berkedudukan di Jalan Sutomo 540, Medan Indonesia, sebagai Penjual dan Sikinos Maritime Ltd., berkedudukan di Vallette Malta, telah melakukan jual beli kapal “M.T. BUMEUGAH”. Permohonan akan fiat eksekusi ini meskipun telah dipertimbangkan bahwa putusan arbitrase ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang 10 Ibid., hal. 238. 88 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 US$ 617,046 berikut bunga 6,5% per tahun sejak 15 Desember 1991, sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, namun permohonan exequatur ditolak oleh Mahkamah Agung11. Penolakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI ini telah memberi kesan buruk, mengingat tatacara/prosedur sudah dilakukan oleh pelaku usaha dan juga tidak ada ketertiban umum yang dilanggar. Salah satu contoh perkara yang ditolak pelaksanaan putusan arbitrase internasionalnya karena melanggar ketertiban umum adalah perkara Yani Haryanto vs. E.D.& F.Man (Sugar) Ltd12 (perusahaan yang berkedudukan di Inggris). E.D. & F. Man (Sugar) Ltd (dalam hal ini sebagai Penjual) telah memperoleh suatu putusan arbitrase dari The Council of the Refined Sugar Association, Arbitration Center di London yang telah menyalahkan pihak Yani Haryanto (sebagai pembeli) telah melakukan default dalam melangsungkan kontrak pengimporan atau pembelian gula pasir untuk diimpor ke Indonesia. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak Yani Haryanto mengajukan gugatan perdata melawan pihak E.D. & F Man sebagai Penjual yang berkedudukan di London. Penggugat mendalilkan dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 1988 bahwa kontrak bersangkutan adalah bertentangan dengan Keppres RI No.43/1974 tanggal 14 Juli 1971 mengenai “penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang pengadaan penyaluran dan pemasaran gula pasir” dan keputusan Presiden RI No. 39/1978 tanggal 6 November 1978 Badan Urusan Logistik (selanjutnya disingkat dengan BULOG). Oleh karena itu menurut Pasal 1320 KUH Perdata ayat (4) agar perjanjian dianggap sah harus ada sebab 11 Ibid., hal. 239. Mahkamah Agung RI No. 1203K/Pdt/1990 jo. 736/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST jo.PT Jkt No. 485/Pdt/1989/PT DKI. 12 Perdata No. 89 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 yang halal (causa yang diperbolehkan). Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian jual beli bersangkutan dimana termuat klausula arbitrase itu adalah kontrak-kontrak yang mengandung cacat dan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia karena itu mempunyai sebab atau kausa yang dilarang, maka perjanjian jual beli gula itu harus dibatalkan. Menurut Pengadilan Negeri, karena dasar dari putusan hakim asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan tertib hukum di Indonesia, maka putusan-putusan hakim asing tersebut tidak mempunyai daya pengikat13. Disamping beberapa contoh perkara di atas, ada pula beberapa contoh perkara yang diterima permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasionalnya, itu terjadi setelah keluarnya Perma. Perkara tersebut dapat dilihat pada Ecom USA Inc., vs. PT Mahameru Centratama Mills (Penetapan Mahkamah Agung RI No. 4 Pen.Ex’r/Arb.Int/Pdt/1992, 06-04-1994). Ecom USA Inc, perusahaan yang berkedudukan di DallasTexas, USA dalam sengketa ini telah bertindak sebagai Pemohon, yang diwakili oleh Executive Vice Presidentnya, Uwe Grobecker lawan PT Mahameru Centratama Mills yang berkedudukan di Bandung, sebagai Termohon14. Selain itu, juga terdapat perkara PT Tripatria Citra Pratama vs. Abdulelah Jamal Al Zamzani Est cs. Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan exequatur yang diajukan oleh Pemohon Citra Pratama, yang telah diajukan oleh Manajernya sebagai kuasa dari Direktur Utamanya terhadap para Termohon, Abdulelah Al Zamzani 13 14 Tinneke L. Longdong, Op. Cit., hal. 244. Ibid., hal. 231. 90 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Holdings Pte. Ltd., yang berasal dari Saudi Arabia (Penetapan Mahkamah Agung RI No. 1 Pen.Ex’r/Arb.Int/Pdt/1993, 3 Juni 199315. Dari beberapa contoh perkara di atas, dapat dikatakan bahwa setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia mulai mendapat kepastian, karena hukum acara yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional sudah jelas. Untuk mengatur pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, pada 12 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari XI Bab dan 82 Pasal. Pada Bab VI UU Arbitrase tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Perlu dilakukan kajian mendalam, apakah setelah berlakunya UU Arbitrase benar-benar tidak ada hambatan atau kendala lagi dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Mengingat bahwa setelah berlakunya UU Arbitrase, masih terdapat penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh Mahkamah Agung RI dengan alasan ketertiban umum, yaitu pada perkara Bankers Trust Company vs. PT Mayora Indah16 dan perkara Bankers Trust Company vs. The Jakarta International Hotel & Development Tbk. Selain 15 Ibid., hal. 231-235. PT Mayora Indah melawan Bankers Trust Company, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 489/PDT.G/1999/PNJS, tanggal 5 Oktober 1999. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 211/PDT/2000/PT DKI, tanggal 20 Juli 2000. Jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 001/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST., tanggal 3 Februari 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/Ex’r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000. 16 91 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 itu, ada pula beberapa putusan-putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan, namun belum mendapatkan penetapan eksekusi17. Di samping ada pula beberapa putusan arbitrase internasional yang telah diberikan penetapan eksekusi, antara lain pada perkara Noble Cocoa vs. PT Wahana Adhireksa Wiraswasta18, perkara Oceanis Shipping Ltd vs. Bp/ibu R. Adji Suryodipuro19, perkara Son Han Pil vs. Herman Tanuraharja (PT Saka Dhana Nugraha)20, perkara Balmac International Incorporation New York vs. Firma Sinar Nusantara21 dan beberapa putusan arbitrase internasional yang dianalisis dalam laporan penulisan ini. Setelah berlakunya UU Arbitrase, satu-satunya putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah putusan arbitrase asal Jenewa, Swiss (tanggal 18 Desember 2000), yaitu pada perkara Karaha Bodas Company (selanjutnya disingkat dengan KBC) vs. PT Pertamina dan PLN22. Kasus tersebut mengundang perhatian berbagai pihak di dalam dan di luar negeri, karena selain melibatkan beberapa saksi ahli dari berbagai negara, juga putusan 17 Antara lain Putusan Arbitrase London No. 6795, tanggal 15 Desember 2006, Putusan Arbitrase London No. 6796, tanggal 15 Desember 2006, Putusan Arbitrase Italia, No. 0408/0553, Livorno, 16 Agustus 2004, Putusan Arbitrase Singapura, SIAC No. 0057 of 2005, 20 Agustus 2007, Putusan Arbitrase London, tanggal 26 Februari 2007, Putusan London Maritime Arbitration Association, pendaftaran tanggal 16 Februari 2009. 18 Putusan Arbitrase The Cocoa Merchants Associated of Amerika Incorporation, 26 Oktober 1999, dengan Penetapan Eksekusi No. 143/2000, tanggal 4 September 2000. 19 Putusan Arbitrase London Intl Arbitration No. 775/1998, dengan Penetapan Eksekusi No. 05/2001, tanggal 16 April 2001. 20 Putusan Arbitrase Korean Commercial Arbitration International Board, no. 981130011, dengan Penetapan Eksekusi No. 25/2001, tanggal 18 April 2001. 21 Putusan Arbitrase The Cocoa Merchants Associated of America Inc, No. 00/04 dan 00/05, dengan penetapan eksekusi No. 44/2001 dan 45/2001. 22 Putusan No. 86/PDT-G/2002, tanggal 19 Agustus 2002, dengan Ketua Majelis Hakim H. Herri Swantoro, SH. 92 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 arbitrase tersebut dimohonkan pelaksanaannya oleh pihak KBC di beberapa negara, sehubungan dengan aset pihak PT Pertamina yang terdapat di beberapa negara23. Pembatalan putusan arbitrase Swiss oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 01/BANDING/WASITINT/2002, tanggal 8 Maret 2004. Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Pembatalan Putusan Arbitrase asal Swiss, maka pihak KBC kemudian menuntut ganti rugi kepada pihak PT Pertamina atas dasar pada perjanjian JOC/Joint Operation Contract dan perjanjian ESC/Energy Sales Contract yang telah dibuat pada tahun 1994. Salah satu kasus yang juga menjadi perdebatan para pihak mengenai putusan arbitrase tersebut apakah putusan arbitrase nasional atau internasional, terlihat pada kasus PT Pertamina dan PT Pertamina EP vs. PT Lirik Petroleum (Putusan No.01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2009). Dalam perjanjian dengan klausul arbitrasenya, para pihak memilih tempat arbitrase di Jakarta dengan rules dari ICC Paris. Dalam kasus tersebut, pada bagian eksepsinya pihak Pertamina sebagai pemohon mengajukan pembatalan putusan arbitrase sehubungan bahwa putusan arbitrase tersebut masuk dalam ruang lingkup arbitrase nasional, bukan putusan arbitrase internasional24. Pada tahun 2010, terdapat putusan arbitrase internasional asal Singapore International Arbitration Center/SIAC yang ditolak pelaksanaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta 23 Antara lain di Hongkong, Singapura, Texas dan Kanada. Dalam kasus diatas, pihak PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung No. 904 K/PDT.SUS/2009, tanggal 9 Juni 2010, telah menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 24 93 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 penolakan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu pada perkara Astro Nusantara Internasional B.V. vs. PT Ayunda Prima Mitra25. Kesimpulan dan Rekomendasi Jika mempelajari perkara-perkara di bidang arbitrase internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi New York 1958 belum maksimal di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa putusan arbitrase internasional yang ditolak pelaksanaannya di Indonesia. Selain itu, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih dirasakan mengandung beberapa kelemahan-kelemahan, sehingga perlu dilakukan revisi. Undang-Undang Arbitrase yang mengatur permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase yang lengkap dan komprehensif diperlukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Rekomendasi yang juga penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik untuk tingkat pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Tingkat Mahkamah Agung. Pemahaman serta penerapan Konvensi New York 1958 dan Hukum Perdata Internasional merupakan hal yang perlu ditingkatkan, mengingat Hukum Perdata Internasional merupakan basic knowledge dari permasalahan putusan arbitrase internasional. 25 Putusan Arbitrase SIAC No. 62 of 2008, tanggal 07 Mei 2009. Pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 5/PNJP/2009, tanggal 1 September 2009. Penolakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 28 Oktober 2009 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/Pdt.Sus/2010, tanggal 26 April 2010. 94 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 RESENSI BUKU Judul Penulis buku Penerbit Bahasa Jumlah halaman Tahun penerbitan Pembuat resensi : : : : : : : Hukum tentang Ekstradisi Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M Fikahati Aneska Indonesia x + 389 2011 AM. Sidqi Maraknya pemberitaan tentang upaya Kejaksaan Agung RI mengekstradisi Joko Tjandra, terpidana BLBI, dari Papua Nugini menghiasi media massa Februari 2013. Sebelumnya, pelarian M. Nazarudin dan Nunun Nurbaeti pada tahun 2011 lalu memunculkan perdebatan berlarut-larut tentang ekstradisi di kalangan penegak hukum, akademisi, politikus, dan masyarakat umum. Jamak dikatakan bahwa dikarenakan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, menjadikan Negara Singa Laut itu menjadi safe haven bagi pelarian kejahatan kerah putih. Akan tetapi, meskipun Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kolumbia, M. Nazarudin tetap bisa dibawa pulang ke Tanah Air untuk diadili. Selain itu, publik juga mengenal sengkarut upaya ekstradisi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap terpidana penyalahgunaan BLBI, Hendra Rahardja, dari Australia yang pada 95 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 akhirnya kasus pidananya gugur demi hukum karena Hendra Rahardja meninggal pada tanggal 26 Januari 2003. Perdebatan-perdebatan seputar hukum tentang ekstradisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang wajib dipahami oleh semua: apa dan bagaimana perkembangan hukum tentang ekstradisi tersebut? Untuk itu, buku “Hukum tentang Ekstradisi” yang ditulis oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M ini terbit timely untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat perihal definisi, karakteristik, dan perkembangan pelbagai model tentang ekstradisi. Disusun dalam bahasa Indonesia yang mudah sederhana membuat buku ini mudah dipahami oleh masyarakat awam hukum sekalipun. Selain itu, kepakaran Romli Atmasasmita sebagai salah satu ahli dalam hukum mengenai ekstradisi tidak lagi diragukan, mengingat Romli memiliki daftar panjang pengalaman sebagai ketua delegasi pemerintah Indonesia ke berbagai konferensi PBB yang membahas kejahatan transnasional. Berdasarkan UU 1/1979 tentang Ekstradisi, ekstadisi diartikan sebagai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka tau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memindananya. Perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan tentang ekstradisi serta terlibatnya dua negara atau lebih dalam suatu kasus ekstradisi, menunjukkan bahwa ekstradisi dapat dipandang sebagai bagian hukum internasional dan juga sebagai bagian hukum nasional. Oleh karena itu ekstradisi sebagai suatu pranata hukum secara resmi telah diakui dan diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Praktik perjanjian ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah hukum baru karena setelah kemerdekaan RI, Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi dengan lima negara, yakni Malaysia, Filipina, Thailand, Australia; dua perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam 96 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Masalah Pidana (mutual legal assistance treaty), yakni dengan Australia dan RRT; dan satu perjanjian penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri antara Indonesia dengan Hongkong. Buku yang terbit pada tahun 2011 ini disusun dalam empat bab, yakni asal-usul dan karakteristik ekstradisi (bab I); prinsip umum ekstradisi yang diakui dalam hukum internasional dan beberapa pengecualian (bab II); perkembangan praktik ekstradisi dan perbandingan model-model ekstradisi (bab III); dan pentutup yang berisi pandangan dan sikap penulis terhadap perkembangan ekstradisi dan masalah yang berkaitan dengan berbagai model hukum tentang ekstradisi (bab IV). Romli Atmasasmita mengkritik pengertian ekstradisi yang sering diucapkan banyak orang termasuk praktisi hukum, tetapi belum dipahami makna sesungguhnya dari pengertian istilah tersebut. Sering disebutkan bahwa ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (extradition, l’extradition) berasal dari bahasa latin, yaitu “extradere”. Ex berarti keluar, sedangkan tradere berarti menyerahkan. Kata bendanya adalah extraditio artinya penyerahan. Sedangkan menurut Romli, pemaknaan pengertian istilah tersebut sangat menyesatkan karena tidak benar. Romli mendefinisikan ekstradisi secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu “extra” dan “tradition”. Sehingga demikian, ekstradisi berarti suatu konsep hukum yang berlawanan dengan “tradisi” yang telah berabad-abad dipraktikan antarbangsa-bangsa. Praktik tradisi tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi pelindung (asylum) bagi siapa saja yang memohon perlindungan, dan tradisi untuk memelihara kehormatan (hospitality) sebagai negara tuan rumah atas mereka yang memohon perlindungan tersebut. Praktik asylum yang mendahului ekstradisi menunjukan bahwa ekstradisi merupakan kekecualian dari asylum. Dalam catatan sejarah, ekstradisi telah dipraktikan sejak tahun 1280 SM antara Raja Ramses II dari Mesir dan Raja Hattusili III dari Hitites, 97 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 kemudian diikuti oleh kerajaan Yunani dan kekaisaran Romawi. Model perkembangan ekstradisi abad tersebut dilandaskan untuk menjaga stabilitas politik kerajaan sehingga ekstradisi terbatas pada kejahatan politik. Dalam perkembangannya, ekstradisi pasca abad ke-20 bukan lagi semata-mata merupakan hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam suatu perjanjian, melainkan juga bagian dari hak asasi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menyatakan pendapatnya terhadap permintaan suatu negara untuk mengekstradisikan ybs. Hal tersebut pernah dipraktikan oleh Hendra Raharja yang menolak ekstradisi dirinya dari Austarlia dengan alasan Pemerintah Indonesia diskrimatif dan tahanan di Indonesia tidak menjamin keselamatan tersangka. Perkembangan ekstradisi sejak awal kelahirannya pada abad 15—16, disepakati bahwa yang dapat diekstradisikan hanya kejahatan politik (makar) dan kejahatan penodaan terhadap agama. Perkembangan ekstradisi selama tahun 1700 dan awal 1800an, justru kejahatan politik termasuk kejahatan tidak dapat diekstradisi (non-extraditable crime) sampai dengan tahun 1830-an. Gagasan bahwa tersangka tidak dapat diekstradisikan untuk tindak pidana yang memiliki motivasi politik, dikemukakan oleh Belgia dan Perancis. Pengakuan tersebut dikuatkan di dalam MLE UN 1990 yang menegaskan bahwa, kejahatan politik merupakan kejahatan yang tidak dapat diekstradisi-kan dan bersifat wajib (mandatory obligation). Prinsip penolakan atas dasar kejahatan politik dewasa ini semakin sirna terutama dengan peristiwa terorisme pemboman World Trade Centre di New York, Amerika Serikat. Kasus ekstradisi mantan PM Thailand, Thaksin Sinawatra, merupakan contoh teranyar (2009) yang mencerminkan prinsip penolakan ekstradisi dengan alasan kejahatan politik masih menguat di dalam hubungan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional. Kasus Thaksin mirip dengan permohonan ekstradisi mantan Presiden Peru Alberto Fujimori. Permohonan Peru kepada Chile untuk mengekstradisi 98 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Fujimori tidak begitu terkendala, karena pengadilan Chile melihat dakwaan terhadap Fujiori murni didasarkan pada pelanggaran korupsi dan pelanggaran HAM. Akhirnya, buku mengenai hukum ekstradisi merupakan substansi yang relatif baru dalam kepustakaan hukum Indonesia, meskipun praktik dan perjanjian ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah hukum baru. Masih sering dijumpai bahwa masih ada yang keliru menyamakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters) baik di kalangan pejabat tinggi pemerintah maupun para sarjana hukum. Dengan terbitnya buku ini, maka diharapkan dapat menjernihkan pemahaman ekstradisi bagi para sarjana hukum, terutama yang sehari-hari menggeluti hukum internasional, dan masyarakat pada umumnya. 99 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 ISTILAH HUKUM Kemal Haripurwanto Rebus sic stantibus The clausula rebus sic stantibus (Latin for "things thus standing") is the legal doctrine in public international law allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an "escape clause" that makes an exception to the general rule of pacta sunt servanda (promises must be kept). Klausul rebus sic stantibus (Dalam bahasa Latin yang berarti “keadaan yang tidak berubah”) merupakan doktrin hukum dalam hukum internasional publik yang memungkinkan perjanjian inetrnasional menjadi tidak bisa diaplikasikan karena adanya suatu perubahan keadaan yang mendasar. Pada dasarnya, klausul ini merupakan “klausul pembebasan” yang mengecualikan diterapkannya ketentuan umum pacta sunt servanda (janji harus ditepati). Laissez Faire, Laissez Passer These two formulas, which are frequently met with in economic, political, social and socialistic discussions, were invented by the physiocrates. By laissez faire they mean simply let work, and by laissez passer, allow exchange; in other words, the physiocrates demand, by these phrases, the liberty of labor, and the liberty of commerce. Kedua formula ini, yang sering ditemui diskusi-diskusi ekonomi, politik, social dan sosialistik, diciptakan oleh kelompok yang dinamakan physiocrates. Laissez faire berarti “biarkan bekerja”, dan laissez passer berarti dipersilahkan melakukan pertukaran; dengan kata lain kelompok physiocrates menuntut adanya kebebasan perburuhan dan kebebasan perdagangan. Money laundering The federal crime of transferring illegally obtained money through legitimate persons or accounts so the its original source cannot be traced. Kejahatan mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal melalui orang atau rekening yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri. 100 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Due prosess of law A fundamental, constitutional guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard before the government acts to take away one's life, liberty, or property. Suatu jaminan dasar yang diberikan konstitusi bahwa semua proses hukum akan dilaksanakan secara adil, dan bahwa seseorang akan diberitahu mengenai proses yang berlangsung dan diberitahu mengenai kesempatannya untuk didengar sebelum pemerintah bertindak untuk mengambil nyawa, kebebasan, atau property seseorang. Locus delicti The place where the tort, offence, or injury has been committed. Tempat di mana kesalahan, pelanggaran atau tindakan yang mengakibatkan kerugian telah dilaksanakan. Tempat terjadinya perbuatan pidana. Tempus delicti Tempus Delicti yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi waktu terjadinya perbuatan pidana. Ius ad bellum Jus (or ius) ad bellum is the title given to the branch of law that defines the legitimate reasons a state may engage in war and focuses on certain criteria that render a war just. The principal modern legal source of jus ad bellum derives from the Charter of the United Nations, which declares in Article 2: “All members shall refrain in their international relations from the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations”; and in Article 51: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations.” Yakni seperangkat ketentuan yang harus diterapkan sebelum peperangan dimulai untuk menentukan justifikasi atas dilakukannya kekerasan bersenjata atau apakah kekerasan bersenjata tersebut dapat dibenarkan 101 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 atau tidak. Untuk mengetahui justifikasi suatu kekerasan bersenjata, dapat dilihat Bab VII Piagam PBB 1945. Ius Bello Ius in bello is the set of laws that come into effect once a war has begun. Its purpose is to regulate how wars are fought, without prejudice to the reasons of how or why they had begun. So a party engaged in a war that could easily be defined as unjust would still have to adhere to certain rules during the prosecution of the war, as would the side committed to righting the initial injustice. This branch of law relies on customary law, based on recognized practices of war, as well as treaty laws (such as the Hague Regulations of 1899 and 1907), which set out the rules for conduct of hostilities. Other principal documents include the four Geneva Conventions of 1949, which protect war victims Ius in bello yakni seperangkat ketentuan yang berlaku ketika telah terjadi peperangan dan menentukan bagaimanakah alat dan cara berperang serta perlindungan para korban perang harus dilakukan. Untuk mengetahui ketentuan ini, dapat dilihat ketentuan-ketentuan pokok Hukum Humaniter yang terdapat dalam Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Ius gentium The ius gentium or jus gentium (Latin, "law of nations") is a concept of international law within the ancient Roman legal system and Western law traditions based on or influenced by it. The ius gentium is not a body of statute law or a legal code, but rather customary law thought to be held in common by all gentes ("peoples" or "nations") in "reasoned compliance with standards of international conduct." Ius gentium atau jus gentium (Latin, "hukum bangsa-bangsa") adalah sebuah konsep hukum internasional dalam sistem hukum Romawi kuno dan tradisi hukum Barat didasarkan pada atau dipengaruhi olehnya. Ius gentium bukanlah undang-undang atau kode hukum, tetapi hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat bangsa. 102 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 TENTANG PENULIS Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum Edward Omar Sharif Hiariej merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Lahir di Ambon, 10 April 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum dari UGM (1998), Master Hukum UGM (2004), dan Doktor Hukum UGM (2009), serta dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Pidana pada 2012. Dapat dikontak melalui [email protected]. Damos Dumoli Agusman, SH., MA, Setelah menyelesaikan studi hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1987, penulis memulai kariernya di Kementerian Luar Negeri. Melalui Kementerian ini penulis kemudian menempuh pendidikan lanjutan di University of Hull Inggris dan berhasil meraih gelar Master di bidang Hukum Internasional dan Politik pada tahun 1991. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum internasional demikian besar sehingga pada tahun 1995 menyempatkan diri untuk mengikuti program hukum internasional pada The Hague Academy of International Law, Den Haag, Belanda. Penulis menduduki jabatan Direktur Perjanjian ekonomi dan Sosial Budaya pada Kementerian Luar Negeri tahun 2006-2010. Saat ini penulis bertugas sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Purna Cita Nugraha, SH., MH. Lahir di Langsa pada 4 November 1986. Merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurusan Hukum Pajak Angkatan 2004, menyelesaikan S2 pada Magister Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran (2010), dan saat ini sedang dalam proses menyelesaikan studi S3 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bergabung dengan Kementerian Luar Negeri RI pada 2009, mengikuti Sekolah Dinas Luar Negeri angkatan XXXV, dan kini menjadi staf Sekretariat Wakil Menteri Luar Negeri, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri RI. 103 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Harry Purwanto, SH., MH. Pengajar hukum internasional di Universitas Gadjah Mada. Memperoleh S1 dari UGM, S2 dari Universitas Padjajaran, dan kini tengah menempuh pendidikan doktoral di UGM. Berpengalaman aktif dalam banyak penelitian di lingkungan FH UGM, seperti “Pertanggungjawaban Negara Tuan Rumah Terhadap Penyerangan Gedung Perwakilan Diplomatik” (2012), “Perlindungan Bagi tawanan Perang Korban Pertikaian Bersenjata dalam Perspektif Hukum Islam” (2012), “Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri” (2011), dan sebagainya. Dapat dihubungi melalui [email protected] Dr. Mutiara Hikmah, SH., MH. Lahir di Jakarta pada 21 Januari 1970. Dosen Tetap di Fakultas Hukum UI sejak Mei 1996, saat ini menjabat Lektor Kepala dengan Pangkat/Golongan IV-b. Menamatkan pendidikan SH (1995), MH (2002), Doktor di FH UI (2003), dan Doktor di Universitas Pelita Harapan (2010). Penulis aktif mengikuti training, workshop, dan konferensi nasional maupun internasional dalam bidang HAM, Hukum Arbitrase, dan Hukum Humaniter. Penulis juga aktif menulis di dalam Jurnal-jurnal ilmiah, antara lain Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Keadilan dan Jurnal Hukum Internasional. Buku-buku yang pernah ditulis, antara lain ”Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Pada Perkara-Perkara Kepailitan” (Penerbit Refika Aditama, 2007) dan “Bunga Rampai Hukum Antar Tata Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Penerbit Fakultas Hukum UI, 2011). 104 JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013 Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional OPINI O JURIS Jurnal Opinio Juris menerima tulisan dengan tema hukum internasional, perjanjian internasional, diplomasi, hubungan internasional, dan isu-isu dalam negeri yang memiliki dimensi hukum dan perjanjian internasional. Ketentuan Penulisan: 1. Panjang tulisan 10—20 halaman kertas A4 (termasuk abstraksi, isi, catatan kaki, dan daftar pustaka), format MS Word, spasi satu setengah, font Book Antiqua 11. Untuk catatan kaki, spasi satu dan font Times New Roman ukuran 10; 2. Tulisan dapat dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; 3. Setiap naskah harus disertai abstraksi dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Jumlah kata abstraksi sekitar 100 kata. 4. Rujukan dibuat dalam bentuk catatan kaki (footnote); 5. Tulisan harus asli dari penulis, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dikirimkan ke penerbit lain; 6. Untuk setiap naskah yang masuk, redaksi berhak mengedit dengan tidak mengubah maksud dan isi tulisan; 7. Apabila diperlukan, redaksi akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada penulis tentang tulisan yang dikirim; 8. Setiap naskah yang dikirim harus disertai daftar riwayat hidup singkat penulis (curriculum vitae) yang setidak-tidaknya terdiri dari pekerjaan, pendidikan, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi; 9. Setiap naskah yang disetujui untuk diterbitkan akan mendapatkan kompensasi finansial; 10. File naskah beserta kelengkapan lainnya dapat dikirim ke email Redaksi. Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Interansional Kementerian Luar Negeri Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat Telp: +62 21 3846633 Fax: +62 21 3858044 Email: [email protected] http://pustakahpi.kemlu.go.id/ 105