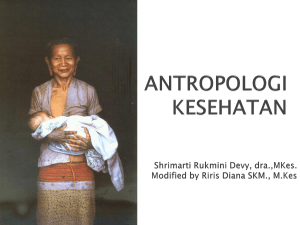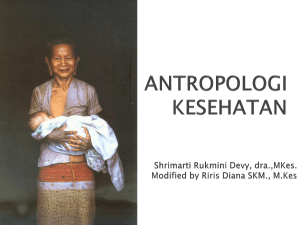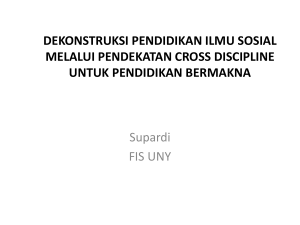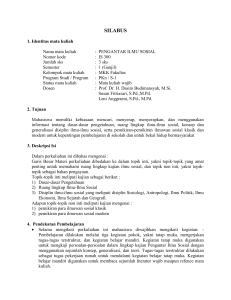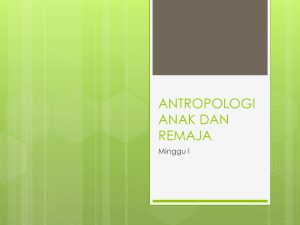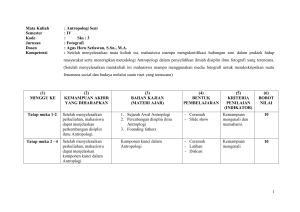SEBUAH `KEGILAAN` BARU: Antropologi sebagai Hal Gila yang
advertisement

SEBUAH ‘KEGILAAN’ BARU: Antropologi sebagai Hal Gila yang Menarik Oleh: Kasyfiyullah ‘kesepz’ (0806481803) Tulisan ini dibuat sebagai tugas untuk Ujian Akhir semester Mata kuliah Metode Penelitian Antropologi Perkenalan dengan Antropologi Terbangun pagi di sebuah kamar berukuran 3x3 yang sudah saya tinggali sekian lama dengan tergagap dan secara otomatis melihat jam dinding di sebelah utara kamar yang menunjukan pukul 6.30. kamar tidur kecil dan agak pengap dengan tempelan banyak foto dan poster di sebelah barat, ditempel di atas keramik bekas dapur dan lemari pakaian besar yang menutupi dinding kamar sebelah timur. Apa yang pertama terlintas di kepala adalah hitungan waktu perjalanan rumah-depok untuk mengukur seberapa lama perjalanan agar tidak telat sampai di kampus hari pertama kuliah, ya!? seperti itulah kurang lebih apa yang adad di pagi hari kedua bulan februari untuk menghadapi sebuah kegilalan baru yang dimulai hari itu. Kegilaan tersebut adalah kembali berstatus mahasiswa aktif pasca sarjana antropologi UI yang memang bahkan sebelumnya hamper tidak terlintas di kepala mengenai antropologi. Begitulah cara diri saya memandang realitas yang sayaa jalani selama ini. Hanya ada dua hal yang berlaku di dunia saya. Yaitu ‘Kesenangan’ dan ‘Kegilaan’. Kesenangan bagi saya dalam pandangan banyak para penganut agama di Indonesia disebut dengan rezeki sedangkaan dalam bahasa lain yang seringkali digunakan oleh para Marxist mengenai proui yaitu sebuah need satisfaction yang bagi saya ‘need’ tidak hanya berupa kebutuhan biologis melaainkan mental need dan kesenangan yang ada dalam cara saya memandang hidup saya adalah mental satisfaction dalam banyak hal. Sedangkan cara pandang saya yang kedua adalah ‘kegilaan’ yang tidak berarti sebagaimana arti gila pada umumnya melainkan bahasa kiasan yang saya gunakan sebagai pengganti dari sebuah tantangan, ‘cobaan’ atau ketidaksenangan dalam hidup. Sebagai alas an yang cukup klise adalah bahwa cara pandang saya ini sebagai bentuk dari usaha saya menghindari apa yang disebut dalam bahasa para penganut agama dengan ‘kufur’ atau pengingkaran, pengingkaran terhadap ‘cobaan hidup’ atau pengingkaran terhadap realitas yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Ya begitulah saya memandang dunia saya sampai saat ini. Seperti pada pagi lainnya dengan ritual yang sepertinya akan mulai berubah setelah hari ini, ritual pagi yang cukup umum dilakukan banyak orang, bangun pagi, ibadah bagi orang islam kemudian mandi dan bersih-bersih serta siap-siap untuk menuju kesesuatu tempat yang hari ini tujuan telah ditetapkan dua minggu sebelumnya, yaitu ke Depok dan tujuan lebih tepat adalah kampus Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia karena telah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa pada hari kedua Februari ini diadakan kumpul hari pertama kegiatan kuliah dan perkenalan kepada anggota baru Antropologi sebagai sebuah komunitas. Pada pagi ini juga seperti kebanyakan perjalanan yang saya telah jalani, jalur perjalanan baru berarti peta baru berarti menjadi sebuah perhatian baru bagaimana agar bisa sampai UI dengan waktu yang terukur mencegah ‘ketidak cocokan’ dengan paraturan yang ada, untuk itu saya sebagai seorang pengendara mulai menghitung perkiraan jarak dan waktu tempuh paling tidak dengan keadaan pagi dan sebagai sedikit pembuktian dari hipotesa prakiraan waktu tempuh yang telah saya coba hitung pagi tadi. Dan aka nada tambahan ritual hamper setiap hari yang ditambahkan dalam kegiatan harian, yaitu pergi ke kampus untuk mengikuti mata kuliah pada semester ini. Perjalanan ke Depok pun cukup lancar walaupun perjalanan Senin pagi karena memang khusus hari ini ada pertemuan jam 9 dengan para akademisi Antropologi lainnya dan ‘orientasi’ mengenai perkuliahan di Pascasarjana Antropologi. Pertemuan para civitas akademika Pasca-antrop dimulai jam 10an lewat yang berarti molor karena memang cukup banyak peserta yang datang agak terlambat. Orang pertama yang saaya kenal dalam pertemuan tersebut adalalh sdri. Tina Napitupulu yang kemudian berkenalan dengan bu Ike dan mas Andi Achdiyan. Setelah cukup banyak peserta yang daatang, acara dilaksanakan di gedung PAU ruang 304, ruang yang cukup besar dan dingin. Dipandu oleh Ketua Program Pasca-Antropologi dan Sekretaris program, ibu Sulis dan pak Tony. Acara dimulai dengan perkenalan satu persatu civitas akademik yang dimulai oleh ibu Sulis dan pak Tony yang kemudian dilanjutkan dengan para mahasiswa yang duduk di bangku paling depan dengan poin perkenalan nama, panggilan, lama menjadi mahasiswa pasca, asal program studi pada jenjang sebelumnya dan alas an menjadikan Antropologi sebagai pilihan kuliah. Setibanya giliran saya memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri dengan nama Kasyfiyullah dan menekankan kepada nama panggilan sebagai Kesep karena bagi saya sendiri nama panggilan tersebut sudah sangat melekat semenjak kelas dua Mts (setara dengan SMP) dan cukup mudah untuk diingat disbanding denga nama asli saya yang terlalu ‘arab’ dan dengan penyebutan yang cukup sulit hingga menyebabkan kesalahan panggil seperti hasbi, kasip, kasbi, kasyif, sampai kasti dan banyak ‘plesetan’ lainnya dari nama asli saya. Jadi saya kira lebih sederhana dengan nama kesep dan terkadang saya menganggap kesep sebagai identitas kedua saya. Kemudian sampai pada penyampaian alas an saya memilih Antropologi sebagai studi lanjut saya setelah sebelumnya saya mempelajari Filsafat sebagai studi tingkat sarjana di UGM. Mengenai alas an memilih Antropologi ini, kepala saya melayang kepada kejadian setahun sebelum hari perkenalan tersebut. Dengan sseting jalan raya Kuningan, sepulang saya dari ‘base camp’ kepanitiaan acara International Youth Forum 2008 lalu. Diatas motor sebagai pengendara bersama kakak saya –dengan posisi sebagai pembonceng- (yang saat itu baru menjadi Mahasiswa Pascasarjana di Sosiologi pedesaan IPB) memulai pembicaraaan mengenai kebingungan saya untuk memilih studi apa untuk jenjang Pascasarjana dengan ilustrasi obrolan seperti ini Kakak saya=K Saya= S *masing-masing dengan logat berbicara orang Betawi yang cukup kental K: *dengan berteriak karena jalan yang cukup ramai dan angin yang memendam suaranya “gimana pih? Lo jadi mo s2? Jadinya mo ngambil jurusan apa?” S: *dengan sedikit kaget karena saat itu agak malas untuk membahas mengenai studi s2 dan juga sambil berteriak karena alas an yang sama dengan kakak saya “kaga tau gw, masih bingung..mo ngambil apa ya?” *sambil tetap memperhatikan jalan K: “lah elu gimana sih? Khan yang mo kuliah juga elu, emang lo tertariknya apa?” S: “au dah…bingung juga nul, gw sih pengennya yang deket aja, kaga usah jauhjauh kaya s1 kemaren di Jogja, nah! Pengennya sih ambil Design Grafis di ITB Bandung” K: “alesannya?” S: “gw pengen seriusin design nul..khan lebih enak tuh klo hoby bisa jadi profesi, lebih seru, lagian design yang bener bagus dmn?? Bukannya di ITB yang bagus?” K: “yah..sebenernya terserah lo, emang klo filsafat lagi kenapa?” S: “waduh…kaga dah, klo gw sih mikirnya, filsafat itu harus di dukung sama kemampuan teknis karena filsafat kan Cuma bermain disekitar konsep aja nul, mo ngapain coba klo cm ngandelin filsasfat? Jaajdi orang gila iya..filsafat klo berdiri sendiri kaga bisa apa-apa nul, hamper sia-sia, paling Cuma wat diri sendiri…” K: “owh,,,ya terserah lu juga sih…tapi dulu lo belajar tentang kebudayaan gak?” S: “iya, ada Filsafat Kebudayaan dulu di Filsafat. Emangnya kenapa?” K: “nah lo sama pembahasan mengenai kebudayaan demen kaga?” S: “gw sih demen, karena banyak juga maen konsep n ritual gitu, apalagi dulu gw banyak ngebahas betawi, ya seru juga ngebahas budaya. Emang kenapa?” K: “ya kaga…gw ada usul aja, kenapa lo kaga ambil Antrop aja? Emang lo kaga tertarik sama antrop?” S: “hmmm..gimana ya?gw sih kaga kepikiran, emang kebudayaan apa??emang ngebahas yang mananya dari kebudaayaan?” K: “ya kurang lebih hamper sama ama Sosiologi, cuma antrop lebih kepada kebudayaan aja” S: “owwhhh…” S: “ya liat aja dah nanti, gw masih bingung juga” *Dan pembicaraan pun berhenti dengan saya tetap konsentraasi pada jalanan dan kakak saya yang juga sibuk dengan dirinya sendiri Dari kejadian tersebut merupakan ‘entry point’ bagi saya secara pribadi mengenai Antropologi dan mulai menyusupi kepala saya sebagai pilihan tambahan untuk kelanjutaan studi saya, begitu juga pada bulan Juli 2008 saya dan kakak saya pergi ke UI untuk ‘survey’ atau pengambilan data atau bahan untuk memperlengkap pertimbangan dan perbimbangan saya mengenai studi S2 yang akan saya ambil, pada saat itu saya mengungjungi pasca antrop untuk mengambil contoh mata kuliah yang ada dan daftar biaya masuk, begitu juga saya menuju FIB UI untu mencari informasi mengenai program pascasarjana Filsafat, dan Sejarah serta mencari informasi di UI salemba untuk kajian Timur-Tengah, kajian Eropa, dan kajian Lingkungan. Dari apa yang saya miliki informasinya, saya mencoba memilih studi apa yang bagi saya cukup ‘logis’ untuk saya jalani, baik dari pembahasan, keuangan, dan kemampuan pribadi termasuk pertimbangan untuk mengambil Design Grafis di ITB. Dan ternyata, saya menyimpulkan bahwa memilih adalah hal yang sulit dengan berbagai pertimbangan yang membuat kebimbangan semakin besar. Sebagai jalan selanjutnya, saya berusaha mengikuti saran dari kakak saya yang paling tua yang menganjurkan untuk bertanya kepada ‘Tuhan’ dengan melakukan Shalat Istikharah yang merupakan sebuah ritual ceremony shalat yang bertujuan untuk meminta tolong kepada tuhan untuk memberikan keyakinan dalam memilih beberapa hal, dari ritual agama tersebut beberapa kali saya mimpi mengenai Antropologi dan keinginan untuk menjadikan Antropologi sebagai pilihan studi S2 sayapun seakan menguat. Jika mengingat kejadian ini saya seakan terbawa kepada pembahasan dari Geertz dalam essaynya Religion as a Cultural System yang memang pernah saya bahas dalam kuliah Filsafat Agama pada masa S1 dahulu yang pada intinya saya pahami agama sebagai sebuah system symbol yang membangun mood dan motivasi serta membungkus semuanya dengan aura faktualitas. Terlepas dari posisi saya sebagai pemeluk agama, saya kira pembahasan kembali pada kuliah pak Tony mengenai agama ini mengingaatkan saya mengenai kejadian saya dan bagaimana agama bisa membangun motivasi dalam diri saya untuk menentukan sebuah pilihan tertentu. Dari kejadian yang saya kira bersifat metafisis religious ini menjadi alasan pamungkas saya kenapa saya memilih Antropologi sedangkan alasan pertama tergambar dari dialog dengan kakak saya di atas motor sseperti yang telah diilustrasikan diatas. Selanjutnya saya memperkenalkan alas an saya memilih antropologi sebagai studi S2 ini dengan 3 alasan yang saya katakana bertingkat (seperti tingkatn pengetahuan dalam banyak pembahasan epistemology) yang saya bagi kepada tiga tingkatan, yaaitu alas an dalam pemahaman saya sebagai common, alas an dalam tingkatan yang lebih logis dan alasan metafisis alas an dalam pemahaman umum adalah bahwa saya menyukai pembahasan mengenai kebudayaan bahkan semenjak saya berada di tingkatan SMA walaupun saya mengambil jurusasn keagamaan, kemudian alas an yang lebih logis adalah sedikit pengembangan dari alas an pertama yaitu hubungan antara Filsafat yang pada masa kini ‘sangat’ Anthropocentic yang memusatakana kepada pembahasan mengenai manusia dan juga banyaak membahas mengenai symbol walalupun banyak membahas dalam tataran konsep sedangkan Antropologi yang membahas kesemuanya itu dalam tataran yang lelbih empiris, dan bagi saya, memilih Antropologi berarti menjejakan kaki ke bumi. Sedangkan alas an terakhir adalah alas an metafisika yaitu ‘petunjuk’ tuhan melalui mimpi dan keyakinan yang sudah diberikan. Acara diteruskan dengan perkenalan para ’senior’ yang lelbih dulu berada di pasca-antrop dengan metode yang sama dan berarkhir sekitar pukul 12.00 dan dilanjutkan dengan pengenalan computer dan kuliah pertama Metode Penelitian Antropologi Persoalan pribadi, apa bedanya antara Filsafat dan Antropologi? Kuliah pertama kali adalaah Metode penelitian antropologi dengan Dosen pertama bapak Iwan Tjitradjaja. Kuliah dimulai pada jam 13.00 setelah orientais mengenai Computer dan bagaimana mendownload buku secara gratis oleh pak Purwono. Pada masa pertama kuliah ini, yang pertama didiskusikan selain silabi perkuliahan adalah perbedaan antara Teori dan konsep, selain itu bagi saya sebagai orang yang masih agak awam mengenai Antropologi mencoba memahami apa yang dibahas oleh pak Iwan dan saya mencoba mencerna apa yang di diskusikan di kelas adalah bahwa antropologi adalah keilmuan social yang radikal, reflektif, dan holistic. Pada saat itu saya masih dengan philosophy view yang telah saya pelajari berfikir bahwa ternyata antara filsafat dan antropologi tidak jauh berbeda. Baik filsafat maupun antropologi memiliki sifat keilmuan yang sama. Begitu juga pada kuliah hari berikutnya, dengan dosen yang sama, mata kuliah Konsep kebudayaan dalam kajian antropologi yang sayaa pahami dengan penekanan yang tidak jauh berbeda bahwa antropologi adalah keilmuan yang reflektif dan saya menjadikan refleksi sebagai kata kunci mengenai antropologi. Hanya saja, pemahaman mengenai antropologi sebagai keimun yng relekti ini menimbulkan pertanyaan dalam benak saya yaitu apa bedanya antropologi dengan filsafat karena jika ternyata ‘hampir’ sama, saya merasa bingung untuk apa saya belajar antropologi jika filsafat juga membahasa hal yang hamper sama, refleksi, holistic, kritis dan radikal. Pertanyaan ini bagi saya penting untuk saya jawab sebagai usaha memuaskan keraguan yang ada dalam benak saya. Paling tidak agar keraguan saya tidak berkembah lebih jauh bahkan berkembang ke arah yang negative. Pada kuliah pertama hari ke tiga, kuliah pak Tony saya memutuskan untuk mengungkapan keraguan yang saya alami dengan bertanya kepada pak Tony mengenai apa perbedaan antaara antropologi dengaan filsafat. Dan dosen menjawab dengan cukup ‘diplomatis’ dengan membedakan keduanya sebagai dunia konsep dan dunia empiris. Mendengar pertanyaan saya, kurang lebih seperti ini “perbedaan filsafat dengaan aantropologi adalah, bahwa filsafat ‘bermain’ dalam dunia konsep dan ide, sedangkan antropologi adalah ‘turunan’ dari konsep filosofis tersebut kedalam realitas, antropologi menerapkan konsep filosofis itu kedalam kehidupan social masyarakat dan juga sebagai ‘pembuktian’ terhadap konsep tersebut”. Jawaban yang dilontarkan terssebut memang tidak menjawab secara keseluruhan dari keingintahuan dan keraguan yang saya rasakan, haanya saja paaling tidak, keraguan saya terhadap antropologi sebagai ilmu yang berbeda dengaan filsafat tetapi paling tidak mempu menggeser keraguan tersebut menjadi rasa penasaran dan keinginan untuk tahu lebih dalam lagi mengenaia antropologi, juga sebagai ajang pembuktian bagi diri sendiri bahwa saya mampu menjejakan kaki kebumi. Mengenai problem pribadi ini menjadi persoalan tersendiri bagi pribadi seoraang Kesep dan bagi saya, akan saya coba menjawab sendiri dengan apa yang saya paahami mengenai antropologi. Obrolan konyol yang berubah menjadi ilmiah Obrolan konyol dalaam konteks yang saya maksud adalah obrolan, candaan, dan obrolan mengenai pengalaman pribadi dengan teman-teman sesame mahasiswa maupun dengan teman non-mahasiswa. Dalam banyak pengalaman pribadi, dalam interaksi dengan individu lain terutma dengan mahasiswa/i antropologi, ternyata banyak hal yang mengejutkan saya dan saya temukan bahwa antropologi sebagai sebuah keilmuan bisa dikatakan membahas haal yang sangat ‘cair’ dalam keseharian dan pergaulan. Pembahasan mengenai hal yang ‘cair’ tersebut tidak melulu menjadi sebuah konsep atau mungkin ‘sampah’ yang berlalu begitu saja melainkan memperkuat antropologi sebagai sebuah bidang keilmuan yang sangat empiris walaupun sebagai sebuah bidang keilmuan selalu berkutat dengan konsep dan teori. Bisa saya berikan salah satu contoh obrolan setelah kuliah hari rabu, kuliah Memahami Teks Antropologi yang diampu oleh pak Tony, seting kejadian di kantin Pascafe di pojok dalam kanan, obrolan terjadi antara tiga orang, saya (S), Tina (T), dan Anne (A): ……setelah makan dan minum, sambil bersendau gurau terjadi percakapan seperti ini: A: “duh…gw lagi bête negh, klo gini biasanya gw ngerokok, enak aja rasanya… paling nggak gw bisa santai lah…rokok lo apa sep?” S: “Dji Sam Soe Filter, kenapa emang? Lo mao??” T: “lah, emang lo ngerokok? Biasanya apa rokok lo An?” A: “waduh sep, rokok lo berat ah, males gw…biasanya gw rokok putih atau yang lebih enteng aja.” S: “owh…ya gimana?gw masuknya ya rokok beginian. Nah elu tin, ngerokok, mao?” A: “aneh ya emang klo gw ngerokok? Gw sih biasanya ngerokok dan gw ngerasa biasa aja, gw jujur klo gw ngerokok” T: “yaaelah…biasa aja kali, gw jugaa ngerokok koq. Dan gw de punyaa perjanjian sama cowok gw, klo die ngerokok ya gw juga boleh, dia nggak boleh protes” A: “ah..gw beli rokok dulu ya?” S: “yaudah gih..di Alfamart Hukum tuh” T: “iya deh sana” Dan Anne pun pergi (ngeloyor) menuju tempat beli rokok T: “emang kenapa yak lo cewe ngerokok?? Aneh apa ya?” S: “ah…gw sih biasa aja tin, lah di filsafat dulu de biasa banget liatnya” T: “iya dah elu mah…tapi kenapa orang lain susah ya?” padahal itu khan Cuma konstruksi social aja, emang kenapa klo cewe ngerokok? Cowok aja ngerokok kaga masalah..” S: “lah itu die tin…banyak yang musti dipertanyakan emang… tapi paling nggak, ada kata wajajr dan nggak wajar, wajar itu gw kira apa yang sudah terkoknstruksi oleh orang pada umumnya… bukanya yang begitu membentuk kebudayaan juga, kebudayaan yang dipahami sebagai ‘faith’ orang banyak?” T: “yang nggak wajar yang melenceng dari pemahaman umum…” S: “ nah itu die, nah secaraa umum cewe jarang ada yang ngerokok mungkin” Anne tiba dengan membawa Rokoknya dan tiga buah coklat wafelatos A: “obrolan lo pada sampe dimana?” T: “sampe rokok, cewe yang ngerokok seakan-akan aneh ato bahkan nista” A: “owh..ya lu liat aja entar, apalagi gw yang berkerudung gini, liat aja mata orang nanti, seakan gw nista banget dah..” A: “gw benci banget sama mata orang yang ngeliat klo gw lagi ngerokok gini” *sambil membuka rokok dan membakarnya dengana meminjam korek dari saya A: “mao tin?” T; “ah iya ah…tapi gw minta rokok lo ajaj sep..bagi ya?” S: “ambil aja silahkan…” Dan kami bertiga pun merokok bersama… A: “tuh liat tuh, mata orang ngeliat gw..benci banget gw, emang gw nista banget apa?” * seorang bapak-bapak lewat dengan mata melirik Anne dengan mata yang agak aneh untuk memandang seseorang A: “bener khan?” S: “ya gitu deh, mungkin dalam pemahaman dia, cewe ya ‘kaga bolelh’ merokok karena akan memperlihatkan ‘kebengalan’” A: “ah…semuanya khan Cuma masalah konstruksi, trus jadi penyimbolan yang berujung kepada bentuk budaya dan point of view, kenapa harus ada baik buruk sih?” T: “iya tuh, gw juga aneh, kenapa ujungnya jadi begitu ya? Bener salah, bête gw, jadi ada penilaian, padahal kadang orang yang menilai kita bisa lebih buruk dari kita” S: “iya, jadi ada penistaan gitu ya? Liat aja mata tadi, symbol banget khan? Symbol penistaan gitu, padahal ya cm beda ekspresi cara pandang, tapi kita juga sudah terikat sama penyimbolan itu, ude jadi kesepakatan yang tertanam di kita juga, klo pandangan model gitu jadi penistaan. Ya gitu khan??kita belajar budaya juga gitu, kita sendiri tercebut di dalamnya T: “iya, padahal konyolnya itu konstruksi manusia sendiri, tapi berpengaruh juga sama individu laen, padahal, relative banget…bisa jadi di kita, biasa aja apa yang dia liat nista, tapi kita juga terpengaruh sama budaya mereka, kita jadi terpengaruh oleh bingkai pandangan mereka…dan mereka seenaknya menilai dari ‘faith’ mereka sendiri.” S: “ ya gitulah kenyataannya…” Obrolan dilanjutkan dengan pembahasan lanjut dan pembahasan masalah pribadi masing-masing hingga masing-masing pergi dengan alasan untuk bertemu pasangan masing-masing… Dari apa yang saya coba ilustrasikan dengan sepotong kejadian tersebut, saya mencoba merefleksikannya secara pribadi dan hal seperti ini cukup mengagetkan terutama pribadi karena bagaimanapun juga, dalam obrolan yang sifatnya sehaari-hari, apa yang terjadi tidak terlepas dari apa yang selama ini banyak dibahas secara teoritis. Hal ini membuat saya berfikir bahwa kebanyakan studi ilmiah yang saya tahu, sisi teoritisnya selalu berada di laboratorium atau berada di kelas dan tercatat dalam buku. Berbeda dengan apa yang saya temui ini, teori, konsep social yang dibahas di kelas dan dibaca di buku, hadir juga dalam kenyataan social yang saya alami sehari-hari, walaupun dalam alasan klisenya, studi ilmiah adalah empiric, dapat dibuktikan secara empiric. Hanya saja secara pribadi, sebagai seorang yang cukup lama berkutat dengan filsafat –yang mempunyai dalil ilmiah yang sama, yaitu empiric- saya kira, konsep dan teori yang banyaak dibicarakan di kelas adalah sebuah proses generalisasi yang cukup panjang, menjadi konsep ideal yang terkadang menjadi jauh dari kenyataan social sehari-hari. Berbeda dengan pembahasan antropologi –atau mungkin banyak keilmuan social yang lain- yang membahas realitas social keseharian, saya merasakan bahwa teori dan konsep ide yang dibahas terasa begitu cair dalam reallitasas social seperti yang sudah saya katakan tadi. Bagaimana saya melihat bukti dari konsep ide tanpa harus secara lebih ‘serius’ ‘membuktikan’ teori yang sudah dibahas. Hal yang bagi saya juga menjadi sebuah hal yang patut dikakaagumi adalah bagaimana secara personal, individu-individu yang berada di dalam lingkungan studi antropologi merupakan individu reflektif yang mampu membuat obrolan sehari-hari, obrolan yang pada umumnya berupa gossip dan hal-hal yang banyak oranag katakana sebagaai ‘saampah’, menjadi obrolan yang ilmiah. Sebagaai penguatan ‘materi’ yang sudah dipelajari sebelumnya. Antropologi adalah ‘GILA’ Seperti apa yang sudah dituliskan sebelumnya, bahwa perkenalan dengan antropologi adalah hal yang cukup luar biasa bahkan dalam pengalaman studi dan pengalaman hidup saya dalam sebuah realita, realitas social seorang kesep. Dalam sebuah sidang hasil Desertasi, pak Afid mengatakan bahwa menjadi seorang Antropolog merupakan hal yang sulit, begitu juga dalam banyak kesempata kuliah memahami text antropologi hari Rabu, pak Tony mengatakan bahwa untuk menjadi Antropologi adalah memperhatikan hal yang dianggap banyak orang sebagai hal yang ‘remeh’, begitu juga dengan kuliah metoli, pak Iwan berkali-kali mengatakan bahwa antropologi membahas hal yang sudah ‘biasa’ dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan salah satu tulisan yang mengatakan bahwa perbedaan antara antropolog –etnograferdengan wartawan adalah bahwa etnografer membahas kejadian yang terjadi sehari-hari, yang biasa sedangkan wartawan selalu menyajikan hal yang luar biasa, kejadian yang ada diluar kebiasaan sehari-hari. Dari apa yang saya pelajari dan dengarkan tersebut, membuat saya berfikir bahwa kepekaan adalah melihat hal yang unik dari ke’biasa’an yang dialami, melihat hal yang tidak biasa dari yang biasa atau jika saya mencoba menarik hal ini lebih jauh lagi kedalam dunia ide adalah bahwa menjadi antropolog adalah bagaimana kita mulai berfikir terbalik. Seperti orang yang ‘gila’ bahwa cara berfikir antropologi adaalah mencoba melihat beras diantara tumpukan padi, melihat hal yang hamper mustahil, hal yang membutuhkan ketelitian, kepekaan, cara berfikir radikal, holistic, dan kritis. Kesemua cara tersebut adalah hal ideal yang ‘hampir’ saya katakan mustahil dalam memilikinya. Akan tetapi menjadi antropolog adalah proses menuju kesana dan exercise untuk bisa memiliki kepekaan, kritis, radikal, dan ketelitian. Proses yang bagi saya berarti sebuah proses yang memberikan arti lebih kepada kehidupan itu sendiri. Tingkat kemustahilan yang tinggi tersebut menjadi sebuah bukti dari kata-kata pak Afid dan menjadi sebuah kata ‘GILA’ dalam kamus hidup saya. Tidak hanya karena saya memiliki prinsip ‘kesenangan’ dan ‘kegilaan’ seperti yang dituliskan di awal tulisan, bagaimanapun juga, menjadi antropologi menambah kegilaan tersebut dan apa yang melebihinya adalah ketertarikan untuk menjadi seorang Gila yang dinamakan Anthropologist. Bodoh dan dibodohi Dalam pengalaman perkuliahan yang telah saya jalani, selama selama semester ini paling tidak ada banyak hal yang terjadi yang membuat mata saya terbuka, perasaan hati turun dan kesombongan mereda. Dan sifat terakhir ini menghentak dan ditabrak oleh pengalamanpengalaman real yang saya alami selama kuliah ini. Selama satu semester, bagi beberapa individu dalam angkatan saya, ada satu mata kuliah yang ‘menakutkan’ atau menegangkan. Alasannya sangat sederhana, karena suasana kelas yang tidak nyaman dan cara dosen yang saat itu kami anggap tidak memperhatikan psikologi siswa hingga siswa merasa cukup tertekan untuk mengikuti perkuliaan. Perkuliahan tersebut adalah perkuliahan hari rabu bagi angkatan kami. Bagi saya pribadi, sebagai seorang yang cukup memegang ‘teguh’ prinsip relativitas, ada hal yang cukup mengganggu prinsip saya tersebut yaitu ketika beberapa kesempatan kelas kuliah bapak Dosen memperbandingkan kemampuan memahami teks siswa dan keluhan siswa dengan pengalamannya dan realitas kehidupan mahasiswa di Luar Negri tempatnya belajar pada masanya, dikatakan bahwa kami, beberapa siswa yang mengikuti kuliah sebenarnya adalah mahasiswa manja karena di luar negri sana dan ketika masa beliau menjadi mahasiswa, para mahasiswa diwajibkan membaca tugas setiap hari sekitar 60 halaman dengan bahasa inggris. Dan kesemuanya saya pahami sebagai sebuah standar mahasiswa yang seakan akan diinginkannya. Ditambahkan oleh Dosen tersebut bahwa bagi beliau, cukup konyol ketika mahasiswa tidak dapt memahami teks yang dimaksud padahal beberapa pembahasan hanya sekitar 40 halaman dan itu dikumpulkan dengan jangka waktu seminggu saja, tidak seperti di ‘Amrik’ sana yang satu hari harus membaca sekitar 60 halaman setiap hari. Apa yang disampaikan oleh Dosen mengenai perbandingan kelas tersebut dengan kelas di ‘Amrik’ itu tidak dapat saya terima, hal ini bagi saya cukup mengganggu kepala dan perasaan saya karena bagi saya secara sederhana, bahwa keadaan di kelas antropologi tidak pantas dipersamakan dengan kelas di luarnegri sana yang notabene berbahasa inggris sebagai bahasa ibu mereka. Dengan jelas saya merasa kecewa dengan perlakuan beliau sebagai dosen karena apa yang saya pahami adalah, ketidak pantasan komparasi yang tidak sejajar. Kami anggota kelas menggunakan bahasa Indonesia sedangkan tugas akan selalu diberikan berbahasa inggris, saya artikan itu bahwa bahasa inggris bukan bahasa ibu kami dan untuk membaca buku berbahasa asing, paling tidak selalu ada proses penterjemahan terlebih dahulu yang pada intinya bahwa kesulitan dalam memahami teks dengan bahasa asing lebih besar dengan dengan bahasa sendiri. Selain itu, masih dalam pikiran saya, dalam satu minggu ada sekitar lima mata kuliah yang masing-masing memiliki tugas, jadi bagi saya cukup tidak relevan apa yang dikatakan oleh Dosen pada hari Rabu tersebut. Walau kesemua ini terkesan apologis dan defensive karena ‘ketidakmampuan’ untuk mengikuti kuliah tersebut, bagaimanpun juga, cara berfikir seperti ini cukup lama bercokol di kepala saya. Setelah beberapa kali berdiskusi dengan beberapa teman saya, ternyata dengan berjalannya waktu, saya mulai mendapat pencerahan, ping tiadadk, jika tidak dikatakan sebagai sebagai pencerahan saya menganggap apa yang mulai saya pahami sebagai sebuah bentuk cara memandang yang positif. Pada awal saya menanggapi cara ‘membimbing’ Dosen dengan memanganggap mahasiswa sebagai orang bodoh. Atau saya menggunakan istilah singkat sebagai ‘dibodohi’ akan tetapi setelah masuk dari beberapa orang saya kira ada sudut pandang lain walaupun masih dalam tataran kata ‘bodoh’. Kata ‘Bodoh’ menjadi kunci dalam permasalahan ini, baik posisi menjadi objek maupun subjek, apa yang saya katakana sebagai cara pandang beda yang lebih positif adalah bahwa saya merasa menjadi orang bodoh tetapi tidak karena dibodohi, melainkan secara reflektif dan sadar bahwa pribadi seorang kesep merupakan pribadi yang bodoh dan masih harus tetap bersemangant untuk melawan kebodohan tersebut. Pandangan ini menabrak rasa sombong yang ada dalam diri pribadi. Sebagai seorang mahasiswa pascasarjana, saya kira menjadi wajar jika timbul sedikit banyak kesombongan dan rasa tinggi hati karena memang teman seumuran saya tidak begitu banyak yang beruntung masih mampu mengecap pendidikan pasca dan ada jugaa perasaan superioritas terhadap individu yang seumur dalam segi kognisi karena jenjang yang lebih tinggi. Dan memang secara jujur saya mengakui bahwa ‘rasa’ seperti itu hadir dalam benak saya, sedikit maupun banyak. Seperti yang saya katakan diatas bahwa rasa ini ditabrak oleh perasaan ‘Bodoh’ pribadi karena masih mencari apologi atas kelalaian dan ketidak mampuan mengikuti class rule yang dibuat oleh Dosen sebagai chief of class saat kuliah berlangsung. Rasa bodoh itu meresap dalam benak saya dan meredam rasa sombong karena saya merasa masih bodoh dan banyak hal yang harus saya pelajari dan gali terus. Walaupun mungkin tidak akan pernah selesai. Dan satu hal lain yang saya pahami bahwa apologi sselalau menunjukan kelemahan pribadi dan mengarah kepada kebodohan itu sendiri. Two sided of life, two as one Dalam buku Emmerson, dituliskan bahwa etnografi merupakan sebuah penelitian yang memerlukan rasa dan logika, ethnography is science and art in same time. Kata dalam tugas membaca tulisan Emmerson membuat saya tergelitik, baik dalam hal etnografi yang memang saat itu, perdebatan dan dialog yang terjadi untuk membahasnya, maupun tergelitik untuk melihatnya sebagai sebuah cara ‘memandang’ dunia. Pada saat pembahasan mengenai ethnography sebagai sains dan seni pada satu waktu bu Ike melemparkan pertanyaan, “bagaimana bisa koq etnografi jadi sains juga seni?” dan saya mencoba menjawab bahwa dalam melakukan etnografi, ada interaksi dengan realitas social yang coba dipahami. Dalam interaksi tersebut dibutuhkan seni berinteraksi begitu juga dalam penyusunan etnografi, dibutuhkan seni penyusunan, seni retorika dalam bercerita, dalam memilih data dan sebagainya. Dan etnografi adalah sebuah hal yang ilmiah karena memang mampu dibuktikan secara teoritis, selain itu juga ilmiah karena etnografi mengangkat teori-teori ilmiah dalam membahas dan memahami sebuah realitas kebudayaan. paling tidak jawaban seperti itu yang terlontar dan memang rasa tergelitik terhadap etnografi sebagai seni dan sains dalam satu waktu, terutama dalam sisi saya memandang hidup menimbulkan pertaanyaan yang senada dengana pertanyaan bu Ike walaupun dengan intisari yang agak berbeda. Yaitu “bagaimana bisa dua hal yang saling “berlawanan” ada di dalam kesatuan yang sama?”. Dari diskusi diatas beberapa kali pula ada diskusi yang membahas hal serupa tau membuat saya membahas hal serupa seperti bagaimana hokum alam ini, dengan percontohan siang dan malam sebagai sebuah hal yang tidak bergeser. Tetapi keduanya diperlawankan dan berada dalam satu hokum. Begitu juga dengan banyak hal yang lain. Teringat dengan konsep Yin-Yang yang juga pernah dibicarakan dalam kelas, saya kira konsep tersebut sebagai sebuah gambaran real dari alam atau realitas ini. Dan sebagai kesimpulan sampai saat ini bahwa tidak pernah ada nomor satu, dalam pengertian bahwa tidak ada ‘ketunggalan’ yang berdiri sendiri. Satu atau kesatuan atau ‘ketunggalan’ merupakan sebuah ‘unity’ artinya keberadaannya tidak serta merta sebagai sebuah yang dalam istilah Immanuel Kant sebagai ‘das ding an sich’ atau berada dengan sendirinya melainkan berdiri sebagai sebuah susunan dari angka setelahnya yaitu dua, tiga, dan seterusnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan konsep Yin-Yang, saya memcoba memahami bahwa secara nyata dalam hidup manusia itu selalu terdiri dari dua sisi, dua sisi yang membentuk kesatuan, dua sisi yang dikatakan ‘berlawanan’ dan menegaskan lawannya satu sama lain, dimana bisa saya katakana bahwa ditengahnya ada kata ‘netral’ yang sangat tipis. Dan dari apa yang pernah dituliskan Emmerson tersebut bagi saya mempunyai banyak hal yang menarik yang menarik diri saya untuk terus membentuk gagasan mengenai realitas saya sendiri. Refleksi: sebuah Kegilaan yang berubah menjadi Kesenangan Sebagaimana yang telah dituliskan di atas, bagaimana saya memandang antropologi sebagai sebuah kegilaan baru dalam hidup saya sebagai kesep dan bagaimana kegilaan tersebut merupakan hal yang membuat hidup saya berwarna dan bisa berubah menjadi sebuah kesenangan. Begitulah dengan kegilaan bernama antropologi tersebut berubah menjadi sebuah kesenangan tersediri untuk berada di dalamnya. Bagaimana juga antropologi memberikan rasa penasaran untuk lebih dalam tercebur, dan bagaimana juga antropologi memperkaya sudut pandang saya. Paling tidak dalam refleksi saya sampai saat ini, apa yang paling berharga untuk saya pelajari adalah Kejujuran, jujur dalam bersikap, memandang, berfikir, jujur terhadap keadaan, bahkan jujur dalam berinteraksi. Bagaimanapun juga, kejujuran juga mampu membuat saya lebih menerima ‘perbedaan’ dalam realitas social. Kejujuran tersebut juga saya pelajari dengan kebebasan yang banyak diberikan dalam system perkuliahan, contoh kecil adalah kebebasan mengutarakan ‘rasa’ dalam tugas mata kuliah pak Iwan yang bagi saya sebagai sebuah bentuk melatih kejujuran itu sendiri. Bebas tidak berarti lepas, melainkan kebebasan sebagai sebuah kejujuran. Hal yang paling jelas dengan banyak kejadian dan pengalaman yang saya utarakan dalam tulisan ini –walaupun hanya sepenggal pengalaman belaka- adalah saya menikmati kesemua itu, menikmati rasa takut, rasa tegang, rasa tersinggung, rasa kecewa dan hal-hal yang timbul dalam lingkungan ‘ke-antropologi-an yang saya alami. Walaupun saya rasa cukup aneh ketika pada awal saya melihat kuliah ini sebagai sebuah kegilaan, tantangan, atau bahkan hal yang bisa ‘merusak’ kesenangan saya selama ini berubah menjadi sebuah bagian kesenangan pribadi. Kesenangan tidak berarti sebuah rasa yang positif atau sebuah satisfaction belaka, lebih dari semua itu, kesenangan tersusun dari bagian-bagian ‘rasa’ dalam pengalaman yang telah terjadi. Kesenangan adalah sebuah unity. Termasuk di dalamnya adalah ‘Kegilaan’ dalam pandangan hidup saya.