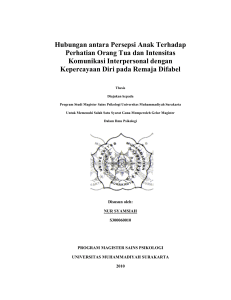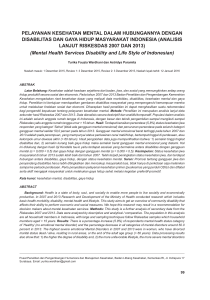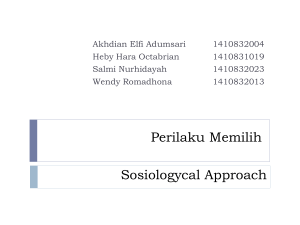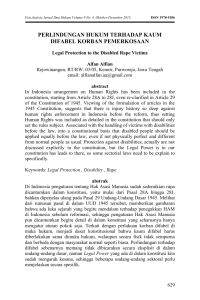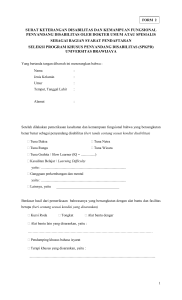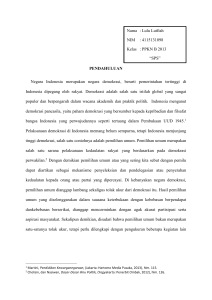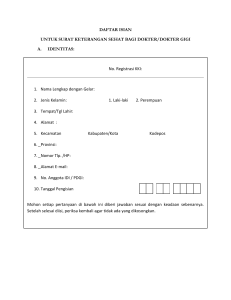politics - Universitas Hasanuddin
advertisement

The Politics | Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015 P-ISSN: 2407-9138 The POLITICS The Politics adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli oleh Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Redaksi menerima naskah artikel, laporan penelitian, dan resensi buku yang sesuai visi jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15-20 halaman kwarto (A4) dengan Times New Roman (TNR) 12 spasi 1,5. Pelindung Rektor Universitas Hasanuddin Direktur PPs Universitas Hasanuddin Dekan FISIP Universitas Hasanuddin Penanggungjawab KPS Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ketua Penyunting Muhammad Nasir Badu, Ph.D. Sekretaris Penyunting Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. Muhammad Randhy Akbar, S.IP. Dewan Penyunting Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si. Drs. A. Yakub, M.Si. Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si. Mitra Bestari Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. (Bidang Politik, Universitas Indonesia) Prof. Madya Dr. Zarina Othman (Bidang Politik Internasional, Universiti Kebangsaan Malaysia) Dr. Philips J. Vermonte (Bidang Politik, Centre for Strategic and International Studies) Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. (Bidang Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Tim Sekretariat Ahmad Silaban, S.IP. Babra Kamal, S.IP. Hendry Bakri, S.IP. Nur Alfiyani, S.IP. Nurlira Goncing, S.IP. Sosiawaty Masrul, S.IP. Alamat Redaksi Gedung FISIP Universitas Hasanuddin Kampus UNHAS Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90245 e: [email protected] w: www.politicsunhas.org f: www.facebook.com/politicsunhas CAIONHFCOIPJ/of DAFTAR ISI DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM Halaman 127—155 Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia Ishak Salim Halaman 157—162 Selective Influence of Political Advertising on Television in Visual Image Building Candidate Presidential Election 2014 Tuti Bahfiarti Halaman 163—172 Sinergitas Pemikiran Muhammad Natsir di Bidang Teologi. Pendidikan dan Politk. (Suatu Kajian Perspektif Pemikiran Politik Islam) M. Basir Syam Halaman 173—181 Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014) Siti Nimrah H. Djanudin dan Sakaria Halaman 183—189 Negara, Pasar dan Problem Pendalaman Demokrasi Pasca Orde Baru Ade M. Wirasenjaya Halaman 191—202 Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politk Muh. Kausar Bailusy Halaman 203—209 The Factors Influencing Young Voters in Determining the Choice Case Study: Local Election in Bengkulu Andi Azhar dan Susyanto Halaman 211—217 Indigenous Elite and Modern Democracy (Case Study: Legislator at Gowa Regency) Haslinda B. Anriani, AnsarArifin dan Rasyidah Zainuddin Halaman 219—224 Exchange and Political Communication Rosmawati, Harifuddin dan Sudirman III Jurnal The Politics Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, jurnal The Politics bisa kembali diterbitkan. The Politics adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli oleh Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Jurnal ini merupakan bagian kedua dari volume 1 yang sebelumnya sudah diterbitkan. Tulisantulisan ini mencoba menggambarkan tentang demokrasi dan pemilihan umum. Kami dari redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada para penulis yang telah memberikan masukan pengetahuan dan ilmu untuk diterbitkan di jurnal ini. Tentunya jurnal ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kami meminta kritik dan saran dari pembaca. Salam Hangat, Redaksi The Politics IV Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia Ishak Salim Universitas Teknologi Sulawesi Abstract This paper seeks to analyze how the contribution of Disability Social Movements in Indonesia to improve the quality of the future elections. The author is one of the organizers of this movements and follow the processes of disabled community organizing during the elections in four regions: Makassar (South Sulawesi), Balikpapan (East Kalimantan), Bantul (Yogyakarta), and Situbondo (East Java). Two things that are the focus of my analysis are the results of a survey on the perception of legislative candidates in 4 regions and election monitoring by Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) and its partners (Disabled people Organizations in a number of districts). The results of this survey and monitoring both contribute to the political science, especially in introducing Disability Perspectives in Electoral and Party Systems. In the present of political science study in Indonesia, scientists are relatively still do not understand yet the disability perspective in their efforts to develop a disability-based research methods and further designing a number of political instruments, in particular the way a difabel choosing political actors who cares for the disabled intersets and designing election models. The survey results indicate that the capacity of knowledge and experience the legislators candidate on the issue of disability is still weak, then how are we supposed to fill this lack of knowledge of disability through cooperation between political parties and organizations with a disability principal approach - agency. While the results of the election monitoring conducted by disabled people organizations have contributed to the explanation of 127 Jurnal The Politics how the election should take place and to accommodate the interests of voters with disabilities. Exposure results of this research and monitoring simultaneously aims to improve the quality of parliamentarians, election administration, and the electoral system so that political practice can take place in inclusion and more meaningful. Kata kunci: perspektif disabilitas, pemilihan umum, inklusi, difabel, organisasi difabel Pendahuluan Pada pertengahan Januari 2014 sejumlah aktifis organisasi difabel di Kota Balikpapan dan Samarinda mendatangi Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk memberi masukan soal Pemilu Inklusif. Di antara mereka ada yang menggunakan kursi roda, kruk, dan tongkat. Rupanya kantor KPUD Kalimantan Timur sebagaimana juga di banyak kantor KPU daerah di Indonesia tidak aksesibel bagi mereka. Untuk memasuki kantor itu, pengguna kursi roda harus turun dan merangkak sekadar melewati tiga anak tangga. Ia berhasil tanpa perlu dipapah walaupun terpaksa menjadi bahan tontonan. Namun begitu disadarinya ruang Komisioner KPU ada di lantai dua, ia menyerah dan memilih dipapah hingga ke ruang Pak Ketua. Bagi pengguna kursi roda, berjalan dengan dipapah adalah bentuk ketidakberdayaan dan hal itu menunjukkan betapa lingkungan memang telah mendiskriminasikan dirinya. Tahun lalu, saat pemilihan Walikota berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemilih difabel netra menemui sejumlah kendala. Template Braille atau alat bantu mencoblos bagi pemilih difabel netra yang disediakan penyelenggara pemilu menimbulkan sejumlah kebingungan. Sistem penomoran braille itu tak terbaca dengan baik saat pemilih menggunakannya. Pemilih tak menemukan kolom nomor bagi kandidat dengan nomor urut 6 dan seterusnya. Akibatnya template braille yang dibuat tanpa berkonsultasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) itu sia-sia dan pemilih difabel netra terpaksa didampingi pihak lain dan kerahasiaan pilihannya menjadi tak sepenuhnya terjamin. Difabel Rungu-wicara juga punya sejumlah pengalaman yang menunjukkan betapa prosedural pemilu mengabaikan kebutuhan atau kepentingan mereka. Saat gencar-gencarnya kampanye calon legislator dan calon presiden melalui media massa, khususnya radio, televisi dan internet, tak ada satupun media yang menyediakan penterjemah bahasa isyarat dalam pertemuan tersebut. Belum lagi soal Manual Pemilu dan segala informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU maupun Bawaslu hingga jajarannya yang masih abai pada kebutuhan pemilih difabel seperti difabel rungu-wicara. Dalam pemberitaan harian Kompas1 pada akhir Juli 2013 disebutkan bahwa perwakilan USAID dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menerima hasil penelitian yang dilakukan ASEAN General Election for Disability (AGENDA) tentang implementasi hak politik difabel. Berdasarkan temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang tergabung dalam AGENDA, Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel. Ketiadaan data ini dalam alam demokrasi merupakan urusan yang serius. Bagi pemilih difabel netra misalnya, hak politik mereka untuk memilih kandidat pilihannya terpaksa tak bisa digunakan lantaran tidak adanya ‘alat bantu mencoblos’ (braille template) yang disediakan penyelenggara pemilu. Sementara itu, bagi difabel daksa, lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang menyulitkan mereka untuk datang sudah cukup membuat mereka pada akhirnya menolak ke TPS. 1 kam. http://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/2245368/Hak.Politik.Penyandang.Disabilitas.yang.Dibung- 128 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Mochammad Afifuddin, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di dalam diskusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (30/7/2013) dengan gusar menyatakan, “Indonesia masih belum ramah terhadap difabel. Dari lima daerah yang kami survei, dua daerah, yakni Tangerang dan Pangkal Pinang, tidak punya sama sekali template braille. Alasannya setiap kali kami berdebat, mereka berdalih tidak ada mandat untuk menyediakan itu.” Pada pemilukada putaran pertama di DKI Jakarta, KPU setempat sama sekali tidak menyediakan template braille bagi pemilih difabel netra. Nanti setelah memperoleh teguran keras dan dibimbing oleh organisasi difabel, pihak KPU DKI Jakarta akhirnya menyediakan kertas suara huruf braille di putaran kedua. Selain itu, bagi pemilih difabel daksa nasibnya setali tiga uang. Posisi TPS hingga kini masih dinilai tidak membuat akses bagi difabel. Seharusnya TPS itu dilengkapi dengan jalan atau titian khusus (rampa) pengguna kursi roda dan bentuk bilik suara yang luas agar nyaman dalam memilih. Ketidakpahaman para penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi hingga pada saat hari pemungutan suara juga menjadi perhatian JPPR. “Di beberapa tempat, bagi difabel, mereka memilih di rumahnya sendiri dengan didatangi petugas. Tetapi, di situ tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja di meja untuk dipilih difabel. Padahal, prinsip utama pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia. Gambaran di atas menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengokomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa (lihat ‘analisis situasi difabel di indonesia: sebuah desk-review’, FISIP UI, 2010). Namun, di luar sejumlah ‘cacat demokrasi’ ini, setidaknya Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Difabel dan sejauh ini parlemen sedang membahas sebuah Rancangan Undang-Undang Tentang Disabilitas. Masih dalam pemberitaan Harian Kompas, pada akhir Juli 2013 Husni Kamil, Ketua Komisi Pemilihan Umum menunjukkan kerisauan atau lebih tepat kegamangannya dalam melaksanakan pesta demokrasi dengan pelibatan penuh difabel. Ia mengharapkan perlunya mendiskusikan lebih jauh soal-soal teknis pelaksanaan Pemilu. Misalnya, soal tuntutan penyediaan kertas suara berhuruf braille dalam setiap pemilihan umum. Pada Pemilu 2014, ujarnya, dalam satu lembar kertas suara bisa ada 144 calon anggota legislatif untuk pemilihan anggota DPR saja. “Bayangkan kalau kertas suara pemilu legislatif dijadikan huruf braille, [jika setiap partai politik mengajukan 12 calon legislatif untuk kursi DPR di tiap daerah pemilihan, penulis] akan ada 144 caleg dari 12 partai politik. Apa ini nantinya nggak bikin bingung? Makanya kita perlu mendiskusikan lagi lebih jauh, model kertas surat suara apa yang pas untuk difabel,” ujar Ketua KPU. Tidak begitu jelas siapa pihak yang Pak Ketua KPU rujuk membikin bingung. Bagi pemilih difabel netra kertas suara dengan template Braille jelas memudahkan. Jika yang dibuat bingung 129 Jurnal The Politics adalah para pihak penyelenggara Pemilu maka di sinilah pentingnya melibatkan mitra organisasi difabel secara maksimal dalam merancang sistem pemilihan yang aksesibel bagi seluruh ragam difabilitas. Sayangnya, sampai pada hari penjoblosan pada 9 April 2014, kertas suara untuk pemilih difabel baik untuk DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pihak KPU tidak menyediakannya. Alasannya adalah rumit secara teknis, padahal di provinsi DI Yogyakarta, KPU setempat bersama KPU kota Yogyakarta dengan kesadaran disabilitas yang baik berani keluar dari kebijakan pusat dan mengambil kebijakan diskresi untuk menyediakan braille template dengan bekerjasama dengan organisasi difabel CIQAL (Center for Impoving Qualified Activity in Live of People with Disabilities). Pemilu inklusif memang mensyaratkan pengetahuan akan segala hal berkaitan dengan isu disabilitas dari penyelenggara. Di sinilah letak pentingnya kehadiran sejumlah pemilih difabel yang kini begitu aktif masuk ke ruang-ruang formal Pemilu 2014 lalu untuk berdiskusi dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di banyak daerah. Tujuannya adalah mengajarkan kepada bangsa ini betapa perspektif disabilitas amat penting dalam pemilu. Penting karena perspektif ini berisi “sisi manusiawi” dari sebuah sistem pemilihan atau sistem politik secara lebih luas. Jika perspektif ini berhasil ditanamkan kepada para penyelenggara sampai kepada para peserta pemilu, dan diterapkan di ranah praktis, maka pemilu ini menjadi akses bagi semua orang, bahkan tak hanya bagi kaum difabel sendiri. Pelaksanaan pemilu 2014 menyimpan sejumlah soal dalam perspektif dan pengalaman pemilih difabel. Dalam pengalaman sejumlah pemilih difabel (sebagaimana dipaparkan sebagian dalam pendahuluan tulisan ini) yang tergabung di dalam organisasi-organisasi difabel di 4 daerah (Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan DI Yogyakarta) di mana penulis terlibat dalam pengorganisasian tersebut, sejumlah permasalahan dalam pemilu ditemukan dan diupayakan penyelesaiannya secara aktif oleh difabel. Serangkaian aktifitas kelompok difabel dalam pemilu ini dikoordinir oleh SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) di sepanjang proses pemilu mulai dari tahap pendataan pemilih sampai pada penyelesaian pemilu.2 SIGAB adalah organisasi yang peduli pada isu-isu disabilitas dan merupakan gerbong utama dalam mendorong gerakan hak-hak disabilitas di Indonesia (disability rights movements). Dari sejumlah aktifitas tersebut, melalui artikel ini, penulis hanya akan memaparkan dua aktifitas penting mengingat keduanya memberi informasi yang berguna bagi perbaikan kualitas pemilihan umum di masa-masa yang akan datang. Dua kegiatan itu adalah penelitian dengan metode survei perspesi calon anggota legislator tentang isu-isu disabilitas dan pemantauan pemilu legislatif 2014. Sejumlah temuan dan pengalaman ini akan diuraikan lebih lanjut setelah pemaparan berbagai perspektif teoritis tentang disabilitas dan bagaimana perspektif disabilitas itu berkontestasi dalam konteks Indonesia. Tulisan akan ditutup dengan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi untuk terjadinya sejumlah pembenahan terkait pelaksanaan pemilihan umum berikutnya. Perspektif Teoritis Tentang Disabilitas Disabilitas dan pengetahuan terkait disabilitas adalah eksis dalam realitas sosial kita (Huber & Gillaspy, 1998, hal. 190). Banyak bidang akademik telah bersandar pada persamaan antara Beberapa aktifitas organisasi difabel adalah pendidikan politik aktifis difabel, dialog publik organisasi difabel di tingkat daerah, penelitian dengan metode survei tentang persepsi calon legislator terkait isu-isu disabilitas di 4 daerah, dialog organisasi difabel lokal dengan KPU dan Panwaslu setempat di 4 daerah, dialog pemilih difabel dengan calon legislator di 4 daerah dan membangun kontrak politik, pemantauan pemilu di 4 daerah dan serangkaian diskusi publik pengawalan kinerja anggota legislator terpilih. 2 130 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 ‘disabilitas’ dengan ‘orang cacat’, membuat seorang difabel tampaknya menjadi sekadar masalah atau bahkan diabaikan. Sosiolog, misalnya, biasanya mengabaikan aspek disabilitas atau hanya mempelajarinya sebagai sesuatu yang eksotis (Barton, 1996). Ketika disabilitas dipelajari dan dibahas secara teoritis, seringkali dengan cara yang ofensif (Hahn, 1997), karena banyak peneliti melihat seorang difabel hanya dalam hal kondisi biologis dan menyimpulkannya sebagai orang yang membutuhkan bantuan (Fine & Asch, 1988). Banyak difabel melihat sejumlah hasil penelitian tentang disabilitas sebagai cerminan dan [justru] mengabadikan mitos sosial yang negatif dan stereotip terhadap difabel (Kitchin, 2000; Stone & Priestly, 1996). Mengingat bahwa disabilitas dapat dipelajari dari berbagai perspektif yang berbeda, seperti aspek pembangunan manusia, kebijakan publik, hukum, budaya, masyarakat, etika, filsafat, dan teknologi (Turnbull & Stowe, 2001) maka kegagalan memahami disabilitas selama ini dapat diperbaiki demi tatanan sosial yang lebih baik bagi semua orang. Penelitian tentang disabilitas telah menghasilkan sejumlah perspektif teoritis untuk mencoba menjelaskan makna disabilitas dalam masyarakat. Beberapa perspektif ini mendekati aspek disabilitas sebagai isu medik, isu sosial, isu ekonomi, dan isu postmodern. Perspektif Medis. Dalam masyarakat maupun dalam penelitian soal kemasyarakatan, individu yang memiliki “kecacatan” atau gangguan fisik dan mental, sering dilihat sebagai disabilitas, dan disabilitas tersebut sering dianggap sebagai murni masalah medik yang dapat dan harus dirawat. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologis’ dalam diri seseorang (Silvers, 1998). Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas atau seorang dengan disabilitas (person with disabilities) sepenuhnya terkait dengan individu difabel, terlepas dari faktor-faktor eksternal diri difabel. Perspektif ini juga biasanya disebut sebagai perspektif perspektif konservatif. Perspektif ini memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh ‘disabilitas’ dianggap berada dan bersumber dalam diri individu tersebut dan terlepas dari konteks sosial, atau mengidentifikasi difabel sebagai masalah biologis. Tujuannya bagi difabel kemudian adalah untuk menemukan obat medis demi menyembuhkan “kecacatannya’. Secara bersamaan, perspektif ini fokus pada disabilitas sebagai sebuah masalah yang dapat ditangani melalui kemajuan medis dan teknologi (Switzer, 2003). Gerakan eugenika (The eugenics movement) adalah salah satu contoh yang mengagungkan pendekatan medis klasik dalam memandang disabilitas. Penekanan medis ini telah berdampak besar pada cara masyarakat luas dalam mengklasifikasikan dan menjelaskan disabilitas. Setiap penelitiannya berfokus pada soal “bagaimana mendefinisikan dan menggambarkan penyakit yang diderita difabel tersebut, atau mengklasifikasikan patologi yang diidap, dan bahkan memberikan wacana mengenai individu yang terkena” (Huber & Gillaspy, 1998, hal. 201). Perspektif medis telah membentuk banyak klasifikasi ‘kecacatan’ atau disabilitas dalam komunitas medis dan masyarakat pada umumnya melalui pendekatan dan melalui terminologi serta mendorong hadirnya persepsi negatif terhadap difabel. “Bahasa medis soal disabilitas atau “kecacatan” kemudian segera menjadi ‘bahasa penghinaan’ secara sosial dan istilah ‘yang menghinakan’ ini--seperti si buntung, si pincang, si buta, si pengkor, si idiot, si autis, dst--kemudian telah kehilangan konotasi medisnya secara asali dan bahkan menjadi alat budaya untuk mendevaluasi dan meminggirkan kelompok masyarakat tertentu” (Christensen, 1996, hal. 64). Pandangan-pandangan budaya yang telah melekat dari perspektif medis ini juga meluas ke lembaga-lembaga sosial. Bahkan kemudian, kebijakankebijakan tertulis tentang kecacatan atau disabilitas dari lembaga-lembaga sosial “cenderung menawarkan pembenaran atas status quo tersebut” (Riddell, 1996, hal. 83). Dalam upaya untuk secara langsung menangani masalah dari dampak ‘pendefinisian yang 131 Jurnal The Politics menghinakan’ ini yang lahir dari perspektif medis, sejumlah ilmuan yang mempelajari isu-isu disabilitas kemudian membuat sejumlah perspektif lain demi mencoba lebih memahami isu disabilitas dalam masyarakat. Perspektif ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan “ilmuan mainstream” demi mempelajari dan mendiskusikan isu disabilitas secara memadai dalam masyarakat (Bowman & Jaeger, 2003). Perspektif sosial. Perspektif sosial tentang disabilitas menegaskan bahwa “kecacatan atau disabilitas adalah hasil dari [pola] pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan ‘difabel’ dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka [beraktifitas atau berpartisipasi]” (Thomas, 1999, hal. 14). Disabilitas, menurut perspektif sosial adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk pemungsian (Silvers 1998, 2000). Amat kontras dengan perspektif medis, perspektif sosial memandang disabilitas seseorang (dan bukan kecacatannya) lebih sebagai akibat dari faktor eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekadar fungsi biologis difabel itu. Perspektif sosial memungkinkan kita untuk melihat disabilitas sebagai efek dari lingkungan [eksternal] yang tidak bersahabat bagi sejumlah bentuk tubuh dan bukan hal yang lain, [dan untuk itu] difabel lebih membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial dan bukan dalam kemajuan kedokteran (Siebers, 2001, hal. 738). Keyakinan-keyakinan dan fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran difabel dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada [jenis] kemampuan mereka. Perspektif sosial fokus kepada “hak kewarganegaraan” dan mengetahui “cara bagaimana organisasi atau kelembagaan-kelembagaan sosial menindas difabel” (Marks, 1999, hal. 77). Perspektif ini bekerja untuk membuat segala prasangka sosial yang negatif terhadap difabel nampak lebih jelas bagi kita agar supaya kita dapat lebih mempromosikan penerimaan seluruh difabel ke dalam dunia sosial demi membuat kehidupan umat manusia lebih inklusif. Dalam perspektif sosial, diskriminasi terhadap individu difabel, yang kadang-kadang diidentifikasi sebagai disablism (disabelisme), dipandang sebagai mirip dengan seksisme, rasisme, homofobia, dan ageisme sebagai penindasan dari kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi (Abberly, 1987). Perspektif sosial menyatakan bahwa memahami konstruksi sosial yang menindas difabel selama ini harus digunakan untuk mengurangi berbagai ‘ketidakberuntungan’ yang sudah diciptakan oleh pandangan bahwa diri individulah yang tidak mampu akibat adanya ‘gangguan fungsi tubuh dan mental’. Tatanan sosial harus diubah melalui perbaikan cara pandang akan disabilitas demi menjamin terciptanya kesetaraan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua orang (Silvers, 1998). Meskipun mungkin kekurangan dalam perspektif sosial disabilitas telah dikemukakan (Corker & French, 1999; Thomas, 1999), tampaknya pendekatan sosial ini mulai berkembang pesat dan menonjol, atau setidaknya paling sering dibahas dalam perbincangan soal ‘klasifikasi sosial disabilitas’. Beberapa pakar telah fokus pada isu-isu disabilitas secara spesifik dalam perspektif sosial sebagai hal yang sangat penting. Salah satu pendekatan ahli itu adalah yang menekankan peran pelabelan dalam konstruksi sosial disabilitas, yang melihat disabilitas sebagai “label sosial yang negatif” yang diterapkan oleh sejumlah orang [di banyak daerah bahkan kebudayaan] kepada orang lain dengan efek yang meminggirkan difabel [baik] secara sosial [maupun politik]” (Riddell, 1996, hal. 86). Perspektif ini memandang disabilitas sebagai ciptaan langsung dari eksklusi atau pengabaian sosial melalui ‘pelabelan’, baik melalui sarana hukum, kebijakan, maupun standar sosial. Selain itu, ilmuan lainnya telah menegaskan akan pentingnya ‘fungsi sosial’ dalam 132 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 pembangunan sosial difabel (disabilitas). Pandangan ini menegaskan bahwa hasil-hasil disabilitas dari berbagai klasifikasi secara khusus oleh organisasi sosial dan lembaga negara (Albrecht, 1992; Stone, 1984). Dari pendekatan ini, disabilitas bukan merupakan produk dari klasifikasi medis, sosial, dan politik, tetapi merupakan hasil dari cara-cara di mana individu difabel diperlakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat itu. Perspektif Ekonomi. Daripada sekadar melihat disabilitas sebagai masalah medis atau sosial, beberapa ilmuan memahami disabilitas sebagai masalah ekonomi. Perspektif ini, yang disebut juga perspektif materialis menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain (Barnes, 1990; Finkelstein, 1980; Oliver, 1990). Menurut perspektif materialis, impairment atau gangguan fungsi fisik tubuh dan mental bukan konstruksi sosial melainkan lebih pada sebab-sebab ekonomi yang nyata, seperti kepentingan ‘profesional pribadi’, ‘perubahan teknologi’, dan ‘prioritas ekonomi’. Dalam pandangan ini, difabel kurang dihargai sebagai pekerja oleh majikan, dipandang sebagai kendala oleh pekerja lainnya, dan dianggap memiliki kesulitan yang lebih besar dalam berurusan dengan teknologi baru. Semua faktor ini berkontribusi terhadap sikap yang berfungsi untuk meminggirkan para difabel karena alasan-alasan ekonomi itu. Perspektif ini memandang bahwa masalah utamanya adalah pada adanya persepsi bahwa ‘difabel memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya’. Perspektif Posmodernisme. Berbeda dari semua perspektif lainnya tentang disabilitas, perspektif postmodernis mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori (Shakespeare, 1994). Karena ada begitu banyak pengalaman dan pertimbangan pribadi yang berdasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, dan jenis impairment, mungkin mustahil untuk mengklasifikasikan secara teoritis parameter-parameter pengalaman yang dialami oleh beragam individu difabel. Disabilitas juga telah dipelajari secara khusus dalam cara pandang postmodernis dari perspektif feminis (Lonsdale, 1990; Thomas, 1999), perspektif ras (McDonald, 1991; Stuart, 1992), dan perspektif teori keanehan [queer theory perspective] (McRuer, 2003; Samuels, 2003). Masing-masing pendekatan ini berupaya menciptakan suatu pemahaman disabilitas yang berangkat dari ‘sebagian populasi difabel’, seperti difabel yang juga adalah warga Afro-Amerika, atau kehidupan keluarga difabel yang hidup di salah satu desa di Pulau Jawa (lihat Salim, 2015). Semua pandangan yang berbeda-beda ini telah berkontribusi untuk mencoba lebih memahami ‘klasifikasi disabilitas’. Demikian pula dalam menganalisa fenomena politik kepemiluan, maka kita dapat melihat bahwa cara bagaimana pemilu didesain dan dijalankan amat dipengaruhi bagaimana perspektif para pelaksananya. Pun demikian, orang-orang yang kemudian duduk di kursi parlemen tak lepas dari cara pandangnya akan disabiltis yang akan menentukan watak kebijakannya. Lihat pula misalnya bagaimana alasan KPU pada Pemilu 2014 dalam meniadakan ‘alat bantu mencoblos’ bagi pemilih difabel netra hanya karena bahwa secara teknis sulit dan berbiaya mahal. Padahal apa yang dipikirkan atau dibayangkan sebagai ‘sulit’ belum tentu secara teknis sulit jika hal itu dikerjakan oleh orang-orang yang paham di bidangnya atau dari cara pandang kaum difabel yang sudah biasa mendesain braille template’. Pun demikian apa yang dipikirannya mahal adalah berangkat dari kalkulasi yang keliru mengingat sesungguhnya ada banyak cara dalam mendesain alat bantu mencoblos yang bisa ditempuh. Apa yang sesungguhnya terjadi hanyalah karena sejumlah bias terhadap difabel sebagai akibat dari sikap sosial pada umumnya. Juga bisa terjadi karena pelaksana pemilu beranggapan bahwa difabel netra itu adalah person yang tidak mampu dan untuk itu mesti dibantu dengan form C3. Anggapan bahwa difabel 133 Jurnal The Politics adalah person yang tidak mampu membuat kebijakan KPU untuk menyiapkan pendamping dan secara tidak sadar sebenarnya telah berlaku mendisabelkan difabel yang dalam konteks tertentu sebenarnya mereka telah berlaku diskriminatif terhadap difabel. Kontestasi Konsep Disabilitas di Indonesia Persoalan konsep dan terminologi disabilitas di Indonesia masih merupakan persoalan pelik yang sejauh ini belum merata pemahamannya. Bagi banyak orang di Indonesia, Disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya. Saat ini ada beberapa istilah yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, yakni penyandang cacat, difabel, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan berbagai istilah lain yang bersifat lokal yang langsung merujuk kepada tampilan fisik atau kebiasaannya, misalnya di Makassar to kandala atau si kusta dan di Jawa si buntung, si pengkor, cah panti (anak yang tinggal di Panti) dan lain sebagainya. Secara internasional, penamaan yang dipakai adalah disabled person, person with disabilities, person with difabilities, dan beberapa lainnya sesuai konteks negaranya. Organisasi Kesehatan Dunia memakai istilah person with disabilities dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan terbitnya sebuah konvensi, yakni Convension on Rights of Persons with Disabilities atau disingkat UN-CRPD. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini pada 2011 dan saat ini sedang mendorong lahirnya UU Disabilitas sebagai tindaklanjut pascaratifikasi dan sekaligus mengganti UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Di Indonesia, kesalahan memahami disabilitas sebagai sesuatu yang sakadar merujuk pada individu merupakan kesalahan yang dipraktikkan berpuluh tahun lamanya. Sejak lama, negara ini menyebut mereka ‘cacat’. Di zaman Orde lama mereka disebut ‘penderita cacat’ dan di zaman Orde Baru mereka disebut ‘penyandang cacat’. Menurut sejumlah aktifis difabel kata ‘cacat’ hendaknya hanya disematkan kepada barang yang rusak. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial bukanlah kreasi yang rusak. Sebagai ciptaan ia sempurna, sebagai makhluk sosial ia punya kemampuan yang berbeda. Dahulu dan bahkan masih terjadi saat ini, seseorang karena disebut ‘cacat’ atau ‘sakit’ maka ia perlu direhab di panti rehabilitasi dan dibedakan secara sosial baik di ranah pendidikan, ranah kesehatan, dan tentu saja di ranah hukum dan politik (Wawancara dengan M. Joni Yulianto, 2013). Menguatnya wacana ‘penyandang cacat’ di Indonesia pada era 1990-an sesungguhnya memperoleh perlawanan dari sejumlah organisasi gerakan sosial. Dua di antara aktifis tersebut adalah Setyo Adi Purwanta (aktifis difabel netra) dan Mansour Fakih (aktifis gerakan sosial Indonesia) memperkenalkan konsep perbedaan kemampuan atau ‘differently able’ yang kemudian secara luas dikenal sebagai difabel (pengindonesiaan dari akronim dif-able). Istilah penyandang disabilitas tergolong baru muncul sebagai pengganti dari penyandang cacat setelah pemerintah meratifikasi konvensi tersebut. Namun bagi banyak kalangan aktifis difabel yang lebih memahami makna ‘difabel’ menyebutkan bahwa istilah penyandang disabilitas tak lebih dari sekadar penghalusan dari kata penyandang cacat yang selama ini sesungguhnya sangat kental dengan perspektif medik yang menganggap tubuh difabel sebagai tubuh yang sakit sehingga harus dibantu dengan berbagai model kebijakan yang charity based. Jumlah difabel di Indonesia secara pasti tidak diketahui, jika merujuk pada TNP2K, maka jumlahnya 10% dari total populasi (TNP2K 2012). Namun jika merujuk pada data ‘World Report on 134 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Disability (WHO 2012), di Negara berkembang seperti Indonesia, jumlahnya mencapai lebih 15%.3 Dengan konsep dan terminologi yang berbeda-beda, BPS, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial masing-masing mempresentasikan data yang tidak seragam. Implikasinya adalah menumbulkan kesulitan menjadikan sebagai bahan acuan untuk formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan pemahaman akan definisi disabilitas. Jika merujuk pada ICF saja, maka ada begitu banyak jenis keragaman disabilitas yang dibedakan berdasarakan Kategori intelektual, Kategori Mobilitas, Kategori Komunikasi, Kategori Sensorik, dan kategori Psikososial (lihat lebih lanjut Are, Who We, et al. “The International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): a global model to guide clinical thinking and practice in childhood disability.” (2003). Untuk itulah, makna disabilitas penting dipahami bersama. Disabilitas, menurut Schneider adalah sebuah capaian dari interaksi antara ‘seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu’ dengan ‘konteks atau lingkungan di mana seseorang itu berada’. Lebih lanjut Menurut Schneider, dalam upaya kita memahami disabilitas, maka disabilitas tidak sekadar merujuk kepada individu seseorang. “disability should be understood by looking at levels of physical and personal functioning and how this interacts with environmental factors” (Schneider, 2006). Hal ini karena ada dua konteks dalam pengertian di atas, yakni konteks eksternal dan internal seseorang. Konteks eksternal adalah lingkungan sosial, budaya, politik yang tidak aksesibel dengan orang tersebut. Lingkungan sosial ini bisa dalam bentuk pengetahuan atau mitos yang mendiskreditkan seseorang, budaya yang diskriminatif, kebijakan sosial yang tidak sensitif terhadap disabilitas dan lain sebagainya. Sedangkan konteks internal menyangkut usia seseorang, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan kepribadian seseorang”. Di Indonesia, faktor-faktor lingkungan inilah yang sesungguhnya seringkali justru lebih dominan dalam menciptakan seseorang menjadi difabel (disabled). Jadi, jika seseorang, karena struktur dan fungsi tubuhnya tidak lengkap sebagaimana atau tidak berfungsi sebagaimana tubuh manusia sewajarnya, maka untuk menopang aktifitasnya seseorang membutuhkan sejumlah alat bantu. Pun demikian, jika karena kondisi tubuh/mental/ pikiran seseorang membuatnya harus mengandalkan alat bantu demi beraktifitas secara layak maka begitu ia memutuskan berpartisipasi dalam ranah publik, ia tentu membutuhkan dukungan sosial. Jika memilih wakil rakyat adalah hak bagi setiap orang dewasa, maka apakah infrastruktur bagi transportasi publik memungkinkan dirinya yang berkursi roda dapat tiba ke lokasi pencoblosan dengan mudah? Apakah dari jalan raya saat dia turun dari kendaraannya atau angkutan publik menuju TPS dan bilik suara juga ia bisa lalui secara mudah sebagaimana pemilih-pemilih lainnya yang berjalan dengan kakinya? Meskipun di Indonesia wacana disabilitas dalam perspektif yang lebih positif masih merupakan impian yang harus diraih, sesungguhnya pemahaman manusia tentang disabilitas sudah berkembang kearah kemajuan. Pada dekade 80 dan 90-an, Nagi, IOM, dan WHO memperkenalkan konsep disabilitas yang bersandar pada cara pandang ‘patologi’ dan ‘penyakit’. Ketiga ragam pemahaman itu membagi tiga level pengertian, yakni level organ tubuh, level personal, dan Data Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa disabilitas telah mencapai sekitar 15% dari total penduduk di Negara-negara dunia. sedangkan di Indonesia, jumlah difabel diperkirakan mencapai 36. 150. 000 orang; sekitar 15% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 difabel Indonesia diperkirakan sebanyak 1. 480. 000 dengan rincian : fisik 162. 800 (11%), tunanetra 192. 400 (13%), tuna rungu 503. 200 (34%), mental dan intelektual 348. 800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberklosis) 236. 800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah difabel yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan (Data-data ini secara keseluruhan dihimpun dari berbagai laporan seperti PERTUNI, GERKATIN, BPS, dan lembaga lainnya, Syafi’ie, 2012). 3 135 Jurnal The Politics level sosial. Pada level organ, tubuh yang tak lengkap karena alasan patologi atau penyakit mereka sebut ‘impairment’. Sedangkan pada level personal seseorang, baik Nagi maupun IOM menggunakan istilah keterbatasan fungsional akibat struktur tubuh yang impairment tadi. WHO sendiri menyebutnya disabilitas. Pada level ketiga atau level sosial, Nagi dan IOM menyebutnya disabilitas, sedangkan WHO menyebutnya handicap. Pembedaan pemahaman atau konsep dan terminologi ini ke dalam 3 level merupakan cara untuk menghindari kesan negatif atau stereotif dari masyarakat kepada seseorang (lihat Whiteneck, Gale. “Conceptual models of disability: past, present, and future.” Workshop on disability in America: A new look. Washington DC: The National Academies Press, 2006). Bandingkan dengan Indonesia yang berdasarkan UU No. 4 tahun 1997 yang menyebut mereka sebagai ‘penyandang cacat’. Dengan menapikan aspek sosial, dampak dari peristilahan dan pemahaman yang keliru ini maka pendekatan pembangunan di Indonesia menjadi lebih ‘charity’ ketimbang ‘pemberdayaan’ dalam arti sesungguhnya. Seiring perkembangan waktu dan pengalaman menerapkan konsep dan terminologi ini di ranah praktis atau kebijakan, penyempurnaan atas konsep itu berkembang ke arah lebih baik. Kini, dimulai sejak 1997 oleh IOM dan 2001 oleh WHO muncul domain baru dalam upaya memahami seorang manusia yang memiliki perbedaan struktur dan fungsi tubuh, yakni domain ‘faktor lingkungan’ dan ‘faktor personal’. Apa yang sebelumnya disebut impairment berubah menjadi struktur dan fungsi tubuh (level 1 [organ]). Di level 2 (person) sebelumnya disebut keterbatasan fungsional menjadi ‘aktifitas’ yang nadanya lebih dinamis ketimbang pasif. Kemudian, apa yang disebut disabilitas atau handicap kini dipahami sebagai ‘partisipasi’ dengan bentuk aktifitas di wilayah publik/sosial. Bagaimana kondisi ketiganya: tubuh, aktifitas, dan partisipasi ini berjalan amat bergantung pada bagaimana faktor lingkungan semisal sistem pengetahuan, ajaran agama, paradigma, dst dan faktor personalitas seseorang terkait usia, jenis kelamin, orientasi seksual, kepribadian dan seterusnya, memperlakukan seseorang. Jika menggunakan konsepsi WHO di atas di mana aspek kesehatan masih menjadi salah satu aspek dalam memahami kehidupan disabilitas, maka gambaran disabilitas kurang lebih sebagai berikut. Fungsi dan struktur tubuh difabel adalah mencakup jenis-jenis impairment atau gangguan fungsi tubuh dan mental. Misalnya seseorang baru saja mengalami operasi amputasi lengan atau kakinya. Lalu, saat ia akan beraktifitas maka kita akan melihat dari aspek ‘aktifitas’ kesehariannya. Aspek aktifitas ini dapat mencakup cara atau metode belajar, cara makan, cara mandi, perawatan tubuh, dan pekerjaaan di rumah dan lain-lain. Dalam beraktifitas inilah maka difabel tadi membutuhkan alat-alat bantu semisal kruk, kaki palsu, atau kursi roda dan tentu saja sejumlah desain yang memudahkan ia beraktifitas seperti model kamar mandi atau WC, model pintu kamar, model meja belajar, dan lain-lain terkait dengan jenis aktifitasnya. Aspek lain adalah Partisipasi di ranah publik. Partisipasi difabel mencakup jenis dan tingkat partisipasi di luar rumah, bagaimana orang-orang kemudian memperlakukan atau menerimanya secara sosial. Contohnya, bagaimana ia menuju mesjid atau gereja untuk beribadah. Bagaimana ia menuju lokasi kantornya saat hendak bekerja, lingkungan kantornya dan perlakukan rekan-rekan kerjanya dan tentu saja kebijakan kantor dan seterusnya dengan beragam jenis partisipasi, apakah partisipasi ekonomi, pendidikan, dan tentu saja politik. Setelah itu, perhatikan lagi bagaimana Faktor Lingkungan difabel yang mencakup: kondisi lingkungan, sistem pengetahuan, budaya, keyakinan warga, dan sebagainya. Sedangkan pada Faktor Personal difabel akan meliputi faktor usianya, jenis kelaminnya, orientasi seksualnya, pandagan hidupnya, latar pengetahuan dan pengalamannya dan lain sebagainya (Sumber: Bahan Pelatihan Penelitian, SIGAB 2014). 136 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Bagan Model Disabilitas ICF Membaca Kualitas Calon Legislator dan Upaya Organisasi Difabel Membangun Perspektif Difabilitas dalam Sistem Pemilu dan Parlemen: Hasil sebuah Survei Pemilu, Politisi, dan Pemilih Difabel Dalam konteks pemilihan umum, dua aktor yang berjibaku dalam ruang-ruang partisipasi adalah politisi (legislator dan calon legislator) dan pemilih (dalam hal ini pemilih difabel). Relasi antar keduanya penting dipelajari, seperti bagaimana calon legislator atau politisi memahami difabel dan memandang seluk beluk penghidupan mereka baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, yakni kehidupan sosial dan politik dan demikian sebaliknya. Sebuah survei yang diselenggarakan oleh SIGAB dengan bekerjasama The Asia Foundation (TAF) merupakan salah satu upaya untuk memahami relasi tersebut. Survei ini berlangsung sepanjang Desember 2013 - Januari 2014 ini menelusuri, [1] Pemahaman calon legislator menyangkut istilah atau peristilahan difabel meliputi ‘penyandang cacat’, ‘penyandang disabilitas’, dan ‘difabel’. [2] Pemahaman calon legislator menyangkut jenisjenis difabel dalam lingkungan sosial-politik calon legislator. [3] Bentuk interaksi sehari-hari antara calon legislator dengan pemilih difabel. [4] Pemahaman calon legislator menyangkut 10 sektor kebijakan sosial. [5] Keberpihakan calon legislator terhadap warga difabel dalam partai politik dan peluang terbangunnya kontrak politik dengan difabel. Dengan memahami kelima aspek di atas, maka akan tergambar bagaimana perspektif difabel dalam diri calon legislator dan dapat memberi gambaran bagaimana tingkat kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi wakil rakyat di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga akan memberi gambaran bentuk relasi antara anggota legislator - difabel secara kelembagaan, DPRD dengan Organisasi difabel di 4 daerah. Survei ini menggunakan metode sampling ‘Model Slovin’ dengan rumus ‘jumlah sampel = jumlah populasi di bagi [dari hasil penjumlahan] 1 + jumlah populasi dikalikan batas toleransi kesalahan [0,07]. Tingkat akurasi survei adalah 93%. Unit populasi dalam penelitian ini adalah besaran Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD di 4 kota. Setelah mengetahui jumlah populasi maka Hasil penghitungan sampel dengan model Slovin menghasilkan jumlah responden sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah. 137 Jurnal The Politics Tabel 1 Jumlah Responden Kota DCT Balikpapan Makassar Bantul Situbondo 508 600 466 501 DCT Perempuan 30% 30% 30% 30% DCT Laki-Laki 70% 70% 70% 70% Responden Perempuan 44 46 53 44 Responden Laki-Laki 102 107 78 102 Total Responden 146 153 142 142 Sumber: SIGAB, 2014 Adapun penentuan sampel adalah dengan metode simple random sampling dengan tahapan sebagai berikut: [1] Seluruh partai politik di setiap daerah pemilihan merupakan area sampling. [2] Dalam menentukan sampling di seluruh partai politik di setiap daerah pemilihan ditetapkan prosentase caleg laki-laki dan perempuan. Tiga dari 4 kota memiliki 30% caleg perempuan, sementara Yogyakarta memiliki 40% caleg perempuan. [3] Setelah menetapkan besaran sampel dari seluruh partai politik di setiap daerah pemilihan maka responden dipilih secara sederhana (simple random sampling). Identitas Responden. Dari empat daerah penelitian ini, gambaran identitas responden diklasifikasi ke dalam beberapa karakteristik. Makassar. Gambaran identitas responden adalah mayoritas dari mereka merupakan kandidat yang baru pertamakalinya mencalonkan diri (54,01%). Dari 45,99% responden yang telah lebih dari sekali mencalonkan diri itu, 81.82% adalah laki-laki. Usia responden didominasi oleh kandidat berusia 40-49 tahun sebesar 49,64%. Tingkat Pendidikan responden adalah mayoritas sarjana sebesar 80,29%. Pekerjaan kandidat mayoritas adalah Pegawai Swasta dan Pengusaha yang mencapai 52,55%. Umumnya, pengeluaran mereka perbulannya lebih dari dua juta, yakni sebesar 81,02%. Balikpapan. Sebagaimana Makassar, Balikpapan memiliki karakter responden yang relatif sama, yakni Mayoritas responden adalah kandidat baru. Sementara itu, mayoritas yang sudah lebih satu kali mencalonkan adalah Laki-laki. Umur responden Rata-rata berusia 40-49 tahun. Tingkat Pendidikan: Mayoritas Sarjana. Pekerjaan: Mayoritas adalah Pegawai Swasta dan Pengusaha. Pengeluaran: Mayoritas di atas 2 juta perbulan dan pengeluaran. Bantul. Mayoritas responden adalah kandidat baru sejumlah 72,26%. Terdapat 27,74% responden yang sudah lebih sekali mendaftar adalah laki-laki dengan jumlah 84.21%. Serupa dengan Balikpapan dan Makassar, responden mayoritas adalah yang berusia 40-49 tahun sejumlah 42,75% dan berusia 30 - 39 tahun sebesar 30,43%. Sebesar 45,65% adalah responden dengan pendidikan sarjana dan merupakan dominan. Dari sisi pekerjaan, mayoritas adalah Pegawai Swasta [21,74%], Pengusaha [6,52%] dan cukup besar menyebut pekerjaan lainnya sebesar 35,51%. Sebanyak 42,75% berpendapatan lebih dari dua juta perbulan. Situbondo. Sebanyak 72,26% adalah kandidat baru. Usia responden mayoritas berusia 4049 tahun [40,15%] dan berusia 30 - 39 tahun [33,58%]. Tingkat Pendidikan responden mayoritas Sarjana, 49,64% dan Tamat SLTA, 46,72%. Pekerjaan: Mayoritas adalah Pegawai Swasta dan Pengusaha dengan mayoritas pendapatan di atas 2 juta perbulan adalah 47,45%. 138 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Analisis Hasil Survei Berawal Dari Istilah Dalam survei terdapat tiga istilah yang dipertanyakan kepada responden, yakni penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Ketiga istilah ini masih silih berganti dipakai oleh pengguna bahasa. Mulai dari perbincangan orang kebanyakan hingga dalam perdebatan sosial politik di ranah publik. Ketiga istilah memiliki akar kesejarahannya yang bukan sekadar bagian dari perbincangan biasa namun sampai pada politik kebahasaan seperti dalam diskursus. Terdapat perbedaan mendasar dalam politik kebahasaan khususnya dalam menggunakan suatu istilah dalam suatu ‘perbincangan’ dengan istilah dalam ‘diskursus. Perbincangan hanyalah hingar bingar komunikasi yang tak memiliki makna dan tujuan politik. Ketika istilah ‘penyandang cacat’ atau ‘penyandang disabilitas’ atau ‘difabel’ dipakai dalam perbincangan, maka itu sekadar perbincangan tanpa tujuan. Penggunaan istilah yang satu dengan istilah lainnya dipertukarkan secara semena-mena dan seolah-olah tak punya makna. Pada satu perbincangan seseorang memakai kata disabilitas dan di sisi lain masih pakai pula kata cacat. Padahal, baik penyandang cacat, penyandang disabilitas, maupun difabel atau difabilitas memiliki akar politiknya. Penyandang cacat misalnya. Istilah ini sangat lazim diucapkan di masa lalu. Khususnya setelah pemerintah Orde Baru menggunakan istilah itu dalam nomenklatur hukum dengan memuatnya dalam satu Undang-undang khusus, yakni UU Penyandang Cacat pada tahun 1996. Istilah ini dipakai dengan asumsi medikal yang kental yang menganggap bahwa sebagai tubuh yang tak lengkap adalah sebuah kerusakan fisik atau fisiologis. Kerusakan itulah yang kemudian disebut sebagai cacat, sebagaimana istilah ini kerap dipakai untuk barang yang rusak. Kerusakan tentu saja bermakna sakit dalam dunia medikal atau kesehatan. Istilah cacat yang berarti sakit secara fisik dan atau fisiologis ini kemudian membutuhkan berbagai tindakan medik baik melalui perawatan di sarana kesehatan maupun rehabilitasi di panti rehabilitasi yang marak berdiri di berbagai kota. Pandangan kesehatan bahwa seseorang yang “cacat” itu adalah seorang yang sakit lalu mempengaruhi cara pandang banyak orang, baik kaum kebanyakan maupun pengambil kebijakan. Akibatnya, di lingkup sosial kemasyarakatan muncullah berbagai stigma negatif terhadap para “kaum cacat” ini yang membuat mereka membangun sebuah konstruksi sosial bahwa mereka adalah warga yang patut dikasihani dan dibantu. Konsekuensi dari perlakuan ini membuat terbangunnya sebuah relasi antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Posisi ini kemudian terus mengalami perkembangan sehingga membuat ‘si pemberi’ menjadi pihak yang lebih tinggi status sosialnya dengan ‘si penerima’ bantuan. Terbentuklah kelas sosial yang membuat ‘kaum cacat’ di masa itu sebagai warga kelas dua, warga marjinal, dan tentu saja miskin dan rentan. Kerentanan difabel (yang disebut ‘kaum cacat’ dalam perspektif Rezim Orde Baru) semakin menjadi-jadi saat kebijakan sosial semakin menempatkan mereka sebagai pihak yang sepatutnya terus menerus dibantu karena adanya anggapan bahwa mereka tak dapat keluar dari masalahnya akibat kekurangan tubuh dan keterbatasan mental yang dimilikinya. Di bidang pendidikan, stigma ini berlanjut dengan pemisahan mereka dengan sistem pendidikan nasional dengan menyebut metode pendidikan mereka sebagai metode pendidikan luar biasa. Istilah ‘luar biasa’ sendiri sudah menunjukkan sebuah upaya eksklusi (penyingkiran) difabel dalam sistem pendidikan yang seharusnya inklusif atau berlaku bagi siapapun tanpa diskriminasi. Tentu saja, makna diskriminasi dapat ditemukan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di mana pada saat itu di masa pemerintahan rezim otoritarian tidak begitu umum dipertimbangkan sebagai dasar pengaturan sosial politik di negeri ini. Wacana hak asasi ini baru muncul kemudian di akhir masa kejatuhan Presiden Soeharto. Dalam alam politik di mana perspektif HAM mulai menjadi wacana alternatif untuk 139 Jurnal The Politics menandingi wacana dominan maka muncullah istilah baru yang disebut difabel pada akhir dekade 90-an. Istilah ini merupakan akronim dari ‘Differently able’ yang kemudian disesuaikan katanya dari dif-able menjadi difabel. Wacana tanding ini lahir di Jogjakarta yang merupakan hasil perbincangan serius antara Setyo Adi Purwanta dengan Mansour Fakih. Setyo Adi Purwanta adalah seorang difabel netra (buta total) dan Mansour Fakih adalah aktifis gerakan sosial yang di masa itu pemikirannya banyak menginspirasi para aktifis gerakan sosial, khususnya orang-orang kampus dan masyarakat sipil lainnya. Dua wacana ini terus menerus berkontestasi dalam ruang politik yang kemudian melahirkan sejumlah pemikiran dan aksi gerakan sosial. Asumsi dasar pengusung istilah difabel adalah manusia makhluk yang sempurna. Tuhan maha sempurna dan tidak ada ciptaannya yang tidak sempurna. Perbedaan hanya pada bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Setiap orang bagaimanapun menggunakan alat bantu untuk melakukan sesuatu. Alat bantu itu kemudian disesuaikan dengan bagian tubuh tertentu untuk mengerjakannya. Jemari untuk menulis atau melukis dan menyuap makanan, kaki untuk melangkah, mata untuk membaca, dan seterusnya. Perbedaannya kemudian adalah pada cara melakukan sesuatu. Setiap orang nyaris bisa melakukan apapun dengan cara sesuai kemampuannya dan sesuai alat bantunya. Persoalan mendasar dalam dunia sosial keseharian setiap orang adalah seberapa tersedia alat bantu baginya di lingkungannya. Seberapa mampu sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah masyarakat atau sebuah pemerintah mampu menyiapkan alat bantu itu dan pada kadar tertentu menyediakan ruang gerak bagi setiap orang. Dengan demikian, ketersediaan dan akses atas alat bantu itu menjadi penentu apakah sebuah sistem sosial baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun dalam bidang politik mampu memberi peluang yang sama kepada setiap orang atau malah memudahkan yang satu dan menyulitkan yang lain. Atau dalam istilah lain menyingkirkan yang satu dan memasukkan yang satu. Pendeknya, wacan difabel menguat seiring dengan menguatnya wacana hak asasi manusia. Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on Rights for Person With Disabilities (CRPD). Istilah Person With Disabilities kemudian diterjemahkan menjadi Penyandang Disabilitas dan kemudian menambah istilah baru untuk menyebutkan subjek yang sama sebagaimana dirujuk oleh Penyandang Cacat dan Difabel. Penggunaan istilah Penyandang Disabilitas lalu menjadi istilah baru yang memperkaya perbincangan dan perdebatan di ranah ini. Dua istilah belakangan ini sudah semakin menyingkirkan wacana dominan dan hingga kini semakin berkurang penggunanya. Hanya mereka yang tak memahami akar historis penggunaan istilah ini yang benar-benar tak bisa memahami kapan harus menggunakan istilah penyandang cacat, difabel, dan penyandang disabilitas. Salah satu aktor yang tidak memahami itu adalah calon legislator sebagaimana tercermin dalam hasil survei ini. Di Kota Makassar, mayoritas responden yang masih menggunakan istilah ‘penyandang cacat’ dalam perbincangan sehari-hari adalah 74,5%, ‘penyandang disabilitas’ sebesar 24,8% dan difabel hanya 7%. Di Kota Balikpapan, jumlah responden yang masih menggunakan istilah penyandang cacat dalam keseharian mereka bahkan lebih besar lagi yang mencapai 80,8%. Sementara itu di Kabupaten Bantul, di mana istilah difabel sudah lazim dipakai jumlah responden yang masih menggunakan istilah penyandang cacat hanya sebesar 31,8%.. Sementara itu di Kabupaten Situbondo provinsi Jawa Timur, penggunan istilah penyandang cacat jumlah penggunanya jauh lebih besar dari ketiga areal lainnya yakni 91,2% responden. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah calon legislator yang hingga kini masih menggunakan istilah penyandang cacat secara umum masih tinggi. Hal ini diakibatkan karena responden memang tidak mengetahui perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Hal ini khususnya terjadi di Situbondo, 140 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Makassar dan Balikpapan. Menyangkut pemahaman calon legislator mengenai istilah ini, berturut-turut jumlah responden yang tidak mengetahui perbedaan mendasar antara istilah penyandang disabilitas dengan penyandang cacat adalah Makassar 60%, Kota Balikpapan 61%, Situbondo 72%, dan Bantul 57%. Mayoritas responden dari 4 daerah juga tidak mengetahui benar perbedaan antara istilah penyandang disabilitas dengan difabel di mana Situbondo memiliki prosentase tertinggi yang tidak mengetahui perbedaan difabel dengan penyandang disabilitas: 77%. Hasil survei ini menunjukkan bahwa dari segi peristilahan, isu disabilitas memang masih menjadi isu langka yang dipahami oleh calon legislator. Untuk mengetahui sejauhmana institusi partai politik memasukkan isu disabilitas sebagai bagian dari platform politik partai harus ada penelitian lanjutan. Namun berdasarkan pemahaman mereka yang belum ditelusuri secara kualitatif melalui penelusuran dokumen kepartaian menunjukkan bahwa di Makassar, Balikpapan, Situbondo dan Bantul mayoritas responden menyebutkan bahwa Partai Politik di mana mereka berkecimpun sudah memasukkan isu disabilitas dalam platform partai politik. Pun dengan apakah calon legislator ini benar-benar aktifis partai politik sehingga paham platform partai politiknya ataukah ia sekadar orang yang ‘dicomot’ menjelang pemilu untuk melengkapi jumlah kontestan dari setiap partai politik untuk bertarung dengan calon legislator dari partai lain juga masih membutuhkan penelitian lanjutan. Namun, secara umum, publik mengetahui bahwa calon legislator ini baru memasuki dunia kepartaian saat pemilu sudah semakin dekat. Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar anggota partai politik dan jauh lebih kecil lagi yang memang menjalankan fungsi kepartaian seperti melakukan pendidikan politik di tingkat warga, mengumpulkan dan menindaklanjuti aspirasi kepentingan rakyat, mengkomunikasikan segala informasi politik semisal sosialisasi kebijakan publik baru dan seterusnya. Disabilitas Bukan sekadar Buta, Tuli, atau Bisu Penelusuran lebih jauh atas pengetahuan responden tentang jenis-jenis disabilitas. Dalam survei ini, jenis disabilitas yang dimaksud dalam survei ini mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hakhak Penyandang Disabilitas. Adapun jenis disabilitas dimaksud adalah gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, cerebral palsy, gangguan pemusatan, perhatian dan hiperaktif, autis, epilepsi, tourette’s syndrome, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, serta retardasi mental. Dengan model bertanya secara terbuka, responden diminta menyebutkan jenis-jenis disabilitas yang ia ketahui di mana pewawancara memberi tanda jenis disabilitas apa saja yang bisa ia sebutkan atau ketahui sampai ia berhenti dan merasa tidak mengetahuinya lagi. Hasil survei menunjukkan bahwa di Kota Makassar, jumlah responden yang menjawab jenis disabilitas di atas 50% adalah difabel netra (89.78%), Difabel Wicara (83,21), Difabel Rungu (81,02%), dan Difabel Motorik dan Mobilitas (55,47%). Sementara jumlah responden yang menyebutkan jenis disabilitas di bawah 50% berturut-turut adalah Difabel autis (22,63%), Difabel Retardasi Mental (16,79%), Difabel Epilepsi (10,22%), Difabel Gangguan Sosialitas, Emosional dan Prilaku (9,49%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (5,84%), Difabel Cerelebral Palsy (5,84%) dan Difabel Tourete’s Syndrome (4,38%). Di Kota Balikpapan, selain difabel netra, rungu, wicara, motorik dan mobilitas yang mencapai angka di atas lima persen, autis juga menempati urutan teratas yang diketahui oleh responden. Adapun urutannya adalah Difabel Netra (95,8%), Difabel Rungu (89,7%), Difabel Wicara (89%), 141 Jurnal The Politics Difabel Motorik dan Mobilitas (60,9%), Difabel autis (60,2%), Difabel Epilepsi (56,1%), Difabel Tourete’s Syndrome (14,3%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (11,6%), Difabel Retardasi Mental (9,5%), Difabel Cerelebral Palsy (6,1%), Difabel Gangguan Sosialitas, serta Emosional dan Prilaku (6,1%). Di Kabupaten Bantul nyaris serupa dengan Makassardi mana hanya Difabel Netra, rungu, wicara dan motorik dan mobilitas yang memiliki poin paling diketahui oleh responden. Adapun prosentasenya adalah sebagai berikut Difabel Netra (89,86%), Difabel Rungu (78,99%), Difabel Wicara (71,74%), Difabel Motorik dan Mobilitas (59,42%), Difabel autis (45,65%), Difabel Epilepsi (30,43%), Difabel Retardasi Mental (28,26%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (20,29%), Difabel Gangguan Sosialitas, Emosional dan Prilaku (18,12%), Difabel Tourete’s Syndrome (9,42%) serta Difabel Cerelebral Palsy (6,52%). Sedangkan di kabupaten Situbondo, merupakan kabupaten dengan tingkat pengetahuan respondennya paling rendah di antara tiga areal lainnya. Hanya difabel rungu, difabel netra, dan difabel wicara yang paling tinggi tingkat diketahuinya jenis disabilitas tersebut. Angkanya pun sesungguhnya masih lebih rendah dari kabupaten lain. Misalnya untuk Difabel Rungu yang hanya 72,99%, Difabel Netra sebesar 67,88%, dan difabel wicara sebesar 63,50%. Di daerah lain, jenis disabilitas tersebut setidaknya mencapai angka di atas 80%. Selain itu, jensi disabilitas diketahui oleh sebagian kecil responden seperti Difabel Motorik dan Mobilitas (24,09%), Difabel autis (10,95%), Difabel Retardasi Mental (8,76%), Difabel Epilepsi (8,76%), Difabel Gangguan Sosialitas, Emosional dan Prilaku (2,92%), Difabel Pemusatan Perhatian dan hiperaktif (2,19%), Difabel Cerelebral Palsy (0,73%), dan Difabel Tourete’s Syndrome (0,73%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik di Kota Makassar, Kota Balikpapan, maupun Kabupaten Bantul dan Situbondo, tingkat pengetahuan responden atas jenis disabilitas difabel berbanding lurus dengan tingkat Interaksi Caleg dengan Difabel. Artinya Pengetahuan Caleg soal Jenis Disabilitas/Difabilitas berdasarkan jenis impairment atau gangguan fungsi fisik dan mentalnya yang mudah teridentifikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang calon pengambil kebijakan di masa datang (jika terpilih) perlu mengetahui bahwa difabel bukan sekadar buta, tuli, atau bisu saja. Namun, difabel lebih dari ketiganya, juga meliputi jenis lain. Mengapa? Karena beda jenis impairment akan membutuhkan beda cara pandang dan mendekatinya. Sehingga dengan memahami perbedaan perlakuan akan membuat kebijakan sosial pun bisa lebih peka dan berpihak pada penyandang disabilitas. Lebih jauh survei ini juga menelusuri bagaimana hubungan dan sejauhmana interaksi calon legislator dengan difabel. Di seluruh area survei menunjukkan bahwa hubungan Caleg dengan difabel mayoritas tidak terkait secara biologis atau memiliki hubungan keluarga melainkan lebih pada hubungan pertemanan atau tetangga. Hanya jumlah yang sangat sedikit mengidentifikasi hubungan dengan difabel sebagai mitra kerja. Hal ini menunjukkan masih minimnya pola hidup inklusi berlangsung dalam kehidupan keseharian di mana responden tinggal menetap. Kemitraan dalam dunia kerja menuntut adanya interaksi pemikiran dan kerjasama dalam mencapai target pekerjaan dan ini tidak tampak dalam keseharian dengan responden. Bentuk Interaksi yang paling dominan yang terjadi antara responden dengan caleg adalah sekadar berbincang biasa dan memberi sumbangan. Dibandingkan dengan Kota Makassar, Kabupaten Bantul, Kabupaten Situbondo, mayoritas responden di tiga areal ini berinteraksi secara dominan dengan menyebut bahwa ‘berbincang-bincang biasa’ masih jauh lebih dominan ketimbang memberi sumbangan. Di Balikpapan yang terjadi sebaliknya. Mayoritas responden justru lebih tinggi dalam memberi sumbangan ketimbang interaksi dengan cara lain semisal berbincang biasa, bertukar pikiran, bekerjasama, dan belajar/mengajar. 142 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Dari sudut pandang difabel, dalam beberapa diskusi internal yang SIGAB lakukan di 4 daerah survei ini. Diskusi soal kehidupan inklusi menunjukkan bahwa komunitas difabel memang merasa diri masih jauh dari menikmati hidup inklusi itu. Faktor utama yang memengaruhinya adalah soal aksesibilitas. Aksesibilitas ke ruang publik misalnya, mulai dari sekolah di mana kebanyakan dari difabel peserta didik harus bersekolah di sekolah khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa. Pun demikian dengan ruang publik lainnya seperti di pemerintahan untuk mengurus segala keperluan difabel sebagai warga negara maupun organisasi sosial politik lainnya seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OSM) atau LSM, dan tentu saja Partai Politik. Hambatan aksesibilitas ini membentang dari hal yang bersifat fisik seperti desain gedung yang tidak aksesibel bagi mereka, hambatan informasi yang menyulitkan dengan ketiadaan atau ketidaksesuaian dengan alat bantu akses informasi yang difabel gunakan, sampai pada aspek hambatan mental di mana difabel merasa diri dikelasduakan dan non-difabel menganggap difabel sebagai warga yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Di masa lalu bahkan ada satu jenis hambatan yang juga dirasakan difabel, yakni adanya aturan untuk tampil di ranah publik yakni harus ‘sehat jasmani dan rohani’. Hambatan legal ini menutup pintu partisipasi difabel untuk mengisi ruang-ruang publik bagi mereka. Jejak Difabilitas Dalam Kebijakan Sosial Survei ini juga berupaya menjangkau sejauhmana pemahaman calon legislator sekaitan dengan praktik kebijakan sosial yang diterapkan di setiap area penelitian. Hal ini penting mengingat mayoritas warga difabel sesungguhnya berada dalam situasi kerentanan yang menyebabkan mereka menderita kemiskinan. Kesulitan akses ke sarana pendidikan misalnya berimplikasi pada sulitnya mereka terserap ke dalam sektor ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja formal yang membutuhkan ijasah. Pun sebenarnya hambatan ini bisa berdiri sendiri, misalnya bisa saja difabel menempuh pendidikan namun setelah selesai tetap saja kesulitan diterima sebagai tenaga kerja karena hambatan internal perusahaan di mana ia hendak bekerja, khususnya hambatan fisik. Banyak perusahaan tidak menerapkan universal design terhadap gedung dan segala perlengkapan kerja. Ada sepuluh sektor kebijakan yang ditelusuri dalam survei ini, yakni pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni/budaya/olahraga, politik, hukum, Penanggulangan Bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Dalam artikel ini, penulis tidak akan memaparkan secara mendalam hasil survei di setiap tema kebijakan namun hanya memaparkan prioritas kebijakan apa yang seharusnya diatasi di wilayah masing-masing. Di Makassar, berdasarkan pemahaman calon legislator, kebijakan sosial yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan penghidupan difabel adalah Pendidikan (83.94%), Kesehatan (69.34%), dan Ketenagakerjaan (59.12%). Sementara untuk kebijakan sosial yang berada urutan yang paling tidak prioritas adalah kebijakan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana (0,73%), kebijakan politik (2,92%), dan seni, budaya dan olah raga (5,11%). Sementara itu, kebijakan sosial berkaitan dengan tempat tinggal (22.63%), Aksesibilitas (18.25%) dan hukum (10.22%) berada di level menenagah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Di Kalimantan Timur, Calon Legislator dari kota Balikpapan hasilnya relatif sama, hanya saja posisi kebijakan berkaitan dengan Aksesibilitas lebih tinggi di mana berada di posisi keempat dibandingkan dengan Makassar diurutan keenam. Sementara itu, di DIY, dalam hal ini di kabupaten Bantul, wilayah yang terkena bencana gempa pada tahun 2006 justru menempatkan kebijakan kebencanaan di titik terakhir. Bahkan tak ada seorang calon legislator pun memilih dan menempatkan kebijakan ini di posisi prioritas. Padahal bencana itu, mengingat kerentanan difabel 143 Jurnal The Politics dan kerentanan fisik tempat tinggal warga Bantul membuat warga difabel kesulitan menyelamatkan diri dan di satu sisi korban yang berjatuhan dan menjadi difabel adalah cukup tinggi. Di Yogyakarta, saat hasil riset ini disampaikan dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh sejumlah difabel dari berbagai organisasi difabel di Yogyakarta, menimbulkan sejumlah diskusi menarik dengan mempertanyakan mengapa calon legislator abai terhadap isu atau kebijakan kebencanaan. Pandangan ini di satu sisi menunjukkan ketidakpekaan kandindat legislator kepada difabel dan di sisi lain menunjukkan betapa ‘kebencanaan’ belum menjadi perspektif utama di wilayah seperti Bantul yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi atas bencana (Bencana Gempa Bumi di Bantul terjadi pada tahun 2006 dan membuat angka penduduk difabel meningkat tajam). Di Situbondo, sebagaimana di 3 area survei lainnya, 3 sektor yakni pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan juga prioritas utama menurut calon legislator untuk diperhatikan pemerintah setempat. Aksesibilitas, yang bagi banyak difabel dianggap sebagai hal yang paling urgen saat mereka hendak menjangkau ruang publik justru berada di tempat yang tidak prioritas. Politisi dan keberpihakan pada Difabel Isu disabilitas dalam politik pemilu di Indonesia, bukanlah isu baru. Perjalanannya sudah relatif panjang, bahkan setua umur reformasi. Regulasi pada Pemilu 2004 telah memasukkan disabilitas sebagai salah satu isu krusial, yang diartikan bahwa secara legal-formal hak-hak politik kaum difabel sudah masuk dalam pertimbangan penting pemilu Indonesia. Perjalanannya yang timbul tenggelam itu lantas menyeruak kembali pada kali ini, Pemilu 2014. Bahkan lebih dari sekadar isu, disabilitas bahkan mewujud menjadi satu entitas politik. Isu difabilitas dapat disepadankan dengan isu perempuan dalam politik. Karena itu, tak salah kiranya untuk mengatakan bahwa representasi kaum difabel dalam politik, sebagaimana pula representasi kaum perempuan, adalah sebuah keniscayaan dalam politik kita hari ini. Di Makassar, mayoritas responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Isu Difabel masih sebagai Prioritas Kedua sebagai visi dan misi Caleg dalam Kampanye. Mayoritas Responden Ingin berkampanye di komunitas difabel namun di sisi lain Mayoritas Responden Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel. Di Balikpapan, mayoritas responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Isu Difabel masih sebagai Prioritas Kedua sebagai visi dan misi Caleg dalam Kampanye. Mayoritas Responden Ingin berkampanye di komunitas difabel namun Mayoritas Responden Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel. Di Bantu, Mayoritas [61,59%] responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Sebanyak 26,81% responden sama sekali tidak menempatkan difabel sebagai isu dalam Kampanyenya. Sebagian besar lainnya: 26,09% menempatkan sebagai isu utama dan 47,10% sebagai prioritas kedua. Mayoritas Responden [65,94%] belum memiliki rencana untuk berkampanye di komunitas difabel (sebagian diantaranya tidak berencana sama sekali), 34,06% BERENCANA berkampanye di komunitas difabel. Sayangnya, hingga sejauh ini, sekira 47,10% Responden sampai saat Mereka mencalonkan diri sebagai Calon Legislator Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel. 44,20% lainnya pernah sesekali. Hanya sekira 8% sering berkunjung. Di Situbondo, Mayoritas responden menyebutkan bahwa Parpolnya sudah memasukkan Isu Difabel dalam Visi dan Misi Parpol. Sebanyak 35,04% responden sama sekali tidak menempatkan difabel sebagai isu dalam Kampanyenya. Sebagian besar lainnya: 35,04% menempatkan sebagai isu utama dan 29,93% sebagai prioritas kedua. Mayoritas Responden [54,01%] belum memiliki rencana untuk berkampanye di komunitas difabel, 29,93% BERENCANA dan 15,33% TIDAK 144 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 BERENCANA sama sekali berkampanye di komunitas difabel. Sayangnya, hingga sejauh ini, sekira 70% Responden sampai saat Mereka mencalonkan diri sebagai Calon Legislator Belum pernah berkunjung ke komunitas difabel. Sisanya hanya berkunjung sesekali. Pada tingkatan maksimal dimana keberadaan mereka dalam politik adalah juga satu dari beberapa entitas politik yang menjadi penentu kebijakan politik Indonesia. Pada tingkatan minimalis dimana mereka adalah sekelompok pemilih yang kehendak politiknya layak diperjuangkan oleh politisi. Jika yang pertama merujuk pada keberadaan mereka di lembaga politik (DPR/DPRD dan DPD) dengan terpilih menjadi anggota legislatif. Maka yang kedua merujuk pada keberadaan mereka sebagai seorang pemilih. Pada yang kedua ini maksud tulisan ini digagas dan hendak diperbincangkan ke publik. Yakni, sejauhmana isu difabilitas diperjuangkan oleh politisi kelak setelah mereka terpilih. Membaca relasi kandidat - pemilih difabel lewat ‘Teori Prinsipal-Agen’ Berbicara soal pemilu dalam kacamata ‘Principal-Agent Theorien’ (Teori Prinsipal-Agen), maka sesungguhnya kita sedang berbicara relasi dua aktor. Yaitu politisi (kandidat partai) di satu pihak (kelak bertindak sebagai agen), dan pemilih (kaum difabel) di pihak lain (kelak bertindak sebagai prinsipal). Teori yang dipinjam dari ilmu ekonomi ini berasumsi bahwa keduanya diyakini hendak atau sedang ingin meraih kepentingan mereka sendiri dalam arena politik (pemilu). Di satu sisi, kandidat partai tentu saja punya kepentingan sangat jelas, yakni ingin terpilih menjadi anggota dewan. Sebaliknya, di sisi lain, kaum difabel tentunya juga memiliki kepentingan jelas, yakni ingin agar kepentingannya diperjuangkan oleh politisi terpilih kelak. Tujuan kita mendiskusikan hal ini dari Perspektif ‘Prinsipal-Agen’ adalah agar bagaimana membuat kepentingan antara kedua aktor itu (kandidat partai dan kaum difabel) berada dalam relasi yang bersifat timbal-balik (resiprositas). Artinya, komitmen politik kandidat partai dalam memperjuangkan kepentingan kaum difabel, jika kelak terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2014 seharusnya adalah gerak maju dari sebuah kontrak politik yang telah dibangun sebelumnya oleh kandidat partai bersama kaum difabel. Hal ini penting ditegaskan karena dalam banyak kasus, politisi terpilih yang bertindak sebagai ‘agen’ tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan pemilihnya. Ingkar atas janji kampanye, misalnya, adalah sebentuk perilaku yang telah melembaga dalam langgam politik kita. Sebaliknya, bagi pemilih yang bertindak sebagai ‘prinsipal’ juga terkadang jauh dari harapan sebagai pemberi mandat dalam pemilu. Fenomena maraknya ‘politik uang’, misalnya, tak lagi dilihat sebagai sebentuk perilaku dari politisi. Kini, hal itu telah pula dilihat sebagai sebentuk perilaku dari pemilih. Dalam posisi ini, keduanya dapat bertindak oportunis. Karena itu, agar kedua aktor keluar dari perilaku oportunistiknya, maka seharusnya keduanya memiliki keinginan untuk menghilangkan peluang munculnya perilaku oportunistik itu dengan membangun sebuah kontrak politik. Kontrak politik: sebuah agenda setting? Dari sisi kandidat partai (agensi), kontrak politik adalah sebuah momentum di tengah arus besar perubahan politik dalam lanskap pemilu Indonesia. Perubahan aturan main pemilu dalam kaitannya dengan penentuan kandidat terpilih di internal partai dengan memakai mekanisme berdasarkan sistem suara terbanyak, dari sebelumnya berdasarkan sistem nomor urut (sebelum MK menganulir Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD). Telah memberikan ruang politik yang terbuka lebar bagi kandidat partai. Sebagai sebuah ‘struktur peluang politik’, perubahan aturan main itu memungkinkan kandidat partai untuk dapat lebih dekat menjangkau para pemilih (prinsipalnya), baik secara kolektif bersama 145 Jurnal The Politics partainya maupun secara individual. Dan saat kandidat partai menjangkau prinsipalnya, maka saat itu juga sebuah komitmen politik harus dibangun. Harapannya, adalah ybs (kandidat partai) dapat terpilih dalam pemilu, saat dimana prinsipalnya pun berkomitmen untuk tidak bertindak oportunis (meminta uang kepada kandidat partai). Dalam kaitan keharusan melakukan kontrak politik antara kandidat partai dan kaum difabel, sebetulnya tak menemukan banyak hambatan. Jika sekiranya kedua aktor itu memang memiliki motivasi politik yang jelas dan arah yang hendak dicapai. Kesimpulannya kira-kira adalah jika motivasi dan arah politik yang keduanya hendak dicapai itu sama, maka kontrak politik itulah jawabannya. Dalam kontrak politik itu, kedua aktor itu membincangkan keinginan masing-masing dalam suasana yang deliberatif. Apa yang harus dan tak harus diperjuangkan itu harus tergambar dalam pertemuan penting itu. Dan kedua aktor itu memaklumatkannya dalam sebuah ‘prasasti politik’ bernama manifesto. Dapat dikatakan bahwa keberadaan sebuah kontrak politik tak hanya mencoba menghadirkan politik yang lebih disiplin, yakni seianya kata dan perbuatan. Melainkan lebih jauh dari itu bahwa kontrak politik adalah senyatanya sebentuk rasionalitas politik, yang telah lama hilang dalam panggung politik kita. Selain yang pasti bahwa dengan kontrak politik itu senyatanya dapat memangkas anggaran politik kandidat partai. Sebuah hal yang juga telah lama dipersoalkan dalam politik kita (Sumber: Risal Suaib, Peneliti Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) – Yogyakarta). Namun, berdasarkan hasil survei, peluang hadirnya sebuah kontrak politik di seluruh wilayah survei relatif kecil mengingat hanya sebagian kecil responden (di bawah 4%) yang benarbenar sudah memutuskan untuk membangun kontrak politik dengan komunitas difabel. Rekomendasi hasil survei Berdasarkan hasil survei tersebut, SIGAB kemudian merekomendasikan sejumlah langkahlangkah yang dapat ditempuh oleh organisasi difabel di daerah pengorganisasian SIGAB menjelang dan pasca pemilihan umum 2014. Pertama, Organisasi difabel daerah menginisiasi terbangunnya kontrak politik antara Pemilih difabel dengan para calon legislator yang memiliki kepedulian dengan isu-isu difabilitas. Kedua, Organisasi difabel daerah membangun relasi politik dengan politisi anggota legislator dan partai politik untuk penguatan kapasitas pengetahuan legislator dan pengurus partai politik mengenai difabilitas dan perspektif difabilitas dalam kebijakan publik. Ketiga, Organisasi difabel daerah membangun kerjasama dengan Partai Politik untuk mengarusutamakan perspektif difabilitas dalam platform Partai Politik dan memasukkan ‘perspektif difabilitas’ ke dalam kurikulum pengkaderan partai politik untuk mempersiapkan kaderkader politisi di pemilu mendatang yang berperspektif difabel. Keempat, organisasi difabel perlu mendorong anggota legislator, khususnya yang telah berkomitmen menyusun dan menandatangani kontrak atau komitmen politik dengan pemilih difabel, untuk membangun kaukus Peduli Difabel di parlemen. Kelima, organisasi difabel daerah membangun mekanisme pengawasan terhadap anggota legislator khususnya dalam mengawal lahirnya kebijakan-kebijakan sosial yang berkaitan langsung dengan penghidupan difabel. Di Yogyakarta, sejumlah organisasi difabel di 4 daerah (Bantul, Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo) dan SIGAB berupaya mengundang sejumlah kandidat yang secara serius hendak membangun kontrak politik. Mereka kemudian berhasil mengundang sejumlah kandidat di tingkat Provinsi untuk menyepakati apa yang mereka sebut sebagai ‘Komitmen Politik’ 6 Maret 2014. Isi dari Komitmen Politik Calon Legislator/DPD 2014 Tentang Keberpihakan Politisi DIY Terhadap Penyandang Disabilitas, adalah pertama, memperjuangkan tersedianya ANGGARAN yang responsif terkait dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, meliputi: aspek kesehatan, 146 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 aspek pendidikan dan keterampilan (dari tingkat usia dini, dasar, menengah, dan perguruan tinggi), aspek ekonomi, kesempatan kerja, dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan/atau keluarga penyandang disabilitas, alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan keperluan penyediaan terhadap sarana dan prasarana publik yang aksesibel. Kedua, kandidat jika terpilih akan memperjuangkan Turunan Kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta agar terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, seperti: Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Ketiga, kandidat akan mempercepat proses Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas dengan substansi yang optimal bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Keempat, kandidat akan menjamin Pengawasan Atas Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta agar terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Kelima, kandidat akan menjalin Komunikasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh DI Yogyakarta untuk memastikan tersampaikannya aspirasi Penyandang Disabilitas dalam penentuan kerangka kebijakan, program, pengawasan, dan anggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas. Keenam, kandidat akan mendorong segera terbentuknya ‘Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas’ di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (SIGAB, 2014). Contoh di atas menunjukkan bahwa relasi politik organisasi difabel atau pemilih difabel yang terorganisir dengan kandidat atau politisi dapat terbangun. Harapannya, dengan terbangun dan membaiknya relasi prinsipal - agen maka upaya mainstreaming perspektif disabilitas dapat pula berjalan semakin menguat. Dampaknya di masa depan tentulah lahirnya kebijakan-kebijakan sosial yang berpihak pada kepentingan difabel dan kelompok marjinal lainnya. Segala hambatan, sebagaimana disebutkan di atas seperti hambatan fisik, hambatan informasi, hambatan legal, dan hambatan mental tidak lagi terjadi dan membatasi aktifitas difabel dalam seluruh aspek kehidupan baik di daerah penelitian maupun di banyak tempat di Indonesia. Pemantauan Pemilu Akses 2014: Apakah Pemilu 2014 Terjangkau Bagi Pemilih Difabel? SIGAB dan mitra lokalnya bersama sejumlah difabel yang telah memiliki hak pilih berpartisipasi secara aktif di sepanjang perhelatan Pemilu 2014. Partisipasi aktif ini telah memberikan sejumlah rekomendasi penting mengenai hambatan-hambatan yang ditemui pemilih difabel saat mengikuti keseluruhan proses pemilu 2014. Secara khusus, SIGAB dan mitra daerahnya juga melakukan pemantauan pada hari pencoblosan4 untuk melihat langsung bagaimana Pemilu berlangsung di sejumlah TPS di mana seorang pemantau ditempatkan. Wilayah pemantauan dilakukan di 4 daerah yang sama dengan wilayah survei di atas. Fokus pemantauan tertuju pada seberapa aksesibel pemilu kali ini berlangsung. Untuk pemantauan pada hari pencoblosan, tim pemantau menggunakan form pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 tahun 2013 tentang Perubahan ke-6 atas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah [terakhir dengan peraturan komisi pemilu nomor 19 tahun 2013], tahapan pemilu 2014 dimulai dengan Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 April 2014 di empat wilayah yang terdiri dari DI Yogyakarta (25 TPS), Kota Balikpapan (19 TPS), Kabupaten Situbondo (20 TPS), dan Kota Makasar (20 TPS). Di Yogyakarta, pemantauan dilakukan dengan melibatkan komunitas difabel pada 25 titik TPS yang menyebar di lima Kabupaten/ Kota. Di Situbondo, pemantauan dilakukan dengan bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) Situbondo. Di Kalimantan Timur, pemantauan dilakukan melalui kerjasama SIGAB dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Balikpapan. Sedangkan di Makassar, pemantauan dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Makassar. 4 147 Jurnal The Politics Tahapan Persiapan, Penyelenggaraan, Pencalonan Peserta pemilu, Kampanye, Pemungutan Suara, pengumuman dan penetapan Hasil Pemilu dan tahap penyelesaian. Berdasarkan tahapan ini, berikut gambaran mengenai pengalaman pemilih difabel pada pemilu 2014 terkait hambatanhambatan yang dihadapinya. Tahapan Persiapan. Pada tahapan ini persiapan Pemilu meliputi: Penataan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan, Pembentukan Badan Penyelenggara, seleksi anggota KPU/D, sosialisasi, publikasi, pendidikan pemilih, pengelolaan data dan informasi, dan logistik. Hambatan yang dihadapi pemilih difabel yang berupaya turut aktif berpartisipasi adalah aksesibilitas informasi bagi difabel dengan segala jenis perbedaan kemampuannya. Selain itu, hambatan yang kerap menjadi batu sandungan difabel adalah ketentuan ‘sehat jasmani dan rohani’ jika difabel hendak mengajukan diri sebagai komisioner. Persyaratanpersyaratan menjadi bagian penyelenggara atau pengawas pemilu seharusnya berazaskan keadilan dan kesetaraan sehingga warga difabel juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota penyelenggara. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pada tahapan ini meliputi aktifitas Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPT di luar Negeri, dan penataan dan penetapan Dapil. Masalah yang dirasakan difabel saat sosialisasi/pengumuman penyelenggara pemilu dalam menginformasikan tahapan pendaftaran peserta pemilu adalah pelaksana pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi bagi difabel rungu-wicara dan difabel netra. Informasi yang disampaikan melalui pengumuman secara tertulis di kantor KPU dan melalui pengumuman media cetak dan eletronik tidak aksesibel bagi mayoritas difabel. Hambatan yang ditemukan difabel khususnya bagi difabel rungu-wicara adalah ketiadaan interpreter atau penerjemah difabel rungu-wicara di layar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tidak tersedianya teks berjalan di TV. Bagi difabel netra, penyelenggara Pemilu kurang memperhatikan jenis media informasi/pengumuman dalam bentuk Braille; Informasi melalui Radio, hingga Website yang seharusnya perlu dilengkapi dengan standar aksesibilitas yang memudahkan difabel netra. Sementara itu, pada fase ‘Penetapan Peserta Pemilu’ dan Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, pemilih difabel masih kesulitan mengakses informasi yang disampaikan baik melalui media cetak, media radio, maupun televisi. Seharusnya, pemilih difabel berhak atas kemudahan mengakses informasi tersebut seperti tersedianya interpreter difabel rungu-wicara di bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan (running texts) di layar TV. Begitu pula bagi pemilih difabel netra selayaknya setiap media informasi melalui media cetak mestilah menyediakan media khusus dengan huruf braille dan jika melalui media internet atau Website semestinya dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan difabel netra. Di tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, banyak pemilih difabel yang mengalami kesulitan pendengaran tidak didaftarkan secara semestinya dan tidak menerima perlakuan sama dengan pemilih lainnya. Namun demikian, dari sisi difabel sendiri, masih ada sejumlah keluarga [yang secara sengaja] menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel untuk didaftar sebagai pemilih. Pun demikian di mana banyak orang diklasifikasikan memiliki keterbatasan kecerdasan “menengah” atau “buruk” tidak didaftarkan dan tidak ada iklan layanan masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih difabel. 148 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Tahapan Pencalonan. Tahapan ini meliputi Pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Verifikasi pencalonan anggota DPD, Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang meliputi perbaikan, pemberitahuan pengganti DCS, dan pengumuman DCT. Masalah yang dirasakan difabel di tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD adalah sosialisasi/pengumuman pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD dilakukan melalui media cetak, elektronik berupa TV dan Radio namun kurang mempertimbangkan hambatan bagi difabel rungu-wicara dan difabel netra. Kandidat difabel rungu-wicara tidak dapat mengakses informasi tahapan penetapan peserta pemilu bila dilakukan di radio dan TV seperti iklan layanan masyarakat tentang pemilu. Pun demikian Kandidat difabel netra tidak dapat akses atas informasi yang dibuat dalam bentuk Cetakan kertas seperti koran, leaflet, poster. Beraudiensi kepada penyelenggara Pemilu bisa menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kebutuhan informasi di atas untuk disediakan oleh KPU. Namun, dari sejumlah upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi difabel di daerah, hambatan lingkungan dan bangunan kantor KPU daerah dan Bawaslu daerah masih tidak aksesibel bagi warga difabel. Bangunan yang tidak akses ini jelas berkontribusi mengabaikan keberadaan difabel untuk berpartisipasi dalam pemilu secara adil. Tahapan Kampanye. Tahapan kampanye mencakup aktifitas seperti pertemuan terbatas, rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, dan masa tenang. Kekurangan yang masih tampak dalam penyelenggaraan Pemilu di tahapan kampanye dan masa tenang adalah [masih] serupa dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi di mana kemampuan pemilih difabel difabel netra dan difabel rungu-wicara mengakses informasi tersebut tidak bisa disamakan dengan pemilih lainnya yang dengan mudah melahap informasi dari media massa baik cetak, audio, visual maupun internet. Kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum wajib memperhatikan aksesibilitas bagi difabel khususnya difabel daksa, netra dan rungu-wicara. Gedung-gedung pertemuan harus mempertimbangkan aspek akses seperti adanya titian (rampa) bagi kursi roda, toilet yang juga akses, tersedia lift jika pertemuan diadakan di lantai atas. Pun demikian jika calon menyampaikan orasi politik atau diskusi, pihak penyelenggara (tim pemenangan calon) harus menyediakan seorang penterjemah bahasa isyarat jika terdapat pemilih yang tidak dapat mendengar dengan baik. Kandidat juga harus memperhatikan peserta dengan difabel netra di mana seorang kandidat tidak menggunakan terlalu banyak media presentasi seperti slides tanpa penjelasan atau deskripsi yang mudah dipahami tanpa harus mengandalkan ilustrasi gambar. Tahapan Pemungutan Suara. Di tahapan ini merupakan tahapan paling penting di mana ada lebih banyak pemilih difabel yang harus memiliki kemudahan yang sama dengan pemilih lainnya. Di fase ini, yang meliputi Proses Pencoblosan dan Perhitungan Suara, sebagaimana banyak didiskusikan antara pemilih difabel dengan penyelenggara pemilu menjadi penting mengingat di fase inilah suara kemudian diberikan dan akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di masa mendatang. Adapun masalah yang dirasakan pemilih difabel Pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara dirasakan oleh pemilih difabel sindroma-down baik sedang maupun berat di mana banyak di antara mereka yang tidak ikut pemungutan suara. Ada pula TPS yang tidak akses bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara bagi pengguna kursi roda petugas yang mendatangi atau tidak sama sekali. Demikian juga terjadi kepada pemilih Difabel rungu-wicara pada saat dipanggil 149 Jurnal The Politics namanya untuk mencoblos, mereka tidak mendengar sehingga tidak mencoblos karena dianggap tidak ada. Kesulitan yang sama juga dihadapi pemilih difabel netra di mana tidak tersedia alat bantu mencoblos (Braille Template) sehingga kesulitan dalam ‘membaca’ kolom dan isi kertas suara. Dalam kondisi tertentu semisal alat bantu mencoblos tidak tersedia, pemilih difabel netra dapat didampingi oleh petugas pemungutan suara namun terdapat konsekuensi di mana kerahasiaan pilihan tidak terjamin atau adanya pelanggaran jenis lain semisal salah coblos, atau lain yang diminta coblos lain yang dicobloskan. Pilihan memberikan asisten pemberi jasa mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh cara pandang pelaksana KPU bahwa difabel adalah person yang tidak mampu sehingga harus dibantu. Padahal, jika saja KPU mau berpikir dan berdiskusi bersama dengan difabel, maka pasti akan ada cara yang lebih baik untuk melibatkan difabel tanpa harus mendiskriminasikannya. Tahapan Hasil Pemilu dan Penyelesaian. Di tahap ini meliputi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan nasional, penetapan hasil pemilu, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, serta pengucapan sumpah/janji. Kesulitan yang dihadapi pemilih difabel pada tahap ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian dan penyebarluasan informasi dari penyelenggara pemilu kepada pemilih dan warga negara secara keseluruhan. Untuk itu perlu dibuatkan sistem informasi khusus yang inklusif. Pada tahap penyelesaian umumnya terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilu. Pemilih difabel, sebagaimana layaknya pemilih umumnya juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk melakukan serangkaian gugatan kepada penyelenggara pemilu jika terjadi kecurangan. SIGAB, berdsarkan hasil pemantauan pada hari pencoblosan di 4 daerah telah melaporkan segala praktik ketidakterjangkauan pemilu bagi sejumlah difabel. Namun, laporan pelanggaran itu hingga kini tak memperoleh respon dari pihak Bawaslu. Besar kemungkinan mengingat laporan pelanggaran aksesibilitas ini bukan merupakan hal yang benar-benar penting dibandingkan misalnya dengan ‘money politic’. Mengatasi hambatan: sebuah tawaran Baik dari hasil pengamatan dalam proses pengorganisasian organisasi difabel maupun pemantauan di sejumlah TPS di 4 daerah di atas, SIGAB menemukan setidaknya ada 4 jenis hambatan yang dihadapi pemilih difabel selama perhelatan pemilu berlangsung pada tahun 2014. Jenis hambatan itu meliputi hambatan struktural, lingkungan, sikap atau perilaku, dan teknologi.5 berikut penulis paparkan tabel tentang jenis dan kategori hambatan yang dihadapi difabel pada Pemilu 2014 dan tawaran SIGAB terkait pengurangan hambatan-hambatan tersebut. Jika merujuk kepada buku ‘Accessible Elections for Persons with Disabilities in Indonesia (Aksesibilitas Pemilu untuk Difabel di Indonesia) yang disusun oleh PPUA Penca 2013, maka sekurang-kurangnya ada 4 macam hambatan yang akan dihadapi pemilih dan kandidat difabel pada Pemilu 2014, yakni: Hambatan Legal, Hambatan Informasi, Hambatan Fisik, dan Hambatan Sikap. 5 150 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Tabel Jenis Hambatan, Kategori Hambatan, dan Tawaran Perbaikan Pelaksanaan Pemilu 1 Jenis Hambatan Struktural 2 Lingkungan Kategori Hambatan Persyaratan Pemilu “Sehat Jasmani dan Rohani Tawaran UU Pemilu tidak lagi mencantumkan prasyarat sehat jasmani dan rohani bagi peserta PEMILU maupun calon anggota KPU yang merugikan difabel, atau mempertegas makna atau pengertian ‘sehat’ sehingga difabel bukan kategori ‘tidak sehat’. Kebijakan pemilu UU Pemilu memuat bagian khusus (UU Pemilu dan yang mengatur prinsip desain Pemilu turunannya) Universal dan Jaminan Hak Politik difabel tidak diabaikan. Fisik (Bangunan Kantor KPU, Bawaslu, Partai Politik, kantor pelaksana, KPPS, kantor layanan publik lainnya pengawas, dan peserta terkait Pemilu menerapkan “Konsep pemilu) Desain Universal” agar difabel dan Organisasi difabel dapat dengan mudah mengunjungi dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak penyelenggara pemilu, partisipan dan pengawas pemilu. Fisik (Tempat TPS didesain dengan mengunakan Pemungutan Suara) prinsip Desain Pemilu Universal yang mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS. Misalnya, lokasi TPS tidak bertanggatangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah, tempat yang rata, tidak di lantai dua. Non-Fisik Pihak Penyelenggara pemilu (Standar Pelayanan memperluas perspektif disabilitas Aksesibilitas Pemilu dan membangun kerjasama dengan organisasi difabel demi memperoleh masukan soal Etika Disabilitas dan Prinsip Universal dalam layanan publik (khususnya pemilu) dan menuangkan pengetahuan tersebut ke dalam suatu Panduan Pelaksanaan Pemilu Aksesisible dan memastikan Petugas Pemilu diberbagai tingkatan memahami isi panduan dan menerapkannya. 151 Jurnal The Politics 3 Sikap/Perilaku Pengabaian KPU, Bawaslu, dan jajarannya bersikap proaktif untuk membuka akses partisipasi pemilih difabel, sehingga tidak terjadi lagi pembiaran difabel yang tidak terdaftar, tidak mencoblos dan lingkungan TPS tidak akses. KPU menyediakan Panduan ‘Etika Disabilitas’ untuk menghindari penghinaan baik sengaja maupun tidak sengaja Seluruh jenis media pemilu yang digunakan KPU dan peserta pemilu dalam keseluruhan siklus Pemilu (cetak, audio, visual, online/offline) menekankan aspek aksesibilitas: seperti tersedia dalam huruf braille, teks berjalan (running texts), penterjemah bahasa isyarat, Audio, Font besar. Instrumen pendataan (kuesioner) memasukkan kategori jenis disabilitas (impairment) berdasarkan kategori UN-CRPD atau ICF (WHO) sebagai indikator yang valid. Instrumen Pendataan memasukkan kategori jenis hambatan sosial/ lingkungan eksternal. Misalnya difabel netra memiliki hambatan dalam mengakses informasi berbasis cetak, untuk itu dibutuhkan model braile maupun audio dan teks bersuara. Instrumen Pendataan memasukkan tawaran kemudahan aksesibilitas mulai dari fase awal sampai fase akhir pemilu. Penghinaan 4 Teknologi Informasi Pendataan Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Tim Pemilu Akses Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel, 2015 Kesimpulan dan Sejumlah Rekomendasi Dari gambaran beragam bentuk partisipasi politik difabel di 4 daerah yang diorganisasi oleh SIGAB, tampaknya menunjukkan bahwa perspektif disabilitas memang menjadi sebuah cara pandang yang dapat memperkaya ilmuan maupun praktisi Pemilu guna memahami kekurangan kapasitas pengetahuan mereka dan sistem pemilunya sendiri bukan saja secara prosedural namun juga secara substansial. Berbagai temuan di atas menunjukkan betapa jaminan aksesibilitas masih sangat kurang dalam penyelenggaraan Pemilihan umum legislatif 2014. Berdasarkan temuan survei dan pantauan di atas, beberapa rekomendasi di bawah ini hendaknya bisa menjadi pertimbangan: 152 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Pertama, Peserta Pemilu, baik secara individual (kandidat) maupun secara kelembagaan (partai politik) perlu memasukkan perspektif disabilitas sebagai salah satu cara organisasi memandang realitas masyarakat. Jumlah difabel yang relatif tinggi sudah seharusnya membuat para politisi mengadopsi cara pandang ini sebagaimana misalnya mereka mengadopsi perspektif kesetaraan gender yang melahirkan tindakan afirmatif action berupa kuota 30% bagi perempuan sebagai calon legislator. Kedua, Penyelenggara pemilu juga perlu mendalami kajian dan perspektif disabilitas untuk mengubah cara pandang mereka yang konservatif terkait dengan isu disabilitas dan pemilih difabel. Dengan memahami perspektif disabilitas, maka desain pelaksanaan pemilu tidak lagi meminggirkan pemilih difabel namun justru membangun kesetaraan dan aksesibilitas kepada pemilih difabel dalam pemilu. Ketiga, Secara teknis, hendaknya penyelenggara pemilu lebih aktif dalam memastikan penempatan TPS pada lokasi yang aksesibel dan mudah terjangkau oleh difabel. Sosialisasi tentang aksesibilitas pemilu yang berdasarkan pemantauan terasa sangat kurang hendaknya dapat lebih ditingkatkan dan dipastikan untuk sampai kepada KPPS. Selain itu, peran Bawaslu dalam memastikan prosedur pemilihan lokasi TPS yang aksesibel juga hendaknya ditingkatkan. Sampai sekarang ini, peran Bawaslu hampir tak terlihat dalam memastikan terpenuhinya penyelenggaraan pemilu yang aksesibel. Keempat, Penyelenggara pemilu hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan pemilu aksesibel melalui pengadaan berbagai kebutuhan logistik seperti alat bantu pencoblosan pada setiap kertas suara. Ketersediaan template yang hanya pada kertas suara DPD pada pemilu 2014 dengan distribusi yang tidak merata membuktikan bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini terutama KPU masih setengah hati dalam menjamin pemenuhan hak politik Difabel sebagaimana jelas tercantum dalam Undang-Undang ratifikasi Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas No.19 tahun 2011, Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang no.8 tahun 2012. Artinya, ini berarti bahwa KPU mengkhianati mandat yang sebenarnya secara konstitusi dibebankan kepadanya. Kelima, Penting kiranya agar dilakukan perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Di luar temuan-temuan yang secara spesifik diperoleh dari pemantauan ini, berbagai tahapan masih sangat mengesampingkan difabel mulai dari pendataan pemilih dan seterusnya hingga pada tahap pencoblosan. Beberapa contoh inisiatif seperti pengadaan template DPR-RI oleh KPUD DIY, serta template DPRD Kota oleh KPUD Kota Yogya hanya merupakan solusi responsif yang tidak menjawab permasalahan yang mendasar. Sementara itu, keterlibatan difabel mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaan pemilu masih sangat minim. Dengan banyaknya permasalahan yang dari pemilu ke pemilu terus terjadi dan belum terjawab, keterlibatan difabel kiranya penting untuk dipertimbangkan. Keenam, Penyelenggara pemilu hendaknya juga lebih terbuka dengan ide-ide inovatif terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif untuk dapat memastikan peningkatan partisipasi semua masyarakat dalam pemilu mendatang, khususnya ide-ide dari pemilih difabel di seluruh negeri di Republik ini mengingat gerakan sosial difabel sedang bangkit[]. 153 Jurnal The Politics Daftar Pustaka Abberly, P. (1987). The concept of oppression and the development of a social theory of disability. Disability, Handicap and Society, 2, 5-20 Barnes, C. (1990). Cabbage syndrome: The social construction of dependence. Lewes: Falmer. Barton, L. (1996). Sociology and disability: Some emerging issues. In L. Barton (Ed.), Disability and society: Emerging issues and insights (pp. 3-17). London: Addison Wesley Longman. Bowman, C. A., & Jaeger, P. T. (2003, April). Making diversity more inclusive: Toward a theory for the representation of disability. Paper presented at the 2003 American Education Research Association Conference, Chicago, IL. Christensen, C. (1996). Disabled, handicapped or disordered: “What’s in a name?” In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.), Disability and the dilemmas of education and justice (pp. 63-78). Buckingham: Open University Press. Corker, M., & French, S. (Eds.). (1999). Disability discourse. Buckingham: Open University Press. Fakih, Mansour., ‘Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik’, INSIST Press, Yogyakarta, 2002. Fine, M., & Asch, A. (1988). Disability beyond stigma: Social interaction, discrimination, and activism. Journal of Social Issues, 44(1), 3-21. Finkelstein, V. (1980). Attitudes and disabled people. New York: World Rehabilitation Fund. Hahn, H. (1997). New trends in disability studies: Implications for educational policy. In D. K. Lipsky & A. Gartner (Eds.), Inclusion and school reform: Transforming Americans classrooms (pp. 315-328). Baltimore: Paul H. Brooks. Joni Yulianto, M (2007), “Investigation on the Influence of the Disability Movement in Indonesia: An Advance Investigation on the Influence of the Disability Movement in Indonesia”, VDM Verlag Dr. Müller, May 2. Kitchin, R. (2000). The researched opinions on research: Disabled people and disability research. Disability and Society, 15, 25-47. Lonsdale, S. (1990). Women and disability. New York: Macmillan. Marks, D. (1999). Disability: Controversial debates and psychological perspectives. New York: Routledge. McDonald, P. (1991, March 8). Double discrimination must be faced now. Disability Now, 7-8. McRuer, R. (2003). As good as it gets: Queer theory and critical disability. GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies, 9(1-2), 79-105. Oliver, M. (1990). The politics of disablement. London: Macmillan. Paul T. Jaeger dan Cynthia Ann Bowman (2005), ‘Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, and Civil Rights. Salim, Ishak, Ed, (2015), “Difabel Merebut Bilik Suara: Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia”, SIGAB. Salim, Ishak. Risal Suaib, Dkk. 2014, Memahami pemilihan umum dan gerakan politik kaum difabel. SIGAB, Yogyakarta. 154 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Salim, Ishak dan Syafi’ie, Muh., Ed., “Hidup Dalam Kerentanan: Narasi Kecil Keluarga Difabel”, SIGAB, 2015). Samuels, E. J. (2003). My body, my closet: Invisible disability and the limits of comingout discourse. GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies, 9(1-2), 233-255. Shakespeare, T. S. (1994). Cultural representations of disabled people: Dustbins for disavowal. Disability and Society, 9(3), 283-301. Siebers, T. (2001). Disability in theory: From social constructionism to the new realism of the body. American Literary History, 13(4), 737-745. Silvers, A. (1998). Formal justice. In A. Silvers, D. Wasserman, & M. Mahowald (Eds.), Disability, difference, and discrimination (pp. 13-145). Lanham, MD: Rowman and Littlefield. Silvers, A. (2000). The unprotected: Constructing disability in the context of antidiscrimination law. In L. P. Francis & A. Silvers (Eds.), Americans with disabilities: Exploring implications of the law for individuals with disabilities (pp. 126-145). New York: Routledge. Stewart, D., Rosenbaum, P (2003)., Are, Who We, et al. “The International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): a global model to guide clinical thinking and practice in childhood disability.” Stone, E., & Priestly, M. (1996). Parasites, prawns and partners: Disability research and the role of non-disabled researchers. British Journal of Sociology, 47, 699-716. Stuart, O. (1992). Race and disability: Just a double oppression? Disability, Handicap and Society, 7(2), 177-188. Suharto, (2010) Community-based Empowerment for Translating Diffabled People’s Right to Work: A Case Study in Klaten Regency, Central Java, Indonesia, Research Paper, The Hague, The Netherlands: International Institute of Social Studies. Switzer, J. V. (2003). Disabled rights: American disability policy and the fight for equality. Washington, DC: Georgetown University Press. Thohari, Slamet, (2013), “Disability In Java: Contesting Conceptions of Disability In Javanese Society after the Suharto Regime”, LAP LAMBERT Academic Publishing. Thomas, C. (1999). Female forms: Experiencing and understanding disability. Buckingham: Open University Press. Turnbull, H. R., Jr., & Stowe, M. J. (2001). Five models for thinking about disability: Implications for policy responses. Journal of Disability Policy Studies, 12(3), 198-205. Whiteneck, Gale. “Conceptual models of disability: past, present, and future.” Workshop on disability in America: A new look. Washington DC: The National Academies Press, 2006). Www.sigab.or.id Www.solider.or.id 155 Jurnal The Politics 156 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Selective Influence of Political Advertising on Television in Visual Image Building Candidat Presidential Election 2014 Tuti Bahfiarti Departement of Communication, Hasanuddin University, Makassar Indonesia Email : [email protected] Abstract Political campaign presidential election in Indonesia has grown, along with the in creasing advances in technology and changes in the electoral system (election). Then, the candidates vying to attract public sympathy, one way to make a Political Advertising that aired on television station. Presidential Elections (Election) in 2014 led to competition both pairs of candidates for president and vice president of the Prabowo-Hatta and Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), heats up. The heat of competition seen also with the rise of political advertising both pairs of candidates. Political advertising is one way to get support from the community, for example in audio visual media television. The problem is how selective influence of political advertisements aired on television is able to construct a visual image of the presidential candidate in 2014. The aim was to determine the influence of selective political ad that aired in the media in the capture space “discourse” candidate image visualization massively so sehimgga able to raise the collective memory selector that will provide sound support when the momentum of the electorate was held. For the achievement of the objectives of this research are used type of research is a mixed-method research. This type of research that combines qualitative and quantitative research methods (triangulation) to provide a comprehensive analysis of the research problem. The goal is to get the data and comprehensive analysis of the research problem. The results of this study indicate that political advertisements on TV were able to build a visual image 157 Jurnal The Politics of the presidential candidates in 2014 by 87% and aims to improve the prospects of promoting the election of a candidate or candidates for president of programs and policies. Political ads this election is able to build the reputation of candidates or political parties to provide information to the public about the qualifications, experience, background, and personality presisen a candidate or political party. Then selective influence political advertising is changing, maintain adding cognitive, affective, and political behavior of audiences. The communication process takes place with all the elements involved. However, other results showed that the selective influence of political advertising in building the image visualization candidate vice effective only on the TV if it is based on specific situations, such as elections (presidential) only focused on situations in which engagement and voter interest and familiarity candidate or party chairman is quite high. The strength of political advertising in the media 2014 lies not in the idea, program, or solidity policy information directly related to the basic needs of the people. That power is the personal figure presidential candidate. Keywords: selective influence, political advertising and television Introduction Communication basis of all social and political activities, no matter whether the messages are communicated it diffusion due to technology, as well as how big an impression of the structure of the mass media and political organizations influence. Because in the end is people who remain will be the maker and controller communication symbols. With this ability, people will relate, interact with each other and form their political and social life. Political advertising is one very potential political activity in today’s era moderent strongly supported by the development of communication channels, especially mass communication channels (TV). Advertising or political advertising is a public announcement of the media to influence the political choices of voters. 2014 presidential elections political campaign through the display method of the vice president of ad impressions are competing to attract public sympathy, one way to make a political ad that aired on television station. Presidential Elections (Election) in 2014 led to competition both pairs of candidates for president and vice president of the Prabowo - Hatta and Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), heats up. The heat competitions seen also with the rise of political adverts both pairs of candidates. Political advertising is one way to get support from the community, for example in audiovisual media television (TV). They competition to contest 01 seats in Indonesian. The development of political advertising and political propaganda in line with the development of communication itself. Since the first, the government and the leaders, either incumbent or who no longer served acknowledge the advantages of advertising accomplishments that have been achieved. In the Visual Image Building Candidate Presidential Election 2014, political advertising campaign is seen as a competition for the support, tolerance and/or sound society, through TV media channels trying to persuade voters throughout the election campaign as a typical characteristic of political advertising in a democratic system. In Constructing a political advertisement Visual Candidate Presidential Election 2014 is political advertising through TV channels in the setting of the election (Electoral), whose role is quite large in the political system is mainly due to the increasing dominance of the broadcast media, especially TV. For example, this favorable data their purchase media time on TV. For example, in 1956 in the United States, a combination of both parties to spend $ 9 billion to pay for 158 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 a television and radio during the presidential campaign (Dreyer, 1964), which occurred 16 years ago, then in 1972, broadcasters radio (broadcasters) sell rating for $ 56 billion to candidates for political officials (Szybillo & Hartenbaum, 1976). And in the general election in 1976, the two candidates for the post of president of the majority party to pay its own $ 17 billion in television advertising (Devlin, 1977). Regardless of how big or small lie political advertising, but almost all modern politicians are very confident of the success of the implementation of the political advertising. (Fagen, Richard. 1975: 23). Display content of political advertising messages in building visual imagery candidate presidential election in 2014 this would be the main reason for the victory of Jokowi-JK is a personal charm Jokowi and JK himself. Jokowi managed to raise public expectations will change the political culture. Since the reform, the political culture is getting away from the public interest. The issue of corruption spread in all directions. Jokowi come as a leader with a different political culture. He feels homely, caring for his people, honest and away from transactional politics. Although, there is little research on the characteristics-characteristics of the message/ content of political advertising that seeks to connect the content of political advertising message with its influence. According to the study of political advertising message content is divided into two basic categories: first, the study of political advertising message content that offers the impression (Impressionistic), namely descriptive analysis of political advertising message content and strategy, second, studies political advertising that offers a systematic content analysis. Study the contents of the message first category doing Tucker, 1959 senate campaign. Oregon between Wayne Morse and Douglas Mc Kay Morse concluded that success in creating ads with messages of various “programs” offered, through radio and television advertising, with the support of a great ability to display the characteristics “personality” positive. It is concerned with building a visual image of the presidential election candidates. Similarly, according Reagents (in Nimmo and Sanders. 1981: 97) uses a simple production techniques and use-oriented advertising spots on the issue or issues, by observing the techniques of film and television advertising spots fill in the presidential election (Rose & Fuchs, 1968 ). A second study that leads to political advertising only delivered through television or newspapers that carried the systematic content analysis. As done Mullen (1963a, 1963b, 1983c) content analysis of newspaper political advertising messages on the presidential and senatorial campaign, there were 90 political advertisement in the newspaper for a period of two weeks, with the content of political advertising messages delivered at most candidates calling for the ‘issues related to domestic and overseas, then in the next research obtained that more candidates using picture messages or pictures, the presidential candidate ads, and at the election of Senate candidate calls using a more vague. (Nimmo and Sanders. 1981: 97) These studies differ from the reality of political advertising message content vice president elections in 2014, although still a little research on the content of the message characterictic Indonesia to join the new political advertising messages with the effect of political advertising, political advertising communicator Indonesia in the ad spots at most lists no longer contains, with support images that theme party political symbol in the form of presentation, the Chairman of the Party with the call, and the candidate with the symbol of his political party that seeks to strengthen the uniqueness of each political party with not too concerned with the content of the party program. In other words, visual images, charismatic, and positive characteristics have become the focus of public attention to the content of political advertising in the election of 2014 peresiden. 159 Jurnal The Politics Research Methods The method used is qualitative approach due to the nature of qualitative methods emphasis on breadth and depth and allow them to study certain issues in depth and in detail because data collection is not limited to certain categories. Selection of research data source is determined by determining the sample data source or informant and research. Researchers refer to the data source or informant and research to replace term research subjects are those who provide information about his own understanding of the experience and what happened. Furthermore, the data source of this research with qualitative methods is determined by determining the informants of this study was done by using a non-probability sampling / nonrandom purposive sampling types. Purposive sampling focuses on the selection of cases (people) who have certain information that can answer the research questions. Result and Discussion To spread the message on television advertising in building a visual image of the candidate presidential elections in 2014, the incentive to produce advertising candidate polities in time for the campaign to be able to get a perspective effect modification, cognitive, attitudes and political behavior. The results of this study revealed that the audience is more focused on political advertising community as a whole is entitled to support the TV media that can reach a wider whether public leadership, public or antentif, or the general public, as well as finding a new audience or audiences opportunities to expand to change the selectivity, reinforce selectivity and strengthen selectivity of cognitive, effective and positive behavior through the utilization of TV media audiences. Data findings showed that political ads on TV is able to construct a visual image of the presidential candidates in 2014 by 87%, aims to improve the prospects of promoting the election of a candidate or candidates for president of programs and policies. Political advertising is able to build the reputation of candidates or political parties to provide information to the public about the qualifications, experience, background, and personality presisen a candidate or political party. The principle of limited effect perspective in political advertising is important as the process of a belief that the tendency of individuals to mediate the effects of political messages, so much attention has been focused on the selective process that takes place in political advertising. Much attention has been directed to the issue of participation or against a candidate of one’s choice as one reason for the emergence of exposure or selektive perspective, because the voting behavior research emphasizes the importance of partisan identification as a long-term strength. Selective influence of Political Advertising on Television In Visual Image Building Candidate Presidential Election 2014, an understanding that is taking into account the effect of psychological processes in the effect, in this connection De Fleur, 1966 which is famous for its model of “psychodynamic” him, explaining that the effect of use of media TV viewers. This shows that something desired by the sender of the message: (1) short-term (immediate and temporary), (2) is related to changes in knowledge, attitudes, and behaviors in individuals, (3) and relatively not mediated. Study “agenda-setting” is also very involved in the process of selective influence of a political advertising messages through mass media, Maxwell McCombs and Donald Shaw (Djuarsa Sendjaja S., et al, 199-200: 1994) wrote that the audience not only learn the news -News (political advertising messages) and other things through the mass media, but also learn how much importance is given to a political message from the media give emphasis to these messages. For example, in reflecting what was said by the messages that political advertising in a political ad aired in the media, the media look to determine which topics are important, the mass media determine the “agenda” of the advertising campaign. 160 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 This study also assumes that if the voters are convinced of the importance of a political advertising message then they will choose the candidate most comptence projected in handling the message. Selective processes influence Political Advertising on Television In Visual Image Building Candidate Presidential Election 2014 begins with responding to political advertising messages on stage selective attention based on, individual differences, membership, and the public interest. Advertising messages to make someone have to pay attention because it resulted in the message was actively associated with the group members, such as family, neighbors, friends, boss, acquaintance. Messages like these are in the selection by the recipient. Further, selective perception (selectively perceive specific message). This stage is the stage of selection to something that message based on certain perceptions, because of differences in cognitive factors, interests and beliefs, knowledge, attitudes and needs, then the individual values are selectively also perceives an ad that reaches it. In the end, selective recall (selective remembering specific message). This process is a selective process in a given political advertising messages Candidate Presidential Election 2014. Assuming that a person tends to pick back only messages in memory only, although parallel with the selection of the attention, but each person choose the most memorable advertising messages only. The principle of selective recall is often found in political advertising that particular character. Although, it is very difficult to determine that the audience will respond back message remember alone, especially in the context of political advertising in which the audience is very affected at the cognitive level, attitudes and perceptions about the political advertising before exposed to the ad, it exposure (frequency-duration) and elections media (print-personal-electronic) are the highest and may affect the formation of strategic response or effect on audiences. Finally, the process of selective action (selective certain actions) political ads on TV in the process of building a visual image of the 2014 presidential election candidate is manifested in the form of action and / or positive political behave in accordance with any message every person will have and choose which of right action and action which are not, all of the response decision to choose something to rely on the influence of other aspects. However, in the study of the effects of mass media audiences are studies that do not deny the problem of socio-cultural background, whether environmental, family, education, religion, culture, etc., which will affect the selective process; selekstif exposure, selective attention, and their retention in the selective receive any messages in political advertising as an ongoing process of political ads on TV effects in the process of building a visual image of the 2014 presidential election candidates. Conclusion 1. Selective influence of Political Advertising on Television In Visual Image Building Candidate Presidential Election 2014 at 87% and aims to improve the prospects of promoting the election of a candidate or candidates for president of programs and policies. This is a political communication process of delivering calls-calls are intended to foster the reputation of candidates or political parties to provide information to the public about the qualifications, experience, background, and personality of a candidate or political party and raising the prospect of election candidates or promote programs and certain policies of politicians to one or more recipients of the message in order to change, maintain adding cognitive, affective, and political behavior of audiences. 2. Selective Process Influence Political Advertising on Television In Visual Image Building Candidate Presidential Election 2014 begins with responding to political advertising messages 161 Jurnal The Politics on stage selective attention based on, further, selective perception (selectively perceive specific message), selective recall (selective remembering specific message ). This process is a selective process in a given political advertising messages Candidate Presidential Election of 2014. Finally, the process of selective action (selective certain actions) political ads on TV in the process of building a visual image of the 2014 presidential election candidate is manifested in the form of positive political action in accordance with any message every people will have and choose Where appropriate measures and actions which do not, all of the response decision to choose something also depends on the influence of other aspects. References Fagen, Richard. 1975. Political and Communication. Little, Brown and Company. Boston. Liliweri, Alo.1992. Dasar-dasar Komunikasi Periklanan. PT Citra Aditya Bajti. Bandung. Nasution, Zulkarimen. 1990. Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta. Nimmo, Dan and Sanders. 1981. Handbook of Political Communication.Sage Publications. London Nimmo, Dan (terjemehan Tjun Surjaman).1993. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media. PT Remadja Roesdakarya. Bandung Petterson, Thomas. 1980. The Mass Media Election. Preger Publisher. New York. Sendjaja, S. Djuarsa. 1994. Teori Komunikasi. Universitas Terbuka. Jakarta 162 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Sinergitas Pemikiran Muhammad Natsir Di Bidang Teologi. Pendidikan dan Poltik (Suatu Kajian Perspektif Pemikiran Politik Islam) M. Basir Syam Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Abstrak Karya ilmiah ini merupakan suatu studi Pemikiran Politik Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan konten analisis melalui beberapa karya tokoh yang bersangkutan. Yang menjadi obyeknya adalah pemikiran Muhammad Natsir, seorang tokoh nasional yang pernah menjabat Perdana Menteri Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan corak pemikiran Beliau sebagai seorang politisi yang memiliki reputasi internasional. Hasil penelaahan penulis menemukan bahwa Muhammad Natsir adalah seorang pemikir muslim yang telah menulis buku dalam beberapa bidang, Tulisannya paling menonjol terutama di bidang agama, pendidikan dan politik. Ketiga bidang ini menyatu dalam sistem pemikirannya. Penulis menemukan sinergitas pemikiran beliau pada ketiga bidang tersebut. Agama adalah soal hidup hidup dan mati (ultimate), pendidikan adalah jalan yang paling efektif untuk menginternalisasikan ajaran agama Islam, sedangkan politik adalah power yang dapat dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Kata kunci: Muhammad Natsir, sinergitas, pemikiran tentang agama, pendidikan dan politik. Pendahuluan Kebangkitan Islam sejak abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan di beberapa negara Islam seperti di Turki, Mesir dan India. Daerah- 163 Jurnal The Politics daerah tersebut merupakan basis kerajaan Islam yang pernah mengalami kejayaan di masa lampau, kemudian bangkit kembali setelah menyadari keterbelakangannya dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara-negara Barat. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebelumnya disepanjang wilayah tersebut juga pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, juga menyadari perlunya gerakan pembaharuan tersebut, meskipun upaya dalam hal itu baru dimulai pada akhir abad ke-19 di Minangkabau, namun sejak awal abad ke-20 gerakan ke arah pembaharuan terus berkembang dengan pesat, terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sejak itu umat Islam diperhadapkan kepada masalah-masalah kontemporer, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Dalam perkembangan tersebut di atas telah melahirkan beberapa tokoh pembaharu yang berbeda-beda karakteristik dan corak yang ditampilkannya sesuai dengan kecenderungan dan sudut pandang masing-masing. Salah seorang di antaranya Muhammad Natsir. Dipilih tokoh tersebut sebagai objek kajian ini, karena penulis tertarik bahwa beliau, selain sebagai pemikir yang hidup dalam tiga zaman di Indonesia yakni era Kolonial, era Orde Lama dan era Orde Baru, juga sekaligus sebagai praktisi pada bidang yang dikajinya. Titik berat yang menjadi fokus kajian makalah ini mengangkat tiga bidang yang terutama dibahas oleh beliau, yakni: bidang keagamaan dengan teologi, bidang pendidikan dan bidang politik. Penulis berasumsi bahwa ketiga bidang itu dalam pemikiran tokoh itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika yang disebut pertama berfungsi sebagai pondasinya, maka kedua bidang lainnya sebagai pilar yang tegak berdiri di atasnya. Dalam mengkaji masalah tersebut di atas, penulis menggunakan pendekatan sosio-historis, dalam artian bahwa selain diungkapkan secara historis, juga diusahakan analisa yang bersifat sosiologis, sehingga pikiran-pikiran Natsir tidak hanya dilihat secara kronologis, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor kondisi pada zaman. Sekilas tentang Biografinya Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, pada tanggal 17 Juli 1908, adalah seorang anak pegawai pemerintah. Pada tahun 1927 ia berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya pada Al-Agemene Middelbare School. Sebelumnya ia telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertamanya pada sekolah HIS dan MULO di daerah Minangkabau. Di daerah ini juga ia pernah belajar pada sekolah agama yang dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Tuan Mondo Amin, seorang kawan dari Haji Rasul. Selain itu ia juga mengikuti pelajaran secara teratur yang diberikan oleh Haji Abdullah Ahmad. Dengan itu dapat dikatakan bahwa Muhammad Natsir telah mengenal paham pembaharuan semenjak ia masih remaja (Deliar Noer, 1990:100). Di samping memasuki sekolah pendidikan barat, di Bandung minat Muhammad Natsir semakin dekat dengan agama. Pada tahun 1928 ia menjadi anggota Jong Islamieten Bond cabang Bandung di mana ia juga memberikan pelajaran kepada sesama anggota. Kemudian ia juga mengajar agama di Holland Illandse Kweekschool (HIK, Sekolah guru) dan MULO. Muhammad Natsir juga aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh organisasi PERSIS, terutama dalam pelaksanaan acara Jum’at, sehingga ia mempunyai hubungan rapat dengan tokoh- tokoh Persatuan Islam ini. Terutama Hassan, banyakmemberikan bimbingan kepada Natsir (Deliar Noer, ibid). Muhammad Natsir sejak awal sudah nampak bakatnya dalam menulis. Majalah Persis ‘Pembela Islam’, dijadikannya sebagai media dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Karena perhatian Natsir yang begitu besar dalam studi keislaman, sehingga ia menolak tawaran 164 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan studinya ke sekolah tinggi hukum di Jakarta atau sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, negeri Belanda. Ia malah memikirkan dan aktif menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak muslim (Deliar Noer, ibid). Untuk keperluan terakhir ini Muhammad Natsir Memulainya dengan tekad yang besar, walau modal yang sangat minim. Ia menyewa sebuah tempat yang amat sederhana dengan kapasitas daya tampung yang sangat terbatas di jalan Pangeran Sumedang di Bandung. Dengan bantuan seorang dermawan, Haji Muhammad Junus, sekolah yang didirikan Natsir dapat berkembang dan mendapat respons dari masyarakat Islam. Dalam memberikan pelajaranMuhammadNatsir dibantu oleh kawan-kawannya pada waktu itu antara lain Nur Nahar, yang kemudian menjadi istri Muhammad Natsir (Yusuf, 1978:29). Ketika itu disadari oleh Natsir, ada tiga syarat yang dapat menunjang tegaknya suatu lembaga pendidikan,yakni: Modal untuk menyewa atau mendirikan gedung dan segala peralatannya, bantuan tenaga pengajar dari kawan-kawannya yang secita-cita dan seperjuangan serta ilmu pendidikan yang dapat mengarahkan jalannya usaha pendidikan tersebut. Untuk keperluan yang terakhir itu, ia memasuki pendidikan guru yang diselenggarakan oleh AMS selama satu tahun. Tahun 1932, ia berhasil menyelesaikan program diploma tersebut. Selama Natsir dalam pendidikan tersebut, ia dapat menyusun rumusan atau rencana pendidikannya yang terdiri dari sekolah dasar, menengah dan sekolah guru. Teman-temannya di AMS seperti Ir. Ibrahim, Ir. Indracaya, Fachruddin Al-Khahiri dan sebagainya disamping Nur Nahar, banyak membantu dalam perkembangan sekolahnya. (Yusuf, ibid). Demikianlah lembaga pendidikan yang dirintis oleh Natsir mengalami perkembangannya dan pada akhirnya mengalami nasib buruk dengan datangnya masa penjajahan Jepang yang menutup semua sekolah partikelir, termasuk sekolah-sekolah Natsir. Namun semangat pendidikan Natsir ini tidak pernah pudar, Beliau terus memikirkan pendidikan Islam walaupun pada akhir hayatnya tidak sempat lagi menekuni bidang pengajaran di lembaga pendidikan formal. Selain di bidang pendidikan, Muhammad Natsir banyak berkiprah di bidang politik. Bagi Natsir, di zaman kolonial, terjun di bidang politik merupakan suatu hal yangsangat lumrah. Seseorang yang telah terjun dl masyarakat, jika ia sadar melihat ketimpangan yang ada dengan sendirinya iapun berusaha merobah hal tersebut. Upaya merobah keadaan yang ada sebenarnya seseorang dengan sendirinya sudah terjun ke dunia politik. Apakah yang bersangkutan berprofesi sebagai seorang guru, dokter, insinyur, ulama atau apa saja. Sebagai anggota Jong Islamieten Bond maupun Persis, Muhammad Natsir giat dalam lapangan politik menghadapi pemerintah kolonial. Ia juga banyak melakukan polemik dengan kalangan politisi kebangsaan yang netral agama, terutama dengan Sukarno. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Natsir sebagai seorang yang kukuh dalam pendirian Islam. Hal tersebut terjadi baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. Kegiatan politik Muhammad Natsir pada garis besarnya dapat dilihat pada jabatan yang pernah dipegangnya antara lain: Ketua Jong Islamieten Bond Bandung (1928-¬1932), Anggota Dewan kabupaten Bandung (1940-1958), Anggota Badan Pekerja KNIP (1945-1946), Menteri Penerangan RI (1950--1951), Ketua Umum Partai Masyumi (1949-1958), Perdana Menteri RI (1950-1951), Anggota Parlemen RI (1950-1958), Anggota Konstituante (1956-1958), Anggota PRRJ (1958-1960), Vice President World Muslim Congres (1967) dan sebagainya (Natsir, 1980:52). Kegiatan dan pemikiran Natsir dalam bidang tersebutdi atas adalah merupakan refleksi dari pandangan teologisnya. Yakni keyakinan akan kebenaran Islam sebagai pandangan hidupnya sekalipun Natsir mentolerir kemerdekaan berpikir (akal), namun baginya akal memerlukan bimbingan untuk dapat berfungsi dan menghasilkan kebenaran yang hakiki. Karena itu tauhid 165 Jurnal The Politics merupakan fundamen dari segala pemikiran dan aktifitasnya. Dan itulah yang ingin ditegakkannya dalam seluruh perjuangannya. Ia dapat menerima apa yang datang dari Barat, khususnya dalam bidang kehidupan duniawi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena menurutnya Islam bukanlah agama Timur ataupun Barat, melainkan agama Allah yang memiliki Timur dan Barat. Karena itu Islam menjadi patokan dalam kehidupan dan seorang muslim dapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang datang dari manapun dan dari siapapun datangnya. Namun dalam hal Aqidah dan ibadah prinsipnya, “semuanya tidak boleh kecuali apa yang telah digariskan”. Dalam bidang keagamaan ini Natsir mengakui, selainbelajar sendiri, juga banyak mempelajari dari ulama dan intelektual yang lebih senior. Di masa mudanya, jika menghadapi problema keagamaan ia dan kawan-kawannya mendatangi para ulama untuk meminta pandangannya. Sebagai pendukung pembaharuan, pada waktu itu ia dekat dengan A. Hassan dan Haji Agus Salim. Intelektual muslim terakhir ini memberikan kesan tersendiri dalam pemikiran Natsir. Satukesannyatentang Haji Agus Salim bahwa beliau jika ditanyakan suatumasalah kepadanya, tidak langsungmengambil keputusan tentang masalah tersebut, melainkan cukup dengan memberikan pengarahan tentang cara pemecahan masalah tersebut, kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk mengambil keputusan tentang permasalahan yang dihadapinya. Hal ini diakui Natsir sebagai motivasi yang sangat kuat untuk mewujudkan kemandiriannya dalam berfikir. Demikian sekilas gambaran umum tentang Muhammad Natsir dan pokok-pokok yang menjadi objek pemikirannya. Dipilihnya ketiga bidang kajian tersebut di atas, tidak berarti bahwa Natsir hanya menulis dan berbicara tentang ketiga masalah tersebut, akan tetapi jika ditelusuri pemikiran dan aktifitasnya dapat disimpulkan penekanannya pada ketiga hal tersebut. Tulisan-tulisannya tentang kebudayaan Islam maupun seluruh aktifitasnya di bidang da’wah dapat dikatagorikan ke dalam bidang pendidikan, demikian juga seluruh aktifitas kepemimpinannya dan pemikirannya dalam menata masyarakat baik yang berskala regional, nasional maupun internasional adalah menyangkut bidang politik. Sedangkan pemikiran teologis yang dimaksud adalah meliputi pandangan keagamaannya yang menjadi fundamen bagi seluruh aspek pemikirannya. Bidang Teologi Pada bagian ini penulis tidak bermaksud menguraikan pandangan Natsir secara rinci tentang tema-tema kajianteologi, melainkan hanya mengangkat sekelumit mengenai sistem teologi yang dianutnya yang pada dasarnya dapat dilihat pada pandangannya tentang hubungan antara wahyu dan akal pikiran serta sikap beliau dalam menghadapi persoalan kehendak mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Dalam karyanya, Islam dan Akal Merdeka. Muhammad Natsir mengawali dengan mengangkat beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan betapa Islam menghargai peranan akal pikiran manusia. Natsir mengutip surah Al-Waqi’ah ayat 58-72, yang antara lain menunjukkan perintah Allah memperhatikan dan memikirkan tumbuh-tumbuhan yang hidup, api yang menyala, air hujan yang turun dari langit, demikian pula keterangan dari ayat-ayat lain yang menyuruh memikirkan tentang hewan-hewan, bumi yang terhampar, langit yang ditinggikan, gunung yang tegak, awan dan mendung yang bergerak beriringan, dan disuruh mengambil konklusi tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Menurut Natsir bahwa Islam sangat mencela orang-orang yang tak menggunakan akalnya, orang yang terikat pikirannya dengan kepercayaan-kepercayaan dan paham-paham manusia yang tidak berdasar kebenaran, mereka yang tidak mau memeriksa, apakah kepercayaan dan pahampaham yang disuruh orang terima itu berdasar kebenaran atau tidak. Tegasnya bahwa Islam melarang bertaklid pada paham dan i’tiqad yang tidak berdasar wahyu Ilahi yang nyata, hanya 166 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 sekedar menurut paham-paham lama (pikiran tradisional) yang turun temurun dengan tidak mengetahui danmemeriksaterlebih dahulu, apakah paham itu berguna dan berfaedah dansuci atau tidak (Natsir, 1988:5) Akan tetapi Natsir menyadari keterbatasan akal pikiran manusia. Karena itu akal memerlukan bimbingan dan petunjuk dari wahyu Ilahi, jika tidak maka akal yang lepas kontrol dapat mengambang, bahkan bisa sesat. Ia menggambarkan bahwa akal yang sedemikian dapat saja melogiskan dan merasionalkan semua khurafat, semua bid’ah dan takhyul. Ia melihat fakta yang kontroversial mengenai hasil kerja akal yang bebas. Dengan akal merdeka mungkin seseorang mencela pemujaan patung, penggunaan azimat karena dianggapnya tidak logis, akan tetapi dengan akal itu pula yang mencarikan alasan mengkultuskan seseorang, menghormati bendera, terpaku dihadapan api unggun, mengadakan patung R.A. Kartini meletakkan patung ituditempat yang terang laras, mengatur upacara berdiri sambil berta’jub tafakkur dihadapan benda yang tak bernyawa itu. Natsir mengemukakan beberapa contoh tentang akal yang terbimbing dengan wahyu Ilahi. Dengan akal merdeka, kaum muslimin terbebas dari kekolotan yang membekukan otak, kejumudan, dengan akal merdeka telah melahirkan seorang Washil Ibn Atha’ yang berani mengritik cara berfikir Imam Hasan Al-Bashri. Dengan akal itu pula telah melahirkan Abu AlHuzail Al-Allaf, Al-Nazzam dan lain-lain pujangga Mu’tazailah yang tak kalah ketajaman otaknya dibandingkandengan filosof-filosof Barat. Dengan akal pula melahirkan Fakhruddin Al-Razi yang melahirkan tafsir Qur’an yang hingga kini tetap up to date, melahirkan Asy’ari yang berani mengeritik kelemahan-kelemahantokoh-tokoh Mu’tazilah dan melahirkan aliran teologi yang diperpegangi sebagian besar ummat Islam hingga dewasa ini. Asy’ari dengan teori ‘Ainusysyai’-nya tak kalah jika dibandingkan dengan teori Das Ding an Sich-nya Immanuel Kant, atau dengan teori “Kasb”-nya yang mendahului teori “Harmonia Praestabilia”-nya Leibnitz. Akal merdeka yang terbimbing pula melahirkan A-Ghazali, Ibn Taimia, seorang Muhammad Abduh dan sebagainya (ibid:8-9). Muhamad Natsir mengakui betapa besar peran Mu’tazilah dalam membela kebenaran Islam dengar argumenrasionalistiknya. Akan tetapi seorang Mu’tazilah seperti AlJubba’i akhirnya harus mengakui kritikan Asy’ari bahwa banyak hal di mana kita terpaksa harus mengatakan “Huwallah A’lam!”,atau menerima informasi wahyu dengan prinsip “Bila-kaifa”. Ia menjelaskan bahwa lapangan akal dapat menjelajahi semua ciptaan Ilahi, akan tetapi dilarang mengorek persoalan tentang (Zat) Allah. Demikian pula jika orang memperdebatkan tentang qadha dan qadar maka sebaiknya kita diam saja, karena persoalan itu diatas jangkauan akal (ibid:18-20). Lebih jauh Muhammad Natsir mengemukakan variasi masalah agama yang harus diterima apa adanya dan yang harus dipikirkan. Baginya ada perintah-perintah agama yang maknanya tidak terjangkau oleh akal seperti shalat, puasa, haji dan semacamnya. Hal seperti ini harus diterima apa adanya menurut petunjuk yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu ada juga perintah agama yang ma’qul dan cukup pula keterangan-keterangan agama yang menunjukkan illat-nya seperti menutup aurat, berbakti kepada ibu-bapak. Hal seperti ini dan semacamnya, cara dan alat-alat melakukannya diserahkan kepada pemikiran ummat Islam untuk memecahkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Selain kedua macam tersebut, terbentang luas persoalan kehidupan dunia yang diserahkan kepada pemikiran manusia untuk memecahkan dan mengambil manfaatnya sesuai dengan keperluan dan tuntutan zaman, akan tetapi diingatkan jangan sampai melanggar nilai-nilai dan prinsip Islam yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Persoalan dunia seperti sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya berlaku prinsip “semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang” (ibid:25-27). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pandangan Natsir, wahyu merupakan landasan 167 Jurnal The Politics tempat berpijak dalam kehidupan keagamaan yang sekaligus berfungsi sebagairujukan yang mesti ditaati dalam soal aqidah dan ibadah. Sedangkan akal merupakan alat yang efektif dalam memahami ajaran agama tersebut. Dalam soal aqidah dan ibadah akal hanya berperan menjelaskan, tidak mesti menghakimi wahyu dengan aturan logika yang ada padanya. Tetapi dalam soal muamalat, akal sebaliknya harus bekerja keras bahkan dituntut oleh wahyu itu sendiri untuk memecahkan berbagai problema kehidupan yang bersifat kontemporer yang tentunya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh wahyu. Bidang Pendidikan Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Muhammad Natsir memperoleh pendidikan formalnya melalui pendidikan Barat. Ia termasuk orang yang beruntung diantara banyak orang pribumi yang tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan modern yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian dengan latar belakang keluarganya dari masyarakat Minangkabau yang taat beragama membekas pula dalam kepribadiannya. Pendidikan bagi Natsir adalah menyangkut kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dia melihat adanya ketimpangan antara pendidikan Barat dengan pendidikan yang selama ini dikelola oleh ummat Islam. Diukur dari segi kemajuan duniawi, pendidikan Barat lebih maju, akan tetapi dari segi nilai etis dan kepentingan ukhrawi pendidikan yang dikelola ummat Islam lebih menonjol. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi pemikiran Natsir sehingga iaterjun ke dunia pendidikan. Ia berusaha menyatukan kedua keutamaan yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut, sehingga dalam hal ini sangat terbuka menerima hal-hal yang bersifat positif yang ada dalam pendidikan Barat. Dalam hal ini terutama yang menyangkut perkembangan sains dan teknologi. Bagi Natsir tidak melihat dari segi Barat dan Timurnya, melainkan kemajuan itu sendiri yang diakuinya ada pada pihak Barat. Natsir juga menunjukkan kekurangan pendidikan Barat dari segi ruhaniah. Dalam hal ini pendidikan Islam dengan landasan tauhidnya merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Suatu contoh fenomena pendidikan Barat dikemukakan Natsir tentang problema yang dihadapi Prof. Paul Ehrenfest, guru besar dalam ilmu fisika. Paul Ehrenfest meskipun seorang terpelajar yang berasal dari keluarga yang berperangai baik-baik dan dia sendiri dikenal sebagai ilmuwan yang bermoral. Tetapi pada akhir hayatnya ia lalu membunuh anak sendiri lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut surat pernyataan yang ditinggalkan bahwa hal itu dilakukan secara sadar karena ada suatu hal yang mengganjal dalam pikirannya yaitu kesadaran akan perlunya kepercayaan tempat bergantung selama ini telah disepelekannya karena percaya akan kebenaran ilmu pengetahuan sebagai tumpuan segalanya, yang kemudian disadarinya pula sebagai suatu hal yang nisbi, yakni kebenarannya hari ini belum tentu kebenarannya hari esok,karena ilmu mengalami perubahan terus menerus. Professor tersebut mempunyai anak yang sangat dicintainya yang diharapkan sebagai generasi satu-satunya yang akan melanjutkan riwayat dan mewarisi intelektualnya, namun anak tersebut mengalami kelemahan otak sehingga pengorbanannya yang besar membiayai anaknya dianggapnya sia-sisa belaka. Karena tidak mempunyai pegangan hidup dalam mengatasi problema itu, lalu secara sadar ia tega membunuh anaknya dan dirinya sendiri. (Natsir, 1954:114). Hal tersebut diatas menunjukkan suatu kelemahan Barat, dan harus disadari bahwa tidak semua yang datang dari Baratpun adalah otomatis bernilai baik. Karena itu Natsir tidak mentolerir westernisasi, pembaratan dan hanya menerima modernisasi dalam bidang muamalah dalam arti yang positif menurut spirit Islam. Suatu hal yang disoroti Natsir pada masalah pendidikan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda adalah usaha mereka mengajak golongan elit Indonesia 168 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 agar merasa diri sebagai orang Belanda yang sama-sama berkiblat ke Denhaag yang diistilahkan Natsir dengan “asimilasi” atau de-Indonesianisasi sehingga orang Indonesia bisa terlepas dari pandangan hidup dan budaya asli yang bersifat positif. Anak-anak yang berotak beriliant dititipkan kepada Kristen Belanda dan salah satu korbannya adalah Amir Syarifuddin yang lahir sebagai anakorang Islam kemudian menjadi orang Kristen Protestan. Oleh karena itu dalam rangka kemajuan pendidikandikalangan muslim pada masa kolonial itu harus ditanganioleh orang Islam sendiri yang memiliki kesadaran mengenaipentingnya kemajuan duniawi dan ukhrawi, atau mereka yangmengikuti pendidikan Barat itu harus memiliki kesiapan imanyang tangguh, kesadaran akan makna baik dan buruk menurutukuran Islam. Sehingga dapat menangkal polusi yang timbuldari kebebasan berpikir yang tidak terkendali oleh nilai-nilai kebenaran wahyu Ilahi. Natsir menyambut baik suatu usaha pendirian perguruan tinggi pada zaman kolonial yangdipelopori oleh Dr. Satiman dari Muhammadiyah. Tetapi jugamengeritik dari segi penerapan idenya bahwa mahasiswa yangakan diterima hanya lepasan H.B.S. atau AMS dan menutuppintu bagi lepasan sekolah menengah Islam. Bagi Natsir padamasa itu justru lepasan sekolah menengah Islam sangatdiperlukan untuk mengenyam pendidikan tinggiyangberorientasi kemajuan Barat memiliki ilmu pengetahuan danteknologi yang akan diterapkan pada perguruan tinggi itu.Sehinggamemungkinkan lahirnya ilmuwan-ilmuwanyangberkepribadian dan berkebudayaan Islam (Ibid, hal. 66). Dalam rangka mengisi peluang tersebut di atas, Natsir mengajukan gagasan koordinasi perguruan-perguruan Islam (1938) yang akan menyatukan rencana pelajaran perguruan tersebut yang selama ini dinilainya belum adakeseragaman dan kesamaan sasaran yang kongkrit. Kalau persamaan dasar dan tujuandiakui memang selama ini sudah dimiliki, tetapi persamaan teknik pengajaran dan ragam ilmu pengetahuan belum nampak terutama yang berorientasi pada masalah kehidupan dunia, karena itu perlu diadakan. Koordinasi bagi Natsir bukan suatu normalisasi yang akan menghancurkan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing perguruan itu sesuai dengan cita-cita pendirinya, karena hal itu merupakan suatu hal yang layak sepanjang tidak mengabaikan kepentingan umum yang dibutuhkan ummat Islam pada waktu itu. Dalam mengatasi khilafiyah perlu ditekankan keterbukaan menerima dan memberi hal yang terbaik, dalam hal ini memerlukan pengorbanan integritas dalam rangka kepentingan integrasi sesama muslim (Ibid, hal. 81). Di zaman kemajuan dewasa ini (pasca kemerdekaan) prinsip penyatuan agama dan ilmu pengetahuan tetap mutlak diadakan. Perkembangan di bidang industri kini ummat Islam harus terlibat, arus informasi dari Barat juga tidak dapat dielakkan. Karena itu yang penting peranan agama menjaga jangan sampai kemajuan industri dan informasi menimbulkan “permissiveness” yaitu melunakkan faktor manusiawi yang terlibat dalam perkembangan itu, agar modernisasi dalam bidang-bidang kehidupan tidak mengakibatkan tumbuhnya pandangan “semau gue” yang mencampakkan manusia padakemerosotan akhlak. Natsir mengingatkan bahwa dinegeri Barat sendiri, dibalik kemajuan industrinya menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran dalam menghadapi polusi yang timbul. Pengotoran udara, air di daerah perindustrian, kemungkinan terjadinya perang nuklir yang berakibat degradasi total bagi penduduk bumi, angka pengangguran akibat mekanisasi industri yang berteknologi tinggi, yang kesemuanya itu merupakan masalah yang tidak mudah dipecahkan. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi dan industri adalah sesuatu yang netral, tergantung kepada manusianya dan masalahnya terletak pada motivasi dan cara penggunaannya, karena itu sebagai seorang muslim bagaimana kita memanfaatkan semua itu sebagai rahmat ilahi dengan motivasi untuk menegakkan kebajikan bagi ummat manusia (Natsir, 1987:2). Prospektif ke arah kemajuan itu bagi Islam merupakan suatu keharusan selain ajaran Islam yang sangat menghargai akal pikiran manusia, memerintahkan menuntut ilmu tanpa membatasi 169 Jurnal The Politics umur maupun tempat menimba ilmu, juga kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Islam dalam bidang tersebut pada masa pertengahan, di saat masyarakat Barat menyepelekan hal yang sama. Justru apa yang telah dicapai ummat Islam pada zaman lampau itu merupakan tindakan penyelamatan dan hasil pimikirannya merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan dengan kemajuan ilmu danteknologi dewasa ini. Bidang Politik Seperti halnya dengan keterlibatan Natsir di bidang pendidikan, di bidang politik ia tampil untuk memperbaiki keadaan masyarakat Islam dan dalam rangka memperjuangkan penerapanprinsip-prinsipIslam dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara. Ummat Islam perlu terlibat dalam menata kehidupan sosialnya sendiri. Bagi Natsir yang menganut prinsip keterkaitan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, tidak membiarkan adanya upaya menetralisir kedudukan ulama memimpin masyarakat. Natsir menegaskan bahwa sejarah revolusi kemerdekaan kita membuktikan betapa besar kekuatan yang dapat terbangun bila sudah bertemu antara pesantren dengan universitas. Samasama berjumpa di mesjid jami setiap jum’at dimana terdengar seruan imam sebelum shalat “sawwu shufufakum” susunlah barisanmu! Seruan itu tidak hanya dipahami dalam mesjid saja, melainkan perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di luar mesjid (Ibid:8). Di zaman kolonial, sebagai ketua Jong Islamiten Bond Natsir aktif memberikan kontribusi pemikirannya di bidang politik. Ia mengeritik beberapa artikel yang ditulis oleh orientalis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip politik Islam, seperti pandangan Dr. I. J Brugmansyang mengajarkan bahwa Islam sesudah mengajarkan kalimat syahadat, terus memerintahkan untuk menaklukkan segala bangsa tanpa memperhatikan pendidikan bangsa yang ditaklukkannya. Brugmans dalam hal ini beralasan bahwa C. Snouck Hurgronje juga menyimpulkan demikian (Op .Cit: 119). Natsir membantah pandangan itudengan menunjukkanbeberapa ayat suci Al-Qur’an dan sunnah Nabiyangmenegaskan bahwa Islam tidak serta merta menyerang suatubangsa kecuali dengan alasan tertentu. Lagi pula bahwaIslam justru sangat mementingkan pendidikan ummat ataubangsa yang ditaklukkannya. Mengenai pernyataan bahwa Islamdikembangkan dengan perantaraan pedang yang dirujukkandengan pandangan Snouck, Natsir menulis bahwa jikaseandainya Snouck masih hidup dan membaca tulisan itu tentuakan membantahnya, sebab Snouck sendiri mengakui hakekatajaran Islam yang menekankan perlunya pendidikan itu,sekalipun Snouck memang mengakui bahwa dalam sejarah ummatIslam terkadang menukar penyiaran Islam melalui kalamdengan menggunakan pedang, yang jelas bukan Islamnya yang berhakekat demikian (Ibid:127). Selain menghadapi pemerintah kolonial, Natsir juga banyak melakukan polemik dengan tokoh-tokoh nasionalis yang netral agama, seperti Sukarno. Berbeda dengan Sukarno, Natsir menyatakan bahwa kita harus menjelaskan konsepkebangsaan itu dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia dan yang mendorong mereka dalam memperjuangkannasib bangsanya. Menurut Natsirbahwapergerakan Islamlah yang lebih dahulu membuka jalan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat kepulauan dan kepropinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengankaum yang sama, senasib di luar batas Indonesia dengan tali keislaman (Natsir, 1931:14). Tujuan kaum muslimin mencari kemerdekaan adalah untuk kemerdekaan Islam, supaya berlaku peraturan dansusunan Islam untuk keselamatan dan keutamaan ummat Islam khususnya dan segala makhluk Allah umumnya (Deliar Noer, Ibid:281). Pandangan seperti itu tetap diperjuangkan 170 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Natsir hingga pascakemerdekaan, terutama pada waktu ia menjabat sebagai perdana menteri RI, ketika itu ia mengusulkan agar Islam dapat diterima sebagai Dasar Negara. Dalam kaitan itu Natsir menjelaskan bahwa sebagai agama yang mengakar dalam kehidupan mayoritas bangsa Indonesia, maka Islam patut diperhitungkan untuk itu. Ahmad (1981:127). Natsir dalam menyampaikan gagasan itu tentunya dengan kepala dingin, karena ia sendiri bukan seorang ekstrimis yang gegabah. Dengan uraian tersebut dapat dipahami pandangan hidup Natsir yang konsisten dengan agamanya. Namun demikian sebagai pemimpin yang arif membaca tanda-tanda zaman ia dapat beradaptasi dengan kenyataan perkembangan yang tidak selamanya menopang ide-ide tersebut di atas. Ia terpaksa diperhadapkan menerima gagasan Sukarno sebagai tokoh yang amat berpengaruh itu mewujudkan negara demokrasi yang netral agama, selanjutnya menerima pula perobahan teks pancasila yang dalam piagam Jakarta menekankan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan kalimat ketuhanan yang maha Esa. Bahkan terpaksa menerima pembubaran partai Masyumi yang dipimpinnya karena dianggap tidak loyal terhadap kebijaksanaan pemimpin revolusi. Di masa hidupnya ia mengalami pula pencopotan asas Islam dalam organisasi sosial dan politik yang selama ini tetap mendapat legitimasi dari pemerintah termasuk dalam era orde lama. Natsir mengakui semua itu merupakan pengorbanan ummat Islam demi keutuhan negara yang telah diperjuangkannya dengan tetesan darah dan air mata. Pada masa orde baru gagasan Natsir lebih ditekankan kepada perlunya iklim kebebasan mengeluarkan pendapat bagi ummat Islam khususnya yang selama ini selalu dipojokkan dan dikambinghitamkan. Kepada ummat Islam, Natsir senantiasa menyerukanpersatuan. Dalam bukunya Mempersatukan Ummat. Natsir mengemukakan iman sebagai dasar persatuan sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ini dipesankan agar terus menerus ditabligkan kepada ummat. Persatuan adalah soal hati bukan sekedar pengetahuan tentang baik buruknya persatuan dan perpecahan, karena itu harus menjadi tujuan hidup yang diniatkan oleh hati untuk mencapainya, juga harus menjadi amal yang bersih dan ikhlas. Perbedaan pendapat dalam kejujuran adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia, yang penting tidak ditunggangi hawa nafsu hendak menang sendiri. Natsir juga menekankan bahwa persatuan yang dipaksakan tidak akan berumur panjang. Karena itu ia tidak setuju dengan gagasan penyatuan organisasi Islam seperti PPP dan semacamnya, karena itu merupakan suatu paksaan. Juga bahwa timbulnya perpecahan ummat Islam tidak ditentukan banyaknya organisasi Islam, melainkan karena sikap ketidakterbukaan untuk salingmemberi dan menerima gagasan yang baik (Natsir, 1983:9). Demikianlah sekilas tentang seorang tokoh dan pemikirannya dalam kajian pemikiran Islam kontemporer. Walaupun penulis menyadari bahwa makalah ini teramat singkat untuk menggambarkan pemikiran Natsir yang telah melewati masa kehidupan yang cukup panjang, namun sebagaisuatu upaya konstruktif kiranya patut dipertimbangkan sebagai bahan diskusi. Kesimpulan 1. Jika dilihat dari segi zamannya pada masa kolonial dan awal pembentukan negara kita, Natsir dengan gagasan pendidikan dan politiknya dapat dimasukkan sebagai kelompok pembaharu. Kesadaran akan perlunya keterbukaan menerima kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam dalam bidang pendidikan merupakan suatu gagasan yang langka pada masanya. Demikian juga gagasan perlunya menjelaskan secara Islam tentang konsep kebangsaan, demokrasi dan persatuan adalah merupakan suatu perjuangan yang tetap menjadi cita-cita dan acuan bagi ummat Islam Indonesia. Gagasan itu secara utuh tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan tersudutkan 171 Jurnal The Politics oleh pandangan lain yang lebih bersifat netral. Namun kegagalan itu dirasakan sebagai milik ummat Islam pada umumnya yang sadar akan arti agamanya. Setidak-tidaknya diakui oleh semua ummat Islam sebagai pengorbanan demi kelanggengan negara yang telah diperjuangkan oleh mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam. 2. Bahwa segala bentuk pemikiran Natsir, khususnya dalam bidang pendidikan dan politik seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan refleksi dari jiwa Islamnya yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Walaupun secara taktis ia harus beradaptasi dengan kenyataan yang diperhadapkan kepadanya. Dalam hal ini Natsir tidak melihatBarat dan Timur sebagai patokan. Baginya dapat saja menerima atau menolak perkembangan Barat maupun tradisi adat istiadat Timur, hal ini tergantung dari nilai positifnya, apakah itu dapat menunjang prinsip-prinsip Islam yang diyakini kebenarannya. 3. Suatu hal yang unik jika dibandingkan dengan para pembaharu pada umumnya di dunia internasional seperti Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh dan sebagainya, bahwa Natsir masih tergolong penganut aliran Ahl-Sunnah yang setia, sekalipun tidak menutup mata untuk mengakui peran yang dimainkan oleh aliran rasional Islam seperti Mu’tazilah. Ia tetap kukuh menganut prinsip tauhid, qada dan qadar ala tradisionalis, namun tidak menjadi penghalang dalam segala upaya pembaharuan. Daftar Pustaka DeliarNoer, Gerakan Modern Islam di Indonesia,Jakarta: LP3ES, 1990, h. 100. Ma’arif Ahmad Syafi’i, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1985 Muhammad Natsir, Word of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980 Muhammad Natsir, Islam dan Akal Merdeka, Jakarta:MediaDa’wah, 1988 Muhammad Natsir, Capita Selecta I. Bandung: N.V. Penerbitan W.Van Hove, 1954 Muhammad Natsir, Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia, Jakarta: MediaDa’wah, 1987 Muhammad Natsir, “Kebangsaan Muslim”, Pembela Islam No. 36 (Oktober 1931) Muhammad Natsir, Mempersatukan Ummat. Jakarta: Samudera.1983 Puar, Yusuf Abdullah (Ed), Mohammad Natsir 70 tahun:Kenang-Kenangandan Perjuangan, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, h. 29 172 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014 ) Siti Nimrah dan Sakaria (Mahasiswa Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin) Abstrak Pasca disahkannya undang-undang keterwakilan perempuan dalam partai politik menyebabkan kaum perempuan terjun ke dunia politik. Namun keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, khususnya dalam kelembagaan formal masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini yaitu 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan caleg perempuan. 2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Adapun metode penulisan ini adalah telaah pustaka. Berdasarkan hasil analisis, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara lakilaki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama budaya patriarki. Faktor kedua partai politik. Ketiga, yaitu media. Keempat, yaitu tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partaipartai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Hal inilah yang membuat masyarakat selalu berpersepsi bahwa politik adalah dunianya lakilaki dan perempuan harusnya berada dalam wilayah domestik sehingga perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Kata Kunci: Perempuan, Politik, dan Budaya Patriarki. Abstract After the enactment of women’s representation in political parties cause women into politics. But the involvement of women in politics, particularly in the formal institutions are still far from the expected. Therefore the aim of this paper is 1. To determine 173 Jurnal The Politics the factors that cause the failure of women candidates. 2.To determine the public perception about women’s representation in legislative elections. The method of this paper is to review of the literature. Based on the analysis, that there are several factors that influence the selection patterns between men and women as legislators. The first factor is the culture of patriarchy. The second factor is political parties. Third, the media. Fourth, namely the lack of networking between organizations, NGOs and political parties to fight for women’s representation. This is what makes people always perceived that politics is his world men and women should be in the domestic sphere so that women are always just seen the second man after man. Keywords: Women, Politics, and Culture Patriarchate. Pendahuluan Sejak konsep gender berkembang, tidak dapat dipungkiri lagi peran perempuan dalam pembangunan telah mengalami pembaharuan. Di bidang pendidikan misalnya, perempuan telah mengalami peningkatan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Posisi-posisi penting baik di pemerintahan maupun non pemerintahan cukup banyak dijalankan oleh perempuan. Dalam bidang politik, yang seringkali disebut sebagai dunia laki-laki, aspirasi perempuan juga telah mendapat tempat walaupun belum semua aspek terwakili. Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia telah muncul sejak lama. Begitu banyak tercatat sejumlah tokoh perempuan yang turut memberikan andil dalam aktivitas politik, dengan perjuangan fisik melawan penjajah, serta berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan (Bakti, 2012:149). Begitu banyak cara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan hal itu membuahkan hasil, yaitu telah membuka jalan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk dunia politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti kaum perempuan, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. Mereka berpikir perempuan juga mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang sama dengan laki-laki, yang juga bisa digunakan untuk mempolitisir dan mengontrol kaum laki-laki, bisa memberikan suara terbanyak, serta bisa dimanfaatkan demi kepentingan tertentu (Primariantari, 1998:41). Salah satu yang perlu diperhitungkan keberadaannya dalam dunia politik sekarang adalah kaum perempuan dimana selain merupakan pemberi suara terbanyak, perempuan juga sudah banyak yang terlibat langsung dalam partai politik misalnya sebagai pengurus partai, pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Perbincangan tentang perempuan politik Indonesia setidaknya bersentuhan dengan upaya untuk memajukan demokrasi, di dalamnya setiap penghuni negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini, perempuan dalam bingkai politik belum sampai pada tingkat maksimal. Meskipun secara historis keterlibatan kaum perempuan di ranah politik di Indonesia 174 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 memiliki akarnya yang panjang, namun realitas kekinian justru memperlihatkan hal yang tidak cukup menggembirakan. Keterlibatan kaum perempuan di dunia politik, khususnya dalam sektor kelembagaan formal (DPR/DPRD), misalnya masih jauh dari yang diharapkan. Kalau dilihat dari segi perbandingan antara jumlah populasi perempuan Indonesia yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah penduduk, dengan mereka yang terlibat dalam politik. Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995 (Putra, 2012:97). Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan mahluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras. Negara yang menganut sistem patriarki, laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Hal inilah yang membuat terjadinya pembagian kerja terhadap perempuan, karena laki-laki lah yang selalu mengambil keputusan, baik dalam keluarga, maupun di tempat kerja. Dengan budaya patriarki seperti ini telah membuat kesempatan perempuan terbatasi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, bahwa telah banyak perempuan-perempuan yang turut berpartisipasi dalam politik, namun hasilnya tidak begitu memuaskan. Hal tersebut di dukung juga oleh Khofifa Indar Parawansa (Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partaipartai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Melihat fenomena sekarang ini bahwa untuk menjadi anggota legislatif perempuan begitu banyak menghadapi rintangan dan tantangan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari partai-partai politik. Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitupun di tempat kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat pada waktu pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Namun dari keikutsertaan mereka belum membuahkan hasil yang baik, masyarakat masih memandang sebelah mata. Dari hasil pemilu legislatif pada tahun 2014 menunjukan bahwa perempuan masih saja sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam kelembagaan formal yaitu kursi anggota DPRD. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka keterwakilan perempuan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal, kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam 175 Jurnal The Politics daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014 (Dina Manafe: Suara Pembaruan). Penurunan angka keterwakilan perempuan memang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Diantaranya yaitu dengan mengubah mindset masyarakat, yang melihat politik hanyalah panggung dari lakilaki dan perempuan tidak mampu untuk bertarung dalam ranah politik. Karena pemikiran seperti inilah yang membuat perempuan selalu saja tidak mendapat dukungan secara maksimal dalam pemilu legislatif. Pembahasan 1. Kendala-kendala yang di Hadapi Perempuan dalam Pemilu Legislatif Upaya untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan adalah suatu perubahan perilaku (kognisi, efeksi, dan keterampilan) positif yang akan membawa kemanfaatan bagi orang banyak yaitu, masyarakat secara keseluruhan. Namun fakta empiris menunjukan bahwa perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan. Ketertinggalan perempuan seperti ini akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi keseluruhan pembangunan jika tidak diperbaiki. Karena itulah peningkatan peran perempuan dalam pembangunan merupakan kesepakatan dunia yang dimulai pada Tahun Dekade Perempuan sebagai tonggak pertama pencanangan peningkatan peran perempuan untuk kemanfaatan pembangunan (Vitayala, 2010:93). Pendekatan gender dan pembangunan merupakan upaya untuk menumbuhkan kemitrasejajaran lelaki dan perempuan dalam konteks kehidupan yang luas. Kemitrasejajaran lelaki dan perempuan yang dimaksudkan adalah mencakup kebersamaan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, pengawasan sumberdaya dan kekuasaan, pengambilan kekuasaan keluarga terhadap penggunaan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagai upah yang lebih adil. Hanya saja perempuan selalu diposisikan pada peran domestik dan reproduksi yang sangat menghambat kemajuan mereka mengguluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan pelabelan atau streotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Hingga perempuan susah untuk ikut berpolitik. Hingga akhirnya, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Pemilu tentang 30% representasi perempuan dalam setiap partai politik, membuat terbukanya peluang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Namun kenyataannya tak seperti yang kita bayangkan, bahwa tidak mudah untuk perempuan dalam mengguluti dunia politik karena begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus di hadapi perempuan saat menjadi calon anggota legislatif. Seperti yang dikatakan oleh Khofifa Indar Parawansa dalam tulisannya bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partaipartai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Apa yang dikatakan Khofifa Indar Parawansa diatas memang benar, bahwa budaya patriarki 176 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 sangat menghambat kemajuan bagi politisi perempuan, karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perempuan tugasnya berada dalam rumah dan tidak pantas untuk bekerja diluar rumah. Apalagi dalam dunia politik yang dianggap adalah dunianya laki-laki. Dari segi partai politik, bahwa memang tidak sedikit partai politik yang memberi akses perempuan hanya sebatas pemenuhan tuntutan representasi 30% perempuan. Dari segi media, seperti apa yang kita lihat selama ini hanya menunjukan bagaimana kerasnya dunia politik. Sedangkan yang terakhir yaitu memang tidak adanya dukungan dari suatu lembaga atau organisasi terhadap perempuan. Tantangan yang terberat bagi caleg perempuan adalah caleg dari sesama perempuan itu sendiri, dengan beragam budaya politik lokalnya, tingkatan keterkungkungan mereka dalam budaya patriarki lokal, tingkat pendidikanya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri. Yaitu menghapus keragu-raguan diantara perempuan sendiri tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor. Pemahaman makna dari politik yang berpersfektif perempuan harus di pahami terlebih dahulu, yang menjadi platform bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan Indonesia. Sehingga bisa mengkritisi pandangan umum/maskulin bahwa politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, ketimbang sebagai prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Sedangkan partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun kendaraanya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu ini, yang mau tak mau harus diikuti oleh para perempuan indonesia. Karena perempuan pun merupakan makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan Negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Negara indonesia merupakan Negara yang masih kental budaya patriarkinya. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara lakilaki dan perempuan dimasyarakat yang kemudian mejadi hierarki gender (2009:33). Hal tersebut memang benar, seperti yang telah kita lihat bahwa sampai sekarang budaya patriarki masih sangat mengikat masyarakat kita. Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim dalam Abbas, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut Djajanegara melahirkan pelabelan atau streotipe bahwa laki-laki adalah sosok yang mendiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan mengandalkan naluri (Abbas, 2006). Hal tersebut berdampak pada kehidupan perempuan yang seringkali digambarkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Mereka seringkali dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri, bergantung, jenis pelengkap lelaki, yang hanya berperan secara domestik saja. Pandangan semacam itu memperoleh legitimasi yang kuat dalam wujud tatanan struktur sosio-politik yang lebih berpihak pada budaya patriarki. Sebagai akibat, perempuan tidak memperoleh peran untuk mengaktualisasikan dirinya sejajar dengan laki-laki (Maiwan, 2006:31). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para penganut feminism radikal, yang mana teori feminis radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur- 177 Jurnal The Politics unsur sosial atau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideology patriarkinya. Dengan demikian kaum laki-laki secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan (Fakih, 1996:84-85). Bagi perempuan, politik sangat berarti, karena politik diartikan sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan dan kepentingan perempuan menyangkut kesetaraan, keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, Negara dan masyarakat. Gender dalam bidang politik melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam politik harusnya sama dan mendapatkan tempat yang sama dengan tempat yang biasa laki-laki tempati (Tandang, 2004:67). Maka dari itu perempuan sampai saat ini masih tetap semangat untuk turut berpartisipasi dalam politik walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Karena partisipasi politik adalah milik semua warga. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga dalam proses politik. Dalam hal ini tidak hanya ikut mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tetapi turut dalam pembuatan keputusan hingga pada pelaksanaan keputusan. Menurut Huntington dan Nelson (1990:4), partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga Negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sementara definisi umum dari partisipasi politik adalah mencakup orientasi-orietasi para warga Negara terhadap politik mereka yang nyata. Dalam konteks tersebut, pertisipasi politik berkaitan dengan perilaku-perilaku dalam suatu kegiatan ataupun sikap dan persepsi masyarakat yang memiliki relevansi secara politisi. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musyawarah. Di Indonesia saat ini penggunaan partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Hal inilah yang membuat suara-suara perempuan tidak begitu dipedulikan karena anggapan masyarakat pada perempuan selalu berada di posisi kedua setelah laki-laki. Padahal sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 2. Persepsi Masyarakat tentang Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia dan Negara-negara berkembang pada umumnya, bisa dikatakan terlambat. Hal itu dikarenakan banyak stigma yang mengatakan bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sehingga masih sangat sedikit perempuan yang turut andil dalam dunia politik. Sementara dunia politik itu sendiri dianggap lekat dengan dunia yang keras , penuh persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, ini dianggap ciri-ciri yang melekat pada laki-laki. Persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah lelaki. Secara jelas memiliki jalur yang judgement, dengan tendensi orang kelas dua yang seharusnya dirumah dan bertabur dengan konsumerisme, hedonisme dalam cengkraman kapitalisme. Anggapan perempuan sebagai mahluk lemah memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan dialektika kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena patron yang telah membentuk perempuan sebagai mahluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan (Putra, 178 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 2012:99). Anggapan-anggapan seperti itulah yang membuat perempuan sedikit ikut berperan dalam dunia politik. Namun sebenarnya peran perempuan Indonesia dalam pembangunan nasional adalah suatu hal yang penting dan isu menarik sepanjang masa. Tapi tetap saja kebanyakan perencana pembangunan mengabaikan perempuan yang merupakan setengah dari populasi. Padahal, mereka adalah sumber daya manusia (SDM) paling signifikan dimana kontribusi ekonomi mereka memiliki kesetaraan status sama halnya dengan laki-laki. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya tepat menjadi ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat, apalagi aktor politik. Hal tersebut serupa yang dikatakan Khofifah Indar Parawansa bahwa dalam negara yang menganut sistem patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (Parawansa. Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan di lembaga itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Demikian seterusnya, sampai pada zaman orde baru, ketika perempuan hanya diberikan status sebagai pendamping suami, organisasi perempuan terbesar waktu itu, yaitu PKK dan Dharma Wanita tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung “top down”. Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dan lembagalembaga atau di sektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi dan menyeimbangkan visi, misi dan operasionalisasi Indonesia selanjutnya, yang objektif, namun berempati dan berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin). Simak jumlah anggota perempuan dari DPR pusat sejak awal kemerdekaan tidak pernah melebihi 13 persen (periode 1987- 1992) , bahkan saat ini hanya sekitar sembilan persen, sedangkan ditingkat daerah hanya sekitar tiga persen. Banyak hal yang terjadi dan terdapat di Indonesia yang memutlakan keterwakilan para perempuannya yang memadai dalam kuantitas dan kualitas di lembaga-lembaga negara dan sektor-sektor publik lainnya untuk menciptakan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peluang-peluang politik telah dibuat agar perempuan turut berpartisipasi dalam politik namun ketika perempuan telah turut andil berpartisipasi masih banyak juga rintangan dan tantangan yang ditemukan. Ani Soetjipto dalam tulisannya memperlihatkan beberapa ironi dari kebijakan afirmatif yang ada di Indonesia. Pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan anggota parlemen yang ada saat ini mempunyai modal finansial dan jaringan yang memadai, namun minim modal politik. Ironi kedua adalah kesenjangan pemaknaan politik yang “tidak nyambung” bagi publik antara mereka yang berjuang di akar rumput dengan mereka yang berjuang di arena politik (parpol dan Parlemen). Banyak pengamat-pengamat politik yang menanggapi peran perempuan dalam politik. Mereka mengatakan bahwa peran perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi dan lainnya lebih maju dibanding negara lain. Tapi perempuan Indonesia masih terjebak pada budaya politik yang 179 Jurnal The Politics tidak memungkinkannya berperan penuh di dalam kehidupan politik. Gerak perempuan yang berkecimpung dalam kehidupan politik sudah dibatasi dan dipolakan. Namun banyak perempuan yang terjun ke dunia politik tidak menyadari akan hal tersebut. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia politik, namun bagitu banyak rintangan dan tantangan yang di hadapi salah satunya yaitu budaya patriarki. Rendahnya keterwakilan anggota legislatif perempuan disebabkan adanya budaya patriarki yang masih mengental dalam masyarakat kita. Sistem dan struktur sosial patriaki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, dan beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki. Hal inilah yang membuat kesempatan perempuan terbatasi untuk menjadi seorang anggota legislatif. Disisi lain, ketidakmengertian, kurangnya empati, dan kurangnya perhatian para personel negara yang kebanyakan laki-laki terhadap persoalan perempuan maupun mengenai kesejahteraan rakyat yang berwawasan gender. Jumlah anggota perempuan dalam pembuatan kebijakan dan hukum-hukum formal/publik negara Indonesia yang sangat minim untuk dapat mempengaruhi sistem. Masalahmasalah seperti inilah yang kemudian membuat masyarakat berpersepsi bahwa perempuan tak pantas berada dalam panggung politik yang keras. Perempuan pantasnya melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik). Saran 1. Untuk pemerintah diharapkan perlu membuat regulasi/kebijakan baru yang dapat mendukung atau memperkuat tentang keberadaan 30% representasi perempuan. 2. Selanjutnya pemerintah agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat khususnya yang terkait dengan perempuan 3. Untuk perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga yang berpolitik namun harus tetap dalam koridor sebagai perempuan. Daftar Pustaka Abbas. 2006. Idealisme perempuan indonesia dan amerika. Makassar: Eramedia Arivia, Gadis. 2006. Feminism : Sebuah kata hati. Jakarta: Kompas Beilharz, Peter. 2005. Teori-teori Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dina Manafe. Suara Pembaruan, Selasa, tgl 16 September 2014 (diakses pada tanggal 10 April 2015) Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Bandung: Pustaka Pelajar Feybe M.P Wuisan. Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014) Huntington, Samuel & Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineke Cipta. Maiwan, Moh. 2006. Perempuan dalam Teori Politik Plato: Persamaan, Ironi dan Kontradiksi 180 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 (dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan). Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Parawansa, Khofifah Indah. 2002. Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. IDEA International Publications. (di akses pada tanggal 27 maret 2015). Primariantari, dkk. 1998. Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis. Yogyakarta: Kanisius. Phierquinn. 2012. Budaya Patriarki dalam Pendidikan Gender di Masyarakat. https://phierda. wordpress.com/ (di akses pada tanggal 27 maret 2015). Putra, Dedi Kurnia Syah. 2012. Media dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Soetjipto, Ani. 2011. Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, Tangerang: Marjin Kiri. Tandang Assegaf, Nurcahaya. 2004. Kembalikan hak Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Timur. Vitayala, Aida. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press. Wardani, Eka Harisma. 2009. Belenggu-Belenggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morrison Dalam The Bluest Eye. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya UNDIP 181 Jurnal The Politics 182 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Negara, Pasar, Dan Problem Pendalaman Demokrasi Pasca Orde Baru Ade M Wirasenjaya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta [email protected] Abstract This paper tries to elaborate about deepening integration of state to neoliberal regime and its implication on deepening of democracy in domestic level. After the New Order era, the mass political identity all channeled through very limited political institutions proved to re-discover the primordial basis. Along with the growth of neo-liberal regime, changing also the constructt of the state formation by the international structures. Construction of the state as an agent of the capitalist is changing. If liberalism tend to create state as repressive apparatus, the neoliberal regime tried to construct a democratic state. Moreover, the neoliberal regime also began creating directly political identity that they expect in domesticlevel. Keywords: neoliberalism, New Order era, deepening democracy, constructivist, floating mass Pendahuluan Upaya rezim pasca Orde Baru membangun harmonisasi antara pembangunan ekonomi melalui jalur liberalisasi dan akomodasi atas ledakkan partisipasi politik masyarakat melalui jalur demokratisasi nampak tidak mudah dilakukan. Berbagai regulasi yang memberi jalan terbuka bagi proses privatisasi terus berlangsung sejak kepemimpinan Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Arena ekonomi-politik internasional yang dihadapi oleh negara Orde Baru dan pasca Orde Baru juga turut memberi penjelasan tentang pergeseran 183 Jurnal The Politics watak negara. Era Orde Baru hidup dalam ruang ekonomi-politik dimana pola-pola developmental state begitu dominan di sejumlah negara berkembang. Sedangkan era pasca Orde Baru hidup di bawah kecenderungan regulatory state yang menunjukkan makin berkuasanya rezim internasional dalam mempengaruhi politik domestik suatu negara. Baik pada model developmental state maupun regulatory state, negara tetap menjadi instrumen pengendalian massa. Pada fase developmental-state, terdapat separasi atau pemisahan antara aspek ekonomi dan politik dari rezim ekonomi internasional pada saat itu. Dalam beberapa aspek, hal ini menyumbang bagi proses stabilitas makro ekonomi. Namun dari aspek lainnya, pola ini membuat persoalanpersoalan pelanggaran politik seperti hak asasi manusia dan demokratisasi menjadi terhambat. Negara, Kapital dan Massa Mengambang Disiplin ekonomi menjadi perhatian paling besar dari lembaga ekonomi internasional pada era Orde Baru.Sementara pada konteks hubungan negara dan masyarakat di level domestik, berlangsung pola pendisiplinan politik oleh negara.Melalui kebijakan politik yang korporatik, negara mengendalikan gerakan sosial-politik yang timbul pada saat itu.Beragam organisasi dan asosiasi tumbuh pada masa Orde Baru, namun tetap harus mengacu pada disiplin politik yang ketat dari negara.Hal ini juga memberi gambaran bahwa kebijakan separatis lembaga ekonomi internasional pada saat itu masih memberi ruang kedaulatan (souvereignty) bagi negara. Posisi negara yang seakan menjadi entitas tunggal membawa implikasi pada dinamika politik domestik. Konsentrasi pada aspek ekonomi mendorong rezim Orde Baru menciptakan model pelembagaan politik korporatik untuk mengendalikan massa. Tujuan dari korporasi ini sangat jelas, yakni bagaimana identitas politik masyarakat tetap dijaga dalam norma dan ideologi negara. Kalangan konstruktivis melihat identitas sebagai sesuatu yang lahir dari hubungan intersubjektif antar aktor (Zehfuss, 2001).Dalam konteks rezim Ore Baru, identitas dari luar tersebut berasal dari negara-negara donor. Sementara pada saat yang sama, negara juga membentuk identitas masyarakatnya dalam rangka menjaga kepentingan negara dan rezim internasional. Otoritarianisme pada dasarnya adalah representasi dari negara yang ingin membentuk identitas masyarakat sebagai unit produksi ketimbang sebagai aktor politik. Konstruksi politik melalui lembaga-lembaga korporatik negara melahirkan identitas politik yang khas pada masa Orde Baru, yang oleh para pengamat politik disebut massa mengambang (floating mass). Massa mengambang sebenarnya adalah massa yang identitasnya dibentuk dari luar – dalam hal ini melalui negara dan agen-agennya seperti militer dan birokrasi. Dengan cara itu, negara mencegah hadirnya identitas lain yang berbasis pada pengalaman dan ideologi politik di luar ideologi yang ada. Secara genealogis, floating mass merepresentasikan cara pandang kekuasaan yang militeristik. Konsep tersebut berasal dari seorang militer-pemikir yang berpengaruh pada masa Orde Baru, Ali Moertopo. Dalam bukunya, Moertopo menyatakan: “…sudah selayaknya bila rakyat, yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan, dialihkan perhatiannya dari masalah politik dan ideologi sempit dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masingmasing. Untuk itu, wajarlah bila kegiatan politik dibatasi sampai daerah tingkat II. Di sinilah letak makna dan tujuan dari proses depolitisasi dan deparpolisasi bagi desa-desa…” (Moertopo, 1972). Ada semacam logika bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa berlangsung dalam situasi politik yang tertib. Pembangunan nasional dipahami dalam konteks tiadanya identitas-identitas 184 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 yang terlalu banyak bersaing, dan jika perlu dilakukan proses penyeragaman. Cara pandang Moertopo kemudian mendorongnya mengkontruksi aktor-aktor yang efisien, yang memudahkan bekerjanya pasar, menjaga harmoni antara pemodal global dan negara sebagai kompratiotnya. Lebih jauh, Moertopo menuliskan secara detail tentang identitas masyarakat yang dianggap cukup parallel dengan tujuan akumulasi modal negara: “……sehingga didapatlah apa yang disebut sebagai “floating mass” yang tidak terikat secara permanen dalam keanggotaan suatu partai politik. Disamping dapat diarahkan kepada usahausaha pembangunan, “floating mass” ini akan merupakan dorongan pula bagi kekuatankekuatan sosial-politik untuk mempersiapkan program pembangunan yang akan ditampilkan dan dinilai dalam pemilihan umum dan golongan yang mempunyai program pembangunan yang menyangkut kepentingan umum akan menang dalam pemilihan umum….” (Dhakidae, 2003: 679-670). Selama kurang lebih tiga dasa warsa, floating mass telah menjadi identitas yang memberi peran negara menjalankan fungsinya sebagai agen rezim kapitalis global waktu itu.Sampai batas tertentu, floating mass menjadi efektif membentuk depolitisasi masyarakat. Namun, dari sisi identitas politik, sebenarnya pola tersebut tidak benar-benar membungkan tumbuhnya identitas lain di luar kehendak negara. Seperti keyakinan kaum konstruktivis, identitas bukanlah sesuatu yang tetap. Identitas akan sangat ditentukan oleh perubahan gagasan dan struktur sosial (Zehfuss, 2001: 12). Massa mengambang dipandang perlu kehadirannya agar potensi resistensi bisa diredam dan tatanan bisa dipelihara. Demokrasi Pasca Orde Baru: Persebaran tanpa Pendalaman Setelah Orde Baru, identitas politik masyarakat yang semua disalurkan melalui lembaga politik yang amat terbatas terbukti kembali menemukan basis primordialnya. Bersamaan dengan tumbuhnya rezim neoliberal, berubah pula konstruksi tentang negara yang dikehendaki oleh struktur internasional.Konstruksi dunia kapitalis tentang agen mengalami perubahan.Jika liberalisme menyukai agen-agen yang represif, rezim neoliberal mencoba mengkonstruksi negara sebagai agen demokratis. Penting untuk ditambahkan bahwa rezim neoliberal juga mulai menggarap secara langsung identitas politik yang mereka harapkan pada level masyarakat domestik.Seperti dikemukakan Ian Bremmer (2011) bahwa rezim neoliberal membutuhkan pemerintahan yang terbuka, efisien, tranparan dan punya akuntabilitas supaya pasar bisa bekerja. Tak mengherankan jika kemudian topik-topik tentang efisiensi, transparansi dan akuntabilitas menjadi wacana kunci rezim neoliberal. Proses demokratisasi yang berlangsung pasca Orde Baru telah memunculkan persebaran namun gagal memperlihatkan pendalaman. Pendalaman negara atas rejim neoliberal memang telah memunculkan demokrasi (liberal) sebagai sistem politik. Namun.watak dan arah demokrasi tersebut berlangsung di tengah negara yang berubah menjadi market apparatus dan dalam fase neoliberal yang bagi konteks negara pasca-kolonial, sedang menjalankan sebuah pola produksi “market make state”. Munculnya proses liberalisasi politik di Indonesia pasca Orde Baru banyak dipuja-puji dunia internasional sebagai sebuah perkembangan yang menonjol dari demokrasi di negara-negara berkembang. Bahkan sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia disebut-sebut sebagai negara muslim yang tingkat demokrasinya paling maju. Lembaga-lembaga internasional segera memberikan fokus bagi penguatan dan pendalaman demokrasi Indonesia. 185 Jurnal The Politics Dalam Konferensi yang diselenggarakan negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD ) atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan di Paris tahun 2005, disepakati “Deklarasi Paris untuk Efektivitas Bantuan”. Deklarasi tersebut mencerminkan perubahan orientasi dan proyek-proyek yang mencoba memperluas dimensi bantuan dari wilayah ekonomi ke non-ekonomi. Kontruski negara pasca Orde Baru oleh rezim neoliberal terlihat dari banyaknya program privatisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Menurut Edward Asprinall, Indonesianis dari Australia National University, orientasi lembaga-lembaga donor internasional mulai mengarah pada agendaagenda “assessing democracy assistance”sebagai upaya membangun harmonisasi demokrasi di level negara dan masyarakat (Asprinall, 2010).Selanjutnya Asprinall mengemukakan uraian menarik tentang kaitan antara program demokrtatisasi Indonesia pasca Orde Baru dengan peran bantuan institusi internasional. Lembaga pemberi bantuan atas program demokrasi di Indonesia datang baik melalui lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF, lembaga pemberi bantuan dari negara-negara besar seperti AUSAID (Australia), USAID (Amerika), NGO internasional dari Eropa seperti Oxfam (Inggris), HIVOS dan NOVIB (Belanda). Disamping itu terdapat pula bantuan yang berafiliasi dengan kekuatan politik di Jerman seperti dari sayap liberal seperti Friederich Naumann Stiftung (FNS) dan dari jalur sosial-demokrat seperti Friedrich Ebert Stiftung (FES). Lembaga Open Society, yang dibentuk pialang saham George Soros, juga merupakan NGO internasional yang menyalurkan bantuan cukup besar untuk program-program LSM demokrasi di Indonesia (Asprinall, ibid). Menurut Aspirinall, Indonesia adalah negara penerima bantuan yang cukup besar dari lembaga internasional bagi proyek-proyek demokrasi. Bantuan-bantuan dari lembaga internasional seperti USAID, Ford Foundation, Asia Foundation dan beberapa bantuan yang berafiliasi dengan partai politik di negara Eropa seperti Jerman, memperlihatkan peningkatan yang amat drastis. Bantuan tersebut baik ditujukan pada civil society organizations (CSO) maupun lembagalembaga baru pemerintah yang dianggap menjadi pilar baru demokrasi seperti KPU, Komnas HAM, DPR (parlemen) dan Mahkamah Agung (Asprinall, ibid). Bahkan Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar dari USAID untuk program demokratisasi. Perhatian atas proses transisi demokrasi di Indonesia tercermin dari strategi besar yang dicanangkan USAID, “Making Democratic Governance Deliver.” Negara-negara dan lembaga donor memberikan perhatian penting pada enam isu penting, yakni: desentralisasi, pengembangan sistem pemilihan umum, komisi pemilihan, kemanan dan lembaga penegakkan hukum, partai politik dan paremen, civil society dan resolusi konflik (Asprinall, ibid). Figura berikut menggambarkan pola hubungan baru antara negara, pasar dan civil society pasca Orde Baru.Konsolidasi modal tetap melalui pintu negara, namun orientasi politik rezim neoliberal telah mengalami perubahan.Terdapat dua pintu pendisiplinan, yakni ekonomi dan politik.Pendisiplinan ekonomi tetap melalui pintu negara seperti tercermin dalam proyek liberalisasi.Tujuan pendisiplinan ekonomi adalah mengkonstruksi negara yang “market friendly” sebagaimana dikemukakan dalam skema Konsensus Washington.Sementara pendisiplinan politik mengambil jalur langsung ke wilayah civil society dalam rangka mengkonstruksi masyarakat yang liberal dan demokratis yang juga mendukung ekonomi pasar. Setelah satu dasawarsa lebih proyek reformasi Indonesia digulirkan sejak kejatuhan Suharto tahun 1998, proses transisi demokrasi berlangsung secara drastis. Semula ada banyak harapan bahwa rezim sipil yang menggantikan Suharto akan membawa perubahan bagi negeri yang secara faktual sangat kaya sumber daya alam ini untuk menjadi pemain utama di level regional dan internasional. 186 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Mozaik politik dalam iklim demokrasi di Indonesia menunjukkan arah yang amat liberal, bahkan menjadi negara paling liberal di dunia.Dalam edisi khususnya tentang perjalanan sepuluh tahun reformasi, Majalah Tempo menurunkan laporan tentang kondisi demokrasi mutakhir. Laporan investigasi majalah terkemuka Indonesia itu membidik kembalinya pemain-pemain lama dalam dunia bisnis dalam ekonomi Yudhoyono, juga aktor-aktor politik lama yang membangun instalasi dan kekuatan politik baru seperti dengan membentuk partai politik maupun bergabung dengan partai politik baru. Gelombang neoliberalisme dan respon Indonesia terhadapnya semakin menunjukkan lemahnya peran negara.Dinamika politik domestik Indonesia pasca Orde Baru memunculkan fragmentasi sosial-politik termasuk dalam gerakan masyarakat sipil (civil society).Negara memang tidak lagi menjadi otoriter sebagaimana dalam fase developmental state Orde Baru, sistem kepartaian tidak lagi hegemonik serta relasi negara dan masyarakat tidak lagi bersifat asimetris. Namun pendalaman atas rejim neoliberal internasional telah mengkontruksi institusi negara sebagai lembaga oligarki yang menjadi arena perebutan institusi neoliberal internasional dengan munculnya aktor-aktor politik dan ekonomi di level domestik (Robison dan Hadiz, 2004). Ketika relasi negara dan rejim neoliberal mengalami pendalaman, politik domestik ditandai dengan hadirnya identitas-identitas politik baru seperti yang dibawa oleh gerakan sosial yang mengusung gagasan radikal.Memanfaatkan ruang politik demokratik, kehadiran kelompokkelompok radikal dari kekuatan politik Islam yang selama Orde Baru bisa dikendalikan oleh negara, mendapatkan artikulasi yang amat bebas.Dalam konflik antar kelompok Ahmadiyah dan kelompok Islam garis keras, misalnya, posisi negara sangat lemah.Tuntutan-tuntutan ekonomi di berbagai daerah yang menuntut keadilan seperti di Papua, gagapnya negara dalam menangani berbagai skandal korupsi dan pajak, merupakan contoh-contoh tentang posisi negara mengambang. Semula, terdapat asumsi-asumsi dari kalangan yang percaya dengan tesis gelombang demokratisasi dari Samuel Huntington. Kaum normatif-liberal juga berasumsi bahwa demokrasi akan melahirkan masyarakat sipil yang kuat dan akan memainkan peran penting dalam fase konsolidasi demokrasi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa asumsi-asumsi tersebut tidak adekuat, setidaknya sampai satu dasawarsa sejak proyek reformasi digulirkan.(Hadiwinata, dalam Bunted dan Uwen, 2006: 276). Gerakan civil society di Indonesia pasca Orde Baru memperlihatkan sebuah pola menarik, dari pahlawan reformasi menjadi pembuat gaduh (trouble makers) demokrasi (ibid, 281). Asumsi-asumsi tentang munculnya kekuatan sipil dalam transisi dan pendalaman demokrasi Indonesia juga mengalami hambatan yang luar biasa ketika kelompok civil society yang hadir tidak sepenuhnya kontributif bagi proses pendalaman demokrasi. Civil society yang hadir dalam konstelasi politik Indonesia pasca Orde Baru menampilkan dirinya dalam dua bentuk, yakni good civil society dan bad civil society. Penutup Posisi negara yang berada dalam hubungan mendalam dengan rezim neoliberal di satu sisi, tumbuhnya gerakan sosial-politik yang bebas dan cenderung liar pada sisi lain, membuat posisi negara di Indonesia pada masa kini semakin mengambang. Sampai kini, tuntutan-tuntutan atas berbagai persoalan seperti penanganan korupsi, hak asasi manusia, otonomi daerah dan berbagai skandal yang melibatkan kebijakan publik terus berlangsung.Sementara negara menjadi aktor yang sibuk menjalankan agenda-agenda yang didesain oleh lembaga-lembaga neoliberal. Beberapa indikator lain pantas diajukan untuk melihat betapa gagalnya demokrasi Indonesia melahirkan pendalaman. Bersamaan dengan diterapkannya demokrasi liberal, berbagai persoalan muncul seperti politik uang, lahirnya dinasti politik di sejumlah daerah, privatisasi partai politik 187 Jurnal The Politics serta aristokrasi wakil rakyat. Semua itu mengindikasikan sebuah demokrasi yang mahal, yang rootless.*** Daftar Pustaka ADB, 2000, Asia Policy Forum, Manila: Asian Development Bank. Bank Dunia, “The State in a Changing World” World Development Report tahun 1997. Bunted an Andreas Ufen, Democratization in Post-Suharto Indonesia, Routledge, London, 2009 Christian Chua, “Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist: Indonesia’s Conglomerates between Authoritarianism and Democracy” dalam Marco Bunted an Andreas Ufen, Democratization in Post-Suharto Indonesia, Routledge, London, 2009. Diamond, Larry; Linz; Juan J; Lipset; Saymor Martin, Democracy and Developing Countries, Asia Lynne Riener Publisher inc., 1989. Dhakidae, Daniel, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, Gramedia Jakarta, 2003 Dieters Evers, Hans, “Bureaucratization of Southeast Asia”, Working Paper No. 71/1985, Sociology of Development Research Centre, University of Bielefeld, 1985, dalam Jurnal Sosiologi, Vol. I, No. 1/1990. Vol.18 No 4, September 1966. Global Justice Update , diterbitkan oleh Institute for Global Justice, Jakarta, volume ke-7, edisi khusus 2009. Hadiwinata, Bob Sugeng, “From ‘Heroes’ to ‘Troublemakers’?: Civil Society and Democratization in Indonesia”, dalam Bunted an Ufen (eds.) Democratization in Post-Suharto Indonesia, Routledge, London, 2009 Henry Wai-chung Yeung,State Intervention and Neoliberalism in the Globalizing World Economy: Lessons from Singapore’s Regionalization Programme,The Pacific Review, Vol. 13 No. 1/2000. Jayasurya, Kanishka “Beyond New Imperialism: State and Transnational Regulatory Governance in East Asia”, dalam Vedi R Hadiz (ed), Empire and Neoliberalism in Asia, Routledge, USA dan Kanada, 2006 Moertopo, Ali Dasar-dasar Pemahaman Tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Yayasan Proklamasi dan CSIS, 1972. Onnis, Ziyya “States, Markets and the Limits of Equitable Growth: The Middle Eastern NICs in Comparative Perspective”. Dalam Atul Kohli, Chung-in-Moon and George Sorensen (eds.), States, Markets and Just Growth: Development in the 21st Century. New York and Tokyo: United Nations University Press, 2003. Robison, Richard, Indonesia: The Rise of Capital, Allen and Unwin, 1986. Robison, Richard dan Vedi R Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market, Routledge, London, 2004. Rueschmeyer, Dietrich dan Theda Skockpol (eds.), Bringing State Back In, Cambridge University Press, 1985, 188 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 TEMPO, majalah berita mingguan ,“Mengapa Pemain Lama Berjaya”?, Edisi 12/18 Mei 2008. UNDP, “Deepening Democracy in Fragmented World”, Human Development Report 2002. UNDP, Indonesia Democracy Index, Project Fact, November 2008 Word Development Report 1997, The State in A Changing World, Bank Dunia dan Oxford University Press, 1997. 189 Jurnal The Politics 190 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik Muh. Kausar Bailusy Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pemahaman Dasar Teoritis Perlu dimaknai dunia kemahasiswaan adalah embrio ilmuan dalam berbagai bidang keilmuan. Bidang yang sedang ditekuni pada saat ini yakni ilmu social dan ilmu politik, sebagai objek mahasiswa sospol yang bergayuh dan terus bergayuh untuk mencapai gelar ilmu social dan ilmu politik. Kondisi formal konstitusional mengakui pemilikan ilmu oleh mahasiswa menjadi sarjana atau disebut ilmuan social politik dan spontan memiliki otoritas ilmuan social politik. Kajian otoritas ilmuan politik yang sedang berinteraksi dalam system politik yang penuh dengan dinamika politik. Pemilihan umum memiliki proses yang rumit dan frekwensi interaksi politik yang cukup tinggi. Oleh karena itu interaksi politik dapat dikatakan sebagai salah satu tanda atau symbol dari dinamika politik. Dalam dinamika politik menggambarkan proses interaksi politik antara supra struktur politik atau lembaga tempat bersemayam para politisi dan penguasa. Infrastruktur politik meruapakan ruang politik warga Negara untuk berinteraksi dengan penguasa yang mempunyai kekuasaan politik, sedangkan warga Negara memiliki kedaulatan politik disebut sebagai mahluk politik. Plato telah memposisikan manusia sebagai mahluk politik (Republik; 2002). Teori politik ini kemudian dikembangkan dilingkungan akademik oleh para akademisi yang konseren dan berkehendak memahami politik sebagai ilmu yang perlu dikembangkan. Pada tahapan ini ilmuan politik perlu memiliki pemahaman secara akademik atau teori 191 Jurnal The Politics politik dan memiliki pemahaman operasional atau partisipasi politik.Disamping itu dibutuhkan kapabilitas ilmuan politik yang tahu dan faham perkembangan ilmu politik yang dirancang dan telah disepakati dan diakui dalam dunia akademik ilmu politik dalam tatanan internasional. Organisasi internasional UNESCO,tahun 1948 mengkontribusi perkembangan ilmu politik dengan menetapkan ruang lingkup ilmu politik dalam 4 bidang induk sebagai berikut; • • • • Teori-teori politik. Lembaga-lembaga politik. Partai-partai, Golongan-golongan dan Pendapat Umum. Hubungan Internasional. [Rodee, Anderson,& Cristol 1967—5- 6 ] Perkembangan ilmu politik jika ditinjau secara luas maka ilmu politik sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek Negara dan kehidupan politik. Perkembangan ini jika disimak pemikiran dan penulisan tentang ilmu politik oleh berbagai ilmuan politik antara lain HEYWOOD ANDREW dalam bukunya POLITICS, mengatakan aspek Negara dan kehidupan politik meliputi; • Politics as the art of government. • Politics as public affairs. • Politics as compromise and consensus. Politics as power and the distribution of resources. [Heywood; 2002 - 5]. Etridge.ME & Handelman.H. dalam bukunya POLITICS IN ACHANGING WORLD…. [.l994 -6] bahwa ilmu politik mencakup; • • • • Politics is the science of who gets what, when and how. Politics is the authoritative allocation of values. Politics is …. the activity by which differing interest within a given unit of rule…… Politics is the processes by which human efforts towards attaining social goals are steered and coordinate. Pemikiran dan pemahaman ilmuan politik yang mencakup berbagai aspek Negara dan kehidupan politik seperti ini secara metodologi menempatkan ilmu politik pada posisi yang dapat dikatakan jauh labih tua umurnya (Miriam Budiardjo 1980-5). Para ilmuan politik menyepakati dan menyebut ilmu politik sebagai ilmu sosial yang tertua didunia. Ilmu politik secara empirik diketahui sebagian besar akademisi yang berkecimpung dalam ilmu sosial dan pada tahapan partisipasi politik atau implementasi teori politik hampir semua akadamisi ilmu-ilmu non sosial juga memiliki kemampuan berpikir politik, berpendapat politik berargumen politik,tapi kurang memiliki pemahaman dasar ilmu politik dan metodologi ilmu politik. Asumsi penulis ini didasarkan pada fenomena politik yang berkembang secara pesat dalam proses reformasi politik, antara lain pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum anggota legislative dan berkesinambungan dengan pemilihan umum Presiden-wakil Presiden yang sedang berproses. Ilmuan sosial dan ilmuan politik pada tahap mengarungi dunia empirik dan dunia partisipasi politik yang berkembang pesat, mereka mengalami kendala psikologis dalam implementasi politik. Sebagian ilmuan politik kurang mampu mengembangkan ilmu politik yang pernah diraih pada pendidikan strata satu strata pendidikan magister of arts dan Doctor atau program S3. Tingkat keberhasilan dalam mencapai gelar magister ilmu politik dan doctor ilmu politik sangat pesat. Sehingga waktu yang tidak begitu lama ilmuan politik dengan gelar magister dan doctor di Indonesia menjadi semarak dan dapat dikatakan cukup signifikan. Namun dikalangan sebagian ilmuan politik kurang memiliki kapabilitas daya saing politik, kurang mampu menerapkan teori 192 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 politik yang diperoleh pada saat kuliah dengan fenomena politik yang sedang dihadapi. Dalam pergulatan dunia empirik partisipasi politik ilmuan politik diharapkan menguasai bidang keilmuan secara komprehensif untuk bangkit dan berkewajiban mengembangkan tafsir politik atau mengemukanan konfigurasi politik dalam dunia empirik. Tafsir politik para ilmuan terbangun oleh proses lingkaran dialogis secara interogatif dalam dunia internal ilmuan sosial politik. Pada tatanan ini faktor pengalaman dan pemahaman perkembangan sejarah politik sangat mengkonstruksi proses tafsir politik setiap ilmuan politik. Menurut Ricouer; menafsir merupakan masalah ”Creative Imagination of the possible”[Tafsir politik; Geertz- xix]. . Pada tatanan akademik, ilmuan politik, elite politik, aktor politik dalam melakukan penafsiran politik harus memiliki kemampuan imajinasi untuk melihat hal-hal yang tersirat dari yang tersurat tentang aneka ragam fenomena politik, partisipasi politik dan kepentingan politik. Ilmuan politik yang memiliki kemampuan, elite politik yang rasional, aktor politik yang rasional, kemungkinan mampu menangkap fenomena politik dalam dunia makna perpolitikan kemudian berupaya memahami realitas politik dan kepentingan politik warga Negara sebagai partisipan politik. Tindakan perpolitikan yang dilakukan oleh ilmuan politik, elite politik, dan aktor politik seperti disebut terdahulu merupakan tindakan politik seorang negarawan. Perspektif politik dinegara maju dominant mengunggulkan konfigurasi teori politik dan diperjelas dengan politik partisipasi atau pragmatisme politik. Tingkat kelurusan dan kejujuran ilmuan politik dan partisipasi politik selalu menjaga keseimbangan teori politik dengan partisipasi politik atau pragmatisme politik. Pada tingkat transfigurasi teori politik oleh ilmuan politik diupayakan meminimalisir tingkat penyimpangan partisipasi politik sampai pada taraf penyimpangan yang semakin kecil menjadi semakin kecil dan bukan tidak ada penyimpangan partisipasi politik atau pragmatisme politik. Para ilmuan politik yang memiliki otoritas politik berkewajiban moral untuk membangun cara berpikir politisi sebagai partisipan politik. Dinegara maju partisipan politik atau kaum pragmatisme politik dibina dan dibimbing oleh Partai Politik dalam sistem manajemen partai politik yang rasional untuk memberi otoritas politik kepada politisi. Oleh karena itu pemimpin partai politik harus berupaya memanfaatkan ilmuan politik yang telah memiliki otoritas politik untuk membangun sumberdaya partai politik dengan menata cara berpikir politik para calon politisi dan partisipan politik. Para filosof berpendapat bahwa manusia bukan hanya ada, tetapi mengerti adanya, karena itu dalam perbuatannya, dialah yang menggerakkan dirinya sendiri (Driya Kara 2006). Secara filosofi para politisi wajib berpikir. Berpikir adalah tindakan yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan fenomena politik dan membuat keputusan politik [UU, PERDA, KEPRES INPRES BANPRES] yang dominant mengkontribusi kepentingan orang banyak atau public. Posisi manusia yang memiliki otoritas akademik, atau otoritas ilmuan politik berkewajiban moral memiliki akal budi, mengetahui kepentingan masyarakat, memahami kepentingan masyarakat, sehingga memposisikan seorang akademisi, atau ilmuan politik yang mampu memahami dirinya. Fenomena teori politik seperti ini perlu dibangun dikalangan politisi dan pragmatisme politik sebagai bekal politik dalam bertindak dan berbuat untuk kepentingan rakyat. Landasannya, berpikir rasional dalam berpolitik, tanpa berpikir rasional para politisi cenderung menjadi hewan predator, atau pemangsa suara rakyat yang telah terjadi pada pemilu kepala daerah dan pemilu anggota legislatif yang baru berakhir, dengan ditetapkan anggota legislatif terpilih pada tingkat lokal dan tingkat nasional. Pada PILPRES yang akan datang politisi yang berprilaku predator suara rakyat semoga makin berkurang. 193 Jurnal The Politics Ilmuan Politik , Aktor Politik Dalam Arena Sistem Politik Perpolitikan dalam system politik demokrasi, system politik otoriter, ulah para elit politik, aktor politik selalu merepotkan para ilmuan politik dalam mencerna system politik yang sedang berlangsung. Ulah para elit politik, aktor politik terhadap aturan system politik terutama yang berhubungan dengan partisipan dan pragmatime politik. System politik demokrasi telah menata alur cara berpikir politik atas dasar otoritas politik yang terbangun dalam struktur system politik. Setiap struktur politik pasti mempunyai fungsi politik. Robbert K.Merton berpendapat bahwa; fungsi adalah akibat yang tampak, yang ditujukan bagi kepentingan adaptasi dan penyetelan (adjustment) dari suatu system tertentu dan dys-function adalah akibat-akibat yang tampak, yang mengurangi daya adaptasi dan penyetelan (ajusment) dari suatu system (S.P.Varma 198769). Gabriel Almond yang berkonsentrasi bidang perbandingan politik berpendapat bahwa fungsi politik selalu berada dalam struktur politik (SP.Varma 1987-97).Pandangan para ahli ini oleh elit politik ,aktor politik kemungkinan belum mengetahuinya atau belum pernah dibaca, oleh sebab itu dalam partisipasi politik sebagai pragmatisme politik selalu membangun masalah politik. Perlu dipahami pada tatanan tertentu para ilmuan politik harus memiliki kecenderungan pragmatisme politik yang tinggi dalam membangun penyelesaian masalah politik. Tingkat kecenderungan ilmuan politik dalam memahami fenomena politik selalu menggunakan pendekatan system. Salah satu bagian dari system yang bersifat dinamik yaitu fungsi politik dari struktur politik. Hal ini memperlihatkan tingkat konsistensi dari ilmuan politik dalam memahami dinamika politik yang dinamis dan kontraproduksi dalam menafsir system politik, Kondisi Indonesia menunjukkan hanya sebgian kecil ilmuan politik yang memiliki cara berfikir yang konsisten pada pendekatan system politik. Ricoeur berpendapat bahwa menafsir adalah soal creative imagination of the possible, semua imajinasi yang mampu melihat yang tersirat dibalik yang tersurat, dan mampu menangkap dunia makna (T.Gibbons XIX – 2002). Dalam sistem politik , dunia makna beda dalam struktur politik yang memiliki fungsi politik. Fungsi politik ini oleh ilmuan politik perlu dikritisi dan bersikap kritis terhadap setiap fungsi politik yang dinamik dalam masyarakat. Dalam sistem politik demokrasi penafsiran ilmuan politik yang bernilai apabila penafsiran itu selalu mengandung kebutuhan masyarakat. Crossan & Taylor (Gibbons.T;xixxx—2002), berpendapat bahwa penafsiran yang bernilai sering justru bersifat dekunstruktif, yang kuasa membongkar topeng-topeng gagasan manusia dan membuat manusia penasaran dan berjuang terus mencari dunia makna dalam sistem perpolitikan demokrasi dan sistem perpolitikan otoriter. Dunia makna bagi ilmuan politik digunakan untuk menafsir dinamika politik dalam system politik. Hakekat menafsir harus bersikap kritis setiap saat terhadap mekanisme system politik. Namun perlu disadari bahwa aktor politik dalam system politik selalu melakukan kegiatan politik untuk memperoleh nilai-nilai politik. Tafsir politik merupakan proses lingkaran dialogis interogatif (Hermeneutic circle). Sasaran menafsir yaitu subject matternya yakni kebenaran tentang kehidupan politik para aktor dalam system politik ( Gibbons.T XIX – 2002). Para ilmuan politik dalam tatanan system politik berupaya untuk menjaga kebenaran politik antara fungsi dan struktur. Namun mekanisme sistem politik yang sudah menjadi format politik selalu ditafsir oleh para elit politik dan aktor politik secara berbeda dan menurut kepentingan elit politik dan aktor politik. Dalam system politik demokrasi, para elit politik, aktor politik dapat dikategorikan secara parsial, yakni aktor politik individual, aktor politik kelompok atau aktor politik organisasi Negara. Teori politik secara aktual mengaktegorikan aktor politik dalam tiga kategori. Menurut Marian D.Irish & Elke Frank, aktor politik yaitu Gladiator, Transisional, dan Spektator (Ala Andre; 92- 1985), dengan menghuni tingkat kekuasaan dan kesalahan dalam 194 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 melakukan analisis politik, dan terutama dalam hal transfigurasi politik. Transfigurasi aktor politik terhadap proses ssstem politik selalu didasarkan pemilikan diri atas ilmu politik atau kemampuan memahami teori politik dalam -sistem politik. Tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas politik atau kegiatan- politik, baik kegiatan politik legal-lunak, maupun kegiatan politik illegal-keras selalu didasarkan tingkat transfigurasi politik yang ditafsir oleh aktor politik terhadap system politik (Robert Dahl : 83-1985). Individu – individu dalam system politik tentunya memperhatikan system politik dan kehidupan politik. Beberapa orang acuh pada politik ada individu yang aktif memperhatikan system politik, bahkan ada beberapa orang yang sangat aktif dalam mengamati kehidupan politik. Pada sisi lain ada beberapa orang berusaha mencari kekuasaan secara aktif. Diantara para pencari kekuasaan ini ada yang memperoleh kekauasaan lebih banyak dari pada individual lain. Para calon anggota legislatif lokal dan calon anggota legislatif nasional sebagai pencari kekuasaan (pemilu legislatif 2009). Diantara para aktor ini sebagian besar sangat kurang memahami kekuasaan yang dicari dalam tatanan sistem politik. Transfigurasi politik elit partai politik membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Tranfigurasi elit partai politik memiliki keutamaan citra politik predator terhadap CALEG yang wajib membayar ke Partai politik. Partai politik peserta PEMILU legislatif dominant memiliki citra politik predator, dan berupaya melupakan citra politik demokrasi yang bermoral dan etis yang sudah tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. CALEG tidak dimenej secara profesional oleh mesin partai politik yang diharuskan oleh AD&ART. Transfigurasi politik yang terbangun dalam elit partai yang oligarkhis berorientasi pada pendapatan (uang pendaftaran CALEG.). Sedangkan transfigurasi politik yang terbangun dalam diri CALEG (aktor politik baru), yakni yang terpenting terdaftar oleh partai politik sebagai CALEG untuk bertarung dalam pemilu legislatif dan mendapat kursi kekuasaan. Kondisi manajemen partai politik seperti ini, muncul keraguan terhadap CALEG terpilih yang dicalonkan oleh partai politik, dan jika mereka terpilih mampukah mereka mengoperasionalkan fungsi lembaga legislatif daerah. Secara nasional CALEG yang telah dicalonkan oleh partai politik disetiap daerah untuk merebut kursi disetiap Legislatif daerah, perbandingannya satu kursi harus direbut oleh pencari kekuasaan CALEG dengan sebaran 24 – 28 CALEG BARU. (KPUD-PILEG 2009). Fenomena politik calon anggota legislatif hanya berusaha untuk dicalonkan oleh partai politik menjadi calon anggota legislatif, peluang untuk terpilih dan tidak terpilih kurang dipikirkan. Menurut teori politik yakni sistem perwakilan politik, partai politik berkewajiban dan penanggung jawab terhadap sistem politik demokrasi. Pada PEMILU Presiden bulan juli yang akan datang partai politik perlu membangun transfigurasi politik yang memiliki moral politik dan etika politik. Kondisi ini perlu dibangun agar elit politik partai politik dan aktor politik yang menjadi tim sukses memiliki moral politik dan etika poltik dalam proses mensukseskan calon presiden calon wakil presiden yang dipromosikan. Para aktor politik yang kurang basis pengetahuan politik kebanyakan mereka tergelincir dalam arena transfigurasi politik. Namun sebagai aktor politik yang merasa memiliki otoritas politik sebagai aktor politik yang dilahirkan oleh lembaga politik, atau partai politik selalu percaya diri, walaupun banyak melakukan penyimpangan tafsir politik dalam partisipasi politik. Konfigurasi politik yang dikemukakan dalam menafsir politik terhadap dinamika system politik selalu dianggap benar. Kondisi dan wacana politik seperti PEMILU Kepala Desa, PEMILU Kepala Daerah, PEMILU Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD dan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli 2009 yang akan datang. Aktor politik yang kalah dalam mencari kekuasaan membuat tafsir politik terhadap mekanisme PEMILU dinyatakan tidak fair atau pelaksana PEMILU yakni KPU dan KPUD curang. Transfigurasi politik aktor politik baru seperti ini, jika dinilai secara akademik dan 195 Jurnal The Politics landasan konstitusional PEMILU, maka dapat dikatakan aktor politik masih sangat minim memiliki pemahaman teori politik tentang sistem politik sehingga menghasilkan dasar alasannya yang sangat lemah. Aktor politik pencari kekuasaan secara psikologi menginterpretasi diri sebagai aktor politik yang merasa dan menganggap memiliki kemampuan politik secara akademik untuk memperoleh kekuasaan yang dicari. Pada sisi lain aktor politik mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa dia dapat memenangkan pertarungan kekuasaan, menentukan kekuasaan dan nilai-nilai politik dan symbol-simbol politik bagi dirinya. Para aktor politik secara individual mengandalkan cara berpikir politik menurut interpretasinya, sedangkan basis ilmu politik dan teori politik yang difahami masih kurang. Oleh sebab itu setiap kebijaksanaan atau aturan main dalam partisipasi politik selalu menjadi arena transfigurasi politik menurut asumsi aktor politik. Tingkat arogansi politik yang dilakukan aktor politik dominant didasarkan pada posisi, dan bukan pemilikan pengetahuan politik dan ilmu politik. Menurut Dahrendhorf metode posisi merupakan unsur kunci, setiap posisi pasti memiliki otoritas, karena otoritas selalu melekat pada posisi.(Ritzer & Goddman;2003 -155). Welsh mengatakan bahwa pemimpin pemerintahan adalah aktor-aktor politik otoritatif.Aspek otoritas adalah salah satu karakteristik penting dari kepemimpinan.(Ala Andre;A1985; 55). Aktor politik dalam berbagai kajian ilmu politik selalu dipisahkan dengan istilah elit politik. Robert Dahl, Ithel Pool,Charles R Nixon, Dwaine Mervick, Alfred de Grazia menggunakan istilah Aktor politik. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system pembuatan keputusan dalam organisasi politik dan organisasi Negara. Para ahli politik yang menggunakan istilah elit politik antara lain,; Aristoteles, Karl W Deutch, Davis F Roth, Frank L Wilson, Suzanna Keller,. Elite politik berkewajiban menguasai lalulintas arus pesan politik dan aliran komunikasi politik. Dalam system politik Indonesia secara empirik praktisi dan pimpinan partai politik menggunakan kedua istilah secara bergantian menurut keenakan dalam berpidato. Bagi pimpinan partai sampai para mentri ,Presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati dan para anggota dewan sangat rendah memiliki alat kontrol dalam menempatkan istilah elit politik dan aktor politik. Fenomena tersebut merupakan kesalahan tradisional dalam berbentuk kesalahan berjamaak. Dalam mengendalikan sistem politik terdapat sejumlah 1000 sampai 1500 elit politik naisonal yang memiliki otoritas politik nasional yang setiap hari membuat keputusan bagi dua ratus jutaan rakyat Indonesia. Pemerintahan lokal Sulawesi Selatan dalam system politik lokal memiliki 100 sampai 150 elite politik lokal yang memiliki otoritas politik yang setiap saat dapat membuat keputusan politik lokal sebagai perwujudan desentralisasi – era otonomi yang dominant berupaya melayani kepentingan delapan juta sampai 9 juta penduduk Sulawesi Selatan. Dalam arena transfigurasi politik PEMILU kepala daerah, para elite politik yang menempati posisi pengambilan keputusan politik sering berulah tanpa dasar alasan yang konstitusional menolak keptutusan politik yang sudah ditetapkan oleh KPUD. Fenomena KPUD dalam perpolitikan lokal menempati posisi yang amat rawan. Jastifikasi KPUD untuk pembenahan keputusan atau menetapkan keputusan masih lemah. Para elite politik memiliki posisi politik, dan sangat rendah pengetahuan bidang politik. Elite politik seperti ini sangat sulit dikategorikan sebagai elit politik. Pemahaman elite politik oleh Ithel Pool dan kawan-kawan berupaya untuk mengkategorikan actor politik/aktivis politik yang dibedakan dengan elit politik dengan enam criteria sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Sudah menjadi anggota satu organisasi politik Memberi uang pada satu organisasi politik atau calon Sering menghadiri rapat-rapat politik Ikut ambil bagian dalam kampanye Menulis surat mengenai topik-topik politik kepada legislator, pejabat politik atau pers 196 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 6. Membicarakan masalah politik dengan orang lain Para elit politik ini menyebar pada organisasi politik tingkat nasional dan lokal. System politik Indonesia yang menerapkan system PEMILU kepala daerah oleh pemilih membuat aktivitas politik para elite politik menjadi dinamis tanpa kendali. Setiap PEMILU kepala daerah mulai dari penetapan daftar pemilih, hari pemilih, perhitungan hasil pencoblosan dan pencontrengan dan penetapan hasil pemilu oleh KPUD selalu depermasalahkan oleh elit politik lokal sampai elite politik nasional. Elite politik ini dalam berpartisipasi politik dominant pada kegiatan spectator namun sering para elit politik ini berada pada kegiatan politik gladiator. Tingkat pemahaman elite politik terhadap mekanisme konstitusional system PEMILU sangat rendah, selalu berupaya untuk tidak boleh kalah memperoleh suara dalam PEMILU kepala daerah. Apabila elite politik yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah atau pasangan calon presiden mengalami kekalahan maka, konfigurasi politik dari elite politik untuk melakukan penafsiran atau tafsir politik, terhadap proses PEMILU oleh KPU yang curang. Tafsir politik oleh elit politik dominan tidak berlandaskan mekanisme PEMILU yang digunakan. Para elite politik ini memiliki kecenderungan untuk mengabaikan aturan PEMILU semakin tinggi, yang diprioritas oleh para elit politik yakni mencari kekuasaan dan harus memperoleh kekuasaan. Penulis berpendapat bahwa sistem politik era reformasi para elite politik dan actor politik melebur dalam satu lembaga baru dengan istilah tim sukses dalam system PEMILU di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh warga negara kepada calon pasangan kepala daerah yang telah ditetapkan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 56 – pasal 119 dan didukung secara konstitusional oleh UU No.22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Para elite politik atau tim sukses sangat minim memahami kedua UU ini dalam partisipasi politik. Akibatnya tindakan-tindakan politik para elite politik atau tim sukses selalu berhayal dan berangan dan membangun tafsir politik yang berlandaskan keinginan berpolitik elite politik/tim sukses atau keinginan untuk harus menang pasangan calon yang didukung. Pasangan calon kepala daerah sebagai elit politik tertinggi tingkat lokal sudah bersedia menerima hasil perhitungan suara oleh KPUD, tapi elit politik, aktor politik/tim sukses pendukung pasangan calon kepala daerah, berupaya membangun transfigurasi politik untuk menolak hasil pemilu kepala daerah. Kondisi politik dan fenomena politik seperti ini terjadi disemua daerah di Indonesia yang pernah melakukan PEMILU kepala daerah, walaupun intensitas dan frekuensi protes elite politik, aktor politik yang tergabung dalam tim sukses terhadap perhitungan suara oleh KPUD secara berbeda-beda. Pada tatanan tertentu para aktor politik sering mengucapkan slogan pada PEMILU kepala daerah yaitu “Tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi”. Transfigurasi politik seperti ini akan merusak cara berpikir warga Negara dan masyarakat Indonesia. Dalama ilmu politik secara teori politik tidak dikenal dengan istilah seperti itu. Para elite politik ,aktor politik yang tergabung dalam tim sukses sering membuat pernyataan politik yang tidak memiliki nuansa akademik dan tidak berlandasakan pada teori politik yang ada dalam system politik. Tim sukses yang hanya memahami fenomena politik secara parsial dan kemudian membuat tafsir politik sesuai kapabilitas yang dimiliki, akibatnya sangat fatal karena dasar pengetahuan politik secara komprehansif sangat rendah. Fenomena tim sukses yang dominan menyimpang dengan tafsir politik parsial, sangat berpengaruh dalam sosialisasi politik dan proses membangun dan mempertahankan system politik demokrasi. Kondisi politik seperti ini menjadi tanggung jawab moral politik oleh ilmuan politik untuk memperbaiki melalui sosialisasi politik, seperti media surat kabar, televisi dan radio. Pada sisi lain ilmuan politik perlu membangun pendidikan politik yang diperuntukan kepada elite politik partai , para calon elite 197 Jurnal The Politics politik dan tim sukses untuk membenahi dan mengurangi tingkat kesalahan pada saat tafsir politik dan membangun transfigurasi politik. Kontribusi Ilmuan Sosial Politik Dalam Pemilu Demokratis Sistem politik demokrasi secara pragmatis membuka ruang bagi ilmuan politik untuk berhadapan dengan pimpinan partai politik yang cenderung oligarkhis yang menguasai partai politik penanggung jawab system politik demokratis. Partai politik secara fungsional memiliki fungsi-fungsi politik yang menentukan bangunan lembaga politik yang demokratis. Secara manajerial partai politik berkewajiaban menata elit politik dan aktor politik untuk menjadi pelaku politik. Gabriel Almond secara gamblang mengemukanan fungsi-fungsi politik dalam system politik. Kemudian fungsi system politik ini oleh Almond sebagian dijadikan fungsi partai politik antara lain ? Parpol sebagai sarana sosialisasi politik dan rekruitmen politik Parpol sebagai sarana komunikasi politik Parpol sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan Parpol sebagai sarana pembuatan kebijakan Parpol sebagai sarana konflik (Shilcote, 2003-222) PEMILU demokrasi membutuhkan partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sarana komunikasi politik dan sarana recruitment politik. Dari sudut manajemen politik, partai politik di Indonesia memiliki kelemahan pada tingkat manajemen partai politik untuk mengaktualisasikan fungsi-fungasi politik. Pada era orde baru partai politik sebagai sarana sosialisasi politik tidak mampu diterapkan oleh kaum oligarkhis partai politik. Partai politik diatur secara sentralistik dan berkewajiban memiliki ideology partai seragam dengan ideology organisasi Negara. Yaitu pancasila atau dikenal dengan azas tunggal pancasila. Kondisi ini membuat partai politik (PPP & PDI) tidak berdaya dalam hal sosialisasi politik pada masyarakat pemilih. Sosialisasi politik oleh partai politik harus seiring dengan keinginan penguasa. System sentralistik era orde baru fungsi partai politik harus sesuai keinginan penguasa. Fungsi sosialisasi Partai Politik sebagai sarana untuk menjaga dan mengatur dinamika politik harus sesuai dengan dinamika politik penguasa Orde baru. Ilmuan politik pun terkekang oleh penguasa Orde Baru .Pada era reformasi dengan trend membangun demokrasi, berlangsung sangat cepat. Sosialisasi politik berlangsung tanpa kendali. Partai politik tumbuh menurut kepentingan dan keinginan warga Negara. Sosialisasi parpol dominan pada upaya mencari kekuasaan. Pada tingkat komunikasi politik, para elite partai politik memanfaatkan sistim demokrasi dengan cara membangun tafsir politik yang cenderung mengabaikan konstitusi. Konfigurasi otoritas aktor politik dan elit politik dijadikan alat kekuasaan untuk memaksakan kehendak. Para elit partai politik dan aktor politik mampu bekerja sama untuk merekruit siapa saja atau warga Negara yang berkeinginan kuat untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatife pada tingkat lokal, maupun nasional, partai politik mengajukan syarat utama yaitu kemampuan calon membayar uang pendaftaran untuk dijadikan calon anggota legislatife oleh partai politik. Sedangkan persyaratan lain seperti lama menjadi anggota partai politik yang tidak dijadikan syarat yang permanent. Kemudian syarat lain yang oleh elite partai politik dianggap sebagai sayarat assesori yang tidak dijadikan tolok ukur oleh partai politik dalam menetapkan calon seperti: •Pernah mengikuti pengkaderan dan sosialisasi anggota parpol •Pernah menjadi pengurus parpol •Tingkat pemahaman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol 198 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Persyaratan ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk seleksi calon anggota legislatif yang diajukan partai politik. Kondisi dan system manajemen partai politik dalam merekruit anggota legislatif tanpa memiliki persyaratan yang rasional, pemahaman dan kapabilitas sebagai elit partai politik dan aktor politik akan membawa dampak yang cukup serius sebagai calon anggota legislatif terpilih tapi, tidak memahami para political system atau sistem partai politik yang harus dinamik dalam manajemen partai politik, dalam sisitem politik lokal dan sistem politik nasional. Sebagai ilmuan sosial politik sangat pesimis dengan sejumlah calon anggota legislatif yang direkruit oleh partai politik tanpa syarat pemahaman parpol dalam system politik. Konstribusi ilmuan politik sangat dibatasi oleh otoritas dan oligarkhis pimpinan parpol dalam menjaring calon anggota legislatif pada tingkat lokal dan nasional. Para ilmuan politik yang sudah direkomendasi oleh pimpinan partai politik sebagai penasehat politik PARPOL hanya dijadikan hiasan struktur partai politik. Pada pemilu legislatif 9 april 2009 ilmuan politik tidak dilibatkan dalam proses rekruitmen politik anggota masyarakat dan anggota partai untuk dijadikan calon anggota legislatif. Secara nasional calon anggota legislatif lokal yang diajukan oleh pimpinan partai politik yang memiliki otoritas, dominant tidak di kunsultasikan dengan penasehat PARPOL atau kuonsultan partai politik, sehingga calon yang diajukan oleh partai politik sangat minim memiliki kapabilitas sebagai calon anggota dewan. Calon anggota dewan seperti ini oleh penulis disebut calon anggota legislatif TOMANURUNG. Calon anggota dewan seperti ini hanya memiliki persyaratan tunggal yaitu membayar uang pendaftaran kepada pimpinan partai politik yang memiliki otoritas dan perilaku oligarkhis dalam proses rekruitmen calon anggota legislatif. Komunikasi politik yang dibangun oleh pimpinan parpol era reformasi selalu berlandaskan komunikasi politik oligarkis. Pimpinan partai dengan otoritas politik memposisikan diri sebagai sumber informasi dalam komunikasi partai politik dengan warga negara pengguna partai politik berlangsung satu arah. Dialogis sulit terbangun, keinginan dan kepentingan pimpinan parpol dijadikan sumber informasi utama yang sulit diabaikan. Anggota masyarakat pengguna secara terpaksa berkewajiban menerima komunikasi politik satu arah. Era reformasi masukan-masukan dari rakyat berupa informasi politik dalam bentuk artikulasi kepentingan masyarakat pengguna partai politik, kebutuhan politik warga Negara untuk menjadi caleg, calon bupati, walikota dan jabatan politik lain perlu diakomodir oleh partai politik secara langsung atau perwakilan partai politik (fraksi) dilegislatif. System demokrasi yang dibangun di Indonesia era reformasi dominan berlaku pada saat otoritas eksekutif dan otoritas anggota legislatif dalam membahas rancangan PERDA atau rancangan UU, namun kebanyakan terjadi rancangan PERDA dan rancangan UU memiliki isi atau eksistensi jauh dari kepentingan rakyat. Hal seperti ini terjadi karena anggota partai politik yang menempati posisi anggota legislatif sangat kurang dan dapat dikatakan tidak membangun komunkasi politik dengan masyarakat pemilih atau warga Negara untuk memperoleh masukan. Ilmuan politik telah membangun wacana dalam berbagai media bahwa komunikasi politik merupakan faktor yang sangat penting bagi anggota legislatif dalam proses membuat keputusan politik. Anggota legislatif membutuhkan informasi dari masyarakat sebagai bahan materil yang menjadi pertimbangan fraksi-fraksi legislatif / anggota legislatif dalam menetapkan keputusan, sehingga keputusan yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Komunikasi politik masih terus berlangsung setelah keputusan politik ditetapkan. Pada tahap implementasi kebijakan, dibutuhkan komunikasi politik yang intensif antra pemerintah dan masyarakat. 199 Jurnal The Politics Pencerahan Perpolitikan Sistem Politik Secara teori politik; lembaga perwakilan politik seperti presiden, gubernur, bupati, walikota termasuk para wakil partai yang didukung oleh warga Negara dalam pemilu harus membangun sistem implementasi kebijakan yang memihak pada masyarakat. Eksekutif sebagai implementator kebijakan berkewajiban melakukan komunikasi politik dengan masyarakat pemilih atas penerapan kebijakan. Kegiatan-kegiatan politik implementasi kebijakan oleh pemerintahan, masyarakat dapat memberi penilaian, atau tanggapan terhadap pelaksanaan kegitan politik oleh pemerintah, apakah implementasi kebijakan mencapai sasaran dengan baik atau tidak, dan dalam implementasi kebijakan terjadi hal-hal yang menyimpang seperti terjadi penyelewengan otoritas, penyalahgunaan otoritas maka kewajiban masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Informasi dari masyarakat yang terkena kebijakan sangat penting untuk konsumsi pemerintah dalam membangun komunikasi politik yang rasional fungsional. Dalam teori system politik hal seperti ini harus dijadikan umpanbalik (feed back) yang sangat penting terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses pelaksanaan atau implemntasi kebijakan. Teori politik mengharuskan hubungan otoritas pemerintah dan rakyat pemilih kedaulatan harus berlangsung timbal-balik yang seimbang. Teori politik balance of power dalam sistem politik menghendaki tingkat keseimbangan yang akurat dan rasional antara legislatif-eksekutif dengan rakyat pemilik kedaulatan untuk menata keseimbangan politik dalam menggunakan kekuasaan, maka legislatif dan eksekutif harus mampu membangun komunikasi politik yang rasional. Komunikasi politik yang rasional ini dimulai pada saat legislatif dan eksekutif melakukan perumusan kebijakan bersama masyarakat dalam wadah MUSREMBANG. Artikulasi kepentingan masyarakat wajib direkruit oleh eksekutif dan legislatif dan ditetapkan sebagai kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan masyarakat menerima berarti komunikasi politik pada saat perumusan kebijakan berlangsung baik. Kondisi ini menggambarkan hubungan otoritas eksekutif dengan legislatif berlangsung terpadu dan kedua lembaga berkeinginan kuat untuk mengurangi dan meminimalkan masalah masyarakat. Pada tatanan ini komunikasi politik berlangsung baik dan bernuansa membangun mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi pasti terbangun tatanan sistem pemilihan umum demokrasi. Jika sistem pemilihan umum demokrasi ini tetap dikawal oleh ilmuan politik bersama elit partai politik maka kemungkinan besar hasil pemilihan umum akan menghasilkan elit politik dan aktor politik yang menjadi anggota dewan dan eksekutif yang bermoral demokrat dan membuat keputusan yang dominan melayani kepentingkan rakyat. Makin tinggi keputusan legislatif – eksekutif melayani masyarakat semakin tinggi nilai demokrasi. Kesimpulan Sebagai mahasiswa baru yang diterima dalam bidang sosial dan politik harus memfokuskan cara berpikir untuk cerdas dan meraih kemenangan dalam menuntut ilmu sosial dan politik. Kondisi sekarang para sarjana atau ilmuan sosial politik sangat dibutuhkan seiring dengan dinamika sistem politik. Oleh sebab itu pada saat sekarang sebagai mahasiswa baru sosial politik harus mampu memahami demonstrasi secara akademik dan bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas dalam berdemonstrasi. Demonstrasi secara akademik dilarang merusak, membakar, tapi membangun ide sebagai kontribusi pada pemerintah. Pada saat itulah titian embrio imluan sosial politik terbangun dalam diri mahasiswa sebagai calon ilmuan yang rasional dan objektif. Selamat berjuang untuk membangun dunia keilmuan yang cerdas. 200 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 DAFTAR PUSTAKA Ala, Andre Bayo. Hakekat Politik : Siapa Melakukan Apa, Untuk Memperoleh Apa. Yogyakarta: Akademika. 1985. Alfian. Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia. 1991. Anderson, Rodees Chirstol. Instroduction To Political Science. Tokyo: Mc Graw-Hil Kogakush. Ltd. 1967. Asnawi Sahlan. Kepemimpinan Dan Kepengikutan Dalam Locus Politik Indonesia. Jakarta: Studia Press. 2001. Bailusy Kausar. Teori Politik. Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka, Cetakan Ketiga. 2001. Brym Robert. Intelektual Dan Politik. Jakarta: Grafiti. 1993. Budiardjo, Miriam. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan. 1986. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia 2008. Chilcote Ronald H. Teori Perbandingan Politik. Jakarta: Grafindo. 2003. Diantha Imade Pasek. Tiga Tipe POkok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Moderen. Bandung: Abardin. 1990. Dragnich Alex N Etl. Politics And Government. New Jersey: Chatam House Publishers, Inc. 1982. Dwiyanto Agus. Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM. 2003. Ethridge, Marcus E, & Howard Handelman. Politics In A Changing World. New York: St. Martin Press, Inc. 1994. Firmansyah. Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positiniong Ideologi politik Di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008. Frisch Morthon J. American Political Thought. USA: Pedroc Publishers. 1976. Gibbons Michael T. Tafsir Politik: Interpretasi Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer. Yogyakarta: CV.Qalam. 2002. Hatta Mohammad. Alam Pemikiran Yunani. Jakarta: Tinta Mas. 1983. Heywood, Andrew. Politics. New York: Published By Palgrave. 2002. Hidayat Syarif. Too Much Too Sun: Local State Elite’s Perspective On And The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy. Jakarta: Raja Grafindo. 2007. Hooser Kenneth R. Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah Dalam Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1989. Jacobsen, G A & Lipman. Political Science. New York: Barnes And Noble, Inc. 1967. Keller Suzanne. Penguasa Dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Moderen. Jakarta: Rajawali. 1984. Lacroix Bernard. Sosiologi Politik Durkheim. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005. Lipset Seymour Martin. Political Man: Basis Sosial Tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007. 201 Jurnal The Politics Losco Yoseph & Leonardo Williams. Political Theory. Jakarta: Grafindo. 2005. Mayer Lawrance C. Comparative Political Inquiry. Illinois: The Dorsey Press. 1972. Mitau. State And Local Government: Politics And Processes. IOWA-USA: The New York Times Company. 1964. Michels Robert. Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi. Jakarta: Rajawali. 1984. Plato. The Republic. New York: Quality Paper Book Club. 1992. Popper Karl R. Epistemologi Pemerintahan Masalah. Jakarta: Gramedia. 1991. 202 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 The Factors Influencing Young Voters In Determining The Choice Case Study: Local Election In Bengkulu Andi Azhar, Susyanto Department of Management, Faculty of Economic, University of Muhammadiyah Bengkulu, [email protected] Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Bengkulu, [email protected] Abstract The aim of this study was to create an explanatory model that allows analyzing the factors influencing young voters in determining the choice; case study in local election in Bengkulu. We also analyzed the combined relationship between these variables, together with age, and area of origin. We worked with a sample group of 400 young adults between the ages of 18-22 from the city of Bengkulu (Indonesia). The data was subjected to a structural equation modeling SEM analysis, which allowed for the corroboration of the following hypotheses: the higher the education level, the more the interest to choose; the more the experiences, the better the perception to choose; the better the tagline and propaganda, the more interest to choose; the closer the ethnic, the more interest to choose. The result showed that candidate who has more experiences is the most interest candidate to choose by young adult voter . The model obtained allows for discussion of the explanatory value of these variables. Keywords: Young Adult Voter, SEM, Bengkulu Political Knowledge (PK) is one of the core variables in the study of mass political behavior and differs from other components of political involvement for being objective rather than subjective. Citizens vary substantially not only in their levels of information or political knowledge but also in the content of this information: current issues, active individuals in politics and government, constitutional 203 Jurnal The Politics principles underlying the government, the real-life operation of the political system, among others. Our approach to PK is formed speciically by socio-cognitive theory. Numerous studies (Brussino & Rabbia, 2007; Fiske, Lau, & Smith, 1990; Gordon & Segura, 1997; Rhee & Capella, 1997; Somin, 2006) maintain that PK is an indicator of the degree of development of political systems. As a result, exposure to political information, motivation, and cognitive ability deine the cognitive process and the learning or level of PK. From this analytical perspective, motivation, ability and opportunity are inextricably connected. Among the motivational dimensions, Van Deth (2000) refers to interest in politics as the degree to which politics appeal to the curiosity of citizens. In this regard, it would be equivalent to paying attention, which is a necessary prerequisite for learning any subject. On the other hand, starting from the theory of autoeficacy, it can be understood how people judge their own capabilities, and how these autoperceptions of eficacy affect an individual’s motivation and behavior (Bandura, 1986). The feeling of personal eficacy is a cognitive mechanism related to individuals’ judgments about their own capabilities; based on these judgments, they will organize their knowledge and carry out their actions. Abramson, Aldrich, and Rohde (2002) maintain that people who feel that they have political eficacy can feel psychologically motivated to become involved and participate in politics. In this line of thought, the model proposed by Bennett (1995) maintains that education and the level of intelligence affect cognitive abilities, which are essential for people to become politically informed. Meanwhile other socio-demographic variables, such as age, ethnicity, gender and socio -economic level, affect people’s opportunities to acquire information on politics, while the force of partisanship, the concern for the results of an election, and the psychological involvement in public issues shape the motivation to pay attention to political affairs. Previous studies suggest that motivational level plays a very important role in relation to PK. Method Participants Participants were selected using a random quota sampling (Lohr, 2000). The choice of this type of sampling was due to the need to improve the conditions of a typical random sampling. Although the selection of young adults is not at random, and therefore bias in the selection of participants is not removed, the use of this technique guarantees that the proportions of the sample, regarding demographic characteristics, relect those of the population at large. In order to achieve this, following the estimated proportions set by the National Institute of Statistics and Census (INDEC), quotas for age, gender and level of education. Participants were selected in ten different locations of the province that are characterized by high concentrations of young adults. The sample was composed of 300 young adults from the Bengkulu, between the ages of 18-23. Measurement Tools Data related to the participants’ age and education level was obtained through the use of closed-ended, mixed-choice questions. It lists a group of twenty questions designed for measuring interest factors. The score was obtained from the sum total of the scale. Studies of internal structure validity, performed using factor analysis by the method of Principal Axes, showed a one-dimensional structure: both the Kaiser and Guttman rule of eigenvalues greater than 1 and the Scree graph showed the existence of one underlying factor that explained 43% of the variance in responses to the test (eigenvalue = 3.64). It should be pointed out also that the scale showed a satisfactory degree of internal consistency (α = .91). Researcher had to use the 5-point Likert scale, from strongly disagree (value = 1) to strongly 204 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 agree (value = 5). The studies conducted to validate the internal structure of the scale by means of exploratory factor analysis (method of extraction of Principal Axes) indicate the existence of one underlying factor that explains 49% of the variance in all items. It is worth pointing out that in establishing the number of factors, both the Kaiser rule (eigenvalue = 2.93) and the Scree graph indicated the existence of one factor. On the other hand, an optimal internal consistency was observed when calculating Cronbach’s alpha coeficient (α = .89). Finally, the Hahn Scale (Brussino, Sorribas, Rabbia, & Medrano, 2006) was adapted in order to measure the Interest in Politics variable. It has six items that evaluate the interest in political processes, or at least, in the results of such processes. The options to the questions are: 1- strongly disagree; 2- disagree; 3- neutral; 4- agree; 5-strongly agree. The results of the exploratory factor analysis (method of extraction of Principal Axes) indicate the existence of one underlying factor that explains 66% of the variance in responses. The existence of a factor was established using the criteria of Kaiser and Guttman (eigenvalue = 3.95) as well as the Scree graph. Together with this, the results obtained using Cronbach’s alpha coeficient (α = .90) indicate an optimal internal consistency. Procedure and Analysis of Data The collection of data was performed individually, emphasizing the voluntary nature of participation in the study. To evaluate the proposed model, a structural equation modelling (SEM) analysis was performed. This type of analysis allows to empirically contrast theoretically constructed models and it has important advantages when compared to other statistical techniques, since it makes it possible to account for measurement error, estimate relationships with more than one causal link, and incorporate observable and latent variables to the analysis which improves the representation of theoretical concepts and statistical estimations (Tabachnick & Fidell, 2001). In this sense, two observable variables (education level and age) and four latent variables are integrated into the contrasts of the proposed model. All the analyses were performed using the SPSS 20.0 statistical package and AMOS 4.0 program. Results First, an exploratory analysis of data was performed in order to know the characteristics of the variables contained in the model and to verify the completion of the statistical requirements for the SEM. To do this, descriptive statistics of the mean and standard deviation were calculated, and asymmetry and kurtosis indexes were obtained to test the normality of distribution. With the objective of determining whether the variables were normally distributed, Shapiro-Wilk and Kolmorogov-Smirnof statistics were estimated with corrections by Lilliefors: statistically signiicant results (p < .01) were observed in both, rejecting the hypothesis of a normal distribution in the studied variables. However, as pointed out by Pérez (2004), these normality statistics prove to be too sensitive to small deviations from normality when working with large samples. This is why it is recommended to use visual analysis of normality graphs as an alternative approach. Demographic Results Demographic data was collected before the respondent started to answer the questions. This data was later being summarized as in Table.\ 205 Jurnal The Politics Table 1. Demographics of Respondents Gender ValidMale Female Total Frequency 83 317 400 Percent 20.8 79.3 100.0 Frequency 202 187 11 400 Percent 50.5 46.8 2.8 100.0 Age Valid17-19 20-22 >23 Total Table shows the distribution of samplings for each of demographic variables. The majority of the samples were female (79.3%) while 20.8% were male. Most of respondent were 17-19 years old (50.5%). Validity and Reliability Hair, Black, Babin and Anderson, (2010) stated, “One of the primary objectives of CFA/SEM is to assess the construct validity of a proposed measurement theory” (p. 708). “A measurement theory specifies how measured variables logically and systematically represent constructs involved in a theoretical model” (Hair et al., 2010, p. 693). Therefore, confirmatory factor analysis (CFA) is performed to determine relationship between constructs. Hair et al. (2010) suggest that a reliability test should be performed before an assessment of its validity. “Reliability is an assessment of the degree of consistency between multiple measurements of a variable” (Hair et al., 2010, p.125). Furthermore, Churchill (1989) also stated, “Coefficient alpha absolutely should be the first measure one calculates to assess the quality of the instrument” (p. 68). Cronbach’s alpha reliability coefficient was conducted to measure of the internal consistency of the survey instrument. Table 2. Reliability Statistics Cronbach's Alpha .600 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .601 N of Items 15 From table 2 the reliability of each measure was tested. The instrument is reliable because the Cronbach’s Alpha in this study is 0.6 for the 15 items. That is above to the min reliability coefficient of 0.6, so this study is reliable (Cronbach, 1951) Measurement Model Confirmatory Factor Analysis CFA was performed to examine the relationship between the items and their respective latent variables using AMOS 20. Relationships between the constructs and their latent variables were specified in the measurement model 206 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Figure1. Confirmatory factor analysis framework Variables with more than 5% of lost values were not observed, and only three atypical univariate cases and one atypical multivariate case were observed. We chose not to remove them on the recommendations of Hair, Anderson, Tatham, and Black (1999). Next, in order to verify the linearity of relationships, the dispersion diagrams between variable pairs were examined and the absence of quadratic components in the evaluated relationships was veriied through the Curvilinear Estimation function of the SPSS 20 (Gardner, 2003); it was observed that all variables exhibited linear relationships with each other. Finally, a multicollinearity diagnostic between the variables was performed with the objective of identifying highly correlating or redundant variables. An absence of multicollinearity between the variables was observed, since values greater than r = .90 in the matrix of bivariate correlations (Tabachnick & Fidell, 2001) were not found, nor were small tolerance values (less than .10) or elevated VIF values (greater than 10; Martínez Arias, 1999). Before estimating and evaluating the proposed structural model, a conirmatory factor analysis was performed to test the latent variables included in it. As pointed out by Byrne (2001), this analysis allows evaluating the measuring model for each latent variable establishing how it is related to the observable indicators. The obtained results are displayed in Table 2. In order to evaluate the it of each model, multiple it indicators were considered, more speciically: the Pearson chi-quadratic statistic, the comparative it index (CFI), the goodness-of-it index (GFI), the normal it index (NFI), the non-normal it index (NNFI), and the root mean square error of approximation (RMSEA). As can be observed, the values obtained for the it indexes were optimal considering the criteria proposed by Hu and Bentler (1995) for values greater than .95 in CFI and GFI, as well as the criterion of Arbuckle (2003) for not working with models that exhibit RMSEA values higher than .08. Once the measuring model for each variable was analyzed, we proceeded to evaluate the structural model speciied in Figure 1. To do this, the identiication of the model was evaluated 207 Jurnal The Politics comparing the number of data (sample variances and covariances) with the number of parameters to be estimated (Uriel & Aldas, 2005). It was observed that the model was over identiied (df = 171), which is why we proceeded to contrast and estimate it. Table 3. Result of Confirmatory Factor Analysis Model Default model Saturated model Independence model CMIN 210.946 .000 1012.510 DF 80 0 105 P .000 CMIN/DF 2.637 .000 9.643 Goodness of fit test was performed and shown in each model to compare with the suggested criteria by the ratio of chi-square to degrees of freedom (χ2/df), goodness-of-fit index (GFI), the adjusted goodness-of-fit index (AGFI), the root mean square error of approximation (RMSEA), and the comparative fit index (CFI). The measurement model of CFA indicated a moderate fit: X²/ df = 2.63; p-value = 0.000; RMSEA = 0.04; GFI = 0.92; AGFI = 0.90; CFI = 0.962. Based on this analysis the confirmatory factor analytic model was accepted. Structural Equation Model (SEM) The results of the CFA analysis indicate that each construct of the research model has a strong reliability, convergent validity, and discriminant validity. Therefore, it is suitable for the study to use an SEM structural model in this section (figure 8). Structural Equation Modeling (SEM) was utilized to analyze, firstly, the measurement model and, secondly, estimate the structural model and test the proposed research hypotheses (Guh, Lin, Fan, Yang,2013). Figure 2. The Result of Structural Model Testing 208 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Table 4. Standardized Coefficients with Standard Errors IC <--- Acdm IC <--- Exp IC <--- Prog IC <--- Etc Estimate .038 .264 .219 .090 S.E. .029 .067 .067 .052 C.R. 1.295 3.935 3.281 1.738 P .195 *** .001 .082 Summary and Discussion of the Findings The hypotheses were tested through structural equation modeling (SEM). Before testing the hypotheses, multi group confirmatory factor analysis was conducted for validation of the survey instrument. The multi group model is supported and provided a good model fit. It could provide useful implications for them to undertake the findings and implement their politic plan in order to understanding more about the Indonesian young voters. It is important for candidates in Bengkulu when they want to fight in local election. Based on the findings of this result, experiences showed positive effect on intention to choose for young voter. It means that when candidates has more experiences, young voter will choose them. Later, candidates who has been a mayor or governor shall to show to public. It will be a good campaigne and will be a good politicl education for young voter. However, this research found that program and tagline which offer by candidate also being an interest factor for young voters. This result correlated with the education background of respondents. When the higher education from respondents, it will make them carefully to choose which candidates will be choose. For 2 others (Academic and Ethnic), has negative effect for young voters. It means that those variables are not the interest variables caused young voters vote them. References Arbuckle, J. L. (2003). Amos user’s guide. Chicago, IL: SmallWaters. Batista Foguet, J. M., & Coenders Gallart, G. C. (2000). Modelos de ecuaciones estructurales [Structural equation modelling ]. Madrid: La Muralla, S.A. Bennett, S. (1988). Know-nothings revisited: The meaning of political ignorance today. Social Science Quarterly, 69, 476-490. Bennett, S. (1997). Knowledge of politics and sense of subjective political competence. American Politics Research, 25(2), 230-241. doi:10.1177/1532673X9702500205 Bennett, L., & Bennett, S. (1989). Enduring gender differences in political interest: The impact of socialization and political dispositions. American Politics Research, 17(1), 105-122. doi:10.1177/1532673X8901700106 Brady, H., Verba, S., & Schlozman, K. (1995) SES: A resource model of political participation. The American Political Science Review, 89(2), 271-290. doi:10.2307/2082425 Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2005). Students’ perceived responsibility and completion of homework: The role of self-regulatory beliefs and processes. Contemporary Educational Psychology, 30(4), 397-417. doi:10.1016/j. cedpsych.2005.05.003 209 Jurnal The Politics 210 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Indigenous Elite & Modern Democracy (Case Study of Legislator at Gowa Regency) Haslinda B. Anriani; Ansar Arifin; Rasyidah Zainuddin Tadulako University of Palu Hasanuddin University of Makassar STIKES Mega Rezky Makassar Email: [email protected] [email protected] [email protected] Abstract This paper aim storeveal ’lunge’ indigenous elite that took place in a modern democratic society in Gowa, especially when the on going process of organizing elections out 2009. Some legislator selected 20092014 Gowa who had a background in traditional elite became evident how important power political bargaining in Gowa. Three of the members of parliament of the indigenous elite serve as the primary data source through in-depth interviews. The findings obtained are: indigenous elites who hav ea sound base large masses have strong political bargaining for gaining seats in parliament Gowa. Most of the indigenous elite who involved as a candidate does not have the capacity of education and political experience. Interestingly, they still dorationality political status attached to him. Keywords: traditional elite, parliament, legislators, modern democracy. Introduction One strong indicator of the on going politicalpatronage inI ndonesian political democracy is int he process of legislative elections take place. As we know that political symbols inherent in a politician in this case the legislator is the mass base or community strength. A political party is recognized as the winner of the election when the percentage of reserved seats in the legislaturemet by most cadres. Cadres who won the ’seat’ politics means having the 211 Jurnal The Politics most votes in the constituency. That is, the party winning the election is certain to have a ‘voice’ most masses. (Shah, 2012). Interesting phenomenon then is to what or how the mechanism performed byp olitical parties along its cadres (read: candidates) in collecting the ‘voice’ of the community. Instantly became the best alternative approach under taken by all political parties, namely recruiting individuals who have a mass base. This condition can be easily detected many in rural areas such as community leaders or spiritual figure or called by Fata has a segment selector primordial (Kompas, December 4, 1998). Additionally, persona is too much inherent in the family ’nobility’ which are here ditary very believable. The royal family has asocial investment in the surrounding community that put him as’patron’. For political parties, the nobility or traditional elite that has a mass of ’capital’ main. Political parties are only concerned with ’mass’ of the indigenous elite despite the ’quality’ of indigenous elite proposed to be a candidate for legislators still need to be adapted in order to meet the standards of a very rational election. This condition is confirmed by the findings Nurhasim (2001:13-14) that the recruitment of members of parliament will affect the quality anyway, whether it’s integrity, independence, loyalty, level of autonomy, responsibility and accountability. There are always interesting things put forward regarding the recruitment of party members. As awakened in Indonesian political culture, most recruiting instant party a head of elections to meet the quota of the party vote. There are recruiting employers, traditional leaders, village heads, village priests, and so on where these people have mass and influence in the community. Legislative reality in Gowa year of 2009-2014, there are a number of party members who become legislators basedr ecruitment ’interests’. There are 82,22% of members of parliament who truly ideal through the recruitment process. Ideal in the sense that the selected individualis indeed the party cadres are well known by constituents, moving from the grass roots and fight for the party platform and understand the expectations and interests of the people they represent. (Anonim, 2009). Conversely, there are 17,78% legislators who were recruited through instant way, they are not the party cadres who build and raise the party but was taken by the need to meet the quota of party representation, in an impromptu fight at the party (Anonim, 2009). Them through the legislative recruitment process instantly and full of bargaining, means that the majority of members of Parliament who was elected representative of the people is that when they entered the legislative nomination process because they have the capital, power, mass, and influence. Reality that can not be denied that in Gowa still thick with local value highly respect and uphold the nobility. When the political process occurs as networking cadre, then those who have a good infl uence because of nobility or because the material is going to be a priority recruitment. In fact, some political parties (including the largest political parties have members in parliament) take, recruiting, became a candidate member of Parliament and later became a member of parliament was not through the recruitment process and procedural standards. Most political parties that recruit indigenous elites often do not meet the standards such as: the level of education that does not reach a bachelor and has not been involved at all in the political party that does not have the experience and political insight. Nevertheless, the indigenous elites who become legislators also perform a variety of adaptation actions to be ensuring representation of their political status. Although they are not educated and lack the experience and the organization of the party, but the passage of time makes them turn into actual legislators. Walinono (1979) defi nes the indigenous elite as elite gain influence,prestige and its roel based on the values and norms of customary or a person or group of 212 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 persons classifi ed as a minority whose existence is respected, honored, exemplary, dipanuti in the community and have the allure, power drag and instinct high impact on indigenous elite society obtained from generation to generation. CASE STUDY OF 3 INDIGENOUS ELITE Here is outlined 3 legislators who were recruited by the party just before the election of 2009. They are recruited without cadrerization process, but considerations of political strategy, as noted above. Case 1, a candidate instant recruited for reasons known and has become a role model for the people around him even though he has no political experience at all. In fact, higher education or undergraduate level as well as the non-fulfi llment of the main conditions to be candidates. Case 2, where the persona in the political community into selling points. A female legislators elected because his parents are known both as employers and as a respected person in the community in the region. Case 3, a female legislator who has a strong background persona. Persona and his extended family is strengthened by the power of their materials through the family business. 1. HSN-LJ HSN-LJ is 55 years old and was a local businessman who is respected. Education is not to fi nish at primary school because he had to help their parents work. Persistence was then that makes it a very skilled in cratiing red brick. For Gowa district, he is well known as a successful entrepreneur for more than 30 years. He also has opened a number of places red brick making in the region. In addition to successfully develop his business network, HSN-LJ also employ residents in the area. The condition has taken place for generations of his father. In fact, a number of families have ‘served’ on HSN-LJ to two generations of off spring. A number of social achievement of HSN-LJ has long been a ‘target’ or ‘game’ political parties in Gowa. ‘Branding’ social inherent in her very tempting the political party officials. Various approaches are used by them to apply and ‘engaging’ HSN-LJ. Starting from a ‘family’, ‘community’, to ‘transactional’ is used to demolish the ‘defense’ principle HSN-LJ. In the end, it came out as the winner is the United Development Party (PPP) HSN-LJ then officially became a member of the PPP in a short time and even directly promoted as one of the candidates for his electoral district is Bontonompo and South Bontonompo. At that moment, HSN-LJ start a new chapter of his life in politics. Although this time she frequently interact with the community, but this time the political context of interaction that is built into a differentitor. Interaction that takes place already laden with political interests. There is a bit of a ‘split’ socially conditioned by HSN action-LJ. After the implementation of the legislative elections of 2009 is over, it can bet as the initial prediction that the ‘branding’ social HSN-LJ will give him political authority. To the overall sound of his election area, he gained a seat No. sequence 2 of 6 seats contested in his election area. In carrying out its status as a legislator, HSN-LJ work hard to give an account of the political status. He began to study political terms, political culture, and the actions and political strategies. Often appearing in the community became the main capital to communicate with constituents. He just needs to improve political insight, such as legislation, local regulations, government regulation, as well as more sensitive to social and political issues in the region. He does not just want to ‘nebeng’ in the party as a complement. He did anything to show decent quality should girded by a legislator. 213 Jurnal The Politics 2. IRM-HRD IRM-HR is one of the youngest legislators in Gowa Regency Period 2009-2014, which is about 37 years old. He was born in one of the rural areas as well as a place Gowa extended family originated. Irmawati itself more to stay in the capital of Gowa is Sungguminasa when entering Secondary School. He has a family and married to a businessman in the city Sungguminasa. IRM-HRD including intelligent people in building social relationships. Its scholarly capital used to be involved in various social activities. Moreover, the status of her husband who is quite well known in the town Sungguminasa also conditioned reputation. Although IRM-HRD Sungguminasa residence in the city, but it remains to establish communication with his extended family in the village. More than that, he also continued the tradition that has been built by parents and grandmother to provide many benefi ts to the people in the village. Therefore, IRM-HR also brought success to the village. He helped a number of public infrastructure development. In addition, a number of estates that had also managed by the local community. Measures like that are further strengthened IRM name-HRD and his family in the village, although he did not live there. In the village it is certain that almost no one who does not know the family IRM-HRD. Social potential possessed by IRM-HR has been the target of a political party. Of the various parties involved such contestation, PDK eventually emerged as the winner through IRM-HRD offi cial to accept the proposal PDK to run as candidates to represent the area that is Bontomarannu Manuju, Tompobulu and Botolempangan. In the ongoing process of legislative elections in 2009, IRM-HRD unstoppable voice acquisition when compared with the other candidates in the region. Interestingly, get voice-HRDIRM far superior to the equivalent of 3 seats in the legislature. In essence, IRM-HRD absolute win. In undergoing its status as a legislator, IRM-HR is not too much technical diffi culty. His experience in the organization during a student and his involvement in a number of social organizations including political parties makes it very fl exible in the political arena. Prototype of an IRM-HRD including the category that combines the capabilities of mass base into selling points that have strong social bargaining. Gait political will become easier with the proverbial both the capital. 3. HSM-LN HSM-LN currently aged 52 years and is one of a legislator who represents the National Democratic Party and of the electoral district and subdistrict Pallangga Barombong. She is the wife of an offi cer in one of the government agencies in Gowa. Her husband’s family is respected and revered for generations-down at the Pallangga area. HSM-LN was originally an ordinary housewife. It includes character quiet, calm. Her marriage to her husband caused her education process stopped only until the high school level. However, her social status in the public eye make-LN HSM had no choice but to accompany her husband should have appeared in various local government offi cial events. HSM-LN involvement in political parties came from the lack of candidates from among women. Application PDK party well parried by HSM-LN who have the intention to advance women through formal involvement. Confi dence is also reinforced by their large family reputation to win a lot of ‘noise’ in the electoral district and Barombong Pallangga. In the end, HSM-LN securing a seat in the legislature. In the initial period underwent job as legislators, HSM-LN-educated high school and did not have enough organizational experience difficulty adapting behavior to the new environment. 214 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 HSM-LN is still dominated by a feeling of ‘shy’ when it should appear in public to promote his political vision. But, as time went on HSM-LN which has a strong spirit to advance women, gradually have the courage to stand before citizens during a working visit in dapilnya. Although it has not been smooth, but the HSM-LN changes have occurred to him that had the courage and had not hesitate. Table 1. Characteristic of 3 legislator of indigenous elite 1 Indegenous Elite/ Legislator HSN-LJ 2 IRM-HRD F Graduate Bussiness 3 HSM-LN F High School Housewife No Sex Education Pekerjaan M Elementary Bussiness Organisation/ Party Experience Family Background No Social organization No Local persona Indigenous elite Indigenous Source: researcher compilations. The table above illustrates that the three indigenous elite won the ‘seat’ in the local legislative caused by background factors known family descendants respected in their electoral area respectively. Although the main requirements for someone to become candidates are educated to degree level and have experience of the organization and the party, but that does not preclude the three to continue to participate in the elections. Analyzing the above description, it can be explained that in the administration of elections and breath modern democracy rational determination of educational background and background experience and the party organization as a prerequisite to participate as candidates indispensable. With the background of the second prediction that the legislator candidate will have knowledge and experience in enforcing the idea of political and social development in the future. But the reality of the above explain the opposite. Electoral system that relies on a sound base of society as a key element to make the pursuit of traditional leaders of political parties that most of the local nobility who already has mass. In another aspect, the local nobility in addition to having a strong mass base, they also have a base of ‘capital’ that qualifi ed. Aspects of this capital makes ‘bargaining’ nobility prioritized in political parties. Aspects of ‘capital’ is used to amplify sound base they already have and can even be used to increase the amount of noise. ANALYSIS In the present democratic system, political parties are more likely to prioritize quantity of seats in the legislature. Speaking about the number of seats in the legislature meant to talk about the power of the masses and the infl uence or power. Naturally, then when all the political par es to compete for an individual who has a strong mass base as the head of the village, the village priest, religious leaders, traditional leaders, and so on. Nurhasim (2001:14) argues that transparency becomes urgent factor in the recruitment process as to whether the ways that can be accountable, open, rational or using dirty tricks. Patterns of recruitment and regeneration mechanisms covering all activities of the party began a major recruitment, coaching quality of cadres to the placement/assignment of party 215 Jurnal The Politics cadres in strategic positions (recruitment). In a political market, cadres is one of the “product” that determine the selling party in public. The better the pattern of recruitment and regeneration in the body of a party, then the better the quality of the “product” that will be produced and off ered to the public. The better the quality of the proposed product, the higher also the marketability of the party in the elections because of the higher confi dence that the figures would have been the best party cadres to be able to represent the interests of the people and changing circumstances. So the performance of a political party, is largely determined by the quality and lunge cadres. In the context of the recruitment process by political parties when a person becomes a member of Parliament was suffi cient to have a role on the political behavior in certain respects. Similarly, the meaning of the process of recruitment of members of Parliament itself and how it presents itself through their own views as a legislator. Is the path to the process that he deserved and deserve to have that role, whether recruitment affect their behavior in Parliament, including the behavior when communicating their political messages. How to recruitment also shows who has the most infl uence in the selection process of candidates for members of Parliament and the motive or interest in it. What political party or outside elements, such as, community organizations, government and other interest groups. The descrip on above into sync with the political ability legislators who appears in the capacity and capability political action. Parliament members who suddenly appeared in an instant were likely to have difficulty adapting to politics especially when not matched with individual capacity in the form of organizational experience including previous experience of practical politics. However some members of Parliament also considered that the adaptation process can be carried out simultaneously. The motivation of 3 indigenous elite above to account for their political status, gradually began to appear. In a variety of programs that they hold, they have taken the role of such HSM-LN and HSN-LJ was able to stand in front of the village meeting meeting / sub formulated the idea though briefl y. The most important for them is emerging courage to do something more. In this context, the indigenous elite position in the middle of a rational modern democracy was evolved in the form of the emergence of awareness of the demands and responsibility for its political role. Bets family background also makes them eager for change. CONCLUSIONS Indigenous elite who managed to become a member of the legislature is generally not due to meet the prerequisite of political capacity and the capacity of education, but they are chosen because they have a mass base and capital base. Both mass base and capital base, both are ‘co-of existence’ and even tend to have become a symbol of modern democrti c politics. With ‘simple’ capabilities, the existence of indigenous elites in the legislature is quite dynamic. They still have to account for the individual consciousness of their political status in the form of full involvement in all legislative work program. At the same time, they gradually take on an important role in the events that took place. This indicates that within the indigenous elite has emerged awareness of individuals to account for their social role entailed. REFERENCES Anonim, 2009. Profi l DPRD Kabupaten Gowa. Sungguminasa Kabupaten Gowa. Fatah, Eep Saefulloh. Bangsa Saya yang Menyebalkan. Kompas, 4 Desember 1998 HSM-LN. Wawancara, Agustus 2012. 216 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 HSN-LJ. Wawancara, Agustus 2012. IRM-HR. Wawancara, Agustus 2012. Nurhasim, Mochammad (Editor). 2001. “Kualitas Keterwakilan Legislatif, Kasus Sumbar, Jateng, Jatim, Sulsel.” (Laporan Penelitian). Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI. Syah, Rahman. 2012. Perilaku Poli k Anggota Legislatif Kabupaten Gowa. Disertasi. PPS Universitas Negeri Makassar: Makassar. Walinono, Hasan, 1979, Tanete : Suatu Studi Sosiologi Politik (Disertasi), Pascasarjana, Unhas. 217 Jurnal The Politics 218 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 Exchange And Political Communication (Study at Regent Election of Soppeng District) Rosmawati, Harifuddin, Sudirman Tadulako University Palu, UVRI Makassar [email protected]; [email protected]; [email protected] Abstract This paper aims to reveal the socio-political reality that is loaded with interest. The interest certainly are mutually-benefi cial but often unbalanced political advantage. In this regard, politics always intersect or identical to ‘exchange’ and ‘communication’. When interpreted in reverse, that isn’t politics if it doesn’t contain elements of ‘exchange’ which must be preceded by a communication strategy its politicians. Specifi cally, this paper reveals the occurrence of a ‘political exchange’ and the ongoing process of ‘political communication’. Set in the elections in Soppeng district iIn 2010, the process of exchange and political communication that takes place generally is ‘transactional’. Although some cases of ‘looks’ is ‘interactional’ but it always ends with a political compensation (transactional). Keywords: exchange; political communication; election; transactional; interactional. Introduction Election is part of the democratic values that are trying to put the competition between individuals, groups, and communities to achieve certain political power, both in the legislative and executive level. Yet another issue illustrates, that many political elites running the pragmatic, political opportunists, who just did a mass mobilization to achieve power without having a clear vision. In the minds of their politics (elite), power is as a tool for political empowerment of 219 Jurnal The Politics personal, group, political affiliation (parties), and as a political investment for the future. The political reality illustrates the political action based on Machiavelli’s political theory (see: Skinner in Ritzer, 2004), which took power by all means, including religion to politics, on behalf of the people’s voice to personal interests, and so on. Such a view is at the ‘spirit’ in modern democracies are based on instrumental rationality, liberal capitalism. At the regional election in the district of Soppeng in 2010, individual politicians including local elites as a public political activity that is mutually exchange for political purposes. Local elites dominated by the nobles have a mass base will tend to make political cooperation with other elite that besides having a mass base also has a material capital. Other forms of political exchanges that occur most often political ‘reply-mind’ and political ‘compensation’. All forms of political exchange of the nature of reciprocity or reciprocity. It is no less important is the political communication among participants election candidates. Political communication determine the political exchanges between them both individually and on behalf of the party. In politics, communication is dominated by models of ‘transactional’ although there are also other models of ‘interactional’. Both the communication model in practice is always applied in turns based on the context of communication takes place. When the communication is in trouble, then certainly there will be no exchange of political cooperation. Mulyana (2004:i) states that failure to communicate is often misunderstood, even catastrophe losses. The risk is not only the individual level, but also at the level of institutions, communities and even nations. Therefore, Mas’oed (1982:30) instead of political communication should be a way for the flow of information through the community and through the various structures that exist in the political system. In regard to the above, it becomes important to be described forms of political exchange and political communication that takes place in the election in 2010 in Soppeng. Political Exchange In a political democracy based on liberal capitalism, every individual interaction that takes place containing the element ‘exchange’ or ‘mutually beneficial’ among the allied political actors. Political dynamics in Soppeng elections laden with political exchanges within, always based on the basic economic assumptions (rational choice), namely politicians give anything and get anything, whether favorable or not, as well as the community. (Ritzer, 2009: 458). Given involved in the political process is not limited to the individual but also involves the greater social groups (social structure), and in this case the group provides a major infl uence in directing the political decisions of individuals. This is revealed by a politician whose political choices depending on the political choices that were ordered by the party, and the party political choices depending instruction regional leaders. So the political direction is institutionalized and has a clear structure. This description indicates the intervention of social structures in the vicinity. The political exchange is also reflected in the atitude of a politician who follow the orders of the party because he has the interest to yourself and move it equally beneficial. He gave voice to the chairman and chief warrant for his career, at least plays later vice chairman. That is the reason why political choices in party leadership following the political choice. “ Political exchanges also have an element of ‘remuneration’ for good deeds a politician to him. It is, as stated by a resident as follows: […]..I want retribution against that has always given the job against my people, so I feel guilty morally if not helped him to win the election of 2010. (AC, 49 years of age, The Winning Team 72).” Most forms of exchange that happens to be ‘material’ either directly or indirectly. It is as the 220 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 following description: […]…To exist in the world of politics in this area, I have to pair up with AD, so that all businesses and educational institutions I also can develop more advanced. (BC, 54 years). Political Communication The primary key of the candidates to be elected in the general election is good communication. Communications made in the general election is different from the communications made on the lives of people in general. Communications made by the candidate usually persuasive to the public. If the candidate can communicate well, the people will be aff ected to support the candidate in the general election. Vice versa, if the communication is done by the candidate so the people will not be interested and inclined indiff erent to the candidate. Political communication is done in the election is a process that takes place on an ongoing basis. Political communication in the election is only the beginning of communication that will continue after the election is finished. This is a follow-up communication of the results of the initial communication on the election. 1. Political Discourse of Regent Candidate Politics as well as communication, which in this case involves a process of delivering a message to the audience or “involves a conversation”. According to Mark Roelofs (see Nimmo, 1993) “Politics is a conversation or rather politics is talking. Further enriched by Cholisin, et al (2007) that political communication is a process of delivering information to the public policy of the government and vice versa. In detail, David Bell express three types of political speech, namely; (a) talks of power, (b) infl uence the conversation, and (c) talks authority (see Nimmo, 1993). a. Discourse of power Bell argued that the speech power means infl uencing others by threats or promises. Related candidate in the General Election of Regent Soppeng, all candidates make promises in the form of an attempt to bring Soppeng become more advanced and counted addition, there are also couples who will advance Soppeng as agricultural areas. The promises made to the candidate’s spouse aff ect others society that people think all the candidates will do so if elected later became Regional Head Soppeng. b. Influence discourse Similarly the discussion of power that is infl uencing others to achieve certain purposes. However, there are diff erences in the tools used to achieve the goal. In talks infl uence, the tools used to achieve the goal is to counsel, encouragement, demand, and warnings. A number of candidates in talks infl uence, will make a visit to the residence of the late Datu All Soppeng, to consult him. This they did so that they get a good image in the eyes of the public, because the public will judge that what was done by the candidates are not rashly to be head of the region later, and led to the possibility of a boost from the community to choose a particular candidate in the elections. c. Authority discourse Authority discussion is more form than the form of conditional orders or contingen that are characteristic of power and infl uence. In the election Soppeng, certainly all regent candidate talks 221 Jurnal The Politics about the authority does not occur during the process of the campaign, but done when candidates concerned elected later. Realized or not the promises that they did during the campaign depends on them. 2. Party as a political vehicle According to Arifi n (2006), the fi gure of a politician, activist or professional will increase, if supported by renowned institutions, or take part in the institution. So the agency is a major force in helping the process of effetive political communication. Institutions are container cooperation of several people to achieve a common goal. Furthermore Arifi n explained that in the political world of the institution in the form of parliamentary political parties and government, or bureaucracy. Institutions non-political, basically has also political power, though small, and certainly not the same as political institutions (2006). Self-image is something that is believed to political parties and expected by the people of what is done by the political parties. A number of political parties is a renowned political parties in Indonesia, such as Golkar, PDI, PPP, Democrat, Gerindra. Their self-image has been evidenced by the people, so that they are at the time of the previous election has always been the top in the world of Indonesian politics. The candidates regent in this hope by bringing major parties that make them win in the elections. 3. Selection of Media in political communication The use of media in political communication, needs to be sorted and carefully selected to suit the conditions and situation of the audience. According to McLuhan (See Arifi n, 2006) the existence of the media is an extension of the human senses. One main channel types that emphasize communication one to many people, the mass communication. Nimmo then classified based on the level of immediate communication in mass communication into two, namely: (a) face to face communication, and (b) communication that requires intermediate or long-distance communication (1993:168). For communicates face to face, is not necessary because the media enough to talk in front of the audience, while for remote communication is required intermediaries to communicate with audiences, such as the required use of the mass media, interactive media (internet, telephone for example). Channels of communication on a number of candidates in the elections Soppeng regent, they use two types of use of mass communication, namely face to face communication and remote communication. First, the use of face-to-face communication, they will come to the community. Second, the use of remote communication, they use social networking media Facebook and give their phone numbers to the public. This they do in order to save money and so that the public can also directly interact with them, by providing insert on issues surrounding Soppeng. Another of the most popular media used in Soppeng are billboards and banners that contain wonderful words and photo of partner candidates. This media is scariered throughout the region long before the election Soppeng implemented. Strengthening the media, candidates also distributed clothes shirts, bags, cards, calendars containing the identity of the candidate concerned. Analysis Interactions between individuals (candidate regent) which exchange with the interests of the legal basis of “rewards and profi ts earned by individuals who did exchange it”. Social exchange that occurs between the candidates do not run static, since it does not individuals benefi t from the 222 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 social exchange process. Theoretically, the exchange that occurs in the political transactions in the election Soppeng always contain the following elements: 1. The more often a person’s action was appreciated, the more often people that do the same “.Conversely, the more often a person’s action failed or did not get an award then the action will not be repeated by him. This substance has the sense that where individuals have the opportunity to more freely social exchange in accordance with the needs of the individual concerned. Case of Soppeng election of 2010 that took place with the confl ict is refl ected in the following paragraphs. “[…] I became part of AKAR as indeed always been supported, began in Musda Golkar DPD II Soppeng, chairman of the parliament elections, mass organizations of all success, and thank God I was also able to gain compensation, the faithful were geting results. (AA, 67 Years of age). The above description confirms that the individual social exchange process to be put in a favorable position, if not, the action will not be performed again. 2. Where in the past there is one or a number of stimuli in which a person’s actions being rewarded, then the existing stimulus stimulus resembles past it, the more likely that the person will do the same. This means that success in one action escort the person to the other measures that are similar. Such as the following expression: […] AKAR as candidates for help to me to be a winner in the election of Chairman Tim KNPI Soppeng, my help and it was a success, then ROOTS grateful, I get a reward that is a compliment or a special position for me. And when AKAR be Soppeng district head candidate in 2010 for help to me to be a winning team, I help and expect success and gain praise or position as desired by me. (AC, 49 years of age). 3. The higher the value of one’s actions, the more likely that person to do the same. If the prize is given each others very valuable, the more likely the actor perform desired actions than if the prize is not worth. Prize is action with a positive value, the higher the value of the gift, the more likely it is to bring the desired behavior. While the sentence is obtained for negative behavior. This is revealed in the case of BC (54 years of age) who lost the election. […] Couple incumbent won not only fraud but also its strategy in suppressing civil bureaucracy, Head, Kadesh, and employees who are close to us as sympathizers or our successful team then surely transferred or fi red, so it can aff ect the choice, because fear and got the rewards of promises promise.’ The description explains that the punishment is not an effective way to change a person’s behavior. Instead, people will be motivated to do something if he gets rewarded. 4. The more often someone gets rewarded at adjacent time, the less valuable the reward for him. The element of time becomes very important. People in general will not be quickly saturated, if the reward was obtained after a long time. One of the opinions of the AC (49 years of age) that: […] Voters in Soppeng already tired and bored with promises directly given real wants. Anyway principle, if there is a promise of chicken after tomorrow and today there who love chicken eggs, then the voters chose the chicken egg today. Once the model is now so does the money point. although not all but average.’ 223 Jurnal The Politics 5. People compare the amount of benefit that is associated with each action. High value reward value will be lost if the actor considers that it all tends not they would earn. While the lowvalue rewards will experience petambahan value if all of it is deemed very likely obtained. Thus, the interaction between the values obtained in exchange for remuneration with the trend. One of the opinions of BC (54 years of age) reinforces this statement is: […] It used to voters still see aspects of family relationships, materials, willing to redeem himself with a price, sugar, gloves, etc. With frequent pick in elections in Soppeng, legislative election, presidential election, governor election, regent elections and gradually began to shft the value of political education and chose not the only factors that but already see the achievements to promote the welfare of the village.” The description explains that, the most desired benefi ts are benefi ts that are very valuable and very likely to be achieved. While most undesirable reward is not worth the reward most and tend not obtainable. (Homans in Ritzer, 2009: 457). Conclusions 1. In the organization of the election of modern political system based rational, exchange which is manifested in the form of ‘promise’, ‘compensation’, ‘remuneration / gratitude’ to those who have and will ‘give help’ into something that is inevitable. 2. Political Communication plays an important role in determining the mutual exchange. In political communication, regent candidate transmits his vision to the people in the hope they selected. For that, use a variety of ways such as social media, billboards, banners, and so on to attract public sympathy. References Arifin, Anwar. 2006. Pencitraan dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Politik). Jakarta: Pustaka Indonesia. Cholisin, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. Mas’oed. 1982. Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Mulyana. 2004. Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu. Nimmo, Dan. 1993. Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ritzer, George dan Goodman. 2009. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern (terterjemhan oleh Nurhadi/ Judul asli: Sosiological Theory. McGrawHill, New York, 2004) Yogyakarta: Kreasi Wacana. --------------, 2004. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (terjemahan oleh Alimandan/ judul asli: Sociology: a multiple paradigm science). Jakarta: RajaGrafindo Persada. Wawancara, AA, 67 Tahun. Wawancara, AC, 49 Tahun. Wawancara, BC, 54 Tahun. 224 Vo. 1 No. 2 Juli 2015 PEDOMAN PENULISAN JURNAL THE POLITICS Naskah yang ditulis pada Jurnal THE POLITICS harus memenuhi pedoman penulisan serta syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1. Naskah yang ditulis belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain. 2. Naskah berupa hasil penelitian (lapangan dan kepustakaan), gagasan konseptual serta kajian aplikasi teori yang terkait dengan ilmu politik. 3. Naskah diketik dengan Ms. Word dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 (210 x 297 mm) dengan huruf Times New Roman 12 pts, spasi 1,5. Batas/margin atas, bawah dan tepi kanan 2 cm dan tepi kiri 2,5 cm. panjang naskah 15-20 halaman termasuk daftar pustaka dan tabel. 4. Sistematika penulisan naskah disusun dengan urutan sebagai berikut: • Judul tulisan: komprehensif, jelas dan singkat. Judul diketik dengan huruf kapital ukuran 14 pts, judul bahasa Inggris diketik miring dengan ukuran huruf capital ukuran 12 pts. • Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademik, asal institusi, beserta email pribadi. • Abstrak minimal 250 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci (keywords) 3-5 kata. Kata kunci harus mencerminkan konsep paling penting yang ada di dalam naskah. • PENDAHULUAN memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, dan metodologi (untuk hasil penelitian lapangan). • PEMBAHASAN membahas secara jelas pokok bahasan dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penulisan. • PENUTUP berisi kesimpulan, inti dari rumusan masalah akan terjawab dikesimpulan. Penulisan kesimpulan harus naratif bukan dalam bentuk pointer. • DAFTAR PUSTAKA berisi referensi yang dikutip dalam jurnal, maupun sumber bacaan yang terkait dengan tulisan jurnal. Daftar pustaka yang digunakan disarankan merujuk pada rujukan 7 tahun terakhir dan minimal 10 rujukan. • Apabila terdapat gambar dan/atau tabel diberi judul, nomor dan keterangan lengkap. • Kutipan dalam naskah menggunakan catatan perut/body note dengan format: (Nama Penulis, Tahun:Halaman). Contoh: (Nasir Badu, 2014:100-105) dan footnote. 5. Daftar pustaka/daftar rujukan disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut: • Rujukan buku: • Bailusy, Muhammad Kausar. 2012. Politik Lokal dalam Sistem Otonomi Daerah. Jakarta: Mazhab Ciputat. • Rujukan jurnal: • Zulfikar, Achmad. 2015. “Rasionalitas Ekonomi Politik dalam Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran Tahun 2012”. The Politics. Vol. 1 No. 1 Januari 2015. • Rujukan buku dengan empat pengarang atau lebih: • Wirasenjaya, Ade M. (ed.) dkk. 2014. Dinamika dan Transformasi Politik Internasional. Yogyakarta: Laboratorium Hubungan Internasional UMY. • Rujukan Koran/majalah • Hiarej, Erik. 2 November 2008. “Terorisme dan Individualisasi Perang”. Kompas: hlm. 6. • Rujukan skripsi/tesis/disertasi: • Bakri, Hendry. 2011. Resolusi Konflik SARA di Kota Ambon. Skripsi. Makassar: Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. • Rujukan internet/artikel dalam jurnal online: • Nasir Badu, Muhammad. 2015. Demokrasi dan Amerika Serikat. Jurnal The Politics 225 Jurnal The Politics (online), Vol. 1 No. 1, (www.politicsunhas.org, diakses 20 Januari 2015). 6. Pengiriman naskah dilakukan secara online melalui Open Journal System (OJS) pada laman www.politicsunhas.org atau melalui email [email protected]. 7. Naskah yang masuk diproses oleh Redaksi melalui Dewan Penyunting dan Mitra Bestari yang ditunjuk berdasarkan bidang kompetensinya. Penulis diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas masukan/saran dari Dewan Penyunting dan Mitra Bestari. 8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui email penulis bersangkutan. Naskah yang tidak dimuat dapat ditarik kembali atasa permintaan penulis. 9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan naskah dan format penulisan sesuai dengan Pedoman Penulisan Jurnal The Politics. 10. Penulis yang naskahnya dimuat akan menerima 2 exp. jurnal cetak (P-ISSN: 2407-9138) dan dimasukkan pada e-journal The Politics di www.politicsunhas.org (E-ISSN). 226 Vo. 1 No. 2 Juli 2015