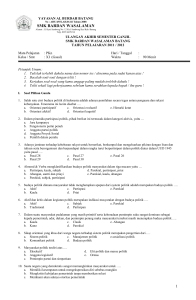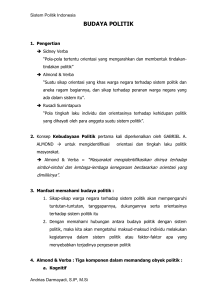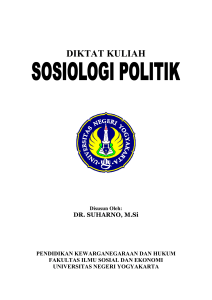budaya politik masyarakat indonesia dalam - E
advertisement

ISSN 2087-2208 BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK Oleh: Drs. Budi Mulyawan, M.Si. Abstrak Budaya politik merupakan sesuatu yang inheren pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern, sehingga menjadi aspek yang siginifikan dalam sistem politik. Sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang, kajian terhadap pembangunan politik suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari budaya politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Seberapa besar harmonisasi yang dicapai oleh budaya politik dengan pelembagaan politik merupakan parameter dari pembangunan politik itu sendiri. Kata kunci: budaya politik, sistem politik, dan pembangunan politik. A. Pendahuluan Kebudayaan, merupakan blue print of behavior yang memberikan pedoman bagaimana warga masyarakat bertindak atau berperilaku dalam upaya mencapai tujuan bersama. Atas dasar kebudayaan, masyarakat membentuk prosedur-prosedur yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Budaya politik – sebagai unsur dari kebudayaan − merupakan sesuatu yang inheren pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. Dalam hal ini Almond dan Verba (dalam Gaffer, 2006:99) mendefinisikan budaya politik sebagai “sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik Sedangkan David Easton (dalam Winarno, 2008:15) menyatakan bahwa budaya politik adalah “all politically relevan orientation whether of cognitive, evaluative, or expressive sort.”1 Budaya politik merupakan aspek yang sangat siginifikan dalam sistem politik.Hal ini dikarenakan bekerjanya struktur dan fungsi politik dalam suatu sistem politik sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya (Winarno, 2008:65).2 Dalam konteks sistem politik Indonesia, Kantaprawira (2006:35) memposisikan budaya politik sebagai satu dari sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik, bahkan yang dianggap paling intens dan mendasari sistem politik. Lebih jauh, Kantaprawira (2006:36) mengkonstatasi bahwa salah satu parameter pembangunan politik Indonesia adalah tercapainya keseimbangan atau harmoni budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada. Berpijak dari paparan di atas, tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran mengenai budaya politik Indonesia untuk mengenal atribut atau ciri yang terpokok untuk menguji proses 1 Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.Sementara itu orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik.Jadi menyangkut feeling terhadap sistem politik.Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya. 2 Struktur-struktur yang umum dalam sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan. FISIP UNWIR Indramayu 1 JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 yang berlanjut maupun yang berubah, seirama dengan proses perubahan dan perkembangan politik masyarakat di masa konsolidasi demokrasi saat ini.3 . B. Tipe-tipe Budaya Politik Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) mengklasifikasikan tipe-tipe kebudayaan politik : (1) Budaya politik parokial (parochial political culture) yang ditandai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang sangat rendah. Hal ini disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; (2) Budaya politik subyek (subject political culture) di mana anggota-anggota masyarakatnya memiliki minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem secara keseluruhan, terutama terhadap output-nya, namun perhatian atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol; dan (3) Budaya politik partisipan (participant political culture) yang ditandai oleh adanya perilaku bahwa seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik sehingga menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) dan dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya. Namun demikian, dalam suatu masyarakat kerapkali ditemukan inklanasi kepada salah satu tipe budaya politik, misalnya, dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individuindividu yang tidak menaruh minat pada obyek-obyek politik secara luas. Menyadari realitas budaya politik yang hidup di masyarakat tersebut, Almond menyimpulkan adanya budaya politik campuran (mixed political culture) yang menurutnya lazim terjadi pada masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan dinamika yang pesat, sehingga sistem politik bisa berubah dan kultur serta struktur politik senantiasa tidak selaras. Budaya politik campuran (mixed political culture) yang dikemukakan Almond sebagai berikut: 1. Budaya Parokial-Subjek (The Parochial-Subject Culture) Tipe budaya politik saat sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuintutan ekslusif masyarakat suku yang feodalistik.Masyarakatnya mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang sentralistis. 2. Budaya Subyek-Partisipan (The Subject-Participant Culture) Proses peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipan yang sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana peralihan budaya parokial menuju budaya subyek. Dalam budaya subyekpartisipan ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi yang aktif; sementara sebagian penduduk masih terorientasi dengan struktur kekuasaan yang otoriter dan menempatkan partisipasi masyarakat pasif. 3. Budaya Parokial-Partisipan (The Parochial-Participan Culture) Kondisi ini biasanya terjadi di dalam negara yang sedang berkembang.Hampir seluruh negara berkembang memiliki budaya parokial.Karenannya sistem politik mereka terancam oleh fragmentasi parokial yang tradisional, padahal mereka ingin secepatnya menjadi sebuah negara modern. Suatu masa, cenderung ke otoritarianisme dan pada waktu yang lain ke arah demokrasi. 4. Budaya Parokial-Subyek-Partisipan (Civic Culture) Civic culture (budaya kewarganegaraan) menekankan pada partisipasi rasional dalam kehidupan politik, digabungkan dengan adanya kecenderungan politik parokial dan subyek warganegara maka menjadikan sikap-sikap tradisional dari penggabungannya dalam orientasi partisipan yang mengarah pada suatu budaya politik dengan keseimbangan aktivitas politik, 3 Esensi konsolidasi demokrasimenurut Larry Diamond adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elite maupun massa yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan ISSN 2087-2208 keterlibatan dan adanya rasionalitas serta kepasifan, tradisionalitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai parokial. Singkatnya, budaya politik ini merupakan penggabungan karakteristik dari ketiga budaya politik murni. Dalam pemahaman yang lebih sederhana, budaya politik kewarganegaraan merupakan kombinasi antara karakteristik-karakteristik aktif, rasional, mempunyai informasi yang cukup mengenai politik, kesetiaan pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemerintah, keterikatan pada keluarga, suku, dan agama. C. Budaya Politik Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Politik Sudah cukup banyak ahli yang melakukan kajian terhadap budaya politik Indonesia. Beberapa diantaranya menjadikan kelompok etnis Jawa sebagai titik tolak analisis mereka atas dasar asumsi bahwa di masyarakat yang multietnik akan ditemukan pola budaya yang dominan. Dalam hal ini, etnis Jawa dipandang sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik di Indonesia4. Pada umumnya para ahli sependapat bahwa pola hubungan yang ditemukan pada masyarakat Indonesia bersifat patronase (patronage) yang sangat dipengaruhi oleh pola relasi antara pemimpin dan pengikut yang berkembang pada kebudayaan Jawa. Jackson (1978:23) misalnya, menyatakan bahwa lingkaran hubungan patron-klien pada masyarakat Jawa disusun atas relasi hubungan yang bersifat diadik, face to face, tidak setara, tetapi saling menghargai antara pemimpin dengan pengikutnya (leaders and followers). Sementara Gaffar (206:109) menyoroti dasar dari pola hubungan antara patron (patron) dan klien (client) tersebut sebagai hubungan yang bersifat resiprokal dengan mempertukarkan sumber daya (exchange of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pola hubungan tersebut walaupun bersifat asimetris, akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak memiliki sumber daya tersebut.5 Dalam konteks struktur sosial masyarakat Jawa, Gaffar (206:107) memandangnya sebagai struktur yang bersifat hiearkhis yang didasarkan pada aspek kekuasaan (politis) ketimbang atribut sosial yang bersifat materialistik. Dalam hal ini ada pemilihan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan (priyayi sebagai pihak penguasa atau wong gedhe) dan rakyat kebanyakan (wong cilik), yang termanifestasi dalam kehidupan sosial di mana birokrat seringkali menampakkan diri dengan self-image atau citra diri yang bersifat benevolensi, yaitu dengan ungkapan sebagai pamong praja yang melindungi rakyat, sebagai pamong atau guru/pendidik bagi rakyatnya, sehingga mewajibkan rakyat loyal kepada mereka. Implikasi negatif dari citra diri seperti itu dalam kehidupan berdemokrasi adalah rakyat mengalami proses alienasi dari proses politik. Rakyat diposisikan sebagai objek yang harus selalu menerima segala keputusan pemerintah dalam setiap kebijakan publik. Dalam kajian selanjutnya, Gaffar (2006:114) mensinyalir kemunculan budaya politik yang bersifat neo-patrimonialistik dalam perpolitikan di Indonesia.Dikatakan neo-patrimonialistik karena negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi; tetapi juga memperlihatkan beberapa atribut yang bersifat patrimonialistik sebagaimana konsep patrimonialisme yang dikembangkan oleh Max Weber.6 Pendapat Rusadi Kantaprawira (2006:37-39) selaras dengan dua ahli sebelumnya. Menurutnya, budaya politik Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi viariabel feodalisme, 4 Beberapa ahli yang dimaksud dalam tulisan ini antara lain Karl D. Jackson (1978),Afan Gaffar (2006 ), Rusadi Kantaprawira (2006), dan Budi Winarno (2008) 5 Sebagai pihak yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih kuat, sudah tentu patronlah yang paling banyak menikmati hasil dari hubungan ini. 6 Atribut yang dimaksud menurut Weber, yaitu: Pertama, kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya. Kedua, kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada universalistik.Ketiga, rule of laws merupakan sesuatu yang sifatnya sekunder dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (rule of man).Keempat, kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan pribadi dan mana yang menyangkut kepentingan publik. FISIP UNWIR Indramayu 3 JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 paternalisme, dan primordialisme. Indikator dari paternalisme dan patrimonial yang masih cukup kuat mewarnai budaya politik Indonesia adalah asal bapak senang (bapakisme); sedangkan indikator primordialisme berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekataan terhadap agama tertentu, puritanisme dan non-puritanisme, dan sebagainya. Namun ditengah-tengah pengaruh tradisionalisme tersebut, Kantaprawira mengidentifikasi tumbuhnya kelompok elit di Indonesia sebagai akibat pengaruh pendidikan modern (Barat) yang merupakan partisipan aktif. Atas dasar analisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap budaya politik masyarakat, Kantaprawira (2006:38) berkesimpulan bahwa budaya politik Indonesia merupakan mixed political culture yang diwarnai oleh besarnya pengaruh kebudayaan politik parokial-subyek.7 Adapun di Era Reformasi, berdasarkan kajian Budi Winarno (2008:66-70), budaya politik masyarakat Indonesia ternyata tidak membawa perubahan yang signifikan, karena masih tetap diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat.Hal ini disebabkan adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut. Dalam mengkaji budaya politik masyarakat Indonesia atas dasar empat budaya politik campuran (mixed political culture) yang dikemukakan Gabriel Almond, Winarno (2008:66-68) berkesimpulan bahwa budaya politik di Indonesia merupakan kombinasi antara parochial-subject culture, subject-participant culture, parochial-participant culture, dan civic culture. Dalam hal ini budaya politik Indonesia, menurutnya, bergerak di antara subject-participant culture dan parochial-participant culture. Subject-participant culture ditandai oleh menguatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik, sementara pada waktu yang bersamaan berkembang rasa ketidakmampuan masyarakat untuk mengubah kebijakan. Rasa sebagai wong cilik, orang-orang tidak mampu, dan termarginalkan membuat mereka hanya berorientasi pada output sistem politik dibandingkan dengan kepedulian terhadap proses input sistem politik. Fenomena seperti ini tidak hanya ditemukan di daerah-daerah pedesaan, tetapi juga di perkotaan di mana masyarakat miskin dan termarginalkan tumbuh subur.Bahkan, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh para penguasa politik yang berorientasi pada kebijakan neo-liberal mendorong kelompok-kelompok marginal ini semakin besar. Parochial-participant culture ditandai semangat primordialisme secara berlebihan, yakni menguatnya wacana kedaerahan pasca diterapkannya otonomi daerah.Dalam hal ini terdapat tekanan dan desakan yang kuat di beberapa daerah agar pemimpin lokal seperti walikota/bupati dan gubernur dipilih dari putra-putra daerah. Situasi ini jelas akan merugikan sistem politik secara keseluruhan karena cenderung menimbulkan konflik horizontal dan menghambat rasa kebangsaan (nation building) yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi. Sejauh ini belum ditemukan kajian ahli tentang budaya politik masyarakat Indonesia dengan menyertakan proporsi pada tiap kategori tipe budaya politik dalam konteks mengetahui model orientasi masyarakat terhadap pemerintahan dan politik. Tulisan ini mencoba memetakan budaya politik masyarakat Indonesia berdasarkan klasifikasi tipe-tipe budaya politik menurut Almond dengan menyertakan proporsi kuantitatif pendukung pada setiap klasifikasi. Langkah pemetaan dilakukan dengan melakukan dikotomi dua struktur komunitas: perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya warga pada masing-masing komunitas dikelompokan 7 Kantaprawiraberusaha menggambarkan kondisi budaya politik Indonesia di masa diterapkannya sistem politik Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila;sementaraGaffar menjadikan budaya politik Orde Baru sebagai objek kajiannya. 4 Program Studi Ilmu Pemerintahan ISSN 2087-2208 berdasarkan status sosioekonomi mereka. Hal ini didasari pada pendapat Lipset (dalam Asrinaldi, 2012:68) bahwa masyarakat yang memiliki status ekonomi yang lebih baik akan lebih mudah berpartisipasi secara efektif ketimbang yang memiliki status ekonomi yang berkekurangan. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara status sosioekonomi seseorang dengan perkembangan demokrasi.Selain sosio-ekonomi, dimensi lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan demokrasi adalah tingkat pendidikan formal. Tinggi-rendah pendidikan individu berkaitan dengan rasionalitas seseorang dalam melakukan evaluasi terhadap aktivitas politik.Dalam hal ini terdapat korelasi antara sosio-ekonomi dengan tingkat pendidikan di mana pendidikan yang rendah pada umumnya ditemukan pada masyarakat kalangan miskin. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat perkotaan dibagi dalam tiga stratifikasi: masyarakat miskin, kelas menengah, dan kelas atas. Sementara warga komunitas perdesaan dibagi berdasarkan stratifikasi: elit − massa. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilu yang baru lalu berjumlah 186.612.255 jiwa8 sementara persentase penduduk perdesaan sebesar 50,2 % dan penduduk perkotaan 49,8%, maka penduduk pedesaan yang memiliki hak pilih sebesar 93.679.352 jiwa dan perkotaan 92.932.903 jiwa. Adapun angka kemiskinan di perdesaan pada tahun 2011 sebesar 16,56% dan di perkotaan 9,87%,9 sehingga jumlah penduduk miskin di pedesaan yang mempunyai hak pilih sebesar 15.513.300 jiwa sedangkan di perkotaan 9.172.478 jiwa. Menyoal struktur sosial masyarakat perkotaan di mana 9,87 persen merupakan masyarakat miskin dan 50,3 persen adalah kelas menengah.10Dalam konteks tersebut menarik untuk dikemukakan hasil penelitian Asrinaldi (2012:215) yang menyatakan bahwa budaya politik masyarakat miskin di perkotaan cenderung parokial dan subjektif. Di sini, Asrinaldi membagi sikap politik masyarakat miskin menjadi dua kategori: kelompok pertama adalah kelompok yang apatis terhadap politik; sedangkan kelompok kedua adalah yang dikategorikan memiliki sikap semi apatis atau semi politik. Pendidikan kelompok terakhir ini hanya tamat SD atau tidak tamat SLTP. Dasar pendidikan inilah yang membantu mereka mendapatkan informasi politik, misalnya mencari pengetahuan mengenai aktivitas politik melalui surat kabar – biasanya surat kabar bekas yang ada di sekitar mereka. Dari dua kategori ini walaupun Asrinaldi tidak secara tegas membedakan masing-masing kategori berdasarkan budaya politiknya, namun dapat diduga kelompok berkebudayaan parokial yang dimaksudkannya adalah kelompok apatis, sedangkan yang berbudaya subjektif merupakan kelompok semi apatis. Sementara berdasarkan hasil survey litbang Kompas, orientasi politik kelas menengah juga cenderung apatis dan belum mau bergerak mengorganisasikan diri untuk perubahan. Mereka tidak begitu menghiraukan apa yang terjadi pada kondisi sosial politik meskipun mereka masih menunjukkan eksistensinya dalam pemilihan umum dan daerah. Dengan demikian eksistensi atau keterlibatan kategori masyarakat ini hanya sebatas partisipasi tidak langsung (representative democracy)11, belum menyentuh partisipasi dengan keterlibatan langsung (representative democracy).Orientasi politik semacam ini dapat dikategorikan kebudayaan politik subyek.Hal ini dikuatkan dengan pendapat Dedi Irawan (dalam Efriza, 2012:118) bahwa masyarakat berkebudayaan politik subjek tergambarkan dalam kelompok-kelompok menengah di 8 Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014 Statistics Indonesia Tahun 2012 (http://puzzleminds.com/kualitas-kependudukan-di-indonesia/) 10 Survey litbang Kompas mengenai kelas menengah 2012 (http://politik.kompasiana.com/2012/ 09/21/ membacapilihan-politik-kelas-menengah-494839.html) 11 Secara teoritis partisipasi politik masyarakat menurut ahli dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung berkaitan dengan keterlibatan langsung (representative democracy), misalnya melakukan debat politik, diskusi publik, lobi politik, dan menghadiri kampanye politik. Sedangkan partisipasi tidak langsung(representative democracy) diidentifikasi dengan keterlibatan publik yang terbatas atau bahkan diwakilkan, misalnya kegiatan mencoblos dalam pemilu. 9 FISIP UNWIR Indramayu 5 JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 perkotaan.Mereka memiliki tingkat kesadaran politik yang memadai, yaitu memahami tentang situasi dan dinamika politik yang mengantarkan mereka untuk bersimpati pada salah satu parpol.Hanya saja kalangan menengah perkotaan ini biasanya bersikap pasif dalam aktivitas politik. Adapun dalam menentukan kategori masyarakat berbudaya politik partisipan, parameter yang digunakan dalam tulisan ini adalah aspek rasionalitas masyarakat dalam kegiatan politik. 12 Apabila diasumsikan rasionalitas seseorang dalam melakukan aktivitas politik ditentukan oleh pengetahuan mereka dan pengetahuan tersebut dibentuk oleh proses pendidikan formal (Asrinaldi, 2012:45), maka budaya politik partisipan dianggap ekuivalen dengan pendidikan tinggi yang dicapai seseorang. Bertolak dari beberapa asumsi dan data kuantitatif tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa dari sejumlah 92.932.903 jiwa penduduk dewasa di perkotaan: - Penduduk miskin apatis bertipe budaya politik parokial diperkirakan berjumlah 4.553.712 jiwa atau 4,9 persen. Sementara warga masyarakat miskin yang memiliki sikap semi apatis atau semi politik berkebudayaan subyek berjumlah 4.646.645 atau 5 persen. - Kelas menengah berjumlah 46.745.250 atau 50,3 persen penduduk dewasa, berbudaya politik subjek.13 - Masyarakat bertipe kebudayaan partisipan diperkirakan berasal dari kalangan berpendidikan tinggi (sarjana dan diploma) yang jumlahnya berkisar antara 5-10%14 atau berkisar antara 9.330.613 sampai 18.661.225 jiwa. Sementara dari kalangan mahasiswa sebanyak 4,8 juta15 jiwa atau 2,56 persen dan kalangan elit yang jumlahnya diperkirakan mencapai kurang dari 2 persen. Dari perhitungan sederhana ini dapat diketahui bahwa jumlah warga masyarakat perkotaan bertipe budaya partisipan berjumlah ± 15 persen atau 13.939.935 jiwa. Adapun identifikasi masyarakat pedesaan dilakukan dengan mendasarkan pada konsep stratifikasi masyarakat pedesaan yang dikemukakan Hofsteede (1992:45-46), yakni: (1) Elit desa, yang terdiri dari lurah, pegawai-pegawai daerah dan pusat, pemimpin formal dan pemuka masyarakat, guru, tokoh-tokoh politik maupun agama, dan petani kaya dan (2) Massa, yang terdiri dari petani menengah, buruh tani, pedagang kecil, serta pengrajin. Dari stratifikasi tersebut akan sangat mudah diketahui bahwa kelompok elit desa sebagai lapisan teratas jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan kelompok massa. Diperkirakan jumlahnya antara 2-3 persen saja dari seluruh warga desa.Kalangan yang dikonstatasi merupakan kelompok terpelajar dan memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi di pedesaan ini kita kategorikan dalam kelompok masyarakat berkebudayaan politik partisipan. Sebagaimana dikemukakan, jumlah penduduk miskin yang mempunyai hak pilih di pedesaan mencapai16,56 persen atau 15.513.301 jiwa. Diasumsikan angka buta aksara 12,2 persen seluruhnya merupakan warga miskin pedesaan, maka sebesar itu pula jumlah warga masyarakat miskin bertipe budaya parokial (11.428.881 jiwa); sementara sisanya sebesar 4.084.420 atau 4,36 persen bertipe budaya politik subjek. Namun dalam hal ini keterbatasan dan minimnya akses 12 Rasionalitas yang dimaksud tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi memperoleh manfaat dari tindakannya, tetapi juga membawa pengaruh pada kebijakan publik, kinerja pemerintahan, dan aspek personal dari pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat (V.O. Key dalam Asrinaldi, 2012: hlm44) 13 Kelas menengah di Indonesia dicirikan dengan rata-rata pendidikannya setingkat SMA, dengan penghasilan Rp. 1,9 Juta per bulan serta pengeluaran Rp. 750 ribu - Rp. 1,9 Juta per bulan (Kompas, 2012). 14 Angkatan kerja Indonesia berpendidikan diploma/sarjanaberdasarkan Statistics Indonesia Tahun 2012 berjumlah 10.318.000 jiwa yang terdiri dari para pekerja 9.418.000 jiwa dan yang belum bekerja 900,000. Dengan demikian angka yang mendekati riil adalah 5,53% dikalikan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih, hasilnya 10.319.657,7 atau 10.319.658 jiwa. 15 Menurut data BPS tahun 2012, jumlah mahasiswa Indonesia saat ini baru mencapai 4,8 juta orang. 6 Program Studi Ilmu Pemerintahan ISSN 2087-2208 terhadap informasi politik memungkinkan jumlah warga miskin di wilayah pedesaan bertipe budaya politik parokial jumlahnya lebih besar lagi. Masyarakat budaya politik parokial yang disebabkan terbatasnya informasi politikditemukan padapada struktur komunitas masyarakat desa terpencil dan suku yang terpencar menjauh dari pusat kekuasaan politik.Sebagai contoh situasi yang ditemukan di desa-desa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di propinsi Kalimantan Barat.Namun jumlah penduduk komunitas ini relatif kecil, diperkirakan hanya beberapa ratus jiwa. Untuk mendeskripsikan kebudayaan politik masyarakat pedesaan, khususnya kelompok massa dengan proporsi yang mendekati kenyataan yang sesungguhnya, sudah tentu memerlukan kajian yang mendalam, menimbang pengaruh budaya tradisional masih sangat kuat berakar pada komunitas ini. Pola hubungan patronase, misalnya, masih sangat kuat mewarnai kehidupan masyarakat pedesaan. Ini diindikasikan dengan suksesnya beberapa elit desa yang ditengarai memiliki kekayaan berupa bidang tanah yang sangat luas berhasil lolos menuju legislatif tingkat Kabupaten bahkan Propinsi karena jumlah suara dari klien mereka memadai dalam mengusung mereka menduduki kursi tersebut. Dalam hal ini kelompok massa pedesaan nampaknya sudah memiliki ciri-ciri tipe budaya politik subjek, namun masih diwarnai budaya tradisional sebagaimana dikemukakan, terlebih paternalisme yang sudah sangat mengakar dalam struktur masyarakat pedesaan. Paparan di atas mendukung pendapat ahli bahwa budaya politik Indonesia merupakan mixed political culture, kombinasi dari 3 (tiga) budaya politik: (1) masyarakat budaya parokial yang jumlahnya diperkirakan kurang dari 20 persen penduduk dewasa yang berasal dari masyarakat miskin berpendidikan sangat rendah dan warga komunitas masyarakat desa terpencil dan suku terasing; (2) masyarakat budaya politik partisipan, jumlahnya diperkirakan 16 persen berasal dari kalangan sarjana, mahasiswa, elit politik perkotaan, dan elit desa; dan (3) masyarakat budaya politik subjek, jumlahnya mencapai lebih dari 60% yang terdiri dari kalangan kelas menengah perkotaan dan massa pedesaan. D. Penutup Budaya politik Indonesia di Era Reformasi tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap budaya politik masyarakat Indonesia, walaupun secara historis pelembagaan formal sistem politik Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan.16Hal ini dapat dipahami mengingat suatu kebudayaan berdasarkan hukum-hukum perkembangan masyarakat (laws of social development) berjalan relatif lambat.Dalam konteks ini perlu kita simak pendapat dari Winarno (2008:67) bahwa mengubah budaya politik tidak semudah mengubah struktur dan fungsi-fungsi politik. Mengubah struktur dan fungsi dapat dilakukan dengan mengubah undangundang dasar suatu negara, tetapi mengubah budaya politik suatu bangsa akan memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Terlebih ketika budaya tersebut telah mengakar dalam kehidupan politik masyarakatnya. Capaian proporsi 12,57% penduduk dewasa berkebudayaan politik partisipan tentunya dibilang masih rendah bila dibandingkan dengan capaian masyarakat demokratik industrial, 17 sebuah masyarakat di mana terdapat cukup banyak ativis politik dan kehadiran pemberian suara yang besar ataupun publik peminat yang kritis dalam mendiskusikan masalah-masalah 16 Pelembagaan formal yang dimaksud adalah sistem politik Demokrasi Liberal ke sistem Demokrasi Terpimpin dan terakhir ke sistem politik Demokrasi Pancasila. 17 Bandingkan dengan pendapat Almond bahwaproporsi kebudayaan politik dalam masyarakat demokratik industrial mencapai 40-60% penduduk dewasa berbudaya politik partisipan; ± 30% berbudaya subyek; dan penduduk dewasa berbudaya parokial kira-kira 10% (Mas’oed dan Andrwew, 2008:52). FISIP UNWIR Indramayu 7 JURNAL ASPIRASI Vol. 5 No.2Februari 2015 kemasyarakatan dan pemerintahan, dan kelompok-kelompok penekan yang mengusulkan kebijakan-kebijkan baru (Winarno, 2008:19). Namun demikian, melihat tingginya proporsi masyarakat bertipe budaya subjek yang terdiri dari kalangan menengah perkotaan dan pemilih pemula yang rata-rata berpendidikan SLTA , maka potensi terjadinya pergeseran budaya politik masyarakat kalangan ini ke arah budaya politik partisipan sangatlah besar. Terlebih fenemona yang terjadi akhir-akhir ini di mana kalangan pengusaha, baik kelas atas atau maupun kelas menengah mulai tertarik untuk terjun dalam kancah politik praktis. Hal ini sudah tentu menjadi fenomena yang sangat menggembirakan dalam pembangunan politik di Indonesia Daftar Pustaka Agustino, Leo, 2009. Politik dan Perubahan.Yogyakarta : Graha Ilmu Asrinaldi, 2012.Politik Masyarakat Miskin Kota.Yogyakarta : Gava Media. Elfriza, 2012.Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung : Alfabeta. Gaffar, Affan,2006. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hofsteede, W.M.F. 1992 Proses Pengambilan Keputusan di Empat Desa Jawa Barat.Yogyakarta.Gajah Mada Press. Jackson, Karl D. & Pye, Lucian W, 1978.Political Power and Communications in Indonesia. Barkeley and Los Angeles : University of California Press. Kantaprawira, Rusadi, 2006. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Marijan, Kacung, 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta : Kencana. Mas’oed, M & MacAndrew, C, 2008.Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Varma, S.P., 2010. Teori Politik Modern.Jakarta : RajaGrafindo Persada. Winarno, Budi, 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.Yogyakarta : MedPress. Website http://revolusidesa.com/category/page/fakta_desa/33/URBANISASI-DAN-KEMISKINAN-DESA http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/26/13202052/Mahasiswa.di.Indonesia. Cuma.4.8.Juta http://puzzleminds. com/kualitas-kependudukan-di-indonesia/ 8 Program Studi Ilmu Pemerintahan