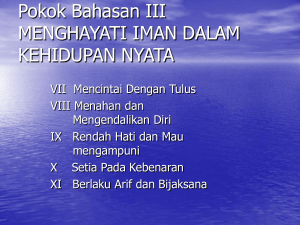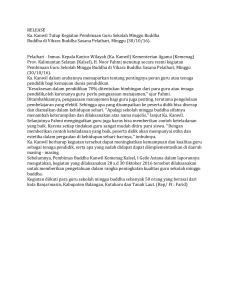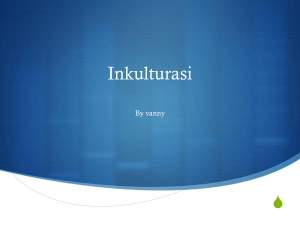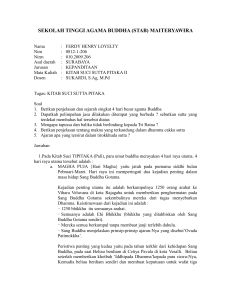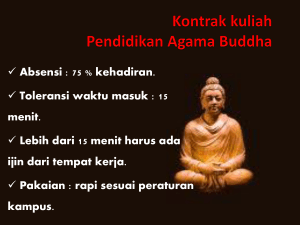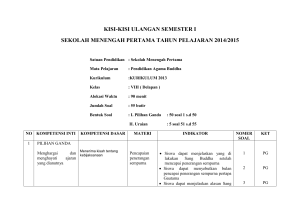Diskriminasi Gender
advertisement

Kekerasan Terhadap Perempuan Bukti Diskriminasi Gender, Benarkah Maraknya isu “Kekerasan terhadap perempuan”, menjadi rangkaian kosakata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang katanya ‘modern’, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme—yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan—justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Di AS sendiri yang konon Negara pengusung HAM, justru menunjukan laporan yang cukup mengejutkan. Andrew L. Sapiro dalm bukunya berjudul Amerika NO.1 menyebutkan “Kita no.1 dalam kasus pemerkosaanyaitu 114 per100 ribu penduduk.” Departemen Kehakiman AS sampai akhir 1992 menyebutkan bahwa 20% pemerkosa adalah bapaknya sendiri, 26% orang dekatnya, 51% orang yang dikenalnya, 4% orang yang tidak dikenalnya. Ini fakta tahun 1992, bagaimana dengan sekarang? Senada dengan kondisi di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Catatan tahun 2004, misalnya, menyebut 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau di-monitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10% ), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti suami, pacar, ayah, kakek, dan paman. Tanggal 25 November, masyarakat dunia memperingati hari internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hari itu merupakan momen untuk menguatkan gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Issue tersebut diterjemahkan dengan cepat oleh pemerintah Indonesia dengan menggagas ‘Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tagga’ melalui UU No. 23 tahun 2004, yang disandarkan pada Deklarasi PBB tentang ‘Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan’ (20 Desember 1998). Terakhir, pada Konferensi Perempuan Internasional di New York, ditandatangani Konvensi Internasional tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (awal Maret 2000). Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan—yang mereka bahasakan dengan kekerasan berbasis jender—merupakan hasil bentukan interaksi social yang terjadi dalam masyarakat patriarki (sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki). Menurut mereka, di Indonesia secara histories sudah mengusung pelembagaan kekerasan jender sejak dulu masa kerajaan, yaitu dengan berlakunya norma kepatuhan dan komoditi di tengah-tengah masyarakat (Jurnal Perempuan, ed. 09). Keadaan-keadaan inilah yang mereka anggap semakin memperkokoh ketidakadilan sistemik terhadap perempuan. Apalagi kebijakan pembangunan dalam seluruh aspeknya selama ini lebih banyak memihak kepada laki-laki. Adapun kebijakan yang berkenaan dengan perempuan cenderung mengarah pada pemberdayaan perempuan sebagai ibu dan istri saja. Akhirnya, posisi perempuan semakin terpinggirkan, terutama dalam hak-hak sosial, ekonomi dan politik; mereka selalu menjadi orang nomor dua setelah laki-laki, baik dalam sektor privat (keluarga) maupun publik (masyarakat). Kondisi ini sering berujung pada penuduhan terhadap Islam yang dianggap lebih memihak laki-laki dan bersifat misoginis (membenci perempuan). Inilah yang, menurut mereka, menjadi penyebab maraknya kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Mereka bahkan menuduh norma agama khususnya Islam turut mendukung langgengnya budaya kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, seperti hukum Islam seputar kebolehan seorang suami berpoligami, wajibnya seorang istri meminta izin suami ketika keluar rumah, kebolehan suami memukul istrinya ketika ia nusyûz, atau keharusan seorang istri melayani suaminya ketika ia menginginkannya, dan lain-lain. Perlu dipahami bahwa kejahatan atau kekerasan tidak ada kaitannya dengan masalah jender (perbedaan jenis kelamin), karena kekerasan tidak hanya menimpa kaum perempuan, tetapi juga menimpa kaum laki-laki, baik di dalam ataupun di luar rumah tangga. Pandangan bahwa kekerasan terkait dengan jender adalah pandangan yang sangat keliru. Ia hanyalah pandangan kaum feminis yang mengukur kejahatan berdasarkan jender, pelaku dan obyeknya. Mereka membela pelacuran ketika perempuan menjadi korban (padahal pelacuran merupakan tindak kejahatan). Mereka pun mencap poligami sebagai bagian dari KDRT karena pihak yang menjadi korban pun—menurut mereka—adalah perempuan. Padahal jika kita mau jujur, jelas sekali bahwa maraknya kekerasan terhadap perempuan atau KDRT merupakan cerminan dari gagalnya bangunan sosial-politik yang didasarkan pada ideologi sekularis-kapitalis ini. Munculnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan maupun KDRT adalah karena tidak adanya perlindungan oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Ini adalah akibat dari tidak adanya pemahaman yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban negara, masyarakat, ataupun anggota keluarga (suami-istri). Diskriminasi perempuan di dalam kehidupan buddhis antara lain : Buddha tidak ada yang perempuan (dalam artian Buddha tertinggi, seperti Gotama) karena seorang Buddha harus mempunyai ciri-ciri Buddha berjumlah 32 (maha purusa) Setelah Buddha meninggal—mungkin beberapa abad setelahnya—timbul pandangan bahwa kelahiran sebagai perempuan lebih rendah karena karma buruk kelahiran sebelumnya. Jadi ada anggapan sampai saat ini bahwa kelahiran sebagai perempuan karena akibat karma buruk masa lampau dibanding kelahiran sebagai laki-laki. Di Kitab Jataka Pali (cerita kehidupan lampau Buddha Gotama sebagai Bodhisatta) Bodhisatta tidak pernah terlahir sebagai seorang perempuan, padahal sebagai hewan ada dalam cerita tersebut. Jataka adalah cerita yang bukan dari Buddha sendiri atau dengan kata lain adalah teks tambahan yang disusun ketika penyusunan Tripitaka. Semenjak Sangha Bhikkhuni ada, umur Sangha Bhikkhu akan menjadi setengahnya dari 1000 tahun menjadi 500 tahun. Cerita penolakan Buddha sebanyak 3 kali terhadap ibu tirinya yang ingin ditahbiskan menjadi bikkhuni. Akhirnya Buddha menerima bhikkhuni dengan syarat 8 garu dhamma. Delapan garu dhamma atau delapan aturan keras bagi bhikkhuni, dua diantaranya adalah: Seorang bhikkhuni, walaupun sudah menjalankan sampai 100 tahun kebiksuniannya, harus menyapa dengan hormat terhadap seorang bhikkhu walaupun bhikkhu tersebut baru sehari menjadi biksu. Seorang bhikkhuni tidak diperbolehkan untuk menasehati seorang bhikkhu, namun seorang bhikkhu boleh menasehati seorang bhikkhuni.