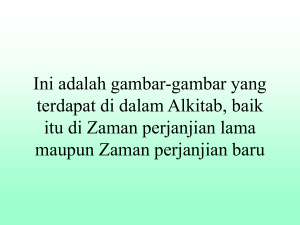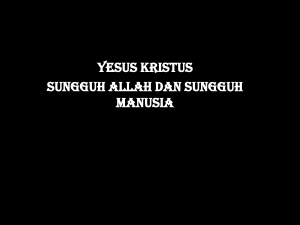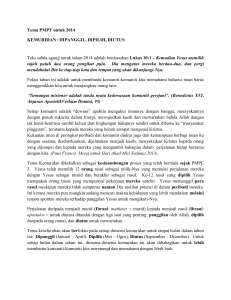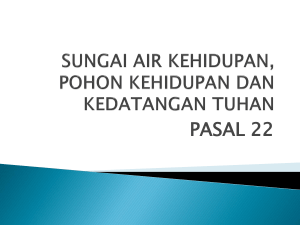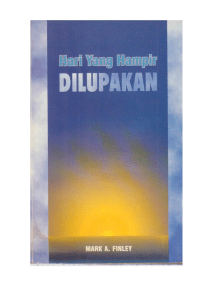Yesus dan Konflik
advertisement

1 “Yesus dan Konflik” (Sekilas menelisik ke dalam Injil Matius dan pemetaan sederhana Management Konflik) Daniel K. Listijabudi Pendahuluan Tulisan ini memuat dua pokok pikiran: Pertama, menelisik sebagian realitas konflik yang dialami dan dikelola oleh Tuhan Yesus sebagaimana dilaporkan dalam beberapa bagian Injil Matius. Bagian Kedua, adalah membahas tentang teori Manajemen Konflik seumumnya. Harapan penulis adalah bahwa pembaca akan dapat melihat keterkaitan keduanya terutama dalam mengambil sikap yang konstruktif terhdap konflik yang mengundang mentransformasikan apa adanya yang keterlibatan dianggap yang negatif intens menjadi dalam saluran upaya bagi terejawantahkannya berbagai hal positif yang menjadi tanda dari hadirnya tata nilai Kerajaan Allah dalam dunia domestik, inter-personal, komunal dan gereja bahkan dalam masyarakat luas. Yesus mengalami Konflik Banyak kisah konflik yang dialami oleh Yesus. Itu tidak berarti bahwa Tuhan dan Guru kita suka berkonflik. Ia adalah pernyataan kehadiran dan perwujudan Allah yang sempurna dalam lawatannya sebagai manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran (Yohanes 1 : 14). Namun, dalam lawatan hidupnya sebagai manusia, Yesus yang mengajarkan agar “mengasihi musuh, dan berdoa bagi yang menganiaya” justru adalah pihak yang dalam banyak hal bersitegang dengan pihak-pihak penguasa agama yang legalistik dalam penerapan Taurat, dalam pemahaman keagamaan konservatif. Dalam versi Injil Matius, benturan Yesus dan para ahli Taurat berkisar soal penerapan dan tafsir Taurat Musa (Mat 12 : 1-15 a; 15: 1-20; 16: 5-12; 191-11 ), kesengajaan mencobai Yesus (Matius 16: 1-4; 22: 15-22); yang dari semua ini Yesus sadar bahwa ia akan mengalami penderitaan dari pihak para pemimpin agama ini (Mat 16: 21; 19: 18-19). Kritik Yesus amat tajam pada para pemuka agama itu. Lihatlah Matius 23: 1-36, betapa 2 keras Yesus menegur mereka dengan kata-kata “Celakalah kamu..” setidaknya 8 kali. Para pemuka agama ini diberi predikat sebagai orang munafik, mereka merintangi orang masuk kedalam Kerajaan Surga, mereka menelan rumah janda-janda dan mengelabui orang dengan doa-doa yang panjang( 23: 13, 14), mereka menobatkan orang untuk kemudian membuatnya menjadi lebih jahat dari mereka sendiri (23: 15), mereka disamakan dengan pemimpin yang buta yang salah kaprah dalam memahami inti dari ritual ( 23: 16-22), mereka dikritik karena di satu pihak memberikan perpuluhan namun di lain pihak lupa esensi perpuluhan yakni soal solidaritas sehingga mereka mengabaikan keadilan, belas kasih dan kesetiaan (23: 23), mereka bahkan disamakan dengan kuburan, yang busuk di dalam walau nampak putih bersih di luar (23: 27)! Apa yang bisa lebih keras dari ini? Untuk mendapatkan gambaran yang agak bulat, berikut adalah beberapa contoh konflik Yesus dan para pemuka agama itu: Menghadapi Jebakan pelaksanaan Sabat1 Dalam Matius 12: 9-15 a, Yesus hendak dijebak oleh orang Farisi melalui pertanyaan “Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?” Ini pertanyaan yang tajam, sebab baru saja Yesus – di ayat 8 – mengucapkan kalimat berdaya hentak luar biasa, yakni : “Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat”. Sekarang Yesus, Tuhan atas hari Sabat itu hendak dijebak. Kalau ia memperbolehkan penyembuhan di hari Sabat, ia melanggar aturan Taurat tentang Sabat. Kalau ia tidak mengijinkan penyembuhan di hari Sabat, itu berarti Yesus bukan Tuhan atas hari Sabat. Apa jawab Yesus? Yesus memakai contoh praktis tentang sikap pemilik domba terhadap domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Pemilik domba pastilah tak akan menunggu Sabat lewat baru kemudian menolong dombanya. Jika domba yang membutuhkan pertolongan saja mendapatkan pertolongan, mengapa pertolongan di hari Sabat pada manusia yang jauh lebih berharga dipermasalahkan ? Atas dasar ini Yesus jelas dan tegas mengeluarkan sikap sebagai Tuhan atas Sabat, yakni “Boleh berbuat baik, boleh melakukan sesuatu yang baik, pada hari perhentian.” Kita belajar bahwa Sabat atau hari perhentian bukanlah saat untuk menunda atau menghentikan cinta kasih. Itu berarti di hari-hari 1 Dimuat dalam Renungan Harian Gloria, by DKL 3 lain , non Sabat, yang tidak mengandung larangan untuk bekerja (bagi orang Yahudi) cinta kasih lebih-lebih lagi tak dilarang untuk ditaburkan. Dibenturkan pada Hukum Taurat Musa soal Perceraian Perikop kita ini, terutama ayat 9, sering dijadikan alasan melarang orang yang pernah bercerai untuk menikah lagi, dengan bayang-bayang : perzinahan. Kalau menikah lagi maka Anda berzinah. Kemudian orang membedakan beda cerai mati dan cerai hidup, maksudnya kalau cerai mati boleh menikah lagi, sedangkan cerai hidup dilarang kembali menjalin pernikahan. Pertanyaannya, apa benar teks bicara soal ini? Jika kita perhatikan konteksnya, maka kita mendapati adanya diskusi. Yesus disudutkan dengan pertanyaan, “apa boleh orang (lelaki) menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?” Perhatikan, betapa “licin” pertanyaan yang mengatasnamakan alasan “apa saja” ini. Reaksi Yesus menarik, Ia pertama-tama merujuk pada suatu prinsip yang terdapat dalam kisah Kejadian, bahwa “apa yang telah disatukan Allah tak boleh diceraikan oleh manusia” (ay 6). Namun orang Farisi yang memang ahli hukum agama terus “masuk” dengan merujuk pada Taurat Musa yang mengetengahkan aturan tentang perlunya surat cerai. Jadi boleh bercerai to? Terhadap ajuan ini Yesus membongkar alasan diterbitkannya surat cerai itu: Itu bukan yang ideal dan bukan menjadi saran untuk memuluskan keinginan lelaki untuk bercerai. Surat cerai dalam Taurat Musa disebabkan oleh kekerasan hati umat yang memaksakan perceraian. Dalam hal ini justru Taurat hendak melindungi kaum perempuan yang sering menjadi korban dalam perceraian (dalam konteks patriarkhi). Tanpa surat cerai, posisi si perempuan begitu rentan.....dengan surat cerai maka status dan haknya sebagai janda menjadi jelas dan dapat dibela. Surat cerai dalam konteks Taurat Musa adalah proteksi hak untuk pembelaan terhadap pihak yang lemah agar bisa membangun hidupnya kembali. Di sinilah letak kalimat di ayat 9 mesti dipahami: Jika seorang suami menceraikan istrinya oleh sebab-sebab lain (kecuali jika istrinya berzinah: berhubungan seksual dengan suami orang lain), maka pernikahan yang kedua itu pada hakikatnya adalah sebuah perzinahan. Ini teguran yang dialamatkan pada lelaki yang semena-mena menceraikan istrinya, bukan larangan orang yang bercerai untuk menikah kembali (yang dalam kasus ini tentu membutuhkan penanganan pastoral khusus). Nilai yang hendak digarisbawahi oleh Yesus adalah : jagalah dirimu dari kekerasan hati yang membenarkan apa yang 4 salah, sebab pada prinsipnya Allah menghendaki agar yang telah disatukanNya tidak dipisahkan oleh manusia. Konflik : Berkat atau Bencana? Agaknya, konflik yang terjadi dalam perjumpaan Yesus dan para pemuka agama, malah bisa menjadi sarana bagi pemekaran gagasan, pendalaman hidup, latihan rohani dan pemerkayaan penghayatan akan kebenaran. Dalam setiap konflik, Yesus dapat menangkap intinya dan mengembangkannya bagi edukasi/pendidikan para pendengarnya malah juga sebagai kesempatan pendalaman hidup bagi para “lawan”Nya. Memang pada akhirnya, konflik antara Yesus dan para pemuka agama ini bermuara pada penyaliban Tuhan. Namun itu bukan berarti kekalahan. Justru di dalam perisitwa salib itu, konflik mendapatkan pemaknaannya yang paling substansial dalam karya Yesus, yakni bahwa salibNya membawa daya keselamatan bagi manusia dan melalui kebangkitanNya, maka Allah menyatakan bahwa Yesus adalah benar dan bahwa Kerajaan Allah yang diwartakan melalui sabda, hidup, karya, mati dan bangkitNya adalah Ya dan Amin. Itu berarti konflik yang dialami Yesus malah menjadi media transformasi radikal bagi setiap pihak yang terlibat dan menyambutNya. Pertanyaan penting dan lestari bagi kita, sebagai murid Yesus adalah : “Bagaimana kita dapat belajar mentransformasi konflik, sehingga ketegangan, luka dan kesulitan bahkan penderitaan dapat ambil bagian dalam menghadirkan suasana dan realitas kemerajaan Allah?” Sekilas Wacana tentang Konflik Selain bercermin dan berakar pada Sabda Suci, kita juga perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang “konlfik” itu sendiri sebagai sesuatu yang relevan dan ada di dalam realitas hidup kita. Kita bisa mulai dengan pengakuan bahwa tidak ada manusia, dan komunitas manusia termasuk gereja, sebagai persekutuan orang beriman 5 yang menyambut karya Allah dalam iman kepada Kristus sang Raja Damai, yang kebal konflik. Sejak dari awal munculnya, gereja malah mengada di tengah-tengah konflik (dalam hal ini konflik identitas kelompok dengan pihak Yahudi dan atau Yahudi Kristen, sebagaimana dikisahkan dalam teks Kisah Rasul). Dalam proses pertumbuhannya, Gereja pun mengalami berbagai proses memekar melalui dan di dalam konflik dalam berbagai skopa (doktrinal-denominasional, sosio-political, dan kultural-religius). Jadi, menganggap kehidupan gereja secara umum kalis atau kebal konflik, keliru. Namun mengganggap kehidupan gereja melulu mengandung konflik juga tak seimbang. Kitapun perlu menyadari bahwa dalam hal manajemen konflik dalam kehidupan komunitas termasuk gereja, mau tak mau kita dihantar pada faktisitas bahwa perjumpaan antara teori dan praksis dalam mengelola konflik adalah insight yang amat berharga. Dari pengalaman pribadi saya belajar bahwa walau teori tentang konflik, kekerasan dan perdamaian telah relatif saya ketahui (mengikuti program Interntional Youth Discovery Team tahun 1995 di Indonesia, India, USA dan Canada di tahun terakhir studi S 1, lalu menulis skripsi tentang kekerasan dan kemudian menerbitkannya sebagai buku perdana di tahun 1997), namun ternyata pengalaman berada di tengah konflik gerejawi2 telah mengajarkan kepada saya secara leboh signifikan bahwa teori melulu memang tidaklah mencukupi. Saya belajar, bahwa kesediaan dan keterbukaan dari seorang person untuk masuk ke dalam lingkaran konflik akan memfasilitas orang untuk disatu pihak berlatih memetakan situasi dengan teori, namun juga berlatih untuk men”daging”kan pengalaman real ke dalam perspektif. Hasilnya macam-macam: pengalaman dan pendalaman hidup (termasuk luka dan obatnya), tulisan-tulisan reflektif dan teoretik dalam dialektika dan penguatan panggilan untuk menanggapi pesan Kristus sebagai Pembawa Damai. Betapapun, saya sadar, ini belum selesai. Hidup jalan terus....konflik dan perdamaian selalu menjadi bagian hidup. Syukurlah, karena itu berarti saya masih hidup! Dari teori dan pengalaman itulah saya belajar bahwa pengelolaan konflik dalam kehidupan manusia, baik domestik maupn gerejawi setidaknya memuat 3 elemen: (a) Pengalaman hidup di tengah-tengah (a) umat yang berpotensi konflik tinggi (di GKMI Salatiga selama 12 tahun, dari 1996-2008) akibat bias dari konflik besar di level lokal dan Sinode, dan yang sekaligus terkait dengan konflik panjang di salah satu perguruan tinggi kristen ternama di kota Salatiga, dan (b) tugas dari Sinode untuk menjadi Tim Mediasi Sinode (bersama 2 kolega: Pdt. Paulus Widjaja dan Pdt. Paulus Hartono) terhadap konflik suatu gereja anggota Sinode di wilayah Jawa Tengah Utara telah menghadirkan realitas konflik gereja setelanjang-telanjangnya di tengah-tengah kehidupan pelayanan saya sebagai Pendeta dan Teolog di gereja Mennonite yang berlabel Gereja Damai (yang nyatanya mesti terus belajar mengolah konflik). 2 6 pemahaman tentang konflik, (b) analisis dan pendalaman ketika konflik terjadi dalam kehidupan komunitas gerejawi dan (c) praksis mediatif yang komprehensif terkait dengan penggarapan dan kesediaan terlibat dalam pengelolaan konflik dengan penyikapan dan nilai yang tepat, konstruktif, kontekstual pula teologis. Empat kualifikasi dari penyikapan dan nilai inilah yang menjadi pedoman dari dinamika pengelolaan konflik secara gerejawi. (a) “Tepat”, yang dimaksudkan adalah perlu dilakukannya analisis yang jitu terhadap konflik (akar masalah, gejala, pemetaan, amplitudo/pemekaran konfliknya); (b) “Konstruktif” terletaklah atmosfer mendasar dari upaya ini, yakni untuk membangun bukan merobohkan. Hal yang hendak dibangun adalah realitas dinamis dari konflik yang terjadi. Sikap mental dari pengelolaan konflik mesti lebih dari sekedar berorientasikan gesekan remeh temah yang dangkal, terlalu pragmatis dan malah dibuat-buat (artifisial: buatan/bukan inti masalah) ; (c) “Kontekstual” dimaksudkan agar pemahaman mengenai konflik diletakkan dalam kerangka kajian interaktif yang mempertimbangkan baik dimensi sosiologis maupun kultural (terkait dengan person dan komunitas yang bersangkutan); (d) “Teologis” dimaksudkan untuk mengolah situasi real dengan perspektif tertentu dimana peran dari iman kristen, kesaksian kitab suci dan tradisi gereja amat berkontribusi dalam menjadi “lensa” untuk memaknai dinamika dan tarik-ulurnya konflik itu. KONFLIK, APA ITU? Patut kita catat bahwa kata KONFLIK, berasal dari kata Latin CONFLIGERE yang berarti “percikan api” atau sparkling fire. Zaman dulu orang membuat api dengan cara menggesekkan dua batu, lalu terciptalah percikan api. Itulah KONFLIK. Ia netral. Karena percikan api itu tidak berbahaya pada dirinya sendiri. Jika ia dikelola dengan baik, maka orang dapat menciptakan api unggun, memasak nasi, mendidihkan air, dan hal-hal lain yang berguna. Namun sebaliknya jika ia tidak dikelola, atau dikelola dengan buruk maka percikan api dapat berubah menjadi api yang membakar rumah, membuat hangus masakan kita dan menghanguskan macam-macam hal. Dengan demikian, kita sekarang tahu bahwa pada dirinya sendiri, KONFLIK adalah sesuatu yang netral. Yang membuatnya positif atau negatif adalah managementnya. Kalau orang tidak mau, tidak bisa, tidak bersedia, dan tidak tahu bagaimana 7 mengelola konflik, maka konflik bisa merusak dan berbahaya, hubungan bisa putus, setidaknya renggang, malah kalau semakin parah bisa destruktif dan merambat ke macam-macam hal lain, sebagaimana halnya dengan kebakaran. Namun jika kita tahu, siap dan paham bagaimana mengelola konflik, maka konflik bisa jadi malah menghasilkan hubungan yang makin konstruktif, mendalam dan penuh potensi positif. Hal yang kita perlukan adalah seni mengelola konflik. Untuk mengembangkan seni in, secara teologis dan pastoral-eklesiologis, maka pertama-tama konflik tidak mesti dimaknai sebagai ancaman, ia dapat juga dimaknai sebagai kesempatan: kesempatan bertumbuh, kesempatan mematang, kesempatan untuk masuk dalam pemurnian hidup batin dan dalam relasi sosial. ANALISIS KONFLIK Kita disadarkan bahwa siapapun kita, dapat saja suatu saat berbenturan satu sama lain bila ada perbedaan prinsip, nilai, persepsi, kepentingan. Benturan bisa dan pasti terjadi. Oleh karena itu, insan religius, umat beriman bahkan para pimpinanpelayan gerejawi tak perlu kaget bila mengalaminya. Hal yang urgen adalah termilikinya kesadaran untuk tak boleh terus terpenjara dalam kekagetan, melainkan dapat memetik pelajaran bahkan mentransformasikan konflik yang terjadi dalam relasi simpang jalan. Konteks persimpangan jalan ini bisa apa saja (pelayanan, keluarga, hubungan suami istri, saudara, hubungan kerja, relasi kemasyarakatan yang homogen ataupun heterogen lintas batas multi dimensi). Eskalasi dan dimensi konfliknya pun bisa meluas, bertaut, beragam dan kompleks . Untuk itu sebagai langkah awal diperlukan pemetaan analisis yang memadai. Pemetaan konflik meliputi baik: (a) peristiwa aktual dan atau pemicu, (b) maupun historical traces (jejak sejarah) yang berakumulasi pada peristiwa konflik itu, dan bagaimana eskalasinya bergerak maju-mundur. (c) apakah ada kondisi sistemik di mana berbagai variabel ditata sedemikian rupa sehingga cenderung menciptakan repetisi yang kuat dalam pola, nilai dan style (yang menjadi konteks “batin”) dari penanganan konflik-konflik yang terjadi, baik durasi maupun siklus dan “how - to”nya. (d) pemetaan posisi, power, bargaining power, role (peran) para “pemain” (formal dan informal) dsb. 8 (e) kepentingan/ideologi/premis yang ekplisit maupun implisit (covert and overt ideas) (f) akar dan fenomena masalah mesti dapat dipindai, ditemukan, dibedakan, dipilahkan, dilihat keterkaitannya. Dalam analisa, kita perlu jeli, utuh dan jernih agar dapat menemukan inti/akar masalah, dan jangan hanya berhenti di fenomena. Merumuskan akar masalah dengan tepat (apalagi jika bisa ditemukan dan dikaji bersama) dan mencoba sedalam mungkin membagi pikiran dan pendapat Anda tentang mengapa hal itu terjadi dan apa yang perlu dilakukan, adalah bagian dari langkah partisipatoris yang strategis. (g) bagaimana “language-games” dari dari setiap pihak yang berkonflik. (h) melakukan aktivitas mendalam untuk mengenali dan malah memahami worldview sosio-kultural-politis-religius seutuh mungkin, akan memberikan lensa yang komprehensif dalam memindai dinamika yang terjadi. (1) Memindai nilai-nilai, gambaran, “simbol-icon” teologis, dan premis-premis dasar apa yang menjadi acuan eklesiologis mereka tentang gereja dan dinamikanya akan menyumbangkan masukan yang berguna dalam kegiatan refleksi-kritis ini. Skema: Analisis, Refleksi dan Aksi dalam model Lingkaran Pastoral Situasi Konflik Aksi Pastoral -Kontekstual Analisis Konteks Pendekatan Integratif Membaca Ulang Kitab Suci dan Tradisi Gereja Siklus dinamisnya adalah gerak dari: Commited Action Reflection Commited and Intellegent Action (mengadaptasi model berteologi kontekstual secara Praxis dari Stephen Bevans (2002) 9 KENISCAYAAN ADANYA PRAKSIS MEDIATIF JP Lederach (2004) mengingatkan, bahwa dalam konflik, mediasi amat diperlukan. Di sini dibutuhkan adanya keterhubungan antara trust (dari pihak peserta konflik) dan responsibility (dari pihak mediator) yang memadai. Trust tidak bisa dipaksakan, mesti dibangun dalam interaksi di lapangan. Progress menuju ke sana membutuhkan harga tertentu: gerak dinamis dari suspicion ke trust (dalam sirkulasinya) tidak boleh tidak diketahui atau tidak disadari oleh semua pihak (terutama mediator). Disinilah kita membangun praksis teologis yang bersikap terbuka dan berani mengolah luka. Setiap pihak yang berkonflik mesti sadar bukan hanya pada luka-lukanya sendiri, maupun juga luka-luka yang ditimbulkannya bagi pihak lain. Pihak mediator juga perlu sadar bahwa tidak ada yang instant dalam mentransformasi konflik, dan tidak ada transformasi tanpa luka-luka yang digarap (pada setiap pihak termasuk pada mediator). Jelas, bahwa keberanian dan kesediaan untuk rentan dan terluka, menjadi syarat mendasar jika kita hendak “sembuh” bersama. Responsibility yang digerakkan oleh cinta kasih, semangat rekonsiliasi, tidak memihak dan independen menjadi vocation (panggilan) lestari dari pelaku mediasi. Hal ini tidak serta merta mudah, namun justru dalam kesulitanlah maka prinsip-prinsip ini akan menjadi penuntun yang terang dalam mengelola konflik di dalam gereja yang notabene tidak asing dengan pendekatan dan prinsip-prinsip Kerajaan Allah (kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, kemurahan hati). NILAI dan PENYIKAPAN TEOLOGIS Tujuan dari pengelolaan konflik gerejawi adalah kebutuhan kita akan TRANSFORMASI bukan sekedar RESOLUSI. Maksudnya, kita diharapkan untuk memikirkan, menganalisis, merefleksikan dan menindakkan apa yang sungguh-sungguh diorientasikan untuk berpotensi MENGUBAH sehingga peristiwa konflik yang terjadi dapat menjadi BERGUNA bagi kehidupan pribadi dan komunitas. Di sini, yang diolah bukan hanya peristiwa namun juga memory (ingatan) dan nilai-nilai dasar serta elan vital yang terjiwai dan menginspirasi dinamika masa kini dan masa depan. Upaya yang kita hendak bangun bukan upaya melupakan. Juga bukan upaya sebaliknya, yakni mengingat-ingat. Melainkan mengingat dalam rangka memberi makna baru. Mengingat dalam rangka meminta maaf dan memberi ampun. Mengingat dalam 10 rangka belajar hidup di hadapan Allah dan sesama dengan pemekaran dan pertumbuhan diri dan komunitas di mana kita mengada bersama sebagai eklesia. Ini sekalilagi terkait dengan soal kesediaan dan keberanian masuk ke wilayah yang rentan namun amat mendasar, penting dan efektif luar biasa. Disinilah kerendahan hati dan spiritualitas perlu terus dibentuk dan didalamkan agar mampu secara gradual namun esensial mengikis dan mentransformasi egosentrisme, harga diri palsu dan kepentingan-kepentingan plus emosi-emosi yang sesaat dan keruh. Hidup dan penggarapan konflik yang terjadi menjadi sesuatu yang didoakan, dipecahkan dan dibagikan sebagai bentuk pengingatan akan karya Tuhan dan sebagai bentuk syukur akan karya Tuhan dalam peristiwa-peristiwa esensial ini. Itulah sebabnya, peristiwa konflik dalam kehidupan kristiani, bisa kita persepsi sebagai realitas teologis di mana penghayatan iman yang merengkuh kerentanan di dalam konflik demi terciptanya pemekaran hidup batin di hadapan sang Kristus yang tersalib tergelar. Ini bukan untuk memuja konflik, namun menyikapinya secara berani dengan mengajukan kerentanan dan keterbukaan menggarap realitas dalam semangat cinta kasih dan perdamaian. Itu sebabnya, dalam proses rekonsiliasi konflik, kita perlu menjauhkan diksi “menang-kalah”. Jika keduabelah pihak berpikir tentang menang-kalah dalam penyelesaian konflik maka sebenarnya keduabelah pihak belum siap untuk berekonsiliasi. Jika hal itu terjadi di dalam gereja, maka kita mesti bertanya:”apa sebetulnya yang diperjuangkan?” Ketika pihak-pihak yang berkonflik mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara psikis atau mengalami “kebosanan” karena berlarut-larutnya masalah, karea berbagai hasutan, fitnah, teror, provokasi dll, maka mulailah terjadi kekaburan tentang “apakah yang menjadi masalah utamanya?”. Ego yang diprovokasi oleh banyak faktor termasuk hal yang dianggap sebagai memperjuangkan keadilan. Dalam situasi ini, hal-hal sederhana menjadi amat pelik misalnya kerumitan memahami emosi, kepentingan, arogansi dan egoisme manusia (Widjaja, Hartono, Listijabudi, 2008-2009). Secara teologis, menggarap konflik gereja adalah panggilan untuk semua orang yang mau menjadi “pembawa damai”. Setiap pihak mendapatkan panggilan yang sama (termasuk para pelaku konflik). Dalam rangka itulah diperlukan latihan batin untuk mengedukasi diri sendiri dan komunitas melalui kesediaan untuk saling mengampuni dan menundukkan diri di bawah salib Sang Kristus yang menjadi ikon rekonsiliasi paling eksistensial dalam teologi Kristen. Di bawah salib itulah, transformasi mulai 11 dipintal kembali. Sebab ketika gereja berkonflik, maka semua pihak tanpa terkecuali membutuhkan pertobatan dan pemulihan diri dalam menata kehidupan keimanan dan pelayanan (Widjaja, Hartono, Listijabudi: 2008-2009). Refleksi Penutup Bahwa pengelolaan konflik memerlukan lebih dari sekedar kemampuan teknis, adalah benar. Kita memerlukan grounding (pendasaran) teologis yang tepat (orthodoxy), darinya ktia membangun praksis yang berkomitmen dan cerdas (orthopraxy) , seiring dengan itu kita perlu terus mewaspadai nilai-nilai dasar dan kemurnian serta dinamika gerak batin yang menjadi sumber dari pengolahan konflik gerejawi yang kita kerjakan dan lakukan (orthospiritus). Keterkaitan ketiga ortho inilah yang menurut saya akan menentukan secara definitif apakah konflik terkelola dengan baik dari segi teologi dan spiritualitas kristen yang mengada di dunia nyata. Dengan demikian, aksi transformasi konflik yang kita libati (commited action), dalam perjumpaan reflektif yang tidak main-main dengan sumber hidup batin dan dalam pemahaman wacana yang secukupnya akan dimensi konflik, bisa menghantar kita pada aksi yang mendalam dan cerah budi (commited and intelegent action). Hasilnya, tak bisa kita jamin 100 %, sebab ada banyak elemen yang bermain dalam setiap konflik (semakin banyak peserta, semakin luas cakupan, semakin kompleks konfliknya). Kita patut mencatat, buah dan perjalanan dari suatu konflik senantiasa mengandung misteri, namun jika kita tahu bagaimana mengelola konflik dan mengelola diri sendiri serta mengelola relasi dengan sesama yang berkonflik dalam kejernihan pemahaman, kesungguhan dan kecerdasan tindakan reflektif dan juga dalam kemurnian batin yang terarah kepada, diinspirasi plus digenangi oleh teladan hidup, sabda, karya Yesus Kristus, maka panggilan untuk “membawa damai” sebagaimana disaksikan dan dipesankan oleh Tuhan Yesus (Matius 5: 9) sudah mulai terjawab, sembari terus mengimani bahwa dalam karya perdamaian ini, parea pembawa damai tidak pernah sendirian. Tidak pernah tanpa partner Illahi. Sebab bukankah telah dituliskan bagi kita bahwa “Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah” (Roma 8: 28) ? Konflik memang akan selalu ada, namun penyertaan Tuhan dan hikmatNya juga terus berjaya. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah kerasnya kehidupan dalam beragam konteks kita. 12 Dona Nobis Pacem, Domine .....Berikanlah Kami Damai, ya Tuhan. Referensi Pustaka: Bevans, Stephen , Models of Contextual Theology, Orbis Book, Markynoll, 2002. Lederach, John Paul, Transformasi Konflik , PSPP, UKDW, Yogyakarta, 2004. Listijabudi, Daniel, Mendulang Sabda , TPK, Yogyakarta, 2012. Listijabudi, Daniel Renungan Harian Gloria Widjaja, Paulus; Hartono, Paulus; Listijabudi, Daniel: Laporan Tim Mediasi Sinode atas Konflik di GKMI Pati, 2008/2009.