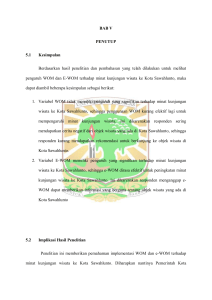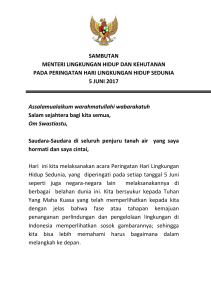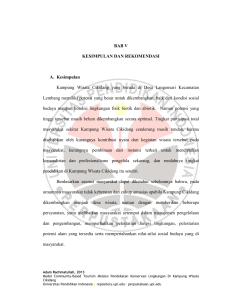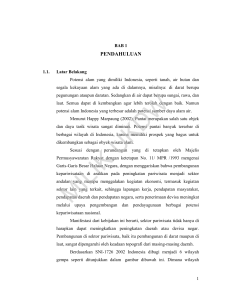CBT - ETD UGM
advertisement

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Wisata berbasis masyarakat atau sering disebut dengan Community Based Tourism (CBT) tengah menjadi tren dalam industri pariwisata. Berakar pada perspektif wisata masyarakat (community tourism perspective), konsep pembangunan wisata yang sifatnya bottom up tersebut menjadi salah satu antitesis dari model wisata top down (sentralistik) yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi income dan menguntungkan kalangan tertentu. CBT merupakan model alternatif pembangunan dan pengelolaan wisata yang mampu memberikan output maupun outcome positif karena berbasis pada kesadaran akan kebutuhan wisata responsif dan demokratis (Moscardo, 2008: 60). Artinya CBT berakar pada kesadaran kebutuhan dan partisipasi masyarakat lokal, yang kemudian dikelola dengan menggunakan asas demokrasi (dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat). Model pariwisata berbasis masyarakat juga didukung dengan adanya UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan program Kementrian Perdagangan dan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjadikan sektor pariwisata sebagai basis program ekonomi kreatif dengan menekankan pada kreativitas produk lokal dan keadilan. Salah satu contoh yang paling kentara dan beberapa tahun ini adalah Desa Wisata. Desa Wisata adalah Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang menampilkan produk kearifan lokal masyarakat seperti tradisi, tempat bersejarah, legenda, hingga produk kerajinan (Kompas, 18 September 2014). 1 Wisata berbasis masyarakat ternyata tidak hanya identik dengan Desa Wisata yang selama ini menjadi contoh umum, melainkan juga telah menjadi acuan dalam pengelolaan wisata pascabencana yang ditujukan sebagai sarana keluar dari krisis. Salah satu fenomena yang menarik adalah tentang Wisata Erupsi Merapi yang muncul pascabencana erupsi tahun 2010 lalu, khususnya di Umbulharjo. Kendati bencana telah memporakporandakan berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik; ternyata bencana justru menjadi magnet bagi kalangan masyarakat luar Cangkringan. Pemandangan sisa-sisa bencana seperti puingpuing rumah atau perkakas rumah tangga, bangkai kendaraan, bangkai hewan ternak, dan material erupsi yang terbawa aliran lahar menjadi objek serta daya tarik bagi banyak orang.1 Kuantitas pengunjung yang datang untuk melihat objek sisa bencana ditaksir mencapai ribuan setiap harinya. Sementara pada situasi demikian sebagian besar warga masih berada di tempat pengungsian dan hidup dalam ketidakpastian. Banyaknya pengunjung yang datang untuk pemandangan pascaerupsi ternyata menjadi setitik asa bagi masyarakat lokal untuk membangun kembali kehidupan pascaerupsi, di mana mereka kehilangan harta benda untuk melanjutkan hidup. Upaya yang ditempuh adalah dengan memanfaatkannya melalui kegiatan wisata bencana dengan 1 Oleh Heddy Shri Ahimsa disebut sebagai wisata bencana (Etnowisata Bencana: Kajian Wisata Lereng Merapi (lihat Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Vol IV No. 5 Tahun 2012), sedangkan Lenon dan Foley menyebutnya dengan dark tourism yaitu wisata yang menyajikan atraksi kematian, kekejaman, dan bencana yang sering dianggap tidak lumrah (John Lenon dan Malcolm Fooley,”Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster.” (International Journal of Tourism Research Vol.4 No.6 Tahun 2002). 2 melibatkan segenap masyarakat sekitar yang notabene menjadi korban dari bencana erupsi.2 Pada fenomena Wisata Erupsi Merapi, partisipasi masyarakat lokal cukup signifikan dalam aktivitas pariwisata yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo kemudian dikenal dengan Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat.3 Wisata tersebut dikelola masyarakat sekaligus ditujukan sebagai sarana bagi pemulihan ekonomi masyarakat yang lumpuh akibat bencana. Realitas tersebut seperti yang disampaikan oleh Wilkinson, Oliver Smith, dan Bankof (dalam Calgaro dan Lloyd, 2008: 288) bahwa wisata sebenarnya mampu menjadi sumber penghidupan alternatif atau harapan baru dalam situasi fragmentasi ekonomi, sumber alam yang terbatas, ketidakseimbangan pasar, dan keterbatasan opsi penghidupan lainnya. Bahkan pariwisata juga memiliki kapasitas untuk menstimulasi pembangunan yang dapat memberikan efek positif seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo juga dapat dipandang sebagai sumber alternatif penghidupan dalam situasi krisis pascabencana, yang mana sumber kehidupan masyarakat seperti peternakan dan pertanian vakum akibat erupsi. Dengan kata lain, wisata 2 3 erupsi menjadi harapan bagi kehidupan masyarakat lokal I Made Asdhiana. “Wisata Erupsi, Geliat Baru Merapi.” Kompas,Rabu 5 Januari 2011. Diakses melalui http://travel.kompas.com/read/2011/01/05/08412332/Wisata.Erupsi..Geliat.Baru.Merapi pada tanggal 14 Agustus 2014 Pukul 6.25 WIB. Berdasarkan hasil penelitian Retnaningtyas Susanti tentang Pengembangan Atraksi Wisata Jelajah Kinahrejo Berbasis Komunitas. Masyarakat lokal berupaya mengembangkan atraksi wisata pasca bencana tersebut agar menjadi destinasi berkelanjutan. 3 pascabencana, sehingga mereka berupaya memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membangun dan mengelolanya sebagai wisata berbasis masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo tidak muncul dan tumbuh dalam ruang yang vakum dan normal. Maksudnya wisata tersebut muncul dan berkembang pada situasi krisis pascaerupsi, yang mana tatanan sosial termasuk pemerintahan mengalami gangguan, masyarakat kehilangan sumber daya ekonominya, bahkan sebagian masyarakat masih berstatus sebagai pengungsi. Secara umum masyarakat yang terdampak bencana besar seperti kasus Bencana Erupsi Merapi tahun 2010 pasti mengalami situasi krisis secara ekonomi maupun psikologis. Krisis secara ekonomi dapat dari kerugian materiil yang dialami, sehingga tidak memiliki sumber daya atau modal untuk melanjutkan hidup. Menurut Koentjoro dan Budi (dalam Jurnal Unisia No. 63/XXX/I/2007) pada kondisi demikian maka mereka dapat dikatakan menderita kemiskinan karena kehilangan sumber penghidupan dan ketiadaan modal. Sedangkan secara psikologis mereka masih diliputi kesedihan, rasa takut, dan ketidakberdayaan karena kehilangan anggota keluarga dan harta benda. Masyarakat lokal secara mayoritas juga belum atau tidak memiliki kemampuan manajerial wisata, walaupun wilayah Umbulharjo sebelumnya telah menjadi destinasi wisata. Hal itu disebabkan jenis wisata sebelumnya berbeda dengan wisata yang muncul pascabencana tahun 2010 karena pengelolaannya secara dominan berada pada wewenang lembaga milik pemerintah yaitu Dinas Pariwisata. Kondisi demikian juga dihadapkan pada 4 ketiadaan dukungan materiil memadai dari pemerintah terkait terhadap pembangunan Wisata Erupsi Merapi 2010, dengan alasan bahwa lahan wisata tersebut berada pada daerah rawan bencana. Namun, sesuatu yang kontras justru terjadi. Dalam waktu yang relatif singkat Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo muncul, tumbuh, dan menjadi sarana pembangkit ekonomi masyarakat setempat. Bahkan hanya dalam hitungan tidak lebih dari 2 bulan setelah bencana pertumbuhannya cukup terasa. Geliat aktivitas wisata tersebut bukan hanya dari jumlah pengunjung yang signifikan melainkan juga adanya pengelolaan secara terorganisir mulai dari pengelolaan tiket masuk, tarif parkir, pemanduan bagi wisatawan, dan pengelolaan usaha niaga yang dikoordinir oleh institusi lokal yang bergerak di bidang pelayanan wisata. Di samping itu terdapat fasilitasfasilitas yang mendukung aktivitas pengunjung seperti pos informasi, tempat sampah di beberapa titik, papan-papan petunjuk, dan sarana ibadah. Oleh karena itu, pada proses kemunculan Wisata Erupsi Merapi sebagai salah satu solusi untuk keluar dari krisis pascaerupsi tahun 2010 di Umbulharjo tidak terlepas dari faktor pendorong lain, disamping faktor kuantitas pengunjung. Apalagi, wisata erupsi tersebut dipandang sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari kondisi krisis pascaerupsi (recovery). Faktor pendorong tersebut bisa jadi merupakan intangible capital, yang kemudian sering diasosiasikan dengan modal sosial. Namun juga bisa mengarah pada hal lain seperti adanya inisiator yang memobilisasi masyarakat korban bencana di Umbulharjo dalam aktivitas wisata atau 5 semacamnya. Asumsi tersebut merujuk dari kurun waktu munculnya Wisata Erupsi dan kondisi masyarakat yang masih berada dalam situasi krisis, sehingga apabila tidak ada faktor apa pun seperti modal sosial atau inisiator sosial tentu hal demikian sulit untuk dilakukan. Bahkan pariwisata berbasis masyarakat yang menekankan pada partisipasi dan kerja sama juga sulit dimanifestasikan di wilayah Umbulharjo. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini berusaha menelusuri mekanisme-mekanisme yang dilakukan dalam memanfaatkan peluang wisata bencana di Umbulharjo Cangkringan, yang mana wisata merupakan sarana keluar dari krisis pascaerupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melihat faktor pendorong atau pemicu progresifnya Wisata Erupsi di Umbulharjo, baik itu adanya inisiator yang mendorong pertumbuhan wisata maupun intangible capital (modal sosial). 1.2 Rumusan Masalah Pariwisata berbasis masyarakat atau CBT tengah menjadi tren dalam industri pariwisata di Indonesia. CBT merupakan model alternatif dari pembangunan wisata top down. Belakangan ini muncul berbagai destinasi wisata yang tumbuh dari kekuatan lokal, dan salah satu contoh populer adalah desa wisata. Namun, CBT ternyata tidak hanya menggeliat pada jenis objek desa wisata melainkan juga wisata yang muncul pascabencana. Wisata pascabencana seperti Wisata Erupsi Merapi merupakan fenomena baru dan unik dalam isu kepariwisataan karena menampilkan atraksi jejak erupsi sebagai daya tarik. 6 Wisata Erupsi Merapi muncul pada situasi krisis. Oleh karena itu, menjadi suatu sumber yang dikelola oleh masyarakat lokal guna membangun kembali kehidupan sosial ekonominya atau keluar dari krisis. Merunut pada permasalahan itu maka penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana upaya masyarakat Umbulharjo untuk keluar krisis pascaerupsi Merapi 2010 dengan memanfaatkan wisata bencana? 1.3 Tujuan Penelitian Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 1.3.1 Mengidentifikasi eksistensi inisiator dalam menginsiasi pemanfaatan wisata bencana di Umbulharjo sebagai jalan untuk keluar dari krisis 1.3.2 Mengetahui partisipasi kolektif masyarakat korban bencana di Umbulharjo dalam pemanfaatan wisata bencana 1.3.3 Mengidentifikasi modal sosial dalam proses pemanfataan wisata bencana. 1.4 Manfaat Penelitian Suatu penelitian akan berharga jika memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti tetapi juga pihak lain. Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain: 1.4.1 Manfaat Akademik Secara akademik penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang insiasi tokoh lokal yang mendorong masyarakat korban bencana untuk berupaya keluar dari krisis melalui pemanfaatan wisata bencana secara bersama-sama, yang mana proses itu juga didukung oleh adanya modal sosial (intangible asset). 7 1.4.2 Manfaat praktis Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat atau lembaga pemerintahan terkait konsep pengelolaan wisata pascabencana dalam prinsip social entrepreneurship sebagai salah satu solusi keluar dari krisis. Termasuk pemanfaatan intangible asset (modal sosial). 1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu Ada beberapa penelitian yang sebelumnya mencoba mengkaji tentang Wisata Erupsi Merapi. Pertama mengenai Pengembangan Atraksi Wisata Jelajah Kinahrejo Berbasis Komunitas yang dilakukan oleh Retnaningtyas Susanti pada tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh komunitas Kinahrejo dalam mengembangkan atraksi wisata Jelajah Kinahrejo, mekanisme partisipasi dan pengelolaan wisata, dan keberlanjutan wisata di Kinahrejo dalam segi ekonomi, lingkungan, dan sosial politik. Kedua, Strategi Pemulihan Penghidupan Masyarakat (Livelihood) melalui Usaha Ekowisata Volcano Tour Pascabencana Erupsi Merapi oleh Narulita Ayu Sri Kharismawanti tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan perubahan aset hidup masyarakat pascaerupsi. Kemudian Ekowisata Volcano Tour telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuka usaha (berdagang, jasa ojek, trail, dan sebagainya) sehingga memberikan perubahan terhadap aktivitas atau perkerjaan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sekian tahun berjalan, wisata justru semakin menurun sehingga memerlukan perubahan strategi dalam mempertahankan penghidupan. Perubahan strategi lebih mengarah pada upaya mengatasi 8 berkurangnya pendapatan karena menurunnya pengunjung yaitu dengan promosi dan pengembangan fasilitas. Ketiga, Pariwisata Pascabencana (Kajian Etnosains Pariwisata di Kampung Kinahrejo Umbulharjo Sleman) oleh Mona Erythrea N. Islami tahun 2014. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan warga Kinahrejo, pengelola wisata Volcano Tour, dan Dinas Pariwisata Sleman terkait kawasan Kinahrejo pascabencana. Bagi warga dan pengelola Volcano Tour, daerah Kinahrejo merupakan lahan penghidupan baru yang harus dijaga demi keberlangsungan ekonomi, sedangkan Dinas Pariwisata Sleman berpandangan bahwa Kinahrejo adalah daerah rawan sehingga tidak diperkenankan untuk membuat bangunan permanen dan akitivitas massal. Penelitian ini juga mendekripsikan upaya pengembangan atraksi dan fasilitas wisata yang dilakukan masyarakat setempat, serta pengembangan SDM oleh Dinas Pariwisata. Ketiga penelitian di atas melihat secara deskriptif tentang wisata bencana yaitu terkait livehood, argumentasi terkait adanya wisata, dan pengembangan wisata. Ketiganya menjadi landasan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai konteks kebencanaan dan wisata erupsi di Umbulharjo. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk mengeksplorasi inisiasi keluar dari kondisi krisis dengan memanfaatkan atraksi pascaerupsi menjadi wisata. Pemanfaatan tersebut berupa pengelolaan wisata seperti tiket dan parkir, maupun bisnis niaga di kawasan wisata yang dikelola secara kolektif melalui institusi lokal dan dibentuk pascaerupsi seperti Tim Volcano Tour dan Paguyuban Kinahrejo. 9 Pada masalah ini perlu ditekankan kembali bahwa ketika itu masyarakat lokal masih berada pada situasi krisis akibat bencana, baik itu kerugian materiil maupun kehilangan sanak saudara. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan yang mumpuni tentang manajemen wisata (human capital) atau usaha bisnis wisata. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengekplorasi bagaimana praktik pengelolaan dan usaha wisata dapat berjalan dalam kondisi demikian. Peneliti kemudian berusaha menelusuri peranan intangible asset dalam proses pembentukan institusi pengelolaan maupun usaha wisata tersebut. Intangible asset sering diasosiasikan dengan modal sosial yang sejatinya tersedia dalam kehidupan masyarakat, tetapi sering tidak disadari keberadaannya sebagai modal. Modal sosial menjadi perhatian karena upaya keluar dari krisis melalui pemanfaatan wisata bencana tidak bisa muncul begitu saja jika hanya mengandalkan modal fisik. Di samping itu, peneliti juga mencoba melihat indikasi inisiator yang berperan dalam menggerakkan ide pengelolaan wisata atau usaha wisata. Inisiator dalam hal ini tidak hanya memiliki kejelian menangkap peluang dan merancang pengelolaan wisata, melainkan juga memanfaatkan kapasitas modal sosial sebagai kekuatan untuk menggerakkan aktivitas pariwisata. 1.6 Landasan Teori Teori merupakan instrumen atau piranti untuk menganalisis temuan lapangan. Penelitian menggunakan beberapa teori yang dapat membantu dalam menganalisis data yang diperoleh. Beberapa teori tersebut antara lain kajian tentang pariwisata, social entrepeneurship (kewirausahaan sosial), dan modal 10 sosial. Kajian tentang pariwisata menjadi introduksi untuk menjelaskan tentang fenomena wisata, sedangkan social entrepeneurship dan modal sosial menjadi instrumen untuk menganalisis tentang upaya masyarakat untuk keluar dari krisis melalui pengelolaan wisata. 1.6.1 Tinjauan tentang Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu program pembangunan ekonomi yang telah memberikan sumbangsih terhadap kehidupan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Sebelum sampai pada penjelasan lanjut, perlu mengulas esensi mengenai pariwisata. Ada banyak definisi tentang pariwisata, namun secara khusus Murphy (dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 45) mendefinisikan pariwisata sebagai: keseluruhan dari elemen-elemen (terkait wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan sebagainya) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata; sepanjang perjalanan wisata tersebut tidak permanen. Selain itu, World Tourism Organization (dalam Muljadi, 2010: 9) mendefinisikan, tourism comprises the activity of person travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purpose. Penjelasan definisi tersebut mirip dengan yang diungkapkan oleh Murphy pada pemaparan sebelumya. Mills (dalam Bra Baskoro, 2010: 26-27) memaparkan bahwa ada 4 dimensi pariwisata yang menyebabkan orang menjadi tertarik untuk melakukan perjalanan wisata. Dimensi-dimensi itulah yang kemudian 11 menjadi perhatian dalam pembangunan dan pengelolaan wisata, yaitu atraksi, fasilitas, transportasi, dan keramahtamahan (sapta pesona). 1.6.2 Wisata Bencana Istilah wisata bencana memang dianggap tidak etis karena berlawan dengan kata wisata yang selalu diidentikkan dengan aktivitas hiburan dan bersenang-senang. Namun, istilah tersebut muncul seiring fenomena banyaknya kunjungan pada lokasi terdampak erupsi pascaerupsi tahun 2010 (Ahimsa, 2012: 140). Fenomena wisata bencana oleh Lenon dan Foley disebut dengan dark tourism. Dark tourism adalah wisata yang menyajikan suasana mencekam. Salah satunya bencana yang memberikan dampak seperti kematian dan kerusakan fasilitas hidup masyarakat4. Hal itu seperti yang terlihat pascaerupsi Merapi tahun 2010, yang mana pemandangan kerusakan pascaerupsi menjadi daya tarik. Dark Tourism menurut Lenon dan Foley menjadi begitu terkenal karena adanya media atau pemberitaan (dalam International Journal of Tourism Research Vol.4 No.6 Tahun 2002). Geliat wisata erupsi juga muncul karena seiring dengan merebaknya pemberitaan dan siaran visual mengenai dampak erupsi Merapi. Oleh karena itu, bencana yang sebenarnya menjadi fenomena biasa di Indonesia justru menjadi terkenal dan menarik rasa penasaran masyarakat untuk melihat langsung. Uniknya 4 International Journal of Tourism Research Vol.4 No.6 Tahun 2002, hlm: 485. 12 lagi wisata bencana tersebut justru menjadi peluang atau solusi bagi masyarakat untuk keluar dari krisis pascaerupsi, khususnya di Umbulharjo. 1.6.3 Wisata Berbasis Masyarakat Semangat wisata berbasis masyarakat secara eksplisit termuat dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata pasal 2 bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan serta kesatuan. Di samping itu pemerintah juga menggencarkan wisata berbasis lokal menjadi ikon pembangunan dalam program ekonomi kreatif berbasis pariwisata. 5 Merujuk pada proses kemunculan dan pengelolaan Wisata Erupsi Merapi, hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan masyarakat lokal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo Cangkringan merupakan salah satu sarana bagi masyarakat memperoleh income guna membantu pemulihan kehidupan pascabencana (Kharismawanti, 2014). Dengan demikian, wisata tersebut tumbuh berbasis pada masyarakat yang notabene menjadi korban bencana, dan dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Pimrawe Rocharungsat (dalam Moscardo, 2008: 67) menguraikan bahwa pariwisata berbasis masyarakat secara umum berfondasi pada kesadaran responsif terhadap wisata dan menekankan asas partisipasi 5 Program ekonomi kreatif berbasis pariwisata merupakan upaya pemerintah memacu masyarakat dengan memanfaatkan segala macam sumber potensial lokal menjadi produk wisata berdasarkan kearifan lokal. Namun, keberlanjutan wisata tersebut perlu didukung oleh etika keadilan yaitu berbasis pada masyarakat lokal (Kompas, 18 September 2014). 13 demokratis dalam penentuan kebijakan wisata oleh masyarakat lokal. Artinya masyarakat lokal merupakan aktor utama yang terlibat aktif dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikain, masyarakat menjadi host/tuan rumah6 dari proyek pariwisata. Dengan penjabaran yang lebih sederhana Argyo Dermatoto (Dermatoto dkk, 2009: 22) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan wisata yang dibangun dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Proses-proses yang dilalui dalam sistem wisata berbasis masyarakat akar rumput tersebut meliputi perencanaan investasi, pengelaksaan, pengelolaan, dan evaluasi. Kendati demikian, peran pemerintah atau swasta juga diperlukan, bukan untuk mendominasi melainkan sekedar memberikan dukungan. 1.6.4 Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Istilah social entrepreneurship/kewirausahaan sosial belum begitu populer di Indonesia. Namun, kewirausahaan sosial merupakan fenomena menarik karena melihat sisi sosial dari suatu kewirausahaan yang selama ini diidentikkan dengan paradigma ekonomis dan cenderung berorientasi pada profit. Konsep kewirausahaan sosial hadir dengan memberikan paradigma baru bahwa kewirausahaan sebagai sarana atau cara untuk mengatasi 6 Istilah host/tuan rumah ditekankan Murphy dalam CBT. Sebagai host, masyarakat adalah pihak yang paling tahu tentang potensi wilayahnya. Mereka punya keinginan, wewenang/hak, dan usaha untuk membangun dan mengembangkannya tanpa mengabaikan kondisi kearifan lokal dan kelestarian alam, sebab segala bentuk konsekuensi secara langsung akan menjadi tanggungan masyarakat. Pada istilah ini masyarakat memiliki rasa ikut memiliki (sense of belonging). Dengan arti bukan memiliki mutlak secara de jure, melainkan rasa memiliki dengan kesadaran untuk menjaga keberlanjutannya (dalam Sunaryo. 2013: 140). 14 masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan akses, dan sebagainya (Perrini dan Vurro dalam Mair dkk, 2006). Salah satu contoh fenomenal yang menjadi kajian dari kewirausahaan sosial adalah Grameen Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Grameen Bank merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan akses wanita untuk memperoleh kredit mikro dengan bunga lunak. Kewirausahaan sosial dengan pendekatan komunitas diuraikan oleh David Bornstein dengan mengkaji beberapa program kewirausahaan sosial berbagai negara. Salah satunya adalah program penyediaan listrik bagi masyarakat distrik Palmares di Negara bagian Rio Grande do Soul Brasil yang diinisiasi oleh Rosa (Bornstein, 2006). Listrik murah menjadi keperluan penting bagi para petani di Palmares guna mengalirkan air tanah ke lahan pertanian. Berdasarkan hal itu, Rosa mencoba membuat terobosan teknologi Amaral dan melibatkan masyarakat petani dalam proses pembangunan dan pengelolaannya, termasuk kredit bagi petani yang memerlukan dana untuk mengolah sawah. Terilhami dari teori Bornstein maka kewirausahaan sosial menjadi rujukan penelitian ini untuk melihat fenomena wisata bencana berbasis masyarakat yang muncul pascaerupsi tahun 2010 di Umbulharjo. Hal itu dikarenakan wisata bencana merupakan sarana bagi masyarakat setempat dalam mengatasi krisis seperti hilangnya berpengaruh dan pada aktivitas 15 sumber penghidupan yang penghasilan masyarakat, serta ketidakjelasan mengenai nasib mereka selanjutnya. Alasan lainnya merujuk pada kondisi masyarakat lokal yang sebagian besar memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan wisata tetapi mampu bekerja sama untuk melakukan pengelolaan. Oleh karena itu, social capital bukanlah modal tunggal yang cukup untuk merintis wisata pascabencana melainkan juga adanya inisiator yang memiliki kemampuan dalam menangkap peluang dan menggerakkan warga korban erupsi. a. Sejarah Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial). Sebelum mengulas konsep, perlu melihat historisitas kewirausahaan sosial. Istilah kewirausahaan sosial pertama kali muncul tahun 1771 di Inggris ketika Robert Owen mendirikan koperasi dan usaha tekstil untuk mengatasi masalah ekploitasi tenaga kerja anak-anak di pabrik tekstil. Ia membeli sebuah pabrik tekstil dan memperkerjakan anak-anak usia sekolah tetapi mengubah sistem kerjanya. Anak-anak bekerja ke pabrik seusai sekolah, sehingga mereka hanya bekerja paruh waktu. Hasil dari usahanya dari memperkerjaan orang-orang sekitar dan tenaga paruh waktu anak-anak, dialokasikan untuk membangun fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan (dalam Dewanto dkk, 2013: 3). Kendati model kewirausahaan sosial telah muncul pada abad 18 di Inggris, namun istilah tersebut baru mencuat dan menjadi kajian ilmu sosial setelah diperkenalkan oleh Bill Drayton melalui karyanya tahun 1980 yaitu Ashoka Foundation. Asoka Foundation didirikan dengan tujuan memberikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat miskin. 16 Karena usaha sosial tersebut, Bill Drayton mendapat penghargaan Mac Arthur Award. Istilah kewirausahaan sosial semakin mencuat ketika Muhammad Yunus mendirikan Grameen Bank, bank rakyat yang memberikan kredit mikro dengan bunga lunak kepada para wanita miskin di Bangladesh untuk membangun usaha mikro (dalam Dewanto dkk, 2013: 43-44). b. Ruang Lingkup Social Entrepreneurship 1) Definisi Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial). Kewirausahaan sosial berbeda dengan bisnis kewirausahaan pada umumnya yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi profit. Karena tidak bertendensi pada profit, banyak yang menganggap bahwa social entrepreneurship merupakan lembaga nirlaba. Padahal tidak sepenuhnya demikian. Perrini dan Vurro (dalam Mair dkk, 2006: 64) menegaskan bahwa kewirausahaan sosial berbeda dengan lembaga nirlaba kebanyakan yang cenderung bersifat charity seperti menghimpun dana dari para filantropi dan sebatas memberikan dana bantuan secara pragmatis tanpa melibatkan peran dari orang-orang yang dibantu sehingga justru sering menimbulkan sikap pasif dan ketergantungan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial bukan lembaga/organisasi yang semata-mata mencari untung atau pun lembaga donor, melainkan merupakan sintesa dari keduanya dengan memberdayakan orang-orang yang dibantu ke dalam proses perintisan maupun pengelolaan usaha sosial. 17 Mc Leod dan beberapa ahli lainnya (dalam Mair dkk, 2006: 62) mendefinisikan social entrepreneurship sebagai inovasi masa kini melalui pemfungsian usaha sosial dan memuat subtansi kompetensi manajerial, serta tindakan berbasis pasar dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kewirausahaan sosial dilihat sebagai paket strategis dalam merespon berbagai macam guncangan lingkungan dan tantangan situasional yang terwujud dalam organisasi non-profit masa kini.7 Oleh sebab itu, kewirausahaan sosial dipandang sebagai manifestasi usaha sosial masa kini yang berupaya merespon masalah sosial dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Profit dalam social entepreneurship bukan sebagai tujuan akhir, namun sebagai pencapai misi sosial (Perrini dan Vurro dalam Mair dkk, 2006: 60). Saifan memberikan 2 batasan untuk mendefinisikan kewirausahaan sosial sebagai berikut (Saifan, 2012). a) Non-Profit with Earned Income Strategies Usaha sosial dilakukan dengan mencangkokkan aktivitas kewirausahaan secara sosial maupun komersial untuk mencapai kecukupan. Dalam skema ini, wirausahawan sosial mengoperasikan organisasi secara sosial dan komersial, yang 7 Organisasi non profit masa kini meninggalkan label charity yang kental dengan fungsi penghimpun dan penyalur dana dari filantropi dan mengubah mekanisme tradisonal dengan langkah transformatif seperti inovasi sosial dan pemberdayaan komunitas lokal dalam perintisan serta pengelolaan usaha sosial. 18 mana hasil dan keuntungan digunakan untuk memajukan penyebaran nilai sosial dan mereduksi masalah sosial.8 b) For Profit with Mission-Driven Strategies Bisnis sosial dan komersial dilakukan secara bersamaan untuk mencapai keberlanjutan. Organisasi mandiri secara finansial dan memperoleh keuntungan secara berlanjut karena adanya tujuan sosial dalam jangka panjang. Pada skema ini, penggagas atau investor turut memperoleh keuntungan. Uraian Saifan senada dengan David Bornstein, bahwa kewirausahaan sosial berfondasi pada etika (dorongan moral), dan uang adalah sarana untuk mencapai misi sosial. Hal demikian yang membedakan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan bisnis pada umumnya. Pernyataan tersebut merupakan ulasan teoritik Bornstein yang didapatkan melalui perbincangan dengan Fabio Rosa, seorang wirausahawan sosial Brasil yang berupaya memberikan perubahan sosial progresif pada kehidupan masyarakat desa terpencil melalui pengadaan listrik. “Tentang uang-saya perlu uang. Uang sangat penting untuk menyelesaikan proyek-proyek saya. Tetapi uang hanya berarti jika membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat dan menciptakan dunia baru, yaitu dunia yang harmonis tanpa kesengsaraan dan orang-orang menjadi kuat karena persahabatan dan kerja sama.” (dalam Bornstein, 2006: 279-280) 2) Inovasi Sosial dalam Social Entrepreneurship 8 Masalah sosial meliputi rendahnya kesejahteraan, masalah kosehivitas, keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan informasi, dan pembangunan masyarakat (Perrini dan Vurro dalam Mair dkk, 2013: 59). 19 Seperti yang dijelaskan pada bagian awal bahwa kewirausahaan sosial merupakan wujud dari usaha inovatif masa kini yang berupaya merespon masalah sosial. Oleh karena itu, inovasi menjadi bahan penting untuk menggerakan usaha. Hal tersebut digarisbawahi oleh Bruyat dan Julien (dalam Mair dkk, 2006: 63) bahwa inovasi secara intrinsik bertalian dengan kewirausahaan. Oleh karena itu ia menguraikan bahwa kemampuan inisiator (penggerak social entrepreneurship) dalam menciptakan sebuah produk baru melalui proses keahlian yang bersifat nirlaba merupakan inovasi. Inovasi pada konteks ini adalah untuk kemaslahatan sosial, sehingga disebut dengan inovasi sosial. Inovasi sosial tersebut dapat berupa proses, produk, maupun prinsip, ide, kebijakan, intervensi, gerakan sosial atau beberapa kombinasi dari semuanya (Phill dalam Dewanto dkk. 2013: 8). Sementara itu, Standford Graduate School Business (dalam Dewanto dkk, 2013: 11-12) menjabarkan bahwa inovasi sosial merupakan proses menemukan dan mengimplementasikan solusi baru atas permasalahan sosial, serta menjamin kesesuaian solusi tersebut dengan kebutuhan masyarakat. c. Wirausahawan Sosial dalam Social Entrepreneurship Berbicara mengenai gagasan kewirausahaan sosial tentu juga membahas mengenai sosok penggerak atau inisiator. Hal demikian ditegaskan oleh David Bornstein (Bornstein, 2006: 107) bahwa gagasan seperti layaknya sebuah pertunjukan drama yang keberhasilannya membutuhkan seorang 20 produser dan promotor yang baik. Jika tidak, drama tidak akan bergerak dari arus pinggiran ke arus utama atau bahkan tidak dapat dipertunjukkan sama sekali, sehingga gagasan harus dipasarkan dengan mahir sebelum benar-benar mengubah pemahaman dan perilaku orang. Oleh karena itu penggerak dalam gagasan kewirausahaan menjadi titik sentral yang disebut dengan wirausahawan sosial (social entrepreneur). Wirausahawan sosial merupakan pelopor inovasi (inisiator) yang dilihat dari kualitas dalam merancang ide kewirausahaan, kecerdasan membangun kapasitas, dan kemampuannya dalam mendemonstrasikan secara konkret kualitas ide dan prakiraan dampak sosial atas upaya kewirausahaan yang dilakukan (Perrini dan Vurro dalam Mair dkk, 2006: 69). Ide yang hadir dalam pemikiran wirausahawan sosial bukan sebatas pada realitas kelangkaan yang terjadi dalam masyarakat, melainkan juga mampu melihat ruang sempit atau hal kecil yang sering dianggap tidak mungkin atau useless menjadi peluang. Pada konteks ini, wirausahawan sosial sekaligus berperan dalam membentuk mindset baru kepada masyarakat yang dimobilisasi bahwa pada dasarnya manusia memiliki kapasitas atau kompetensi kendati dari kacamata mainstream dipandang tidak kompenten atau berdaya (Bornstein, 2010: 76). Inovasi dari wirausahawan sosial juga didorong oleh hasrat untuk menciptakan perubahan sosial progresif melalui proyek kewirausahaan. Artinya inovasi sosial yang muncul dari gagasan 21 insiator, salah satunya karena didorong oleh keinginan untuk mengentaskan masyarakat dari permasalahan sosial. Tindak lanjut dari inovasi dan hasrat sosial tersebut adalah penuangan gagasan (visi dan misi) dan skema konkret yang hendak dilakukan (lihat gambar 1.1). Gambar 1.1 Skema Inovasi dalam Social Entrepreneurship Repon dengan membuat portofolio (penuangan gagasan dan rancangan usaha) untuk mengatasi problem sosial (misi sosial) Stimulan berupa problem sosial dan hasrat untuk mengatasi dan mencapai perubahan sosial d. Proses Kewirausahaan Sosial Kendati bukan merupakan lembaga komersial murni, prinsip entrepreneurship turut dipakai dalam kewirausahaan sosial. Pertama yang dilakukan adalah menentukan secara jelas misi sosial dan identifikasi peluang. Misi merupakan hasil dari kolaborasi inovasi, kecakapan diri, dan ekspektasi terhadap outcome (luaran atau efek). Sementara identifikasi atau penangkapan peluang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor krisis dan visi. Seperti yang digambarkan sebelumnya (gambar 1.1) bahwa respon wirausahawan sosial atas peluang didorong oleh adanya problem sosial (krisis) dan hasrat terhadap perubahan sosial (visi). Misi dan peluang untuk memenuhi kebutuhan sosial diformulasikan ke dalam sebuah inovasi konkret yang biasanya dilihat dari 4 dimensi yaitu produk/jasa, relasi, metode-metode, dan faktorfaktor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kewirausahaan sosial 22 menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat lokal yang notabene merupakan sasaran kewirausahaan sosial didayakan untuk menjalankan usaha sosial. Hal demikian ditekankan oleh Bornstein bahwa perlu mendayagunakan komunitas lokal karena sesungguhnya masyarakat yang mengalami krisis atau masalah memiliki daya atau kreatifitas. Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya dipandang sebagai objek melainkan subyek aktif untuk merealisasikan dan mengelola kewirausahaan sosial.9 Inovasi tidak akan efektif tanpa adanya model usaha atau bisnis. Model usaha dalam hal ini biasanya berorientasi pada pasar dan kebutuhan stakeholder. Hal itu dicapai melalui orientasi jaringan yang kuat, fleksibilitas organisasi, kebijakan yang melihat dimensi global dan lokal, dan manajemen partisipatoris. Model usaha tersebut secara eksplisit adalah untuk mencapai social outcome dan sebuah transformasi sosial dalam jangka panjang. Transformasi sosial dalam hal ini mencakup penciptaan pekerjaan, akses terhadap informasi maupun pengetahuan sosial, kohesi sosial, serta pengembangan ekonomi dan komunitas. Secara garis besar, proses kewirausahaan sosial tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1.2 9 Ulasan lebih jauh mengenai pemberdayaan ini dipaparkan David Bornstein dalam analisisnya mengenai sekolah komputer yang dilakukan Rodrigo Baggio (Bornstein, 2006: 181-182). 23 Kerangka Proses Kewirausahaan Sosial Proses kewirausahaan sosial olehPerrini dan Vurro (dalam Johanna Mair,dkk, 2006: 78-79) 1.6.5 Modal Sosial (Social Capital) Christenson dan Robinson (dalam Philips dan Pittman, 2009) memaparkan bahwa pembangunan masyarakat adalah social capital atau social capacity, karena menjabarkan tentang kemampuan masyarakat untuk mengatur sumber daya dan memobilisasi sumber daya guna mencapai tujuan bersama. Sumber daya pada konteks pariwisata adalah atraksi wisata sendiri yang perlu dikelola dengan kapasitas lokal (termasuk modal sosial) guna mencapai tujuan bersama. 24 Urgensi modal sosial dalam mobilisasi aktivitas pariwisata yang muncul pascabencana diuraikan oleh Idah Rosida dalam penelitiannya mengenai Desa Wisata Candran pascagempa Bantul tahun 2006. Ketika masyarakat mengalami krisis akibat bencana, modal sosial menjadi kekuatan (entry point) dalam membangun wisata pascagempa. Wisata tersebut kemudian menjadi sarana memulihkan kehidupan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang sempat krisis pascagempa tahun 2006 (Rosidah, 2014). Pemanfataan modal sosial terindikasi pula pada perintisan dan pengembangan Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo Cangkringan. Asumsi tersebut merujuk pada kondisi masyarakat yang didera krisis dan modal material sulit diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan landasan teori modal sosial sebagai instrumen untuk menganalisis proses mobilisasi warga dalam rangka mewujudkan wisata sebagai sarana bangkit dari krisis. a. Definisi Modal Sosial Modal sosial berbeda dengan modal fisik dan modal lainnya (human capital) yang nampak dan terukur. Modal sosial bersifat less tangible dan sulit diukur, seperti kepercayaan, relasi, dan semacamnya. Namun modal sosial ada dan tumbuh di masyakarakat dalam tempo yang relatif lama, sehingga kadang tidak disadari (Nurhadi dalam Agnes Sunartiningsih 2004: 73). Pengertian demikian juga disampaikan Putnam (dalam Dasgupta dan Serageldin, 2000: 18-19) bahwa modal sosial 25 berkaitan dengan adanya relasi atau hubungan yang secara tidak otomatis dilakukan setiap manusia sebagai makhluk sosial dan hal itu tidak disadari sebagai modal. Dalam konsep yang sangat luas, modal sosial merujuk pada relasi sosial antaranggota kelompok yang dapat memberikan dukungan pada kegiatan yang produktif yaitu dengan menekankan pada kepercayaan, sumber daya norma-norma, dan jaringan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah (dalam Maarif, 2011: 9). Sedangkan Coleman (dalam Nan Lin, 2003: 27-28) secara khusus mendefinisikan modal sosial dengan melihat fungsinya. Social capital is defined by its function and that, it is not a single entity, but a variety of different entities having two characteristics: they all consist of some aspect of social sctucture and they facilitate certain action of individuals who are within the structure. Pemaparan Coleman tersebut menunjukkan bahwa modal sosial bukan entitas yang tunggal, melainkan meliputi beberapa wujud. Entitas-entitas tersebut kemudian menjadi sarana bagi aktor maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan yang sifatnya produktif. b. Bentuk-bentuk Modal Sosial Seperti yang dijelaskan Coleman bahwa modal sosial bukanlah entitas tuggal tetapi terdiri dari beberapa entitas yang mampu menjadi sarana bagi tindakan produktif baik secara individual maupun kelompok. Coleman (dalam Field, 2010: 32) mengungkapkan bahwa modal sosial merupakan sumber daya melibatkan beberapa bentuk seperti kepercayaan (trust), resiprokal, jaringan-jaringan (network), serta norma 26 dan nilai (norms and value). Stephen Knack pun memiliki pandangan yang hampir sama bahwa modal sosial masyarakat meliputi nilai (common value), norma, jaringan informal, dan keanggotaan asosiasional, yang mana dimensi-dimensi tersebut memberikan pengaruh terhadap kemampuan tiap-tiap individu dalam kelompok untuk berkerja sama demi mencapai tujuan (dalam Grootaert dan Bastelaer, 2002: 42). Kendati demikian, modal sosial bersifat kontekstual. Artinya bentuk modal sosial di masing-masing tempat dapat berbeda-beda (Grootaert dan Bastelaer, 2002). Dari pemaparan tersebut setidaknya ada beberapa entitas umum yang merepresentasikan suatu modal sosial, antara lain sebagai berikut. 1) Kepercayaan Fukuyama menguraikan kepercayaan sebagai pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas dengan berperilaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma bersama demi mencapai kepentingan anggota yang lain dari komunitas tersebut. Kepercayaan tidak muncul begitu saja tetapi tumbuh melalui proses kultural. Artinya kepercayaan memang modal yang sebenarnya telah tumbuh melekat dalam kehidupan sosial. Gidden memaparkan bahwa kepercayaan tumbuh dalam berbagai lingkungan. Pada masyarakat pramodern, kepercayaan tumbuh dalam hubungan kekerabatan, komunitas lokal, kosmologi religious, dan tradisi. Sedangkan pada masyarakat modern, kepercayaan tumbuh dalam sistem abstrak, relasi 27 personal, dan orientasi masa depan (dalam Damsar dan Indrayani, 2013). Kepercayaan menjadi fondasi untuk mencapai tujuan sosial, sebab seperti pelumas yang dapat memuluskan kerja sistem sosial dan menciptakan sebuah efisiensi, serta menghadapi berbagai kendala yang mendistorsi (Fukuyama, 2002: 36-37). Demikian pula, Rafael La Porta dkk (dalam Dasgupta dan Serageldin, 2000: 311) menyatakan bahwa kepercayaan adalah entitas yang urgen dan esensial dalam suatu kerja sama. Kepercayaan yang tinggi akan memanifestasikan kerja sama yang tinggi pula. 2) Nilai dan Norma Nilai dan norma, sebab keduanya merupakan pranata sosial yang memiliki legitimasi sebagai sebuah acuan dalam bertindak. Norma sangat dipengaruhi oleh adanya nilai atau pandangan tentang baik dan buruk seperti yang disampaikan Coleman “specifiy what actions are regarded by a set of person as proper or correct, or improper or incorrect.” Berdasarkan itu, norma kemudian diekspresikan dalam bahasa formal atau informal sebagai sebuah kebijakan atau kesepakatan, sehingga semua orang yang terikat dengan norma sadar sekaligus melaksanakan tatanan norma (dalam Lubis). Nilai dan norma hadir melalui proses sosial maupun kultural. nilai dan norma juga memiliki peran sebagai pedoman dalam berperilaku, baik yang sifatnya individual maupun kolektif. Oleh 28 karena itu nilai dan norma sosial sesungguhnya merupakan aset sosial yang penting bagi masyarakat, tanpa terkecuali bagi keberadaan Wisata Erupsi Merapi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nilai dan norma menjadi patokan dalam bersikap di kehidupan seharihari, sehingga praktik nilai dan norma juga dapat mempengaruhi praktik dalam pengelolaan wisata pascabencana di Umbulharjo.Tinggal kemudian melihat nilai dan norma yang seperti apa yang berperan dalam mendukung pengelolaan Wisata Erupsi Merapi di Umbulharjo. 3) Jaringan Jaringan dilihat sebagai hubungan antar individu atau kelompok yang memiliki makna subyektif serta berhubungan dengan simpul dan ikatan. Simpul dilihat melalui aktor dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antaraktor (dalam Damsar dan Indriyani, 2013: 158). Pola jaringan sosial dapat berbentuk pertemanan, bisnis, atau perkawinan (Newman, 2003: 174). Menurut Hasbullah (Hasbullah, 2006: 10), jaringan yang terbentuk melalui hubungan relasional memiliki kapasitas atau dampak positif bagi kemajuan serta pembangunan masyarakat. Manfaat positifnya bukan hanya sebagai perekat sosial antar aktor yang terikat di dalamnya melainkan menurut Powel dan Smith juga mampu memberikan kemudahan akses modal maupun informasi (Damsar dan Indrayani, 2013: 173). Oleh karena itu, jaringan menjadi salah satu aset atau investasi yang dapat 29 dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Merujuk pada pemanfaatan dan pengelolaan wisata bencana di Umbulharjo memungkinkan adanya jalinan antarindividu maupun kelompok lain secara produktif. c. Tipe Modal Sosial Penentuan tipe modal sosial bergantung pada konteks masyarakat yang menjadi kajian. Secara umum Putnam (dalam Field, 2010: 52) membagi modal sosial menjadi dua tipe yaitu modal sosial yang mengikat (bonding social capital) dan modal sosial yang menjembatani (bridging social capital). Tipe bonding berada pada ranah yang sifatnya eksklusif seperti rukun warga dan teman akrab, sehingga homogenitas begitu kentara. Karena cenderung eksklusif maka pola hubungannya lebih berorientasi ke dalam (inward looking), sehingga perluasan jaringan yang produktif sulit tercipta (dalam Hasbullah, 2006:28). Namun, modal sosial bonding mampu menopang resiprositas spesifik, mobilisasi solidaritas, dan menjadi perekat sosial. Bridging social capital adalah tipe modal sosial yang menyatukan orang dari ranah sosial yang beragam. Modal sosial ini terbentuk dalam kelompok yang memiliki pandangan terbuka (outward looking) dan mandiri. Kemandirian juga tumbuh dari relasi atau jaringan sebagai hasil dari interaksi dengan banyak pihak di luar kelompok (Hasbullah, 2006:30). Oleh karena itu jaringan produktif yang terbentuk dapat semakin meluas. Bridging social capital mampu menghubungkan 30 aset eksternal, persebaran informasi, membangun identitas, dan hubungan timbal balik yang lebih luas (Field, 2010: 52). 1.7 Kerangka Pikir Erupsi Merapi tahun 2010 telah meluluh lantahkan sebagian wilayah Cangkringan, terutama Umbulharjo. Bencana erupsi berdampak pada rusaknya sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, erupsi telah menimbulkan krisis bagi masyarakat Umbulharjo terutama warga yang mengalami dampak langsung seperti kehilangan sanak saudara, rumah dan harta benda lainnya, serta sumber penghidupan. Masyarakat korban erupsi terpaksa menganggur, tidak memiliki sumber kehidupan, terancam miskin, serta tidak ada kejelasan mengenai nasib atau kehidupan mereka selanjutnya. Tidak hanya menimbulkan krisis sosial ekonomi, bencana erupsi juga menimbulkan dampak yang ambivalen. Bencana erupsi justru menarik animo masyarakat luar untuk datang melihat kondisi pascaerupsi di Umbulharjo sehingga mendatangkan potensi secara finansial. Namun, banyaknya animo kunjungan justru memberikan dampak laten. Respon pragmatis dari sekelompok warga lokal dengan menarik uang sukarela telah memunculkan kontravensi/ketegangan internal, sebab hanya sebagian orang yang menikmati hasilnya. Selain itu, animo masyarakat juga menarik pedagang dari luar Umbulharjo untuk membuka usaha di kawasan destinasi kunjungan. Banyaknya pedagang luar memunculkan kekhawatiran karena dapat merampas peluang warga lokal untuk memperoleh pendapatan. 31 Atraksi bencana yang menarik animo kunjungan (faktor eksternal) dan krisis pascaerupsi (faktor internal) kemudian direspon oleh tokoh lokal. Tokoh lokal sebagai inisiator berperan dalam menginisiasi pemanfaatan peluang atraksi wisata dan animo pengunjung sehingga hal itu menjadi cara atau strategi untuk keluar dari krisis pascaerupsi. Secara konkrit, upaya itu dilihat dari pembentukan lembaga kewirausahaan sosial komunitas yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan upaya-upaya keluar dari krisis. Upaya-upaya itu terutama dalam proses perintisan dan pengelolaan usaha komunitas maupun intensifikasi pengembangannya dengan melibatkan kapasitas masyarakat lokal selaku korban bencana erupsi. Aktivitas tersebut menjadi jalan bagi masyarakat untuk keluar dari krisis. Di samping hal di atas, perlu diingat kembali bahwa pemanfaatan wisata erupsi melibatkan masyarakat lokal yang menjadi korban bencana sehingga relasi-relasi produktif diperlukan. Relasi produktif tersebut terutama dilihat pada proses pembentukan lembaga kewirausahaan sosial, aktualisasi pemanfaatan wisata melalui perintisan usaha kolektif, dan intensifikasi pengembangannya juga pelu dilihat. Relasi produktif sering diasosiasikan dengan modal sosial. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa modal sosial dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas secara terarah (Grootaert dan Bastelaer. 2002: 5). Merujuk pada konteks pascaerupsi maka peran modal sosial adalah poin yang juga perlu diperhitungkan. Apalagi masyarakat Umbulharjo merupakan merupakan kelompok sosial gemeinschaft yang terikat dalam nilai kolektivitas. 32 Respon insiator terhadap krisis sosial ekonomi yang terjadi pascaerupsi melibatkan masyarakat secara kolektif dalam mekanisme kewirausahaan sosial dan didukung dengan modal sosial bertujuan untuk memberikan efek pada pengentasan masyarakat korban bencana dari krisis. Untuk memperjelas kerangka konseptual di atas maka dibuatlah gambar sebagai berikut. Gambar 1.3 Kerangka Pikir Bencana Erupsi 2010 Krisis sosial ekonomi Atraksi Wisata Erupsi Animo kunjungan masyarakat luar Cangkringan ketegangan antarwarga karena penarikan sumbangan kepada pengunjung merebaknya pedangang dari luar Respon Insiator (Social entrepreneur) Pembentukan lembaga kewirausahaan sosial Perintisan Usaha Secara Kolektif Intensifikasi Kewirausahaan Keluar dari krisis pascaerupsi Sumber: pemikiran peneliti, 2015. 33 Modal Sosial 1.8 Metode Penelitian 1.8.1 Lokasi Penelitian Lokus penelitian adalah Wisata Erupsi Merapi (Merapi Volcano Tour) di Umbulharjo. Wisata Erupsi Merapi muncul secara darurat yang menawarkan atraksi dan panorama pascaerupsi Merapi tahun 2010. Wisata Erupsi Merapi melibatkan peran serta masyarakat lokal yang notabene korban dari bencana erupsi dan menjadi sarana untuk mengentaskan masyarakat dari krisis. 1.8.2 Waktu Penelitian Proses penyusunan laporan penelitian dilakukan selama beberapa bulan mulai awal sampai dengan akhir. Pada bulan Agustus penulis mulai menyusun proposal. Kendati demikian, pada proses tersebut penulis juga mulai melakukan observasi awal di lokasi penelitian. Penelitian atau pengumpulan data secara intens dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2014. 1.8.3 Metode Berkaitan dengan topik yang diangkat maka bentuk penelitian yang digunakan adalah metode etnografi. Penelitian etnografi berusaha untuk mendapatkan data secara holistik terkait dengan sejarah, budaya (di dalamnya memuat nilai-nilai lokal), program pada suatu komunitas/kelompok masyarakat (Fetterman, 2010: 11). Etnografi berakar dari semangat eksplorasi terhadap suatu setting penelitian dan lekat dengan metode observasi partisipatoris (Atkinson, 2007: 5). Dengan demikian, 34 metode etnografi digunakan untuk menggali secara holistik mengenai inisiasi terhadap masyarakat Umbulharjo Cangkringan dalam upaya keluar dari krisis melalui pemanfaatan wisata erupsi, yang komudian fokus pada proses pemanfaatan wisata. 1.8.4 Penentuan Unit Penelitian Penentuan unit penelitian menggunakan teknik snowball yaitu teknik pengambilan informan yang awalnya bersumber pada satu orang dan lamalama jumlahnya menjadi besar dan luas. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan akurat (dalam Sugiyono, 2009: 219). Awalnya peneliti menentukan informan awal yang akan menjadi narasumber kunci yaitu perintis wisata Volcano Tour bernama Nartukiyo. Informan awal merupakan orang yang memang benar-benar memiliki informasi lengkap terkait wisata dan usaha pengembangannya. Informan pertama menjadi acuan untuk memperoleh informan selanjutnya yang layak untuk diwawancarai dan seterusnya. 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik dalam mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut. a. Observasi Partisipan Observasi dilakukan secara partisipan yaitu dengan ikut dalam aktivitas yang dilakukan oleh komunitas atau subyek penelitian. Observasi partisipan bukan berarti melakukan apa yang dilakukan oleh subyek penelitian, melainkan hanya berinteraksi sementara subyek melakukan 35 kegiatan (Delamont dalam Seale, dkk, 2010: 206). Oleh karena itu, observasi partisipan merupakan sarana membangun hubungan dengan subyek yang diteliti, sehingga gambaran sosial kultural dan praktik sosial bisa diperoleh (Salim, 2001: 158-159). Oleh karena itu, peneliti melakukan pengamatan partisipastif terhadap subyek penelitian dalam aktivitas pengelolaan Wisata Erupsi Merapi dan kehidupan sehari-hari. Pada tahap awal peneliti melakukan observasi dengan menjadi wisatawan selama beberapa kali untuk melihat kondisi wisata dan aktivitas wisata yang dilakukan masyarakat Umbulharjo Cangkringan. Pada pengamatan ini, peneliti melihat berbagai banyak komunitas tumbuh di kawasan Wisata Erupsi Merapi. Dari pengamatan tersebut peneliti terdorong untuk mengkaji pihak yang sesungguhnya memiliki otoritas sebagai pengelola wisata erupsi Merapi, serta bagaimana komunitas-komunitas usaha wisata begitu menjamur di kawasan wisata tersebut. Peneliti pun terlibat dalam kegiatan pemungutan retribusi baik di pintu 1 maupun 2 kawasan wisata Volcano Tour yang dilakukan Tim Lapangan Kelompok 3. Namun, dalam proses ini peneliti hanya berusaha mengamati dan mewawancari. Pada awalnya, peneliti menemui kendala ketika melakukan pendekatan. Ketua kelompok (Mas Mesiam) cenderung menghindar ketika diajak berbincang dan menjaga jarak. Oleh karena itu peneliti mencoba membangun interaksi secara lebih bersahabat dengan membicarakan topik yang lebih ringan. 36 Akhirnya kemudian, peneliti diterima hangat oleh kelompok 3 dan diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata (menjaga pos tiket dan parkir). Peneliti mengamati bagaimana tim lapangan menghitung hasil uang yang diperoleh pada hari itu dengan mencocokkan jumlah lembaran tiket yang terjual, kemudian menyetorkannya kepada ketua kelompok (Mas Mesiam). Pada proses itu peneliti mengamati sembari berbincang banyak hal dengan anggota kelompok. Dari observasi ini, peneliti kemudian mengetahui bagaimana mekanisme kerja tim lapangan, alur uang hasil penjualan tiket dan parkir, dan mekanisme pelibatan mereka dalam tim lapangan. Bahkan peneliti sering mendengarkan keluh kesah dan derita mereka sebagai korban bencana. Selain itu peneliti juga sempat tinggal beberapa hari di Hunian Tetap Karangkendal Umbulharjo yaitu hunian relokasi yang ditempati warga padukuhan Pelemsari pascabencana. Peneliti tinggal di rumah Simbah Sudi, yang kebetulan rumahnya tidak ditempati karena beliau memilih tinggal di rumah aslinya yaitu di kawasan dusun Pelemsari (kawasan obyek wisata erupsi Merapi). Pada awalnya peneliti agak canggung berinteraksi dengan warga Huntap, tetapi ternyata mereka begitu ramah dan sopan. Peneliti berkunjung ke beberapa rumah tetangga untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Pada interaksi tersebut peneliti memperoleh gambaran mengenai kehidupan masyarakat Pelemsari pascaerupsi tahun 2010. Bahkan peneliti banyak 37 mendengarkan mengenai proses masyarakat padukuhan Pelemsari ketika mengungsi secara berpindah-pindah karena situasi diselimuti dengan kepanikan saat itu. Peneliti pun memperoleh penjelasan mengenai aktivitas warga saat di pengungsian, sampai pada usaha keluar dari kondisi krisis sosial ekonomi melalui pembentukan Paguyuban Kinahrejo, serta upaya relokasi mandiri ke Huntap Karangkendal. Melalui perbincangan dengan warga tersebut peneliti memperoleh gambaran mengenai ikatan kuat (bonding) yang terjalin di antara warga Pelemsari, terutama juga karena dipengaruhi oleh rasa senasib sebagai korban erupsi Merapi. b. Wawancara Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam. Pada proses wawancara, juga diperlukan upaya mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan informan (Heyl dalam Atkinson, 2007: 370). Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mendengarkan secara antusias serta membangun relasi secara lebih cair dengan informan. Wawancara mengarah pada kondisi kehidupan masyarakat pascaerupsi tahun 2010, kronologis munculnya banyak pengunjung ke kawasan Umbulharjo, respon awal yang dilakukan masyarakat sekitar terhadap banyaknya pengunjung, serta inisiasi pemanfaatan peluang atraksi bencana sebagai sarana untuk keluar dari krisis pascaerupsi melalui agenda wisata. Pertama peneliti mewawancarai Bapak Nartukiyo yang ternyata merupakan salah satu informan kunci yang mampu membuka 38 informasi terkait wisata pascaerupsi tahun 2010 di Umbulharjo Cangkringan. Pertemuan peneliti dengan Bapak Nartukiyo terjadi secara tidak sengaja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Pada proses itu peneliti mencoba mencari sekilas info terkait Wisata Erupsi di Umbulharjo Cangkringan. Akhirnya peneliti dianjurkan untuk bertemu dengan Bapak Nartukiyo, yang ternyata inisiator dari wisata erupsi tersebut. Informan pertama membuka jalan untuk bertemu dengan informan-informan selanjutnya. Ada 8 orang yang menjadi subyek inti wawancara yaitu Nartukiyo, Subagio Hadi, Bejo Mulyo, Sriyono, Ramijo, Margo Utomo, Mesiam, Eko Susilo, dan Badiman dengan profil sebagai berikut. 1) Nartukiyo Salah satu pendiri Wisata Erupsi Merapi 2006 (Lava Tour) dan 2010 (Volcano Tour), yang bertempat tinggal di Dusun Karanggeneng Umbulharjo. Ia juga merupakan tokoh masyarakat Umbulharjo karena keterlibatannya pada organisasi dan lembaga tingkat Desa maupun Kecamatan antara lain: Ketua Karang Taruna Merapi Umbulharjo (2005-2013), Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) Umbulharjo, Sekretaris Tim Volcano Tour (2010-sekarang), Pendamping Difable Kecamatan Cangkringan, dan Penggerak Sanggar Anak Mutiara Abadi Dusun Karanggeneng. Ia tercatat sebagai PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2007. Peneliti memilihnya sebagai informan karena perannya dalam 39 pendirian wisata Lava Tour dan Volcano Tour yang masih memiliki benang merah, sehingga dapat menjelaskan seluk beluk dan proses munculnya wisata Volcano Tour. Bahkan ia juga banyak memberikan data sekunder terkait pengelolaan wisata. 2) Subagio Hadi Subagio Hadi merupakan Kepala Dukuh Pangukrejo yang juga menjadi Ketua Tim Koordinator Volcano Tour sejak tahun 2012. Ia juga merupakan salah satu tokoh masyarakat yang turut rembug (musyawarah) dalam rencana penataan wisata pascaerupsi tahun 2010. Peneliti memilihnya sebagai informan karena keterlibatannya dalam kepengurusan Volcano Tour dan perannya sebagai tokoh masyarakat sehingga mampu memberikan informasi terkait dengan konteks sosial masyarakat pascaerupsi, seluk beluk, maupun proses dan mekanisme pengelolaan yang dilakukan Tim Volcano Tour. 3) Mesiam Ia merupakan salah satu korban dari bencana erupsi Merapi tahun 2010 lalu, yang kehilangan harta benda dan 5 orang kerabatnya. Pascabencana ia kemudian bergabung dalam Tim Lapangan Volcano Tour. Pada saat itu statusnya masih sebatas anggota biasa. Namun pada tahun 2011, ditunjuk sebagai ketua kelompok karena adanya pemekaran kelompok dari 5 kelompok tim lapangan menjadi 10 kelompok. Keterlibatannya sebagai tim lapangan Volcano Tour dapat 40 memberikan informasi tentang kondisi pascabencana, mekanisme pembentukan tim lapangan, dan aktivitas tim lapangan. 4) Margo Utomo Ia merupakan kerabat Mesiam yang bertempat tinggal di Pelemsari. Ia merupakan salah satu korban yang kehilangan rumah dan harta benda lainnya seperti ternak serta lahan pertanian. Pascabencana ia bergabung dalam Tim Lapangan Volcano Tour (satu tim dengan Mesiam). Di samping itu dia merupakan ketua RT Pelemsari dan menjadi salah satu pengurus Paguyuban Kinahrejo dengan jabatan sebagai bendahara. Keterlibatannya dalam tim lapangan Volcano Tour sejak awal mampu memberikan informasi tentang deskripsi kerja dan mekanisme rekruitmen tim lapangan. Di samping itu ia juga banyak memberikan informasi tentang kondisi dan aktivitas masyarakat pascaerupsi. Bahkan ia juga memberikan informasi tentang Paguyuban Kinahrejo sampai pada upaya relokasi mandiri yang dilakukan warga Pelemsari dan Ngrangkah 2. 5) Bejo Mulyo Ia merupakan Kepala Desa Umbulharjo, yang bertempat tinggal di dusun Balong Umbulharjo. Ia juga menjadi ketua paguyuban pondok wisata Kalikuning Kaliadem. Pada tahun 2011-2012 sempat menjabat sebagai Ketua Tim Volcano Tour sampai akhirnya digantikan oleh Bapak Subagio Hadi. Peneliti menjadikannya sebagai informan karena perannya sebagai Kepala Desa dan Ketua 41 Tim Volcano Tour, sehingga peneliti merasa perlu untuk mendapatkan informasi tentang konteks wisata sebelum maupun pasca 2006 serta pembangunan wisata erupsi 2010 dari sudut pandang pemerintah Desa yang waktu itu diberi wewenang langsung oleh Pemda untuk membuat Surat Keputusan dan peraturan tentang pengelolaan wisata di Umbulharjo Cangkringan. 6) Sriyono Ia merupakan tokoh pemerintah Desa Umbulharjo dan menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2006, yang bertempat tinggal di dusun Balong Umbulharjo. Ia pernah bergabung dalam Karang Taruna Merapi Umbulharjo, dan menjadi salah satu perintis wisata Lava Tour bersama Bapak Nartukiyo. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang mempengaruhi terbentuknya Tim Wisata Volcano Tour, dan menjabat sebagai bendahara. Peranannya dalam perencanaan dan perintisan wisata Volcano Tour dan Lava Tour mampu memberikan informasi terkait benang merah dua wisata tersebut sekaligus seluk beluk dan proses penetapan wisata Volcano Tour. Kemudian upaya pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Tim Volcano Tour. 7) Badiman Ia merupakan PNS dan salah satu tokoh Pelemsari yang berpengaruh dalam pembentukan Paguyuban Kinahrejo. Ia menjabat sebagai ketua dalam lembaga paguyuban sampai sekarang. Ia pun juga merupakan salah satu korban erupsi Merapi yang menderita kerugian 42 materiil. Berdasar pada perannya dalam pembentukan Paguyuban Kinahrejo maka peneliti memilihnya sebagai informan karena mampu memberikan informasi terkait kondisi masyarakat pascabencana sekaligus seluk beluk dan proses pembentukan Paguyuban Kinahrejo sebagai salah satu bentuk kewirausahaan sosial pascaerupsi. 8) Eko Susilo Ia merupakan salah satu tokoh masyarakat Pelemasari yang juga berpengaruh pada pembentukan Paguyuban Kinahrejo dan menjabat sebagai sekretaris sampai sekarang. Ia pun merupakan salah satu korban erupsi Merapi yang menderita kerugian materiil. Sehari-hari ia bekerja di kantor Kementrian Kehutanan divisi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Berdasarkan itu peneliti memperoleh informasi terkait kondisi masyarakat pascabencana sekaligus seluk beluk dan proses pembentukan Paguyuban Kinahrejo sebagai suatu bentuk solusi untuk keluar dari krisis. Selain itu mampu memberikan dokumen sekunder terkait Paguyuban Kinahrejo. 9) Ramijo Ia merupakan tokoh masyarakat Pelemsari yang menjabat sebagai kepala dukuh. Selain itu, ia juga menjadi salah satu pengurus inti Tim Volcano Tour sebagai Humas. Oleh karena itu ia dapat menjadi informan dan mampu memberikan informasi terkait konteks sosial 43 masyarakat baik sebelum maupun pascabencana dan wisata di Umbulharjo. Wawancara dengan informan tidak hanya berlangsung sekali, namun berlangsung sebanyak dua sampai empat kali tatap muka. Hal itu terjadi karena pada wawancara pertama peneliti mengalami kesulitan untuk membangun komunikasi dua arah secara luwes dengan informan. Selain itu, waktu yang dimiliki informan untuk wawancara terbatas sehingga informasi terkait dengan alur dan proses tumbuhnya wisata pascaerupsi tahun 2010 masih minim. Oleh karena itu peneliti mencoba menghubungi kembali beberapa informan untuk melakukan wawancara lanjutan. Untungnya, para informan tersebut bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai kembali. c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu pengambilan data-data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat atau informan yang hendak diteliti (dalam Usman dan Akbar, 2004: 73). Dokumen-dokumen tersebut melengkapi data penelitian. Dokumen dapat berupa foto, rekaman audio, atau pun catatan-catatan yang diperoleh saat peneliti melakukan observasi maupun wawancara. Di samping itu, peneliti juga memperoleh salinan dokumen tertulis (data sekunder) yang dimiliki oleh informan yaitu Nartukiyo dan Eko Susilo terkait laporan kegiatan maupun administrasi Tim Volcano Tour dan Paguyuban Kinahrejo. 44 1.8.6 Teknik Analisis Data Analisis dilakukan setelah data observasi atau catatan lapangan dikumpulkan dan rekaman wawancara ditranskrip. Untuk menganalis data, peneliti menggunakan metode analisis naratif. Narasi merupakan data yang mengacu pada teks (lisan maupun tulisan) dan praktik dalam kehidupan sosial (dalam Newman, 2013: 578). Pada dasarnya narasi menurut Labov meliputi 6 bagian yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda10 yang secara keseluruhan terangkai secara koheren dan terkoneksi. Narasi juga memiliki beberapa karakteristik yaitu mengisahkan cerita/peristiwa, memiliki gerakan/proses, memiliki keterkaitan dalam konteks yang kompleks, menyangkut individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan, koheren, dan memiliki urutan peristiwa secara temporal (dalam Neuman, 2013: 579) Analisis narasi fokus pada identifikasi atau pemetaan berbagai peristiwa dan hubungan antara peristiwa tersebut. Oleh karena itu, narasi atau data yang dikumpulkan dipetakan berdasarkan rangkain kejadian secara kronologis. Rangkaian kejadian itu merupakan suatu gerakan atau proses yang juga melibatkan subyek-subyek di dalamnya (orang atau kelompok). Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik path depencency (lintasan ketergantungan) yaitu menyusun rangkaian peristiwa yang saling terhubung atau saling mempengaruhi. Artinya peneliti mencoba mengindetifikasi bagian-bagian peristiwa penting pascaerupsi Merapi 10 Martin Cortazi “Narrative Analysis in Ethnography” dalam Paul Atkinson, dkk. 2007. Handbook of Ethnography London: SAGE Publications. Hal 391. 45 tahun 2010 yang ditandai dengan masa krisis, fenomena kunjungan yang menimbulkan krisis laten, insiatif bangkit secara kolektif, perintisan kewirausahaan sosial sebagai wadah masyarakat lokal selaku korban bencana, dan pemrakarsaan misi kewirausahaan sosial sebagai bentuk strategi masyarakat keluar dari krisis. Kedua, mencari linkage action yaitu mengindentifikasi cara subyek terlibat dalam tindakan untuk mengubah suatu situasi atau kondisi menjadi situasi atau kondisi lain. Artinya pada setiap peristiwa atau proses melibatkan suatu cara bertindak dalam upaya mengubah situasi atau kondisi. Proses ini dilakukan dengan menentukan dan menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh insiator yang memprakarsai upaya pemanfaatan wisata sebagai sarana keluar dari krisis dan respon serta keikutsertaan masyarakat lainnya dalam upaya tersebut. Proses pemetaan narasi merupakan mode dari analisis data atau penjelasan (dalam Newman, 2013: 580). Oleh karena itu pada saat memetakan action linkage serta urutan peristiwa dalam konteks kehidupan masyarakat Umbulharjo Cangkringan pascaerupsi tahun 2010 dan upaya bangkit melalui pemanfaatan daya peneliti turut membedah atau mengalisisnya dengan teori yaitu social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) dan modal sosial. 46