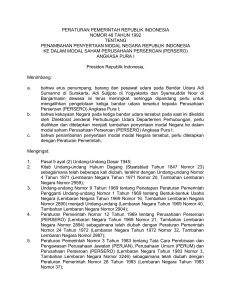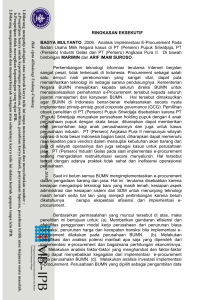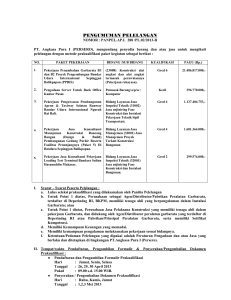dampak komodifikasi daya tarik wisata di desa pecatu, kuta selatan
advertisement

DAMPAK KOMODIFIKASI DAYA TARIK WISATA DI DESA PECATU, KUTA SELATAN, BALI. I Made Adhika PPLH-UNUD Jl PB Sudirman Denpasar –Bali [email protected] ABSTRAK Perkembangan kawasan pariwisata di Bali telah memicu perkembangan di sekitarnya. Kondisi ini akan dapat mengubah bentang alam di daerah tersebut yang akan berdampak terhadap lingkungan. Di Desa Pecatu yang memiliki Pura Uluwatu dan panorama yang indah sebagai daya tarik wisata, serta berdekatan dengan kawasan pariwisata Nusa Dua telah berkembangdan dan telah menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan. Makalah akan membahas tentang bagaimana dampak-dampak pengembangan pariwisata di Desa Pecatu, Bali. Penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan tokoh dan masyarakat sebagai informan, menganalisa dampak lingkungan pengembangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil telaah tersebut kemudian dideskripsikan, dinarasikan, serta dinterpretasi sesuai dengan pengetahuan peneliti sehingga tersusun makalah ini. Dengan telaah yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, pengembangan pariwisata di Desa Pecatu telah memicu perbaikan infrastruktur, bertambahnya kunjungan wisatawan, munculnya kesenian baru, perkembangan ekonomi, kekuasaan baru, dan juga terjadi degradasi lingkungan, konflik lahan, tergusurnya petani penggara, friksi interna,l dan disharmonis hubungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung . Dengan telaah ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan pengembangan kawasan pariwisata lainnya di Bali khususnya, dan pengembangan kawasan pariwisata lainnya di Indonesia . Kata kunci: dampak, lingkungan, pengembangan pariwisata. COMMODIFICATION IMPACTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN VILLAGE PECATU, SOUTH KUTA, BALI. I Made Adhika PPLH-Udayana University, Jl PB Sudirman Denpasar, Bali [email protected] ABSTRACT The development of a tourism area in Bali has triggered the development in the vicinity. This condition will be able to change the landscape in the area that will impact on the environment. In the village of Pecatu has Pura Uluwatu which has a beautiful and panoramic views as a tourist attraction, and adjacent to the Nusa Dua tourist area has grown and and has caused impacts on the environment. The paper will discuss about how the impacts of tourism development in the village of Pecatu, Bali. Research carried out by conducting direct observation, interviews with leaders and people as informants, analyzed the environmental impacts of such development. Research using qualitative descriptive approach. The results of its review later described, narrated, and interpretation accordance with the knowledge of researchers that made this paper. In the study conducted it can be concluded that, the development of tourism in the village of Pecatu has sparked infrastructure improvements, increased tourist arrivals, the emergence of new arts, economic development, new powers, as well as environmental degradation, land conflicts, internal friction, l and discord Bali Provincial government relations and Badung regency. With this study is expected to be used as a reference in the consideration of the development of other tourism areas in Bali in particular, and development of other tourism areas in Indonesia. Key words: impact, environment, development of tourism. PENDAHULUAN. Bali sebagai salah daerah tujuan wisata di Indonesia, sangat ramai (1.386.448 orang tahun 2005) dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Konsekuensi dari ramainya kunjungan tersebut adalah meningkatnya fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, seperti: hotel, restaurant, villa, biro perjalanan, usaha, dan jasa-jasa lainnya. Konsekuensi lanjutannya adalah meningkatnya kebutuhan akan energi listrik di Bali rata-rata 9,83 % per tahun (Bapeda Bali, 2004). Berdasar keterangan dari General Manager PLN Wilayah Bali Nusra yang berkekdudukan di Denpasar, menyatakan bahwa kebutuhan listrik pada saat puncak mencapai 360 MW, sedangkan energi yang tersedia 453,8 MW yang disuplai dari: PLTG/PLTD Pesanggaran dengan kapasitas 120 MW, PLTG Gilimanuk dengan kapasitas 133,8 MW, dan jaringan interkoneksi Jawa-Bali dengan kapasitas 200 MW (adhika, 2010). Dampak ikutan dari tersedianya energi listrik adalah kawasan-kawasan potensial terutama yang dekat dengan kawasan pariwisata mulai berkembang, demikian seterusnya secara siklikal akan tetap berlanjut. Kawasan Desa Pecatu, di Kecamatan Kuta Selatan, memiliki potensi pemandangan alam yang indah. Tebing-tebing terjal dengan ketinggian mencapai 165 meter di atas permukaan laut berhadapan dengan laut lepas, adalah pemandangan yang sangat menarik bila dipandang dari bawah (laut) maupun dari atas (tepi jurang). Selain itu, pada wilayah tersebut juga terdapat sebuah pura yang disebut Pura Uluwatu. Bagi masyarakat Hindu di Bali, pura ini dipandang atau digolongkan sebagai pura sad kahyangan dimana pura tersebut diperuntukan bagi umat Hindu di Bali, dan juga merupakan salah satu pura yang penting di Bali. Berkembangnya pariwisata di Bali, menyebabkan pura ini dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Hal tersebut disebabkan oleh uniknya pura tersebut. Terletak di semenanjung pada ketinggian 72 meter di atas permukaan laut. Sealin peninggalan sejarah, kawasan juga memiliki ombak yang bagus untuk kegiatan berselancar, bahkan pada musim tertentu banyak wisatawan minat khusus yang datang ke kawasan hanya untuk melakukan kegiatan berselancar. Dijadikannya Pura Uluwatu sebagai destinasi wisata beserta potensi lingkungan sekitar menyebabkan kawasan menjadi berkembang. Perkembangan kawasan telah menyebabkan halhal yang ada di kawasan yang awalnya merupakan benda, kualitas, ruang dan lainnya merupakan hal biasa, yang berupa peninggalan sejarah (pura), ruang (kawasan) untuk berbagai keperluan, kualitas lingkungan, budaya telah dijadikan komoditas untuk mendapatkan uang (komodifikasi). Pada Penelitian ini ingin memdapatkan jawaban tentang dampak yang ditimbulkan dari berkembangnya kawasan akibat dari kegiatan pariwisata. METODE PENELITIAN Rancangan penelitian pada dasarnya memuat uraian tentang kegiatan sebelum penelitian dilaksanakan, yang di dalamnya mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan (Moleong, 1990: 236). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang lebih condong pada persepektif kajian budaya. Penelitian ini merupakan hasil catatan pengamatan langsung, wawancara dengan tokoh dan masyarakat Desa Pecatu, serta pendalaman terhadap litratur dan hasil studi yang terkait lainnya. Dalam tulisan ini akan dikemukakan tentang dampak (fisik dan non fisik) lingkungan, baik yang berupa dampak positif maupun dampak negatif pengembangan kawasan. Dari paparan tersebut akan diinterpretasikan, dianalisis, dan dideskripsikan dari sudut pandang sosial kritis. Hasil dari deskripsi tersebut akhirnya ditarik simpulan pembahasan masalah dampak lingkungan pengembangan pariwisata di Kawasan Desa Pecatu, Kuta Selatan, Bali. HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak pengembangan kawasan Desa Pecatu, Kuta Selatan, dapat dilihat dari dampak positif maupun dampak negatif, sebagai berikut. A. Dampak Positif Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan tokoh dan masyarakat Desa Pecatu, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh pengembangan kawasan pariwisata di Desa Pecatu, Kuta Selatan sebagai berikut. a. Bertambahnya Kunjungan Wisatawan Pura Uluwatu merupakan pura dang kahyangan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang datang dengan tujuan sembahyang. Seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali, maka pura dan sekitarnya (kawasan suci) dikomodifikasikan menjadi daya tarik wisata. Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu telah banyak wisatawan yang datang untuk memenuhi keinginan menikmati indahnya pura dan pamandangan alam di luar pura ataupun pemandangan yang ada di kawasan tersebut (di bagian luar Pura Uluwatu dan di sekitarnya). Tujuan mereka datang ke kawasan adalah untuk melakukan kegiatan wisata, selain yang bertujuan melaksanakan kegiatan keagamaan (sembahyang). Namun demikian, antara pengunjung yang bertujuan untuk sembahyang dan pengunjung yang berwisata berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Pengunjung dengan tujuan berwisata umumnya sangat serius menikmati pemandangan alam di sekitar pura, mengamati arsitektur pura, memotret, maupun menyaksikan masyarakat yang melakukan ritual persembahyangan. Walaupun banyak pengunjung yang datang menonton dan mengamati masyarakat yang melakukan ritual sembahyang, namun masyarakat tidak merasa terganggu karena areal wisata dan areal masyarakat yang sembahyang sudah terpisah dan dibatasi. Di sekitar Pura Uluwatu berbatasan dengan jurang yang dalam. Untuk menjamin amannya wisatawan yang berkunjung, maka dibangun tembok pengamanan wisatawan agar terhindar dari kemungkinan jatuh ke jurang. Selain itu, jurang yang dalam juga memberikan pemandangan yang eksotik antara jurang dan laut. Untuk menikmati panorama tersebut, maka dibangun beberapa gardu pandang (shelter) agar wisatawan dapat menikmati panorama tersebut. Pembangunan tembok pengaman mengambil bentuk tembok panyengker yang dibuat serasi dengan bangunan tembok Pura Uluwatu, sedangkan bangunan gardu pandang juga mengambil bentuk bangunan tradisional Bali. Hal ini menunjukan bahwa kondisi alam dan lingkungan telah dikomodifikasikan yang merangsang libido kapitalis (Pujaastawa, 2006:177) untuk menanam modal dalam bentuk pagar, shelter, yang serasi dengan alam dan lingkungannya, sebagai jaminan keberlanjutannya fungsi kawasan sampai anak cucu nanti. Agar kapital yang ditanankan tidak sia-sia, maka dilakukan dengan para ahli yang terkait dengan hal tersebut, untuk lebih menjamin agar pembangunan dan dampaknya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dengan banyaknya kujungan wisatawan maka timbul ide untuk membentuk sekaha cak, yang membutuhkan ruang untuk pentas. Oleh karena itu, berdasar pada hasil rembug desa, maka dibangun stage sebagai tempat pentas sekaha cak tersebut. Lokasi panggung berada di lingkungan sekitar Pura Uluwatu dan masih dalam lingkup karang kekeran. Pada awal terbentuknya sekaha, kegiatan pentas hanya dilakukan hanya tiga kali seminggu dengan mamanfaatkan pelataran pura. Namun demikian, karena permintaan dari wisatawan bertambah maka pentas dilakukan setiap hari sampai saat ini, dengan memanfaatkan sebagian karang kekeran untuk panggung pementasan untuk menjamin keamanan, kenyamanan wisatawan serta kesucian pelataran pura. Harvey dalam Barker (2009:316) menyatakan bahwa penguasa dalam hal ini desa memegang peran utama dalam reproduksi kapitalis dan budaya dan pembentukan lingkungan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan potensi ombak dan tebing-tebing di kawasan. Hal ini adalah modal (capital) yang dapat mendatangkan uang, dan bagi kaum kapitalis sumber daya alam adalah komoditas utama untuk mengeruk keuntungan (Pujaastawa, 2006:176). Adanya potensi tersebut maka muncul libido masyarakat, pengusaha, pemerintah menbangun jalan, fasilitas penunjang pariwisata yang berupa hotel, jasa pernikahan, tempat minum kopi, dan jasa lainnya. Adanya akses dan fasilitas penunjang lainnya, maka kunjungan wisatawan semakin meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maka dibangun pula fasilitas baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini berarti bahwa secara siklikal ada tambahan komodifikasi ruang di kawasan suci Pura Uluwatu. Kondisi tersebut nampaknya merepresentasikan komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu menyebabkan kunjungan wisatawan meningkat, dan sebaliknya kunjungan wisatawan meningkat menyebabkan adanya komodifikasi kawasan. Memang hal ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga akan terjadi penyusutan sumber daya alam untuk pembangunan, dan timbulnya peniruan-peniruan (demontration effect) yang mengarah pada degradasi lingkungan (Tjokrowinoto, 2004:10). b. Perbaikan dan Pembuatan Jalan Baru Perkembangan kawasan suci Pura Uluwatu juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu, telah memudahan akses ke pura-pura yang ada di sekitarnya, maupun tempat destinasi di kawasan. Berkembangnya akses disebabkan oleh dijadikannya (dikomodifikasikannya) kawasan suci Pura Uluwatu sebagai destinasi wisata. Jalan-jalan sebagai penghubung antara potensi pariwisata yang satu dan yang lainnya telah dibangun, seperti jalan penghubung Pura Uluwatu dengan wilayah Pantai Suluban, jalan yang menuju ke Pura Kulat, dan jalan yang menuju Pura Selonding. Pada awalnya antara Pura Uluwatu dan Pantai Suluban tidak ada akses yang memadai. Wisatawan yang ingin berselancar ke pantai tersebut harus menyewa jasa pengangkut barang dan penunjuk jalan agar sampai ke tujuan. Namun dengan bertambahnya kunjungan wisatawan maka masyarakat pemilik lahan merelakan sebagian lahannya untuk difungsikan sebagai jalan. Adanya jalan tersebut telah terjadi kemudahan dalam pencapaian lokasi tersebut. Karena jalan relatif sempit, maka pemerintah menyempurnakan akses tersebut seperti sekarang adanya. Memang dalam kehidupan sosial, infrastruktur merupakan hal yang penting dalam mendistribusikan kegiatan sosial masyarakat dalam ruang/ kawasan, seperti yang disampaikan Gidden dalam Barker (2009:307). Pembangunan infrastruktur dalam kawasan merupakan penanaman modal Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengkomodifikasi kawasan untuk mendapatkan uang. Adanya infrastruktur akan berdampak dan memicu berkembangnya kawasan, dan berkembangnya kawasan akan meningkatkan pajak, yang berarti pula peningkatan pendapatan daerah. c. Aktivitas Keagamaan dan Aktivitas Budaya Semakin Semarak Berdasarkan kegiatan upacara keagamaan yang dilakukan oleh pamedek (orang yang datang untuk sembahyang) dan juga jumlah pamedek, maka komodifikasi (ruang) kawasan suci Pura Uluwatu nampaknya tidak mengurangi kegiatan religi ataupun religiusitas kawasan tersebut. Kegiatan religi dalam kawasan masih tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Hasil wawancara dengan pamedek-pun menunjukkan bahwa komodifikasi kawasan tidak berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk datang sembahyang ke Pura Uluwatu, maupun terhadap kegiatan persembahyangan yang dilakukannya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Massey tentang ruang dalam Barker (2009:311) yang menyatakan bahwa ruang kawasan telah digenderkan yang meliputi ruang untuk sembahyang/ritual, dan ruang untuk kegiatan non ritual, sehingga peruntukkan pembangunan vila tidak menggangu kegiatan persembahyangan. Kawasan suci Pura Uluwatu merupakan ruang dimana terjadi pertarungan dan interaksi antara pengunjung yang bersembahyang dan pengunjung yang berwisata (Nzegwu, 2006:312). Selain itu, dengan adanya komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu berdampak pula pada peningkatan kualitas bangunan di pura-pura yang ada di lingkungan Pura Uluwatu, seperti Pura Kulat, Pura Parerepan yang berlokasi di Desa Pecatu, dan Pura Pangleburan yang terletak di pantai Labuan Sait. Secara tidak langsung komodifikasi ruang berdampak positif terhadap pembangunan rangkaian pura yang terkait dengan Pura Uluwatu. Hal ini sejalan dengan pandangan Kuntjaraningrat (1974:12) yang menyatakan bahwa yang paling susah berubah berturut-turut sampai yang gampang berubah adalah, sistem relegi dan keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. Sejalan dengan pemikiran Kuntjaraningrat, Inskeep (1986:13) juga menyatakan bahwa pembangunan pariwisata juga dapat memperkuat kondisi religius masyarakat dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas keagamaan, terpeliharaanya situs-situs arkeologi, dan terpeliharanya aset-aset budaya. Demikian pula halnya jumlah pamedek. Semakin hari semakin meningkat jumlahnya, walaupun terjadi komodifikasi di kawasan suci Pura Uluwatu. Peningkatan pamedek dapat diukur dari meningkatnya kebutuhan parkir saat piodalan. Banyaknya jumlah pemedek yang parkir mengindikasikan bahwa kedatangan masyarakat untuk sembahyang semakin meningkat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat. Hal ini disebutkan oleh Hendropuspito (2006:60) bahwa sikap masyarakat terhadap agama meningkat seiring dengan kondisi sosial masyarakatnya, dan strata sosial masyarakatnya. Kaum petani akan memiliki kecendrungan yang lebih besar dalam bidang religi dibandingkan dengan kaum pedagang ataupun kaun elit. Namun demikian, pemedek di Pura Uluwatu nampaknya meningkat dari semua strata sosial masyarakat di Bali. Aktivitas ini dilakukan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan jati diri dengan melaksanakan tradisi, untuk mendekatkan diri dengan Hyang Widhi/ Tuhan Yang Esa, seperti yang disampaikan oleh Prior (2006:191). d. Muncul Kesenian Baru Ramainya kunjungan wisata untuk menikmati sunset maka timbul ide kreatif dari masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatannya. Masyarakat Desa Pecatu yang diprakarsai oleh tokoh masyarakat desa membuat sekaha cak yang melibatkan masyarakat yang ada di sekitar Pura Uluwatu. Pada awalnya pertunjukkan dilakukan dalam tiga kali dalam seminggu, namun sejalan dengan permintaan (pasar) wisatawan maupun pengelola jasa perjalanan, maka pentas cak dilakukan setiap hari. Untuk menjamin pemerataan pendapatan masyarakat sekitar dan ada kesempatan istirahat, maka dibentuk sekeha cak yang berikutnya yang diambil dari masyarakat sekitar dengan pentas dilakukan secara bergantian satu sama lain. Dengan demikian, maka terjadi pemerataan pendapatan. Selain kesetaraan pendapatan, dengan adanya sekeha baru, maka masing-masing sekeha cak dapat istirahat sehari setelah pentas. Pertunjukkan cak yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Pura Uluwatu telah meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Bangunan panggung pertunjukan cak di lingkungan karang kekeran Pura Uluwatu juga dikatakan tidak berpengaruh terhadap religiusitas Pura Uluwatu. Letak bangunan panggung berada di luar pelataran Pura Uluwatu, sehingga secara fisik tidak berhubungan langsung dengan pelataran pura. Bentuk bangunan yang berupa panggung terbuka, arsitektur lokal (Bali) sehingga tidak kontras dengan lingkungannya. Selain itu, panggung dengan bangunan tersebut (tidak massif) sehingga terjadi hubungan yang transparan terhadap alam lingkungannya. Kesenian cak juga juga terbentuk di lingkungan Labuan Sait. Berawal dari keinginan masyarakat di lingkungan Labuhan Sait untuk bergabung dengan sekeha cak di Uluwatu. Karena tidak diterima, maka dia membentuk sekaha sendiri. Pada awalnya pentas dua kali seminggu, namun meningkatnya permintaan dan dalam mempermudah pengaturan jadwal agen perjalanan, maka sekarang pentas dilakukan setiap hari. Dijadikannya bagian luar Pura Uluwatu sebagai daya tarik wisata juga dipandang tidak memberikan dampak terhadap religiusitas dari Pura Uluwatu. Hal ini disebabkan oleh kunjungan wisatawan hanya dibatasi pada areal yang ada di luar dari mandala utama Pura Uluwatu. Wisatawan yang berkunjung ke daya tarik bagian luar Pura Uluwatu hanya terbatas pada bagian luar saja. Menurut pandangan masyarakat Bali pada umumnya (Suparta:2007: 90) dan aturan awig-awig Desa Pecatu menyebutkan bahwa orang yang ada keluarganya meninggal ataupun bagi wanita yang sedang datang bulan dilarang memasuki bagian dalam (jeroan) pura. Pembangunan dan perkembangan pariwisata di kawasan suci Pura Uluwatu juga memberikan inspirasi dan keinginan untuk meningkatkan tingkat kereligiusan masyarakat. Hal ini dilakukan karena kegiatan sosial budaya masyarakat tersebut menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Agar wisatawan yang datang ke kawasan berlanjut, maka dilakukan peningkatan peran dan tata cara dalam melakukan kegiatan upacara keagamaan. Dengan kata lain dengan terjadinya komodifikasi kawasan maka terjadi peningkatan sikap religiusitas masyarakat yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan, seperti yang dikemukan oleh Pior (2006:192). e. Muncul Sejumlah Usaha Perekonomian Sektor Informal. Ramainya kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan manca negara, maka sejak tahun 1995 telah dimulai pembangunan kios-kios untuk memenuhi kebutuhan tamu-tamu yang berkenjung ke kawasan suci Pura Uluwatu, khususnya di sekitar Pura Uluwatu. Pembangunan kios-kios ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Pura Uluwatu dan hanya dilakukan oleh masyarakat di sekitar daya tarik wisata luar Pura Uluwatu. Adanya kios-kios ini menjadikan masyarakat setempat mempunyai lapangan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kegiatan baru ini sangat berarti ketika masyarakat tak dapat bercocok tanam karena musim kemarau yang relatif panjang. Lapangan pekerjaan bukan semata oleh kaum remaja yang usia kerja saja, tetapi juga dilakukan oleh para ibu-ibu yang sudah lanjut usia dengan menjajakan makanan monyet dengan bahasa asing sekenanya. Hanya masyarakat lokal yang diijinkan oleh pengelola kawasan untuk memanfaatkan kios-kios maupun sebagai pedagang makanan kera, maka pertambahan nilai (value added) dari komodifikasi kawasan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian komodifikasi ruang kawasan suci Pura Uluwatu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Pitana (2005: 109) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengembangan kawasan atau kapitalisme pada kawasan telah menumbuhkan investasi alternatif sesuai dengan kebutuhan pasar (Barker, 2009:316) dan akhirnya dapat mensejahterakan, meningkatkan jati diri masyarakat di sekitar Pura Uluwatu. Hal ini dapat dilihat dari penataan lingkungan unit permukimannya yang nampak lebih modern, rumah-rumah sudah memanfaatkan teknologi kekinian, sarana peregerakan (transportasi) sudah meningkat. Selain mempercepat waktu, kendaraan ini juga menjadi simbol kelas ekonomi, citra masyarakat di dalam lingkungan komunitasnya. Berkembangnya luar Pura Uluwatu dan kawasannya menjadi daya tarik wisata, maka beberapa penginapan di sektarnya mulai bermunculan. Di antaranya: Gobleg Inn, Pondok Pugir, Mama and Yenny Inn, Jacko House, Vila De Gong, dan penginapan lainnya yang tumbuh di sepanjang Jalan Pantai Suluban. Selain penginapan ataupun vila, jasa lainnya juga bermunculan, seperti: jasa tempat pernikahan, laundry, jasa penyewaan sepeda motor, mobil, internet, perbaikan papan selancar, dan kios-kios penjualan bensin, cafe, bar dan restoran, serta jasa jual beli tanah (lahan). Hal tersebut menunjukkan bahwa, dengan adanya perkembangan (komodifikasi) kawasan suci Pura Uluwatu maka terjadi perkembangan di kawasan, utamanya pada jalur-jalur yang strategis, pada daerah dapat akses, pada daerah pemandangan yang indah, dan di sepanjang jalan Uluwatu – Labuan Sait – Pecatu. Munculnya jasa-jasa tersebut tidak semata sampai pada jasa tersebut, akan tetapi akan ada bangkitan kegiatan dalam lingkaran jasa tersebut. Dengan demikian, adanya satu jasa akan memungkinkan menimbulkan bangkitan jasa pendukung jasa utama tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi diversifikasi kegiatan ekonomi, investasi modal, dan jasa di luar Pura Uluwatu, sehingga tampak jelas tampilan masing-masing unit permukiman sesuai dengan kemajuan ataupun kemunduran ekonomi dan kultural, seperti yang disampaikan Sassen (1994:26). Bila kawasan dipandang secara analogi sama dengan pola ruang kota Burgess, maka Pura Uluwatu merupakan pusat ruang kota, sedangkan daerah yang berkembang di sekitarnya merupakan lapis perkembangan akibat dari berkembangnya/dikenalnya pusat kawasan yang berfungsi sebagai titik mula perkembangan kawasan. Hal ini pula sejalan dengan pandangan Barker (2009:319) yang menyatakan bahwa perkembangan kawasan diawali oleh perkembangan inti, dan selanjutnya diikuti oleh lingkungan di sekitarnya, dalam hal ini adalah suci Pura Uluwatu dan sekitarnya. B. Dampak Negatif Selain dampak positif yang ditimbulkan oleh komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu, juga menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan ataupun mengganggu perkembangan atau keberlanjutannya fungsi kawasan, seperti terjadinya konflik pemanfaatan lahan, ketidak berdayaan masyarakat dalam mempertahankan hak milik lahannya, tergusurnya petani penggarap, terjadinya disharmonis hubungan antara sejumlah pihak, dan munculnya kekuasaankekuasaan baru. Masing-masing dampak negatif tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut. a. Polemik Masalah Lahan Salah satu dampak dari komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu adalah terjadinya polemik masalah tanah/lahan. Pada tanggal 27 Oktober 1995 Pemerintah Kabupaten Badung melakukan tukar lahan dengan PT. Bali Pecatu Graha (BPG). Lahan yang dipergunakan oleh BPG adalah lahan petani penggarap yang sudah berlangsung ratusan tahun, akan ditukar dengan tanah seluas 200 m2 dalam bentuk lahan dan kebun. Akan tetapi, lahan pengganti tak kunjung ada sedangkan lahan yang lama sudah dikuasai oleh BPG. Selain itu, pada tanggal 13 Desember 1995 Jro Kuta mengadakan pertemuan dalam rangka inventarisir tanah/lahan dan pembentukan badan pengelola tanah laba Pura Uluwatu yang digarap masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai tempat bangunan hotel pada lahan tersebut. Dengan demikian, petani penggarap secara tidak langsung akan tergusur walaupun telah menggarap lahan tersebut secara turun temurun (Darmana, 2009:138). Paparan tersebut menunjukkan bahwa komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu telah menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, disebabkan oleh nilai lahan sudah meningkat dan menjanjikan keuntungan di masa mendatang. Konflik kepentingan penggunaan lahan juga terjadi antara penerintah Desa Pecatu dan pihak pengempon Pura Uluwatu (Puri Jro Kuta dan Celagi Gendong). Pemerintah Desa Pecatu tak ingin rencananya ditolak oleh kedua pengempon tersebut, maka pembangunan panggung pentas cak dibangun terlebih dahulu, setelah jadi baru disampaikan kepada pihak pengempon. Kegiatan itu, secara tidak langsung tersirat ada ketidak harmonisan hubungan antara pihak Desa Pecatu yang mempunyai tugas dan peran sebagai pelaksana pembangunan di Pura Uluwatu dan pihak pengempon (Puri Jero Kuta dan Celagigendong) yang cenderung menguasai pihak pelaksana pembangunan. Penuturan sekretaris desa juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pecatu berada di bawah subordinat, dan tidak ada pembaharuan terhadap hubungan dari pihak penguasa akan hal tersebut, sehingga muncul perlawanan (Baker, 2009:190). Oleh karena itu, ada kekuatan yang membedakan nilai-nilai yang sudah berlaku dengan apa yang dilakukan seperti yang disampaikan Bourdieu dalam Barker (2009:368). Hal ini menunjukkan adanya perlawanan yang dipresentasikan secara halus dan apik oleh masyarakat Desa Pecatu untuk menghindari ketersinggungan, serta agar tetap menjaga hubungan yang baik pada ke dua pihak. b. Petani Penggarap Tergusur Komodifikasi ruang kawasan suci Pura Uluwatu berdampak pada terpinggirkannya masyarakat. Terjadinya keterpinggiran masyarakat pada dasarnya berasal dari masyarakat pemilik tanah sendiri. Pemilik lahan saat menjual lahan telah membuat kesepakatan dengan pembeli agar anaknya dapat bekerja pada saat bangunan dioperasikan. Karena pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, maka posisi pada manajemen tidak dapat menduduki jabatan yang strategis. Pada umumnya mereka siap menjadi tukang kebun, maupun satuan pengamanan (satpam) perusahaan atau vila. Hal ini menunjukkan bahwa petani telah disusupi oleh kapitalisme yang datang dari luar, membeli tanah/lahan sebagai sarana produksi dengan tujuan keuntungan. Masyarakat yang mengharapkan dapat bekerja adalah hal yang diekplotasi oleh kaum kapitalis (Barker, 2009:14). Ada dorongan dari masyarakat akan kebebasan dari kemiskinan, dengan menjual lahan adalah sebuah solusi untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dalam posisi lemah, dan tidak memiliki nilai tawar yang dapat menguntungkan dirinya. Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu juga secara tidak langsung berdampak pada terjadinya pemiskinan masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh beberapa masyarakat (yang tak mau disebutkan namanya) mengatakan bahwa penjualan lahan oleh masyarakat pada awalnya memberikan kontribusi jumlah uang yang cukup banyak. Hasil tersebut kemudian dibelikan lahan di kabupaten lain (Tabanan, Klungkung, dan di sekitar Desa Pecatu) dengan luas yang lebih banyak dibandingkan dengan luas sebelumnya. Dengan demikian jumlah yang dibeli akan lebih banyak dari jumlah yang dijual. Hitungan secara ekonomi sudah mendapatkan keuntungan dari jumlah luasan. Keuntungan lainnya adalah pembangunan lingkungan bangunan tempat hunian, tempat persembahyangan dan lainnya. Namun demikian, karena lokasi lahan yang baru letaknya relatif jauh, maka kontrol terhadap hasil kebun/tegalan dianggap kurang memadai. Berdasar atas pemikiran tersebut maka akhirnya lahan tersebut di jual dengan harga yang relatif murah. Hal tersebut menunjukan bahwa ketidak berdayaan masyarakat dalam menerima budaya baru yang progresif dibandingkan dengan budaya tradisi, sehingga terjadi benturan budaya, seperti yang disampaikan oleh Suputra (2006:193). Dampaknya adalah ketidakmampuan mengelola aset yang dimiliki, sehingga menjadi miskin kembali. Selain itu, kegagalan dalam mempertahankan lahannya merupakan ancaman bagi budaya dan identitas lokal (Pujaastawa, 2006:179). Hilangnya lahan menyebabkan sebagian budaya yang terkait dengan lahan menjadi hilang pula, hal ini justru menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kekawatiran serupa juga disampaikan Maunati (2004) dalam Pujaastawa (2006:179) tentang runtuhnya identitas lokal akibat perkembangan pembangunan pariwisata suku Dayak di Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan lahan tersebut hanya berdampak positif sementara saja, setelah beberapa tahun kemudian lahannya dijual kembali. Berbeda halnya dengan masyarakat yang membeli lahan di sekitar Desa Pecatu, jumlah kepemilikannya tidak banyak bertambah namun kini harganya sudah mahal dan dapat dijadikan sebagai tempat usaha. Mereka umumnya berhasil, tapi sayangnya lokasi kepemilikan yang tersebar. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa komodifikasi ruang kawasan suci Pura Uluwatu tidak semuanya berdampak positif, tetapi juga terjadi sebaliknya, yaitu pemiskinan kembali masyarakat setempat, atau tergusurnya sebagai petani penggarap lahan pertanian. Sebagian dari mereka akan menjadi tidak berdaya lagi, sedangkan sebagian lagi dapat meningkatkan identitas dan tarap hidupnya. c. Disharmonis Hubungan di Antara Sejumlah Pihak Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu juga berdampak pada terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara masyarakat dusun dan dusun lainnya, antara Adat dan Dinas, serta antara masyarakat dusun dengan Pemerintahan Desa Pecatu. Komodifikasi kawasan suci telah memunculkan ide untuk membentuk kelompok kesenian cak khususnya bagi masyarakat di sekitar Pura Uluwatu. Karena mendapatkan hasil yang menjanjikan, maka masyarakat dari Dusun Labuan Sait ingin bergabung. Hal ini ditolak oleh warga sekitar Pura Uluwatu, karena masuknya anggota lain berarti pula mengurangi pendapatan kelompok masyarakat tersebut. Penolakan ini berdampak pada pembentukan kelompok Cak Labuan Sait. Selain itu, komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu telah menimbulkan disharmonis antara Desa Adat dengan Desa Dinas, walaupun belum muncul kepermukaan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Pecatu I Wayan Kanten bahwa Pemerintah Desa Pecatu setiap tahun mencanangkan pembangunan di desa terutama yang terkait dengan infrastruktur desa, seperti jalan, tempat parkir, LPD dan lainnya untuk kemajuan desa. Namun demikian, setelah infrastuktur terwujud dan menghasilkan, Desa Adat yang memiliki wilayah yang sama, anggota masyarakat yang sama, lebih banyak mengatur dan menikmati hasil pembangunannya. Pernyataan Sekretaris Desa Pecatu tersebut mengindikasikan ketidak harmonisan antara Pemerintah Desa dengan Desa Adat. Karena wilayahnya sama, masyarakatnya sama sehingga sulit dipisahkan antara program untuk kepentingan desa dinas dan desa adat. Pada sisi lain pengaturan yang dilakukan oleh Desa Adat lebih efektif dibandingkan dengan Desa Dinas, sehingga timbul friksi di antara ke duanya. Selain itu, di Lingkungan Labuan Sait telah terbentuk pula sekeha cak yang dipentaskan di lingkungan dusun sambil menikmati sunset. Pada dasarnya konsep pemikiran sekeha cak Labuan Sait adalah karena adanya keinginan bergabung dengan sekeha di Pura Uluwatu. Karena ditolak, maka masyarakat Labuan Sait membentuk sekeha cak sendiri di lingkup lingkungan saja. Harapannya dapat menikmati tambahan pendapatan dari periwisata seperti halnya sekeha cak di Pura Uluwatu. Awalnya sekeha cak pentas didasarkan pesanan wisatawan yang tak tertampung di Pura Uluwatu, akan tetapi mulai akhir tahun 2009 atas permintaan biro perjalanan yang diajak bekerjasama, maka pentas dilakukan setiap malam walau belum seramai pentas cak di Pura Uluwatu. Dengan demikian, telah terjadi imbas dari pengembangan cak di Pura Uluwatu. Indikasi hubungan kurang harmonis juga tampak antara desa (Pecatu) dan aparat pembuat akta tanah, baik yang pemerintah maupun swasta (notaris). Hal ini tercermin dari penuturan kepala desa I Made Sumerta bahwa kalau ada masalah baru desa dilibatkan, kalau tidak lewat saja. Pembeli dan penjual dalam proses sertifikasinya lahannya langsung ke notaris ataupun ke BPN (Badan Pertanahan Negara), sehingga desa tidak tahu. Hal ini mengekpresikan kekecewaan aparat desa dalam proses jual beli lahan. Selain faktor kepentingan pendataan penjualan lahan oleh masyarakat, pelibatan desa dalam proses jual beli lahan juga sebagai ekpresi ”ada kepentingan”, ketidak nyamanan karena orang lain yang menikmati hasil jual beli lahan tersebut. Desa hanya dapat pengaduan bila proses tidak berjalan dengan semestinya. d. Terjadi Friksi antara Kelompok Pedagang dengan Pemerintah Desa Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu juga menimbulkan friksi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat pedagang di Pantai Labuan Sait. Pemerintah Desa Pecatu mengharapkan kawasan Pantai Labuan Sait tetap bersih dari bangunan-bangunan terporer pedagang, karena kawasan tersebut merupakan kawasan suci/tempat melasti dan juga untuk menghindari kesan kumuh kawasan. Oleh karena itu, pemerintah desa membangun kios-kios yang diperuntukkan bagi pedagang dan tempat parkir bagi pengunjung. Namun demikian, setelah kios-kios terbangun masyarakat pedagang hanya sebagian kecil yang memanfaatkan, sedangkan yang lainnya tidak mau menyewa/ menempati kios-kios tersebut. Hal ini merupakan bentuk penolakan secara halus oleh masyarakat setempat sebagai representasi dari disharmonis antara desa dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Desa Pecatu I Wayan Kanten bahwa sulit menghadapi perilaku masyarakat semenjak adanya reformasi pada tahun 1998. Di pantai Labuan Sait terdapat Pura Pengeleburan yang merupakan salah satu pura yang ada di kawasan suci Pura Uluwatu yang berkaitan dengan prosesi upacara melasti di Pura Uluwatu. Di pelataran pura, pada bagian pantai yang berpasir, juga dijadikan sebagai tempat tujuan wisata pantai yang terkadang disebut dream land. Di pelataran tersebut dalam kesehariannya banyak wisatawan yang datang untuk berjemur di pasir yang putih di antara batubatu karang. Sebagian lagi ada yang berselancar pada ombak yang bergemuruh. Masyarakat setempatpun juga ikut ke sana terutama para penjaja barang cinderamata dan penawar jasa-jasa kepentingan wisatawan. Sebagian masyarakat juga membangun rumah-rumah sementara untuk berteduh ataupun sebagai tempat berjualan (warung makanan dan minuman). Secara visual memang tampak ketidakteraturan pada kawasan tersebut. Kegiatan mereka tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan seperti persembahyangan tetap berlangsung seperti sedia kala. Upacara-upacara yang terkait dengan tempat dan kawasan tersebut tetap berlangsung sebagaimana mestinya, baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseharian maupun dalam periode-periode tertentu yang dilaksanakan oleh desa. Persembahan kepadaNya dalam keseharian tetap dilakukan oleh masyarakat penyedia jasa di sekitar lokasi tersebut. Upacara-upacara yang terkait dengan kegiatan di Desa Adat Pecatu juga tetap dilaksanakan. Masyarakat tetap melakukan kegiatan upacara-upacara keagamaan walaupun tempat tersebut dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Namun demikian, pihak desa memandang bahwa ketidakteraturan dapat mengurangi nilai kesakralan (desakralisasi) dari kawasan tersebut. Oleh karena itu, pihak desa yang memiliki kekuasaan terhadap wilayah, membersihkan rumah dan warung-warung tersebut diganti dengan kios-kios yang dibangun oleh desa di tepian parkir di bagian atas jalan raya. Kios-kios tersebut dapat dimanfaatkan dengan menyewa kepada pemerintah desa. Pemerintah desa berharap akan terwujud keteraturan, kesakralan, kesucian dari pelataran pura. Namun, kenyataannya kios-kios yang disiapkan oleh desa hanya dihuni oleh sebagian kecil pedagang, sebagian lagi memilih berjualan di pantai. Hal tersebut dilakukan karena kios jauh dari pantai dan harus sewa, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan bila memilih di tempat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat berusaha mendekatkan diri dengan pasar (wisatawan) dengan membangun kembali rumah-rumah/kios-kios di tanah nampan tersebut, seperti yang disampaikan Ibu Iluh bahwa Desa telah menyiapkan kios-kios di samping parkir, namun pedagang tidak mau berjualan di sana, karena aktivitas tamunya di bawah tidak mau berbelanja di dekat parkir. Dengan demikian, ideologi keagamaan yang menganggap kawasan tersebut suci, akan dipandang berbeda bila dipandang dari ideologi pasar. Wisatawan membutuhkan kepraktisan dan masyarakat menyambutnya dengan jasa-jasa yang dibutuhkan, sedangkan pemerintah desa menginginkan kawasan tersebut tetap menjadi kawasan suci yang bebas dari bangunan-bangunan yang dianggap mengganggu kesucian kawasan tersebut. Dengan begitu, terjadi pertentangan antara budaya progresif yang berorientasi pada pasar dengan budaya represif yang berlandaskan agama dan cenderung mempertahankan tradisi yang ada (Alisyahbana, 1986: 17-24). e. Disharmonis antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu juga berdampak pada disharmonis hubungan antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Badung melalui instansi bawahannya (Bappeda) menyusun Rencana Detail Penataan Lingkungan Pura Luhur Uluwatu di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan di kawasan tersebut. Rencana ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 79 tahun 2000 tentang hal tersebut. Selain itu, dalam mengantisipasi dan mengendalikan pembangunan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan maka Pemerintah Kabupaten Badung menyusun RDTR wilayah Kuta Selatan. Dalam rencana tersebut termasuk di dalamnya kawasan suci Pura Uluwatu. Selain untuk mengantisipasi perkembangan dan pengendalian kawasan Kuta Selatan, RDTR ini dibuat sebagai tindak lanjut penjabaran rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali (RTRW-Bali) ke dalam rencana yang lebih rinci. Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 639 tahun 2003. Dalam RDTR tersebut telah diatur pola pemanfaatan ruang kawasan. RDTR ini dijadikan pedoman dalam pemanfaatan ruang dalam bentuk ijin-ijin pemanfaatan ruang kawasan. Karena ke dua Surat Keputusan Bupati Badung berdasarkan pada kecendrungan pemanfaatan ruang yang ada di lapangan, maka ada ketimpangan antara kawasan suci yang ditetapkan berdasrkan atas RTRW Provinsi Bali dengan RDTR kawasan suci Pura Uluwatu maupun RDTR wilayah Kuta Selatan. Berdasar pada RTRW Provinsi Bali maka dalam radius kawasan suci (lima kilometer) dari Pura Uluwatu tidak diperbolehkan membangun vila-vila dan fasilitas pariwisata sejenis lainnya. Namun demikian, bila didasarkan pada RDTR yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati Badung, maka di beberapa bagian kawasan suci dalam radius lima kilometer masih diijinkan mendirikan vila-vila dan sejenisnya. Pada tahun 2000-an berkembang wacana maraknya pembangunan vila-vila di kawasan suci Pura Uluwatu. Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya mengeluarkan ijin pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR yang telah ditetapkan, sedangan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengaturan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Bali berdasarkan RTRWP Bali yang dituangkan dalam peraturan daerah. Karena pemerintah Provinsi Bali merasa dilanggar, maka tindak lanjutnya adalah mengeluarkan surat teguran kepada Bupati Badung atas maraknya wacana dan kegiatan pembangunan vila-vila di kawasan suci Pura Uluwatu. Kemudian pemerintah Kabupaten Badung membalas teguran tersebut, seperti diwartakan oleh harian Bali Post tanggal 1 Juli 2008. Adanya polemik tentang pembangunan vila-vila di kawasan suci Pura Uluwatu, telah mengindikasikan bahwa ada ketidakharmonisan antara pemerintah Kabupaten Badung dengan pemerintah Provinsi Bali. Walaupun secara herarkhi hukum pemerintah kabupaten berada di bawah herarkhi hukum pemerintah provinsi yang berarti bahwa aturan yang dikeluarkan oleh kabupaten tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Demikian pula halnya aturan yang dikeluarkan Kabupaten Badung, secara hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Secara herarkhi, pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewenangan dalam fungsi pengaturan ruang wilayah, walau otonomi daerah berada di Kabupaten Badung. Balasan surat tersebut dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perlawanan yang disampaikan dalam bentuk surat balasan terhadap teguran yang disampaikan. Teguran dianggap sebagai penetratsi (Barker, 2009:349) daerah kekuasaan otonomi daerah kabupaten yang dikuasai oleh bupati (Badung) dan merupakan pembatasan-pembatasan ruang gerak pengaturan (ruang) kawasan suci Pura Uluwatu. Perlawanan yang dilakukan pada dasarnya merupakan tindakan yang menentang kekuasaan (Pemerintah Provinsi Bali) untuk mencapai nilai-nilai tertentu, seperti yang disampaikan Foucault dalam Barker (2009:368). Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidak harmonisan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali mempertahankan kekuasaannya dalam pengaturan ruang wilayah provinsi, sedangkan Kabupaten Badung juga berwenang mengatur wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti telah diungkap sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan bagian-bagian wilayah yang dapat dibangun dan bagian mana yang menjadi kawasan konservasi maupun kawasan suci. Namun, di sisi lain Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan perda tentang tata ruang wilayah Provinsi Bali yang tidak sejalan dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga terjadi ketidak sejalanan kebijakan di bidang tata ruang. Pemerintah Kabupaten Badung merasa keberatan dengan Perda tersebut. Bila diterapkannya perda tersebut (yang di dalamnya memuat bhisama PHDI Pusat) maka beberapa vila tidak beroperasi lagi, seperti di Puri Bali di pantai Nyang-Nyang. Puri Bali Nyang-Nyang terletak 1,5 kilometer di sebelah timur dari Pura Uluwatu, sehingga masih dalam radius kesucian Pura Uluwatu yang menetapkan radius kesucian pada jarak lima kilometer. Puri Bali direncanakan sebelas lot vila yang dilengkapi dengan restaurannya. Dari sebelas yang direncanakan lima yang sudah di bangun. Bila mengacu pada peraturan tersebut, maka Puri Bali Nyang-Nyang tidak sesuai aturan yang ditetapkan. Namun demikian, kegiatan restoran masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Wisatawan sangat berminat menikmati tebing, minum teh ataupun kopi di tempat tersebut, dan menikmati pemandangan menjelang matahari terbenam. Demikian pula halnya di daerah Pantai Suluban yang sudah banyak dibangunan vila-vila sebagai bentuk komodifikasi ruang kawasan, mesti dihilangkan apabila perda tersebut diterapkan. Hal ini juga berarti hilangnya modal (capital), yang berarti pula hilangnya pendapatan daerah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung berusaha mempertahankan kondisi tersebut dengan dasar peraturan RDTR yang telah disusun, baik mengenai RDTR kawasan Pura Uluwatu maupun RDTR wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Dengan penerapan bhisama yang ditetapkan PHDI Pusat dan dihembuskannya isu tentang penertiban kawasan di media masa, maka terjadi menurunan minat investor di kawasan tersebut. Para investor yang telah membeli lahan mengurungkan niatnya untuk melakukan kegiatan pembangunan karena ada kekhawatiran terhadap kegiatan penertiban dan pelaksanaan secara ketat sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini diindikasikan dari penurunan jumlah yang mengurus perijinan pada unit pelayanan teknis di Kantor Bupati Badung. Penurunan minat terkait langsung dengan tingkat keamanan dan keberlanjutan dari investasi yang dilaksanakan. Menurunnya minat investasi yang berarti pula penurunan tingkat pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung. f. Kebebasan dalam Melaksanakan Ibadah Terganggu. Perkembangan kawasan pembangunan di kawasan suci Pura Uluwatu telah menjadikan Pura Batu Belah sebagai salah satu pura yang ada terletak di kawasan suci Pura Uluwatu berada di bagian lingkungan risort. Pada awalnya berada pada salah satu kebun/ladang milik masyarakat setempat, namun karena lahan itu dijual kepada pihak lain (kini pemiliknya orang Australia), maka pura tersebut kini berada di dalam salah satu bagian dari Uluwatu Resort. Walaupun berada dalam kawasan pengembangan fasilitas penunjang fasilitas yang berupa bungalow dan restoran, namun kegiatan upacara kegamaan yang berlangsung di tempat tersebut tetap berlangsung seperti sediakala. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat setempat bahwa kesakralan/relegiusitas dari pura tersebut sangat tergantung dari masyarakat yang memposisikannya dalam keadaan sakral atau tidak. Namun demikian, keberadaannya di dalam resort menjadikan nilainya berbeda bila dibandingkan dengan bangunan suci tersebut masih lingkungan lahan milik sendiri. Paling tidak meski meminta ijin terlebih dahulu bila memasuki resort tersebut. g. Munculnya Kekuasaan Baru. Komodifikasi kawasan suci Pura Uluwatu telah memunculkan penguasa-penguasa kecil pada daerah tujuan wisata. Di Pantai Suluban, telah terbentuk kelompok pengelola parkir yang dikoordinir oleh masyarakat pemilik lahan, yang dahulu sebagian lahannya direlakan untuk kepentingan pembangunan jalan ke pantai tersebut. Atas jasanya tersebut, maka mereka membentuk kelompok yang memunggut retribusi parkir pengunjung di ujung jalan menuju Pantai Suluban. Hasil retribusi parkir pengunjung kemudian dibagi kepada anggotanya. Demikian pula halnya di jalan menuju Blue Point. Setiap kendaraan yang masuk akan dikenakan retribusi. Retribusi dipunggut oleh pemilik lahan yang kini disewa oleh wisatawan Jepang untuk pembangunan hotel dan restoran. Seperti yang disampaikan oleh pemungut parkir yang dipanggil Pak Sontar atau Pak Sugiama bahwa dahulu tanah ini milik saya sebelum dikontrakan kepada orang Jepang selama 30 tahun. Dulu hanya pada musim penghujan saja dapat dimanfaatkan untuk perkebunan padi gaga (gogo), bila tidak ada hujan lahan tidak menghasilkan apa-apa. Sewa lahanya luwayan. Sewa lahan untuk kios 400.000/m2/tahun. Saya munggut parkir di sini karena tanah milik saya yang dipakai jalan. Dari penuturan Pak Sontar tersebut telah menunjukkan adanya kekuasaan baru dalam satu wilayah yang berada di kawasan suci Pura Uluwatu. Hal ini disebabkan oleh karena dia memiliki modal yang berupa tanah yang dijadikan jalan, walaupun kini telah dijadikan jalan umum, ataupun modal tanah yang kini sebagian lagi disewakan pada orang lain. Selain itu, kekuasaan baru ini nampak sanggat erat hubungannya dengan pendapatan (hasil) dari parkir tersebut. Kendaraan roda dua yang masuk dipunggut retribusi 2.000 rupiah, sedangkan roda empat 5.000, sehingga dalam sehari pendapatan dari parkir cukup banyak. Dengan demikian, kekuasaan yang timbul sangat erat kaitannya dengan uang maupun komodifikasi kawasan. KESIMPULAN Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Komodifikasi kawasan telah membawa dampak positif terhadap masyarakat disekitarnya, seperti kegiatan sosial ekonomi berkembang, kegiatan sosial budaya berkembang, munculnya kesenian baru, dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan. Hal ini berarti pula kawasan akan tetap berkembang. 2. Selain dampak positif, pengembangan kawasan juga berdampak negatif, antara lain ditemukan adanya konflik masalah lahan, tergusurnya petani penggarap, ketidak berdayaan masyarakat, ketidak harmonisan hubungan antara sejumlah pihak, kebebasan aktivitas ritual terganggu, serta munculnya kekuasaan baru. DAFTAR PUSTAKA Adhika, I Made. 2010. “Permasalahan Sosial Budaya dalam Pemanfaatan Panas Bumi (geothermal) di Bali”. Penelitian Masalah Lingkungan di Indonesia. Buku 1, IATPI, 246257. Alisjahbana, Sutan Takdir. 1986. Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Nilai-Nilai. Ardika, I Wayan. 2007. Pusaka Budaya dan Pariwisata. Denpasar: Pustaka Larasan. Barker, Chris. 2005. Cultural Studies, Teori dan Praktek. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. ...................... 2009. Cultural Studies, Teori dan Praktek. Yogyakarta: Kreasi Wacana Darmana, Ketut. 2009. “Polemik Masalah Tanah Kawasan Suci di Bali, Sebuah Kasus Tanah Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu, Pecatu Bukit Jimbaran”. Pustaka, Jurnal IlmuIlmu Budaya. Volume IX, Denpasar: Yayasan Guna Widya Fakultas Sastra UNUD. Hendropuspito, D. 1983. Sosiologi Agama.Yogyakarta: Kanisius Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.1990:236. Pitana, I Gde. Putu G Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : Andi. Pujaastawa, I.B.G.. (ed). 2006. Wacana Antropologi, Kusumanjali untuk Drs. I Wayan Geriya. Denpasar: Pustaka Larasan Tjokrowinoto, Moelyarto. 2004. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.