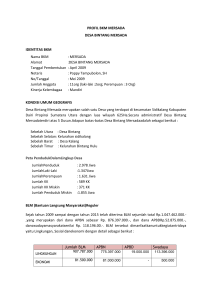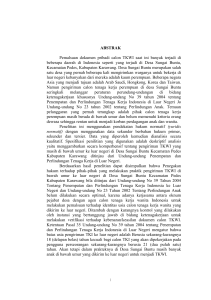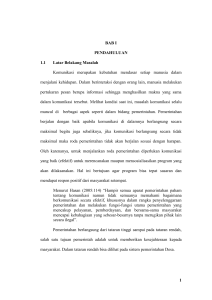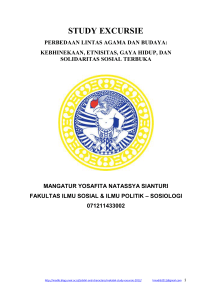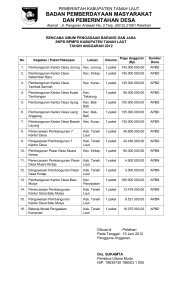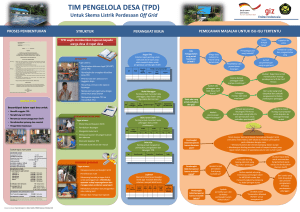sistem tata-kelola atau tata-pemerintahan desa
advertisement

Project Working Paper Series No. 01 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Penulis: Arya Hadi Dharmawan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-IPB Bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Penulis: Arya Hadi Dharmawan Layout dan Design Sampul : Dyah Ita M. dan Husain As’adi Diterbitkan pertama kali, Mei 2006 Oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB Bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP Kampus IPB Baranangsiang Gedung Utama, Bagian Selatan, Lt. Dasar Jl. Raya Pajajaran Bogor 16151 Telp. 62-251-328105/345724 Fax. 62-251-344113 Email. [email protected] Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit ISBN: 979-8637-32-1 2 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik KATA PENGANTAR Kebijakan Otonomi Daerah (OTDA) adalah keputusan politik yang menjadi tonggak penting sejarah sistem tata-pengaturan dan pemerintahan (governance and government system) di Indonesia. Undang-Undang no. 32/2004 yang melegitimasi OTDA, merupakan produk hukum yang pantas disambut baik oleh semua pihak, karena memberikan platform yang jelas pada penegakan kedaulatan lokal, keberdayaan dan kemandirian lokal, kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat dan demokrasi dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan. Sebagai innovasi di bidang politik-pemerintahan yang bertujuan mengoreksi dan mendekonstruksi sistem pemerintahan sentralistik yang cenderung negara-sentris, maka OTDA memerlukan waktu yang mencukupi untuk menyesuaikan dirinya dengan realitas tatanan-sosial sistem kemasyarakatan di Indonesia. Pada tataran lokalitaspun, otonomi desa (sebagai penjabaran OTDA) menghadapi sejumlah kendala struktural kelembagaan, sosio-kultural, dan politik-lokal untuk bisa mewujudkan tata-pemerintahan desa yang mandiri dan kuat. Alih-alih sebuah pengaturan desa yang efektif dan baik (good governance), sindroma ketergantungan politik dan ekonomi, ketidakberdayaan dan hegemoni pemerintah pusat tetap saja membelenggu keleluasaan pemerintah lokalitas (desa). Akibatnya, desa beserta pemerintah desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengemban operasionalisasi pemerintahan pada hierarkhi terendah dalam tata-pengaturan administrasi dan pelayanan publik, menghadapi ancaman kegagalan kelembagaan. Studi-aksi “partnership-based rural governance reform” (pembaharuan tatapemerintahan desa berbasiskan kemitraan) mencoba untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses otonomisasi desa menggunakan pendekatan jejaring para-pihak (kemitraan). Studi-aksi ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana format pembaharuan (revitalisasi dan rekonstruksi) sistem pemerintahan desa agar secara institusional dan organisasional, pemerintah desa berjalan efektif, transparan, akuntabel, controlable, dan mampu mewujudkan cita-cita kemandirian dan kewibawaan lokal. Studi-aksi yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB dan Kemitraan bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia-UNDP ini, dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap I adalah investigasi empirik (riset) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (survai) dan pendekatan kualitatif atau non-survai (indepth interview, focus group discussion, observasi lapangan) dalam menghimpun informasi dan data faktual dari lapangan. Lima provinsi ditetapkan sebagai daerah contoh yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali dan Papua. Di masingmasing provinsi yang memiliki persoalan ketata-pemerintahan khas itu, 3 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik ditetapkan sebuah kabupaten contoh dimana di setiap kabupaten ditetapkan dua desa lokasi studi-aksi secara purposif. Pada tahap I, diperoleh hasil berupa gambaran atau peta potensi serta permasalahan tata-pemerintahan daerah dan lokalitas (desa) secara cepat namun clear. Kegiatan riset yang dijalankan pada tahap I meliputi sejumlah bidang ilmu yang relevan, diantaranya kelembagaan pemerintahan, politik desentralisasi, jender dan komunikasi administratif, ekonomi lokal, pengembangan wilayah, ekonomi rumahtangga pedesaan, proses-proses kebijakan, serta kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya alam/agraria. Kegiatan pada tahap I menghasilkan sejumlah hasil penelitian sementara yang didokumentasikan pada Working Paper Series ini. Tahap II studi-aksi berupa investigasi persoalan-persoalan pemerintahan di tingkat lokalitas (desa) dan penggalian alternatif solusi yang layak dijalankan secara operasional. Sebuah rencana operasional tentang rekonstruksi dan revitalisasi tata-pemerintahan lokalitas (desa) disusun secara partisipatif sesuai ketersediaan anggaran dan waktu, pada tahap ini. Tahap III adalah tahap penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam tata-pemerintahan lokalitas (desa). Tahap IV berupa kegiatan pendampingan dan perbaikan proses-proses pembelajaran serta kegiatan praktikal di tingkat lokal sebagai tindak-lanjut kegiatan penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM. Tahap V adalah pengamatan jalannya pendampingan dan dokumentasi proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengumpulkan pengalaman lapangan (lessons learned). Tahap VI adalah proses pertanggungjawaban publik atas apa yang telah dijalankan di lapangan, berupa lokakarya dan seminar di tingkat kabupaten dimana studi-aksi dilaksanakan. Tahap VII adalah proses akumulasi keilmuan di bidang tata-pemerintahan lokalitas (desa), yang dipandang dari berbagai bidang-ilmu, dalam bentuk penulisan sebuah buku. Diharapkan, buku tersebut berguna menjadi salah satu sumber rujukan untuk proses penataan pemerintahan desa-desa di Indonesia di kemudian hari. Singkatnya waktu yang tersedia bagi kegiatan studi-aksi (enam bulan efektif selama tahun 2006), jelas menjadi pembatas yang signifikan bagi para peneliti untuk mengembangkan gagasan secara lebih leluasa. Namun, rentang-waktu yang singkat bukan berarti mengurangi nilai kualitas tulisan yang disajikan dalam makalah ini. Akhir kata semoga working paper ini memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat mengenai pelaksanaan otonomi desa khususnya atau OTDA pada umumnya bagi semua pihak. Salam kemitraan, Dr. Arya Hadi Dharmawan Ketua Tim Studi-Aksi 4 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………... iii Daftar Isi ………………………………………………………………… v 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah dan Konseptualisasi Gagasan ................. 1.1.1. Mempertanyakan Kebijakan Otonomi Daerah sebagai Platform Otonomi Lokalitas (Desa) ..................................... 1.1.2. Otonomi Lokalitas (Desa) dan Jebakan Ketergantungan 1.1.3. Otonomi Lokalitas (Desa) dan Jebakan Konflik Vertikal 1.1.4 Konseptualisasi Otonomi Lokalitas (Desa) ……………. 1.2. Tujuan dan Manfaat Studi-Aksi ……………………………..... 1.3. Ruang Lingkup Studi dan Metodologi ……………………….... 2. 15 16 18 22 REFORMASI TATA-PEMERINTAHAN DESA 3.1. Pemerintah Desa dalam Perspektif Actor-Oriented Theory ………. 3.2. Mewujudkan Good Rural Governance System …………………..… 3.3. Isyu-Isyu Kritikal Pembaharuan Tata-Pemerintahan Desa …...... i. Masalah Struktural-Institusional dan Politiko-Kultural ……... ii. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ........................................................ iii. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Nagari di Ranah Minangkabau ........................................................................... iv. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Desa di Jawa Barat ....... v. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan ”Desa Dinas” di Bali... vi. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Kampung di Papua 4. 1 2 4 8 12 13 KERANGKA KONSEPTUAL 2.1. Desa sebagai Entitas Sosial: Pandangan dari beberapa Perspektif .................................................................................... 2.2. Desa sebagai Social Container: Dilema dan Konflik Eksistensial . 2.3 Desa sebagai Arena Pertarungan Otoritas Kelembagaan ............ 2.4. Desa sebagai Konsep Pemerintahan Lokalitas: Konstelasi Beragam Kekuatan Pengaruh ..................................................... 3. 1 25 27 30 30 32 35 39 40 42 PENUTUP Rekonfigurasi Keterlibatan Para Pihak untuk Good Rural Governance System ........................................................................ 44 Daftar Rujukan ............................................................................. 46 5 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 6 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah dan Konseptualisasi Gagasan 1.1.1. Mempertanyakan Kebijakan Otonomi Daerah sebagai Platform Otonomi Lokalitas (Desa) Kebijakan “Otonomi Daerah” (OTDA) sebagaimana gagasannya tertuang pada Undang Undang (UU) no. 22/1999 dan revisinya pada UU no. 32/2004 tentang ”Pemerintahan Daerah” menjadi salah satu landasan perubahan sistem tatapengaturan atau tata-pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintahan secara nasional. UU tersebut merupakan keputusan yang pantas disambut baik oleh semua pihak, namun sekaligus juga perlu diamati perkembangannya secara seksama, dievaluasi dan selalu dikritisi secara terus-menerus agar imlementasinya tidak menyimpang dari “ruh” atau ideologi (kesetaraan para pihak pemangku kekuasaan, kemandirian, kesejahteraan sosial, demokratisme, partisipasi, keberdayaan masyarakat, tata-kelola pemerintahan yang baik) yang diperjuangkannya. Dalam konsepnya, OTDA (sesuai UU no. 22/1999 dan penyempurnaannya pada UU no. 32/2004) secara eksplisit ataupun implisit hendak mengedepankan cita-cita penegakan prinsip-prinsip demokratisme (kesetaraan, kesejajaran, etikaegalitarianisme), keunggulan lokal, komitmen pada rule of the game yang telah disepakati, apresiasi terhadap keberagaman, prinsip bottom-up, desentralisme administratif yang elegan dan berwibawa di tingkat lokal serta berkemampuan mengatasi persoalan riil di lapangan, penghargaan pada prakarsa serta hak-hak politik masyarakat lokal, kemandirian dan kedaulatan sistem sosial-ekonomi lokal serta pembebasan dari segala bentuk ketergantungan sosial-politik pada semua pihak. Salah satu aspek penting dari good-governance principle, yaitu control of power yang diwujudkan secara operasional dalam prinsip transparansi ketatapemerintahan dan akuntabilitas (pengelolaan keuangan) publik juga menjadi salah satu ciri-utama UU tersebut. Dalam konteks efektivitas capaian atau kinerja UU terhadap pencapaian cita-cita desentralisme, persoalan yang segera muncul adalah: apakah keseluruhan isi UU dapat segera mampu mewujudkan cita-cita tersebut pada aras lokal (desa)? Apakah sesungguhnya UU no. 32/2004 memberikan lokalitas (desa) benar-banar kekuasaan dan kewenangan yang otonom dalam mengatur rumahtangganya? Dalam setting geo-sosio-kultural komunitas desa yang sangat beraneka, dapatkah UU no. 32/2004 bekerja secara efektif mewujudkan cita-cita luhur tersebut bagi masyarakat lokal? Jika jawabannya “tidak atau belum terjadi”, maka hal-hal apakah yang perlu diperbaiki? 7 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Studi ini secara umum akan mengarahkan perhatiannya pada upaya menjawab pertanyaan di atas. Untuk dapat menjawab dengan sempurna semua pertanyaan tersebut, maka investigasi teoretik dan empirik (meliputi: kajian deduktif teoretik, kajian induktif empirik via pemetaan pola tata-pengaturan desa, pemahaman persoalan lokal, dan exercise atas beberapa alternatif tatapemerintahan desa yang paling layak secara lokal) sepantasnya dilakukan. Gagasan diarahkan pada fokus perhatian “tata-pemerintahan desa yang memberdayakan dan memandirikan” entitas sosial-kemasyarakatan lokal dalam atmosfer politik OTDA, dengan tetap memelihara harmonisasi hubungan antarhierarkhi kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan daerah. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa UU no. 32/2004 diasumsikan sebagai given-factor yang keberadaannya tidak bisa dielakkan atau dihindari. Segala upaya perbaikan terhadap kapasitas keberdayaan dan kedaultan lokalitas (desa) harus didasarkan pada platform UU no. 32/2004 dan perangkat hukum dibawahnya. 1.1.2. Otonomi Lokalitas (Desa) dan Jebakan Ketergantungan Dalam sejarah tata-pemerintahan di Indonesia, otonomi yang asli, sesungguhnya berada dan telah berlangsung sejak lama di aras lokalitas, dan bukan di aras Kabupaten atau Kota sebagaimana yang diketahui orang saat ini. Mengapa? karena pengaturan atau pengorganisasian kehidupan sosial kemasyarakatan telah berlangsung di aras lokalitas sejak ”jauh hari” sebelum perangkat-perangkat organisasi pemerintahan di tingkat ”supra lokal” dibentuk oleh pusat kekuasaan pemerintah (Anonymous, 2006). Dalam kerangka pengaturan kehidupan sosialkemasyarakatan yang otonom tersebut, komunitas lokal membentuk kesatuan masyarakat hukum adat dengan berbagai nama asli yang beragam-ragam sesuai setting budaya daerah masing-masing. Nagari dikenal sebagai tata-pemerintahan asli bagi lokalitas di ranah Minangkabau, Pakraman di Bali, Ondoafi (andewapi) di Papua, dan Gampong di Aceh. Kesatuan masyarakat adat yang membentuk kesatuan masyarakat hukum tersebut dibangun berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di dalam dan di atasnya. Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut mengembangkan perangkat kelembagaan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan masyarakatnya. Namun, sebagaimana telah dikemukakan oleh banyak studi terdahulu, kelembagaan adat dan kesatuan masyarakat hukum adat mengalami peminggiran (marjinalisasi) dan penghancuran-kelembagaan yang sangat sistematis sejak diundangkannya UU no. 5/1979 tentang pemerintahan daerah (sebelum dikoreksi oleh UU no. 22/1999), yang menyeragamkan konsep tata-pemerintahan lokalitas di seluruh Indonesia dengan konsep desa ala Jawa (lihat Syafa’at, 2002). Pengenalan konsep desa sebagai satu-satunya sistem pemerintahan lokalitas telah men-displace (melemparkan) keberadaan kelembagaan adat yang sesunguhnya kekuasaan dan otoritasnya masih sah secara tradisional. 8 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Berangkat dari semangat untuk merekonstruksi puing-puing kehancuran kesatuan masyarakat hukum lokalitas (adat), maka UU no. 22/1999 dan UU no. 32/2004 berupaya mengembalikan kedaulatan hukum lokal itu melalui pasal-pasal pemerintahan desa. Meski, tata-pengaturan daerah tidak dapat melepaskan dirinya dari konsep pemerintah-desa sebagai pusat kekuasaan pemerintahan lokal, namun semangat untuk kembali kepada pengaturan lokalitas tampak menonjol pada UU no. 32/2004. Sebenarnya dengan diterimanya UU no. 32/2004 sebagai given-and-agreed regulating institution seperti itu, maka kebijakan OTDA sudah berada pada jalur yang benar untuk mengapresiasi ”kedaulatan lokalitas” sebagai wilayah otonomi-asli dalam menata, mengelola, dan menentukan tatanan pengadministrasian segala urusan yang menyangkut interaksi warga negara dan kesatuan sosialnya dan warga negara dengan negaranya. Persoalannya, dengan konsep pemerintahan-desa sebagai satu-satunya system of government yang ditawarkan, maka potensi konflik antar otoritas kelembagaan segera tampak di depan mata. Bagamanakah upaya memandirikan dan mensejahterakan masyarakat lokal yang masih mengakui eksistensi sistem pengaturan adat dalam bingkai pemerintahan desa ala Jawa? Artinya, sejauhmana kedaulatan lokal (termasuk kedaulatan adat) bisa diterjemahkan dalam bahasa kedaulatan desa, sebagai satu-satunya sistem tata-pemerintahan tingkat lokalitas yang sah menurut UU no. 32/2004? Bagaimana cara mentransformasikan kepentingan-kepentingan (termasuk kepentingan adat) dalam pengaturan lokalitas kepada kelembagaan tunggal yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan perangkatnya itu? Berpijak pada cita-cita keberdaulatan dan otonomi lokalitas itu, UU no. 32/2004, (meski masih mengandung beberapa pertanyaan) menegaskan pengakuan “kedaulatan desa” secara eksplisit pada pasal 200-216 serta penajamannya pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 72/2005. Dalam UU dan PP tersebut, juga ditegaskan platform bagi penyelenggaraan sistem administrasi pembangunan yang memungkinkan setiap stakeholder mengaktualisasikan cita-cita pencapaian derajat keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik (better and sustainable socio-economic standard of living) secara mandiri dan bersamasama, mengatur rumahtangga desa secara mandiri, menjalin jejaring kerjasama desa, menggali sumber keuangan desa mandiri, serta memperjuangkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable natural resources and environment) secara aspiratif (lihat pasal 209-211 UU no. 32/2004). Dengan demikian, konsep otonomisasi lokal (desa) sebagaimana gagasannya tertuang pada UU no. 32/2004 sebenarnya telah memberikan landasan yang memadai bagi semua pihak (di desa) untuk menjalankan sistem pembangunan yang demokratis-partisipatif, inklusif-kolektivistik, serta tumbuhnya semangat collegiate-participatory development, harmonis (menekan peluang terjadinya konflik diametral antar pihak). Pada saat yang bersamaan UU no. 32/2004 tetap menjunjung tinggi asas perbedaan pandangan dan pluralisme dalam pemutusan 9 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik kebijakan. Memang, sejumlah persoalan ”tetap dibiarkan menggantung”, dalam hal ini, terutama berkenaan dengan fungsi pemerintah desa sebagai ”tumpahan segala urusan” yang seharusnya menjadi urusan dan kewenangan pemerintah supra-desa (kabupaten). Sementara itu, pemerintah desa ”dibiarkan” tetap dalam ketidakberdayaan secara finansial dengan segala macam tuntutankewajiban yang harus diselesaikannya. Jika otonomi lokalitas (untuk sementara) disepakati mengambil bentuk sebagaimana formatnya tercermin dalam pasal-pasal 200-216 UU no. 32/2004 (otonomi desa), maka muncul pertanyaan berikutnya, mampukah UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 tentang Pemerintahan Desa menjamin kedaulatandan-kemanidirian desa sepenuhnya (kemandirian dalam pengambilan keputusan, pendanaan, pengelolaan lokalitas)? Dapatkah semua prasyarat pembangunan di ranah administrasi publik desa tersebut dijalankan dengan baik sesuai cita-cita otonomi lokalitas (desa)? Benarkah organisasi pemerintahan desa yang posisisosiologisnya ”berada dalam perangkap birokrasi pemerintahan pusat dan kabupaten” mampu membebaskan dirinya dan mewujudkan segala cita-cita keberdayaan dan kedaulatan lokalitas/desa secara konstruktif? Adakah potensi konflik yang muncul akibat bekerjanya ”jebakan-jebakan biokrasi” via aturanaturan yang sangat mengikat serta secara rigid ditentukan oleh pemerintah ”atas desa”? Strategi apakah yang harus disusun untuk memberdayakan dan meneguhkan otonomi lokalitas (desa) sesuai cita-cita dan selaras dengan UU 32/2004? 1.1.3. Otonomi Lokalitas (Desa) dan Jebakan Konflik Vertikal Sebagai keputusan innovatif di bidang politik-pemerintahan, OTDA sesungguhnya bertujuan utama mengoreksi dan mendekonstruksi ideologi “sentralisme-otoritarianisme” sebagaimana mekanismenya telah berjalan pada sistem pemerintahan Orde Baru (ORBA) sejak 1966-1998. Persoalannya, ”ruh sentralisme” yang telah begitu lama mendarah-daging dalam sistem birokrasi dan tata-pemerintahan nasional, sulit untuk dihapuskan secara serta-merta oleh sebuah undang-undang pemerintahan daerah, yang didalamnya pun masih banyak hal-hal yang diperdebatkan. Oleh karena itu, OTDA memerlukan waktu yang cukup panjang untuk sampai pada cita-cita mewujudkan tuntutan tatanansosial sistem kemasyarakatan yang baru di Indonesia (kemandirian lokal, demokratisme, partisipasi publik, good-governance). Dalam perjalanannya, implementasi konsep OTDA bahkan tidak sedikit menghadapi halangan, kendala serta persoalan-persoalan struktural dan kultural pada tingkatan implementasi, yang besarannya beragam menurut kawasan, setting ekosistem, setting latar-belakang sosio-budaya dan setting sistem sosial-kemasyarakatan setempat. Artinya setting geo-sosio-kultural memberikan pengaruh sangat berarti bagi efektivitas implementasi UU Pemerintahan Daerah itu sendiri. Dalam pada itu, penataan sistem tata-pemerintahan baru yang berorientasikan desentralisme di tingkat kabupaten/kota, juga menghadapi persoalan-persoalan 10 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik struktural (termasuk kelembagaan), kultural, psikologikal, dan tata-administratif menyangkut “hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa-desa” di bawahnya. Wewenang yang melimpah di tingkat pemerintah kabupaten, sebagai akibat diberlakukannya OTDA, justru telah menyebabkan munculnya gejala baru berupa “resentralisasi” kekuatan dan akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat otoritas-kabupaten/kota. Akibatnya, kemandirian desa (sebagai wilayah-administrasi di bawah hierarkhi kabupaten) kembali mengalami “dekapitalisasi kekuasaan”, dimana desa “gagal” mendapatkan dukungan modalpolitikal dan modal-kultural yang diperlukan bagi tumbuhnya sistem pengaturan desa yang mandiri dan berwibawa. Desa menjadi semakin tergantung pada ritme dan arahan kebijakan politik pemerintahan pada hierarkhi kekuasaan di atasnya. Dengan kondisi yang demikian, dikhawatirkan, desa-desa di Indonesia – yang semula diharapkan menguat status keberdayaannya – kenyataannya, justru mengalami realitas sebaliknya yaitu reduksi-kekuatan yang sangat signifikan vis a vis pemerintah kabupaten dan pusat. Otoritas administrasi kawasan-lokal (desa) kembali “tersedot” konsentrasinya ke tingkat kabupaten/kota, dan menyisakan peningkatan derajat ketergantungan desa terhadap kabupaten/kota yang cukup substansial (desa kehilangan kedaulatan dan kemandiriannya). Desa kembali mengalami dependency-syndrome, yang situasinya mirip sebagaimana terjadi pada era ORBA. Ketergantungan sosial-ekonomi dan politik desa terhadap otoritas central-government di masa ORBA kini beralih ketergantungan struktural terhadap pemangku otoritas kabupaten/kota. Sejauh ini, desa tetap menghadapi persoalan inferioritas serta ketidakmandirian dan “ketidakberdaulatan” atas wilayahnya sendiri dikarenakan ketidakmampuannya untuk “berkompetisi serta bersaing” melawan kekuatan yang dimiliki oleh otoritas kabupaten. Dengan kata lain, pembaharuan sistem tata-pemerintahan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana melekat pada konsep OTDA, tidak memberikan dampak perubahan berarti terhadap sistem tata-pemerintahan di tingkat desa. Jika hal ini diangap persoalan yang mengganggu cita-cita otonomi lokalitas (desa), maka pertanyaannya, model reformasi tata-pemerintahan (desa) seperti apakah yang seharusnya dilakukan? Jika pembenahan di tingkat kabupaten pun harus dilakukan, maka bagaimana strategi yang harus ditempuh? Selain persoalan di atas, pelemahan kemandirian desa seterusnya akan menyebabkan ketimpangan sosial dalam struktur tata-pemerintahan yang akhirnya bisa mereduksi keseluruhan capaian pembangunan sosial-ekonomi dan politik yang dicita-citakan bersama. Sejumlah persoalan dan tantangan yang muncul, adalah: 1. Desa berpotensi mengalami guncangan stabilitas sosial-politik dan kekacauan organisasi tata-pemerintahan sebagai akibat berlangsungnya konflik-konflik kekuasaan dan wewenang secara vertikal, antara pemegang otoritas pemerintahan desa versus pemegang otoritas pemerintahan kabupaten (di “atas desa”). 11 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 2. Secara horisontal, tata-pemerintahan desa formal menghadapi “lawan-lokal” berupa sistem tata-pengaturan “pemerintahan adat” yang secara historis telah berurat-berakar di tingkat lokal. Konflik otoritas kelembagaan di tingkat lokal sungguh sulit dihindarkan, oleh karena setiap sistem tata-pemerintahan memiliki dasar rasionalitas dalam cara-berpikir (“logika”) tersendiri, yang semuanya sama-sama masuk akal. Dalam UU no. 32/2004 pemerintahan desa memang menjadi satu-satunya organisasi pengaturan “super-power” di lokalitas (desa) yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan segala macam urusan (lihat UU no. 32/2004 pasal 206). Namun, sebelum pemerintahan desa hadir dan diakui, secara kesejarahan kelembagaan adat telah eksis terlebih dahulu. Hingga kini pun relevansi dan eksistensinya dalam pengaturan kehidupan sosial-kemasyarakatan lokal tetap diakui oleh masyarakat lokal. 3. Kapasitas infrastruktur kelembagaan desa yang ada (pada kenyataannya) terlalu lemah (atau hampir tidak berarti) dan rapuh kekuatan finansialnya dalam menopang proses-proses tata-pemerintahan menurut tuntutan otonomi dan kemandirian lokalitas (desa) – sehingga kemungkinannya, pemerintahan lokalitas (desa) akan mengalami kelumpuhan bila tidak direvitalisasi. 4. Sistem sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa tetap mengalami stagnasi, insecure, tak mampu berkembang, tidak mandiri, bergantung dari sumber kekuatan ekonomi dari luar, serta tidak sustainable sebagai akibat tidak langsung dari ketidakmampuan pemangku otoritas-pemerintahan desa dalam menggerakkan pemerintahan dan menggali potensi lokal. Secara ringkas, hal ini dikatakan sebagai krisis ketatapemerintahan lokalitas (desa). 5. Jurang-komunikasi dan koordinasi antara otoritas administrasi pemerintahan kabupaten dan desa tetaplah lebar, sekalipun UU no. 32/2004 telah memberikan koridor komunikasi yang konstruktif. Hal ini menyebabkan tidak semua aspirasi desa tersambungkan ke “atas desa” dan menjadi masukan penting dalam proses perumusan kebijakan oleh pemangku otoritas pemerintahan kabupaten. 6. Organisasi pemerintahan desa bersama lembaga kemasyarakatan di desa, kenyataannya, juga sangat lemah kemampuannya dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan secara internal, pelayanan publik, kapasitas untuk berinisiatif, serta kapasitas keuangan dan penganggaran. Prasyarat minimal tata-pemerintahan ini jelas akan menyulitkan pencapaian derajat good-rural governance yang lebih baik seperti adanya jaminan akses keterlibatan/ partisipasi publik dalam pengelolaan dan kontrol terhadap pemerintahan yang lebih baik. Sementara itu kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa cita-cita komunitas lokal (desa) untuk dapat merealisasikan derajat kesejahteraan, keadilan, keberdayaan dan kemandirian yang lebih tinggi “secara segera”, menjadi faktor pendorong terus diresponsnya UU no. 32/2004 secara antusias. Respons tersebut terutama sangat terasakan di kawasan pedesaan Jawa, dimana struktur 12 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik tata-pemerintahannya memang telah well-adapted terhadap UU tata-pemerintahan tersebut. Hal sebaliknya terjadi di “desa-desa adat” atau desa dimana sistem tata-pengaturan sosial-kemasyarakatannya menggunakan basis legitimasi selain UU Pemerintahan Daerah. Sekalipun UU no. 32/2004 mengapresiasi keberadaan tata-aturan adat (pasal 203 dan pasal 216), namun otoritas adat dengan sistem tata-pemerintahan asli, sulit beradaptasi/menyelaraskan dengan keberadaan sistem tata-pemerintahan formal dalam konsep desa. Alhasil, dalam merespons peluang desentralisasi1 atau otonomi lokalitas (desa) yang ditawarkan oleh negara melalui platform UU no. 32/2004, otoritas adat seringkali berbenturan secara kelembagaan dengan otoritas formal (pemerintah desa) yang legitimate menurut hukum positif kenegaraan. Sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisme menurut UU no. 32/2004, maka “perubahan nasib” sebuah komunitas lokal (desa) hanya bisa direalisasikan bila komunitas lokal tersbut mengambil prakarsa penuh, kewenangan dan tanggung jawab yang subtansial pada praktek pemerintahan dari kelembagaan pemerintahan pada hierarkhi kewenangan jurisdiksional di atasnya. Prinsip ini tercermin pada pasal 212 dan 213 bahkan pasal 214 (tentang kerjasama desa) UU no. 32/2004 yang memberikan keleluasaan penuh bagi pemerintah desa untuk menghimpun sumber-sumber pendanaan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan tersebut dilimpahkan “ke bawah” dan dimanfaatkan sebagai “modal” bagi penyelenggaraan tata-pemerintahan desa. Persoalannya kemudian: (1) apakah setiap desa mampu untuk menjalankan otonomisasi desa dengan pendekatan yang seragam sesuai UU no. 32/2004 1 Rondinelli and Nellis (1986) sebagaimana dikutip oleh Cohen and Peterson (1999) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah “the transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels of government, semi autonomous public authorities or corporations, area-wide regional or functional authorities, or non-governmental private or voluntary organizations ”. Ada tiga bentuk desentralisasi-administratif yang dikenal dan penting untuk diketahui yaitu: (1) dekonsentrasi, yang menunjuk pada transfer kewenangan dari jenjang hierarkhi adminstrasi tertentu ke bawah, namun masih tetap dalam satu jurisdictional authority pada pemerintah pusat; (2) delegasi, yang menunjuk pada transfer of government decision-making and administrative authority untuk sebuah tugas tertentu kepada suatu organisasi tertentu yang sifatnya bisa tidak-secara-langsung ataupun independen dari kontrol pemerintah; (3) devolusi, yang menunjuk pada transfer kewenangan dari pemerintah (central government) kepada local-level governmental units yang mengemban status sebagai holding institution yang disahkan oleh peraturan hukum (legislation) (lihat Cohen and Peterson, 1999). Menurut Work (2001), devolusi dapat dikategorikan juga sebagai desentralisasi “politik” jika pengertiannya mencakup “adanya transfer tanggungjawab atau kekuasaan pengaturan/regulasi secara penuh dalam decision-making, penggunaan resources, dan penciptaan pendapatan, dari otoritas tunggal-negara kepada otoritas publik (masyarakat sipil, negara dan swasta) yang otonom di tingkat lokal dan bekerja secara independent legal entity”. 13 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik (padahal jelas dimaklumi bahwa setiap desa menghadapi kendala-kendala yang khas, dimana derajat persoalannya pun berbeda antara satu dan lain desa)? (2) Melihat aspeknya yang begitu kompleks dihadapi oleh sistem tata-kelola pemerintahan desa, maka muncul pertanyaan: sejauhmana kebijakan desentralisasi-desa bisa diterima dan operasional sesuai dengan keragaman struktur sosial masyarakat desa di Indonesia? Jika devolusi-kekuasaan adalah citacita desentralisasi yang dipilih untuk memberdayakan desa, maka muncul pertanyaan: bagaimanakah pentahapan penataan tata-pemerintahan desa seyogianya dilakukan agar cita-cita “kedaulatan desa” (keberdayaan desa) dan kesejahteraan desa terwujud? 1.1.4. Konseptualisasi Otonomi Lokalitas (Desa) ”Devolusi kekuasaan” jelas sulit direspons secara serta-merta oleh setiap lokalitas (desa). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tidak semua lokalitas (desa) memiliki derajat perkembangan kemajuan seperti yang terjadi di kebanyakan desa di Pulau Jawa. Ada keragaman yang sangat tinggi yang menyebabkan otonomisasi desa harus mengambil strategi berbeda-beda. Sistem pemerintahan lokalitas (desa) di berbagai kawasan Indonesia seperti Nanggroe Aceh Darussalam, ranah Minangkabau, Bali, dan Papua, telah mengenal tata-pengaturan sosial-kemasyarakatan asli yang berbasis pada ikatanikatan tradisi keturunan sedarah (genealogis), dan ikatan religiositas. Tata-pengaturan adat tersebut telah ada bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dilahirkan (lihat Syafa’at, 2002). Dengan kata lain, devolusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan di sektor publik terhadap pemerintah desa akan berbenturan dengan kelembagaan pemerintahan adat yang telah eksis terlebih dahulu dan legitimate secara tradisonal. Siapa yang harus mendapatkan devolving power dari “atas-desa”? Pemerintah desa formal (menurut UU no. 32/2004) ataukah otoritas adat? Devolusi mengandung dua makna sekaligus, yaitu: transfer tanggung jawab pemerintahan dan pengambil-alihan kekuasaan regulasi atau pengaturan atas segala sesuatu hal (urusan publik) di tingkat lokal. Dalam tata-pengaturan pemerintahan yang mandiri (berbasiskan devolusi), berarti tata-pemerintahan desa harus “relatif bebas” dari campur tangan kekuatan-kekuatan pemerintahan pada hierarkhi otoritas di ”atas-desa” (supra desa) yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Pusat. Namun demikian, studi dari berbagai kasus dan daerahdaerah, mengkonfirmasikan realitas yang sebaliknya. Desa menghadapi tingkat kesulitan yang sangat buruk untuk bisa mengambil alih limpahan kekuasaan yang diberikan oleh otoritas jurisdiksional ”atas-desa” tersebut. Beberapa hambatan struktural yang segera tampak adalah, ketidaklengkapan dan ketidakberfungsian kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan kapasitas kepemimpinan serta sumberdaya manusia (perangkat desa), sumber keuangan desa yang terbatas, dan lingkungan lain yang tidak mendukung. Dengan demikian, dorongan keinginan desa untuk mampu menjalankan sistem tata-kelola pemerintahan desa yang otonom dan 14 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik mandiri serta baik (rural good and self-reliant governance system), tidak mungkin diwujudkan segera (dalam hitungan hari atau bulan), bahkan bisa bertahun-tahun lamanya. Secara konseptual-teoretikal, untuk bisa mencapai derajat kemandirian yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi lokal, maka harus dilakukan pentahapan pengembangan kelembagaan pemerintahan desa. Dengan mengadaptasi konsep “state building” dari Fukuyama (2004), akan didapatkan dua dasar penting terbentuknya sebuah tata-pemerintahan (lokal) yang efektif, yaitu: (1) derajat efektivitas pemerintahan yang tinggi, dan (2) spektrum dari fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan – the the scope of governmental function yang tidak terlalu melebar. Dari konsepsi Fukuyama, tersebut dirumuskan empat bentuk tata-kelola pemerintahan (desa) sebagaimana tampak pada Gambar 1. Derajat Efektivitas Pemerintahan – sangat tinggi I IV Tipe ideal pemerintahan desa yang kuat dan sangat efektif dengan fungsi terbatas/ringkas Scope of governmental function – Pemerintah desa yang sangat efektif/kuat dengan peran/fungsi sangat luas Kondisi “ideal “ untuk Indonesia Scope of governmental function – sangat sangat ringkas luas Pemerintah desa yang lemah, tidak efektif dengan fungsi/peran yang sedikit Pemerintah desa yang tidak efektif dengan fungsi/peran yang sangat luas kondisi riil di Indonesia III II Derajat Efektivitas Pemerintahan – sangat rendah Gambar 1. Empat Tipe Sistem Tata Pengaturan Pemerintahan Desa (dimodifikasi dari Fukuyama, 2004) Pada Gambar 1, terpetakan empat tipe sistem tata-pengaturan pemerintahan desa dengan kombinasi derajat efektivitas pemerintahannya dan luasnya fungsi pemerintahan yang dijalankan. Setiap kombinasi diwakili oleh satu ruang. Dimulai pada ruang I, adalah wilayah dimana ditemukan pemeritahan desa dengan rentang fungsi/peran administratif-kewenangan yang sangat luas, namun dalam waktu yang bersamaan kekuatan organisasi pemerintahan desa pun sangat efektif dan kuat untuk menopang penyelenggaraan semua urusan tersebut. Ruang ini bila tercapai, adalah kondisi ideal tata-pemerintahan lokalitas (desa) ala Indonesia (sesuai yang diamanatkan oleh UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005). 15 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Sebagaimana diketahui hasil studi di Sumatera Barat, misalnya, mengkonfirmasi ditemukannya lebih dari 100 urusan publik yang harus ditangani oleh organisasi pemerintah desa pada saat ini. Jumlah tersebut sangat besar untuk ukuran sebuah sumberdaya pemerintahan desa yang kebanyakan dalam keadaan sangat terbatas. Meski baik untuk mewujudkan cita-cita kemandirian masyarakat lokal, namun secara organisasional kelembagaan pemerintahan desa seperti ini berpotensi mengarah ke chaotic-bureaucracy yang bergerak sempoyongan ”tanpa fokus”, karena banyaknya fungsi yang harus ditangani/diselesaikan. Pada ruang II, terdapat kawasan dimana ditemukan kelembagaan dengan kapasitas/efektivitas pemerintahannya yang sangat rendah (sehingga sangat lemah) namun pada waktu yang bersamaan, pemerintahan desa juga harus menjalankan fungsi yang sangat luas. Tipe ini adalah tipikal pemerintahan desa yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia saat ini. Pada ruang ini pemerintahan desa benar-benar berada pada status failed-government. Tipe tatakelola pemerintahan yang demikian, dinilai sangat buruk karena memiliki ketahanan organisasionalnya sangat kecil sehingga rentan mengalami “destabilisasi” dan “guncangan” atau organizational chaos. Dalam posisi seperti ini”bantuan” dari kelembagaan ”atas-desa” mutlak diperlukan. Dengan kata lain, fenomena ketergantungan pemerintah desa pada sumberdaya luar tampak sangat menonjol di ruang II ini. Ruang III mewakili kawasan dimana pemerintahan desa yang sangat lemah (tidak efektif) meskipun fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebenarnya tidaklah banyak. Tipe tata-kelola pemerintahan pada ruang III adalah tipe terburuk dari keempat tipe yang ada. Pemerintahan desa benar-benar gagal berperan, sekalipun tidak banyak hal yang harus ditangani. Sementara itu, Ruang IV mewakili kawasan dimana ditemukan ”tipe ideal” sebuah tata-pemerintahan desa menurut konsep Fukuyama. Pada wilayah ini, kekuatan efektivitas-pemerintahan desa berada pada derajat yang sangat kuat. Artinya pemerintahan desa mampu mengendalikan semua kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menopang dan mewujudkan cita-cita masyarakat desa (kesejahteraan, kemandirian, keadilan, dan martabat). Karena fungsinya yang sangat ringkas, pemerintahan desa mampu melakukan fokus, dan menjalin sinergi serta kerjasama kemitraan dengan pihak luar pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan tersebut. Jika dipetakan dengan menggunakan kerangka pemikiran Fukuyama (2004) tersebut, maka semua desa di Indonesia akan “terbagi habis” (teralokasikan) ke dalam setiap ruang. Persoalannya, jika ruang IV adalah ”tipe ideal” yang hendak dicapai, maka bagaimanakah cara mentransformasikan sistem tata-pemerintahan desa-desa yang berada di ruang I, II, dan III ke ruang IV. Apakah ruang I adalah tipe ideal ”sementara” yang seharusnya dicapai terlebih dahulu (sesuai UU no. 16 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 32/2004). Di ruang ini, dilakukan tahapan paling penting yaitu pemberdayaan2 infrastruktur kelembagaan pada sistem tata-kelola pemerintah desa seraya terus mengefisienkan fungsi dan peranannya. Pemerintahan desa sepantasnya berkonsentrasi pada fungsi eksekusi di tingkat kepala desa, yaitu: pelayanan publik dan pelaksanaan regulasi dimana scope-nya pun harus ringkas. Sementara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkonsentrasi pada fungsi legislasi, supervisi, dan joint-decision making di saat diperlukan bersama-sama dengan pemerintahan desa. Fungsi lain seperti incomegenerating function dilakukan secara terpisah dalam tata-pemerintahan desa namun tetap dalam kendali kelembagaan eksekutif dan legislatif desa. UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 juga memungkinkan dikembangkannya jejaring kerjasama sosial-ekonomi melalui pola kemitraan atau partnership dengan pihak lain (publik) sesuai koridor hukum yang berlaku. Agar good rural governance system bisa tercapai, maka diperlukan sejumlah upaya membangun keberdayaan desa (rural empowerment). Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu adalah penataan fungsi kelembagaan, perkuatan kapasitas organisasional melalui pengembangan kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia (SDM), serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan desa yang efektif. Pertanyaannya, penataan spesifik apa sajakah yang semestinya dilakukan? Meski demikian, agenda pekerjaan untuk mereformasi tata-pemerintahan desa ke arah otonomi lokal (desa) yang kuat, bukanlah hal yang mudah untuk sertamerta diwujudkan tanpa perhitungan dan analisis yang matang. Diperlukan serangkaian riset-aksi yang memadai untuk bisa mengindentifikasi kekhasankekhasan yang dimiliki oleh setiap desa, sehingga strategi penataan tatapemerintahan desa menjadi khas sifatnya. Setting geo-sosio-ekologi-lokal, sosiobudaya, struktur-kemasyarakatan, spasial-kewilayahan, sosio-politik, dan faktorfaktor lain akan sangat mempengaruhi tampilan sistem tata-pemerintahan desa di suatu kawasan, yang selanjutnya menghendaki pendekatan yang berbeda-beda antara satu dan lain desa. 2 Terdapat banyak batasan tentang pemberdayaan (empowerment), dalam hal ini dua batasan yang bisa dikutip adalah: “empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally “taking over power from somebody else” at the purely political level. This means, it includes knowledge, education, organization, rights, and ‘voice’ as well as financial and material resources” (Schneider, 1999). Sementara itu batasan lain adalah: empowerment may, sociopolitically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance (Osmani, 2000). 17 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Diharapkan, ditemukan sebuah innovasi rancangan sistem tata-pemerintahan desa yang bisa dihasilkan melalui rangkaian studi-aksi yang dilakukan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Institut Pertanian Bogor (PSP3IPB) yang bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform – United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia. Riset-aksi berjudul “Partnership-Based Rural Governance Reform” yang dilaksanakan sepanjang tahun 2006 ini, diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan sebagaimana terpapar di atas yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban dalam memberdayakan/memperbaiki kapasitas pemerintahan lokal (desa). Studi-aksi pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan konstruktif tatakelembagaan dan gagasan ke arah reformasi tata-kelola pemerintahan desa dan tatakelembagaan yang konstelasi fungsional-strukturalnya lebih adil, lebih baik, efektif dan mandiri. Good-rural governance dicapai pada aras lokalitas (desa) yang mencerminkan otonomi pemerintahan lokalitas (desa) yang sejatinya. Hasil studi-aksi diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi tercapainya sistem tata-pemerintahan yang lebih kondusif dalam pencapaian cita-cita demokrasi, otonomi, serta kesejahteraan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan lokalitas (desa). Hasil studi secara umum diharapkan menjadi sumber ilmu-pengetahuan khususnya dalam hal kajian sistem ketata-pemerintahan desa (rural governance system) di Indonesia. 1.2. Tujuan dan Manfaat Studi-Aksi Masalah utama yang menantang untuk segera ditangani oleh studi-aksi ini adalah menjawab permasalahan: (1) lemahnya atau tidak efektifnya kinerja sistem tatapemerintahan yang mewadahi beragam kepentingan di tingkat lokal (desa) sebagai akibat akumulasi kekuatan kewenangan kelembagaan di hierarkhi “atas desa” maupun “dalam desa”; (2) ketidakmandirian desa dalam menopang dan mewujudkan masyarakat desa yang berdaya dalam menghadapi segala persoalan sosial-ekonomi-kemasyarakatan, (3) Tidak kondusifnya tata-pemerintahan desa sebagai akibat berbagai persoalan yang melekat secara struktural seperti dominasi kekuasaan oleh otoritas “atas desa” serta adanya faktor kultural lainnya, (4) ketiadaan wadah kebersamaan yang bisa menjadi infrastruktur sosial kelembagaan penyambung kepentingan/aspirasi di tingkat lokal maupun regional untuk menekan munculnya ketidakselarasan dalam tata-pengaturan desa. Singkatnya, kehidupan sosial-ekonomi, politik desa (lokalitas) akan mengalami stagnasi (kemandegan), bila sistem pemerintahan desa yang berperan sebagai aktor penting penggerak dinamika sosial-kemasyarakatan desa dan sebagai pivotal institution pada pemerintahan otonom desa tidak direvitalisasi dan diperbaharui. Pendekatan strategis yang dirancang (diharapkan mampu) untuk menjawab permasalahan di atas adalah: 18 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 1. Memperlengkapi dan memperkuat kapasitas dan fungsi-fungsi sistem kelembagaan pemerintahan desa sehingga desa mampu memberikan pelayanan kehidupan sosial-ekonomi dan politik yang lebih memadai di tingkat lokalitas (desa). 2. Mengembangkan pola-pola partnership-based rural administrative management and rural governance system di aras lokal, yang memegang teguh prinsip partisipasi, dimana setiap pemangku kepentingan diakomodasi aspirasinya 3. Mengintegrasikan para pihak dalam suatu pendekatan pengelolaan tatapemerintahan desa yang demokratis dan berlandaskan pada solidaritas serta kemitraan. Dengan prinsip-prinsip ini, keberdayaan pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh inisiatif sepihak, top-down, dan dijauhkan dari praktekpraktek intransparansi yang tidak akuntabel dan tidak adil. Untuk menjawab permasalahan tata-pemerintahan desa di atas, dirumuskan tujuan studi-aksi ini sebagai berikut: 2. Mengidentifikasi permasalahan penting dan melakukan pemetaan atau tipologi sistem tata-pemerintahan desa (termasuk konstelasi kekuasaan dan kewenangannya dengan kelembagaan adat) di beberapa kawasan terpilih, yaitu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali dan Papua. 3. Menemukan alternatif tata-pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip OTDA namun juga memberdayakan dan memandirikan masyarakat (warga desa) secara sosial-ekonomi dan politik. 4. Merumuskan dan mengembangkan tata-kelembagaan yang sesuai dengan konteks sosio-budaya dan ekonomi lokal dalam sistem tata-pemerintahan desa yang berbasiskan prinsip kemitraan. 5. Mengembangkan mekanisme pembaharuan tata-pemerintahan pedesaan di Indonesia, melalui diseminasi temuan akademik dan pengembangan wacana ilmiah dalam kerangka governance studies. 1.3. Ruang Lingkup Studi dan Metodologi Studi-aksi dijalankan di lima provinsi terpilih dengan pertimbangan kekhasan yang dimilikinya, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam (mewakili provinsi yang mengalami konflik sosial cukup lama), Sumatera Barat (mewakili kawasan dengan pengaturan adat “Nagari” yang kuat dan terpelihara), Jawa Barat (mewakili desa ala Jawa), Bali (mewakili kawasan dengan tata-pengaturan komunitas lokal berbasis religiositas yang kuat), dan Papua (mewakili kawasan Timur Indonesia dengan sistem ondoafi yang masih dominan). Pada setiap provinsi kasus, dipilih satu kabupaten yang akan dijadikan lokasi penelitian, dimana di setiap kabupaten tersebut ditentukan dua desa sebagai lokasi penelitian dan aksi. Studi-aksi partnership-based rural governance reform ini akan didekati dari berbagai disiplin. Setiap disiplin terintegrasi dengan disiplin lainnya, sehingga sifat penelitian adalah interdisipliner namun tetap memberikan ruang yang 19 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik mencukupi bagi setiap disiplin untuk menjalankan aktivitas dan metodologi riset secara mandiri. Setiap disiplin ilmu memberikan fokus perhatian pada suatu fokus kajian penelitian, sebagai berikut: (1) sosiologi pedesaan memfokuskan pada kajian kelembagaan dan kepemimpinan lokal, (2) ilmu pengembangan wilayah pedesaan memfokuskan pada kemungkinan-kemungkinan pengembangan desa di masa OTDA, (3) ilmu administrasi-pembangunan, memfokuskan pada proses-proses perumusan kebijaksanaan di berbagai aras pengambilan keputusan, (4) ilmu politik, melihat lebih dalam politik desentralisasi dan otonomi desa, (5) ilmu komunikasi dan gender, mengkaji komunikasi administratif dan peranan wanita, (6) ilmu ekonomi, memperhatikan derajat kesejahteraan ekonomi rumahtangga di masa OTDA, (7) ilmu ekonomi, melihat peluang pengembangan ekonomi lokal, (8) sosiologi agraria, melihat persoalan konflik agraria, (9) manajemen sumberdaya alam, melihat kelembagaan pengaturan sumberdaya alam lokal. Output dari studi-aksi ini adalah sebuah lessons learned yang akan didokumentasikan secara sistematis dalam working paper series dan buku, serta disebarluaskan ke khalayak akademik, praktisi, maupun masyarakat luas. Secara metodologis, pendekatan kuantitatif maupun kualitatif (metode indepth interview, focus group discussion, obervasi berpartisipasi) digunakan untuk memahami persoalan riil di lapangan. Beberapa temuan awal studi-aksi berupa peta permasalahan tatakelola pemerinthan lokalitas (desa) di lima provinsi kasus tersebut disajikan pada bagian-bagian akhir paparan ini pada working paper ini. 20 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 2 KERANGKA KONSEPTUAL 2.1. Desa sebagai Entitas Sosial: Pandangan dari Beberapa Perspektif Sebelum membahas secara lebih komprehensif dan mendalam tentang pembaharuan dan revitalisasi tata-pengaturan pemerintahan desa (rural governance), dipandang sangat mendesak, untuk terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang makna desa. Dalam ilmu sosial, desa memiliki multi-makna dan dapat ditafsirkan berbeda-beda tergantung perspektif atau “logika” apa yang digunakan untuk memahaminya. Dari perspektif, geografi-kultural, desa sematamata dipandang sebagai ruang yang terbentuk dari kesatuan lokalitas-spasial, dimana di”atas”nya dibina sebuah kehidupan sosial. Pola adaptasi-ekologis yang dijalin-berkesinambungan di kawasan itu, menyebabkan ditemukannya sistemsistem sosio-kemasyarakatan dengan karakter budaya yang khas. Oleh karena karakter tersebut melekat pada setting sistem sosio-eko-geografi setempat (yang distinct), maka setiap desa secara geografis menampilkan kekhasan karakter sosioeko-geo-budaya sesuai kekhasan kawasan tersebut. Perspektif geografi-kultural memberikan pesan penting tentang adanya pola-pola perilaku sosial-budaya dan sosio-politik yang terbentuk sebagai konsekuensi bekerjanya kekuatan-kekuatan alam. Dari perspektif sosiologis, desa dipahami sebagai sebuah ruang dimana sebentuk entitas-sosial hadir dan membina dinamika hubungan sosial secara intensif. Entitas sosial tersebut mendiami dua sub-ruang, sekaligus yaitu ruang-sosial dimana proses-proses sosial berlangsung, dan ruang fisik spasial/teritorial dimana warga mendapatkan berbagai dukungan-penghidupan – livelihood supporting system – (sandang, pangan, papan) yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Ruang sosial sendiri, bisa berwujud “abstrak” manakala, space tersebut dipahami dalam konteks sosio21 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik budaya, dimana di dalamnya didapati gugusan supra struktur sosial yang terdiri dari “sistem ideologi, sistem nilai, orientasi etika kehidupan sosial, dan norma-norma sosial dari berbagai tingkatan”. Supra struktur sosial tersebut selanjutnya membina dan mengokohkan kesatuan kehidupan sosial masyarakat di lokalitas yang bersangkutan. Di kedua sub-ruang (spasial dan sosial) tersebut, pengaruh negara hadir melalui infrastruktur kelembagaan administrasi pemerintahan desa. Bersama-sama dengan supra struktur sosial, kelembagaan pemerintahan desa ikut menjaga harmoni kehidupan sosial, utamanya memastikan berjalannya proses-proses pelayanan sosial, dan proses fasilitasi interaksi warga dan negara di ruang publik (public sphere). Jadi, desa dalam pengertian sosiologis adalah ruang dimana entitas sosial terbentuk dan membina dirinya, di suatu teritorial tertentu, dimana infrastruktur kelembagaan pemerintahan desa (bersama supra struktur sosial) memungkinkan interaksi sosial antara negara (state) dan warga negara, serta antara sesama warga negara (citizen) berlangsung secara harmonis dan intensif. Dari perspektif sosiologi masyarakat kecil, konsep kesatuan sosial di suatu desa seringkali dipahami dalam konteks yang boleh saling-dipertukarkan (interchangeable) dengan konsep komunitas3. Dalam hal ini desa dipandang sebagai sebuah entitas sosial di suatu kawasan mikro, dan merupakan subset (himpunan bagian) dari gugus sistem sosial yang lebih besar. Warga atau penduduk yang ada di dalam kawasan tersebut membangun sebuah konfigurasi sosial-budaya yang khas. Ruang-interaksional yang terbentuk membangun dinamika hubungan sosial kerjasama, hingga persaingan, ketegangan ataupun konflik sosial antar sesama warga/penduduk, dan antara warga/penduduk dengan lingkungannya. Dengan pemahaman seperti ini, desa menjadi teritori yang memungkinkan konfigurasi sosio-budaya terbangun secara sistematis. Dalam kenyataan, sebuah desa bisa menjadi “habitat” dari satu atau bahkan lebih dari satu komunitas khas. Dari perspektif administrasi pemerintahan, desa dipahami semata-mata sebagai sebuah ruang-tempat bekerjanya sistem administrasi pemerintahan publik dimana batasbatas pelayanan dan fungsi-administratif terdefinisi secara jelas. Dalam ruang yang demikian itu, pemangku otoritas administrasi publik memenuhi hak-hak kewarganegaraan yang dimiliki oleh warga desa. Sementara, pada saat yang bersamaan pemangku otoritas administrasi mengelola dan mengontrol berbagai 3 Wilkinson (1970) memahami komunitas secara sederhana sebagai: “ kumpulan orangorang yang hidup di suatu tempat (lokalitas), dimana mereka mampu membangun sebuah konfigurasi sosial-budaya, dan secara bersama-sama menyusun aktivitas-aktivitas kolektif (collective action)”. Sementara Warren dalam Fear dan Schwarzweller (1985) memahami konsep komunitas sebagai: “kombinasi dari lokalitas (kawasan) dan unit-unit sosial (manusia dan kelembagaan sosial) yang membentuk keteraturan, dimana setiap unit sosial menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara konsisten, sehingga tersusun sebuah tatanan sosial yang tertata secara tertib” 22 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik kewajiban yang melekat dan harus ditunaikan oleh warga desa setempat kepada negara. Dengan kata lain, desa menjadi ruang dimana pemangku otoritas melakukan olah-kekuasaan sesuai dengan mandat kewenangan sah yang diperoleh dan disandangnya dari negara. Dalam menjalankan kewenangannya, pemangku otoritas administrasi mendapatkan legitimasi hukum yang dikukuhkan oleh peraturan perundangan negara. Dengan pengertian ini, maka desa adalah tempat dimana sebuah organisasi pemerintahan yang sah menjalankan aktivitas-aktivitas organisasional secara sistematis. Keseluruhan jejaring fungsi dan peran di setiap lapisan tata-pemerintahan desa tersebut membentuk kesatuan administrasi pemerintahan yang kemudian disebut sebagai pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh sejumlah perangkat desa dan seperangkat kelembagaan desa. 2.2. Desa sebagai Social Container: Dilema dan Konflik Eksistensial Dalam kajian dinamika sosial-kemasyarakatan, pemahaman seseorang pada konsep desa selalu merujuk pada mindset desa sebagaimana pengertiannya terbentuk dalam gambaran perspektif sosiologis, yaitu sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat yang membentuk sistem sosial dengan proses-proses sosial yang dinamis. Kawasan tinggal mereka terdefinisi dengan baik dimana batas-batas geo-sosio-ekologis ditentukan secara spesifik berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antar berbagai pihak dan diapresiasi dengan baik. Dalam perspektif yang demikian itu, desa digambarkan sebagai penyatuan dua ruang yang sebenarnya memiliki eksistensi yang terpisah, yaitu ruang sosial dan ruang spasial. Dalam pemahaman seperti ini, desa dipandang sebagai “social container” yang mengangkut sekumpulan orang yang mengembangkan sejumlah atribut kelembagaan, sosio-budaya, sistem-sistem ekonomi produksi dan subsistensi, kekuasaan, sistem iodeologi, tradisi, dan sistem norma yang melekat dan berlaku sah di suatu kawasan. Di “atas” kesatuan sosial yang firm itu, bekerja sebuah sistem pengaturan berupa administrasi pemerintahan yang menyatukan keseluruhan elemen sosial di ruang sosial dan spasial menjadi kesatuan yang utuh-terintegrasi menjadi sebuah sistem sosial desa. Pada titik inilah, pemerintahan desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem sosial desa, dimana pemerintahan desa adalah infrastruktur pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan satu-satunya yang bekerja secara sah di kawasan tersebut. Namun, pada kenyataannya, desa tidak selalu membawa sistem pengaturan sosial-kemasyarakatan yang tunggal. Selalu dimungkinkan adanya beberapa sistem pengaturan yang hadir secara bersama-sama dengan pemerintahan desa. Salah satunya adalah sistem tata-pengaturan adat yang tunduk pada sistem norma yang berlaku pada customary-law (hukum adat). Kehadiran dua atau lebih sistem pengaturan sosial-kemasyarakatan, mengantarkan desa menjadi sebuah sistem sosial yang sangat kompleks. 23 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Realitas semacam ini boleh-jadi berlangsung di sebuah teritori desa yang “mengangkut” beberapa sub-ruang sosial dimana di setiap sub-ruang diisi oleh karakter sosio-budaya yang khas. Artinya, desa menjadi “tempat-hidup” (Lebensraum) bagi sejumlah komunitas dengan ciri sosio-budaya yang beraneka (pluralistik) dimana masing-masing komunitas memberlakukan sistem pengaturan sesuai sistem norma yang dianutnya. Oleh karena itu, terbentuklah sistem kekuasaan, sistem sosio-politik dan tata-pengaturan pemerintahan yang terkotak-kotak sesuai sistem ideologi masing-masing komunitas. Dengan setting yang demikian, maka desa menjadi arena olah-kekuasaan (power and authority exercise) dari sejumlah komunitas, dimana setiap sistem hanya tunduk pada “logika” sistem norma yang dipelihara oleh komunitas masing-masing. Konstelasi beragam kekuatan sistem pengaturan mengantarkan desa menjadi ruang konflik kepentingan dan konflik tata-pengaturan. Kenyataan inilah yang makin mempertajam makna desa sebagai ruang konflik sosial (social conflict) daripada sekedar ruang hidup bersama. Kebanyakan desa-desa di pelosok luar Pulau Jawa, menggunakan ikatan kinship atau kesatuan-genealogis sebagai justifying reason untuk mengoperasionalisasikan tatapengaturan berbasiskan hukum adat. Ikatan genealogis pula yang digunakan sebagai dasar pemetaan luas-wilayah cakupan otoritas pemerintahan tradisional (adat). Dengan kata lain “batas-batas” keturunan sedarah digunakan untuk mendefiniskan seberapa luas cakupan wilayah ruang sosial dan ruang spasial sebuah komunitas dalam membangun tatanan sosial-kemasyarakatan di suatu kawasan. 2.3 Desa sebagai Arena Pertarungan Otoritas Kelembagaan Dalam banyak hal, seringkali ditemukan fakta bahwa, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemangku otoritas kelembagaan (pemerintahan) adat saling tumpangtindih dengan fungsi-fungsi pengaturan yang dijalankan oleh otoritas pemerintahan desa formal. Disinilah kemudian terjadi sindroma dilema eksistensial dan dilema konflik wilayah otoritas diantara kelembagaan-kelembagaan pengaturan kehidupan sosial-kemasyarakatan. Di satu sisi masyarakat desa sebagai warga negara, harus mengakui eksistensi pemangku otoritas pemerintahan desa (kelembagaan formal), namun di sisi lain, sebagai warga adat yang terikat oleh kesatuan kinship dalam “logika” kesatuan genealogi, harus pula mengakui dan tunduk pada pranata-pranata sosial yang dipelihara oleh pemangku otoritas adat. Sementara itu, baik pemangku otoritas adat maupun pemangku otoritas kelembagaan formal (pemerintah desa), seringkali keduanya berada di “wilayah urusan-urusan publik” yang saling overlapping sesamanya. Sebagai misal, kedua pemangku otoritas berkepentingan terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut penyelesaian persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan umum, seperti penataan dan pemanfaatan sumberdaya agraria lokal, pengelolaan pemukiman, transaksi ekonomi, pewarisan, jual-beli tanah, penyelesaian konflikkonflik sosial, masalah kependudukan, dan sebagainya. Jebakan krisis eksistensial 24 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik dan krisis konfliktual di ruang publik itu bisa dipahami, karena wilayah otoritas kedua kelembagaan seringkali tumpang-tindih. Tumpang tindih kekuasaan dan otoritas di ruang (pelayanan administrasi) publik seperti ini, membuat desa menjadi sebuah kesatuan sosial-kemasyarakatan yang tidak sederhana. Secara spasial, cakupan luas-wilayah otoritas adat yang dasar operasionalisasinya menggunakan basis ikatan-genealogis, – lazim ditemukan pada suku-bangsa Minangkabau (di Sumatera Barat daratan), Batak di Sumatera Utara, Dayak (di Pulau Kalimantan), ataupun suku-suku asli di Papua –, akan sangat ditentukan oleh seberapa luas penyebaran tempat tinggal (fisik) penduduk seketurunan berada di wilayah itu. Semakin luas persebarannya, semakin luas wilayah otoritas adat akan mendapatkan justifikasi spasial yang sah. Kesatuan wilayah otoritas adat berbasiskan sedarah-seketurunan yang juga mencirikan kesatuan (kesamaan) karakter sosio-budaya-spasial di Minangkabau disebut sebagai “kaum”. Pimpinan otoritas adat “kaum” adalah para ninik-mamak (tetua adat). Bagi suku Dayak di Kalimantan, basis ikatan-genealogis membentuk kesatuan wilayah otoritas adat “ketemenggungan”, dengan temenggung sebagai pemegang otoritas tunggal (single authority actor) dalam tata-pengaturan adat (lihat Dharmawan, 2001). Di Papua, dikenal ondoafi (andewapi) sebagai penguasa adat yang memiliki cakupan luas-wilayah otoritas kelembagaan meliputi beberapa suku di bawahnya. Setiap suku tinggal di wilayah-wilayah yang bisa lebih luas daripada luas-wilayah sebuah sistem administrasi pemerintahan desa formal. Sekali lagi, luas wilayah (spasial) otoritas adat dan luas wilayah spasial “kaum”, “ketemenggungan” ataupun “desa adat di Papua” tidak selalu sama luasnya dengan wilayah (spasial) pemerintahan desa. Sementara, fungsi-fungsi (wilayah fungsional dan kewenangan) yang dimiliki oleh otoritas kelembagaan adat seringkali tumpang-tindih dengan otoritas kelembagaan formal (administrasi pemerintahan desa). Dalam hal ini, krisis eksistensial berpotensi terjadi di dua ranah sekaligus, yaitu ranah spasial dan ranah fungsional bagi dua kelembagaan yang hidup saling bersinggungan. Pesinggungan wewenang ini digambarkan oleh otoritas Ondoafi di Papua sebagai berikut: 1. Memelihara sumberdaya alam lokal (hutan, tanah, air). Ondoafi menjaga hak ulayat di wilayahnya, termasuk pengaturan pengalihan hak-pakai atas tanah dari satu warga masyarakat ke warga yang lain. Proses sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional pun tidak akan pernah bisa berlangsung tanpa ada persetujuan dari ondoafi. Dalam hal ini kewenangan ondoafi sangat mutlak. Artinya, pengalihan hak atas tanah tidak akan pernah absah tanpa persetujuan lisan dan tertulis dari ondoafi. Kewenangan yang mutlak dalam hak ulayat, ini seringkali menyulitkan pihak pemerintah kampung (desa) untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di tingkat lokal secara segera. Alokasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam lokal seringkali menjadi titik-rawan konflik antara dua pemangku otoritas (kelembagaan adat ondoafi versus kepala kampung). 25 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 2. Menjaga keamanan, menjaga keselarasan kehidupan, serta melindungi warga masyarakat. Ondoafi menjaga harmonisasi hubungan antar suku yang hidup bermasyarakat di suatu lokalitas. Konflik warga antar suku, harus diselesaikan oleh ondoafi sebelum persoalannya dibawa ke otoritas pemerintah desa atau kepolisian. 3. Pengaturan perkawinan antar warga masyarakat. Tata-aturan adat perkawinan harus dipelihara dan ditegakkan oleh ondoafi selain oleh pemerintah desa dalam urusan administrasi formalnya. Jadi, suatu persoalan sosial-kemasyarakatan, dapat menempuh dua cara penyelesaian, yaitu: ”diselesaikan secara adat” atau ”diselesaikan secara hukum formal”. Meski demikian supremasi hukum adat tampak nyata di Papua. Dalam berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan, tidak akan pernah ada suatu keputusan administrasi formal yang ditetapkan secara definitif sebelum dicapai kesepakatan/keputusan di tingkat adat terlebih dahulu. Dalam hal ini, kekuatan keputusan adat jauh lebih legitimate di mata masyarakat daripada keputusan pemerintah kampung (pemerintah desa). Sekalipun demikian, kewenangan ondoafi pun tidak selalu bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan kedudukannya selalu dikontrol secara penuh oleh kelembagaan “sulung” (terdiri dari mereka yang dituakan dalam keluarga sedarah-seketurunan ondoafi). Demikianlah tatapengaturan sosial-kemasyarakatan yang ”berlapis” dijalankan di tanah Papua. Jika ondoafi (di Papua) atau ninik mamak (di ranah Minang) memiliki legitimasi kekuasaan dan wewenang berbasis keturunan sedarah, maka di beberapa kawasan ditemukan pula sistem tata-pengaturan adat lainnya yang berbasiskan bukan sedarah-seketurunan. Dalam hal ini, basis religiositas dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendefinisikan wilayah otoritas adat di suatu lokalitas (desa). Sistem kesatuan masyarakat mukim di Aceh – yang menggunakan masjid jamie (tempat peribadatan umat Islam, yang dipimpin oleh Imum Mukim) sebagai benchmark –, dan “desa adat” di Bali – yang menggunakan pura (tempat peribadatan agama Hindu) di Bali sebagai patokan wilayah otoritas adat –, adalah dua contoh kasus yang mewakili pendefinisian (penetapan) kesatuan lokalitas dalam konteks kesatuan sosio-budaya dimana wilayah otoritas adat ditetapkan dengan dasar sistem religi. Di Bali, desa adat tersebut dikenal sebagai pakraman dimana Pendeso Adat atau Kelian Adat merupakan pemangku otoritas utama pada kelembagaan adat dengan cakupan kekuasaan yang lebih luas daripada cakupan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa formal menurut UU no. 32/2004 (desa formal di Bali disebut dengan sebutan lokal sebagai “desa dinas”). Kewibawaan para Kelian Adat (di Bali), Ondoafi (di Papua), Imum Mukim (di Aceh) ataupun Ninik Mamak (di ranah Minangkabau) seringkali lebih kuat daripada Kepala Desa. Hal ini dikarenakan, hubungan sosial warga dengan para tetua adat didasarkan pada ikatan-ikatan emosional yang telah mengakar sejak lama dan bukan hanya sekedar ikatan atau hubungan administrasi saja. Sifat hubungan “lebih hangat”, karena basis hubungan ikatan persaudaraan. Juga, prinsip primus 26 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik inter pares, membuat mereka lebih dihargai sekalipun cakupan luas-wilayah spasial dan luas-wilayah otoritas adat “kaum” dan “ondoafi” (dalam sistem berbasiskan ikatan-genealogis), ataupun “kemukiman” dan “ pakraman” (dalam sistem berbasiskan ikatan-religi), memiliki coverage secara geografis yang lebih luas (melintasi batas desa formal menurut definisi negara). Sekali lagi, disinilah seringkali benturan kepentingan atau konflik otoritas dan kekuasaan pada kelembagaan pengaturan (institutional conflict) terjadi. Konflik kelembagaan itu biasanya dipicu oleh ketidakjelasan tentang siapa sesungguhnya pengambil keputusan prinsipial (utama) yang harus bertanggungjawab atas suatu urusan di ruang publik desa. Untuk membanding perbedaan antara kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan desa lokal, Gambar 2 di bawah ini dapat diperiksa. Ketidakjelasan pembagian batas-fungsional, dimana deskripsi “tugas, fungsi, peran dan cakupan kewenangan” (seringkali) berbenturan satu sama lain atau overlapping diantara para pemangku otoritas administratif pemerintahan formal (kepala desa) dan pemangku otoritas adat (ketua adat) membuat sebuah urusan yang sesungguhnya “sederhana” seringkali menemui jalan buntu untuk bisa segera diputuskan. Pada titik ini, tata-pemerintahan desa di banyak kawasan adat menghadapi krisis eksistensial kelembagaan dan konflik-kelembagaan, terutama di ranah fungsional dan spasial (Alfitri, 2006; Busra, 2006, Fahmi, 2006). Kenyataan bahwa pemangku otoritas kelembagaan adat ikut mengatur urusanurusan sosial-kemasyarakatan di ruang publik (memang) sangat dapat dimengerti, karena bagi warganya, mereka (para pemangku otoritas adat) mendapatkan mandat penuh untuk memelihara kesatuan sosial-adat secara seutuhnya. Secara kesejarahan sistem tata-pemerintahan adat ini telah eksis dan berjalan sejak dahulu kala, bahkan ketika tata-pemerintahan desa belum terbentuk. Dalam hal ini, otoritas kelembagaan adat juga dimandatkan sepenuhnya untuk memelihara social-conformity atas pelaksanaan norma-norma sosial sejak tingkatan yang paling rendah seperti tatacara, kebiasaan, adat-istiadat, hingga pelaksanaan/ implementasi hukum adat dalam ranking tingkatan norma yang paling tinggi dengan konsekuensi sanksi-hukum yang sangat tegas. Di Bali, para Kelian Adat juga ikut-serta mengurus hal-ihwal pemeliharaan jalan-jalan desa yang menghubungkannya ke pura tempat peribadatan agama Hindu. Dalam hal ini, sulit dipisahkan secara tegas, mana urusan publik yang menjadi kewenangan pemerintah desa dan mana yang menjadi porsi otoritas adat. Basis kekuasaan Wilayah kewenangan Pemerintah Desa Rakyat via Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Negara atau Pemerintah Semua urusan yang diatur oleh peraturan perundangan Kelembagaan Adat Asal-usul keturunan, kewibawaan, kecendekiaan prinsip primus inter pares (kematangan kepribadian/usia) Semua urusan di satuan wilayah genealogis atau religi biasanya cakupannya pada hak ulayat 27 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Sistem pengendalian organisasi sosial Kepatuhan/keterlibatan emosional masyarakat terhadap pimpinan Sistem Birokrasi Utilitarian optimalisasi manfaat ekonomi, efisiensi, produktivitas Kalkulatif, ”kering”, formalistik, organik-fungsional Legal-rasional mekanisme kerja terdefinisi dalam prosedur yang baku Sistem Insentif Remunerasi dari negara Decision-making process Kepala Desa, kelembagaan formal pemerintahan desa (BPD) dan “arahan” pemerintah Kabupaten Peraturan desa dan sistem hukum legal di “atas”nya (Perda, PP, UU) Semua urusan administrasi publik, dan pembinaan kehidupan sosialkemasyarakatan Instrumen pengatur kehidupan sosial Urusan pokok yang ditangani Normatif operasionalisasi nilainilai budaya leluhur Kewajian moral, ”hangat”, informal dan melibatkan ikatan emosional, mekanis-interpersonal Melekat pada kharisma pemimpin adat (misal: ninik-mamak, ondoafi) tergantung kearifan sang pemimpin Penghargaan sosial dari masyarakat kehormatan dan rasa disegani Forum penghulu (pemimpin) adat dan musyawarah pimpinan masyarakat adat Norma-norma adat lokal dan pranata sosial lokal Pengaturan sumberdaya alam (tanah ulayat) dan pemeliharaan harmoni kehidupan sosial kemasyarakatan Gambar 2. Perbandingan Karakter Pemerintah Desa dan Otoritas Kelembagaan Adat Dalam bidang tata-kelola sumberdaya agraria di desa misalnya, otoritas kelembagaan adat mendefinisikan secara jelas mekanisme baku alokasi sumberdaya alam, tata-cara pewarisan tanah, jual-beli tanah dan penetapan sistem upah dalam pola hubungan sosial-produksi agraria, sistem kontrak, sewamenyewa, bagi-hasil, pengukuhan hak atas tanah, pemanfaatan tanah, mekanisme konservasi sumberdaya alam, mekanisme penyelesaian konflik agraria, dan sebagainya. Dalam bidang tata-kelola sumberdaya keluarga, otoritas kelembagaan adat juga mendefinisikan secara rinci proses-proses pengambilan keputusan dalam soal-soal domestik dan publik rumahtangga, kepemimpinan nafkah, hak asuh anak, perkawinan, perceraian, hubungan pertetanggaan, mekanisme local social-security system, dan sebagainya. Dalam bidang sumberdaya sosial, otoritas kelembagaan adat telah mendefiniskan secara rinci mekanisme aksi-kolektif seperti gotong-royong, kehidupan beragama, keamanan, penegakan peraturan ketertiban, dan sebagainya. “Warna” dari tata-pengaturan dan pengelolaan urusan-urusan ini akan berbeda-beda dari satu ke lain kawasan. Penting untuk disebutkan disini, bahwa dalam banyak kasus, pimpinan (pemangku otoritas) adat adalah kelembagaan adat yang memiliki kekuasaan penuh dan sangat legitimate secara sosial untuk mengendalikan otoritas pengaturan urusan-urusan kehidupan sosial-kemasyarakatan di kawasannya (otoritas adat). Persinggungan kelembagaan terjadi karena urusan-urusan tersebut sesungguhnya juga diamanatkan oleh undang-undang kepada pemerintah desa formal. Secara rinci 28 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik pasal 206 UU no. 32/2004 menyatakan dengan tegas bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Dengan cakupan yang begitu luas, maka pemerintah desa memang berpotensi meng”hegemoni” kekuasan dan wewenang adat. Sehingga konflik sulit dihindarkan. 2.4. Desa sebagai Konsep Pemerintahan Lokalitas: Konstelasi Beragam Kekuatan Pengaruh Berbeda dengan perspektif sebelumnya, disini desa dipahami sebagai konsep tata-pemerintahan lokalitas. Sebagai kesatuan administrasi pemerintahan, maka desa (pemerintahan desa) berhadap-hadapan langsung dengan sistem pemerintahan adat yang telah terlebih dahulu hadir di tengah-tengah masyarakat lokal. Persoalan persinggungan (baca: konflik) kelembagaan sebagaimana disinggung pada sub-bab sebelumnya, hingga taraf tertentu, berpotensi mengacaukan sistem pengaturan-administrasi desa (sebagaimana yang dicitacitakan oleh UU no. 32/2004). Manakala dua kelembagaan yang berbeda karakter dan seharusnya ”hidup di ruang sosial yang berbeda” harus hadir secara bersama-sama di suatu ”wilayah-kehidupan” yang sama, maka pada saat itu keduanya berpotensi untuk melakukan conjunction ataupun separasi, yaitu: bersinergi-kerjasama atau konflik-berbenturan sesamanya. Dua kelembagaan itu adalah kelembagaan adat (menguasai wilayah pengaturan pemerintahan adat) dan kelembagaan pemangku otoritas administrasi pemerintahan desa (menguasai wilayah otoritas pengaturan administrasi formal). Mengapa konflik seringkali berlangsung berkepanjangan dan tidak kunjung menghadirkan solusi yang tuntas? Jawabannya, karena kedua kelembagaan sama-sama memperoleh legitimasi yang sah, yaitu legitimasi tata-peraturan yang melekat pada sistem norma atau hukum adat lokal bagi pemangku otoritas kelembagaan adat, dan legitimasi hukum/peraturan perundangan formal bagi pemangku otoritas pemerintahan desa. Inilah konflik kelembagaan dalam arti yang sebenarnya. Fakta sosial “tumpang tindih fungsi/kewenangan” yang dijalankan oleh dua atau lebih pemangku otoritas di suatu lokalitas, seringkali menghantarkan kawasan ini menjadi arena perebutan wilayah otoritas kelembagaan (institutional conflict) yang memprihatinkan. Alih-alih mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi, warga masyarakat seringkali justru menyeret dua pemangku otoritas untuk ikut dalam pertarungan yang sulit mencapai solusi. Desa secara total menjadi arena konflik kekuasaan (the battlefield of power) yang pengaruhnya dilancarkan oleh kelembagaan-kelembagaan berbeda karakter. Melihat fakta seperti ini, maka 29 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik penataan/pembaharuan ataupun revitalisasi tata-pemerintahan desa sebagaimana idenya dicita-citakan oleh pemerintah melalui UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 jelas menghadapi persoalan yang tidak ringan. Dengan konstelasi kekuasaan dan wewenang antara pemerintah desa dan pemerintahan adat, maka empat kemungkinan pola hubungan fungsional dapat dibangun secara hipotetik. Relasi hubungan tersebut tercermin dalam Gambar 3, di bawah ini. Kelembagaan/Pem erintahan Adat yang Kuat dan Legitimate Kelembagaan/Pem erintahan Adat yang Lemah dan Tak memiliki Legitimasi Pemerintahan Desa yang Kuat dan Legitimate 1. Konflik kekuasaan antara Pemerintahan Desa dan Adat kesamaan kekuatan dan legitimasi 2. Sinergisme kekuasaan bila setiap pihak bersedia mengurangi klaim wilayah kewenangannya Kekuasaan pemerintahan desa berpengaruh lebih dominan dalam menentukan tata-pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal Pemerintahan Desa yang Lemah dan Tak Memiliki Legitimasi Otoritas kelembagaan adat berpengaruh lebih dominan dalam menentukan tata-pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal Pemerintahan desa dan kelembagaan adat, keduanya gagal memelihara sistem sosialkemasyarakatan di lokalitas kegagalan negara dan kegagalan kelembagaan adat Gambar 3. Relasi Kekuasaan dalam Tata-Pemerintahan di Kawasan Lokalitas Dari Gambar 3 dapat dijelaskan empat tipe pola relasi kekuasaan antara pemerintah desa formal dan otoritas adat dalam pengaturan kehidupan sosial di desa. Perinciannya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah desa dan adat yang sama-sama kuat akan menghasilkan dua kemungkinan hubungan kekuasaan dalam pengaturan desa. Pertama, terbentuk hubungan konfliktual karena kekuatan pengaruhnya yang sama kuat. Kedua, terbangun sinergisme kekuasaan, bila setiap pihak berkemauan untuk mengurangi klaimnya atas wilayah otoritas yang dimiliki. Kolaborasi antara pemerintah ”desa adat” dan “desa dinas” di Bali merepresentasikan tipe sinergisme ini. Sementara hubungan konfliktual tampak pada hubungan yang ditunjukkan oleh kelembagaan adat (ninik mamak) versus pemerintahan nagari (baca dalam hal ini sebagai: desa) di ranah Minangkabau. 2. Pemerintah desa yang kuat yang berhadapan dengan kelembagaan adat yang lemah serta tidak legitimate, menghasilkan tata pemerintahan desa formal yang sangat dominan. Desa-desa di Jawa merepresentasikan tipe ini. 3. Pemerintah desa yang lemah bersanding dengan kelembagaan adat yang sangat kuat dan legitimate akan membentuk kelembagaan adat yang sangat dominan. Tipe ini adalah ciri-khas pengaturan lokalitas sebelum konsep (pemerintahan) desa diperkenalkan oleh UU Pemerintahan Daerah. Fenomena ini bisa juga terjadi pada pemerintahan lokalitas di kawasan terisolasi dimana pengaruh kekuasaan negara sangat lemah lemah disana. 30 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 4. Pemerintahan desa dan pemerintahan adat yang sama-sama tidak berdaya, sehingga keduanya gagal membina kehidupan sosial-kemasyarakatan di kawasan yang bersangkutan. Tipe ini jarang ditemukan di Indonesia. Permasalahannya kemudian adalah, bagaimanakah revitalisasi dan pembaharuan tata-pemerintahan lokalitas (desa) dapat dilakukan, dengan melihat tipologi desa semacam itu? Jalur dan arah yang mana yang seharusnya ditempuh untuk memperbaharui sistem tata pengaturan pemerintahan desa di Indonesia? Kelembagaan manakah yang sepantasnya diapresiasi untuk melaksanakan tatapengaturan kehidupan sosial-kemasyarakatan di desa? Persoalan institutional survival menjadi mengemuka karena pasti ada satu atau lebih kelembagaan yang harus dikorbankan atau disisihkan dalam dilema eksistensial dan konflik kelembagaan ini. 3 REFORMASI TATA-PEMERINTAHAN DESA 3.1. Pemerintah Desa dalam Perspektif Actor-Oriented Theory Dipandang dari perspektif “sistem tata-pemerintahan daerah” Republik Indonesia, sebagaimana aturannya tertulis dalam UU no. 32/2004, desa sematamata dipahami sebagai kawasan atau unit administratif terkecil pada hierarkhi terendah dalam sistem tata-pemerintahan negara. Negara sendiri didefinisikan oleh Weber sebagaimana dikutip oleh Luiz (2000), sebagai: “an organization, composed of numerous agencies led and co-ordinated by the state’s leadership (executive authority) that has the ability or authority to make and implement the binding rules for all the people as well as 31 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik the parameters of rule-making for other social organizations in a given territory, using force if necessary to have its way”. Menurut Martinussen (1996) sebagaimana dikutip oleh Luiz (2000) dikatakan bahwa sebuah negara dengan pemerintahannya adalah: (1) produk dari beragam konflik kepentingan, (2) manifestasi dari struktur-struktur yang dirancang dan dimanifestasikan dalam mekanisme-mekanisme fungsional (mode of functioning) yang nyata, (3) arena interaksi dan konflik, (4) aktor yang memiliki legitimasi untuk melakukan segala tindakan yang sah menurut hukum. Dengan mengacu pada pemahaman seperti dikemukakan oleh Weber dan Martinussen, maka pemerintah desa sebagai representasi negara di tingkat lokalitas diibaratkan sebuah “arena” sekaligus “aktor” yang dapat menentukan sikap dan memiliki energi untuk melakukan sesuatu. Artinya, dinamika kehidupan sosial masyarakat desa ditentukan oleh sejauh mana “sang aktor” melakukan manuver-manuver dalam pemerintahan dan berinisiatif menuju perubahan. Semakin terbatas kapasitas kelembagaannya maka akan semakin lemah manuver yang dilakukannya. Artinya, semakin statis pula kehidupan desa setempat. Namun sebaliknya, jika “sang aktor” terlalu agresif bermanuver tanpa ada kontrol yang sistematis dari publik, maka inipun akan membahayakan keseluruhan entitas sosial di tingkat lokal. Berangkat dari perspektif ini, pemerintahan desa memang akan dipahami secara “sempit” semata-mata sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam sistem administrasi pemerintahan negara di aras lokal yang tugas-pokok-fungsi, dan kewenangannya mencakup semua urusan publik (multi-responsibilities) yang dihadapi oleh warga negara setempat. Dengan posisinya yang demikian, maka pemerintah desa adalah aktor penentu tunggal yang mendapatkan legitimasi hukum formal untuk melakukan “apa saja” yang terbaik dan sah menurut hukum formal dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokalitas. Pemerintah desa juga memiliki derajat kebebasan sesuai legitimasinya dalam menentukan langkah dan inisiatifnya dalam mengatur masa depan masyarakat lokal. Model pemerintahan desa menurut UU no. 32/2004, yang sejalan dengan gagasan Weber dan Martinussen ini sebenarnya tipikal mengacu pada sistem tata-pemerintahan desa ala Jawa, dimana tidak ada pemangku otoritas lain yang boleh melakukan tindakan serupa di tingkat lokalitas kecuali pemerintah desa. Sebagai sebuah organisasi sosial4, konsep pemerintahan desa ala Jawa secara historis, memang cenderung menjalankan fungsi dan peran yang multiresponsibilities atau lintas bidang/lintas dimensi (sosio-budaya, pemerintahan, ekologis). Dengan fungsinya yang demikian, maka desa menjadi sebuah “pusatkekuasaan” pengaturan urusan administrasi publik sekaligus pusat pengaturan 4 Konsep organisasi sosial menurut Firth (1955) adalah: “tatanan dari sejumlah elemen tindakan yang dibangun menjadi sebuah sistem yang dibingkai oleh hubungan-hubungan sosial yang dibentuk sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh para pelaku (arrangment of elements of action into a system by limitation of their social relations in reference to given ends as conceived by the actors)” 32 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik urusan adat/tradisi yang relatif all-round. Pemerintah desa juga menjadi aktor penggerak pembangunan dan “sumber ide” bagi masyarakatnya. Pemerintah desa dari dimensi actor-oriented theory, merepresentasikan sebuah entitas yang memiliki kemampuan berkreasi dan bertindak. Masyarakat desa yang kuatprogresif, boleh jadi cerminan dari pemerintah desanya yang mampu mengembangkan gagasan dan inisiatif. Sebaliknya, pemerintah desa yang lemah, maka akan menyebabkan seluruh elemen masyarakat desa yang bersangkutan mengalami kemunduran. Sebagai organisasi pengatur sosial-kemasyarakatan tunggal, maka pemerintah desa merangkap mendistribusikan/memisahkan fungsi, peran dan kewenangan kepada pihak-pihak tertentu berkenaan dengan urusan-urusan yang menyangkut urusan publik,termasuk bila urusan itu bersinggungan dengan adat dan keagamaan. Pengertian ini jelas memiliki konsekuensi yang berbeda secara diametral dengan konsep tata-pengaturan lokalitas yang memisahkan secara tegas urusan di wilayah adat dan urusan pemerintahan formal sebagaimana dikenal pada sistem-sistem pengaturan pada lokalitas asli di luar Pulau Jawa (Nanggroe Aceh Darussalam, Minangkabau di Sumatera Barat, Bali, dan Papua). Dalam perkembangan politik tata-pemerintahan desa, konsep pemerintahan desa ala Jawa terus-menerus mendapatkan peneguhan untuk diterapkan sebagai satu-satunya sistem yang sah dan diakui sebagai mekanisme pemerintahan lokal (tunggal) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Legitimasi hukum itu tampak dari pemberlakuan UU tentang Pemerintahan Daerah sejak UU no. 5/1974, UU no. 5/1979, UU no. 22/1999, hingga UU no. 32/2004. Mengacu pada realitas desa sebagai arena konflik kelembagaan yang tidak dapat dielakkan, maka bila sistem tata-pemerintahan lokalitas ala pemerintahan desa formal hendak dijalankan dengan baik, logikanya harus ada sejumlah asumsikerja yang secara mutlak dipenuhi. Asumsi-asumsi kerja tersebut antara lain adalah: (1) kesatuan teritorial hanya mengenal kesatuan administrasi-spasial dan tidak mengenal kesatuan genealogis (kesatuan wilayah yang dibentuk oleh penduduk seketurunan atau sedarah yang terikat sesamanya serta membentuk konfigurasi sosio-budaya sekaligus sosio-politis), (2) Dalam menjalankan wewenangnya di sektor publik, kepemimpinan formal desa terbebas dari “campur-tangan” otoritas kelembagaan adat, (3) hanya ada sistem ketata-pemerintahan tunggal (single governmental system) dalam pelayanan publik maupun dalam pengaturan persoalanpersoalan kehidupan sosial-kemasyarakatan di tingkat lokalitas (urusan kependudukan, pertanahan, penyelesaian sengketa, perpajakan, dst) , (4) wilayah persoalan adat dan persoalan pemerintahan di sektor administrasi publik, kongruen sesamanya, yang semuanya diserahkan pada pemangku otoritas formal sehingga tidak menyisakan “ruang-kompromi” yang memungkinkan perseteruan bagi pemangku kewenangan adat dan pemangku kewenangan formal. Pada mekanisme pemerintahan desa ala formal, maka kekuasaan untuk menjalankan 33 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik kewenangan formal (formal authority) dan kewenangan adat berada di satu tangan atau posisi kepemimpinan. Persoalannya tidak semua asumsi-asumsi ini dapat dipenuhi oleh sistem pemerintahan desa di setiap lokalitas yang ada di Indonesia. Sistem sosialkemasyarakatan lokalitas di Nanggroe Aceh Darussalam, Minangkabau, Bali dan Papua memberikan pelajaran betapa tata-pemerintahan desa menghadapi persoalan kompleksitas tata-pengaturan dan benturan antara otoritas pemerintah desa formal dengan otoritas adat. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, sejauhmana suatu urusan dianggap berada di “ruang adat” atau di “ruang administrasi formal”? Apakah suatu urusan seperti transaksi “jual-beli tanah” (misalnya) berada sepenuhnya di “ruang administrasi pemerintahan desa/publik” sehingga keputusan atas pengaturannya cukup diselesaikan oleh kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengaturan ruang publik? Atau urusan itu masih menyentuh/berada di “ruang adat”, sehingga kepemimpinan adat harus turut “campur-tangan” untuk mengaturnya? Jika tanah di suatu lokalitas diatur dalam rezim communal property rights, maka tak pelak lagi bahwa transaksi jual beli tanah terpaksa melibatkan pemangku otoritas adat. Namun apakah, tatapengaturan pemerintahan lokalitas “berlogika” desa (formal), mengantisipasi “konflik kelembagaan” seperti di atas? Pertanyaan selanjutnya, sejauhmana terdapat clear-cut yang tegas bahwa suatu urusan berada di ruang wewenang pemangku otoritas publik ataupun di tangan pemangku otoritas adat? Dalam konteks governance, lembaga apa saja (di luar sistem pemerintahan formal) yang berhak dan wajib mengontrol jalannya pemerintahan desa agar berlangsung tata-pemerintahan yang baik? Sebagai aktor penggerak dinamika kehidupan, halhal apakah yang harus dibenahi oleh pemerintahan desa agar organisasi pemerintah desa formal tersebut mampu memberikan energi dan menggerakkan kehidupan sosial-masyarakat desa? Berbagai pertanyaan itulah yang akan menjadi persoalan untuk dijawab dalam pembaharuan tata-pemerintahan desa. 3.2. Mewujudkan Good Rural Governance System Sebagai konsep pengaturan lokalitas terkecil di seluruh wilayah hukum Indonesia, desa sesuai Bab I tentang “Ketentuan Umum” UU no. 32/2004 dijelaskan sebagai berikut: “desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan penerapan rumusan desa sebagaimana konsepnya dipahami pada rumusan UU no. 32/2004 tersebut, maka pemerintah desa adalah satu-satunya sistem tata-pemerintahan atau tatapengaturan sosial kemasyarakatan di lokalitas terkecil yang diakui oleh hukum. Konsekuensinya konsep pemerintahan desa juga akan terus-menerus menghadapi sejumlah konflik-fundamental baik secara kultural (akar normatif) 34 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik maupun secara struktural (konflik kelembagaan). Sebagai “aktor”, pemerintah desa juga dimungkinkan untuk mengambil inisiatif-inisiatif dan menjalankan kehendaknya. Ketika diimplementasikan, tindakan ini berpotensi untuk menabrak wilayah otoritas pihak lain baik pada hierarkhi di atasnya ataupun pada tataran horisontal. Konflik tersebut selanjutnya bisa meluas ke dimensi fungsional berupa benturan kewenangan, dan dimensi wilayah spasial, ataupun meluas ke persoalan konflik yang menyentuh identitas ras, golongan serta etnisitas di suatu kawasan. Sebenarnya, persoalan menegakkan tata-pemerintahan desa yang baik juga dihadapkan pada sejumlah persoalan lain yang lebih luas dari sekedar konflik kelembagaan. Persoalan effectiveness of government (di bawah tekanan konflik kelembagaan) dan control of power (di bawah tekanan perbedaan kekuatan politik lokal) adalah aspek-aspek penting lain yang harus juga diperhatikan dari sistem tata-pengaturan pemerintahan (desa). Inilah persoalan rural governance yang sebenarnya. Terlebih, jika mengacu pada definisi governance (tata-pengaturan, tata-kelola, tatapemerintahan) yang dikemukakan oleh Weiss (2000) seraya mengutip dari Commision on Global Governance, sebagai: “the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is the continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action may be taken”, maka tata-pemerintahan desa di banyak kawasan Indonesia utamanya menghadapi persoalan bagaimana mengelola urusan-urusan publik (common affair), agar transparan dan akuntabel serta diterima secara sosial. Sementara itu World Bank seperti dikutip Weiss (2000) memberikan batasan tatapemerintahan atau governance agak berbeda yakni: “the manner in which power is exercised in the management of the country’s economic and social resources”. Ini berarti persoalan praktek tata-pemerintahan desa yang baik terletak pada kapasitas kelembagaan/organisasi pemerintahan desa dalam mengelola organisasi pemerintahannya. Mengikuti dua batasan di atas, maka setidaknya terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhitungkan/dipermasalahkan dalam sistem tata-pemerintahan yaitu: (1) bentuk rezim (pengaturan) dan mekanisme pengaturan seperti apakah yang sepantasnya dikembangkan, (2) bagaimana proses menjalankan kewenangan dalam tata-kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan, (3) sejauh mana kapasitas (institusi) organisasi-pemerintahan harus dipacu agar mampu melakukan desain dan formulasi kebijakan serta implementasi kebijakan dalam tata-pemerintahan desa. Dari hasil pengamatan sementara yang dihasilkan oleh studi-aksi “partnershipbased rural governence reform” oleh PSP3IPB, teridentifikasi beberapa masalah khusus yang dapat diturunkan dari sistem tata-pemerintahan di tingkat lokalitas/desa. Temuan ini selaras konseptualisasi governance system dari Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2005), yang dapat disebutkan sebagai berikut: 35 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 1. Masalah administrative authority overlapping atas beberapa kelembagaan pada sistem tata-pengaturan pemerintahan yang di lokalitas desa. Konflik rasionalitas adat versus rasionalitas pemerintahan formal. Proses pemutusan kebijakan menjadi berlarut-larut, jika titik-temu antara dua pemangku otoritas tidak dapat saling dipertemukan. 2. Masalah konflik kepentingan yang terjadi sebagai akibat tumpang-tindih wewenang untuk memutuskan suatu persoalan sosial-kemasyarakatan antara para pemangku otoritas hukum adat versus pemangku otoritas hukum formal. Masalahnya berpusat pada persoalan, tata-aturan mana yang akan dipegang, apakah tat-aturan formal yang berada pada regime administrasi formal? Ataukah mengandalkan regime adat yang memiliki sistem lebih informal, namun lebih mengakar dan dipercaya oleh masyarakat lokal? 3. Masalah policy consistency yang rendah yang berkaitan dengan public administration management skill yang dipunyai oleh perangkat desa. Kapasitas kelembagaan dan SDM yang lemah bertanggung jawab atas realitas ini. 4. Masalah government effectiveness yang rendah, karena penyelenggara pemerintahan desa yang under-skilled dan seringkali bukan dari kalangan yang memiliki visi secara memadai. 5. Voices and Accountability dalam tata-kelola pemerintahan desa menghadapi persoalan besar. Seringkali, elit pemerintah desa bermanuver sendirian tanpa ada kontrol yang memadai dari publik yang dipimpinnya. Perangkat kelembagaan formal yang ada pun tidak mampu mengawasi manuver politik para elit (karena ketiadaan akses, ketiadaan mekanisme kontrol yang disepakati, dan perasaan “ewuh-pakewuh” (perasaan tak enak untuk menegur), sehingga praktek pemerintahan merepresentasikan kehendak pribadi daripada institusi. 6. Mekanisme power control yang tidak memadai atau tidak berfungsi, sebagai akibatnya konflik-konflik otoritas kelembagaan yang terjadi di desa sulit mendapatkan solusi segera. Masalah governance system di atas menjadikan proses otonomisasi desa tidak berlangsung sesuai harapan dan seringkali mengalami hambatan. 3.3. Isyu-Isyu Kritikal Pembaharuan Tata-Pemerintahan Desa 3.3.1. Masalah Struktural-Institusional dan Politiko-Kultural Luiz (2000) mengemukakan bahwa pemerintah sebagai unsur organisasi negara, peranannya akan sangat menentukan derajat perkembangan sosial-ekonomi dan dinamika sosial-kemasyarakatan di suatu kawasan yang menjadi wilayah otoritasnya. Hal ini disebabkan negara melalui organisasi pemerintahannya akan menentukan kondisi lingkungan sosio-politik yang selanjutnya menentukan derajat pertumbuhan/perkembangan ekonomi kawasan tersebut (political environment conducive to growth). Dengan sifatnya yang seperti itu, maka pemerintah (baik di tingkat desa ataupun di tingkatan manapun yang lebih tinggi) harus 36 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik mengemban missi otonom (embedded autonomy) sebagai penggerak utama kehidupan desa Otonomi yang melekat pada ciri-natural organisasi pemerintahan ini seolah mengabaikan apapun kehendak yang diinginkan oleh negara (pada tataran pusat) secara keseluruhan. Dengan posisinya yang otonom dalam mengembangkan kawasan, maka kelembagaan pemerintahan (desa) akan berfungsi sebagai pivotal institution dalam proses-proses pembangunan selain juga berfungsi sebagai meta-entrepreneur dalam menggerakkan perekonomian di kawasan di bawah otoritasnya. Apa yang hendak dikatakan oleh Luiz (2000) dalam hal ini adalah, bahwa “hidup dan matinya” sebuah kehidupan sosialkemasyarakatan di suatu kawasan akan sangat ditentukan oleh kualitas tatapemerintahan atau pengaturan dari organisasi pemerintah lokalnya. Selaras dengan pemikiran Luiz (2000) itu, hasil pengamatan empirik tahap awal yang dilakukan oleh tim studi-aksi PSP3IPB menemukan beberapa bukti awal tentang tata-pengaturan pemerintahan desa yang menarik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa operasionalisasi UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 – yang menghendaki pemerintah desa bersifat mandiri dan menjadi organisasi penggerak-utama kehidupan sosial kemasyarakatan desa – dalam keadaan yang sangat beragam, jika tidak ingin dikatakan sebagai kemandegan. Hal ini dikarenakan UU no. 32/2004 secara “by nature” telah membawa kompleksitas persoalan tata-pemerintahan lokalitas (desa) yang sebelumnya telah memiliki dasar pengaturan asli. Permasalahan itu adalah: aspek pertama berupa institutional conflict di tingkat lokal, yang bisa berdampak luas pada inefektivitas pemerintahan desa. Kelembagaan pemerintahan desa formal dan kelembagaan adat sama-sama bekerja di wilayah otoritas yang sama, menjadikan pemerintahan desa formal sulit berfungsi efektif. Terlepas dari persoalan konflik kelembagaan yang mengganggu dan berpotensi terus dijumpai, namun semangat good rural governance harus tetaplah menjadi isyu pokok yang senantiasa diperjuangkan. Hal ini mendapat tempat paling tinggi dalam skala prioritas, karena untuk sementara diyakini bersama bahwa hanya dengan prinsip-prinsip tata-kelola desa yang baik, maka kesejahteraan sosial (terbebas dari penderitaan kemiskinan), keadilan (terbebas dari kesewenangwenangan dan penindasan), dan martabat (terbebas dari keterlecehan) yang lebih tinggi dapat direalisasikan. Pertanyaannya, sejauh mana sesungguhnya sistem tata-kelola desa yang baik harus ditempuh? Apa ukurannya dan bagaimana mencapai ukuran-ukuran tersebut? Bila governance system dimaknai sebagaimana pengertiannya diberikan oleh Commision on Global Governance (dikutip oleh Weiss, 2000) dimana conflicting of diverse interests diakomodasi dan jejaring kerjasama bisa dibangun antar komponen komunitas desa, maka muncul pertanyaan baru: sejauhmana desa dengan segala perangkatnya sesuai UU no. 32/2004 sesungguhnya mampu melayani dua misi dari governance system yang sangat berat untuk dijalankan ini? Persoalannya yang terkait kemudian adalah: seberapa besar capacity of endurance to resist terhadap 37 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik persoalan-persoalan konfliktual harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan desa – sebagai sebuah entitas administratif lokal – atau bahkan seringkali kesatuan antar pemerintah desa (namun dalam kawasan dalam sistem ekologi sehamparan) demi mewujudkan tata-pemerintahan yang tangguh dan andal? Kapasitas untuk bertahan dan mengelola permasalahan konflik yang krusial di pedesaan menjadi aspek kedua kompleksitas tata-kelola pemerintahan desa di era desentralisasi. Sebagaimana telah dipaparkan di sub-bab sebelumnya, dimensi konflik bisa bersifat hierarkhikal-vertikal (antar entitas namun berada pada posisi yang berbeda secara hierarkhikal), atau secara horisontal antar entitas yang setara (pemerintah desa versus kelembagaan adat). Persoalan kapasitas untuk bertahan dari pemerintahan desa (institutional survival) akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dan kepemimpinan pemerintahan desa, yang berarti kata-kuncinya adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan sistem manajemen pemerintahan yang baik. Kualitas SDM dan kepemimpinan organisasi pemerintahan desa menjadi aspek ketiga sementara sistem manajemen pemerintahan menjadi aspek keempat sistem tata-kelola pemerintahan desa yang penting untuk diperhatikan. Kualitas dan kapasitas (kemampuan) infrastruktur kelembagaan penopang sekaligus “pengawas” jalannya sistem pemerintahan desa menjadi faktor yang sangat decisive terhadap keberlangsungan sistem tatapemerintahan lokal yang efektif dan transparan serta akuntabel. Faktor ini adalah aspek kelima yang penting bagi terselenggaranya good rural governance. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa saja tidak cukup bila SDM di dalamnya tidak memiliki kapasitas memadai. Pada aras ”ekstra entitas administratif lokal” didapati entitas-entitas pemangku kepentingan yang tidak selalu berideologikan selaras dengan ideologi keseluruhan entitas komunitas desa. Oleh karenanya, mereka setiap saat siap berhadap-hadapan secara politik vis a vis kekuatan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, persoalannya adalah bagaimana kemampuan survival of the fittest dari struktur pemerintahan desa dapat dibangun agar mampu melawan pesaingpesaingnya dalam ruang konflik terbuka yang bisa jadi akibatnya akan sangat mematikan. Dalam hal ini, bila konteks exercise of different power dimasukkan dalam sistem tata-kelola pemerintahan desa, maka relasi-relasi kekuasaan politik dan ekonomi pada komunitas desa harus dipahami secara seksama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini berarti, kompleksitas tata-kelola desa memasuki aspek keenam yaitu wilayah politik-ekonomi, dimana semua kekuatan dan kemungkinan tekanan politis yanga ada diperhitungkan. Realitas sosial adanya olah-kekuasaan dari beragam pihak terhadap pemerintahan desa (yang seringkali berpotensi destruktif), jelas sulit di-address secara langsung dalam pasal-pasal UU no. 32/2004, namun semua pihak mafhum akan kehadiran kekuatan penekan semacam ini. Pertanyaannya, haruskah kekuatan ekstra-pemerintahan itu dieliminasi, atau sebaliknya diakomodasi keberadaannya dalam wadah kemitraan yang konstruktif? 38 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Aspek berikutnya (aspek ketujuh) berkaitan dengan aspek kelima secara langsung yaitu berkenaan dengan terselenggaranya fungsi-fungsi manajemenorganisasional seperti kontrol, advokasi, supervisi-monitoring, dan evaluasi yang dijalankan oleh masyarakat sipil terhadap sistem pemerintahan desa. Pertanyaan yang diajukan dalam hal ini adalah sejauhmana dan seberapa besar kapasitas kekuatan sipil yang ditampilkan oleh asosiasi masyarakat sipil (civil society association) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mampu mengawasi jalannya pemerintahan desa? Mampukah kelembagaan kontrol berbasiskan masyarakat sipil tersebut “mengawal” jalannya pemerintahan desa secara konstruktif – bukan asal berbeda pendapat saja – demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan, kemandirian, dan kemartabatan masyarakat luas. Persoalannya kemudian adalah bagaimana membangun sistem tata-kelola pemerintahan desa yang konstruktif di saat sejumlah persoalan terus mengendala? Sementara itu prinsip-prinsip desentralisme (bottom-up, partisipatif, demokrasi, kesejajaran, apresiasi terhadap kekuatan lokal) dan prinsip good rural governance (transparansi, keadilan, akuntabilitas) terus diperjuangkan secara konsisten dan kontinu? 3.3.2. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pembaharuan tata-kelola atau tata-pengaturan pemerintah lokalitas (desa) di Provinsi NAD dihadapkan pada persoalan-persoalan berkaitan dengan kondisi makro politik di kawasan itu. Meski telah berakhir, tetapi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) selama berpuluh-puluh tahun masih membekaskan dampak destruktif yang buruk terhadap perkembangan kelembagaan pemerintahan lokal. Desa (gampong) menjadi benar-benar sebagai arena konflik nyata antar berbagai pihak yang memiliki perbedaan kepentingan politik dan ideologi. Sebagai institusi penting di tingkat lokal, pemerintah desa tidak saja menghadapi fakta ketidakberdayaan secara organisasional, konseptual, bahkan finansial dalam menggerakkan dinamika kehidupan pembangunan, namun juga harus menghadapi masalah sosio-psikologikal berupa distrust-syndrome yang sangat parah. Kecurigaan tersebut disebabkan oleh bekerjanya kekuatan tarik-menarik beragam kekuatan politik di tingkat grass-root di masa konflik. Pada titik kulminasi era konflik antara GAM dan RI, kecurigaan antar warga memuncak dan seringkali berakhir dengan berbagai cerita tragis berupa kematian di salah satu pihak yang bersengketa. Di masa konflik, pihak pro GAM selalu mencurigai program-program yang di-set up oleh pemerintah desa atau oleh 39 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Keuchik (kepala gampong/desa) sebagai bagian dari propaganda pemerintah RI. Sebaliknya, pihak RI selalu mengawasi pemerintah gampong (desa) dengan ketat, agar setiap kegiatannya tidak berakhir dengan makar. Akibatnya, pemerintah gampong (desa) ibarat pelanduk yang terjepit di antara dua posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kecurigaan dan ketidakpercayaan baik dari RI maupun GAM itu menghantarkan pemerintah desa menjadi sangat apatis, fatalis, pesimis, dan frustrasi sehingga lebih baik desa mengambil posisi tidak melakukan kegiatan apapun. Pada masa konflik itu ukuran keberhasilan pemerintahan gampong sangatlah sederhana, yaitu ”asal tidak mati” ditembak oleh pihak berkonflik. Berkembangnya etika ”safety-first”, menyebabkan status kehidupan organisasi pemerintah gampong menjadi dormant. Fakta ”mati-suri”nya kelembagaan pemerintahan gampong (desa) menjadi penciri penting dinamika pemerintahan desa di NAD semasa konflik, bahkan hingga saat ini (pasca konflik). Pada era pasca konflik dimana pulihnya saling-kepercayaan dan perbaikan derajat kehidupan sosial-kemasyarakatan menjadi cita-cita semua pihak, maka fokus diarahkan pada upaya menumbuhkan keberdayaan pemerintah desa ke arah terbentuknya rural civilization di NAD. Meski demikian, penumbuhan trust memang tidak mudah dilakukan, karena kehancuran struktur sosial dan sendisensi kehidupan sosio-politik desa berjalan hampir sempurna. Hasil investigasi empirik di dua desa kasus di Kabupaten Aceh Besar, ditemukan persoalan rural governance yang berdimensi distrust sangat kuat. Selain itu terdapat beberapa persoalan derivat dari distrust yang bisa disebutkan sebagai berikut: 1. Kelembagaan Keuchik sebagai kepala gampong (desa) mengalami krisis legitimasi dan dormansi. Keuchik kehilangan legitimasi sosial dalam memerintah dan karenanya tak memiliki daya lagi untuk melancarkan pengaruhnya pada masyarakat. Kewenangan yang melekat pada tugas-pokok dan fungsinya pun tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintahan gampong terasa mandeg (mengalami stagnasi pemerintahan) sehingga sebagai satu-satunya organisasi penggerak dinamika lokalitas, pemerintah gampong menghadapi persoalan government effectiveness yang serius. Konflik GAM versus RI dapat menjelaskan mengapa situasi stagnasi ini bisa terjadi (pemerintah desa mengambil posisi sebagai safe-player di antara dua pihak yang bertikai). Selain itu, budaya ketergantungan yang ditinggalkan oleh Orde Baru telah membuat sikap keswadayaan asli masyarakat Aceh terkikis habis secara sistematis. Sebagai akibatnya, inisiatif lokal dan dinamika desa tidak dapat atau sangat sulit ditumbuhkan. 2. Lumpuhnya sistem komunikasi organisasional dan koordinasi antar pemerintahan desa dalam pengelolaan ekosistem (air-irigasi) antar-kawasan (antar-desa) adalah persoalan tata-pemerintahan yang khas di NAD. Kelembagaan ”keujruen balang” sebagai pranata-sosial pengatur air-irigasi asli yang menyatukan beberapa wilayah administratif desa sekawasan tidak diakui lagi eksistensinya. Satu desa menaruh syak wasangka terhadap desa tetangganya dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Akibatnya, setiap desa cenderung 40 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik mengatur sendiri penggunaan air di wilayahnya tanpa mempedulikan pemenuhan kebutuhan air di desa tetangganya. Desa-desa mengalami proses dekapitalisasi modal sosial (hilangnya trust, norma-norma sosial dan jejaring sosial kerjasama antar desa) yang mengakibatkan krisis tata-pengaturan ekosistem (eco-governance crisis) di tingkat lokalitas semakin berlarut-larut. Konflik-kepentingan antar desa dalam hal pemanfaatan sumberdaya air ini merupakan dimensi tata-kelola pemerintahan desa yang penting, utamanya dalam aspek perekonomian. 3. Diskoneksi komunikasi antara warga, tokoh adat, dan pemerintahan desa beserta seluruh infrastruktur kelembagaannya menjadi aspek persoalan tersendiri dalam tata-pengaturan desa di NAD. Kehidupan civil-society diliputi oleh perasaan apatisme, sebagai akibat langsung dari konflik sosial-politik antara GAM dan RI yang berlarut-larut di masa lalu. Masyarakat sipil seolah tidak ingin terseret pada polemik politik regional yang bisa-bisa menyulitkan kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka lebih suka untuk mengambil posisi tidak bersuara dan tidak bersikap. Dalam kondisi masyarakat tanpa sikap, maka proses-proses komunikasi pada aras societal life benar-benar terganggu. Demikian juga daya-kritis masyarakat (yang biasanya terasah oleh proses dialogis dan aksi-komunikatif) sebagaimana diharapkan dalam kehidupan masyarakat sipil yang dinamis, menjadi betul-betul mandul. 4. Konflik otoritas kelembagaan dimungkinkan terjadi antara otoritas adat Imum Mukim, yang memiliki cakupan-wilayah kekuasaan dan kewenangan (kesatuan masyarakat hukum adat) yang lebih luas daripada wilayah administratif sebuah desa. Dalam kondisi yang demikian, maka para Keuchik secara tidak langsung berada dalam pengaruh kekuasaan seorang Imum Mukim. Menurut perundang-undangan yang berlaku, kewenangan administratif pengelolaan kawasan desa memang berada di tangan Keuchik dan Camat (”atasan langsung” dari Keuchik), namun legitimasi sosial kepemimpinan adat dan pengaturan masyarakat (secara Islam) berada sepenuhnya di tangan Imum Mukim. Hingga taraf tertentu, imum mukim pun ikut mengetahui (meski tidak menentukan) proses-proses pengalihan hak-hak atas tanah di wilayah kekuasaannya. 5. Kelembagaan adat di NAD mengalami kelumpuhan secara perlahan namun pasti, sebagai akibat tidak-lagi dipahaminya fungsi-fungsinya dalam keseluruhan tata-pemerintahan oleh masyarakat lokalitas. Pranata sosial asli seperti keujruen balang (pranata-sosial tata-guna air irigasi dalam pemerintahan lokal), tuha lapan (musyawarah di tingkat civil-society untuk mengambil keputusan di dalam gampong), secara praktikal telah ditinggalkan para-pihak dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Sementara itu, proses peralihan ke kelembagaan pemerintahan (desa) formal belum sepenuhnya bisa dijalankan oleh karena hambatan sosial-psikologis, dan kendala sosio-politik-keamanan, serta ketidakcukupan dukungan qanun (peraturan daerah) tentang pemerintahan desa yang kuat. 41 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 6. Secara kultural masyarakat Aceh mengenal sebuah kode-etik yang disebut sebagai ”etika pemuliaan” terhadap seseorang (mengagungkan posisi seseorang pada derajat yang lebih tinggi daripada posisi diri sendiri). Sebagai code of conduct, etika ini memandu perilaku masyarakat sedemikian rupa sehingga sangatlah tabu bagi seseorang untuk mengontrol secara langsung akuntabilitas keuangan sebuah kelembagaan atau seseorang. Etika yang demikian itu, menyulitkan jalannya proses control of power demi terbentuknya tatanan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selain itu, tradisi masyarakat Aceh yang menyerahkan secara totalitas segala persoalan kepada para ulama (sebagai pemimpin adat), juga mengendala jalannya prosesproses demokrasi secara ideal. Sikap-sikap semacam itu, dapat menyulitkan realisasi cita-cita demokratisme, kesetaraan, public accountability dan good governance di tingkat grass-root dan implementasinya di tingkat pemerintahan lokalitas (desa). Secara umum, dua desa kasus tersebut memberikan pelajaran yang berguna tentang pemahaman pada proses-proses pelumpuhan tata-pemerintahan desa di NAD secara sosio-politiko-kultural. Kebijakan ”Otonomi Khusus NAD” (melalui UU no. 18/2001 disamping UU no. 32/2004) yang pada awalnya diharapkan mampu menyegarkan kembali pelaksanaan pemerintahan daerah melalui strategi otonomisasi desa, ternyata masih jauh dari harapan. Otonomi khusus NAD bahkan tidak mampu menggerakkan pemerintahan desa di tingkat lokalitas secara signifikan dan efektif (lihat juga Hanafiah, 2006). Dengan demikian, persoalan mendesak yang harus segera dipecahkan dalam rekonstruksi tata-pemerintahan desa (gampong) di NAD, belum menyentuh ke tataran bagaimana mewujudkan otonomisasi lokalitas (desa/gampong) secara efektif. Melainkan, persoalan baru sekedar menyentuh aras yang sangat elementer berupa: bagaimana menggerakkan pemerintahan lokalitas (desa/gampong) agar berfungsi secara efektif dalam pelayanan publik, administrasi pembangunan, menginisiasi gagasan dan yang sejenisnya. 3.3.3. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Nagari di Ranah Minangkabau Minangkabau merupakan konsep sosio-budaya masyarakat yang tinggal di kawasan yang secara geografis bertepatan posisinya dengan daratan provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui, kawasan kepulauan Mentawai sebagai bagian dari wilayah administratif provinsi Sumatera Barat tidak dapat dikatakan sebagai ranah Minangkabau, karena sistem nilai budaya dan agama penduduknya yang berbeda dengan kawasan daratan Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau mendasarkan kehidupannya pada tatanan sosial adat yang semua aturannya akhirnya bersandarkan atau merujuk kepada Al Qur’an dan Hadist. Jadi atmosfer keislaman terasa sangat kuat dalam tata-pengaturan sosial kemasyarakatan adat 42 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik di Minangkabau. Berbeda dengan NAD yang secara eksplisit menetapkan syariat Islam sebagai hukum pengatur kehidupan sosial-kemasyarakatan, maka masyarakat Minangkabau terkesan lebih implisit dan tidak secara terang-terangan mengatakan syariat Islam sebagai basis tata-kehidupan hukum sosialkemasyarakatan. Sebaliknya, tata-aturan adat justru dijalankan lebih ketat, termasuk dalam hal pengaturan lokalitas (nagari/desa). Nagari adalah konsep tata-pemerintahan lokalitas yang ditetapkan sebagai satusatunya tata-pemerintahan lokalitas (desa) di ranah Minangkabau. Operasionalisasi nagari sebagai sistem pemerintahan lokalitas (desa), dikukuhkan oleh Peraturan Daerah (Perda no. 9/2000) Provinsi Sumatera Barat tentang pemerintahan nagari. Dengan diundangkannya peraturan daerah tersebut, maka sejak tahun 2000, tata-pemerintahan lokalitas (desa) di ranah Minang Sumatera Barat secara resmi kembali ke asal-usulnya, yaitu tata-pemerintahan adat. Sejak saat itu, harapan di kalangan warga masyarakat melambung. Dengan perda tersebut, diperkirakan tidak akan ada lagi hegemoni sistem pemerintahan desa ala Jawa yang diberlakukan di ranah Minang. Kelembagaan asli akan mengalami revitalisasi dan bangkit dari kelumpuhan. Supremasi tata-pemerintahan adat akan menjadi sangat kuat dan konflik-konflik otoritas kelembagaan antara pemerintah desa ala Jawa (yang konseptualisasinya mengemuka sejak UU no 5/1979 hingga UU no. 32/2004) melawan pemerintahan adat, bakal hilang sama sekali. Begitulah kira-kira harapan masyarakat terhadap Perda no. 9/2000. Pertanyaan yang muncul kemudian, benarkah bahwa konsep nagari yang dikukuhkan oleh Perda tersebut, pada kenyataan dan implementasinya samadengan apa yang diidam-idamkan oleh sebagian besar masyarakat adat? Ternyata, perjalanan Perda no. 9/2000 selama enam tahun terakhir menghasilkan kisah yang samasekali lain dari harapan. Banyak gugatan dan catatan yang terhimpun dalam investigasi empirik studi ini yang mencatat, bahwa konsep nagari yang diterapkan semakin menjauh dari sifatnya dan justru karakternya semakin mendekatkan diri pada struktur pemerintahan desa ala Pemerintah atau UU no. 32/2004 (yang termodifikasi). Salah satu ciri pemerintahan nagari yang digugat adalah karakternya yang makin jauh (memudar) dari prinsip musyawarah-mufakat dan terbentuknya realitas pemusatan kekuasaan pada wali-nagari (”kepala desa”) sebagai kelembagaan eksekutif nagari. Dalam adat Minangkabau, tidak dikenal demokrasi yang bersandarkan pada basis voting. Juga tidak dikenal, dalam sistem pemerintahan adat Minangkabau, kekuasaan otoritarian. Dalam ”logika” adat Minangkabau, kebenaran tunggal yang menjadi keputusan akhir, selalu disandarkan pada proses-proses musyawarah dan mufakat sejak di tingkat grass-root, dengan selalu memperhatikan norma dan aturan adat yang merujuk pada Al Qur’an dan Hadist. Musyawarahmufakat itu dimulai dari aras para ninik-mamak dalam satu kaum. Kemudian bila persoalan makin kompleks, dilakukan musyawarah-mufakat di aras antar ninik43 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik mamak dari kaum yang berbeda-beda hingga akhirnya pada aras tertinggi yaitu kerapatan adat nagari. Dengan demikian, demokrasi ala Minangkabau tidak mengenal sistem perolehan suara mayoritas. Dalam musyawarah-mufakat suara minoritas boleh jadi bernilai kebenaran yang lebih tinggi dan akhirnya diikuti sebagai kebenaran umum. Sebaliknya, dalam sistem voting akan selalu terjadi hegemoni mayoritas sekalipun keputusan yang disahkan melawan logika kebenaran hakiki yang diyakini oleh masyarakat luas. Hal seperti ini jelas tidak dikehendaki menurut ”logika” adat Minangkabau. Apa yang terjadi dalam tata-pemerintahan nagari? Pokok gugatan yang langsung mengenai sasaran adalah berkenaan dengan implementasi prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang jelas tidak mencerminkan tata-kehidupan demokrasi berprinsipkan musyawarah-mufakat adat Minangkabau. Dalam struktur tata-pemerintahan nagari menurut Perda no. 9/2000 disebutkan kehadiran beberapa kelembagaan pemerintahan penopang pemerintahan yang mirip trias-politica. Tersebutlah, Wali Nagari (kepala desa) yang memiliki kekuasaan eksekutif dan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai simpul kekuasaan legislatif yang biasanya diisi oleh unsur dari para ninik-mamak. BPN juga diisi oleh unsur Majelis Ulama Nagari, Bundo Kanduang (para Ibu yang dituakan) dan Pemuda Nagari (lihat Busra, 2006). Dalam posisi demikian, kekuasaan wali nagari memang ”di atas angin” dan mendominasi pengambilan keputusan. Disinilah, proses peminggiran prinsip musyawarah-mufakat ala Minangkabau berpotensi terjadi, dan menjadi pokok gugatan oleh banyak pihak (lihat Fahmi, 2006 dan Busra, 2006). Singkat kata, bentuk pemerintahan nagari saat ini sebenarnya ”setali tiga uang” dengan bentuk pemerintahan desa ala UU. No. 32/2004, hanya namanya saja yang berbeda. Dari sinilah, maka persoalan konflik internal kelembagaan pada tataran pemerintahan lokalitas bermula. Pemerintahan adat nagari yang mewakili struktur pemerintahan desa formal seringkali berhadap-hadapan secara diametral melawan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Campur tangan atau intervensi KAN (sebagai kelembagaan informal yang menghimpun para ninik-mamak yang diakui otoritas adatnya oleh pemerintah daerah) seringkali terlalu dalam pada urusan administrasi pemerintahan. Sebenarnya KAN memiliki otoritas yang sangat elegan yaitu mengawal hak ulayat dalam tata-pengaturan agraria lokal. Namun, tampaknya KAN ingin berperan lebih besar daripada sekedar menjaga hak ulayat. Gejala ini disebutkan sebagai dualisme pemerintahan dalam mengurus kepentingan masyarakat lokal, yang tentu saja tidak sehat untuk sebuah sistem tata-pemerintahan lokal (lihat Busra, 2006). Selain persoalan konflik kelembagaan, pertanyaan berikutnya adalah: apakah kebijakan penerapan nagari sebagai satu-satunya sistem pemerintahan lokalitas di ranah Minang, telah memungkinkan berkembangnya otonomi lokalitas (nagari) seluas-luasnya? Artinya, apakah pemerintahan nagari dapat berdaya, dan mampu mengatur rumahtangga lokalitas secara mandiri serta mampu melepaskan diri dari 44 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik pengaruh kekuasaan-sentralisme pemerintah pusat dan kabupaten dalam melayani masyarakat? Pada titik ini, Alfitri (2006), paling tidak mencatat ketidakberdayaan nagari dalam hal pembangkitan kekuatan partisipasi masyarakat. Pemerintah nagari jelas mengalami kelumpuhan dalam menstimulir kekuatan rakyat untuk berperanserta memikul tanggung jawab perubahan (pembangunan). Masyarakat cenderung beranggapan bahwa pemerintah nagari adalah administratur negara yang mendapatkan mandat, kekuasaan dan wewenang untuk membereskan segala persoalan pembangunan. Oleh karena itu partisipasi lokal tidak diperlukan lagi. Ketidakberdayaan nagari ini selain mengindikasikan ketidakmampuan dalam menggerakkan dan mengorganisasikan masyarakat, juga mengandung makna hubungan sosial antara pemerintah lokalitas dan rakyat yang kehilangan ruh mutual-trust. Dalam situasi semacam itu, maka satu-satunya harapan dan tumpuan pemerintah nagari untuk mengadu hanyalah pemerintah ”supra lokal”, yaitu Pemerintah Kabupaten atau Pusat. Selain itu, kemandirian ekonomi nagari, sebagai salah satu indikator otonomi desa, pun belum banyak terwujud. Nagari masih menghadapi persoalan bagaimana meggerakkan perekonomian lokal yang mampu menghasilkan pendapatan asli nagari. Lemahnya struktur finansial nagari, menyebabkan sindroma ketergantungan yang masih sangat tinggi pada pemerintah kabupaten. Dana alokasi umum nagari (DAUN) yang berasal dari pemerintah kabupaten adalah salah satu sumber keuangan penting yang menentukan hidup-dan-matinya sebuah nagari. Secara ringkas persoalan rural governance yang menjadi tantangan di Sumatera Barat, antara lain adalah: 1. Konflik otoritas kelembagaan antara pemerintahan nagari (desa) dan pemerintahan adat yang diwakili oleh KAN menggerogoti eksistensi dan kualitas pemerintahan nagari. Persoalan distrust syndrome dalam hal ini, sangat kental mewarnai tata-hubungan antara KAN dan pemerintahan nagari. 2. Effectiveness of government menjadi persoalan tersendiri dalam tata-pengaturan nagari di ranah Minangkabau. Beberapa faktor yang bertanggungjawab atas keadaan ini adalah: (a) kualitas SDM yang lemah, (2) infrastruktur yang lemah, (3) sistem manajemen pemerintahan yang masih terbatas. 3. Lemahnya partisipasi masyarakat (publik) dalam menggerakkan pembangunan nagari. Konfigurasi keterlibatan publik dalam pemecahan persoalan-persoalan pemerintahan masih harus ditingkatkan. 4. Pada beberapa kasus, didapati adanya superioritas kekuasaan Wali Nagari yang berlebihan, yang menyebabkan control of power sulit dilakukan oleh publik (masyarakat adat). 5. Struktur finansial nagari masih sangat memprihatinkan. Kemampuan nagari untuk bisa melakukan self-financing bagi pembangunan, masih merupakan cita-cita yang sulit diwujudkan secara segera. Dengan melihat temuan-temuan di atas, maka disimpulkan bahwa cita-cita untuk mewujudkan otonomi nagari memang masih ”jauh panggang dari api”. 45 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik 3.3.4. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Desa di Jawa Barat Jawa Barat mewakili kawasan desa ala Jawa yang merepresentasikan praktek tatapemerintahan desa secara murni menurut UU no. 32/2004. Sekilas, tidak terdapat persoalan yang berarti dihadapi oleh pemerintahan desa di provinsi ini. Namun, bila diselami lebih dalam segera tampak persoalan-persoalan tata pemerintahan desa di daerah tersebut. Salah satu isyu penting dalam hal ini adalah otonomi desa yang masih belum berlangsung secara memadai. Dilema ketergantungan prakarsa dan ekonomi desa pada supra-struktur kabupaten serta pusat, tetap tinggi. Selain itu, terdapat ketidakleluasaan dan ketidakmandirian desa dalam menggerakkan pembangunan dikarenakan ketiadaan sumber-sumber pendanaan program yang asli berasal dari desa. Ketergantungan gagasan dan finansial terhadap pemerintah kabupaten yang tetap tinggi tersebut, mengindikasikan masih adanya persoalan ketidakberdayaan dan ketidakberdaulatan desa yang nyata. Dalam hal ini, persoalan penguatan kelembagaan pemangku otoritas administratif lokal menjadi isyu penting. Penguatan tersebut meliputi aspek SDM di semua lini, aspek sistem pengelolaan administrasi desa, aspek keberfungsian kelembagaan pengawasan seperti Badan Permusyawatan Desa (BPD) sebagai pengawas eksekutif, dan kemampuan civilsociety (grass root) untuk berpartisipasi dalam segala aras pembangunan. Dalam penguatan kemampuan ekonomi lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai institusi ekonomi yang absah/dimungkinkan oleh UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 untuk berperan sebagai rural income-generator, masih berada sebatas cita-cita. Ketiadaan inisiatif lokal dan jejaring ekonomi yang memungkinkan tumbuhnya BUMD menjadi persoalan tersendiri dalam mewujudkan cita-cita otonomi di tingkat desa. Rumahtangga desa tetap tergantung pada sumber pendanaan kabupaten. Sementara itu, konflik antar otoritas kelembagaan yang lazimnya berlangsung antara pemerintahan adat versus pemerintah desa sebagaimana di NAD dan di ranah Minangkabau, memang tidak dijumpai pada kasus Jawa Barat atau Jawa pada umumnya. Dalam struktur tata-pemerintahan lokalitas di Jawa, pemerintah desa adalah kelembagaan tunggal dalam pengaturan segala macam urusan publik. Pemerintah desa adalah ”penguasa tunggal” dalam pengaturan segala persoalan kehidupan sosial-kemasyarakatan lokal. Persoalan rural good governance yang penting dalam Kasus Jawa Barat adalah, bagaimana menciptakan dinamika kelembagaan pemerintahan lokal sedemikian rupa sehingga mampu mendorong pemerintah desa mampu berperan sebagai inisiator perubahan (transformasi pedesaan) yang mandiri tanpa membuat kelembagaan ini berubah menjadi penguasa-tunggal yang berpotensi menjadi otoriter. Artinya, struktur organisasi civil society di tingkat lokal harus berdaya mengontrol kiprah pemerintah desa. 3.3.5. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan ”Desa Dinas” di Bali 46 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Bali adalah contoh kasus tata-pemerintahan lokalitas yang sangat menarik, dimana disana ditemukan tiga tipe desa berdasarkan karakter tata pemerintahan lokal. Pemerintahan desa formal menurut UU no. 32/2004 didapati dalam bentuk desa dinas (dikepalai oleh Kepala Desa) Desa formal ini memiliki wilayah kerja administratif sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara itu, terdapat pula desa adat atau pakraman (dikepalai oleh Kelian Adat) yang wilayah kewenangannya diukur dari jauhnya jangkauan tempat peribadatan agama Hindu Bali (sebuah pura) terhadap masyarakat yang dapat dilayaninya. Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang tata-pengaturannya berbasiskan pada sistem religi Hindu. Sindroma dualisme pemerintahan sebagaimana terjadi pada nagari di Minangkabau dimungkinkan terjadi pada sistem pemerintahan desa Bali, karena secara teknikal pakraman juga melakukan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh desa dinas. Namun demikian, karena kedua sistem pemerintahan mampu mengurangi klaim-klaim otoritasnya, maka justru sinergitas yang tampak berlangsung antara sistem desa adat dan desa dinas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam filosofi desa adat, ada tiga fungsi pokok yang harus mereka jalankan, yaitu pelayanan hubungan manusia dengan Tuhan, pelayanan hubungan manusia dengan manusia, dan pelayanan hubungan manusia dengan alam. Secara administratif, fungsi-fungsi itu juga merupakan tugas yang diemban oleh kelembagaan desa dinas. Oleh karena itu tidak berlebihan bila, desa di Bali memiliki ”satu badan dengan dua kepala”. Namun, berbeda dengan nagari dan gampong yang menghadapi konflik kelembagaan secara internal, di Bali hal itu tidak terjadi. Meski dualisme pemerintahan bisa berlangsung, namun derajat koordinasi antara dua kelembagaan (pemerintah desa adat dan pemerintah desa dinas) dalam tata-pengaturan kehidupan sosial-kemasyarakatan berjalan sangat baik. Dalam hal urusan pemeliharaan jalan-jalan menuju ke Pura (tempat peribadatan Hindu Bali), tanggung jawab desa adat dirasakan sangat dominan. Proyek-proyek perbaikan jalan menuju pura menjadi tugas utama desa adat, sementara desa dinas berkonsentrasi di segmen jalan yang lain. Persoalan mulai muncul di desa-desa sekitar perkotaan, dimana derajat heterogenitas keberagamaan dan pluralisme etnisitas dan deferensiasi pekerjaan serta aktivitas ekonomi mulai meningkat. Pada kawasan seperti itu, relevansi tatapengaturan adat berbasiskan hinduisme, terasa makin tidak relevan. Ikatanikatan emosional yang biasanya terjalin lebih kuat antara masyarakat Hindu Bali dengan desa adat, perlahan-lahan namun pasti melemah. Karena secara kuantitas, proporsi umat Hindu berkurang dengan makin banyaknya pendatang yang beragama non-Hindu ke kawasan Bali. Proses pelumpuhan struktur dan peranan kelembagaan desa adat melalui dinamika kependudukan seperti ini menjadi dimensi khas dari tata-pemerintahan adat Bali. Tuntutan-tuntutan sementara kalangan penduduk asli Bali yang menghendaki ”revitalisasi” dan pemberian peran lebih luas bagi sistem tata-pemerintahan desa adat dalam tata-kehidupan masyarakat Bali kontemporer, menjadi kurang relevan dengan berkembangnya 47 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik pluralisme kebudayaan di kawasan ini. Ke depan, kecenderungan akan hilangnya pengaruh adat dalam tata-pengaturan kehidupan sosial-kemasyarakatan terus menguat. Bentuk desa ketiga di Bali adalah ”desa subak” yang memiliki legitimasi hukum atas dasar kesatuan masyarakat tata-air irigasi pertanian sawah di suatu kawasan. Dalam ”logika” subak, kesatuan kawasan sehamparan sistem pengairan, berada dalam satu otoritas pengaturan administratif air. Luas wilayah pengaturan subak, bisa melintasi wilayah administratif beberapa desa dinas. Konflik otoritas kelembagaan antar sistem pemerintahan lokalitas tidak terjadi dalam hal ini, karena memang fungsi utama setiap kelembagaan telah terdefinisi dengan baik. Dengan demikian, beberapa persoalan rural governance yang didapatkan dari hasil pembelajaran di dua desa kasus di Bali dapat disebutkan antara lain adalah: 1. Otoritas desa adat dan desa subak mengalami irrelevance secara fungsional, selaras dengan berkembangnya sebuah desa yang asalnya berciri agraris menjadi sebuah desa berciri sub-urban. Dalam hal ini kepentingankepentingan bisnis ekonomi di sektor industri-perdagangan, yang biasanya tunduk pada kekuasaan modal dan netral terhadap kepentingan sumberdaya alam, menggeser pengaturan kepentingan-kepentingan yang terdapat di desa bercirikan religius-agraris. 2. Tingkat keswadayaan masyarakat desa dalam mendanai kegiatan pembangunan (jalan, jembatan, sarana air bersih) sangat tinggi. Seringkali proporsi dana partisipasi masyarakat jauh lebih besar daripada proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan prasarana fisik desa. Meski demikian, mekanisme pertanggung-jawaban pemanfaatan dana masih perlu pemikiran lebih lanjut agar transparansi dan akuntabilitas publik dapat ditegakkan. Otonomi desa di desa-desa Bali sesungguhnya secara realitas telah berjalan baik, dan lebih maju daripada apa yang dicita-citakan. Derajat keswadayaan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Derajat penyampaian prakarsa oleh masyarakat desa yang dipelopori kelembagaan desa adat pun cukup tinggi. Desa adat juga mampu menghimpun legitimasi yang kuat untuk menopang kinerja desa dinas dalam melaksanakan pembangunan. Semua ini tentu berkaitan dengan sistem pengaturan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang konsisten menggunakan nilainilai dan norma-norma pengaturan berbasiskan religi secara konsekuen dan konsisten. Persoalan kemudian muncul manakala kekuatan-kekuatan adat melemah (ternetralisasi peranannya) seiring dengan perubahan karakter sistem sosial masyarakat lokal dari yang bercirikan keaslian kepada komunitas bercirikan lebih pluralistik. Sebagai ruang kehidupan, desa yang memuat beragam kepentingan, dipaksa harus menyesuaikan dirinya dengan berbagai sistem nilai baru yang tidak asli lagi. 3.3.6. Isyu-Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Kampung di Papua 48 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Persoalan terberat yang dihadapi oleh Papua secara umum dalam mengembangkan tata-pemerintahan lokalitas/desa yang baik (desa disebut sebagai ”kampung” dengan diberlakukannya UU no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua), pada dasarnya berfokus pada dua persolan utama. Pertama, mutu SDM warga masyarakat dan pengelola pemerintahan kampung pada umumnya masih sangat terbatas. Kapasitas intelektual, keterampilan/ability, dan sikap yang ditunjukkan oleh insan Papua umumnya masih jauh dari mencukupi untuk bisa menyelaraskan langkah dengan apa yang dituntut oleh UU no. 32/2004. Pada titik ini, tata-pemerintahan kampung di Papua masih menghadapi persoalan yang sangat elementer, yaitu memberdayakan dan memberikan suasana yang kondusif setiap insan Papua terutama aparat kampung untuk mengembangkan gagasan-gagasan kreatif dan progresif. Dampak langsung keterbatasan kualitas SDM adalah terpengaruhnya organisasi pemerintahan kampung, yang kinerjanya tidak sesuai harapan masyarakat luas. Daya kreasi, inisiatif dan daya kritis terkendala oleh kualitas SDM yang belum memadai di semua lini sistem pemerintahan kampung. Tiga ”wilayah wewenang” yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah kampung (sebagaimana rumusannya dijelaskan pada pasal 206 UU no. 32/2004 atau penjabarannya pada pasal 7 PP. 72/2005) juga tidak bisa dilaksanakan secara memuaskan. Akibat lebih lanjut atas persoalan SDM, adalah terganggunya kinerja kelembagaan pemerintahan kampung secara keseluruhan. Kemandirian dan keberdayaan pemerintah kampung sulit dikembangkan dikarenakan ketiadaan dinamisator dan innovator yang mampu menggerakkan ”mesin” administrasi pemerintahan secara baik. Pada titik ini, otonomi kampung menjadi sulit dicapai. Persoalan kedua adalah isolasi daerah yang menjadikan setiap kawasan menjadi terpencil dari kawasan lainnya. Dampak paling langsung atas kondisi ini adalah sulitnya aksesibilitas dan high-cost economy di sektor transportasi yang harus ditanggung masyarakat. Secara sosio-geografis, entitas sosial yang membentuk suatu kampung secara total menjadi saling terpisah satu dengan yang lainnya. Pergaulan sosial antar kampung juga menjadi sangat terbatas sehingga jejaringjejaring kerjasama antar lokalitas pun sulit dikembangkan. Sebagai akibatnya, secara kultural setiap entitas sosial membentuk konfigurasi sosio-budaya yang distinct. Batas-batas sosio-kultural-geografis yang mengisolasi suatu kampung atas kampung lainnya biasanya berwujud dalam bentuk ”wilayah ulayat ondoafi” yang teritorialnya disekat secara fisik oleh gunung, tebing atau sungai. Isolasi sosio-kultural-geografis suatu kawasan yang menyebabkan keterpencilan bagi suatu komunitas itu makin memprihatinkan ketika prasarana dan sarana perhubungan udara (satu-satunya sarana transportasi yang paling mungkin) sekalipun tidak tersedia bagi warga. Perkembangan tata pemerintahan kampung di dua kampung kasus ditandai oleh hal-hal khusus yang menarik. Kampung pertama adalah kawasan ex-transmigrasi 49 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik sedang kampung kedua adalah kampung asli. Pada kampung pertama, pluralisme dan heterogenitas sosial sangat tinggi sementara kampung kedua dicirikan oleh derajat homogenitas suku asli yang sangat kuat. Persoalan tata-pengaturan desa di kampung pertama adalah mulai ”berkompetisinya” wilayah kekuasaan dan kewenangan adat ondoafi melawan wilayah kekuasaan dan kewenangan kepala kampung beserta aparat dan kelembagaan pendukungnya. Persoalan persinggungan kekuasaan dan kewenangan tidak terjadi secara nyata pada kampung kedua, dimana pengaruh ondoafi terasa lebih dominan disana. Orientasi pemecahan masalah sosial-kemasyarakatan berdasarkan adat masih sangat terasa meski legitimasi kepala kampung juga mulai menguat. Dari investigasi empirik di lapangan, beberapa pelajaran yang bisa dipetik adalah adanya realitas keberagaman sosio-kultural geografis di Papua yang tinggi yang menghendaki pendekatan ketata-pemerintahan spesifik di setiap kawasan. Selain persoalan/tantangan umum yang harus dihadapi seperti peningkatan kualitas SDM, dinamisasi kelembagaan, dan penyelesaian konflik otoritas, Papua juga menyimpan potensi modal-kultural-institusional yang bisa dikembangkan. Khususnya dalam disain tata-pemerintahan, potensi sinergitas antara dua kelembagaan (ondoafi dan pemerintahan kampung) bersama organisasi civil-society lainnya seperti gereja atau masjid, dipandang dapat menjadi jalan alternatif untuk menggerakkan organisasi pemerintahan ke arah kemajuan. 4 PENUTUP Rekonfigurasi Keterlibatan Para Pihak untuk Good Rural Governance System Keputusan politik dan kebijakan OTDA sesuai UU no. 32/2004, secara eksplisit menghendaki daerah menjadi kawasan yang lebih berdaya, mandiri, berdaulat dan memiliki kekuatan/kemampuan dalam mengatur dan mendanai segala aktivitas dan dinamika sosial-kemasyarakatan yang berlangsung di dalamnya. Desa sebagai ruang dimana didapati kesatuan masyarakat hukum dan entitas sosial terkecil dalam sistem/tata-pemerintahan di Indonesia, pun diharapkan menjadi kawasan yang mampu menegakkan cita-cita kemandirian tersebut. Untuk itu pemerintahan lokalitas dituntut memiliki kapabilitas yang mencukupi dalam menyelenggarakan sistem administrasi, mencari solusi masalah, mengembangkan gagasan kreatif, serta mampu menggerakkan kehidupan masyarakat lokal ke arah yang lebih progresif. 50 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Pada era otonomi daerah saat ini, proses-proses pemerintahan lokalitas (desa/desa dinas/gampong/nagari/kampung) juga diharapkan dapat berlangsung pada platform demokrasi yang matang, yaitu demokrasi yang memahami perlunya inisiatif lokal tanpa harus larut dalam perbedaan pendapat yang berakhir dengan anarkhisme. Demokrasi yang beradab harus mengembangkan kesetiakawanan sosial serta mendorong proses-proses partisipasi publik dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan yang sehat. Salah satu kegagalan pemerintahan desa selama ini, disebabkan ruang dialog dan ruang komunikasi publik yang matang itu tidak terbentuk. Inisiatif-inisiatif menjadi sangat tergantung pada pemerintah ”atas desa” dan demokrasi-partisipatif tersumbat. Jika, lokalitas diharapkan makin berdaya dan matang serta mampu mengembangkan sistem pemerintahan (administrasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik) berdasarkan demokrasi yang matang, maka ruang-ruang keterlibatan publik harus direkonfigurasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan jaman. Pada akhirnya, dengan statusnya yang otonom, desa diharapkan menjadi pusat kemandirian sosial-politik, budaya dan ekonomi, rural as a centrality of culture and economic growth. Selain itu desa diharapkan mampu menopang kehidupan sosialkemasyarakatannya pada tingkat antar-lokalitas dan regional di ”atas”nya. Desa diharapkan memiliki government and governance capacity yang memadai. Jika semua itu terjadi, maka cita-cita keberdayaan desa akan terpenuhi. Dari investigasi awal yang dilakukan oleh tim studi-aksi ”partnership-based rural governance reform” diperoleh beberapa aspek penting tata-kelola pemerintahan lokalitas (desa) yang harus dibenahi (lihat Gambar 4). Aspek Penting Dalam Tata Pemerintahan Desa (Kasus) Provinsi studi-aksi Konflik/Persaingan antara pemerintahan adat versus pemerintah desa formal karena persoalan overlapping kewenangan Efektivitas pengaturan Common Pool Resources (hutan & sungai) pada sistem pemerintahan lokalitas (desa) Wujud kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pengaturan pemerintahan lokalitas (desa) Efektivitas kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelayanan Pengawasan Pemerintahan Lokalitas (Desa) – control of power Nanggroe Aceh Darussalam Ada, namun dalam derajat yang lemah Rendah kelembagaan yang ada telah lama lumpuh Lembaga imum mukim dan tokoh agama di gampong Sangat rendah masalah SDM dan konflik GAM vs RI Imum mukim dan Badan Permusyawaratan Desa Sumatera Barat Persinggungan kepentingan sangat terlihat nyata KAN vs Wali Nagari vs BPN Sangat tinggi hak ulayat berada di tangan lembaga adat ninik-mamak sepenuhnya Elemen-elemen kelembagaan pemerintahan nagari Meski kualitas SDM terbatas, efektivitas pemerintahan sangat tinggi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jawa Barat Tidak ada karena, lembaga adat tidak eksis dalam masyarakat Rendah tidak dikenal hak ulayat, melainkan stateproperty Kelembagaan desa formal sesuai UU no 32/2004 Tinggi/efektif mendapatkan legitimasi legalrasional Badan Permusyawaratan Desa 51 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Bali Secara potensial ada, tetapi tidak tampak justru sinergitas tampak lebih menonjol Tinggi oleh lembaga Subak, meski mengalami penggerusan peranan dalam masyarakat Kelembagaan desa formal sesuai UU no. 32/2004, tokoh adat, dan tokoh agama Tinggi/efektif ada sinergitas dengan pemerintah desa adat/pakraman yang sangat baik Badan Permuswaratan Desa dan kelembagaan adat, serta kelembagaan lokal lainnya Papua Secara potensial ada tapi tidak tampak dipermukaan Secara latent, konflik kewenangan dirasakan kehadirannya Sangat tinggi kontrol sangat kuat hak ulayat berada pada kepemimpinan adat ondoafi (andewapi) Kelembagaan formal dan Sukusuku di bawah koordinasi ondoafi Rendah/sedang masalah SDM dan kelembagaan formal secara operasional cenderung kurang efektif Badan Permusyawaratan Kampung dan forum ”tiga tungku” (tokoh pemerintah, adat dan agama) + ”dua peran” (wanita dan pemuda) Gambar 4. Gambaran Ringkas Permasalahan Tata-Pemerintahan Lokalitas (Desa) Dari pelajaran yang didapat dari lapangan, maka sepantasnya rencana reformasi atau revitalisasi tata-pemerintahan lokalitas (desa) difokuskan pada persoalan riil dan mendesak sebagaimana gambarannya tampak pada Gambar 4. Satu hal yang penting untuk ditegaskan sekali lagi adalah upaya untuk merekonfigurasi keterlibatan publik (via skema kemitraan) lebih banyak dan lebih intensif dalam tata-pemerintahan desa. Dengan cara demikian, maka baik-buruknya dan ”perjalanan nasib” otonomi lokalitas (desa) tidak lagi bergantung sepenuhnya hanya pada sebuah institusi (pemerintah) saja, namun semua elemen masyarakat ikut bertanggung jawab. Pola-pola kemitraan di ranah publik inilah yang hendak dicari formatnya oleh studi aksi ini. Untuk itu, sejumlah studi pendukung telah disiapkan. Hasil studi dan pembahasan secara detail akan disajikan pada rangkaian Working Paper Series dari studi-aksi ini. Daftar Rujukan Alfitri. 2006. Nagari dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kemitraan. Seminar Studi-Aksi “Pembaruan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan”, diselenggarakan oleh PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Padang 23 Maret 2006. Anonymous. 2006. Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Berbasiskan Kemitraan di Propinsi Papua. Makalah disampaikan pada Seminar Awal ”Pembaruan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan” diselenggarakan oleh PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jayapura 19 April 2006. Busra, 2006. Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berbasis Kemitraan Budaya Lokal di Sumatera Barat. Makalah disampaikan pada Seminar Studi-Aksi “Pembaruan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan”, 52 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik diselenggarakan oleh PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Padang 23 Maret 2006. Cohen, J. M and Peterson, S. B. 1999. Administrative Decentralizatiruan on: Strategies for Developing Countries. Kumarian Press. West Hartford. Connecticut. Cornwall, A. 2002. Making Spaces, Changing Places: Situating Participation in Development. Institute of Development Studies. Sussex. Dharmawan, A. H. 2001. Livelihood Strategies and Rural Socio-Economic Change in Indonesia. Vauk. Kiel. Fahmi, K. 2006. Nagari dalam Polemik. Makalah disampaikan pada Seminar Studi-Aksi “Pembaruan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan”, diselenggarakan oleh PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Padang 23 Maret 2006. Fear, F. A and Schwarzweller, H.K. 1985. Introduction: Rural Sociology, Community and Community Development, in Fear, F. A and Schwarzweller, H. K. (eds.). 1985. Research in Rural Sociology and Development, Focus on Community. JAI. Greenwich and London. Firth, R. 1955. Some Principles of Social Organization. Journal of Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 85, Issue 1/2 , pp. 118. Fukuyama, F. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press. New York. Haeruman, M. 2006. Pembaharuan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan. Makalah dipresentasikan pada Seminar StudiAksi “Pembaruan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan”, diselenggarakan oleh PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Bandung, 20 April 2006. Hanafiah, M. 2006. Tata-Kelola Pemerintahan Gampong Berbasiskan Lokalitas Kemitraan. Makalah disampaikan pada Seminar Studi-Aksi “Pembaruan Tata-Kelola Pemerintahan Desa Berbasiskan Kemitraan”, diselenggarakan oleh PSP3IPB dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Banda Aceh, 25 Maret 2006. Kaufmann, D; Kraay, A; and Mastruzzi, M. 2005. Governance Matters IV: Governance Indicators 1996-2004. World Bank. Washington, D.C. Luiz, J. M. 2000. The Politics of State, Society and Economy. International Journal of Social-Economics, Vol. 27/3, pp. 227-243. 53 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik Osmani, S. R. 2000. Participatory Governance, People’s Empowerment and Poverty Reduction. SEPED Conference Paper Series No. 7. UNDP. Washington, D.C. Piliang, I. J; Ramdani, D dan Pribadi, A. 2003. Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi. Yayasan Harkat Bangsa dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta. Schneider, H. 1999. Participatory Governance: The Missing Link for Poverty Reduction. OECD Development Center, Policy Brief No. 17. Paris. Syafa’at, R. 2002. Kelembagaan Pemerintahan Desa: Tinjauan Historis Sosial Budaya Keberadaan Masyarakat Adat Dalam Konteks Desentralisasi Desa dalam Maryunani dan Ludigdo, U. (eds.). 2002. Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa: Monitoring dan Evaluasi Berpartisipasi. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang. Weiss, T. G. 2000. Governance, Good Governance, and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges. Third World Quarterly, Vol. 21/5, pp. 795-814. Wilkinson, K. P. 1970. The Community as a Social Field. Social Force, Vol. 48/3, pp. 311-322. Work, R. 2001. The Role of Participation and Partnership in Decentralized Governance: A Brief Synthesis of Policy Lessons and Recommendations of Nine Country Case Studies on Service Delivery for the Poor. UNDP. New York. 54 Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi TataKelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik BIODATA PENULIS Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc. Agr, lahir di Surakarta tanggal 14 September 1963. Menyelesaikan pendidikan S-1 tahun 1988 pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi-Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya sejak Mei 1990 hingga saat ini bekerja sebagai Dosen pada Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan Dosen pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, dan Program Studi Sosiologi Pedesaan. Tahun 1993 menyelesaikan program pendidikan S-2 di Georg-August University of Goettingen Germany in integrated Tropical Agricultural and Forestry, dan pada tahun 2000 menyelesaikan program doktor pada Rural and Agricultural Sociology di Georg-August University of Goettingent Germany. Selama bekerja sebagai dosen di IPB telah mengikuti berbagai jenis kegiatan penelitian seperti Rural Livelihood strategies and Social Changes in Indonesia (1997-2001); Study on the Clove Marketing System in Daerah Istimewa Aceh Indonesia (1994-1995); Strategy of Survival of the Shifting Cultivators in West Kalimantan Indonesia (1994-1995); Study on the Effectivenness of Credit Absorption of Small Enterprise and Small-Scale Industries in Central Java Indonesia (1992-1993), Studi on Rural Income Generating Activities (20022003), Poverty Alleviation Study (2003-2004), Environmental Governance Partnership System (2004-2005), Studi Kedaulatan Pangan (2005) dan lain-lain. Selain sebagai dosen, juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan (PSP-IPB) sejak 1988 sampai sekarang. Aktif dalam kegiatan seminar dan workshop baik nasional maupun internasional seperti Presenting Papers in the Annual International Conference on Tropical and Subtropical Agriculture (organized by ATSAF) in : Goettingen Germany (1998), Berlin Germany (1999) dan di Hohenheim Germany (2000). 55