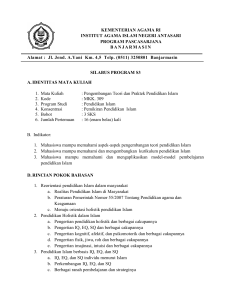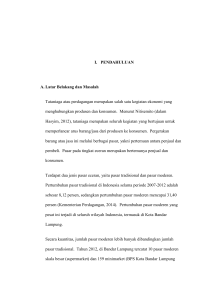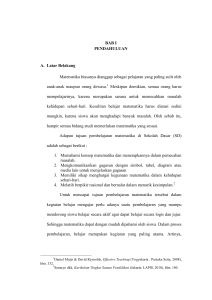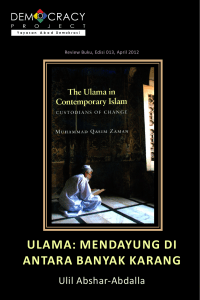Sebuah Ketakwaan di Rumah Ulil Abshar
advertisement

Syariah: Sebuah Ketakwaan di Rumah Ulil Abshar Abdalla Masa kecil saya jauh dari kehidupan yang “liberal” dan bebas dari kehidupan beragama. Masa kecil saya di Desa Cebolek, kota Pati di Jawa Tengah bersama ayah yang keras dan ketat dalam menentukan standar moral untuk saya dan saudara-saudara lainnya. Tidakaneh hal seperti ini terjadi dalam keluarga saya; semua orang di rumahnya mempunyai aturan yang sama. Kita hidup di desa dimana moralitas yang ketat menjadi satu-satunya aturan main. Musik, contohnya merupakan kutukan bagi keluarga, alasannya karena bisa menjauhkanmu dari mengingat Tuhan. Prinsip utama kaum beriman, yang menjadi kebijaksanaan keluarga saya yang taat adalah selalu mengingat dan menyembah Tuhan. Apapun yang mengalihkanmu dari tujuan yang mulia ini harus dijauhkan. Apapun yang mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan harus dijalankan. Tetapi aturan ini tidak berlaku pada musik dari Om Kalthoum, seorang penyanyi wanita asal Mesir yang memiliki suara indah dan menakjubkan, dan mendapatkan gelar kehormatan sebagai “Bintang dari Timur” atau kaukab al-sharq. Ayah saya mengidolainya. Dia mempunyai koleksi sederhana dari album-albumnya. Tetapi dia tak membiarkan dirinya menuruti “urusan duniawi” setiap hari. Dia hanya memainkan rekaman lagu Khalthoum pada Jumat pagi setelah dia selesai mengajar Tafsir Al-Qur’an pada pukul 7 pagi. Dia akan menghabiskan dua-tiga jam untuk lagu Om Kalthoum sebelum dia pergi sholat jumat di Masjid. Karena rutinitas ayah saya inilah, telinga saya terbiasa pada musik Kalthoum. Hanya inilah musik indah yang beruntung bisa saya rasakan. Musik Barat ataupun Indonesia jauh dari rumah saya. Saya pernah suatu kali tertangkap mendengarkan musik dangdut di radio dengan seorang teman. Ayah saya saat itu sangat marah, lalu menyitanya dan merusaknya seketika. Ayah saya memiliki daftar hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dan daftar tersebut berkembang seiring waktu ketika menurutnya masyarakat kita telah dinodai oleh teknologi moderen. Dia tidak senang dengan segala bentuk olahraga, terutama sepak bola. Ayah saya mengatakan hanya mengikuti otoritas kakek saya, yang merupakan seorang alim ulama dan faqih, bahwa sepak bola adalah haram karena mengalihkan dari tujuan tunggal manusia, yaitu menyembah Tuhan yang mulia. Selain itu, sepak bola merupakan permainan yang tak penting khas kehidupan kaum tak beriman. Mereka yang beriman memiliki alasan yang lebih baik dan lebih mulia untuk membantu sesama daripada urusan tidak berguna semacam itu. Ketakwaan mengatur seluruh aspek dalam hidup kami di pedesaan. Semua tindakan diatur dalam aturan yang kini disebut “syariah”. Ayah saya tidak pernah menjadi anggota partai Islam yang memperjuangkan penerapan syariah. Tetapi dalam seluruh hidupnya dijiwai dan diatur oleh hukum Tuhan. Baginya, syariah bukanlah retorika politis atau agenda ideologis yang kita lihat kini merajalela di antara kelompok Islamis dengan berbagai variannya. Hukum Islam diterapkan dalam keluarga saya, bukan sebagai motif politik. Bukan diterapkan oleh aparat negara. Syariah adalah bagian dari kehidupan ayah saya karena dia memilih secara suka rela untuk menghidupkannya. Tidak ada yang menaruh senjata di kepalanya untuk menjalani kehidupan semacam itu. Tidak ada otoritas moral yang mengatur kehidupannya. Apapun yang muncul datang dari keputusan suka relanya untuk hidup di bawah aturan Tuhan. Walaupun saya menderita dengan moralitas ketat seperti ini, saya sempat bangga ketika hidup dalam keimanan. Saya tak pernah menyesal masa kecil saya di masa lalu dalam lingkungan ketabahan. Ketika saya berpikir mengenai debat terkini di antara kaum Islamis, saya melihat perbedaan yang mencolok di antara syariah yang didorong oleh kaum Islamis moderen dan syariah yang hidup oleh ayah saya. Syariah dalam kehidupan ayah saya diwujudkan seperti yang diistilahkan Tarek Fatah dalam bukunya, Chasing Mirage, sebagai “State of Islam” untuk mengajukan kebalikan dari “Islamic State”. Syariah dalam retorika kelompok Islamis moderen merupakan bagian dari ideologi besar mereka untuk menciptakan “Islamic State”, sebuah proyek yang sangat sulit dipahami dan tak lebih dari khalayak belaka, seperti yang diungkapkan oleh Fatah. Masalah dengan Syariah yang diajukan oleh kelompok Islamis cenderung “dipadatkan” dalam formula yang baku dan jumud yang tidak bisa dikritik. Segala kritik yang datang berakhir pada tuduhan melawan Tuhan, Islam, dan Nabi. Pada akhirnya, syariah yang dibayangkan dalam ideologi Islamis moderen bersandar pada perwujudan otoritas negara. Syariah ditegakkan dengan paksaan, bukan dari ketakwaan yang saya lihat dalam keteladanan hidup ayah saya. Saya katakan tidak pada syariah sebagai bagian dari ketakwaan di rumah; tetapi tidak pada syariah sebagai proyek politik! Pernah dipublikasikan di Jakarta Post, Jumat 24 April 2015. Dipublikasikan dengan seizin penulis. Ulil Abshar Abdalla merupakan cendekiawan Islam dan pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL). Bisa dihubungi melalui akun twitter @ulil